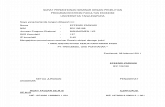metodebermain2
description
Transcript of metodebermain2

12
BAB II
METODE BERMAIN KONSTRUKTIF DAN
PERKEMBANGAN KEAGAMAAN ANAK
A. Metode Bermain Konstruktif
1. Pengertian Metode Bermain Konstruktif
Dalam pengertian umum, metode diartikan sebagai cara mengerjakan
sesuatu. Dalam pengertian letterlijk, kata “metode” berasal dari bahasa Greek
yang berarti dari “meta” yang berarti “melalui” dan “hodos” yang berarti
jalan. Jadi metode berarti “ jalan yang dilalui”.1
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai
berikut :
“Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.”2
Metode mengandung implikasi bahwa proses penggunaannya bersifat
konsisten dan sistematis, mengingat sasaran metode itu adalah manusia yang
sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan.3
Pengertian bermain adalah melakukan suatu perbuatan untuk
menyenangkan hati (dengan alat-alat tertentu atau tidak).4 Sedangkan pengertian
Konstruktif adalah bersifat membina, memperbaiki, dan membangun.5
Dengan demikian yang dimaksud dengan Metode Bermain Konstruktif
adalah cara bermain yang bersifat membangun, membina, memperbaiki, dimana
anak-anak menggunakan bahan untuk membuat sesuatu yang bukan untuk
bertujuan bermanfaat, melainkan ditujukan bagi kegembiraan yang diperolehnya
dari membuatnya.6
1 H.M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), cet. III, hal. 97 2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), hal. 652 3 H.M. Arifin, Op.cit., hal. 98 4 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 580-581 5 Ibid., hal. 457 6 Elizabeth B. Hurlock, Child Development, Med. Meitasari Tjandrasa dan Muslichah
Zarkasih, Perkembangan Anak, Jilid I, (Jakarta : Erlangga, 1997), Cet. V, hal. 330

13
Yang dimaksud konstruktif adalah bahwasanya anak-anak membuat
bentuk-bentuk dengan balok-balok, pasir, lumpur, tanah liat, manik-manik, cat,
pasta, gunting dan krayon. Sebagian besar konstruksi yang dibuat merupakan
tiruan dari apa yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari atau dari layar
bioskop atau televisi. Menjelang berakhirnya awal masa kanak-kanak, anak-
anak sering menambahkan kreatifitasnya ke dalam konstruksi-konstruksi yang
dibuat berdasarkan pengamatannya dalam kehidupan sehari-hari.7
2. Teori-teori Permainan
a. Teori Rekreasi
Teori ini dikembangkan oleh Schaller dan Lazarus, keduanya
ilmuwan bangsa Jerman, yang berpendapat bahwa permainan merupakan
kesibukan untuk menenangkan pikiran atau beristirahat. Orang melakukan
kesibukan bermain bila mereka bekerja ; maksudnya untuk mengganti
kesibukan bekerja dengan kegiatan lain yang dapat memulihkan tenaga
kembali.8 Maka disebut juga teori pemulihan tenaga.9 Atau disebut juga
teori Istirahat.10
b. Teori Penglepasan
Teori ini berasal dari Herbert Spencer, ahli pikir bangsa Inggris. Ia
mengatakan bahwa dalam diri anak terdapat kelebihan tenaga. Sewajarnya ia
harus mempergunakan tenaga itu melalui kegiatan bermain. Kelebihan
tenaga itu harus dipergunakan, paling tidak harus dilepaskan dalam kegiatan
bermain-main. Dengan demikian dapat mencapai keseimbangan dalam
dirinya.11 Teori ini disebut juga sebagai teori kelebihan tenaga
(Krachtoverschot-theorie).12
c. Teori Atavistis
Teori ini berasal dari Stanley Hall, ahli psikologi bangasa Amerika,
yang berpendapat bahwa di dalam perkembangannya, anak melalui seluruh
taraf kehidupan umat manusia. Sebelumnya Hackel merumuskan pendapat
ini berupa hukum biogenetis. Anak-anak selalu mengulangi apa yang pernah
dikerjakan atau diperbuat nenek moyangnya sejak dari masa dahulu sampai
kepada keadaan yang sekarang. Karena alasan itulah maka teori ini dinamai
atavistis. Dalam bahasa latin, atavus artinya nenek moyang. Jadi atavistis
7 Elizabeth B.Hurlock, Development Psycology A Life-Span Apprroach, Istiwidiyanti,
Soejarwo, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, (Jakarta : Erlangga, 1999) Cet. VII, Hal. 122
8 Zulkifli L, Psikologi Perkembangan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), cet. IX, hal. 39
9 Abu Ahmadi dan Zul Afdi Ardian, Ilmu Jiwa Anak, (Bandung : Armico, 1989), hal. 79 10 Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), cet Vii, hal. 29 11 Zulkifli L, Loc. Cit. 12 Kartini Kartono, Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan), (Bandung : Mandar Maju,
1995_, cet. V, hal. 118

14
artinya kembali kepada sifat-sifat nenek moyang di masa lalu. Dalam
permainan timbul bentuk-bentuk kelakuan seperti bentuk kehidupan yang
pernah dialami oleh nenek moyang.13
Hall yang banyak mendengarkan teorinya kepada Rousseau dan
Darwin, memandang permainan berdasarkan teori rekapitulasi, yaitu
sebagai ulangan (rekapitulasi) bentuk-bentuk aktivitas yang dalam
perkembangan jenis manusia pernah memegang peranan yang dominan.
Menurut teori rekapitulasi perkembangan individu (ontogenesa)
adalah ulangan perkembangan jenis manusia (filogenesa). Menurut Hall
permainan merupakan sisa-sisa periode perkembangan manusia waktu dulu
tetapi yang sekarang perlu sebagai stadium transisi dalam perkembangan
individu.14Teori rekapitulasi berhasil memberi penjelasan lebih rinci
mengenai tahapan kegiatan bermain yang mempunyai urutan yang sama
seperti evolusi mahluk hidup.15
d. Teori Biologis
Teori ini berasal dari Karl Gross, seorang bangsa Jerman.
Selanjutnya Dr. Maria Montessori, pendidik kenamaan bangsa Italia (1870-
1952), mengembangkan teori biologis ini. Permainan merupakan tugas
biologis (hidup atau hayat). Dengan pedoman pendapat itu, permainan di
kalangan anak-anak mempunyai persamaan dengan permainan dalam dunia
binatang. Permainan merupakan latihan untuk menyesuaikan diri dengan
keadaan lingkungan kehidupan, juga dianggap sebagai latihan jiwa dan raga
untuk kehidupan dimasa yang akan datang.16
Dasar teori Groos adalah prinsip seleksi alamiah yang
dikemukakan oleh Charles Darwin. Binatang dapat mempertahankan
hidupnya karena dia mempunyai keterampilan yang diperoleh melalui
bermain. Bayi yang baru lahir juga binatang mewarisi sejumlah instink yang
tidak sempurna dan instink ini penting guna mempertahankan hidup.
Bermain bermanfaat untuk mahluk yang masih muda dalam melatih dan
menyempurnakan instinknya. Jadi tujuan bermain adalah sebagai sarana
latihan dan mengelaborasi keterampilan yang diperlukan saat dewasa
nanti.17
13 Zulkifli L., Loc. Cit. 14 F.J. Monks, A.M.P.Knoers, Ontwikkelings Psykologie Inleiding tot de verschillende
Deelgebieden, Siti Rahayu Haditono, Psikologi Perkembangan : Pengantar dalam Berbagai Bagiannya, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998), cet. 11, hal. 132- 133
15 Mayke S. Tedjasaputra, Bermaian, Mainan dan Permainan Untuk Pendidikan Usia Dini, (Jakarta : PT. Grasindo, 2001), cet. I, hal. 4
16 Zulkifli L., Op.cit., hal. 40 17 Mayke S. Tedjasaputra, Op.cit., hal. 5

15
Montessori menyebut permainan ini sebagai latihan fungsi-fungsi.
Fungsi-fungsi dilatih dengan cara berlari-lari, dengan cara berjingkrak-
jingkrak, dan sebagainya. Perasaan senang dalam bermain ini dapat
membantu dan mendorong untuk menimbulkan kekuatan-kekuatan yang
dibutuhkan.18
e. Teori Psikologi Dalam
teori ini berasal dari Sigmund Freud dan Adler, kedua tokoh itu
membahas permainan dari sudut pandang psikologi dalam. Menurut Freud,
permainan merupakan pernyataan nafsu-nafsu yang terdapat di daerah
bawah sadar, sumbernya berasal dari dorongan nafsu seksual. Permainan
merupakan bentuk dari pemuasan dari nafsu seksual yang terdapat di
komplek terdesak. Sedang menurut Adler, pernyataan nafsu-nafsu yang
terdapat di bawah sadar itu sumbernya berasal dari dorongan nafsu
berkuasa. Permainan merupakan usaha untuk menutup-nutupi perasaan
“harga diri kurang”.19
f. Teori Fenomenologis
Profesor Kohnstamm, seorang sarjana Belanda yang
mengembangkan teori fenomenologi dalam pedagogik teoritisnya
menyatakan bahwa, permainan merupakan suatu fenomena atau gejala yang
nyata, yang mengandung unsur-unsur permainan (spels feer). Dorongan
bermain merupakan dorongan untuk menghayati suasana bermain itu. Yakni
tidak khusus bertujuan untuk mencapai prestasi-prestasi tertentu, akan tetapi
anak bermain untuk permainan itu sendiri. Jadi, tujuan permainan adalah
permainan itu sendiri.
Dalam suasana permainan itu terdapat :
1) Kebebasan
2) Harapan
3) Kegembiraan
4) Unsur Ikhtiar dan
5) Siasat untuk mengatasi hambatan serta perlawanan.20
3. Jenis- Jenis Permainan
H. Zetzer, seorang ahli psikologi bangsa Jerman, meneliti permainan
dikalangan anak-anak. Tokoh ini menyebutkan jenis-jenis permainan sebagai
berikut :
a. Permainan Fungsi
18 Zulkifli L., Loc,cit 19 Ibid, hal. 40 20 Kartini Kartono, Op.cit., hal. 121

16
Dalam permainan ini yang diutamakan adalah gerakannya. Bentuk
permainan ini gunanya untuk melatih fungsi-fungsi gerak dan perbuatan.
b. Permainan Konstruktif
Dalam permainan ini yang diutamakan adalah hasilnya, ada pula
yang disebut permainan destruktif. Bentuk permainan ini lebih bersifat
merusak.
c. Permainan Reseptif
Sambil mendengarkan cerita atau melihat-lihat buku bergambar,
anak berfantasi dan menerima kesan-kesan yang membuat jiwanya sendiri
menjadi aktif.
d. Permainan Peranan
Anak itu sendiri memegang peranan sebagai apa yang sedang
dimainkannya.
e. Permainan Sukses
Dalam permainan ini yang diutamakan adalah prestasi, untuk
kegiatan permainan ini sangat dibutuhkan keberanian, ketangkasan,
kekuatan dan bahkan persaingan.21
Menurut Drs. Agus Sujanto, jenis-jenis permainan adalah :
a. Permainan Gerak atau Fungsi
Yang dimaksud adalah permainan yang mengutamakan gerak dan
berisi kegembiraan di dalam bergerak.
b. Permainan Destruktif
Yang dimaksud adalah permainan dengan merusakkan alat-alat
permainannya itu. Seakan-akan ada rahasia di dalam alat permainannya dan
ia mencari rahasia tersebut.
c. Permainan Konstruktif
Yang dimaksud anak senang sekali membangun, disusun balok-
balok, satu dan sebagainya menjadi sesuatu yang baru dan dengan itu si
anak menemukan kegembiraannya.
d. Permainan Peranan, atau ilusi
Yang dimaksud adalah permainan peranan yang di dalamnya, si anak
menjadi seorang yang penting.
e. Permainan Reseptif
Yang dimaksud adalah apabila orang tuanya sedang menceritakan
sesuatu , maka di dalam jiwanya si anak mengikuti cerita dengan
menempatkan dirinya sebagai tokohnya.
f. Permainan Prestasi
21 Zulkifli L., Op.cit., hal. 42-43

17
Yang dimaksud adalah di dalam permainan itu si anak berlomba-
lomba untuk menunjukkan kelebihannya, baik kelebihan dalam kekuatan,
dalam keterampilan maupun dalam ketangkasannya.22
4. Fungsi Bermain
Sesuai dengan pengertian bermain yang merupakan tuntutan dan bagi
perkembangan anak usia TK, menurut Hartley, Frank, dan Goldenson
sebagaimana dikutip oleh Moeslichatoen, ada 8 fungsi bermain bagi anak :
a. Memainkan apa yang dilakukan oleh orang dewasa
b. Untuk melakukan berbagai peran yang ada dalam kehidupan nyata
c. Untuk mencerminkan hubungan dalam keluarga dan pengalaman hidup yang
nyata.
d. Untuk menyalurkan perasaan yang kuat
e. Untuk melepaskan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima
f. Untuk kilas balik peran-peran yang biasa dilakukan
g. Mencerminkan pertumbuhan
h. Untuk memecahkan masalah dan mencoba berbagai penyelesaian
masalah.23
Sedangkan menurut Hetherington dan Parke bermain juga berfungsi
untuk mempermudah perkembangan kognitif anak. Dengan bermain akan
memungkinkan anak meneliti lingkungan, mempelajari segala sesuatu yang
dihadapinya. Bermain juga meningkatkan perkembangan sosial anak. Dengan
menampilkan bermacam-macam peran, anak berusaha memahami peran orang
lain dan menghayati peran yang akan diambilnya setelah ia dewasa kelak.
Sejalan dengan Hetherington dan Parke di atas, Dworetzky (1990) juga
mengemukakan fungsi bermain dan interaksi dalam permainan mempunyai
peranan penting bagi perkembangan kognitif dan sosial anak.
Fungsi bermain tidak saja dapat meningkatkan perkembangan kognitif
dan sosial, tetapi juga perkembangan bahasa, disiplin, perkembangan moral ,
kreatifitas dan perkembangan fisik anak. Beberapa fungsi bermain antara lain :
a. Mempertahankan keseimbangan
b. Menghayati berbagai pengalaman yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari
c. Mengantisipasi peran yang akan dijalani di masa yang akan datang
d. Menyempurnakan keterampilan-keterampilan yang dipelajari
e. Menyempurnakan keterampilan memecahkan masalah
f. Meningkatkan keterampilan berhubungan dengan anak lain.24
22 Agus Sujanto, Op.cit., hal. 32 23 Moeslichatoen R., Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,
1999), cet. I, hal. 33-34 24 Ibid., hal. 34-36

18
B. Perkembangan keagamaan Anak
1. Pengertian Perkembangan Keagamaan Anak
Psikologi berasal dari kata Psyche dan Logos, masing-masing kata itu
mempunyai arti “jiwa” dan “ilmu”. Psikologi adalah ilmu yang menyelidiki
dan membahas tentang perbuatan dan tingkah laku manusia.
Dalam usaha memahami psikologi perkembangan, ada baiknya kita
ketahui apa yang dimaksud dengan perkembangan. Mulanya kata
perkembangan berasal dari biologi, kemudian pada abad ke-20 ini kata
perkembangan digunakan oleh psikologi. Karena penggunaannya pertama-
tama dalam biologi , pada masa berikutnya ada ahli-ahli yang menyebut
pertumbuhan, disamping kata perkembangan, bahkan ada yang menyebut
istilah itu untuk maksud yang sama.25
Menurut Robert G Myers, dalam bukunya “Toward a fair Start For
Childern“, sebagaimana dikutip oleh Washington P. Napitupulu,
perkembangan anak tidak sama dengan pertumbuhan, walaupun sebagaimana
disarankan pada diskusi sebelumnya, istilah-istilah itu berkaitan dan sering
digunakan bergantian. Jika pertumbuhan digambarkan oleh perubahan dalam
ukuran, untuk perkembangan dicirikan oleh perubahan di dalam kerumitan
dan fungsi.26 Proses perkembangan akan berlangsung sepanjang kehidupan
menusia, sedang proses pertumbuhan sering kali akan berhenti bila seorang
telah mencapai kematangan fisik.27
Arti perkembangan anak menurut Robert G. Mayers sebagaimana
dikutip oleh Washington P. Napitupulu adalah suatu proses perubahan di
mana anak belajar menangani taraf-taraf yang semakin rumit tentang gerakan,
pemikiran, perasaan (emosi) dan hubungan dengan orang lain.28
Sedangkan arti jiwa agama menurut Zakiah Daradjat adalah pengaruh
agama terhadap sikap dan tingkah orang karena cara seseorang berfikir,
bersikap, bereaksi dan bertingkah laku, tidak dapat dipisahkan dari
keyakinannya, karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi keyakinannya.29
Perkembangan jiwa keagamaan di sini dapat diartikan sebagai proses
perubahan keagamaan dalam diri seorang anak terhadap sikap dan tingkah
laku karena cara anak tersebut berfikir, bersikap, bereaksi, bertingkah laku,
tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya.
25 Zulkifli, Op.cit, hal. 4 26 Robert G. Myers, Toward a fair Start For Childern, Washington P. Napitupulu , Masanya
Untuk Anak- Semasa Kecil: Menuju Awal yang Adil Bagi Anak-anak, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992) hal. 27
27 Hj. Endang Poerwanti, Nur Widodo, Perkembangan Peserta Didik, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), cet. II, hal. 27
28 Robert G Mayers, Loc.cit 29 Zakiyah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 2

19
2. Teori-Teori Perkembangan
Pengertian teori di sini bukan sebagai lawan praktek, melainkan
sebagai anggapan pakar mengenai hakekat perkembangan. Karena sebagai
anggapan, maka walaupun mengenai hal yang sama, yaitu perkembangan akan
tetapi berbeda-beda antara pakar yang satu dengan pakar yang lain. Adapun
beberapa teori yang perlu dikemukakan di sini adalah sebagai berikut :
a. Teori Nativisme
(Latin, Nativus : Pembawaan). Pelopor Nativisme adalah seorang
filosof bangsa Jerman bernama Arthur Schopenhauer (1788-1860).
Menurut pendapatnya anak sejak lahir telah memiliki sifat-sifat dasar
tertentu yang disebut sifat pembawaan. Sifat-sifat itu tidak dapat dirubah
dengan pengalaman, lingkungan atau pendidikan.30 Dan sifat bawaan
inilah yang akan menentukan wujud keperibadian seorang anak.31
Kelompok atau aliran ini dijuluki aliran Pesimisme atau aliran
yang sangat pesimis terhadap hasil pendidikan dan lingkungan dalam
menentukan perkembangan, karena bayi lahir seolah sudah menjadi
barang jadi, yang tidak dapat diotak-atik dan sama sekali tidak
memperhitungkan pengaruh lingkungan, pengalaman, hasil belajar dan
pendidikan yang diperoleh anak setelah lahir, sehingga juga tidak
memperhitungkan fungsi sekolah atau pengaruh teman.
Menurut aliran ini berbagai keistimewaan orang tua akan dapat
begitu saja diturunkan kepada anaknya tanpa pendidikan, sementara anak
yang sudah berpembawaan buruk, juga tidak akan ada gunanya dididik
atau dilatih untuk menjadi baik. Aliran ini tidak dipertahankan mengingat
uraiannya kurang bisa dipertanggung jawabkan.32
b. Teori Empirisme
(Latin Emperia : Pengalaman). Pelopor yang utama dari faham
ini adalah seorang ahli filsafat Inggris yang bernama John Locke (1632-
1704). Faham ini bertentangan dengan faham Nativisme dan berpendapat
bahwa anak sejak lahir belum memiliki sifat-sifat pembawaan apapun.33
Dan perkembangan manusia sepenuhnya tergantung pada lingkungan atau
pendidikan yang diperoleh. Aliran ini juga disebut dengan Optimisme
karena sangat optimis terhadap usaha pendidikan dalam memberi arah
perkembangan anak. Ajaran yang terkenal dalam aliran ini adalah “Tabula
Rasa” yang berarti meja lilin atau kertas kosong, artinya anak dilahirkan
30 Ahmad Thantowi, Psikologi Perkembangan, (Bandung : Angkasa, 1993), hal. 25 31 Abu Ahmadi, Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,
1991), Cet. I, Hal. 21 32Endang Poerwanti, Nur Widodo, Op.Cit., hal. 55 33 Ahmad Thantowi, Op.Cit., hal. 25-26

20
dalam keadaan putih bersih, yang dapat diisi apa saja dengan belajar dan
pengalaman yang diperoleh.34
c. Teori Konvergensi
Konvergensi (Converge : Memusatkan pada satu titik ;
bertemu).35 Teori Konvergensi ini dipelopori oleh Louis William Stern
(1871-1938) yang juga psikolog dan filosof Jerman. Pendapatnya tentang
teori ini adalah bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia
adalah integritas antara pembawaan dan lingkungan. Pembawaan tak ada
artinya bila tidak didukung pengalaman, kesempatan dan usaha belajar,
sebaliknya lingkungan juga tidak bermanfaat bila anak ternyata tidak
membawa kecenderungan yang potensial untuk dikembangkan.
Adanya teori dan tafsiran tentang kertas putih (tabula rasa) dari
teori Empirisme yang diperkenalkan oleh John Locke mendasari
keyakinan Ki Hajar Dewantoro sejak tahun 1940-an tentang daya
konvergensi antara dasar dan ajar. Dasar adalah kodratnya anak-anak,
sedangkan ajar adalah lingkungan pendidikan.36
Disini diutarakan pula tentang pandangan Islam terhadap
hereditet dan lingkungan sebagai berikut :
1. Firman Allah SWT
)84: اإلسراء ... (قل آل يعمل على شاآلتهKatakanlah, “ Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”.(QS. Al-Isra' ; 84)37
2. Sabda Nabi Muhammad saw :
حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيد عن الزهرى أخبرنى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أنه آان يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آل مولود يولد على
38)رواه مسلم (الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه “Diriwayatkan dari Hajib bin al-Walid diriwayatkan dari Muhammad bin Harbi dari Zabidi dari Zuhri menceritakan kepadaku Said bin Musayyaib dari Abu Hurairah bahwasanya dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Tiap-tiap anak dilahirkan menurut fitrahnya (bakatnya, orang tualah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi)”. (HR. Muslim)
34 Endang Poerwanti, Nur Widodo, Op.Cit., hal. 55-56 35 Abu Ahmadi, Munawar Sholeh, Loc. Cit. 36 Endang Poerwanti, Nur Widodo, Op.Cit., hal. 56-57 37 R.H.A. Soenarjo, Al- Quran dan Terjemahannya, (Semarang : PT. Kumudasmoro
Grafindo, 1994), hal. 437. 38 Imam Muslim, Shohih Muslim juz II, (Beirut Libanon: Darul Kutub al-Alamiyah), hal. 458.

21
3. Prinsip-Prinsip Perkembangan
Ciri-ciri perkembangan menunjukkan gejala-gejala yang secara
relatif teratur, sehingga terjadi adanya pola-pola perkembangan yang
sistematis. Atas dasar itu maka para ahli merumuskan dalam bentuk prinsip
perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan itu kadang-kadang juga
dipandang sebagai hukum-hukum perkembangan. Beberapa prinsip-prinsip
perkembangan yang perlu dibicarakan di sini adalah :
a. Perkembangan fungsi-fungsi jasmaniah dan fungsi-fungsi rohaniah
berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh (integral).
b. Setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam
perkembangannya.
c. Perkembangan seorang individu, baik keseluruhan, maupun setiap
aspeknya, kelangsungannya tidak konstan, melainkan berirama.
d. Proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu
e. Proses perkembangan berlangsung secara bersambungan atau kontinyu.
f. Antara aspek perkembangan yang satu dengan ayang lain saling berkaitan
atau saling berkorelasi secara bermakna.
g. Perkembangan berlangsung dari pola-pola yang bersifat umum ke pola-
pola yang bersifat khusus.39
Elizabeth B. Hurlock dalam bukunya perkembangan anak
menjelaskan bahwa prinsip-prinsip perkembangan tersebut meliputi :
a. Perkembangan melibatkan adanya perubahan yang bersifat progresif,
yang bertujuan agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan
lingkungan dengan cara realistis diri dan pencapaian genetik.40
b. Perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya.
Perkembangan merupakan proses kontinum, di mana perkembangan
sebelumnya akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Maka
kesalahan ataupun gangguan pada perkembangan awal akan terus
mempengaruhi perkembangan-perkembangan berikutnya. Kondisi yang
mempengaruhi perkembangan awal adalah hubungan pribadi yang
menyenangkan, keadaan emosi, metode melatih anak, peran yang dini,
struktur keluarga di masa kanak-kanak serta rangsangan lingkungan41.
c. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Dalam
kehidupan sering sulit dibedakan antara perubahan yang merupakan hasil
belajar dengan perubahan karena kematangan, hasil dari keduanya sering
terintegrasi. Hanya dapat ditandai bahwa perubahan karena belajar
39 Ahmad Thantowi, Op.Cit., hal. 30 - 32 40 Elizabeth B. Hurlock, Op.Cit., hal. 23 41 Ibid., hal. 25-27

22
diperoleh dengan usaha sadar atau latihan. Pengaruh hubungan antara
kematangan dan belajar adalah sebagai berikut :
1. Variasi pola perkembangan.
2. Kematangan membatasi perkembangan.
3. Batas kematangan yang dicapai.
4. Hilangnya kesempatan belajar membatasi perkembangan.
5. Rangsangan diperlukan untuk perkembangan sempurna.
6. Keefektifan belajar tergantung pada ketepatan waktu.42
d. Pola perkembangan dapat diramalkan. Karena pola perkembangan
manusia mengikuti pola umum, maka dengan melakukan pengamatan
longitudinal sejak awal perkembangan anak, akan dapat diramalkan pola
perkembangan berikutnya baik yang menyangkut pertumbuhan fisik
ataupun perkembangan psikis43.
e. Pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan, tidak
hanya pola perkembangan yang dapat diramalkan, juga karakteristik
tertentu dari tingkat perkembangan yang bisa diramalkan, baik dalam hal
ukuran, dan kapan kematangan atau sering disebut dengan masa peka
(masa yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan tertentu)
akan muncul, perencanaan pendidikan, kesiapan untuk tahap berikutnya,
perencanaan pekerjaan maupun untuk kepentingan adopsi.44
f. Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Meskipun
perkembangan manusia mengikuti pola umum namun tempo dan irama
perkembangan bersifat individual, pemahaman terhadap perbedaan irama
dan tempo yang individual ini, bisa dipakai untuk landasan dalam
menentukan harapan yang berbeda, dengan individualitas (perlakuan yang
berbeda), pendidikan anak harus bersifat perseorangan, serta meramal
adalah sulit.45
g. Pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Harapan sosial
sering dipakai oleh kelompok masyarakat sebagai kriteria untuk
menetapkan apakah perkembangan seseorang termasuk perkembangan
yang normal atau tidak.
h. Setiap bidang perkembangan mengandung bahaya yang potensial.
Walaupun pola perkembangan bergerak normal, selalu perlu diwaspadai
adanya gangguan baik yang berasal dari dirinya sendiri ataupun
lingkungan. Gangguan akan dapat mempengaruhi penyesuaian phisik,
psikhologis maupun sosial, akibatnya secara tidak sengaja memungkinkan
anak mengubah pola perkembangan, sehingga menghasilkan daerah
42 Ibid., hal. 28-29. 43 Ibid., hal. 31. 44 Ibid., hal. 33. 45 Ibid., hal. 35-37.

23
mendatar atau bahkan menurun pada grafik perkembangan anak. Bila
tidak diwaspadai hal ini akan merugikan keseluruhan perkembangan anak.
i. Kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan kebahagiaan
merupakan pengalaman subyektif yang tidak mungkin digambarkan
dengan ukuran dan prosedur obyektif. Subyektifitas rasa bahagia ini
menyangkut perbedaan individual yang berbeda antara satu dengan yang
lain, juga menyangkut subyektifitas pada setiap tahapan perkembangan.46
4. Periode-periode Perkembangan Cara menyusun atau memberikan periodesasi perkembangan tidak
sama antara pakar yang satu dengan yang lain, ini disebabkan oleh perbedaan pandangan yang mendasari cara pembagian itu. Beberapa macam cara pembagian periode perkembangan yang didasarkan pada dasar pandangan yang berbeda misalnya sebagai berikut : a. Periodesasi perkembangan berdasar pada ciri-ciri biologis
Yaitu berdasarkan ciri-ciri jasmaniah yang menandai setiap masa pada periode itu. Periodesasi itu dikemukakan oleh Aristoteles (384-322 S.M). Ia membagi ke dalam tiga masa (0-21 tahun) yaitu : 1. Masa anak kecil atau masa bermain (0-7 th) 2. Masa belajar atau masa sekolah rendah (7-14 th) 3. Masa remaja atau masa pubertas, yaitu masa peralihan dari masa anak-
anak menjadi dewasa (14-21th) b. Periodesasi perkembangan berdasar konsep didaktik
Periode ini dikembangkan oleh Amos Comenius, seorang ahli pendidikan bangsa Cekoslovakia (1592-1671) yang termuat dalam bukunya Didactika magna (Didaktik yang agung), sebagaimana dikutip oleh Ahmad Thantowi. Ia membagi perkembangan sejak lahir-usia 24 tahun, dalam empat masa, masing-masing meliputi enam tahunan yaitu : 1. Masa sekolah ibu (Scola Maferna), (0-6 th). 2. Masa sekolah bahasa ibu (Scola Vernacula), (6-12 th). 3. Masa sekolah latin (Scola Latena), (12-18 th). 4. Masa sekolah tinggi (Academia), (18-24 th).47
Rosseau, membagi periodesasi perkembangan menjadi empat masa yaitu : 1. Masa usia asuhan, (0-2 th). 2. Masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera, (2-12 th). 3. Masa pendidikan akal, (12-15 th). 5. Masa pendidikan watak dan pendidikan agama.48
46 Ibid., hal. 40-42. 47 Ahmad Thantowi, Op.Cit., hal. 34-35. 48 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung : PT. Remaja
Rosda Karya, 2000), cet. I, hal. 22.

24
c. Periodesasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologi
Ciri-ciri psikologis adalah ciri-ciri kejiwaan yang menonjol, yang
menandai masa pada periode itu. Periodesasi seperti ini dikemukakan oleh
Oswarl Kroch. Ciri-ciri psikologis yang ia kemukakan, yang dipandang
terdapat pada anak-anak yang pada umumnya adalah pengalaman
kegoncangan jiwa yang memanifestasikan dalam bentuk Trotz atau sifat
“keras kepala”. Atas dasar ini ia menyusun periode perkembangan
menjadi tiga masa yaitu :
1. Masa anak awal ; berlangsung sejak 0-3 tahun. Disebut juga trotz
periode pertama, yaitu masa menentang.
2. Masa keserasian sekolah ; berlangsung dari 3-13 tahun, disebut juga
trotz periode kedua, yaitu masa keserasian.
3. Masa kematangan ; berlangsung dari usia 13-21 tahun, disebut juga
trots periode ketiga, yaitu masa kematangan, dari pada masa krisis.49
d. Periodesasi perkembangan berdasarkan konsep tugas perkembangan.
Tugas perkembangan adalah pelbagai ciri perkembangan yang
diharapkan timbul dan dimiliki oleh setiap anak pada setiap masa dalam
periode perkembangannya. Periodesasi ini dikemukakan oleh Robert J.
Harighurt. Dalam bukunya yang berjudul Human Development and
Education, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Thantowi. Ia membagi
seluruh masa perkembangan menjadi masa sebagai berikut :
1. Masa bayi dan anak-anak (in fancy and Childhood); 0-6 tahun.
2. Masa sekolah atau pertengahan kanak-kanak (Middle Childhood); 6-12
tahun.
3. Masa remaja (Adolascence); 13-18 tahun.
4. Masa dewasa :
a. Masa mula dewasa (erly adulthood), 18-30 tahun.
b. Masa usia pertengahan (Middle age), 30-55 tahun.
c. Masa tua (latter maturity), 55 tahun keatas.50
5. Aspek Perkembangan Keagamaan Anak Usia Prasekolah (Perkembangan
Keagamaan Anak Usia Taman kanak-kanak)
Fitrah beragama ini merupakan disposisi (kemampuan dasar) yang
mengandung kemungkinan atau berpeluang untuk berkembang. Namun
mengenai arah dan kualitas perkembangan beragama anak sangat bergantung
kepada proses pendidikan yang diterimanya. Hal ini seperti yang telah
dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw: “ Setiap anak dilahirkan dalam
keadaan fitrah, hanya karena orang tuanyalah, anak itu menjadi yahudi,
49 Ahmad Thantowi, Op.Cit., hal. 35 50 Ibid., hal. 36

25
nasrani, atau majusi”. Hadis ini mengisyaratkan bahwa faktor lingkungan
(terutama orang tua) sangat berperan dalam mempengaruhi perkembangan
fitrah keberagamaan anak.
Jiwa beragamaatau kesadaran beragama merujuk kepada aspek
rohaniah individu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah yang
direfleksikan ke dalam peribadatan kepadaNya, baik yang bersifat
hablumminallah maupun hablumminannas.51
Perkembanganberagama seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor
pembawaan dan lingkungan.
a) Faktor Pembawaan (internal)
Dalam perkembangannya, fitrah beragama ini ada yang
berjalan secara alamiah, dan ada juga yang mendapat bimbingan dari para
rasul Allah Swt, sehingga fitrahnya itu berkembang sesuai dengan
kehendak Allah Swt.52
Keyakinan bahwa manusia itu mempunyai fitrah atau
kepercayaan kepada Tuhan didasarkan pada firman Allah surat Ar-Ruum
ayat 30 sebagai berikut:
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, (Ar-Ruum:30)53
b) Faktor Lingkungan (Eksternal)
Faktor pembawaan atau fitrah beragama merupkan potensi
yang mempunyai kecenderungan untuk berkembang. Namun,
perkembangan itu tidak akan terjadi manakala tidak ada factor luar
(eksternal) yang memberikan rangsangan yang memungkinkan fitrah
itu berkembang dengan sebaik-baiknya. Faktor eksternal itu adalah
lingkungan dimana individu itu hidup. Lingkungan itu adalah
keluarga, sekolah, dan masyarakat.
(1) Lingkungan Keluarga
Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama
bagi anak, oleh karena itu kedudukan keluarga dalam
pengembangan kepribadian anak sangatlah dominan.
51 Syamsu Yusuf LN., Op. Cit., hal. 136
52 Ibid, hal. 137 53 R.H.A. Soenarjo dkk, Op. Cit, hal. 645

26
Dalam hal ini, orang tua mempunyai peranan yang
sangat penting dalam menumbuhkan fitrah beragama anak.54
Orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup
anak. Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka
merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, yang
dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang
sedang tumbuh. Sikap anak terhadap pendidikan agama di
sekolah sangat dipengaruhi oleh sikap orang tuanya.55
Dalam mengembangkan fitrah beragama anak dalam
keluarga, ada beberapa hal yang perlu menjadi kepedulian orang
tua yaitu:
(a) Karena orang tua merupakan pembina pribadi yang pertama
bagi anak, dan tokoh yang diidentifikasi atau ditiru anak,
maka seharusnya dia memilki kepribadian yang baik
(berakhlakul karimah).
(b) Orang tua hendaknya memperlakukan anaknya dengan baik.
Karakteristik sikap orang tua yang baik: (1)
memberikan curahan kasih sayang yang ikhlas; (2)
menghargai pribadi anak; (3) mau mendengar pendapat atau
keluhan anak; (4) memaafkan kesalahan anak; (5)
meluruskan kesalahan anak; (6) menerima anak sebagaimana
mestinya.
(c) Orang tua hendaknya memelihara hubungan yang harmonis
antar anggota keluarga.
(d) Orang tua hendaknya membimbing, mengajarkan agama
terhadap anak, seperti: syahadat, sholat, berwudlu, doa-doa,
bacaan al-Quran dan lain-lain.56
Pentingnya peranan orang tua dalam mengembangkan fitrah
beragama anak ini, dinyatakan dalam surat at-Tahrim ayat 6
sebagai berikut:
Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…..,(at-Tahrim:6)57
( 2) Lingkungan Sekolah
54 Syamsu Yusuf LN., Op. Cit., hal. 137-138 55 Zakiah Daradjat,. Op. Cit., hal. 56 56 Syamsu Yusuf LN,. Op. Cit,. hal. 138-139 57 R.H.A. Soenarjo dkk, Op. Cit., hal. 951

27
Sekolah merupakan lembaga pendidiksn formal yang
mempunyai program yang sistemik dalam melaksanakan
bimbingan, pengajaran dan latihan kepada anak agar mereka
berkembang sesuai dengan potensinya.
Faktor yang menunjang perkembangan fitrah beragama
siswa adala:
(a) Kepedulian kepala sekolah, guru-guru dan staf sekolah
lainnya terhadap pelaksanaan pendidikan agama di sekolah.
(b) Tersedianya sarana ibadah yang memadai dan
memfungsikannya secara optimal.
(c) Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian bagi
para siswa dan ceramah-ceramah atau diskusi keagamaan
secara rutin.
(3) Lingkungan Masyarakat
Yang dimaksud lingkungan masyarakat di sini adalah
situasi atau kondisi interaksi social dan sosiokultural yang secara
potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama
atau kesadaran agama individu.58
Menurut Abin Syamsuddin Makmun sebagaimana yang
dikutip oleh Syamsu Yusuf LN, mengemukakan bahwa
kesadaran agama pada usia ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai
berikut:
a) Sikap keagamaannya bersifat reseptif (menerima) meskipun
banyak bertanya.
b) Pandangan ketuhanannya bersifat anthropormorph
(dipersonifikasikan).
c) Penghayatan secara rohaniah masih superficial (belum
mendalam) meskipun mereka telah melakukan atau
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ritual.
d) Hal ketuhanan dipahamkan secara ideosyncritic (menurut
khayalan pribadinya) sesuai dengan taraf berfikirnya yang
masih bersifat egosentrik (memandang segala sesuatu dari
sudut dirinya).59
Hendaknya setiap pendidik menyadari bahwa dalam
pembinaan pribadi anak sangat diperlukan pembiasaan-
pembiasaan dan latihan-latihan yang cocok dan sesuai dengan
perkembangan jiwanya. karena pembiasaan dan latihan tersebut
akan membentuk sikap tertentu pada anak, yang lambat laun
58 Syamsu Yusuf LN., Op. Cit., hal. 140-141 59 Ibid, hal. 176-177

28
sikap itu akan bertambah jelas dan kuat, akhirnya tidak
tergoyahkan lagi, karena telah masuk menjadi bagian dari
pribadinya.60
Pembiasaan-pembiasaan tersebut diantaranya adalah
akhlakul karimah, seperti (a) mengucapkan salam; (b) membaca
basmalah pada saat akan mengerjakan sesuatu; (c) membaca
hamdalah pada saat mendapatkan kenikmatan dan setelah
mengerjakan sesuatu; (d) menghormati orang lain; (e) memberi
shodaqoh; (f) memelihara kebersihan. Adapun doa-doa yang
diajarkan: (a) doa sebelum makan dan sesudahnya; (b) doa keluar
dan masuk rumah; (c) doa mau tidurdan bangun tidur; (d) doa
untuk orang tua; (e) doa keselamatan di dunia dan akhirat.
Untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak
pada usia ini, orang tua menyekolahkannya ke TK atau TPA,
apabila orang tua tidak mempunyai kesempatan untuk mendidik
anak, karena kesibukan bekerja. TK /TPA ini mempunyai
peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kesadaran
beragama anak, baik menyangkut penghayatan dan pengamalan
ibadah mahdloh (hablum minallah) maupun hablum
minannaas.61
Mengenai pentingnya menanamkan nilai-nilai agama kepada anak
pada usia ini, Zakiyah Daradjat, mengemukakan bahwa umur TK adalah
umur yang paling subur untuk menanamkan rasa agama kepada anak, umur
penumbuhan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan ajaran agama, melalui
permainan dan perlakuan dari orang tua dan guru. Keyakinan dan
kepercayaan guru TK itu akan mewarnai pertumbuhan agama pada anak.62
C. Metode Bermain Konstruktif dalam Belajar dan Pengaruhnya terhadap
Perkembangan Keagamaan Anak.
Bermain memberi pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan diri
anak, baik secara fisik maupun mental. Beberapa pengaruh bermain bagi
perkembangan anak adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Hurlock sebagai
berikut :
1. Perkembangan fisik.
Bermain berguna untuk mengembangkan otot dan melatih seluruh
bagian tubuh. Bermain juga berfungsi untuk menyalurkan tenaga yang
60 Zakiah Daradjat, Op. Cit., hal. 61-62 61 Syamsu Yusuf Ln., Op. Cit., hal. 177-178 62 Zakiah Daradjat, Op. Cit., hal. 111

29
berlebihan yang bila dibiarkan dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental
anak.
2. Dorongan berkomunikasi.
Melalui aktivitas bermain, anak terdorong untuk berbicara dan
berkomunikasi dengan teman lain. Dan tanpa disadari anak belajar
mengungkapkan pikiran dan perasaannya pada orang lain, serta belajar
memahami pembicaraan orang lain.
3. Penyaluran energi emosional yang terpendam
Bermain merupakan sarana bagi anak untuk menyalurkan berbagai
ketegangan yang disebabkan oleh pembatasan lingkungan terhadap perilaku
mereka. Dengan demikian bermain merupakan terapi cepat dan murah bagi
pengembalian kondisi psikis anak yang terganggu.
4. Penyaluran bagi kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi
Tidak semua kebutuhan dan keinginan anak dapat terpenuhi.
Keinginan yang tidak terpenuhi dalam dunia riil dapat dikompensasikan
melalui kegiatan bermain.
5. Sumber belajar
Melalui kegiatan bermain, anak belajar berbagai hal, baik bersifat fisik
maupun pengembangan mental.
6. Rangsangan kreatifitas
Dalam bermain, anak bebas memilih dan bebas berekplorasi. Maka
bermain dapat mengembangkan kreatifitas anak sedemikian rupa.
7. Perkembangan wawasan diri
Dengan bermain anak mengetahui tingkat kemampuannya
dibandingkan dengan temannya bermain. Ini memungkinkan mereka untuk
mengembangkan konsep dirinya dengan lebih pasti dan nyata.
8. Belajar bersosialisasi dan bermasyarakat
Semakin tambah usia, anak akan cenderung bermain semakin banyak
teman, dengan demikian secara otomatis anak akan belajar bersosialisasi dan
berinteraksi.
9. Belajar standart moral
Melalui kegiatan bermain, anak belajar hal-hal yang dapat diterima
oleh lingkungan, dan hal-hal yang ditolak.
10. Belajar bermain sesuai dengan peran jenis kelamin
Anak belajar di rumah dan di sekolah mengenai apa saja peran jenis
kelamin yang disetujui. Akan tetapi, mereka segera menyadari bahwa mereka
juga harus menerimanya bila ingin menjadi anggota kelompok bermain.
11. Perkembangan ciri keperibadian yang diinginkan

30
Secara pelan dan pasti keperibadian anak akan terbentuk melalui
kegiatan bermain.63
Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat ditegaskan pengaruh dari
kegiatan bermain yaitu : Secara fisik,Mengembangkan kemampuan otot dan
kesehatan tubuh, Secara psikis, Mengembangkan berbagai aspek keperibadian
dan sikap mental.64
63 Menurut Alizabeth B. Hurlock yang dikutip oleh Hibana S. Rahman dalam bukunya
Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini,PGTKI Press, 2002 hal. 86-89. 64 Hibana S. Rahman, Op.Cit., hal. 89.