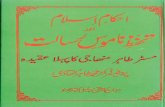Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala...
Transcript of Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala...
Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah1
Oleh Abd Moqsith Ghazali
[Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]
Email: [email protected]
Pengantar
Negara sebagai entitas kelembagaan politik merupakan manifestasi
dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk
mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Eksistensi negara, dalam
tataran ini, meniscayakan adanya perpaduan, meminjam istilah Georg W.F.
Hegel (w. 1831 M.), antara kebebasan subyektif (subjective liberty), yaitu
kesadaran dan kehendak individual untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
dan kebebasan obyektif (objective liberty), yaitu kehendak umum yang
bersifat fundamental.2
Sebagai faktor instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan
bersama, adanya seorang kepala negara (pemimpin) merupakan sesuatu
yang niscaya.3 Lembaga kepala negara (imamah)4 dipandang sebagai salah
1 Artikel ini dimuat dalam JAUHAR: Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual, Volume 2,
No. 1 , Juni 2001, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 1-21. 2Din Syamsuddin, Hak-Hak Rakyat Warga Negara dalam Perspektif Sejarah
Kekuasaan Negara-Agama, dalam Agama dan Hak Rakyat, (Jakarta: P3M, 1993), hlm. 21. Dengan mengatakan ini, Hegel beranggapan bahwa dia telah berhasil memecahkan masalah pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Baginya, bila seorang menyerahkan kepentingan individunya demi kepentingan umum, dia bukan sedang mengurangi haknya, melainkan memperluasnya. Dalam kepentingan umum itu terdapat kepentingan individualnya. Baca Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi, (Jakarta: Gramedia, 1997), Cet. II, hlm. 16.
3Begitu pentingnya kepala negara, Ibnu Taymiyah berkata “keberadaan kepala negara, meskipun dzalim, lebih baik bagi rakyat daripada kalau mereka harus hidup tanpa kepala negara”. Ibnu Taymiyah mengutip riwayat, “enam puluh tahun di bawah sulthan yang dzalim lebih baik daripada satu malam tanpa sulthan”. Ibnu Taymiyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah fiy Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah, cet. IV (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1979), hlm. 162.
4Kata “imamah” sering digunakan secara bergantian dan secara sinonim dengan kata khilafah. Menurut Mikhail, pilihan al-Mawardi dan para penulis sunni lain pada kata imamah dari pada kata khilafah sebagai respons terhadap kaum syi’ah yang memilih menggunakan imam daripada khalifah dalam menyebut pemimpin-pemimpin mereka. John H Mikhail, Mawardi: A Study in Islamic Political Thought, (Disertasi PhD, Harvard University, 1986), hlm. 32.
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 2
satu aspek penting dalam sistem ketatanegaraan.5 Selain memiliki kekuatan
sentral dalam menjalankan aturan-aturan politik kenegaraan bagi rakyatnya,
dalam banyak kasus, ia juga memegang peran dalam pengambilan dan
pelaksanaan keputusan-keputusan keagamaan. Begitu besar pengaruh dan
peranan lembaga tersebut, sehingga seolah-seolah tanpa keberadaannya,
sebuah negara akan terjerumus pada anarkisme dan kehancuran (fawdla).6
Dengan kata lain, kehadiran kepala negara menjadi faktor yang menjamin
eksistensi dan kelangsungan sebuah komunitas.
Dalam pemikiran politik Islam, paling tidak terdapat empat pokok soal
yang mendasari hadirnya seorang pemimpin (waliy al-amr).7 Pertama,
terwujudnya kemaslahatan umum sangat tergantung pada adanya amar
makruf nahi munkar. Karena itu, menegakkannya diperintahkan agama.
Pelaksanaan amar ma’ruf-nahi munkar menghendaki adanya pemimpin,
mengingat bahwa kelompok yang kecilpun diharuskan mengangkat seorang
pemimpin, sebagaimana ditegaskan hadits Nabi dalam riwayat Abu Daud dari
Abu Sa’id dan Abu Hurairah, 8
إذا خرج ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم
Hadits ini melalui dalalah al-nash (fahwa al-khitab, qiyas aulawi)
memerintahkan pula mengangkat seorang pemimpin dalam komunitas
(masyarakat) besar. Jika dalam kelompok kecil manusia saja diperlukan
seorang pemimpin, secara logis tentu saja kelompok manusia yang lebih
besar (rakyat) lebih memerlukan seorang pemimpin untuk mengatur urusan
kehidupan mereka.
Kedua, al-Qur’an ayat 59 surat al-nisa’ أطيعواالله وأطيعواالرسول وأولي أالمر منكم
Ayat ini tegas memerintahkan umat Islam agar menaati apa yang
diperintahkan ulil amri. Perintah ini tentu menghendaki adanya ulil amri.
5Plato mengatakan bahwa negara harus dikuasai para filsuf. Bagi Plato, hanya filsuf
yang dapat melihat persoalan yang sebenarnya, yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Filsuf melihat nilai-nilai abadi; filsuf dapat membebaskan diri dari dunia lahir yang berubah. Mereka mengetahui persoalan sampai pada intinya. J.J von Schmid, Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Sardjana, 1965), hlm. 17-18.
6Lihat Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Beirut: Dar al-Jil, Tanpa Tahun), hlm. 166. Bandingkan dengan Affandi Mukhtar, Konsep Kepala Negara (Imamah) dalam Pandangan Politik Al-Mawardi, (Cirebon: Jilli, 1997), hlm. 3
7Ibrahim Hosen, Fiqh Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik, dalam Ulumul Qur`an (Jakarta: 1992), No.2 Vol. IV, hlm., 58
8Ibnu Taymiyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah…., hlm. 161.
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 3
Ayat ini melalui isyarah al-nash memerintahkan adanya ulil amri. Dus,
mengangkat pemimpin (uli al-amr) adalah wajib. Lebih jauh, cukup banyak
hadits yang menegaskan kewajiban taat kepada pemimpin. Dan berdasarkan
isyarah al-nash, hadits-hadits tersebut mengharuskan pula adanya pemimpin,
yang dalam lingkup luas diwujudkan dalam sosok kepala negara.9
Ketiga, terhadap hukum fiqh yang berkenaan dengan persoalan
kemasyarakatan, intervensi pemerintah mutlak diperlukan, demi
menghindarkan kesimpangsiuran dan ketidakpastian hukum, di samping,
tentunya, agar terwujud keseragaman amaliah umat dan terciptanya
kemaslahatan umum. Karena itu, jika pemerintah telah memilih sesuatu
hukum dan menetapkannya, maka semua masyarakat terikat dengannya dan
harus mematuhinya, sejalan dengan kaidah: حكم الحاكم يرفع الخالف
Keempat, berdasarkan hukum aqliy (rasio) adalah tepat dan sudah
seharusnya menyerahkan urusan (persoalan kemasyarakatan) kepada
seorang pemimpin yang berkuasa untuk mencegah kezaliman dan mengatasi
perselisihan dalam masyarakat. Sebab, jika tidak demikian, tentu kekacauan
akan melanda umat manusia.
Dari keterangan di atas dan berdasarkan sejumlah nash lain yang
mengharuskan taat kepada pemimpin, dapatlah ditegaskan bahwa dalam
siyasah syar’iyyah hukum mengangkat pemimpin atau kepala negara adalah
wajib, baik secara syar’i maupun aqliy. Persoalannya adalah bagaimana
mekanisme pengangkatan sekaligus pemberhentiaan kepala negara itu. Ini
signifikan, setidak-tidaknya bagi mereka yang berminat mengkaji masalah
politik. Sebab, dari cara-cara itu dapat diketahui, dari mana sumber
kekuasaan kepala negara diperoleh, bagaimana kedudukan kepala negara?
Dalam konteks ini, al-Mawardi10 banyak menulis tentang masalah politik dan
9Al-Qur`an sendiri tak memuat secara eksplisit perintah mendirikan negara. Walau
terdapat sejumlah istilah politik dan pemerintahan dalam al-Qur`an, seperti khalifah, ulu al-amr, sulthan, mulk, dan hukm, penafsiran terhadap istilah-istilah itu tak pernah mencapai suatu konsensus bahwa al-Qur`an memerintahkan pendirian negara. Di dalam al-Qur`an hanya terdapat konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, seperti musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, dan penegakan keadilan. Karena itu, dapat dimaklumi jika sebagian pemikir Muslim dalam karangan politiknya mengembangkan teori kemunculan negara tidak selalu berpijak pada ayat-ayat al-Qur`an, melainkan banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani.
10Nama Lengkapnya Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi. Ia lahir di Bashrah tahun 364 H. dan meninggal tahun 450 H. Ia termasuk penganut Sunni, dalam bidang fikih bermadzhab Syafi’i. Ia pernah menjabat ra`is al-qudhat, semacam hakim tinggi. Lihat pengantar Mushthafa al-Saqa (editor) dalam al-Mawardi, Adab al-Dunya wa al-Din, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), hlm. 3-5
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 4
ketatanegaraan. Hasil karyanya yang cukup spektakuler di bidang itu adalah
al-Ahkam al-Sulthaniyah (Ajaran-Ajaran tentang Pemerintahan).11
Kitab yang banyak menyitir tentang teori kenegaraan ini dinilai oleh
sebagian pihak sebagai teori kenegaraan yang lebih bercorak fiqh oriented.
Artinya, bahwa segala sesuatu yang dijadikan obyek bahasan selalu dilihat
dari segi sah atau tidaknya menurut fiqh Islam. Karena itu, wajar bila
kemudian al-Mawardi lebih mengutamakan aspek formal negara.
Kecenderungan formalistik ini--kalau tidak mau dikatakan pragmatis--dapat
dibaca pada bagian pertama kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah ketika
membicarakan persoalan imamah. Ia mengatakan, bahwa imamah (khilafah)
merupakan lembaga penting untuk meneruskan tugas nubuwwah dalam
rangka memelihara agama dan mengatur persoalan dunia. Inti teori al-
Mawardi adalah bahwa institusi imamah (khilafah) yang ia anggap sebagai
kepemimpinan Nabi untuk menyelenggarakan masalah-masalah keagamaan
atau pun yang bersifat temporal, adalah niscaya, dan keniscayaannya
didasarkan atas syari’ah dan akal melalui ijma’ dari umat.
Dengan pernyataannya ini, al-Mawardi ingin meletakkan agama dalam
politik dalam hubungan yang bersifat simbiotik, di mana di antara keduanya
terjadi hubungan timbal balik dan saling melengkapi. Persoalannya adalah
ketika ingin mendudukkan agama dalam konteks politik. Jawaban dari
persoalan inilah yang kemudian menjadi sasaran kritik dari pemikir lainnya.
Al-Mawardi dikritik, karena justru agama tidak berada dalam posisi sentral,
tapi sebaliknya, agama menjadi alat legitimasi realitas politik yang ada,
sehingga ada yang mengatakan bahwa al-Ahkam al-Sulthaniyah adalah
bahasa status quo terhadap kenyataan politik saat itu.12
Analisis fiqhiyah yang dikemukakan al-Mawardi sekurang-kurangnya
seperti yang tertulis dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah diarahkan kepada teori
ketatanegaraan, terutama menyangkut eksistensi kepala negara dan
mekanisme pengangkatan serta pemberhentiannya, akan menjadi fokus
11Karya-karya lain al-Mawardi di bidang politik; 1] Qawanin al-wuzara` wa Siyasah
al-Muluk, dicetak tahun 1929 di Mesir; 2] Tashil al-Nadhar wa Ta’jil al-Dhafar, masih dalam bentuk manuskrip; 3] Nashihah al-Muluk juga dalam bentuk manuskrip, 4] Adab al-Dunya wa al-Din. Lihat juga Mushthafa al-Saqa, ibid., hlm. 6-7. Dalam keempat kitab politik ini, dimensi hukum tidak terlalu tampak. Justru aspek etik-moral dominan mengisi buku tersebut. Artinya, keempat kitab ini merupakan buku etika politik, sementara al-Ahkam al-Sulthaniyyah adalah pedoman konstitusi dan hukum ketatanegaraan.
12Tentu saja yang mempunyai kecenderungan seperti ini bukan hanya al-Mawardi, melainkan ada lagi pakar politik dalam Islam lainnya yang mempunyai kecenderungan sama, baik dari kalangan Sunni maupun Syi’i.
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 5
utama bahasan tulisan ini. Namun, sebelumnya akan dipaparkan sejarah
sosio-politik al-Mawardi.
Biografi Sosio-Politik Al-Mawardi
Al-Mawardi adalah seorang pemikir politik Islam abad ke-5 H. atau ke-
11 M. Beberapa kitab politiknya telah menjadi acuan bagi masyarakat Muslim
Sunni. Dengan demikian, bagi masyarakat politik tertentu, al-Mawardi (365
H.-450 H./974 M.-1058 M.) bukan nama asing. Dalam kancah pemikiran dan
praksis politik, ia sangat disegani lawan maupun kawan.13 Bukan saja karena
tidak merugikan kepentingan-kepentingan pihak lain, melainkan konsep-
konsep yang ditawarkan al-Mawardi mencerminkan sebuah refleksi
pemikiran yang kukuh.14 Ia dikenal sebagai ilmuwan produktif.15 Cukup
banyak karya yang lahir dari tangannya, menyangkut berbagai cabang ilmu,
mulai dari ilmu bahasa, hingga sastra, tafsir, fikih dan ketatanegaraan.
Namun, disiplin ilmu hukum politik ketatanegaraan (al-fiqh al-siyasiy)-lah
tampaknya yang secara khusus mengantarkan kesohoran namanya. Ia lebih
populer dengan pemikiran-pemikiran politiknya ketimbang spesialisasinya
sebagai faqih-qadli yang pernah mencapai karir jabatan tertingginya sebagai
qadli al-qudlat.
Tampaknya, al-Mawardi memiliki ke-khas-an tersendiri yang
membedakannya dengan para pemikir politik pendahulu dan generasi
13Kenyataan ini terlihat, kendatipun al-Mawardi seorang pengikut madzhab Syafi’i
(aliran Sunni), ia tidak hanya disenangi dan disegani penguasa-penguasa Abbasiyah yang memang beraliran Sunni, melainkan juga oleh penguasa-penguasa Buwaihi yang beraliran Syi’ah, dua buah aliran yang sepanjang sejarahnya selalu berseberangan dan berkutat dalam konflik. Usman Abu Bakar dkk., Laporan Penelitian Kolektif Negara dan Pemerintah (Studi Komparatif Pemikiran al-Mawardi dan Ibn al-Farra`), tidak diterbitkan, (Semarang: IAIN Walisongo, 1994), hlm. 22.
14Marzuki Wahid, Latar Historis Narasi Ketatanegaraan al-Mawardi dan Ibnu al-Farra`: Bacaan “Seorang Rakyat” atas Dua Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Cirebon: Jilli, 1997), hlm. 6.
15Salah satu indikator bahwa al-Mawardi adalah seorang ilmuwan yang serba-bisa dapat terlihat dari ragam karya yang dihasilkannya, baik yang sudah dicetak (mathbu’ah) maupun yang masih berbentuk manuskrip (makhthuthah). Karya-karya tersebut di antaranya, adalah [1] al-Hawi al-Kabir, [2] al-Ahkam al-Sulthaniyah, [3] Nashihah al-Muluk, [4] Qawanin al-Wuzara` wa Siyasah al-Mulk, [5] al-Tafsir, [6] al-Iqna’ (Mukhtashar Kitab al-Hawiy), [7] Adab al-Qadli, [8]A’lam al-Nubuwwah, [9]Tashil al-Naddhar wa Ta’jil al-Dhafar, [10] Kitab fiy al-Nahw, [11] al-Amtsal wa al-Hikam, [12] Adab al-Dunya wa al-Din. Lihat Mushthafa al-Saqa, dalam Muqaddimah kitab Adab al-Dunya wa al-Din, hlm. 4-6. Kemudian dalam Tarikh Baghdad disebutkan kitab lain, yatu; [13] al-Buyu’, dan [14] al-Nukat wa al-‘Uyun. Lihat al-Khatib al-Baghdadiy, Tarikh Baghdad, (Beirut: Maktabah Musamma, Tanpa Tahun), hlm. 102
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 6
sesudahnya, seperti Ibn Abi Rabi’ (w. 840 M.),16 Ibnu Qutaybah (w. 889 M.),17
al-Baqillani (w. 403 H./1013 M.),18 al-Baghdadi (w. 429 H./1037),19 al-
Juwaini (w. 478 H./1087 M.),20 al-Ghazali (w. 505 H./1111 M.),21 Ibn
Taymiyah (w. 728 H./1328 M.),22 dan Ibn Khaldun (w. 808 H./1406 M.)23. Al-
Mawardi barangkali bisa disebut sebagai ulama-istana. Ia seorang ulama
yang dekat dengan penguasa (khalifah) Abbasiyah. Selain pernah menabat
qadli di beberapa kota, oleh Khalifah al-Qadir (w. 422 H.) ia diangkat sebagai
qadli al-qudlat, di Ustuwa dekat Nishapur. Sedemikian tinggi tingkat
kedekatannya pada khalifah, al-Mawardi pernah memperoleh tugas khusus
saat Dinasti Buwaihi mulai berkuasa, yakni sebagai penghubung (safir)
antara pemerintah Khalifah al-Qadir dari Daulah Abbasiyah (yang beraliran
Sunni) dengan amir al-umara` dari Dinasti Buwaihi (yang berhaluan Syi’ah).
Tugas ini diperuntukkan bagi penyelesaian konflik-konflik politik yang
berkepanjangan akibat prahara yang berkecamuk antar-daulah saat itu.
Lebih dari karir-karir politik, dalam fatwa hukum pun agaknya al-
Mawardi menjadi orang kepercayaan Khalifah. Kitab al-Iqna’ (mukhtashar
kitab al-Hawi) ditulis al-Mawardi untuk memenuhi permintaan Khalifah al-
Qadir (pada tahun 429 H.). Khalifah meminta empat orang ahli hukum yang
mewakili madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) agar menulis
ikhtisar hukum madzhabnya masing-masing. Al-Mawardi dalam hal ini
16Nama lengkapnya Syihab al-Din Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Rabi’. Pemikiran
politiknya, di antaranya, termuat dalam Suluk al-Malik fiy Tadbir al-Mamalik, (Kairo: Dar al-Sya’ab, 1970).
17Nama kitabnya yang membahas perkembangan pemikiran politik Islam sejak zaman awal sampai abad ke-9 M. adalah al-Imamah wa al-Siyasah.
18Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad ibn al-Thayyib ibn Muhammad ibn Ja’far al-Qasim al-Baqillaniy. Pemikiran politiknya, salah satunya, tertuang dalam al-Tamhid fiy al-Radd ‘ala Mulhidat wa al-Khawarij wa al-Mu’tazilah.
19Nama lengkapnya Abu Manshur Abd al-Qadir ibn Thahir al-Baghdadiy. Percikan pemikiran politiknya, sebagian diwadahi dalam kitab Ushul al-Din.
20Nama lengkapnya Abd. Al-Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwaini, populer dengan sebutan Imam al-Haramain al-Juwaini. Pemikiran politiknya, di antaranya, terdapat dalam Kitab al-Irsyad.
21Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Curahan pemikiran politiknya, di antaranya, terdapat dalam Ihya` ‘Ulum al-Din, al-Iqtishad wa al-I’tiqad, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk.
22Nama lengkapnya Taqiy al-Din Abu al-Abbas ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah. Formulasi pemikiran politiknya yang masyhur terdapat dalam al-Siyasah al-Syar’iyyah fiy Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’iyyah.
23Nama lengkapnya Abu Zaid Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun Waliy al-Din al-Tunisi al-Hadrami. Gagasan politiknya terdapat dalam masterpiece-nya Muqaddimah (dari Kitab al-‘Ibar wa Diwan al-Mubtada` wa al-Khabar fiy Ayyam al-‘Arab wa al-‘Ajam wa al-Barbar wa man ‘asharahum min dzawiy al-Sulthan al-Akbar .
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 7
mewakili madzhab Syafi’i. Dalam upaya ini, al-Mawardi memperoleh gelar
aqdla al-Qudlat dari Khalifah karena karyanya dinilai sebagai karya terbaik.
Meski begitu, kritisisme al-Mawardi tidak luntur dan berubah menjadi
legitimator kehendak-kehendak politik sang penguasa. Sebagai misal, pada
tahun 429 H. Jalal al-Daulah minta diberi gelar al-Sulthan al-Mu’azhzham
Malik al-Umam. Pada saat itu, para fuqaha` dengan gampang melegitimasi
dan menjustifikasi dengan berbagai fatwanya. Berbeda dengan para ahli fikih
itu, al-Mawardi tetap kukuh pada pendiriannya semula bahwa gelar itu hanya
milik Allah. Dia menolak permintaan Jalal al-Daulah itu, walau berimplikasi
pada kerenggangan hubungan antara al-Mawardi dan Jalal al-Daulah.
Semenjak itu, al-Mawardi tidak bertandang ke istana, hingga ia dipanggil oleh
Khalifah. Anehnya, tatkala bertemu Khalifah al-Mawardi tidak mendapatkan
sanksi apapun, bahkan diberi penghormatan atas kejujuran dan keterus-
terangannya.24 Pada setting demikian, di antaranya, karya-karya politik al-
Mawardi ditulis.25
Sumber Kekuasaan Kepala Negara
Prihal asal-muasal (sumber) kekuasaan kepala negara sudah lama
menjadi topik diskusi di kalangan pemikir muslim. Hal yang menarik
perhatian mereka adalah adanya tuntutan dalam kehidupan masyarakat
muslim untuk melembagakan “kepala negara” sebagai salah satu institusi
politik. Peristiwa-peristiwa suksesi politik yang berlangsung pada masa al-
Khulafa’ al-Rasyidun selalu mengundang tanya mengenai keabsahan
pergantian kepemimpinan itu dalam konteks ajaran Islam. Problem yang
sama juga dipertanyakan berkaitan dengan kekuasaan khalifah-khalifah
sesudahnya. Pertanyaannya adalah siapakah sebenarnya yang berhak
menjadi kepala negara? Penyelesaian masalah ini mau tak mau harus terlebih
dahulu tentang siapakah yang memiliki kekuasaan dalam konteks
ketatanegaraan ?
Al-Mawardi melerai masalah di atas dengan mengkombinasikan sisi
teologis yang menyangkut kekuasaan mutlak Tuhan dan sisi politis-
pragmatis yang berkaitan dengan kekuasaan massa. Al-Mawardi mengajukan
24Abd. Hakim Rahman, Visi Politik al-Mawardi tentang Negara dan Pemerintahan,
Tesis S2, Tidak diterbitkan, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1996), hlm. 23. Bandingkan dengan Marzuki Wahid, Latar Historis …, 1997), hlm. 7
25Bahkan disinyalir bahwa penyusunan kitab masterpeice, al-Ahkam al-Sulthaniyah, adalah atas perintah seorang penguasa yang tidak disebut namanya. Lihat Donald Litle, “A New Look at al-Ahkam al-Sulthaniyah”, dalam The Muslim World, No. 1 Vol. LXI, 1981, hlm. 2
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 8
teori bahwa kesepakatan massa merupakan sumber kekuasan negara.
Menurutnya, adalah rakyat (melalui ahl al-hal wa al-‘aqd atau ahl al-ikhtiyar)
yang mempercayakan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai kepala negara
untuk bertindak atas nama negara dalam mengatur kehidupan bersama.
Dengan demikian, selain berhak untuk ditaati, kepala negara mempunyai
kewajiban terhadap rakyatnya, misalnya memberikan perlindungan. Dalam
ilmu politik modern, pandangan al-Mawardi ini disebut teori “kontrak sosial”.
26
Di bagian lain, al-Mawardi juga mengakui bahwa kekuasaan kepala
negara bersumber dari kekuasaan Tuhan yang didelegasikan kepada
manusia pilihannya sebagai penerus kepemimpinan Rasul. Dengan demikian,
al-Mawardi memberikan dua baju kepada kepala negara; baju agama dan
baju politis. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang
pemimpin sebagai pengganti (khalifah) Nabi, untuk menjaga agama (harasah
al-din), dengan disertai mandat politik. Konsekuensinya, seorang kepala
negara di samping sebagai pemimpin politik juga pemimpin agama.
Argumen al-Mawardi tentang konsensus massa sebagai sumber
kekuasaan kepala negara bertolak dari pandangannya mengenai
karakteristik (watak) manusia yang cenderung membutuhkan bantuan dari
sesama. Baginya, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Ia
membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan, demikian al-Mawardi,
dibandingkan dengan binatang pada umumnya, tingkat kebutuhan manusia
terhadap sesama lebih tinggi. Dalam banyak kasus, tidak sedikit binatang
yang bisa bertahan hidup sendirian, sedangkan manusia hanya bisa bertahan
hidup dalam konteks komunal (bersama-sama). Kebutuhan manusia
terhadap sesama adalah mutlak.
Pada sisi lain, menurut al-Mawardi, di antara manusia terdapat
keberagaman watak, bakat, kecenderungan serta kemampuan. Keberagaman
itu, tandas al-Mawardi, yang mendorong manusia untuk bersatu dan saling
membantu, dan pada gilirannya sepakat mendirikan negara. Sebab, jika
setiap manusia memiliki kemampuan, karakter dan kecenderungan yang
sama, maka eksistensi masyarakat (komunitas) tidak akan terbentuk, karena
26Yang menarik tentang hal ini bahwa al-Mawardi mengemukakan teori kontraknya
itu pada abad XI, sedangkan di Eropa teori kontrak sosial baru muncul untuk pertama kalinya pada abad XVI. Uraian tentang teori kontrak sosial ini dapat dibaca dalam Munawir Sazdali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 67-70.
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 9
masing-masing tidak perlu menggantungkan pemenuhan kebutuhannya pada
orang lain.27
Dari paparan itu tampak bahwa al-Mawardi mempertimbangkan
faktor kebutuhan manusia sebagai basis pembentukan negara.28 Ia melihat
kesepakatan warga negara (konsensus) sebagai sumber kekuasaan yang
dalam implementasinya dilimpahkan kepada kepala negara. Harapannya,
agar ia dapat menjamin kelangsungan hidup bersama. Ini berarti kepala
negara bukan lembaga yang bebas mengatur kebutuhan rakyat sesuka
hatinya. Dengan kekuasaan yang diterimanya, kepala negara harus
mengusahakan kemungkinan yang bisa mendatangkan apa yang menjadi
kebutuhan warganya.
Al-Mawardi, tampaknya, tidak terpuaskan oleh pandangannya sendiri
yang menetapkan konsensus rakyat sebagai sumber kekuasaan kepala
negara. Di dalam mukaddimah al-ahkam al-sulthaniyah, ia dengan terus
terang mengakui kemutlakan kekuasaan Tuhan yang merupakan sumber
kekuasaan kepala negara. Berikut ini dikutip pernyataannya:
جلت قدرته ندب لالمة زعيما خلف به النبوة وحاط به الملة وفوض فإن الله…… إليه السياسة ليصدر التدبير عن دين مشروع وتجتمع الكلمة علي رأي متبوع فكانت االمامة أصال عليه إستقرت قواعد الملة وانتظمت به مصالح االمة حتي إستثبتت بها
االمور العامة
Seperti dalam kutipan di atas, al-Mawardi melihat bahwa otoritas
kekuasaan kepala negara itu berasal dari Tuhan. Tuhan mempercayakan
otoritas tersebut kepada kepala negara untuk dapat melanjutkan
kepemimpinan Rasul. Kepercayaan itu tidak saja berkaitan dengan masalah-
masalah keagamaan, tapi juga dengan masalah pemerintahan. Karena al-
Mawardi berpandangan bahwa kehendak Tuhan itu sudah dituangkan dalam
syari’at Islam, maka berarti kekuasaan kepala negara itu bersumber dari
syari’ah.
Paparan di atas mengindikasikan ketegasan al-Mawardi dalam
memandang sumber kekuasaan kepala negara dengan mengombinasikan sisi
teologis dan politis sekaligus. Ia memegang prinsip bahwa pada awalnya
27Al-Mawardi, Adab al-Dunya wa al-Din, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), hlm. 132. 28Teori ini sesungguhnya tidak hanya dinyatakan oleh al-Mawardi. Sebelumnya, al-
Farabi (w. 950 M.) juga mengajukan pendapat yang sama mengenai saling ketergantungan manusia sebagai sebab terbentuknya negara. Secara lebih detail, lihat al-Farabi, Kitab Ara` Ahl al-Madinah al-Fadlilah, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1985), hlm. 117 dan 122
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 10
Tuhan melalui syari’atnya telah mendelegasikan kekuasaan-Nya kepada
kepala negara. Di sisi lain, ia memahami kecenderungan masyarakat manusia
yang secara individual memiliki kemampuan yang berbeda dan mempunyai
kepentingan masing-masing. Untuk mengatur kebersamaannya, manusia
memerlukan kepala negara yang diberi kepercayaan untuk melindungi hak-
hak semua warga negara secara adil.
Kriteria Kepala Negara
Membaca motivasi dan alasan diperlukannya lembaga kepala negara
(imamah) dalam satu komunitas, jelas tanggung jawab seorang kepala negara
tidak ringan. Ia diharapkan bisa menjaga keutuhan “negara” dengan tanpa
membatasi hak-hak dasar setiap pribadi warga dan sekaligus mengusahakan
pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Untuk dapat menjalankan fungsi
kepemimpinannya dengan baik, seorang kepala negara harus memiliki
sejumlah kelebihan.Al-Mawardi menyodorkan beberapa syarat seorang
kepala negara. Syarat-syarat kepala negara itu meliputi:29
1. Bersifat adil (al-‘adalah)
Sifat adil ini, bagi al-Mawardi, adalah fundamental.30 Tanpa al-‘adalah,
kepemimpinan negara tak ideal. Ia mensinyalir, sifat adil ini pertama kali
tercermin dalam sikap pribadi, yang kemudian diharapkan menjelma
dalam kehidupan masyarakat.31 Keadilan kepala negara adalah keadilan
dalam mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya.
29Al-Mawardi, Adab al-Dunya wa al-Din, hlm. 6. 30Sedemikian pentingnya keadilan, sampai-sampai Ibnu Taymiyah mengatakan
bahwa sesungguhnya Tuhan menolong pemerintahan yang adil sekalipun kafir, tetapi tidak menolong pemerintahan yang zalim walaupun muslim. Keadilan walaupun dengan kekafiran memungkinkan kehidupan dunia yang terus berkesinambungan, tetapi kezaliman sungguhpun dengan keislaman tak akan mampu melestarikan kehidupan di dunia ini. Lihat Ibnu Taimiyah, al-Hisbah fiy al-Islam wa Wadlifah al-Hukumah al-Islamiyah, (Tanpa Tempat Penerbit: Dar al-Katib al-‘Arabiy, Tanpa Tahun), hlm. 3 & 81. Dengan mengungkapkan hal itu, Ibnu Taymiyah sesungguhnya hendak mengajukan pandangan bahwa esensi lebih penting daripada bentuk; dan nilai lebih berharga ketimbang simbol. Bagi Ibnu Taymiyah, negara tak lain adalah instrumen mewujudkan keadilan. Maka apapun label, simbol dan bentuk yang dipakai oleh suatu negara dan pemerintahan, sejauh berguna bagi terwujudnya cita-cita keadilan adalah islami dan wajib untuk didukung. Sebaliknya, suatu negara, pemerintahan dengan label, simbol dan bentuk apapun yang cenderung selalu melecehkan cita keadilan dan kepentingan rakyat banyak adalah tidak islami dan tidak perlu ditaati.
31Umar ibn Khattab pernah memungut sebagian harta kekayaan pejabat (gubernur) yang memerintah di daerah makmur, dan kemudian membagi-bagikannya secara adil-merata kepada pejabat-pejabat yang memerintah di daerah-daerah yang miskin. Ibnu Taymiyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah, hlm. 45-47.
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 11
2. Berpengetahuan (al-‘alim)
Pengetahuan yang luas dibutuhkan untuk menopang kemampuan kepala
negara dalam berjihad dan berijtihad. Dalam proses pengambilan
keputusan, ijtihad seorang kepala negara mutlak diperlukan.32
3. Memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara secara sempurna,
sehingga ia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat
mengkomunikasikannya dengan baik dalam proses penentuan hukum .
4. Mempunyai kondisi fisik yang sehat.
5. Memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur
kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum.
6. Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan
untuk mempertahankannya dari serangan musuh.
7. Berasal dari keturunan quraisy 33
Persyaratan yang terakhir ini menurut al-Mawardi berdasarkan ketentuan
yang disepakati umum.
32Di sisi lain, mestinya al-Mawardi menyadari bahwa kepemimpinan pasca-al-
Khulafa` al-Rasyidun tidak lagi dipegang oleh orang yang berpredikat sebagai ulama dan umara` secara sekaligus. Pada era ini, ulama bertindak sebagai pendamping umara`. Dalam hal itu, kelihatan idealisme al-Mawardi untuk menjadikan al-Khulafa` al-Rasyidun sebagai acuan utamanya.
33Para penulis Barat menilai bahwa persyaratan itu sengaja diungkap al-Mawardi untuk melanggengkan kekuasaan Bani Abbas yang telah dirongrong Bani Buwaih dan Bani Fatimiyah yang Syi’ah. Ini juga menutup kemungkinan adanya khalifah dari kalangan non-Arab, seperti orang Persia dan Turki yang pada waktu itu sudah banyak yang mengendalikan roda pemerintahan. Baca Ana K.S Lambton, State and Government in Medieval Islam, (New York: Oxford University Press, 1981), hlm. 83. Al-Mawardi menentang pendapat seorang tokoh Mu’tazilah, Dirar ibn al-Ghatafani (w. 815 M.) yang mengatakan bahwa kepala negara boleh dipilih dari kalangan luar suku quraisy, terbuka untuk umum. Penolakan al-Mawardi didasarkan kepada hadits Nabi, “Imam (kepala negara) harus dari suku quraisy”. Dan hadits inilah yang meredam ambisi tokoh-tokoh Anshar dalam perebutan kepemimpinan umat Islam sepeninggal Nabi Muhammaad. Di samping itu, ada hadits lain, “Pilihlah [pemimpin] dari suku quraisy, dan jadikan dirimu sendiri sebagai pemimpin pemimpin mereka”. Ibnu Khaldun dengan alasan yang lebih rasional, juga mengakui kebenaran hadits-hadits itu. Nabi memang menentukan agar pemimpin negara [umat Islam] berasal dari suku quraisy, karena dalam konstelasi sosial politik pada waktu itu suku quraisy itu memiliki kekuatan yang lebih, yang mampu mengarahkan negara. Konsekuensinya, jika suku quraisy itu memiliki kekuatan yang tangguh, maka kepemimpinan bisa saja diberikan kepada suku (solidaritas kelompok) lain yang lebih kuat, di antara suku-suku yang ada pada masanya. Lihat Muhammad Nafis, The Concept of Imamate in the Works of al-Mawardi, (Montreal: McGill University, Tesis M.A, 1993, tidak diterbitkan), hlm. 49. Bandingkan dengan Affandi Mukhtar, Konsep Kepala Negara…”, hlm. 27
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 12
Mekanisme Pengangkatan Kepala Negara
Tentang pengangkatan kepala negara, ia mengemukakan dua cara.
Pertama, seorang kepala negara mungkin diangkat melalui lembaga pemilih
(ahl al-hall wa al-‘aqd). Kedua, ia mungkin juga diangkat melalui penunjukan
kepala negara yang sedang berkuasa. Al-Mawardi mengajukan beberapa
syarat yang harus dipenuhi setiap anggota pemilih.34 Yaitu, 1] adil, 2]
memiliki pengetahuan yang dapat menentukan siapa yang layak menjadi
kepala negara, 3] memiliki wawasan yang luas dan sikap yang arif sehingga
dapat memilih calon yang paling tepat untuk jabatan kepala negara dan yang
paling mumpuni untuk menangani dan mengelola kepentingan umum.35
Persyaratan yang diberikan al-Mawardi seperti di atas merupakan
persyaratan yang tepat, sebab dari kelompok pemilih itu diharapkan
terwujudnya kepala negara yang cakap, terampil, dan mengetahui mana yang
harus dilakukan untuk kepentingan rakyat. Untuk itu hanya kelompok
tertentu yang berhak menjadi kelompok pemilih kepala negara.
Kemudian, terhadap pengangkatan kepala negara melalui pemilihan
tersebut terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah peserta dalam
pemilihan tersebut.36 Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa ahl al-hall
wa al-‘aqd terdiri dari perwakilan seluruh kota yang ada di bawah kekuasaan
negara. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa pemilihan baru dianggap
sah apabila paling kurang dilakukan lima orang. Seorang di antara mereka
diangkat sebagai imam dengan persetujuan empat orang yang lain. Dasar
pertimbangan kelompok ini ialah bahwa dahulu Abu Bakar diangkat sebagai
khalifah pertama melalui pemilihan lima orang,37 dan bahwa Umar ibn
Khattab telah membentuk dewan formatur yang terdiri dari enam orang
untuk memilih seorang di antara mereka sebagai khalifah penggantinya
dengan persetujuan lima anggota yang lain dari dewan itu.38
34Al-Mawardi tidak memberikan preferensi mana yang terbaik dari dua cara itu.
Kecenderungan dari al-Mawardi penting diungkapkan karena berhubungan erat dengan teori yang dikemukakannya mengenai mekanisme pengangkatan kepala negara melalui pemilihan. Dapat diduga, ia sebenarnya ia menghendaki pemilihan itu. Akan tetapi karena tradisi yang berlaku waktu itu adalah monarchi, ia cukup menyuguhkan cara penunjukan meskipun secara agak terinci memberikan prasyarat yang cukup ketat.
35Lambton, ibid. hlm. 6. 36Lambton, ibid. hlm. 6-7. Bandingkan dengan Munawir Sadzali, op.cit. hlm. 64 37Kelima orang tersebut adalah Umar ibn Khattab, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Usaid ibn
Hudhair, Bisyr ibn Sa’ad dan Salim (seorang budah Abu Khudaifah). 38Keenam orang tersebut adalah Ali ibn Abi Thalib, Utsman ibn Affan, Sa’ad ibn Abi
Waqash, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Awwam, dan Thalhah ibn Ubaidillah. Abdullah ibn
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 13
Ketiga, pemilihan itu sah kalau dilakukan tiga orang; seorang di antara
mereka diangkat sebagai imam dengan persetujuan dua orang yang lain.
Pendapat ini diajukan ulama Kufah.39 Keempat, pemilihan imam sah
walaupun dilakukan satu orang. Menurut kelompok ini, dahulu Ali ibn Abi
Thalib diangkat hanya oleh satu orang, Abbas. Abbas berkata kepada Ali,
“ulurkan tanganmu, aku hendak berbai’at kepadamu”. Menyaksikan apa yang
diperbuat oleh Abbas itu, semua yang hadir serentak berkata, “paman Nabi
telah berbai’at kepada anak pamannya”. Dan semua mengikuti jejak Abbas.40
Al-Mawardi tampaknya tidak memberikan ketentuan secara pasti
mengenai jumlah ahl al-hall wa al-‘aqd.41 Akan tetapi, yang jelas, ia mengakui
keabsahan pemilihan kepala negara melalui lembaga pemilih tersebut. Sebab,
dengan proses ini berarti telah terjadi kontrak pemberian kewenangan
formal bagi seseorang untuk menjadi kepala negara yang bertanggung jawab
dalam upaya menjaga keutuhan dan pemenuhan hidup bersama. Proses kerja
dewan pemilih dimulai dengan meneliti persyaratan para calon kepala
negara. Selanjutnya, kepada calon yang paling memenuhi persyaratan, dewan
melakukan bai’at untuk menjadikannya sebagai pemimpin negara.
Namun, keputusan itu baru berlaku hanya jika ada pernyatan
kesediaan dari calon pemilih. Bagi al-Mawardi, pernyataan kesediaan itu
sungguh perlu dalam proses kontrak antara umat yang diwakili oleh dewan
pemilih dengan calon kepala negara. Di sini tidak boleh ada tekanan dan
paksaan dalam proses tersebut.42 Jika sang calon menyatakan tidak bersedia,
maka ia tidak bisa dipaksa menjadi kepala negara. Sebaliknya, apabila ia
menerima penunjukan, maka dewan pemilih melakukan bai’at kepadanya.
Umar ibn Khattab masuk dalam tim ini, tetapi ia hanya memiliki hak memilih dan tidak memiliki hak untuk dipilih. Baca Ahmad Syalabi, Mausu’ah al-Tarikh al-Islamiy wa al-Hadlarah al-Islamiyah, (Cairo: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyah, 1978), Jilid I, hlm. 422-423.
39Ia mengqiyaskan dengan ke-sah-an suatu akad nikah dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi. Baca al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, hlm. 7
40Dalam hal yang terakhir ini, maka sesungguhnya tidak terjadi pemilihan, melainkan penunjukan.
41Secara sepintas terlihat, lagi-lagi ia berusaha menjadikan praktik al-Khulafa` al-Rasyidun sebagai patokan. Padahal, diakui bahwa usaha itu sulit diwujudkan oleh karena ternyata tidak ada satu model pemilihan pun yang dianggap baku pada masa-masa awal Islam itu. Bahkan al-Maraghi menegaskan bahwa Nabi Muhammad saja tidak memiliki model yang baku dalam bermusyawarah, terlebih para sahabat sesudahnya. Tidak adanya model yang baku justru memberika peluang kepada umat Islam untuk menentukan model tertentu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Baca Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Juz X, hlm. 114.
42Al-Mawardi, al-ahkam al-Sulthaniyah, hlm. 8.
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 14
Dalam hal ini, masyarakatpun harus ikut memberikan bai’at dan mematuhi
kepemimpinanya.43
Masalah mungkin muncul ketika terdapat dua calaon yang sama-sama
memenuhi kriteria pemilihan. Untuk menyelesaikannya, al-Mawardi
berpendapat bahwa calon yang lebih tua usianya memiliki hak yang lebih
terbuka untuk dipilih sebagai kepala negara. Akan tetapi, jika faktor usia
tidak menjadi pertimbangan dan kondisi riil mendukung, calon yang lebih
mudapun dapat dipilih. Kondisi obyektif memang menjadi faktor tatkala
menghadapi pilihan calon-calon yang berimbang kualitasnya. Misalnya, jika
terdapat dua calon yang memenuhi syarat, tetapi yang satu memiliki
keunggulan dalam hal keberanian, sementara yang lain memiliki kelebihan
secara intelektual, maka pemilihan harus diambil dengan
mempertimbangkan situasi riil yang dihadapi oleh negara itu. Apabila
situasinya sedang dihadapkan pada ancaman dan instabilitas, pilihan jatuh
pada calon yang memiliki keberanian. Apabila situasinya menuntut
penyelesaian dalam masalah kebebasan berfikir, pilihan diberikan kepada
calon yang ntelektual.44
Hal lain yang menjadi perhatian al-Mawardi dalam proses pemilihan
ini adalah ketika terjadi kemacetan proses, yang terjadi akibat adanya dua
calon yang memenuhi syarat dan masing-masing memperlihatkan ambisinya.
Menurutnya, mayoritas ulama mengajukan dua solusi.45 Pertama, diundi
sehingga salah seorang di antaranya memperoleh kemenangan yang
kemudian di bai’at. Kedua, dewan pemilih menggunakan hak pilihmya secara
penuh dengan memberikan bai’at kepada siapapun yang menjadi pilihannya
di antara dua calon itu.
Adapun tentang pengangkatan kepala negara melalui penunjukan
kepala negara yang sedang berkuasa, al-Mawardi menyatakan:46
وأما إنعقاد االمامة بعهد من قبله فهو مما إنعقد االجماع على جوازه ووقع االتفاق على صحته المرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما أحدهما أن أبا بكر رضي الله عنه
وأن عمر عهد …عهد بها إلي عمر رضي الله عنه فأثبت المسلمون إمامته بعهده بها إلي أهل الشوري
43Al-Mawardi, ibid. hlm. 7. 44Al-Mawardi, ibid., hlm. 7. 45Al-Mawardi, ibid., hlm. 8 46Al-Mawardi, ibid. hlm. 10.
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 15
Lagi-lagi alasan yang diajukan adalah praktik al-Khulafa’ al-
Rasyidun,47 terutama Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Suksesi
kepemimpinan dari Abu Bakar kepada Umar ibn Khattab lebih didasarkan
kepada pesan (wasiat) Abu Bakar kepada Umar sebagai putra mahkota (waliy
al-‘ahd).48 Begitu juga selanjutnya, Umar ibn Khttab mewasiatkan kepada
beberapa orang sahabat yang kemudian dikenal sebagai “ahl al-syura” untuk
memilih kepala negara.49
Kecuali itu, al-Mawardi memberikan beberapa persyaratan yang
mesti dipenuhi dalam proses penunjukan tersebut. Pertama, orang yang akan
di tunjuk itu--di samping harus memiliki kriteria yang sudah dikemukakan
sebelumnya--juga harus dewasa dan memiliki reputasi baik. Jika, misalnya,
beberapa saat setelah kepala negara yang menunjuknya wafat, ia sudah
dewasa dan sudah dikenal tentang kebaikannya, maka kepemimpinan yang
bersangkutan tidak sah sampai ada pemilihan dan bai’at baru dari dewan
pemilih. Kedua, calon yang diangkat harus hadir pada saat penunjukan atau--
kalau memang ia tidak bisa hadir--ada kepastian bahwa ia masih hidup.
Ketika kepala negara yang menunjuknya meninggal dunia, sementara ia
sendiri belum juga hadir untuk dilakukan bai’at, maka dewan pemilih
47Robert N. Bellah mengungkapkan bahwa pandangan dan praktek politik Islam di
masa al-Khulfa` al-Rasyidun sangat maju dan modern. Letak kemodernannya adalah; 1] semua lapisan warga masyarakat diminta turut serta memberi komitmen, berpartisipasi dan terlibat dalam proses politik, 2] kedudukan pimpinan kenegaraan yang tidak kebal terhadap penilaian kemampuan berdasarkan ukuran-ukuran obyektif, 3] proses suksesi kepemimpinan yang terbuka bagi siapapun dan tidak bersifat hereditatif (turun-temurun). Lihat Robert N. Bellah (ed.), Beyond Belief, (New York: Harper & Row, 1976), hlm. 150-151.
48Al-Qalqasyandi, Ma’atsir al-‘Anaqah fiy Ma’alim al-Khilafah, tahqiq Abdus Satar Ahmad Faraj (Beirut: Alam al-Kutub, Tanpa Tahun), hlm. 48. Akan tetapi, penunjukan terhadap Umar tersebut dilakukan setelah lebih dahulu Abu Bakar berkonsultasi secara informal kepada beberapa pemuka umat Islam. Penunjukan tersebut kemudian diikuti bai’at atau pengambilan sumpah setia dari orang-orang yang ada di tempat tersebut atas nama seluruh umat Islam. Hal ini dilakukan ketika Abu Bakar masih hidup. Lihat Montgomery Watt, Politik Islam dalam Lintasan Sejarah, terjemah Helmi Ali dan Muntaha Azhari, (Jakarta: P3M, 1988), hlm. 55.
49Sebelum wafat, Umar berwasiat, “Seandainya Abu Ubadillah ibn Jarrah masih hidup, jabatan khalifah akan saya serahkan kepadanya. Karena dia sudah meninggal, saya tidak bisa menunjuk seseorang. Masalah ini akan saya serahkan kepada enam tokoh sebagai dewan formatur. Anak saya, Abdullah ibn Umar, masuk dalam tim, tetapi tidak boleh dipilih. Dari Baniy ‘Ady cukup saya saja yang menjadi khalifah. Enam orang tersebut, seperti dikemukakan sebelumnya, adalah Ali, Utsman, Abdurrahman ibn ‘Auf, Sa’ad ibn Abi Waqash, Zubair ibn Awwam, Thalhah ibn Ubaidillah. Dalam waktu empat hari sudah harus ada keputusan mengenai pengganti Khalifah. Jika belum, maka ketua tim segera mengambil kebijaksanaan. Siapa yang tidak menyetujui apa yang sudah disepakati bunuhlah dia”. Baca Ahmad Syalabi, op.cit.
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 16
bertanggung jawab untuk mengangkat orang lain sebagai pejabat pelaksana
tugas-tugas kepala negara.50
Tampaknya, al-Mawardi menghendaki adanya perlindungan bagi
masalah-masalah kenegaraan, sehingga tidak perlu terjadi kekacauan akibat
situasi yang tidak menentu Namun, al-Mawardi tidak menentukan tenggang
waktu sampai kapan atau berapa lama ketidakhadiran kepala negara itu bisa
ditolerir sehingga tidak membatalkan pengangkatannya sebagai kepala
negara.51
Pada dasarnya, kepala negara yang sedang berkuasa boleh dari
kalangan keluarga sendiri. Tanpa memberikan komentar, al-Mawardi
menyajikan beberapa pendapat sebagai berikut:52
Pertama, kepala negara yang sedang berkuasa tidak diperkenankan menunjuk anak atau ayahnya sebagai pengganti, tanpa dimusyawarahkan (bedakan dengan dikonsultasikan !) melalui forum ahl al-hall wa al-‘aqd atau ahl al-ikhtiyar. Alasan kelompok ini, masalah penunjukan ini sama dengan kesaksian kepada anaknya atau sebaliknya. Tujuannya adalah agar terhindar dari jebakan subyektifitas. Kedua, kepala negara yang sedang berkuasa dibenarkan menunjuk anak atau ayahnya sebagai penggantinya. Pasalnya, kepala negara--ketika menunjuknya sebagai pengganti--berkedudukan sebagai amir al-ummah yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan mutlak. Karena itu, tidak perlu dilihat unsur kekeluargaannya, melainkan unsur penguasanya. Ketiga, penunjukan kepala negara hanya dibenarkan kepada ayahnya tidak sebaliknya. Artinya, kepala negara tidak boleh menunjuk anaknya sebagai penggantinya. Dalihnya, karena kecenderungan untuk menunjuk anak jauh lebih besar ketimbang menunjuk ayah.
Mestinya al-Mawardi melakukan tarjih terhadap tiga pendapat di atas.
Namun, oleh karena situasinya tidak cukup kondusif, terpaksa ia tidak
melakukannya. Sesungguhnya, dengan diajukannya pendapat pertama dan
ketiga bisa diduga bahwa ia sendiri condong untuk mengatakan bahwa kedua
pendapat tersebut adalah rajih. Implikasi terjauh dari kecenderungan ini, ia
harus menyatakan bahwa khalifah tidak dibenarkan mengangkat putera
mahkota. Agaknya, ia tidak berani untuk mengemukakan pendapatnya itu. Ia
tak mungkin menentang tradisi dan konvensi khilafah abbasiyah.53
50Al-Mawardi, ibid., hlm. 11 51Muhammad Nafis, The Concept …”, hlm. 54. 52Al-Mawardi, ibid. hlm. 12. 53Kecenderungan absolut pada kekuasaan Abbasiyah ditunjukkan, umpamanya, oleh
proses suksesi yang berlangsung saat itu. Lembaga semacam ahl al-hall wa al-‘aqd kurang berfungsi.
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 17
Hal lain yang cukup menarik adalah mengenai dua orang calon
pengganti yang ditunjuk kepala negara yang sedang berkuasa dalam rangka
melanjutkan kepemimpinan berikutnya. Dengan merujuk pada kebijakan
Nabi Muhammaad tatkala mengangkat lebih dari seorang pengganti panglima
tentara muslim pada perang mu`tah, al-Mawardi mengakui keabsahan
penunjukan seperti itu. Praktik Nabi Muhammad dalam bidang
kepemimpinan militer ini, menurutnya, bisa dijadikan patokan untuk
mempraktekkan cara yang sama dalam bidang kenegaraan.54
Di samping itu, ada dua peristiwa lain yang bisa dijadikan
yuresprudensi; masing-masing pada masa Umawiyah dan Abbasiyah. Pada
masa Umawiyah, Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik menunjuk Umar ibn
Abdul Aziz sebagai penggantinya dan Yazid ibn Abdul Malik sebagai
pengganti Umar. Sedangkan pada masa Abbasiyah, adalah Harun al-Rasyid
yang mengangkat tiga anaknya; al-Amin, al-Makmun, dan al-Muktamin untuk
berturut-turut menjadi kepala negara (khalifah) sesudahnya.55
Sikap al-Mawadi ini tidak luput dari kritik para penulis modern.
Qomaruddin Khan, misalnya, mengatakan bahwa teori al-Mawardi seperti
inilah yang membuat cita-cita politik umat Islam pasca-al-Khulafa` al-
Rasyidun menjadi buyar kembali. Setiap penguasa muslim berusaha untuk
melestarikan dinastinya. Itulah yang kita saksikan sampai dihapuskannya
sistem khilafah oleh Musthafa Kemal di Turki.56
Pemberhentian Kepala Negara
Tidak sebagaimana dalam pengangkatan kepala negara, dalam hal
pemberhentian kepala negara al-Mawardi tidak menyuguhkan resep dan
mekanisme pemberhentian atau penggantian kepala negara. Ia hanya
berpendapat jika ternyata kepala negara telah menyimpang dari nilai-nilai
moral agama, maka rakyat berhak untuk menyatakan”mosi tidak percaya”.
Secara tegas, al-Mawardi mensinyalir, seorang kepala negara dapat
diturunkan dari kursi kekuasaannya kalau ternyata sudah keluar dari cita
keadilan,57 hilangnya panca indera,58 atau organ-organ tubuh yang lain59 atau
54Al-Mawardi, ibid., 18. ِ
55Al-Mawardi, ibid., 13 56Qamaruddin Khan, Al-Mawardi’s Theory of the State, Delhi: Idarah al-Adabiyah,
1979, hlm. 19. 57Dimaksud dengan penyimpangan tersebut adalah fisq; Pertama, suka
melaksanakan kemungkaran dengan memperturutkan hawa nafsu. Kedua, menakwil ayat-ayat mutasyabihat, sehingga menyimpang dari kebenaran (pendapat mayoritas). Yang terakhir ini masih diperselisihkan para ulama. Baca, al-Mawardi, ibid., hlm. 17.
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 18
tidak cakap bertindak.60 Al-Mawardi sampai disini kehilangan jejak dan
berhenti tidak meneruskan penjelajahan lebih lanjut. Sehingga, bagaimana
jika kepala negara menyimpang dari amanat rakyat ? Tambahan pula, ia tidak
menjelaskan tentang bagaimana cara atau mekanisme pemakzulan seorang
kepala negara yang sudah dipandang tidak kridibel untuk memimpin sebuah
negara. Tidak jelas pula, siapa yang harus melakukan pemakzulan itu ?
Tampaknya, masalah ini lepas dari amatan dan kajian al-Mawardi. Padahal
beberapa pokok soal ini sangat penting dikemukakan untuk mengetahui
sejauh mana hak pemberi mandat--dalam hal ini rakyat--terhadap
mandatarisnya. Dari sini terlihat, al-Mawardi tidak berpretensi untuk
mempersoalkan apa yang sudah baku atau dibakukan menyangkut
absolusitas seorang khalifah. Namun, teori al-Mawardi tentang kemungkinan
adanya pemberhentian kepala negara--disaat khalifah masih absolut--sudah
dapat dikatakan sebagai langkah maju dan berani.
Penting dicatat bahwa al-Mawardi lah satu-satunya dari enam pemikir
politik Islam sejak zaman klasik sampai zaman pertengahan (Ibnu Abi Rabi’,
al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun) yang
berpendapat tentang kemungkinan dilengserkannya seorang kepala negara
jika ternyata tidak mampu lagi untuk melaksanakan tugas, baik disebabkan
oleh soal moral maupun soal-soal lain. Apa yang telah diberikan dan
dilakukan al-Mawardi, itulah andil dia yang sangat berharga. Selanjutnya, dia
sendiri berhak bertanya apa kemudian andil kita. [..]
58Berkaitan dengan kehilangan panca indera, al-Mawardi membagi kepada tiga
bagian. Pertama, dapat mencegah atau menghalangi imamah, seperti hilang akal (gila), atau hilangnya penglihatan (buta). Kedua, tidak dapat menghilangkan imamah seperti hilangnya daya cium pada hidung, atau hilangnya daya rasa pada lidah. Ketiga, masih diperselisihkan para ulama, antara dapat dan tidaknya menggagalkan imamah, seperti tuli atau bisu. Baca al-Mawardi, ibid., hlm. 17-18.
59Sedangkan menyangkut hilangnya anggota badan, al-Mawardi mengklasifikasi kepada empat macam. Pertama, tidak dapat mencegah keabsahan akad imamah, seperti hilangnya penis atau hilangnya testis. Kedua, dapat mencegah akad imamah dan keberlangsungannya, seperti hilangnya dua tangan atau dua kaki. Ketiga, dapat mencegah akad imamah dan diperselisihkan dan diperselisihkan tentang keberlangsungannya, seperti hilangnya satu tangan. Keempat, tidak dapat mencegah keberlangsungan imamah dan masih diperselisihkan tentang akadnya, seperti terpotongnya hidung. Baca al-Mawardi, ibid., hlm. 19.
60Adapun tentang ketidak cakapan bertindak al-Mawardi mengelompokkan kepada dua macam kategori. Pertama, ketidak cakapan bertindak itu disebabkan karena telah dikuasai oleh orang-orang terdekatnya, semantara tindakan mereka sudah keluar ajaran agamaa. Kedua, imam sudah terkooptasi oleh musuh-musuh yang kuat dan ia tidak bisa keluar dari belenggu tersebut. Dengan kedua sebab ini, seorang imam dapat di-makzul-kan. Baca, al-Mawardi, ibid., hlm. 20.
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 19
DAFTAR PUSTAKA
Abd. Hakim Rahman, Visi Politik al-Mawardi tentang Negara dan
Pemerintahan, Tesis S2, Tidak diterbitkan, (Jakarta: IAIN Syarif
Hidayatullah, 1996.
Affandi Mukhtar, Konsep Kepala Negara (Imamah) dalam Pandangan Politik
Al-Mawardi, Cirebon: Jilli, 1997.
Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa
Tahun
Ahmad Syalabi, Mausu’ah al-Tarikh al-Islamiy wa al-Hadlarah al-Islamiyah,
Cairo: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyah, 1978
Al-Farabi, Kitab Ara` Ahl al-Madinah al-Fadlilah, Beirut: Dar al-Masyriq, 1985.
Al-Khatib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, Beirut: Maktabah Musamma, Tanpa
Tahun.
Al-Mawardi, Adab al-Dunya wa al-Din, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.
Al-Qalqasyandi, Ma’atsir al-‘Anaqah fiy Ma’alim al-Khilafah, tahqiq Abdus
Satar Ahmad Faraj, Beirut: Alam al-Kutub, Tanpa Tahun.
Ana K.S Lambton, State and Government in Medieval Islam, New York: Oxford
University Press, 1981.
Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Jakarta:
Gramedia, 1997.
Din Syamsuddin, Hak-Hak Rakyat Warga Negara dalam Perspektif Sejarah
Kekuasaan Negara-Agama, dalam Agama dan Hak Rakyat, Jakarta:
P3M, 1993.
Donald Litle, “A New Look at al-Ahkam al-Sulthaniyah”, dalam The Muslim
World, No. 1 Vol. LXI, 1981.
Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Beirut: Dar al-Jil, Tanpa Tahun.
Ibnu Taimiyah, al-Hisbah fiy al-Islam wa Wadlifah al-Hukumah al-Islamiyah,
Tanpa Tempat Penerbit: Dar al-Katib al-‘Arabiy, Tanpa Tahun
Ibnu Taymiyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah fiy Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah, cet.
IV, Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1979.
Ibrahim Hosen, Fiqh Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik, dalam
Ulumul Qur`an, Jakarta: 1992, No.2 Vol. IV.
J.J von Schmid, Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum, (Jakarta:
Pustaka Sardjana, 1965.
John H Mikhail, Mawardi: A Study in Islamic Political Thought, (Disertasi PhD,
Harvard University, 1986.
Abd Moqsith, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara
JAUHAR, VOLUME 2, NO.1, JUNI 2001 20
Marzuki Wahid, Latar Historis Narasi Ketatanegaraan al-Mawardi dan Ibnu
al-Farra`: Bacaan “Seorang Rakyat” atas Dua Kitab al-Ahkam al-
Sulthaniyah, Cirebon: Jilli, 1997.
Montgomery Watt, Politik Islam dalam Lintasan Sejarah, terjemah Helmi Ali
dan Muntaha Azhari, Jakarta: P3M, 1988.
Muhammad Nafis, The Concept of Imamate in the Works of al-Mawardi,
Montreal: McGill University, Tesis M.A, 1993, tidak diterbitkan.
Munawir Sazdali, Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI Press, 1993
Mushthafa al-Saqa (editor) dalam al-Mawardi, Adab al-Dunya wa al-Din,
Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.
Qamaruddin Khan, Al-Mawardi’s Theory of the State, Delhi: Idarah al-
Adabiyah, 1979.
Robert N. Bellah (ed.), Beyond Belief, New York: Harper & Row, 1976.
Usman Abu Bakar dkk., Laporan Penelitian Kolektif Negara dan Pemerintah
(Studi Komparatif Pemikiran al-Mawardi dan Ibn al-Farra`), tidak
diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 1994.