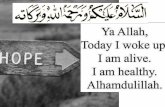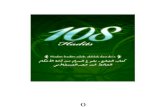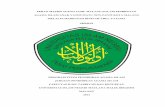Masjid jami part 2
-
Upload
pt-likers-ficecom -
Category
Documents
-
view
99 -
download
1
Transcript of Masjid jami part 2

Masjid Jami Tua Palopo
1. Sejarah
Sesuai namanya, Masjid Jami Tua Palopo, masjid ini berusia sangat tua, diperkirakan berdiri pada tahun 1604 M. Artinya, usia masjid ini sudah lebih dari empat abad. Masjid Palopo merupakan masjid kerajaan yang didirikan ketika Kerajaan Luwu sedang berada dalam masa kejayaannya. Saat itu, yang berkuasa di Luwu adalah Datu Payung Luwu XVI Pati Pasaung Toampanangi Sultan Abdullah Matinroe. Sejarahnya, ketika ia naik menggantikan ayahnya pada tahun 1604 M, ia memindahkan ibukota kerajaan dari Patimang ke Ware, dengan alasan Ware berada di pantai dan lebih dekat dengan pelabuhan, sehingga aktifitas ekonomi bisa lebih mudah dilakukan. Sumber sejarah lain ada juga yang mengkaitkan perpindahan ibukota kerajaan ini dengan kepentingan untuk penyebaran Islam. Jika pendapat ini benar, maka perpindahan tersebut juga menandakan bahwa pengaruh Islam semakin menguat dalam Kerajaan Luwu. Hal ini bisa dilihat dari konstruksi kompleks ibukota kerajaan yang baru, di mana masjid dan istana dibangun berdekatan membentuk satu komplek kerajaan. Satu unsur lagi yang dibangun dalam kompleks kerajaan Luwu adalah lapangan luas yang terbuka (alun-alun). Struktur dan tata letak pusat pemerintahan yang seperti ini mirip dengan struktur dan tata letak kerajaan Islam di Jawa. Seiring dengan penamaan masjid ini dengan Masjid Palopo, daerah tersebut kemudian juga disebut sebagai daerah Palopo. Maka, sejak tahun 1604 M tersebut, daerah Ware ini berubah nama menjadi Palopo. Kata Palopo berasal dari bahasa Bugis dan Luwu yang memiliki dua arti. Arti pertama adalah penganan gula ketan dan air gula merah yang dicampur; sedangkan arti yang kedua adalah memasukkan pasak ke dalam tiang bangunan. Kedua makna kata ini memiliki relasi dengan proses pembangunan Masjid Jami Tua ini. Oleh sebab itulah, timbul kemudian inspirasi untuk menamakan masjid yang dibangun tersebut dengan Palopo. Demikianlah sejarah asal usul munculnya kata Palopo.
2. Arsirektur
Arsitektur Masjid Tua Palopo ini sangat unik. Ada empat unsur penting yang bersebati (melekat) dalam konstruksi masjid tua ini, yaitu unsur lokal Bugis, Jawa, Hindu dan Islam.
a. Unsur Lokal Bugis

Unsur ini terlihat pada struktur bangunan masjid secara keseluruhan yang terdiri dari tiga susun yang mengikuti konsep rumah panggung. Konsep tiga susun ini juga konsisten diterapkan pada bagian lainnya, seperti atap dan hiasannya yang terdiri dari tiga susun; tiang penyangga juga terdiri dari tiga susun, yaitu pallanga (umpak), alliri possi (tiang pusat) dan soddu; dinding tiga susun yang ditandai oleh bentuk pelipit (gerigi); dan pewarnaan tiang bangunan yang bersusun tiga dari atas ke bawah, dimulai dari warna hijau, putih dan coklat.
b. Unsur Lokal JawaUnsur ini terlihat pada bagian atap, yang dipengaruhi oleh atap rumah joglo
Jawa yang berbentuk piramida bertumpuk tiga atau sering disebut tajug. Dua tumpang atap pada bagian bawah disangga oleh empat tiang, dalam konstruksi Jawa sering disebut sokoguru. Sedangkan atap piramida paling atas disangga oleh kolom (pilar) tunggal dari kayu cinna gori (Cinaduri) yang berdiameter 90 centimeter. Pada puncak atap masjid, terdapat hiasan dari keramik berwarna biru yang diperkirakan berasal dari Cina.
Terdapat dua pendapat seputar bentuk atap Masjid Tua Palopo ini[2]. Yang pertama mengatakan bahwa atap tersebut mendapat pengaruh dari arsitektur Jawa. Sementara yang kedua menolak pendapat itu, dengan berargumen bahwa bentuk tersebut merupakan pengembangan dari konsep lokal masyarakat Sulawesi Selatan sendiri. Namun demikian, mengingat hubungan antara kedua masyarakat telah terjalin begitu lama, wajar jika terjadi akulturasi budaya.
Susunan atap pertama dan kedua disangga empat tiang yang terbuat dari kayu cengaduri, dengan tinggi 8,5 meter dan berdiameter 90 cm. Keempat tiang tersebut dalam konsep Jawa disebut sokoguru. Sementara itu, atap paling atas ditopang dengan satu tiang terbuat dari kayu yang sama. Dalam kearifan lokal Sulawesi Selatan, satu tiang penyangga atap paling atas yang didukung oleh empat tiang lainnya merefleksikan yang sentral (wara) dikelilingi oleh unsur-unsur lain di luar yang sentral (palili).[2]