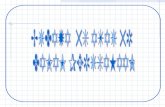makalahBAB1-BAB4lampiran
-
Upload
chandra-kurniawan -
Category
Documents
-
view
76 -
download
0
description
Transcript of makalahBAB1-BAB4lampiran
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
International labour Organization (ILO) memperkirakan di seluruh dunia
ada 6000 pekerja kehilangan nyawa setiap hari akibat kecelakaan, luka-luka,
dan penyakit akibat resiko kerja. Selain itu setiap tahun 270 juta pekerja
menderita luka parah dan 160 juta lainnya mengalami penyakit jangka panjang
ataupun pendek terkait dengan pekerjaan mereka. Banyak perusahaan tidak
menyediakan alat keselamatan dan pengaman untuk pekerjanya. dan banyak
pengusaha juga mengabaikan K3 karena enggan mengeluarkan biaya
tambahan.Hukum sudah dengan ketat mengaturnya cuma implementasi di lapa-
ngan tidak semudah itu. Sekarang semua harus menyadari bahwa K3 sangat
penting artinya untuk diiplementasikan dengan nyata di lapangan demi perusa-
haan maupun pekerja sendiri.
Di era globalisasi dan pasar bebas WTO dan GATT yang akan berlaku tahun
2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu
prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan
jasa antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk
bangsa Indonesia.
Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu
bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari
pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat
meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.Kecelakaan kerja tidak saja
menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha,
tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak
lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas.
Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) di kalangan
petugas kesehatan dan non kesehatan kesehatan di Indonesia belum terekam
1
dengan baik. Jika kita pelajari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di
beberapa negara maju (dari beberapa pengamatan) menunjukan kecenderungan
peningkatan prevalensi. Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena
kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang
kurang memadai. Banyak pekerja yang meremehkan risiko kerja, sehingga
tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia.
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses
produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah
Indonesia merdeka menimbulkan konsekwensi meningkatkan intensitas kerja
yang mengakibatkan pula meningkatnya risiko kecelakaan di lingkungan
kerja.Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi
dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun
jenis kecelakaannya.
Setiap tahun di dunia terjadi 270 juta kecelakaan kerja, 160 juta pekerja
menderita penyakit akibatkerja, kematian 2.2 juta dan kerugian finansial
sebesar 1.25 triliun USD. Sedangkan di Indonesiamenurut data PT. Jamsostek
(Persero) dalam periode 2002-2005 terjadi lebih dari 300 ribu kecelakaankerja,
5000 kematian, 500 cacat tetap dan konpensasi lebih dari Rp. 550 milyar.
Kompensasi ini adalahsebagian dari kerugian langsung dan 7.5 juta pekerja
sektor formal yang aktif sebagai pesertaJamsostek. Diperkirakan kerugian tidak
langsung dari seluruh sektor formal lebih dari Rp. 2 triliun,dimana sebagian
besar merupakan kerugian dunia usaha.(DK3N,2007) Melihat angka-angka
tersebuttentu saja bukan suatu hal yang membanggakan, akan tetapi hendaklah
dapat menjadi pemicu bagidunia usaha dan kita semua untuk bersama-sama
mencegah dan mengendalikannya
Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perusahaan di Indonesia
secara umum diperkirakan termasuk rendah. Pada tahun 2005 Indonesia
menempati posisi yang buruk jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina dan
Thailand. Kondisi tersebut mencerminkan kesiapan daya saing perusahaan
Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah. Indonesia akan sulit
2
menghadapi pasar global karena mengalami ketidakefisienan pemanfaatan
tenaga kerja (produktivitas kerja yang rendah). Padahal kemajuan perusahaan
sangat ditentukan peranan mutu tenaga kerjanya. Karena itu disamping
perhatian perusahaan, pemerintah juga perlu memfasilitasi dengan peraturan
atau aturan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nuansanya harus
bersifat manusiawi atau bermartabat.
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kesehatan lingkungan yang diterapkan di Rumah Sakit Islam
Malang?
2. Bagaimana pengelolaan limbah yang dilakukan di Rumah Sakit Islam
Malang?
1.3. Tujuan
1. Memahami tentang kesehatan lingkungan yang diterapkan di tingkat rumah
sakit.
2. Memahami tentang pengelolaan limbah yang dilakukan di tingkatrumah
sakit.
1.4. Manfaat
1. Bagi penelaah
Dapat memahami topik bahasan dalam materi kedokteran komunitas ini,
yang meliputi: kesehatan lingkungan dan pengelolaan limbah rumah sakit.
2. Bagi pembaca
Dapat mengetahui topik bahasan dalam materikedokteran komunitas ini,
yang meliputi: kesehatan lingkungan dan pengelolaan limbah rumah sakit.
3. Bagi ilmu pengetahuan
Dapat memberikan kontribusi tentang ilmu pengetahuan topik bahasan
dalamkedokteran komunitas materi ini, yang meliputi: kesehatan
lingkungan dan pengelolaan limbah rumah sakit.
3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Sistem Manajemen K3 (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen
secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung
jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi
pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko
yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang
aman, efisien, dan efektif. (Permen 05/MEN/1996)
A. Tujuan penerapan SMK3 :
1. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya
sebagai manusia
2. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja
3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi
globalisasi
4. Proteksi terhadap industri dalam negeri
5. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional
6. Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor
nasional
7. Meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem
8. Pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan
penerapan K3L.
4
B. SMK3 terdiri dari 5 prinsip dasar dan 12 elemen
1. Prinsip Dasar
Penetapan kebijakan K3
Perencanaan penerapan K3
Penerapan K3
Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja K3
Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara
berkesinambungan
2. Elemen
Pembangunan dan pemeliharaan komitmen
Pendokumentasian strategi
Peninjauan ulang desain dan kontrak
Pengendalian dokumen
Pembelian
Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
Standar pemantauan
Pelaporan dan perbaikan
Pengelolaan material dan perpindahannya
Pengumpulan dan penggunaan data
Audit SMK3
Pengembangan kemampuan dan ketrampilan
Berdasarkan Pedoman ILO tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja yang mencakup langkah-langkah berikut:
1. Membuat kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip K3 dan partisipasi
pekerja serta menetapkan unsur-unsur utama program.
5
2. Pengorganisasian suatu struktur untuk menerapkan kebijakan, termasuk
garis tanggung jawab dan akuntabilitas, kompetensi dan pelatihan,
pencatatan dan komunikasi kejadian.
3. Perencanaan dan penerapan, termasuk tujuan, peninjauan ulang,
perencanaan, pengembangan dan penerapan sistem.
4. Evaluasi pemantauan dan pengukuran kinerja, investigasi kecelakaan,
gangguan kesehatan, penyakit dan kejadian yang berhubungan dengan
pekerjaan, audit dan peninjauan ulang manajemen.
5. Tindakan perbaikan melalui upaya-upaya pencegahan dan korektif,
pembaruan dan revisi yang terus menerus terhadap kebijakan, sistem dan
tehnik untuk mencegah dan mengendalikan kecelakaan, gangguan
kesehatan, penyakit dan kejadian-kejadian berbahaya yang berhubungan
dengan pekerjaan.
B. Sanitasi Lingkungan
1. Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
I. Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman Rumah Sakit
A. Pengertian
1. Ruang bangunan dan halaman rumah sakit adalah semua ruang/unit
dan halaman yang ada di dalam batas pagar rumah sakit (bangunan
fisik dan kelengkapannya) yang dipergunakan untuk berbagai
keperluan dan kegiatan rumah sakit.
2. Pencahayaan di dalam ruang bangunan rumah sakit adalah intensita
penyinaran pada suatu bidang kerja yang ada di dalam ruang
bangunan rumah sakit yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
secara efektif
3. Pengawasan ruang bangunan adalah aliran udara di dalam ruang
banguna yang memadai untuk menjamin kesehatan penghuni
ruangan.
6
4. Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga
mengganggu dan/atau membahayakan kesehatan.
5. Kebersihan ruang bangunan dan halaman adalah suatu keadaan atau
kondisi ruang bangunan dan halaman bebas dari bahaya dan risiko
minimal untuk terjadinya infeksi silang, dan masalah kesehatan dan
keselamatan kerja.
B. Persyaratan
1. Lingkungan Bangunan Rumah Sakit
a. Lingkungan bangunan rumah sakit harus mempunyai batas yang
kelas, dilengkapi dengan agar yang kuat dan tidak
memungkinkan orang atau binatang peliharaan keluar masuk
dengan bebas.
b. Luas lahan bangunan dan halaman harus disesuaikan dengan luas
lahan keseluruhan sehingga tersedia tempat parkir yang memadai
dan dilengkapi dengan rambu parkir.
c. Lingkungan bangunan rumah sakit harus bebas dari banjir. Jika
berlokasi di daerah banjir harus menyediakan fasilitas/ teknologi
untuk mengatasinya.
d. Lingkungan rumah sakit harus merupakan kawasan bebas rokok
e. Lingkungan bangunan rumah sakit harus dilengkapi penerangan
dengan intensitas cahaya yang cukup.
f. Lingkungan rumah sakit harus tidak berdebu, tidak becek, atau
tidak terdapat genangan air dan dibuat landai menuju ke saluran
terbuka atau tertutup, tersedia lubang penerima air masuk dan
disesuaikan dengan luas halaman
g. Saluran air limbah domestik dan limbah medis harus tertutup dan
terpisah, masing-masing dihubungkan langsung dengan instalasi
pengolahan limbah.
7
h. Di tempat parkir, halaman, ruang tunggu, dan tempat-tempat
tertentu yang menghasilkan sampah harus disediakan tempat
sampah.
i. Lingkungan, ruang, dan bangunan rumah sakit harus selalu
dalam keadaan bersih dan tersedia fasilitas sanitasi secara
kualitas dan kuantitas yang memenuhi persyaratan kesehatan,
sehingga tidak memungkinkan sebagai tempat bersarang dan
berkembang biaknya serangga, binatang pengerat, dan binatang
pengganggu lainnya.
2. Konstruksi Bangunan Rumah Sakit
a. Lantai
Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air,
permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah
dibersihkan.
Lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai
kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan air
limbah
Pertemuan lantai dengan dinding harus berbentuk
konus/lengkung agar mudah dibersihkan
b. Dinding
Permukaan dinding harus kuat, rata, berwarna terang dan
menggunakan cat yang tidak luntur serta tidak
menggunakan cat yang mengandung logam berat
c. Ventilasi
Ventilasi alamiah harus dapat menjamin aliran udara di
dalam kamar/ruang dengan baik.
Luas ventilasi alamiah minimum 15 % dari luas lantai
Bila ventilasi alamiah tidak dapat menjamin adanya
pergantian udara dengan baik, kamar atau ruang harus
dilengkapi dengan penghawaan buatan/ mekanis.
8
Penggunaan ventilasi buatan/ mekanis harus disesuaikan
dengan peruntukkan ruangan.
d. Atap
Atap harus kuat, tidak bocor, dan tidak menjadi tempat
perindukan serangga, tikus, dan binatang pengganggu
lainnya.
Atap yang lebih tinggi dari 10 meter harus dilengkapi
penangkal petir.
e. Langit-langit
Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan mudah
dibersihkan.
Langit-langit tingginya minimal 2,70 meter dari lantai.
Kerangka langit-langit harus kuat dan bila terbuat dari kayu
harus anti rayap.
f. Konstruksi
Balkon, beranda, dan talang harus sedemikian sehingga
tidak terjadi genangan air yang dapat menjadi tempat
perindukan nyamuk Aedes.
g. Pintu
Pintu harus kuat, cukup tinggi, cukup lebar, dan dapat
mencegah masuknya serangga, tikus, dan binatang
pengganggu lainnya
h. Jaringan Instalasi
Pemasangan jaringan instalasi air minum, air bersih, air
limbah, gas, listrik, sistem pengawasan, sarana
telekomunikasi, dan lain-lain harus memenuhi persyaratan
teknis kesehatan agar aman digunakan untuk tujuan
pelayanan kesehatan.
9
Pemasangan pipa air minum tidak boleh bersilangan
dengan pipa air limbah dan tidak boleh bertekanan negatif
untuk menghindari pencemaran air minum.
i. Lalu Lintas Antar Ruangan
Pembagian ruangan dan lalu lintas antar ruangan harus
didisain sedemikian rupa dan dilengkapi dengan petunjuk
letak ruangan, sehingga memudahkan hubungan dan
komunikasi antar ruangan serta menghindari risiko
terjadinya kecelakaan dan kontaminasi
Penggunaan tangga atau elevator dan lift harus dilengkapi
dengan sarana pencegahan kecelakaan seperti alarm suara
dan petunjuk penggunaan yang mudah dipahami oleh
pemakainya atau untuk lift 4 (empat) lantai harus
dilengkapi ARD (Automatic Rexserve Divide) yaitu alat
yang dapat mencari lantai terdekat bila listrik mati.
Dilengkapi dengan pintu darurat yang dapat dijangkau
dengan mudah bila terjadi kebakaran atau kejadian darurat
lainnya dan dilengkapi ram untuk brankar.
j. Fasilitas Pemadam Kebakaran
Bangunan rumah sakit dilengkapi dengan fasilitas
pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
C. Ruang Bangunan
1. Zona dengan Risiko Rendah
Zona risiko rendah meliputi: ruang administrasi, ruang komputer,
ruang pertemuan, ruang perpustakaan, ruang resepsionis, dan ruang
pendidikan/pelatihan.
2. Zona dengan Risiko Sedang
Zona risiko sedang meliputi : ruang rawat inap bukan penyakit
menular, rawat jalan, ruang ganti pakaian, dan ruang tunggu pasien.
10
Persyaratan bangunan pada zona dengan risiko sedang sama dengan
persyaratan pada zona risiko rendah.
3. Zona dengan Risiko Tinggi
Zona risiko tinggi meliputi : ruang isolasi, ruang perawatan intensif,
laboratorium, ruang penginderaan medis (medical imaging), ruang
bedah mayat (autopsy), dan ruang jenazah
4. Zona dengan Risiko Sangat Tinggi
Zona risiko tinggi meliputi : ruang operasi, ruang bedah mulut,
ruang perawatan gigi, ruang gawat darurat, ruang bersalin, dan ruang
patologi
D. Kualitas Udara Ruang
1. Tidak berbau (terutana bebas dari H2S dan Amoniak)
2. Kadar debu (particulate matter) berdiameter kurang dari 10 micron
dengan rata-rata pengukuran 8 jam atau 24 jam tidak melebihi 150
μg/m3, dan tidak mengandung debu asbes.
E. Pencahayaan
Pencahayaan, penerangan, dan intensitasnya di ruang umum dan khusus
harus sesuai dengan peruntukkannya
F. Pengawasan
1. Ruang-ruang tertentu seperti ruang operasi, perawatan bayi,
laboratorium, perlu mendapat perhatian yang khusus karena sifat
pekerjaan yang terjadi di ruang-ruang tersebut.
2. Ventilasi ruang operasi harus dijaga pada tekanan lebih positif
sedikit (minimum 0,10 mbar) dibandingkan ruang-ruang lain di
rumah sakit.
3. Sistem suhu dan kelembaban hendaknya didesain sedemikian rupa
sehingga dapat menyediakan suhu dan kelembaban
G. Kebisingan
H. Fasilitas Sanitasi Rumah Sakit
I. Jumlah Tempat Tidur
11
Perbandingan jumlah tempat tidur dengan luas lantai untuk kamar
perawatan dan kamar isolasi sebagai berikut:
1. Ruang bayi :
a. Ruang perawatan minimal 2 m2/tempat tidur
b. Ruang isolasi minimal 3,5 m2/tempat tidur
2. Ruang dewasa :
a. Ruang perawatan minimal 4,5 m2/tempat tidur
b. Ruang isolasi minimal 6 m2/tempat tidur
J. Lantai dan dan Dinding
Lantai dan dinding harus bersih, dengan tingkat kebersihan sebagai
berikut:
1. Ruang Operasi : 0 - 5 CFU/cm2 dan bebas patogen dan gas gangrene
2. Ruang perawatan : 5 – 10 CFU/cm2
3. Ruang isolasi : 0 – 5 CFU/cm2
4. Ruang UGD : 5 – 10 CFU/cm2
II. Penyehatan Higiene dan Sanitasi Makanan Minuman
A. Pengertian
1. Makanan dan minuman di rumah sakit adalah semua makanan dan
minuman yang disajikan dan dapur rumah sakit untuk pasien dan
karyawan; makanan dan minuman yang dijual didalam lingkungan
rumah sakit atau dibawa dari luar rumah sakit.
2. Higiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan
melindungi kebersihan individu. Misalnya, mencuci tangan, mencuci
piring, membuang bagian makanan yang rusak.
3. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan
melindungi kebersihan lingkungan. Misalnya, menyediakan air
bersih, menyediakan tempat sampah dan lain-lain.
B. Persyaratan Higiene dan Sanitasi Makanan
12
1. Angka kuman E.Coli pada makanan harus 0/gr sampel makanan dan
pada minuman angka kuman E.Coli harus 0/100 ml sampel
minuman.
2. Kebersihan peralatan ditentukan dengan angka total kuman
sebanyak-banyaknya 100/cm2 permukaan dan tidak ada kuman E.
Coli.
3. Makanan ayng mudah membususk disimpan dalam suhu panas lebih
dari 65,5° atau dalam suhu dingin kurang dari 4° C. Untuk makanan
yang disajikan lebih dari 6 jam disimpan suhu – 5° C sampai -1° C.
4. Maknaan kemasan tertutup sebaiknya disimpan dalam suhu ± 10° C.
5. Penyimpanan bahan mentah dilakukan dalam suhu tertentu
6. Kelembaban penyimpanan dalam ruangan 80 -90 %.
7. Cara penyimpanan bahan makanan tidak menempel pada lantai,
dinding, atau langit-langit dengan ketentuan tertentu
C. Tata Cara Pelaksanaan
1. Bahan Makanan dan Makanan Jadi
a. Pembelian bahan sebaiknya ditempat yang resmi dan berkualitas
baik.
b. Makanan jadi yang dibawa oleh keluarga pasien dan berasal dari
sumber lain harus selalu diperiksa kondisi fisiknya
c. Bahan makanan kemasan (terolah) harus mempunyai label dan
merek serta dalam keadaan baik.
2. Bahan Makanan Tambahan
Bahan makanan tambahan (bahan pewarna, pengawet, pemanis
buatan) harus sesuai dengan ketentuan.
3. Penyimpanan Bahan Makan dan Makanan Jadi
Tempat penyimpanan bahan makanan harus selalu terpelihara dan
dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, bahan kimia berbahaya,
serangga dan hewan lain.
4. Pengolahan Makanan
13
Unsur-unsur yang terkait dengan pengolahan makanan :
a. Tempat Pengolahan Makanan
b. Peralatan Masak
c. Penjamah Makanan
d. Pengangkutan Makanan
e. Penyajian Makanan
5. Pengawasan Higiene dan Sanitasi Makanan dan Minuman
III. Penyehatan Air
A. Pengertian
1. Air minum adalah air ayng melalui proses pengolahan atau tanpa
proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung diminum.
2. Sumber penyediaan air minum dan untuk keperluan rumah sakit
berasal dari Perusahaan Air Minum, air yang didistribusikan melalui
tangki air, air kemasan dan harus memenuhi syarat kualitas air
minum.
B. Persyaratan
1. Kualitas Air Minum
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan
Pengawasan Kualitas Air Minum.
2. Kualitas Air yang Digunakan di Ruang Khusus
a. Ruang Operasi
Bagi rumah sakit yg menggunakan air yg sudah diolah
seperti dari PDAM, sumur bor, dan sumber lain untuk
keperluan operasi dapat melakukan pengolahan tambahan
dgn catridge filter dan dilengkapi dgn disinfeksi
menggunakan ultra violet (UV)
b. Ruang Farmasi dan Hemodialisis
14
Air yang digunakan di ruang farmasi terdiri dari air yang
dimurnikan untuk penyiapan obat, penyiapan injeksi, dan
pengenceran dalam hemodialisis.
C. Tata Laksana
1. Kegiatan pengawasan kualitas air dengan pendekatan surveilans
kualitas air
2. Melakukan inspeksi sanitasi sarana air minum dan air bersih rumah
sakit dilaksanakan minimal 1 tahun sekali.
3. Pengambilan sampel air pada sarana penyediaan air inum dan/ atau
air bersih rumah sakit tercantum
4. Pemeriksaan kimia air minum dan/atau air bersih dilakukan minimal
2 (dua) kali setahun (sekali pada musim kemarau dan sekali pada
musim hujan) dan titik pengambilan sampel masing-masing pada
tempat penampungan (reservoir) dan keran terjauh dari reservoir.
5. Titik pengambilan sampel air untuk pemeriksaan mikrobiologik
terutama pada air kran dari ruang dapur, ruang operasi, kamar
bersalin, kamar bayi, dan ruang makan, tempat penampungan
(reservoir), secara acak pada kran-kran sepanjang sistem distribusi,
pada sumber air, dan titik-titik lain yang rawan pencemaran.
6. Sampel air pada butir 3 dan 4 tersebut diatas dikirim dan
diperiksakan pada laboratorium yang berwenang atau yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau Pemerintah Daerah
setempat.
7. Pengambilan dan pengiriman sampel air dapat dilaksanakan sendiri
oleh pihak rumah sakit atau pihak ketiga yang direkomendasikan
oleh Dinas Kesehatan.
8. Sewaktu-waktu dinas kesehatan provinsi, kabupaten/ kota dalam
rangka pengawasan (uji petik) penyelenggaraan penyehatan
lingkungan rumah sakit, dapat mengambil langsung sampel air pada
15
sarana penyediaan air minum dan/atau air bersih rumah sakit untuk
diperiksakan pada laboratorium.
9. Setiap 24 jam sekali rumah sakit harus melakukan pemeriksaan
kualitas air untuk pengukuran sisa khlor bila menggunakan
disinfektan kaporit, pH dan kekeruhan air minum atau air bersih
yang berasal dari sistem perpipaan dan/ atau pengolahan air pada
titik/ tempat yang dicurigai rawan pencemaran.
10. Petugas sanitasi atau penanggung jawab pengelolaan kesehatan
lingkungan melakukan analisis hasil inspeksi sanitasi dan
pemeriksaan laboratorium.
11. Apabila dalam hasil pemeriksaan kualitas air terdapat parameter
yang menyimpang dari standar maka harus dilakukan pengolahan
sesuai parameter yang menyimpang.
12. Apabila ada hasil inspeksi sanitasi yang menunjukkan tingkat risiko
pencemaran amat tinggi dan tinggi harus dilakukan perbaikan
sarana.
IV. Pengelolaan Limbah
A. Pengertian
1. Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari
kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas.
2. Limbah padat rumah sakit adalah semua limbah rumah sakit yang
berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari
limbah medis padat dan non-medis.
B. Tata Laksana
1. Limbah Medis Padat
Minimasi Limbah
Pemilahan, Pewadahan, Pemanfaatan Kembali dan Daur Ulang
Pengumpulan, Pengangkutan, dan Penyimpanan Limbah Media
Padat di Lingkungan Rumah Sakit
16
Pengumpulan, Pengemasan dan Pengangkutan ke Luar Rumah
Sakit
Pengolahan dan Pemusnahan
2. Limbah Medis Non Padat
Pemilahan dan Pewadahan
Pengumpulan, Penyimpanan, dan Pengangkutan
Pengolahan dan Pemusnahan
3. Limbah Cair
Kalitas limbah (efluen) rumah sakit yang akan dibuang ke badan
air atau lingkungan harus memenuhi persyaratan baku mutu.
4. Limbah Gas
Standar limbah gas (emisi) dari pengolahan pemusnah limbah
medis padat dengan insinerator mengacu pada Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/MenLH/12/1995 tentang Baku
Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
V. Pengelolaan Tempat Pencucian Linen (Laundry)
A. Pengertian
Laundry rumah sakit adalah tempat pencucian linen yang dilengkapi
dengan sarana penunjangnya berupa mesin cuci, alat dan disinfektan,
mesin uap (steam boiler), pengering, meja dan meja setrika.
B. Persyaratan
1. Suhu air panas untuk pencucian 70° C dalam waktu 25 menit atau
95° C dalam waktu 10 menit
2. Penggunaan jenis deterjen dan disinfektan untuk proses pencucian
yang ramah lingkungan agar limbah cair yang dihasilkan mudah
terurai oleh lingkungan
3. Standar kuman bagi linen bersih setelah keluar dari proses tidak
mengandung 6 x 103 spora spesies Bacilus per inci persegi.
C. Tata Laksana
17
1. Di tempat laundry tersedia kran air bersih dengan kualitas dan
tekanan aliran yang memadai, air panas untuk disinfeksi dan
desinfektan
2. Peralatan cuci dipasang permanen dan diletakkan dekat dengan
saluran pembuangan air limbah serta tersedia mesin cuci yang dapat
mencuci jenis-jenis linen yang tersedia mesin cuci yang dapat
mencuci jenis-jenis linen yang berbeda.
3. Tersedia ruangan dan mesin cuci yang terpisah untuk linen infeksius
dan non infeksius.
4. Laundry harus dilengkapi saluran air limbah tertutup yang
dilengkapi dengan pengolahan awal (pre-treatment) sebelum
dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah.
5. Laundry harus disediakan ruang-ruang terpisah sesuai kegunaannya
yaitu ruang linen kotor, ruang linen bersih, ruang untuk
perlengkapan kebersihan, ruang perlengkapan cuci, ruang kereta
linen, kamar mandi dan ruang peniris atau pengering untuk alat-alat
termasuk linen.
6. Untuk rumah sakit yang tidak mempunyai laundry tersendiri,
pencuciannya dapat bekerjasama dengan pihak lain dan pihak lain
tersebut harus mengikuti persyaratan dan tatalaksana yang telah
ditetapkan.
VI. Pengendalian Serangga, Tikus dan Binatang Pengganggu Lainnya
A. Pengertian
Pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya adalah
upaya untuk mengurangi populasi serangga, tikus, dan binatang
pengganggu lainnya sehingga keberadaannya tidak menjadi vektor
penularan penyakit.
B. Persyaratan
1. Kepadatan jentik Aedes sp yang diamati melalui indeks kontainer
harus 0 (nol).
18
2. Tidak ditemukannya lubang tanpa kawat kasa yang memungkinkan
nyamuk masuk ke dalam ruangan, terutama di ruangan perawatan.
3. Semua ruang di rumah sakit harus bebas dari kecoa, terutana pada
dapur, gudang makanan, dan ruangan steril.
4. Tidak ditemukannya tandaq-tanda keberadaan tikus terutana pada
daerah bangunan tertutup (core) rumah sakit.
5. Tidak ditemukannya lalat di dalam bangunan tertutup (core) di
rumah sakit.
6. Di lingkungan rumah sakit harus bebas kucing dan anjing.
C. Tata laksana
1. Surveilans
a. Nyamuk: Pengamatan Jenitik, Pengamatan lubang dengan
kawat kasa, Konstruksi pintu harus membuka ke arah luar.
b. Kecoak: Mengamati keberadaan kecoa yg ditandai dgn adanya
kotoran, telur kecoa, dan kecoa hidup atau mati di setiap
ruangan yang dilakukan 2 tiap minggu
c. Tikus: Mengamati/ memantau secara berkala setiap 2 (dua)
bulan di tempat-tempat yang biasanya menjadi tempat
perkembangbiakan tikus
d. Lalat: Mengukur kepadatan lalat secara berkala dengan
menggunakan fly grill pada daerah core dan pada daerah yang
biasa dihinggapi lalat
e. Kucing dan anjing: Mengamati/ memantau secara berkala
kucing dan anjing.
2. Pencegahan
a. Nyamuk
Melakukan Pembersihan Sarang Nyamuk (PSN) dengan
Mengubur, Menguras, Menututp (3M)
Pengaturan aliran pembuangan air limbah dan saluran
dalam keadaan tertutup.
19
Pembersihan tananam sekitar rumah sakit secara berkala
yang menjadi tempat perindukan.
Pemasangan kawat kasa di seluruh ruangan dan
penggunaan kelambu terutama di ruang perawatan anak.
b. Kecoa
Menyimpan bahan makanan dan amkaan siap saji pda
tempat tertutup.
Pengelolaan sampah yang memenuhi sayarat kesehatan.
Menututp lubang-lubang atau celah-celah agar kecoa tidak
masuk ke dlam ruangan.
c. Tikus
Melakukan penutupan saluran terbuka, lubang-lubang di
dinding, plafon, pintu, dan jendela.
Melakukan pengelolaan sampah yang memenuhi syarat
kesehatan.
d. Lalat
Melakukan pengelolaan sampah/limbah yang memnuhi syarat
kesehatan.
e. Binatang pengganggu lainnya
Melakukan pengelolaan makanan dan limbah yang memenuhi
syarat kesehatan.
3. Pemberantasan
a. Nyamuk
Pemberantasan dilakukan apabila larva atau jentik nyamuk
Aedes sp. > 0 dengan abatisasi.
Melakukan pemberantasan larva/jentik dengan
menggunakan predator.
Melakukan oiling untuk memberantas culex.
20
Bila diduga ada kasus demam berdarah yang tertular di
rumah sakit, maka perlu dilakukan pengasapan (fogging) di
rumah sakit.
b. Kecoa
Pembersihan telur kecoa denga lemari, peralatan dan telur
kecoa dimusnahkan dengan dibakar/dihancurkan.n cara
mekanis, yaitu membersihkan telur yang terdapat pada
celah-celah dinding,
Pemberantasan kecoa secara fisik dan kimiawi
c. Tikus
Melakukan pengendalian tikus secara fisik dengan pemasangan
perangkap, pemukulan atau sebagai alternatif terakhir dapat
dilakukan secara kimia dengan menggunakan umpan beracun.
d. Lalat
Bila kepadatan lalat di sekitar tempat sampah (perindukan)
melebihi 2 (dua) ekor per block grill maka dilakukan
pengendalian lalat secara fisik, biologik, dan kimia
e. Binatang pengganggu lainnya
Bila terdapat kucing dan anjing, maka perlu dilakukan:
Penangkapan, kemudian dibuang jauh dari rumah sakit
Bekerjasama dengan Dinas Peternakan setempat untuk
menangkap kucing dan anjing.
VII. Dekontaminasi melalui Disinfeksi dan Sterilisasi
A. Pengertian
1. Dekontaminasi adalah upaya mengurangi dan/atau menghilangkan
kontaminasi oleh mikroorganisme pada orang, peralatan, bahan,
dan ruang melalui disinfeksi dan sterilisasi dengan cara fisik dan
kimiawi.
21
2. Disinfeksi adalah upaya untuk mengurangi/menghilangkan jumlah
mikroorganisme patogen penyebab penyakit (tidak termasuk
spora) dengan cara fisik dan kimiawi.
3. Sterilisasi adalah upaya untuk menghilangkan semua
mikroorganisme dengan cara fisik dan kimiawi.
B. Persyaratan
1. Suhu pada disinfeksi secara fisik dengan air panas untuk peralatan
sanitasi 80° C dalam waktu 45-60 detik, sedangkan untuk peralatan
memasak 80° C dalam waktu 1 menit.
2. Disinfektan harus memenuhi kriteria tidak merusak peralatan
maupun orang, disinfektan mempunyai efek sebagai deterjen dan
efektif dalam waktu yang relatif singkat, tidak terpengaruh oleh
kesadahan air atau keberadaan sabun dan protein yang mungkin
ada.
3. Penggunaan disinfektan harus mengikuti petunjuk pabrik.
4. Sterilisasi harus menggunakan disinfektan yang ramah lingkungan.
5. Petugas sterilisasi harus menggunakan alat pelindung diri dan
menguasai prosedur sterilisasi yang aman.
6. Hasil akhir proses sterilisasi untuk ruang operasi dan ruang isolasi
harus bebas dari mikroorganisme hidup.
C. Tata Laksana
1. Kamar/ruang operasi yang telah dipakai harus dilakukan disinfeksi
dan disterilisasi sampai aman untuk dipakai pada operasi
berikutnya.
2. Instrumen dan bahan medis yang dilakukan sterilisasi harus
melalui persiapan.
3. Indikasi kuat untuk tindakan disinfeksi/sterilisasi :
Semua peralatan medik atau peralatan perawatan pasien yang
dimasukkan ke dalam jaringan tubuh, sistem vaskuler atau
22
melalui saluran darah harus selalu dalam keadaan steril
sebelum digunakan.
Semua peralatan yang menyentuh selaput lendir seperti
endoskopi, pipa endotracheal harus disterilkan/ didisinfeksi
dahulu sebelum digunakan.
Semua peralatan operasi setelah dibersihkan dari jaringan
tubuh, darah atau sekresi harus selalu dalam keadaan steril
sebelum dipergunakan.
4. Semua benda atau alat yang akan disterilkan/didisinfeksi harus
terlebih dahulu dibersihkan secara seksama untuk menghilangkan
semua bahan organik (darah dan jaringan tubuh) dan sisa bahan
linennya.
5. Sterilisasi (132° C selama 3 menit pada gravity displacement
steam sterilizer) tidak dianjurkan untuk implant.
6. Setiap alat yang berubah kondisi fisiknya karena dibersihkan,
disterilkan atau didisinfeksi tidak boleh dipergunakan lagi.
7. Jangan menggunakan bahan seperti linen, dan lainnya yang tidak
tahan terhadap sterilisasi
8. Pemeliharaan dan cara penggunaan peralatan sterilisasi harus
memperhatikan petunjuk dari pabriknya dan harus dikalibrasi
minimal 1 kali satu tahun.
9. Peralatan operasi yang telah steril jalur masuk ke ruangan harus
terpisah dengan peralatan yang telah terpakai.
10. Sterilisasi dan disinfeksi terhadap ruang pelayanan medis dan
peralatan medis dilakukan sesuai permintaan dari kesatuan kerja
pelayanan medis dan penunjang medis.
VIII. Pengamanan Dampak Radiasi melalui Disinfeksi dan Sterilisasi
A. Pengertian
1. Radiasi adalah emisi dan penyebaran energi melalui ruang (media)
dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel-partikel
23
atau elementer dengan kinetik yang sangat tinggi yang dilepaskan
dari bahan atau alat radiasi yang digunakan oleh instalasi di rumah
sakit.
2. Pengamanan dampak radiasi adalah upaya perlindungan kesehatan
masyarakat dari dampak radiasi melalui promosi dan pencegahan
risiko atas bahaya radiasi, dengan melakukan kegiatan
pemantauan, investigasi, dan mitigasi pada sumber, media
lingkungan dan manusia yang terpajan atau alat yang mengandung
radiasi
B. Persyaratan
Persyaratan sesuai Keputusan Badan pengawas Tenaga Nuklir Nomor
01 Tahun 1999, tentang Ketentuan Keselamatan Kerja terhadap
Radiasi adalah :
1. Nilai Batas Dosis (NBD) bagi pekerja yang terpajan radiasi sebesar
50 mSv (mili Sievert) dalam 1 (satu) tahun.
2. NBD bagi msyarakat yang terpajan sebesar 5 mSv (mili Sievert)
dalam 1 (satu) tahun.
C. Tata laksana
1. Perizinan
Penerimaan dosis radiasi terhadap pekerja atau masyarakat tidak
boleh melebihi nilai batas dosis yang ditetapkan oleh Badan
Pengawas.
2. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap
Pemanfaatan Radiasi Pengion
a. Organisasi
b. Peralatan Proteksi Radiasi
c. Pemantauan Dosis Perorangan
d. Pemantauan Dosis Perorangan
e. Pemantauan Dosis Perorangan
f. Jaminan Kualitas
24
g. Pendidikan dan Pelatihan
3. Kalibrasi
a. Pengelola rumah sakit wajib mengkalibrasikan alat ukur radiasi
scara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
b. Pengelola rumah sakit wajib mengkalibrasi keluaran radiasi
(output) peralatan radioterapi secara berkala sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
c. Kalibrasi hanya dapat dilakukan oleh instalasi yang telah
terakreditasi dan ditunjuk oleh Badan Pengawas.
4. Penanggulangan Kecelakaan Radiasi
a. Pengelola rumah sakit harus melakukan upaya pencegahan
terjadinya kecelakaan radiasi.
b. Jika terjadi kecelakaan radiasi, pengelola rumah sakit harus
segera melaporkan terjadinya kecelakaan radiasi dan upaya
penanggulangannya kepada Badan Pengawas dan instansi
terkait lainnya.
5. Pengelolaan Limbah Radioaktif
a. Penghasil limbah radioaktif tingkat rencah dan tingkat sedang
wajib mengumpulkan, mengelompokkan, atau mengolah dan
menyimpan semenatara limbah radioaktif sebelum diserahkan
kepada Badan Pelaksana.
b. Limbah radioaktif yang berasal dari luar negeri tidak diizinkan
untuk disimpan di wilayah Indonesia.
IX. Upaya Promosi Kesehatan Dari Aspek Kesehatan Lingkungan
A. Pengertian
1. Promosi higiene dan sanitasi adalah penyampaian pesan tentang
higiene dan sanitasi rumah sakit kepada pasien/keluarga pasien dan
pengunjung, karyawan terutama karyawan baru serta masyarakat
sekitarnya agar mengetahui, memahami, menyadari, dan mau
25
mmbiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta
dapat memanfaatkan fasilitas sanitasi rumah sakit dengan benar.
2. Promosi kesehatan lingkungan adalah penyampaian pesan tentang
yang berkaitan dengan PHBS yang sasarannya ditujukan kepada
karyawan.
B. Persyaratan
Setiap rumah sakit harus melaksankan upaya promosi higiene dan
sanitasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga/unit organisasi
yang menangani promosi kesehatan lingkungan rumah sakit.
C. Tata laksana
Promosi higiene dan sanitasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan
cara langsung, media cetak, maupun media elektronik.
Secara langsung: konseling, diskusi, ceramah, demonstrasi,
partisipatif, pameran, melalui pengeras suara, dan lain-lain.
Media cetak: penyebaran, pemasangan poster, gambar, spanduk,
tata tertib, pengumuman secara tertulis, pemasangan petunjuk.
Media elektronik: radio, televisi (televisi khusus lingkungan rumah
sakit), Eye-catcher.
2. Pengelolaan Limbah
Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik
industri maupun domestik (rumah tangga). Dimana masyarakat bermukim,
disanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus
(black water), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya
(grey water).
Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak
dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau
secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia Senyawa organik dan
Senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran
limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan
26
manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat
bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan
karakteristik limbah.
Beberapa faktor yang memengaruhi kualitas limbah adalah volume
limbah, kandungan bahan pencemar, dan frekuensi pembuangan limbah. Untuk
mengatasi limbah ini diperlukan pengolahan dan penanganan limbah. Pada
dasarnya pengolahan limbah ini dapat dibedakan menjadi:
1. Pengolahan menurut tingkatan perlakuan
2. pengolahan menurut karakteristik limbah
Untuk mengatasi berbagai limbah dan air limpasan (hujan), maka suatu
kawasan permukiman membutuhkan berbagai jenis layanan sanitasi. Layanan
sanitasi ini tidak dapat selalu diartikan sebagai bentuk jasa layanan yang
disediakan pihak lain. Ada juga layanan sanitasi yang harus disediakan sendiri
oleh masyarakat, khususnya pemilik atau penghuni rumah, seperti jamban
misalnya.
1. Layanan air limbah domestik: pelayanan sanitasi untuk
menangani limbah Air kakus.
2. Jamban yang layak harus memiliki akses air besrsih yang cukup
dan tersambung ke unit penanganan air kakus yang benar.
Apabila jamban pribadi tidak ada, maka masyarakat perlu
memiliki akses ke jamban bersama atau MCK.
3. Layanan persampahan. Layanan ini diawali dengan pewadahan
sampah dan pengumpulan sampah. Pengumpulan dilakukan
dengan menggunakan gerobak atau truk sampah. Layanan
sampah juga harus dilengkapi dengan tempat pembuangan
sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA), atau fasilitas
pengolahan sampah lainnya. Dibeberapa wilayah pemukiman,
layanan untuk mengatasi sampah dikembangkan secara kolektif
oleh masyarakat. Beberapa ada yang melakukan upaya kolektif
27
lebih lanjut dengan memasukkan upaya pengkomposan dan
pengumpulan bahan layak daur-ulang.
4. Layanan drainase lingkungan adalah penanganan limpasan air
hujan menggunakan saluran drainase (selokan) yang akan
menampung limpasan air tersebut dan mengalirkannya ke badan
air penerima. Dimensi saluran drainase harus cukup besar agar
dapat menampung limpasan air hujan dari wilayah yang
dilayaninya. Saluran drainase harus memiliki kemiringan yang
cukup dan terbebas dari sampah.
5. Penyediaan air bersih dalam sebuah pemukiman perlu tersedia
secara berkelanjutan dalam jumlah yang cukup. Air bersih ini
tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, mandi,
dan kakus saja, melainkan juga untuk kebutuhan cuci dan
pembersihan lingkungan.
Karakteristik limbah
1. Berukuran mikro
2. Dinamis
3. Berdampak luas (penyebarannya)
4. Berdampak jangka panjang (antar generasi)
I. Limbah Industri
Berdasarkan karakteristiknya limbah industri dapat dibagi menjadi empat
bagian, yaitu:
1. Limbah cair biasanya dikenal sebagai entitas pencemar air. Komponen
pencemaran air pada umumnya terdiri dari bahan buangan padat, bahan
buangan organik dan bahan buangan anorganik
2. Limbah padat
3. Limbah gas dan partikel
Proses pencemaran udara semua spesies kimia yang dimasukkan atau masuk
ke atmosfer yang “bersih” disebut kontaminan. Kontaminan pada konsentrasi
28
yang cukup tinggi dapat mengakibatkan efek negatif terhadap penerima
(receptor), bila ini terjadi, kontaminan disebut cemaran (pollutant).Cemaran
udara diklasifihasikan menjadi dua kategori menurut cara cemaran masuk atau
dimasukkan ke atmosfer yaitu: cemaran primer dan cemaran sekunder.
Cemaran primer adalah cemaran yang diemisikan secara langsung dari sumber
cemaran. Cemaran sekunder adalah cemaran yang terbentuk oleh proses kimia
di atmosfer.
Lima cemaran primer yang secara total memberikan sumbangan lebih dari
90% pencemaran udara global adalah:karbon monoksida (CO),nitrogen oksida
(Nox),hidrokarbon (HC),sulfur oksida (SOx), dan partikulat.Selain cemaran
primer terdapat cemaran sekunder yaitu cemaran yang memberikan dampak
sekunder terhadap komponen lingkungan ataupun cemaran yang dihasilkan
akibat transformasi cemaran primer menjadi bentuk cemaran yang berbeda.
Ada beberapa cemaran sekunder yang dapat mengakibatkan dampak penting
baik lokal,regional maupun global yaitu:CO2 (karbon monoksida),cemaran
asbut (asap kabut) atau smog (smoke fog),hujan asam,CFC (Chloro-Fluoro-
Carbon/Freon), dan CH4 (metana).
II. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari
suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri,
pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan
debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat
beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3).
Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan
berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun
tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau
membahayakan kesehatan manusia.Yang termasuk limbah B3 antara lain
adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi
karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang
29
memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini termasuk
limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah
meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi,
bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat
diketahui termasuk limbah B3.Macam limbah beracun
1. Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat
menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat
dapat merusak lingkungan.
2. Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api,
percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau
terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu
lama.
3. Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena
melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang
tidak stabil dalam suhu tinggi.
4. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya
bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian
atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut.
5. Limbah penyebab infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi
penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian
tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena
infeksi.
6. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi
pada kulit atau mengkorosikan baja, yaitu memiliki pH sama atau kurang
dari 2,0 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk
yang bersifat basa.
PengelolaanLimbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi,
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan
penimbunan limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 ini bertujuan untuk mencegah,
menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas
30
lingkungan tercemar, dan meningkatan kemampuan dan fungsi kualitas
lingkungan
Teknologi pengolahan air limbah adalah kunci dalam memelihara kelestarian
lingkungan. Apapun macam teknologi pengolahan air limbah domestik maupun
industri yang dibangun harus dapat dioperasikan dan dipelihara oleh
masyarakat setempat. Jadi teknologi pengolahan yang dipilih harus sesuai
dengan kemampuan teknologi masyarakat yang bersangkutan.
Berbagai teknik pengolahan air buangan untuk menyisihkan bahan
polutannya telah dicoba dan dikembangkan selama ini.Suatu jenis air buangan
tertentu, ketiga metode pengolahan tersebut dapat diaplikasikan secara sendiri-
sendiri atau secara kombinasi. Teknik-teknik pengolahan air buangan yang telah
dikembangkan tersebut secara umum terbagi menjadi 3 metode pengolahan:
1. Pengolahan secara Fisika
Pada umumnya, sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air
buangan, diinginkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan
yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih
dahulu. Penyaringan (screening) merupakan cara yang efisien dan murah
untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan
tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan
proses pengendapan. Parameter desain yang utama untuk proses
pengendapan ini adalah kecepatan mengendap partikel dan waktu detensi
hidrolis di dalam bak pengendap.
31
Gambar 1. Skema Diagram Pengolahan Fisik
Proses flotasi banyak digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang
mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses
32
pengolahan berikutnya. Flotasi juga dapat digunakan sebagai cara
penyisihan bahan-bahan tersuspensi (clarification) atau pemekatan lumpur
endapan (sludge thickening) dengan memberikan aliran udara ke atas (air
flotation).
Proses filtrasi di dalam pengolahan air buangan, biasanya dilakukan
untuk mendahului proses adsorbsi atau proses reverseosmosis-nya, akan
dilaksanakan untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi
dari dalam air agar tidak mengganggu proses adsorbsi atau menyumbat
membran yang dipergunakan dalam proses osmosa.
Proses adsorbsi, biasanya dengan karbon aktif, dilakukan untuk
menyisihkan senyawa aromatik (misalnya: fenol) dan senyawa organik
terlarut lainnya, terutama jika diinginkan untuk menggunakan kembali air
buangan tersebut.
Teknologi membran (reverse osmosis) biasanya diaplikasikan untuk unit-
unit pengolahan kecil, terutama jika pengolahan ditujukan untuk
menggunakan kembali air yang diolah. Biaya instalasi dan operasinya
sangat mahal.
2. Pengolahansecara Kimia
Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk
menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap (koloid),
logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun; dengan
membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Penyisihan bahan-
bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat bahan-
bahan tersebut, yaitu dari tak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan
(flokulasi-koagulasi), baik dengan atau tanpa reaksi oksidasi-reduksi, dan
juga berlangsung sebagai hasil reaksi oksidasi.
33
Gambar 2. Skema Diagram pengolahan Kimiawi
Pengendapan bahan tersuspensi yang tak mudah larut dilakukan dengan
membubuhkan elektrolit yang mempunyai muatan yang berlawanan dengan
muatan koloidnya agar terjadi netralisasi muatan koloid tersebut, sehingga
akhirnya dapat diendapkan. Penyisihan logam berat dan senyawa fosfor
dilakukan dengan membubuhkan larutan alkali (air kapur misalnya)
sehingga terbentuk endapan hidroksida logam-logam tersebut atau endapan
34
hidroksiapatit. Endapan logam tersebut akan lebih stabil jika pH air > 10,5
dan untuk hidroksiapatit pada pH >9,5. Khusus untuk krom heksavalen,
sebelum diendapkan sebagai krom hidroksida [Cr(OH)3], terlebih dahulu
direduksi menjadi krom trivalent dengan membubuhkan reduktor (FeSO4,
SO2, atau Na2S2O5).
Penyisihan bahan-bahan organik beracun seperti fenol dan sianida pada
konsentrasi rendah dapat dilakukan dengan mengoksidasinya dengan klor
(Cl2), kalsium permanganat, aerasi, ozon hidrogen peroksida.
Pada dasarnya kita dapat memperoleh efisiensi tinggi dengan pengolahan
secara kimia, akan tetapi biaya pengolahan menjadi mahal karena
memerlukan bahan kimia.
3. Pengolahan secara Biologi
Semua air buangan yang biodegradable dapat diolah secara biologi.
Sebagai pengolahan sekunder, pengolahan secara biologi dipandang sebagai
pengolahan yang paling murah dan efisien. Dalam beberapa dasawarsa telah
berkembang berbagai metode pengolahan biologi dengan segala
modifikasinya.
Pada dasarnya, reaktor pengolahan secara biologi dapat dibedakan atas
dua jenis, yaitu:
1. Reaktor pertumbuhan tersuspensi (suspended growth reaktor);
2. Reaktor pertumbuhan lekat (attached growth reaktor).
Di dalam reaktor pertumbuhan tersuspensi, mikroorganisme tumbuh dan
berkembang dalam keadaan tersuspensi. Proses lumpur aktif yang banyak
dikenal berlangsung dalam reaktor jenis ini. Proses lumpur aktif terus
berkembang dengan berbagai modifikasinya, antara lain: oxidation ditch
dan kontak-stabilisasi. Dibandingkan dengan proses lumpur aktif
konvensional, oxidation ditch mempunyai beberapa kelebihan, yaitu
efisiensi penurunan BOD dapat mencapai 85%-90% (dibandingkan 80%-
85%) dan lumpur yang dihasilkan lebih sedikit. Selain efisiensi yang lebih
tinggi (90%-95%), kontak stabilisasi mempunyai kelebihan yang lain, yaitu
35
waktu detensi hidrolis total lebih pendek (4-6 jam). Proses kontak-stabilisasi
dapat pula menyisihkan BOD tersuspensi melalui proses absorbsi di dalam
tangki kontak sehingga tidak diperlukan penyisihan BOD tersuspensi
dengan pengolahan pendahuluan.
Kolam oksidasi dan lagoon, baik yang diaerasi maupun yang tidak, juga
termasuk dalam jenis reaktor pertumbuhan tersuspensi. Untuk iklim tropis
seperti Indonesia, waktu detensi hidrolis selama 12-18 hari di dalam kolam
oksidasi maupun dalam lagoon yang tidak diaerasi, cukup untuk mencapai
kualitas efluen yang dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Di dalam
lagoon yang diaerasi cukup dengan waktu detensi 3-5 hari saja.
Di dalam reaktor pertumbuhan lekat, mikroorganisme tumbuh di atas
media pendukung dengan membentuk lapisan film untuk melekatkan
dirinya. Berbagai modifikasi telah banyak dikembangkan selama ini, antara
lain:
1. trickling filter
2. cakram biologi
3. filter terendam
4. reaktor fludisasi
Seluruh modifikasi ini dapat menghasilkan efisiensi penurunan BOD
sekitar 80%-90%.
Ditinjau dari segi lingkungan dimana berlangsung proses penguraian
secara biologi, proses ini dapat dibedakan menjadi dua jenis:
1. Proses aerob, yang berlangsung dengan hadirnya oksigen;
2. Proses anaerob, yang berlangsung tanpa adanya oksigen.
Apabila BOD air buangan tidak melebihi 400 mg/l, proses aerob masih
dapat dianggap lebih ekonomis dari anaerob. Pada BOD lebih tinggi dari
4000 mg/l, proses anaerob menjadi lebih ekonomis.
36
C. B3 dan Kebakaran
1. Definisi dan Sumber Limbah Medis
Sampah dan limbah rumah sakit adalah semua sampah dan limbah
yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya.
Secara umum sampah dan limbah rumah sakit dibagi dalam dua kelompok
besar, yaitu sampah atau limbah klinis dan non klinis baik padat maupun cair.
Jenis perawatan/aktivitas kesehatan yang dapat menghasilkan limbah
adalah :
a. Rumah sakit dengan aktifitasnya:
Rumah sakit umum
Rumah sakit khusus
Sanotarium
Aktifitas spesifik dalam sebuah rumah sakit misalnya : paediatric,
oncolagy, rehabilitasi, mata dan telinga, psychiatric, terbakar,
orthopaedic, penyakit-penyakit pernafasan
b. Klinik:
Ruang dokter dan perawat
Pusat dialysis
Pusat penanganan kecanduan alcohol
Pusat penanganan kecanduan obat bius
Klinik bersalin
Klinik thrombosis.
c. Asrama dan sejenis:
Perawat
Rumah jompo
Rumah sakit jiwa
d. Kegiatan-kegiatan penunjang:
Bank darah
Apotik
Pusat pelatihan medis
38
Ruang mayat
Ruang steril
Ruang cuci pakaian
Ruang teknis
Laboratorium : klinis, pathology, haemathology, kimiawi, penelitian,
termasuk untuk hewan maupun genetis.
Timbulan limbah dari kegiatan rumah sakit bervariasi dari satu institusi ke
institusi sesuai dengan besarnya aktivitas. Sebagai gambaran, di bawah ini
diberikan beberapa angka, yaitu (Kg/bed/hari):
Spanyol : 1,2 sampai 4,4
Inggris : 0,25 sampai 3,3
Belanda : 1,2 sampai 6,0
USA : 4,1 sampai 5,24
Penelitian yang dilakukan di RSHS Bandung oleh Jurusan Teknik Lingkungan
ITB (1993) memberikan angka rata-rata sebesar 2,12 Kg/bed/hari.
2. Pengelompokkan Limbah Medis
Limbah rumah sakit merupakan campuran yang heterogen sifat-
sifatnya. Seluruh jenis limbah ini dapat mengandung limbah berpotensi
infeksi. Kadangkala, limbah residu insinerasi dapat dikagorikan sebagai
limbah berbahaya bila insinerator sebuah rumah sakit tidak sesuai dengan
kriteria, atau tidak dioperasikan sesuai dengan kriteria. Deskripsi umum
tentang kategori utama limbah rumah sakit adalah:
Limbah umum: sejenis limbah domestik, bahan pengemas, makanan
binatang noninfectious,limbah dari cuci serta materi lain yang tidak
membutuhkan penanganan spesial atau tidak membahayakan pada
kesehatan manusia dan lingkungan
Limbah patologis: terdiri dari jaringan-jaringan, organ, bagian
tubuh, plasenta, bangkai binatang, darah dan cairan tubuh
39
Limbah radioaktif: dapat berfase padat, cair maupun gas yang
terkontaminasi dengan radionuklisida, dan dihasilkan dari analisis
in-vitro terhadap jaringan tubuh dan cairan, atau analisis in-vivo
terhadap organ tubuh dalam pelacakan atau lokalisasi tumor,
maupun dihasilkan dari prosedur therapetis
Limbah kimiawi: dapat berupa padatan, cairan maupun gas
misalnya berasal dari pekerjaan diagnostik atau penelitian,
pembersihan/pemeliharaan atau prosedur desinfeksi. Pertimbangan
terhadap limbah ini adalah seperti limbah berbahaya yang lain,
yaitu dapat ditinjau dari sudut: toksik, korosif, mudah terbakar
(flammable), reaktif (eksplosif, reaktif terhadap air, dan shock
sensitive), dilanjutkan dengan sifat-sifat spesifik seperti genotoxic
(carcinogenic, mutagenic, teratogenic dan lain-lain), misalnya obat-
obatan cytotoxic. Limbah kimiawi yang tidak berbahaya adalah
seperti gula, asam- asam animo, garam-garam organik lainnya,
Limbah berpotensi menularkan penyakit (infectious): mengandung
mikroorganisme patogen yang dilihat dari konsentrasi dan
kuantitasnya bila terpapar dengan manusia akan dapat menimbulkan
penyakit. Katagori yang termasuk limbah ini antara lain jaringan
dan stok dari agen-agen infeksi dari kegiatan laboratorium, dari
ruang bedah atau dari autopsi pasien yang mempunyai penyakit
menular , atau dari pasien yang diisolasi, atau materi yang
berkontak dengan pasien yang menjalani haemodialisis (tabung,
filter, serbet, gaun, sarung tangan dan sebagainya) atau materi yang
berkontak dengan binatang yang sedang diinokulasi dengan
penyakit menular atau sedang menderita penyakit menular
Benda-benda tajam yang biasa digunakan dalam kegiatan rumah
sakit: jarum suntik, syring, gunting, pisau, kaca pecah, gunting kuku
dan sebagainya yang dapat menyebabkan orang tertusuk (luka) dan
40
terjadi infeksi. Benda-benda ini mungkin terkontaminasi oleh darah,
cairan tubuh, bahan mikrobiologi atau bahan citotoksik
Limbah farmasi (obat-obatan): produk-produk kefarmasian, obat-
obatan dan bahan kimiawi yang dikembalikan dari ruangan pasien
isolasi, atau telah tertumpah, daluwarsa atau terkontaminasi atau
harus dibuang karena sudah tidak digunakan lagi
Limbah citotoksik: bahan yang terkontaminasi atau mungkin
terkontaminasi dengan obat citotoksik selama peracikan,
pengangkutan atau tindakan terapi citotoksik
Kontainer di bawah tekanan: seperti yang digunakan untuk
peragaan atau pengajaran, tabung yang mengandung gas dan
aerosol yang dapat meledak bila diinsinerasi atau bila mengalami
kerusakan karena kecelakaan (tertusuk dan sebagainya).
Dari sekian banyak jenis limbah klinis tersebut, maka yang
membutuhkan sangat perhatian khusus adalah limbah yang dapat
menyebabkan penyakit menular (infectious waste) atau limbah
biomedis. Limbah ini biasanya hanya 10 - 15 % dari seluruh volume
limbah kegiatan pelayanan kesehatan. Jenis dari limbah ini secara
spesifik adalah:
Limbah human anatomical: jaringan tubuh manusia, organ, bagian-
bagian tubuh, tetapi tidak termasuk gigi, rambut dan muka
Limbah tubuh hewan: jaringan-jaringan tubuh , organ, bangkai,
darah, bagian terkontaminasi dengan darah, dan sebagainya, tetapi
tidak termasuk gigi, bulu, kuku.
Limbah laboratorium mikrobiologi: jaringan tubuh, stok hewan atau
mikroorganisme, vaksin, atau bahan atau peralatan laboratorium
yang berkontak dengan bahan-bahan tersebut. Limbah darah dan
cairan manusia atau bahan/peralatan yang terkontaminasi
dengannya. Tidak termasuk dalam katagori ini adalah urin dan tinja.
41
Limbah-limbah benda tajam seperti jarum suntik, gunting, pacahan
kaca dan sebagainya.
Limbah reaktif yang berasal dari rumah sakit adalah senyawa-senyawa
seperti:
Shock sensitive: senyawa-senyawa diazo, metal azide, nitro
cellulose, perchloric acid, garam-garam perchlorat, bahan kimia
peroksida, asam picric, garam-garam picrat, polynitroaromatic.
Water reactive: logam-logam alkali dan alkali tanah, reagen alkyl
lithium, larutan- larutan boron trifluorida, reagen Grignard, hidrida
dari Al, B, Ca, K, Li, dan Na, logam halida dari Al, As, Fe, P, S, Sb,
Si, Su dan Ti, phosphorus oxychloride, phosphorus pentoxide,
sulfuryl chloride, thionyl chloride.
Bahan reaktif lain: asam nitrit diatas 70%, phosphor (merah dan
putih).
3. Pengelolaan Limbah Medis
Sasaran pengelolaan limbah rumah sakit adalah bagaimana menangani
limbah berbahaya, menyingkirkan dan memusnahkannya seekonomis
mungkin, namun higienis dan tidak membahayakan lingkungan. Untuk limbah
yang bersifat umum, penanganannya adalah identik dengan limbah kota yang
lain. Daur ulang sedapat mungkin diterapkan pada setiap kesempatan. Bahan-
bahan tajam yang terinfeksi harus dibungkus secara baik serta tidak akan
mencelakakan pekerja yang menangani dan dapat dibuang seperti limbah
umum, sedang bahan-bahan tajam yang terinfeksi diperlakukan sebagai
limbah berbahaya.
Untuk memudahkan pengenalan berbagai jenis limbah yang akan
dibuang, digunakan pemisahan dengan kantong-kantong yang spesifik
(biasanya dengan warna yang berbeda atau dengan pemberian label).
42
Beberapa contoh warna yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI
adalah:
Kantong warna hitam: limbah sejenis rumah tangga biasa
Kantong warna kuning: semua jenis limbah yang harus masuk
insinerator
Kantong warna kuning strip hitam: limbah yang sebaiknya ke
insinerator, namun bisa pula dibuang ke landfill bila dilakukan
pengumpulan terpisah dan pengaturan pembuangan
Kantong warna biru muda atau transparans strip biru tua : limbah
yang harus masuk ke autoclave sebelum ditangani lebih lanjut.
Limbah yang harus dipisahkan dari yang lain adalah limbah patologis
dan infektious. Limbah infectious beresiko tinggi perlu ditangani terlebih
dahulu dalam autoclave sebelum menuju pengolahan selanjutnya atau
sebelum disingkirkan di landfill. Limbah darah yang tidak terinfeksi dapat
dimasukkan ke dalam saluran limbah kota dan dibilas dengan air, sedang yang
terinfeksi harus diperlakukan sebagai limbah berbahaya. Kontainer-kontainer
dibawah tekanan (aerosol dan sebagainya) tidak boleh dimasukkan ke dalam
insinerator.
Limbah yang telah dipisahkan dimasukkan kantong-kantong yang kuat
(dari pengaruh luar ataupun dari limbahnya sendiri) dan tahan air atau
dimasukkan dalam kontainer-kontainer logam. Kantong-kantong yang
digunakan dibedakan dengan warna yang seragam dan jelas, dan diisi
secukupnya agar dapat ditutup degan mudah dan rapat. Disamping warna
yang seragam, kantong tersebut diberi label atau simbol yang sesuai.
Kontainer harus ditutup dengan baik sebelum diangkut. Bila digunakan
kantong dan terlebih dahulu harus masuk autoclave, maka kantong-kantong
itu harus bisa ditembus oleh uap sehingga sterilisasi dapat berlangsung
sempurna. Limbah radioaktif juga harus mempunyai tanda-tanda yang standar
43
dan disimpan untuk menunggu masa aktifnya terlampaui sebelum
dikatagorikan limbah biasa atau limbah berbahaya lainnya.
Mobilitas dan transportasi limbah baik internal maupun eksternal
hendaknya dipertimbangkan sebagai bagian menyeluruh dari sistem
pengelolaaan dari institusi tersebut. Secara internal, limbah biasanya diangkut
dari titik penyimpanan awal manuju area penampungan atau menuju titik
lokasi insinerator. Alat angkutan atau sarana pembawa tersebut harus dicuci
secara rutin dan hanya digunakan untuk membawa lim bah. Di rumah sakit
modern, transportasi limbah ini
bisa menggunakan cara pneumatis dengan perpipaan, namun cara ini
tidak boleh digunakan untuk limbah patologis dan infectious. Limbah yang
akan diangkut ke luar, misalnya oleh Dinas Kebersihan setempat, harus tidak
mengandung resiko terhadap kesehatan pengangkut tersebut. Limbah
berbahaya dari rumah sakit yang akan diangkut, diatur seperti halnya aturan-
aturan yang berlaku pada limbah berbahaya lain, misalnya jenis kontainer,
tanda-tanda dan tata caranya.
Secara umum jenis pengolahan limbah rumah sakit adalah :
a. Limbah umum
Tidak diperlukan pengolahan khusus, dan dapat disatukan dengan
limbah domestik
Seluruh makanan yang telah meninggalkan dapur pada prinsipnya
adalah limbah bila tidak dikonsumsi dan sisa makanan dari bagian
penyakit menular perlu di autoclave dulu sebelum dibuang ke
landfill.
b. Limbah patologis
Pengolahan yang dilakukan adalah dengan sterilisasi, insinerasi
dilanjutkan dengan landfilling
Insinerasi merupakan metode yang sangat dianjurkan, kantong-
kantong yang digunakan untuk membungkus limbah juga harus
diinsinerasi.
44
c. Limbah radioaktif
Bahan radioaktif yang digunakan dalam kegiatan kesehatan/medis
ini biasanya tergolong mempunyai daya radioaktivitas level
rendah, yaitu di bawah 1 megabecquerel (MBq)
Limbah radioaktif dari rumah sakit dapat dikatakan tidak
mengandung bahaya yang signifikan bila ditangani secara baik
Penangan limbah dapat dilakukan di dalam area rumah sakit itu
sendiri, dan umumnya disimpan untuk menunggu waktu paruhnya
telah habis, untuk kemudian disingkirkan sebagai limbah non-
radioaktif biasa
d. Limbah kimia
Bagi limbah kimia yang tidak berbahaya, penanganannya adalah
identik dengan limbah lainnya yang tidak termasuk katagori
berbahaya
Konsep penanganan limbah kimia yang berbahaya adalah identik
dengan penjelasan sebelumnya yang terdapat dalam diktat ini
tentang limbah berbahaya
Beberapa kemungkinan daur-ulang limbah kimiawi berbahaya
misalnya :
- Solven semacam toluene, xylene, acetone dan alkohol lainnya
yang dapat diredistilasi
- Solven organik lainnya yang tidak toksik atau tidak
mengeluarkan produk toksik bila dibakar dapat digunakan
sebagai bahan bakar
- Asam-asam khromik dapat digunakan untuk membersihkan
peralatan gelas di laboratorium, atau didaur-ulang untuk
mendapatkan khromnya
- Limbah logam-merkuri dari termometer, manometer dan
sebagainya dikumpulkan untuk didaur-ulang; limbah jenis ini
45
dilarang untuk diinsinerasi karena akan menghasilkan gas
toksik
- Larutan-larutan pemerosesan dari radioaktif yang banyak
mengandung silver dapat direklamasi secara elektrostatis
- Batere-batere bekas dikumpulkan sesuai jenisnya untuk didaur-
ulang seperti : merkuri, kadmium, nikel dan timbal
Insinerator merupakan sarana yang paling sering digunakan dalam
menangani limbah jenis ini, baik secara on-site maupun off-site;
insinerator tersebut harus dilengkapi dengan sarana pencegah
pencemaran udara, sedang residunya yang mungkin mengandung
logam-logam berbahaya dibuang ke landfill yang sesusai.
Solven yang tidak diredistilasi harus dipisahkan antara solven
yang berhalogen dan nonhalogen; solven berhalogen
membutuhkan penanganan khusus dan solven non- halogen dapat
dibakar pada on-site insinerator
Limbah cytotoxic dan obat-obatan genotoxic atau limbah yang
terkontaminasi harus dipisahkan, dikemas dan diberi tanda serta
dibakar pada insinerator; limbah jenis ini tidak di autoclave karena
disamping tidak mengurangi toksiknya juga dapat berbahaya bagi
operator
Beberapa jenis limbah kimia berbahaya juga dihasilkan dari
bagian pelayanan alat-alat kesehatan, misalnya: disinfektan, oli
dari trafo dan kapasitor atau dari mikroskop yang mengandung
PCB dan sebagainya, sehingga perlu ditangani sesuai jenisnya
e. Limbah berpotensi menularkan penyakit (infectious)
Memerlukan sterilisasi terlebih dahulu atau langsung ditangani
pada insinerator ; autoclave tidak dibutuhkan bila limbah tersebut
telah diwadahi dan ditangani secara baik sebelum diinsinerasi.
f. Benda-benda tajam
46
Dikemas dalam kemasan yang dapat melindungi petugas dari
bahaya tertusuk, sebelum dibakar dalam insinerator
g. Limbah farmasi
Obat-obatan yang tidak digunakan dikembalikan pada apotik,
sedangkan yang tidak dipakai lagi ditangani secara khusus misalnya
diinsinerasi atau di landfilling atau dikembalikan ke pemasok.
h. Kontainer-kontainer di bawah tekanan: di landfilling atau didaur-
ulang.
Limbah kimiawi berbahaya yang tidak dapat didaur-ulang segera
dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan pengolahannya, misalnya melalui
sebuah insinerator, karena limbah jenis ini kadangkala toksik dan
flammable, sehingga tidak boleh dibuang melalui sistem riolering.
4. B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
I. Definisi
B 3 adalah bahan berbahaya dan beracun. B 3 merupakan bahan berbahaya
dan beracun yang memiliki sifat (toxicity, flammability, reactivity, dan
corrosivity) serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung
maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau
membahayakan kesehatan manusia.
II. Macam-macam B3:
- Logam Berat : Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg dan Zn.
- Zat Kimia : pestisida, sianida, sulfida, fenol.
- Partikel di udara : abu, asap, debu dan gas.
- Bahan yang dihasilkan oleh aktivitas organisem : panas, radiasi dan udara
- Bahan-bahan organik : sampah organik dan kotoran hewan
- Bahan-bahan sintetis : kaca, plastik dan kaleng
- Sedimen : abu gunung berapi.
47
III. Simbol limbah B3:
IV. Klasifikasi limbah B 3
Primary sludge, yaitu limbah yang berasal dari tangki sedimentasi pada
pemisahan awal dan banyak mengandung biomassa senyawa organik yang
stabil dan mudah menguap
Chemical sludge, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses koagulasi dan
flokulasi
Excess activated sludge, yaitu limbah yang berasal dari proses pengolahan
dengn lumpur aktif sehingga banyak mengandung padatan organik berupa
lumpur dari hasil proses tersebut
Digested sludge, yaitu limbah yang berasal dari pengolahan biologi dengan
digested aerobic maupun anaerobic di mana padatan/lumpur yang
dihasilkan cukup stabil dan banyak mengandung padatan organik.
V. Pengolahan Limbah
48
Terdapat banyak metode pengolahan limbah B3 di industri, tiga metode
yang paling populer di antaranya ialah chemical conditioning,
solidification/Stabilization, dan incineration.
1. Chemical Conditioning
Salah satu teknologi pengolahan limbah B3 ialah chemical
conditioning. Tujuan utama dari chemical conditioning ialah:
o menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di
dalam lumpur
o mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air dalam
lumpur
o mendestruksi organisme patogen
o memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning
yang masih memiliki nilai ekonomi seperti gas methane yang
dihasilkan pada proses digestion
o mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan
dalam keadaan aman dan dapat diterima lingkungan
Chemical conditioning terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Concentration thickening
Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi volume lumpur yang akan
diolah dengan cara meningkatkan kandungan padatan. Alat yang
umumnya digunakan pada tahapan ini ialah gravity thickener dan
solid bowl centrifuge. Tahapan ini pada dasarnya merupakan
tahapan awal sebelum limbah dikurangi kadar airnya pada tahapan
de-watering selanjutnya. Walaupun tidak sepopuler gravity
49
thickener dan centrifuge, beberapa unit pengolahan limbah
menggunakan proses flotation pada tahapan awal ini.
2. Treatment, stabilization, and conditioning
Tahapan kedua ini bertujuan untuk menstabilkan senyawa organik
dan menghancurkan patogen. Proses stabilisasi dapat dilakukan
melalui proses pengkondisian secara kimia, fisika, dan biologi.
Pengkondisian secara kimia berlangsung dengan adanya proses
pembentukan ikatan bahan-bahan kimia dengan partikel koloid.
Pengkondisian secara fisika berlangsung dengan jalan memisahkan
bahan-bahan kimia dan koloid dengan cara pencucian dan destruksi.
Pengkondisian secara biologi berlangsung dengan adanya proses
destruksi dengan bantuan enzim dan reaksi oksidasi. Proses-proses
yang terlibat pada tahapan ini ialah lagooning, anaerobic digestion,
aerobic digestion, heat treatment, polyelectrolite flocculation,
chemical conditioning, dan elutriation.
3. De-watering and drying
De-watering and drying bertujuan untuk menghilangkan atau
mengurangi kandungan air dan sekaligus mengurangi volume
lumpur. Proses yang terlibat pada tahapan ini umumnya ialah
pengeringan dan filtrasi. Alat yang biasa digunakan adalah drying
bed, filter press, centrifuge, vacuum filter, dan belt press.
4. Disposal
Disposal ialah proses pembuangan akhir limbah B3. Beberapa
proses yang terjadi sebelum limbah B3 dibuang ialah pyrolysis, wet
50
air oxidation, dan composting. Tempat pembuangan akhir limbah
B3 umumnya ialah sanitary landfill, crop land, atau injection well.
2. Solidification/Stabilization
Di samping chemical conditiong, teknologi
solidification/stabilization juga dapat diterapkan untuk mengolah
limbah B3. Secara umum stabilisasi dapat didefinisikan sebagai proses
pencapuran limbah dengan bahan tambahan (aditif) dengan tujuan
menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk
mengurangi toksisitas limbah tersebut. Sedangkan solidifikasi
didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan
penambahan aditif. Kedua proses tersebut seringkali terkait sehingga
sering dianggap mempunyai arti yang sama. Proses
solidifikasi/stabilisasi berdasarkan mekanismenya dapat dibagi
menjadi 6 golongan, yaitu:
1. Macroencapsulation, yaitu proses dimana bahan berbahaya
dalam limbah dibungkus dalam matriks struktur yang besar
2. Microencapsulation, yaitu proses yang mirip
macroencapsulation tetapi bahan pencemar terbungkus
secara fisik dalam struktur kristal pada tingkat mikroskopik
3. Precipitation
4. Adsorpsi, yaitu proses dimana bahan pencemar diikat secara
elektrokimia pada bahan pemadat melalui mekanisme
adsorpsi.
5. Absorbsi, yaitu proses solidifikasi bahan pencemar dengan
menyerapkannya ke bahan padat
6. Detoxification, yaitu proses mengubah suatu senyawa
beracun menjadi senyawa lain yang tingkat toksisitasnya
lebih rendah atau bahkan hilang sama sekali
51
Teknologi solidikasi/stabilisasi umumnya menggunakan
semen, kapur (CaOH2), dan bahan termoplastik. Metoda yang
diterapkan di lapangan ialah metoda in-drum mixing, in-situ mixing,
dan plant mixing. Peraturan mengenai solidifikasi/stabilitasi diatur oleh
BAPEDAL berdasarkan Kep-03/BAPEDAL/09/1995 dan
Kep-04/BAPEDAL/09/1995.
3. Incineration
Teknologi pembakaran (incineration ) adalah alternatif yang
menarik dalam teknologi pengolahan limbah. Insinerasi mengurangi
volume dan massa limbah hingga sekitar 90% (volume) dan 75% (berat).
Teknologi ini sebenarnya bukan solusi final dari sistem pengolahan limbah
padat karena pada dasarnya hanya memindahkan limbah dari bentuk padat
yang kasat mata ke bentuk gas yang tidak kasat mata. Proses insinerasi
menghasilkan energi dalam bentuk panas. Namun, insinerasi memiliki
beberapa kelebihan di mana sebagian besar dari komponen limbah B3
dapat dihancurkan dan limbah berkurang dengan cepat. Selain itu,
insinerasi memerlukan lahan yang relatif kecil.
Aspek penting dalam sistem insinerasi adalah nilai kandungan
energi (heating value) limbah. Selain menentukan kemampuan dalam
mempertahankan berlangsungnya proses pembakaran, heating value juga
menentukan banyaknya energi yang dapat diperoleh dari sistem insinerasi.
Jenis insinerator yang paling umum diterapkan untuk membakar limbah
padat B3 ialah rotary kiln, multiple hearth, fluidized bed, open pit, single
chamber, multiple chamber, aqueous waste injection, dan starved air unit.
Dari semua jenis insinerator tersebut, rotary kiln mempunyai kelebihan
karena alat tersebut dapat mengolah limbah padat, cair, dan gas secara
simultan.
52
BAB III
PEMBAHASAN
III. 1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Rumah
Sakit Islam Malang
1. Tujuan
A. Tujuan Umum
Terjamin dan terjaganya keselamatan hidup pasien, pegawai dan pengunjung.
B. Tujuan Khusus
1. Adanya sistem yang terpadu dalam menghadapi bencana (Disaster Plan).
2. Tidak terjadi kebakaran di lingkungan rumah sakit.
3. Pasien, pengunjung dan pegawai terjaga keamanannya.
4. Keselamatan dan kesehatan pegawai terjaga dengan baik.
5. Bahan dan barang berbahaya dapat dikelola dengan baik dan aman.
6. Kesehatan lingkungan kerja terjaga dengan baik.
7. Tersedianya sanitasi rumah sakit yang memenuhi persyaratan.
8. Semua sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit telah tersertifikasi /
kalibrasi secara berkala.
9. Limbah padat, cair dan gas dapat dikelola dengan baik dan aman.
10. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai, pasien dan
pengunjung terhadap keselamatan kerja, kebakaran dan kewaspadaan
bencana (K3).
11. Data K3 dapat terkumpul, dapat diolah dan dilaporkan kepada pihak-pihak
terkait secara lengkap.
2. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
A. Kegiatan Pokok
Adapun program pokok K3 terdiri dari :
1. Program Disaster Plan
2. Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
53
3. Program Keamanan Pasien, Pengunjung dan Pegawai
4. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5. Program Pengelolaan Bahan dan Barang Berbahaya
6. Program Kesehatan Lingkungan Kerja
7. Program Sanitasi Rumah Sakit
8. Program Sertifikasi / Kalibrasi Sarana, Prasarana dan Peralatan
9. Program Pengelolaan Limbah Padat, Cair dan Gas
10. Program Diklat K3
11. Program Pengumpulan, Pengolahan dan Pelaporan Data
B. Rincian Kegiatan
1. PROGRAM DISASTER PLAN, terdiri dari :
a. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
b. Penanggulangan Kecelakaan Massal
c. Penanggulangan Keracunan Massal
d. Penanggulangan Gempa Bumi
e. Penanggulangan Bencana Banjir
2. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
KEBAKARAN
a. Identifikasi resiko kebakaran.
b. Penyusunan petunjuk pelaksanaan penanggulangan kebakaran.
c. Pemantauan peralatan penanggulangan kebakaran.
d. Pelatihan penanggulangan bencana kebakaran dan Evakuasi.
3. PROGRAM KEAMANAN PASIEN, PENGUNJUNG DAN
PEGAWAI
a. Pemantauan alat keamanan pasien.
b. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas.
4. PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEGAWAI
a. Pemeriksaan kesehatan pegawai.
b. Pelaporan tentang Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
54
5. PROGRAM PENGELOLAAN BAHAN DAN BARANG
BERBAHAYA
a. Identifikasi resiko kontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
dan tempat-tempat beresiko.
b. Pemantauan tempat penyimpanan bahan berbahaya dan beracun.
c. Penyusunan prosedur tetap penanggulangan kontaminasi Bahan
Berbahaya dan Beracun.
d. Pelatihan penanggulangan kontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun
6. PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA
a. Pengelolaan penyehatan lingkungan kerja.
b. Pengelolaan penyehatan air.
c. Pengelolaan sampah dan limbah.
d. Pengelolaan makanan dan minuman.
e. Pengelolaan tempat cucian.
f. Pengendalian serangga, tikus dan kucing.
g. Sterilisasi / Disenfeksi
h. Perlindungan radiasi.
i. Upaya penyuluhan kesehatan lingkungan.
7. PROGRAM SANITASI RUMAH SAKIT
a. Program sanitasi Kerumahtanggaan yang meliputi penyehatan ruang
dan bangunan serta lingkungan rumah sakit.
b. Program sanitasi dasar yang meliputi penyediaan air minum,
pengelolaan limbah cair dan padat, penyehatan makanan dan
minuman, pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu.
c. Program dekontaminasi yang meliputi kontaminasi lingkungan karena
mikroba, bahan kimia dan radiasi.
d. Program pengembangan manajemen dan perundang-undangan yang
meliputi penyusunan pedoman kerja dan pengembangan tenaga
sanitasi melalui pelatihan, penyuluhan dan konsultasi
55
8. PROGRAM SERTIFIKASI/ KALIBRASI SARANA, PRASARANA
DAN PERALATAN
Sertifikasi dan pemeliharaan lift, instalasi listrik, genset, penangkal petir,
instalasi radiologi, instalasi laboratorium dan pengolahan limbah.
9. PROGRAM PENGELOLAAN LIMBAH PADAT, CAIR DAN GAS
a. Penanganan limbah rumah sakit
b. Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat, cair dan gas
10. PROGRAM DIKLAT K – 3
a. Pengembangan keilmuan tenaga K3 melalui seminar, pelatihan, dan
lain-lain.
b. Sosialisasi, penyuluhan dan konsultasi untuk seluruh pegawai.
11. PROGRAM PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN
PELAPORAN DATA
a. Program pengumpulan seluruh data-data K3 RSI Malang
b. Program pengolahan data
c. Program Pelaporan, Evaluasi, Rekomendasi dan Tindaklanjut.
3. Cara Melaksanakan Kegiatan
Setiap program, masing-masing akan dilengkapi dengan kerangka acuan
program sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Masing-masing program akan
dikoordinir oleh masing-masing anggota dari staf Tim K3 yang telah diberi tugas.
Setiap koordinator melaporkan kepada ketua Tim K3 dibantu oleh sekretaris Tim K3
untuk menyusun laporannya. Data K3 dapat diperoleh dari pelaksanaan unit-unit yang
terkait dengan pelaksanaan program K3, contohnya seperti : unit kerja IPS / RT untuk
sertifikasi / kalibrasi, pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan, pemeriksaan
kesehatan pegawai dan diklat oleh unit kerja kepegawaian dan diklat, pengadaan B3
oleh tim pengadaan, dan lain-lain.
4. Sasaran
1. Tersedianya tenaga yang terlatih dalam menghadapi bencana minimal 75
% dari seluruh jumlah tenaga pada unit-unit kerja yang ditunjuk.
2. Mengurangi angka kejadian kebakaran sampai 100 %.
56
3. Melengkapi fasilitas keamanan pasien minimal 75 %.
4. Mengurangi angka kecelakaan kerja sebesar 50 %.
5. Mengurangi angka kontaminasi B3 sampai dengan 50 %
6. Program penyehatan lingkungan dilakukan secara rutin dan terus-menerus
sepanjang tahun sesuai kerangka acuan.
7. Tersedianya fasilitas sanitasi lengkap 100 %.
8. Sarana, prasarana dan peralatan tersertifikasi/ kalibrasi 100 %.
9. Hasil pengolahan masih dalam standar/ nilai normal 100 %.
10. Tersedianya tenaga pendukung dan staf terlatih minimal 50 %.
11. Pencatatan/ pelaporan K3 lengkap dan disebarluaskan ke institusi terkait
di luar maupun di dalam rumah sakit.
5. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan
Evaluasi pelaksanaan setiap program akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan
sekali, dan dilakukan oleh masing-masing anggota staf Tim K3 sebagai koordinator
program beserta unit-unit lain yang terkait dengan pelaksanaan program K3 tersebut.
Sedangkan laporan evaluasi setiap pelaksanaan program akan disusun setiap 3
(tiga) bulan sekali setelah evaluasi 3 (tiga) bulanan dilakukan. Laporan evaluasi akan
diserahkan kepada Direktur RSI Malang dan unit-unit lain yang terkait dengan K3.
6. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan
Pencatatan pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setiap kali kegiatan selesai
berlangsung/ setiap kegiatan selesai dilakukan. Dimana setiap catatan tersebut akan
dihimpun oleh masing-masing koordinator program K3 dan diserahkan kepada
Sekretaris Panitia K3 untuk disusun Laporan Pelaksanaan Program K3 selama 3
(tiga) bulanan.
Seluruh pelaksanaan program akan dievaluasi oleh Tim K3 beserta unit-unit
lain yang terkait dengan program-program K3 tersebut. Evaluasi dilakukan selama 3
(tiga) bulanan dan dilaporkan kepada Direktur.
III. 2 Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit Islam Malang
1. Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Islam Malang
Kegiatan kesehatan lingkungan Rumah Sakit Islam (RSI) Malang
57
menerapkan Sembilan progam, yaitu:
1. Program penyehatan lingkungan kerja antara lain : penyehatan bangunan
dan ruangan kerja termasuk pencahayaan, penghawaan dan kebisingan.
2. Program penyehatan makanan dan minuman antara lain : pengadaan bahan
makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyajian
makanan, pendistribusian makanan serta pemeliharaan tempat pengolahan
makanan dan pemeriksaan alat makan dan makanan serta pemeriksaan
kesehatan petugas gizi / penjamah makanan dan penyehatan air.
3. Program penyehatan air antara lain : pemeriksaan rutin kondisi perpipaan /
saluran air di lingkungan RSI Malang, pengajuan pemeriksaan rutin oleh
dinas terkait, melakukan jadwal pemeriksaan rutin air baik secara kimia
maupun mikrobiologi.
4. Program penyehatan tempat pencucian (linen / laundry) antara lain :
kegiatan penyehatan linen yang dilakukan secara rutin, pemakaian APD
bagi petugas, pemeliharaan fasilitas linen, proses laundry (infeksius dan non
infeksius), sanitasi, gudang linen, dan pemeriksaan berkala pada petugas
linen.
5. Program penanganan sampah dan limbah antara lain : penyediaan,
pemantauan dan pemeliharaan fasilitas pembuangan sampah / limbah padat,
cair dan gas serta pengolahan limbah padat, cair dan gas.
6. Program pengendalian serangga, tikus, kucing dan hewan berbahaya lain,
antara lain : pengendalian nyamuk, kecoa / semut, lalat, tikus, dan kucing
serta pemeliharaan kebersihan.
7. Program sterilisasi / desinfeksi antara lain : penggunaan desinfektan,
sterilisasi, pengemasan, penyimpanan serta indikasi kuat untuk tindakan
sterilisasi / desinfeksi.
8. Program perlindungan radiasi antara lain : kegiatan umum pengamanan,
pengawasan kontaminasi, pemantauan perorangan dan tempat kerja serta
pelayanan pemantauan.
58
9. Program upaya penyuluhan kesehatan lingkungan antara lain : sosialisasi
dan simulasi K3 pada internal dan eksternal lingkungan Rumah Sakit Islam
Malang.
Fasilitas sanitasi RSI
1. Fasilitas penyediaan air berupa air PDAM dan sumur gali/ bor 3 (dua) buah
dengan penempatan di samping masjid, depan kelas IRNA III-A dan
belakang gedung IRNA VIP.
2. Toilet sejumlah 57 buah.
3. Kamar mandi sejumlah 57 buah
4. Pembuangan sampah padat medis berupa incinerator.
5. Pembuangan sampah padat non medis berupa tempat sampah disetiap
ruangan.
6. Pengendalian tikus menggunakan racun tikus.
7. Pengendalian serangga menggunakan lem lalat.
8. Pembuangan limbah cair menggunakan septik tank.
9. Pembuangan limbah gas menggunakan cerobong asap yang dialirkan ke
udara dengan ketinggian tertentu.
2. PENGELOLAAN LIMBAH PADAT, CAIR DAN GAS RSI MALANG
Rumah Sakit Islam Malang merupakan salah satu fasilitas kesehatan
masyarakat yang ada di Kota Malang. Dengan berjalannya kegiatan didalam
rumah sakit, maka salah satu dampaknya adalah timbulnya limbah. Adapun
jenis limbah yang muncul adalah limbah padat, cair dan gas. Hal ini perlu
diantisipasi efek-efek yang akan ditimbulkannya terhadap kualitas kesehatan
dan keselamatan para pegawai, pasien maupun pengunjung di RSI Malang.
Oleh karena itu perlu adanya program pengelolaan limbah padat, cair dan gas
yang ada di RSI Malang.
Sampah rumah sakit adalah bahan yang tidak berguna, tidak dipergunakan
lagi ataupun yang terbuang yang dapat dibedakan menjadi sampah medis dan
non medis, dan dikategorikan menjadi : sampah infeksius, sampah radioaktif,
59
sampah sitotoksik dan sampah umum (domestik).Sedangkan limbah rumah
sakit adalah hasil buangan yang berasal dari rumah sakit yang kemungkinan
mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, bahan radioaktif yang
berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.
A. Pengolahan limbah RSI sebagai berikut:
1. Terdapat IPAL.
2. Adanya cerobong gas buang di Instalasi Kamar Bedah.
3. Tempat sampah medis, non medis dan sampah benda tajam.
4. Penanganan limbah rumah sakit, antara lain : limbah padat, cair dan gas.
Penanganan limbah padat, terdiri dari : sampah medis, sampah non
medis dan sampah benda tajam.
Penanganan limbah cair melalui septik tank dan IPAL.
Penanganan limbah gas melalui cerobong asap yang diarahkan ke
udara bebas.
5. Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas pengumpul dan pengelola
limbah rumah sakit seperti : sarung tangan, masker, apron/ skoret dan
lain-lain.
6. Pemeliharaan seluruh fasilitas pengolah limbah secara berkala.
B. Tujuan dari kegiatan pengolahan limbah:
1. Tujuan Umum
Terciptanya lingkungan Rumah Sakit Islam Malang yang bersih, sehat
dan aman bagi pegawai, pasien dan pengunjung.
2. Tujuan Khusus
a. Tidak terjadi pencemaran air, udara dan lingkungan.
b. Tidak terjadi penimbunan limbah rumah sakit.
c. Hasil uji laboratorium terhadap zat hasil olahan limbah diambang
batas normal.
C. Kegiatan pokok dan rinciannya:
Kegiatan Pokok, antara lain :
1. Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat, cair dan gas.
60
2. Penanganan limbah rumah sakit.
3. Pemeliharaan fasilitas pengolah limbah padat, cair dan gas.
D. Rincian Kegiatan, antara lain :
1. Pembangunan IPAL.
2. Pembuatan cerobong gas buang di Instalasi Kamar Bedah.
3. Melengkapi dan menambah tempat sampah medis dan non medis di
ruangan.
4. Penanganan limbah rumah sakit, antara lain : limbah padat, cair dan gas.
Penanganan limbah padat, terdiri dari : sampah medis, sampah non
medis dan sampah benda tajam.
Penanganan limbah cair melalui septik tank dan IPAL.
Penanganan limbah gas melalui cerobong asap yang diarahkan ke
udara bebas.
5. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas pengumpul dan
pengelola limbah rumah sakit seperti : sarung tangan, masker, apron/
skoret dan lain-lain.
6. Pemeliharaan seluruh fasilitas pengolah limbah secara berkala.
E. Cara melaksanakn kegiatan pengolahan limbah di RSI Malang :
Koordinator program dari Tim K3 yang ditunjuk akan mengkoordinir
dan memonitor jalannya pelaksanaan kegiatan program pengolahan limbah
padat, cair dan gas yang dilaksanakan oleh unit kerja Urusan Rumah Tangga
dan juga unit kerja Urusan Pemeliharaan Sarana. Pengelolaan limbah padat
non medis bekerjasama dengan TPA (wilayah Lowokwaru). Sedangkan
limbah padat medis akan diproses di incinerator RSI Malang dengan jadwal
tertentu. Sementara ini untuk limbah cair dilakukan pembuangan ke septik
tank. Sedangkan limbah gas dibuang ke udara bebas melalui pipa / cerobong
asap.
F. Evaluasi kegiatan program :
Evaluasi pelaksanaan kegiatan program akan dilaksanakan setiap 3 (tiga)
bulan sekali oleh Koordinator Program dari Tim K3 beserta dengan unit
61
kerja Rumah Tangga dan Urusan Pemeliharaan Sarana khususnya dan unit-
unit kerja lain yang terkait dengan pelaksanaan pengolahan limbah padat,
cair dan gas.
Hasil evaluasi tersebut akan dilaporkan kepada Ketua Tim K3 oleh
Koordinator Program Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas.
III. 3 B3, APD, dan Penanggulangan Kebakaran Rumah Sakit Islam Malang
BAHAN-BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYADI RUMAH SAKIT ISLAM MALANG
No. Nama Bahan Nama Kimia Lokasi Penyimpanan Jenis Bahaya1. Air Raksa Mercury Bagian Perawatan Iritasi2. Alkohol Ethyl Alcohol, Ethanol Bagian Perawatan,
FarmasiIritasi, Mudah Terbakar
3. Barium Sulfat Barium Sulphate Radiologi Iritasi4. Cidex Glutaraldehyde Bagian Perawatan,
FarmasiIritasi
5. Elpiji Liquid Petroleum Gas Rumah Tangga, Gizi Mudah Terbakar6. Fenol Phenol Rumah Tangga Iritasi, Toksik7. Formalin Formaldehyde Farmasi, Gudang Iritasi, Mudah
Terbakar8. Freon Carbon Tetrachloride Pemeliharaan Sarana Iritasi9. Hidrogen Peroksida Hydrogen Peroxide Bagian Perawatan,
FarmasiReaktif, Iritasi
10. Karbondioksida Carbon Dioxide Kamar Bedah, Laboratorium
Iritasi
11. Klorin Chlorine Pemeliharaan Sarana, Rumah Tangga
Reaktif, Iritasi
12. Las Karbid Acetylene Pemeliharaan Sarana Mudah Terbakar, Mudah Meledak
13. Metanol Methyl Alcohol Laboratorium Mudah Terbakar, Iritasi, Toksik
14. Natrium Hidroksida Sodium Hydroxide Laboratorium Iritasi15. Nitrogen Dioksida Nitrogen Dioxide Kamar Bedah,
Pemeliharaan SaranaIritasi
16. Timbal Plumbum Radiologi Toksik 17. Xylen Xylene Laboratorium Mudah Terbakar,
Iritasi
62
PROGRAM PENGELOLAAN BAHAN DAN BARANG BERBAHAYA1. Identifiaksi resiko kontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan tempat –
tempat beesiko.2. Pemantauan tempat penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun.3. Penyususnan prosedur tetap penanggulangan kontaminasi Bahan Berbahaya dan
Beracun.4. Pelatihan penanggulanagan Bahan Berbahaya dan Beracun.
63
BAB IV
PENUTUP
4.1. Simpulan
Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran
dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun
rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya
dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan
pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya
dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat
kerja.
Tujuan K3 di RS adalah dapat menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang terkait Kesehatan dan KeselamatanKerja di Rumah Sakit
dari aspek pengelolaannya, serta lebih meningkatkan profesionalisme SDM
Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang ada di rumah sakit. Selanjutnya
diharapkan para SDM Kesehatan dan Keselamatan Kerja tersebut lebih peka
dan kreatif dalam implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah
Sakit. Dengan penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit
yang baik dan benar, maka berbagai PAK dan KAK dapat diminimalisasi,
produktivitas pekerja dapat ditingkatkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan
profit bagi Rumah Sakit.
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifatnya
dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan
atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia
serta mahluk hidup lainnya.
64
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah instrumen yang
memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar
dari bahaya akibat kecelakaan kerja. K3 tersebut bertujuan mencegah,
mengurangi, bahkan meniadakan resiko kecelakaan kerja (zero accident).
Instalasi Gawat Darurat adalah salah satu bagian di rumah sakit yang
menyediakan penangan awal bagi pasien yang berada pada kondisi kritis dan
mengancam jiwa. IGD bertujuan untuk mencegah kematian dan terjadi
kecacatan.
Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat-alat yang digunakan untuk
melindungi diri dan mencegah dari bahaya dan efek samping akibat kerja, hal
ini bertujuan agar pekerja tidak terkontaminasi bahan-bahan berbahaya.
Pada RSI UNISMA belum banyak kasus K3 yang tejadi baik penyakit
akibat kerja maupun penyakit yang berhubungan degan kerja.
4.2. Saran
Salah satu komponen yang dapat meminimalisir Kecelakaan dalam kerja
adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai kemampuan untuk
menangani korban dalam kecelakaan kerja dan dapat memberikan penyuluhan
kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan
kerja.
65
DAFTAR PUSTAKA
Fakultas teknik Universitas Indonesia. 2008. Panduan Akademik Program Pendidikan Sarjana Teknik 2008-2011. Fakultas teknik Universitas Indonesia. Depok Hunt, G.E. 1995.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JaminanSosial
Tenaga Kerja.
Industrial Pollution Prevention Handbook. Freman. USA Manahan, S.E. 2005. Environmental Chemistry. CRC Press: USA Metcalf and Eddy. 1991. Wastewater Engineering. McGrawHill: USA Ostler, N.K. 1998. Industrial Waste Stream generation (vol 6). Prentice Hall.
USA. Poerwanto, Helena dan Syaifullah. Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan
dan Keselamatan Kerja. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2005.
Qasim, S.R. 1985. Wastewater Treatment Plants: Planning, Design, and Operation. Holt, Rinehart, and Winston: USA
Silalahi, Bennett N.B. [dan] Silalahi,Rumondang.1991. Manajemen
keselamatan dankesehatan kerja.[s.l]:Pustaka Binaman Pressindo.
Suma'mur .1985. Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan.
Jakarta :Gunung Agung, 1985.
Universitas Indonesia. Rencana Strategis Universitas Indonesia 2007-2012: Membangun masa Depan Yang Lebih Baik Melalui Keunggulan Universitas Indonesia. Download dari http//www.ui.edu/download/renstra.ui.pdf
73