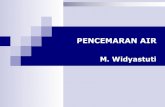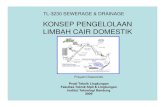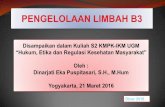limbah cair2.pdf
Transcript of limbah cair2.pdf
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Selaras dengan laju pembangunan nasional, pembangunan
di sektor industri pun maju dengan pesat. Pembangunan di sektor ini dianggap mampu memberikan nilai tambah secara nasional serta mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan teknologi bagi kehidupan manusia. Sebagai realisasi dan konsekuensi kegiatan pembangunan di sektor industri, muncul pula berbagai masalah lingkungan secara langsung maupun tidak langsung berupa pengotoran perairan oleh limbah cair. Pengamatan menunjukkan bahwa dari berbagai jenis industri, ternyata industri kecil dan industri rumah tangga sangat berpotensi memberikan kontribusi besar pada pengotoran perairan, salah satunya pabrik tahu. Kondisi yang demikian itu disebabkan oleh berberapa faktor, yaitu kurangnya pengetahuan pengusaha tentang pencemaran lingkungan, teknologi proses produksi, serta tidak adanya unit sarana pengolahan limbah cair (Nurtiyani, 2000).
Tahu merupakan suatu produk yang terbuat dari hasil penggumpalan protein kedelai. Dalam perdagangan dikenal dua jenis tahu, yaitu tahu biasa dan tahu Cina, yang mana kedua jenis tahu ini berbeda dalam hal bentuk dan cara pembuatannya. Tahu dikenal masyarakat sebagai makanan sehari-hari yang umumnya sangat digemari serta mempunyai daya cerna yang tinggi (Hartati, 1988). Kedelai dan produk makanan yang dihasilkannya merupakan sumber makanan yang dapat diperoleh dengan mudah dan murah serta memiliki kandungan gizi yang tinggi. Industri tempe dan tahu menghasilkan limbah organik baik dalam bentuk cair maupun padat, namun kebanyakan industri tersebut membuang limbahnya secara langsung ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga mencemari lingkungan.
1
-
2
Sebagian besar limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuatan tahu adalah cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut air dadih, dimana cairan ini mengandung kadar protein yang tinggi. Limbah cair ini sering dibuang secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga menghasilkan bau busuk dan mencemari sungai. Sumber limbah cair lainnya berasal dari pencucian kedelai, pencucian peralatan proses, pencucian lantai dan pemasakan serta larutan bekas rendaman kedelai. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh industri pembuat tahu kira-kira 15-20 l/kg bahan baku kedelai (EMDI dan BAPEDAL, 1994). Sedangkan karakteristik dari limbah cair tahu adalah temperaturnya melebihi temperatur normal badan air penerima (60-80C), warna limbah putih kekuningan dan keruh, pH < 7, COD (Chemical Oxygen Demand) 1534 mg/L, BOD (Biochemical Oxygen Demand) 950 mg/L, TSS (Total Suspended Solid) 309 mg/L. Padatan tersebut sebagian berupa kulit kedelai, selaput lendir, protein, lemak, dan karbohidrat. Limbah cair ini di perairan selain berpotensi menimbulkan bau busuk karena proses anaerob pada perombakan protein, lemak, dan karbohidrat oleh mikroorganisme, juga menambah beban pencemaran air (Supriyanto, 1997).
Dalam kegiatan industri, air limbah akan mengandung zat-zat atau kontaminan yang dihasilkan dari sisa bahan baku, sisa pelarut atau bahan aditif, produk terbuang atau gagal, pencucian dan pembilasan peralatan, blowdown beberapa peralatan seperti kettle boiler dan sistem air pendingin, serta sanitary wastes. Agar dapat memenuhi baku mutu, industri harus menerapkan prinsip pengendalin limbah secara cermat dan terpadu baik di dalam proses produksi (in-pipe pollution prevention) dan setelah proses produksi (end-pipe pollution prevention). Pengendalian dalam proses produksi bertujuan untuk meminimalkan volume limbah yang ditimbulkan, juga konsentrasi dan toksisitas kontaminannya. Sedangkan pengendalian setelah proses produksi dimaksudkan untuk menurunkan kadar bahan pencemar sehingga pada akhirnya air tersebut memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan. Tujuan
2
-
3
utama pengolahan air limbah ialah untuk mengurai kandungan bahan pencemar di dalam air terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroorganisme patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam (Hidayat, 2008).
Industri pembuatan tahu dan tempe harus berhati-hati dalam program kebersihan pabrik dan pemeliharaan peralatan yang baik karena secara langsung hal tersebut dapat mengurangi kandungan bahan protein dan organik yang terbawa dalam limbah cair. Kunci untuk mengurangi pencemaran adalah mencegah bahan-bahan yang masih bermanfaat terbawa limbah cair. Larutan bekas pemasakan dan perendaman dapat didaur ulang kembali dan digunakan sebagai air pencucian awal kedelai. Perlakuan hati-hati juga dilakukan pada gumpalan tahu yang terbentuk dilakukan seefisien mungkin untuk mencegah protein yang terbawa dalam air dadih (EMDI dan BAPEDAL, 1994).
Biasanya industri fermentasi tidak mengandung material toksik, tetapi limbah tersebut banyak mengandung senyawa organik yang mudah didegradasi oleh mikroorganisme. Sehingga limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan perlu diolah terlebih dahulu baik secara fisik, kimia atau secara hayati menggunakan mikroorganisme. Kandungan fosfor, nitrogen dan sulfur serta unsur hara lainnya dengan konsentrasi tinggi di dalam limbah cair tahu akan mempercepat pertumbuhan tumbuhan air. Kondisi demikian lambat laun akan menyebabkan kematian biota dalam air (Alaert dan Santika, 1984).
Penanganan limbah secara fisik yaitu dengan menyisihkan limbah padat secara fisik dari bagian cairan, sedangkan secara kimiawi partikel diendapkan atau dikonjugasi atau flokulasi menggunakan ferrous atau ferisulfat, almunium sulfat atau kalsium hidroksida sebagai koagulan. Penanganan limbah secara hayati, dapat menggunakan mikroorganisme baik secara aerob atau anaerob (Sugiharto, 1987).
Berdasarkan data karakteristik air limbah pabrik tahu diketahui bahwa komposisi terbesar dari kandungan senyawa
-
4
organiknya adalah protein (1,72%), lemak (0,63%), dan karbohidrat (0,105%), sehingga dari komposisi tersebut telah dilakukan penelitian untuk mengurangi kandungan senyawa organiknya, diantaranya Nurtiyani (2000) menggunakan Chlorella sp untuk menurunkan kadar organik dari limbah cair tahu, dimana Chlorella sp merombak senyawa organik yang terkandung di dalam limbah cair tahu hingga ratusan mg/L. Penelitian pengurangan kadar protein air limbah pabrik tahu (ALPT) sebelumnya telah dilakukan oleh M. Ridwan (2003) dengan menggunakan bakteri penghasil enzim protease yang diisolasi dari ALPT tersebut, dimana bakteri penghasil enzim protease tersebut mampu mendegradasi protein dalam ALPT sebanyak 55,934% selama 48 jam. Penelitian ini dilanjutkan oleh Didik Darmadi (2006) yang memanfaatkan enzim amobil yang dihasilkan oleh bakteri penghasil enzim protease. Penggunaan enzim proteolitik yang lain untuk mengurangi kandungan protein dalam ALPT adalah enzim yang terdapat dalam buah nanas (enzim bromelin) yang telah dilakukan oleh Maria Etasari (2005). Hasilnya protein yang terdegradasi sebesar 10,3% selama 5 jam. Pada penelitian tersebut enzim bromelin yang digunakan tidak dapat digunakan berkali-kali karena enzimnya dalam keadaan tidak teramobilisasi. Supaya enzim dapat digunakan berkali-kali maka enzim tersebut haruslah dalam bentuk teramobilisasi sehingga mudah memisahkannya setelah digunakan. Di samping dapat digunakan berkali-kali, dengan amobilisasi juga dapat meningkatkan aktivitas enzim bila dibandingkan dengan enzim yang tidak diamobilisasi, lebih efisien dan lebih murah (Smith, 1990). Pada penelitian ini dicoba menggunakan enzim bromelin amobil yang diisolasi dari nanas dengan alginat sebagai pengamobilnya untuk mengurangi kandungan protein dalam ALPT. Penggunaan alginat sebagai pengamobil dikarenakan mudah didapatkan dan harganya terjangkau.
Enzim bromelin di sini masih dalam bentuk kasar (crude) yang tidak murni, karena pemurnian enzim membutuhkan biaya yang mahal. Sedangkan enzim yang digunakan dalam penelitian
4
-
5
ini hanya untuk mengurangi kandungan protein pada ALPT, maka penggunaan enzim murni menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, tahap pemurnian hanya dilakukan sampai pada tahap pengendapan enzim dengan menggunakan larutan amonium sulfat jenuh. Pengukuran kandungan protein dalam ALPT pada penelitian ini menggunakan metode Bradford.
1.2 Perumusan Masalah
Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah apakah enzim bromelin amobil yang diisolasi dari buah nanas dapat mengurangi kandungan protein dalam air limbah pabrik tahu (ALPT), dengan adanya faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim berupa konsentrasi alginat (zat pengamobil), pH, dan konsentrasi substrat, serta pengaruh perulangan penggunaan enzim bromelin amobil terhadap pengurangan kadar protein dalam ALPT.
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengurangan kandungan protein dalam ALPT menggunakan enzim bromelin amobil dengan pengaruh konsentrasi alginat, pH, dan konsentrasi substrat, serta juga untuk mengetahui pengaruh perulangan penggunaan enzim bromelin amobil terhadap pengurangan kadar protein dalam ALPT.
1.4 Batasan Penelitian
Untuk menentukan kandungan protein dalam ALPT hanya dibatasi pada uji secara Kolorimetri. Serta pengurangan kandungan protein dalam ALPT dilakukan dengan optimasi konsentrasi alginat (sebagai pengamobil), pH dan konsentrasi substrat (ALPT), serta uji perulangan.