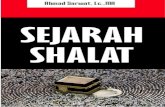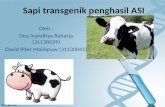LC Dan Participatory Planning by Herman Hermit
-
Upload
herman-hermit -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of LC Dan Participatory Planning by Herman Hermit

1
ALUR PROGRAM DAN KEGIATAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
Oleh Herman Hermit
(dikutip dari buku Herman Hermit, 2009. Teknik Penaksiran Harga Tanah Perkotaan: Teori
dan Praktek Penilaian Tanah, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung)

2
Alur Pengelolaan Program Konsolidasi Tanah
Masukan
Proses
Keluaran
RTRW
Kabupaten/K
ota
RPJMD
Kabupaten/K
ota
Penetapan Lokasi-lokasi
Konsolidasi Tanah oleh
Bupati/Walikota.
Daftar Lokasi dan
Peta Lokasi
Rencana
Konsolidasi Tanah
di Wilayah
Kabupaten/Kota.
Pembentukan Tim Koordinasi
Konsolidasi Tanah dan Satgas
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah,
baik di Tingkat Propinsi (oleh
Gubernur) maupun di Tingkat
Kabupaten (oleh
Bupati/Walikota).
Tim Koordinasi
Konsolidasi Tanah
dan Satgas
Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah
Tingkat Propinsi
dan Tingkat
Kabupaten/Kota.
Pembinaan Pelaksanaan
Konsolidasi oleh Kepala BPN
Pengendalian Pelaksanaan
Konsolidasi oleh Kakanwil
BPN Propinsi
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Konsolidasi oleh
Kakan Pertanahan Kab/Kota.
Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
menyelenggarakan pengelolaan-
pengelolaan:
Bendaharawan khusus
Buku Kas Umum (BKU)
Buku Pembantu (BP) Dana
Konsolidasi Tanah
Daftar Rencana Kegiatan
Konsolidasi Tanah (DRKK)
Laporan pertanggungjawaban
bulanan Kepala Kantor Pertanahan
atas pengelolaan dana konsolidasi
tanah kepada Kepala BPN melalui
Kabiro Keuangan BPN, dengan
tembusan disampaikan kepada
Kakanwil BPN.
Laporan
Pertanggung-
jawaban
Pelaksanaan
Konsolidasi
Tanah dari
Kepala Kantor
Pertanahan
kepada Kepala
BPN
Sumber Informasi: Diolah Herman Hermit dari Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun
1991 tentang Konsolidasi Tanah.

3
Alur Pengelolaan Kegiatan Konsolidasi Tanah
Masukan
Proses
Keluaran
Perangkat
Pengelolaan
Program
Konsolidasi
Tanah (Lihat:
Alur
Pengelolaan
Program)
Pencapaian persetujuan para
pemilik tanah yang setara dengan
sekurang-kurangnya 85% dari
luas tanah yang akan
dikonsolidasi.
Kesiapan
seluruh pemilik
tanah yang akan
dikonsolidasi.
Penyiapan/Penyusunan:
Kesepakatan nilai atau harga
“Sumbangan Tanah Untuk
Pembangunan” (STUP) bagi
keperluan: prasarana
lingkungan atau fasilitas
umum dan “Tanah Pengganti
Biaya Pelaksanaan”(TPBP).
Rencana Penataan Kapling.
Persetujuan seluruh pemilik
peserta konsolidasi tanah
terhadap kedua hal tersebut di
atas.
Pelepasan hak atas tanah dari
seluruh peserta konsolidasi
kepada negara di Kantor
Pertanahan.
Status Tanah
menjadi Tanah
Negara
Usulan Kepala Kantor Pertanahan
kepada Kepala BPN melalui
Kakanwil BPN tentang Penetapan
tanah-tanah tersebut sebagai tanah
obyek konsolidasi.
SK Kepala BPN
tentang
Penetapan
Tanah Obyek
Konsolidasi
Pemberian Surat Izin
Menggunakan Tanah (SIMT) atas
Tanah Pengganti Biaya
Pelaksanaan (TPBB) oleh Kepala
Kantor Pertanahan kepada pihak
Surat Izin
Menggunakan
Tanah (SIMT)
untuk pihak
ketiga/pembeli.

4
ketiga/pembeli.
Bukti
pembayaran
biaya
administrasi.
(Biaya Uang
Pemasukan
dibebaskan)
Gambar
rencana tata
kapling
Surat Izin
Mengguna-
kan Tanah
(SIMT) bagi
pihak ketiga.
Pemberian Hak atas tanah (Hak
Milik) kepada para peserta
konsolidasi tanah dan pihak
ketiga yang membeli “Tanah
Pengganti Biaya Pelaksanaan”
(TPBP) sesuai dengan gambar
rencana tata kapling.
SK
Pemberian
Hak atas
tanah (Hak
Milik)
SK
Pemberian
Hak
Honorarium
PPAT
Pembuatan Akta oleh PPAT
(Pejabat Pembuat Akta Tanah)
tentang Pemberian Hak Baru
Akta PPAT
Bukti
pembayaran
Pendaftaran
Tanah dan
Sertipikat
Pembukuan dan Pendaftaran
hak pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung.
Sertipikat Hak
Milik atas
tanah untuk
setiap peserta
konsolidasi
dan pihak
ketiga.
Sumber Informasi: Diolah Herman Hermit dari substansi Peraturan Kepala
BPN No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

5
Ringkasan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang
Konsolidasi Tanah :
Konsolidasi Tanah merupakan suatu kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali
penguasaan-pemilikan dan penggunaan tanah sekaligus sebagai suatu upaya pengadaan
tanah bagi pembangunan, mempunyai tujuan-tujuan mendasar: meningkatkan dayaguna
dan hasilguna penggunaan tanah, menyelaraskan kepentingan individu dengan fungsi
sosial tanah, meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam
dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (Pasal 1 dan Konsiderans)
Masyarakat pemilik tanah baik di perkotaan maupun di perdesaan atas biaya sendiri
mempunyai hak melakukan konsolidasi tanah apabila sekurang-kurangnya 85 persen dari
luas tanah mendapat persetujuan pemiliknya dan mendapat Penetapan Lokasi dari
Bupati/Walikota sesuai dengan rencana peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 4 dan 7)
Untuk memungkinkan mencapai kondisi penguasaan-pemilikan tanah dan penggunaan
tanah dalam bentuk persil tanah yang teratur/terencana, pemilik tanah peserta konsolidasi
harus melepaskan hak atas tanahnya terlebih dahulu kepada negara (menjadi tanah
negara) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Obyek Konsolidasi Tanah oleh Kepala
Badan Pertanahan Nasional atas usul Kepala Kantor Pertanahan melalui Kepala Kantor
Wilayah BPN. (Pasal 8 ayat 1)
Obyek Konsolidasi Tanah diberikan kembali kepada para peserta Konsolidasi Tanah
sesuai dengan rencana tata kaveling yang disetujui oleh para peserta Konsolidasi Tanah
dan dibebaskan dari pembayaran Uang Pemasukan Negara namun tetap harus membayar
Biaya Administrasi dan Biaya Pendaftaran Tanah. (Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3)
Pemenuhan biaya pembangunan prasarana dan sarana lingkungan serta biaya pelaksanaan
konsolidasi tanah, bersumber dari "Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan" (STUP) atau
bentuk lain yang bisa diuangkan dari para peserta. (Pasal 6 dan 7)
Pihak yang ikut terlibat dalam program Konsolidasi Tanah berikut fungsinya masing-
masing adalah sebagai berikut: (1) Kepala BPN sebagai pembina pelaksanaan, (2) Kepala
Kantor Wilayah BPN sebagai pengendali pelaksanaan, (3) Kepala Kantor Pertanahan
sebagai penanggung jawab pelaksanaan, (4) Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah yang
dibentuk Gubernur untuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di Daerah
Propinsi, dan (4) Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah dan Satuan Tugas Pelaksanaan

6
Konsolidasi Tanah yang dibentuk Bupati/Walikota untuk melakukan koordinasi dengan
instansi-instansi terkait di Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 5)

7
PARTICIPATORY PLANNING AND BUILDING
& PRINSIP DASAR KONSOLIDASI TANAH
oleh Herman Hermit
Cuplikan atas Buku Herman Hermit, 2009. Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan
Permukiman (UU No 4 Tahun 1992), Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
I. PARTICIPATORY PLANNING AND BUILDING
Dalam pemikiran UU Perumahan dan Permukiman ini warga, khususnya pemilik tanah dalam kawasan
peruntukan perumahan/permukiman, ditempatkan sebagai subyek pembangunan: pelaku dan sekaligus alasan
tujuan pembangunan perumahan dan permukiman. Dalam sistem perencanaan dan pembangunan yang
berkembang di dunia, terutama Negara-negara liberal, telah sejak tahun 1940-an menganut pendekatan
participatory planning and building, bukan hanya dalam bidang perumahan dan permukiman, melainkan telah
menjangkau aspek yang lebih luas seperti bidang infrastruktur atau prasarana umum. Dalam teori-teori sering
disebut juga sebagai pendekatan bawah-atas (bottom up planning).
Belakangan ini di Indonesia berkembang apa yang disebut dengan “teknik” penjaringan aspirasi
masyarakat (“jaring asmara”), di mana masyarakat berpartisipasi aktif sejak merumuskan masalah yang
dihadapinya sendiri hingga alternatif-aternatif solusinya sebagai masukan bagi penyusunan rencana-rencana
pembangunan kewilayahan ataupun sektoral, termasuk sektor perumahan dan permukiman. Teknik serupa juga
telah biasa dipraktikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) terutama dalam rangka
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.1
Dalam sistem perencanaan, sebagaimana diinginkan oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa partisipasi masyarakat sebagai wujud
“keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana
pembangunan” perlu didorong dan dikembangkan.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan pemeliharaan lingkungan perumahan melalui
pemugaran dan rehabilitasi perumahan memang telah sejak tahun 1970-an dimulai di Indonesia yang
diintegrasikan melalui program-program perbaikan kampong (Kampoeng Improvement) sebagai bagian dari
peremajaan kota (urban renewal) untuk lingkungan-lingkungan permukiman yang dinyatakan pemerintah
sebagai kawasan kumuh – yang kala itu banyak dibiayai oleh bantuan-bantuan Bank Dunia.
Untuk sekadar mengingatkan kita kepada salah satu bukti keberhasilan pengalaman partisipasi
masyarakat bersama-sama pemerintah dalam pemugaran rumah dan perbaikan lingkungan permukiman yang
dikaitkan dengan program peremajaan kota adalah Bandung Urban Development Project (BUDP) atau yang
sering disebut dengan “Proyek Dewi Sartika” pada tahun 1980-an. Program atau proyek tersebut telah berhasil
1 Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak lahirnya UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan tidak lagi menganut Repelita atau Repelita Daerah,
demikian pula pendekatan GBHN dihapus, dan sebagai gantinya adalah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional dan RPJM Daerah dengan masa perencanaan 5 tahunan.

8
menata lingkungan permukiman yang tadinya kumuh dan miskin prasarana lingkungan menjadi lingkungan
perumahan yang tertata rapi yang dilengkapi dengan sanitasi lingkungan yang relatif baik, termasuk prasarana
dasar dan utilitas. Sayang, seiring dengan menciutnya bantuan program dan pembiayaan Bank Dunia, proyek-
proyek yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat “kelas bawah” ini pun meredup dan nyaris
menghilang pada tahun 1990-an, yang justeru saat lahirnya UU Perumahan dan Permukiman ini dan UU
Penataan Ruang yang lama (UU No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang digantikan oleh UU No.26
Tahun 2007).
Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman,
pemerintah tentu saja melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan terhadap
komunitas-komunitas lokal, terutama pada lingkungan permukiman yang dianggap sebagai perumahan kumuh
(slums area). Informasi yang benar dan pengalaman sukses yang dikomunikasikan kembali kepada masyarakat
sasaran penyuluhan, pendidikan dan pelatihan akan sangat menentukan keberhasilan partisipasi masyarakat
dalam jangka panjang – penulis kira inilah yang dikehendaki oleh pasal 29 UU ini dengan apa yang disebut
sebagai pemerintah melaksanakan sosialisasi dan diklat dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat.
II. KONSOLIDASI TANAH MASIH WUJUD TERBAIK DARI PARTISIPASI MASYARAKAT
Wujud konkret partisipasi masyarakat yang dikehendaki oleh UU ini sebetulnya antara lain adalah Konsolidasi
Tanah oleh para pemilik tanah dalam lokasi-lokasi yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai Kawasan Siap
Bangun ataupun Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri terutama untuk menghasilkan kaveling-kaveling
tanah matang. Namun pengalaman penulis dalam mengikuti perkembangan pengamalan kebijakan konsolidasi
tanah (baik konsolidasi perumahan/perkotaan maupun konsolidasi tanah pertanian/perdesaan) memperlihatkan
bahwa sangat sedikit sekali masyarakat pemilik tanah yang tergerak untuk melakukan konsolidasi tanah –
meskipun pedoman teknis dan kepastian serta perlindungan hukum oleh pemerintah telah diberikan, terutama
terhitung sejak terbitnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang
Konsolidasi Tanah.
Oleh karena itu materi Pasal 29 UU Perumahan dan Permukiman ini sebaiknya kita
kaitkan/korespondensikan dengan materi dan semangat Pasal-pasal 22, 24, 25 dan 32 UU ini. Pasal 22 UU ini,
misalnya, menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan penyuluhan, bimbingan, bantuan dan pemberian kemudahan
yang dilakukan pemerintah etrhadap masyarakat pemilik tanah dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai
kawasan siap bangun ditujukan agar masyarakat pemilik tanah bersedia dan mampu melakukan konsolidasi
tanah dalam rangka antara lain penyediaan kaveling tanah matang.
Terdapat kecenderungan umum di dunia bahwa semakin maju atau sejahtera suatu bangsa semakin tinggi
partisipasi masyarakat melalui kegiatan konsolidasi tanah. Jepang, Korea, Taiwan dan Australia adalah beberapa
dari sekian banyak Negara maju di dunia yang terkenal dengan prestasi masyarakatnya dalam melakukan
konsolidasi tanah. Masyarakat Jepang dan Korea menyebut konsolidasi tanah dengan istilah land consolidation,
masyarakat Australia menyebutnya dengan istilah land pooling, sedangkan di Negara-negara Eropa dan
Amerika Serikat biasanya disebut dengan land readjustment.
Di Jepang dan Korea, misalnya, konsolidasi tanah perkotaan telah terbukti merupakan suatu cara
pembangunan kota yang telah secara luas digunakan dan sukses diterapkan. Di Jepang, konsolidasi tanah telah
berhasil hingga mencapai 27 persen dari total luas daerah perkotaan seluruhnya. Di beberapa kota seperti Osaka

9
dan Yokohama, konsolidasi tanah telah berperan lebih besar lagi hingga mencapai bagian terbesar daerah kota.
Di Republik Korea sekitar 60% tanah layak huni dalam radius 10 km hingga 15 kilometer sekitar Seoul telah
berhasil dikembangkan melalui proyek konsolidasi tanah.2
Konsolidasi tanah sebagai upaya pengadaan tanah sekaligus cara pembangunan perumahan dan
permukiman, sebagaimana juga tampak disadari benar oleh penyusun UU Perumahan dan Permukiman kita ini,
adalah cara yang lebih murah dan sederhana secara teknis dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
Oleh karena itu sebetulnya konsolidasi tanah perkotaan sangat cocok untuk Negara-negara sedang berkembang
seperti Indonesia. Dengan diperbolehkannya peserta konsolidasi tanah menjual kaveling-kaveling tanah hasil
konsolidasi kepada pihak lain (pembeli), maka dengan demikian sebetulnya biaya (cost recovery) proses
konsolidasi yang semula ditanggung masyarakat peserta konsolidasi menjadi berpindah jadi beban pembeli
kaveling tanah matang. Jadi, biaya pelaksanaan konsolidasi tanah hanya ditanggung sementara saja oleh para
peserta konsolidasi.
III. PRINSIP-PRINSIP PROGRAM DAN KEGIATAN KONSOLIDASI TANAH
Secara substantif, kebijakan konsolidasi tanah mencakup arahan pengelolaan program dan pengelolaan kegiatan.
Pengelolaan program, hampir sepenuhnya adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan
pengelolaan kegiatan hampir sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab para peserta konsolidasi tanah.
Pengelolaan program konsolidasi tanah meliputi aktivitas rutin dalam rangka perencanaan dan implementasi
erncana tata ruang dan penyusunan program-program pembangunan daerah (kota atau kabupaten), termasuk di
dalamnya koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah. Sedangkan pengelolaan kegiatan meliputi tahapan-
tahapan pekerjaan teknis dan administrasi yang harus ditempuh oleh para peserta konsolidasi di lapangan.
Adapun prinsip-prinsip konsolidasi tanah di Indonesia, sebagaimana diperlihatkan melalui materi
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, adalah sebagai
berikut:
Konsolidasi Tanah merupakan suatu kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan-
pemilikan dan penggunaan tanah sekaligus sebagai suatu upaya pengadaan tanah bagi pembangunan,
mempunyai tujuan-tujuan mendasar: meningkatkan dayaguna dan hasilguna penggunaan tanah,
menyelaraskan kepentingan individu dengan fungsi sosial tanah, meningkatkan kualitas lingkungan dan
pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (Pasal 1 dan Konsiderans)
Masyarakat pemilik tanah baik di perkotaan maupun di perdesaan atas biaya sendiri mempunyai hak
melakukan konsolidasi tanah apabila sekurang-kurangnya 85 persen dari luas tanah mendapat
persetujuan pemiliknya dan mendapat Penetapan Lokasi dari Bupati/Walikota sesuai dengan
peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
(Pasal 4 dan 7)
Untuk memungkinkan mencapai kondisi penguasaan-pemilikan tanah dan penggunaan tanah dalam
bentuk persil tanah yang teratur/terencana, pemilik tanah peserta konsolidasi harus melepaskan atas
tanahnya terlebih dahulu untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Obyek Konsolidasi Tanah oleh Kepala
2 John M. Courtney, Intervention through Land Use Regulation dalam Harold B. Dunkerly (eds), 1983, Urban
Land Policy: Issues and Policy, A World bank Publication, Oxford University Press, hlm.162.

10
Badan Pertanahan Nasional atas usul Kepala kantor Pertanahan melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
(Pasal 8 ayat 1)
Obyek Konsolidasi Tanah diberikan kembali kepada para peserta Konsolidasi Tanah sesuai dengan
rencana tata kaveling yang disetujui oleh para peserta Konsolidasi Tanah dan dibebaskan dari
pembayaran Uang Pemasukan Negara namun tetap harus membayar Biaya Administrasi dan Biaya
Pendaftaran Tanah. (Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3)
Pemenuhan biaya pembangunan prasarana dan sarana lingkungan serta biaya pelaksanaan konsolidasi
tanah, bersumber dari Sumbangan Tanah atau bentuk lain yang bisa diuangkan dari para peserta. (Pasal
6 dan 7)
Pihak yang ikut terlibat dalam program Konsolidasi Tanah berikut fungsinya masing-masing adalah
sebagai berikut: (1) Kepala BPN sebagai pembina pelaksanaan, (2) Kepala Kantor Wilayah BPN
sebagai pengendali pelaksanaan, (3) Kepala Kantor Pertanahan sebagai penanggung jawab
pelaksanaan, (4) Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah yang dibentuk Gubernur untuk melakukan
koordinasi dengan instansi-instansi terkait di lingkungan pemerintahan provinsi, dan (4) Tim
Koordinasi Konsolidasi Tanah dan Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang dibentuk
Bupati/Walikota untuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di lingkungan
pemerintahan kabupaten/kota. (Pasal 5)