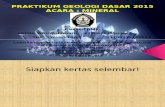LAPORAN PRAKTIKUM ILMU TANAH HUTAN ACARA 1 F.doc
-
Upload
rulisubekti -
Category
Documents
-
view
324 -
download
40
Transcript of LAPORAN PRAKTIKUM ILMU TANAH HUTAN ACARA 1 F.doc
LAPORAN PRAKTIKUM ILMU TANAH HUTANACARA IPENGAMBILAN CONTOH TANAHOleh :
Nama: Rulli Sbekti
NIM : 13/351850/SV/04593
Kelompok : IV(empat)
Co. Ass : DesyPROGRAM DIPLOMA III PENGELOLAAN HUTANSEKOLAH VOKASI
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2014ACARA IPENGAMBILAN CONTOH TANAH
I. TUJUAN
1. Mahasiswa mampu mengetahui bagaimana cara pengambilan contoh tanah
2. Mahasiswa mengetahui perbedaan pengambilan contoh tanah yang disesuaikan dengan sifat-sifat tanah yang akan diusik.
II. ALAT DAN BAHAN
1. Cangkul, cethok, sekop
2. Plastik beretiket
3. Pisau
4. Tangkai penjepit tabung pengambil contoh tanah
5. Tanah di areal laboratorium silvikultur intensif, Klebengan, dan jalan setapak
6. Bor, Tabung berbentuk silinder atau cincin (cupu)III. CARA KERJA Pengambilan Contoh Tanah Terusika. Pengambilan Contoh Tanah Terusik dalam Profil
1. Memilih tempat yang tidak tergenang air, tak terkena sinar matahari secara langsung, datar, dan mewakili tempat sekitarnya.2. Menggali lubang untuk profil tanah dengan dinding tegak lurus disebelah utara/selatan ukuran 1x1x1 meter..
3. Menandai lapisan yang ada berdasarkan warna, suara ketukan, dan kekerasan.4. Mencatat ciri morfologi, ciri-ciri dakhil pelapisan, dan mengambil 1-2 kilogram contoh tanah kering angin tiap perlapisan.b. Pengambilan Contoh Tanah Terusik di Lapisan Permukaan.1. Memilih tempat seperti pada point a.1.
2. Membersihkan seresah atau kotoran lain diatas tanah.
3. Mengambil sekitar 1-2 kgcontoh tanah dengan cangkul/cethok ke dalam kantong plastik dan memberi label.c. Pengambilan Contoh Tanah Terusik dengan Bor
1. Mata bor diletakkan di permukaan tanah.
2. Pegangan bor diputar perlahan-lahan ke arah kanan dengan disertai tekanan sampai seluruh kepala bor terbenam.
3. Kepala bor perlahan-lahan dikeluarkan dari tubuh tanah dengan memutar pegangan bor tanah ke arah kiri dengan disertai tarikan.
4. Contoh tanah yang terbawa kepala bor dilepaskan perlahan sampai bersih dan diusahakan tidak banyak merusak susunan tanah.
5. Pengeboran dilanjutkan lagi pada setiap ketebalan tanah 20 cm.
6. Memasukkan 1-2 kg contoh tanah kering angin kedalam plastik dan memberi label. Contoh Tanah Utuh (Tidak Terusik)1. Membersihkan permukaan tubuh tanah, meletakkan tabung diatas permukaan tubuh tanah dengan bagian yang tajam berada di sisi yang bersinggungan.2. Menekan perlahan tabung dengan tekanan merata sampai terbenam bagian.3. Meletakkan tabung kedua diatas tabung pertama, dan menekannya hingga tabung pertama terbenam sesuai keinginan.4. Menggali tanah disekitar tabung, dan mengambil tabung bersamaan dalam keadaan bertautan.5. Merapikan permukaan tanah dengan pisau tipis, dan menutup tabung silinder, serta memberi label. Pengambilan Contoh Tanah dengan Agregat Tak Terusik dan Contoh Tanah Terusik1. Menggali tanah sampai lapisan tanah yang diinginkan .2. Mengambil gumpalan tanah yang masih menunjukkan agregat aslinya, dan dimasukkan dalam kotak yang tersedia.3. Untuk contoh tanah terusik, contoh tanah dimasukkan kedalam kantong plastik.4. Mencatat lokasi dan jeluk pengambilannya, dan memberi label.IV. DASAR TEORI
Hampir semua mahluk hidup yang ditemukan dalam tanah bergantung pada bahan organik dalam tanah itu sendiri sebagai bahan makanan dan energinya. Bahan organic yang ditemukan dalam tanah jumlahnya tidak besar, hanya sekitar 3 5 %. Tetapi pengaruhnya terhadap tanah cukup besar, misalnya mempengaruhi tingkat kesuburan tanah, aerasi, drainase. Istilah bahan organik tanah lebih mengacu pada bahan (sisa jaringan tanaman/hewan) yang telah mengalami perombakan/dekomposisi baik sebagian atau seluruhnya yang telah mengalami humifikasi maupun belum (Cahyono Agus, 1998).Kononova (1966) dan Scinitzer (1978) dalam (Black, 1965) membagi bahan organik tanah menjadi 2 kelompok yaitu bahan yang telah terhumifikasi yang disebut bahan humik (humic substance) dan bahan bukan humik (non humic substance). Kelompok lebih dikenal dengan humus yang merupakan hasil akhir dari proses dekomposisi bahan organik. Humus menyusun 90% bagian bahan organik tanah (Mansur, 2003). Bagian organik dari jaringan tanaman terdiri dari sejumlah besar senyawa organik tetapi hanya sedikit yang ditemukan dalam tanah tersidik., setelah pelapukan. Senyawa-senyawa organik tersebut terutama karbohidrat, asam amino dan protein, lipid, asam nukleat, lignin dan humus. Senyawa-senyawa tersebut selain humus biasanya terkena reaksi-reaksi degradasi dan dekomposisi. Namun kadangkala mereka dapat diserap oleh komponen inorganik tanah, seperti lempung atau mereka ada dalam kondisi anaerobik. Di dalam kondisi-kondisi semacam ini, senyawa tersebut lebih terlindung dari dekomosisi.Kelompok kedua meliputi senyawa senyawa organik seperti karbohidrat, asam amino, peptide, lemak, lignin, asam nukleat. Bahan organik tanah berada pada kondisi sebagai akibat adanya mikroorganisme tanah yang memanfaatkan sebagaisumber energi dan karbon (Tejoyuwono. 1985). Humus merupakan senyawa yang bersifat cukup resisten terhadap perombakan terhadap jasad renik, bersifat amorf ( tidak mempunyai bentuk tertentu ) berwarna hitam atau coklat dan mempunyai daya menahan air yang tinggi serta unsure hara yang tinggi. Tingginya daya menahan air dan unsure hara adalah akibat tingginya kapasitas tukar kation dari humus karena humus mempunyai beberapa gugus aktif sepertigugus karboksil. Tanah yang mengandung humus adalah tanah lapisan atas. Semakin kebawah, kandungannya semakin berkurang (Black, 1965). Di daerah rawa, seperti daerah rawa pasang surut sering dijumpai tanah dengan bahan organic yang sangat tinggi dan tebal.Tanah tanah yang kandungan liatnya tinggi, cenderung mempunyai kandungan bahan organic yang tinggi (Foth, 1988).VI. PEMBAHASAN
Contoh tanah adalah suatu volume massa tanah yang diambil dari suatu bagian tubuh (horizon/lapisan/solum) dengan cara-cara tertentu disesuaikan dengan sifat-sifat yang akan diteliti secara lebih detail di laboratorium (Bambang, 1998). Fungsi mempelajari contoh tanah antara lain:
1) Mempelajari sifat fisik dan kimiawi tanah.2) Mengetahui apabila terdapat kandungan unsur beracun dalam tanah.
3) Sebagai dasar penetapan dosis pupuk dan kapur, sehingga lebih efektif, efisien, dan rasional.
4) Sebagai database dalam program perencanaan dan pengolahan hutan.
Analisis Perhitungan
Pengamatan dan pengambilan data contoh tanah ini dilakukan di laboratorium Silvikultur Intensif Universitas Gadjah Mada, dengan pengamatan contoh tanah terusik dan contoh tanah tidak terusik.
a) Contoh Tanah Terusik
Kedalaman 0-20 cm: struktur remah, tekstur lembut, bewarna coklat.
Kedalaman 20-40 cm : struktur pasir, tekstur agak kasar, bewarna coklat gelap. Kedalaman 40-60 cm: struktur pasir, tekstur lebih kasar, dan bewarna coklat kehitaman.
b) Contoh Tanah Tidak Terusik
Jalan setapak
: nisbah luas = 0,19
Rerumputan
: nisbah luas = 0,19
Bawah tegakan: nisbah luas = 0,19
Nisbah luas ketiga lokasi diatas hasilnya sama, karena diameter dalam nya sama, yaitu 4,39 cm, dan diameter luarnya 4,79 cm.VII. KESIMPULAN
Cara pengambilan contoh tanah ada 3 macam, yaitu:
a. Pengambilan contoh tanah tidak terusik.
b. Pengambilan tanah dalam keadaan agregat tidak terusik.
c. Pengambilan contoh tanah terusik.
Untuk pengambilan contoh tanah terusik dapat menggunakan bor, dan parameter pembandingannya adalah kedalaman lubang tiap 20 cm. Sedangkan untuk pengambilan contoh tanah tidak terusik berdasarkan lokasi dan katagori kedalaman tanah (dalam/luar). Pengambilan contoh tanah disesuaikan dengan sifat-sifat tanah yang akan diteliti/diselidik lebih lanjut sehingga terdapat perbedaan, karena berbeda sifat yang diteliti, berbeda pula teknik pengambilannya. Contoh:
a. Contoh tanah secara utuh/tak terusik
Untuk menyelidiki tentang analisis BV, pF, kesarangan, perembihan tanah, dsb.
b. Contoh tanah secara tidak utuh/terusik
Untuk menyelidiki watak fisiokimiawi tanah. Analis BJ, Ped, tekstur, warna, konsistensi, kandungan unsur hara, pH, BO, KB, KPK, dsb.VIII. DAFTAR PUSTAKA Brandy, N.C. 1985. The Nature and Properties of Soil. Tenesse, New Jearsey, USA: Agronomy Inc.
Kertonegoro, Bambang D., Sri Hartuti Suparnawa, Supriyanto Notohadisuwarno, Susi Handayani. 1998. Panduan Analisis Fisika Tanah. Yogyakarta: Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian UGM. Suprayogo, 2010. Pengambilan Contoh Tanah. Jakarta: Akademika Press.
DAFTAR LAMAN
Ehsa, 2011. Pengambilan Contoh Tanah. http://ehsablog.com. (diakses pada hari Sabtu, 23 Maret 2013. Pukul 15.00 WIB).
Jacob Agustinius, 2010. Pengambilan Contoh Tanah. http://tumoutou.net.html. (diakses pada hari Sabtu, 23 Maret 2013. Pukul 15.24 WIB).
Mittha, 2009. Pengambilan Contoh Tanah. http://khmandayu.blogspot.com. (diakses pada hari Sabtu, 23 Maret 2013. Pukul 15.26 WIB).