laporan biofar
-
Upload
sharon-susanto -
Category
Documents
-
view
18 -
download
2
Transcript of laporan biofar

Disolusi obat adalah suatu proses pelarutan senyawa aktif dari bentuk sediaan padat ke
dalam media pelarut. Pelarut suatu zat aktif sangat penting artinya bagi ketersediaan suatu
obat sangat tergantung dari kemampuan zat tersebut melarut ke dalam media pelarut
sebelum diserap ke dalam tubuh. Sediaan obat yang harus diuji disolusinya adalah bentuk
padat atau semi padat, seperti kapsul, tablet atau salep. (Ansel, 1985)
Agar suatu obat diabsorbsi, mula-mula obat tersebut harus larutan dalam cairan pada
tempat absorbsi. Sebagai contoh, suatu obat yang diberikan secara oral dalam bentuk tablet
atau kapsul tidak dapat diabsorbsi sampai partikel-partikel obat larut dalam cairan pada
suatu tempat dalam saluran lambung-usus. Dalam hal dimana kelarutan suatu obat
tergantung dari apakah medium asam atau medium basa, obat tersebut akan dilarutkan
berturut-turut dalam lambung dan dalam usus halus. Proses melarutnya suatu obat disebut
disolusi. (Ansel, 1985)
Bila suatu tablet atau sediaan obat lainnya dimasukkan dalam saluran cerna, obat
tersebut mulai masuk ke dalam larutan dari bentuk padatnya. Kalau tablet tersebut tidak
dilapisi polimer, matriks padat juga mengalami disintegrasi menjadi granul-granul, dan
granul-granul ini mengalami pemecahan menjadi partikel-partikel halus. Disintegrasi,
deagregasi dan disolusi bisa berlangsung secara serentak dengan melepasnya suatu obat
dari bentuk dimana obat tersebut diberikan. (Martin, 1993)
Di dalam pembahasan untuk memahami mekanisme disolusi, kadang-kadang
digunakan salah satu model atau gabungan dari beberapa model antara lain adalah:
Model Lapisan Difusi (Diffusion Layer Model)
Model ini pertama kali diusulkan oleh Nerst dan Brunner. Pada permukaan
padat terdapat satu lapisan tipis cairan dengan ketebalan ℓ, merupakan
komponen kecepatan negatif dengan arah yang berlawanan dengan permukaan
padat. Reaksi pada permukaan padat – cair berlangsung cepat. Begitu model
solut melewati antar muka liquid film – bulk film, pencampuran secara cepat
akan terjadi dan gradien konsentrasi akan hilang. Karena itu kecepatan disolusi
ditentukan oleh difusi gerakan Brown dari molekul dalam liquid film.
Model Barrier Antar Muka (Interfacial Barrier Model)
Model ini menggambarkan reaksi yang terjadi pada permukaan padat dan
dalam hal ini terjadi difusi sepanjang lapisan tipis cairan. Sebagai hasilnya, tidak
dianggap adanya kesetimbangan padatan – larutan, dan hal ini harus dijadikan
pegangan dalam membahas model ini. Proses pada antar muka padat – cair

sekarang menjadi pembatas kecepatan ditinjau dari proses transpor. Transpor
yang relatif cepat terjadi secara difusi melewati lapisan tipis statis (stagnant).
Model Dankwert (Dankwert Model)
Model ini beranggapan bahwa transpor solut menjauhi permukaan padat
terjadi melalui cara paket makroskopik pelarut mencapai antar muka – cair
karena terjadi pusaran difusi secara acak. Paket pelarut terlihat pada
permukaan padatan. Selama berada pada antar muka, paket mampu
mengabsorpsi solut menurut hukum difusi biasa, dan kemudian digantikan oleh
paket pelarut segar. Jika dianggap reaksi pada permukaan padat terjadi segera,
prosex pembaharuan permukaan tersebut terkait dengan kecepatan transpor
solut ataudengan kata lain disolusi.
(Firdha, 2013)
Secara sederhana kecepatan pelarutan didefinisikan sebagai jumlah zat yang terlarut
dari bentuk sediaan padat dalam medium tertentu sebagai fungsi waktu. Dapat juga
diartikan sebagai kecepatan larut bahan obat dari sediaan farmasi atau granul atau partikel-
partikel sebagai hasil pecahnya bentuk sediaan obat tersebut setelah berhubungan dengan
cairan medium. Dalam hal tablet bias diartikan sebagai mass transfer, yaitu kecepatan
pelepasan obat atau kecepatan larut bahan obat dari sediaan tablet ke dalam medium
penerima. Penelitian tentang disolusi telah dilakukan oleh Noyes Whitney dan dalam
penelitiannya diperoleh persamaan yang mirip hukum difusi dari Fick :
dcdt
=KS(Cs−C )
dimana :
dc/ct : laju pelarutan obat
K : tetapan laju difusi
S : luas permukaan partikel
Cs : kadar obat dalam “stagnant layer”
C : konsentrasi obat dalam bagian terbesar pelarut
Dari persamaan di atas terlihat bahwa kinetika pelarutan dapat dipengaruhi oleh sifat
fisikokimia, formulasi, dan pelarut.
Banyak cara untuk mengungkapkan hasil kecepatan pelarutan suat zat atau sediaan.
Selain persamaan di atas cara lain untuk mengungkapkan pelarutan adalah sebagai berikut :
1. Metode Klasik

Metode ini dapat menunjukkan jumlah zat aktif yang terlarut pada waktu t, yang
kemudian dikenal dengan T-20, T-50, T-90, dan sebagainya. Karena dengan metode ini
hanya menyebutkan 1 titik saja, maka proses yang terjadi di luar titik tersebut tida
diketahui. Titik terebut menyatakan jumlah zat aktif yang terlarut pada waktu tertentu.
2. Metode Khan
Metode ini kemudian dikenal dengan konsep dissolution efficiency(DE)area di bawah
kurva disolusi di antara titik waktu yang ditentukan. Dirumuskan dengan persamaan
sebagi berikut :
DE = 0t ∫Y dt x 100%
Y100.t
Beberapa peneliti mensyaratkan bahwa penggunaan DE sebaiknya mendekati 100%
zat yang terlarut. Keuntungan metode ini adalah :
a. Dapat menggambarkan seluruh proses percobaan yang dimaksud dengan harga DE
b. Dapat menggambarkan hubungan antara percobaan in vitro dan in vivo karena
penggambaran dengan cara DE ini mirip dengan cara penggambaran pecobaan in
vivo
3. Metode linierisasi kurva kecepatan pelarutan dengan menggunakan sebagai contoh
persamaan wagner
Metode ini berdasarkan pada asumsi sebagai berikut :
a. kondisi percobaan harus dalam keadaan sink yaitu Cs>>>C
b. proses pelarutan mengikuti orde I
c. luas permukaan spesifik (S) turun secara eksponensial fungsi waktu
d. kondisi proes pelarutannya non reaktif
(Rara, 2008)
Laju disolusi atau kecepatan melarut obat-obat yang relatif tidak larut dalam air telah
lama menjadi masalah pada industri farmasi. Obat-obat tersebut umumnya mengalami
proses disolusi yang lambat demikian pula laju absorpsinya. Dalam hal ini partikel obat
terlarut akan diabsorpsi pada laju rendah atau bahkantidak diabsorpsi seluruhnya. Dengan
demikian absorpsi obat tersebut menjadi tidak sempurna (Abdou,1989).
Pelepasan zat aktif dari suatu produk obat sangat dipengaruhi oleh sifat fisikokimia zat
aktif dan bentuk sediaan. Ketersediaan zat aktif biasanaya ditetapkan oleh kecepatan
pelepasan zat aktif dari bentuk sediaannya. Pelepasan zat aktif dari bentuk sediaan biasanya
ditentukan oleh kecepatan melarutnya dalam media sekelilingnya (Amir, 2007).
Faktor yang mempengaruhi Disolusi

1. Suhu
Suhu akan mempengaruhi kecepatan melarut zat. Perbedaan sejauh lima persen dapat
disebabkan oleh adanya perbedaan suhu satu derajat.
2. Medium
Media yang paling umum adalah air, buffer dan 0,1 N HCl. Dalam beberapa hal zat tidak
larut dalam larutan air, maka zat organik yang dapat merubah sifat ini atau surfaktan
digunakan untuk menambah kelarutan. Gunanya adalah untuk membantu kondisi “sink”
sehinggan kelarutan obat di dalam medium bukan merupakan faktor penentu dalam proses
disolusi. Untuk mencapai keadaan “sink” maka perbandingan zat aktif dengan volume
medium harus dijaga tetap pada kadar 3-10 kali lebih besar daripada jumlah yang diperlukan
bagi suatu larutan jenuh.
Masalah yang mungkin mengganggu adalah adanya gas dari medium sebelum
digunakan. Gelembung udara yang terjadi dalam medium karena suhu naik dapat
mengangkat tablet, sehingga dapat menaikkan kecepatan melarut.
3. Kecepatan Perputaran
Kenaikan dalam pengadukan akan mempercepat kelarutan. Umumnya kecepatan
pengadukan adalah 50 atau 100 rpm. Pengadukan di atas 100 rpm tidak menghasilkan data
yang dapat dipakai untuk membeda-bedakan hasil kecepatan melarut. Bilamana ternyata
bahwa kecepatan pengadukan perlu lebih dari 100 rpm maka lebih baik untuk mengubah
medium daripada menaikkan rpm. Walaupun 4% penyimpangan masih diperbolehkan,
sebaiknya dihindarkan.
4. Ketepatan Letak Vertikal Poros
Disini termasuk tegak lurusnya poros putaran dayung atau keranjang, tinggi dan
ketepatan posisi dayung/ keranjang yang harus sentris. Letak yang kurang sentral dapat
menimbulkan hasil yang tinggi, karena hal ini akan mengakibatkan pengadukan yang lebih
hebat di dalam bejana.
5. Goyangnya poros
Goyangnya poros dapat mengakibatkan hasil yang lebih tinggi karena dapat
menimbulkan pengadukan yang lebih besar di dalam medium. Sebaiknya digunakan poros
dan bejana yang sama dalam posisi sama bagi setiap percobaan karena masalah yang timbul
karena adanya poros yang goyang akan dapat lebih mudah dideteksi.
6. Vibrasi
Bilamana vibrasi timbul, hasil yang diperoleh akan lebih tinggi. Hampir semua masalah
vibrasi berasal dari poros motor, pemanas penangas air atau adanya penyebab dari luar. Alas

dari busa mungkin dapat membantu, tetapi kita harus hati-hati akibatnya yaitu letak dan
kelurusan harus dicek.
7. Gangguan pola aliran
Setiap hal yang mempengaruhi pola aliran di dalam bejana disolusi dapat
mengakibatkan hasil disolusi yang tinggi. Alat pengambil cuplikan serta adanya filter pada
ujung pipet selama percobaan berlangsung dapat merupakan penyebabnya.
8. Posisi pengambil cuplikan
Posisi yang dianjurkan untuk pengambilan cuplikan adalah di antara bagian puncak
dayung (atau keranjang) dengan permukaan medium (code of GMP). Cuplikan harus diambil
10-25 mm dari dinding bejana disolusi, karena bagian ini diperkirakan merupakan bagian
yang paling baik pengadukannya.
9. Formulasi bentuk sediaan
Penting untuk diketahui bahwa hasil kecepatan melarut yang aneh tidaklah selalu
disebabkan oleh masalah peralatan saja, tetapi beberapa mungkin juga disebabkan oleh
kualitas atau formulasi produknya sendiri. Beberapa faktor yang misalnya berperan adalah
ukuran partikel dari zat berkhasiat, Mg stearat yang berlebih sebagai lubrikan, penyalutan
terutama dengan shellak dan tidak memadainya zat penghancur. Ada juga yang
menambahkan faktor kekerasan tablet.
10. Kalibrasi alat disolusi
Kalibrasi alat disolusi selama ini banyak diabaikan orang, ternyata hal ini merupakan
salah satu faktor yang paling penting. Tanpa melakukannya tidak dapat kita melihat adanya
kelainan pada alat. Untuk mencek alat disolusi digunakan tablet khusus untuk kalibrasi yaitu
tablet prednisolon 50 mg dari USP yang beredar di pasaran. Tes dilakukan pada kecepatan
dayung atau keranjang 50 dan 100 rpm. Kalibrasi harus dilakukan secara teratur minimal
setiap enam bulan sekali
(Martin, et. al., 2008)
Menurut US Pharmacopea edisi 29 ada 7 alat disolusi sebabagai berikut
Alat 1
Alat terdiri dari sebuah wadah tertutup yang terbuat dari kaca atau bahan transparan
lain yang inert, suatu motor, suatu batang logam yang digerakkan oleh motor dan keranjang
berbentuk silinder. Wadah tercelup sebagian di dalam suatu tangas air yang sesuai
berukuran sedemikian sehinnga dapatmempertahankan suhu dalam wadah pada 37o ±
0,5o selama pengujian berlangsung dan menjaga agar gerakan air dalam tangas air halus dan
tetap. Bagian dari alat termasuk lingkungan tempat alat diletakkan tidak dapat memberikan

gerakan, goncangan atau getaran signifikan yang melebihi gerakan akibat perputaran alat
pengaduk. Penggunaan alat yang memungkinkan pengamatan contoh dan pengadukan
selama pengujian berlangsung. Lebih dianjurkan wadah disolusi berbentuk silinder dengan
dasar setengah bola, tinggi 169 mm hingga 175 mm, diameter dalam 98 mm hingga 106 mm
dan kapasitas nominal 1000 ml. Pada bagian atas wadah ujungnya melebar, untuk mencegah
penguapan dapat digunakan suatu penutup yang sesuai. Batang logam berada pada posisi
sedemikian sehingga sumbunya tidak lebih dari 2mm pada tiap titik pada sumbu vertikal
wadah, berputar dengan halus dan tanpa goyangan yang berarti. Suatu alat pengatur
kecepatan digunakan sehingga memungkinkan untuk memilih kecepatan putaran yang
dikehendaki dan mempertahankan kecepatan seperti yang tertera dalam masing-masing
monografi dalam batas ± 4%.
Alat 2
Sama seperti Alat 1, bedanya pada alt ini digunakan dayung yang terdiri dari daun
(propellor) dan batang sebagai pengaduk. Batang berada pada posisi sedemikian sehingga
sumbunya tidak lebih dari 2 mm pada setiap titik dari sumbu vertikal wadah dan berputar
dengan halus tanpa goyangan yang berarti. Daun melewati diameter batang sehingga dasar
daun dan batang rata. Jarak 25mm ± 2mm antara daun dan bagian dalam dasar wadah
dipertahankan selama pengujian berlangsung. Untuk mencegah mengapungnya sediaan
digunakan sepotong kecil bahan inert seperti gulungan kawat berbentuk spiral.

Alat 3
Alat terdiri dari satu rangkaian labu kaca beralas rata berbentuk silinder; rangkaian
silinder kaca yang bergerak bolak-balik; penahan dari baja tahan karat; (tipe 316 atau yang
setara) dan kasa polipropilen yang dirancang untuk menyambungkan bagian atas dan alas
silinder yang bergerak bolak-balik; dan sebuah motor serta sebuah kemudi untuk
menggerakkan silinder bolak-balik secara vertikal dalam labu dan jika diinginkan, silinder
dapat diarahkan secara horizontal pada deretan labu kaca yang lain. Labu – labu tercelup
sebagian dalam tangas air dengan ukuran sesuai yang da[at mempertahankan suhu 37o ±
0,5o selama pengujian. Tidak ada bagian alat, termasuk tempat di mana alat diletakkan,
memberikan gerakan, goyangan atau getaran yang berarti.
Alat 4
Alat terdiri dari sebuah wadah dan sebuah pompa untuk media disolusi; sebuah sel yang
dapat dialiri, sebuah tangas air yang dapat mempertahankan suhu media disolusi pada 37o ±
0,5o. Pompa mendorong media disolusi ke atas melalui sel. Pompa memiliki kapasitas aliran
antara 240 ml per jam dan 960 ml per jam, dengan laju aliran baku 4 ml, 8 ml, dan 16 ml per
menit. Pompa harus secara volumetrik memberikan aliran
konstan tanpa dipengaruhi tekanan aliran dalam alat penyaring. Sel terbuat dari bahan yang
inert dan transparant, dipasang vertikal dengan suatu sistem penyaring yang mencegah
lepasnya partikel tidak larut dari bagian atas sel; diameter sel baku adalah 12 mm dan 22,6
mm; bagian bawah yang runcing umumnya diisi dengan butiran kaca kecil dengan diameter
lebih kurang 1 mm dan sebuah butiran dengan ukuran lebih kurang 5 mm diletakkan pada
bagian ujung untuk mencegah cairan masuk ke dalam tabung.

Alat 5
DAYUNG DI ATAS CAKRAM
Gunakan labu dan dayung dari Alat 2, dengan penambahan suatu cakram baja tahan
karat dirancang untuk menahan sediaan transdermal pada dasar labu. Suhu dipertahankan
pada 32o ± 0,5o. Jarak 25 mm ± 2 mm antara bilah dayung dan permukaan cakram
dipertahankan selama penetapan berlangsung. Labu dapat ditutup selama penetapan untuk
mengurangi penguapan. Cakram untuk menahan sediaan transdermal dirancang agar
volume tak terukur antara dasar labu dan cakram minimal. Cakram diletakkan sedemikian
rupa sehingga permukaan pelepasan sejajar dengan bilah dayung.

Alat 6
Gunakan labu dari Alat 1, kecuali keranjang dan tangkai pemutar diganti dengan elemen
pemutar silinder yang terbuat dari baja tahan karat, dan suhu dipertahankan pada 32o ±
0,5o selama penetapan berlangsung. Sediaan uji ditempatkan pada silinder pada permulaan
tiap penetapan. Jarak antara bagian dasar labu dan silinder dipertahankan 25 mm ± 2 mm
selama penetapan.
Alat 7
CAKRAM TURUN NAIK
Terdiri dari suatu rangkaian wadah volumetrik untuk larutan yang sudah dikalibrasi atau
ditara, terbuat dari kaca atau bahan inert yang sesuai, sebuah rangkaian motor dan
pendorong untuk menggerakkan sistem turun naik secara vertikal dan mengarahkan sistem
secara horizontal secara otomatis ke deret labu yang berbeda jika diinginkan, dan satu
rangkaian penyangga cuplikan berbentuk cakram. Wadah larutan sebagian terendam dalam
sebuah tangas air yang sesuai dengan ukuran yang memungkinkan untuk mempertahankan
suhu bagian dalam wadah larutan 32o ± 0,5o selama pengujian berlangsung. Tidak ada

bagian alat termasuk tempat diletakkannya alat, yang memberikan gerakan, goncangan,
atau getaran yang berarti.
`Martin, A., Swarbrick, J., & Cammarata, A. 2008. Farmasi Fisik 2. Universitas Indonesia
Press. Jakarta.
Amir, Syarif.dr, dkk.2007. Farmakologi dan Terapi. Edisi kelima. Gaya Baru. Jakarta.
Anonim. 2007. The United States Pharmacopoeia 30 – The National
Formulary.25. United States Pharmacopoeia Convention, Inc.
Ansel,H.C., (989. Pengatar Bentuk sediaan Farmasi. Edisi 4. UI Press. Jakarta
Firdha, 2013, biofarmasetika,
http://firdhaahdrif29.blogspot.com/2013/09/biofarmasetika.html diakses tanggal 1
Desember 2013
Rara, 2008, Uji disolusi (ketersediaan hayati),
http://rara87.wordpress.com/2008/11/29/ diakses tanggal 1 Desember 2013
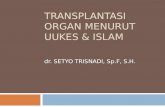








![Biofar Pv Disolusi-Anggi[1]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/5695d2a31a28ab9b029b30eb/biofar-pv-disolusi-anggi1.jpg)











