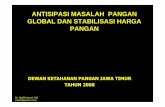Krisis Air, Pangan Dan Energi
description
Transcript of Krisis Air, Pangan Dan Energi

Dunia Dilanda Krisis Pangan Diiringi Krisis Air dan Energi
Iklim di Wilayah utara negara bagian Gujarat, India barat cenderung semi-kering dan rentan terhadap kekeringan. Padahal daerah tersebut selama musim hujan antara Juni dan September rutin diguyur hujan alami. Namun, dalam tiga dekade terakhir, banyak lahan tanaman serta peternakan susu tetap hijau walau saat musim kemarau.
Itu karena para petani di sana banyak yang berinvestasi untuk sumur dan pompa air. Umumnya mereka memakai listrik dalam jumlah besar untuk mengambil air dari akuifer (wilayah bawah tanah yang berisi air) dalam. Pemerintah memang menyokong tumbuhnya sektor pertanian melalui subsidi listrik dan harga.
Akan tetapi, ketika kian banyak air diangkat ke permukaan, pemompaan tidak mungkin tanpa dampak negatif bagi lingkungan. Kabarnya lapisan air tanah telah menipis secara drastis, sampai harus menembus hingga 600 meter ke bawah di beberapa tempat, selain jgua membutuhkan pompa lebih kuat untuk membawa air ke permukaan. Konsumsi berlebihan atas jaringan listrik ini tentu menghambat pasokan listrik bagi industri atau penduduk lainnya.
Untungnya, contoh pengurasan air tanah besar-besaran dari utara Gujarat itu terdata dengan baik, walau hal itu adalah contoh buruk tentang pengembang sektor pertanian yang tidak berkelanjutan (bakal habis). Masalahnya masih banyak lokasi-lokasi parah lainnya di India, Cina, serta Timur Tengah di mana kebutuhan energi meningkat sejalan dengan eksploitasi sumber air dipompa untuk menghasilkan makanan. Para ahli telah memperingatkan bahwa pertanian di daerah-daerah tersebut berada dalam zona berbahaya mengingat hubungan tak berkelanjutan antara kebutuhan energi dan air tanah yang berlebihan.
Dampak kerusakan potensial lain tak hanya keringnya akuifer dan gagal panen di lahan pertanian dan peternakan, tetapi juga peningkatan salinitas tanah ditambah emisi karbon dioksida. Perubahan iklim turut memperparah situasi tersebut (atau mungkin pengrusakan inilah salah satu sebabnya). Petani miskin pasti berada dalam posisi sangat sulit karena mereka tak mampu berinvestasi di bidang teknologi yang mahal, hanya untuk mengebor sumur dan membeli pompa air besar bagi lahan yang tak seberapa besar.
Lalu, apakah ini salah petani? Tentu tak adil bila menyalahkan mereka. Bertani adalah mata pencarian mereka yang utama atau satu-satunya. Para ahli perlu mencari solusi menang-menang bagi petani maupun lingkungan. Kalau hanya demi preservasi lingkungan, para petani bisa kehilangan pekerjaan, sedangkan masyarakat umum kelaparan. Jadi harus dua-duanya baik.
Sains untuk sebagian besar solusi sebetulnya sudah ada, tapi implementasinya bisa sangat sulit mengingat kaitan yang erat antara sektor energi dan air, di samping perlu kerja sama berbagai departemen pemerintahan. Dilemanya, permintaan sumber daya pangan terus meningkat. Produksi pertanian harus meningkat sekitar 70 persen pada 2050, energi primer sebesar 50 persen pada 2035 (data FAO).
Di Cina, penggunaan air tanah untuk mengairi tanaman tumbuh lebih dari sepuluh kali lipat sejak 1950, menurut penelitian yang dirilis Maret lalu oleh University of East Anglia (Inggris). Para peneliti memerkirakan bahwa pemompaan air dari kedalaman rata-rata 230 kaki (70 meter) di sejumlah tempat menyisakan lebih dari 30 juta ton buangan karbon dioksida setahun, setara dengan jumlah yang dipancarkan seluruh Selandia Baru tiap tahun.
Di India, pengguna air tanah terbesar di dunia, konsumsi listrik pertanian meningkat lebih dari 25 kali lipat antara 1970 dan 2009, menurut angka pemerintah setempat.
Di Indonesia sih tidak tahu deh. Tapi mengingat seringnya kita mendengar berita bahwa pemerintah mengimpor sejumlah bahan pangan, bisa diasumsikan kita juga mengalami hal yang sama, minimal beti (beda tipis).

Terus gimana? Sebagai masyarakat awam kita mungkin bisa mengambil peran. Misalnya, jangan membeli sawah produktif kalau akan dikonversi jadi perumahan. Lebih parah lagi kalau lahan pangan jadi lapangan golf atau ruko atau mal. Mungkin masih banyak hal lain yang bisa kita perbuat. Entahlah.
See more at: http://bp.dapur.in/2012/04/dunia-dilanda-krisis-pangan-diiringi.html#sthash.VwNL3EmN.dpuf
Kaitan Krisis Air, Energi dan PanganBeras, air atau rumah sejuk? Perang melawan kelaparan dapat memperparah kurangnya persediaan air, atau sebaliknya. Haruskah kita melakukan pilihan itu?

Perkiraan para pakar jelas: jika jumlah penduduk bumi semakin meningkat, kebutuhan akan pangan pada tahun-tahun mendatang sampai
2030 akan melonjak hingga 35 persen. Dampaknya akan terlihat jelas di negara yang juga kekurangan energi dan air bersih. "Pertumbuhan
ekonomi global menimbulkan perubahan pola makan. Konsum daging dan produk susu meningkat. Tapi untuk memproduksi daging
diperlukan sepuluh kali lipat jumlah air ketimbang bagi tanaman gandum", ujar Bettina Rudloff dari yayasan Ilmu Pengetahuan dan Politik
(SWP).
Ilmuwan ini adalah salah satu peneliti mengenai kaitan krisis air, pangan dan energi yang baru-baru ini menerbitkan hasil studinya itu.
"Kaitannya juga terlihat pada perkembangan harga, misalnya dari produk agrar dan minyak bumi. Tren harga dan fluktuasinya sangat
mirip." Jadi, haruskan kita ke depan memutuskan pilihan antara peningkatan air bersih, pengurangan bahaya kelaparan atau perbaikan
penyediaan energi"
Penyisihan Dampak Samping
Perkebunan kelapa sawit Malaysia
Franz-Josef Batz dari Yayasan Kerjasama Internasional (GIZ) menjelaskan sebuah contoh "dampak yang tidak diinginkan" dari India:
Pemerintah negara itu mensubsidi pemakaian energi di sektor pertanian. Akibatnya, para petani kemudian menggunakan pompa air yang
banyak memakai energi. Permukaan air tanah menurun dan ujungnya, produksi menurun. "Kita harus memikirkan, bagaimana tepatnya

kita mau menggunakan air. Akses terhadap air bersih memang merupakan hak asasi manusia, tetapi perekonomian juga memerlukan air
dan energi demi pertumbuhan."
Pemikiran "yang menjaring"
Perdebatan umum yang cukup ramai mengenai hubungan antara pangan, air bersih dan energi terdengar sejak dua tahun ini. Pada forum
ekonomi dunia di Davos 2011, tema itu merupakan fokus laporan risiko. Pemerintah di Berlin bahkan mengangkat tema ini dalam sebuah
konferensi tersendiri di Jerman. Namun menurut Bettina Rudloff, langkah nyata secara politis sulit dilaksanakan. Jerman dan juga negara
lainnya membahas tema air, energi dan pangan di dalam kementrian terpisah dan di tatanan politik yang berbeda. Kebijakan pertanian
terutama dipegang Uni Eropa di Brussel, sementara energi di bawah wewenang negara-negara anggotanya.
Bettina Rudloff, pakar SWP
Tetapi kemajuan pertama terlihat bergerak menuju "pemikiran yang menjaring": Subsidi pertanian semakin sering dikaitkan dengan
persyaratan tertentu yang relevan bagi penyediaan air. Misalnya larangan penggunaan pupuk dan pestisida tertentu. Rudloff juga

menyebut kebijakan bahan energi ramah lingkungan UE sebagai contoh. Tidak ada lagi target tinggi bagi penggunaan produk tanaman
berkelanjutan, setelah dipastikan bahwa banyak lahan yang diperlukan bagi produksi pangan.
Kebijikan menjaring di lokasi terkait
Pemikiran yang menjaring juga memasuki sektor bantuan pembangunan Jerman, apakah itu di India ataupun di Yordania. GIZ berupaya
membuat pemerintah dan rakyat mengerti keterkaitan antara kebijakan energi dan produksi pertanian serta penyediaan air minum. "Target
kami di Yordania adalah efisiensi pompa air. Dalam tiga sampai empat tahun ke depan kami akan dapat memperlihatkan bahwa
penghematan bisa mencapai 30 persen", demikian disampaikan Franz-Josef Batz kepada DW. Dia mengharapkan dukungan dari perusahaan
swasta besar ketimbang mitra yang kuat, karena perusahaan seperti Coca-Cola juga dikatakan mempunyai minat besar pada upaya
pengamanan air minum.
Christina RutaDW.DE
Pertumbuhan atau Pelestarian Lingkungan
Bisakah pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan berjalan berdampingan? Ada pihak yang berbicara tentang pertumbuhan hijau. Apakah ini tidak merupakan unsur yang bertentangan? (18.06.2013)
IEA: Perubahan Iklim Semakin Mengancam
Mimpi buruk jika negara-negara tak mengurangi emisi gas karbondioksidanya. Diperkirakan kenaikan suhu bisa mencapai hingga 5,3 derajat celsius pada tahun 2100. (13.06.2013)
Memerangi Kelaparan adalah Mungkin
Tiga puluh delapan Negara diakui untuk pertama kalinya oleh Badan Urusan Pangan dan Pertanian PBB yakni FAO, telah berhasil mengurangi setengah jumlah orang yang menderita kekurangan gizi. (18.06.2013)

Darurat Konstitusi Sektor Pangan, Air, dan EnergiDewi Aryani ; Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
SINDO, 14 Maret 2013
Pangan, air, dan energi merupakan kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Secara sederhana manusia membutuhkan makan dan air untuk hidup serta butuh energi guna menunjang mendapatkan kedua hal tersebut.
Geoff Hiscock dalam bukunya, Earth War,menyatakan bahwa ketahanan pangan, air, energi, dan logam merupakan isu utama yang menjadi perhatian berbagai negara di dunia saat ini. Selain karena keberadaannya terbatas, laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhan akan sumber daya pun meningkat. Hal ini berimplikasi terhadap intensitas perebutan kekuasaan antara negara atas sumber daya.
China dan India akan menjadi penentu pasar energi di dunia, sedangkan di Asia tenggara pada 2050 menjadi masa keemasan bagi Indonesia, di mana ada bonus demografi diikuti oleh sumber daya yang kaya akan minyak/ gas, termal, batu bara, kelapa sawit, dan pangan (Hiscock, 2012). Krisis air, pangan, dan energi tak terelakkan. Harga pangan akan tetap tinggi dan fluktuatif.
Begitu pula dengan energi, khususnya minyak dan gas bumi (migas), cadangan minyak diperkirakan 1,2 triliun barel yang diperkirakan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dunia selama 30 tahun ke depan. Sedangkan untuk air secara global satu dari empat orang di dunia kekurangan air minum, sementara satu dari tiga tidak mendapatkan sanitasi yang layak.
Dengan potensi kerentanan itu, perlu kebijakan antisipatif. Pembuat kebijakan harus lebih arif dalam membuat kebijakan terkait ketahanan energi, pangan, dan air, serta jaminan keberlangsungan pada masa akan datang.
Antisipasi Indonesia
Tidak berbeda jauh dengan apa yang melanda dunia, Indonesia juga mengalami krisis baik pada pangan, air, maupun energi. Berdasarkan Kepala BNPB, Indonesia

akan mengalami krisis air, terutama musim kemarau. Pada 2020 potensi air yang layak diperkirakan sebesar 35% dari total air yang dikelola atau sekitar 400 meter kubik per kapita per tahun. Angka ini tentu jauh dari angka minimum dunia yaitu 1000 meter kubik per kapita per tahun.
Pada pangan pemenuhan swasembada pangan lima komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula belum optimal, terlihat dari ada ketergantungan terhadap impor, kedelai sekitar 70%, gula 54%, dan daging sapi sekitar 20%. Selain itu juga permasalahan terkait ketersediaan lahan garapan ratarata petani yang hanya 0.3 hektare. Idealnya petani memiliki lahan garapan seluas 2 hektare, ditambah maraknya ada konversi lahan pertanian, contoh penyusutan lahan pertanian dari 1,550 hektare menjadi 1300 hektare pada 2012.
Sedangkan pada sektor energi, khususnya minyak bumi, dapat diketahui bahwa konsumsi minyak bumi pada 2010 mencapai 388,241 ribu barel dengan konsumsi per hari rata-rata 1,063,674 barel per hari. Sayangnya, Indonesia hanya mampu memproduksi BBM sebesar 241,2 juta barel sehingga pemerintah masih mengambil kebijakan mengimpor produk BBM sebesar 23,633 juta barel.
Departemen ESDM pada 2011 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki cadangan minyak bumi hampir sebesar 8 miliar barel (7.764,48 MMSTB), di mana 3,7 miliar barel telah terbukti, dan sisanya merupakan cadangan potensial. Ketersediaan minyak bumi tersebut, jika diukur dengan rasio cadangan terbukti terhadap produksi (RP ratio), dapat bertahan selama 12,27 tahun.
Berdasar pada persoalan di atas, tidak heran jika isu ketahanan pangan dan energi menjadi urgensi tersendiri bagi pemerintah saat ini. Hal ini tercermin dalam program dua tahun kedepan (hingga 2014) yang menekankan ada ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat baik harga maupun aksesibilitas dalam membeli produk pangan.
Amanat Konstitusi
Berdasarkan undang-undang yang mengatur komoditas strategis ini, di antaranya UU No 30/2007 mengenai energi, UU No 7/2004 mengenai sumber daya air, dan UU No 18/2012 mengenai pangan, dan tujuan bangsa dan negara, ketahanan pangan, serta air dan energi diupayakan berbasis pada kedaulatan dan kemandirian yang sejatinya berupaya untuk mewujudkan kedaulatan nasional yang tangguh.
Kedaulatan mencerminkan hak menentukan kebijakan secara mandiri, menjamin hak atas sumber daya tersebut, dan memberi hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem usaha sesuai dengan potensi sumber daya dalam negeri. Sedangkan kemandirian lebih menekankan pada kemampuan negara memproduksi kebutuhannya di dalam negeri.
Undang-undang pangan dan energi pun menjelaskan bahwa dapat melakukan impor dengan catatan produksi pangan dan energi tidak mencukupi. Sayangnya, yang terjadi masih tingginya impor pangan dan energi nasional dalam memenuhi kebutuhan. Kembali pada makna yang tersirat dari UUD 1945, sumber daya alam dipergunakan dan dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Jika dipahami lebih dalam, tidak hanya memandang energi, pangan, dan air sebagai sebuah produk yang perlu disediakan, melainkan juga perlu ada kebijakan yang mengarah pada pembangunan dan pengembangan industri pangan, air, dan energi nasional. Dengan demikian, kebijakan yang mengimpor kebutuhan dengan dalih

lebih murah bukanlah hal yang tepat karena berkaitan dengan kemandirian negara.
Dari tiga komoditas strategis yang dibahas, saat ini sektor migas mengalami darurat konstitusi, pola pengelolaan saat ini belum dilindungi secara utuh oleh undang-undang. Darurat konstitusi arahnya kepada mengembalikan lagi semua isi UU dan kebijakan turunannya sesuai kepada UUD 1945 Pasal 33.
Kata “darurat” menjadi penting untuk dikupas demi menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi dan segala bidang kehidupan jika ketiganya makin langka, musnah, bahkan tidak ada cadangan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi darurat konstitusi tentu dapat dijadikan peluang bagi berbagai pihak untuk mengambil keuntungan, terutama dalam kontrak eksplorasi dalam sektor migas.
Pada pangan, kemampuan produksi nasional perlu diimbangi dengan keberadaan lembaga pemerintah sebagai stabilisator harga pangan. Peranan Perum Bulog perlu diperkuat sehingga harga pangan dapat dikendalikan, baik mengurangi fluktuasi harga sekaligus mengantisipasi cadangan pangan untuk kondisi darurat. Setidaknya harga produk pangan strategis seperti beras, jagung, gula, daging sapi, dan kedelai terjangkau oleh masyarakat dan tersedia.
Ketersediaan ini pula didorong untuk tidak lagi mengimpor dari negara tetangga, tetapi dihasilkan dari pertanian lokal. Pada sektor energi, negara wajib mengambil alih kembali kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Menyiapkan cadangan energi baik untuk cadangan operasional maupun cadangan strategis demi menanggulangi kondisi darurat dan krisis energi.
Intinya dari permasalahan krisis pada komoditas strategis ini adalah tata pengelolaan sehingga solusi perlu diarahkan mengefisienkan dan mengefektifkan tata kelola sektor-sektor strategis ini. Secara umum terdapat beberapa rekomendasi dalam menyikapi kondisi darurat pangan air dan energi ini.
Pertama, ada harmonisasi kebijakan pemerintah baik undang-undang hingga keputusan menteri yang terkait dengan pengelolaan sumber daya energi, air, dan pangan. Kedua, ada penguatan kelembagaan dan koordinasi antarlembaga yang terkait, baik perbankan, akademisi, LSM, maupun swasta guna meningkatkan inovasi dan produktivitas sumber daya terkait. Ketiga, ada jaminan ketersediaan khususnya dalam mengembangkan potensi produksi melalui pengembangan teknologi.
Keempat, keterjangkauan melalui penataan kembali sistem logistik, baik pergudangan, cadangan, perbaikan, maupun pengembangan infrastruktur transportasi. Terutama guna memperpendek supply chain energi, pangan, dan air. Kelima, membangun sistem pengawasan terkait distribusi dari sumber daya energi, pangan, dan air. ●