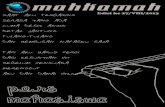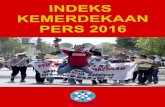(Komas) Kemerdekaan Pers Di Indonesia
-
Upload
divagol-wiranata -
Category
Documents
-
view
22 -
download
0
Transcript of (Komas) Kemerdekaan Pers Di Indonesia

I. PENDAHULUAN
Kemerdekaan pers dalam arti luas adalah pengungkapan kebebasan berpendapat
secara kolektif dari hak berpendapat secara individu yang diterima sebagai hak asasi manusia.
Masyarakat demokratis dibangun atas dasar konsepsi kedaulatan rakyat, dan keinginan-
keinginan pada masyarakat demokratis itu ditentukan oleh opini publik yang dinyatakan
secara terbuka. Hak publik untuk tahu inilah inti dari kemerdekaan pers, sedangkan wartawan
profesional, penulis, dan produsen hanya pelaksanaan langsung. Tidak adanya kemerdekaan
pers ini berarti tidak adanya hak asasi manusia (HAM).
Pembahasan RUU pers terakhir 1998 dan awal 1999 yang kemudian menjadi UU no.
40 Tahun 1999 tentang pers sangat gencar. Independensi pers, dalam arti jangan ada lagi
campur tangan birokrasi terhadap pembinaan dan pengembangan kehidupan pers nasional
juga diperjuangkan oleh kalangan pers. Komitmen seperti itu sudah diuslukan sejak
pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia PWI tahun 1946. Pada saat pembahasan RUU
pers itu di DPR-RI, kalangan pers dengan gigih memperjuangkan independensi pers. Hasil
perjuangan itu memang tercapai dengan bulatnya pendirian sehingga muncul jargon
“biarkanlah pers mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi campur
tangan birokrasi”. Aktualisasi keberhasilan perjuangan itu adalah dibentuknya Dewan Pers
yang independen sebagaimana ditetapkan dalam UUD No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
Kemerdekaan pers berasal dari kedaulatan rakyat dan digunakan sebagai perisai bagi
rakyat dari ancaman pelanggaran HAM oleh kesewenang-wenangan kekuasaan atau uang.
Dengan kemerdekan pers terjadilah keseimbangan dalam kehidupan bangsa dan bernegara.
Kemerdekaan pers berhasil diraih, karena keberhasilan reformasi yang mengakhiri kekuasan
rezim Orde Baru pada tahun 1998.
Pembredelan Tempo serta perlawanannya terhadap pemerintah Orde Baru
Pembredelan 1994 ibarat hujan, jika bukan badai dalam ekologi politik Indonesia
secara menyeluruh. Tidak baru, tidak aneh dan tidak istimewa jika dipahami dalam
ekosistemnya.
Sebelum dibredel pada 21 Juni 2004, Tempo menjadi majalah berita mingguan yang
paling penting di Indonesia. Pemimpin Editornya adalah Gunawan Mohammad yang
merupakan seorang panyair dan intelektual yang cukup terkemuka di Indonesia. Pada 1982
majalah Tempo pernah ditutup untuk sementara waktu, karena berani melaporkan situasi
1

pemilu saat itu yang ricuh. Namun dua minggu kemudian, Tempo diizinkan kembali untuk
terbit. Pemerintah Orde Baru memang selalu was-was terhadap Tempo, sehingga majalah ini
selalu dalam pengawasan pemerintah. Majalah ini memang popular dengan independensinya
yang tinggi dan juga keberaniannya dalam mengungkap fakta di lapangan. Selain itu kritikan-
kritikan Tempo terhadap pemerintah di tuliskan dengan kata-kata yang pedas dan bombastis.
Goenawan pernah menulis di majalah Tempo, bahwa kritik adalah bagian dari kerja
jurnalisme. Motto Tempo yang terkenal adalah “ enak dibaca dan perlu”.
Meskipun berani melawan pemerintah, namun tidak berarti Tempo bebas dari
tekanan. Apalagi dalam hal menerbitkan sebuah berita yang menyangkut politik serta
keburukan pemerintah, Tempo telah mendapatkanberkali-kali maendapatkan peringatan.
Hingga akhirnya Tempo harus rela dibungkam dengan aksi pembredelan itu.
Namun perjuangan Tempo tidak berhenti sampai disana. Pembredelan bukanlah akhir
dari riwayat Tempo. Untuk tetap survive, ia harus menggunakan trik dan startegi.Salah satu
trik dan strategi yang digunakan Tempo adalah yang pertama adalah mengganti kalimat aktif
menjadi pasif dan yang kedua adalah stategi pinjam mulut. Semua strategi itu dilakukan
Tempo untuk menjamin kelangsungannya sebagai media yang independen dan terbuka.
Tekanan yang dating bertubi-tubi dari pemerintah tidak meluluhkan semangat Tempo untuk
terus menyampaikan kebenaran kepada masyarakat.
Setelah pembredelan 21 Juni 1994, wartawan Tempo aktif melakukan gerilya, seperti
dengan mendirikan Tempo Interaktif atau mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi)
pada tahun 1995. Perjuangan ini membuktikan komitmen Tempo untuk menjunjung
kebebasan pers yang terbelenggu ada pada zaman Orde Baru. Kemudian Tempo terbit
kembali pada tanggal 6 Oktober 1998, setelah jatuhnya Orde Baru.
II. PEMBAHASAN
Kemerdekaan Pers di Indonesia
Kemerdekaan Pers Masa Penjajahan Belanda
Di Indonesia jurnalistik pers mulai dikenal abad 18, tepatnya tahun 1744, ketika
sebuah surat kabar bernama Bataviasche Nouvelles diterbitkan dengan penguasaan orang-
orang Belanda. Pada 1776 di Jakarta terbit surat kabar Vendu Niews yang mengutamakan
2

pada berita pelelangan. Abad 19 terbit berbagai surat kabar lainnya yang kesemuanya masih
dikelola orang-orang Belanda untuk para pembaca orang Belanda atau bangsa pribumi yang
mengerti bahasa Belanda, yang umumnya merupakan kelompok kecil saja. Sedangkan surat
kabar pertama sebagai bacaan untuk kaum pribumi dimulai pada 1854 ketika majalah
Bianglala diterbitkan, disususl oleh Bromartani pada 1885, keduanmya di Weltevreden, dan
tahun 1856 terbit Soerat Kabar Bahasa Melajoe di Surabaya.
Sejarah jurnalistik pers abad 20, ditandai dengan munculnya surat kabar pertama
milik bangsa Indonesia. Namanya Medan Prijaji terbit di Bandung. Dengan modal bangsa
Indonesia untuk bangsa Indonesia. Medan Prijaji yang dimiliki dan dikelola oleh Tirto
Hadisurjo alias Raden Mas Djokomono tahun 1907, berbentuk mingguan. Tiga tahun
kemudian pada tahun 1910 berubah menjadi harian. Tirto Hadisurjo inilah yang dianggap
sebagai pelopor yang meletakkan dasar-dasar jurnalistik modern di Indonesia. baik secara
pemberitahuan maupun cara pemuatan karangan dan iklan1.
Pemerintah penjajah Belanda sejak menguasai Indonesia, mengetahui dengan benar
pengaruh surat kabar terhadap masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu dipandang perlu
membuat undang-undang khusus untuk membendung pengaruh pers Indonesia, karena
merupakan momok yang harus diperangi.
Saruhum dalam tulisannya yang berjudul “Perjuangan Surat Kabar Indonesia” yang
dimuat dalam sekilas “Perjuangan Surat Kabar”, menyatakan: “Maka untuk membatasi
pengaruh momok ini, pemerintah Hindia Belanda memandang tidak cukup mengancamnya
saja denagn Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Setelah ternyata dengan KUHP itu saja
tidak mempan, maka diadakanlah pula artikel-artikel tambahan seperti artikel 153 bis dan ter.
161 bis dan ter. dan artikel 154 KUHP. Hal itu pun belum dianggap cukup, sehingga
diadakan pula Persbreidel Ordonantie, yang memberikan hak kepada pemerintah penjajah
Belanda untuk menghentikan penerbitan surat kabar / majalah Indonesia yang dianggap
berbahaya”2. Pemberhentian ini dilakukan paling lama delapan hari. Tetapi jika sesudah
delapan hari surat kabar yang bersangkutan dinilai mengganggu lagi “ketertiban umum,”
maka larangan terbit bisa menjadi lebih lama3.
Tindakan lain, di samping Persbeidel Ordonantie adalah Haatzai Artikelen, karena
pasal-pasalnya mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan
permusuhan, kebencian serta penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan Hindia Belanda
1 Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita Dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional (Bandung: Simbiosa Rekatma Media, 2005), h. 19-20.2 Eko Kahya, Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 92-93.3 Nurudin, Jurnalisme Masa Kini (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 38.
3

(Pasal 154 dan 155) dan terhadap sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk di Hindia
Belanda (Pasal 156 dan 157). Akibatnya, banyak korban berjatuhan, antara lain S.K.
Trimurti, sampai melahirkan di penjara, bahkan ada yang sampai di buang ke Boven Digul.
Kemerdekaan Pers Masa Penjajahan Jepang
Di zaman pendudukan Jepang yang totaliter dan facistis, orang-orang surat kabar
(pers) Indonesia banyak yang berjuang tidak dengan ketajaman penanya (tulisan), melainkan
menempuh cara dan jalan lain (misalnya melalui organisasi keagamaan, pendidikan, politik,
dan sebagainya). Hal ini menggambarkan bahwa kehidupan pers ketika itu sangat tertekan4.
Tahun 1942, Indonesia dijajah oleh Jepang dan surat kabar Belanda ditutup. Segala
penerbitan diurus oleh Jepang. Seperti terbitnya koran Sinar Selatan itu modalnya berasal dari
Jepang. Sebelum 1942, Jepang sudah tertarik pada penerbitan di Indonesia. Pada tahun 1924-
1932, Tuan Ogawa menerbitkan surat kabar Bendee di Solo.
Pada zaman penjajahan Jepang, penguasa Jawa-Madura mengatur sarana publikasi
dan komunikasi dengan Undang-Undang No. 16. Dua segi yang menonjol dari UU itu adalah
berlakunya sistem izin terbit dan sensor preventif. Di pulau Jawa hanya boleh terbit 5 buah
harian dalam bahasa Indonesia. Diantaranya Asia Raya (di Jakarta), Tjahaja (di Bandung),
Sinar Baroe (di Semarang), Sinar Matahari (di Yogya), dan Soeara Asia (di Surabaya). Pada
masa ini, surat-surat kabar di Indonesia hanya sebagai alat pemerintah Jepang. Berita dan
karangan yang dimuat hanya yang pro Jepang. Penyebarannya rata-rata antara 20.000-30.000
eksemplar per hari.
Pada 14 Agustus 1945 (Jepang menyerah pada sekutu), muncul surat kabar yang
didirikan oleh Regering Voorlichtings Dienst (RVD), seperti Warta Indonesia (Jakarta) dan
Persatoean (Bandung). Di kota-kota yang diduduki sekutu berdiri surat-surat kabar nasional,
seperti di Jakarta Harian Merdeka (BM Diah) dan Harian Rakyat (Sjamsuddin Sutan
Makmur). Pada Juni 1949 (setelah persetujuan Roem-Royen), surat kabar nasional mulai
bangkit. Pelopor surat kabar setelah revolusi adalah Berita Indonesia (BI)5.
Kemerdekaan Pers Masa Revolusi Fisik
Periode revolusi fisik terjadi antara tahun 1945 sampai 1949. Masa itu adalah masa
bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang berhasil diraihnya pada
4 Kahya, Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers, h. 92-93.5 Nurudin, Jurnalisme Masa Kini (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 39.
4

tanggal 17 Agustus 1945. Belanda ingin kembali menduduki Indonesia, sehingga terjadilah
perang mempertahankan kemerdekaan. Pada saat itu, pers terbagi menjadi dua golongan,
yaitu :
1) Pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh tentara pendudukan Sekutu dan Belanda yang
selanjutnya dinamakan Pers Nica (Belanda).
2) Pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh orang Indonesia yang disebut Pers Republik.
Kedua golongan ini sangat berlawanan. Pers Republik disuarakan oleh kaum
Republik, yang berisi semangat mempertahankan kemerdekaan dan menentang usaha
pendudukan Sekutu. Pers ini benar-benar menjadi alat perjuangan masa itu. Sebaliknya, Pers
Nica berusaha mempengaruhi rakyat Indonesia agar menerima kembali Belanda untuk
berkuasa di Indonesia.
Beberapa contoh Koran Republik yang muncul pada masa itu, antara lain harian
“Merdeka”, “Sumber”, “Pemandangan”, “Kedaulatan Rakyat”, “Nasional” dan “Pedoman”.
Jawatan Penerangan Belanda menerbitkan Pers Nica, antara lain “Warta Indonesia” di
Jakarta, “Persatuan” di Bandung, “Suluh Rakyat” di Semarang, “Pelita Rakyat” di Surabaya
dan “Mustika” di Medan. Pada masa revolusi fisik inilah, Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI) dan Serikat Pengusaha Surat Kabar (SPS) “lahir”. Kedua organisasi ini mempunyai
kedudukan penting dalam sejarah pers Indonesia.
Pemerintah republik Indonesia untuk pertama kali mengeluarkan peraturan yang
membatasi kemerdekaan pers terjadi pada tahun 1948. Menurut Smith, “dalam kegembiraan
kemerdekaan ini, pers dan pemerintah bekerja bergandengan tangan erat sekali dalam seratus
hari pertama masa merdeka itu”.
Pemerintah memperlihatkan itikad baik terhadap pers dan berusaha membantunya
dengan mengimpor dan mensubsidi kertas koran dan dengan memberikan pinjaman
keuangan. Pada awalnya semua berjalan lancar, namun saat pers mulai bertindak dengan
menyerang pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat sampai pada presiden sendiri,
nampaknya pemerintah yang baru ketika itu belum dapat menerima kritikan yang pedas.
Sesuai dengan fungsi, naluri dan tradisinya, pers harus menjadi penjaga kepentingan
publik. Pers telah menyampaikan saran-saran yang amat diperlukan oleh pemerintah. Kritik-
kritik pers yang pedas dan menjengkelkan, menjadi beban pemerintah yang terlampau berat,
sehingga pemerintah mulai memukul balik kepada pers. Konflik keduanya berkembang
menjadi pertentangan permanen dan pers dipaksa tunduk di bawah kekuasaan pemerintah6.
6 Edward Cecil Smith, Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia (Jakarta: Pustaka Grafitti, 1986), h. 73.
5

Untuk menangani masalah-masalah pers, pemerintah membentuk Dewan Pers pada
tanggal 17 Maret 1950. Dewan Pers tersebut terdiri dari orang-orang persuratkabaran,
cendikiawan, dan pejabat-pejabat pemerintah, dengan tugas :
1) Penggantian undang-undang pers kolonial,
2) Pemberian dasar sosial ekonomis yang lebih kuat kepada pers Indonesia (artinya, fasilitas-
fasilitas kredit dan mungkin juga bantuan pemerintah),
3) Peningkatan mutu jurnalisme Indonesia,
4) Pengaturan yang memadai tentang kedudukan sosial dan hukum bagi wartawan
Indonesia (artinya, tingkat hidup dan tingkat gaji, perlindungan hukum, etik jurnalistik
dan lain-lain).
Namun akibat kekuasaan pemerintah yang tidak terlawan, menyebabkan organisasi-
organisasi pers tidak berkutik. Tidak tampak bukti bahwa lembaga-lembaga ini berhasil
membelokkan jalannya kegiatan-kegiatan anti pers, secara berarti.
Pers di Era Demokrasi Liberal (1949-1959)
Di era demokrasi liberal, landasan kemerdekaan pers adalah Konstitusi Republik
Indonesia Serikat (RIS 1949) dan Undang-Undang Dasar Sementara (1950). Dalam
Konstitusi RIS -- yang isinya banyak mengambil dari Piagam Pernyataan Hak Asasi Manusia
sedunia Universal Declaration of Human Rights, -- pada pasal 19 menyebutkan “Setiap orang
berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”. Isi pasal ini kemudian
dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Dasar Sementara (1950)7.
Saat kebebasan Pers tercantum dalam UUDS, tepatnya pada bagian V yang mengatur
hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia yang terdiri dari pasal 7 sampai pasal 34,
pada masa pemerintahan ini pemerintah masih kejam, dan banyak surat kabar yang dibredel
serta banyak pula wartawan yang ditangkap. Berdasarkan undang-undang tersebut maka
Penguasa Perang Daerah (Peperda) menetapkan keputusan bagi setiap penerbitasn surat kabar
dan majalah untuk dapat mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 oktober 1958 kepada Penguasa
Perang Daerah (Peperda). Dan ini dilakukan untuk mendapatkan surat izin terbit (SIT).
Meskipun demikian tidak selamanya surat izin lansung diterbitkan, hal ini terbukti ketika
harian Indonesia Raya (HI) begitu mengajukan SIT kepada Peperda (Penguasa Perang
Daerah) tidak langsung diberikan SIT. Dengan tidak diterbitkannya SIT, maka surat kabar
tersebut tidak bisa terbit lagi.
7 Eko Kahya, Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 96.
6

Tanggal 1 Oktober 1958 merupakan awal matinya kebebasan Pers di Indonesia.
Dimana penguasa pada saat itu telah menjadikan Pers sebagai alat penguasa untuk
memerdekakan tindakan-tindakan penguasa. Dan pada tahun inilah sejarah hitam Pers
Indonesia, dimana pada saat itu telah tercatat kurang lebih 42 peristiwa yang dialami Pers
Indonesia, sebagain besar mereka mengalami pembredelan, penahanan, dan penganiayaan
wartawan.
Dalam sejarah kebebasan Pers di Indonesia 1949-1959 yang lazimnya diartikan
sebagai kebebasan Demokrasi Liberal yang digunakan sebebas-bebasnya oleh Pers. Liberal
pada saat itu diartikan sebagai kebebasan politik (saling mencaci, memfitnah lawan politik)
serta sensasi dan pornografi. Apalagi setelah munculnya Party Bound Press (pers dibawah
kendali partai politik), seperti Abadi (Masyumi), Duta Masyarakat (NU), suluh Indonesia
(PNI), harian Rakyat (PKI). Begitulah sejarah singkatpers mulai zaman klasik hingga
modern, tepatnya ketika pers tersebut masuk ke Indonesia yang mengalami pasang surut8.
Pers di Zaman Orde Lama atau Pers Terpimpin (1956-1966)
Lebih kurang 10 hari setelah Dekrit Presiden R.I. yang menyatakan kembali ke UUD
1945, tindakan tekanan terhadap pers terus berlangsung, yaitu pembredelan terhadap Kantor
berita PIA dan Surat Kabar Republik, Pedoman, Berita Indonesia, dan Sin Po yang dilakukan
oleh Penguasa Perang Jakarta.
Upaya untuk membatasi kebebasan pers itu tercermin dari pidato Menteri Muda
Penerangan Maladi, ketika menyambut HUT Proklamasi Kemerdekaan R.I ke-14, antara lain
ia menyatakan; “...Hak kebebasan individu disesuaikan dengan hak kolektif seluruh bangsa
dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Hak berfikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh
penghasilan sebagaimana yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 harus ada batasnya:
keamanan negara, kepentingan bangsa, moral dan kepribadian Indonesia, serta tanggung
jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
Pada tahun 1960, penekanan kepada kebebasan pers diawali dengan peringatan
Menteri Muda Penerangan Maladi bahwa “langkah-langkah tegas akan dilakukan terhadap
surat kabar, majalah-majalah, dan kantor-kantor berita yang tidak mentaati peraturan yang
diperlukan dalam usaha menerbitkan pers nasional”. Masih pada tahun 1960, penguasa
perang mulai mengenakan sanksi-sanksi perizinan terhadap pers. Demi kepentingan
8 Nurudin, Jurnalisme Masa Kini (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 45-46.
7

pemeliharaan ketertiban umum dan ketenangan, penguasa perang mencabut izin terbit Harian
Republik.
Memasuki tahun 1964 kondisi kebebasan pers semakin memburuk, hal ini
digambarkan oleh Edward Cecil Smith dengan mengutip dari “Army Handbook“ bahwa
Kementerian Penerangan dan badan-badannya mengontrol semua kegiatan pers. Perubahan
yang ada hampir-hampir tidak lebih dari sekedar perubahan sumber wewenang karena sensor
tetap ketat dan dilakukan secara sepihak.
Berdasarkan uraian di atas, tindakan-tindakan penekanan terhadap kemerdekaan pers
oleh penguasa Orde Lama, bertambah bersamaan dengan meningkatnya ketegangan dalam
pemerintahan. Tindakan-tindakan penekanan terhadap kebebasan pers merosot, ketika
ketegangan dalam pemerintahan menurun. Lebih-lebih setelah percetakan-percatakan diambil
alih oleh pemerintah dan para wartawan diwajibkan untuk berjanji mendukung politik
pemerintah, sangat sedikit pemerintah melakukan tindakan penekanan kepada pers9.
Pers di Era Demokrasi Pancasila dan Orde Baru
Pers menyandang berbagai atribut yang menyebabkan sering terpojok pada posisi
yang dilematis. Di satu sisi tuntutan masyarakat mengharuskan memotret realitas sosial
sehingga pers berfungsi sebagai alat kontrol. Namun pada posisi lain, sebagai institusi yang
tidak lepas dari pemerintah, menyebabkan pers cenderung tidak vis a vis terhadap
pemerintah. Ini artinya, pers mau tidak mau harus mematuhi mekanisme yang menjadi
otoritas pemerintah. Inilah yang membuat pers sulit menentukan pilihan, antara kewajiban
moral terhadap masyarakat dan keharusan untuk mematuhi aturan pemerintah sebagai
konsekuensi logis. Jalan alternatif yang harus dilakukan adalah melakukan harmonisasi
hubungan pers, pemerintah, dan masyarakat10.
Di awal pemerintahan Orde Baru, menyatakan bahwa akan membuang jauh-jauh
praktek demokrasi terpimpin dan menggantinya dengan Demokrasi Pancasila. Pernyataan
tersebut tentu saja membuat para tokoh politik, kaum intelektual, tokoh umum, tokoh pers
terkemuka dan lain-lain menyambutmya dengan antusias sehingga lahirlah istilah Pers
Pancasila.
Pemerintahan Orde Baru sangat menekankan pentingnya pemahaman tentang Pers
Pancasila. Menurut rumusan Sidang Pleno XXV Dewan Pers, (Desember 1984) bahwa “Pers 9 Eko Kahya, Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 98.
10 Nurudin, Sistem Komunikasi Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 80.
8

Pancasila adalah pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya
berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hakekat Pers Pancasila adalah pers
yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya
sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol
sosial yang konstrukrif”
Masa “bulan madu” antara pers dan pemerintah ketika itu dipermanis dengan
keluarnya Undang-undang Pokok Pers (UUPP) Nomor 11 Tahun 1966, yang dijamin tidak
ada sensor dan pembredelan, serta penegasan bahwa setiap warga negara mempunyai hak
untuk menerbitkan pers yang bersifat kolektif, dan tidak diperlukan surat izin terbit.
Kemesraan tersebut ternyata hanya berlangsung kurang lebih delapan tahun, karena sejak
terjadinya “Peristiwa Malari” (peristiwa lima belas Januari 1974), kebebasan pers mengalami
set-back (kembali seperti zaman Orde Lama).
Terjadinya Peristiwa Malari tahun 1974, berakibat beberapa surat kabar dilarang terbit
Tujuh surat kabar terkemuka di Jakarta (termasuk Kompas) diberangus untuk beberapa waktu
dan baru diijinkan terbit kembali, setelah para pemimpin redaksinya menandatangani surat
pernyataan maaf. Penguasa lebih menggiatkan larangan-larangan melalui telepon supaya pers
tidak menyiarkan suatu berita, ataupun para wartawan lebih diperingatkan untuk mentaati
kode etik jurnalistik sebagai “self censorship”(penyensoran diri).
Pers pasca Malari merupakan pers yang cenderung “mewakili” kepentingan penguasa,
pemerintah atau negara. Pada saat itu pers jarang, malah tidak pernah melakukan kontrol
sosial secara krisis, tegas dan berani. Pers pasca Malari tidak artikulatif dan mirip dengan
jaman rezim Demokrasi Terpimpin. Perbedaan hanya pada kemasan yakni rezim Orde Baru
melihat pers tidak lebih dari sekedar institusi politik yang harus diatur dan dikontrol seperti
halnya dengan organisasi massa dan Partai Politik11.
Kebebasan Pers di Era Reformasi
Sejak masa reformasi tahun 1998, pers nasional kembali menikmati kebebasan pers.
Hal demikian sejalan dengan alam reformasi, keterbukaan dan demokrasi yang
diperjuangkan rakyat Indonesia. Pemerintahan pada masa reformasi sangat mempermudah
izin penerbitan pers. Akibatnya, pada awal reformasi banyak sekali penerbitan pers atau
koran-koran, majalah atau tabloid baru bermunculan. Bisa dikatakan pada awal reformasi
kemunculan pers ibarat jamur di musim hujan.
11 Eko Kahya, Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 115-120.
9

Kalangan pers mulai bernafas lega ketika di era reformasi pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kendati belum sepenuhnya memenuhi keinginan
kalangan pers, kelahiran undang-undang pers tersebut disambut gembira, karena tercatat
beberapa kemajuan penting dibanding dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers (UUPP).
Di dalam Undang-undang Pers yang baru ini, dengan tegas menjamin adanya
kemerdekaan pers, sebagai hak asasi warga negara (Pasal 4). Itulah sebabnya mengapa tidak
lagi di singgung perlu tidaknya surat izin terbit. Di samping itu ada jaminan lain yang
diberikan oleh undang undang ini, yaitu terhadap pers nasional tidak di kenakan penyensoran,
pembredelan dan pelarangan penyiaran sebagaima tercantum dalam Pasal 4 ayat (2).
Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan
mempunyai hak tolak. Tujuan hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber
informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat
digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh penjabat penyidik dan atau dimintai
menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan
negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.
Pada masa reformasi ini dengan keluarnya Undang-Undang tentang pers, yaitu
Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, maka pers nasional melaksanakan peranan
sebagai berikut :
1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi.
2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan
hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan
dengan kepentingan umum.
5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran12.
III. KESIMPULAN
12 Eko Kahya, Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 120.
10

Pers Indonesia senantiasa berkembang dan berubah sejalan dengan tuntutan
perkembangan zaman. Pers di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan identitas.
Adapun perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:
Tahun 1945-an, pers Indonesia dimulai sebagai pers perjuangan.
Tahun 1950-an dan tahun 1960-an menjadi pers partisan yang mempunyai tujuan sama
dengan partai-partai politik yang mendanainya.
Tahun 1970-an dan tahun 1980-an menjadi periode pers komersial, dengan pencarian
dana masyarakat serta jumlah pembaca yang tinggi.
Awal tahun 1990-an, pers memulai proses repolitisasi.
Awal reformasi 1999, lahir pers bebas di bawah kebijakan pemerintahan B.J. Habibie
yang kemudian diteruskan pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati
Soekarnoputri.
Daftar Pustaka
11

Eisy, M Ridlo. Peranan Media dalam Masyarakat. Jakarta: Dewan Pers, 2007.
Siregar, RH. Setengah Abad Pergulatan Etika Pers. Jakarta: Dewan Kehormatan PWI, 2005.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Wartawan Independen, Sebuah Pertanggungjawaban AJI.
Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 1995.
Sumadiria, Haris. Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita Dan Feature Panduan Praktis
Jurnalis Profesional. Bandung: Simbiosa Rekatma Media, 2005.
Kahya, Eko. Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers. Bandung: Pustaka Bani Quraisy,
2004.
Nurudin. Jurnalisme Masa Kini. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
Nurudin. Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Smith, Edward Cecil. Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia. Jakarta: Pustaka Grafitti,
1986.
Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. “Pers Indonesia.” Artikel diakses pada 29
Oktober 2013 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pers_Indonesia
Ardy, Vera Widiaswari. “Sistem Pers Indonesia, Sistem Komunikasi Pada Masa Orde Baru,
Terbelenggunya Media Massa Dalam Kekuasaan Orde Baru (Kasus Pembredelan Majalah
Tempo).” Artikel diakses pada 29 Oktober 2013 dari
http://disinijurnalvera.blogspot.com/2008/12/sistem-pers-indonesia-masa-orde-baru.html
12