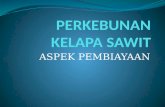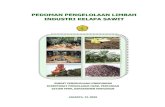kelapa sawit
-
Upload
ihwan-fadli -
Category
Documents
-
view
14 -
download
2
description
Transcript of kelapa sawit

Ameilia Zuliyanti Siregar : Kelapa Sawit : Minyak Nabati Berprospek Tinggi, 2006
USU Repository©2006
1
KELAPA SAWIT: MINYAK NABATI BERPROSPEK TINGGI Ameilia Zuliyanti Siregar, S.Si, M.Sc
Staf Pengajar Departemen HPT Fakultas Pertanian USU Dr. A. Sofyan No. 3 Kampus USU Medan/[email protected]
Pendahuluan Laju perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia semakin pesat, terutama peningkatan luas lahan kelapa sawit yang akan memerlukan jumlah pupuk dan penyerbukan dengan bantuan serangga untuk pertumbuhan tanaman sangat berperan strategis. Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) adalah salah satu palma yang menghasilkan minyak nabati, yang lebih dikenal dengan sebutan palm oil. Sumber minyak nabati dapat berasal dari kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedele, biji bunga matahari dan lainnya. Kelapa sawit adalah penyumbang minyak nabati terbesar di dunia (2000-3000 kg/ha), manakala kelapa hanya mencapai angka 700-1000 kg/ha. Menurut Corley (1976), ada tiga jenis kelapa sawit yaitu Elaeis guineensis Jacq (ditanam di Indonesia, berasal dari Afrika), E. deifera (E. melanocca), dan E. odora (Barcella odora). Ada beberapa varietas tanaman kelapa sawit yang telah dikenal seperti: Dura, Pisifera, Tenera, Macro carya, dan Diwikka-wakka (Fauzi, dkk., 2006). Kelapa sawit adalah tanaman monoecius, dimana bunga jantan dan bunga betina tumbuh secara terpisah pada satu pokok tanaman. Masa masak atau “anthesis” dari kedua jenis bunga tersebut sangat jarang atau tidak pernah bersamaan. Ini berarti bahwa proses pembuahan bunga betina terjadi dengan diperolehnya tepung sari dari pokok lainnya (Hartley, 1977). Proses penyerbukan dapat terlaksana apabila ada perantara yang mampu memindahkan tepung sari dari satu pokok ke pokok lain yang mempunyai bunga betina yang sedang mekar atau “receptive” Hasil penelitian membuktikan bahwa proses persarian tersebut sebagian besar berlangsung dengan perantaraan kompleks serangga (Hardon, 1976, Syed, 1981a). Serangga Penyerbuk Kelapa Sawit (SPKS) Di Indonesia dan Malaysia, serangga penyerbuk kelapa sawit adalah Thrips hawaiiensis (Syed, 1981a, Sipayung dan Soedharto, 1982) dan di Kamerun adalah Elaeidobius kamerunicus. Peranan E. kamerunicus sebagai penyerbuk kelapa sawit adalah lebih baik dibandingkan dengan T. hawaiiensis disebabkan E. kamerunicus hanya dapat makan dan berkembang biak dengan sempurna pada bunga jantan tanaman kelapa sawit, serangga tersebut tidak berbahaya pada tanaman lain, perkembangan telur hingga kumbang berkisar 8-21 hari untuk betina dan 9-24 hari untuk jantan dengan sex ratio 1:1 (Syed, 1982b). Manakala Mangoesoekarjo dan Semangun (2003) menyatakan keberadaan SPKS menyebabkan penyerbukan bantuan tidak diperlukan lagi, SPKS dapat hidup dan berkembang biak secara alami di perkebunan kelapa sawit sehingga tidak memerlukan penyebaran ulang, tidak terlihat dampak negatif, kualitas tandan mengalami peningkatan dan panen awal dipercepat. Elaeidobius kamerunicus, serangga penyerbuk kelapa sawit berasal dari Kamerun, Afrika diintroduksi dari Malaysia ke Indonesia atas kerjasama antara Pusat Penelitian Marihat dengan

Ameilia Zuliyanti Siregar : Kelapa Sawit : Minyak Nabati Berprospek Tinggi, 2006
USU Repository©2006
2
PT. PP. London Sumatera dan tenaga ahli R.A.Syed pada tanggal 16 Juli 1982 dengan izin Menteri Pertanian RI No. 03/SIP/Bun/II/1982 sebanyak 4623 pupa, berkembang menjadi imago 508 ekor, terdiri dari 394 ekor betina dan 114 ekor jantan. Selanjutnya diadakan penelitian terhadap kekhususan tanaman inang yang ditujukan pada jenis-jenis tanaman palmae dan tanaman perkebunan seperti Tabel 1. Tabel 1. Pengujian kekhususan inang Elaeidobius kamerunicus Bunga Tanaman Dimakan Peneloran Berkembang Biak Kelapa Sawit (E. guineensis) Dengan baik- tidak Ada-tidak ada Dengan baik-tidak Kelapa (Cocos nucifera) Dengan baik- tidak Sedikit-tidak Tidak Aren (Arenga catechu) Tidak Tidak ada Tidak Coklat (Theobroma cacao) Tidak Tidak ada Tidak Kopi (Coffea robusta) Tidak Tidak ada Tidak Karet (Hevea sp) Tidak Tidak ada Tidak Lada (Piper nigrum) Tidak Tidak ada Tidak Tembakau (N. tobacum) Tidak Tidak ada Tidak Jagung (Zea mays) Tidak Tidak ada Tidak Ubi Kayu (M. utilissima) Sedikit Tidak ada Tidak K.Sepatu (H.rosa-sinensis) Sedikit Tidak ada Tidak Kanna (Canna indica) Sedikit Tidak ada Tidak
Sumber : Hutahuruk dkk (1982).
Elaeidobius kamerunicus bersifat spesifik dan beradaptasi sangat baik pada tanaman kelapa sawit. Disamping itu serangga ini dapat beradaptasi pada musim basah dan musim kering, dapat memindahkan bunga tepung sari dengan kualitas yang sama baik pada tanaman muda maupun pada tanaman tinggi serta mencari dan mengenali bunga betina. Sejalan dengan hal ini maka pelaksanaan penyerbukan oleh serangga ini akan jauh lebih baik dari penyerbukan alamiah maupun dengan bantuan (assisted pollination). Dengan memanfaatkan serangga ini penyerbukan bantuan yang biasa dilakukan dapat dihentikan sama sekali. Pada musim penghujan, thrips sangat rendah dan kurang berfungsi. Keadaan sedemikian merupakan salah satu penyebab terjadinya penyebaran panen yang sanagt bergoyang sepanjang tahun yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pengaturan tenaga kerja di lapangan dan di pabrik. Sesuai dengan sifatnya yang tahan terhadap perubahan keadaan iklim, Elaeidobius cenderung lebih suka pada keadaan basah. Susunan Buah dan Berat Tandan Dari satu seri survei yang diadakan diberbagai lokasi di Sumatera Utara (Tabel 2) diperoleh bahwa susunan buah di daerah ini berkisar antara 44 sampai dengan 74%. Hasil pengamatan yang diadakan oleh staf Penelitian PT. PP. London Sumatera menujukkan bahwa susunan buah tanaman tahun 1972 bervariasi dari 25% sampai dengan 44% yakni apabila penyerbukan diserahkan pada lingkungan (Tabel 2). Dengan penyerbukan bantuan (assisted pollination) susunan buahnya meningkat menjadi 75%. Selanjutnya berdasarkan angka statistik SPBN Departemen Pertanian diperoleh bahwa rendemen inti untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 3.66% rata-rata untuk athun 1976 sampai dengan 1980. Angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan milik PNP/PTP di Indonesia dan bahan tanamannya dapat

Ameilia Zuliyanti Siregar : Kelapa Sawit : Minyak Nabati Berprospek Tinggi, 2006
USU Repository©2006
3
dikatakan sama. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa rendahnya rendemaen inti di Indonesia adalah akibat dari miskinnya penyerbukan. Tabel 2. Persentase susunan buah dan berat tandan rata-rata yang berasal dari petak dengan dan
tanpa penyerbukan bantuan di beberapa perkebunan di Sumatera. Kebun Bulan PA.Susunan
Buah (%) PA. Berat Tandan (kg)
PB.Susunan Buah (%)
PB Berat Tandan (kg)
Naiknya Berat Tandan (%)
R.Sialang (1972)
Jun Juk Aug
30.4 34.9 31.7
16.0 16.8 16.4
62.6 64.8 67.7
18.5 18.9 19.7
15.6 12.5 20.1
S.Bejangkar (1970)
Jun Jul Aug
43.4 27.5 33.1
12.6 11.7 12.0
51.4 66.5 65.8
16.3 16.4 16.1
29.4 40.9 34.2
(1972) Jun Jul Aug
27.6 27.7 30.8
12.8 12.3 12.8
46.6 60.5 68.0
15.1 15.7 16.0
18.0 27.6 25.0
G.Melayu (1970)
Jun Jul Aug
25.0 32.0 35.3
18.1 18.7 19.0
44.5 67.0 68.0
19.9 21.4 20.6
9.9 14.4 8.4
(1973) Jun Jul Aug
44.5 27.0 37.3
15.1 14.6 14.0
64.4 74.3 73.4
17.1 16.5 16.2
13.2 13.0 15.7
Sumber: Hutahuruk dkk. (1982)
Pada beberapa kebun produksi kelapa sawit jauh diatas data tersebut terutama inti yang dapat mencapai 1200 sampai dengan 1500 (rendemen inti 6-7%). Pada awalnya terdapat kesulitan dalam pengolahan karena padatnya buah sehingga memerlukan pembelahan tandan dan perpanjangan tekanan uap pada perebusan tanaman yang sudah dapat diatasi. Pengalaman di Sabah (Malaysia) menunjukkan kenaiakn produksi tandan sampai 23.1% pada tanaman pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1968. Berat tandan akan naik menjadi 30.6%, meski jumlah tandan kurang dari 5.8%. Untuk mengamankan perkembangan SPKS pada awal penyebarannya telah dilakukan percobaan menggunakan insektisida berupa: Alsystin 25 WP, IKI 25 WP, IKI 5 EC, Dimilin 25 WP, Ambush 2 EC, Bayrusil 25 EC, Baythroid 50 SL, Cymbush 5 EC, Hosthation 40 EC, Sevidan 70 WP. Disamping itu perlu disebarluaskan penggunaan bioinsektisida lainnya seperti Bacillus thuringiesis (Thuricide HP, Bactospeine) dan Chitine inhibitor dengan komposisi yang tepat dan sempurna agar tikus lebih menyukai umpan tersebut (Lubis, 1992). Laju perkembangan kelapa sawit yang semakin pesat membutuhkan perhatian yang besar dimulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, pengontrolan organisme pengganggu tanaman (OPT) sehingga mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Dengan semakin gencarnya peningkatan produksi CPO maka dinilai strategis untuk menginventarisasi musuh alami SPKS sehingga memberikan keuntungan positif bagi pihak perkebunan, pabrik, masyarakat, dan lingkungan.

Ameilia Zuliyanti Siregar : Kelapa Sawit : Minyak Nabati Berprospek Tinggi, 2006
USU Repository©2006
4
Di Malaysia menunjukkan bahwa setelah pemanfaatan E. kamerunicus diperoleh kenaikan produksi tahunan dalam arti keseluruhan untuk minyak (CPO) dan inti masing-masing 2% dan 100% (Syed, 1982a, Lubis dan Hutahuruk, 1982). Manakala berdasarkan pengamatan fruit set kelapa sawit di Sumatera Utara, maka pelepasaan serangga ini diperhitungkan akan dapat memberikan kenaikan produksi minyak dan inti yang setara dengan 40.000 juta rupiah pertahun. Adanya segi positif yang memberikan keuntungan terhadap usaha perkelapasawitan menyebabkan dianjurkannya SPKS digunakan di Indonesia (Hutahuruk dkk, 1982).
Dengan pelepasan E. kamerunicus, penyerbukan akan lebih sempurna, kenaikan produksi CPO sebesar 20% dan inti sebesar 100% seperti di Malaysia adalah sangat mungkin tercapai di Indonesia, mengingat kondisi penyerbukan sebelumnya yang sangat miskin. Seiring dengan kenaikan produksi, penghematan tenaga kerja dinyatakan dalam bentuk rupiah maka tambahan perolehan sektor perkebunan besar milik Negara pertahun berkisar antara Rp 30 milyard dan Rp 40 milyard, masing-masing untuk harga penjualan ekspor dan harga penjualan lokal apabila kondisi tersebut dicapai. Musuh Alami SPKS Hasil penelitian Syed (1981b, 1982a), Hutahuruk dkk.(1982), Lubis dan Hutauruk (1982) dan Poiner (2002) menunjukkan bahwa musuh alami SPKS masih dalam bentuk hipotesis dari kelompok tikus, semut dan hanya penelitian mendalam dan terkini tentang cacing yang bersifat parasit pada tubuh E. kamerunicus. Tikus membutuhkan protein untuk melengkapi bahan makannya. Di perkebunan kelapa sawit sumber protein adalah terbatas. Pada bunga jantan kelapa sawit yang sedang membusuk akan terdapat banyak pupa dan larva E. kamerunicus yang merupakan sumber protein tambahan. Dengan demikian ada kemungkinan perkembangbiakan tidak akan lebih baik yang berarti keperidian akan meningkat. Populasi tikus di perkebunan kelapa sawit selama ini dikontrol dengan menggunakan umpan beracun yang mengandung protein seperti rodentisida Klerat dengan 3 pusingan dan interval 3 hari (Mangoesoekarjo dan Semangun, 2003). Cara lain adalah penggunaan model pagar parit berair, sanitasi lingkungan dan mendatangkan predator sangat berperan dalam mengendalikan tikus (Kusnaedi, 2005). Manakala semut dapat dikendalikan dengan mendatangkan predator dan memindahkan semut sebagai serangga penyerbuk tanaman lain (Kusnaedi, 2005). Namun hingga sekarang penelitian mengenai pemanfaatan musuh alami SPKS belum dilakukan secara intensif dan diperlukan penelitian lanjutan Pembentukan Minyak Minyak terdapat pada daging buah (mesokarp) dan minyak inti/kernel (eudokarp), keduanya berasal setelah 100 hari penyerbukan dan berhenti setelah 180 hari setelah dalam buah minyak sudah jenuh. Proses pengolahan hasil minyak sawit didapatkan dengan memproses daging buah dan memecah tempurung inti (kernel) yang akan menghasilakn minyak inti (palm kernel oil).

Ameilia Zuliyanti Siregar : Kelapa Sawit : Minyak Nabati Berprospek Tinggi, 2006
USU Repository©2006
5
Seiring dengan meningkatnya mutu dengan rendemen yang tinggi maka proses pengolahannya harus memperhatikan tingkat efisiensi mesin pengolah yang tinggi dan mutu tandan buah segar serta kecepatan proses panen hingga pengolahan. Jika pembentukan minyak berakhir, terjadi pemecahan minyak (trigliserida) menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Hal ini ditandai dengan buah secara membrondol normal dari tandan. Proses biokimia pembentukan minyak pada buah secara alami disintesis satu molekul gliserol dengan tiga molekul asam lemak yang terbentuk dari kelanjutan oksidasi karbohidrat dalam proses respirasi. Proses pembentukan minyak dalam tanaman dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pembentukan gliserol, pembentukan asam lemak dan kondensasi asam lemak dengan gliserol yang akan membentuk lemak. Minyak/lemak dibentuk dalam sel hidup, merupakan hasil dari serangkaian reaksi yang kompleks dalam proses respirasi. Minyak pangan biasanya diekstrasi dalam keadaan tidak murni dan bercampur dengan komponen-komponen lain yang disebut fraksi lipida. Fraksi lipida terdiri dari minyak atau lemak (edible fat oil), malam (wax) dan karotenoid yang merupakan provitamin A. Terbentuknya minyak pangan setelah mengalami proses fraksinasi, vaksinasi dan higronisasi. Produk CPO difraksinasi akan menghasilkan fraksi cair olein (70%) dan fraksi padat stearin (30%) sebagai bahan baku untuk minyak makan yang digunakan dalam kemasan minyak goreng, margarine, butter, vanspati/shortening untuk pembuatan kue dan lain-lain. Manfaat Minyak Kelapa Sawit Secara alami, minyak sawit dijadikan obat karena kandungan karoten, penyimpan potensi sumber provitamin A (obat anti kanker dalam bentuk kapsul dan cair). Tokoferol merupakan sumber vitamin E yang cukup potensial untuk mengurangi kerusakan sel tubuh, antioksidan, asam lemak linoleat rendah denagn kemantapan, kalori yang tinggi dan tidak mudah teroksidasi. Minyak sawit merupakan bahan baku yang digunakan untuk industri kimia, mentega, sabun, lilin, dan terutama untuk produk minyak makan. Selain itu, digunakan untuk industri baja, kawat. radio, tekstil, bahan perekat, industri farmasi dan kosmetik. Minyak sawit tahan oksidasi dengan tekanan tinggi, mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, mempunayi daya melapis tinggi dan dapat menimbulkan iritasi dalam bidang kosmetika. Daftar Pustaka Hardon, J.J. 1976. Oil Palm breeding-introduction. In Oil Palm Research Edited by R H
V.Corley; J.J.Hardon and B.J.Wood. Elsevier Scientific Publishing Company: 89-108. Hartley, C.W.S. 1977. The oil palm. Longman, London and New York : i-xvii: 1-806. Hutauruk, Ch, Sipayung, A dan Soedharto, Ps. 1982. Elaeidobius kamerunicus F. Hasil uji
kekhususan inang dan peranannya sebagai penyerbuk kelapa sawit. Bull PPM. 3 (2): 7-21.

Ameilia Zuliyanti Siregar : Kelapa Sawit : Minyak Nabati Berprospek Tinggi, 2006
USU Repository©2006
6
Fauzi, Y, Y.E. Widyastuti, Iman S., dan Rudi Hartono 2006. Kelapa Sawit: Budidaya, Pemanfaatan Hasil dan Limbah, Analisis Usaha dan Pemasaran. Penebar Swadaya, Jakarta.
Kusnaedi. 2005. Pengendalian Hama Tanpa Pestisida. Penebar Swadaya, Jakarta. Lubis, A.U. dan Hutauruk, C.H. 1982. Serangga penyerbuk kelapa sawit, Elaeidobius
kamerunicus Fst di Semenanjung Malaysia dan Sabah (Laporan Kunjungan). Pusat Penelitian Marihat, Marihat Ulu-Pematang Siantar: 1-27.
Lubis, A.U. 1992. Kelapa Sawit (Elaeis guineensisi Jacq) di Indonesia. Pusat Penelitian Marihat,
Marihat Ulu-Pematang Siantar: 204-208. Mangoensoekarjo, S. dan Semangun, H. Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit. Gajah Mada
University Press, Yogyakarta. Poiner, G. O, Jackson, T.A, Bell, N. L. and Wahid, M.B. 2002. Elaeolenchus parthenomena
n.g.n.sp (Nematoda: Sphaerulanioidea: Anandramentidae n. Fam) parasitic in the palm ioil pollinating weevil E. kamerinicus Fraust; with a phylogenetic synopsis of the Sphaerularicidae Lubbock, 1861. Systematic Parasitology 52: 219-225
Sipayung, A. dan Soedharto Ps. 1982. Penelitian Laboratorium Serangga Penyerbuk Kelapa
Sawit Elaeidobius kamerunicus Fst di Pusat Penelitian Marihat, Marihat Ulu-Pematang Siantar.
Syed, R.A. 1981a. Pollinating Thrips of oil palm in West Malaysia. Planter. 52: 62-81. Syed, R.A. 1981b. Insect pollination of palm oil: feasibility of introducing “Oil Palm in
Agriculture in the Eighties”. Kuala Lumpur, Incorporated Society of Planters. Syed, R.A. 1982a. Insect pollination of oil palm: introduction, establishment and pollinating
eficiency of Elaeidobius kamerunicus in Malaysia. Commonwealth Institute of Biological Control (mimeo): 1-34.
Syed, R.A. 1982b. Insect pollination of oil palm. Di dalam Elaeidobius kamerunicus Fst di Pusat
Penelitian Marihat. Laporan Pertemuan Diskusi 4 Agustus 1982 di edit oleh Ir. Ch. Hutauruk. Pusat Penelitian Marihat, Marihat Ulu-Pem.Siantar: 1-37.