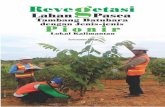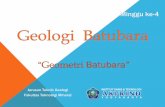Karakter Tanah Untuk Lahan Revegetasi Terminal Batubara
-
Upload
edho-aza-dah -
Category
Documents
-
view
539 -
download
0
Transcript of Karakter Tanah Untuk Lahan Revegetasi Terminal Batubara
KARAKTER TANAH UNTUK LAHAN REVEGETASI TERMINAL BATUBARA
OLEH : GUSTI IRMA MAULINA
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penambangan batubara di Kalimantan Selatan pada umumnya menyebabkan kerusakan dan perubahan lansekap lahan karena menggunakan sistem pertambangan terbuka. Untuk mengatasi dampak tersebut dilakukan kegiatan reklamasi yang diharapkan dapat memulihkan kondisi ekosistem mendekati seperti kondisi semula atau rona awalnya sehingga lahan bekas tambang dapat kembali produktif. Reklamasi adalah kegiatan pengelolaan tanah yang mencakup perbaikan kondisi fisik tanah overburden agar tidak terjadi longsor, pembuatan waduk untuk perbaikan kualitas air asam tambang yang beracun, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan revegetasi. Revegetasi sendiri bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, kimia dan biologis tanah tersebut dimana pada umumnya revegetasi ini menggunakan jenis-jenis tanaman cepat tumbuh yang adaptif pada kondisi yang sangat marjinal. Revegetasi areal tambang harus dilihat secara menyeluruh (holistik) karena yang diharapkan dari kegiatan ini adalah kelestarian fungsi dari lahan sesuai peruntukkannya. Wacana yang umum dikemukakan dalam usaha reklamasi ini adalah pembentukan kantong-kantong pelestarian vegetasi yang dilakukan sebelum kegiatan pertambangan berlangsung; pemantapan fase revegetasi yang meliputi penanaman prakondisi menggunakan jenis cepat tumbuh/pioner yang dilanjutkan dengan fase introduksi jenis-jenis klimaks; dan pengelolaan areal revegetasi untuk menjaga keberlangsungan prose suksesi dari ancaman seperti kebakaran hutan dan lahan. Reklamasi lahan ini juga diikuti dengan adanya rehabilitasi lahan dimana rehabilitasi ini dilakukan dengan cara penanaman kembali pepohonan atau penghijauan kawasan yang telah rusak akibat kegiatan penambangan tersebut. Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi, dapat dilakukan pula secara bersamaan sejauh dengan kemajuan aktifitas penambangan. Untuk bekas
tambang yang tidak dapat ditutup kembali, pemanfaatan dapat dilakukan dengan berbagai cara serta tetap memperhatikan aspek lingkungan, seperti untuk pemanfaatan sebagai kolam cadangan air, pengembangan ke sektor wisata air, pembudidayaan ikan serta pengembalian kondisi dan kualitas tanah dengan remediasi. Remediasi merupakan suatu teknik untuk mengembalikan kualitas tanah dari saat setelah tercemar menjadi saat sebelum tercemar dimana teknik ini hanya dilaksanakan setelah penanganan kontaminan pada sumbernya cukup memadai (kontaminasi kontaminan telah berhenti) untuk megurangi terlepasnya kontaminan ke lingkungan sehingga lingkungan (dalam hal ini tanah) dapat diremediasi secara efisien dan maksimal. Pelaksanaan remediasi tanah dan air tanah yang tercemar dapat dilakukan baik in -situ (on site) atau eks situ (off site). Pengolahan in-situ merupakan cara yang disarankan bila memungkinkan karena akan mengurangi resiko penyebaran pencemar dan menghemat biaya bila dibandingkan dengan pengolahan eks situ. Tentu saja hal ini tergantung kondisi lapangan dan fasilitas penunjang yang tersedia. Namun upaya perbaikan dengan cara ini masih dirasakan kurang efektif, hal ini karena tanaman (sebagai hasil dari revegetasi dan rehabilitasi) secara umum kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan ekstrim, termasuk bekas lahan tambang. Oleh karena itu aplikasi lain untuk memperbaiki lahan bekas tambang perlu dilakukan, salah satunya dengan mikroorganisme yang dikenal dengan nama teknik bioremediasi.
B. Peraturan Terkait Adapun peraturan peraturan terkait mengenai revegetasi lahan terminal batubara adalah sebagai berikut : Undang-Undang Republik Indonesia 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1967 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tentang
3) Undang-Undang Republik Indonesia Perindustrian.
Nomor
5 tahun 1984 tentang
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Penambangan Di Dalam Kawasan Hutan
Peraturan Pemerintah 1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Udara 7) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
8) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 9) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 10) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
Keputusan Presiden 1) Keputusan Presiden Nomor 66 tahun 1971 tentang Peningkatan Prasarana Pengusahaan Hutan 2) Keputusan Presiden Nomor 106 tahun 1999 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL).
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-
07/MENKLH/6/1987 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
TINJAUAN PUSTAKA
A. Sejarah Terciptanya Revegetasi/ Rehabilitasi Pertambangan merupakan kegiatan pembukaan lahan untuk
mengambil mineral yang terkandung dalam satu lahan. Dalam penambangan timah ada dua tipe metode yang dilakukan. Untuk didarat, tambang semprot atau tambang terbuka, sedangkan untuk penambangan dilaut menggunakan kapal keruk atau kapal hisap. Untuk penambangan didarat biasanya dilakukan dengan cara membuka vegetasi yang ada dipermukaan dan melakukan penggalian sampai pada lapisan mineral yang dituju, untuk kemudian dilakukan penambangan dengan cara disemprot atau terbuka (open pit). Pembukaan vegetasi dalam kegiatan penambangan menyebabkan perubahan komposisi ekosistem yang berada di areal pertambangan. Kegiatan ini tentunya menyebabkan terjadinya perubahan struktur sifat fisik dan kimia tanah. Bahkan limbah dari sisa kegiatan ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan disekitarnya. Karena hal itulah pemerintah membuat aturan untuk revegetasi kembali lahan pasca hasil tambang diambil. Apabila revegetasi ini dijalankan tanpa perencanaan yang matang dan lamban, maka akan menghasilkan kerugian dan bencana di kemudian hari misalnya adanya ancaman banjir ke daerah yang lebih rendah di sekitar lahan yang belum terevegetasi secara maksimal. B. Revegetasi dan Rehabilitasi Areal Bekas Pertambangan di Indonesia Pada prinsipnya kawasan atau sumberday alam yang dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan harus dikembalikan ke kondisi yang aman dan produktif melalui reklamasi/ rehabilitasi. Kondisi akhir reklamasi diarahkan untuk mencapai kondisi seperti sebelum ditambang atau kondisi lain yang telah disepakati. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus/berlanjut sepanjang umur pertambangan sampai pasca tambang. Tujuan jangka pendek reklamasi adalah membentuk bentang alam (landscape) yang stabil terhadap
erosi. Selain itu juga bertujuan untuk mengembalikan lokasi tambang ke kondisi yang memungkinkan untu digunakan sebagai lahan produktif. Bentuk lahan produktif yang akan dicapai menyesuaiakan dengan tataguna lahan pasca tambang. Penentuan tataguna lahan pasca tambang sangat tergantung pada berbagai faktor antara lain potensi ekologis lokasi tambang dan keinginan masyarakat serta pemerintah. Bekas lokasi tambang yang telah direklamasi harus dipertahankan agar tetap terintegrasi dengan ekosistem bentang alam sekitarnya. Lebih lanjut dijelaskan, untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan beberapa upaya seperti : rekonstruksi lahan dan manajemen top soil. Pada kegiatan ini, lahan yang masih belum rata harus terlebih dahulu ditata dengan penimbunan kembali (back filling) dengan memperhatikan jenis dan asal bahan urugan, ketebalan, dan ada tidaknya sistem aliran air (drainase) yang kemungkinan terganggu. Sebaiknya bahan-bahan galian dikembalikan keasalnya mendekati keadaan aslinya. Ketebalan penutupan tanah (sub-soil) disarankan berkisar 70-120 cm yang dilanjutkan dengan redistribusi top-soil. Untuk memperoleh kwalitas top-soil yang baik, maka pada saat pengerukan, penyimpanan dan re-distribusinya harus dilakukan pengawasan yang ketat. Realokasi top-soil pada lahan tanam bisa dilakukan secara lokal (per-lubang) atau disebarkan merata dengan kedalaman yang memadai. selain itu juga dilakukan revegetasi lahan kritis. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2008), menguraikan beberapa kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang, sebagai berikut: PT.Freeport Indonesia melakukan reklamasi dan suksesi alami pada area pengendapan pasir sisa tamban (sirsat). Sirsat mengapung bersama aliran sungai dan mengendap di daerah dataran rendah, dibantu dengan pembuatan tanggul. Di daerah dataran rendah inilah dilakukan suksesi dan reklamasi. Sirsat secara natural akan mencapa komunitas klimaks yang memberikan nilai ekologi dan nilai ekonomi. Saat ini sekitar 126 spesies berhasil ditanam dan
dibudidayakan pada lahan sirsat baik dengan maupun tanpa penambahan bahan organik. PT.Koba Ti menggunakan metode Pot System untuk mengatasi minimnya top soil pada rehabilitasi lahan bekas tambang. Metode Pot System dinilai efektif untuk mengatasi lahan bekas tambang yang miskin unsur hara. Prinsip-prinsip yang digunakan diantaranya pembuatan lubanglubang tanam; lubang-lubang tanam dikeringkan; penambahan top soil yang telah dicampur pupuk, kompos, dan mikroryza; dan penanaman. PT.Nusa Halmahera Minerals (PT.NHM) menggunakan metode enkapsulasi batuan potentially acid forming (PAF) di timbunan batuan pentutup tambang PT.NHM. PT. Newmont memilih metode suksesi progresif dimana ekosistem buatan manusia nantinya akan berkembang menjadi ekosistem alami. Secara umum, integrasi kegiatan penambangan dan reklamasi bertujuan mempercepat pemulihan lahan yang terganggu akibat kegiatan penambangan dan mengurangi luas lahan yang harus direklamasi pasca penambangan. Beberapa kegiatan reklamasi oleh perusahaan tambang batubara di Kalimantan Selatan; PT. Bahari Cakrawala Sebuku menggunakan pola suksesi alam dengan menanam land cover crop (LCC) dan beberapa tanaman berkayu. PT. Adaro Indonesia melakukan kegiatan revegetasi dengan melakukan ujicoba penanaman beberapa jenis tanaman cepat tumbuh seperti Acacia spp. dll. Namun upaya revegetasi ternyata juga harus menghadapi beberapa persoalan antara lain: lapisan tanahnya tipis, sehingga ruang perakaran sempit, kandungan unsur hara rendah, daya menahan air rendah, masam, dan kandungan logam-logam berat tinggi. Persoalan-persoalan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan tanaman revegetasi maupun kegagalan dalam usaha penanaman yang coba dilakukan. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman pada lahan bekas tambang, dapat ditentukan dari persentasi daya tumbuhnya, persentasi penutupan tajuknya, pertumbuhannya, perkembangan akarnya,
penambahan spesies pada lahan tersebut, peningkatan humus, pengurangan erosi, dan fungsi sebagai filter alam. Evaluasi terhadap tanaman revegetasi di Sepapah, Kalimantan Selatan menunjukkan 48-61% tanaman terjadi percabangan rendah. Hal tersebut menunjukkan kondisi tanah yang marjinal. Tetapi pada sisi lain ditemukan tumbuhan bawah sebagai indikator masuknya tumbuhan pioner, seperti: kerinyu (Chromolaena odorata), karamunting (Melastoma affine) dan tumbuhan berkayu mahang (Macaranga sp.). Tanaman revegetasi yang ditanam telah diketahui dapat mendukung proses suksesi alami di sekitarnya. Pemantauan tanaman pada lahan tambang selanjutnya dilaksanakan untuk memberikan informasi dan umpan-balik. Suksesi secara alami memiliki tahap-tahap tertentu, yang terjadi secara perlahan-lahan dan biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Penerapan kaedah suksesi menciptakan keseimbangan antara intervensi manusia dengan usaha ekosistem untuk mendesain lingkungannya sendiri (self design). Self design ini memberikan keuntungan dalam hal memberikan daya tahan hidup pada kondisi awal terjadinya suksesi, pemantapan kondisi hutan setelah fase awal suksesi, dan memerlukan sedikit biaya. Pada kegiatan revegetasi lahan bekas tambang ini, fenomena alam tersebut akan dicoba untuk dimodifikasi supaya tahapan suksesi (nudation, migrasi, ecesis, agregation, evolution of community relationship, invation, reaction, stabilization, dan klimaks) dapat berlangsung dengan cepat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menanam jenis tanaman tertentu secara beruruta seperti halnya yang terjadi pada fase-fase dari suksesi alami. Dalam kegiatan reklamasi areal bekas tambang, prinsip-prinsip dan pengetahuan ekologi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, seperti pengetahuan tentang spesies, komunitas dan ekosistem, ekotype, substitusi spesies, interaksi antar individu, spesies dan ekosistem, serta suksesi (Rahmawaty, 2002). Pemilihan jenis adalah tahap yang paling penting dalam upaya revegetasi lahan bekas tambang. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih spesies tanaman yang disesuaikan dengan kondisi lahan tersebut. Pemilihan jenis pohon yang akan ditanam didasarkan pada
adaptabilitas, cepat tumbuh, diketahui teknik silvikultur, ketersediaan bahan tanam, dan dapat bersimbiosis dengan mikoriza. Adapun peraturan terkait secara spesifik mengenai kegiatan reklamasi dan rehabilitasi ini adalah :y
UU
No.
11/1967,
tentang
Ketentuan-Ketentuan
Pokok
Pertambangany
PP No. 32/1969, tentang Pelaksanaan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
y y
PP No. 75/2001, tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32/1969 Kepmen PE No. 1211.K/1995, tentang Pecegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Umum
y
Kep Dirjen PU No. 336/1996, tentang Jaminan Reklamasi
Dimana pokok-pokok permasalahan reklamasi/ rehabilitasi dibahas pada UU No. 11/1967 pada:y
Pasal
30
yang
berbunyi
Apabila
selesai
melakukan
penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang KP diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya.y
Pasal 46 ayat (4) yang berbunyi Sebelum meninggalkan bekas wilayah KP-nya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang KP harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun
bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.y
Pasal 46 ayat (5) yang berbunyi Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang KP sebelum meninggalkan bekas wilayah KP.
C. Dasar Teori a. Tanah Tanah (bahasa Yunani: pedon; bahasa Latin: solum) adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbu h. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Ilmu yang mempelajari berbagai aspek mengenai tanah dikenal sebagai ilmu tanah. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi, meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi. Komposisi tanah berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi yang lain. Air dan udara merupakan bagian dari tanah. Tubuh tanah (solum) tidak lain adalah batuan yang melapuk dan mengalami proses pembentukan lanjutan. Usia tanah yang ditemukan saat ini tidak ada yang lebih tua daripada periode Tersier dan kebanyakan terbentuk dari masa Pleistosen. Tubuh tanah terbentuk dari campuran bahan organik dan mineral. Tanah non-organik atau tanah mineral terbentuk dari batuan sehingga ia mengandung mineral. Sebaliknya, tanah organik (organosol/humosol) terbentuk dari pemadatan terhadap bahan organik yang terdegradasi. Tanah organik berwarna hitam dan merupakan pembentuk utama lahan gambut dan kelak dapat menjadi batu bara. Tanah organik cenderung memiliki keasaman tinggi karena mengandung beberapa asam organik (substansi humik) hasil dekomposisi berbagai bahan organik. Kelompok tanah ini biasanya miskin mineral, pasokan mineral berasal dari aliran air atau hasil dekomposisi jaringan makhluk hidup. Tanah
organik dapat ditanami karena memiliki sifat fisik gembur (sarang) sehingga mampu menyimpan cukup air namun karena memiliki keasaman tinggi sebagian besar tanaman pangan akan memberikan hasil terbatas dan di bawah capaian optimum. Tanah non-organik didominasi oleh mineral. Mineral ini membentuk partikel pembentuk tanah. Tekstur tanah demikian
ditentukan oleh komposisi tiga partikel pembentuk tanah: pasir, lanau (debu), dan lempung. Tanah pasiran didominasi oleh pasir, tanah lempungan didominasi oleh lempung. Tanah dengan komposisi pasir, lanau, dan lempung yang seimbang dikenal sebagai geluh (loam). Warna tanah merupakan ciri utama yang paling mudah diingat orang. Warna tanah sangat bervariasi, mulai dari hitam kelam, coklat, merah bata, jingga, kuning, hingga putih. Selain itu, tanah dapat memiliki lapisan-lapisan dengan perbedaan warna yang kontras sebagai akibat proses kimia (pengasaman) atau pencucian (leaching). Tanah berwarna hitam atau gelap seringkali menandakan kehadiran bahan organik yang tinggi, baik karena pelapukan vegetasi maupun proses pengendapan di rawa-rawa. Warna gelap juga dapat disebabkan oleh kehadiran mangan, belerang, dan nitrogen. Warna tanah kemerahan atau kekuningan biasanya disebabkan kandungan besi teroksidasi yang tinggi; warna yang berbeda terjadi karena pengaruh kondisi proses kimia pembentukannya. Suasana aerobik/oksidatif menghasilkan warna yang seragam atau perubahan warna bertahap, sedangkan suasana anaerobik/reduktif membawa pada pola warna yang bertotol-totol atau warna yang terkonsentrasi. Struktur tanah merupakan karakteristik fisik tanah yang terbentuk dari komposisi antara agregat (butir) tanah dan ruang antaragregat. Tanah tersusun dari tiga fasa: fasa padatan, fasa cair, dan fasa gas. Fasa cair dan gas mengisi ruang antaragregat. Struktur tanah tergantung dari imbangan ketiga faktor penyusun ini. Ruang antaragregat disebut sebagai porus (jamak pori). Struktur tanah baik bagi perakaran apabila pori berukuran besar (makropori) terisi udara dan pori berukuran kecil (mikropori) terisi
air. Tanah yang gembur (sarang) memiliki agregat yang cukup besar dengan makropori dan mikropori yang seimbang. Tanah menjadi semakin liat apabila berlebihan lempung sehingga kekurangan
makropori. Berikut ini penjelasan lebih detil dari sifat-sifat tanah baik secara fisika, kimia maupun biologi: 1. Sifat Fisika Tanah Sifat fisik tanah antara lain adalah tekstur, permeabilitas, infiltrasi, perkoalisasi dan lainnya. Setiap jenis tanah memiliki sifat fisik tanah yang berbeda. Usaha untuk memperbaiki kesuburan tanah tidak hanya terhadap perbaikan sifat kimia dan biologi tanah tetapi juga perbaikan sifat fisik tanah. Perbaikan keadaan fisik tanah dapat dilakukan dengan pengolahan tanah, perbaikan struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Selain itu sifat fisik tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Kondisi fisik tanah menentukan penetrasi akar dalam tanah, retensi air, drainase, aerasi dan nutrisi tanaman. Sifat fisik tanah juga mempengaruhi sifat kimia dan biologi tanah. Tanah terdiri dari 3 komponen yakni padatan, cairan dan gas. Komponen padatan terdiri atas mineral anorganik dan bahan organik. Komponen cair (liquid) terdiri atas air, ion yang terlarut, molekul, gas yang secara kolektif disebut cairan tanah (soil solution). Komponen gas tanah seperti gas atmosfer di atas tanah tetapi berbeda proporsinya. Volume tanah = volume pori (air, gas) + volume padatan = konstan; untuk tanah yang tidak mengembang/swelling. Tanah berswelling tidak konstan tergantung dari kandungan airnya. Tanah ideal = 50% padatan dan 50% pori (45% bahan anorganik,5% organik) Pori = makro berisi udara atmosfer berisi air (air ditahan oleh gaya adhesi partikel tanah dengan air melawan gaya gravitasi).
Untuk analisis diperlukan berat tanah kering mutlak. Caranya dengan mengeringovenkan pada suhu 105C selama 48 jam yang dikenal dengan nama oven-dry-weight. Jumlah kalsium, potassium, bahan organik, air tanah dihitung berdasarkan oven-dry-weight.
2.
Sifat Kimia Tanah Tanah sebagai bagian dari tubuh alam mempunyai komposisi kimia berbeda-beda. Tanah terdiri atas berbagai macam unsur kimia. Penentu sifat kimia tanah antara lain kandungan bahan organik, unsur hara, dan pH tanah. Tanah yang kita lihat adalah suatu campuran dari material-material batuan yang telah lapuk (sebagai bahan anorganik), material organik, bentuk-bentuk kehidupan (jasad hidup tanah), udara, dan air. Bahan organik tanah terdiri atas sisasisa tanaman serta hewan dalam tanah, termasuk juga kotoran dan lendir-lendir serangga, cacing, serta binatang besar lainnya. Kandungan bahan organik dalam tanah memengaruh karakteristik i tanah. Pada tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi akan memberikan efek warna tanah cokelat hingga hitam. Sehingga sifat kimia tanah berupa kandungan bahan organik dapat dikenali dari warnanya. Selain itu, pengenalan ada tidaknya bahan organik secara kualitatif dapat dilakukan dengan cara menetesi contoh tanah dengan hydrogen peroxyde (H2O2 ) 10%. Jika tanah mengandung bahan organik, maka setelah ditetesi H2 O2 akan tampak adanya percikan atau gelembung-gelembung. Sifat kimia tanah yang lain, yaitu berupa derajat keasaman atau pH tanah. pH tanah dikatakan normal antara 6,5 sampai dengan 7,5. Pada keadaan ini, semua unsur hara pada larutan tanah dalam keadaan tersedia, seperti ketersediaan nitrogen serta unsur hara lainnya. Sifat Biologi Tanah Tanah sebagai tempat tumbuh tanaman dan tempat hidup organisme di dalamnya menyediakan unsur-unsur yang dibutuhkan
3.
oleh tanaman dan organisme lainnya. Di dalam tanah terjadi prosesproses yang menghasilkan sifat biologi tanah. Adapun sifat biologi yang dimiliki tanah adalah total mikroorganisme tanah, jumlah fungi tanah, jumlah bakteri pelarut fosfat (P) dan total respirasi tanah. Jumlah total mikroorganisme yang terdapat didalam tanah digunakan sebagai indeks kesuburan tanah (fertility indeks), tanpa mempertimbangkan hal-hal lain. Tanah yang subur mengandung sejumlah mikroorganisme, populasi yang tinggi ini menggambarkan adanya suplai makanan atau energi yang cukup ditambah lagi dengan temperatur yang sesuai, ketersediaan air yang cukup, kondisi ekologi lain yang mendukung perkembangan mikroorganisme pada tanah tersebut. Jumlah mikroorganisme sangat berguna dalam menentukan tempat organisme dalam hubungannya dengan sistem perakaran, sisa bahan organik dan kedalaman profil tanah. Data ini juga berguna dalam membandingkan keragaman iklim dan pengelolaan tanah terhadap aktifitas organisme didalam tanah. Fungi berperan dalam perubahan susunan tanah. Fungi tidak berklorofil sehingga mereka menggantungkan kebutuhan akan energi dan karbon dari bahan organik. Fungi dibedakan dalam tiga golongan yaitu ragi, kapang, dan jamur. Kapang dan jamur mempunyai arti penting bagi pertanian. Bila tidak karena fungi ini maka dekomposisi bahan organik dalam suasana masam tidak akan terjadi. Bakteri pelarut P pada umumnya dalam tanah ditemukan di sekitar perakaran yang jumlahnya berkisar 103 106 sel/g tanah. Bakteri ini dapat menghasilkan enzim Phosphatase maupun asam asam organik yang dapa melarutkan fosfat tanah maupun sumber fosfat yang diberikan. Fungsi bakteri tanah yaitu turut serta dalam semua perubahan bahan organik, memegang monopoli dalam reaksi enzimatik yaitu nitrifikasi dan pelarut fosfat. Jumlah bakteri dalam tanah bervariasi karena perkembangan mereka sangat bergantung dari keadaan tanah. Pada umumnya jumlah terbanyak dijumpai di
lapisan atas. Jumlah yang biasa dijumpai dalam tanah berkisar antara 3 4 milyar tiap gram tanah kering dan berubah dengan musim. Respirasi mikroorganisme tanah mencerminkan tingkat aktivitas mikroorganisme tanah. Pengukuran respirasi
(mikroorganisme) tanah merupakan cara yang pertama kali digunakan untuk menentukan tingkat aktifitas mikroorganisme tanah. Pengukuran respirasi telah mempunyai korelasi yang baik dengan parameter lain yang berkaitan dengan aktivitas
mikroorganisme tanah seperti bahan organik tanah, transformasi N, hasil antara, pH dan rata-rata jumlah mikroorganisrne
b. Teknik Revegetasi Revegetasi merupakan salah satu upaya reklamasi pada lahan bekas penambangan. Reklamasi harus sudah diperhitungkan dalam kegiatan pasca tambang, sehingga areal bekas penambangan tidak ditinggalkan begitu saja dan rusak. Sebelum kegiatan revegetasi dilakukan terlebih dahulu dilakukan penataan lahan agar siap untuk ditanami. Setelah lahan ditata kemudian dilakukan analisis terhadap sifatsifat fisik dan kimia tanah sehingga dapat diketahui tanaman yang cocok terhadap kondisi tanah yang ada. Perbaikan kondisi tanah meliputi perbaikan ruang tubuh, pemberian tanah pucuk dan bahan organik serta pemupukan dasar dan pemberian kapur. Kendala yang dijumpai dalam merestorasi lahan bekas tambang yaitu masalah fisik, kimia (nutrients dan toxicity), dan biologi. Masalah fisik tanah mencakup tekstur dan struktur tanah. Masalah kimia tanah berhubungan dengan reaksi tanah (pH), kekurangan unsur hara, dan mineral toxicity. Untuk mengatasi pH yang rendah dapat dilakukan dengan cara penambahan kapur. Sedangkan kendala biologi seperti tidak adanya penutupan vegetasi dan tidak adanya mikroorganisme potensial dapat diatasi dengan perbaikan kondisi tanah, pemilihan jenis pohon, dan pemanfaatan mikroriza.
Secara ekologi, spesies tanaman lokal dapat beradaptasi dengan iklim setempat tetapi tidak untuk kondisi tanah. Untuk itu diperlukan pemilihan spesies yang cocok dengan kondisi setempat, terutama untuk jenis-jenis yang cepat tumbuh, misalnya sengon, yang telah terbukti adaptif untuk tambang. Dengan dilakukannya penanaman sengon minimal dapat mengubah iklim mikro pada lahan bekas tambang tersebut. Untuk menunjang
keberhasilan dalam merestorasi lahan bekas tambang, maka dilakukan langkah-langkah seperti perbaikan lahan pra-tanam, pemilihan spesies yang cocok, dan penggunaan pupuk. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman pada lahan bekas tambang, dapat ditentukan dari persentasi daya tumbuhnya, persentasi penutupan tajuknya, pertumbuhannya,
perkembangan akarnya, penambahan spesies pada lahan tersebut, peningkatan humus, pengurangan erosi, dan fungsi sebagai filter alam. Dengan cara tersebut, maka dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam merestorasi lahan bekas tambang