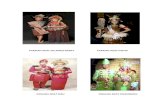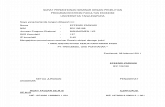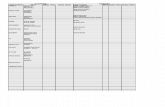KapukKkkkk
-
Upload
melika-sopiana-simbolon -
Category
Documents
-
view
20 -
download
3
description
Transcript of KapukKkkkk

1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Eksplorasi minyak bumi yang terus menerus menyebabkan cadangan
minyak akan habis, termasuk di Indonesia diperkirakan cadangan minyak bumi
akan habis 30 tahun mendatang sebagai akibat ketersediaan bahan bakar yang
terbatas dan sifatnya yang tidak dapat diperbaharui. Konsumsi terhadap bahan
bakar yang semakin banyak tersebut juga berdampak pada sektor lingkungan,
salah satunya adalah pemanasan global. Untuk itu, perlu dicari sumber energi
alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar diesel. Salah satu sumber energi
alternatif yang kini banyak dikembangkan adalah biodiesel (Asnawati, 2014).
Biodiesel diketahui sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan dan
dapat diperbarui. Biodiesel biasanya dibuat dengan transesterifikasi minyak
tumbuhan atau lemak hewan dengan methanol atau etanol (Susilowati, 2006).
Biodiesel merupakan campuran dari mono alkil ester asam lemak dari minyak
nabati atau lemak hewan. Minyak dan lemak merupakan trigliserida karena
minyak dan lemak membentuk ester dari tiga molekul asam lemak yang terikat
pada molekul gliserol. Minyak nabati yang lazim digunakan dalam produksi
biodiesel merupakan trigliserida yang mengandung asam oleat dan asam linoleat,
dan juga yang mengandung asam palmitat, asam stearat, dan asam oleat
(Muhammad, 2012).
Banyak tumbuhan yang ada di Indonesia yang biasa diolah menjadi
biodiesel. Namun baru beberapa tumbuhan yang sudah dimanfaatkan seperti
kelapa sawit, kelapa, dan jarak. Beberapa Negara telah memanfaatkan biodiesel
adalah Ghana (bahan baku kacang-kacangan), Amerika Serikat (biodiesel dari
minyak kedelai), Jerman (bahan baku kalona), serta Inggris dan Prancis (bahan
baku dari bunga matahari). Seharusnya Indonesia lebih maju dan berjaya
dibandingkan Negara lain karena Indonesia memiliki iklim, terutama sinar
matahari yang sangat mendukung pertumbuhan tanaman bahan baku green fuel.

2
Selain itu, banyak tumbuhan dapat diolah menjadi bahan bakar hayati
(Prihandana, 2006).
Proses produksi biodiesel umumnya dilakukan melalui dua tahap yaitu
tahap ekstraksi minyak dari bahan baku dan tahap transesterifikasi minyak
biodiesel. Ekstraksi minyak nabati umumnya dilakukan secara mekanik
menggunakan expeller atau hydraulic press yang kemudian diikuti oleh ekstraksi
n-heksana. Adapun transesterifikasi minyak nabati menjadi biodiesel umumnya
dilakukan melalui proses transformasi kimia dengan menggunakan pereaksi
metanol atau etanol dan katalisator asam atau basa. Kedua tahapan tersebut
dilakukan secara terpisah dan diskontinyu, sehingga proses produksi biodiesel
menjadi kurang efisien dan mengkonsumsi banyak energi. Selain itu, proses
produksi minyak dari biji membebani 70 % dari total biaya proses produksi
biodiesel (Kartika, 2009).
Kandungan minyak randu atau kapuk tidak terlalu besar, hanya 18-25 %
dari berat biji atau sekitar 40 % berat daging biji. Minyak tersebut memilki
kerapatan 0,917 kg/liter dengan bilangan iodin 88. Selain itu, minyak kapuk
mengandung asam lemak tak jenuh sekitar 71,95 % lebih tinggi daripada minyak
kelapa. Hal itu menyebabkan minyak kapuk mudah tengik sehingga kurang bagus
untuk minyak makan. Namun, minyak kapuk merupakan salah satu pembuat
bahan margarine (Prihandana, 2007).
Penelitian Santoso (2012), pada Sintesis Biodiesel Dari Minyak Biji
Kapuk Dengan Katalis Zeolit Sekam Padi diperoleh kadar metil ester tertinggi
dihasilkan pada kondisi rasio mol minyak terhadap metanol 1:15, temperatur
reaksi 60˚C, dan waktu reaksi 1 jam, yaitu sebesar 88,576 %. Hasil karakterisasi
GC-MS diperoleh 3 jenis senyawa metil ester yang terbentuk, yaitu metil ester
palmitat, metil ester linoleat dan metil ester oleat. Hasil GC diperoleh rendemen
metil ester (biodiesel) sebesar 21,94%. Pada penelitian Suryandari (2013),
Pembuatan Biodiesel dari Minyak Biji Kapuk (Ceiba Pentandra) Melalui Proses
Transesterifikasi dengan Katalis MgO/CaO diperoleh Yield biodiesel tertinggi
sebesar 55,22% pada kondisi operasi suhu 70oC dan waktu reaksi 75 menit.

3
Sedangkan penelitian Salamah (2014), Reaksi transesterifikasi pada kondisi
perbandingan mol minyak dan metanol 1:3, dengan kecepatan putaran pengaduk
600 rpm selama 105 menit dan suhu reaksi 90 0 C memberikan konversi tertinggi
sebesar 0,916 mol (%). Kondisi optimum yang diperoleh yaitu dengan
penggunaan enzim 0,1 gr (96,66%), waktu reaksi 10 jam (97%), perbandingan
methanol dan minyak yaitu 3:1 (93,33%) dan suhu reaksi 40 oC (93,33%)
(Asnawati, 2014). Minyak biodisel kapuk randu diperoleh dari minyak kapuk
randu yang direaksikan dengan methanol serta katalis NaOH yang menghasilkan
metil ester (biodiesel) dan gliserin. Temperatur reaksi diatur 50 oC–55 oC.
Konversi biodiesel kapuk randu akan optimum pada komposisi 80 % minyak
kapuk randu, 20 % metanol dan 2 gram NaOH tiap 100 ml metanol (Darmanto,
2010).
Sebagian besar industri biodiesel saat ini menggunakan metode
transesterifikasi-basa konvensional dalam produksi biodiesel, yaitu reaksi bahan
baku dalam bentuk minyak/lemak (trigliserida) dengan alkohol (metanol atau
etanol) menjadi senyawa ester biodiesel (metil ester atau etil ester) menggunakan
katalis basa. Minyak nabati hasil pemurnian dan lemak hewan berkualitas tinggi
sangat cocok jika ditransesterikasi dengan metode ini dan menghasilkan biodiesel
berkualitas baik dengan efisiensi kimiawi yang tinggi. Namun, upaya untuk
mendapatkan dan mempertahankan kandungan minyak yang tinggi menyebabkan
harga bahan baku menjadi mahal. Hal ini berbeda dengan metode transesterifikasi
insitu. Metode transesterifikasi insitu adalah proses transesterifikasi yang
didasarkan pada kemampuan reagen (seperti alkohol) berpenetrasi secara
langsung ke dalam bahan baku untuk bereaksi dengan gliserida (Hass, 2004b).
Selain itu, metode proses transesterifikasi insitu merupakan metode dimana proses
ekstraksi ditiadakan. Pada reaksi transesterifikasi insitu proses ekstraksi minyak
dan reaksi transesterifikasi minyak menjadi biodiesel terjadi secara simultan
dalam satu kali proses (Kartika, 2009).
Saat ini, beberapa studi telah dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi
metode transesterifikasi insitu dengan katalis basa pada berbagai bahan baku.

4
Produksi senyawa ester asam lemak sederhana dihasilkan dari transesterifikasi
insitu flake kedelai menggunakan katalis natrium hidroksida pada suhu 60 °C
(Haas, 2004b). Pengeringan flake kedelai sebelum transesterikasi insitu dapat
mengurangi kebutuhan metanol dan natrium hidroksida sebesar 55–60 %,
sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi (Haas, 2004a). Sedangkan Kartika
(2009), melakukan transesterifikasi insitu minyak biji jarak pagar pada suhu
reaksi 60 oC, waktu reaksi 240 menit dan kecepatan pengadukan 800 rpm.
Rendemen biodiesel tertinggi (71%) didapatkan pada kadar air 0,5% dan ukuran
partikel bahan 35 mesh. Biodiesel yang dihasilkan mempunyai bilangan asam
0,27 mg KOH/gr dan viskositas < 3,5 cSt, serta memenuhi Standar Biodiesel
Indonesia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Daryono (2013), Biodiesel dari
minyak biji pepaya dengan Transesterifikasi insitu menggunakan variasi metanol
yaitu (200, 300 dan 400 mL) dan waktu proses transesterifikasi insitu (30, 60, 90,
120 dan 150 menit). Pada penelitian ini didapat konsentrasi metil ester 77,68%
pada suhu reaksi 60 oC, waktu reaksi 120 menit, kecepatan pengadukan 600 rpm
dan ratio bahan:methanol= 20 g : 400 ml.
Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang telah ada, maka
peneliti termotivasi melakukan penelitian ini dengan judul “Sintesis Biodiesel
dari Minyak Biji Kapuk Randu Dengan Reaksi Transesterifikasi Insitu”.
Peneliti mensintesis minyak biji kapuk randu menjadi biodiesel dengan reaksi
transesterifikasi menggunakan katalis NaOH dalam metanol. Pada penelitian
menggunakan volume metanol sebanyak 400 mL dan waktu 90 dan 120 menit.
Suhu reaksi yaitu 60 0C dan kecepatan pengadukan yaitu 600 rpm. Kemudian
metil ester (biodiesel) dianalisis dengan menggunakan Gas Kromatografi (GC).
dan melakukan parameter uji fisika dan kimia seperti densitas dan kadar asam
lemak bebas.
1.2 Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Memperoleh biodiesel dari biji kapuk randu dengan cara
transesterifikasi insitu dengan katalis NaOH dalam metanol.

5
2. Melakukan parameter uji fisik dan kimia biodiesel biji kapuk randu
yaitu densitas dan kadar asam lemak bebas.
3. Menganalisis komponen biodiesel biji kapuk randu dengan
menggunakan alat kromatografi gas (GC).
4. Mengetahui randemen metil ester (biodiesel) yang diperoleh pada lama
reaksi transesterifikasi 90 dan 120 menit.
1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian diatas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penggunaan metode transesterifikasi insitu dengan katalis
NaOH dalam metanol untuk membuat biodiesel dari biji kapuk randu?
2. Apakah yield biodiesel dari biji kapuk randu cukup memenuhi nilai
parameter uji fisik dan kimia (densitas dan asam lemak bebas) standar
syarat mutu biodiesel?
3. Apa saja hasil identifikasi jenis asam lemak dari minyak biji kapuk
randu dengan kromatografi gas (GC)?
4. Berapa randemen metil ester (biodiesel) hasil reaksi transesterifikasi
selama 90 dan 120 menit?
1.4 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui penggunaan metode transesterifikasi insitu dengan katalis
NaOH dalam metanol untuk membuat Biodisel dari biji kapuk randu.
2. Menentukan komposisi asam lemak dari biji kapuk randu sebagai dasar
penafsiran nilai-nilai parameter standar syarat mutu biodiesel.
3. Mengidentifikasi komposisi metil ester biji kapuk randu dengan gas
kromatografi (GC).
4. Mengatahui randemen metil ester (biodiesel) hasil transesterifikasi selama
90 dan 120 menit.

6
1.5 Manfaat Penelitian
Setelah penelitian ini dilakukan maka diharapkan memberi manfaat
sebagai berikut:
1. Sebagai informasi kepada pembaca tentang proses produksi biodiesel
secara langsung dari biji kapuk randu melalui proses transesterifikasi
insitu.
2. Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti dalam mengembangkan pengetahuan
dan pengalaman ilmiah dalam penelitian.
3. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memecahkan
masalah proses produksi minyak dari biji papaya mengkonsumsi banyak
energi dan biaya.

7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kapuk Randu
Kapuk randu atau kapuk (Ceiba pentandra) adalah pohon tropis
yang tergolong ordo Malvales dan famili Malvaceae (sebelumnya dikelompokkan
ke dalam famili terpisah Bombacaceae), berasal dari bagian utara dari Amerika
Selatan, Amerika Tengah dan Karibia, dan (untuk varitas C. pentandra var.
guineensis) berasal dari sebelah barat Afrika. Kata "kapuk" atau "kapok" juga
digunakan untuk menyebut serat yang dihasilkan dari bijinya. Pohon ini juga
dikenal sebagai kapas Jawa atau kapok Jawa, atau pohon kapas-sutra. Juga
disebut sebagai Ceiba, nama genusnya, yang merupakan simbol suci dalam
mitologi bangsa Maya. Asal dan penyebaran geografi Kapuk adalah Amerika
Tropik. Dari sana meyebar ke Afrika, sepanjang pantai barat dari Senegal ke
Angola. Tanaman ini dibawa dari Afrika ke Asia untuk dibudidayakan. Kapuk
terlukis di relief Jawa sejak 1000 Setelah Masehi. Kini, tanaman ini
dibudidayakan di seluruh daerah tropik, terutama di Asia Tenggara, termasuk
Indonesia dan Thailand.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Kapuk_randu)
Klasifikasi tumbuhan kapuk randu atau kapuk yaitu:
Kingdom: Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)
Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)
Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)
Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)
Sub Kelas: Dilleniidae
Ordo: Malvales
Famili: Bombacaceae

8
Genus: Ceiba
Spesies: Ceiba pentandra L. Gaertn
(http://www.plantamor.com/index.php?plant=301)
Gambar 2.1 Biji Kapok yang berisi serat di dalamnya
Pohon ini tumbuh hingga setinggi 8-70 m dan dapat memiliki batang
pohon yang cukup besar hingga mencapai diameter 3 m. Pohon ini banyak
ditanam di Asia, terutama di pulau Jawa, Malaysia, Filipina, dan Amerika Selatan.
Di Bogor terdapat jalan yang di sepanjang tepinya dinaungi pohon kapuk. Pada
saat buahnya merekah suasana di jalanan menyerupai hujan salju karena serat
kapuk yang putih beterbangan di udara. (Setiadi, 1983)
Kapok tumbuh bagus pada ketinggian di bawah 500 m. Temperatur malam
hari di bawah 17°C. Untuk hasil bagus, tumbuh baik pada 20°N dan 20°S. Kapok
menyukai curah hujan yang melimpah selama periode vegetatatif dan lebih kering
pada periode berbunga dan berbuah. Curah hujan sebaiknya sekitar 1500 mm per
tahun. Periode kering tidak lebih dari 4 bulan dengan curah hujan kurang dari 100
mm per bulan, dan dalam periode ini, total curah hujan 150-300 mm. Di daerah
yang lebih kering, persediaan air terdapat di dalam tanah. Di delta Mekong
(Vietnam), dimana curah hujan tidak mencukupi, kapok tumbuh bagus di
sepanjang sungai. Untuk hasil yang bagus, tanaman ini sebaiknya ditanam di
tanah yang bagus, di Indonesia ditanam di tanah lempung vulkanik. Pohon ini

9
mudah rusak oleh angin yang kuat. di Indonesia, daerah datar di sepanjang sisi
jalan dan sungai dipilih untuk penanaman tanaman ini, selama lokasi tersebut
cukup sinar matahari dan pengairan..
2.1.1 Manfaat dan Kegunaan tumbuhan
Berikut merupakan manfaat dan kegunaan tumbuhan kapuk randu
(Ceiba pentandra):
1) Buah Ceiba pentandra merupakan sumber serat, digunakan untuk bahan dasar
matras, bantal, hiasan dinding, pakaian pelindung dan penahan panas dan
suara.
2) Tali pinggang untuk menolong orang yang tenggelam ("lifebelts") dan jaket
penolong ("life-jackets") dibuat dari serat kapuk, tetapi hanya efektif ketika
tidak ada minyak didalam air. Selama Perang Dunia Kedua banyak orang
tenggelam karena jaket penolong mereka kehilangan daya mengapungnya;
sekarang digunakan bahan sintetik.
3) Di Jawa, plasenta dihancurkan untuk memproduksi serat kapuk kualitas
sekunder untuk membuat matras yang lebih murah dan sebagai penyerap air
laut yang terkontaminasi minyak.
4) Bahan plasenta juga digunakan untuk mengkultur jamur. Kulit buah sebagai
pengganti bahan kertas untuk pembuatan kertas di Jawa.; Kulit kaya akan
potasium dan abu yang dapat digunakan sebagai pupuk. Mereka juga
digunakan untuk membuat baking soda dan sabun.
5) Kulit kering digunakan sebagai bahan bakar. Biji mengandung minyak yang
digunakan dalam industri sabun sebagai pelumas dan minyak lampu, oleh
sebab itu dapat dipakai sebagai bahan baku energi.
6) Minyak juga digunakan untuk campuran minyak goreng, tetapi tidak
disarankan untuk alasan kesehatan. Residu pembuatan kue digunakan sebagai
makanan binatang. Di Indonesia dan Malaysia biji dimakan, tetapi hanya
dalam jumlah sedikit karena akan mengganggu pencernaan.

10
7) Daun muda dimakan sebagai sayuran di Filipina, bunga dan buah muda
dimakan di Thailand, dan polong yang masih sangat muda dimakan di Jawa.
8) Daun digunakan sebagai makanan ternak dan untuk memperbaiki tanah.
9) Kayunya digunakan untuk pembuatan kertas, pintu, furniture, kotak dan
mainan.
10) Bunganya merupakan sumber madu yang bagus.
11) Di banyak lokasi, kapuk ditanam untuk reforestasi, konservasi air dan untuk
mensupply kayu bakar juga untuk pembuatan pagar.
(https://www.google.com/search?biw=1024&bih=461&q=tanaman+kapuk+randu)
Tumbuhan randu merupakan salah satu tanaman yang dimanfaatkan
dibidang pengobatan antara lain: minyak dari biji untuk obat kudis dan membantu
pertumbuhan rambut, sari daun yang masih muda dipergunakan untuk membantu
pertumbuhan rambut dengan cara digosokkan pada kulit kepala kemudian dipijit-
pijit. Infus daun digunakan untuk batuk, radang selaput lendir pada hidung, suara
serak, usus dan uretritis. Daun muda diberikan untuk mengobati gonore. Kulit
digunakan sebagai obat untuk mengatasi muntah, diuretik, demam dan diare.
Rebusan bunga digunakan untuk mengatasi sembelit. Memanfaatkan daun randu
atau kapuk sebagai obat herbal merupakan alternatif dari penggunaan obat-obatan
pada umumnya. Kandungan kimia pada daun randu (Ceiba pentandra L.) terdiri
dari polifenol, saponin, damar yang pahit, hidrat arang, flavonoid dan minyak
dalam bijinya.Dari kandungan ini dapat dimanfaatkan sebagai indikator obat
penurun panas. (Suhermanema.blogspot.com/2014/09/pemanfaatan-daun-randu-
atau-kapuk-ceiba.html)
2.1.1 Karakteristik Biji Durian
Biji durian berbentuk bulat telur, berkeping dua, berwarna putih
kekuning-kuningan atau coklat muda seperti terlihat pada Gambar 1. Kandungan
patinya cukup tinggi, sehingga berpotensi sebagai alternatif pengganti bahan
makanan. Di Indonesia biji durian memang belum memasyarakat untuk digunakan

11
sebagai bahan makanan. Di Thailand biji durian biasa diolah menjadi bubur
dengan diberi campuran daging buahnya. Bubur biji durian ini menghasilkan
kalori yang cukup potensial bagi manusia. Biasanya biji durian dapat dikonsumsi
setelah direbus atau dibakar, bahkan saat ini biji durian dibuat tepung yang bisa
digunakan sebagai bahan baku wajik dan berbagai produk yang lainnya
(Rukmana, 1996).
Gambar 1. Biji durian (basah)
Tanaman durian adalah tanaman tahunan. Bila ditanam melalui biji,
tanaman ini akan mulai berbunga untuk pertama kali sepuluh tahun setelah tanam.
Namun, tanaman ini akan menghasilkan buah yang lezat dan memiliki banyak
manfaat. Selain buahnya, biji durian dapat dimanfaatkan sebagai bioetanol. Biji
merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena di dalam biji terdapat calon
tumbuhan baru. Biji durian terdiri dari beberapa bagian yaitu kulit biji, tali biji,
dan inti biji (Aak, 1997:27).
2.1.2 Komposisi Biji Durian
Biji durian yang sering dianggap limbah tidak dimanfaatkan untuk
sesuatu yang lebih besar manfaatnya seperti untuk pembuatan biodiesel ini.
Kandungan nutrisi dalam 100 gram biji durian seperti yang dikutip dari Michael J.

12
Brown, Durio–A Bibliographic Review, 1997, ditunjukkan dalam tabel di bawah
iniBerikut adalah tabel komposisi biji durian dalam buku Michael J. Brown
(1997:157).
Tabel 2.1 Komposisi Biji Durian
ZatPer 100 gram biji segar
(mentah) tanpa kulitnya
Per 100 gram biji telah
dimasak tanpa kulitnya
Kadar air 51,5 gram 51,5 gram
Lemak 0,4 gram 0,2-0,23 gram
Protein 2,6 gram 1,5 gram
Karbohidrat total 47,6 gram 48,2 gram
Serat kasar - 0,7 gram-0,71 gram
Nitrogen - 0,297 gram
Abu 1,9 gram 1,0 gram
Kalsium 17 miligram 3,9-88,8 miligram
Fosfor 68 miligram 86,65-87 miligram
Besi 1,0 miligram 0,6-0,64 gram
Natrium 3 miligram -
Kalium 962 miligram -
Beta karoten 250 𝞵gram -
Riboflavin 0,05 miligram 0,05-0,052 miligram
Thiamin - 0,03-0,032 miligram
Niacin 0,9 miligram 0,89-0,9 miligram
Dari tabel dapat dilihat bahwa kandungan lemak pada biji durian
sebanyak 0,4 gram per 100 gram biji segar, sedangkan bila dimasak menjadi 0,2-
0,23 gram.
Hasil penelitian yang dilakukan Eni Susilo Rahayu (2001), minyak biji
durian diperoleh komposisi asam lemak dan diuji parameter fisika dan kimianya
antara lain warna, bilangan-bilangan: asam, penyabunan, iodin, peroksida dan

13
komposisi asam lemak diuji dengan kromatografi gas. Berikut tabel komposisi
asam lemak dan sifat kimia-fisika biji durian.
Tabel 2.2. Komposisi Asam Lemak Dari Minyak Biji Durian
Jenis Asam Lemak %
Asam stearat 45,85
Asam palmitat 26,75
Asam oleat 14,95
Linoleat 12,45
(Enni, 2001)
Beberapa sifat kimia dan fisika minyak biji durian dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.3. Sifat Kimia dan Fisika Minyak Biji Durian
Parameter Nilai (%)
Bilangan Asam 19,4 ± 0,17
Bilangan Penyabunan 190,65 ± 0,84
Bilangan Iodium 81,7 ± 0,53
Bilangan Peroksida 3,93 ± 0,12
(Enni, 2001)
2.1.3 Manfaat Tanaman Durian
Manfaat tanaman durian selain buahnya sebagai makanan buah segar
dan olahan lainnya, juga terdapat manfaat dari bagian lainnya (AAK, 1997), yaitu:
1. Tanamannya sebagai pencegah erosi di lahan-lahan yang miring.
2. Batangnya untuk bahan bangunan/perkakas rumah tangga. Kayu durian
setaraf dengan kayu sengon sebab kayunya cenderung lurus.
3. Bijinya yang memiliki kandungan pati cukup tinggi, berpotensi sebagai
alternatif pengganti makanan.
4. Kulit dipakai sebagai bahan abu gosok yang bagus, dengan cara dijemur
sampai kering dan dibakar sampai hancur, dapat juga digunakan untuk

14
campuran media tanaman di dalam pot, serta sebagai campuran bahan
baku papan olahan serta produk lainnya.
5. Bunga dan buah mentahnya dapat dijadikan makanan, antara lain dibuat
sayur.
2.1.4 Pengolahan Minyak Biji Durian Menggunakan Pengepresan
Hidroulik (Hidroulic Pressing)
Ekstraksi adalah suatu cara untuk mendapatkan minyak atau lemak dari
bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak. Adapun cara ekstraksi ini
bermacam-macam yiatu rendering (dry rendering dan wet rendering), mechanical
expression dan solvent extraction.
Pengepresan mekanis merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak,
terutama untuk bahan yang berasal dari biji-bijian. Cara ini dilakukan untuk
memisahkan minyak dari bahan yang berkadar minyak tinggi. Pada pengepresan
mekanis ini diperlukan perlakukan pendahuluan sebelum minyak atau lemak
dipisahkan dari bijinya. Perlakukan pendahuluan tersebut mencakup pembuatan
serpih, perajangan dan penggilingan serta pemanasan.
Pada cara hydraulic pressing, bahan dipres dengan tekanan sekitar 2000
pound/inch2 (140,6 kg/cm = 136 atm). Banyaknya minyak atau lemak yang dapat
diektraksi tergantung dari lamanya pengepresan, tekanan yang dipergunakan, serta
kandungan minyak dalam bahan asal. Sedangkan banyaknya minyak yang tersisa
pada bungkil bervariasi sekitar 4 sampai 6 persen, tergantung dari lamanya
bungkil ditekan di bawah tekanan hidraulik (Ketaren, 1986).
2.2 Biodiesel
Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif berbahan baku minyak
nabati. Biodiesel dapat digunakan secara murni maupun dicampur dengan
petrodiesel (Irene, 2008). Secara kimia biodiesel termasuk dalam golongan
monoalkil ester dengan panjang rantai karbon antara 18-20 yang mengandung
oksigen. Hal ini yang membedakannya dengan petroleum diesel yang komponen
utamanya terdiri hanya hidrokarbon tanpa oksigen.

15
Biodiesel mempunyai sifat kimia dan fisika yang serupa dengan
petroleum diesel sehingga dapat digunakan langsung untuk mesin diesel atau
dicampur dengan petroleum diesel. Walaupun kandungan kalori biodiesel serupa
dengan petroleum diesel, tetapi karena biodiesel mengandung oksigen, flash
pointnya (titik nyala) lebih tinggi sehingga tidak mudah terbakar. Disamping itu,
biodiesel tidak mengandung sulfur dan senyawa bensin yang karsigonik sehingga
biodiesel merupakan bahan bakar yang bersih dan lebih mudah ditangani daripada
petroleum diesel.
Penggunaan minyak nabati sebagai bahan bakar telah dikenal sejak
awal penciptaan mesin diesel. Pada tahun 1911, Rudolph Diesel membuat mesin
dengan cara kerja berdasarkan berdasarkan pengapian-bertekanan (mesin desel).
Pada saat itu tidak ada mesin khusus menjalankan mesin ini dan
menggerakkannya ia menggunakan minyak kacang tanah. Rudolph Disel
menyebutkan bahwa mesin disel dapat menggerakkan oleh minyak nabati.
Pengalaman Rudolph diesel telah mengilhami beberapa beberapa Negara maju di
Eropa untuk mengkonversi minyak nabati menjadi bentuk bionergi guna
menggerakkan kendaraan bermotor. Dewasa ini diperkirakan 100.000 lebih
kendaraan menggunakan biodiesel di beberapa Negara Eropa, misalnya jerman
dimana bioenergi telah menjadi energi masa depan.
Bahan bakar diesel relatif mudah terbakar sendiri (tanpa harus dipicu
dengan letikan api busi) jika disemprotkan kedalam udara panas bertekanan udara
panas. SNI telah menetapkan titik nyala biodiesel lebih tinggi dibanding dengan
minyak solar fosil ataupun biosolar. Dimana titik nyala adalah apabila suatu
minyak dipanaskan sampai mulai menguap membentuk gas. Gas tersebut menyala
apabila terkena dengan nyala api, sedang suhu nyala penyalaan sendiri (self
ignited) tanpa terkena nyala api pada motor diesel terjadi pada suhu yang lebih
tinggi dari titik nyala (Thay, 2010).
2.2.1 Standar Mutu Biodiesel

16
Berikut adalah tabel yang berisikan parameter, batas nilai, dan metode
uji dari suatu biodiesel berdasarkan Standar Mutu Biodiesel yaitu (SNI) 04-7182-
2006.
Tabel 2.4. Parameter Biodiesel Indonesia
No Parameter Satuan Nilai Metoda Uji
1 Massa jenis (15 ºC) Kg/m3 850-890 ASTM D 1298
2 Viskositas kinematik (40 ºC) mm2 /s 2,3-6,0 ASTM D 445
3 Angka setana Min 51 ASTM D 613
4 Titik nyala ºC Min 100 ASTM D 93
5 Titik kabut ºC Maks 18 ASTM D 2500
6 Korosi lempeng tembaga
(3 jam pada 50ºC)
Maks no.3 ASTM D 130
7 Residu karbon
Dalam sampel asli, atau
Dalam 10% ampas destilasi
%-m Maks, 0,05
Maks 0,30
ASTM D 4530
8 Air dan sediman %-v Maks 0,05 ASTM D-1266
9 Temperature detilasi 90ºC ºC Maks 360 ASTM D 1160
10 Abu tersulfatkan %-m Maks, 0,05 ASTM D 874
11 Belerang Ppm-m
(mg/Kg)
Maks 100 ASTM D5453
ASTM D-1266
12 Fosfor Ppm-m
(mg/Kg)
Maks 10 AQCS Ca 12-55
13 Angka asam Mg
KOH/g
Maks 0,8 AQCS Ca 12-55
14 Gliserol bebas %-m Maks, 0,02 AQCS Ca 30-65
ASTM D-6584
15 Gliserol total %-m Maks, 0,24 AQCS Ca 30-65

17
ASTM D-6584
16 Kadar ester alkil %-m Maks 96,5 Dihitung*
17 Angka iodium %-m Maks 115 AQCS Cd 1-25
18 Uji halphen Negatif AQCS Cd 1-25
(Thay, Gan Kong, 2010
2.2.2 Karakterisasi Biodiesel
Karakterisasi yang umum perlu diperlu diketahui untuk menilai kinerja
bahan bakar biodiesel antara lain:
2.2.2.1 Densitas
Densitas atau berat jenis menunjukkan berat per satuan volume.
Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin
diesel adalah dengan metode ASTM D 1298 dan mempunyai satuan kilogram
permeter kubik (kg/m3) (Irene Wenas, Roweyna, 2008).
2.2.2.2 Viskositas
Viskositas adalah suatu kekentalan dari suatu fluida dimana kekentalan
ini dapat menentukan aliran pada fluida tersebut. Ada dua jenis aliran fluida yaitu
aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran laminar yaitu hubungan antara
viskositas dan jenis aliran, semakin besar viskositas yang dimiliki oleh suatu
fluida maka aliran yang mungkin terjadi pada fluida tersebut adalah laminar,
begitu juga sebaliknya.
Viskositas merupakan sifat fisik yang penting bagi bahan bakar mesin
diesel. Viskositas yang terlalu tinggi dapat mempersulit proses pembentukan
butir-butir cairan/kabut saat penyemprotan/automisasi. Viskositas bahan bakar
yang terlalu rendah akan dapat mengakibatkan kebocoran pada pompa injeksi
bahan bakar. Kedua hal ini menimbulkan kerugian, sehingga salah satu
persyaratan bahan bakar mesin diesel adalah nilai viskositas standar bakar mesin
diesel. Nilai viskositas harus berada dikisaran 2,3-6,0 mm, dimana nilai viskositas
yang tinggi artinya cairan tersebut cukup kental akan mengganggu kinerja injektor
pada mesin diesel.

18
2.2.2.3 Bilangan Asam
Bilangan asam adalah ukuran dari jumlah asam lemak bebas, serta
dihitung berdasarkan berat molekul dari asam lemak atau campuran asam lemak.
Bilangan asam dinyatakan sebagai jumlah milligram NaOH 0,1 N yang
dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram
minyak/lemak. Asam-asam lemak bebas ini terdapat dalam minyak karena proses
oksidasi dan hidrolisis enzim selama pengolahan dan penyimpanan minyak
(Ketaren, S, 1986).
2.2.3 Keunggulan Biodiesel
Biodiesel adalah suatu molekul kimia yang mempunyai rantai karbon
antara 12 sampai 20 serta mengandung oksigen. Adanya oksigen pada biodiesel
membedakannya dengan petroleum diesel (Solar) yang komponen utamanya
hanya terdiri dari hidrokarbon. Jadi komposisi biodiesel dan petroleum diesel
sangat berbeda.
Biodiesel memiliki keunggulan dengan minyak diesel lainnya, antara
lain:
1. Termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui.
2. Tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada.
3. Kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum
diesel.
4. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena
memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum.
5. Memiliki flash point yang tinggi, yaitu sekitar 200 0C, sedangkan bahan
bakar petroleum diesel flash pointnya hanya 70 0C.
6. Bilangan setana (cetana number) yang lebih tinggi daripada petroleum
diesel.
7. Biodiesel tidak mengadung sulfur dan senyawa benzen yang karsinogenik,
sehingga biodiesel merupakan bahan bakar yang lebih bersih dan mudah
ditangani dibandingkan dengan petroleum diesel.
8. Mengurangi emisi gas rumah kaca.

19
Jumlah CO2 diatmosfer yang berlebihan hasil emisi dari bahan bakar fosil
akan merusak lingkungan melalui efek rumah kaca. Dengan
memanfaatkan minyak tumbuhan sebagai bahan bakar, maka pembetukan
CO2 baru diatmosfer diperkirakan hampir tidak ada, dikarenakan CO2 hasil
pembakaran dari biodiesel akan dikosumsi kembali oleh tanaman untuk
kebutuhan proses fotositesis (Bahadir, 2005).
2.2.4 Komponen Biodiesel
Metil ester asam lemak memiliki rumus molekul CnH2(n-1)CO-OCH3
dengan nilai n yang umum adalah angka genap antara sampai dengan 24 dan nilai
r yang umum 0, 1, 2 atau 3. Beberapa metil ester asam lemak yang di kenal dapat
dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.5.Beberapa Metil Ester Asam Lemak sebagai komponen biodiesel
Nama Struktur Keterangan
Metil stearat CH3(CH2)16COOH 18:0
Metil palmitat CH3(CH2)14COOH 16:0
Metil laurat CH3(CH2)10COOH 12:0
Metil oleat CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 18:1(9C)
Metil linoleat CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6COOH 18:2(9C:12C)
Metil linolenat CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH 18:3(9C,12C,15C)
Angka pertama menyatakan jumlah atom karbon dalam asam, kedua
menyatakan jumlah ikatan rangkap dan bilangan dalam tanda kurung menyatakan
bilangan dalam tanda kurung menyatakan kedudukan dan struktur ikatan rangkap
(Matsjeh, Sabirin, 1994). Kelebihan metil ester asam lemak dibanding asam-asam
lemak lainnya:
1. Ester dapat diproduksi pada suhu reaksi yang rendah.
2. Gliserol yang dihasilkan dari metanolisis adalah bebas air.
3. Pemurnian metil ester lebih mudah dibanding dengan lemak lainnya
karena titik didihnya lebih rendah.
4. Metil ester dapat diproses dalam peralatan karbon steel dengan biaya lebih
rendah daripada asam lemak yang memerlukan peralatan stainless stell.

20
Metil ester asam lemak tak jenuh memiliki bilangan setana yang lebih
kecil dibanding metil ester asam lemak jenuh (r = 0). Meningkatnya jumlah ikatan
rangkap suatu metil ester asam lemak akan menyebabkan penurunan bilangan
setana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk komponen biodiesel
lebih dikehendaki metil ester asam lemak jenuh.
Lemak dan minyak terdiri dari trigliserida campuran, yang merupakan
ester dari gliserol dan asam lemak rantai panjang, molekul gliserol berikatan
dengan radikal asam lemak yang berbeda. Minyak dan lemak (trigliserida) yang
diperoleh dari berbagai sumber mempunyai sifat fisika-kimia yang berbeda satu
sama lain, karena jumlah perbedaan jumlah dan jenis ester yang terdapat
didalamnya. Minyak nabati terdapat dalam buah-buahan, kacang-kacangan, biji-
bijian, akar tanaman dan sayur-sayuran (Ketaren, S, 2005).
Reaktivitas kimia dari trigliserida dicerminkan oleh reaktivitas ikatan
ester dan derajat ketidakjenuhan dari rantai hidrokarbon. Asam lemak bebas yang
terbentuk hanya terdapat dalam jumlah kecil dan sebagian besar terikat dalam
bentuk ester (trigliserida). Secara alamiah, asam lemak jenuh yang mengandung
atom karbon C1–C8 berwujud cair, sedangkan jika lebih besar dari C8 akan
berwujud padat. Makin banyak jumlah ikatan rangkap pada suatu karbon tertentu,
maka titik cairnya semakin rendah dan titik didihnya makin tinggi.
2.3 Pemurnian Minyak
Tujuan utama proses pemurnian minyak adalah untuk menghilangkan
rasa dan bau yang tidak enak, mencegah timbulnya warna yang tidak menarik,
serta memperpanjang masa simpan minyak sebelum digunakan. Pada proses
pembuatan biodiesel dari sampel perlu dimurnikan terlebih dahulu untuk
menghilangkan senyawa pengotor yang terkandung dalam minyak kasar.
Senyawa pengotor dapat menyebabkan rendahnya kualitas biodiesel,
sehingga mesin diesel tidak dapat berjalan dengan baik atau bahkan dapat
merusak bagian alat pada mesin diesel. Senyawa pengotor yang terkandung dalam
minyak diantaranya adalah gum (getah/lender yang terdiri dari posfatida, protein,
residu, karbohidrat, air dan resin), asam lemak bebas, dan senyawa pengotor

21
lainnya. Sebagai contoh, asam lemak bebas yang terdapat dalam biodiesel dapat
menyebabkan terbentuknya karat (korosif), dan juga dapat menimbulkan jelaga
(kerak) di permukaan injektor mesin diesel. Proses pemurnian minyak yang perlu
dilakukan untuk pembuatan biodiesl adalah proses pemisahan gum (degumming)
dan proses pemisahan asam lemak bebas (netralisasi) (Reweyna, 2008).
2.3.1 Proses Pemisahan Gum (degumming)
Pemisahan gum merupakan suatu proses pemisahan getah atau lendir
yang terdiri dari fosfatida, protein, residu, karbohidrat, air dan resin tanpa
mengurangi jumlah lemak bebas dalam minyak. Biasanya proses ini dilakukan
dengan penambahan asam fosfat kedalam minyak lalu dipanaskan sehingga akan
terbentuk senyawa fosfolipid yang lebih mudah terpisah dari minyak kemudian
disusul dengan proses pemusingan (sentrifuse).
2.3.2 Proses Pemisahan Asam Lemak Bebas (Netralisasi)
Netralisasi adalah suatu proses pemisahan asam lemak bebas dari
minyak atau lemak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa
sehingga membentuk sabun. Pemisahan asam lemak dapat juga dilakukan dengan
cara penyulingan yang dikenal dengan istilah de-asidifikasi. Netralisasi dengan
kaustik soda banyak dilakukan dalam skala industri, karena lebih efisien dan lebih
murah dibandingkan dengan cara netralisasi lainnya. Selain itu, penggunaan
kaustik soda membantu dalam mengurangi zat warna dan kotoran yang berupa
getah dan lender dalam minyak.
Reaksi antara asam lemak bebas dengan NaOH adalah sebagai berikut:
O O
R C + NaOH R C + H2O
basa
OH ONa air
Asam lemak bebas sabun
2.4 Reaksi Transesterifikasi

22
Transesterifikasi adalah penggantian gugus metal dari ester dengan
gugus metal dari alkohol lain dalam suatu proses yang menyerupai hidrolisis.
Namun berbeda dengan hidrolisis, pada proses transesterifikasi bahan yang
digunakan bukan air melainkan alkohol. Umumnya katalis yang digunakan adalah
NaOH atau KOH (Efendy, 2005). Salah satu tujuan transesterifikasi untuk
menurunkan viskositas dan meningkatkan daya pembakaran sehingga dapat
digunakan sesuai dengan standar minyak diesel untuk kendaraan bermotor
(Prihandana, Rama dan Roy Hendroko, 2006).
Transesterifikasi pada dasarnya terdiri dari 4 tahapan, yakni:
(Indartono, 2006)
1. Pencampuran katalis alkalin (umumnya sodium hidroksida atau potassium
hidroksida) dengan alkohol (umumnya metanol). Alkohol diset pada rasio
molar antara alkohol terhadap minyak sebesar 9:1.
2. Pencampuran alkohol dengan alkalin dengan minyak didalam wadah yang
dijaga pada temperatur tertentu (sekitar 40-60 ºC) dan dilengkapi dengan
pengaduk (baik magnetic motor elektrik) dengan kecepatan konstan.
Reaksi metanolisis ini dilakukan sekitar 1-2 jam.
3. Setelah reaksi metanolisis berhenti, campuran akan mengakibatkan
separasi antara metil ester dan gliserol. Metil ester dipisahkan dari gliserol
dengan teknik separasi gravitasi.
4. Metil ester (biodiesel) kemudian dibersihkan menggunakan air distilat
untuk memisahkan zat-zat pengotor seperti metanol, sisa katalis alkalin,
gliserol dan sabun-sabun (soaps).
Biodiesel minyak durian dibuat dengan teknologi transesterifikasi
yaitu proses mengeluarkan gliserin dari minyak dan mereaksikan asam lemak
bebas dari minyak dan alkohol (misalnya metanol) menjadi alkohol ester (Fatty
Acid Metil Ester/FAME) atau biodiesel. Transesterifikasi dilakukan dengan
menggunakan katalisator NaOH.
2.5 Pemurnian Biodiesel

23
Produk biodiesel harus dimurnikan dari produk samping, gliserin,
sabun sisa metanol dan soda. Sisa soda (NaOH) yang ada pada biodiesel dapat
menghidrolisa dan memecah biodiesel menjadi asam lemak bebas yang kemudian
terlarut dalam biodiesel itu sendiri. Kandungan asam lemak bebas dalam biodiesel
akan mengakibatkan terbentuknya suasana asam sehingga dapat membuat korosi
pada logam mesin diesel (Mulyantara, 2005).
Proses transesterifikasi berlangsung selama 2 jam pada suhu sekitar 60 0C. Campuran kemudian didiamkan sehingga terbentuk dua lapisan. Lapisan
bawah adalah gliserin dan lapisan atas adalah metal ester (biodiesel). Agar reaksi
berlangsung sempurna, biodiesel hasil dari tahap pertama kemudian direaksikan
dengan metanol (tahap kedua), kemudian dicuci dengan aquades. Hal ini
dimaksudkan untuk menurunkan kadar gliserin total, sisa NaOH dalam biodiesel
agar tidak terjadi deposit apabila diaplikasikan pada motor (Sibuea, 2003).
Mekanisme reaksi kimia yang terjadi pada pembuatan biodiesel adalah
sebagai berikut:
NaOH(l) + CH3OH(l) CH3Na(aq) + H2O(g)

24
Gambar 2 Mekanisme Reaksi Pembuatan Biodiesel
Faktor utama yang mempengaruhi randemen metil ester yang
dihasilkan pada reaksi transesterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan
alkohol, jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air,
dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku (yang dapat menghambat
reaksi yang diharapkan).
1. Pengaruh asam lemak bebas dan zat menguap
Kandungan asam lemak bebas dan zat menguap merupakan parameter
kunci untuk menetukan proses transesterifikasi minyak/lemak tersebut.
Proses transesterifikasi dengan menggunakan katalis basa, bila asam harus
lebih kecil dari 3 % keasaman yang lebih tinggi pada minyak akan
memperkecil konversi minyak serta akan menghambat kerja katalis karena
sebagai katalis akan menyebabkan pembentukan sabun.
2. Pengaruh waktu reaksi dan temperatur
Laju konversi trigliserida bertambah dengan bertambahnya waktu reaksi.
Transesterifikasi dapat berjalan dengan temperatur berbeda teratur pada
jenis minyak yang diuapkan temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi
dan pembetukan yield ester bila reaksi bersifat endotermik (membutuhkan
panas) maka naikya suhu akan menggeser kesetimbangan kearah
pembentukan produk untuk meniadakan pengaruh naiknya suhu. Bila

25
reaksi bersifat eksotermik (naiknya suhu) akan menggeser kearah
sebaliknya (Bird, 1993).
3. Kecepatan Pengadukan
Pencampuran penting dalam proses transesterifikasi karena minyak tidak
larut dalam larutan NaOH-metanol. Ketika kedua fasa dicampur dan reaksi
dimulai, pengadukan tidak begitu diperlukan. Untuk reaksi bimolekuler
menurut teori tumbukan agar molekul bereaksi harus saling bertumbukan,
mempunyai tenaga hingga molekul-molekul menjadi aktif (Sibuea, 2003).
Kondisi proses produksi biodiesel dengan menggunakan katalis basa
1. Reaksi berlangsung pada temperature dan tekanan yang rendah
2. Menghasilkan konversi yang tinggi (98 %) dengan waktu reaksi dan
terjadinya reaksi dan terjadinya reaksi samping yang minimal.
3. Konversi langsung menjadi biodiesel tanpa tahap intermediate.
4. Tidak memerlukan kontruksi peralatan yang mahal.
2.6 Kromatrografi Gas
Kromatrografi gas ada dua jenis yaitu dengan fasa gas diam cair (GC
atau GLC = Gas Liquid chomatrography) dan kromatrografi gas padat (GSC =
Gas Solid Chromatrography). Kedua jenis kromatrografi gas ini adalah dalam
bentuk instrument dan untuk analisa senyawa organik yang lazim digunakan
adalah GC (Sanusi dan Marham, 2013).
Kromatrografi gas merupakan metode yang tepat dan cepat untuk
memisahkan campuran yang sangat rumit. Waktu yang dibutuhkan beragam,
mulai dari beberapa detik untuk campuran sederhana sampai berjam-jam untuk
campuran yang mengandung 500-1000 komponen. Komponen campuran dapat
diidentifikasikasikan dengan menggunakan waktu tambat (waktu retensi) yang
khas pada kondisi yang tepat.
Waktu retensi adalah waktu yang menunjukkan berapa lama suatu
senyawa tertahan dalam kolom. Waktu retensi diukur dari jejak pencatat pada

26
kromatogram dan serupa dengan retensi dalam KCKT dan Rf dalam KLT. Dalam
kromatografi gas, fase bergeraknya adalah gas dan zat terlarut terpisah sebagai
uap. Pemisahan tercapai dengan partisis sampel antara fase gas bergerak dan fase
diam berupa cairan dengan titik didih tinggi (tidak mudah menguap) yang terikat
pada zat padat peninjaunya (Khopkar S.M, 1990)

27
BAB III
METODE PENELITIAN
4.1 Lokasi dan Waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium KIMIA FMIPA UNIMED
dan penggunaan GC (gas kromatografi) dipusat penelitian kelapa sawit (PPKS) di
Jalan Brigjen Katamso No.51 Kampung Baru Medan. Penelitian ini dilaksanakan
pada bulan April-Mei 2015.
4.2 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah sampel biji durian yang ada di
sumatera utara. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah biji durian dengan
berbagai jenis secara random.
4.3 Alat dan Bahan
4.3.1 Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat pengepresan
hidraulik (Hydraulic Pressing), gelas kimia (250 mL dan 1000 mL), gelas
erlemeyer (200 mL, 400 mL), gelas ukur (25 mL, 50 mL dan 100 mL), pH meter,
labu ukur 100 mL, labu leher tiga, magnetic stirrer, hot plate, neraca analitik,
oven, buret, piknometer, termometer, viscometer Ostwald, stopwatch, blender,
corong pisah 100 ml, sentrifuse dan alat GC.
4.3.2 Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji durian,
minyak biji durian yang telah diekstraksi, NaOH p.a, phenolptalein, Asam Posfat
(H3PO4) p.a, dan aquades.

28
4.4 Pembuatan Larutan (HAM, Mulyono, 2005)
4.4.1 Larutan NaOH 0,1 N (0,1 M)
NaOH ditimbang sebanyak 4 gram bersama gelas kimia 50 mL, (yang
sudah diketahui massanya) dengan cepat, lalu tuangkan ke dalam 25 mL aquadess
dan aduk hingga melarut, pindahkan kedalam labu ukur 100 mL. Lakukan
pembilasan, encerkan larutan dengan aquades sampai volumenya 100 mL, tutup
rapat dan homogenkan.
4.5 Prosedur Kerja
4.5.1 Pembuatan Minyak Biji Durian Dengan Metode Pengepresan
Hidraulik (Hidraulic Pressing) (Ketaren, S, 1986)
1. Biji durian dicuci dengan air, dikupas kulit arinya, dan kemudian
dijemur dibawah sinar matahari.
2. Kemudian biji durian dirajang-rajang dan diblender hingga berbentuk
tepung.
3. Kemudian dipanaskan dalam oven selama 6 jam pada suhu 100 ºC.
4. Untuk mendapatkan minyak dilakukan dengan pengepresan dan
didapat minyak kasar dan ampas/bungkil. Setelah itu minyak
ditimbang.
4.5.2 Proses Pemurnian Minyak Biji Durian
4.5.2.1 Pemurnian Minyak (Dian, 2009)
1. Proses Pemisahan Gum (Degumming)
a. Kedalam minyak hasil ekstrak diberi asam posfat 1 % dari berat
minyak.
b. Kemudian dilakukan pengadukan konstan dan pemanasan hingga
terbentuk fosfolipid yang ditandai warna menjadi lebih hitam.
c. Lalu dipisah dengan menggunakan sentrifuge pada 2000 rpm
selama 5 menit.

29
2. Netralisasi
a. Minyak hasil perlakukan degumming diberi NaOH sebanyak 1%
dari berat minyak, diaduk dengan kuat sampai terbentuk dua fasa.
b. Kedua fasa yaitu fasa sabun dan minyak dipisahkan dengan
menggunakan corong pisah.
c. Kemudian diambil fasa minyak, diukur pHnya hingga netral dan
diberi air panas sebanyak 10 % dari berat minyak.
d. Kemudian dikeringkan dalam oven pada 100 0C untuk
menghilangkan kandungan air.
4.5.2.2 Proses Transesterifikasi Dan Pencucian Biodiesel
1. Dimasukkan 100 g minyak biji durian dan magnetic stirrer kedalam labu
leher tiga yang dilengkapi dengan kondenser refluks dan thermometer.
Kemudian minyak dipanaskan pada suhu 50-60 ºC.
2. Dilarutkan 1 g NaOH kedalam 25,5 ml metanol.
3. Kemudian Natrium metoksida dimasukkan kedalam labu transesterifikasi
yang berisi minyak biji durian. Biarkan reaksi berjalan dengan suhu tetap
50-60 ºC selama 2 jam.
4. Isi labu transesterifikasi dipindahkan kedalam corong pisah 500 ml, labu
didiamkan selama 24 jam.
5. Gliserol yang ada dilapisan bawah dipisahkan dari biodiesel.
6. Kedalam biodiesel ditambahkan air panas sebanyak 10 % dari berat
biodiesel kemudian dikocok hingga terbentuk campuran berwarna susu
dan biarkan tenang hingga air dan biodiesel memisah.
7. Biodiesel dapat dipisahkan dari lapisan air dan diukur pHnya netral (7),
lalu dikeringkan melalui pemanasan.
8. Kemudian biodiesel dianalisis dengan Kromatografi Gas (GC) disesuaikan
dengan SNI bahan bakar nasional.

30
4.5.3 Penentuan Parameter Kimia Biodiesel
4.5.3.1 Penentuan Densitas
1. Piknometer kosong yang telah bersih dan kering ditimbang (Go).
2. Kemudian diisi dengan sampel biodiesel, lalu tutup kapiler dimasukkan
sampai tanda batas. Lalu ditimbang (G).
Maka harga densitas dapat dihitung dengan persamaan berikut:
ρ=G−GoVt
+0 , 0012
Dimana: ρ = Densitas (g/cm3)
Go = Berat piknometer kosong (g)
G = Berat piknometer dan sampel (g)
Vt = Volume piknometer (10 cm3)
0,0012 = Bilangan adalah koreksi terhadap udara.
4.5.3.2 Penentuan Viskositas Biodiesel
1. Dimasukkan sampel kedalam Viscometer Ostwald yang bersih dan kering.
2. Sampel biodiesel kemudian dihisap melalui labu pengukur dari
vxiscometer sampai permukaan biodiesel lebih tinggi dari batas ‘a’.
Kemudian cairan biodiesel dibiarkan turun.
3. Stop-watch dihidupkan saat biodiesel melewati batas ‘a’ dan dimatikan
saat melewati batas ‘b’ (Bird, 1985).
4. Dilakukan perlakuan yang sama terhadap air.
Maka volume cairan yang mengalir melalui pipa persatuan waktu adalah:
ηb
ηa
=ρb tb
ρa ta
Dimana: ηadanηb = Viskositas air dan biodiesel (1 mm2/s)
t a dant b = Waktu yang dibutuhkan air dan biodiesel (s)
ρa danρb = Berat jenis (densitas) air dan biodiesel (1 g/cm3)

31
4.5.3.3 Penentuan Asam Lemak Bebas/Free Fatty Acid (FFA)
1. Minyak sampel yang telah dilakukan penentuan kandungan minyak
dipergunakan untuk test FFA ini ditimbang 5 ± 0,1 gram.
2. Lalu ambil 50 ml metanol dan masukkan dalam erlemeyer,
tambahkan 4 tetes phenolptalein dan aduk dengan baik.
3. Netralisir alkohol dengan menambahkan 0,1 N NaOH tetes demi
tetes dari pipet sampai campuran menjadi berwarna jingga tipis.
4. Pindahkan alkohol yang telah dinetralisir kedalam gelas ekstraksi
yang berisikan minyak.
5. Panaskan sampai campuran mendidih, goyangkan isi tabung secara
teratur untuk mencegah penggumpalan.
6. Setelah mendidih titrasi larutan tersebut dengan 0,1 N NaOH
sehingga campuran berubah menjadi jingga dan warna ini bertahan
paling tidak selama 30 detik.
7. Catat berapa pemakaian NaOH.
Maka kadar asam lemak bebas adalah:
% FFA sebagai palmitat acid¿25,6 x N NaOH x Volume titrasi
berat sampel

32
4.5.4 Diagram Alir Penelitian
3.5.4.1 Pengekstrakan Minyak Biji Durian
Dicuci dengan air dan dikupas kulit
arinya.
Dijemur dibawah sinar matahari.
Dipotong hingga kecil-kecil.
Dihaluskan dengan blender.
Dipanaskan dalam oven selama 6 jam
pada suhu 100 ºC.
Dipress dengan pengepresan hidrolik.
Biji Durian
Serbuk biji durian
Serbuk biji durian
Ampas/Bungkilkil
Minyak kasar

33
3.5.4.2 Proses Pemurnian Minyak Biji Durian
a. Degumming
Asam Posfat 0,2% dari berat minyak.
Dilakukan pengadukan konstan dan pemanasan
hingga terbentuk warna lebih hitam.
Di sentrifuge 2000 rpm selama 5 menit
b. Netralisasi
Ditambahkan NaOH 0,1 N Sebanyak 1% dari berat minyak
diaduk dengan kuat sampai terbentuk dua fasa.
Kedua fasa yaitu fasa sabun dan minyak dipisahkan dengan
menggunakan corong pisah.
Diambil fasa minyak, diukur pHnya hingga netral dan
diberi air panas sebanyak 10 % dari berat minyak
Ditambahkan air panas sebanyak 10% dari berat minyak.
Dikeringkan dalam oven pada 100 0C untuk menghilangkan
kandungan air.
Minyak kulit durian kasar
Minyak I Gum
Minyak murni

34
3.5.4.3 Proses Transesterifikasi Dan Pencucian Biodiesel
(+) NaOH 1 g
(+) Metanol 25,5 mL
Diaduk dengan magnetic stirrer
Minyak Murni 100 g
Gelas Beaker 500 mL
Larutan Homogen Metanol-NaOH
Erlenmeyer 250 mL
Reaksi Trans-esterifikasi
(56 0C, aduk, 2 jam)
Pemisahan dengan corong pisah 500 mL
Lapisan Bawah (Gliserol)
Lapisan atas (Ester Karboksilat, kualitas rendah)
Dimasukkan dalam corong pisah 500 mL
Ditambah air panas 10 % dari berat minyak
Dikocok dan didiamkan
Lapisan biodiesel
Lapisan airDiukur pH = 7 dan dikeringkan dalam oven
Biodiesel Murni
Viskositas (ASTM D-445)Densitas
(ASTM D-1298
Analisis Struktur GC

35
3.5.4.4 Penentuan Asam Lemak Bebas/Free Fatty Acid (FFA)
Ditimbang sebanyak 5 ± 0,1 gram.
Dimasukkan 50 ml metanol.
Ditambahkan 4 tetes phenolptalein.
Dinetralisir dengan menambahkan 0,1 N
NaOH tetes demi tetes
Dimasukan kedalam gelas kimia yang
berisikan minyak.
Dipanaskan hingga mendidih dan diaduk
untuk mencegah penggumpalan.
Dititrasi dengan 0,1 N NaOH
Sampel Minyak
Erlenmeyer 250
Alkohol berwarna jingga tipis
Alkohol + Minyak
Terbentuk warna jingga bertahan dalam 30 s