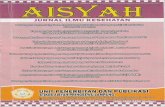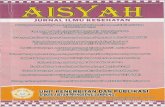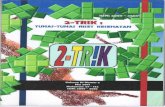JURNAL_2
Click here to load reader
-
Upload
bahestikhan -
Category
Documents
-
view
16 -
download
3
description
Transcript of JURNAL_2
-
Anis Fajrin, 0911220006. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya,
Malang
Kontribusi Nilai Kearifan Lokal Terhadap Komunikasi Pelayanan Dari Aparat Instansi
Pemerintah Di Kabupaten Sumenep.
Oleh : Anis Fajrin, 0911220006. 2014.
Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya, Malang.
Pembimbing Utama: Akh. Muwafik Saleh, S.Sos, M.Si dan Pembimbing Pendamping: Yuyun Agus
Riyani, S.Pd., M.Sc.
ABSTRAKSI
Sumenep merupakan kabupaten yang memiliki banyak nilai kearifan, namun peneliti melihat
aspek pelayanan dari salah satu bagian nilai kearifan yaitu parebhesan, salah satu contoh ungkapan
tersebut adalah bapak, babuk, guru, rato yang bermakna kehormatan masyarakat terhadap keempat
tokoh tersebut. Walaupun Sumenep memiliki ciri-ciri sebagai bangsa eastern, namun aspek
pelayanan yang diaplikasikan oleh aparat pemerintah Sumenep merupakan aplikasi perspektif
western & eastern, namun antara kedua perspektif tersebut belum dapat teraplikasi secara sempurna
atau optimal. Banyak kekecewaan yang masih diungkapkan oleh masyarakat terhadap tindak
pelayanan, bahkan masyarakat menyatakan bahwa nilai kearifan lokal (parebhesan) belum dapat
diaplikasikan oleh aparat dalam tindakannya, karena memang hasil dari wawancara dan observasi
menyatakan bahwa nilai kearifan lokal yang teraplikasi pada tindak pelayanan adalah nilai kearifan
lokal yang bermakna negatif.
Kata Kunci : nilai kearifan lokal, pelayanan & handling complain, instansi pemerintah
Pendahuluan
Komunikasi sebagai disiplin ilmu
akademisi yang telah dipelajari sejak jaman
dahulu, dan menjadi topik penting pada abad
kedua puluh, hal ini dijelaskan dalam buku
Littlejohn (1999, h. 3) theories of human
communication. Walaupun begitu,
perspektif teori yang telah dibahas
dikalangan peneliti sebagian besar adalah
produk dari wacana teoritikal Barat
(western). Pemikiran teoritik komunikasi
yang menjadi bahan diskusi para peneliti
dan praktisi komunikasi Indonesia masih
sebatas atau bahkan berhenti pada upaya
melakukan verifikasi atau pengujian
terhadap teori-teori komunikasi yang
merupakan produk dari sejarah intelektual
Barat (western). Hingga saat ini belum
cukup terlihat upaya dari peneliti
komunikasi di Indonesia untuk menggali
kearifan lokal (lokal wisdom) guna
membangun gagasan teoritik komunikasi
yang relevan dengan kajian persoalan
komunikasi yang terjadi di Indonesia (kajian
non-western).
Sebagai gambaran awal peneliti
menyajikan gagasan yang dikemukakan oleh
Lawrence Kincaid (Dalam Littlejohn, 1999,
h. 4) yang menyebutkan bahwa teori
komunikasi Asia (eastern) diharapkan dapat
memberikan sumbangan dan pemahaman
kita tentang perspektif komunikasi dunia
Timur (eastern). Dalam konteks keilmuan
dan filsafat, disadari atau tidak, dominasi
pemikiran Barat terhadap pemikiran Timur
(Asia) masih sangat besar. Teori komunikasi
Asia yang dimaksud adalah memberi
perhatian kepada filosofi besar India dan
Cina serta negara-negara Asia lainnya.
Lawrence Kincaid mengkaji komunikasi
dari aspek kultural yang mendalami
perspektif ketimuran (eastern), yang mana
Kincaid membedakan pandangan Barat dan
Timur, secara sederhana peneliti
menyimpulkan bahwa Kincaid membedakan
-
Anis Fajrin, 0911220006. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya,
Malang
ciri-ciri masyarakat pada pandangan Timur
sebagai masyarakat yang memiliki ciri-ciri
masyarakat layaknya bangsa timur, yang
sangat terkenal dengan keramah tamahannya
terhadap orang lain bahkan orang asing
sekalipun. Bagaimana mereka saling
memberikan salam, tersenyum atau berbasa
basi menawarkan makanan atau minuman.
Bangsa timur juga sangat menjunjung tinggi
nilai-nilai atau norma-norma yang tumbuh
di lingkungan masyarakat mereka sebagai
kepercayaan atau adat istiadat. Sedangkan
budaya Barat (Western) yang mana ciri-
cirinya adalah tegas, spontan, tidak suka
basa-basi atau to the point, imajinatif,
objektif, dan logis (tidak percaya terhadap
hal-hal yang tidak ilmiah).
Negara-negara yang berada di wilayah
Asia Timur dikenal memiliki beragam
filsafat yang berbasis pada aspek
kepercayaan atau keyakinan yang dianut
oleh penduduknya, seperti kepercayaan yang
dianut oleh perspektif bangsa Korea. Pada
dasarnya terdapat beberapa paham yang
berkembang dan menjadi dasar berpikir
masyarakat Korea, diantaranya pemikiran
taoisme, konfusianisme dan buddhisme
(Kincaid, 1987, h. 13). Cara pandang dari
taoisme ini kemudian berkembang ke dalam
lingkup sosial. Di mana ide orang Korea
akan terciptanya keharmonisan
mengharuskan manusia untuk bisa
menyesuaikan diri dan tidak terfokus pada
kepentingan individu. Sehingga,
terbentuklah masyarakat yang hidup
berdampingan tetapi tidak saling
menganggu. Kemudian ajaran kedua adalah
pemikiran konfusionisme yang tidak
terfokus pada karakter individualistik dan
sesuatu yang mistik seperti dalam ajaran
taoisme. Melainkan lebih menekankan pada
hubungan sosial dan perilaku sosial
masyarakat. Selain itu, konfusianisme juga
menekankan kepada disiplin diri,
pendidikan, ikatan keluarga dan harmoni
sosial yang kuat. Hingga kemudian,
pemikiran buddhisme juga masuk dan
mempengaruhi kehidupan masyarakat Korea
yang ingin hidup secara spritual. Buddhisme
lebih menekankan pada sebuah
pengembangan spritual yang mencari
ketenangan hati dan menemukan arti hidup
yang sebenarnya, seperti melalui meditasi,
Kincaid (1987, h. 14).
Dalam jurnal Rahardjo (2013, h. 74)
dijelaskan bahwa dalam konteks diskusi
tentang teori Komunikasi Asia, para
akademisi dan peneliti komunikasi Jepang,
Korea, dan China telah melakukan praktik-
praktik intelektual guna menghasilkan teori-
teori komunikasi yang berbasis pada
kearifan lokal. Salah satu contohnya adalah
Chinese Harmony Theory yang diciptakan
oleh Guo-Ming Chen. Teori ini menjelaskan
bahwa harmoni merupakan nilai fundamental dalam budaya China. Harmoni,
bagi orang China merupakan tujuan dari
komunikasi antarmanusia dimana pihak-
pihak yang berinteraksi mencoba untuk
menyesuaikan diri satu sama lain guna
mencapai suatu keadaan, yaitu
interdependensi dan kooperasi. Kemampuan
untuk mencapai harmoni dalam relasi antar
manusia merupakan kriteria utama yang
dipakai orang China untuk mengevaluasi
kompetensi komunikasi. Meningkatnya
kemampuan seseorang untuk mencapai
harmoni akan meningkatkan kompetensi
komunikasi. Guo-Ming Chen dalam
membangun Chinese Harmony Theory
menggunakan konsep-konsep yang berbasis
pada kearifan lokal, yaitu pertama,
menginternalisasikan kemanusiaan,
kejujuran, dan ritual, kedua,
mengakomodasikan kemungkinan-
kemungkinan dalam konteks waktu,
kemungkinan-kemungkinan dalam konteks
ruang/spasial, dan awal suatu tindakan, dan
ketiga, secara strategis menerapkan antar
hubungan, image/citra diri, dan kekuasaan
dalam tataran perilaku.
-
Anis Fajrin, 0911220006. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya,
Malang
Contoh lain mengenai nilai-nilai non-
western yang berasal dari Jepang
dikemukakan oleh Linda C. Ehrlinch dan
Naomi Tonooka (Dalam Christians&Faber,
1997, h. xii) yang membahas mengenai
pentingnya nilai tradisi tahun baru di Jepang
yang biasa disebut keheningan, lebih mendalam Yoshikawa menjelaskan masih
dalam (Christians&Faber, 1997, h. xii)
bahwa budaya tersebut menunjukan pada
kita bagaimana membentuk ketenangan
dalam diri manusia masing-masing yang
dipercaya dapat mempengaruhi pola
komunikasi masyarakat, yang mengajarkan
bagaimana menentukan refleksi dalam
memenejerial perilaku dan sikap dalam
kehidupan masyarakat.
Wujud nyata dari pemikiran teoritik
komunikasi yang berbasis pada nilai-nilai
budaya Timur (eastern/non-western) cocok
untuk mewakili ciri-ciri sifat dari
masyarakat Indonesia terutama masyarakat
jawa, yang masih menjunjung tinggi nilai
kepercayaan, nilai kearifan, memiliki rasa
sosial, menjunjung tinggi nilai kesopanan,
kekerabatan yang tinggi dan lain sebagainya,
namun yang peneliti lihat lebih kontras
adalah masyarakat Sumenep, karena
ditengah sifat masyarakat Madura yang
keras, spontan dan tegas. Masyarakat
Sumenep terkenal dengan masyarakat yang
memiliki sikap yang lebih halus dalam tutur
katanya, sehingga Kabupaten Sumenep
dijuluki sebagai 'Solo of Madura'. Kota
Sumenep juga terkenal sebagai kota
Keraton, karena semenjak dahulu wilayah
ini terdapat puluhan keraton/ istana sebagai
pusat pemerintahan sang Adipati. Seperti
halnya keraton-keraton di Jawa, budaya
halus dan tata krama yang sopan serta
bahasa sehari-hari yang santun juga menjadi
identitas budaya, baik di seputar lingkungan
Keraton Sumenep maupun di lingkungan
masyarakat Sumenep pada umumnya.
Keunikan tersebut yang telah menarik
peneliti untuk meneliti unsur nilai kearifan
lokal yang ada di Sumenep berkenaan
dengan aspek pelayanan.
Dilihat dari karakter masyarakat
Madura yang bertempramen keras dan tegas,
masyarakat Sumenep cenderung lebih ramah
dan lembut. Hal ini diperkuat dengan adanya
hasil penelitian Rachmadiana (2004, h. 40)
mengenai etos budaya menunjukan bahwa
penduduk yang tinggal di kota yang terletak
semakin ke Timur kepulauan Madura
berperilaku lebih santun daripada penduduk
yang hidup di wilayah Madura bagian barat.
Kesantunan tersebut terlihat dari segi
tingkah laku atau yang sering disebut oleh
masyarakat Madura sebagai istilah (Adep
Asor) dan tuturkata sopan santun saat
berbicara dengan orang lain. Namun,
walaupun terdapat beberapa hal yang
berbeda dengan saudara luar kabupaten,
kabupaten Sumenep tetap serupa dengan
kabupaten lain di Madura. Seperti halnya
masyarakat Madura pada umumnya,
masyarakat Sumenep juga sangat
menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan
yang mayoritas beragama Islam. Hal itupun
tergambar dalam nilai kearifan lokal berupa
ungkapan atau yang sering disebut
parebasan. Parebasan ini mengandung
nilai-nilai kebijakan dan petuah untuk dapat
saling mengingatkan masyarakat dalam
kehidupan bersosialisasi dan kehidupan
kerohanian.
Dewasa ini merupakan hal yang sangat
penting melakukan interprestasi terhadap
kearifan lokal tersebut, karena nilai kearifan
lokal tersebut akan dapat menjadi citra bagi
masyarakatnya jika nilai-nilai budaya
tersebut berhasil ditanamkan sehingga, akan
dihasilkan pula manusia-manusia yang
berdaya guna dalam kehidupan manusia,
manusia yang sadar budaya. Artinya,
memiliki nilai-nilai budaya nasional yang
transetnik dan bersifat menyongsong masa
depan, serta mampu pula menghayati
kearifan-kearifan lokalnya. Dengan jati diri
yang kuat, kita tidak akan jatuh terhadap
-
Anis Fajrin, 0911220006. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya,
Malang
bangsa lain atau terhindar dari posisi yang
subordinatif. Paling tidak, demikian itu yang
menjadi idealisasinya. Terlebih nilai
kearifan lokal dapat mendorong motivasi
kerja dan sosial kontrol, hal ini menguatkan
keyakinan bahwa perlunya karakter yang
positif pula pada setiap penggerak lembaga,
karena sesungguhnya secara konstitusional
lembaga memang dihadirkan dengan norma-
norma yang positif. Begitu juga dalam
lingkup pelayanan, yang mana hal ini berarti
bahwa, institusi pemerintah mempunyai
fungsi pelayanan dan meningkatkan
kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Para
unsur penyelenggaran pemerintahan dan
penyelenggara pelayanan publik yang saling
memanusiakan, saling mengingatkan dan
saling menghargai serta kepemimpinan yang
berdasarkan agamis dan saling menjunjung
tinggi nilai tatakrama, kesopanan yang
sesuai dengan norma dan nilai kearifan yang
berlaku dalam suatu masyarakat tersebut
akan membuat organisasi pelayanan publik
maju dan makin berkembang.
Ditengah masyarakat Semenep yang
memiliki banyak nilai-nilai budaya yang
menjadi nilai kearifan, peneliti menemukan
masih banyaknya keluhan yang disampaikan
oleh masyarakat berkenaan dengan sistem
pelayanan yang diberikan oleh aparatur
pemerintah. Maka hal itulah yang mendasari
pemikiran peneliti untuk meneliti sejauh
mana kontribusi nilai kearifan yang dimiliki
oleh masyarakat Sumenep dapat teraplikasi
pada aspek tindakan pelayanan aparat
pemerintah Sumenep. Sehingga,
berdasarkan perspektif eastern mengenai
aspek pelayanan, peneliti berasumsi bahwa
salah satu teori yang dapat dijadikan acuan
adalah aspek pelayanan dengan hati nurani
seperti yang diungkapkan oleh Saleh (2010)
dalam buku public service communication.
Melayani dengan hati nurani seperti
yang diungkapkan oleh Saleh (2010, h. 199)
adalah budaya melayani dengan hati nurani
adalah suatu sikap pelayanan yang
dilakukan dengan setulus hati. Ketulusan
dalam pelayanan adalah pekerjaan hati dan
bukan semata pekerjaan rasionalitas alih-alih
pemenuhan tugas pekerjaan yang
terformulasi dalam standart operasional
procedur (SOP) pelayanan. Masih dalam
Saleh (2010, h. 199) yang menyatakan
bahwa pelayanan yang tulus yang diberikan
merupakan amal yang tidak ternilai
harganya di hadapan sang Khaliq dan
pelayanan yang tulus sesungguhnya
merupakan wujud pengabdian kita kepada
Sang Pencipta. Dalam melayani, Saleh
(2010, h. 200) juga mengungkapkan bahwa
sebagai aparat pelayanan yang bertugas
memberikan pelayanan maka harus mampu
menanggalkan sikap ego dan keangkuhan,
dan menggantikannya dengan rasa
kebersamaan. Asumsi peneliti mengenai
pelayanan dengan hati nurani dari Saleh ini
sesuai dengan karakter masyarakat Sumenep-Madura yang memiliki banyak
nilai kearifan dan menjunjung tinggi nilai
keagamaan (Islam).
Menggali dan mengenali kearifan lokal
ini merupakan upaya untuk menumbuhkan
kesadaran dan kepekaan keilmuan
akademisi dan peneliti komunikasi
Indonesia tentang pentingnya memahami
pemikiran filosofis, nilai-nilai budaya dan
moral guna membangun gagasan-gagasan
teoritik komunikasi yang relevan dengan
lingkup persoalan komunikasi yang terjadi
di Indonesia. Dilihat dari kajian komunikasi
mengenai aspek budaya seperti yang
diungkapkan oleh Kincaid (Dalam
Littlejohn, 1999, h. 4) mengenai budaya
Western dan estern, yang mana Kincaid
berpendapat bahwa kajian budaya estern
yang memiliki ciri-ciri masyarakat yang
tidak to the point atau berbelit-belit, dan
basa-basi seperti pada ciri masyarakat
keraton yang halus, serta masyarakat yang
memiliki banyak kepercayaan dan religius
yang tinggi, hal ini mencerminkan sifat
masyarakat Sumenep, bahkan banyak dari
-
Anis Fajrin, 0911220006. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya,
Malang
ungkapan Parebhesan Sumenep yang
memiliki makna tidak langsung atau
menyindir dan terkesan bertele-tele atau
berbelit belit dalam memberikan nasehat.
Contohnya ungkapan yang berbunyi Bapak
Babuk Guru Rato ungkapan atau pepatah ini
menjadi suatu dasar tindakan sosialisasi dari
masyarakat Madura khususnya Sumenep
yang secara arti sederhanya adalah kedua
orang tua (Bapak Babuk) adalah urutan
pertama yang harus kita hormati, baru pada
urutan berikutnya adalah guru/pemuka
agama (Guru) baru hormat pada
pemerintah/pimpinan/raja (Rato).
Komunikasi dan budaya merupakan dua
konsep yang tidak dapat dipisahkan. Budaya
adalah komunikasi dan komunikasi adalah
budaya. Budaya dan komunikasi
berinteraksi secara erat dan dinamis. Inti
budaya adalah komunikasi, karena budaya
muncul melalui komunikasi dan budaya
merupakan pengetahuan yang dapat
dikomunikasikan. Pusat perhatian studi
komunikasi dan kebudayaan juga meliputi
bagaimana menjejaki makna, pola-pola
tindakan, dan bagaiman makna serta pola-
pola itu diartikulasi dalam sebuah kelompok
sosial, kelompok budaya, kelompok politik,
serta proses pendidikan (Liliweri, 2007, h.
12). Namun Geertz (Dalam West & Turner,
2008, h.323) menyatakan bahwa untuk
memahami budaya, seseorang harus
melihatnya dari sudut pandang anggota
budaya tersebut.
Karena pembahasan dalam penelitian
ini mencakup nilai kearifan lokal berupa
parebhesan yang ada pada masyarakat
Sumenep madura yang terkontribusi pada
komunikasi (tindakan) pelayanan, serta
bagaimana aparat pelayanan pemerintah
sebagai bagian dari masyarakat Sumenep
tersebut nantinya mampu mengaplikasikan
nilai-nilai kearifan yang masih dijunjung
tinggi oleh masyarakat diaplikasikan dalam
tindakan pelayanan sebagai bagian dari
komunikasi sosial dengan masyarakat
pengguna jasa maka, kajian etnografi
komunikasi akan masuk didalamnya,
penelitian etnografi dalam bidang
pemahaman budaya yang tercermin dalam
peribahasa sangat penting dilakukan dalam
kaitannya dengan pemahaman kepribadian
dan nilai-nilai budaya lokal, Kuswarno
(2008, h. 13) menjelaskan mengenai
etnografi komunikasi yang merupakan
pengkajian terhadap bahasa dalam perilaku
komunikasi suatu masyarakat, yaitu melihat
bahasa secara umum dihubungkan dengan
nilai-nilai sosial kultural. Sehingga tujuan
deskripsi etnografi adalah untuk
memberikan pemahaman global mengenai
pandangan dan nilai-nilai suatu masyarakat
sebagai cara untuk menjelaskan sikap dan
prilaku anggota-anggotanya. Sehingga
peneliti mengambil judul KONTRIBUSI NILAI KEARIFAN LOKAL TERHADAP
KOMUNIKASI PELAYANAN DAN
HANDLING COMPLAINT DARI
APARAT INSTANSI PEMERINTAH DI
KABUPATEN SUMENEP.
Metode
Metodologi penelitian yang dipakai
dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Berdasarkan metodologi kualitatif dikenal
beberapa metode riset (Kriyantono, 2006, h.
62), salah satu dari metode yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu metode etnografi.
Menurut Kriyantono (2006, h. 67) etnografi
adalah riset yang digunakan untuk
menggambarkan bagaimana individu-
individu menggunakan kebudayaannya
untuk memaknai realitas. Riset ini juga
bertujuan untuk menggambarkan atau
mendeskripsikan kebudayaan tertentu secara
mendalam dari berbagai aspek seperti
artefak budaya, pengalaman hidup,
kepercayaan, dan sistem nilai dari suatu
masyarakat. Sedangkan jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
deskriptif. Menurut Kriyantono (2006, h.
69), penelitian deskriptif bertujuan
-
Anis Fajrin, 0911220006. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya,
Malang
membuat deskripsi secara sistematis, factual
dan akurat tentang fakta dan sifat populasi
atau objek tertentu.
Fokus instansi yang dipilih dalam
penelitian ini adalah instansi yang lebih
umum atau sering kali di manfaatkan oleh
masyarakat sebagai instansi pemenuhan
jasa, atau dapat dikatakan merupakan
instansi yang memiliki pengguna jasa
dominan, sehingga akan lebih banyak juga
masyarakat yang dapat merasakan pelayaan
dari aparat pelayanan di instansi tersebut,
maka akan lebih mudah bagi peneliti
mencari informasi mengenai tingkat
pelayanan yang diberikan oleh para aparat di
instansi. Sebagai fakta awal penelitian,
peneliti memanfaatkan situs resmi
pemerintahan Sumenep untuk
mengumpulkan beberapa data dan berita
mengenai adanya keluhan-keluhan
masyarakat yang diajukan kepada beberapa
instansi tersebut. Adapun fokus instansi
yang akan diteliti adalah instansi pelayanan
pemerintah Kabupaten Sumenep, tiga
instansi yang dipilih peneliti adalah sebagai
berikut : RSUD. Dr. H. Moh. Anwar, Dinas
Kependudukan & Catatan Sipil, dan
Kapolres Sumenep.
Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teknik pemilihan informan
Menurut Sampling Purposif (Purposif
Sampling) yang menurut Kriyantono (2006,
h. 158) Teknik ini mencakup orang-orang
yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria
tertentu yang dibuat periset berdasarkan
tujuan riset. Sedangkan orang-orang dalam
populasi yang tidak sesuai dengan criteria
tersebut tidak dijadikan sampel. Peneliti
akan mewawancarai orang-orang atau
aparat/divisi (sebagai informan utama) yang
berhubungan langsung kepada masyarakat
dan menangani masalah keluhan yang
diajukan masyarakat misalnya humas atau
disivi penanganan komplain serta costumer
service dan bekerja pada instansi pemerintah
dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 3
tahun. Sedangkan pada informan golongan
masyarakat (sebagai key informan) peneliti
akan memilih masyarakat yang pernah
menggunakan jasa instansi yang telah dipilih
menjadi fokus (RSUD, CAPIL dan
POLRES). Dan Informan tambahan dalam
penelitian ini yaitu budayawan atau orang-
orang yang mengerti lebih dalam mengenai
asal-usul dan selukbeluk masyarakat
Sumenep dan nilai kearifannya.
Karakteristik informan tambahan
dalam penelitian ini, yaitu:
Mengerti terhadap makna yang terdapat pada ungkapan nilai kearifan.
Mengerti keanekaragaman kebudayaan dan nilai-nilai luhur masyarakat
Sumenep
Bersedia terbuka dan tidak terbelit-belit dalam memberikan informasi.
Analisis data dilakukan saat
pengambilan data berlangsung dan setelah
selesai pengumpulan data dalam periode
tertentu. Pada saat wawancara, peneliti
sekaligus melakukan analisis data terhadap
jawaban dari para informan. Miles and
Huberman mengemukakan bahwa aktivitas
data dalam analisis kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai tuntas, sehingga
datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2011, h.
246). Penelitian ini menggunakan model
triangulasi metode, dengan menggunakan
triangulasi metode peneliti akan
membandingkan dan mengecek hasil
wawancara dengan keadaan yang peneliti
lihat dilapangan dari hasil observasi serta
diperkuat dengan hasil gambar-gambar,
bagan atau dokumen yang menguatkan
pernyataan. Misalnya, hasil wawancara
aplikasi ungkapan/parebesan yang dianut
oleh aparat pelayanan dengan hasil
observasi implementasi tindak pelayanan
dan penanganan komplain yang benar-benar
ditunjukan oleh aparat saat melayani.
-
Anis Fajrin, 0911220006. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya,
Malang
Hasil dan Pembahasan
Masyarakat sumenep merupakan
masyarakat yang memiliki banyak nilai
kearifan lokal. Nilai kearifan lokal bukan
lagi merupakan hal yang tabu untuk
diaplikasikan pada berbagai aspek, tidak
hanya pada aspek interaksi sosial sehari-hari
masyarakat, namun juga pada aspek
pelayanan publik. Nilai kearifan lokal dalam
kajian komunikasi dilihat sebagai bagian
dari perspektif non-western, yang mana
dalam perspektif tersebut, menurut Kincaid
dicirikan sebagai masyarakat layaknya
bangsa Timur yang sangat menjunjung
tinggi nilai kesopanan, tatakrama, sistem
kekerabatan yang kental, dan nilai
keagamaan/ religius yang tinggi. Sedangkan
perspektif barat memandang bahwa
perspektif timur memiliki pandangan yang
kurang rasional dan objektif. Hal tersebut
membuat kincaid memunculkan teori
budaya bandingan berasal dari timur,
dimana negara Cina, Jepang dan India
sebagai subjek penelitian. Jepang misalnya,
dengan mengedepankan nilai budaya
kearifan yang dimilikinya dapat membawa
budaya tersebut menjadi negara maju,
menjadi negara yang memiliki sistem politik
yang baik dimata global, serta budaya kerja
yang patut dicontoh.
Kita sebagai bangsa dari negara Asia
(non-western) juga harus mampu
menguatkan paham poskolonial, dimana
paham ini mengedepankan rasa/ kemauan
untuk menjadikan nilai budaya lokal bangsa
menjadi budaya global, terutama terhadap
budaya Barat, yang kita tahu bersama bahwa
budaya barat telah banyak menanamkan
hegemoni budayanya terhadap budaya
Timur.
Sebenarnya antara bangsa Timur dan
Barat sama-sama menganggap bahwa
pelayanan yang nyaman adalah, pelayanan
yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakatnya secara cepat, tidak
menyulitkan serta menenangkan hati/tidak
memberatkan. Namun dalam prosesnya,
bagi pandangan barat, pelayanan yang
nyaman adalah pelayanan yang serba mudah
dengan menggunakan fasilitas/ teknologi
yang super canggih agar semua dapat
terlaksana dengan otomatis, cepat, efektif
dan efisien. Namun pada pandangan bangsa
Timur aplikasi nilai kearifan yang berdasar
pada norma sangat penting dalam setiap
aspek kehidupan tidak terkecuali aspek
tindak pelayanan, pelayanan yang baik
dianggap pelayanan yang berasal dari hati,
sesuai dengan norma yang berlaku dan
mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan
saling menghormati, dalam hal ini peneliti
berasumsi bahwa pelayanan dari hati nurani
yang diungkapkan oleh Saleh sesuai untuk
menjadi acuan dalam menganalisis aspek
pelayanan di Sumenep.
Jika dihubungkan dengan nilai-nilai
kearifan local yang masih dijunjung tinggi
oleh masyarakat Madura yaitu nilai
keagamaan, maka seharusnya para aparat
juga harus mampu mengaplikasikan nilai
tersebut pada tindak pelayanan, karena
tindakan melayani apa yang dibutuhkan dan
di inginkan masyarakat jika dipenuhi dengan
rasa iklas akan menghasilkan kebaikan pula
pada diri kita sendiri atau aparat pelayanan
dan instansi itu sendiri, karena semua
tindakan dan apapun yang kita kerjakan
adalah semata-mata sebagai pengabdian
kepada Allah semata (Saleh, 2010, h. 199),
dengan kata lain tindakan melayani
masyarakat sama halnya berbuat baik
kepada sesama yang dapat menghasilkan
pahala dikehidupan akherat dan
menciptakan kebaikan pada kehidupan
bermasyarakat sebagai aplikasi tindak saling
menghormati/tatakrama dan saling
membantu antar manusia.
Sedangkan hasil observasi dan
wawancara yang dilakukan oleh peneliti
adalah, komunikasi yang kurang baik
(kurang sopan) dan sistem pelayanan yang
tidak tertib (RSUD). Serta kurangnya empati
-
Anis Fajrin, 0911220006. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya,
Malang
dari aparat pelayanan menjadi daftar negatif
bagi kinerja aparat pelayanan di RSUD dan
Polres yang tidak sesuai dengan makna nilai
kearifan lokal. Hal tersebut dapat dilihat dari
cara komunikasi aparat kepada masyarakat
yang masih terkesan kasar atau membentak,
maka hal tersebut dianggap tidak sesuai
dengan makna ungkapan/parebesan nilai
kearifan Sumenep yang berbunyi Asel ta adhina asal, yang menurut para aparat ungkapan ini memiliki arti bahwa sebagai
orang yang bertugas untuk melayani
masyarakat maka, tidak boleh lupa diri
(jangan mentang-mentang) sebagai seorang
aparat kita tidak boleh bertindak semena-
mena kepada masyarakat. Namun, tindakan
aparat pelayanan tersebut lebih sesuai
dengan ungkapan Tadhak Basana (tidak
perduli terhadap orang lain) sikap aparat
yang tidak perduli dengan perasaan
masyarakat pengguna jasa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan
aparat pelayanan, diketahui bahwa aparat
telah mengungkapkan beberapa parebhesan
yang dianggap baik dan dapat menjadi dasar
dari tindak pelayanan, namun berdasarkan
hasil observasi, ternyata diketahui
implementasi tindakan pelayanan tidak
sesuai dengan parebhesan yang menurut
para aparat dapat mewakili tindakannya
tersebut, namun tindakan pelayanan dari
aparat lebih menggambarkan parebhesan
yang mengandung makna negatif, hal ini
akan dijelaskan lebih dalam pada point
berikutnya.
Dari hasil waancara yang telah
dilakukan peneliti kepada
informan/masyarakat pengguna jasa
pelayanan, dapat disimpulkan bahwa
ungkapan yang berbunyi Bapak Babuk Guru Ratoh dianggap tidak sesuai dengan tindakan aparat karena masyarakat
menganggap aparat tidak dapat
menghormati dan mengaplikasikan sikap
saling menghormati kepada masyarakat atau
pengguna jasa. Walaupun masyarakat
merasa tidak nyaman dengan pelayanan
yang diberikan oleh aparat di RSUD namun
sebagian besar dari masyarakat memilih
bersikap cuek dan tidak terlalu memikirkan
hal tersebut karena merasa tidak memiliki
pilihan lain, karena kota Sumenep memang
hanya memiliki satu rumah sakit besar yaitu
RSUD H. Moh Anwar.
Begitu pula pelayanan yang diberikan
oleh pihak instansi DinKepCaPil dan RSUD
Walaupun aparat tidak menerapkan sistem
senyum, sapa, dan salam, masyarakat tetap
menilai tindakan pelayanan yang diterapkan
oleh aparat adalah hal biasa yang mereka
lihat selama ini dan tidak terlalu
mempermasalahkan. Walaupun dari hasil
data keluhan masyarakat di instansi
Dinkepcapil selama kurun waktu satu tahun
terakhir terdapat banyak masalah yang
masih dikeluhkan terkait dengan masalah
keterlambatan waktu pelayanan dengan
waktu yang telah ditentukan, pelayanan
yang sangat berbelit, adanya pungutan liar,
serta ketidak jelasan alur pelayanan. Namun
dari hasil wawancara peneliti dengan para
pengguna jasa, diketahui bahwa pelayanan
di Dinkepcapil ini telah mengalami
peningkatan yang cukup baik.
Sedangkan dari hasil observasi peneliti
ke instansi DinKepCaPil berkenaan dengan
penempatan sarana keluhan yang kurang
baik di instansi tersebut, hal ini menegaskan
bahwa ungkapan Bango jhubaa e ada etembang jhuba a e budi (lebih baik jelek di depan daripada jelek di belakang) hal
tersebut mencerminkan bahwa masyarakat
Madura tidak suka akan kemunafikan, hal
ini tidak sesuai dengan keadaan di instansi
DinKepCaPil. Aparat terlihat ingin dianggap
memiliki sarana keluhan yang memadai
dihadapan peneliti walau sebenarnya
keberadaan kotak saran pun tidak begitu
penting menurut mereka, hingga
penempatannya tidak strategis, bahkan pada
akhir-akhir ini kotak saran sudah tidak
digunakan lagi.
-
Anis Fajrin, 0911220006. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya,
Malang
Seperti yang terdapat pada makna
falsafah beberapa nilai kearifan lokal
mengenai nilai kekerabatan (tanian lanjang)
yang masih dijunjung tinggi oleh
masyarakat, seharusnya aparat dapat
menganggap semua masyarakat pengguna
jasa merupakan bagian dari keluarga dan
kerabat yang penting untuk diberikan
pelayanan yang istimewa, sehingga
pengaplikasian nilai kearifan lokal dalam
aspek pelayanan tidak pada jalur yang
kurang tepat. Namun, system kekerabatan
tersebut hanya berlaku pada sebagian
masyarakat yang memang aparat kenal dan
dianggap memiliki hubungan kerabat baik
sehingga memunculkan system tebang pilih.
Hal ini menimbulkan adanya kecenderunga
ketidak-adilan dalam pelayanan publik di
mana masyarakat yang tergolong miskin
akan sulit mendapatkan pelayanan.
Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki
uang, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan, contohnya yang ada
pada instansi Polres.
Pelayanan publik perlu dilihat sebagai
usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak
dasar masyarakat. Pelayanan publik masih
diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk
diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika
harus mengurus suatu perijinan tertentu
biaya yang tidak jelas, merupakan indikator
rendahnya kualitas pelayanan publik dari
aparat pelayanan di Polres. Nilai kearifan
lokal yang masyarakat anut dan diharapkan
menjadi dasar dalam tindakan pelayanan
belum dapat dirasakan, sehingga masyarakat
menganggap aparat Polres belum
menggunakannya sebagai dasar dari
tindakan pelayanan. Tidak sesuai dengan
anggapan bahwa orang atau masyarakat
Madura selalu menekankan bahwa mon oreng riya benni bagusse, tape tatakramana,
sanajjan bagus tapi tatakramana jube,ma celep ka ate (yang penting bukan ketampanan atau kecantikan, namun utama
tatakramanya). Dasar utama dari nilai-nilai
kesopanan adalah penghormatan orang
Madura kepada orang lain, terutama yang
lebih tua. Nilai-nilai kesopanan ini mengatur
hubunganan antargenerasi, kelamin, pangkat
dan posisi sosial. Maka aparat pelayanan di
Polres tidaklah mencerminkan hal tersebut
dan masyarakat tidak merasakan nilai
kearifan menjadi dasar dari tindakan aparat.
Hasil analisis disini mengemukakan
bahwa banyak keluhan yang di temukan
oleh peneliti berkenaan dengan
implementasi tindak pelayanan dari aparat
pemerintah. Mulai dari aspek empati, yaitu
cara komunikasi aparat yang terkesan sering
membentak dan bernada tinggi, seakan
membenarkan ungkapan nongkok basa yang
mencerminkan bahwa aparat pelayanan
tidak memiliki tatakrama pada saat
berbicara, sehingga yang memungkinkan
ungkapan Basa gamberenna budi akan
dilontarkan oleh masyarakat yang artinya,
dapat dilihat sifat seseorang dari cara
bicaranya. Banyaknya aparatur yang tidak
memandang efisiensi waktu dan biaya,
sehingga masyarakat banyak mengeluhkan
jika banyak waktu yang terbuang hanya
untuk menyelesaikan kepentingannya di
instansi pelayanan, hal itu juga dipengaruhi
suasana pelayanan yang kurang dirasa
nyaman oleh pengguna jasa, serta aspek
keadilan aparat dalam memberikan
pelayanan yang masyarakat nilai seharusnya
tidak begitu. Kesadaran petugas akan
memberikan pelayanan dengan sikap yang
sopan, adil, ikhlas, menyenangkan, dan
nyaman masih belum dapat dirasakan, agar
menghilangkan anggapan masyarakat akan
ungkapan tadhak basana yang bermakna
tidak perduli terhadap orang lain.
Berdasarkan pernyataan beberapa aparat
pelayanan yang dalam wawancara telah
menjawab dengan cukup jelas mengenai apa
itu pelayanan, dan bagaimana seharusnya
memberikan pelayanan, bahkan mereka juga
mengerti mengenai keikhlasan yang
seharusnya ada pada sikap pemberi
-
Anis Fajrin, 0911220006. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya,
Malang
pelayanan, ditambah lagi keikhlasan tersebut
merupakan sebagian dari nilai keagamaan
yang dijunjung tinggi oleh masyarakat
setempat. Namun masih banyak oknum
aparat pelayanan yang masih
mengaplikasikan sikap negatif dalam
memberikan pelayanan.
Hal ini disinyalir karena mereka
memiliki anggapan bahwa profesionalisme
bukan menjadi tujuan utama mereka.
Mereka mau melayani hanya karena tugas
dari pimpinan instansi yang jika dilihat dari
ungkapan bapak babuk guru rato pimpinan dapat diistilahkan sama dengan
rato sehingga kata-kata seorang pimpinan adalah petuah yang wajib untuk dijalankan
dengan adanya rasa penghormatan yang
begitu tinggi pada seorang pimpinan atau
atasan, dan bukan karena tuntutan
profesionalisme kerja, ini yang membuat
keberpihakannya kepada masyarakat
menjadi sangat rendah. Aparat akan bersikap
ramah kepada masyarakat pengguna layanan
hanya jika ada sesuatu yang memberikan
keuntungan atau melatar belakanginya,
seperti hubungan pertemanan, hubungan
kekerabatan yang sesuai dengan nilai-nilai
yang juga dijunjung tinggi oleh masyarakat
Sumenep, serta mereka yang
mempunyai status sosial terpandang
dimasyarakat biasanya juga akan
memperoleh perlakuan khusus dari para
aparat pelayan publik, misalnya saja tokoh
agama. Jika dilihat sekilas ini memang
buruk, namun bagi masyarakat Madura, hal
ini danggap wajar, karena mengandung asas
kehormatan atau yang sering disebut oleh
masyarakat Madura dengan Cangkolang masyarakat bahkan percaya jika kita dapat
mengutamakan tokoh agama (seseorang
yang dekat dengan Tuhan) maka Tuhan pun
akan memberikan keberkahannya untuk kita.
Serta adanya sistem tebang pilih
dibeberapa instansi pemerintah yang ditemui
oleh peneliti, hal ini dapat dilihat dari
konsep penting yang berkaitan dengan relasi
sosial yang dibangun oleh orang Madura
yaitu teman (bhala, kanca). Menurut Wiyata
(2013, h. 18) Konsep teman tersebut
merujuk pada relasi sosial dengan derajat
keakraban pada taraf tertentu hingga ke
derajat paling tinggi, dengan kata lain
kehidupan harmonis muncul karena
dominasi semangat pertemanan. Menurut
orang Madura, bhala selain merujuk pada
pengertian teman juga merujuk pada orang
yang mempunyai hubungan kekerabatan.
Sistem kekerabatan masyarakat Madura
sangat kuat, tindakan baik akan dibalas
dengan yang lebih baik, apabila kita mampu
menjaga harga diri orang tersebut maka
orang itu akan dapat lebih menghormati kita.
Hal ini tentu berpengaruh pada tindak
layanan pada aparat pelayanan, sikap aparat
yang masih menganut tebang pilih,
kemungkinan hal tersebut terpengaruh oleh
nilai-nilai kekerabatan tersebut. Sehingga
hal itu mempengaruhi tindakan aparat
kepada masyarakat yang dianggap memiliki
hubungan kekerabatan atau dikenal baik
oleh aparat maka, akan diistimewakan dalam
melayani. Seharusnya apabila hal ini
diluruskan, maka sistem kekerabatan yang
dianut oleh aparat dapat berlaku pada semua
masyarakat tanpa terkecuali, dengan cara
melihat atau menganggap semua masyarakat
yang hidup dengan kebudayaan yang sama
adalah kerabat, bukan hanya untuk
masyarakat tertentu saja yang dianggap
kenal atau benar-benar kerabat, sehingga
tidak akan muncul sistem tebang pilih.
Kesimpulan
Dari hasil analisis ditemukan bahwa
sistem pelayanan yang diterapkan oleh
instansi pelayanan Sumenep masih sedikit
mengandung perspektif barat, hal itu dapat
dilihat dari segi sarana keluhan (kotak
pengukuran kepuasan, prosedur penanganan
keluhan, divi yang diperuntukkan
menangani keluhan) walaupun
penerapannya masih sangat tidak maksimal.
-
Anis Fajrin, 0911220006. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya,
Malang
Serta pembenahan SOP yang dinyatakan
oleh beberapa aparat walaupun tidak secara
berkala, dan lain sebagainya. Sedangkan
dari sisi nilai kearifan yang dipandang
sebagai perspektif Timur, pihak instansi
pelayanan juga telah menerapkan unsur
tersebut, hal ini dapat dilihat dari cara aparat
dalam melayani masyarat. Misalnya aparat
lebih mengedepankan unsur kekerabatan
walaupun implikasinya adalah sistem tebang
pilih. Serta ungkapan/ parebhesan yang
sesuai dengan tindakan pelayanan tersebut
walaupun parebhesan yang bermakna
negatif. Serta adanya nilai ungkapan bapak,
babuk, guru, ratoh yang teraplikasi secara
negatif.
Maka pelayanan yang baik dan sesuai
dengan nilai kearifan lokal dan norma-
norma yang berlaku di masyarakat Sumenep
adalah
1) pelayanan yang menyenangkan, masyarakat berharap aparat pelayanan
lebih bersikap ramah dengan
menampakkan senyuman yang ikhlas.
Aparat pelayanan diharapakan mampu
bersikap saling menghormati tidak
mentang-mentang dan berkomunikasi
yang sopan.
2) Pelayanan yang adil, diharapakan aparat tetap mengedepankan nilai kekerabatan,
namun pengaplikasiannya agar lebih
terarah, jadi tidak hanya sebagian orang
saja yang dianggap kerabat namun semua
masyarakat yang datang membutuhkan
pelayanan harus dilayani sebaik mungkin
dianggap sebagai kerabat, sehingga tidak
ada lagi sistem tebang pilih.
3) Pelayanan yang tidak memberatkan, diharapkan menerapkan sistem pelayanan
yang berpihak pada masyarakat. Aparat
pelayanan harus mampu memposisikan
sebagai masyarakat yang membutuhkan
sehingga aparat dapat merasakan apa yang
masyarakat inginkan, apabila ada hal-hal
yang dirasa memberatkan baik dari sisi
biaya maupun dari segi waktu, maka harus
ada pembenahan.
4) Pelayanan yang mendasar pada hati, apabila aparat telah mampu mendasarkan
tindakannya pada hati nurani maka,
dengan sendirinya rasa ikhlas akan
tumbuh, apabila aparat mendasarkan
tindakannya dengan keikhlasan maka
komitmen pelayanan dengan wujud
keimanan akan terealisasi sesuai dengan
nilai yang selama ini dijunjung tinggi oleh
masyarakat Sumenep.
Daftar Pustaka
Christians, C., & Faber, M. (1997).
Communication Ethics and Universal Value.
London : New Delhi.
Kincaid, L. (1987). Communication Theory
Eastern and Western Perspective. Albany
New York : Academic Press, INC.
Kuntowijoyo. (1993). Paradigma Islam:
Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan.
Kuswarno, E. (2008). Etnografi Komunikasi.
Bandung :Widya Padjadjaran
Kriyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset
Komunikasi. Jakarta : PT Kencana Prenada
Media Group.
Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman.
(2005). The Ethics Challenge in Public
Service: A Problem-Solving Guide. Market
Street, San Fransisco:Jossey-Bass.
Liliweri, A. (2007). Dasar-Dasar
Komunikasi Antarbudaya. Jogjakarta:
Pustaka Pelajar.
Littlejohn, S. W. (2002). Theories Of Human
Communication (7th
ed). Beltmont : CA.
Wadsworth.
Muakmam. (2005). Lalonget Ban Oca Keyasan. Pamekasan : Yayasan Pelestarian
dan Penembangan Bahasa dan Sastra.
Neuman, L. (2000). Social Research
Methods (4th
ed). USA : A Pearson
Education Company.
Pudentia. (2003). Antologi Prosa Rakyat
Melayu Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
-
Anis Fajrin, 0911220006. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya,
Malang
Saleh, A. M. (2010). Public Service
Communication. Malang : UMM Press.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian
Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung:
Alfabeta.
West, R & Turner, L. (2008). Pengantar
Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi (3th
ed). Jakarta : Salemba Humanika.
Wiyata, L. (2013). Mencari Madura. Jakarta
: Bidik-Phronesisi Publishing.
Jurnal
Rachmadiana, M. (2004). MENCIUM
TANGAN, MEMBUNGKUKKAN BADAN
Etos Budaya Sunda, Yogyakarta, Madura.
Humanitas : Indonesian Psychologycal
Journal. Fakultas Psikologi Universitas
Ahmad Dahlan, Vol.1 No.2, hal34-35
Rahardjo, T. (2013). Konstruksi Teori
Komunikasi Berbasis Kearifan Lokal. FISIP
Universitas Diponegoro. vol.1 No.1, Hal75
Tulistyantoro, L. (2005). Makna Ruang
Pada Tanean Lanjang Di Madura. Dosen
Fakultas Seni dan Desain, Jurusan Desain
Interior Universitas Kristen Petra Surabaya.
Vol 3, No 2
Wismantara, P. Pratitis. (2009). Politik
Ruang Gender Pada Pemukiman Tanian
Lanjhang Sumenep. UIN Malang. Vol.4
No.2.