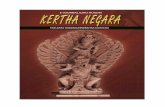Jurnal Humaniora, Vol II, No. 1, Maret 2014
Transcript of Jurnal Humaniora, Vol II, No. 1, Maret 2014
Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014ISSN 2302-5719
Vol II, Nomor 1
Ultima Humaniora merupakan gabungan dua konsep kunci yaitu Ultima yang berarti “dalam, berbo-bot, bernilai”, dan Humaniora (Latin) yang berarti “ilmu-ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya.” Secara umum, yang tergolong dalam rumpun ilmu humaniora adalah: Teologi, Filsafat, Hukum, Sejarah, Filologi, Bahasa, Budaya & Linguistik (Kajian bahasa), Kesusastraan, Kesenian, dan Psikologi. Jurnal Ultima Humaniora merupakan jurnal ilmiah interdisipliner yang menghimpun gagasan, dan riset terkini di bidang Pancasila, kewarganegaraan, religiositas (agama), bahasa Indonesia, bahasa Inggris sebagai bahasa asing (EFL), pengembangan metode belajar serta mengajar yang efektif di Perguruan Tinggi, kepemimpinan dan kewirausahaan. Jurnal ini diterbitkan Universitas Multimedia Nusantara, di bawah kordinasi Departemen Mata Kuliah Umum (MKU), secara semi-annual atau dua kali dalam seta-hun, yaitu pada Maret dan September.Redaksi mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan siapapun yang berminat untuk menyum-bangkan tulisan mengenai topik umum rumpun ilmu humaniora maupun topik khusus Jurnal Ultima Humaniora. Artikel yang dimuat dalam Jurnal Ultima Humaniora tidak selalu mencerminkan pandang-an/pendapat redaksi.
SUSUNAN REDAKSI Pelindung : Dr. Ninok LeksonoPenanggungjawab : Hira Meidia, Ph. D.Pemimpin Umum : Dr. Ir. P. M. Winarno, M. Kom.Mitra Bestari : Dr. Max Lane (College of Arts, Victoria University, Australia) Dominggus Elcid Li, Ph. D. (Founding Executive Director of Institute of
Resources Governance & Social Change) Samsul Maarif Mujiharto (Ph. D. Candidate, Charles Sturt University,
Australia) Dr. Otto Gusti Madung (STFK Ledalero, Maumere, Flores) Ketua Dewan Redaksi : Hendar Putranto, M. Hum.Dewan Redaksi : Niknik Kuntarto, M. Hum., Johannes Langgar Billy, M. M., M. V. Santi Hendrawati, M. Hum., Qusthan Firdaus, M. A.Tata Usaha : Canggih G. Farunik, M. Fil., Alexander Aur, M. Hum.Sirkulasi dan Distribusi : SularminKeuangan : I Made Gede Suteja, S. E., Regina Fika , S. E.
Alamat Redaksi Jurnal Ultima Humaniora:UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA (UMN)Gedung Rektorat Lantai 3 Jalan Boulevard Gading Serpong, Desa Curug Sangereng, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15333Telp + 6221 5422 0808 ext. 3622; Faks: (021) 5422 0800
00-daftarisi.indd 1 4/24/2014 7:12:46 AM
ii Daftar Isi VOL II, 2014
Pengantar Redaksi ........................................................................................................... iii
Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi ADITYA PERMANA ................................................................................................. 1
Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos YOGIE PRANOWO .................................................................................................. 14
A Platonian Democracy QUSTHAN FIRDAUS ............................................................................................... 30
Pemilu 2014: Kartelisasi Elite Versus Representasi Publik WASISTO RAHARJO JATI ....................................................................................... 45
Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara JOHANES SUPRIYONO .......................................................................................... 59
Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama:Memotret Deliberasi Politik Berbasis Agama di Indonesia dengan Perspektif Filsafat Politik Jürgen Habermas ALEXANDER AUR ................................................................................................... 79
Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia:Sebuah Kritik terhadap Artikel “Chilean Socialism 1: Indonesian Facism 0” CANGGIH GUMANKY FARUNIK ....................................................................... 98
Pancasila sebagai Etika Politik di Indonesia SURAJIYO ................................................................................................................. 111
Kekerasan Media: Kapitalisme, Industri Hiburan, dan Masyarakat Tontonan EKA NADA SHOFA ALKHAJAR ........................................................................... 124
[Resensi Buku]Bukan Sekedar Biografi: Menyelami Sisi Humanis Driyarkara JUMAR SLAMET ....................................................................................................... 132
DAFTAR ISIVolume II, Nomor 1
00-daftarisi.indd 2 4/24/2014 7:12:46 AM
Pengantar Redaksi iii
Salam kemanusiaan!
Sidang pembaca yang budiman, mari kita cermati daftar kegiatan politisi berikut ini1:
1. Blusukan ke pasar tradisional, 2. Kandidat presiden, CDE, makan di angkringan Tanah Abang,3. HIJ menuju kampus sebuah universitas di Depok dengan menumpang kereta rel lis-
trik Commuter Line,4. Seorang Ketua Umum Partai, MNO, mengunjungi korban banjir di Kalibata, JakSel,
guna menyerahkan bantuan untuk para korban banjir serta berdialog dengan war-ga,
5. Seorang anggota legislatif, XYZ, memilih bermalam di rumah warga miskin milik ABC, buruh tani berusia 69 tahun, ketimbang di hotel yang nyaman.
6. Dengan menumpang ojek untuk sampai ke lokasi panen raya, seorang calon presiden dari partai GHI, bernama RST, disambut antusias ribuan petani dan warga sekitar yang ingin bersalaman dan menyapanya.
Daftar tersebut di atas masih bisa ditambahi sampai mata kita berair membacanya.
Pertanyaannya, inikah wajah “sejati” politik di Indonesia sebagaimana dilakoni para elit-nya? Apa pesan yang bisa kita tangkap di sana? Bahwa tindakan politis bukanlah seke-dar umbar gagasan, dan tarung wacana namun juga pandai beraksi di depan kamera guna merebut simpati rakyat, dan menaikkan citra serta elektabilitas?
“Politik kita adalah politik pencitraan. Kita punya tugas, bagaimana wacana tidak sekadar wacana kamera. (Bagaimana) Dia punya isi. Saya kira substansinya ada di situ. Bagaimana nasionalisme dalam arus politik kamera bisa dilakukan dengan konkret,” demikian ditegaskan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampouw, dalam diskusi bertajuk “Nasionalisme di Tengah Krisis Kepemimpinan”, di Cikini, Ja-karta Pusat, Minggu (18 Agustus 2013) seperti dilaporkan oleh beritasatu.com (http://www.beritasatu.com/pemilu-2014/132392-pemilih-harus-bisa-ambil-bagian-di-tengah-politik-pencitraan.html)
KATA PENGANTAR
1 Dikutipdengansedikitmodifikasidanpenyederhanaandarihttp://politik.kompasiana.com/2012/05/13/kamus-politik-pencitra-an-indonesia-456901.html.Demialasankesantunandanmenjaganamabaik,politikusyangdijadikancontohdalampemeriansingkatinisengajadisamarkan.
00-daftarisi.indd3 4/24/2014 7:12:46 AM
iv Pengantar Redaksi VOL II, 2014
Dalam bukunya Transpolitika: Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas (2005), Yasraf Amir Piliang meratapi hilangnya gaung perdebatan ideologi yang berkelas yang men-jadi ciri khas ranah politik (political realm) di awal abad ke-20. Alih-alih bertarung secara ideologis dengan argumentasi-argumentasi yang ketat dan jernih, dipayungi visi agung masyarakat serta negara yang mau dibangun, para politisi kita justru menguatkan soal citra dan pencitraan dalam ranah politik kontemporer Indonesia pasca reformasi. Ketika pragmatisme politik sudah mendaulat diri dengan “jatah” kursi dan jatah “menteri” yang diperebutkan, dan diskursus politik tidak lebih dari sekedar perhelatan transaksio nal seperti dagang sapi, tidaklah mengherankan jika pola-pola komunikasi elit politik pun mengalami pergeseran yang cukup signifikan, untuk tidak mengatakan “dekadensi”.
Hadi Saputra (dalam http://www.hadi-saputra.com/2011/10/gizi-buruk-politik-citra.html) dengan cerdas merangkum fenomena politik pencitraan itu sebagai berikut, “Ko-munikasi politik elite lebih menggunakan strategi komunikasi politik berorientasi massa (mass political communication), yang bersifat emosional ketimbang menggunakan strategi komunikasi politik yang berorientasi warga (civil political communication) yang lebih ra-sional. Karena itulah politik di era mediasi menggunakan trik, manajemen, dan bahkan manipulasi citra untuk membentuk persepsi publik atas suatu isu. Iklan politik lebih berorientasi citra (image-oriented), daripada berorientasi persoalan (issue oriented). Citra lebih penting dari substansi. Citra telah menggantikan pengalaman dan wacana sebagai cara untuk memahami dunia sosial. Kini kita hidup dalam dunia citra yang spektakuler dan menakjubkan.”
Dalam rangka menyambut, dan mempersiapkan perhelatan demokrasi terbesar yaitu Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 dan Pemilu untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014, Jurnal Ultima Humaniora edisi ketiga (Vol. II, No. 1, Maret 2014), mengangkat tema besar “Politik Pencitraan dan PEMILU: Multiplisitas Perspektif” dengan menyajikan sepuluh naskah berbobot berikut ini. Enam naskah pertama meru-pakan makalah yang mengupas tema utama jurnal. Tiga naskah berikutnya merupakan makalah non-tematis. Tulisan yang dijadikan penutup jurnal kali ini merupakan resensi buku.
Pemilu sebagai “pencitraan demokrasi” dan metode serta siasat menghadapinya ...Tulisan pertama berjudul “Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Wa-tak Totaliter dalam Demokrasi” disumbangkan oleh Aditya Permana. Dalam tulisan ini, Aditya menguraikan pandangan bahwa di dalam masyarakat demokrasi, pencitraan to-koh politik diwujudkan dalam politik praktis yang menonjolkan aspek figural, dan cen-derung abai pada prestasi yang jelas. Pencitraan melalui simulasi tanda (model Baudril-lard) dilakukan karena bentuk-bentuk kebijakan represif dan totaliter à la Machiavelli sudah tidak mungkin lagi diterapkan dalam masyarakat “demokrasi” kontemporer. De-ngan menggunakan alur pemikiran Claude Lefort, Aditya berargumen bahwa ba ngunan demokrasi yang bertumpu pada aspek pencitraan ketokohan tak lain merupakan pe-rubahan bentuk (mutasi) dari totalitarianisme yang menjadi watak zaman monarkis, dan hal ini tidak patut dipertahankan.
00-daftarisi.indd 4 4/24/2014 7:12:46 AM
Pengantar Redaksi v
Tulisan kedua yang disajikan Yogie Pranowo, “Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos”, secara cerdik mengangkat kembali pemikiran filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche, lewat genealogi moralnya yang berlandaskan pada argumentum ad hominem. Yogie secara imajinatif meminjam pemikiran Nietzsche untuk “menasehati” kita para calon pencoblos di Pemilu 2014 agar mampu menilai kualitas para calon pemimpin Indonesia dengan tepat lewat metode ad hominem yang memiliki peran sentral dalam genealogi moral Nietzsche, yakni sebagai metode un-tuk mendiagnosis pandangan manusia terhadap realitas secara lebih mendalam. Lewat metode ad hominem Nietzsche, kita diingatkan bahwa tak selamanya seorang calon pe-mimpin yang terlihat mengumbar janji, atau yang terlihat baik, pada dasarnya sungguh orang baik, sebab seringkali apa yang tertangkap indera adalah tipuan, dan karena itu, perlu dilampaui.
“Pesta demokrasi”: dalam tegangan antara yang ideal dan yang faktual...“A Platonian Democracy” yang ditulis Qusthan Abqary merupakan tulisan ketiga yang mengajak sidang pembaca untuk kembali menengok ke belakang guna menemukan harta kekayaan intelektual dari khazanah Yunani klasik. Qusthan mengusulkan revisi terhadap praktik demokrasi di Indonesia, dengan menggunakan kritik Plato terhadap demokrasi dan rekomendasinya terhadap filosof-pemimpin, sebagai landasan teoritis bagi upaya untuk merevisi praktik demokrasi, khususnya untuk memilih calon pre siden di Indonesia. Jika kritik Plato terhadap demokrasi, dan mekanisme perekrutan 12 calon pemimpin nasional dapat dijustifikasi, maka sebuah demokrasi model Plato barangkali dapat diterima serta dipraktikkan secara realistis. Dengan kata lain, kritik Plato justru dapat digunakan secara konstruktif untuk membangun serta mengembangkan demokra-si di Indonesia.
Wasisto Raharjo Jati dalam makalahnya “Pemilu 2014: Kartelisasi Elite versus Rep-resentasi Publik” mendaratkan kita, para pembaca, pada konteks, dan kekinian Pemilu di Indonesia yang historis – komparatif. Dengan menggunakan data dan analisis Pemilu 2004 dan 2009 yang disampaikan dalam bentuk tabel, Wasisto mencelikkan mata kita bahwa Pemilu 2014 kali ini bisa jadi merupakan kontinuitas dari pola oligarkis yang su-dah melembaga, dan mengurat-akar, namun bisa juga menjadi momentum publik untuk memperbaiki demokrasi. Pemilu di Indonesia, dalam sejarahnya, terutama sejak dimu-lainya era Reformasi, sudah senantiasa meletak sebagai pesta demokrasi yang dilematis antara pertarungan kuasa representasi dengan elite. Menurutnya, Pemilu 2014 menjadi determinan utama untuk mengukur tingkat kecerdasan publik maupun juga mengukur memudarnya elitisme dalam ranah publik sebagai demos.
Yang terserak dan termarjinalkan dari “Pesta Demokrasi” ... Dua tulisan utama berikutnya, Supriyono dengan “Diskursus Kolonialistik dalam Pem-bangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara” dan Alex Aur dengan “Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama: Memotret Deliberasi Politik Berbasis Agama di Indonesia dengan Perspektif Filsafat Politik Jürgen Habermas” membawa kita pada tegangan yang tidak mudah dengan dua klaim sejarah pembentukan nasib sekali-
00-daftarisi.indd5 4/24/2014 7:12:46 AM
vi Pengantar Redaksi VOL II, 2014
gus identitas negara-bangsa Indonesia yang sarat akan manipulasi, dan konflik ideologis maupun pertempuran berdarah.
Tulisan Supriyono mempersoalkan klaim “pembangunan di Papua” oleh pemerin-tah Indonesia yang nyatanya malah membuat orang-orang Papua mengalami praktik peminggiran, dan diskriminasi secara sistematis lewat tangan militer, dan muslihat meja perundingan. Bagi orang Papua, pembangunan didapati sebagai sebuah paradoks. Alih-alih mendudukkan mereka di pusat proses, orang Papua justru berada di pinggir are-na. Cita-cita mulia “pembangunan sebagai pemberadaban” justru dialami orang Papua menjadi “perusakan sebagai dalih pe-liyan-an identitas, dan perampasan hak untuk me-nentukan nasib sendiri.”
Sementara itu, tulisan Alex Aur mengupas secara jernih gejala eskalasi konflik antara agama dengan negara hukum demokratis yang urat-akarnya (ternyata!) sudah terpan-cang sejak deliberasi awal dari para bapak pendiri bangsa, utamanya menjelang penge-sahan UUD 1945, yang, atas prakarsa Muhammad Hatta, menghapuskan frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dari sila pertama Pancasila dan juga selama rezim Orde Baru yang menerapkan depolitisasi, dan deideologisasi agama sebagai rekayasa politik untuk melemahkan peran politik agama. Alex Aur menyaran-kan agar pengandaian-pengandaian metafisik agama harus diuji dengan rasio sekuler, supaya agama tidak menjadi horor sekaligus teror bagi negara hukum demokratis.
Membandingkan “Pesta Demokrasi”: Persona Pemimpin dan Pancasila sebagai Etika Politik... Canggih G. Farunik dalam makalahnya “Peran Media dalam Membangun Persona Pe-mimpin di Indonesia: Sebuah Kritik terhadap Artikel ‘Chilean Socialism 1: Indonesian Facism 0’” mencoba membandingkan Soeharto dan Pinochet sebagai tokoh pemimpin kharismatis Indonesia dan Chili dari masa lalu, dengan segala kelebihan dan kekurang-annya. Dengan bertolak dari kritik terhadap artikel yang ditulis Andre Vltchek, yang menyebutkan bahwa rakyat Indonesia semata-mata bodoh, dan tidak peduli terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Soeharto, hal mana tidak sepenuhnya benar, Canggih membangun analisisnya. Menurutnya, kemampuan Soeharto dalam menampil-kan persona yang berbeda dari pandangan seorang fasis serta kuatnya pencitraan yang dilakukan olehnya dan tim suksesnya, berhasil menggiring pandangan umum bahwa sistem Soeharto masih tetap bertahan, meskipun ia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden Indonesia. Hasil pencitraan Soeharto sebagai seorang pahlawan bangsa yang tegas namun tetap merakyat membuatnya dianggap lebih layak oleh rakyat Indonesia ketika itu, daripada seorang pemimpin yang demokratis, untuk memimpin bangsa In-donesia menuju tahap kemajuan, dan kesejahteraan yang sulit diulangi oleh penerusnya.
Meskipun tidak bisa dikatakan membahas Pemilu 2014 atau politik pencitraan secara langsung, makalah Surajiyo “Pancasila sebagai Etika Politik di Indonesia” dapat dilihat sebagai penjangkaran politik di Indonesia dalam dasar filosofis dan ideologi resmi NKRI, yaitu Pancasila. Tentu Pancasila di sini tidak melulu dilihat secara normatif ideal, namun lebih sebagai etika politik yang lebih praktis, yang menuntut agar kekuasaan dalam ne-
00-daftarisi.indd 6 4/24/2014 7:12:46 AM
Pengantar Redaksi vii
gara dijalankan sesuai dengan: asas legalitas, disahkan, dan dijalankan secara demokra-tis, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral.
Yang tersirat dari “Pesta Demokrasi”: Kekerasan Media dan Penyelamatan Republik Tercinta... Eka Nada Shofa Alkhajar dalam tulisannya yang berjudul “Kekerasan Media: Kapitalis-me, Industri Hiburan, dan Masyarakat Tontonan” mewanti-wanti akan bahaya pendang-kalan kemanusiaan yang terpapar lewat tayangan bermuatan kekerasan di media cetak, terlebih elektronik. Eka menyarankan agar para pelaku media harus mahir berikhtiar untuk berhenti menampilkan kekerasan baik di tayangan televisi maupun film meng-ingat keburukan-keburukannya terhadap pembentukan karakter bangsa, khususnya anak-anak dan generasi muda.
Jumar Slamet dengan resensi buku “Driyarkara Si Jenthu: Napak Tilas Filsuf Pendi-dik (1913-1967)” mengingatkan kita akan pentingnya role model dalam hal berpikir, ber-politik dan bernegara. Krisis panutan tokoh dan kepemimpinan yang dialami Indonesia pasca-lengsernya rezim Soeharto dan Orde Baru bisa saja diselamatkan jika kita mau mengamini bersama Romo Driyarkara bahwa meskipun “Republik Indonesia dapat dile-nyapkan, dikuasai, atau dijadikan apapun, akan tetapi Republik sebagai semangat masi-hlah tetap, dan akan terus melahirkan diri lagi demi negara yang merdeka.”
Akhirul kata membalut frasa, selamat membaca, merenung, dan berpesta demokra-si!
Medio April 2014,
Hendar Putranto, M. Hum.Ketua Dewan Redaksi
00-daftarisi.indd 7 4/24/2014 7:12:46 AM
Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, hal 1-13ISSN 2302-5719
Vol II, Nomor 1
Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi
ADITYA PERMANA
Dosen Tidak Tetap di Universitas Bina Nusantara dan Surya UniversitySurel: [email protected]
Diterima: 27 Februari 2014Disetujui: 27 Maret 2014
ABSTRACT
Claude Lefort (1924-2010) stated that the relation among the “ruler” and the “ruled”, be it totalitarianism or democratic society, originated from an institutionalized conflict. This ontological conflict, or “the politi-cal”, is exactly the condition of possibility or the ontological ground for the being of society and the politics itself. Through Lacanian insight, Lefort stated that democracy is a mutation or change of form of society that happened in symbolic level. But this mutation tends to be merely a shift in singularity of power from the monarch to the people. Consequently, democracy still inherits totalitarian characters. These characters reserve a big risk. In the context of political imaging implemented by current politicians, mutation of sym-bolic level in mechanism of exercise of power in democracy is instead reserving the risk of society’s disinte-gration. The reason behind this is that democracy exercises the logic of otherization which tends to divide and categorize one as either on the inside or outside a certain identity displayed as quasi-representation of people.
Keywords: democracy, totalitarian, (political) imaging, “the political”, mutation, symbolic level
“For if politics was identified with evil and tyranny and understood in opposition to philosophy’s concern with the good and moral reasoning,
then reason itself would have no actuality within human co-existence, it would be enclosed ‘within nihilistic moralism’.”
(Paul Ricoeur, “The Political Paradox”, 1965: 249)
PendahuluanIstilah “pencitraan” dalam dunia politik merujuk pada adanya kesenjangan antara apa yang ditampakkan oleh seorang poli-tikus, dan apa yang sebenarnya dia laku-kan (atau tidak dia lakukan). Pencitraan diri dibutuhkan untuk memberikan kesan yang mendorong orang-orang untuk mem-percayai apa yang ditampilkan. Dalam
pemikiran seorang realis politik abad-16, Niccolò Machiavelli merekomendasikan bahwa seorang pangeran (il Principe) atau pe nguasa perlu menggunakan virtù-nya untuk memperoleh kekuasaan, dan me-ngetahui bagaimana cara paling efektif dalam mempertahankannya – meskipun itu ber arti harus memelintir agama, mo-ralitas, atau bahkan menggunakan cara-
001-[Aditya Permana] Pencitraan dalam Dunia Politik.indd 1 4/24/2014 7:48:25 AM
2 Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi VOL II, 2014
cara represif sebagai instrumennya. Bagi Machiavelli, yang terpenting bukanlah kualitas pribadi sang penguasa – meski jika memiliki kuali tas-kualitas kardinal lebih diutamakan – melainkan bagaimana cara pe nguasa “menampakkan dirinya” (Ma-chiavelli, 1961: 101). Pada masa kontempo-rer, Jean Baudrillard mempertajam kritik tentang pencitraan dengan mengajukan konsep simulacrum, yakni citraan-citraan (images) yang dianggap sebagai realitas, meski tidak memiliki acuan pada reali-tas itu sendiri. Dalam simulacrum, yang dipenting kan dalam pencitra an adalah citraan itu sendiri, kemasan, kulit, bung-kus, atau medium pesannya, sedangkan isi pesan dikaburkan, digelapkan, dibelok-kan, ditutupi secara luar biasa atau bahkan diabaikan (Baudrillard, 1983: 32). Dengan demikian, makna kata “pencitraan” seolah menjadi identik dengan “rekayasa” (mani-pulation) atau “pengaburan” (obscurity).
Rakyat Indonesia tentu tidak hidup dalam zaman monarki seperti masa hid-up Machiavelli. Namun mentalitas “de-mokrasi” yang diterapkan di Indonesia tampaknya masih sukar diceraikan den-gan ketergantungan pada kepemimpinan kharismatik – atau bahkan mitos Ratu Adil warisan zaman kerajaan monarkistik; serta ditambah dengan belum berjalannya exercise of power secara efisien, tertib, dan rasional. Tulisan sederhana ini akan mem-bahas aspek pencitraan tokoh-tokoh poli-tik tersebut dalam kaitannya dengan relasi antara penguasa dan yang dikuasai dalam masyarakat demokratis. Dalam masyara-kat demokrasi, pencitraan itu sendiri diwu-judkan atau ditubuhkan (embodied) dalam politik praktis yang menonjolkan aspek figural, dan cenderung abai pada prestasi yang jelas. Pencitraan melalui simulasi tan-da – dalam pengertian model Baudrillard – dilakukan karena bentuk-bentuk kebijakan represif dan totaliter seperti dibayangkan dan di sarankan Machiavelli sudah tidak
mungkin lagi diterapkan dalam masyara-kat “demokrasi” dewasa ini. Namun penu-lis akan berargumentasi bahwa demokrasi yang bertumpu pada aspek pencitraan ke-tokohan tak lain merupakan perubahan bentuk (mutasi) dari totalitarianisme yang menjadi watak zaman monarkis. Penulis akan menyoroti permasalahan ini dengan menggunakan pemikiran Claude Lefort (1924-2010), seorang pemikir politik dan sosiolog Prancis kontemporer.
1. Kelupaan akan “Yang Politis” (The Political [le politique])
Pemikiran Lefort mengenai demokrasi ti-dak dapat dipisahkan dari gagasannya ten-tang pembedaan antara “politik” (politics [la politique]) dan “yang politis” (the political [le politique]). Pembedaan antara “politik” dan “yang politis” pertama kali muncul ta-hun 1956 melalui tulisan Paul Ricoeur, “The Political Paradox”.
“If politics refers to the use of power (the struggle to found and preserve a political association and make decisions on behalf of all), for Ricoeur the po-litical refers to the self-representation of the polity as a rational association of free and equal members. Since the political only emerges through politics, conversely, this gives rise to a paradox: ‘the greatest evil adheres to the greatest rationality’” (Ricoeur dalam Schaap, 2013: 2).
Paradoks ini menjadi locus pembedaan antara dua “ranah” tersebut. Pemikiran Lefort mengenai “yang politis” juga be-rada dalam tegangan paradoks ini. Apa itu “yang politis” bagi Lefort? Untuk mu-dahnya kita simak penafsiran Steinmetz-Jenkins berikut,
“The political (le politique) became the popular term to describe the notion of a symbolic form that institutes society but is yet not equivalent with so-ciety itself…[…] The political for Lefort is the form and means of societal institution. Put differently, the political is the flesh of the world that simulta-neously appears and is occulted” (Steinmetz-Jen-kins, 2009: 102-105).
001-[Aditya Permana] Pencitraan dalam Dunia Politik.indd 2 4/24/2014 7:48:25 AM
Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi ADITYA PERMANA 3
Bagaimana memahami maksud Stein-metz-Jenkins bahwa Lefort mengatakan “yang politis” merupakan bentuk simbolis yang menyusun masyarakat namun tidak ekuivalen dengan masyarakat itu sendiri? Untuk memahami maksud Lefort tentang “yang politis”, kita dapat mengingat kem-bali ide pemisahan antara sains politik (il-mu-ilmu partikular yang mengkaji tentang politik) dan filsafat politik. Menurutnya, untuk menafsirkan apa itu “yang politis” kita mesti memisahkan diri dengan sudut pandang umum sekaligus memisahkan diri dari sains politik dan sosiologi politik (Lefort, 1988: 11). Sains politik tidak dapat melihat perbedaan antara politik dan “yang politis” oleh karena “hasrat objekti-vitasnya” (Lefort, 1988: 12).
Lefort mendaku bahwa hasrat akan objektivitas membuat seorang ilmuwan politik melakukan pemisahan (separation) antara “subjek yang mengkaji” dan “ob-jek yang dikaji” agar netral, serta meng-hindari penilaian (judgment) dan sekedar pendapat (mere opinion). Namun risikonya si ilmuwan terpisah (detached) atau berjarak dari kehidupan sosial yang nyata. Sesuai tafsiran Marchart, bagi Lefort “ideologi” saintifik mustahil menjaga netralitas kare-na objek itu sendiri sudah dilekati makna (Marchart, 2007: 87). Lefort mengatakan bahwa dengan bersikap objektif dan netral, ideologi sains secara sistematis
“…deprives the subject of the means to grasp an experience generated and ordered by an implicit conception of the relations between human beings and of their relations with the world. It prevents the subject from grasping the one thing that has been grasped in every human society, the one thing that gives it its status as human society: namely the difference between legitimacy and illegitimacy, between truth and lies, between authenticity and imposture, between the pursuit of power or of pri-vate interests and the pursuit of the common good.” (Lefort, 1988: 12).
Di lain pihak, filsafat memang ber-pendapat bahwa subjek tidak dapat mela-rikan diri dari dunia dan mesti menerima risiko untuk membuat penilaian. Namun filsafat dinilai tidak cukup untuk menge-nali perbedaan antara politik dan “yang politis”. Lefort memandang bahwa filsafat tidak lain adalah upaya untuk mengambil keputusan dalam dunia yang darinya kita tak dapat melarikan diri. Namun fi lsafat di-Namun filsafat di-hantui oleh “momok pikiran murni” (phan-tom of pure thought), yakni kesatuan konsis-kesatuan konsis-tensi internal dalam pikiran yang terpisah dari pengaruh sejarah, independen dari “dunia luar”, tak tersentuh oleh peristiwa-peristiwa historis, pemikiran yang murni metafisis (Lefort, 2000: xi).
Lefort mendaku bahwa filsafat politik diinspirasi oleh pertanyaan yang dising-kirkan oleh sains politik, yaitu pertanyaan “apa yang menjadi sifat dasar perbedaan antara bentuk-bentuk masyarakat”? Pe-nyingkiran atas pertanyaan ini dinilai Le-fort sebagai “kelupaan akan perbedaan antara politik dan ”yang politis”. Padahal ba-ginya pertanyaan-pertanyaan sains politik hanya mungkin diutarakan jika telah dibe-ri makna (mise en sens) dan dipanggungkan atau ditampilkan (mise en scène) dengan jalan memberinya bentuk (mise en forme) (Lefort, 1988: 13). Segi mise en sens adalah ketika ranah sosial terbuka sebagai ranah inteligibilitas yang diartikulasikan mela-lui modus khusus yang memampukannya membedakan antara yang nyata dan ima-jiner, benar dan salah, adil dan tidak adil, yang boleh dan yang jangan, yang normal dan patologis. Sedangkan segi mise en scè-ne adalah ketika politik dipanggungkan dalam kuasi-representasi dirinya sebagai aristokrasi, monarki, despotis, demokratis, atau totaliter (Lefort, 1988: 13).
Untuk memikirkan dasar ontologis ma-memikirkan dasar ontologis ma-syarakat tanpa melalui metafisika/filsafat, Lefort menawarkan model pembacaan yang ia sebut berpikir secara non-metafisis,
001-[Aditya Permana] Pencitraan dalam Dunia Politik.indd 3 4/24/2014 7:48:25 AM
4 Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi VOL II, 2014
yakni ‘an unlocalizable and indeterminable question that accompanies all experience of the world’ (Marchart, 2007: 88). Berpikir meta-Berpikir meta-fisis/filosofis memerlukan fondasi positif – dapat didefinisikan, tetap (fixed) dan hakiki (essential). Namun ”berpikir” non-metafisis atau berpikir sebagai bentuk interogasi tan-pa batas (infinite form of interrogation) justru mengindikasikan bahwa tidak ada jawa-ban final dan pasti yang dapat dipegang. Fondasi yang stabil hanya dimungkinkan di atas “jawaban” yang final. Akan tetapi karena tidak ada jawaban yang berhenti sebagai sekedar jawaban tanpa menimbul-kan pertanyaan lain, sejak suatu jawaban tak lain adalah pertanyaan baru sehingga mempersulit adanya fondasi yang stabil – kalau bukan mustahil (Lefort, 1978: 20). Lefort tidak berniat mencari fondasi atau landasan metafisis masyarakat, melainkan menggunakan cara pikir non-fondasional tersebut sebagai cakrawala (horizon) un-tuk memahami asal-muasal bentuk-bentuk masyarakat, seperti totalitarianisme mau-pun demokrasi.
Lefort mengatakan bahwa “konsep” tentang “yang politis” adalah pembangun-an “lapangan interogasi” dari pemikiran filsafat (Lefort, 1978: 20). Sains politik di-Lefort, 1978: 20). Sains politik di-. Sains politik di-nilainya tidak mampu (atau menghindar-kan diri) untuk mencari prinsip dasar yang memungkinkan (atau memustahilkan) per -bedaan-perbedaan antara ranah-ranah dan sistem-sistem sosial karena sains politik
berusaha memisahkan politik sebagai su-perstruktur (dalam pengertian Marxian) dan lapangan-lapangan lain seperti fakta ekonomi, fakta yuridis, ataupun fakta es-tetis (Lefort, 1988: 12). Bagi Lefort, perbe-(Lefort, 1988: 12). Bagi Lefort, perbe-. Bagi Lefort, perbe-daan-perbedaan (difference) dan pembeda-an-pembedaan (differentiation) itu justru merupakan hal yang mendasar dan men-jadi locus dalam setiap fakta ontis dalam masyarakat dan politik. Sederhananya, sains politik menemukan kelemahan da-lam merespon, katakanlah, “partikularitas dan kontingensi” yang terjadi dalam kon-teks penyelenggaraan politik. “Partikula-ritas dan kontingensi” itulah yang disebut “yang politis”, yang justru menjadi syarat yang memungkinkan (atau memustahil-kan) politik dan masyarakat.
“Partikularitas dan kontingensi” tampil sebagai ”peristiwa” (event [evenement]).2 Da-lam pengertian Derridean, suatu peristiwa dapat terjadi pada saat dan tempat ketika ”kebarangkalian” (perhaps [peut-etre]) mele-pas semua pengandaian menyangkut apa yang akan terjadi dan membiarkan masa depan datang sebagai masa depan, sebagai kedatangan dari suatu ketidakmung kinan (Kearney, 2001: 94). Dalam pengertian terse-but, ”peristiwa” bukan lapangan sains poli-tik. Menurut Lefort, “yang politis” sebagai ”peristiwa” mesti didekati lewat bentuk pemikiran non-metafisis. Politik bagi Le-fort adalah sub-sistem dari pelbagai mode tindakan dan merupakan medan kompetisi
2 Menurut Merriam Webster Dictionary, sesuai konteks tulisan ini, “event” dapat diartikan sebagai “a noteworthy hap-pening”. Dalam Thefreedictionary.com, “event” diartikan sebagai (a) “something that take place; an occurrence”; (b) “a significant occurrence o r happening”. Secara khusus dalam pengertian filosofisnya, “event” diartikan sebagai “an oc-currence regarded in isolation from, or contrasted with, human agency.” Dalam pengertian tersebut, “event” (peristiwa) memiliki ciri “momentum”, yakni (a) “an exact point in time when something important, special, or unusual happens”, (b) “particular timen when something happens”, (c) “a very short period of time”. Artinya, “peristiwa” memiliki ciri temporal, partikular, dan kontingen. Temporalitas dan kontingensi acap menjadi argumen untuk melawan kecenderungan filsafat yang menekankan kepada “esensi” yang dianggap bersifat tetap, tak berubah, pasti, mutlak, tak tersentuh waktu (timeless). Ciri yang dimiliki filsafat ini juga dimiliki oleh ilmu-ilmu positif dengan tendensi mencapai univer-salitas dan generalitas yang mengandaikan ketetapan, “kemutlakan”, dan ke-nirwaktu-an (timelessness). Temporali-tas, partikularitas, dan kontingensi jika dijadikan horizon pendekatan terhadap suatu fenomena akan membawa kita kepada kemungkinan (possibility) atau kebarangkalian (perhaps), tidak pernah membawa kepada kepastian, univer-salitas, generalitas, esensi, dan seterusnya.
001-[Aditya Permana] Pencitraan dalam Dunia Politik.indd 4 4/24/2014 7:48:25 AM
Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi ADITYA PERMANA 5
antara protagonis yang di dalamnya mode tindakan dan program-programnya secara eksplisit mendesain mereka sebagai klaim dasar dalam otoritas publik. Sedangkan “yang politis” merupakan mode dan ben-tuk paling mendasar dari masyarakat yang memiliki peran sebagai dimensi pendasar (grounding dimension) sekaligus sebagai di-mensi pemberi-bentuk (form-giving dimen-sion) bagi masyarakat.
Dengan lain kalimat, pembicaraan ten-tang ”yang politis” adalah penyelidikan tentang apa yang tersurat dari pertanyaan “what is the nature of the difference between forms of society” ataupun “apa yang asal mula perbedaan antara bentuk lapangan sosial satu dengan yang lain”? Pertanyaan tentang “asal mula” (origin) inilah yang membedakan pemikiran “yang politis” (“ontologis”) dengan sains politik yang se-mata-mata “ontis” sejak sains politik (yang objektif-netral) memiliki keterbatasan da-lam merespon peristiwa sebagai peristiwa, peristiwa dalam kekhususan, keunikan, dan singularitasnya (Marchart, 2007: 89).
2. Relasi antara Politik, ”Yang Politis”, dan Kekuasaan
Tegangan antara politik dan “yang politis” bagi Lefort adalah permainan penghadiran (“presencing”) dan penghilang an (“absenc-ing”), yang terjadi ketika yang satu mun-cul, yang lain menghilang – bukan dalam arti benar-benar lenyap (disappear) melain-kan “tersembunyi” (hidden). “Yang poli-tis” muncul sebagai syarat pemberi makna (form-giving) masyarakat. Lalu apa esensi “yang politis” itu sendiri? Esensi dari “yang politis” ini ditemukan Lefort dalam “kon-flik” atau ”antagonisme”. Atau lebih jauh lagi, dasar atau fondasi dari masyarakat demokrasi modern adalah “konflik yang dilembagakan” (institutionalized conflict).
Konflik bagi Lefort memiliki makna sebagai bentuk dan syarat bagi posibilitas yang membedakan ranah sosial satu de-
ngan ranah sosial lain. Sebagai fondasi ma-syarakat, konflik merupakan dasar ontologis yang tidak dapat direduksi maupun dide-rivasi dari sesuatu yang lain: ia bukan fakta empiris. Konflik mendahului (precede) segala macam fondasi yang mungkin. Dalam kon-teks ini, dibedakan dua jenis konflik, yaitu konflik sebagai dasar masyarakat (ontolo-gis) atau, katakanlah, “Ada-nya masyara-kat” (the Being of the society), dan konflik sebagai fakta ”ontis” yang muncul sebagai efek dari pembentukan masyarakat (kon-flik kepentingan, konflik kelas). Konflik se-bagai “Ada” mendasari pembentukan iden-titas sosial masyarakat yang bersangkutan. Identitas sosial dimulai dengan pembagian mendasar (basic division) antara masyarakat (society) dan ”liyan” (other) (Marchart, 2007: 92).
Bagi Lefort, “yang politis” memiliki dua poros. Poros pertama (“inside”) adalah poros identitas-diri yang tercipta dari ba-sic division dengan cara alienasi-diri atau eksternalisasi-diri terhadap liyan. Poros kedua (“outside”) adalah pembagian-pem-bagian (divisions) di dalam masyarakat itu sendiri. Inilah yang menjadi liyan bagi iden-titas sosial masyarakat. Tegangan antara dua poros ini – yang disebut Lefort sebagai “antagonisme” – merupakan keniscayaan yang tak terelakkan dari dimensi totalitas masya rakat. Artinya, apabila kedua po-ros ini diceraikan, maka masyarakat tidak mungkin ada.
Antagonisme ini menubuh dalam pe-nguatan akan identitas-diri dengan jalan, katakanlah, “penciptaan musuh bersama” – yakni afirmasi diri melalui negasi atas li-yan. Sebagai gambaran, dalam masyarakat totalitarianisme yang berbasis proletariat, “borjuis” menjadi “musuh bersama”, yang dengan itu segala hal yang terkait dengan-nya diletakkan di seberang identitas-diri sebagai proletar sebagai identitas yang di-representasikan oleh rezim totaliter. “Bor-juis” menjadi liyan bagi proletar. Penegas-
001-[Aditya Permana] Pencitraan dalam Dunia Politik.indd 5 4/24/2014 7:48:25 AM
6 Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi VOL II, 2014
an simbolis ini memunculkan perasaan bahwa individu merupakan anggota dari masyarakat yang sama (Marchart, 2007: 97). Namun di lain pihak, pada saat yang sama, alteritas-alteritas tidak benar-benar lenyap. Dalam arti, banyak bentuk “divisi-divisi” lain yang tidak dapat direduksi dalam identitas yang dikonstruksi rezim totaliter tersebut. Dalam divisi-divisi ini tak jarang muncul konflik partikular.
Liyan tidak ditemukan di luar (ekster-nal) dari masyarakat itu sendiri. Liyan me rupakan bentuk ekternalisasi-diri (self-externalization) dari identitas sosial masya-rakat. Tidak ada identitas tanpa adanya pengenalan atau penjarakan (distancing) dengan liyan (Marchart, 2007: 92). Identi-Marchart, 2007: 92). Identi-. Identi-tas (inside) mengeksternalisasi liyan (out-side) dalam kelindan enigmatik, tatkala li-yan (outside) bukan merupakan kehidupan yang independen pada dirinya sendiri, me-lainkan sesuatu yang dihadirkan (present) bagi inside. Dengan demikian, outside ada-lah kondisi posibilitas bagi inside. Dalam skema hubungan antara kekuasaan dan identitas sosial, hal ini lebih jelas. Kekuasa-an di arahkan menuju kepada outside. Iden-titas adalah apa yang disignifikansi oleh kekuasa an. De ngan signifikansi ini, orang dapat mengaitkan (identitas) diri pada ru-ang tempat mereka hidup dalam scope kekuasa an tersebut. Yang tidak dapat dika-itkan dengan ruang tempat mereka hidup dalam scope kekuasaan tersebut disigni-fikansi sebagai outside (Marchart, 2007: 93).
Menurut Steinmetz-Jenkins relasi an-tara politik dan “yang politis” dapat dika-takan sebagai,
“What appears as politics is an extraction and there-fore quasi-representation of the political. In Lefort’s thought there is a moment of alterity apparent here,
whereby a fundamental difference between figure and ground takes place. Notice that, though, politics is inseparable from the political, the two are, nev-ertheless, ever so slightly estranged” (Steinmetz-Jenkins 2009: 106).
Politik merupakan kuasi-representasi dari ”yang politis”. Relasi memiliki mak-na bahwa kekuasaan bekerja dalam tata-nan simbolis. Wujud simbolisasi tersebut ditemukan dalam pemanggungan (staging) kekuasaan, atau apa yang disebut Lefort sebagai mise-en-scène (Marchart, 2007: 93). Pemanggungan kekuasaan tersebut ada-lah peristiwa simbolis (symbolic event) yang memberikan makna (sens) sekaligus bentuk (forme) pada yang sosial dengan merepre-sentasikannya pada dirinya sendiri. Lefort mengatakan,
“When we speak of symbolic organization, symbolic constitution, we seek to disclose beyond practices beyond relations, beyond institutions which arise from factual givens, either natural or historical, an ensemble of articulations which are not deducible from nature or from history, but which order the apprehension of that which presents itself as real” (Lefort dalam Flynn, 2005: 118).
Dengan kata lain, pemanggungan ke-kuasaan harus digiring ke ranah tempat ia menemukan bentuknya: kekuasaan perlu panggung tempat ia direpresentasikan. Tidak ada masyarakat tanpa kekuasaan, namun tidak ada kekuasaan tanpa representasi,
“Lefort suggests that power can only operate as rep-resented; therefore political power and its represen-tation are inseparable” (Steinmetz-Jenkins, 2009: 109).
Dengan kalimat lain, tidak ada masyara-kat tanpa ”kuasi-representasi” (Marchart, 2007: 93).3 Segi mise-en-forme inilah yang
3 Secara kasar, kuasi-representasi merupakan penyebutan atas referen (rujukan) yang menjadi representasi dari ke-Secara kasar, kuasi-representasi merupakan penyebutan atas referen (rujukan) yang menjadi representasi dari ke-kuasaan sesungguhnya tidak berdiri di atas landasan yang stabil, padat, dan tetap, melainkan ketidakpastian dan kontingensi.
001-[Aditya Permana] Pencitraan dalam Dunia Politik.indd 6 4/24/2014 7:48:25 AM
Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi ADITYA PERMANA 7
membedakan bentuk-bentuk pemerintah-an, apakah totalitarianisme atau demo-krasi, sekaligus menjadi pembeda dalam pendivisian asali masyarakat. Macey me-ngatakan,
“The comparison between democracy and totali-tarianism shows that these societies do not differ only by the form of their government, but also by their mise en forme of human coexistence. In other words, the way in which they are organized and the relationships between people tied, is specific to each one of them” (Macey, 1988: 15).
Apabila boleh disederhanakan, rang kai-an di atas dapat digambarkan sebagai ling-karan semiosis, yang di dalamnya kekuasa-an berfungsi sebagai petanda (signified) dari identitas sosial sebagai penanda (signifier) yang memiliki acuan “panggung peristiwa simbolis” yang merepresentasikan jalinan signifikansi tersebut. Karena ini berada dalam level simbolis, maka tidak ada fon-dasi yang benar-benar kukuh, melainkan sebaliknya, representasi yang menjadi re fe-ren dari pemanggungan kekuasaan justru dijamin oleh tatanan simbolis itu sendiri.
3. ”Pengosongan Kekuasaan” dan Ab-sennya Fondasi Masyarakat sebagai Syarat Adanya Masyarakat
Pemotongan atau pemenggalan panggung simbolis akan memiliki konsekuensi ke-pada terpotongnya panggung kekuasaan (stage of power). Pada momen ini, represen-tasinya pun menjadi kosong. Momentum tatkala panggung kekuasaan ini kosong – atau “pengosongan kekuasaan” (empty of power) – inilah yang disebut Lefort sebagai “momen yang politis” (moment of the po-litical) (Marchart, 2007: 94). Namun ”keko-
songan” yang digambarkan di sini bukan di mengerti sebagai tiadanya kekuasaan. Momen ”pengosongan kekuasaan” ter-jadi ketika level simbolis pada kekuasaan ”lama” – sebelum mengalami momen yang politis – dimutasi atau mengalami perubah-an bentuk. Ini adalah momen mise-en-scène yang secara langsung akan mempengaruhi bagaimana masyarakat yang baru diben-tuk (mise-en-forme) dan mendapat makna (mise-en-sens).
”Pengosongan kekuasaan” harus di-lihat sebagai ”peristiwa” dalam singula-ritas dan keunikannya – kontingensinya. Pe ngosongan kekuasaan bukan berarti kondisi yang terus menerus berada tanpa kekuasa an. Hal ini mesti dilihat dalam kaitannya dengan pendivisian asali ma-syarakat itu sendiri. Dalam kasus revolu-si4 mahasiswa Mei 1998, kekuasaan lama mendapat gangguan dari divisi lain yang antagonis terhadapnya. Kekuasaan lama diindikasi sebagai rezim totaliter dengan Soeharto sebagai simbol kuasi-transenden-tal ”Bapak Negara”, dua peran dalam satu tubuh: Bapak Pembangunan Bangsa (sim-bolis) sekaligus diktator bertangan besi. Peristiwa Mei 1998 merupakan momen yang politis, suatu peristiwa ketika rezim lama di tumbangkan, yang segera mem-beri bentuk dan makna bagi masyarakat yang terbentuk pasca-revolusi: masyarakat reformasi. Namun momen tersebut juga merupakan momen kekosongan kekuasa-an. Kekuasaan tidak kosong dalam arti ti-dak ada kekuasaan, melainkan bertransfor-masi menjadi bentuk baru yang diisi oleh divisi lain dalam masyarakat yang berbeda dengan rezim lama.
Dalam level simbolis, antagonisme meng -andaikan konflik antara penguasa dan yang
4 Lefort tidak menggunakan term ”revolusi” dalam makna kuat. Pemanggungan revolusi – revolusi sebagai peristiwa – adalah disposisi simbolis, ketika fiksi rakyat menempati tempat kekuasaan yang kosong. Namun ini justru mem-buka celah antara rakyat ”ideal” dan rakyat ”empiris” dalam penentuan relasi kawan-lawan yang dideterminasi oleh ”kediktatoran”. Kediktatoran revolusioner ini bagi Lefort bersifat non-permanen (Lefort, 1988: 107-108)
001-[Aditya Permana] Pencitraan dalam Dunia Politik.indd 7 4/24/2014 7:48:25 AM
8 Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi VOL II, 2014
dikuasai (”masyarakat”). Antagonisme ini dapat dipandang sebagai kelindan antara konflik dalam tataran ontologis dan kon-flik dalam tataran ontis seperti diuraikan sebelumnya. Namun sebaliknya, masyara-kat yang berbasis konflik murni juga tidak mungkin karena justru akan self-destruc-tive. Oleh karena itu, konflik ontologis se-bagai “Ada”-nya masyarakat memerlukan penya luran simbolis (symbolic outlet), sebab menurut Lefort, tanpa adanya penyaluran simbolis, kumpulan manusia hanya akan menjadi “state of nature”.
Dengan demikian, kelindan antara konflik ontologis-ontis ini bukan semata-mata perbedaan atau oposisi, melainkan relasi bolak-balik. Antara politik dan “yang politis” dihubungkan oleh relasi permai-nan penghadiran dan penghapusan (pre-sencing and absencing) secara sinambung. Bagi Lefort, syarat posibilitas bagi hadir-nya (presence) politik adalah justru peng-hapusan/peng hilangan (absencing) elemen ontologisnya. Sebaliknya, “yang politis” hadir (presence) ketika terjadi penghilangan ”pengada ontis” (ontic being) dari fakta-fakta partikular politik. Akan tetapi ini dimainkan dalam level simbolis. Dick Ho-ward menafsirkan “yang politis” sebagai kehadiran simbolis ketika ”eksistensi seba-gai ketidakhadiran yang nyata (the real ab-sence) membuat perubahan politik menjadi mungkin” (Howard dalam Marchart, 2007: 91).
Dalam masya rakat demokratis, antago-nisme semacam ini memustahilkan adanya sebuah partai tunggal (sebagai salah satu bentuk penya luran simbolis) yang secara penuh mendominasi partai-partai lain. Juga tidak ada seorang aktor sosial yang dapat memegang peran sebagai pemben-tuk makna sosial sebagai keseluruhan, ka-rena permainan divisi-divisi sosial akan selalu mencegah aktor tunggal yang me-monopoli makna sosial (“figure of absence”).
Penguasa dan masyarakat bersifat rela-sional, tanpa saling meniadakan. Yang satu menjadi syarat posibilitas bagi identitas yang lain. Fondasi masyarakat dibentuk melalui relasi konfrontasi mutual sebagai syarat posibilitasnya. Masyarakat hanya dapat terbentuk melalui proses self-division. Namun sekali lagi, ini terjadi dalam level simbolis, sebab kemutlakan itu tidak mun-gkin terjadi. Artinya, masyarakat sesung-guhnya dibangun di atas fondasi yang hampa (void). Setiap bentuk masya rakat harus selalu melalui pengalaman akan yang hampa ini. Implikasinya, identitas masyarakat juga berdiri di atas basis yang hampa tersebut. Dalam insight Lacanian, kekosongan ini kemudian diisi oleh Yang Simbolis (The Symbolic), sebagaimana di-terangkan sebelumnya. Namun yang sim-bolis ini selalu diganggu oleh konti ngensi radikal yang niscaya, yaitu absennya fondasi itu sendiri. Absennya fondasi inilah Yang Nyata (The Real), yakni keniscayaan yang tidak dapat sepenuhnya dikontrol, diring-kus, dan ditotalisasi oleh sistem apapun. Oleh karena itu, keniscayaan ini membutu-hkan proses yang bersifat imajiner, dengan tujuan untuk menutupi atau menyembu-nyikan absennya fondasi yang berpangkal pada konflik pendivisian asali (original di-vision) tersebut. Penyembunyian ini dalam wawasan Lacanian disebut fase “Imajiner” (The Imaginary), dalam pelbagai bentuknya.
Mengapa absennya fondasi masyara-kat mesti disembunyikan dalam Yang Ima-jiner? Lefort beralasan, mana mungkin kita dapat menerima fakta bahwa fondasi ma-syarakat kita hanyalah sebuah jurang tan-pa dasar yang secara paradoksikal justru menjadi syarat posibilitas berdirinya ma-syarakat? Namun kendati demikan usaha penutupan dan penyembunyian imajiner ini “ditakdirkan” untuk selalu gagal akibat gangguan dari keniscayaan The Real terse-but.
001-[Aditya Permana] Pencitraan dalam Dunia Politik.indd 8 4/24/2014 7:48:26 AM
Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi ADITYA PERMANA 9
4. Demokrasi dalam Pandangan LefortLefort menafsirkan demokrasi yang di-mengerti oleh Tocqueville sebagai mutasi level simbolis. Tocqueville berusaha me-nempatkan prinsip fundamental demokra-si, yakni kesetaraan (equality), dengan mengeksplorasi perubahan-perubahan yang terjadi pada semua arah, dalam ikatan-ika-tan lembaga sosial dan politik, individu, mekanisme opini publik, agama, hukum, bahasa, sastra, sejarah, dan seterusnya. Me-nurut pembacaan Lefort, eksplorasi terse-but membawa Tocqueville pada kesimpu-lan bahwa revolusi dari totalitarianisme ke demokrasi mengandung ambiguitas dalam segala domain.
Demokrasi di satu sisi membawa tanda baru tentang kebebasan (new signs of free-dom), namun di sisi lain demokrasi juga membawa tanda baru tentang perbudakan (new signs of servitude) (Lefort, 1988: 14). Se-bagai gambaran, pada level individual, de-pendensi individu pada pemerintahan to-taliter terhapus dan individu memperoleh kebebasan berpikir, berbicara, dan bertin-dak seturut norma yang ia anut. Namun di sisi lain ia juga terisolasi, termiskinkan, dan terjebak dalam citraan (image) rekan-rekannya di dalam tempat ia dikelom-pokkan (agglutinated) sebagai akibat dari pendivisian asali.
Kemudian pada level opini publik, Tocqueville menandaskan bahwa dukun-gan kepada hak dan kebebasan berbicara dan berekspresi secara bersamaan justru menjadi lepas (detached) dari subjek dan menjadi kuasa anonim (anonymous power) yang berpikir dan berbicara untuk dirinya sendiri (Lefort, 1988: 15). Namun bagi Le-fort, Tocqueville luput melihat perubahan-perubahan, penga ruh dan kontra-penga-ruh, penyerbuan (irrup ti on) makna-makna baru, munculnya cara-cara ekspresi baru yang mengalahkan kuasa anonimitas, me-ningkatnya he terogenitas kehidupan sosial yang ko-eksis bersama kehidupan sosial
dan bernegara yang meng atasi individu, dan seterusnya (Lefort, 1988: 15).
Bagi Lefort, Tocqueville melihat real-isasi demokrasi sebagai suatu bentuk ma-syarakat (form of society) yang lahir dari perlawanan akan rezim yang mendahului-nya, yaitu masyarakat aristokratik (Lefort, 1988: 13). Dalam konteks ini, demokrasi juga merupakan suatu mutasi level sim-bolis yang berkaitan dengan pemosisian kekuasa an secara baru. Namun bagi Lefort demokrasi sebagai kekuasaan di tangan rakyat bukan sejenis bentuk kekuasaan yang jauh berbeda dengan totalitarianisme. Alasan Lefort, demokrasi hanya memin-dahkan bentuk singularitas kekuasaan dari tangan monarki ke tangan “rakyat” (people).
Pada pemerintahan monarkis, teruta-ma yang dibentuk oleh matriks teologiko-politik, pangeran (the prince) mendaku kekuasa annya berasal dari Tuhan dan membuatnya menjadi sebagai agen sekuler sekaligus wakil Tuhan. Kekuasaan diwu-judkan atau ditubuhkan (embodied) dalam pangeran. Ini kemudian memberi ma-syarakat suatu bentuk. Lefort menyebut-nya sebagai “tubuh masyarakat” (body of society). Namun dalam demokrasi, posisi pangeran lenyap. Hal ini membawa tubuh masyarakat kepada hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yakni kekosong an lo-cus kekuasaan yang semula diisi oleh pa-ngeran (Lefort, 1988: 15-16).
Kekosongan kekuasaan ini lantas di-isi oleh pemerintahan baru yang diawasi, dan dikontrol secara ketat dengan aturan-aturan yang permanen agar kekuasa an tersebut tidak diapropriasi sendiri oleh pe-merintah baru. Konsekuensinya, mekanis-me peng awasan ini menjadi konfliktual. Konflik ini sendiri dilembagakan. Ironis-nya, mekanisme exercise of power ini meng-akibatkan adanya pendivisian antara inside dan outside dan kompetisi siapa yang mera-sa layak untuk memangku kekuasa an (Le-fort, 1988: 17). Dalam konteks ini, kekuasa-
001-[Aditya Permana] Pencitraan dalam Dunia Politik.indd 9 4/24/2014 7:48:26 AM
10 Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi VOL II, 2014
an mesti diisi namun sekaligus juga dijaga agar tetap kosong agar masyarakat tidak jatuh dalam totalitarianisme kembali. De-mokrasi, de ngan demikian, menghidupi suatu asas yang kontradiktif. Lefort me-ngatakan,
“The legitimacy of power is based on the people; but the image of popular sovereignty is linked to the im-age of an empty place, impossible to occupy, such that those who exercise public authority can never claim to appropriate it. Democracy combines these two apparently contradictory principles: on the one hand, power emanates from the people; on the other, it is the power of nobody. And democracy thrives on this contradiction. Whenever the latter risks be-ing resolved or is resolved, democracy is either close to destruction or already destroyed. If the place of power appears, no longer as symbolically, but as re-ally empty, then those who exercise it are perceived as mere ordinary individuals, as forming a faction at the service of private interests and, by the same token, legitimacy collapses throughout society” (Lefort, 1986: 279).
Masyarakat yang tercipta dari pendi-visian yang konfliktual ini dikawal oleh ranah hukum dan pengetahuan yang in-dependen dari pemangku kekuasaan tunggal. Namun sebagai konsekuensinya masyarakat demokrasi tidak pernah men-capai totalitas sebagaimana terjadi dalam masyarakat monarkis atau totaliter. De-ngan kata lain, masyarakat demokrasi adalah masyarakat tanpa tubuh (society without a body). Setidaknya ada dua alasan yang dapat dikemukakan untuk pernyata-an tersebut. Pertama, tanpa adanya figur tunggal yang memegang kekuasaan secara mutlak, masyarakat demokrasi berdiri di atas fondasi kompetisi dan konflik yang dilembagakan sebagaimana dijelaskan di atas. Kedua, masyarakat demokrasi tidak memiliki ke utuhan organis sejak masyara-kat demokrasi menghindari pemerintahan monarkis (atau totaliter, aristokratik, dan
sejenisnya) yang determinasi kekuasaan-nya terletak di tangan pangeran sebagai wakil Tuhan yang absolut (Lefort, 1988: 18). Menurut Lefort, secara paradoksikal, masyarakat demokrasi yang direpresenta-sikan oleh partai-partai cenderung masih mewarisi watak totalitarianisme. Sebab ke-tika kuasi-representasi yang dibawa oleh partai tertentu diidentikkan dengan citra masyarakat, pada titik ini justru akan ter-jadi pereduksian divisi-divisi asali dalam masyarakat; atau lebih parah lagi, tidak ada “civil society”. Ia mengatakan,
“…there is no longer a civil society. But if the im-age of the people is actualized, if a party claims to identify with it and to appropriate power under the cover of this identification, then it is the very prin-ciple of the distinction between the state and society, the principle of the difference between the norms that govern the various types of relations between individuals, ways of life, beliefs and opinions, which is denied; and, at a deeper level, it is the very prin-ciple of a distinction between what belongs to the order of power, to the order of law and to the order of knowledge which is negated. The economic, legal and cultural dimensions are, as it were, interwoven into the political. This phenomenon is characteristic of totalitarianism” (Lefort, 1986: 279-280).5
Keutuhan atau kesatuan organis ma-syarakat demokrasi dijamin dan dideter-minasi oleh masyarakat sosial dan bangsa atau negara sebagai entitas universal, yang di dalamnya setiap kelompok memiliki sta-tus dan hak yang sama. Kehendak rakyat menjadi kehendak negara. Dengan kata lain, singularitas kekuasaan berpindah ke tangan orang banyak (the people) – ke-tika orang banyak ini dibicarakan sebagai statistik – yang tidak selalu terikat oleh ke samaan kepentingan, melainkan justru terikat oleh perdebatan ideologis. Bagi Le-fort, hal ini berbahaya karena
“The danger of numbers is greater than the dan-ger of an intervention by the masses on the politi-
5 Cetak tebal dari penulis.
001-[Aditya Permana] Pencitraan dalam Dunia Politik.indd 10 4/24/2014 7:48:26 AM
Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi ADITYA PERMANA 11
cal scene; the idea of number as such is opposed to the idea of the substance of society. Number breaks down unity” (Lefort dalam Näsström, 2009: 348).
5. Pencitraan dalam Demokrasi dan Kaitannya dengan Tubuh Masyarakat
Dalam konteks demokrasi representatif In-donesia, kekosongan kekuasaan diisi oleh partai-partai dan organisasi-organisasi lain yang dianggap merepresentasikan kelompok-kelompok yang ada. Di satu sisi, mekanisme exercise of power demokrasi Indonesia yang multi-partai tampaknya memustahilkan okupasi dan hegemoni seorang figur untuk menjadi pemang-ku kekuasaan. Namun di sisi lain sistem multi-partai di Indonesia masih bertumpu pada aspek ketokohan alih-alih program kerja yang efektif.
Dalam kasus pemilihan gubernur di Ja-karta tahun 2012, kendati masing-masing calon memiliki program kerja yang jelas, namun aspek ketokohan masih demikian ditonjolkan sehingga baik para pendukung maupun para penentang sama-sama terje-bak argumentum ad hominem yang membela ataupun menyerang pribadi tokoh, latar belakang etnis, agama, dan seterusnya, namun justru abai untuk mengkritisi pro-gram-program yang ditawarkan para calon. Konsekuensi sistem multi-partai, dengan demikian, justru adanya pengkotak-ko-takan yang menegaskan ciri asli masyara-kat demokratis, yakni penyembunyian konflik dalam divisi-divisi institusi-institu-si sosial. Masyarakat demokratis secara iro-nis justru mempertaruhkan keutuhan dan kohesi sosial dengan sistem yang dianggap mewakili karakter heterogen, independen, bebas, dan setara masyarakat.
Di sisi lain, jika figur politikus diang-gap sebagai seseorang yang akan mem-bawa keutuhan dan menciptakan tubuh masyarakat, secara ironis ini akan mem-
pertahankan watak monarkis-totaliter ma-sya rakat yang dianggap telah dilampaui. Bangsa Indonesia telah melewati perjalan-an sejarah zaman kerajaan-kerajaan hingga masuknya demokrasi Barat yang dijalan-kan oleh Soekarno hingga SBY. Peristiwa Mei ’98 yang menjadi tonggak lepasnya Indonesia dari kuasa represif Soeharto di-pandang membawa arah baru demokrasi Indonesia. Akan tetapi era reformasi hanya merupakan mutasi level simbolis pemerin-tahan represif sebelumnya yang berbasis pada kharisma dan ketokohan Soeharto.
Represi yang beroperasi sejak era Soekar no mengangkat diri menjadi pre-siden se umur hidup hingga era militer-istik Soeharto hingga modus pencitraan yang mendadak populer di era SBY tak lain merupakan mutasi level simbolis yang menyembunyikan watak dan identitas asli masyarakat Indonesia yang berdiri di atas ruang hampa (void) sepeninggalan kejaya-an masa keraja an-kerajaan dan harapan akan datangnya “Ratu Adil”. Pencitraan figur justru memperlihatkan aspek ketoko-han yang lemah karena proses ini berbasis pada manipulasi, pengaburan, maupun pengindah-indahan. Para politikus citraan ini jelas-jelas tidak memperjuangkan ide-ologi politik, program, ataupun manifesto politik yang kuat, melainkan sibuk ber-solek dan memperindah apa yang nampak atau ingin di tampakkan belaka.
Masyarakat demokrasi Indonesia yang masih mempertahankan nilai-nilai monar-kis warisan zaman Kerajaan, sesuai tafsiran penulis atas pemikiran Lefort, merupakan masyarakat tanpa tubuh, tanpa kesatuan dan kohesi yang utuh, sekaligus tanpa arah. Sistem demokrasi yang melandaskan diri pada aspek ketokohan membuat figur politikus harus terlihat mencolok (conspicu-ous). Ini dapat ditempuh dengan beragam cara, baik dengan prestasi maupun dengan sensasi.
001-[Aditya Permana] Pencitraan dalam Dunia Politik.indd 11 4/24/2014 7:48:26 AM
12 Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi VOL II, 2014
Meskipun demikian, kemajuan teknolo-gi informasi saat ini membuat masyarakat berada dalam dunia dromology, yakni dunia yang dideterminasi oleh logika kecepatan (logic of speed), dalam konteks ini kecepatan informasi dan pengetahuan, serta rotasi kekuasaan yang cepat temponya, membuat para politikus mencari cara tercepat untuk menarik perhatian masyarakat alih-alih mengerjakan program yang hasilnya atau buktinya tidak dapat dipetik secara instan (Bratton dalam Virilio, 2006: 13). Pencitraan para politikus menjadi bagian dari modus para politikus untuk meraih kekuasaan, sekaligus untuk melembagakan watak to-taliter ini. Dengan demikian pencitraan, dilihat dari sudut pandang semiotis, meru-pakan mutasi di atas mutasi. Mutasi pertama terjadi di level ontologis, yakni bertahannya watak totaliter yang coba disembunyikan dengan demokrasi sebagai panggungnya. Mutasi kedua terjadi di level ontis, yakni disembunyikannya ketergantungan pada figur kharismatik yang bertindak sebagai kuasi-representasi kehendak rakyat – yang nota bene terdivisi secara “alamiah”. Sekali lagi, divisi-divisi yang dikuasi-representa-sikan oleh caleg, cabup, cagub, capres, dan seterus nya ini justru menyimpan risiko disintegrasi masyarakat.
6. Penutup: Risiko Disintegrasi dalam Demokrasi
Dalam pemikiran Lefort, baik dalam ma-sya rakat totaliter maupun demokratis, pem bicaraan mengenai politik (politics) menggambarkan dikotomi antara “pe-nguasa” dan “yang dikuasai” sebagai syarat yang memungkinkan (condition of possibility) politik itu sendiri. Dalam makna ini, yang satu menjadi “liyan” (other) bagi yang lain. Liyan dalam makna ini dapat di-artikan sebagai “yang asing” (the strangers), yang berjarak satu sama lain, yang tidak dapat diketahui secara pasti maunya, yang tidak dapat diantisipasi kehendaknya,
yang tidak dapat sepenuhnya dikontrol dan ditotalisasi. Dalam dikotomi tersebut, penguasa menjadi “yang asing” bagi yang dikuasai, demikian pula sebaliknya.
Dari sudut pandang penguasa, rakyat adalah sekumpulan orang asing yang tidak dapat diketahui secara pasti apa maunya, yang tidak dapat diantisipasi kehendak-nya, yang tidak dapat sepenuhnya dikon-trol dan ditotalisasi, sehingga dalam logika demikian, represi dan hegemoni menjadi senjata ampuh untuk menundukkan dan mendominasi stranger (rakyat). Namun ke-tika cara-cara represif sudah tidak dapat dipertahankan, cara-cara lain bermunculan – salah satunya adalah dengan pencitraan. Di lain pihak, dari sudut pandang rakyat, penguasa adalah stranger yang tidak me-mahami kehendak rakyat, abai terhadap kebutuhan nyata rakyat, melecehkan ke-daulatan rakyat. Terma “rakyat” hanya ada sejauh penguasa “membutuhkan” rakyat, sedangkan terma “penguasa” muncul ke-tika hak rakyat terampas. Dengan kalimat lain, pada masa kini ketika kita membicara-kan politik (para penguasa), rakyat nihil di situ. Ketika kita membicarakan rakyat, politik hanya menjadi satu berita di antara berita lain yang biasa-biasa saja tanpa efek signifikan bagi rakyat.
Permainan “saling menghilangkan” ini suka atau tidak suka harus diakui adanya. Kedua sisi ini saling mengandaikan, namun begitu salah satu sisi disorot, sisi yang lain “menghilang”. Permainan “saling meng-hilangkan” ini, menurut Lefort, merupa-kan dimensi ontologis dari masyarakat dan politik itu sendiri. Politik membutuhkan sejumlah syarat. Yang paling utama tentu adanya masyarakat dan segala relasinya, seperti solidaritas kelas, kerjasama religi-us, dan seterusnya. Di sini politik muncul dengan segala karakter totaliternya – seka-lipun dalam demokrasi.
Demokrasi menggantikan relasi-relasi sosial yang telah ada sebelumnya de ngan
001-[Aditya Permana] Pencitraan dalam Dunia Politik.indd 12 4/24/2014 7:48:26 AM
Pencitraan dalam Dunia Politik sebagai Contoh Mutasi Watak Totaliter dalam Demokrasi ADITYA PERMANA 13
satu dimensi tunggal yang mengatur hie-rarki siapa yang mengatur (those who or-der) dan siapa yang mesti patuh (those who obey). Ini yang disebut Lefort sebagai “pagar ganda” (double “fence”). Di sini ter-jadi asosiasi hirarkis antara negara dan partai-partai yang selalu dekat sehingga partai selalu dianggap menjadi kekuat-an demokrasi yang efektif. Watak totali-ter politik dan demokrasi muncul karena pada titik ini sekaligus terjadi pengkotak-kotakan masyarakat. Sebagai konsekuensi-nya, terjadi “penghancuran” ruang publik (Lefort, 1986: 293). Artinya dalam politik, masyarakat tidak pernah betul-betul meru-pakan suatu “kenyataan”, melainkan suatu “peristiwa” yang kontingen dan partikular, yang ada sejauh diadakan oleh mekanisme exercise of power. Secara ironis, exercise of power ini justru memiliki konsekuensi mendivisi masyarakat dan menimbulkan disintegrasi. Dengan kata lain, politik jus-tru “menghilangkan” (annihilate) masyara-kat yang justru menjadi syarat adanya poli-tik itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Baudrilard, Jean. (1983). Simulations. New York: Semiotext(e).
_____ (1994). Simulacra and Simulations. Diterjemahkan oleh Sheila Faria Gla-ser. Ann Harbor, Michigan: University of Michigan Press.
Bratton, Benjamin H. “Introduction” dalam Virilio, Paul. (2006). Speed and Politics: Essay on Dromology. New York: Semiotext(e).
Flynn, Bernard. (2005). The Philosophy of Claude Lefort: Interpreting the Political. Il-linois, Evanston: Northwestern Univer-sity Press.
Kearney, Richard. (2001). God Who May Be: A Hermeneutics of Religion. Blooming-ton, Indiana: Indiana University Press.
Lefort, Claude. (1978). Les Formes de l’historie. Paris: Galimard.
_____ (1986). The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy, Totali-tarianism. Disunting dan diberikan pe-ngantar oleh John B. Thompson. Cam-bridge – Massachusets: MIT Press.
_____ (1988). Democracy and Political Theo-ry. Diterjemahkan oleh Richard Macey. Cambridge: Polity Press
_____ (2000). Writing: The Political Test. Diterjemahkan oleh David Ames Cur-tis. Durham, North Carolina: Duke University Press.
Macey, David. “Introduction”dalam Lefort, Claude. (1988). Democracy and Political Theory. Polity Press.
Machiavelli, Niccolò. (1961). The Prince. Diterjemahkan dan diberikan pengan-tar oleh George Bull. Penguin Books.
Marchart, Oliver. (2007). Post-Foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau. Ed-inburgh, UK: Edinburgh University Press.
Näsström, Sofia. (2009). Democracy Counts: Problems of Equality in Transnational De-mocracy. Makalah yang disampaikan dalam Konferensi APSA di Toronto, Kanada, 2009, dan dalam Transdemos Workshop di Stockholm, Swedia, 2009.
Ricoeur, Paul. (1965). “The Political Para-dox” dalam History and Truth. Diter-jemahkan oleh Charles A Kelby. Evan-ston, Ill: Northwestern University Press, hlm. 247-270
Schaap, Andrew. (2013). “Human Rights and the Political Paradox” dalam Aus-tralian Humanities Review 55 (2013): 1-22.
Steinmetz-Jenkins, Daniel. (2009) “Claude Lefort and the Illegitimacy of Moder-nity” dalam Journal for the Cultural and Religious Theory, vol JCRT 10.1 Winter 2009
001-[Aditya Permana] Pencitraan dalam Dunia Politik.indd 13 4/24/2014 7:48:26 AM
Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, hal 14-29ISSN 2302-5719
Vol II, Nomor 1
Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos1
YOGIE PRANOWO2
D o s e n N a s i o n a l i s m e d i K A L B I S I n s t i t u t e Pulomas Selatan Kav 22, Jakarta Timur 13210.
Surel: [email protected]
Diterima: 17 Januari 2014Disetujui: 20 Maret 2014
ABSTRACT
Nowadays, our eyes are “forced” to feast upon the gleaming campaign advertisements of presidential candi-dates. Not only in screens, their personages have even packed road markings with flashy banners that bedazzle the eyes. They are putting out a wholesale of promises and vows! But are their words merely absolute dimen-sions with objective values? Or are they only clichés to actualize their ambitions on the upcoming 2014 Gen-eral Elections? On that, the writer wants to try once again to raise Friedrich Nietzsche’s reasoning. Because through his thoughts, (it is as if) he wants to advise us – the soon-to-be electors in 2014 General Elections to come – to be able to assess a person properly through the ad hominem method. If the phrase ad hominem is commonly perceived as a type of ambiguous thinking, Nietzsche will say otherwise, that argumentum ad hominem in all conscience has a central role in its moral genealogy, that is as a method to diagnose our outlook of reality in a more profound way. By following Nietzsche’s advice, hopefully in the end we are able to evaluate and decide: who will be the person worthy of the title “Indonesia’s Number One”.
Keywords: ad hominem method, moral genealogy, will, “slave” and “master” morality, perspec-tivism.
Pada tahun 1987 seorang pelukis-seniman, Paul Gauguin mempublikasikan lukisannya tentang asal-usul manusia yang mengajak kita untuk berfikir dan mencari jawaban atas ek-sistensi diri kita.3 Karya ini menggambarkan siklus kelahiran, kehidupan, dan kematian—asal-usul, identitas, dan takdir tiap-tiap indi-vidu—dan persoalan personal.
1 Saya berterima kasih kepada Dr. A. Setyo Wibowo, dosen pengajar mata kuliah Gaya Filsafat Nietzsche pada Pro-gram Pasca Sarjana STF Driyarkara, yang telah memberi banyak masukan (dalam seri kuliahnya) bagi pengemban-gan tulisan ini.
2 SaatinimasihmenyelesaikanstudimasterdibidangfilsafatdiSTFDriyarkaraJakarta.3 D’ou venons-nous? Qui sommes-nous? Ou allons-nous? Dari mana kita? siapa kita? dan akan kemana kita? Adalah per-
tanyaan yang menjadi cikal bakal lukisannya. Lihat berita selengkapnya di http://www.gauguin.org/where-do-we-come-from-what-are-we.jsp.
“Das Kriterium der Wahrheit lieght in der Steigerung des Machtgefuls”
(Nietzsche, Nietzsches Werke XXVI, 45)
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 14 4/24/2014 8:39:44 AM
Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos YOGIE PRANOWO 15
Sama seperti Nietzsche yang menganjurkan kita untuk mengenal diri kita lebih dalam4, Gau-guin seakan juga ingin mengajak kita berefleksi untuk mengenal diri kita, dan meneguhkan “iman” kita, agar kita tahu apa tujuan hidup kita dan tahu kemana kita akan melangkahkan kaki ini agar tidak terjerumus pada hidup yang dekaden dan terserak.
Akhir-akhir ini, marak dijumpai per-soalan pluralisme di Indonesia, mulai dari perselisihan antar agama hingga perang suku. Bhinneka Tunggal Ika yang diyakini menjadi “kekuatan” nasionalpun harus bungkam, ia telah menutup mulutnya. Ia tidak lagi mau bersaksi ataupun menjelas-kan apa maksud dari kebinekaannya itu. Dapat dikatakan bahwa Pancasila kita tinggal wacana kebangsaan yang abu abu, tak jelas juntrungannya. Alih-alih sebagai alat pemersatu bangsa, ideologi semacam itu malah menjadi doktrin untuk sema-kin menyengsarakan rakyat. Pemerintah seakan tak lagi peduli dengan nasib bang-sanya. Hal itu dapat kita lihat dari minim-nya usaha pemerintah dalam mengatasi persoalan kemanusiaan di negeri ini. Per-lahan namun pasti, negeri ini terjangkit krisis moral akut: di sana-sini, orang si-buk dengan Blackberry, I-phone, I-pad, dan Apple-nya, namun mereka juga semakin cuek dengan realita kehidup an, tak peduli lagi dengan apa yang telah terjadi dengan keadaan sekitar. Setidaknya dalam lima ta-hun belakangan ini, peristiwa demi peris-tiwa “tak bermoral” pun marak terjadi, mulai dari teror bom buku, “pe rampokan” uang nasabah Citybank, kasus korupsi Ratu
Atut, hingga kasus pemerkosaan yang di-lakukan oleh Sitok Srengenge5 terhadap mahasiswi jurusan Sastra Jerman Univer-sitas Indonesia menjadi bukti kemerosotan moral bangsa ini.
Persoalan demi persoalan yang terjadi membuat rakyat gelisah. Rakyat merasa tak nyaman hidup di Indonesia. Perlahan namun pasti, banyak pihak baik individu maupun kelompok yang mulai memper-tanyakan eksistensi bangsa ini dari ber-bagai tempat, dan dengan kepentingan yang berbeda-beda pula. Sebenarnya ada apa dengan Indonesia? Siapa yang harus bertanggungjawab atas situasi kaos ini? Apakah Presiden beserta jajarannya atau masyarakat yang harus bertanggungjawab? Kegelisahan dan ketaknyamanan ini mem-buat rakyat bingung untuk percaya ke-pada siapa (lagi), rakyat menjadi bingung untuk memilih, sebab tak ada yang dapat menjamin secara pasti bahwa kehidupan rakyat Indonesia di masa mendatang akan jauh lebih baik dari sekarang. Apalagi ka-lau kita melihat sikap, dan tindak-tanduk para calon presiden dan wakilnya (entah dari partai politik manapun), seperti tak ada perbedaan. Parpol di Indonesia tam-paknya tak punya sikap tegas, dan cen-derung kekanak-kanakan. Semua tampak sama saja, baik partai X, partai Y, maupun partai Z, seperti tidak ada bedanya. Mereka semua sepakat mengatasnamakan rakyat, membela rakyat, pro rakyat, dan intinya embel-embel rakyat adalah harga mati untuk sebuah propaganda parpol (yang sebenar-nya hanya sebuah kamuflase belaka). Ini-lah yang tampak dalam peta perpolitikan
4 “Kita bisa mengikuti langkah-langkah nietzschean justru ketika kita menjadi diri kita sendiri. Personalitas pengala-man nietzschean tidak bisa dipahami dari luar –seolah-olah menjadi pengamat yang membedah korpus nietzschean. Ia justru bisa dipahami manakala kita sendiri memahami pengalaman personal kita.” Setidaknya dalam kata pen-gantar buku Gaya Filsafat Nietzsche yang diuraikan oleh Sindhunata digunakan istilah Gnosi se auton yang ber-makna: kenali dirimu sendiri! Lihat Wibowo, 2004 : xi.
5 Sitok Srengenge adalah seorang kurator seni di komunitas Salihara Jakarta.
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 15 4/24/2014 8:39:44 AM
16 Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos VOL II, 2014
bangsa kita dewasa ini. Tidak seperti di negara-negara maju, dengan dua atau tiga partai besar dimana posisi masing-masing partainya berbeda. Kebijakan dan sikapyang ditawarkanpun oleh partai tersebut juga jelas alias tidak hanya samar-samar berlindung di balik kata rakyat belaka. De-ngan begitu, rakyat macam apa yang me-reka perjuangkan pun menjadi jelas pula. Masyarakat tidak begitu dibingungkan. Mereka dapat melihat dengan jelas posisi partai mana yang lebih sesuai dengan as-pirasi mereka, itulah partai yang mereka pilih. Berbeda jauh dengan di Indonesia, dengan banyaknya partai, bukan semakin jelas posisi dan sikap mereka, malah seba-liknya, semakin tidak dapat dibedakan, se-makin tidak jelas.6
Sejak awal Februari 2014, kita sudah dapat menemukan pelbagai atribut partai yang menghiasi jalan-jalan kota besar di In-donesia. Mata kita “dipaksa” untuk meli-hat gemerlapnya iklan-iklan para kandidat calon presiden tersebut. Mereka mengobral janji! Namun apakah janji mereka dapat di-pertanggungjawabkan nantinya dan ber-nilai objektif? Atau itu semua hanya klise untuk mewujudkan ambisi mereka pada Pemilu 2014 mendatang? Mengenai hal itu, saya ingin mencoba mengangkat kembali pemikiranseorangfilsufJerman,FriedrichNietzsche lewat genealogi moralnya yang berlandaskan argumentum ad hominem. Se-bab lewat pemikirannya, (seakan) ia ingin menasehati kita para calon penyoblos di Pemilu 2014 mendatang agar mampu me-nilai seseorang dengan tepat lewat metode yang ia usulkan. Jika istilah ad hominem biasanya kita dengar sebagai salah satu je-nisdarikerancuanberfikir,Nietzscheakan
berkata lain, bahwa argumentum ad hominem sesungghnya memiliki peran sentral dalam genealogi moralnya, yakni sebagai metode untuk mendiagnosis pandangan kita ter-hadap realitas secara lebih mendalam.
Nietzsche menggunakan argumen ad hominem untuk menelanjangi apa yang diterima orang begitu saja sebagai kebenar-an dan moralitas. Caranya menelanjangi ber bagai konsep kebenaran dan moralitas suatu pemikir adalah dengan mencari rela-si esensial antara pikiran atau ide dengan pemikir bersangkutan. Cara menelanjangi berbagai konsep moralitas seperti inilah yang membenarkan argumen ad hominem (Solomon, 1996: 193). Baginya, kualitas atau nilai dari suatu pemikiran misalnya paham moralitas tergantung pada manu-sia bersangkutan dan konteks dimana nilai atau kualitas itu terbentuk. Kontekstualitas argumen ad hominem ini bisa kita temukan setidak-tidaknya pada dua ranah kehidup-an praktis, yakni ranah profesional dan ra-nah kehidupan sehari-hari.
Pada ranah profesional, kita biasanya mengakui dan menerima begitu saja kapa-sitas profesi yang dimiliki seseorang lewat gelaryangiasandang,ataulewatsertifikatyangiapunya.Keahlian,sertifikasi,peng-akuan internasional, merupakan beberapa contoh pengandaian yang berlaku di ranah profesional, dan yang pada akhirnya men-dudukkan orang yang memegang keahlian tersebut pada suatu posisi atau profesi ter-tentu. Argumen ad hominem persis melaku-kan investigasi terhadap pengandaian tersebut, yakni dengan menilik objektivi-tas, atau semacam prinsip bebas nilai yang diterapkan dengan sumpah atau janji, serta diawasi oleh pranata kode etik posisi atau profesi itu. Argumen ad hominem menilik
6 Bdk. dengan sebuah ulasan menarik mengenai sikap para parpol di Indonesia yang ditulis di salah satu blog alum-nus STF Driyarkara, yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di Roma, Italy. http://nikolaskristiyantosj.word-press.com/2012/08/19/parpol-butuh-sikap.
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 16 4/24/2014 8:39:44 AM
Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos YOGIE PRANOWO 17
dasar pengandaian tersebut bukan pada sumber pengetahuannya, melainkan pada kaitan antara keahlian dengan pegangan ideologinya.
Argumentum Ad hominem dan Genealogi
Argumen ad hominem7 merupakan metode yang sering digunakan dalam kehidupan bersama terlebih dalam berbagai dialog ataupun debat. Bukan hal yang baru ketika masyarakat melihat (setidaknya di televisi) bagaimana antara satu calon pemimpin/politisi dengan yang lainnya saling menye-rang dengan menggunakan argumen ad hominem. Banyak hal yang bisa dikaitkan sebagai senjata, misalnya saja, memba-wa-bawa ras, agama, cara kerja masa lalu musuh-politik bersangkutan hingga kredi-bilitas partai tempat sang lawan tersebut bernaung.8 Sementara berbagai ide atau visi yang dilemparkan terkait kesejahtera-an rakyat tidaklah diperhitungkan bah-kan tidak ditanggapi oleh pihak lawan. Adapun tujuan penggunaan argumen ad hominem yang dipakai tersebut adalah un-tuk menunjukkan pada masyarakat bahwa sang lawan bukanlah pribadi yang benar-benar sempurna dan layak memangku ja-batan pemimpin.
Lalu, sebenarnya apakah layak argu-men ad hominem ini digunakan dalam
perdebat an? Kita bisa saja dengan cepat langsung mengatakan bahwa argumen ad hominem tidak tepat karena ketika se-seorang menjadi seorang pemimpin, su-dah seharusnyalah ia memiliki ide atau visi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dan tidak hanya berdasarkan latar belakang ras ataupun agamanya saja. Namun, argumen ad hominem tidak serta-merta secara universal dapat dikatakan keliru. Argumen ad hominem sah saja di-gunakan dalam kasus-kasus tertentu. Mi-salnya, pada kasus persidangan yang di dalamnya saksi yang memberi kesaksian kemudian “diserang” dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kaitannya de-ngan kasus melainkan lebih mengarah ke-pada kehidupan saksi tersebut. Hal itu bisa saja dilakukan mengingat bahwa saksi bisa jadi dibayar untuk tidak mengatakan yang sebenarnya sehingga objektifitas dari ke-saksiannya dipertanyakan. Jadi penekanan argumen ad hominem adalah membongkar hingga ke kedalaman sehingga apa yang dianggap kebenaran benar-benar ditelan-jangi, dan dianalisis kemurnian atau objek-tivitasnya.
Dengan strategi ad hominem, sebe-narnya Nietzsche menampilkan diri seba-gai seorang pemikir yang menaruh curiga pada setiap pernyataan dogmatis, yaitu pernyataan yang menetapkan konsep dan
7 Istilah ad hominem setidaknya oleh sebagian besar orang dikenal pertama kali dalam kelas-kelas logika. Memang benar bahwa ad hominem masukdalamranahlogika,terutamadalam“kelompok”kerancuanberfikir.DalambukuPengantar Logika yang ditulis Arief Sidharta, dikemukakan bahwa argumentum ad hominem adalah bagian dari keran-cuan relevansi. Lebih lanjut, Sidharta, yang mengutip Irving Copi, menjelaskan bahwa dalam kerancuan relevansi terdapat sepuluh jenis kerancuan, salah satunya adalah argumentum ad hominem. “Kerancuan ini (argumentum ad ho-minem) terjadi jika suatu argumen diarahkan untuk menyerang pribadi orangnya, khususnya dengan menunjukkan kelemahan atau kejelekan orang yang bersangkutan, dan tidak berusaha secara rasional membuktikan bahwa apa yang dikemukakan orang yang diserang itu salah”. Lihat. Sidharta, 2010: 60.
8 Sebagai contoh, dalam majalah Indonesia 2014 no. 6, volume 1, tahun 2013, tertulis: “Dua tahun lalu, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dengan enteng menghinanya sebagai walikota (ndeso) yang bodoh karena menolak pembangu-nan mal di Solo […] Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul pun menghinanya dengan sindiran ‘mana bisa tukang mebel jadi capres’”. Dari ungkapan tersebut, Jokowi terlihat diserang dengan menggunakan ad hominem, karena serangannya diarahkan kepada orang yang bersangkutan, bukan kepada argumentasinya.
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 17 4/24/2014 8:39:44 AM
18 Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos VOL II, 2014
teori tertentu untuk berlaku secara pasti dan universal. Selain itu, ia juga mengarahkan perhatiannya pada kecenderungan moral seseorang yang terwujud dalam kebajikan serta kecacatan moralnya. Kecurigaan Ni-etzsche tersebut dapat dipahami sebagai semacam diagnosis. Maksudnya, Nietzsche mendiagnosis berbagai bentuk acuan nilai dan mengungkapkan apa yang sesungguh-nya menjadi pendorong orang untuk me-matuhi atau melaksanakan nilai tersebut. Diagnosis Nietzsche ini bersifat spekulatif, dan cara kerjanya adalah melalui penerap-an argumen ad hominem (Solomon, 2003: 99).
Argumen ad hominem itu sendiri meru-pakan dasar dari genealogi moral. Artinya dengan menggunakan metode ad hominem sebenarnya Nietzsche ingin membongkar apa yang di fixed-kan begitu saja, baik oleh tradisi, maupun oleh ajaran agama. De-ngan demikian ia ingin mencari sesuatu nilai yang lebih mendalam dari suatu re-alitas. Genealogi itu sendiri bagi Nietzsche adalah pertanyaan tentang apa yang ku-maui sesungguhnya saat aku menghendaki se suatu. Apa yang sesungguhnya dikehen-daki oleh kehendak, itulah yang dilacak dandicari. Isipemikiranfilosofis, isidok-trin,danmetodesaintifikdigunakanhanyasebagai symptom. Persoalan yang diajukan oleh genealogi bukanlah kebenaran atau kesalahan doktrin ideal, melainkan perso-alan tersebut hanya diperlakukan sebagai symptom untuk diselidiki oleh sang fisio-psikolog (Setyo Wibowo, 2004: 171). Lebih lanjut lagi, Nietzsche mengatakan bahwa terhadap apapun yang di fixed kan, hal tersebut akan didiagnosis ke kebertubuhan pemikir, ke soal bagaimana mekanisme penghendakan si pemikir bekerja. Metode ini mengarahkan bukan pada argumentasi
rasional, tetapi mencari mengapa pemikir-an seperti itu dikehendaki, dimaui, dan di-percayai (Setyo Wibowo, 2004: 172).
Genealogi juga merupakan sebuah proyek untuk mencari asal-usul dari nilai-nilai. Hal ini diangkat oleh Nietzsche ber-dasarkan ketidaksetujuannya terhadap pandangan tradisional yang mengang-gap bahwa nilai-nilai memiliki kebenaran pada dirinya sendiri terlepas dari campur tangan manusia. Penelusuran historis ter-hadapnya mau menghalau asumsi-asumsi metafisis, sambilberpalingkepada situasireal terbentuknya nilai-nilai tersebut. Studi sejarah moralitas pada zaman Nietzsche sebenarnya sudah dimulai oleh Paul Ree. Akan tetapi, Nietzsche tidak setuju de ngan pandangannya karena masih memuat asumsi-asumsi kebenaran final. Sejarahyang dimaksudkan Ree masih bercampur dengan teori evolusi Darwin yang mau menunjukkan alur maju sejarah perkem-bangan manusia. Hal ini ingin ditolak oleh Nietzsche.
Ree memang menyusun sebuah “se-jarah moralitas” namun sejarah yang di-maksud masih berkutat dengan spekulasi metafisisbahwaadaperkembanganlinearmenuju suatu tujuan tertentu seperti da-lam teori evolusi. Apa yang ditawarkan oleh genealogi adalah sejarah yang ber-warna ‘abu-abu’—tanpa cerita-cerita ro-mantik per kembangan manusia, yang ber-kutat dengan “teks hieroglif panjang, yang sulit dipecahkan, dari masa lalu moralitas manusia”—inilah yang tidak dimiliki oleh Ree. Artinya, jika kita mau jujur mempela-jari sejarah—dokumen-dokumen masa lalu, kita akan menemukan kompleksitas dan keterpecahan situasi-situasi dan keja-dian-kejadian yang membentuk moralitas, yang tidak akan bisa kita kerangkakan ke
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 18 4/24/2014 8:39:44 AM
Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos YOGIE PRANOWO 19
dalam sebuah alur yang rapi seperti teori evolusi. Inilah yang ingin ditunjukkan oleh genealogi: sejarah digunakan oleh genea-log justru untuk mengungkap bahwa mo-ralitas tidak punya “asal-muasal” (origin) yang utuh.9
Genealogi memang sebuah usaha un-tuk membongkar asumsi-asumsi menge-nai nilai dalam pandangan tradisional ser-ta memberi alternatif tafsiran yang baru. Namun, untuk mencapai hal itu orang tidak hanya berspekulasi saja, mengkri-tik sana-sini tanpa rujukan yang jelas. Se-baliknya, untuk mencapai kritik semacam itu seorang genealog harus terlebih dahulu mencemplungkan diri di antara tumpukan dokumen/ arsip-arsip sejarah; mengum-pulkan berbagai macam sumber dari mana saja, mempelajarinya dengan teliti untuk kemudian menjadikannya alat membong-kar asumsi-asumsi tradisional.
Genealogi, seperti dikatakan Nietzsche dalam “Genealogy of Morals” pada bagian pengantar paragraf dua, adalah sebuah usaha untuk mencari asal-usul dari nilai-ni-lai (Nietzsche, 1956: 150). Namun, asal-usul seperti apa yang dimaksud? Ber hadapan dengan dokumen-dokumen sejarah yang menunjukkan kompleksitas ke jadian-kejadian, penyimpangan-penyim pangan, dan kesalahan-kesalahan, seorang genealog tidak akan berpretensi untuk mem perbaiki susunan tak beraturan ini dan menyusun-nya dalam sebuah skema rapi. Sebaliknya
dengan dokumen-dokumen tersebut, ia akan menunjukkan bahwa apa yang ada di balik nilai-nilai yang kita pegang selama ini ternyata lahir dari segala macam komplek-sitas kejadian-kejadian seperti itu, dan de-ngan begitu punya asal-usul timpang yang dengannya tidak dapat lagi orang berkata bahwa nilai itu punya keluhuran yang in-trinsik di dalamnya. Di sinilah letak peran dari argumentum ad hominem yang diguna-kan Nietzsche. Argumentum ad hominem di-gunakan bukan dalam rangka menjelaskan kerancuan relevansi atau ke salahan ber-fikir, namun dalam rangka inginmenun-jukkan sesuatu yang sungguh real, sesuatu yang melampaui, dan sesuatu yang bagi paragenealogpenting,yaknimelihat/men-diagnosis gejala yang nampak dari tinda-kan agar akhir nya manusia atau kita dapat mengetahui realitas seada-adanya.
Nietzsche menolak realitas yang sering kali ditujukan berada di balik dunia senyatanya, yang menurut Plato adalah ide, menurut Descartes adalah kesadaran, atau bagi Kant adalah das ding an sich. Bagi Nietzsche, realitas yang ada itu adalah re-alitas seada-adanya. Dalam hal ini, terli-hat bahwa Nietzsche tidak ingin melihat terlalu jauh. Baginya, justru dengan meli-hat ke kejauhan ke dunia di sebrang sana, manusia seringkali lupa akan apa yang ada di sampingnya. Nietzsche ingin menunjuk-kan bahwa manusia seringkali ingin mem-
9 Pandangan mengenai genealogi Nietzsche ini pada akhirnya dikritik dan dilampaui oleh Foucault. Apa yang dipa-hami Foucault sebagai genealogi dalam banyak hal masih sejalan dengan Nietzsche, yaitu dalam hal konsep dasar dari genealogi sebagai sebuah usaha, dengan memakai sejarah, mengungkap asal-usul nilai-nilai yang akan mem-bongkar asumsifinalitas.Namun,persis di sini juga terlihat perbedaan, bahwaFoucaultmenyerukankematiansubjek sementara Nietzsche tidak sampai se-ekstrem itu. Titik perbedaan lainnya adalah bahwa genealogi Foucault dipraktekkan di dalam sebuah disiplin studi yang ketat, bergumul dengan dokumen-dokumen sejarah, dan men-uliskan fakta-fakta yang detail, sementara pada Nietzsche tidak. Dapat terlihat bahwa Foucault mengekstrimkan Nietzsche.“Genealogy does not oppose itself to history as the lofty and profound gaze of the philosopher might compare to the molelike perspective of the scholar; on the contrary, it rejects the metahistorical deployment of ideal significations and indefinite teleologies. It opposes itself to the search for ‘origins’.”Bdk.Foucault,1998:370.
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 19 4/24/2014 8:39:44 AM
20 Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos VOL II, 2014
buat fiksi tentangdunia yang lebih nyatadari kenyataan. Bagi Nietzsche, cogito, das ding an sich, dan roh absolut hanyalah kha-yalan belaka (Wibowo, 2004: 112).
Realitas seada-adanya itu bagi Ni-etzsche memiliki sifat kontradiktif, am-bigu, kaos, juga benar dan salah10. Namun ia tidak berhenti disitu saja. Ia tentu saja berusaha untuk memahami realitas seada-adanya itu melalui kata. Dan pada saat bersamaaan, ia sadar mengenai keterba-tasan kata itu sendiri. Walaupun demikian, ia tetap menggunakan kata, namun tidak berujung pada fiksasi sebuah idea ataukonsep. Baginya, lewat kata yang ada, pe-mikiran dapat membuat kita paham atas apa yang lebih luas lagi (Wibowo, 2004: 236).
Nietzsche beranggapan bahwa realitas bersifat kaotik dan konsep-konsep tentang-nya selalu merupakan merupakan peng-kata-an terlambat dalam usaha meng-kos-mos-kan kaos tersebut. Realita yang kaotik ini membuat orang terserak-serak: terlem-par dari satu situasi ke situasi lain, mera-sakan denyut-denyut hasrat yang tidak be-raturan di dalam dirinya dan sebagainya. Manusia tidak akan tahan hidup di dalam realita yang membuatnya terserak seperti ini. Maka, dari dalam dirinya selalu ada kompleksitas kehendak yang bekerja untuk mengomando dirinya sendiri, keluar dari situasi keterpecahan menuju keutuhan. Namun, kehendak selalu dapat dibedakan antara yang kuat dan yang loyo. Genealogi adalah suatu usaha untuk mengungkap ke-hendakdibaliksetiapmoralitas;apayangterungkap bukan masalah benar-salahnya moralitas tersebut, melainkan kualitas ke-hendak yang menghendakinya. Morali-tas yang di-fixed-kan, diberi sifat ilahi,
dan diluhurkan hanya menunjukkan sifat loyo dari kehendak seseorang. Genealogi akan memperlihatkan bahwa berhadapan dengan realitas yang kaotik, orang terse-but tidak mampu mengukuhkan dirinya sendiri sehingga memilih untuk mencari pegangan di luar dirinya yang dengannya ia merasa utuh. Hasilnya adalah moralitas-budak, yaitu moralitas yang di dalamnya orang memberikan diri tunduk kepada otoritas konsep-konsep atau nilai di luar dirinya. Apa yang akhirnya tampak mela-lui genealogi adalah bahwa di balik nilai-nilai yang dianggap luhur, punya esensi, tetap, dan sebagainya ternyata merupa-kan produk dari apa yang terpecah-pecah. Moralitas bermula dari respon orang ter-hadap realita yang kacau. Kalau ada asal-mula, asal-mula tersebut bersifat kaotik dan penuh kesalahan. Patut diperhatikan disini bahwa konsep ‘realita sebagai yang kaotik’ dalam pemikiran Nietzsche harus dimengerti sebagai peng-kata-an terlam-bat dari realita. Nietzsche tidak bermak-sud mengungkap realita pada dirinya atau mengakomodasi keseluruhan realita di da-lam kata ‘kaotik’. ‘Realita kaotik’ hanyalah perkataan sementara yang tidak berpret-ensi menemukan sebuah kebenaran akhir. Perkataan ini tidak dimaksudkan untuk menangkap realita yang tidak terkatakan, yang sudah mendahului kata ‘realita kao-tik’ itu sendiri.
Peran Tubuh bagi Pemikiran
Nietzsche sering mengklaim dirinya sebagai seorangpsikolog(Solomon,1996:180),yangseringkali tidak ditanggapi secara serius olehparafilsuf.Apabilafilsufmenyatakandengan tegas tentang kebenaran dari suatu
10 Bdk. Wibowo, 2004: 111, 114.
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 20 4/24/2014 8:39:45 AM
Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos YOGIE PRANOWO 21
hal yang dipercayai, maka para psikolog lebih tertarik kenapa seseorang memercayai sesuatu. Seorang psikolog lebih cenderung memeriksa mengapa seseorang berpegang atau percaya pada ‘kebenaran-khusus’ se-dangkanseorangfilsufmemeriksaapa‘ke-benaran’ itu. Nietzsche sendiri mengatakan bahwa psikologi-lah jalan menuju problem yang fundamental. Namun psikologi yang dimaksudkan Nietzsche bukanlah seperti pemahaman psikologi modern (yang pada umumnya). Psikologi bagi Nietzsche bu-kan berhubungan dengan kisah atau cerita tentang ‘pikiran. Psikologi bagi Nietzsche berhubungan dengan tubuh, tentang pem-bentukan diri melalui praktek (dinamika) sosial beserta pengarahnya.
Apabila doktrin filosofis menyajikanke universalan dan keniscayaan, maka ana -lisis psikologis pastilah tetap akan terikat pada kontingensi partikular dari kerpibadi-an atau diri seseorang. Hal tersebut bisa terlihat pada serangan Nietzsche ter-hadap Sokrates dimana ia malah mengejek Sokrates sebagai si miskin yang buruk rupa atau menyebut Kant sebagai dekadensi Jer-man. Nietzsche memandang dirinya send-irisebagaipakardiagnostik,danfilsafatnyasendiri terdiri dari begitu banyak diagnosis spekulatif, mengenai kebijaksanaan maupun sifat buruk dari mereka yang bukunya dia baca. Argumentum ad hominem yang di-gunakan oleh Nietzsche tidaklah sebegitu telak membuktikan kesalahan dengan ter-kadang bertitik tolak dari emosi pathetic. Nietzschemelakukan refleksi,dan speku-lasi tentang motif dan emosi tersembunyi yang menggerakkan orang-orang tentang “mo ral” dan secara dogmatis membela berbagai kepercayaan. Dia ingin memaha-mi apa yang disebutnya sebagai “kehendak akan kebenaran” dan dia ingin merambah ke sifat asli dari sentimen pra sangka terse-but sebagai belas kasih, kesaleh an, dan ter-utama sekali apa yang terjadi dengan “cin-
ta”. Di atas itu semua, dia ingin melacak perubahan dari serangkaian kemunafik-an yang khas serta tersembunyi namun membahayakan dari emosi-emosi yang memungkinkan munculnya sesuatu yang kemudian kita sebut sebagai “moralitas”, khususnya “ressentiment” beserta prinsip, dan prasangka moralnya yang berjangkau-an jauh.
Nietzsche juga merupakan seorang pemikir yang berusaha membawa kem-bali peran penting tubuh bagi pemikiran. Ia tidak setuju dengan pandangan bahwa pemikiran adalah sesuatu yang dapat lepas sama sekali dari tubuh. Pemikiran tidak hanya keluar dari roh atau jiwa manusia, melainkan dari seluruh kebertubuhan ma-nusia itu sendiri, dari darah dan daging-nya. Nietzsche melawan setiap pemikiran dualistik tentang manusia yang memper-lawankan tubuh dan jiwa. Baginya, tubuh adalah pemikiran dan tidak ada pemikiran yang tidak bertubuh (Wibowo, 2004: 43-44).
Doktrin bahwa ada pemikiran yang terlepas dari kebertubuhan hanyalah meru-pakan pelarian seorang pemikir dari realita kebertubuhan yang penuh dengan impuls-impuls, keresahan-keresahan, hasrat, dan instabilitas yang sulit dikendalikan. Hal ini hanya akan menunjukkan keloyoan kehendak sang pemikir yang tidak berani berhadapan dengan realitas yang kaotik. Dengan buah pemikiran yang mereka ang-gap terlepas dari tubuh: esensi, sifat tetap, keluhuran, dan sebagainya. Mereka dapat merasa lebih nyaman, sebab realita mereka percayai sebagai suatu keteraturan. Apa yang ditunjukkan dari hal itu adalah bah-wa pemikiran yang mencari esensi tetap hanya lah ilusi akibat kesalahpahaman me-rekaatastubuh;“jangan-jangansemuafil-safat sampai saat itu hanyalah sebuah ekse-gesis terhadap tubuh dan kesalahpaham an terhadap tubuh.” Menurut Nietzsche selu-
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 21 4/24/2014 8:39:45 AM
22 Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos VOL II, 2014
ruh filsafat, etika, sains, atau pandanganapapun yang berpretensi menemukan ke-benaran akhir.
“[…] apakah bukan penyakit yang mengilha-misifilsuf.Kebutuhanfisikyangdisamarkandengan topeng objektivitas, ide, intelek murni, bisa mengambil bentuk yang mengerikan—dan setelah saya menghitung ini semua, saya sendiri sering bertanya pada diri saya sendiri, jangan-jangan semua filsafat sampai saat ituhanyalah sebuah eksegesis terhadap tubuh dan kesalahpahaman terhadap tubuh.” (Nietz-sche, 2003)
Kutipan di atas ada dalam konteks membahas hubungan sakit dengan pe-mikiran bahwa penyakit yang tidak diha-dapi secara waspada dapat membuat orang mengambil reaksi yang naif, yaitu lari ke-pada pemikiran-pemikiran final. Denganini genealogi menolak analisis pemikiran yang melulu hanya berkutat pada soal bagaimana satu pemikiran kontras dengan pemikiran lain atau bagaimana rasionali-tas dari suatu sistem nilai. Genealogi akan mengungkap relasi pemikiran seseorang dengan tubuhnya; pemikiran adalah ha-sil dari bagaimana orang menanggapi ke-adaan tubuhnya yang penuh instabilitas dan keterserakan. Teori tradi sional berang-gapan bahwa sebuah ide dapat ditegakkan oleh suatu oknum karena memang sejak awal oknum tersebut hendak memper-juangkan sebuah tujuan. Penjara, misalnya, dibuat agar mendatangkan efek jera. Gene-alogi akan curiga dengan pemahaman se-perti ini. Genealogi akan menyingkapkan bahwa apa yang mendo rong munculnya ide-ide bukanlah suatu tujuan rasional me-lainkanpermainandominasi/kekuasaan.
Apa yang genalogi tunjukkan malah bahwa perjanjian damai itu sendiri adalah wujud dari dominasi yang sedang menang. Dominasi lain tidak akan berhenti dan te-rus membayangi dan mengulangi adegan
yang sama di balik layar. Perjanjian damai selalu saja terancam oleh kekuatan baru yang ingin meruntuhkannya. Nietzsche, masih mengandaikan adanya pemberian style atau gaya pada realitas yang mengan-daikan secara niscaya sebuah diri-seniman atau subjek yang utuh (Wibowo, 2004: 253). Di dalam pemikiran Nietzsche kita tidak hanya mengenal manusia dekaden, yang terjerat di dalam permainan kekuasaan otoritas di luar dirinya. Kita juga mengenal manusia menaik, yang dengan kreativi-tas mengolah kaos di dalam diri nya men-jadi kosmos tanpa terjebak di dalam ide fix. Hal ini mengandaikan adanya subjek “hidup”—yang lahir dari kompleksitas penguasaan dorongan kaos—yang tidak tunduk atau bergantung kepada kekuatan di luar dirinya, sebaliknya mampu meme-rintah dan mengukuhkan dirinya sendiri.
Nietzsche tidak memaksudkan kata dan konsep ‘kehendak’ dapat mengako-modasi keseluruhan kedalaman realita. ‘Kehendak Kuasa’ hanyalah peng-kata-an terlambat dari realita yang tidak bisa be-gitu saja di singkap sepenuhnya. Di dalam Nietzsche dibedakan realitas sebagai ke-dalam-an dan realitas pada permukaan. Peng-kata-an atau konsep-konsep kita mengenai realita hanyalah menyentuh permukaan realita, tetapi tidak pernah merengkuh ke-dalam-annya. Maka, pada pemikiran Nietzsche selalu masih diberi-kan ruang bagi ke-dalam-an realita yang tidak dapat di singkap begitu saja. Realitas adalah kedua-duanya: ke-dalam-an dan permukaan.
Moralitas dalam Perspektif Nietzschean
Lewat penggunaan argumen ad hominem, Nietzsche ingin kita melihat melampaui permukaan moralitas tradisional untuk masuk ke dalam perkembangan histo-ris dan manusia aktual dibalik moralitas
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 22 4/24/2014 8:39:45 AM
Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos YOGIE PRANOWO 23
tersebut (Solomon, 1996: 187). Apa yangdianggap benar secara moral tergantung pada konteks seperti bagaimana pandang-an seseorang, budaya, dan pengalaman baik dalam keluarga, teman, kelas dalam masyarakatsertaposisifinansialseseorang(Solomon, 1996: 195). Pandangan moralitas Nietzsche yang seperti ini sangat terkait dengan pandangan perspektivisme yakni, bahwa seseorang selalu mengetahui atau berpikir tentang sesuatu dari perspektif tertentu saja (Solomon, 1996: 195). Dari sini-lah kita bisa melihat bagaimana bangunan moralitas Nietzsche juga terkait dengan perspektivisme. Lantas pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana men-jelaskan posisi kebenaran seturut kerangka perspektivisme dalam pandangan morali-tas Nietzsche?
Pandangan moralitas Nietzsche yang lekat dengan perspektivisme melahirkan pertanyaan mengenai apakah ada kebe-naran dalam dirinya sendiri? Perspek-tivisme jika tidak dibawa hati-hati dapat melahirkan kesalahan interpretasi sehingga jatuh pada relativisme. Ada dua kesalah-anyangmungkinmunculyakni;pertama,anggapan bahwa interpretasi tidak memi-liki dasar dan perspektif yang satu dengan lainnya tidak bisa dibandingkan. Kedua, perspektivisme tidak memiliki dasar dari-mana suatu perspektif tidak bisa di evalua-si kebenarannya (Solomon, 1996: 196). Dengan kata lain, setiap pemikiran tidak bisa dievaluasi kebenarannya karena tidak memiliki dasar dan tidak bisa dibanding-kan satu sama lain. Anggapan ini tentulah tidak tepat karena suatu perspektif selalu merupakan perspektif akan sesuatu. Sa-ngat mustahil jika kita berbicara mengenai perspektif dari sesuatu tanpa melibatkan perbandingan perspektif dalam kaitan-nya dengan “sesuatu” tersebut. (Solomon, 1996: 196). Lalu bagaimana dengan kebe-naran atau fakta itu sendiri? Jawabannya
bisa ditemukan dalam karyanya “Beyond Good and Evil” di mana ia mengklaim bah-wa tidak ada fakta-fakta, yang ada adalah interpretasi. (Solomon, 1996: 196).
Kebenaran terkait perspektivisme da-lamfilsafatNietzscheiniharusdilihatda-lam konteks moralitas yang dibangunnya. Nietzsche membedakan dua jenis moralitas yakni;moralitastuandanmoralitasbudakyang diperkenalkannya lewat genealogi moral yang tak lain adalah penyingkapan kedok nafsu-nafsu, berbagai kebutuhan, ketakutan, dan harapan yang terung-kap dalam sebuah pandangan moralitas (Hardiman, 2011: 232). Baik kebenaran maupun moralitas yang berkembang da-lam masyarakat adalah hasil bentukan dari kepribadian sang pemikir dan konteks ke-hidupannya.
Dalam moralitas tuan, moral merupa-kan ungkapan hormat dan penghargaan terhadap diri mereka sendiri. Mereka sa-ngat yakin bahwa apa yang dikerjakan ada-lah baik dalam arti “ningrat” namun tidak mengatakan bahwa moralitasnya berlaku universal (Hardiman, 2011: 232). Bagi para tuan, yang menjadi persoalan bukanlah baik atau jahat melainkan apa kah tindakan tersebut merupakan tindakan “ningrat” atau rendah. Berbeda dengan moralitas kaum tuan, kaum budak sangat terobsesi dengan persoalan yang melibatkan ka-tegori jahat dan keutamaannya (Solomon, 1996: 206). Dengan kata lain, suatu tindak-an dilihat mereka dalam kerangka baik atau jahat. Salah satu contoh menarik yang diberikan Nietzsche terhadap jenis mo-ralitas ini adalah perumpamaannya me-ngenai domba dan elang. Dalam perumpa-maan tersebut, para domba merasa sangat marah kepada elang yang selalu menukik dan berusaha untuk mengambil salah satu domba. Kemarahan para domba tidak bi-sa dilampiaskan kepada elang ka rena mereka tidak mempunyai kemampuan
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 23 4/24/2014 8:39:45 AM
24 Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos VOL II, 2014
untuk melawan elang. Para domba yang membenci elang kemudian membentuk suatu pemikiran yakni elang merupakan makhluk yang jahat dan domba sebagai korban adalah yang baik. Berbeda dengan domba, sang elang justru sangat menyukai domba. Elang mencintai daging domba se-hingga tidak ada alasan untuk membenci domba-domba itu.11 Cerita tersebut meng-gambarkan bagaimana Nietszche melihat moralitas di zamannya seperti layaknya para domba. Domba-domba tersebut tidak bisa menguasai elang dan dalam kemara-hannya yang tak disertai kemampuan un-tuk membalas, para domba kemudian ber-usaha menguasai elang dalam dunia nilai dimana elang dikategorikan sebagai “yang jahat”. Moralitas domba inilah yang dise-but Nietszche sebagai moralitas kaum bu-dak. Moralitas ini menuntut adanya suatu universalitas moral yang menguntungkan para kaum tertindas.
Dengan membentuk dalam pikirannya bahwa kaum tuan adalah “jahat” maka se-tiap kualitas dan tindakan dari kaum tuan pundijungkirbalikan.Segalakualitasbaikyang dimiliki kaum tuan yakni, kedaulatan diri, kekuasaan, dan keningratan dibenci dan diganti oleh kualitas seperti, sim-pati, kelemahlembutan, kerendahan hati. (Hardiman, 2011: 233). Moralitas budak ini-lah yang dipertahankan oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, moralitas budak dibentuk bukan oleh kumpulan perso-alan sosial melainkan oleh kondisi pathetic dari pikiran, yang merupakan kumpulan emosi-emosi reaktif. (Solomon, 2006: 207). Emosi reaktif menunjukkan bahwa kaum budak tidaklah bertindak dari diri sendiri melainkan menunggu atau tergantung pada aksi dari luar. Apa yang mendorong
moralitas kaum budak ini? Bagi Nietzsche, dorongan kuat terciptanya moralitas kaum muda adalah rasa benci yang tidak bisa disalurkan lewat tindakan (ressentiment).
Menurut Nietzsche, rasa benci ini me-rupakan emosi yang buruk dimana bagi kaum tuan, emosi seperti ini tidak ada dan tidak dapat dirasakan oleh mereka (Solo-mon, 2006: 210). Emosi kebencian yang dipendam oleh kaum budak ini suatu saat meledak menjadi kekuatan yang besar untuk mengalahkan kaum tuan. Namun usaha mengalahkan ini bukanlah terjadi di dalam dunia nyata seperti politik ataupun hukum melainkan terjadi pada dunia ima-jiner dimana tatanan nilai dijungkirbalik-kan. Dengan kata lain, ressentiment menjadi daya kreatif untuk menciptakan nilai-nilai (Hardiman, 2011: 233). Nilai-nilai dari ma-nusia unggul atau kaum muda diturunkan derajatnya sebagai “nilai yang jahat” se-mentara nilai kaum budak dinaikkan men-jadi “nilai yang baik”. Moralitas kaum bu-dak inilah yang dikenal sebagai moralitas kristiani dimana segala apa yang rendah, lemah, celaka, jelek, dan menderita malah disebut “baik” (Hardiman, 2011: 234).
Dari penjabaran mengenai moralitas tersebut, kita bisa melihat bagaimana Ni-etzsche menggunakan argumen ad homi-nem untuk menjelaskan apa sebenarnya yang ada dibalik moralitas masyarakat. Ia mempertanyakan moralitas kristiani yang berkembang pada masanya dan mencoba menganalisa bukan pada seberapa benar argumen atau pemikiran terkait suatu mo-ral melainkan mencoba menggali intensi-intensi yang ada dibalik moral tersebut. Tujuan dari analisis Nietzsche ini bukan-lah pertama-tama untuk mengagungkan moralitas kaum tuan di atas kaum budak,
11 Nietzsche mengilustrasikan cerita tersebut dalam teks ‘Genealogi Moral’ I, paragraf 13. Kutipan teks tersebut bisa dilihat juga dalam: Robert C. Solomon, 2006, hlm. 204-205.
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 24 4/24/2014 8:39:45 AM
Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos YOGIE PRANOWO 25
melainkan semata-mata sebagai tanggapan kita kepada realitas yang kaos. Ia menun-jukkan bahwa kita patut merasa curiga akan berbagai hal dibalik setiap klaim ke-benaran dan moralitas. Jika kita kembali melihat pandangannya mengenai morali-tas maka bisa kita katakan bahwa morali-tas merupakan hasil bentukkan dari manu-sia bersangkutan dan konteks kehidupan dimana manusia itu berdiam. Namun, ia tidak hanya bermaksud menunjukkan bah-wa moralitas merupakan hasil bentukkan dari manusia bersangkutan dan konteks kehidupan melainkan lebih dalam dari itu yakni, memeriksa manusia atau subjek ber-sangkutan apakah masuk dalam tipe ma-nusialemah/dekadenatautipekuat/ascen-den (Wibowo, 2004: 171).
Kedua tipe manusia di atas memiliki perbedaan dalam menerima realitas. Bagi tipe manusia lemah diperlukan kebutuh an untuk percaya. Dalam masyarakat Eropa saat itu, kepercayaan pada moralitas dan ajaran kristiani masih sangat diperlukan se-hingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Eropa menurut Nietzsche adalah masyara-kat yang dekaden atau kelompok manusia lemah. Sementara manusia yang bertipe kuat adalah manusia yang mampu meng-ambil jarak dari kebutuhan untuk percaya ini (Wibowo, 2004: 172). Dengan demikian, moralitas kristiani tidak hanya menjung-kirbalikan nilai tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat Eropa saat itu masihlah merupakan kumpulan manusia-manusia lemah. Manusia yang lemah tergambar jelas pada perumpamaan mengenai domba dan elang dimana domba adalah gamba-ran manusia lemah. Dalam kelemahannya, para domba menciptakan konsep “elang sebagai yang jahat” dan mempertahankan hal tersebut sebagai suatu kepercayaan. Terkait dengan kebutuhan akan percaya yang melanda Eropa Nietszche menulis:
“Menurutku Di Eropa saat ini kristianis me ma-sih dibutuhkan oleh kebanyakan orang. nya mengapa kristianisme masih dipercaya. Kare-na manusia memang terbentuk seperti itu. Jika ia membutuhkan sebuah ajaran iman, pun jika ajaran itu dibantah dengan seribu satu macam cara, dia tidak akan berhenti untuk meme-gangnya sebagai “benar”- sesuai dengan apa yang sangat terkenal dalam kitab suci: “bukti yang tak terbantahkan”......” (Wibowo, 2004: 175-176)
Melalui kutipan di atas kita bisa me-ngetahui bagaimana pandangan Nietzsche terhadap situasi masyarakat Eropa zaman itu. Dari pandangannya mengenai kebutuh-an akan percaya dan persoalan moralitas yang melanda Eropa ini, kita bisa melihat bagaimana Nietzsche berusaha sekaligus untuk mengambil jarak terhadap realitas dimana ia hidup. Dengan mengambil jarak ini, ia mampu menelaah secara lebih men-dalam apa yang ada dibalik moralitas ma-syarakat zaman itu dengan menggunakan argumen ad hominem. Argumen ad homi-nem oleh Nietzsche justru dipergunakan bukan untuk menyerang setiap pemikir-an yang berkembang, melainkan untuk menunjukkan bahwa setiap pemikiran ter-masuk di dalamnya moralitas perlu dikaji lebih mendalam sehingga kita me nemukan pemaham an yang lebih menyeluruh.
Filsafat Nietzsche tidak bisa hanya dini-lai sebagai suatu pengakuan, dengan kata lain,isidarifilsafatNietzschebukanhanyaterdiri dari persoalan psikologis semata. Namun tidak berarti bahwa argumen ad hominem tidak perlu diterapkan. Argumen ad hominem sendiri bukanlah semata-mata “penyerangan” atas seorang pemikir tapi lebih daripada itu, mencoba melihat latar belakang dan berbagai unsur yang men-dorong terciptanya suatu pemikiran. Hal di atas sesuai dengan pandangan Nietz-schemengenaisuatupemikiranataufilsa-fat. Filsafat bagi Nietzsche pertama-tama bukan hanya merupakan argumen atau
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 25 4/24/2014 8:39:45 AM
26 Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos VOL II, 2014
penolakansebuahargumen, tetapifilsafatadalah sebuah keterikatan (Solomon, 2006: 217). Filsafat memperlihatkan pandangan dari seorang filsuf dan mengartikan ke-terikatannya dengan dunia serta relasinya dengan manusia lain (Solomon, 2006: 216). Dengan demikian, kita tidak hanya perlu bertolakdari isipandanganseorangfilsuftetapi juga harus jeli memperhatikan apa yang ada dibalik pemikiran tersebut.
Sebagai contoh, seseorang yang kelihat-annya baik, belum tentu secara hakiki ia baik. Ada motif/dorongan tertentu yangharus diselidiki secara mendalam. Apakah seseorang yang berkelimpahan harta yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan sebuah rumah ibadah, pada dasarnya adalah seorang yang sungguh-sungguh baik? Atau itu hanya klise, agar ia dianggap baik? Sama halnya dengan apa-kah para kandidat calon presiden beserta jajarannya yang (misalkan saja) membagi-kan uang, sembako, dan sebagainya sung-guh orang baik yang tulus membagikan-nya demi alasan kemanusiaan? Atau hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk menarik simpati masyarakat agar memili-hnya pada PEMILU mendatang? Bagi Ni-etzsche, konsep baik dapat ditinjau dari dualitas makna antinominya, yaitu buruk dan jahat. Sepanjang sejarah bagi Nietsche, telah terjadi penjungkir-balikan nilai oleh kaum budak.12 Budak mengatakan tidak pada segala sesuatu yang ada diluar diri-nya, sementara tuan mengatakan ya. Bagi tuan, kekeliruan yang melahirkan tragedi bagi manusia adalah sebuah keberadaan di ranah yang keliru saja tetapi tidak jahat. Budak digambarkan sebagai orang yang terpecah dalam personalitasnya. Dalam “Genealogy of Morals” bagian satu para-
graf15(Nietzsche,1956:182-185)dikatakanbahwa menurut Nietzsche, yang memper-budak manusia tak lain adalah adanya de-terminasi Allah yang ironisnya diciptakan dalam konsep manusia yang serba terba-tas. Outletnya adalah kecemburuan hebat atau ressentiment terhadap yang berbau moralitas tuan. Ia mengekang diri demi pembalasan yang tidak mampu diusa-hakan kepada sang pemberani. Inilah yang harus dikerjakan: Nietzsche’s ja-saagen, a re-evaluation of all values, a new determination, a new comportment toward existence. Evaluasi nilai baik dan buruk harus dilakukan agar manusia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Re-evaluasi nilai berarti melampaui apa yang bagi moralitas popular merupakan baik dan buruk.
Penggunaan ad hominem
Pada bulan April tahun ini, bangsa Indo-nesia akan merayakan tahun politiknya, dengan agenda pencoblosan untuk memi-lih wakil rakyat untuk periode lima tahun kedepan. Namun, menjelang pesta politik tersebut, rakyat kebingungan untuk me-nentukan pilihannya. Rakyat bingung un-tuk memilih serta bingung untuk percaya kepada siapa, sebab seperti tak ada perbe-daan antara sikap parpol yang satu dengan lainnya. Apalagi mendekati waktu pencob-losan, begitu banyak iklan-iklan yang bu-kan hanya ada di layar kaca televisi, tetapi juga di jalan-jalan ibukota yang kerap me-nyilaukan mata karena janji-janji mereka yang bernada sama, yakni demi kepenting-an rakyat. Tidak jelas demi kepentingan rakyat yang mana dan seperti apa.
Hal ini menimbulkan persoalan. Per-soalan ini sebenarnya dapat diatasi jika pihak yang terlibat secara khusus, pihak
12 “ […] that the slaves revolt in morality begins with the Jews: a revolt which has two thousand years of history behind it and which has only been lost sight of because-it was victorious […]” Bdk. Nietzsche, 1956: 173-176.
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 26 4/24/2014 8:39:45 AM
Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos YOGIE PRANOWO 27
yangadadalamparpolmaumerefleksikanhidupnya dengan lebih serius lagi, dengan lebih dalam lagi. Hal itu dapat ditempuh salah satu caranya dengan mendengarkan dan menjalankan laku-tapa dari pemikiran Nietzsche.
Bagi Nietzsche kedalaman ha nya bisa dialamisendirianlewatrefleksi.Pengkata-an akan kedalaman tak akan pernah me-ngatakan kedalaman itu sendiri. Alih-alih mengungkapkan secara persis apa yang mau dikatakan, kata ternyata hanya topeng atas apa yang mau dikatakan. Kesadaran tajam akan keterbatasan kata sebagai to-peng itulah yang membuat Nietzsche me-masukkan dirinya pada permainan topeng. Topeng adalah penyamaran, dan sejauh itu pula, bagi Nietzsche, topeng adalah strategi untuk menyampaikan kedalaman. Dalam “TheGayScience”paragraf381,Nietzschemengatakan bahwa kita tidak ha nya ingin dimengerti saat kita menulis se suatu, teta-pi juga supaya tidak dimengerti oleh sem-barang orang.13 Dia tidak mau dipahami secara gampangan dan meng ajak setiap pembacanya untuk menjadi diri nya sen-diri. Pengalaman kedalaman mesti dimiliki justru supaya orang bisa menari di permu-kaan dengan topeng tanpa tergoda untuk mengeraminya.
Topeng bagi Nietzsche, selain menya-markan sesuatu di balik topeng juga ber arti menyuarakan dan mengkomunikasikan secara lebih keras kedalaman yang ingin disuarakan. Nietzsche bermain dengan to-peng, bertahan di level permukaan, bukan karena dia tidak tahu soal kedalaman teta-pi justru karena dia tahu diri di depan apa yang mendalam. Lagipula sudah kodrat-
nya kedalaman untuk selalu menyelubu-ngi dirinya dengan penyamaran.
Mungkin salah satu sosok yang ber-main dengan topeng adalah Jokowi. Kita lihat saja, bagaimana reaksi masyarakat ketika PDI-P mengumumkan bahwa kan-didat presiden dari partai itu adalah Joko Widodo, seorang figur yang selama inimenjadi buah bibir dimana-mana. Begitu banyak reaksi yang muncul, ada yang me-ngatakan bahwa Jokowi tak harus banyak berkampanye, karena kemenangan adalah keniscayaan buatnya, ada pula yang menga-takan bahwa pencalonannya sebagai presi-den adalah kesalahan prosedural, lantaran masa jabatannya sebagai Gubernur DKI belumlah seumur jagung. Dengan adanya reaksi-reaksi tersebut Jokowi hanya ber-sikap tenang. Sikap Jokowi yang tenang ini memunculkan beberapa interpretasi. Perta-ma, sikap tenang Jokowi ini dinilai sebagai bukti kalau sebenarnya ia masih menyusun sebuah strategi besar dalam “peperangan” politik. Kedua, sikap tenang Jokowi ini menggambarkan sosok pemimpin yang arifbijaksana.Ketiga,sikaptenangJokowiini, tak berarti apa-apa alias karena ia me-mang tak tahu harus bersikap apa.
Dengan pencalonannnya sebagai pre-siden, dan jika kita mengacu pada argu-mentum ad hominem, maka sebenarnya kita tak boleh begitu saja menerima superioritas Jokowi, melainkan kita harus mendiagno-sisnya seperti apa yang diusulkan oleh Ni-etzsche lewat genealogi moralnya. Dalam majalah Indonesia 2014 no 6, vol. 1, tahun 2013, dikatakan bahwa Jokowi hadir dalam momentum yang tepat. Ia hadir di tengah masyarakatJakartayangmerindukanfiguryang menarik seperti Jokowi. Daya tarik
13 “One does not only wish to be understood when one writes; one wishes just as surely not to be understood […] he didn’t want to be understood by just anybody […]” Bdk. Nietzsche, 2003: 245.
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 27 4/24/2014 8:39:45 AM
28 Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos VOL II, 2014
Jokowi terletak pada kebiasaannya blusu-kan dan gaya komunikasinya. Ia dianggap sebagaifiguryangotentik,danitudisukaioleh warga Indonesia, khususnya Jakarta. Lepas dari suka atau tidak suka terhadap sikap Jokowi, kita masih harus memper-tanyakan kinerjanya di kursi pemerintah-an. Selama masa Pemerintahannya di Solo, memang harus diakui bahwa Jokowi ber-hasil memberikan dampak positif, namun Solo berbeda dari Jakarta dan Indonesia. Menangani Jakarta, Jokowi juga terlihat begitu fasih manakala berhadapan de-ngan rakyat kecil, ia pun berhasil merapi-kan pasar Tanah Abang, sehingga sekarang pasar itu tidak lagi terlihat kumuh.
Namun kepemimpinannya dalam menangani Jakarta masih seumur jagung, dan kini ia telah dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon presiden. Seandainya ia ber-hasil keluar sebagai pemenang dalam PE-MILU mendatang, apakah seorang Jokowi mampu memegang tampuk pemerintahan Republik Indonesia?
Kalau kita berpijak pada gagasanNi-etzsche menyangkut strategi penerapan argumen ad hominem, dan pandangan ge-nealogis terhadap moralitas, pertanyaan tersebut harus dijawab dengan menggu-nakan suatu diagnosis psikologis dan in-vestigasi historis dengan terus bertanya dan mempertanyakan kehidupan sehari-harinyaberkenaandengankebijakanatauvisi misi yang (akan) ia lontarkan kepada publik.
Penutup
Dengangayaargumentasifilsafatnya,yak-ni dengan memakai analisis genealogi yang mengejawantahkan teori perspektivis me dan argumentasi ad hominem, Nietzsche menyerang ketetapan logika sebagai metode berpikir yang tunggal dan univer-sal. Dengan demikian, argumentasi ad ho-
minem yang menyasar karakter personal, dan motif pribadi seseorang sepatutnya tidak dibuang begitu saja sebagai sebuah kesesatan, melainkan dihargai berkat ber-bagai keutamaan yang telah ditunjukkan oleh diagnosis filosofis Nietzsche. Lewatpemikiran Nietzsche, kita diingatkan bah-wa tak selamanya seseorang yang terlihat mengumbar janji, atau yang terlihat baik pada dasarnya sungguh orang baik. Kita harus mampu mendiagnosisnya melam-paui apa yang terlihat, sebab seringkali apa yang tertangkap indera adalah tipuan. Lewat pemikirannya, kita diajak bere-fleksi untuk setidaknya mengetahui apaitu kedalaman, dan apa pentingnya bagi kehidup an sehari-hari. Dengan mengikuti nasehat Nietzsche, harapan saya adalah semoga pada akhirnya kita mampu meni-lai dan memutuskan untuk memilih siapa orang yang cukup pantas menjadi orang nomor satu di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Copleston, Frederick. (1963). A History of Philosophy Vol VII. London: Search Press.
_______. (1975). Friedrich Nietzsche: Philoso-pher of Culture. New York: Barnes dan Nobles Books.
Foucault,Michel.(1998).“Nietzsche,Gene-alogy, History” dalam Essential Works of Foucault 1954-1984, hlm. 369-391. New York: New Press.
_______.(1988).Philosophy, Politics, Culture. Interview and Other Writings 1977-1984. London: Routledge.
Hardiman, Budi F. (2011). Pemikiran-Pe-mikiran yang Membentuk Dunia Modern. Jakarta: Erlangga.
Hollingdale,R.J.(1985).Nietzsche: The Man and His Philosophy. London: Ark Paper-backs.
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 28 4/24/2014 8:39:45 AM
Peran Argumentum ad Hominem dalam Genealogi Moral: Nasehat Nietzsche bagi Calon Penyoblos YOGIE PRANOWO 29
Magnis-Suseno, Franz. (1998). “F. Ni-etzsche: Dekonstruksi Kemunafikan”dalam 13 Model Pendekatan Etika. Yog-yakarta: Kanisius.
Nietzsche, Friedrich. (2003). The Gay Sci-ence. Cambridge: Cambridge Univer-sity Press.
_______. (1956). The Birth of Tragedy and The Genealogy of Morals. NewYork: Double-day dan Company, Inc.
Sunardi, St. (1996). Nietzsche. Yogyakarta: LKiS.
Sedgwick, Peter R. (2009). Nietzsche: The Key Concepts. Oxon: Routledge.
Sidharta, Arief. (2010). Pengantar Logika. Bandung:PTRefikaAditama.
Solomon, Robert C. (1996). “Nietzsche ‘Ad Hominem’: Perspectivism, Personali-ty and Ressentiment’” dalam Bernd Magnus dan Kathleen M. Higgins (Tim Editor), The Cambridge Companion to Ni-etzsche. Cambridge: Cambridge Univer-sity Press.
_______. (2003). “Friedrich Nietzsche”. dalam The Blackwell Guide to Continen-tal Philosophy. Robert C. Solomon dan David Sherman (Tim Editor). Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Spinks, Lee. (2003). Friedrich Nietzsche. Lon-don: Routledge.
Wibowo, A. Setyo. (2004). Gaya Filsafat Ni-etzsche. Yogyakarta: Galang Press.
002-[Yogie Pranowo] Nasehat Nietzsche bagi Calon Pencoblos.indd 29 4/24/2014 8:39:46 AM
Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, hal 30-44ISSN 2302-5719
Vol II, Nomor 1
A PLATONIAN DEMOCRACY
QUSTHAN FIRDAUS
A lecturer at the Universitas Multimedia NusantaraSurel: [email protected]
Diterima: 28 Maret 2014Disetujui: 4 April 2014
ABSTRAK
Artikel ini mengusulkan revisi terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Revisi dimungkinkan ka rena se-jarah menunjukkan bahwa demokrasi mengalami perubahan dari masa ke masa. Belakangan, partai politik dan elit politik menjadi dua faktor terpenting bagi arah perkembangan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kritik Plato terhadap demokrasi, dan rekomendasinya terhadap filosof-pemimpin akan digunakan se-bagai landasan teoritis bagi upaya untuk merevisi praktik demokrasi, khususnya untuk memilih calon presiden di Indonesia. Akibatnya, artikel ini merekomendasikan agar dibuat serangkaian tes yang wajib diikuti oleh seluruh warga negara untuk menghasilkan 12 kandidat pemimpin nasional di mana enam di antaranya mewakili enam umat beragama di Indonesia, dan enam pulau besar maupun gugus kepulauan di Indonesia. Hal ini penting guna memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh warga negara yang memiliki latar belakang kedaerahan serta keyakinan relijius yang berbeda. Jika kritik Plato terhadap demokrasi, dan mekanisme perekrutan 12 calon pemimpin nasional dapat dijustifikasi, maka sebuah de-mokrasi model Plato barangkali dapat diterima serta dipraktikkan secara realistis. Dengan kata lain, kritik Plato justru dapat digunakan secara konstruktif untuk membangun serta mengembangkan demokrasi di Indonesia.
Keywords: democracy, Plato, criticism, presidential candidates, Indonesia.
1. Introduction
There is no verse in the Indonesian’s consti-tution (Undang-Undang Dasar) which com-pels that a president and a vice president of Indonesia ought to be Muslims and Java-nese individuals. However, minorities -- in the sense of non-Muslims and non-Javanese -- almost have no chance to be a president and a vice president due to their numbers and the nature of democracy which com-pels that majority rules.
Such nature of democracy is well reflect-ed by this following example. Jusuf Kalla is asked by a Christian priest whether he be okay or not had Kalla led by a non-Muslim president. Kalla brilliantly answered that:
“Discussing about the non-Muslim president, we should follow the UUD 45 (constitution), it does not require any specific religion (to be held by a candidate). But what happen is peo-ple’s choices, which is generally based on the
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 30 4/24/2014 8:41:35 AM
A PLATONIAN DEMOCRACY QUSTHAN FIRDAUS 31
religious similarity. Yet, it happens not only in Indonesia. The US, which is the Mecca of de-mocracy, needs 171 years for a Catholic person to be elected as a president. John F Kennedy was the first Catholic president in the US. And then the US needs 220 years for a black person to be elected as the US president” (NN, 2013).
Kalla’s answer compares a socio-polit-ical reality between Indonesia and the US where, in fact, most voters prefer a candi-date who has the similar religious affilia-tions with voters. This comparison could explain why the minority in Indonesia would not be able to be a president if the system of presidential election does not be radically changed.
There are some available options for minorities to be either the first or second most important persons in this country. Firstly, making more children and then be the majority of this country. This option is done by the Javanese during the Dutch col-onization in between the end of eighteenth century where the population was merely three millions; up to the end of nineteenth century where the population was already 28 millions. The Javanese elites establish a myth of ‘banyak anak, banyak rezeki’ (‘the more children, the more income’ because children would assist their parents in farm-ing or other works). One might reckon that such cultural strategy is done in order to prepare more soldiers to fight against the Dutch. Although the Javanese do not have adequate military weapons, but they have more soldiers compared to the Dutch at the time. Yet, this option seems to be unreal-istic nowadays because more Indonesian families (including the minority) just want to have two children. They wish to spend for education, health, and other basic needs instead of making more children.
Secondly, minorities should be involved in politics and they convince the public that they are clean politicians. This scenario is
done by Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), a media tycoon Hary Tanoesoedibjo and probably a district-head (Lurah) Susan. They severely develop a political image that minorities could be some good leaders because there are some corrupters which also be minorities such as Eddy Tansil, Ng Tjuen Wie (David Nusa Wijaya), Anggodo Widjojo, Robert Tantular, Sie Ping Tjhing (Slamet Riadi) and others.
Thirdly, minorities should propose an-other way to do an election. Even though such proposal might not be possible in the near future, at least, we already have a po-litical discourse and a justification for it. Those discourse and justification would be essential in the future. Regarding the ver-satile Indonesian society, we could admit that election would not be the best way for minority to grab some political positions because, however, majority would not eas-ily allow minority to win the election, and minority are reluctant to do either the first way or they are doubtful to do the second way. Therefore, selecting a president and a vice president should not be done through election. Rather than elections, some tests might be the best way for minority. Yet, the ordinary democracy has no philosophical framework to do it.
Therefore, a philosophical compound-ing between Plato’s ideal of philosopher-leaders and democracy might be a suitable way to do it, though we do not need to buy Plato’s ‘king.’ Therefore, this paper will try to answer a question: is a Platonian democ-racy possible as a revision for Indonesian democracy? To answer that question, this paper will proceed as follow. Section 2 will discuss the Indonesian constitution and the requirements of being a president and a vice president in this country. Moreover, section 3 will explore roles of political parties and elites because they have the legal right to decide the presidential candidates. Besides,
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 31 4/24/2014 8:41:35 AM
32 A PLATONIAN DEMOCRACY VOL II, 2014
if democracy is so attractive because it al-lows the voting systems, then we will in-vestigate some flaws of the voting systems in section 4 while the concept of democracy will be challenged in section 5. Moreover, section 6 will inquire some theoretical pos-sibilities of combining democracy and the philosopher-rulers. Plato’s ideal is chosen here because it provides a philosophical framework to oblige the best candidate to run the state. In contrast, democracy cannot oblige the best candidate to run the country if he or she does not want it. Moreover, his philosopher-ruler is not a mere dream but it has a historical example as we will dis-cuss below. Section 7 will establish some justifications for the six religious represen-tatives while section 8 will justify six island representatives. Consequently, we need to discuss some appropriate tests in section 9. Have we discussed those aforementioned sections, this paper would hopefully be able to establish a view which holds that an intersection between Plato’s ideal concep-tion of state and a democracy is not impos-sible. Indeed, it might be an innovation in the contemporary practice of democracy.
2. Indonesian Constitution
Some, if not most of them, voters reckon that the president and vice president of In-donesia should be Muslims and Javanese. However, they do not read the constitution carefully, and hold arbitrarily such view based on the factual reality where Muslims and Javanese are majority. Now, we will explore the constitution in order to reject such fallacious presumption. In fact, Mus-lims and Javanese do not actually dominate the economic and educational process in Indonesia. For instance, most richest per-sons in Indonesia are Chinese-Indonesians (Tionghoa) while some best private schools and higher educational institutions are
managed by the non-Muslims and non-Javanese individuals. In other words, mi-norities dominate the economic and educa-tional activities while majority commands the Indonesian politics. But Ahok inspires other Tionghoa persons to take roles in the practical politics. Let us say this as the Ahok effect. Ahok effect shows us that the minor-ity already cross, let us say, the red line. In other words, the Indonesian minorities are no longer playing some minor roles in In-donesia. There might be a moral problem here, viz., Ahok’s previous administration in Belitung Timur indicated that democracy cannot be merely comprehended as ‘ma-jority rules.’ In short, democracy evolves practically. If that is sound, then it might be justified to redesign its concept due to its practices which has changed. Nevertheless, there is no legal problem with that as we will discuss here.
The Indonesian constitution compels some requirements such as the physical and mental capabilities to deliver duties and ob-ligations as president and vice president, no treason against the state, never holds other passport or citizenships, and should be the Indonesian citizen since he or she was born (article 6, verse 1). Furthermore, the presi-dent and vice-president candidates should be elected as one package by the people (ar-ticle 6A verse 1), and they have the rights to be elected as presidents and vice-presidents through the internal mechanism of political parties (article 6A verse 2). Here, a moral problem arises because political parties in-tercepts the citizen’s right to be elected ei-ther as president and vice-president or as a member of parliament (in the sense of DPR) because the participants of general election for electing members of DPR are not citi-zens but political parties (article 22E verse 3). Those articles are in contradiction with article 28C verse 2 which compels “Every person shall have the right to improve him/
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 32 4/24/2014 8:41:36 AM
A PLATONIAN DEMOCRACY QUSTHAN FIRDAUS 33
herself through collective struggle for his/her rights to develop his/her society, nation and state.”1
Running for a presidential position is part of one’s personal improvement in or-der to develop his or her nation though it is not the one and only best way to do it. Therefore, minority should propose a ju-dicial review to the MK (Constitutional Court) that there is such contradiction in our constitution. Without this review, minority has only one chance to grab the presidential seat through the current presi-dential election. Hoping merely on the Ahok effect is useless because, sooner or later, majority would prepare more good politicians to take back the seat. They do not like to be led by a just non-Muslim and non Javanese. For having a corrupt leader sounds better to them insofar as he or she is a Javanese Muslim person. Besides, minor-ity should bear in mind that Ahok effect is not stronger compared to the Jokowi effect. Indeed, they have similar backgrounds and ages. They both develop their political ca-reers from their hometown, then jumping to build Jakarta, and then attracting the na-tional media coverage. If Jokowi and Ahok run for the presidential seat separately and the political situation proceeds in ceteris paribus,2 then Jokowi would beat Ahok. In other words, minority should seek another institution to widen their opportunities to take the presidential seat.
Furthermore article 6A verse 2 of the constitution urges: “Each ticket of candi-dates for President and Vice-President shall be proposed prior to the holding of general elections by political parties or coalitions
of political parties which are participants in the general elections.” Article 6A verse 3 of the constitution states: “Any ticket of candidates for President and Vice-Presi-dent which polls a vote of more than fifty percent of the total number of votes during the general election and in addition polls at least twenty percent of the votes in more than half of the total number of provinces in Indonesia shall be declared elected as the President and Vice-President.” Article 6A verse 4 of the constitution tells: “In the event that there is no ticket of candidates for President and Vice-President elected, the two tickets which have received the first and second highest total of votes in the general election shall be submitted direct-ly to election by the people, and the ticket which receives the highest total of votes shall be sworn in as the President and Vice-President.” Thereby, paying more attention to the roles of political parties and its politi-cal elites are essential whenever one wishes to criticize democracy as we will explore in the following section.
3. Roles of political parties and elites
Have we discussed the Indonesian Con-stitution, we need to examine the roles of political parties and its political elites in this section. This section will discuss Bot-tomore’s, Batstone’s, and Anderson’s views about the political elites and the political parties.
Bottomore doubts that the competition between political elites and political par-ties would foster democracy because, as he believes, that the theory of democratic gov-
1 I use the translation from this links [http://www.embassyofindonesia.org/about/pdf/IndonesianConstitution.pdf].2 A Latin expression means the current condition would be the same with the future condition, given that every com-
ponent works similarly with the current trend. In other words, there is no radical change in between the present and the future.
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 33 4/24/2014 8:41:36 AM
34 A PLATONIAN DEMOCRACY VOL II, 2014
ernment is not compatible with the theory of social democracy. The social democratic theory contains some divisions in society which is based on education and wealth, with which unmistakably determine the practice of democracy. Consequently, he believes that democracy should provide opportunities for the largest majority to take decisions in society instead of some political elites and political parties (Botto-more, 1968: 119-26).
Regarding the rapid changes in our time, Batstone conceives the network soci-ety is a term which refers to the aggregate conditions of a new political process and the economic development in our rapid time. Under the network society, the notion of ‘community’ is replaced by ‘net’ because our existence as citizens evolves. Commu-nity means associations which are based on gender, religion, ethnicity or labour orga-nization in the industrial era meanwhile it means duties and the struggle for survival in the agrarian era. Clear roles and obliga-tions, and stability between personal rela-tionships are the consequences of commu-nity. Net means our existence is completely decided by our membership because the most important thing here is the forms of intelligence of our connection, its costs, and its practices. Even though many tech-nological developments can enhance our performance in lives, we should not sacri-fice our human potential such as goodness, compassion, peace, joy and love (Batstone, 2001: 338-44). Batstone’s accounts mean political elites and political parties should pay more attention to the transition from the notion of ‘community’ to the notion of ‘net.’ Indeed, they may adjust political campaigns but they should not disregard the human potential.
Moreover, Anderson believes that elites or leaders always play significant roles in the contemporary South-East Asian politics
as is shown by Philippines, Thailand, and Indonesia. He furthermore argues that we could borrow Tacitus’ account of history which is determined by two factors. Firstly, the bad morality of leaders. Secondly, the chance which is completely unpredictable. Besides, Anderson explores the term ‘dem-ocratic fatalism’ which consists of three factors. First of all, the Western democracy could not be transcended in the sense that other forms of politics would work no better. Secondly, all countries would only need to calmly wait because there is no alternatives to the Western democracy either sooner or later. Thirdly, no need to be excited because the Western democracy would appear it-self, and cannot be transcended. Anderson calls this as ‘the half-logical conclusion.’ The Western democracy needs the notion of nationalism to deflect the expansion and splintering of democracy. Nationalism here means solidarity and the collective imagi-nation. Indeed, someone might reckon that what happen in Indonesia, Philippine, and Thailand is the lack of nationalism instead of democracy (Anderson, 2001: 41-5). In other words, either political parties or its political elites exaggeratedly command de-mocracy in some negative ways. Roles of political parties and political elites should be put proportionally. The tickets for presi-dential candidacy should not be given by the political parties because it creates oli-garchy in the party, and we do not want that our democracy transforms into ochloc-racy. This cannot be continued even though the voting system seems to be so attractive in democracy. Therefore, we need to check whether or not the voting system has less problems in the next section.
4. Voting systems
Here, we will discuss an implication of de-mocracy, to wit, the voting system. Walzer
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 34 4/24/2014 8:41:36 AM
A PLATONIAN DEMOCRACY QUSTHAN FIRDAUS 35
reckons the bloc voting (a new voting be-havior in the US) as a very useful political mechanism for maintaining the political equality; and transferring political resourc-es among different states (Walzer, 2004: 42, 58). Bloc voting itself is trading a certain political votes with another political pref-erences across different states in the US for the sake of greater political aims and some vested interests. Such might be bad because, firstly, manipulating deliberately the voters’ decisions, and secondly, violating the prin-ciple of secrecy in deciding their political decisions, given that such principle is taken for granted in an election.
Moreover, Hartvigsen explains further about such political behavior in the Ameri-can Electoral College System. Bloc voting could be categorized as a part of strategic voting, viz., for increasing the probability of preferred political outcome, some vot-ers choose another political candidates. This behavior is made possible by the vote trading which bartering some votes in be-tween two different states at least. Thus, we should identify the lost states and the swing states and then registering each voter who wish to exchange with another voter in other states (Hartvigsen, 2008: 13-6). There-fore, each voter exchanges his or her votes equally. Hartvigsen gives an example:
“The first step in vote trading was to identify the swing states, where Gore and Bush were neck and neck (like Florida) and the ‘‘lost’’ states, where Bush had a big lead (like Texas). Nader supporters (whose second choice was Gore) in swing states and Gore supporters in lost states would be asked to sign up at an In-ternet site. When one of each type had signed up, the site would put the pair in contact with each other and ask them to trade votes. That is, the Nader supporter would vote for Gore and the Gore supporter would vote for Nader. Thus Gore would have a better chance of winning the swing state (hence the election) and Nader would receive the same number of votes na-tionally. In particular, Nader’s chances of get-
ting 5% of the popular vote (and hence receiv-ing federal funding in the next election) would not be hurt and Nader supporters would at least be voting for their second choice...” (Hart-vigsen, 2008: 16).
Hartvigsen conceives the vote trading
is fair because the barter process is done sincerely and it uses no money. Indeed, the notion of sincere is so important in Hart-vigsen’s account whether or not a voting behavior could be taken as cheating. In a nutshell, Hartvigsen considers the vote trading as merely a political persuasion and a fair game in an electoral system (Hartvig-sen, 2008: 16-20). Consequently, the idea of strategic voting and vote trading might handicap democracy in a certain limit-ed way because the swing and lost states could have more determination compared to other states, and individuals do not vote secretly.
The issue of secrecy deals not only with the voters’ decisions but also causing, ac-cording to Cassati, a moral dilemma. On the one hand, accuracy in counting the votes could be improved but it does not mean that secrecy could be guaranteed by the practice of counting as well. Indeed, the voters’ knowledge of the counting system is decisive for the issue of secrecy: whether or not voters be aware with the process of counting the ballots. For instance, when ballots are mixed and be opened in an urn, this is the limit of secrecy in an election. On other hand, the issue of accuracy is delegat-ed by the issue of secrecy in election. Thus, an election requires not only accuracy and secrecy but also transparency in the sense of all voters could access and understand the mechanism of election comprehensive-ly (Cassati, 2010: 20-2).
In short, the voting system contains some flaws which certainly reduce the quality of democracy. Yet, democracy has no alternative. Unfortunately, democracy
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 35 4/24/2014 8:41:36 AM
36 A PLATONIAN DEMOCRACY VOL II, 2014
has other problems which deal with its owned concept as we will discuss in the next section.
5. Incoherency of democracy
The coherency of the concept of democracy is put at stake because its concept evolves across history. When an idea changes its practices, then it might affect its owned concept. Therefore, this section will discuss the evolving meanings of democracy since its beginning in Athens, and some mean-ingful criticism against democracy.
Firstly, I will expose Dennis Schmidt’s criticism against democracy. He reckons: 1) Demographics and democracy links
each other because the early use of the word ‘democracy’ deals with the ma-jority of the people as is founded in Aeschylus’ The Suppliant Maidens (463 BCE). Additionally, Pericles argues that the Athenian people are a form of democracy because the participa-tion in governing is taken by the many (Schmidt, 2008: 228-9; 230-1).
2) Democracy implies a line to the people who be inside of it and they who be outside of democracy. Such refers to the question of who counts in democ-racy. For example, only 30,000 out of 250,000 persons who be considered as citizens in Athens in the fifth century BCE (Schmidt, 2008: 228; 231).
3) The inside of democracy contains two types of questions. Firstly, the question about the process of democracy. Sec-ondly, the question about the majority. Additionally, democracy is naturally similar with chameleon which is able to adjust but it is still be itself (Schmidt, 2008: 232; 234).
4) Democracy has two obligations. Firstly, to the equality of people. Secondly, to the liberty of individual. Consequently,
democracy could only extenuate some conflicts (Schmidt, 2008: 235).
5) The idea of democracy is messy in the sense that it be the place for contesting different claims and never be complete (Schmidt, 2008: 237).
6) Democracy initially appeared as a peaceful process of succession in the political power, and democracy is justi-fied in order to avoid violence in such transition (Schmidt, 2008: 239).
7) Democracy always deals with the change of power, the liberation of his-tory, and the future. Indeed, our future contains two determinants, to wit, tech-nologization and globalization. Indeed, the ancient question of democracy (‘who counts’) tallies with globaliza-tion where individuals matter and they must count (Schmidt, 2008: 242).
Premise number five is tempting be-cause the notion of ‘never be complete’ might mean democracy would not decide which claim is true or which claim would be used in the system. Therefore, democ-racy merely accumulates various claims without solving it or, on the other hand, it only extenuates conflicts as is reflected on premise number four. In short, democracy is fulfilled with either sound or unsound arguments.
Secondly, Raphael interestingly argues that there are some inconsistencies in de-mocracy which deal with Lincoln’s ac-count, a gap between the representative government and the representative bodies, Burke’s distinction between the notion of representatives and delegations, and Mon-tesquieu’s separation of power in democra-cy. Raphael’s argument proceeds as follow. Democracy deals with equality and liberty. Indeed, it strives to balance a tension be-tween the notion of liberty and equality. In some democratic countries, one outweighs
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 36 4/24/2014 8:41:36 AM
A PLATONIAN DEMOCRACY QUSTHAN FIRDAUS 37
another such as in New Zealand after the Second World War where the equalitar-ian sentiments outweighs liberty (Raphael, 1970: 143-4; 164).3 Lincoln’s compelling de-scription of democracy as ‘(a) government of the people (b) by the people (c) for the people’ is a bit vague because (a) actually functions in all types of government while (c) works within the regime of despotism because it would serve all -- or at least the majority’s -- interests though there is no consensus among all citizens -- including the minority -- for doing so. Indeed, Ra-phael believes that the necessary meaning of democracy is only (b) with which reflects the principle of equality in the sense of par-ticipation in electing a government, though Raphael admits that (b), by itself, is im-possible (Raphael, 1970: 146-7; 155).4 Even though democracy implies a representa-tive government, the decision-making pro-cess is done by the representative bodies because the ordinary individuals involve to the extent of casting votes in elections. Practically speaking, people choose which persons to take seats in an oligarchy (Ra-phael, 1970: 147). Indeed, Burke’s distinc-tion of a delegate and a representative is essential to democracy. A delegate means that a politician works only as a mirror for his or her constituents while a representa-tive implies a certain degree of freedom to judge some political issues based on his or her conscience. Yet, the system of political party interrupts the work of representa-tives (Raphael, 1970: 149). He furthermore reckons that Montesquieu’s separation of power does not work in all democratic gov-ernment. It works in the US with its check
and balance system but does not function in the UK where some top executives be the members of legislature. He believes that Montesquieu put emphasize on the ju-diciary’s independence from the executive (Raphael, 1970: 154-5). In short, Raphael’s critiques strike the concept of democracy. Consequently, one might say that the con-cept of democracy is not coherent.
If democracy evolves in history, then its coherency might be put at stake. Plato at-tacks democracy because it cannot oblige some potential candidates to lead the coun-try as well as democracy allows everyone to run for office, no matter they are com-petent or not. Such might not violate the coherency of democracy but it contributes to the weakness of democracy instead. In other words, Plato’s criticism against de-mocracy is actually fruitful in the sense it could be used by us to revise the practices of democracy at least in Indonesia.
6. Democracy and the Philosopher-Rulers
Democracy might learn from capitalism about the latter’s way to survive in history. An important keyword for capitalism is its ability to do self-reflection which means capitalism has no doubt to radically adopt any criticism against capitalism for the sake of its survival. Similarly, democracy might adopt any criticism against itself in order to survive here and now. Therefore, this section will deal with an ancient critique against democracy viz., Plato’s criticism over democracy in The Republic that pro-ceeds as follow:
3 Interestingly, Raphael mentions Tocqueville’s account that the American democracy show the notion of equality pre-ponderate liberty. However, one might easily rebut such opinion nowadays where American democracy puts more emphasize on liberty compared to equality as clearly be shown by the US’ foreign policy to invade other countries after 9/11. In other words, the US undermines the notion of equality among states.
4 I myself give the alphabets a, b, and c in those brackets.
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 37 4/24/2014 8:41:36 AM
38 A PLATONIAN DEMOCRACY VOL II, 2014
1) Democracy comes out from oligarchy especially when rulers in the oligar-chic system wish to accumulate the wealth that they currently possess. Since the disciplinary citizens cannot coexist with the love of money, then one should be neglected for the sake of another. Here, oligarchic rulers tend to sacrifice the disciplinary citizens for the sake of earning more money. Con-sequently, they violate the law, barring youths to accumulate their money, and pushing people to spend their money prodigally (1983: 373).
2) Have ordinary citizens become poorer, they would be easily provoked by some-one to do rebellions. Here, democracy appears when civil rights are equally distributed to all citizens, and the poor win the fight against the rich. Conse-quently, freedom and liberty arises for all individuals as well as it contains ver-satility though lacks of principles (1983: 375; 377).
3) Nevertheless, democracy is merely a place for reshaping the constitution because the freedom that is preserved by democracy. In addition, democracy cannot force some talented individuals to lead the country as well as cannot compel them to go to war -- though we know that some democratic countries implement conscription in a few centu-ries after Plato (1983: 375-6).
4) Democracy shamefully provides oppor-tunities for all people -- including they who are not well trained in leadership, education, military services and other necessary skills to run a country -- to seat in government. Consequently, gov-ernment is fulfilled with persons who always show the unsound arguments,
and there is no restrictions in their lives with which would benefit people (1983: 376-81). Moreover, Plato proposes the philos-
opher-king as an ideal national leader. It might mean two things. Firstly, his agree-ment to monarchy where the top leader is a king. Secondly, his rejection to democracy which contains no king. Additionally, a phi-losopher could not compete against politi-cians in democracy because they would prefer to criticize the democratic regime in-stead of governing it. However, we will use the notion of philosopher-rulers instead of philosopher-king because the previous has a wider scope compared to the latter. Plato’s argument on the important of philosopher-rulers proceeds as follow: 1) Philosophy and power should be han-
dled by the same person in order to solve problems in a country. Therefore, a philosopher should be a king or oth-erwise a king should be a philosopher though he reckons such is a paradox (1983: 263).
2) Furthermore, he defines a distinguish feature of philosopher as loving all dis-ciplines which could assist to disclose the unchanged reality, and loving truth as well as hating an untruth (1983: 277-8).
3) Some necessary knowledge should be mastered by the philosopher such as arithmetic, geometry (either the plane one or the solid one), astronomy, and harmonics (1983: 332-41).5
4) Those philosopher-ruler candidates should be trained from they were 15 years old. Therefore, the state ought to take them out from their family for the sake of creating the ideal society quickly. Furthermore, those candidates would
5 Plato records Socrates’ interesting explanation for it viz., “I think we may say that, just as our eyes are made for as-tronomy, so our ears are made for the movements of harmony...” (Plato, 1983: 340).
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 38 4/24/2014 8:41:36 AM
A PLATONIAN DEMOCRACY QUSTHAN FIRDAUS 39
do three things in cycle for the rest of their lives. Firstly, doing philosophy. Secondly, doing politics. Thirdly, ruling the state (1983: 354-5). It is important to be noted that Plato does not refer such society to the Spartan because he par-tially rejects the latter and indicate it as what he calls as Timarchy.6
Additionally, Silverman proposes two theses about the philosopher-rulers. First-ly, every rational individual is able to be a philosopher, and secondly, there is no ideal form of state for such philosopher-rulers. If philosophers could not create an ideal state for the philosopher-rulers, then philosophers should educate all persons to be philosophers. Yet, they would face a significant problem viz., the rational eu-daimonism where happiness -- in the sense of psychic harmony -- is the ultimate aims of all persons. Therefore, minimizing the bodily needs is the key to purifying the state though cannot clean it at all from the rational eudaimonism (Silverman, 2007: 42-69).
Furthermore, Beauchamp gives a chal-lenging interpretation of The Republic. First-ly, justice is the harmony between workers, auxiliaries, and rulers who play their own roles well. These three divisions of labour are consistent with a just man who compris-es appetite, will, and reason. Nevertheless, we cannot change the intrinsic nature of a man because the psychological conditions have a certain limits as well as silver cannot be changed into gold. Thereby, obliging lay-men to follow what the philosopher-rulers order is taken for granted because laymen could not decide by themselves rights and wrongs. Interestingly, Plato conceives the
majority could not be simply taught rea-sonably, and this conviction underlays his rejection to democracy (Beauchamp, 2007: 284-6).
Beyond democracy, there are two other institutions which command the practices of democracy. These institutions determine whether or not democracy would prevail viz., the rule of law and constitutionalism. Mandelbaum conceives constitutionalism, rule of law, and democracy as below:
“If democracy is an invention of the Greeks of antiquity and constitutionalism an innovation of Great Britain in the age of absolutism, the rule of law has its origins in ancient Rome. The practice was lost for centuries, then revived in medieval Europe and in particular in the Brit-ish Isles” (Mandelbaum, 2003: 270).
Therefore, the pre-ancient Rome-de-mocracy has nothing to do with rule of law as well as the pre-Great Britain-democracy has nothing to do with constitutionalism. In other words, democracy develops itself from time to time. Next, one cannot say that a Platonian democracy is not possible at all because Plato’s philosopher-rulers has an historical example. Some historical examples of philosopher-rulers are: a) Ibnu Sina (Avicenna) as the vizier (Wa-
zir azim) or a chief minister in the ad-ministration of Sultan Shams al-Dawlah (1015-1022) of the Buwyhid dynasty in Ray (Iran) (cf., Bakker, 1978: 44; Watt, 1987: 116-7).
b) Nizam al-Mulk (1018-1092) as the vizier of the Seljuk sultans. His writing is The Siyasat-nama or Siyar al-muluk which is failing to be accomplished. Further-more, he also appointed Al Ghazali as the head of the Nizamiyyah College
6 Timarchy or Timocracy is an ambitious society with the competitive spirit where they just prioritize their love for money as the oligarchy does (Plato, 1983: 363).
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 39 4/24/2014 8:41:36 AM
40 A PLATONIAN DEMOCRACY VOL II, 2014
at Baghdad in AH 484/AD 1091 (cf., Kojiro, 2008; NN, 1999). Beside Plato, Aristotle also rejected de-
mocracy for some reasons. Biondi thinks Aristotle ranked some systems from the worst to the best as follow: tyranny (the one), oligarchy (the few), democracy (the multitude), polity (the many), aristocracy (the few), and kingship (the one) (Biondi, 2007: 179). Nevertheless, this might be her weakest point because between the worst and the best systems have no much differ-ences. Both are about one person who rules justly or unjustly. Even though kingship is the best constitution for Aristotle, Biondi re-buts it because, as Aristotle does agree with this, a king tends to be distracted by his pas-sions, and he has limitations in his knowl-edge. Therefore, a king cannot be regarded as a divine leader (Biondi, 2007: 180). Aris-tocracy outnumbers polity because not all individuals could be considered as citizens. Indeed, Aristotle defines citizens as they who have the capabilities to take part in ju-dicial and deliberative office (Biondi, 2007: 181). Yet, Aristotle himself suggests that we should learn what is attainable, easier, pos-sible, instead of pursuing merely the best one because not all people could achieve the best one (Biondi, 2007: 185). Similarly, Grayling interestingly notes:
“With Plato and after him Aristotle against it, democracy had small chance with later think-ers. Renaissance thinkers assumed that democ-racy promised nothing but unlimited turmoil. Enlightenment thinkers saw it as a threat to virtue. The founding fathers of the United States believed it would lead to a dangerous equalization of property. And as the much grudged change towards today’s simulacrum of democracy began in Britain in 1832, its op-ponents lamented that they were being sold to the mob, because for them democracy meant only the terrors of ochlocracy as experienced in the French revolution...Most of the major West-
ern democracies are very imperfect, and rely on the population’s general acceptance of their imperfections in return for more or less satis-factory performance otherwise. The imperfec-tions in question include always producing governments elected by an absolute minority of voters...” (Grayling, 2010: 141-2).
Such implies we need no worries to criticize democracy because democracy is usually attacked by many philosophers across history because they do realize the imperfections of democracy. Yet, if we do nothing about those imperfections, then our democracy would not develop well.
7. Six religious representatives
This section will deal with the geographi-cal and religious complexities of Indonesia. Should we regard those complexities, we need to adjust Plato’s philosopher-rulers to the Indonesian socio-cultural settings where it contains five big islands and ap-proximately 17,000 islands across the archi-pelago. Indeed, there are six religions and faiths which are recognized by the state. Therefore, the state cannot arbitrarily pick all teenagers from the age of ten, as So-crates suggested, because we should con-sider those plurality.
Islam, Catholic, Christian, Hindu, Bud-dhism, and Confucianism are acknowl-edged by the Indonesian government. This paper suggests that the election commis-sion organizes six tests, which will be dis-cussed in section 8, in each religious com-munity in order to find out six persons to represent their religious communities. This test is done in order to provide an equal opportunity for all candidates to compete within their owned religious communities. Moreover, religious organizations should not monopolize either the candidates or the selection criterion due to denominations or its single religious authority.
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 40 4/24/2014 8:41:36 AM
A PLATONIAN DEMOCRACY QUSTHAN FIRDAUS 41
Selection for these six candidates ig-nores ethnicity and probably gender. They would be combined with another candidate who is selected based on ethnicity in order to determine who would be a presidential candidate and also a vice-presidential can-didate. Consequently, if there is a combina-tion which shares either a similar religious and ethnic backgrounds, then they cannot be considered as a cheating but is merely a result of a set of fair tests. They who are lost in competition have only another chance to take the future tests.
I myself have a conjecture that Muslim candidates might face some difficulties as well as some advantages. Firstly, Muslim candidates will compete with approximate-ly 80% Indonesian Muslim citizens (assum-ing that all Indonesian Muslims would take the tests) while other religious candidates will compete with less than 20% citizens in their owned religious communities. In other words, Muslim candidates would struggle harder compared to other religious candidates. It seems unfair but it does fair for Muslim candidates because it provides some opportunities for some brilliant Mus-lim candidates to win the tests. Money will have no determination in this mechanism, given that the tests would proceed fairly. Additionally, Indonesian Muslims could realise that themselves are left behind in education compared to other religious communities in Indonesia. Consequently, Muslims would prepare themselves with good education in the long run.
Secondly, Muslim candidates might lose whenever they are challenged by other religious candidates in tests. I myself have nothing to say about this but preparing Muslim candidates with the best education which they could access either in Indone-sia or overseas. Had they failed to access it, then they would be looser for some se-lections. However, I believe that there are
some Muslim tycoons who would pay the costs. In a nutshell, Muslims do not need to worry that they would be led by a non-Muslim president.
8. Six island representatives
This section contains a short discussion about representations of big islands in the archipelago. There are six big islands in In-donesia, viz., Java, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, and a set of islands be-tween Bali and Nusa Tenggara Timur. Each island contains various ethnicities which could not be represented well. Moreover, some ethnics live across those main islands. Thereby, using six islands as a category might be the best way to represent the cul-tural diversity in Indonesian politics. Each island should organize some tests in order to search for a single person who would represent the island. This presidential can-didate might be a Muslim, a Christian, a Catholic, a Hindunese, a Buddhist or a Con-fucian believer but he cannot be considered as a representation of those religious com-munities. Indeed, he should be considered as a representation of his island.
Some islands between Sulawesi and Papua could choose whether they would be included into the previous or the latter. Otherwise, their affiliation might be decid-ed by their province. For instance, people in Tual should be tested in the region of Sulawesi instead of Papua because they are part of the province of Maluku though they are closer to Papua geographically. Such account might be implemented in other is-lands across the Indonesian archipelago.
These divisions are necessary because of two important things. First of all, there is no Indonesian president with a cultur-al background from outside Java unless Habibie. Secondly, there were some histori-cal events, such as rebellions, through time
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 41 4/24/2014 8:41:36 AM
42 A PLATONIAN DEMOCRACY VOL II, 2014
in Indonesia -- such as PRRI, Permesta, NII, GAM, RMS, OPM and others -- which deals with injustices.
By implementing the idea of taking one presidential candidate from each big island in Indonesia, the issue of unjust Javanese political domination would be solved once and for all. Nevertheless, some Javanese might reckon that this is unfair but they ac-tually enjoy a vast growing number of Java-nese educated people compared to people in Papua, Tulang Bawang, Nusa Tenggara Timur, and other regions. Indeed, those Javanese educated individuals outnumber the Minangkabaunese educated people who painstakingly built this nation on the last century (Tan Malaka, Hatta, Sjahrir, Agus Salim, Natsir, and others). In other words, they need no worries to be beaten by other ethnics in the tests.
9. Tests
There are many kinds of leadership tests but we need at least two general tests, viz., the IQ and EQ tests. Other tests might be conducted but those tests should share the same criterion which will be discussed in this section. Firstly, I suggest that the tests are compulsory for all citizens, and we seek for the highest result as well as a balance result among those tests. A balance higher result is better than a mere higher result be-cause leading a nation requires a balance between the intellectual abilities and the emotional abilities.
Moreover, tests ought to be done fairly, openly, and interactively. An organization such as KPU (the general election commis-sion) supposes to be established in order to organize the tests. Members and officials of KPU have no rights and duties to compete in the tests as well as military officers do not have the similar rights. Results of tests have to appear right after the test are con-
ducted. This is crucial because the longer the results appear, the bigger chance for cheating.
Elections induce the accumulation of wealth to be spent on the candidacy, but tests provide the same opportunity for all citizens to be a national leader as well as compelling all citizens to prepare them-selves academically. They who do not wish to be a national leader might pretend to be stupid in the tests but their track records might be checked as well to make a com-parison. A legal punishment might be nec-essary had there were some individuals who pretend to be stupid.
Some necessary subjects to be tested are civic education, mathematics, Bahasa Indo-nesia (not necessarily English), geopolitics, and others. Civic education is indispens-able here because a national leader should not deliver some racist comments as well as should not govern unjustly. His willingness to represent Indonesia might be reflected in his tendency to use Bahasa Indonesia either in the country or overseas. Thereby, testing all presidential candidates in a Bahasa In-donesia test is essential. Moreover, their knowledge in geopolitics determines the existence of a country because it deals with the power of a state itself and its economic geography.
Arithmetic, geometry, astronomy, har-monics, and dialectic might also be neces-sary to be tested as Plato suggested. Ad-ditionally, some other tests might also be essential such as the leadership test, the psychological test, the SQ (Spiritual Quo-tient) test, the health test, the lying test, and other necessary tests. The winners are de-cided by a combination between the highest result and they who achieve a balance re-sult among those tests. Have we got twelve candidates, then they should be tested as a couple. Now, a fair mechanism to pair off them is by casting lots. On the contrary, po-
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 42 4/24/2014 8:41:37 AM
A PLATONIAN DEMOCRACY QUSTHAN FIRDAUS 43
litical lobbying should be avoided here be-cause it would destruct the importance of ethnic and religious representations.
Those tests are hopefully able to pro-vide some equal opportunities as well as obliging some potential individuals to lead the country. In contrast, current democracy cannot oblige some potential candidates to do the same because it lacks reasons of why they should run for office instead of, for in-stance, keep doing business.
10. Conclusion
The concept of democracy extends across history since its appearance and practices in the five century BCE Athens. Therefore, we might develop the concept of democra-cy as we have discussed above. One might think that a combination of Plato’s concept of philosophers-rulers and democracy is not compatible. Yet, democracy itself is not a static concept which means that we have an opportunity to develop it locally. More-over, an equal opportunity for all citizens are provided by these tests because all citi-zens should follow it. Tests do not mean that this proposal violate the principal of democracy which imply elections. Elec-tions are only able to produce some rep-resentatives who are rich enough to pay the costs of campaign as well as those rep-resentatives might be dominated by some majorities in the sense of religious and eth-nic communities. In contrast, selections are paid by the state, and all citizens are com-pelled to follow it. Additionally, this pro-posal strives to establish an equal symbolic representation for all religious and ethnic groups in Indonesia. Indeed, a Platonian democracy proposal could be justified in-sofar as it does not violate the Indonesian constitution (Undang-Undang Dasar), and providing an equal opportunity for all citi-zens. The philosopher-rulers are not mere-
ly Plato’s imagination but it reaches its manifestation about fifteen centuries after Plato’s lifetime. Thereby, re-implementing his idea is not impossible at all nowadays.
Bibliography
Anderson, Benedict. (2001). Democratic Fa-talism in South-East Asia. In NN. The Alfred Deakin Lectures: Ideas for the fu-ture of a civil society (pp. 40-58). Sydney: ABC Books.
Bakker, JWM. (1978). Sejarah Filsafat dalam Islam. Yogyakarta: Kanisius.
Batstone, David. (2001). Virtually Demo-cratic. In NN. The Alfred Deakin Lectures: Ideas for the future of a civil society (pp. 338-44). Sydney: ABC Books.
Beauchamp, Gorman. (2007). Imperfect Men in Perfect Societies: Human nature in utopia. Philosophy and Literature 31, 280-93.
Biondi, Carrie-Ann. (2007). Aristotle on the Mixed Constitution and Its Relevance for American Political Thought. Social Philosophy and Policy, 24 (02) 176-198.
Bottomore, T. B. (1968). Elites and Society. Middlesex: Penguin Books.
Casati, Roberto. (2010). Trust, secrecy and accuracy in voting systems: the case for transparency. Mind Soc 9, 19–23.
Grayling, A. C. (2010). Democracy. In A. C. Grayling. Ideas that Matter: A personal guide for the 21st century (pp. 139-43). London: Phoenix.
Hartvigsen, David. (2008). The Manipula-tion of Voting Systems. Journal of Busi-ness Ethics 80, 13–21.
Inston, Kevin. (2010). Representing the unrepresentable: Rousseau’s legislator and the impossible object of the people. Contemporary Political Theory 9 (4), 393–413.
Mandelbaum, Michael. (2003). The Ideas that Conquered the World: Peace, democ-
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 43 4/24/2014 8:41:37 AM
44 A PLATONIAN DEMOCRACY VOL II, 2014
racy, and free markets in the twenty-first century. New York: PublicAffairs.
Nakamura, Kojiro. (2008). AL-GHAZALI, ABU HAMID (1058-1111). Ghazali.Org, January, 25th, 2008. Could be accessed at [http://www.ghazali.org/articles/gz1.htm]; last accessed January, 16th, 2014.
NN. (n.d). The 1945 Constitution of the Re-public of Indonesia: As amended by the First Amendment of 1999, the Second Amendment of 2000, the Third Amend-ment of 2001 and the Fourth Amend-ment of 2002 (unofficial translation). EmbassyOfIndonesia.Org. Could be ac-cessed at [http://www.embassyofin-donesia.org/about/pdf/IndonesianCon-stitution.pdf]; last accessed December 24th, 2013.
NN. (1999). NIZAM al-MULK. MuslimPhi-losophy.Com, 1999. Could be accessed at [http://www.muslimphilosophy.com/ei2/nizam.htm]; last accessed January 16th, 2014.
NN. (2013). Bagaimana Jika Presiden dari Non-Islam? Ini Jawaban Jusuf Kal-la. JusufKalla.Info, June 2013. Could
be accessed at [http://jusufkalla.info/archives/2013/06/18/bagaimana-jika-presiden-dari-non-islam-ini-jawaban-jusuf-kalla/]; last accessed December 24th, 2013.
Plato. (1983). The Republic. Middlesex: Pen-guin Books.
Raphael, D. D. (1970). Problems of Politi-cal Philosophy. Macmillan and Co Ltd.: London and Basingstoke.
Schmidt, Dennis J. (2008). Who Counts? On democracy, power, and the incalcu-lable. Research in Phenomenology 38 (2), 228-43.
Shields, Christopher. (2007). Forcing Good-ness in Plato’s Republic. Social Philoso-phy & Policy 24 (2), 21-39.
Silverman, Allan. (2007). Ascent and De-scent: The philosopher’s regret,” Social Philosophy & Policy 24 (2), 40-69.
Walzer, Michael. (2004). Politics and Passion: Toward a more egalitarian liberalism. New Heaven: Yale University Press.
Watt, W. Montgomery. (1987). Pemikiran Te-ologi dan Filsafat Islam. Jakarta: P3M.
003-[Qusthan] A Platonian Democracy.indd 44 4/24/2014 8:41:37 AM
Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, hal 45-58ISSN 2302-5719
Vol II, Nomor 1
PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK
WASISTO RAHARJO JATI
Peneliti di Pusat Penelitian Politik (P2P), LIPISasana Widya Graha, Lantai 11, Jalan Jend. Gatot Subroto, No.10, Jakarta 12710
Surel: [email protected]
Diterima: 24 Februari 2014Disetujui: 10 April 2014
ABSTRACT
This article aims to analyze the 2014 general election as a major determinant in electoral democracy in Indonesia. The election process held post-1998 was considered as a political base in succession after the New Order government. The elections held in 1999 and 2004 were claimed as consolidated elections after a transition period. The results of both elections are strengthening elite from political parties in control of the government. Consequently, it was then creating a type of government cartel based on transactional logic and principles of oligarchy. The said government was running in permissive logic that further generated many setbacks and scandals. Those conditions led to the needs of strengthening public representation and advocacy. The 2014 election will be decisive in predicting whether the cartel would still continue exist or public as demos would strengthen its role as watchdog of government.
Keywords: Election; Political Cartel; Representation; Electoral Democracy
Pendahuluan
Pasca-lengsernya rezim otoriter Orde Baru pada 21 Mei 1998, Indonesia kemudian mengalami masa Reformasi. Reformasi di sini berarti segenap usaha untuk mengem-balikan tatanan kelembagaan maupun produk legislasi pemerintah ke jalur yang lebih demokratis. Reformasi sendiri juga mengamanatkan agar demokrasi diberi jalan sebagai sistem suksesi kekuasaan eksekutif maupun legislatif yang langsung dipilih, diketahui, dan diawasi publik. Pe-
nyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) kemudian menjadi hal teknis transformasi kepemimpinan yang di dalamnya proses mufakat melalui sistem suara digunakan untuk menyelesaikan, dan memutuskan suatu permasalahan. Bersamaan dengan hal tersebut, euforia pemilu juga ditunjuk-kan dengan tumbuhnya sistem multipartai dalam sistem politik Indonesia. Munculnya banyak partai mengindikasikan idealisme politik dari masyarakat begitu besar untuk diwujudkan dan direalisasikan dalam se-buah kebijakan. Idealisme demokrasi yang
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 45 4/24/2014 8:52:18 AM
46 PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK VOL II, 2014
mencuat pada periode awal reformasi sa-ngat jelas terpancar tatkala partisipasi pub-lik begitu kuat pada pemilu tahun 1999. Pada pemilu tahun 1999 tercatat persentase pemilih sebesar 92,7 persen memilih partai maupun kandidat calon legislatif.
Namun demikian, di tengah iklim de-mo krasi yang menggelora tersebut, de-ngan menjadikan publik sebagai peme-gang mandat tertinggi kedaulatan negara, ternyata masih tersimpan beberapa kenda-la. Hal penting yang mesti dicatat juga da-lam proses transisi rezim otoriter menuju rezim demokrasi adalah reorganisasi elite lama untuk bisa beradaptasi dalam nuansa demokrasi baru tersebut. Reorganisasi itu sangatlah erat dengan praktik survivalitas maupun sustainabilitas elite orde sebelum-nya untuk bisa eksis memegang jabatan publik (Hadiz, 2013). Adanya kedua proses tersebut mengindikasikan adanya prak-tik politik predator dalam lingkup poli-tik nasional maupun politik regional atau kedaerahan. Munculnya praktik predator tersebut sangatlah kontras dengan keingin-an demokrasi yang dicita-citakan yaitu menjadikan demos sebagai penguasa repub-lik dan bukan para kleptokrat elite. Ada-nya proses dilematis dalam eksperimentasi demokrasi di Indonesia memberikan gam-baran mengenai kontestasi kekuasaan, baik yang dilakukan dalam politik formal mau-pun politik informal.
Adapun kajian-kajian politik nasional maupun lokal yang menitikberatkan pada proses pemilu sebagai lokus penelitian me-negarai bahwa oligarki sebagai suatu an-caman terhadap eksistensi demokrasi se-makin lama semakin jelas terlihat. Berbagai perspektif politik yang melihat historisitas pemilu cenderung melihat politik patrimo-nial masih berkuasa dalam proses demokra-si yang belum sempurna seperti halnya bos lokal, orang kuat, negara bayang an, tribal-isme, politik etnis, pemburu rente, oligarki,
politik kartel, politik dinasti, dan lain se-bagainya. Gejala menguatnya elite dalam demokrasi kontemporer ditunjukkan de-ngan hadirnya beragam perspektif terse-but. Tentunya kita perlu mempertanyakan mengenai konteks pemilu yang telah di-langsungkan selama kurun waktu 15 tahun terakhir ini (1999 – 2014). Dalam kurun 15 tahun terakhir tercatat adanya penurunan suara partisipasi politik sebanyak 21 persen dengan rincian tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999 sebesar 93,3 persen, pada Pemilu 2004 turun menjadi 84,9 persen, ke-mudian pada Pemilu 2009 turun lagi men-jadi 70,99 persen.
Adapun pada pemilu tahun 2009 si-lam, tingkat golongan putih saja menjadi 63 persen. Hal itu tentu akan menjadikan pemilu di Indonesia tak terlegitimasi lagi dalam kerangka suksesi kepemimpinan nasional. Maka jangan sampai kemudian demokrasi elektoral yang kita bangun ini menjadi demokrasi yang membeku (frozen democracy) yakni hak politik publik menjadi tereduksi dan kekuasaan elite menjadi kian maksimal (Sorensen, 2007). Oleh karena itu-lah, pelacakan terhadap akar permasalah-an tersebut yakni menurunnya partisipasi maupun menguatnya elite perlu untuk ditelisik lebih lanjut. Pemilu 2014 bisa jadi merupakan kontinuitas dari pola oligarkis tersebut, namun bisa juga menjadi momen-tum publik untuk memperbaiki demokra-si. Tulisan berikut akan membahas secara lebih lanjut mengenai pemilu Indonesia se-bagai sesuatu yang dilematis antara perta-rungan kuasa representasi dengan elite.
Namun demikian, kita perlu mema-hami terlebih dahulu mengenai definisi representasi dan elite yang menjadi lokus tulisan ini. Kedua hal tersebut menjadi urgen dan signifikan dalam mendedah proses demokrasi elektoral di Indonesia. Representasi berarti upaya mendudukkan publik sebagai demos yang memiliki kekua-
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 46 4/24/2014 8:52:18 AM
PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK WASISTO RAHARJO JATI 47
saan negara tertinggi. Sedangkan elite ada-lah sekumpulan orang yang menjalankan kekuasaan negara secara oligarkis melalui mekanisme pemilihan suara. Sesuatu yang perlu dicatat perihal kontestasi elite dan publik dalam kekuasaan negara sangat-lah terkait dengan pemaknaan demokrasi itu sendiri. Secara konseptual, demokrasi memang mengamanatkan suara publik sebagai determinan utama dalam pemi-lihan jabatan publik. Elite sendiri merupa-kan manifestasi dari pejabat publik yang terpilih yang kurang peduli dengan pe-layanan masyarakat. Tentunya pemaham-an demokrasi elektoral menjadi penting dalam konteks ini. Elite melihat bahwa demokrasi elektoral menjadi penting seba-gai upaya survivalitas politik di arena jaba-tan publik sehingga sangatlah pragmatis dalam mendekati publik. Sementara itu, publik condong melihat demokrasi elek-toral sebagai ajang kontinuitas kekuasaan para pejabat korup untuk terus mengeruk kekayaan dan kekuasaan. Hal itulah yang membuat partisipasi publik semakin turun dari tahun ke tahun. Adanya depolitisasi partisipasi publik tersebut dalam demokra-si elektoral tentu akan mereduksi makna penyelenggaraan pemilu. Pemilu sendiri bertujuan untuk menghadirkan demokrasi yang menyejahterakan namun kenyataan-nya justru malah menyengsarakan publik. Tulisan ini bermaksud untuk mengelabo-rasi lebih lanjut mengenai konteks pemilu 2014 sejauh dihubungkan dengan posisi dilematis antara kartelisasi dengan repre-sentasi tersebut.
Adapun argumen utama yang ingin dis-ajikan dalam penulisan makalah ini adalah untuk memetakan sisi-sisi ambiguitas yang tercipta selama implementasi demokrasi elektoral di Indonesia. Ambiguitas yang dimaksud adalah kehadiran distorsi utama yaitu munculnya oposisi biner dalam im-plementasi demokrasi langsung di Indone-
sia. Munculnya politik kartel yang terjadi paska pemilu 2004 mengindikasikan ada-nya kontradiksi-kontradiksi dalam aktor, sistem, maupun struktur politik elektoral di Indonesia. Kontradiksi dalam sisi ak-tor dapat dilihat dari segi kecenderungan konvergensi politik yang dilakukan aktor guna mengamankan kekuasaan. Suksesi kekuasa an tersebut pada akhirnya hanya berlangsung pada ‘lingkaran dalam’ terten-tu saja yang sejatinya lebih mengarah pada arisan kekuasaan. Secara sistem, kartel ter-cipta dari sistem demokrasi yang belum sempurna. Perumpamaan demokrasi seba-gai manifestasi one man, one vote, one value masih dipahami secara literal dan tekstual, tanpa pernah ada usaha untuk memahami muatan aspirasi yang ingin diperjuang-kan. Hal inilah yang menjadikan demokra-si, secara sistem, lebih dipahami sebagai cara mencari kuasa dengan menggunakan popularitas dan materialitas saja. Secara struktur, kartel juga mengubah demokrasi menjadi ajang patronase kekuasaan. Secara institusional sendiri, munculnya partai pa-tron (patronage party) dalam sistem multi-partai mengindikasikan adanya barter poli-tik antara partai-partai terkait. Hal itulah yang menjadikan dimensi egalitarianisme dalam demokrasi justru menghi lang ka-rena adanya politik patronase partai terse-but.
Representasi yang menjadi aksioma po litik dalam makalah ini sebenarnya me-rupakan sebentuk anti tesis terhadap pro-ses kontradiksi demokrasi yang menghasil-kan politik kartel tersebut. Adapun politik representasi yang menjadi perhatian dan kepedulian dalam pesta demokrasi seka-rang ini adalah sebentuk resistensi populis yang dihadirkan pubik sebagai tanggap-an atas proses demokrasi elektoral yang dijalankan oleh berbagai macam partai po litik itu sendiri. Hadirnya semangat representasi sebenarnya mengindikasikan
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 47 4/24/2014 8:52:18 AM
48 PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK VOL II, 2014
ada nya upaya reaktivasi makna demokrasi substantif yang diinginkan publik sendiri untuk mereduksi adanya praktik pemba-jakan demokrasi yang selama ini dilaku-kan partai politik. Maka isu penting dalam penulisan makalah ini adalah mengetahui seberapa jauh proses tarik menarik kekua-saan antara kekuatan politik formal yang diwakili institusi partai dengan kekuatan politik informal yang dilaksanakan oleh kekuatan politik ekstra parlementer pub-lik dengan tujuan mengembalikan kem-bali esensi demokrasi substantif dalam pe-milu. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai kontestasi kedua kutub politis tersebut yakni bagaimana kekuat-an politik kartel ingin menegaskan domi-nasi politiknya, namun di saat bersamaan muncul juga rasionalisme pemilih yang me ngusung adanya representasi populis secara lebih meluas di ranah politik formal.
Representasi dan Politik Kartel dalam Demokrasi Elektoral
Membincangkan masalah representasi da-lam demokrasi elektoral sangatlah ter-kait dengan krisis kepercayaan dalam de-mokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat tiga penyebab alasan mengapa proses de-mokrasi menjadi macet. Pertama, saluran aspirasi publik tidak diperhatikan oleh para pemangku pejabat publik ketika men-jalankan roda pemerintahan. Para pejabat publik berkembang menjadi elite oligarkis yang lebih mementingkan kepen tingan pribadi maupun kelompok di atas kepen-tingan publik. Kedua, tidak adanya agen penghubung (intermediary) yang menjem-batani antara kepentingan publik dengan pemerintah. Adapun media, organisasi non pemerintah, maupun partai politik yang se-lama ini menjembatani, kurang begitu me-miliki peranan signifikan dalam konstelasi aspirasi. Ketiga, munculnya perilaku klep-
tokrat yang dilakukan oleh para pemangku jabatan publik. Dalam hal ini, perilaku klep-tokrat sendiri ditunjukkan dengan adanya perilaku korupsi yang dilakukan oleh para elite dalam menjarah anggaran publik. Ad-anya politik predatoris tersebut mengindi-kasikan adanya kejengahan publik terha-dap aksi pejabat publik. Demokrasi yang diharapkan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua kalangan jus-tru tergantikan dengan pemerintahan plu-tokrat yang hanya memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Hal itu tentu sudah me nyalahi arti demokrasi sendiri dengan menjadikan demokrasi sebagai ajang unjuk kekuasaan pribadi dan kelompok.
Publik tidak lagi dilihat esensinya se-bagai demos yang memiliki kekuasaan atas pemerintahan dan negara. Kondisi tersebut yang mendorong munculnya kedaulatan publik untuk kembali berkua-sa dengan menggantikan para pemangku jabatan yang tidak peduli dengan nasib masyarakat. Maka kata ‘chain of popular sov-ereignty’ menjadi artikulasi menarik dalam mewujudkan representasi publik tersebut. Hal itu merupakan respons dari adanya hubungan negara dan masyarakat yang serba terbelakang (underdeveloped) yang di dalamnya peran masyarakat semakin termarjinalkan dalam negara. Kondisi itu pula yang memicu urgensi ditegakkannya popular control dari dalam masyarakat yang meliputi tiga pilar berikut, yakni: (1) demos (2) public affairs, (3) intermediary (Tonrquist, 2009:10).
Representasi dalam hal ini bisa juga mengarah pada proses depolitisasi di-karena kan ketiga fungsi tersebut di atas tidak dijalankan oleh intermediary sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara. Yang terjadi justru model pemba-jakan demokrasi yang di dalamnya elite se-makin memperkuat dirinya dalam bentuk kartel oligarkis sedangkan publik justru
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 48 4/24/2014 8:52:18 AM
PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK WASISTO RAHARJO JATI 49
kian teralienasi dengan menguatnya kartel tersebut. Jika sudah demikian, maka makna pemilu sebagai sarana suksesi kekuasaan justu semakin terkaburkan.
Adapun pemahaman elite sendiri sebe-narnya terletak pada kemampuan mereka dalam memberikan peran dan pengaruh lebih besar pada masyarakat berkat keung-gulan-keunggulan yang dimilikinya. Se-cara sederhana, elite sendiri dapat dikate-gorisasikan sebagai pemuncak dalam hirarki masyarakat berkat keistimewaan yang mereka miliki. Oleh karena itulah, sejatinya kelompok bernama elite ini me-rupakan minoritas dalam masyarakat, na-mun yang kemudian memiliki kekuasaan besar. Melalui kemampuannya tersebut, mereka bisa memaksa orang lain untuk mengakui pengaruh politisnya. Pengerti-an elite bukanlah pengertian yang tung-gal saja, melainkan memiliki tingkatan atau jenjang seperti elite sebagai penguasa (governing elite), elite yang tak memerintah (non governing elite), dan terakhir adalah masyarakat (Haryanto, 2007).
Kartel yang dipaparkan dalam tulisan ini sebenarnya merupakan sekelompok elite yang telah menjadi satu organ de-ngan memiliki monopoli kekuasaan. Isti-lah kartel merupakan istilah baru dalam lanskap sosial dan politik di Indonesia karena kartel berasal dari bahasa ekonomi yang mengindikasikan adanya politisasi kekuasaan ekonomi dalam satu kelompok berikut dengan regulatornya. Istilah kartel sendiri dipopulerkan oleh Dodi Ambardi (2009) yang menyebutkan adanya sekelom-pok oligarkis yang berkuasa atas suprema-si kekuasaan negara dengan basis aliansi beberapa partai politik. Istilah kartel dalam politik Indonesia sendiri pertama kali digu-nakan oleh Slater (2004) yang menyebutkan kartel sebagai usaha untuk membangun aliansi kekuasaan antara partai pemenang dengan partai yang kalah dalam pemilu
demi harmonisasi kekuasaan. Partai pe-menang membutuhkan suara partai yang kalah untuk menjaga stabilitas kekuasaan dan meminimalkan suara kritis dari pihak yang kalah terhadap jalannya pemerintah-annya.
Yang terjadi kemudian adalah proses pragmatisme yang terjalin dalam dinami-ka kekuasaan yakni pengejaran terhadap rente ekonomi, survivalitas, dan sustaini-bilitas kekuasaan. Adapun karakteristik mendasar daripada kelompok kartel sen-diri kemudian meniadakan adanya batasan antara pemenang dan oposisi. Konteks ideologi dan progam menjadi tidak pen-ting untuk dibicarakan dan konsekuensi untuk masuk pemerintahan terbuka bagi semua partai asal masuk menjadi anggota koalisi. Maka keberadaan dan posisi kartel tersebut justru berbanding terbalik dengan representasi publik dalam arti nyata yang diinginkan oleh demos secara murni dan seluas-luasnya. Bagi publik, pemilu meru-pakan sebentuk instrumen representasi suara mayoritas yang perlu diperjuangkan dan direalisasikan. Namun justru dalam proses tersebut terjadi proses pembajakan yang dilakukan oleh para elite. Dalam hal ini, esensi demokrasi substantif yang in-gin direalisasikan oleh demos dalam sistem demokrasi perwalian justru tidak mem-buahkan hasil yang diharapkan. Posisi kartel yang sedemikian kuat sendiri sudah membuat posisi publik kian terjepit dalam memperjuangkan aspirasi dalam pemilu.
Kartel sendiri merupakan bentuk dari-pada embrio reorganisasi elite yang ingin mempertahankan cara-cara politik pre-dato risme. Mereka memanfaatkan celah keluguan publik dalam melihat demokrasi sebagai alat perjuangan. Mayoritas pen-duduk Indonesia masih melihat bahwa demokrasi masih dipahami secara terbatas. Bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berada di kalangan akar rumput, proses
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 49 4/24/2014 8:52:18 AM
50 PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK VOL II, 2014
demokrasi lebih dimaknai pada pemenuh-an kebutuhan sehari-hari dan mereka be-lum mengerti adanya proses advokasi terhadap kepentingan mereka ke dalam ranah publik. Celah itulah yang kemu-dian dimanfaatkan dalam kerangka prag-matisme politik yang dilakukan oleh elite, terutama oleh para kandidat, untuk men-jalankan mekanisme politik jual beli suara di ranah masyarakat. Dari proses tersebut, lahirlah yang disebut sebagai patronase politik yang berjalan secara turun temurun dalam setiap peristiwa pemilu. Adanya pelbagai proses advokasi terbarukan yang muncul pada era sekarang ini cenderung melihat adanya suatu kejengahan luar bisa dari publik yang sudah semakin skeptis ter hadap proses politik selama ini. Repre-sentasi simbolis melalui keterpilihan peja-bat publik tidak membuahkan hasil, malah justru kian menumbuhkan pemerintahan yang plutokrat. Kondisi itulah yang men-jadikan representasi menjadi kata kunci menarik untuk melawan gejala kartelisasi.
Lahirnya Kartelisasi Politik Paska Pemilu 2004
Lahirnya kartelisasi dalam ranah demokrasi di Indonesia terjadi paska pemilu 2004. Hal tersebut didasari pada perimbangan kekua-saan yang berlainan antar partai pemenang pemilu presiden dan pemilu legislatif. Da-lam pemilu 2004, partai Golkar muncul se-bagai pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau dengan persentase 21,58 persen; sedangkan partai Demokrat sendiri-- sebagai pemenang pemilu Pre-siden---hanya memenangi 8.455.225 suara atau setara dengan 7,45 persen. Adanya perimbangan kekuasaan yang berbeda dalam dua ranah tersebut yang kemudian menimbulkan adanya kompromi politik. Golkar sebagai penguasa mayoritas legis-latif sendiri tentu tidak bisa mewujudkan
ide-idenya dalam bentuk progam-program kebijakan. Sedangkan Demokrat tidak bisa mengesahkan produk kebijakan maupun progamnya tanpa lewat pengesahan suara mayoritas dari legislatif maupun partai mi-noritas yang memiliki kursi di DPR.
Kondisi itulah yang kemudian men-ciptakan adanya pragmatisme politik di antara beberapa partai politik yang akhir-nya mengerucut pada pembentukan koalisi permanen dan menimbulkan pola oligarki kekuasaan dalam bentuk kartel. Kartel ter-cipta lantaran masih kentalnya penguat-an faktor suka atau tidak suka pada so-sok figur yang mencitrakan etnis tertentu dalam pembentukan preferensi memilih pada pemilu 2004 hingga 2009 (Aspinall, 2010:85). Gejala tersebut merupakan ekses reduksi dari makna demokratisasi selama era transisi politik yang lebih mengarahkan pada proses representasi formal institusion-al di ranah pemerintahan nasional maupun lokal. Dikarenakan terjadi proses penguat-an pada ranah representasi formal, maka proses penyerapan aspirasi dari bawah kemudian cenderung terpolitisasi sesuai dengan selera partai maupun elite. Model pelembagaan yang terjadi paska 2004 ke-mudian menghasilkan party based govern-ment atau party based democracy electoralism, serta voting centric. Party based government adalah konsepsi yang memberikan justi-fikasi pada peran partai di pemerintahan. Adanya model pelembagaan itulah yang menyebabkan posisi partai politik menjadi menggurita baik sebagai pengawas, pelak-sana, maupun pengontrol kebijakan nega-ra. Dalam kondisi demikian, publik seba-gai demos hanya menjadi partisipan pasif dalam proses demokrasi tersebut.
Sejalan dengan itu, proses pembangun-an demokratisasi dalam ranah informal dan masyarakat sendiri kurang diperha-tikan. Fenomena itulah yang kemudian menimbulkan adanya pembusukan dalam
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 50 4/24/2014 8:52:18 AM
PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK WASISTO RAHARJO JATI 51
demokrasi. Pemahaman demokrasi yang melulu dipahami secara formal inilah yang mengebiri hak dan kewajiban masyarakat. Pemilu kemudian hanya dipahami secara formal sebagai manifestasi demokrasi oleh publik. Pemilu 2004 sendiri menjadi ajang politik pengharusan bagi para kandidat legislator untuk mendekati publik. Publik merasa diperlakukan sebagai tuan dalam proses seremonial tersebut. Dalam proses itu, para kandidat mendekati publik de-ngan segenap janji dan impian manis. Ada berjuta harapan dan janji yang disampai-kan para kandidat dalam proses kampanye tersebut. Namun setelah pemilihan selesai dilangsungkan, para pemilih kemudian ditinggalkan, utamanya ketika para kan-didat sudah merengkuh kekuasaan dalam genggaman tangannya.
Adanya model pemilihan langsung yang mulai dijalankan pada tahun 2004 merupakan hal baru dalam eksperimen-tasi demokrasi Indonesia. Dalam konteks tersebut, demokrasi masih dianggap awam dalam pendidikan politik Indonesia se-cara keseluruhan. Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia tengah memasuki periode rekonsiliasi dan konsolidasi paska konflik sekaligus transisi demokrasi. Maka konteks pemilu langsung kemudian masih dianggap sebagai suatu selebrasi poli-tik semata yang dilakukan oleh elite dan masyarakat.
Dikarenakan sifatnya yang masih eks-perimentatif, maka proses demokrasi elek-toral pada akhirnya mulai mengenalkan istilah-istilah baru guna meningkatkan kualitas pemilu seperti threshold (bilangan pembagi pemilih), baik itu electoral thresh-
old maupun parliamentary threshold. Imple-mentasi kebijakan elektoral tersebut dirasa urgen dan signifikan mengingat konteks multipartai di Indonesia mempunyai in-dikasi patologis yakni hanya mengejar rente kekuasaan dan berebut materi angg-aran. Asumsi tersebut sebenarnya tidaklah salah mengingat esensi pendirian partai adalah mewujudkan aspirasi publik dalam ranah kebijakan dan pemerintahan.
Namun rupanya, ada pelbagai upaya distorsi yang dilakukan oleh para elite baik dari pejabat maupun partai politik dalam rangka mengukuhkan hegemoninya. Salah satunya adalah dengan penerapan nominal persen dalam threshold. Alibi yang dikemu-kakan selama ini adalah untuk penguatan elektoral, namun hal tersebut sebenarnya merupakan dalih saja untuk memperkuat sistem kartel yang dibangun paska 2004. Ada perubahan yang cukup drastis dalam eskalasi nominal threshold tersebut mulai dari 2,5 persen, 3,5 persen, hingga ada yang mewacanakan dinaikkan menjadi 5 persen. Adanya kebijakan sporadis semacam ini tentu hanya akan meningkatkan populari-tas partai besar saja yang memiliki sum-ber daya lebih tinggi daripada partai kecil dalam setiap peristiwa pemilu. Implikasi yang ditimbulkan ialah membesarnya fungsi dan pengaruh kartel partai dalam setiap pembuatan kebijakan. Maka jika di-lacak dari segi historisitasnya, komparasi pemilu 2004 dengan pemilu 2009 dapat dilihat sebagai manifestasi penguatan kartel ter utama dalam pembuatan sistem demokrasi elektoral, yang secara lengkap dapat dilihat dalam tabulasi berikut ini.
Komparasi Pemilu 2004 dan Pemilu 2009
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 51 4/24/2014 8:52:18 AM
52 PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK VOL II, 2014
Tabel 1: Rule of Electoral Reform / Pemilu 2004 ke Pemilu 2009
No Faktor Pembeda Pemilu 2004 Pemilu 2009
1 Sistem Pemilihan UmumA. Pemilu DPR /
DPRD dan DPRD Kabupaten / Kota
A. Pada Pemilu 2004, sistem yang digunakan adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka yang merupakan persilangan hibrida antara sistem distrik dan proporsional (Joko Prihatmoko, 2008)
B. Adapun setiap daerah pemilihan (district magnitude), kursi yang diperebutkan baik DPR dan DPRD adalah 3-12 kursi. (M. Nadjib, 2005 : 4)
A. Masih sama dengan sistem pemilu sebelumnya yakni sistem proporsional dengan daftar terbuka
B. Berbeda dengan pemilu 2004, kursi DPR yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan yakni berkisar antara 3 – 10 kursi sedangkan kursi DPRD yang diperebutkan berkisar antara 3 – 12 kursi (Sigit Pamungkas, 2009 : 143)
2 B. Pemilu DPD A. Pemilu DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak dengan setiap distrik pemilihan / provinsi memperebutkan 4 kursi (M. Nadjib, 2005 : 3 ; Sigit Pamungkas, 2009 : 149)
B. Sama dengan sistem pemilu sebelumnya.
3 C. Pemilu Presiden / Wakil Presiden
A. Pemilu Presiden dan Wapres menggunakan sistem dua putaran pemilu / Run - Off Election
B. Sama dengan sistem pemilu sebelumnya
Tabel 2: Elements of Electoral System (Unsur – unsur sistem Pemilu)
No Unsur – unsur Sistem Pemilu Pemilu 2004 Pemilu 2009
1 Balloting (Penyuaraan) A. Mengacu pada UU No. 12 tahun 2003 yang menyatakan bahwa “surat suara dinyatakan sah apabila tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota berada pada kolom yang disediakan. Atau tanda coblos pada tanda gambar partai politik berada pada kolom yang disediakan
B. Suara dinyatakan tidak sah apabila pemilih hanya mencoblos nama calon saja dan tidak disertai dengan mencoblos tanda gambar partai nama calon yang dicoblosnya.
C. Implikasi lain adalah persilangan antara open list system yakni pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calonnya tanpa intervensi partai politik nama calon yang dicoblosnya dan closed list system yakni pemilih hanya memilih partai saja, untuk
A. Mekanisme penyuaraan / balotting dengan menandai (mencontreng) salah satu di antara gambar partai, nomor urut calon, atau nama calon. Suara tidak sah apabila memberi tanda lebih dari satu kali pada kertas suara.
B. Tipe penyuaraan bertipe kategorikal yakni memilih partai atau calon saja
C. Oleh karena itu kemudian, Pemilu 2004 menggunakan mekanisme menandai / pencontrengan dalam penyuaraannya.
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 52 4/24/2014 8:52:18 AM
PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK WASISTO RAHARJO JATI 53
kemudian partai itu mendistribusikan suara tersebut kepada daftar para calon kader partai politik tersebut. Oleh karena itu kemudian, Pemilu 2004 menggunakan mekanisme pencoblosan dalam penyuaraannya.
2 Jumlah Kursi Legislatif
A. Jumlah kursi bagi DPR sebesar 550 kursi.
B. Implikasi yang muncul adalah fenomena The New State Paradox yakni kenaikan kursi tidak memperhitungkan daerah propinsi pemekaran baru.
A. Jumlah kursi bagi DPR sebesar 560 kursi.
B. Rasionalitas penambahan kursi antara lain seperti :1) Mengikuti alur penambahan
daerah pemekaran2) Mengatasi
disproporsionalitas pemilih jawa dan luar jawa
3) Standarisasi proporsi jumlah pemilih dengan jumlah kursi di parlemen.
3. Threshold (Ambang Batas)
A. Pemilu 2004 masih menggunakan mekanisme electoral threshold yakni 3% dari jumlah kursi DPR atau sekurang – kurangnya 4% kursi dari jumlah kursi DPRD.
B. Implikasi yang muncul adalah The Threshold Paradox yakni ambang batas melebihi 4% dari yang semestinya 3%.
A. Pemilu 2009 menggunakan dua threshold yakni electoral threshold sebesar 3 % dan parliamentary threshold sebesar 2,5 %.
4. Election Formula (Rumusan Pemilu)
A. Dalam Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009 sama – sama memakai sistem pemilu hibrida yakni campuran antara sistem distrik dan sistem proporsional. Penggabungan tersebut justru menimbulkan berbagai problematika antara lain sebagai berikut ini :1) Sistem pemilihan ini dirasa sangat rumit karena penentuan daftar pemilih
ini dirasa sangat dilematis. Posisi dilematis terletak pada penduduk pada daerah pemilihan tersebut yakni jika menggunakan sistem proporsionalitas akan lebih efisien karena hanya menggunakan daerah pemilihan yang besar dan tunggal dan tak perlu membuat batas – batas daerah pemilihan lainnya sehingga efisien dan murah akan tetapi tidak memperhatikan aspek sosio kultural, ekonomi, maupun aspek geografis warganya dan terkesan “kurang demokratis” karena daerah pemilihan yang tunggal dan tidak jamak sehingga kurang mampu menjaring aspirasi masyarakat secara luas. Sedangkan kalau menggunakan sistem distrik, justru yang terjadi adalah kerepotan karena mengurusi dan mengawasi banyaknya daerah pemilihan sehingga sering kali muncul permasalahan seperti data kependudukan maupun administrasi kependudukan tumpang tindih dikarenakan arus mobilisasi penduduk yang begitu dinamis.
2) Permasalahan kemudian yang muncul adalah fenomena The Population Paradox yakni kuota kursi di setiap pemilihan sering kali berubah – ubah mengikuti alur dinamisasi penduduk tersebut seperti alur peningkatan dan penyusutan penduduk yang selalu terjadi terutama di bekas daerah konflik. Maka permasalahan yang jamak terjadi kasus pemilih ganda yang memilki hak pilih ganda, kasus munculnya pemilih di bawah umur, kasus orang yang sudah meninggal punya hak pilih, anggota TNI / Polri yang punya hak pilih padahal dalam undang – undang dikatakan tidak boleh berpolitik praktis, kasus pemilih yang tak mempunyai hak pilih karena tidak terdaftar dalam data kependudukan.
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 53 4/24/2014 8:52:19 AM
54 PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK VOL II, 2014
3) Selain itu permasalahan lain yang mucul adalah The Alabama Paradox yang muncul akibat kuota kursi yang tidak tetap (tentatif) menimbulkan kerugian bagi calon maupun partai politik yakni seorang calon yang sudah dipastikan mendapat kursi di daerah pemilihan tersebut sewaktu -waktu bisa hilang serta partai yang mendapatkan “bonus” ekstra karena mendapat limpahan kursi baru yang seharusnya mendapat satu kursi bisa mendapat lebih. Hal ini dikarenakan pergeseran kuota jumlah kursi tersebut yakni bertambah kursinya atau berkurang kursinya.
B. Pengingkaran terhadap sistem distrik telah menimbulkan banyak kekhawatiran yakni kurangnya derajat demokrasi karena partai – partai politik yang kecil justru kalah bersaing dengan partai – partai besar yang sudah mapan sehingga “demokrasi” hanya berlaku bagi partai besar bukan bagi partai kecil.
C. Setiap daerah pemilihan yang dibentuk didasarkan pada data dan administrasi kependudukan dan partai yang telah lolos verifikasi untuk menjadi partai peserta pemilu. Hal ini tentu saja rawan diskriminasi, sebagai contoh partai A lolos verifikasi tingkat daerah akan tetapi tak lolos verifikasi nasional sehingga partai A tersebut tidak bisa menjadi peserta pemilu.
D. Munculnya oligarki elite dalam proses pencalonan di tingkat kader artinya calon yang akan bertarung dalam arti calon yang diusung ternyata calon yang dekat dengan elite serta yang punya banyak uang sehingga kader yang kompeten digusur demi kader “instan” tersebut.
E. Sistem ini belum menjamin hadirnya aktor independen untuk bertarung dalam proses pemilihan umum karena saling tumpang tindih peraturan KPU dan MK yang masing – masing sangat paradoksal. Dalam hal ini MK dalam amar keputusannya memperbolehkan calon independen untuk bertarung dalam pemilu. Akan tetapi KPU “setengah hati” untuk melaksanakannya (Joko Prihatmoko, 2008 : 303).
Tumpang tindih sistem, artinya dalam regulasi jelas dikatakan bahwa menganut sistem daftar terbuka yang memberikan keleluasaan dalam memilih calon dan partai. Akan tetapi sering juga ditemui praktek daftar tertutup yakni praktek nomor urut calon yang potensial meraih suara banyak dan memenangkan par-tai tersebut akan ditempatkan pada nomor urut yang lebih kecil.
Adapun kebaikan dari sistem campuran ini adalah bisa meminimalisasi konflik dan menghapuskan pembilahan (cleavage) yang terjadi antara calon yang dipilih berdasar nomor urut (sistem proporsionalitas) dan lolos dari Bilangan Pembagi Pemilih.
5 District Magnitude Permasalahan yang kerap muncul dalam setiap penentuan district magnitude antara lain:A. DM sering kali ditetapkan pada border yang kurang tepat sehingga saling
tumpang tindih satu sama lainnya.B. DM tidak selalu memperhatikan aspek sosial kultural, budaya, maupun
geopolitik masyarakatnya sehingga sering kali merugikan partai politik yang kehilangan konstituen mereka.
C. DM sering kali ditempatkan pada kontur geografi yang berlainan seperti kasus pemilih di salah satu distrik di beberapa kabupaten yang terletak di daerah pegunungan Jayawijaya (Papua) yang harus berjalan kaki beberapa kilometer untuk mencapai TPS.
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 54 4/24/2014 8:52:19 AM
PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK WASISTO RAHARJO JATI 55
Tabel 3: Controlling of Vote / Structure of the Ballot
No Pemilu BPP (Sistem Distrik)Daftar Nomor Urut (Proporsional)
1 Pemilu 2004 Walaupun dalam pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Akan tetapi masih ditemui beberapa kendala seperti Penyuaraan dengan mencoblos tanda gambar partai sahA. Calon yang terpilih memperoleh suara sama / lebih dari BPP setara dengan calon
yang dipilih berdasar nomor urut pada daftar calon partai.B. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan bias dalam mekanisme kontrol suara
dalam pemilu 2004. Di satu sisi calon dapat terpilih dengan berjuang mati – matian memperebutkan dukungan suara sebanyak – banyaknya dari masyarakat sehingga merasa “berhutang budi kepada rakyat” dan saluran akuntabilitas dan kredibilitasnya dapat dikontrol masyarakat. Sementara di sisi lainnya, calon dapat terpilih tanpa “berkeringat” yakni dengan distribusi suara partai kepada daftar calon partainya. Tentu saja dalam hal ini calon yang berada di nomor urut kecil mempunyai harapan besar untuk terpilih dibandingkan mereka yang bernomor urut besar sehingga calon yang terpilih cenderung memperjuangkan aspirasi partai daripada rakyat
2 Pemilu 2009 Dalam Pemilu 2009, struktur penyuaraan maupun mekanisme penyuaraan teregulasi pada mekanisme perolehan dukungan suara minimal 30 % BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Oleh karena itu kemudian :1) Calon yang terpilih harus memperoleh dukungan lebih besar atau kurang dari 30 %
BPP.2) Calon yang terpilih memiliki dukungan suara yang persentasenya sama atau
sekurang – kurangnya 30 % BPP dengan syarat jumlah suara sama / kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu
Oleh karena itu kemudian, intervensi partai politik dalam pemenangan calonnya dijamin tidak akan terjadi sehingga dalam hal ini baik calon yang bernomot urut kecil dan banyak harus berjuang mendapat 30 % suara BPP untuk terpilih (Sigit Pamungkas, 2009 : 148-149).
Dari hasil komparasi dua hasil Pemilu di atas, beberapa temuan yang menarik sebenarnya lebih merujuk pada penguatan politik kartel. Berbagai indikasi maupun parameter bisa dilihat dari tabulasi di atas. Yang pertama, tentu saja eksperimentasi sistem pemilu yang selalu fluktuatif. Da-lam setiap peristiwa pemilu di Indonesia sangat terlihat bahwa penguatan kekua-saan semakin lama semakin mengerucut pada penguatan politik kartel. Penegasan-nya adalah pencampuran sistem pemilu kadang kala membingungkan dan lebih mengutamakan pada pengistimewaan kandidat dan partai politik. Yang kedua, menguatnya nominal dalam ambang batas yang sejatinya memarjinalkan representasi suara pemilih yang tidak memilih pada sosok figur yang populer maupun partai
besar. Hal itulah yang menjadikan konteks pelaksanaan pemilu di Indonesia semakin tidak terlegitimasi dari penyelenggaraan pemilu dari ke tahun ke tahun. Indikasinya bisa tercermin dari semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilih yang semula mencapai 92,7 persen pada pemilu 1999 kini hanya menyisakan 70,2 persen pada pemilu 2009. Menurunnya tingkat parti-sipasi pemilih sebanyak 20 persen tentu menjadi tanda waspada kuning terhadap penyelenggaran pemilu selama ini. Yang ketiga adalah semakin bertambahnya jum-lah kasus korupsi paska pemerintahan otoriter, baik yang dilakukan oleh partai maupun kandidatnya selama mereka me-megang kekuasaan. Implikasinya adalah menguatnya rasa distrust maupun distract yang ditunjukkan oleh publik selama pe-
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 55 4/24/2014 8:52:19 AM
56 PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK VOL II, 2014
merintahan yang dihasilkan kurang begitu maksimal dalam memberikan pelayanan publik. Adanya fait accompli yang dihasil-kan dalam proses pemilu dikorelasikan dengan gejala deprivasi politik yang di-alamatkan publik kepada para elite yang berkuasa di tampuk kekuasaan baik level legislatif maupun eksekutif.
Secara makro, temuan-temuan baru (kernel points) yang bisa diuraikan dalam perbincangan representasi publik dengan politik kartel adalah 1) menguatnya pro ses advokasi publik yang dilakukan melalui jaringan-jaringan masyarakat sipil dari berbagai macam latar belakang isu gencar dalam membuat framing isu kepada kartel elite demi menurunkan kredibilitasnya. 2) politik kartel di Indonesia hanya bersifat temporer dan berbasis nir ideologi yang mengikat bersama, akibatnya konsolidasi dan kohesivitas politik kartel sendiri dalam menanggapi isu kritikan dari publik tidak-lah seia sekata. 3) Representasi po pulis yang hendak ditujukan oleh publik dalam demokrasi elektoral di Indonesia sebenar-nya juga setali tiga uang dengan pemba-ngunan basis politik kartel yakni hanya berbasis by issue yang didesain secara ar-tifisial saja. Representasi menguat hanya ketika isu korupsi mencuat selama peme-rintahan, sedangkan kartel menguat berkat adanya figur yang kuat.
Maka yang perlu dielaborasi lebih lanjut dari temuan makalah ini sebenar-nya adalah menemukan institusionalisasi yang tepat dalam menampung aspirasi demokratis baik yang berada di tataran in-traparlementer maupun tataran ekstrapar-lementer. Adapun di tataran intra sendiri, sebenarnya lebih pada penguatan moral dan etika untuk melihat kekuasaan sebagai wakaf politik yang dimandatkan oleh pub-lik. Sedangkan di level ekstra, institusion-alisasi bisa mengarah pada pembentukan jaringan epistemik baik itu di dalam or-
ganisasi maupun yang berbasis komunitas, namun tetap saja kedua-duanya memiliki kepedulian dan resistensi kritis yang kuat untuk mengawal pemerintahan.
Pemilu 2014 Sebagai Pertaruhan Politik
Membaca konstelasi yang berkembang selama peristiwa pemilu saat ini sejatinya merupakan pertaruhan politik antara me-lemahnya politik kartel dengan menguatnya representasi publik. Dalam beberapa tahun terakhir disebutkan tingkat ketertarik an publik terhadap masalah-masalah politik sendiri kini berkisar 23 persen. Secara lebih lengkap menurut rilis Pusat Penelitian Poli-tik (P2P LIPI) pada 2012-2013 menyebutkan bahwa hanya 12,8% responden yang mera-sa bisa mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, hanya 30% responden yang merasa keluhannya diperhatikan pemerintah.
Menguatnya dimensi apolitis yang di-tunjukkan oleh publik khususnya menjelang perhelatan pemilu legislatif ini menunjuk-kan bahwa geliat tingkat informasi publik sendiri sudah semakin menguat dari tahun ke tahun. Adanya gejala penguatan apoliti-sasi tersebut tentunya dapat dilacak mela-lui semakin terbukanya sumber informasi yang sudah semakin plural untuk disimak oleh masyarakat. Setidaknya preferensi bu-daya politik yang berkembang saat ini lebih banyak didominasi sekitar 48,5% pemberi-taan media. Paradigma pemberitaan yang dibangun media yakni bad news is good news rupanya memberikan andil besar dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Praktik jurnalisme yang menghasilkan pemberitaan negatif tentu memberikan pengaruh signifikan terhadap elektabili-tas partai politik maupun kandidat yang terkena efek media tersebut. Adapun ba-hasa politik pencitraan yang selama ini di-gunakan tidak bisa digunakan kembali un-
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 56 4/24/2014 8:52:19 AM
PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK WASISTO RAHARJO JATI 57
tuk menutupi berbagai kebopengan politik yang dimiliki oleh partai politik maupun kandidat. Hal tersebut justru menimbul-kan efek paradoksal terhadap proses elek-tabilitas politik karena akan berimplikasi pada munculnya efek politik hipokrit yang disematkan pada elite.
Pemilu 2014 baik dari segi aturan regu-lasi threshold maupun sistem pemilu me-mang menawarkan aturan yang tidak jauh berbeda dengan pemilu 2009 dengan ba-tas 3,5 persen bagi suara legislasi nasional maupun 25 persen bagi gabungan partai untuk mengajukan calon presiden pada pemilihan presiden 9 Juli 2014 mendatang. Adanya persyaratan tersebut tentu saja akan lebih menguntungkan eksistensi par-tai kartel yang telah berada dalam lingkar kuasa selama 10 tahun ini. Namun hal itu bisa saja menjadi blunder politik bagi kartel di tengah lesunya keinginan memilih yang ditunjukkan partai politik. Tingkat kema-tangan dan kecerdasan publik tentu sudah semakin tinggi pada Pemilu 2014 ini. Hal inilah yang justru menjadi titik balik antara tenggelamnya politik kartel maupun me-nguatnya proses representasi publik dalam demokrasi elektoral.
Selain menjadi titik balik, hal penting lainnya adalah pemilu ini merupakan mo-mentum adanya transisi politik pada era kekuasaan presidensialisme. Selama dua periode ini terlihat bahwa pola reorgan-isasi yang berlangsung selama ini justru te-lah menghasilkan pembajakan demokrasi yang dilakukan para elite. Para elite yang kembali memerintah pada era ini justru mengarah pada kembalinya kekuasaan neo-otoriter yang dikemas secara komodi-tas demokrasi semu (pseudo democracy). Hal itulah yang membuat proses pemerintahan hasil elektoral selama ini lebih mengarah pada proses transaksional maupun pat-ronase politik yang justru mengarahkan kekuasaan terbentuk dan terkonsolidasi di
puncak menara gading. Hal tersebut pada gilirannya malah dapat memicu muncul-nya gejala depolitisasi pada ranah lokal maupun nasional yakni gelombang apa-tisme yang semakin membuncah dan se-makin menguat.
Gerontokrasi yang berada dalam ling-kar kekuasaan, yakni munculnya para politisi uzur yang sudah lama eksis da-lam lingkar kekuasaan istana maupun ge-dung kura-kura, sudah waktunya diakhiri. Pemilu 2014 mendatang ini dinilai tepat untuk memberikan tongkat estafet kepada ge nerasi muda yang lebih akuntabel dan kredibel dalam mengelola pemerintah-an agar sesuai dengan jalur treknya yang benar. Konsekuensinya, hasil pemilihan umum tahun ini menarik untuk dicermati. Apakah melanjutkan adanya kartelisasi edisi ketiga ataukah menjadi era baru da-lam pemerintahan yang di dalamnya hak publik sebagai demos sangatlah dihargai dalam pemerintahan lima tahun menda-tang (2014 – 2019)?
Penutup
Menguatnya proses demokratisasi yang kini telah mengalami proses pematangan (matured) perlu diapresiasi sebagai bentuk pendewasaan politik kontemporer. Hal inilah yang membuat pemilu menjadi sa-rana penting dalam hal transfer kekuasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berkaca pada pengalaman Indonesia, ben-tuk pemilu selalu bernuansa temporer dari satu fase ke fase berikutnya. Pemilu 1999 dan 2004 sendiri masih dianggap sebagai pemilu konsolidasi sekaligus pemilu rekon-siliasi antara hubungan negara dengan ma-syarakat. Masyarakat masih mengalami pengobatan atas trauma konflik yang men-jadikan konteks pemilu sendiri lebih pada usaha pencapaian stabilitas politik. Namun
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 57 4/24/2014 8:52:19 AM
58 PEMILU 2014: KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK VOL II, 2014
demikian, tak dinyana, proses demokrati-sasi tersebut justru menghasilkan adanya reorganisasi elite yang semakin membesar.
Pemilu tahun 2004 mengindikasikan adanya perubahan signifikan terhadap sistem politik. Sistem politik yang dulunya serba otoriter menuju akumulasi kekua-saan yang bernama kartel. Kartel dibangun atas logika kompromistis dan transaksion-al demi mengejar kursi publik. Adapun kondisi dalam publik sendiri masih belum memahami benar mengenai konteks pemi-lu. Hal itulah yang kemudian menjadikan pemahaman demokrasi menjadi formal institusional. Proses representasi publik cukup diwakilkan oleh partai politik yang berimplikasi pada menguatnya organisa-sional di tingkat elite. Maka tidaklah meng-herankan apabila luaran hasil pemilu ta-hun 2004 hingga pemilu tahun 2009 hanya menghasilkan pemerintahan eksekutif dan legislatif nasional yang tidak efektif dan efisien dalam mengeksaminasi kebijakan. Kondisi tersebut jelas saja menimbulkan kegeraman publik terhadap proses peme-rintahan yang tidak stabil dengan skandal negatif yang memicu menguatnya proses advokasi dan representasi publik. Pemi-lu 2014 adalah determinan utama dalam mengukur tingkat kecerdasan publik mau-pun juga mengukur memudarnya elitisme dalam ranah masyarakat. Maka patut disi-mak pula dinamika rivalitas, dan kontesta-si yang akan berlangsung di dalamnya. Baik elite maupun publik mau tidak mau harus siap dengan dinamika yang berkem-bang selama maupun sesudah pemilihan legislatif dilangsungkan pada April ini.
Sedang kan publik dalam arti sebagai demos perlu menguatkan posisinya sebagai suatu forum yang kuat dalam mengawal, dan meng awasi jalannya pemerintahan, siapa-pun yang memegang kekuasaan formal di kursi legislatif maupun eksekutif, ke de-pannya.
DAFTAR PUSTAKA
Ambardi, Kuskridho. (2009). Mengungkap Politik Kartel. Jakarta: Gramedia.
Aspinall, Edward. (2010). Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society. Singapura: ISEAS Publishing.
Hadiz, Vedi. (2013). Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. Indonesia 96 (2), 35-57.
Haryanto. (2007). Kekuasaan Elite. Yogya-karta: PolGov UGM.
Nadjib, Muhammad. (2005). Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi. Yogya-karta: KPU DIY.
Pamungkas, Sigit. (2009). Perihal Pemilu. Yogyakarta: PolGov UGM.
Prihatmoko, Joko. (2008). Mendemokratiskan Pemilu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Slater, Dan. (2004). Indonesia’s Accountabil-ity Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition. In-donesia 78 (2), 61-92.
Sorensen, Georg. (2007). Demokrasi dan Demokratisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tornquist, Olle. (2009). Rethinking Popular Representation. London: Palgrave Mac-millan.
004-[Wasisto] PEMILU 2014 KARTELISASI ELITE VERSUS REPRESENTASI PUBLIK.indd 58 4/24/2014 8:52:19 AM
Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, hal 59-78ISSN 2302-5719
Vol II, Nomor 1
Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara
JOHANES SUPRIYONO
Peneliti dan Pemerhati PapuaSurel: [email protected]
Diterima: 28 Februari 2014Disetujui: 24 Maret 2014
ABSTRACT
This article aims to trace how Papuan is represented or even defined by the state in order to legitimize de-velopment qua civilizing process. It appears that the discourse of development---with progress as the main reason behind it--- entangled with colonial discourse, i.e. how Papuan has been represented for years, has opened the door to variety of practices where knowledge and power of the State has appropriated Papua as ‘the desiring object of the State’s Will.’ In this article, I will argue thoroughly how Papua has been con-structed by the State as the other. Ever since Papua had been re-integrated formally into Indonesia post-Pepera in 1969, the development process had had just begun. Several documentations which contain the progress of development process portray Papuan as a tribe who desperately needs development for various reasons. For that matter, the State (qua government) owes its development project based on the image of Papuan already represented, that is an expanding discourse rooted in Dutch expeditions exercised in Papua.
Keywords: Colonial discourse, Papua, development, state (Indonesia).
Pendahuluan
Menyimak dokumen-dokumen pembangun-an tentang Irian Barat yang dikeluarkan oleh Bappenas sejak Repelita I, saya menemukan penggambaran tentang Papua yang mirip dan berulang-ulang. Pemerintah meng-gambarkan manusia Papua, penduduk di wilayah yang baru saja diintegrasikan itu, sebagai masyarakat yang masih sangat sederhana sedangkan wilayahnya masih belum memiliki fondasi pembangunan ekonomi. Gambaran lengkapnya sebagai
berikut, “Masyarakat pedalaman Irian Jaya pada umumnya masih dalam taraf kegiatan mencari/memenuhi kebutuhan makanan sendiri/keluarga sendiri.” Dokumen yang sama menuliskan, “Tingkat sosial budaya dan pendidikannya sangat sederhana.”
Pada Repelita I Pemerintah pusat se-bagai agen pembangunan yang paling ber kuasa pada masa-masa awal berfokus lebih pada infrastruktur transportasi laut, udara, dan darat serta upaya untuk “me-ningkatkan kesadaran masyarakat menu-
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 59 4/24/2014 9:49:07 AM
60 Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara VOL II, 2014
ju persatuan dan kesatuan Nasional.” Re-pelita-repelita berikutnya memang mulai berfokus pada bidang yang lain, seperti eksplorasi sumber-sumber daya alam. Inti pemba ngunan di Papua adalah mendorong Papua untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Amat jelas, arah pembangunan masa itu adalah pencapaian angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Sepanjang riwayat pembangunan oleh pemerintah pusat, sekurang-kurangnya yang tertera dalam dokumen, orang-orang Papua tampaknya tidak menjadi bagian yang penting. Dalam Repelita III, peme-rintah mengejar target di bidang hasil pertanian sehingga membutuhkan tenaga kerja yang besar. Akibatnya, pemerintah menggenjot angka peserta transmigrasi. Keputusan Presiden No.7/1978 tentang transmigrasi memberikan kerangka dan landasan hukum yang kuat. Maka, wilayah-wilayah dataran rendah seperti Nabire, Kla-mono, Genyem, dan Jayapura dibanjiri para migran dari Jawa yang dimulai sejak 1982. Orang-orang ini menggarap sawah-sawah yang baru saja dicetak. Semua ke perluan ditanggung oleh pemerintah. Wajarlah ka-lau pemerintah menargetkan 140-200 ribu KK untuk bertransmigrasi ke Papua.1
Pada Mei 1984, Presiden Soeharto me-ngumumkan bahwa pada Repelita IV, transmigrasi memiliki peran yang krusial. “Para transmigran itu membawa dampak
besar bagi kemajuan pembangunan masa depan Indonesia dan terutama untuk upa-ya meletakkan fondasi masyarakat Panca-silais yang sangat diharap-harapkan oleh bangsa ini” (Otten, 1986: 3).2 Transmigrasi telah menjadi penyumbang perubahan de-mografis yang serius di Papua sehingga di wilayah-wilayah perkotaan jumlah popu-lasi non-Papua mengungguli orang Papua, dan secara ekonomi, yang pertama me-nguasai yang terakhir (Upton, 2009: 4).3
Ketika menyimak dokumen-dokumen pembangunan itu, saya menyimpan per-tanyaan yang cukup serius untuk saya pi-kirkan jawabannya. Sementara para trans-migran itu diberi peran untuk mengolah sawah dan mengupayakan pusat-pusat perkebunan baru untuk mendorong per-tumbuhan ekonomi; lantas apa peran yang dipercayakan kepada orang-orang Papua? Apabila orang-orang dari Jawa itu dilihat sebagai tenaga kerja yang bisa memenuhi tuntutan kebutuhan, apakah begitu juga dengan orang Papua? Pada ujungnya, per-tanyaan saya adalah siapakah orang Papua itu menurut negara? Pertanyaan lain yang mungkin menyusul seketika adalah me-ngapa wacana semacam itu yang dikon-struksi oleh pemerintah?
Gugus pertanyaan di atas muncul da-lam benak saya ketika saya menyimak se-jarah pembangunan dan transmigrasi di Pa pua setelah integrasi. Dalam perkem-bangan berikutnya, orang-orang Papua di
1 Sejarah pemindahan penduduk ke Papua sudah terjadi sejak pemerintah Belanda berkuasa di Papua. Ketika pe-merintah Belanda membuka pos pemerintahan di Merauke pada awal dekade 1900-an, mereka memindahkan pen-duduk dari Jawa untuk menopang pos itu. Pada masa Republik Indonesia, pemindahan penduduk sudah dimulai dari skala kecil pada tahun 1963 ketika Soekarno menghimpun relawan untuk Papua, dan atas prakarsa pemerintah masih berlanjut hingga menjelang akhir abad yang lalu. Di Nabire, tempat penelitian ini dilakukan, program itu masih berjalan pada tahun 1998 ketika Departemen Transmigrasi dikepalai oleh A.M. Hendropriyono.
2 Kutipan ini merupakan terjemahan saya atas kata-kata Soeharto yang dimuat di harian The Jakarta Post pada 28 Mei 1984 dalam Marriel Otten. (1986). Transmigrasi: Indonesia Resettlement Policy 1965-1985 IWGIA Document 57, hlm. 3. Dalam bahasa Inggris tertulis demikian, “They will have a strong bearing on the progress of development in Indonesia for the future, especially to the endeavors to lay down the foundation of the Pancasilaist Society, long cherished by the nation.”
3 Tentang perubahan demografis dan dampaknya yang menyingkirkan orang asli Papua dari ranah ekonomi lihat disertasi Stuart Upton. (2009). The Impact of Migration on the People of Papua, Indonesia. A historical demographic analysis. University of New South Wales.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 60 4/24/2014 9:49:07 AM
Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara JOHANES SUPRIYONO 61
kawasan urban menjadi termarjinalisasi. Selain minoritas dalam soal jumlah popula-si, mereka juga sekunder dalam soal keter-ampilan dan kemampuan ketenagakerjaan. Tidak sedikit dari mereka kemudian hidup lontang-lantung tanpa masa depan yang jelas. Seperti disimpulkan oleh penelitian LIPI (2009), orang-orang Papua sungguh-sungguh terpinggirkan dan tertinggal jauh dari penduduk imigran. Akan tetapi, sejauh ini usaha negara dalam hal ini pemerintah untuk memberdayakan penduduk lokal Papua tidak tampak serius.
Dalam menguraikan jawaban atas gu gus pertanyaan di atas itu, saya berusaha me-nempatkan jawaban saya dalam kerangka sejarah Papua-Indonesia yang menjadi latar belakang historis bagi konsep Peme rintah Indonesia dalam memandang orang Pa-pua. Dalam lintasan sejarah pembangun an dan mengacu pada penelitian di lapang an, saya melihat orang-orang Papua ditampil-kan oleh pemerintah sebagai kelompok yang membutuhkan pembangunan sementara pemerintah dan para transmigran adalah kelompok yang melakukan pembangunan. Pe-merintah, yang dalam hal ini juga berperan sebagai agen pembangunan, dalam doku-men-dokumen pembangunan mengatego-rikan masyarakat Papua sebagai kelompok yang kurang berkembang. Maka, pemerin-tah memprogramkan serangkaian proses pembangunan untuk masyarakat Papua.
1. Konteks Historis Relasi Indonesia-Papua
Papua sekarang adalah salah satu provinsi di Indonesia yang diatur secara khusus. Sejak diberlakukan Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus, pemerintah Papua mendapatkan sejum-lah kewenangan yang lebih luas untuk meng atur daerahnya dibanding provinsi-provinsi yang lain.4 Undang-undang ini dipandang sebagai jalan tengah antara kehendak pemerintah pusat yang meng-inginkan Pa pua tetap berada di NKRI de-ngan aspirasi orang Papua untuk merdeka. Lewat Undang-undang itu, orang Papua dianggap bisa merdeka tapi masih di dalam NKRI.
Papua, dahulu Irian Barat, masuk ke Indonesia melalui referendum yang dini-lai bermasalah oleh penduduk Papua dan oleh pihak-pihak luar, terutama yang men-jadi saksi mata ketika pemungutan su-ara dilaksanakan pada Juli-Agustus 1969 (Drooglever, 2009).5 Pokok yang masih terus dipermasalahkan tentang plebisit itu adalah bahwa Indonesia tidak melakukan-nya sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 18 dan 20 New York Agreement. Bu-kannya menyelenggarakan dengan prinsip satu orang, satu suara (one man, one vote), refe rendum justru dilaksanakan dengan prinsip perwalian. Pemerintah Indonesia menetapkan 1.025 orang Papua untuk me-mutuskan bergabung atau tidak bergabung dengan Indonesia.
4 Pasal 4 ayat 1 UU No. 21 tahun 2001 berbunyi, “Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perun-dang-undangan.”
5 Tentang referendum yang menentukan Papua atau Irian Barat masa itu masuk ke Indonesia silahkan lihat P. J. Drooglever. (2010). TINDAKAN PILIHAN BEBAS!: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri. Yogyakarta: Kanisius. Selain dari buku itu, cerita tentang bagaimana referendum dilaksanakan di bawah tekanan atau ancaman masih bisa dituturkan oleh orang-orang Papua sendiri yang pada masa itu turut memberikan suara. Ketika Orde Baru berkua-sa, cerita seperti itu hanya bisa dituturkan di belantara hutan. Sekarang, para pelaku dengan berani menuturkannya sembari diberi tekanan emosional yang menonjol. Lihat juga International Center for Transitional Justice (2012). The Past That Has Not Passed: Human Rights Violations in Papua Before and After Reformasi. ICTJ dan ELSHAM-Papua.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 61 4/24/2014 9:49:07 AM
62 Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara VOL II, 2014
Lebih lagi, dalam perjanjian interna-sional itu, orang Papua tidak memiliki wakilnya sama sekali. Tiga pihak yang be-runding adalah Pemerintah Indonesia, Pe-merintah Belanda, dan Pemerintah Ameri-ka Serikat. Orang Papua sendiri tidak turut menentukan nasibnya dalam perjanjian itu. Sebaliknya, masa depan mereka di-tentukan oleh orang-orang lain. Artinya, Papua menjadi bagian dari NKRI melalui proses politik internasional yang manipu-latif. Bagi orang Papua, yang kala itu sudah membayangkan akan berdiri tegak sebagai sebuah negara merdeka setelah disiapkan oleh Belanda pasca-Indonesia merdeka, proses politik itu telah menumpas harapan mereka untuk menjadi negara merdeka.6 Proses referendum di bawah pengawasan PBB pun tidak menjadi proses bagi orang Papua untuk secara bebas menentukan na-sibnya sendiri.
Sejarah Papua sejak berada di bawah penguasaan Indonesia telah diwarnai oleh perlawanan panjang yang sporadis oleh berbagai kelompok masyarakat. Kelompok terpelajar Papua membuat reaksi dengan menggelar pertemuan komite nasional. Pe-
mimpin Partai Nasionalis (Parna), Herman Wayoi, dan seorang anggota Dewan Nu-gini, Nicolaas Tanggahma, mengorganisasi pertemuan yang diikuti oleh sekitar 90 pe-mimpin Papua. Robin Osborne mengata-kan bahwa mereka terpaksa setuju untuk menerima pemindahan kekuasaan dari Be-landa ke United Nations Temporary Executive Administration (UNTEA) dan mereka juga akan bekerja sama dengan UNTEA serta Pemerintah Indonesia. Mereka meminta UNTEA untuk tetap menghormati bendera dan lagu kebangsaan mereka. Satu hal lagi, mereka meminta referendum yang dijanji-kan diselenggarakan pada tahun 1963 (Os-borne, 2001: 68). Pada akhirnya, tidak satu-pun dari permintaan mereka itu dipenuhi. Periode UNTEA secara de facto adalah kon-trol Indonesia terhadap Papua (Pigay, 2001: 242).7
UNTEA menyerahkan pemerintahan atas Irian kepada Pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963. Akan tetapi, kehadiran orang Indonesia di sana telah dimulai se-jak sebelumnya. Operasi militer yang di-maksudkan untuk mengintegrasikan Irian Barat ke Indonesia sudah diawali pada ta-
6 Ketika perundingan-perundingan antara Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia berlangsung, rakyat di Papua sudah memiliki angan-angan untuk berdiri sebagai negara sendiri. Pada 1 Desember 1961, orang-orang sudah me-nyebarkan bendera negara, yaitu Bintang Kejora, begitu pula alat-alat kelengkapan yang lain bagi sebuah negara. Angan-angan untuk merdeka tersapu oleh fakta bahwa Indonesia yang memenangkan perundingan setelah di-sokong diplomasi Amerika Serikat yang mencegah Indonesia berkiblat ke Blok Timur, dan bantuan peralatan militer dari Uni Soviet agar Indonesia tetap bersahabat dengan Blok Timur.
7 Pada 31 Juli 1962 diadakan persetujuan sementara antara Indonesia dengan Belanda yang isinya memberatkan Be-landa sekaligus menegaskan kontrol Indonesia atas Papua sejak pemerintahan masih di tangan badan sementara PBB. Isi perjanjian sementara itu: Pertama, setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dengan Belanda maka selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 penguasa dari Badan Pemerintah sementara PBB (UNTEA) akan tiba di Irian untuk melakukan serah terima dari pemerintah Belanda. Saat itu juga bendera Belanda diturunkan. Kedua, Pemerintah Sementara PBB (UNTEA) akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan Indonesia bersama-sama dengan putra-putri Irian sendiri, dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan. Ketiga, Pasukan-pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian yang berstatus di bawah kekuasaan sementara PBB. Ke-empat, Angkatan Perang Belanda mulai saat itu secara berangsur-angsur dikembalikan. Yang belum berangkat akan ditempatkan di bawah pengawasan PBB, dan tidak boleh dipergunakan untuk operasi-operasi militer. Kelima, antara Irian dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas. Keenam, tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB. Ketujuh, pemulangan anggota sipil dan militer Belanda harus sudah selesai sebelum tanggal 1 Mei 1963 dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 Pemerintah Indonesia secara resmi menerima Irian dari Pemerintah Sementara PBB (Pigay, 2001: 242).
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 62 4/24/2014 9:49:07 AM
Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara JOHANES SUPRIYONO 63
hun 1961 (Rahab, 2010: 42).8 Sejak Soekarno menyerukan Trikora di Yogyakarta, peme-rintah sudah mengirimkan para penyu-sup ke Irian. Kemudian, pada tahun 1964, pemerintah mengirim para sukarelawan yang dinamai Tim Pelopor Pembangunan Serba Guna atau Pelopor Pembangunan Irian Barat (TPPSG/PPIB). Tim ini dibentuk oleh Presiden Soekarno. Mereka umumnya dari Jawa dan ditempatkan di Manokwari, Jaya pura, dan Merauke. Ada pula yang ditempatkan di pedalaman seperti di En-arotali. Banyak dari mereka adalah guru dan juga tentara yang rela diberi peran se-bagai pasukan pendahuluan untuk bekerja membuka jalan dan sarana umum lain-nya.9 Dengan lekas, Pemerintah Indonesia meng ambil peran sebagai pemerintah yang sah atas Irian. Pos-pos yang sebelumnya di-tempati oleh orang Belanda beralih tangan.
Setelah penyerahan administrasi oleh UNTEA, pemerintah mengambil kebijakan yang bersifat politis (Pigay, 2001: 259). Jabat an gubernur diberikan kepada E.J. Bonay, seorang putra daerah Irian, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya dikontrol
oleh militer, dan dikoordinasikan dengan Wakil Perdana Menteri Pertama Koordi-nator Irian Barat. Tampak bahwa yang memimpin Irian adalah putera daerahnya sendiri. Akan tetapi, menurut Pigay, ia ti-dak berdaya untuk mengambil kebijakan. Inpres 1963 No.2-Rahasia Bab III pasal 2 ayat 7 mengatur bahwa gubernur dibantu oleh Dewan Pembantu dan Penasihat yang terdiri atas Komando Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di Irian Barat, Kepala Kepolisian Komisariat Irian Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala-kepala Dinas. Aparatur pemerin-tahan di Irian Barat disebut sebagai Panca Tunggal.10
Sistem pemerintahan di Irian Barat di-kendalikan oleh militer dan militer sa ngat dominan, termasuk dalam mengontrol aparat pemerintah dan warga sipil. Siapa pun yang akan menduduki jabatan pub-lik harus disetujui oleh presiden setelah ia mendengar masukan dari bawahannya. Militer juga diberi peran yang besar dalam pemerintahan sipil. Militer di tingkat dis-trik dan desa mengordinasi aktivitas-ak-
8 Rahab memberikan informasi pembabakan infiltrasi yang berharga bahwa “fase pertama ditujukan untuk memben-tuk basis-basis gerilya dan mempersiapkan pembentukan pos terdepan bagi upaya penyerbuan Papua oleh Indone-sia. Dalam fase ini, sekitar 10 kompi prajurit ABRI dimasukkan ke Papua. Fase kedua adalah melakukan serangan terbuka di beberapa daerah seperti Biak, Fak-fak, Sorong, Kaimana dan Merauke. Fase ketiga adalah konsolidasi pasukan sebagai kekuatan militer Indonesia di Papua.”
9 Seluruh pasukan infiltran ini tunduk pada perjanjian New York, dan diatur ke dalam Kontingen Indonesia (Kotindo) sebagai pasukan keamanan UNTEA. Pasukan Indonesia ini kemudian diperbantukan di United Nation Security Force (UNSF) yang adalah aparat keamanan UNTEA. Namun, komando mereka tetap di tangan Panglima Mandala. Maka, ABRI di Papua memiliki misi formal sebagai alat kelengkapan UNTEA dan di sisi yang lain, atau misi informal, ada-lah kelanjutan dari Komando Trikora. ABRI bisa saja lebih mengawasi UNTEA agar tidak merugikan Indonesia, dan agar bisa menekan kekuatan sosial politik orang Papua yang anti-Indonesia (Rahab, 2010: 42-43).
10 Informasi yang cukup penting untuk membangkitkan gambaran pemerintah di Irian Barat masa itu tentang Panca Tunggal saya kutip dari Pigay sebagai berikut, “Pantja Tunggal dibentuk berdasarkan keputusan Presiden 1964/71 guna memperingati ketahanan dan kesiap-siagaan revolusi Indonesia, mewujudkan swadaya dan swasembada dalam rangka pengerahan segala dana dan daya masyarakat serta guna memberantas segala pikiran dan pelaksa-naan yang masih bersifat rutin konvensional yang ada pada masyarakat seperti pemberantasan kelompok-kelompok yang menginginkan kemerdekaan Papua Barat. Selanjutnya berdasarkan Instruksi Wakil Perdana Menteri I No.6/B/instr/tahun 1965 tentang pedoman pokok pelaksanaan musjawarah Pantja Tunggal Irian Barat. Berdasarkan per-aturan tersebut, Pantja Tunggal bagi Propinsi Irian Barat terdiri dari: Gubernur Irian Barat, Panglima Komando Dae-rah Militer XVII/Tjenderawasih, Panglima Komando Daerah Maritim VII, Panglima Regional Udara IV, Panglima Komando Daerah Angkatan Kepolisian XXI, Kepala Kedjaksaan Tinggi di Sukarnopura, Ketua Pengadilan Tinggi Sukarnopura, Ketua Front Nasional Daerah Propinsi Irian Barat, dan Rektor Universitas Cenderawasih. Kemudian Pantja Tunggal berlaku juga bagi setiap kabupaten yang ada di Irian Barat” (Pigay, 2001: 259-260).
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 63 4/24/2014 9:49:07 AM
64 Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara VOL II, 2014
tivitas penyuluhan dan pengembangan masyarakat ketika mekanisme sipil tidak berjalan. Militer juga dikerahkan untuk task forces seperti membuka jalan-jalan raya (Pigay, 2001: 262).
Sejak Irian Barat masih disengketakan serta dibawa ke serangkaian perundingan, Kodam XVII/Cenderawasih sudah disiap-kan dua hari sebelum perjanjian New York ditandatangani. Kodam XVII dibentuk ber-dasarkan Surat Keputusan Menpangad No. KPTS-1058/8/1962 tanggal 8 Agustus 1962. Kodam ini baru dapat diwujudkan setelah Irian Barat diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Cukup banyak diketahui bahwa militer juga hadir dalam berbagai ope-rasi militer seperti Operasi Sadar, Operasi Bratajudha, Operasi Wibawa, dan Operasi Pamungkas.11 Tidaklah salah untuk memi-liki kesan bahwa wajah Indonesia tampak militeristik di hadapan orang-orang Papua kala itu. Tentara hadir di mana-mana, dan untuk tugas apa saja.
Kehadiran Indonesia di Papua mendapat reaksi keras dari sekelompok orang. Pem-berontakan bersenjata pertama kali pecah pada 26 Juli 1965 di Kebar, Manokwari. Johannes Djambuani memimpin 400-an orang dari suku Karun dan Ayamaru. Ke-mudian, pada 28 Juli 1965 perlawanan se-rupa muncul yang dipimpin oleh Permanas Ferry Awom dengan 400-an pengikutnya dari suku Biak, Ayamaru, Serui, dan Num-for. Mereka menyerang asrama Yonif 641/Tjenderawasih I. Tiga prajurit ABRI tewas. Perlawanan juga digalang oleh Lodewijk Mandatjan dari suku Arfak, Manokwari. Ia mengajak pengikutnya untuk lari masuk ke dalam hutan (Rahab, 2010: 47).
Setelah penyerangan itu, ABRI melan-carkan operasi militer untuk menumpas gerakan-gerakan perlawanan OPM. Me-reka bergerak untuk menghabisi basis-ba-sis perlawanan masyarakat di sekitar Ma-nokwari sejak 10 Agustus 1965. Targetnya adalah menangkap hidup ataupun mati para pemimpin pergerakan. Terbukti per-lawanan orang Papua terhadap tentara ber-umur panjang. Konflik-konflik bersenjata antara orang Papua, yang oleh Pemerintah Indonesia dikategorikan sebagai kelompok separatis, dengan tentara Indonesia meng-akibatkan sejarah Papua mengalir dengan darah dan menelan korban nyawa.
Masih ada kewajiban yang harus di-tuntaskan menurut Perjanjian New York, yaitu menyelenggarakan Referendum atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) se-belum tahun 1969 berakhir. Perjanjian itu menjamin orang Papua untuk secara bebas memilih nasib mereka: bergabung ke Indo-nesia atau berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Tentang penyelenggaraan Refe-rendum ini, Pigay menulis bahwa Indone-sia mengajukan protes ke PBB agar tidak perlu menyelenggarakan referendum. Se-lain menyampaikan langsung, Pemerintah Indonesia menggunakan putera Irian yang pro-Indonesia untuk membuat pernyata-an-pernyataan yang mendukung integrasi ke Indonesia (Pigay, 2001: 276).12
Perubahan situasi politik pasca-penye-rahan pemerintahan dari UNTEA kepada Pemerintah Indonesia menguntungkan Indonesia dalam rangka memenangkan referendum yang digelar pada Juli hingga Agustus 1969. Dengan segala cara, Peme-
11 Tentang operasi militer di Papua secara sekilas dapat dilihat di Rahab, 2010: 39-67.12 Pada bagian ini, Pigay memberikan keterangan yang lebih detil. Pernyataan itu dimulai di Manokwari pada tahun
1962 dan terus berlangsung ke tempat-tempat lain sampai tahun 1968, sebelum Pepera dilaksanakan. Jumlahnya bervariasi. Pada 1962 ada 21 pernyataan, pada 1963 ada 25 pernyataan, pada 1964 ada 7 pernyataan, pada 1965 ada 4 pernyataan, dan pada 1968 ada 35 pernyataan.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 64 4/24/2014 9:49:07 AM
Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara JOHANES SUPRIYONO 65
rintah Indonesia membuat agar referen-dum menghasilkan Irian Barat berinteg-rasi ke Indonesia. Penolakan masyarakat di Paniai terhadap Pepera diatasi dengan operasi bersenjata. Sementara itu, para pe-mimpin lokal yang berpotensi menyusah-kan dibungkam lebih dulu.
Sejarah relasi antara Papua dengan In-donesia sejak masa integrasi hingga seka-rang masih berkisar pada tegangan antara mempertahankan Papua sebagai wilayah NKRI dengan melepaskan Papua untuk merdeka sebagai negara sendiri. Di masa lalu, upaya Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan Papua bercorak mili-teristik.
Sementara, meskipun ada gerakan-ge-rakan bersenjata, perlawanan sipil di antara orang Papua terus berkembang. Arnold Ap, Kepala Museum Antropologi Universitas Cenderawasih, membungkus gerakan yang membangkitkan nasionalisme orang Pa-pua pada 1970-an hingga awal 1980-an de-ngan merayakan kultur lokal melalui grup musik Mambesak. Kemudian, Dr. Thomas Wanggai, seorang doktor administrasi ne-gara, pada tahun 1988 mengibarkan bende-ra Bintang Kejora di Jayapura. Ia kemudian ditangkap, dan dipenjara selama 20 tahun dengan tuduhan makar. Ia meninggal di penjara pada tahun 1996. Pada tahun 1998, Filep Karma, seorang pegawai negeri sipil di Biak, memimpin pengibaran bendera Bintang Kejora di menara air di kota Biak. Setelah berkibar selama beberapa hari, dan
orang-orang digiring untuk berkumpul di bawah menara air itu, terjadilah insiden pada awal Juli 1998 yang dikenang seba-gai Biak Berdarah. Kemudian, pada tahun 2000 masyarakat Papua juga menggelar Musyawarah Besar (Mubes) Rakyat Papua di Jayapura yang diikuti penangkapan dan pemenjaraan pemimpinnya, antara lain Forkorus Yaboisembut, dengan tuduhan makar.
Di luar negeri, para tokoh Papua terus menggalang dukungan internasional. Isu Hak Azasi Manusia (HAM) menjadi ba-sis pergerakan nir-kekerasan mereka. Di bawah kekuasaan Indonesia, Papua me-ngalami serangkaian pelanggaran HAM berat.13 Mereka mendapat tambahan ke-kuat an dari para intelektual, termasuk dari berbagai negara di Asia, Eropa, dan Ameri-ka yang simpatik dengan Papua.14
Sementara itu aspirasi merdeka di Pa-pua yang sifatnya diam-diam (clandestine) sampai saat ini masih belum cukup terdo-kumentasikan dengan baik. Meski begitu, dalam berbagai kesempatan, mereka meng-artikulasikan aspirasi ini dalam percakap-an sehari-hari. Saya cenderung berpenda-pat bahwa hingga saat ini relasi Indonesia de ngan Papua masih terus diwarnai dina-mika antara mempertahankan Papua, yang diwakili slogan “NKRI harga mati”, de-ngan aspirasi memerdekakan Papua.
Setelah Orde Baru jatuh pada tahun 1998, sejarah relasi Indonesia-Papua ditan-dai dengan upaya-upaya serius dari para
13 Asian Human Rights Commission yang berbasis di Hongkong bersama dengan Human Rights and Peace for Papua mener-bitkan laporan dwibahasa Indonesia-Inggris berjudul The Neglected Genocide (Genosida yang Diabaikan): Human rights abuses against Papuan in Central Highlands 1977-1978. Sementara laporan tahunan tentang HAM di Papua sejak pertengahan dekade 1990-an secara rutin diterbitkan oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskup an Jayapura dengan serial Memoria Passionis.
14 Pada pokok ini, menurut hemat saya, agak terlalu tendensius dan kurang beralasan untuk menautkan begitu saja kiprah para intelektual dengan kepentingan modal. Saya memilih untuk tidak menjangkau pembahasan ke arah ini. Saya pikir keprihatinan dan kepedulian mereka yang menonjol terlihat dan konsisten soal Papua adalah menyang-kut HAM. Klaim ini saya buat antara lain didasarkan pada kritik-kritik mereka terhadap Freeport yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Papua.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 65 4/24/2014 9:49:07 AM
66 Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara VOL II, 2014
intelektual, baik di Jakarta maupun di Papua, yang menggagas dialog Jakarta-Papua sebagai upaya damai menyelesai-kan masalah Papua. Muridan S. Widjojo dari LIPI dan Neles Tebay, seorang imam Katolik dari Keuskupan Jayapura, melalui Jaringan Damai Papua (JDP), terus menye-barluaskan gagasan dialog Papua-Jakarta kepada banyak pihak: kepada para elit di Papua dan Jakarta, kepada orang-orang asli Papua, dan kepada para pemangku ke-pentingan yang lain di Jakarta serta Papua. Sumbangan yang cukup serius diberikan oleh tim kajian LIPI---Muridan ada di da-lamnya--- berupa buku Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future (2009) yang meme-takan jalan keluar untuk permasalahan yang membelit Papua. Meskipun prakarsa dialog ini mendapatkan banyak dukungan, termasuk dari orang asli Papua, baik dari Papua maupun Papua Barat, yang berkum-pul di Hotel Sahid, Entrop, Papua pada Juli 2013 bersama Majelis Rakyat Papua (MRP),15 sampai tulisan ini selesai, masih belum ditanggapi secara tuntas dan me-muaskan oleh pemerintahan SBY.
Jatuhnya rezim otoriter Orde Baru membuka katup perlawanan orang Papua. Inilah masa yang disebut sebagai “Papuan Spring” atau musim semi Papua meng ingat gerakan-gerakan sipil dan politik yang lama berderap di bawah tanah, kini tampil di permukaan dan semakin menguat guna menyerukan aspirasi untuk merdeka (van den Broek dan Szalay 2001; Chauvel 2002;
Chauvel 2005:10). Sebagai jalan tengah antara kehendak Papua untuk merdeka dengan Pemerintah Indonesia yang tidak ingin Papua lepas, Pemerintah Indonesia pada masa Megawati memberikan oto-nomi khusus (UU No.21/2001) kepada Provinsi Papua. Melalui undang-undang ini, Pemerintah Provinsi Papua memiliki kewenangan yang cukup luas untuk meng-atur sendiri Papua.
Tidak seperti diharapkan oleh Peme-rintah Indonesia, kebijakan otonomi khu-sus rupanya tidak menjadi obat yang cu-kup ampuh untuk meredam keinginan orang Papua untuk merdeka dan lepas dari NKRI. Apalagi, kebijakan otonomi khusus tidak berhasil mengubah kehidup-an mereka secara signifikan. Laporan eks-pedisi jurnalistik Kompas pada Agustus 2007 tentang pendidikan, yang menurut UU Otonomi Khusus mendapatkan porsi anggaran cukup besar di samping keseha-tan dan infrastruktur, melukiskan dengan sangat gamblang keadaan yang parah itu. Oleh karena itu, orang-orang Papua mem-butuhkan bukti nyata kehadiran otonomi khusus.16 Lama sebelumnya, rakyat Papua sudah merasakan bahwa Otonomi Khusus tidak berdampak pada mereka. Pada tahun 2005, Dewan Adat Papua bersama massa rakyat Papua dalam jumlah ribuan ber-demonstrasi menggotong keranda mayat berkerudung hitam. Pada keranda itu, mereka menuliskan Otsus. Secara simbolik, mereka menilai bahwa otonomi khusus sudah mati atau tidak bermanfaat untuk
15 Majelis Rakyat Papua (MRP) pada 24-27 Juli 2013 menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan orang asli Papua yang mewakili seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat—mereka berasal dari tujuh wilayah adat di Pulau Papua—di Hotel Sahid Papua, Entrop, Jayapura. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus, per-wakilan orang asli Papua menilai Otonomi Khusus telah gagal. Sebagai tindak lanjut menyelesaikan masalah Papua-Jakarta mereka merekomendasikan dua hal. Pertama, mengadakan dengan segera dialog Papua-Jakarta di tempat yang netral dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral juga. Kedua, perubahan atas Undang-Undang Otonomi Khusus 2001 hanya akan dilakukan setelah didahului oleh dialog Jakarta dan Papua
16 “Papua Butuh Bukti Nyata Otonomi Khusus” dimuat di harian KOMPAS, 18 November 2009. Laporan jurnalistik yang senada adalah tulisan Pattisina, Edna C. dan Ichwan Susanto, “Otonomi Khusus Belum Berasa” yang dimuat di harian KOMPAS, 24 Februari 2010.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 66 4/24/2014 9:49:07 AM
Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara JOHANES SUPRIYONO 67
orang-orang Papua.17 Ungkapan-ungkapan serupa yang menilai otonomi khusus tidak banyak artinya untuk orang-orang Papua, tapi memiliki arti bagi elite lokal Papua, ja-mak terdengar dalam Rapat Dengar Penda-pat Majelis Rakyat Papua di Jayapura.18 Se-telah Otonomi Khusus berjalan lebih dari satu dekade, ketegangan yang menandai sejarah Papua di dalam NKRI masih terus ada, termasuk upaya-upaya kreatif dari badan-badan non-negara atau individu-individu berpengaruh untuk menata ulang hubungan itu, dan memulai sejarah Papua yang baru.
2. Pembangunan: Menumpas Nasionalis-me Papua dan Mengonstruksi Identitas
Setelah memenangkan referendum tahun 1969 yang disahkan dalam sidang di Maje-lis Umum PBB, Indonesia bisa mengklaim secara legal bahwa Papua merupakan bagian sah dari NKRI. Akan tetapi, sejak beberapa tahun sebelumnya dan sampai sekarang ini, organisasi-organisasi lokal, regional, maupun internasional masih terus mempertanyakan posisi Indonesia. Kam-panye luas yang mendesak penyelidik an dan pengakuan bahwa terjadi pelanggar-an HAM berat di Papua masih terus ber-langsung, dan cenderung semakin meluas. Iklim demokratisasi yang berkembang di Indonesia lebih memungkinkan gerakan sipil se perti itu menyebar. Orang-orang Papua lebih berani mengartikulasikan pe-
ngalaman kekerasan oleh negara.19 Un-dang-undang Otonomi Khusus menetap-kan juga pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang hingga seka-rang belum ditindaklanjuti oleh pemerin-tah.
Sejarah pembangunan Papua oleh Pe-merintah Indonesia sulit untuk dilepaskan dari upaya-upaya meredam perlawan-an orang Papua atau untuk memangkas potensi-potensi perlawanan. Dengan kata lain, Indonesia memiliki kepentingan yang cukup besar untuk mempertahankan ke-utuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa orang-orang Irian Barat tidak sepenuh-nya menyambut kehadirannya. Kekuatan-kekuatan politik yang berjuang untuk Pa-pua merdeka dari masa sebelum integrasi tidak lenyap. Perlawanan lokal bersenjata tradisional telah terjadi sebelum integrasi.20 Di samping itu, kenyataan yang sulit untuk disangkal adalah berkembangnya nasion-alisme Papua yang semarak menjelang in-tegrasi.
Nasionalisme Papua yang telah ber-semi sebelumnya disikapi sebagai sebuah kenyataan yang memerlukan pembanding. Agenda Indonesianisasi atau usaha-usaha untuk mengakulturasi nasionalisme Indo-nesia di Papua termasuk dalam prioritas pembangunan. Gietzelt melihat proses In-donesianisasi itu adalah upaya sistematis untuk mengindoktrinasi orang-orang Pa-pua menjadi Indonesia. Proses itu ditem-
17 Muridan S. Widjojo berpendapat bahwa kegagalan kebijakan otonomi khusus sudah dimulai sejak perencanaan karena tidak melibatkan seluruh pihak baik yang pro- maupun yang anti-Jakarta di Papua. Ia mengatakan, “Pihak-pihak yang berkonflik, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta faksi lain yang pro-kemerdekaan maupun pihak Jakarta yang pro-NKRI, tidak pernah duduk bicara dan menyusun jalan keluar. Ini yang membuat pelaksan-aan otsus tidak terasa karena tidak ada legitimasi dari pihak yang berkonflik” (lih. KOMPAS, 18 November 2009).
18 Lihat catatan kaki no. 17 di atas.19 Sebagai contoh Decki Zonggonau dan Ruben Edowai atas inisiatif sendiri membuat laporan historis dengan judul
Kronologis Sejarah Pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai (Pegunungan Tengah) Propinsi Irian Jaya pada tahun 1999. Tra-gedi kekerasan di Paniai kurang disorot dibandingkan yang terjadi di perbatasan dengan PNG (Papua New Guinea) atau yang terjadi di wilayah pesisir Papua.
20 Contoh perlawanan lokal di antara orang Mee di Paniai dapat dilihat di Pigay, 2001.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 67 4/24/2014 9:49:07 AM
68 Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara VOL II, 2014
puh dengan penanaman pandangan-dunia (Pancasila), pembangunan, dan transmi-grasi (Gietzelt, 1989). Boleh jadi Gietzelt bisa memberikan gambaran yang umum bahwa proses Indonesianisasi melibatkan pula proses dominasi terhadap orang asli Papua. Catatan yang penting terhadap pe-nelitian Gietzelt adalah bahwa ia terbatas melihat proses Indonesianisasi seolah-olah bergerak hanya dari satu sisi, yaitu Indone-sia. Gietzelt luput menggambarkan adanya proses sebaliknya, yaitu orang-orang Pa-pua, tentu dalam jumlah yang lebih sedikit, yang terbuka terhadap proses asimilasi yang antara lain tampak dalam perkawin-an campuran.21
Bila membuka kembali dokumen pem-bangunan Repelita I (1969) yang dikeluar-kan pemerintah, kita akan mendapati jejak bahwa membangun nasionalisme Indone-sia di antara orang Papua adalah salah satu agenda yang penting. Supriyono (2012) menulis tentang pembangunan di Papua sebagai berikut,
“Legitimasi yang lain untuk pemba-ngunan di Papua adalah nasionalisme. Bukan lagi rahasia bahwa pemikiran ten-tang pembangunan juga mencakup agen-da pem bentukan nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua (Gietzelt, 1989; Rutherford, 2001). Rumusan dalam doku-men pembangunan berbunyi, “mening-katkan kesadaran masyarakat menuju per-satuan dan kesatuan Nasional.” Repelita I memprioritaskan juga semua usaha untuk membangun kesadaran orang Papua se-bagai bagian dari Indonesia. Dalam kata
lain, ada kesadaran di antara orang Papua bukan sebagai bagian dari Indonesia, me-lainkan sebagai bangsa yang berdiri sen-diri.” (Supriyono, 2012: 74)
Nasionalisme Papua, yang telah ber-kembang sejak masa pendudukan Jepang (Chauvel, 2005), dipandang sebagai kondisi potensial yang membahayakan kehadiran Indonesia. Lebih lagi, di dataran tinggi pe-gunungan tengah, orang-orang suku Mee telah memiliki pengalaman historis ber-perang melawan tentara Indonesia dalam rangka menolak penyelenggaraan Pepera pada tahun 1969. Bahkan, sejak sebelum Pepera hingga tahun-tahun ini, semangat perlawanan yang dulu dikomandani oleh Thadius Yogi berhasil diwariskan kepada anak-anak dan pengikutnya yang berbasis di hutan-hutan di dataran tinggi Pegunung-an Tengah. Kendati belum banyak ditelisik, wilayah pegunungan tengah sekitar Paniai pernah menjadi wilayah operasi militer seperti kawasan lain di provinsi ini.22 Per-lawanan-perlawanan yang mengekspresi-kan nasionalisme Papua juga telah menjadi sejarah panjang di antara orang Biak dan Numfor di sebelah utara Pulau Papua.
Persoalan nasionalisme Papua adalah isu yang serius bagi Pemerintah Indonesia, bukan hanya ketika awal-awal integrasi tetapi hingga sekarang ini. Dari percakap-an-percakapan saya dengan beragam infor-man di Papua—antara lain yang mengala-mi masa-masa persis setelah Pepera tahun 1969, dan yang mengalami masa-masa sesudahnya— muncul kesan bahwa na-sionalisme Indonesia ibarat suatu barang asing yang dicangkokkan secara koersif.23
21 Dalam penelitian lapangan saya di Nabire pada 2011, dua puluh tahun lebih setelah tulisan Gietzelt terbit, saya bertemu dengan orang-orang Papua yang tertarik untuk belajar keterampilan praktis dari orang-orang transmigran. Saya juga menyaksikan orang-orang Mee yang belajar pertanian pada orang-orang Jawa.
22 Percakapan penulis dengan Ruben Edowai di Nabire, pada 14 Maret 2012. Lihat juga catatan Decki Zonggonau dan Ruben Edowai seperti saya sebut di catatan kaki no. 19
23 Tentang sejarah bagaimana nasionalisme Indonesia ditumbuhkan di antara orang Papua bisa dilihat disertasi Ber-narda Meteray (2012) yang kemudian diterbitkan menjadi Nasionalisme Ganda Orang Papua. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 68 4/24/2014 9:49:08 AM
Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara JOHANES SUPRIYONO 69
Secara metaforis, Pak Edowai mengatakan “Kami ini dipaksa menikah dengan pemu-da yang tidak kami cintai.”24 Dengan kata lain, proyek besar Pemerintah Indonesia di Papua adalah menghancurkan nasional-isme Papua, dan menggantikannya dengan nasionalisme Indonesia.
Agenda lain yang cukup penting bagi rezim Orde Baru bersangkutan langsung dengan paradigma pembangunan. Arah pembangunan masa itu adalah proses mengejar pertumbuhan ekonomi. Pulau Papua yang sangat kaya dengan sumber daya alam memenuhi kriteria untuk menja-di pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di wilayah timur Indonesia. Pemerintah segera mengidentifikasi kota-kota seperti Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Ti-mika dan beberapa kota lain sebagai pusat kegiatan ekonomi eksploitatif. Sejak tahun 1967, sebelum Pepera dilakukan, rezim Orde Baru sudah memberikan izin kepa-da PT. Freeport untuk berinvestasi di bi-dang pertambangan di Timika. Pemerintah mendirikan perusahaan pengalengan ikan di Sorong. Kemudian, pemerintah juga membuka perusahaan kayu di Holtekamp, Jayapura. Untuk mencapai tujuan pembu-kaan pusat-pusat perekonomian yang baru itu, pemerintah membangun infrastruktur perhubungan laut, darat, dan udara. Prasa-rana perhubungan ini berguna sekaligus untuk efektivitas pemerintahan, menyam-bungkan Papua dengan pusat demi men-stabilkan situasi politik di Papua.
Pada tahapan perencanaan pemban-gunan selanjutnya, sekitar dekade 1980-an yang bertujuan mencapai swasembada beras, pemerintah mencetak ribuan hektar sawah di pesisir-pesisir Papua. Program ini dibarengi dengan mendatangkan para imi-gran dari Jawa. Orang-orang dari seberang
itulah yang kemudian dipercaya untuk menggarap sawah, dan diberi peran oleh negara untuk terlibat dalam pembangunan negara, yakni swasembada pangan.
Orang-orang Papua tidak memiliki pe -ngalaman menggarap sawah. Seperti orang-orang Dayak di Kalimantan, mereka adalah peladang berpindah. Padi adalah jenis tanaman pangan yang relatif baru mereka kenal. Artinya, kecakapan praktik bertani orang Papua tidak cocok dengan kebutuh-an pembangunan. Untuk merespon model pembangunan seperti itu, saya menulis:
“Pemerintah mendekati Papua dalam kerang-ka pikir yang cenderung Jawa-sentris sejak permulaan yang diperlihatkan dengan penja-jakan penanaman padi di Merauke, di daerah Kumba, serta di Dosasi Jayapura. Dosasi di-anggap lebih berprospek dan untuk menanga-ni proyek itu pemerintah mendatangkan trans-migran dari Jawa.” (Supriyono, 2012: 77)
Pembangunan di tangan pemerintah pusat berfungsi sebagai kategori demo-grafis yang mendudukkan orang Papua sebagai masyarakat yang tidak sesuai de-ngan kebutuhan pembangunan, dan orang dari luar Papua (migran) sebagai kelompok yang sebaliknya. Orang-orang Papua tidak memiliki kemampuan untuk mengambil peran dalam pembangunan. Mereka tidak mampu mengolah sawah dan menghasil-kan beras. Dihadapkan kepada para pen-datang dari Jawa, orang-orang Papua ini terlihat sebagai ‘masyarakat terbelakang’ yang masih membutuhkan pembangunan. Tidak jarang dalam ungkapan kesehar-ian, orang Papua disebut sebagai primitif. Orang-orang Papua terlihat lebih inferior dibandingkan dengan kelompok yang lain. Orang-orang Papua menjadi warga kelas dua.
24 Percakapan penulis dengan pak Edowai yang terjadi di Nabire pada 14 Maret 2012.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 69 4/24/2014 9:49:08 AM
70 Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara VOL II, 2014
Pandangan pendatang yang merendah-kan orang Papua kadangkala masih ter-ungkap. Perasaan sebagai kelompok yang superior juga hidup di antara para pen-datang. Pada suatu hari Minggu di bulan Oktober 2007, bertempat di Kapel di Wang-garsari, saya bertemu dengan seorang imi-gran di kampung yang mayoritas pen-duduknya imigran. Ketika dibuka, satuan pemukiman ini didesain sebagai wilayah campuran antara imigran dari Jawa dengan orang-orang Papua. Bapak itu mengatakan bahwa ia, dan para imigran lain, dikirim ke Papua untuk memajukan orang Irian. Meskipun percakapan berlangsung pada tahun 2007, ia masih menggunakan nama “Irian”.25 Kehadiran para pendatang, yang jumlah populasi di wilayah urban sudah mengungguli orang asli Papua, secara ob-jektif sudah mendominasi sektor ekonomi dan terus membuat orang asli Papua mera-sa terancam.26
Pembangunan dialami oleh orang Pa-pua sebagai suatu sejarah yang paradoksal. Proses pembangunan berhasil mengon-struksi episteme yang mengeksklusi orang Papua atau menjebak mereka pada kerang-ka pengetahuan bahwa orang Pa pua ada-lah warga kelas dua yang tidak punya cu-kup kemampuan dibandingkan ke lompok etnis yang lain. Selanjutnya, konsep ‘orang tidak mampu’ bermanfaat untuk merong-rong, melemahkan, atau membuat orang meragukan bahwa orang Papua bisa merdeka dan cakap mengurusi negaranya. Pihak-pihak luar yang sekadar menyaksi-kan lewat selembar foto atau secuil berita
tentang orang Papua ‘yang terbelakang’ diarahkan tanpa sadar untuk melegitima-si pembangunan yang dilakukan negara. Mereka dibujuk untuk menyetujui gagasan bahwa orang Papua adalah masyarakat ter-belakang yang perlu dibangun.
3. Jejak Kolonialistik Pembangunan
Pada bagian sebelumnya, tulisan ini menyajikan analisis bahwa nasionalisme Indonesia menjadi agenda penting untuk menggantikan nasionalisme Papua yang telah bertumbuh-kembang sejak sebelum integrasi dan menjadi semakin subur ber-kat integrasi. Kemudian, saya terkenang pada percakapan di tengah malam 14 Maret 2012 dengan Pak Edowai di teras rumahnya. “Dari mana Indonesia menda-patkan wewenang untuk mengindonesia-kan orang Papua?” Lalu pertanyaan itu ia jawab sendiri, “Indonesia memberi kuasa pada dirinya sendiri.”27
Percakapan sampai dini hari itu berisi gugatan terhadap kehadiran Indonesia di Papua. Berkali-kali Pak Edowai mengata-kan tidak pernah orang Papua meminta In-donesia melepaskan Papua dari penjajahan Belanda. Malah, ia sendiri menganggap Be-landa tidak menjajah Papua. Dengan nada geram dan suara gemetar, sebaliknya ia mengatakan, “Indonesialah yang menjajah Papua!”
“Pernahkah Papua mengundang In-donesia untuk datang dan membangun di sini? Tidak pernah.” Pertanyaan yang juga bisa disodorkan: “Apa yang membuat pe-
25 Presiden Abdurahman Wahid mengembalikan nama Papua pada 1 Januari 2000. Bagi orang Papua, pengembalian nama ini bermakna pengakuan terhadap identitas mereka sebagai orang Papua, nama mereka sendiri. Sedangkan, nama Irian adalah nama yang diberikan oleh orang lain (baca: pemerintah) terhadap mereka. Freddy, informan pe-nelitian saya, mengatakan bulu-bulu di tangannya berdiri ketika disebut sebagai orang Irian. Ungkapan ‘bulu yang berdiri’ menandakan ketidaksukaan yang sampai pada tingkat tersinggung dan marah karena merasa tidak diakui.
26 Pandangan seperti ini terungkap dengan sangat jelas dalam Rapat Dengar Pendapat Majelis Rakyat Papua di Jay-apura 24-27 Juli 2013. Di antara mereka, banyak yang mendesak diberlakukannya pembatasan migrasi masuk dari luar Papua.
27 Percakapan dengan Bapak Edowai di Nabire, 14 Maret 2012
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 70 4/24/2014 9:49:08 AM
Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara JOHANES SUPRIYONO 71
merintah merasa punya kuasa untuk me-nempatkan keluarga-keluarga suku Mee tinggal diapit dua rumah penduduk imi-gran dari Jawa yang bahasanya tidak mere-ka mengerti?” Satu pihak merasa lebih ber-hak atau berkuasa atas pihak yang lain. Dia merumuskan bahwa Anda membutuhkan ini, dan ini tetapi bukan itu.28 Sangat jelas, orang-orang Papua tidak pernah mengun-dang dan meminta pertolongan kepada bangsa asing untuk mengubah keadaan hidup mereka.
Dalam sejarah Papua, yang pada masa Belanda disebut West New Guinea, praktik-praktik pemerintah yang dimaksudkan untuk kepentingan memasukkan popu-lasi pulau itu ke dalam administrasi demi kepentingan pembangunan telah jamak. Sangat jelas bahwa Belanda memiliki ke-pentingan kolonialistik di Papua. Kendati Belanda mendirikan pos-pos di wilayah pesisir Papua pada tahun 1898, jangkauan administrasi mereka bisa dikatakan ham-pir tidak menyentuh penduduk pulau itu. Pekerjaan administrasi dipraktikkan pula oleh para misionaris Protestan di pesisir utara dan Katolik di pesisir selatan untuk penanganan penyakit epidemik serta pem-bukaan sekolah yang disubsidi oleh Gereja (Wolf dan Jaarsma, 1992: 110).29
Untuk keperluan pemerintahan itu pula, Pemerintah Belanda membuka Kan-toor voor Bevolkingszaken (Kantor Urusan
Penduduk Setempat) yang bertugas untuk mengumpulkan segala informasi, bukan hanya tentang sumber daya alam, tapi juga tentang orang Papua (Wolf dan Jaarsma, 1992). Salah satu tugas dari para staf kantor ini adalah memimpin, menginisiasi, dan mengevaluasi riset sosial ekonomi. Masih menurut penelitian Wolf dan Jaarsma, baik riset dari kantor pemerintah maupun dari para misionaris memiliki tujuan luas yang sama, yakni pasifikasi dan akulturasi.30 Pa-tokan pemerintah untuk tujuan umum ini sederhana saja, yakni terjaganya tatanan, dan pencegahan terhadap kerusuhan so-sial, dan implementasi yang tepat untuk tujuan pembangunan ekonomi, sosial dan politik (Wolf dan Jaarsma, 1992). Pemerin-tah Belanda merekrut tenaga-tenaga dari kawasan Indonesia bagian timur untuk mencapai beberapa tujuan tersebut (Chau-vel, 2005).
Tiga golongan penduduk yang meng-huni Papua pada masa pendudukan Belan-da adalah orang asli Papua, orang-orang dari kawasan Indonesia timur (Manado, Ambon, Kei, dan lain-lain) yang sudah ter-didik, dan para orang Belanda (misionaris, zending, dan pegawai pemerintah). Orang-orang dari Eropa berada di posisi yang paling tinggi, orang dari Indonesia timur berada di kelas menengah, dan orang asli Papua berada di dasar piramida. Dalam dinamika sehari-hari, orang-orang Papua
28 Literatur yang mendalami pertanyaan ini adalah Li, Tania. (2007). The Will to Improve: Governmentality, Development, and The Practice of Politics. Durham dan London: Duke University Press.
29 Wolf, J.J. de dan Jaarsma, S. R. (1992). “Colonial Ethnography: West New Guinea (1950-1962). Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, Deel 148, 1ste Afl., hlm 110. Di Kokonao, Distrik Mimika Barat, peninggalan aksi-aksi pembangunan dari para misionaris yang mulai bekerja pada tahun 1927 masih bertahan hingga sekarang. Di sana, para misionaris Katolik membuka kampung di pesisir dan berhasil membangun sekolah berasrama, gereja, rumah sakit, dan kursus untuk para perempuan. Pada tahun 1949, Pemerintah Belanda memindahkan penduduk dari Kiyura Gunung ke sebuah kampung yang dinamai sama tapi di di wilayah pesisir. Untuk menjalankan karya-karya itu, para misionaris mendatangkan para guru dari wilayah Kei.
30 Pemaknaan yang berbeda di antara pemerintah dan gereja tentang pasifikasi dan akulturasi diterangkan sebagai berikut. Bagi misionaris, makna keduanya tidak terlepas dari tugas yang mereka emban: Kristenisasi dan pelayanan pendidikan. Pasifikasi berarti menyingkirkan hambatan untuk membangun hidup Kristiani yang sejati. Sekolah-sekolah yang dikelola oleh para misionaris tampak lebih ekstensif dalam hal akulturasi. Kebanyakan sekolah ini disubsidi oleh pemerintah dan memiliki kurikulum seperti yang disyaratkan oleh pemerintah.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 71 4/24/2014 9:49:08 AM
72 Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara VOL II, 2014
kadang diperlakukan kasar atau menjadi objek kekerasan para pegawai Belanda yang menilai diri mereka lebih tinggi.31 Un-gkapan-ungkapan bernada merendahkan, dalam kesaksian para pamong praja, men-jadi peristiwa yang berulang-ulang mereka temukan.
Di antar orang-orang Mee, di mana saya mengadakan penelitian, gambaran orang yang berhasil adalah menjadi ogai, yaitu menjadi seperti orang kulit putih dari Eropa. Orang-orang tua, ketika mengirim-kan anaknya bersekolah, mengharapkan anaknya menjadi ogai. Saya masih belum mendapatkan keterangan bagaimana pros-es menjadi orang ogai atau menjadi orang kulit putih Eropa. Di Epouto, orang-orang tua mengatakan bahwa di masa mereka, anak-anak SD sudah fasih berbicara dalam bahasa Belanda, suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada masa seka-rang. Sebagian orang tua menilai bahwa pendidikan masa Belanda berhasil meng-antarkan mereka menjadi ogai.32
Saya tidak mendapatkan keterangan yang memadai mengapa orang-orang Mee melihat orang Eropa sebagai model dan mereka ingin menyerupainya. Saya men-duga kuat pengalaman yang baik orang
Papua terhadap Pemerintah Belanda pas-ca-perang pasifik, yaitu ketika Belanda mendidik calon elite lokal Papua yang dipersiapkan untuk menjalankan peme-rintahan sendiri, berkontribusi pada proses formasi tipologi manusia ideal.33 Di bawah kepemimpinan van Eechoud, orang-orang Papua merasakan dinamika ditarik dari golongan perifer ke kaum yang berada di sentral dan mulai mengimajinasikan diri sebagai aktor-aktor sentral di Papua.34
Langkah ini pun terbaca sangat jelas sebagai upaya mempertahankan kepentin-gan kolonialistik Belanda atas Papua. Sete-lah Indonesia merdeka, Papua diharapkan menjadi “tropical Holland” di mana orang-orang Belanda yang terusir dari Indonesia akan tinggal dan tidak perlu kembali ke Eropa. Secara geopolitik, jika masih punya tempat berpijak di Papua, maka Belanda masih berpeluang untuk kembali ke Indo-nesia. Harapan Belanda dipupus oleh re-ferendum yang diduga ditekan oleh pihak Indonesia demi integrasi.
Setelah orang-orang Belanda pergi, ke-pentingan Pemerintah Indonesia adalah mengidentifikasi, memastikan, dan mema-tikan anasir-anasir yang bukan Indonesia. Anasir yang non-Indonesia digolongkan
31 Pengalaman-pengalaman itu sebagian masih terekan dan ditulis oleh Leontine Visser dan Amapon Jos Marey. (2008). Bakti Pamong Praja Papua di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Buku ini me-muat kisah-kisah para orang Papua yang mengenyam pendidikan dan disiapkan oleh Belanda untuk menduduki posisi dan jabatan di pemerintahan. Mereka menempuh pendidikan yang sekarang layaknya IPDN.
32 Percakapan dengan Ausilius You di Jakarta, pada Agustus 2012. Orangtua Ausilius adalah generasi pertama dari wilayah Epouto yang mendapatkan pendidikan masa Belanda. Keterangan juga diberikan oleh Yakobus Dumupa, anak seorang guru agama di wilayah yang sekarang Kab. Dogiyai dalam percakapan di Jakarta, pada November 2011.
33 Untuk menjawab sanggahan yang sering diajukan pembaca awam terkait dengan hipotesis ini: “Mengapa Belanda tidak melakukan hal serupa terhadap Indonesia?”, saya dapat menjawab demikian. Konteks politiknya berbeda. Be-landa berharap mereka bisa mempertahankan kekuasaan di Papua dan memenangkan hati orang Papua. Geopolitik setelah perang dunia II berubah. Belanda terancam kehilangan Papua.
34 Lihat Visser dan Marey (2008) dan juga Meteray, Bernarda. (2012). Nasionalisme Ganda Orang Papua. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Disertasi Meteray yang kemudian diterbitkan menjadi buku ini meneliti soal penyemaian nasional-isme orang Papua, antara lain tercapai melalui pendidikan dan pengaderan mereka untuk menempati jabatan-jaba-tan publik dan untuk menjadi pemimpin lokal. Ketika New Guinea Raad dibentuk, orang-orang Papua dari generasi inilah yang berada di dalamnya. Tokoh-tokoh perlawanan Papua seperti Nic Jouwe, dkk., juga berasal dari model pendidikan Belanda ini.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 72 4/24/2014 9:49:08 AM
Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara JOHANES SUPRIYONO 73
sebagai separatis dan mengandung unsur kriminal. Hal ini adalah langkah sepihak dan berada dalam kewenangan penuh Pemerintah Indonesia. Akan tetapi, sebe-narnya tidak pernah sepenuhnya jelas apa yang digolongkan sebagai anti- atau non-Indonesia itu. Jejak kolonialistik yang tebal dan mencolok amat tampak di sini.
Pertemuan saya dengan Tebay, seorang muda belia yang kala itu baru akan me-nyelesaikan jenjang SLTA, di pertengahan tahun 2012, membuka cakrawala saya ba-gaimana kategori itu tidak cukup jelas, bahkan untuk pejabat atau aparat Peme-rintah Indonesia sendiri. Setiap menjelang hari Kemerdekaan RI, warga di kampung-nya dipanggil berkumpul dan diwajibkan mengikuti upacara bendera pada tanggal 17 Agustus. Masing-masing keluarga juga harus mengibarkan bendera merah putih di rumahnya. Pada hari H, aparat militer sudah bersiap dan sebagian lagi berpa-troli untuk menyuruh semua warga meng-ikuti upacara. Orang-orang berkumpul di lapang an dengan rasa kurang gembira. Jika boleh jujur dan tetap dijamin keamanan-nya, kata Tebay, maka orang-orang di kam-pung itu tidak mau mengikuti upacara.
Ketika ia masih SMP, ia dan teman-te-mannya menghindari paksaan dengan da-lih sakit malaria atau yang lain. Juga ada yang berpura-pura pingsan ketika upacara baru dimulai lima menit. Ada juga yang berpura-pura hormat bendera, tetapi se-sungguhnya orang itu sedang menggaruk-garuk kepala atau memilin rambut.
Yang agak membingungkan saya ada-lah ketika pelajaran muatan lokal tidak
boleh digunakan untuk mengajarkan seni budaya masyarakat setempat. Sejatinya, tidak ada dasar hukum yang diacu. Peja-bat setempat berdalih bahwa bahasa lokal Papua lebih dari 250 bahasa. Jika hanya memelajari satu saja, maka kelompok pengguna bahasa yang lain akan cemburu. Ketika bertemu empat mata, orang yang sama mengatakan bahwa membuka muat-an lokal untuk memelajari seni dan budaya lokal malah akan membuat orang Papua merasa semakin Papua, tidak menjadi se-makin Indonesia. Ia mengacu pada kiprah grup musik Mambesak yang dimotori oleh Arnold Ap, seorang antropolog Universi-tas Cenderawasih.35
Menempatkan kepapuaan sebagai an-cam an bagi proses pembangunan—terma-suk dalam bidang pendidikan yang akan ikut membentuk karakter orang-orang Papua di masa depan—sama saja dengan kurang memberi ruang bagi berkembang-an nilai-nilai lokal. Boleh jadi yang di-tulis dalam dokumen Repelita I dengan “Meningkatkan kesadaran masyarakat menuju persatuan dan kesatuan Nasional” sama maksudnya dengan menekan semua anasir kepapuaan, dan membuka ruang seluas-luasnya untuk mereka yang bukan etnis Papua. Logika pembangunan masa itu bertendensi untuk melemahkan atau bah-kan melenyapkan anasir-anasir Papua, dan menggantinya dengan anasir Indonesia.
Jejak kolonialistik yang pernah ditoreh-kan dalam proses pembangunan: orang-orang Papua dilarang untuk mencapai apa yang mereka ingin capai, tetapi sebaliknya ditekan untuk meraih yang ditetapkan oleh orang lain (baca: pemerintah).
35 Grup musik Mambesak menghimpun lagu-lagu tradisional suku-suku di Papua, dan menyanyikannya dalam aneka pentas. Selain itu, kelompok seni ini juga menampilkan tarian-tarian lokal Papua. Secara berkala, grup ini meng-adakan pertunjukkan di halaman Museum Antropologi Unversitas Cenderawasih, dan mendapatkan perhatian yang besar dari orang-orang Papua. Diakui bahwa prakarsa Arnold Ap dkk., ini berhasil membangun harga diri orang Papua, dan turut merawat nasionalisme Papua sehingga dinilai membahayakan. Arnold Ap dibunuh oleh Kopasanda di sebuah pantai di Jayapura pada tahun 1984.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 73 4/24/2014 9:49:08 AM
74 Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara VOL II, 2014
4. Pembangunan atau Kolonisasi: Dis-kursus “Bangsa Terjajah”
“Keinginan untuk merdeka adalah suatu yang bersifat intrinsik di dalam diri setiap orang Pa pua. Sebagai akibat sejarah penjajah yang berbeda dengan bagian lain di Indonesia. Sekarang dan ke depan hanya ada dua pilihan bagi pemerintah dan bangsa Indonesia dalam menying kapi keinginan merdeka orang Papua, yaitu membangun Papua dengan sungguh-sungguh sehingga orang Papua merasa merde-ka di dalam NKRI atau mengulangi kembali kesalahan di zaman Orde Baru yang sarat pe-langgaran HAM untuk selanjutnya menodai amanat pembukaan UUD 1945 yang melarang bangsa ini untuk melakukan pelanggar an HAM secara terus-menerus terhadap seke-lompok manusia dan bangsa Indonesia yang disebut orang Papua sehingga pada saatnya mendatangkan bencana dan malapetaka bagi bangsa ini.”“Bila kita tidak mampu melaksanakan amanat UUD 1945 itu dengan sungguh-sungguh dan dengan baik di dalam menying kapi keingin-an merdeka orang Papua maka jalan terbaik adalah membangun suatu percakapan yang etis antara orang Papua dengan bangsa dan negara ini untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan seadil-adilnya dan sedemokratisnya bagi orang Papua untuk me-nentukan sendiri posisi terbaik mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik untuk hidup sejahtera dan dalam suasana damai de-nagn bangsa yang ada di dunia ini.” (Wospak-rik dalam Raweyai, 2002: vi-vii)
Representasi diri orang Papua sebagai bangsa terjajah dan sedang menjelang ke-binasaan sudah cukup jamak serta dilaku-kan tanpa sembunyi-sembunyi. Begitu juga dengan tuntutan mereka untuk berdiri
merdeka sebagai bangsa yang berdaulat.36 Ketika Habibie menjadi presiden, Tim 100 yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat Papua menghadap ke B.J. Habibie untuk menyampaikan aspirasi orang-orang Pa-pua. Mereka ingin merdeka dan berdiri sebagai negara sendiri yang berdaulat atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Re-publik Indonesia. Menanggapi permintaan itu, Habibie menyuruh tim ini pulang un-tuk merenungkan kembali permintaan mereka.
Di luar negeri, orang-orang Papua yang mengasingkan diri setelah integrasi Papua, secara konsisten memperjuangkan ke-merdekaan Papua. Mereka tersebar di Aus-tralia, Inggris, Swedia, Amerika Serikat, Belanda, dan negara-negara Pasifik. Me-reka terus membina kontak dengan orang-orang di Papua untuk terus update dan menyampaikan temuan-temuan mereka di ba nyak negeri. Di sana, mereka berkolab-orasi dengan beberapa cendekiawan asing yang simpatik dengan persoalan Papua un-tuk menggalang dukungan bagi perjuang-an mereka. Pusaran diskursus mereka be-rada di ranah hak asasi manusia (HAM) yang telah menjadi bahasa lintas bangsa. Dengan mengandalkan temuan-temuan pelanggaran HAM di lapangan, seperti penembakan oleh aparat militer dan ke-polisian, mereka menampilkan betapa ne-stapanya orang Papua di bawah kekuasaan Indonesia.37
Di Papua sendiri, pasca-Orde Baru, dan dalam semangat reformasi, ketika iklim demokrasi sedang berkembang di Indo-
36 Sejumlah publikasi tentang itu misalnya Sendius Wonda, Tenggelamnya Rumpun Ras Melanesia (2008), Yorrys Raw-eyai, Mengapa Papua Ingin Merdeka (2002). Buku yang pertama mengangkat pula wacana genosida yang sedang ber-langsung secara sistematis dan tersembunyi di Papua. Selain telah menjadi pembicaraan yang sehari-hari di antara orang-orang kritis Papua, di antaranya para mahasiswa, tokoh-tokoh adat, dan juga Gereja, genosida di Papua men-jadi pokok laporan Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinics Yale Law School dengan judul Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control (2004).
37 Pada September 2013, Asian Human Rights Commission yang berbasis di Hongkong bersama dengan Human Rights and Peace for Papua menerbitkan laporan dwibahasa Indonesia-Inggris berjudul The Neglected Genocide: Human rights abuses against Papuan in Central Highlands 1977-1978.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 74 4/24/2014 9:49:08 AM
Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara JOHANES SUPRIYONO 75
nesia, wacana Papua merdeka dilakukan secara terbuka. Tumbangnya rezim Orde Baru yang berlanjut dengan dilangsung-kannya referendum Timor Leste, mem-bangkitkan harapan di kalangan orang-orang Papua untuk menyusul keluar dari Indonesia. Periode ini dikenal sebagai Pap-uan Spring atau musim semi Papua yang di dalamnya nasionalisme Papua menyeruak serta dieks presikan secara semarak setelah periode panjang represi oleh rezim Orde Baru.
Sementara itu, di awal periode refor-masi, kita menyaksikan orang-orang Pa pua mengibarkan bendera Bintang Kejora di Biak, Nabire, Wamena, dan sejumlah tem-pat lain diiringi lagu Hai Tanahku Papua—suatu tindakan yang cukup mendatangkan hukuman berat di bawah rezim Orde Ba-ru—secara amat santai dan terbuka, bah-kan sudah menjadi tindakan sehari-hari, untuk mengartikulasi keterjajahan mereka. Percakapan tentang orang Papua yang ter-jajah, yang dirampok kekayaan alamnya, dan diinjak-injak hak asasinya dengan gampang terdengar di sudut-sudut pasar, di lapangan sepak bola, atau di ruang-ruang terbuka, terutama setiap tanggal 1 Desember.
Kalangan nasionalis Indonesia tidak setuju untuk menyebut Papua sebagai kaum terjajah. Seperti ditulis sebagai seja-rah resmi negara, Indonesia justru membe-baskan Papua dari penjajahan Belanda dan dikembalikan ke pangkuan ibu pertiwi. Wacana itu terus direproduksi, termasuk yang bisa kita saksikan pada plakat-plakat di pos-pos militer di Papua, misalnya “NKRI harga mati”: sebuah wacana yang mencipta imaji teritorial Indonesia dari Sa-bang sampai Merauke sebagai keutuhan yang harus dipertahankan. Persoalan seja-rah integrasi Papua ke Indonesia sudah fi-nal dan tidak untuk ditilik kembali. Upaya-upaya demokratis sejumlah kelompok sipil
di Papua untuk meninjau kembali sejarah integrasi justru menabrak tembok dingin yang nyaris mustahil untuk ditembus.
Individu-individu dan kelompok-ke-lompok sipil maupun bersenjata yang kri-tis dan vokal menggugat praktik-praktik kekuasaan negara justru diringkus serta dikategorikan secara generik sebagai gerak-an separatis-makar-ancaman bagi keutuhan NKRI. Nasib yang sama menjumpai figur-figur kritis yang mengobarkan semangat anti-Indonesia meski de ngan strategi re-sistensi yang sangat kultural. Ketika iklim demokrasi kita belum seperti yang seka-rang ini, orang-orang atau kelompok-ke-lompok semacam itu seketika ditangkap lantas ditetapkan sebagai tahanan politik selama bertahun-tahun. Bahkan, ada juga yang tanpa proses semacam itu tapi lang-sung dibunuh. Untuk menyebut satu nama dari sekian yang ada adalah Arnold Ap yang dibunuh pada tahun 1984.
Sementara langkah-langkah meredam perlawanan orang Papua tetap berjalan, pemerintah merepresentasikan kehadiran dalam program-program pembangunan yang telah dimulai tidak lama setelah per-alihan administrasi dari UNTEA pada Mei 1963. Orang-orang Papua yang saya temui selama penelitian di lapangan menilai pembangunan berdasarkan pengalaman mereka secara berbeda-beda.
Wospakrik, seperti saya kutip di atas, melihat harapan bahwa pembangunan yang sungguh-sungguh bisa menyelesai-kan persoalan Papua. “Pembangunan yang sungguh-sungguh” bisa menjelmakan NKRI yang adil, yang menghormati Hak Asasi Manusia, melepaskan orang Papua dari perasaan terintimidasi, memberikan pendidikan berkualitas serta bisa diakses, memberikan layanan kesehatan yang baik, dan menghadirkan pemerintahan beserta aparat negara yang melayani (Widjojo, ed., 2009). Harapan semacam itu cukup masuk
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 75 4/24/2014 9:49:08 AM
76 Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara VOL II, 2014
akal mengingat praktik pembangunan di Papua masih dibelenggu wacana-wacana kolonialistik yang bukan saja menjauh-kan orang-orang Papua dari pengalaman pembangunan yang adil dan menghargai HAM, tetapi juga tampak dibutuhkan oleh pemerintah pusat demi melegitimasi prak-tik-praktik kekerasan dan untuk melemah-kan perjuangan politik orang Papua.
Permintaan orang-orang Papua untuk merdeka ekuivalen dengan perasaan atau anggapan bahwa mereka belum merdeka. Di Papua, tuntutan untuk merdeka serta berdaulat sebagai bangsa sendiri sudah menjadi pemandangan yang jamak dan menjadi kesadaran kolektif yang diartiku-lasikan ke dalam berbagai ekspresi, mulai dari graffiti di jembatan, pamflet, hingga nyanyian-nyanyian malam sebelum tidur.
Penutup
Dalam sejarah pembangunan di Papua, orang Papua tidak menempati bagian yang cukup penting. Posisinya lebih dominan sebagai ‘yang didefinisikan’ atau ‘yang dibangun’ tetapi tidak cukup memiliki ruang untuk terlibat membangun dirinya sendiri. Pada akhir pendudukan Belanda, gagasan untuk melahirkan elite lokal Pa-pua sepertinya sudah akan mengarahkan sejarah orang Papua ke titik cerah. Akan tetapi, Pemerintahan Indonesia yang se-jatinya kekurangan legitimasi dari orang Papua justru membelokkan sejarah ke arah yang lain. Di bawah Indonesia, orang-orang Papua mengalami praktik pembangunan yang meminggirkan dan mendiskriminasi mereka. Rancangan pembangunan yang berfokus pada tumbuhnya pusat-pusat
ekonomi baru di Papua yang konsekuen-sinya menimbulkan gelombang imigrasi dari luar Papua dalam kurun waktu yang panjang, telah berdampak pada rasio pen-duduk asli dan pendatang yang saling ber-imbang, serta pada kekalahan penduduk asli dalam persaingan di bidang-bidang ekonomi, utamanya di perkotaan.
Pembangunan juga telah berperan se-bagai alat kategorisasi tenaga kerja. Orang-orang Papua dipandang bukan sebagai tenaga kerja yang cocok untuk, misalnya, mencapai target swasembada beras. Seba-liknya, orang-orang dari Jawa lebih cocok. Dalam hal ketenagakerjaan, orang-orang Papua dieksklusikan.38
Bagi orang Papua, pembangunan dida-pati sebagai sebuah paradoks. Alih-alih mendudukkan mereka di pusat proses, me-reka justru berada di pinggir arena. Tidak jarang mereka malah menjadi korban yang tidak bisa menuntut. Pada awal dekade 1980-an, ketika pemerintah menggencarkan transmigrasi, antara lain ke Papua; ribuan hektar hutan diubah menjadi permukiman dan persawahan. Kepemilikan orang Papua atas area itu disangkal. Hutan diklaim mi-lik negara. Mereka tidak bisa protes. Mung-kin mereka takut dengan tentara. Apalagi, Papua ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Protes-protes mereka, jika sampai membesar, maka akan dicap seba-gai gerakan anti-pembangunan. Padahal, pemerintah sedang mengejar pembukaan pusat-pusat perekonomian baru.
Yang terjadi di Papua atau lebih persis bagi orang Papua, adalah kegagalan pem-bangunan (Widjojo, ed., 2009). Indikator yang dengan gampang disepakati adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
38 Gobay, seorang informan penelitian saya di Nabire, menilai proyek-proyek fisik selama proses pembangunan men-jadi ruang yang cukup kentara betapa orang asli Papua minoritas. Tidak banyak yang memiliki keterampilan di situ. Di perusahaan tambang, kehadiran orang asli Papua pun terhitung minoritas. Sepertinya orang-orang Papua ditakdirkan untuk menjadi penonton. Begitu katanya pada percakapan di Nabire, November 2011.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 76 4/24/2014 9:49:08 AM
Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara JOHANES SUPRIYONO 77
tetap tergolong terbawah di Indonesia. Su-dah semestinya arah pembangunan di Pap-ua tidak lagi dibebani dengan membasmi nasionalisme Papua atau dikendalikan oleh ketakutan akan bertumbuh-kembangnya nasionalisme Papua. Konsekuensi nya su-dah jelas. Orang-orang Papua tidak mera-sakan manfaat pembangunan. Kegagalan pembangunan hanya menyuburkan keti-dakpercayaan orang-orang Papua terha-dap pemerintah Indonesia yang selama ini sudah mereka ekspresikan dengan bera-gam penolakan, dan sikap apatis ter hadap program-program pemerintah.
Apabila sejarah panjang Papua didomi-nasi oleh wajah kekerasan militeristik demi mempertahankan Negara Kesatuan Repub-lik Indonesia, maka pemerintah kini bo-leh berpikir untuk mengubah haluan dan menjawab harapan orang-orang Papua. Se-perti disarankan oleh Wospakrik, satu jalan yang masih bisa ditempuh saat ini adalah melakukan pembangunan yang sungguh-sungguh, yang adil, dan menghargai Hak Asasi Manusia, memberikan pendidikan yang baik dan layanan kesehatan yang gampang diakses. Belenggu ketakutan se-harusnya sudah dipatahkan.
Praktik-praktik kekerasan yang mem-bawa pesan di baliknya penegasan akan kewibawaan negara hampir tidak ada gu-nanya. Tindakan-tindakan semacam itu, di samping terus menjaga kesan kolonialistik, tidak membuka kesempatan bagi berkem-bangnya iklim pembangunan yang men-junjung Hak Asasi Manusia. Secara umum, jika pemerintah hendak meninggalkan para digma pembangunan kolonialistik, maka saya mendesak pemerintah untuk melampaui pola yang sudah ajek diprak-tikkan bertahun-tahun ini dan menempuh suatu jalan baru. Widjojo cs., sudah mem-berikan bantuan pemetaan yang amat cu-kup de ngan Papua Roadmap mereka untuk menuju Papua tanah damai.
DAFTAR PUSTAKA
Asian Human Rights Commission dan Human Rights and Peace for Papua. (2013). The Neglected Genocide - Human rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977 - 1978. Kwun Tong dan Wupper-tal: Asian Human Rights Commission dan Human Rights and Peace for Papua (Inter-national Coalition for Papua).
Brundige, Elizabeth cs. (2004). Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Ap-plication of the Law of Genocide to the His-tory of Indonesian Control diakses dari http://www.law.yale.edu/documents/pdf/intellectual_life/west_papua_final_report.pdf pada 12 September 2011.
Chauvel, Richard. (2005). Constructing Pap-uan Nationalism: Historicity, Ethnicity, and Adaptation. New York: East West Center.
Drooglever, P. J. (2010). TINDAKAN PILI-HAN BEBAS!: Orang Papua dan Penentu-an Nasib Sendiri. Yogyakarta: Kanisius.
Gietzelt, Dale. (1989). “The Indonesianiza-tion of West Papua” dalam Oceania 56 (3): 201-221.
Li, Tania. (2007). The Will to Improve: Gov-ernmentality, Development, and the Prac-tice of Politics. Durham dan London: Duke University Press
Meteray, Bernarda. (2012). Nasionalisme Ganda Orang Papua. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Osborne, Robin. (2001). Kibaran Sampari, Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat, (terj.). Jakarta: Elsam.
Otten, Mariel. (1986). “Transmigrasi: Myths and Realities - Indonesian Resettle-ment Policy, 1965 -1985,” IWGIA Docu-ment No. 57. Copenhagen: International Work Group for International Affairs.
Pattisina, Edna C. dan Ichwan Susanto. (2010). “Otonomi Khusus Belum Bera-sa,” KOMPAS, 24 Februari 2010.
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 77 4/24/2014 9:49:08 AM
78 Diskursus Kolonialistik dalam Pembangunan di Papua: Orang Papua dalam Pandangan Negara VOL II, 2014
Pigay, Decki Natalis. (2001). Evolusi nasion-alisme dan sejarah konflik politik di Papua: sebelum, saat, dan sesudah integrasi. Ja-karta: Sinar Harapan.
Rahab, Amiruddin Al. (2010). Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme. Depok: Komunitas Bambu.
Supriyono, Johanes. (2012). Menarik Batas: Reproduksi Modernitas dan Resistensi Orang Mee terhadap Pendatang dan Nega-ra. Tesis. Universitas Indonesia.
Upton, Stuart. (2009). The Impact of Migra-tion on the People of Papua, Indonesia. A historical demographic analysis. Univer-sity of New South Wales.
Visser, Leontine dan Amapon Jos Marey. (2008). Bakti Pamong Praja Papua di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Widjojo, Muridan S. (ed). (2009). Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future. Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa, Yayasan Obor Indo-nesia.
Wolf, J.J. de dan S.R. Jaarsma, S. R. (1992). “Colonial Ethnography: West New Guinea (1950-1962). Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / Journal of the Hu-manities and Social Sciences of Southeast Asia, Deel 148, 1ste Afl., hlm. 103-124. Diterbitkan oleh KITLV, Royal Nether-lands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies.
Wospakrik, Frans A. (2002). “Kearifan Men-cari Solusi Persoalan Papua” dalam Yor-
rys Th. Raweyai. Mengapa Papua Ingin Merdeka. Jayapura: Presidium Dewan Papua, hlm. vi-vii
Zonggonau, Decki dan Drs. Ruben Edowai atas inisiatif sendiri membuat laporan historis dengan judul Kronologis Sejarah Pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai (Pegunungan Tengah) Propinsi Irian Jaya pada tahun 1999.
N. N. (2009). “Papua Butuh Bukti Nyata Otonomi Khusus,” KOMPAS, 18 No-vember 2009.
Sumber data dari laman Bappenas:http://www.bappenas.go.id/node/42/1702/
repelita-ii-tahun-197475---197879/ (di-akses pada 7 September 2012.)
http://www.bappenas.go.id/node/42/1701/repelita-i-tahun-196970---197374/ (di-akses pada 6 September 2012)
http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/7166/ (diakses pada 6 September 2012)
http://www.bappenas.go.id/node/42/1703/repelita-iii-tahun-197980---198384/ (di-akses pada 7 September 2012)
http://www.bappenas.go.id/node/42/1703/repelita-iii-tahun-197980---198384/ (di-akses pada 7 September 2012)
http://www.bappenas.go.id/node/42/1704/repelita-iv-tahun-198485---198889/ (di-akses pada 7 September 2012)
http://www.bappenas.go.id/node/42/1704/repelita-iv-tahun-198485---198889/ (di-akses pada 7 September 2012)
005-[Supriyono] untuk Jurnal Humaniora UMN 1.6.indd 78 4/24/2014 9:49:09 AM
Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, hal 79-97ISSN 2302-5719
Vol II, Nomor 1
Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama:Memotret Deliberasi Politik Berbasis Agama di Indonesia dengan
Perspektif Filsafat Politik Jürgen Habermas
ALEXANDER AUR
Dosen Religiositas dan EtikaUniversitas Multimedia Nusantara dan KALBIS Institute
Surel: [email protected]
Diterima: 13 Februari 2014Disetujui: 4 April 2014
ABSTRACT
Enlightenment (Aufklärung) is not entirely successful confining religion to be a problem for private realm. Religion still exists in the public sphere. Today, religion is pushed into the democratic constitutional state. Jürgen Habermas argues that a dialogue between democratic state and religion is important today. Demo-cratic state has rationality when religion has a place in the deliberation process. Thus, religion gives the normative principles for the democratic state. Yet religion can not be the basis for a democratic state. There-fore, it is beneficial for democracy if religion should translate its metaphysical language into the language espoused by the secular democratic state. Religious metaphysical assumptions must be tested by the secular reason and the institutional translation proviso. By meeting the terms of the secular reason, democratic state and religion can learn from each other and do dialogue.
Keywords: negara hukum demokratis, tindakan komunikatif, rasio prosedural, agama rasional, situasi epistemik pluralitas.
Pendahuluan
Dalam sejarah politik dunia, khususnya di benua Eropa, setelah kelahiran Pencerahan (Aufklärung) yang mengusung rasio seku-lar, agama didomestifikasi menjadi urusan privat, dan dilenyapkan dari ruang publik. Meski demikian, setelah sekian lama dido-mestifikasi, Pencerahan tidak sepenuhnya berhasil mengurung agama dalam ruang privat. Alih-alih “mematikan” agama de-ngan mendomestifikasikannya, yang terjadi malah sebaliknya: agama memetamorfosis
dirinya, dan sekarang merangsek ke ruang publik dalam berbagai bentuk. Terorisme berwajah agama, partai-partai politik ber-basis agama, gerakan-gerakan kemanusia-an berbasis spiritualitas lembaga-lembaga agama, gerakan pembaharuan politik ber-nuansa agama merupakan beberapa contoh konkrit agama yang eksis di ruang publik.
Fenomena domestifikasi agama dan merangseknya agama ke dalam ruang pu-blik merupakan fenomena yang berlang-sung dalam bingkai hubungan agama dan negara. Parakitri T. Simbolon memetakan
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 79 4/24/2014 10:01:20 AM
80 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama VOL II, 2014
tiga pola hubungan agama dan negara (Pa-rakitri T. Simbolon dalam JB. Kristanto dan Nirwan Ahmad Arsuka (ed.), 2002: 430), yakni integral simetris, integral asimetris, dan sipil. Dalam pola integral simetris hu-bungan agama dengan negara tidak dipi-sahkan, keduanya bersatu. Pola ini sering disebut theocracy. Dalam pola integral asi-metris, hubungan antara agama dengan negara bisa berbentuk “agama dalam nega-ra” atau “negara dalam agama.” Pada ben-tuk “agama dalam negara”, agama tetap harus tunduk pada kekuasaan negara me-skipun agama mempunyai pengaruh yang besar. Pada bentuk “negara dalam agama”, negara tunduk pada kekuasaan agama me-skipun negara mempunyai pengaruh yang besar. Sedangkan dalam pola sipil, berda-sarkan format formal negara dan agama dipisahkan tetapi pada format praktik satu agama atau lebih yang dominan.1
Negara hukum demokratis dan aga-ma masing-masing mempunyai tujuan. Dengan bertumpu pada kedaulatan rakyat, nujuan negara hukum demokratis adalah membentuk tatanan sosial demi tercapai-nya keadilan dan kesejahteraan hidup para warga negara di dunia ini. Dengan kata lain, alasan adanya sebuah negara terletak pada usaha manusia untuk membentuk sebuah tatanan sosial, dan tatanan itu dia-tur dengan hukum-hukum yang dicipta-kan oleh manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia di dunia saja. Sedangkan tujuan agama adalah mengarahkan para pemeluknya (umat beriman) untuk mem-peroleh kesalehan hidup di dunia ini, dan
kesalehan itu sebagai antisipasi bagi ke-hidupan setelah kematian (hidup di akhi-rat). Meskipun agama mempunyai tujuan yang berbeda, tetapi bukan berarti agama berada di luar negara hukum demokratis. Agama merupakan salah satu unsur da-lam negara hukum demokratis. Itu artinya, agama turut berperan secara aktif dalam menguatkan negara hukum demokratis.
Tetapi problem yang sering kali terjadi adalah konflik antara agama dengan nega-ra hukum demokratis. Tidak jarang, kon-flik yang terjadi bersifat saling menakluk-kan satu sama lain. Hal yang terjadi pada akhirnya adalah agama takluk di hadap-an negara atau negara takluk di hadapan agama. Atau sekurang-kurangnya dari sisi negara, aparatus negara ragu-ragu dalam menyikapi secara tegas relasi konfliktual tersebut. Relasi konfliktual yang mengarah pada penaklukkan ini tidak sehat bagi demokrasi itu sendiri. Demokrasi sebagai bentuk dan cara berpolitik, yang di dalam-nya semua unsur dimungkinkan berparti-sipasi-aktif membangun hidup bersama, maka upaya-upaya penaklukkan terhadap demokrasi mesti diantisipasi dan diatasi oleh semua unsur.
Agama dengan klaim metafisiknya mempunyai kecenderungan untuk menakluk-kan demokrasi. Supaya tidak menjadi “duri dalam daging” demokrasi serta tidak melumpuhkan demokrasi dengan klaim-klaim metafisiknya, agama mesti mampu berkomunikasi dengan negara hukum de mokratis. Komunikasi dapat berlang-sung bila, bahasa agama ditranslasikan ke
1 Parakitri T. Simbolon memberikan contoh negara yang menganut tiga pola hubungan negara dan agama terse-but. Negara-negara yang menganut integral simetris antara lain Vatikan, Tibet sebelum dikuasai Tiongkok, Iran di bawah Khomeini, dan mungkin Arab Saudi. Negara-negara yang menganut pola integral asimetris antara lain mulai dari sangat lunak sampai keras seperti Inggris dan Pakistan. Negara-negara yang menganut pola sipil dengan variasinya masing-masing, antara lain Malaysia, Brunei, Filipina, dan Indonesia. Malaysia dan Brunei menetapkan adanya agama negara tetapi tetap menjamin hak-hak agama lain. Filipina dan Indonesia mengakui pluralitas agama dengan satu agama yang dominan.
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 80 4/24/2014 10:01:20 AM
Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama ALEXANDER AUR 81
dalam bahasa negara hukum demokrasi. Mengapa agama harus mentranslasikan bahasanya ke dalam bahasa negara hukum demokratis? Uraian ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Uraian didasarkan pada pemikiran Jurgen Habermas tentang agama dalam negara hukum demokratis. Pembahasan berikut berpijak pada tesis ini: agama dan negara hukum demokratis dapat saling berdialog hanya jika agama mengubah dirinya dari agama mitis men-jadi agama rasional dan negara hukum memberi ruang (kesempatan) bagi agama untuk berdeliberasi.
Tulisan ini terbagi dalam beberapa ba-gian. Pertama akan diuraikan upaya Haber-mas melampaui positifikasi rasio sekular oleh Pencerahan (Aufklärung).2 Upaya Ha-bermas ini juga mendasari optimismenya bahwa rasio sekular merupakan proyek modernitas yang belum tuntas. Kedua, akan diuraikan teori Habermas tentang tindak-an komunikatif, etika diskursus, dan de-mokrasi deliberatif. Ketiga, akan disajikan pemikiran Habermas tentang agama di dalam negara hukum demokratis. Keempat, akan disampaikan potret deliberasi politik berbasis agama di Indonesia.
Dalam pemikirannya tentang posisi agama dalam negara hukum demokratis, Habermas menempatkan pokok itu dalam bingkai teorinya tentang tindakan komuni-katif (communicative action), etika diskursus (discourse ethics), dan demokrasi deliberatif. Oleh karena itu, artikel tentang pemikiran Habermas mengenai agama ini ditempat-
kan dalam bingkai teori Habermas tentang tindakan komunikatif, etika diskursus, dan demokrasi deliberatif. Ada dua alasan pe-rihal penempatan itu: pertama, supaya kita dapat memahami pemikiran Habermas ten-tang status sosiologis-politik agama secara tepat, utuh, dan tidak keluar dari arena pe-mikirannya secara keseluruhan. Kedua, su-paya kita bisa menimba inspirasi dari Ha-bermas terutama tentang keberadaan dan peran agama atau politik berbasis agama dalam konteks perpolitikan di Indonesia.
1. Rasio Komunikatif: Upaya Habermas Melampaui Rasio Instrumenal
Sebelum memaparkan pemikiran Haber-mas tentang rasio komunikatif, terlebih da hulu digambarkan secara singkat ke-munculan ilmu pengetahuan modern. Paparan tentang hal itu didasarkan pada analisis yang dibuat Francisco Budi Hardi-man (1990, 22-26). Dalam analisisnya, Budi Hardiman mengatakan ilmu pengeta-huan yang mendasarkan posisinya pada ke sanggupan rasio manusia lahir untuk memeroleh pengetahuan. Dari tujuan itu, ilmu pengetahuan melakukan positivikasi rasio sehingga menjadi rasio instrumental. Positivikasi dilakukan oleh para filsuf dan ilmuwan yang beraliran positivisme.3
Pencerahan (Aufklärung) menjadi titik awal bagi perkembangan ilmu pengeta-huan modern. Dalam ilmu pengetahuan modern, rasio manusia menjadi acuan uta-ma untuk memeroleh pengetahuan. Dalam filsafat modern itu sendiri, terdapat dua
2 Para eksponen Ma�hab Frankf�rt generasi pertama, seperti Adorno dan Horkheimer mencemaskan bahwa Pencera-ara eksponen Ma�hab Frankf�rt generasi pertama, seperti Adorno dan Horkheimer mencemaskan bahwa Pencera-han telah menggiring rasio menjadi sangat instrumental.
3 Francisco Budi Hardiman mencatat bahwa meskipun positivisme yakin bahwa pengetahuan yang sahih adalah pengetahuan yang berdasarkan fakta objektif. Dengan menyingkirkan pengetahuan yang melampaui fakta, positi-visme mengakhiri riwayat ontologi atau metafisika, karena ontologi menelaah apa yang melampaui fakta indrawi. Meski demikian, positivisme terutama ilmuilmu positif seperti fisika, kimia, biologi, menerima warisan ontologi atau metafisika dalam dua hal. Pertama, ilmu-ilmu positif mewarisi sikap teoritis murni sebagai metodologi. Kedua, ilmu-ilmu positif masih menyimpan pengandaian dasar ontologi bahwa struktur dunia dan struktur masyarakat tidak tergantung dari subjek yang mengetahuinya.
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 81 4/24/2014 10:01:20 AM
82 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama VOL II, 2014
blok besar yakni rasionalisme dan empiri-sisme. Rasionalisme menekankan bahwa pengetahuan murni dapat diperoleh mela-lui kemampuan rasio manusia itu sendiri. Oleh karenanya, pengetahuan bersifat a priori. Sedangkan empirisisme menekan-kan bahwa pengetahuan sejati hanya da-pat diperoleh melalui pengalaman empiris. Oleh karenanya, pengetahuan bersifat a posteriori.
Dalam perkembangan selanjutnya, pe-ngetahuan empiris-analitis menjadi ilmu alam yang direfleksikan secara filosfis seba-gai pengetahuan yang benar mengenai rea-litas. Pada titik ini ilmu alam dikembang-kan sebagai teori murni dengan bantuan rasionalisme serta empirisisme. Para ilmu-wan alam pun memahami alam sebagai sebuah kosmos dengan seluruh hukumnya yang teratur, tertib, dan tetap.
Dari rahim filsafat empirisme, kemu-dian lahir positivisme yang dirintis oleh Auguste Comté. Bagi positivisme, fakta ob-jektif merupakan pengetahuan yang benar. Positivisme tidak percaya pada ontologi atau pengetahuan yang melampaui fakta. Dari positivisme inilah lahir pula sosio-logi sebagai ilmu pengetahuan sosial. Po-sitivisme dalam ilmu sosial mengandung tiga pengandaian yang saling bertautan. Pertama, prosedur metodologis ilmu alam dapat diterapkan secara langsung pada ilmu sosial. Artinya, subjektivitas seperti kepentingan serta kehendak manusia sama sekali tidak berpengaruh terhadap perilaku manusia yang menjadi objek yang diamati. Dengan demikian, perilaku manusia seba-gai objek ilmu pengetahuan setara dengan dunia alamiah. Kedua, hasil penelitian diru-muskan ke dalam ‘hukum’ sama layaknya dalam ilmu alam. Ketiga, ilmu sosial tidak-bisa-tidak bersifat teknis yang murni ins-trumental.
Positivisme logis mendapat kritik ke-ras dari Ma�hab Frankf�rt yang dikenal dengan sebutan Teori Kritis. Para ekspo-nen Teori Kritis generasi pertama antara lain T.W. Adorno dan Horkheimer. Mereka berpendapat bahwa positivisme logis me-rupakan saintisme. Pencerahan telah mem-buat manusia menghadapi alam dengan kalkulasi. Pencerahan melahirkan konsep rasionalitas yang positivistik. Rasionali-tas pencerahan adalah rasio instrumental (Zweckrastionalität). Pencerahan membuat rasio kehilangan tujuan pada dirinya sen-diri. Di tangan positivisme, rasio menja-di instrumental, tukang atau alat untuk kalkulasi, verifikasi, dan pelayan klasifi-kasi. Bagi Adorno dan Horkheimer, pen-dakuan Pencerahan akan netralitas rasio instrumental, justru menunjukkan bahwa karena netralitasnya itulah, rasio instru-mental tunduk pada berbagai tujuan dan dapat dipakai oleh siapa saja. Ciri instru-mental dalam cara berpikir manusia tam-pak dalam perhatian yang ketat terhadap prinsip-prinsip kerja rasio sehingga dapat diterapkan untuk tujuan apa saja yang di-kehendakinya. Dalam situasi yang demi-kian, rasio instrumental dapat menjadi alat untuk memanipulasi.
Bagi Ma�hab Frankf�rt, rasionalitas se-bagaimana diperjuangkan pencerahan itu tidak memeroleh kemajuan apapun, dan menampakkan kembali mitos yang sebe-lumnya disingkirkan. Rasio pencerahan justru menciptakan kembali mitos dengan berorientasi pada hal di luar dirinya yakni ekonomi dan politik. Rasio lalu tunduk ter-hadap ekonomi dan politik. Pola kerja rasio pencerahan itu sama dengan/atau merupa-kan peniruan (mimesis) pola masyarakat tradisional yang tunduk terhadap sesuatu yang metafisik di luar dirinya. Alihalih netral dan tak memikirkan tujuan pada dirinya sendiri, rasio pencerahan justru
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 82 4/24/2014 10:01:20 AM
Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama ALEXANDER AUR 83
merupakan pengulangan atas mitos lama (Hardiman, 1990: 30, 64-65).4
2. Tindakan KomunikatifSebagai generasi baru Teori Kritis, Haber-mas optimis bahwa rasionalitas merupa-kan proyek modernitas yang belum tuntas. Ia bermaksud mengatasi positivikasi rasio oleh positivisme logis dengan teorinya ten-tang rasio komunikatif (Hardiman, 1990: 86).5 Dalam teori tindakan komunikatif, Habermas membedakan antara tindakan strategis dengan tindakan komunikatif. Secara fundamental, teori tindakan ko-munikatif terletak dalam pembedaan dua konsep rasionalitas yang menuntun penge-tahuan kepada tindakan. Dua konsep rasio-nalitas yang dimaksud adalah rasionalitas instrumental dan rasionalitas komunikatif. Kedua konsep itu merupakan bagian dari tindakan. Rasionalitas instrumental adalah rasionalitas yang mengarahkan tindakan untuk mencapai berbagai tujuan yang te-lah ditetapkan secara pribadi. Rasionalitas ini akan bersifat instrumental bila diarah-kan kepada alam, misalnya dalam bentuk kerja. Rasionalitas ini juga bersifat strategis apabila diarahkan untuk memengaruhi ke-putusan-keputusan yang akan dibuat oleh pihak lain, seperti dalam bentuk hubung-an dominasi. Tindakan manusia di bawah kendali rasionalitas instrumental bersifat mengobjekkan.
Sedangkan rasionalitas komunikatif adalah rasionalitas yang mendasari tindak-an untuk saling pengertian di antara dua orang subjek atau lebih yang sedang ber-tukar pikiran untuk mencapai tafsir yang harmonis perihal dunia. Jika tindakan stra-tegis adalah pemanfaatan orang lain demi kepentingan subjek tertentu, maka sebalik-nya tindakan komunikatif didasarkan atas perbincangan argumentatif yang bebas, tanpa dominasi, yang bermuara pada ke-sepakatan bersama. Perbedaan mendasar keduanya adalah tindakan strategis bersi-fat monologis, sedangkan tindakan komu-nikatif bersifat dialogis (Habermas, 1996: 2-3).
Konstruksi konseptual Habermas me-ngenai tindakan komunikatif tersebut tidak terlepas dari konsepnya tentang rasionali-sasi dalam bidang komunikasi (interaksi). Baginya, suatu tindakan komunikatif ber-sifat rasional apabila dalam dan melalui tindakan itu, manusia mampu mengura-ngi berbagai penindasan dan mengura ngi kekerasan pada tingkat pribadi-pribadi yang menjadi partisipan dalam komunika-si, sehingga pribadi-pribadi bisa mengem-bangkan diri. Dengan kata lain, melalui tindakan komunikatif rasional, setiap pri-badi terbebaskan dari berbagai penindasan dan kekerasan. Rasionalisasi yang sesung-guhnya bagi Habermas adalah rasionalisa-si humanis, dan hal itu seharusnya ditem-
4 Teori Kritis lahir di tengah ketegangan dialektis di antara ilmu pengetahuan khususnya sosiologi dan filsafat. Teori Kritis tidak berhenti pada fakta objektif yang sebagaimana yang diagung-agungkan oleh positivisme logis. Realitas sosial bagi Teori Kritis merupakan fakta sosiologis yang di dalamnya terdapat aspek-aspek transendental yang me-lampaui data empiris. Dengan demikian, Teori Kritis dapat melakukan dua macam kritik yaitu kritik transendental dan kritik imanen. Kritik transendental berupaya menemukan syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan da-lam diri subjek. Kritik imanen merupakan upaya menemukan kondisi-kondisi sosio-historis dalam konteks tertentu yang berpengaruh terhadap pengetahuan manusia. Dalam bingkai dua kritik itu, Teori Kritis merupakan Kritik Ideologi.
5 Generasi pertama Teori Kritis memahami praksis (praxis) sebagai kerja (Arbeit). Konsep praksis merupakan sebuah kategori dalam filsafat ilmu pengetahuan, yang bermaksud menunjukkan hubungan antara teori dan praktik. Prak-tik merupakan perwujudan konkrit dari teori. Filsafat ilmu pengetahuan bermaksud menunjukkan hubungan anta-ra rasionalitas dalam teori dan rasionalitas dalam praktik. Berbeda dengan generasi pertama Teori Kritis, Habermas membedakan antara kerja dengan interaksi atau komunikasi. Kerja dan komunikasi merupakan dua dimensi dari praksis.
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 83 4/24/2014 10:01:20 AM
84 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama VOL II, 2014
puh melalui rasio komunikatif (Hardiman, 1990: 98). Humanisasi dicapai bukan mela-lui positivikasi rasio manusia seperti yang dilakukan positivisme melainkan melalui tindakan komunikatif (Deflem, 1996: 23).6
Bagi Habermas, rasio modern tetap mempunyai dimensi emansipatif serta da-pat dikembangkan lebih lanjut. Oleh kare-na itu, ia mengajukan konsep mengenai ra-sio prosedural. Rasio ini tidak terpisah dari rasio komunikatif. Melalui rasio prosedu-ral, berbagai keputusan atau kesepakatan yang merupakan buah dari proses-proses rasional mendapat kesahihannya. Dalam rasio prosedural, prosedur diakui seca-ra bersama-sama oleh semua orang yang terlibat aktif dalam proses-proses rasional (intersubjektif).7 Rasio prosedural inilah yang kelak menjadi “jiwa” dari demokrasi deliberatif.
Relasi antarmanusia menurut Haber-mas bersifat rasional karena semua orang yang terlibat dalam relasi itu bermaksud agar terjadi kesalingpahaman certa bermu-ara pada kesepakatan bersama. Artinya, setiap tindakan yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama merupakan tindakan komunikatif. Dengan demikian, tindakan komunikatif mengandung rasio komuni-katif. Kesalingpahaman dan kesepakatan sebagai tujuan dari tindakan komunikatif merupakan daya kerja dari rasio komuni-katif. Tujuan tindakan komunikatif bisa tercapai jika rasio komunikatif bekerja da-lam tindakan komunikatif.
Habermas menekankan bahwa tindak-an komunikatif yang rasional harus be-bas dari tekanan, paksaan, dan dominasi
sehingga semua orang yang terlibat aktif di dalam komunikasi menerima kesepa-katan yang dihasilkannya. Dengan de-mikian, kesepakatan itu memiliki legiti-masi kebenaran, kejujuran, dan ketepatan. Komunikasi yang demikian terjadi da-lam dunia-kehidupan (Lebenswelt). Dalam dunia-kehidupan, hal-hal yang dianggap benar diterima begitu saja tanpa diperso-alkan. Selain itu, dalam dunia-kehidupan, anggota-anggota masyarakat sama-sama membangun dan mengedepankan solida-ritas. Apakah hubungan antara dunia-ke-hidupan dan tindakan komunikatif? Bagi Habermas, mengikuti analisis Budi Har-diman, dunia-kehidupan memungkinkan terjadinya tindakan komunikatif. Dunia-kehidupan menjadi basis bersama bagi para pelaku tindakan komunikatif. Oleh karenanya, dunia-kehidupan membantu pencapaian sebuah kesepakatan (konsen-sus). Dalam perkembangan lebih lanjut, masyarakat berkembang menjadi modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang tersistematisasi. Masyarakat yang ter-sistematisasi itu tampak dalam sistem-sis-tem yang ada dalam masyarakat modern, yakni sistem pasar (uang) dan sistem keku-asaan negara. Habermas mengeksplisitkan perbedaan dunia-kehidupan dan sistem dengan istilah “solidaritas” untuk dunia-kehidupan (Lebenswelt) dan “sistem” untuk “uang” dan “kuasa”. Solidaritas, uang, dan kuasa adalah tiga komponen penyangga integritas masyarakat modern. Yang ideal bagi Habermas adalah keseimbangan anta-ra sistem dan dunia-kehidupan. Hubungan antara dunia kehidupan, pasar, dan negara
6 Habermas juga mencatat bahwa untuk menghindari salah paham (misunderstanding) dalam tindakan komunikatif, dan untuk memperoleh pemahaman bersama, maka para partisipan komunikasi tidak bisa hanya mengandalkan tindakan berbicara (speech-act) melainkan juga harus memerhatikan bentuk-bentuk tindakan lain yang tidak linguis-tik seperti tanda-tanda dan simbol-simbol.
7 Penjelasan tentang pengertian rasio prosedural sangat menarik disampaikan oleh F. Budi Hardiman dengan contoh di bidang peradilan yang dipaparkan dalam Hardiman, 2009: 32-33.
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 84 4/24/2014 10:01:20 AM
Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama ALEXANDER AUR 85
berlangsung secara seimbang (Hardiman, 2009: 38-41).
2.1. Etika diskursusDalam bingkai opitimismenya pada pro-yek modernitas yang segera dituntaskan, Habermas berusaha membangun sebuah masyarakat yang komunikatif (masyarakat kosmopolit). Masyarakat yang demikian adalah tujuan universal masyarakat. Oleh karena itu, Habermas tidak melepaskan konsepnya dari fakta pluralisme dalam masyarakat modern. Untuk memperkuat masyarakat komunikatif, Habermas meng-ajukan proposal berupa etika diskursus un-tuk menata kembali norma-norma hidup bersama (Stephen, 1995: 12).8
Etika diskursus (Regh, 1994; 161-166), menuntut dua prinsip pokok yang harus diberlakukan agar norma sungguh-sung-guh bersifat moral. Pertama, norma harus dapat diterima oleh semua orang atau ber-laku umum. Prinsip ini disebut prinsip uni-versalisasi (prinsip U). “Semua pihak yang (mungkin akan) terkena dampak kepa-tuhan hukum atas norma dapat menerima konsekuensi dan efek sampingnya, yang diharapkan dapat memenuhi kepentingan setiap orang,” demikian ketentuan prinsip U mengenai kesahihan sebuah norma. Ke-dua, kepastian akan universalisasi norma itu ditempuh melalui diskursus (prinsip D). “Norma-norma hanya dapat diklaim sebagai sahih kalau mendapat persetuju-an dari semua peserta yang kemungkinan terkena dampak dari norma itu dalam se-buah diskursus praktis,” demikian keten-
tuan prinsip D mengenai klaim kesahihan universalisasi norma.
2.2. Negara Hukum DemokratisHabermas melihat bahwa ciri dasar kehidup-an bersama manusia adalah komunikasi. Oleh karena itu, demokrasi harus menjadi medium bagi perwujudan berbagai struk-tur komunikasi dalam negara hukum mo-dern. Dengan demikian, negara hukum dapat mendekati asas-asas normatif dari dalam dirinya sendiri.9 Model demokrasi yang tepat untuk itu adalah demokrasi deliberatif. Model demokrasi ini sesuai dengan prinsip rasio prosedural dan etika diskursus yang telah dikemukakan di atas.
Fokus utama demokrasi deliberatif adalah prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Keputusan-keputusan politis atau kese-pakatan-kesepakatan politis yang dicapai harus melalui prosedur-prosedur yang ra-sional. Dalam prosedur yang rasional, para warga negara atau kelompok-kelompok kecil yang mempunyai kepentingan dalam negara dapat memperjuangkan kepenting-an-kepentingannya. Berbagai kepentingan warga negara dideliberasi berdasarkan prosedur-prosedur rasional. Melalui pro-ses deliberasi itulah, sebagian kecil warga negara yang tidak sepakat dengan suara mayoritas, bisa menerima dan mematuhi pendapat-pendapat yang disepakati oleh sebagian besar warga negara sebagai suara mayoritas. Dalam proses deliberasi, semua orang yang terlibat mempunyai kesetaraan sebagai warga negara.
8 Etika diskursus yang diajukan Habermas juga merupakan upayanya untuk mengatasi imperatif kategoris dalam Etika Kant yang lebih menekankan prosedur individual atau etika yang dilakukan secara individual. Habermas meragukan tesis Kant bahwa sebuah norma dapat berlaku secara universal apabila dipastikan oleh suara hati setiap pribadi. Tesis Kant ini sulit diterapkan dalam masyarakat yang pluralistik.
9 Tentang asas-asas normatif itu, dikemudian hari saat berdiskusi dengan Rat�inger, hal itu diungkapkan kembali ketika Habermas menggali akar-akar religius rasio sekular.
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 85 4/24/2014 10:01:21 AM
86 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama VOL II, 2014
3. Agama dalam Negara Hukum Demokratis
Di atas, kita sudah melihat alur berpikir Habermas ditinjau dari rasio komunikatif, etika diskursus, sampai demokrasi deliber-atif. Pada bagian ini, dipaparkan pemikiran Habermas tentang agama dalam negara hukum demokratis. Ia memulainya de-ngan pertanyaan: Apakah negara hukum demokratis memiliki akar-akar religius? Bagian ini penting untuk diperhatikan karena terkait dengan posisi agama da-lam negara hukum demokratis. Habermas memang mengakui bahwa negara hukum demokratis atau rasio sekuler mempunyai akar religius. Meski demikian, basis negara hukum demokratis tidak kembali bertum-pu pada agama. Mengapa?
Dalam sebuah diskusi dengan Kardi-nal Rat�inger, Habermas menggali dan menanggapi secara kritis akar-akar religius rasio sekuler.10 Dalam bingkai teks berjudul ”Prepolitical Foundations of the Constitutional State?” (Habermas, 2008: 101-113; Kleden dan Sunarko, 2010: 1-28), Habermas menge-Habermas menge-mukakan beberapa pokok pemikirannya. Pertama, negara sekuler tidak mendasar-kan diri pada berbagai pengandaian kos-mologis tertentu sebagaimana diandaikan hukum kodrat. Konsekuensinya, negara sekuler tidak memihak kelompok agama tertentu dengan seluruh sistem nilainya, dan setiap warga negara mempu nyai kese-taraan dalam memainkan perannya dalam negara hukum demokratis. Dengan meng-acu pada pertanyaan kritis yang diajukan Bökenförde tentang seberapa jauh warga masyarakat dapat menyatukan diri dalam negara dengan jaminan kebebasan indi-vidu saja tanpa ada ikatan; Habermas me-ngatakan bahwa proses demokrasilah yang menjadi ikatan yang menyatukan para
warga negara. Proses demokrasi menjadi syarat kemungkinan bagi para warga ne-gara untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
Tentunya, demokrasi yang dimaksud-kan Habermas pada poin pertama di atas adalah demokrasi deliberatif yang menga-cu pada rasio prosedural dan digerakkan oleh rasio komunikatif. Rasio komunikatif yang ada dalam diri warga negara mengge-rakkan mereka untuk menyatukan diri da-lam negara secara bebas dan tanpa tekan-an, melalui demokrasi deliberatif.
Kedua, berdasarkan perspektif kognitif dan motivasi, negara hukum demokratis bisa mencukupi dirinya secara internal. Tetapi, ada faktor eksternal yang merusak jaringan solidaritas para warga negara dan proses demokrasi, yakni pasar (Habermas, 2008: 107-108; Kleden dan Sunarko, 2010: 13-17). Rasio pasar mempunyai cara kerja yang berbeda dengan rasio negara. Pasar mempunyai metode pengelolaan yang ber-beda dengan administrasi negara. Rasio pasar menggiring warga ke dalam indivi-du-individu yang menggunakan kebeba-san individualnya secara ketat. Bersamaan dengan itu, bidang-bidang yang menjadi wewenang negara hukum demokratis untuk mengaturnya semakin berkurang. Privatisme warga negara kian menguat, se-mentara proses demokratisasi para warga negara kian melemah. Habermas menyebut fenomena itu sebagai penyimpangan mo-dernisasi. Dalam kondisi seperti ini, negara hukum demokratis mesti melegitimasi diri-nya dengan perangkat hukum yang dibuat oleh para warga negara.
Gagasan pokok dalam poin kedua tersebut dikemukakan Habermas ketika ia mengulas masalah dunia-kehidupan (Lebenswelt) serta sistem. Jika dalam urai-
10 Diskusi dengan Rat�inger itu berlangsung di Katholiche Akademie M�nchen, Jerman tanggal 19 Januari 2004.
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 86 4/24/2014 10:01:21 AM
Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama ALEXANDER AUR 87
annya tentang dunia-kehidupan dan sis-tem, Habermas mengatakan bahwa sis-tem – yak ni pasar dan negara – mengoloni dunia-kehidupan, maka dewasa ini rasio pasar justru mengoloni dunia-kehidupan serta negara secara sekaligus. Dalam situa-si kolonisasi rasio pasar – yang merupa-kan bentuk penyimpangan dari moderni-tas – Habermas mengatakan bahwa para warga negara harus mengatasinya dengan memaksimalkan rasio komunikatif melalui mekanisme rasio prosedural.11 Setiap usaha para warga negara untuk mencapai kese-pakatan dalam bidang tertentu untuk sta-bilitas kehidupan bersama, para warga ha-rus mematuhi prosedur-prosedur tertentu yang digunakan untuk mencapai kesepa-katan tertentu yang dimaksud. Prosedur-prosedur yang berlaku merupakan produk dari rasio. Prosedur-prosedur rasional yang tersedia menjadi medium bagi para warga untuk berdeliberasi. Proses deliberasi me-lalui rasio prosedural inilah yang disebut Habermas sebagai tindakan komunikatif. Hal itu berarti, rasionalitas dari sebuah kesepakatan merupakan pencapaian ber-sama dari para warga yang terlibat dalam proses deliberasi.
Ketiga, menjawab keraguan yang diaju-kan oleh Bökenförde bahwa apakah negara hukum bisa mencukupi dirinya dengan asas-asas normatif dalam dirinya, Haber-mas mengatakan bahwa dari perspektif kognitif hukum yang telah mengalami po-sitivisasi tetap membutuhkan pandangan religius dan metafisik untuk memastikan secara kognitif prinsip-prinsip etis hukum dalam negara hukum demokratis. Sedang-
kan dari perspektif motivasi, Habermas mengharapkan bahwa para warga negara menggunakan hak-haknya secara aktif da-lam proses pembuatan hukum untuk ke-pentingan komunal sekaligus kepentingan bersama (Habermas, 2008: 104-105; Kleden dan Sunarko, 2010: 7, 9).
Pada poin ini, Habermas mengakui bahwa negara hukum demokratis tetap membutuhkan agama atau ”kekuatan pe-mandu” (sustaining power) sebagai pemasti kognitif asas-asas normatif dalam negara hukum demokratis (negara sekuler). Kebe-radaan agama atau ”kekuatan pemandu” bukan berarti negara mengganti asas-asas normatif dari dirinya dengan asas-asas nor-matif dari agama atau ”kekuatan peman-du” lain. Sebaliknya, Habermas hendak mengatakan bahwa agama – dengan asas-asas normatif metafisik – sebagai bagian dari dunia-kehidupan juga mempunyai kesempatan sama untuk berpartisipasi da-lam negara hukum demokratis. Partisipasi agama merupakan bentuk kongkret dari perspektif motivasi.
Tentunya, model partisipasi tetap da-lam bingkai demokrasi deliberatif yang mengacu pada rasio prosedural. Partisi-pasi agama dalam bingkai rasio prosedural itulah sekaligus merupakan pemasti kog-nitif rasio prosedural. Dengan kata lain, jika agama tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam negara hukum demo-kratis, maka demokrasi deliberatif kurang (tidak) memiliki rasionalitas. Jika agama didomestifikasikan dan tidak punya ke-sempatan untuk berdeliberasi di ruang publik, maka rasio prosedural mengalami
11 F. Budi Hardiman menjelaskan gagasan Habermas tentang rasio prosedural dengan mengambil contoh di bidang hukum yakni peradilan. Proses pengadilan hanya mungkin dan dapat terlaksana bila ada ide tentang keadilan. Ide keadilan adalah unsur konstitutif dari pengadilan. Ide itu juga bersifat regulatif karena berlaku sebagai prosedur untuk memeriksa apakah proses pengadilan berlangsung adil atau tidak. Hal yang penting dalam rasio prosedural adalah prosedur yang diakui secara intersubjektif. Lewat prosedur itulah produk-produk dari setiap proses rasional memperoleh kesahihannya. Dari situ tampak bahwa sifat rasional merupakan hasil pencapaian bersama. Sifat ra-sional dari klaim rasio tertentu dicapai secara komunikatif, melalui pemahaman timbal-balik antar subjek.
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 87 4/24/2014 10:01:21 AM
88 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama VOL II, 2014
defisit rasionalitas. Demokrasi deliberatif memiliki kepastian rasional apabila agama dilibatkan dalam debat-debat di ruang pu-blik politis.
Keempat, Habermas memberi catatan kritis tentang masalah hermeneutika teks-teks agama seperti tentang kesalahan dan keselamatan. Hal-hal itu ditafsirkan dan dihayati secara hermeneutik selama berta-hun-tahun. Selama teks-teks agama itu ti-dak mengalami distorsi dalam penafsiran dan tidak jatuh dalam dogmatisme dan pemaksaan suara hati, maka rasio sekuler bisa belajar juga dari agama, atau masyara-kat sekuler dan masyarakat religius bisa saling belajar (Habermas, 2008: 108-113; Kleden dan Sunarko, 2010: 20-28).
3.1. Dari Agama Mitis ke Agama RasionalHabermas mengakui bahwa setiap aga-ma pada hakikatnya adalah ”pandangan hidup” atau ”comprehensive doctrine” (dok-trin yang lengkap) (Habermas, 2008: 111; Kleden dan Sunarko, 2010: 24). Dengan pendasaranpendasaran mitis dan metafi-sik, agama juga memberikan elan vital ke-pada para penganutnya (orang beriman) yang hidup di tengah-tengah masyarakat modern. Bahkan, etika substansial yang di-anut banyak orang pun berakar pada tradi-si agama-agama. Masyarakat modern yang pluralistik itu sendiri terdiri atas orang-orang beriman serta orang-orang tidak be-riman (Adam, 2006: 1). Masyarakat modern berada dalam dua area besar yakni dunia-kehidupan dan sistem yang di dalamnya ada pasar dan negara. Ada masyarakat (in-dividu atau kelompok) yang menjadi ba-gian integral dari dunia-kehidupan, pasar, dan negara secara serentak. Ada masyara-kat (individu atau kelompok) yang menjadi bagian dari negara dan pasar saja.
Masyarakat modern hidup dalam sebu-ah ruang publik (public sphere) yang sama. Ruang publik itu sendiri bersifat politis ka-
rena dihuni oleh masyarakat modern yang pluralistik dengan segala kepentingannya. Dalam kondisi masyarakat modern dan ru-ang publik yang demikian, agama meng-hadapi tantangan yang serius. Habermas dengan tegas mengatakan bahwa ruang pu-blik politis atau negara hukum demokratis tidak bisa menjadi ”religius” atau ”ditradi-sikan” berdasarkan doktrin lengkap agama apapun (Adam, 2006: 2). Tampak jelas pen-Adam, 2006: 2). Tampak jelas pen-. Tampak jelas pen-dirian Habermas bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Agama mempunyai do-main kerja yang sangat berbeda dengan ne-gara. Meski demikian, agama tidak boleh didomestifikasikan karena bertentangan dengan hakikat demokrasi.
Mengacu pada gambaran idealnya ten-tang keseimbangan antara dunia-kehidup-an, negara, dan pasar, Habermas menan-tang – agama yang olehnya dikategorikan sebagai bagian dari dunia-kehidupan – untuk menunjukkan eksistensinya dalam ruang publik politis atau negara hukum demokratis. Hal itu serius bagi agama ka-rena di satu sisi ajaran-ajaran agama ber-sifat mitis dan metafisik, di sisi lain, ruang publik bersifat rasional dan postmetafisik. Habermas secara tegas berargumen bahwa hanya sebuah forum sekulerlah yang dapat secara memadai menjadi pemandu atau penata bagi perbedaan antara ruang meta-fisik dengan ruang postmetafisik.
Forum sekuler yang dimaksud adalah negara hukum demokratis atau ruang pu-blik politis. Negara hukum demokratis menjadi forum yang di dalamnya semua partisipan berdeliberasi sekaligus berargu-mentasi sesuai dengan rasio prosedural un-tuk mencapai kesepakatan bersama yang adalah tujuan tindakan komunikatif. Dalam proses deliberasi, pengandaian-pengandai-an metafisik agama diuji secara rasional atau dengan cara berpikir postmetafisik. Artinya, agama harus mentransformasi diri dari agama mitis (religious-metaphysical) ke
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 88 4/24/2014 10:01:21 AM
Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama ALEXANDER AUR 89
agama rasional (religious-post-metaphysical) (Adam, 2006: 125-126). Melalui pengujian dalam proses deliberasi, dan dalam kori-dor etika diskursus, agama mitis bisa men-jadi agama rasional. Jika berhasil menjadi agama rasional, maka etika substansial agama-agama bisa memberi warna dalam etika universal.
Meski demikian, Habermas tetap tidak mengi�inkan agama campur-tangan se-cara langsung dalam negara. Agama bisa masuk ke dalam negara setelah melewati institutional translation proviso. Institusi ini semacam dewan yang bertugas menterje-mahkan bahasa (ajaran-ajaran) agama yang bersifat mitis-religius dan partikular ke da-lam bahasa universal yang bersifat sekuler. Melalui hal itu, pengandaian-pengandaian metafisik agama diuji oleh rasio post-meta-fisik dan bahasa agama diterjemahkan ke dalam bahasa rasio sekuler. Dalam konteks ini, warga negara yang tidak beriman bisa membantu dalam proses alih bahasa ki-tab suci. Jika mekanisme itu dicapai, maka agama bisa bermanfaat bagi demokrasi, dan negara hukum demokratis (Habermas, 2008: 131-132).
Dengan demikian, antara warga ber-agama dengan warga sekuler dalam masya-rakat post-sekuler dapat saling belajar satu sama lain. Apalagi, warga negara beriman didorong untuk mengenakan cara berpi-kir (episteme) postmetafisik di tengah plu-ralitas agama. Warga negara beriman juga harus tunduk certa mengakui rasio sekuler yang menjadi basis legitimasi untuk negara hukum demokratis (Habermas, 2008: 138-139).
4. Hubungan Negara dengan Agama di Indonesia: Melacak Deliberasi Politik Berbasis Agama
Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, hu-bungan antara negara dengan agama me-ngalami pasang-surut (Parakitri T. Sim-bolon dalam Kristanto dan Arsuka (ed.), 2002: 430).12 Hubungan yang demikian mengindikasikan bahwa deliberasi politik antara negara dengan agama pun menga-lami pasang-surut. Situasi pasang-surut deli berasi politik berbasis agama dengan negara itu bisa kita telusuri dari beberapa peristiwa historis berikut ini.
4.1 Penolakan Piagam Jakarta: Islam me-nemukan “Situasi Epistemik” Plurali-tas
Persoalan hubungan negara dan agama sungguh disadari oleh para pendiri bangsa sebagai hal yang krusial. Oleh karena itu, dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indone-sia) dibentuklah Panitia Sembilan yang di-pimpin oleh Soekarno untuk membahas hal itu. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembi-lan13 berhasil merumuskan pembukaan UUD. Oleh Muhammad Yamin, pembu-kaan UUD 1945 itu disebut Piagam Jakarta karena dalam sila pertama Pancasila ber-bunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.”
Menjelang pengesahan UUD 1945, atas prakarsa Muhammad Hatta, frasa “Dengan kewajiban menjalankan syariat Is-lam bagi pemeluknya” dari sila pertama
12 Untuk kepentingan tulisan ini, kurun waktu yang dijadikan sebagai acuan adalah setelah Indonesia menjadi se-buah merdeka sampai sekarang. Meski demikian, sejarah hubungan agama dan negara bisa ditelusuri sejak �aman kerajaan-kerajaan, �aman penjajahan Belanda dan Jepang. Sejarah mengenai hal itu dapat dibaca dalam Parakitri T. Simbolon, “Pasang-surut Hubungan Agama dan Negara di Indonesia” dalam Kristanto dan Arsuka, 2002: 429-442.
13 Panitia Sembilan terdiri dari Soekarno, Achmad Soebardjo, Abdul Kahar Mu�akkir, Alex Andries Maramis, Abi-koesno Tjokrosoejoso, Mohammad Hatta, Abdul Wahid Hasyim, Agus Salim, Muhammad Yamin.
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 89 4/24/2014 10:01:21 AM
90 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama VOL II, 2014
Pancasila dihapus. Penghapusan itu di-setujui oleh empat tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kas-man Singodimejo, dan Teuku Hasan. Hatta memprakarsa penghapusan frasa tersebut setelah utusan Angkatan Laut Jepang (Kai-gun) menemui Hatta untuk menyampai-kan keberatan dari wakil Protestan serta Katolik dari Indonesia Timur dengan frasa tersebut. Bila frasa itu tetap dipertahankan menjadi bagian dari sila pertama Pancasila, maka UUD 1945 mengandung diskrimi-nasi. Konsekuensi lebih lanjut adalah In-donesia Timur akan keluar dari Republik Indonesia (Soeprapto, 2013: 8).
Hatta berargumen bahwa UUD adalah pokok daripada pokok, sebab itu harus ter-untuk bagi seluruh bangsa Indonesia de-ngan tanpa kecuali. Jalan pikiran Hatta itu disetujui oleh keempat tokoh Islam dengan argumentasi bahwa dengan penghapusan frasa tersebut, sama sekali tidak melenyap-kan “semangat Piagam Jakarta” (Parakitri T. Simbolon dalam Kristanto dan Arsuka (ed.), 2002: 436). Dari argumen keempat tokoh Islam yang setuju dengan argumen Hatta, menunjukkan bahwa unsur diskrim-inatif tidak terletak pada makna atau isi dari frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Unsur diskriminatif terletak pada bahasa formal. Bila bahasa formal yang terwujud melalui frasa itu dimasukkan menjadi ba-hasa formal UUD, maka tampak jelas un-sur diskriminatifnya. Karena UUD meru-pakan hukum umum, maka bahasa formal dalam hukum umum harus mencerminkan keumumannya. Sedangkan bahasa formal yang tampak jelas dalam frasa tersebut
menunjukkan kekhususan. Atas dasar itu, keumuman bahasa formal yang diuta-makan dalam UUD, yang tampak dalam rumusan formal sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Dalam ruang partikular Islam, syariat Islam merupakan unsur konstitutif agama Islam. Islam dihayati sebagai sebuah agama oleh pemeluk-pemeluknya karena salah satu unsur konstitutifnya itu. Ke-wajiban menjalankan syariat merupakan sebuah imperatif etis untuk berbuat baik dalam konstelasi hidup beriman orang Is-lam. Mengenai hal itu, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa saat diturunkannya al-Qur’ân kepada Rasullulah SAW, Tuhan berpesan bahwa dalam setiap kelompok dalam Komunitas Madina, Allah telah me-netapkan sistem hukum (syir’ah, syarî’ah) dan cara hidup (minhâj) agar setiap orang dalam komunitas keagamaannya masing-masing berusaha terus-menerus berbuat baik (Madjid, 1992: 312-324).14
Ada dua hal yang muncul dari kete-rang an Nurcholish Madjid tersebut. Per-tama, cakupan hukum agama adalah par-tikular. Dari sisi formal, hukum agama – dari setiap agama – hanya berlaku dalam agama tertentu dan bagi penganut agama tertentu itu. Dalam konteks Piagam Jakar-ta, penghapusan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, menunjukkan bahwa hu-kum syariat bersifat partikular dan hanya berlaku bagi penganut Islam. Penghapusan frasa itu, menunjukkan juga bahwa parti-kularitas hukum agama, tidak bisa begitu saja diuniversalkan melalui rumusan for-mal produk hukum (undang-undang) yang
14 Nurcholish Madjid menempatkan penjelasannya tentang konsep “hukum” dalam al-Qur’ân pada konteks historis yakni Madînah. Pada �aman Rasullulah s.a.w., masyarakat Madînah bukan masyarakat homogen melainkan hetero-gen. Selain ada komunitas Islam, juga ada komunitas Yahudi, komunitas Nasrani, dan komunitas pagan. Terhadap komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasullulah SAW mengatakan bahwa Allah pun menurunkan hukum bagi komuni-tas-komunitas itu, dan setiap anggota komunitas harus menjalankan hukum yang diturunkanNya itu.
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 90 4/24/2014 10:01:21 AM
Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama ALEXANDER AUR 91
berlaku umum. Tentu, Tentu, ketidakbisaan itu sama sekali tidak membatasi dampak etis dari partikularitas hukum agama.
Kedua, dampak etis hukum agama. Bagi orang Islam, hukum (syir’ah, syarî’ah) merupakan sarana untuk berbuat baik dan menghasilkan kebaikan bagi hidup ber-sama. Hukum syariah yang bersifat parti-kular itu, dalam pengahayatan konkritnya, mendatangkan dampak etis berupa kebai-kan. Dampak etis itu bukan saja bagi hidup orang Islam tetapi juga bagi orang lain di luar Islam. Rumusan yang jelas mengenai hal itu adalah “Islam sebagai rahmatan lil âlamin. Rumusan itu menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam bersifat partiku-lar, tetapi dampak etis dari penghayatan (pelaksanaan) hukum Islam itu bersifat universal (publik). Dan dampak etis inilah yang disoroti oleh keempat tokoh Islam yang sepakat dengan argumen Hatta yang menekankan dimensi universal dari UUD 1945.
Dalam perspektif deliberasi Habermas, argumen Hatta dan keempat tokoh Islam mengenai penghapusan frasa yang bersifat partikular tersebut, menunjukkan bahwa agama Islam berhasil menemukan dan me-netapkan “situasi epistemik” di hadapan agama lain yang dianut oleh para warga negara Indonesia bagian timur. Hatta dan keempat tokoh Islam berhasil merelati-visasikan posisi hukum (syariah) Islam da-lam ruang publik (negara Indonesia) tanpa harus merelativisasikan syariat sebagai inti dogmatis Islam. Bahkan, bila dipandang dari perspektif institusional translation provi-so, Hatta dan keempat tokoh Islam berhasil mentransformasikan Islam yang mitis dan partikular menjadi Islam yang rasional dan universal. Islam yang mitis dan partikular tercermin dalam inti dogmatisnya, yakni menjalankan hukum syariah. Sedang kan
Islam yang rasional dan universal tercer-min dalam rahmatan lil âlamin.
Keberhasilan Islam menemukan dan menetapkan “situasi epistemik” tersebut tidak semata-mata bersifat politis seperti yang dinilai oleh Paraktri T. Simbolon. Ia menilai bahwa penghapusan frasa tersebut menunjukkan bahwa kesatuan dan persat-uan nasional menjadi dasar pola hubung-an antara agama dengan negara RI. Pola itu bersifat politis sekaligus negatif karena penghapusan itu menampakkan penolakan terhadap hubungan resmi antara agama Is-lam dengan kekuasaan negara. Penolakan akan bersifat positif bila dilanjutkan de-ngan menetapkan pola lain sebagai peng-gantinya (Parakitri T. Simbolon dalam Kristanto dan Arsuka (ed.), 2002: 436).
Keberhasilan Islam tersebut bersifat politis sekaligus filosofis. Dalam konteks menetapkan sebuah hukum dasar – UUD 1945 – bagi negara RI yang baru saja mem-proklamasikan kemerdekaannya, sifat poli-tis memang tak terhindarkan. Keputusan Hatta dan keempat tokoh Islam, dan selan-jutkan diafirmasi oleh para anggota sidang BPUPKI, memang merupakan keputusan dan kesepakatan politis. Keputusan dan kesepakatan itu juga mempunyai dasar filosofis yang terletak pada dimensi uni-versal (dimensi publik) yang merupakan aspek konstitutif dari UUD 1945. Dimensi universal inilah yang menjadi dasar pe-mikiran Hatta untuk memprakarsa peng-hapusan frasa tentang syariah Islam dari sila pertama Pancasila.
Keputusan dan kesepakatan itu juga bukan merupakan penolakan terhadap hubungan resmi antara agama – secara khusus Islam – dengan kekuasaan negara. Agama-agama tetap dimungkinkan untuk mempunyai hubungan yang resmi dengan kekuasaan negara, melalui pembentukan
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 91 4/24/2014 10:01:21 AM
92 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama VOL II, 2014
partai politik-partai politik, dan berbagai organisasi massa berbasis agama.15 Melalui partai politik serta organisasi massa ber-basis agama, agama-agama mempunyai kemungkinan terlibat aktif dalam kekua-saan negara. Keterlibatan aktif tidak berarti memindahkan begitu saja hukum agama menjadi hukum positif negara, melainkan harus melalui proses pengujian atas hukum agama-agama yang akan diintegrasikan ke dalam hukum positif negara. Pengujian itu berdasarkan nalar sekuler yang terepresen-tasi melalui UUD 1945.
Fakta mengenai berbagai partai politik berideologi agama serta organisasi massa berasaskan agama menunjukkan bahwa politik berbasis agama memang dimung-kinkan di Indonesia. Di atas ideologi Pancasila, setiap warga negara dari latar belakang agama apapun dimungkinkan untuk beraktivitas politik dengan seman-gat agama. Kemungkinan itu semakin luas bila kita melihat pada imperatif-imperatif agama yang berkaitan dengan urusan-urusan publik. Agama-agama mempunyai imperatif moral yang menjadi landasan etis untuk menyikapi atau merespon persoalan-persoalan publik.
Warga masyarakat di dalam negara hukum demokratis yang dapat berpar-tisipasi dalam ruang publik tidak hanya
dari satu agama, melainkan dari berbagai agama yang berbeda dan ada pula yang tidak beragama. Itulah fakta pluralitas dalam negara hukum demokratis. Itulah “situasi epistemik” masyarakat modern yang plural. Mengingat bahwa pluralitas merupa kan keniscayaan demokrasi dan modernitas, maka agama yang berpolitik dan bertindak politis harus menetapkan “situasi epistemik”, yakni harus merela-tivisasikan posisinya di hadapan plurali-tas warga dan agama-agama. Tentu saja relativisasi posisi tidak dengan sendirinya mengakibatkan relativisasi inti dogmatis-nya (Borradori, 2005: 105). Dalam merela-tivisasi posisi, agama tidak mengabaikan situasi epistemik masyarakat plural, dan tidak menuntut penerapan ortodoksinya secara ketat dalam masyarakat plural.
Dalam konteks Indonesia, meskipun ideologi Pancasila memungkinkan agama berpolitik dan bertindak politis, tetapi tidak berarti bahwa agama mengabaikan situasi epistemik masyarakat plural. Sebaliknya, agama seharusnya menetapkan “situasi epistemik” supaya sinkron dengan situasi epistemik masyarakat plural. Agama yang mengabaikan situasi epistemik masyarakat plural dan bernafsu mengatur masyarakat plural dengan inti dogmatisnya (hukum agama), maka agama itu akan menjadi
15 Pada era Orde Lama, partai politik-partai politik berideologi agama Islam antara lain, Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Masyumi Indonesia (MI), Partai Syariah Islam Indonesia (PSII), dan Perti. Sedangkan partai politik yang berideologi Katolik dan Protestan adalah Partai Katolik Indonesia dan Partai Kristen Indonesia. Pada masa Orde Baru, partai politik berbasis agama hanya 1: Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada masa reformasi, beberapa partai politik baru berbasis agama tampil sebagai peserta pemilu, antara lain PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bang-sa), Partai Keadilan Sejahtera, PBB (Partai Bulan Bintang), dan PDS (Partai Damai Sejahtera). Agama juga tampil dalam bentuk organisasi-organisasi massa, baik yang berbasis massa agama secara umum maupun berbasis massa kampus. Organisasi massa kampus, antara lain HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Persatuan Mahasiswa Muslim Indonesia), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia). Organisasi-organisasi massa agama umum antara lain, PK (Pemuda Katolik), ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), ISKA (Ikatan Sar-jana Katolik Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), HTI (Hi�buth Tahrir Indonesia) dsb.. Berbagai organisasi massa berbasis agama tersebut tampil ke publik, dan merespon masalah-masalah publik. Berbasis semangat keagamaan-nya masing-masing, setiap organisasi massa itu terdorong untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup ber-bangsa dan bernegara. Meski demikian, dorongan itu mesti tetap sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 92 4/24/2014 10:01:21 AM
Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama ALEXANDER AUR 93
horor sekaligus teror bagi demokrasi, ke-manusiaan maupun pluralitas.
4.2 Gerakan Anti Pancasila: Ketiadaan Deliberasi Politik Agama
Pada masa-masa awal kekuasaan Orde Baru, roda pemerintahan yang dikendali-kan oleh Soeharto mempersempit ruang politik bagi agama untuk berdeliberasi da-lam kancah perpolitikan Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan Orde Baru adalah memfusikan beberapa partai politik berbasis agama. Partai politik-partai politik berbasis agama Islam seperti NU, PSII, dan Perti difusikan menjadi PPP. Partai politik yang berbasis agama di luar agama Islam, seperti Partai Katolik dan Partindo difusi-kan ke dalam partai nasionalis PDI. Orde Baru menerapkan depolitisasi dan deide-ologisasi agama sebagai rekayasa politik untuk melemahkan peran politik agama.
Kelompok agama yang paling mera-sakan dampak dari penghilangan delibe-rasi politik berbasis agama adalah Islam. Selama kurang lebih 25 tahun peran poli-tik agama Islam dipangkas. Akses Islam ke lingkaran kekuasaan politik negara di-tutup. Strategi itu dipertajam dengan ke-bijakan politik berbunyi Pancasila sebagai asas tunggal dalam berpolitik dan aktivitas organisasi. Kebijakan itu tertuang dalam UU No. 3/1985 yang merupakan perubah-an atas UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta UU No. 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Melalui kebijakan itu, Orde Baru sekaligus menyatakan bahwa Islam tidak boleh menjadi asas organisasi sosial-poli-tik. Bahkan, Islam politik menjadi sasaran teropong kecurigaan ideologis Orde Baru. Aktivis Islam politik dicurigai sebagai anti terhadap Pancasila (Hasani dan Naipospos (ed.), 2012: 28-29; Magnis-Suseno dalam Kristiyanto (ed.), 2010: 304).
Kebijakan politik orde baru tersebut mendatangkan tanggapan serius dari Islam politik. Pada mulanya, hampir semua par-tai politik dan organisasi-organisasi Islam menentang kebijakan itu. Dalam perkem-bangan selanjutnya, organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah menerima kebijakan tersebut. Seiring dengan itu, gerakan radikal untuk menentang Pancasila sebagai asas tunggal pun terus berlangsung. Dua tokoh Islam yang meno-lak tegas Pancasila sebagai asas tunggal adalah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir. Organisasi yang menolak Pancasi-la sebagai asas organisasi adalah PII (Pela-jar Islam Indonesia). PII dibubarkan Orde Baru pada tahun 1988. Selain itu, banyak pula cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga dibubarkan Orde Baru. Pem-bubaran cabang-cabang HMI ini, belakang-an terkenal dengan istilah HMI (MPO).
Dalam konstelasi filsafat politik Haber-mas, gerakan menentang Pancasila sebagai asas tunggal dari beberapa tokoh dan or-ganisasi Islam lebih merupakan cerminan dari dua problem. Pertama, ketiadaan de-liberasi politik bagi agama dalam negara. Dengan mengharuskan Pancasila sebagai ideologi bagi partai politik dan ormas yang berasaskan agama, negara (pemerintah Orde Baru) telah menutup pintu masuk sekaligus tidak menyediakan akses bagi agama untuk berdeliberasi secara politik. Pemerintah Orde Baru tidak menyediakan prosedur-prosedur rasional – yang meru-pakan cermin dari negara hukum demokra-tis – bagi agama untuk memperjuangkan kepentingannya. Problem kedua ini meru-pakan akibat dari problem pertama. De-ngan tidak disediakan prosedur-prosedur rasional oleh negara, maka tidak ada pula kemungkinan bagi agama untuk melaku-kan translasi bahasa agama berdasarkan prosedur-prosedur rasional yang dianut
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 93 4/24/2014 10:01:21 AM
94 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama VOL II, 2014
oleh negara hukum demokratis. Tiadanya kemungkinan bagi agama untuk mentrans-lasikan bahasa agama itu membuat agama juga tidak dapat menyumbangkan nalar metafisiknya dalam menguatkan negara hukum demokratis.
Sebuah negara disebut negara hukum demokratis apabila negara itu (baca: peme-rintah) membuka kemungkinan bagi agama untuk melakukan translasi doktrin-doktrin metafisiknya ke dalam bahasa universal dan sekuler. Doktrindoktrin metafisik agama harus diuji melalui proses deliber-asi yang sesuai dengan prosedur-prosedur rasional dalam negara hukum demokratis. Jika berhasil melewati proses deliberasi itu, maka doktrindoktrin metafisik agama menjadi pemasti kognitif prinsip-prinsip etis negara hukum demokratis. Dengan demikian, gerakan anti Pancasila dari seke-lompok orang Islam merupakan cermin kegagalan pemerintah Orde Baru dalam menyediakan kemungkinan bagi agama untuk berdeliberasi politik dan mentrans-lasikan bahasa agama.
4.3 Radikalisme dan Terorisme Agama: Respon Ekstrim Agama terhadap Demokrasi
Pasca keruntuhan re�im pemerintahan Orde Baru, gerakan radikal agama (Islam) dan terorisme berwajah agama yang di-lakukan oleh sekelompok orang Islam se-makin marak. Front Pembela Islam (FPI) dan Jamaah Islamiyah (JI) merupakan dua contoh dari sekian banyak kelompok yang berkarakter radikal dan teroristik (Hasani dan Naipospos (ed.), 2012: 37). Sebuah gerakan disebut radikalistik dan teroristik karena berciri menggunakan kekerasan, bom, organisasinya bersifat tertutup, dan menyerang simbol-simbol negara (Hasani dan Naipospos (ed.), 2012: 42).
Pada bagian akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institute terhadap
relasi dan transformasi organisasi radikal di Jawa Tengah dan Yogyakarta, terda-pat lampiran tentang 10 (sepuluh) dosa demokrasi menurut kelompok radikal dan teroris agama (Hasani dan Naipospos (ed.), 2012: 317-320). Bagi kelompok radikal dan teroris, demokrasi memiliki beberapa ca-cat antara lain, demokrasi menyebabkan terkikisnya nilai-nilai akidah, demokrasi tidak membedakan antara orang beriman dengan orang tak beriman, dan dalam demokrasi, partai politik memanfaatkan sarana dan tindakan religius untuk kepen-tingan partai politik.
Bagi kelompok radikal dan teroris agama, sistem demokrasi harus dianulir dan diganti dengan sistem khilafah Islam. Inilah yang oleh Habermas disebut sebagai “ortodoksi yang mengarah kepada funda-mentalisme.” Ortodoksi semacam itu me-mang secara sengaja (sadar) mengabaikan situasi epistemik masyarakat plural, yang menjadi ciri khas demokrasi. Bahkan, de-ngan cara kekerasan kelompok radikal dan teroris mewajibkan penerimaan ortodoksi itu secara politis.
Berhadapan dengan fenomena itu, negara hukum demokratis ditantang un-tuk meredefinisi demokrasi dan merefor-mulasi prosedur-prosedur rasional, supaya negara hukum demokratis tidak terjebak dalam praktik-praktik yang mengatasna-makan demokrasi, tetapi sesungguhnya merupakan penyimpangan dari demokra-si. Penyimpangan demokrasi yang paling vulgar dan kentara adalah kolonisasi rasio pasar atas negara hukum demokratis dan dunia-kehidupan. Rasio pasar yang ber-watak instrumental menjadi warna domi-nan dalam praktik-praktik politik dan agama. Demokrasi transaksional tampil secara kongkret dalam ucapan para politi-kus yang fasih menggunakan istilah-istilah seperti “suara terbanyak”, “aset politik”, “ongkos politik”, dan sebagainya. Istilah-
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 94 4/24/2014 10:01:22 AM
Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama ALEXANDER AUR 95
istilah yang diucapkan para politisi meru-pakan proyeksi dari praktik yang sesung-guhnya. Hal itu menunjukkan bahwa rasio pasar tengah mengoloni praktik politik da-lam negara hukum demokratis.
4.4 Agama yang Berpolitik: Agama yang Membela dan Merawat Kemanusiaan dan Demokrasi
Sejak keruntuhan re�im politik Orde Baru, kesempatan agama untuk berpolitik terbu-ka. Banyak partai politik berbasis ideologi agama muncul dan terlibat dalam perpoli-tikan riil. Partai politik berbasis ideologi agama Islam yang paling eksis sejak Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009. Partai politik-partai politik yang dimaksud ada-lah PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai politik-partai politik tersebut akan menjadi peserta pemilu 2014. Dengan berbasis ideologi Islam, partai politik-partai politik itu merupakan repre-sentasi agama (Islam) yang berpolitik se-cara riil dalam negara hukum demokratis Indonesia.
Agama yang berpolitik bukan monopo-li agama Islam. Agama-agama lain pun ber-politik melalui organisasi massa berhaluan agama. Melalui ormas-ormasnya, agama-agama lain seperti Katolik, Protestan, Hin-du, Buddha, Konghucu juga terlibat secara aktif dalam merespon isu-isu publik seperti kerusakan lingkungan hidup, korupsi, ter-orisme, ketidakadilan ekonomi, pelangga-ran hak-hak asasi, dan sebagainya. Agama-agama yang merespon isu-isu publik juga merupakan modus politik agama dalam negara hukum demokratis Indonesia.
Dalam perspektif filsafat politik Habermas di atas, tantangan yang paling se-rius bagi agama-agama yang berpolitik, baik melalui partai politik maupun or-ganisasi massa, adalah mentranslasikan
doktrindoktrin metafisiknya ke dalam ba-hasa negara hukum demokratis. Apabila agama gagal melakukan itu, maka agama menjadi “duri dalam daging” demokrasi. Tanpa melakukan translasi doktrin-doktrin metafisiknya, maka agama yang berpoli-tik justru menjadi horor bagi kemanusiaan dan demokrasi. Doktrindoktrin metafisik agama dapat menjadi pemasti kognitif prin-sip-prinsip etis negara hukum demokratis apabila agama memastikan suatu “situasi epistemik” di dalam modernitas atau di dalam negara hukum demokratis. Agama yang demikian adalah agama yang merela-tivisasikan posisinya berhadapan dengan agama-agama lain tanpa merelativisasikan inti dogmatismenya sendiri (Borradori, 2005: 105). Dengan demikian, agama yang berpolitik adalah agama yang membela-merawat kemanusiaan dan demokrasi.
Penutup
Habermas berpikir tentang status sosiolo-gis dan politis agama dalam negara hu-kum demokratis. Bukan karena ia sangat berbakat dalam hal agama, melainkan ka-rena ia memandang bahwa agama meru-pakan salah satu elemen dalam negara hukum demokratis. Dalam bingkai teori tindakan komunikatif, etika diskursus, dan demokrasi deliberatif, Habermas meng-ingatkan agama bahwa jika agama berman-faat bagi demokrasi, maka agama ha rus menerjemahkan bahasa agama ke dalam bahasa sekuler. Pengandaian-pengandaian metafisik agama harus diuji dengan rasio sekuler, supaya agama tidak menjadi horor sekaligus teror bagi negara hukum de-mokratis.
Dalam sejarah politik di Indonesia, par-tisipasi agama dalam politik mengalami pasang surut. Pada masa-masa persiap-an kemerdekaan Indonesia dan penetap-an UUD 1945, para pendiri bangsa yang
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 95 4/24/2014 10:01:22 AM
96 Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama VOL II, 2014
berasal dari organisasi-organisasi agama berdeliberasi perihal rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara. Doktrin agama (Islam) yang hendak dimasukkan dalam rumusan dasar negara didiskusikan dan diperdebatkan. Hasil dari itu adalah rumus-an Pancasila yang sekarang menjadi dasar bagi negara hukum demokratis Indonesia.
Pada masa Orde Baru, agama dibeku-kan dari aktivitas politik riil. Doktrin-dok-trin agama dilarang untuk diintegrasikan ke dalam politik negara. Partai politik-par-tai politik baik yang berdasarkan agama maupun nasionalis diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai basis ideologi. Demikian pula, organisasi massa-organisasi massa berhaluan agama pun harus menjadikan Pancasila sebagai basis ideologinya. Kebi-jakan Orde Baru ini menimbulkan perla-wanan, khususnya dari agama Islam.
Keruntuhan Orde Baru menjadi angin segar bagi agama untuk berpolitik secara riil. Partai politik-partai politik berbasis agama lahir, dan menjadi peserta pemilu. Beberapa partai politik berbasis ideologi agama (Islam) berhasil eksis serta me-nempatkan politisinya di DPR, dan masuk menjadi bagian dari pemerintahan. Dalam periode ini, agama mendapat kesempatan luas untuk berpolitik baik melalui politik riil maupun melalui keterlibatannya dalam isu-isu dan persoalan-persoalan publik.
Dalam perkembangan demokrasi yang kian matang di Indonesia, agama memang harus dipisahkan dari negara hukum demokratis. Pemisahan ini tidak berarti agama tidak mempunyai ruang politik un-tuk ekspresi politik. Agama tetap mempu-nyai ruang politik untuk ekspresi politik. Dalam ekspresi politiknya, agama harus merelativisasikan posisinya di dalam nega-ra hukum demokratis tanpa harus merela-tivisasikan doktrindoktrin metafisiknya. Artinya, agama tidak bisa menjadi dasar
bagi negara hukum demokratis. Hal lain yang harus dilakukan agama adalah me-nerjemahkan doktrindoktrin metafisiknya ke dalam bahasa universal supaya bisa diterima oleh warga negara hukum yang lain, baik yang beragama maupun tidak beragama. Pada titik ini, doktrin-doktrin metafisik agama bisa menjadi pemasti kog-nitif prinsip-prinsip etis negara hukum demokratis. Jika agama gagal menerjemah-kan doktrindoktrin metafisiknya, maka agama yang berpolitik hanya menjadi teror sekaligus horor yang mengancam kemanu-siaan, demokrasi, dan mencoreng agama itu sendiri. Kegagalan ini yang mesti di-antisipasi oleh agama bila agama bermak-sud memberi makna pada negara hukum demokratis.
DAFTAR PUSTAKA
Adam, Nicholas. (2006). Habermas and The-ology. Cambridge: Cambridge Univer-sity Press.
Budi-Kleden, Paul dan Adrianus Sunarko (ed.). (2010). Dialektika Sekularisasi, Dis-kusi Habermas-Ratzinger dan Tanggapan. Maumere-Yogyakarta: Penerbit Ledale-ro-Lamalera.
Borradori, Giovanna. (2005). Filsafat dalam Masa Teror: Dialog dengan Jürgen Haber-mas dan Jacques Derrida. Jakarta: Pener-bit Buku Kompas.
Deflem, Mathieu (ed). (1996). Habermas, Modernity and Law. London: SAGE Pub-lication.
Habermas, J�rgen. (2008). Between Natural-ism and Religion: Philosophical Essays. Malden, MA: Polity Press.
_______. (1996). ”Postscript to Between Facts and Norms” dalam Mathieu Deflem (ed.). Habermas, Modernity and Law. London: SAGE Publication.
_______. (1984). The Theory of Communicative Action, vol. 1. Boston: Beacon Press.
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 96 4/24/2014 10:01:22 AM
Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama ALEXANDER AUR 97
Hardiman, F. Budi. (1990). Kritik Ideologi-Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan. Yogyakarta: Kanisius.
_______. (1993). Menuju Masyarakat Komu-nikatif. Yogyakarta:Kanisius.
_______. (2009). Demokrasi Deliberatif – Me-nimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jürgen Ha-bermas. Yogyakarta: Kanisius.
Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (ed.). (2012). Dari Radikalisme menujuTe-rorisme – Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Jakarta: SETARA Institute.
Kieser, Bernard. (2004). “Agama Bubar jika Tidak Bercampur Nalar: Being religiosus a la Habermas” dalam Majalah BASIS, nomor 11-12, tahun ke-53, November-Desember.
Kristanto, JB dan Nirwan Ahmad Arsuka (ed.). (2002). Bentara Esei-esei 2002, Ja-
karta: Penerbit Buku Kompas. Madjid, Nurcholish. (1992). Islam Doktrin
dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis ten-tang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan. Jakarta: Yayasan Wa-kaf Paramadina.
Magnis-Suseno, Fran�. (2010). “Per-kembangan Hubungan Kristiani-Mus-lim di Indonesia” dalam A. Eddy Kris-tiyanto (ed.), Spiritualitas Dialog: Narasi Teologis tentang Kearifan Religius. Yogy-akarta: Kanisius.
Regh, William. (1994). Insight and Solidarity: A Study in the Discourse Ethics of Jurgen Habermas. California: University of Cal-ifornia Press.
Soeprapto. (2013). Pancasila: Makna dan Pe-rumusannya. Jakarta: LPPKB.
Stephen, K. White (ed.). (1995). The Cam-bridge Companion to Habermas. New York: Cambridge University Press.
006-[Alex Aur] Dialog Negara dan Agama_Habermas.indd 97 4/24/2014 10:01:22 AM
Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, hal 98-110ISSN 2302-5719
Vol II, Nomor 1
Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia:Sebuah Kritik terhadap Artikel “Chilean Socialism 1: Indonesian
Facism 0”
CANGGIH GUMANKY FARUNIK
Dosen Tidak Tetap Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di Surya University dan Universitas Multimedia Nusantara
Surel: [email protected]
Diterima: 27 Februari 2014Disetujui: 7 April 2014
ABSTRACT
Based on an article, “Chilean Socialism 1: Indonesian Facism 0” by Andre Vltchek in www.counterpunch.org, Indonesia was studied as a bad and uncivilized country during the new order era under Soeharto regime. The people still considered Soeharto as a national hero, contrary with Andre’s perspective where Soeharto was perceived as a dictator. The first thing that comes to mind after reading the article is that Soe-harto has had some well-built personage thanks to the media coverage, which was fully controlled by him. Rendering theory from Karl Popper to frame the article in question, one can’t overlook the rich contribution of Popper’s Three World. In his system, every results of human’s mind are contained, i.e. theories, testi-monies, arguments, buildings, cultures, technologies, even media. The character of world 3 is autonomous, which means human being couldn’t erase the testimonies that had already been spoken, but it could be de-veloped and completed by the others. That’s the reason why the well-built theories or testimonies couldn’t be erased or replaced so easily, in this case, Soeharto’s personage.The main purpose of this research is to find the correlation between media’s power and its problems upon leadership’s personage, by using Popper’s Three World perspective.
Keywords: media, personage, testimonies, Three World.
Pendahuluan
Artikel berjudul “Chilean Socialism 1: In-donesian Facism 0”yang ditulis dan dipub-likasikan Andre Vltchek, seorang jurnalis investigasi pada sebuah situs jurnal inves-
tigasi internasional, www.counterpunch.org1, membincang perbandingan dinamika antara pemimpin diktator dengan rakyat di negara Indonesia dan Chili. Vltchek meng-ambil perbandingan suasana politik di
1 Bisa diakses di http://www.counterpunch.org/2013/11/22/chilean-socialism-1-indonesian-fascism-0/
007-[Canggih G. Farunik] Perna Media dalam membangun persona pemimpin di Indo.indd 98 4/24/2014 10:24:51 AM
Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia CANGGIH GUMANKY FARUNIK 99
Indonesia, utamanya masyarakat Jakarta, pada masa pemerintahan Soeharto, khu-susnya pada tahun 1965, dengan suasana politik di Chili pada pemerintahan Pino-chet. Vltchek menulis:
“Jakarta is not just the capital of the fourth most populous country on earth; it is also the ‘least hab-itable major city in Asia Pacific’. Jakarta is also a concept, an enormous experiment on human beings, which was quickly turned into a blueprint that has later been implemented by the West all over the de-veloping world. The experiment was about trying to figure out this: What happens to a poor country that is hit by a brutal military coup, then thrown to religious zealots, and forced to live under the heel of extreme capitalism and fascism? And what hap-pens if almost its entire culture gets destroyed, and instead of education, some brainwashing mecha-nism perfected abroad, gets implemented? What if you kill 2-3 million people, and then you ban entire languages and cultures, theatres, art films, atheism, everything that is to the left of center? And what if you use thugs, paramilitaries, archaic family and religious structures and a ridiculously toothless me-dia, to maintain ‘the new order’?” (Vltchek, 2013)
Lebih lanjut, Vltchek menjawab perta-nyaan-pertanyaan di atas sebagai berikut:
“The answer is this: You get your Indonesian mod-el! Which means – almost no production, a ruined environment, collapsed infrastructure, endemic corruption, not even one sound intellectual of inter-national caliber, and frankly speaking, a ‘function-ally illiterate’ population, ignorant about the world, about its own history, and about its own position in the world” (Vltchek, 2013).
Kalaupun ada perbedaan pendapat dari dalam lingkungan akademisi di In-donesia terkait hal-ihwal yang dikatakan Vltchek tentang keadaan sebenarnya di In-donesia pada masa itu, maka kemungkin-an yang terjadi adalah bahwa pandangan Vltchek tersebut benar, dan yang selama ini menjadi cara pandang bangsa Indone-
sia terhadap rezim Soeharto salah. Atau, sebaliknya,yang dikatakan Vltchek meru-pakan kritik yang subjektif, dan kasar de-ngan komparasi yang berat sebelah.
Kemungkinan pertama, masyarakat Indonesia yang salah dalam memandang Soeharto, dengan melakukan komparasi dengan situasi yang terjadi di Chili. Rakyat Chili melakukan perlawanan terhadap junta militer, dengan Pinochet sebagai pemimpinnya, melalui sebuah usaha ku-deta pada 1973. Jika Soeharto dan Pinochet digambarkan sebagai sosok fasis, dan rakyat sebagai pendukung sosialis, maka yang terjadi di Chili adalah perjuang an rakyat sosialis melawan fasisme. Hal tersebut ber-banding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia di mana rakyat sosialis dibantai oleh fasisme.Vltchek memandang bahwa yang terjadi di Indonesia merupakan suatu kemunduran dibandingkan dengan rakyat Chili; bahwa rakyat Indonesia terlalu bodoh untuk mendiamkan begitu saja pelanggar-an HAM yang nyata terjadi didepan mata mereka, dan usaha rakyat Chili melakukan gerakan bawah tanah untuk mengguling-kan kekuasaan junta militer dianggapnya sebagai usaha yang heroik. Sederhananya, rakyat Indonesia bodoh, sedangkan rakyat Chili lebih kritis.
Kemungkinan kedua dapat juga dijadi-kan pertimbangan.Ternyata Vltchek mem-buat sebuah argumentasi subjektif tanpa mengetahui sama sekali situasi politik yang berkembang di Indonesia pada masa peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soe-harto. Pada masa peralihan tersebut, ter-cuat ungkapan yang terkenal di kalangan mahasiswa Indonesia ketika itu, “Yang pa-ling penting kita sudah menurunkan suatu rezim; jika rezim yang baru tidak cocok, kita tinggal turunkan lagi”2. Artinya, ada
2 Penulis mencatat ungkapan tersebut dari film ‘Gie’ (2005), sebuah film tentang pejuang muda Indonesia di era 1966, Soe Hok Gie (1942 – 1969). Film yang disutradarai Riri Riza ini diangkat dari buku ‘Catatan Seorang Demonstran’, memoar yang ditulis sendiri oleh Soe Hok Gie.
007-[Canggih G. Farunik] Perna Media dalam membangun persona pemimpin di Indo.indd 99 4/24/2014 10:24:51 AM
100 Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia VOL II, 2014
komitmen dari kalangan mahasiswa untuk terus berjuang melawan rezim yang tidak berpihak kepada rakyat. Satu hal yang me-narik dicatat mengenai perjuangan maha-siswa pada zaman Soeharto:ternyata butuh waktu sekitar 31 tahun bagi mahasiswa untuk mewujudkan ungkapan tersebut da-lam realita! Mahasiswa kembali berperan secara aktif dalam politik praktis dengan cara mengawal era reformasi yang ditan-dai dengan mundurnya Soeharto dari ja-batan presiden yang dijabatnya sejak tahun 1967. Kenyataan bahwa Soeharto berhasil menjadikan Indonesia swasembada beras pada tahun 1984, menekankan pada per-tumbuhan ekonomi sebagai tujuan, dan seringnya melakukan peninjauan langsung ke pasar-pasar tradisional, serta ikut serta turun ke sawah saat panen raya, merupa-kan sebuah upaya penciptaan kesan baik pada masyarakat Indonesia yang berhasil diciptakan pribadi Soeharto selama masa kepemimpinannya.
Analisis atas Persoalan-persoalan di dalam artikel Andre Vltchek
Hal yang paling mendasar dari pemaham-an Vltchek dalam artikel yang ditulisnya adalah bahwa ia berusaha membanding-kan kondisi sosialisme di Indonesia dan di Chili. Menurut hematnya, fasisme Soe-harto menang melawan sosialisme/komu-nisme, sedangkan sosialisme di Chili justru menang melawan fasisme. Masa perali-han kedua negara yang diperbandingkan memang memiliki dua unsur pokok yang sama, sehingga perbandingan antara In-donesia dengan Chilidapat dijustifikasi. Vltchek juga mengulas karakter dua tokoh pemimpin kedua negara tersebut (yaitu Soeharto dan Pinochet) yang hampir sama.
Di antaranya adalah membiarkan terjadi-nya pembunuhan massal, pemerkosaan, dan berbagai kejahatan kemanusiaan lain-nya.
Bahkan, secara tersirat, Vltchek me-ngatakan bahwa Soeharto adalah panut-an (role model) dari gerakan fasisme baru pasca perang dunia kedua. Keberpihakan Vltchek mulai terlihat ketika ia mengambil sikap yang berbeda antara Indonesia dan Chili. Kemenangan sosialisme di Chili-oleh Vltchek dianggap sebagai kemajuan dari proses pendewasaan masyarakat, yang dimulai dari menyadari persoalan, mengambil sikap, hingga konsisten ter-hadap sikap tersebut. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dalam persepsi Vltchek dianggap menyerah pada fasisme Soeharto, menutup mata, bahkan turut ber-tanggung jawab atas pembunuhan massal para pendukung Partai Komunis Indone-sia (PKI). Menurut Vltchek, “kebodohan” rakyat Indonesialah yang dituding men-jadi penyebab terhambatnya kemajuan di Indonesia, bahkan rakyat Indonesia juga dianggap tidak mampu bereaksi terhadap fasisme dan segala bentuk pelanggaran ke-manusiaan yang dibuat rezim fasis tersebut. Berikut penulis akanmembahas mengenai kekeliruan cara pandang Vltchek dalam memahami persoalan Indonesia dan Chili.
Kekeliruan pertama adalah sikap Vltchek yang sangat sinis dalam meman-dang Indonesia hanya melalui pemahaman psikologi massa. Menurut situs Geographia.com3, Chili mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1817, tetapi justru bagian yang paling penting dari sejarah Chiliterjadi pada tahun 1973 ketika berlangsung peralihan kekuasaan dari Dr. Salvador Allende,yang baru saja menduduki jabatan presiden se-lama tiga tahun sejak 3 November 1970
3 http://www.geographia.com/chile/chilehistory.htm (diakses penulis pada 26 Februari 2014, pukul 15.30 WIB)
007-[Canggih G. Farunik] Perna Media dalam membangun persona pemimpin di Indo.indd 100 4/24/2014 10:24:51 AM
Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia CANGGIH GUMANKY FARUNIK 101
dengan pemerintahan bercorak Sosialisme - Marxisme, yang kemudian dikudeta oleh Jenderal Augusto Pinochet Ugartedari go-longan sayap kanan pemerintahan Chili. Sedangkan Indonesia baru saja “dua pu-luh tahun merdeka” sebelum Soeharto di-anggap bertanggung jawab atas peristiwa 1965. Berdasarkan artikel Vltchek, gerakan sosialis di Chili diawali oleh Movimiento de Izquierda Revolucionaria atau MIR, sebuah gerakan revolusi kiri yang dibentuk para mahasiswa pada tahun 1965 diinspirasi-kan gerakan revolusi Kuba. Menurut situs latinamericanhistory.about.com4, Salvador Allende memiliki hubungan dekat dengan MIR. Keponakan Salvador Allende, yaitu-Andrés Pascal Allende, merupakan salah satu pemimpin muda MIR. Secara tidak langsung, bisa dikatakan bahwa pemerin-tahan Salvador Allende yang bercirikan So-sialisme - Marxisme mendapat dukungan kuat dari MIR sebagai organisasi pemuda yang mapan.
Perjuangan serupa juga sempat ter-jadi di Indonesia sebagai efek dari peno-lakan terhadap pemerintahan demokrasi terpimpin à la Soekarno yang dimulai se-jak 1955. Setelah 1955, pemikiran Marx-berkembang pesatdi kalangan mahasiswa Indonesia ketika itu dan Partai Komunis juga menjadi partai yang sangat populer di lapisan bawah masyarakat.Hal yang di-lupakan Vltchek adalah kenyataan bahwa gerakan mahasiswa juga memiliki peranan yang penting bagi pergerakan sejarah di Indonesia. Salah satu faktor krusial yang membedakan gerakan mahasiswa di Indo-nesia dengan gerakan MIR di Chili adalah asal-muasal perubahan pemerintahan pas-ca tergulingnya pemimpin pemerintahan.
Setelah Soekarno diturunkan dari ja-batan Presiden, sebagian mahasiswa yang
tadinya terlibat dalam gerakan menjadi anggota parlemen dan berpandangan bah-wa perubahan dapat dilakukan dari dalam wilayah kekuasaan.Hal ini berbeda de ngan MIR yang sebagian simpatisannya justru masuk ke wilayah militer dan menjadi ba-gian dari pertahanan negara sebelum Pino-chet melakukan kudeta terhadap pemerin-tahan Salvador Allende.Berkaitan dengan gerakan mahasiswa di Indonesia, Vltchek sama sekali tidak menyebutkan hal terse-but secara jelas di dalam artikelnya, pada-hal gerakan mahasiswa Indonesia adalah bagian yang penting ketika membanding-kan Indonesia dan Chili. Memang terdapat perlawanan dari kalangan mahasiswa keti-ka Soeharto menjabat sebagai presiden, na-mun puncak perjuangan mahasiswa baru terwujud pada tahun 1998, ketika Soeharto akhirnya mundur sebagai presiden dan era reformasi dimulai.
Kritik Vltchek terhadap “kebodohan” masyarakat Indonesia diungkapkan seba-gai berikut:
“Like those guys, who dutifully cut people to pieces, raped 14-year old girls and terrorized those people who were still willing to think and to speak, every-thing was shown in detail in the award winning film by Joshua Oppenheimer: “The Act of Killing”. And what did the Indonesian viewers and TV hosts do when the thugs confessed to kill hundreds? They laughed, and cheered, and applauded!”(Vltchek, 2013)
Pertanyaan mengenai “mengapa bisa terjadi kondisi yang di dalamnya manusia justru mendukung pembunuhan dan da-pat bersikap berlawanan seperti yang se-harusnya manusia lakukan ketika terjadi pembunuhan?” sama sekali tidak pernah dibahas oleh Vltchek, karena yang men-jadi perhatiannya adalah kenyataan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang
4 http://latinamericanhistory.about.com/od/thehistoryofchile/a/09ChileMIR.htm (diakses penulis pada 26 Februari 2014, pukul 15.45 WIB)
007-[Canggih G. Farunik] Perna Media dalam membangun persona pemimpin di Indo.indd 101 4/24/2014 10:24:51 AM
102 Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia VOL II, 2014
bodoh secara mental, yang dianggap ber-sikap tidak manusiawi dengan cara me-nertawakan dan justru berbangga dengan pengakuan seorang pembunuh. Selain itu, Vltchek juga mengatakan:
“In 1965, in Jakarta, there was no struggle. The victims allowed themselves to be slaughtered. They were begging for mercy as they were strangled, stabbed, shot to death. They called their tormentors, their murderers, their rapists, ‘pak’ and ‘mas’ (re-spectful form of addressing a man). They cried and begged for mercy” (Vltchek, 2013).
Dalam kutipan tersebut, Vltchek ingin menegaskan bahwa yang menjadi korban justru pasrah dan masih menghormati orang yang menyiksa mereka dengan me-manggilnya “pak” atau “mas”. Vltchek melihat fenomena tersebut sebagai sesuatu yang otonom, sedangkan dirinya hanya pengamat, dan dari hasil pengamatannya, komunisme di Indonesia tidak sehebat sosialisme di Chili. Pertanyaan mengenai “mengapa bisa begitu?” sama sekali tidak muncul dalam artikel tersebut. Vltchek melakukan generalisasi masyarakat Indo-nesia menjadi sebuah kelompok masyarakat yang bodoh, pesimis, dan pasrah.
Pertanyaan “mengapa bisa begitu?” ha nya bisa dijawab jika memahami kebingungan situasi ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia menjelang tahun 1965.Demokrasi terpimpin yang dilakukan Soekarno menyebabkan kinerja pemerin-tahan menjadi anti-klimaks.Masyarakat Indonesia menaruh kepercayaan penuh bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) dapat membuat perubahan di Indonesia.Vltchek melewatkan bagian bahwa peris-tiwa pembunuhan massal anggota, kader, dan simpatisan PKI ketika itu berhubung-an erat dengan dugaan pemberontakan
yang dilakukan oleh PKI terhadap peme-rintahan Soekarno. Malcolm Caldwell dan Ernest Utrecht dalam buku Sejarah Alter-natif Indonesia, justru mengatakan bahwa Aidit menerima informasi dari Jenderal Polisi Sutarto bahwa dewan Jenderal akan memecat Soekarno dan mengambil alih kekuasaan pada tanggal 5 Oktober 1965. Karenanya, ada dugaan dari pihak mili-ter sendiri bahwa Aidit akan mendahului rencana jenderal dengan mengorganisasi suatu pemberontak an bersenjata untuk merebut kekuasaan (Caldwell dan Utrecht, 1979: 255).
Caldwell dan Utrecht juga mengatakan bahwa anggota PKI selain kader di Ja-karta, tidak mengetahui apa-apa tentang rencana pemberontakan bersenjata terse-but (Caldwell dan Utrecht, 1979: 256).Jika Caldwell dan Utrecht mengatakan demikian, lalu siapakah yang melakukan penculikan para Jenderal? Mereka menye-butkan bahwa yang melakukan pencu-likan para Jenderal TNI Angkatan Darat adalah Resimen Cakrabirawa (pasukan pengawal presiden), sebagian dari ang-gota TNI Angkatan Udara, dan beberapa milisi pemuda PKI yang kebetulan sedang melakukan latihan di pangkalan udara Halim Perdana kusuma. Mereka juga me-negaskan bahwa para serdadu yang ter-libat, bukan merupakan bagian dari PKI, dan belum ada bukti bahwa para jenderal disiksa sebelum dibunuh oleh para serda-du tersebut (Caldwell dan Utrecht, 1979: 257). Hal tersebut diperkuattestimoni yang dimuat di situs jurnal3.com5 bahwa dokter ahli forensik yang meng otopsi jasad para jenderal, yaitu dr. Brigadir Jenderal Roebi-ono Kertopati, seorang perwira kesehatan di RSP Angkatan Darat, dan empat dokter lainnya, menyatakan bahwa “dari hasil vi-
5 http://www.jurnal3.com/hasil-otopsi-7-jenazah-pahlawan-revolusi-utuh-semua/ (diakses penulis pada 26 Februari 2014, pukul 17.05 WIB)
007-[Canggih G. Farunik] Perna Media dalam membangun persona pemimpin di Indo.indd 102 4/24/2014 10:24:51 AM
Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia CANGGIH GUMANKY FARUNIK 103
sum et repertum atas 7 jenazah, semuanya dalam kondisi utuh, dan tidak ada bekas-bekas peng aniayaan dan siksaan, seperti yang disaksikan dalam film.”
Berdasarkan pemahaman Caldwell dan Utrecht tersebut, propaganda yang mengatakan seluruh anggota dan simpa-tisan PKI bersalah atas terbunuhnya para Jenderal, pada dasarnya dibangun dari argumen yang tidak jelas, dan cenderung digeneralisasi. Anggota PKI selain yang di Jakarta, sama sekali tidak mengetahui rencana penculikan para jenderal terse-but. Bahkan yang melakukan penculikan pun bukanlah anggota PKI, karena para serdadu TNI Angkatan Darat dan Resi-men Cakrabirawa merasa berkepentingan untuk mengamankan para jenderal seb-agai reaksi dari dugaan kudeta yang akan dilakukan para anggota Dewan Jenderal terhadap pemerintahan Soekarno. Akibat dari propaganda yang dilancarkan selepas peristiwa pembunuhan para jenderal, rakyat Indonesia seketika itu juga terbagi menjadi dua pihak, pendukung dan peno-lak PKI.
Jika Vltchek menyebutkan film The Act of Killing karya Joshua Oppenheimer5, teta-pi tidak memahami bahwa kondisi Indo-nesia hampir seperti pembunuhan massal kaum militer, dan sipil non-PKI terhadap sipil PKI, maka Vltchek melakukan suatu generalisasi, bahwa seluruh rakyat Indone-sia adalah komunis, dan menganggap fa-sisme Soeharto melalui tangan militernya saja yang melakukan pembunuhan mas-sal terhadap mereka tanpa perlawanan. Keterlibatan milisi dari rakyat sipil non-PKI untuk mencari, dan ikut serta dalam
pembunuhan simpatisan, dan anggota PKI menunjukkan suatu bukti bahwa kondisi yang terjadi di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Chili.
Persoalan selanjutnya “mengapa para milisi dari rakyat non-PKI ini dengan mu-dahnya membunuh, tanpa ada rasa kasih-an? Apa yang menjadikan mereka sangat membenci PKI dan menganggap bahwa PKI layak untuk mati?” Salah satu faktor adalah kuatnya “tuduhan”, dan propa-ganda dari media. Peristiwa 1965 adalah suatu kebingungan massal yang berujung pada usaha untuk keluar dari kebingung-an tersebut dengan menentukan sikap.Harus ada yang disalahkan atas krisis eko-nomi yang melanda Indonesia pada masa itu, dan rakyat Indonesia menganggap bahwa sumber dari segala krisis adalah keberadaan PKI. Selain itu, kepercayaan rakyat terhadap Soekarno semakin menu-run, dan posisi ini dimanfaatkan secara efektif oleh Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan.
Berbeda dengan Pinochet yang meng-ambilalih kekuasaan dengan kudeta ter-buka, Soeharto mengambil alih kekuasa-an dengan persona seorang penyelamat bangsa. Langkah yang diambil Soeharto juga dianggap memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia, meskipun wacana alter-natif yang berkembang adalah kecurigaan bahwa situasi yang terjadi di tahun 1965 su-dah direncanakan oleh Soeharto. Soeharto menjadikan tanggal 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila, bahwa pembunuh-an massal anggota PKI merupakan usaha membela negara yang berlandaskan Pan-
5 Film tersebut merupakan suatu reka ulang para milisi di Medan, Sumatra ketika mereka membunuh banyak anggota dan simpati-san PKI. Di dalam film tersebut, rasa kemanusiaan mereka tertutupi oleh kebencian dan suatu keyakinan bahwa PKI adalah pihak yang bersalah secara moral, sehingga mereka merasa bahwa PKI ‘layak’ untuk mati. Pada saat ini, kelompok milisi di Medan tersebut berada di bawah naungan Pemuda Pancasila.
007-[Canggih G. Farunik] Perna Media dalam membangun persona pemimpin di Indo.indd 103 4/24/2014 10:24:51 AM
104 Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia VOL II, 2014
casila. Pancasila menjadi oposisi biner dari komunisme yang divonis sebagai paham terlarang di Indonesia, sehingga siapapun yang terbukti mengembangkan paham ko-munisme, dianggap anti Pancasila.
Media sebagai Dunia Ketiga dan Implikasi-nya
Pemikiran Three World atau tiga dunia, bu-kan merupakan pemikiran Popper yang paling terkenal.Teori Popper yang paling dikenal adalah falsifiabilitas, suatu teori perkembangan ilmiah (scientific progress) yang berisikan ajaran bahwa suatu teori dapat dikatakan ilmiah apabila dapat di-sangkal dan mampu bertahan dari segala penyangkalan yang menyerangnya. Impli-kasi langsung dari pemikiran ini adalah dibangunnya pengetahuan yang bercorak problem solving, yang didalamnya berisi pandangan bahwa sebuah teori yang di-sangkal, secara tidak langsung juga memi-liki cara untuk keluar dari penyangkalan melalui penyelesaian persoalan. Sisi lain dari teori perkembangan ilmiah terse-but, Popper mengembangkan persoalan keilmiahan suatu teori menuju arah yang sangat metafisis, meskipun Popper tidak menyadari hal tersebut. Hal yang men-jadi persoalan utama Popper sejak dirinya masih sangat muda, bahwa teori yang di-dasarkan pada pemahaman bahasa yang definitif tidak akan memberikan jawaban yang memadai daripada didasarkan pada realitas sebenarnya. Membangun pemaha-man filosofis dari perenungan yang defini-tif hanya akan menjadi pemahaman yang surreal dan lepas dari konteks asalnya, yai-tu realitas. Popper mengatakan,
“Never let yourself be goaded into taking seriously problems about words and their meanings. What must be taken seriously are questions of fact, and assertion about facts: theories and hypotheses; the
problems they solve; and the problems they raise” (Popper, 1992: 14).
Meskipun Popper menganggap bahwa dirinya adalah seorang penganut rasiona-lisme kritis, tetapi dirinya tidak menolak dianggap sebagai seorang realis. Dasar-dasar realisme Popper inilah yang menjadi awal dari perkembangan pemikiran tiga dunia.
Pemikiran tiga dunia merupakan teori alternatif dari pandangan monisme dan dualisme tentang alam semesta.Popper membagi sub-universes menjadi tiga bagian yang saling berinteraksi (Popper, 1978: 3). Popper membagi realitas menjadi tiga macam ‘dunia’, yaitu:
Dunia fisik, yang realitasnya dapat di-jangkau oleh indera manusia. Mengenai hal ini, Popper tidak menjelaskan secara detail, apakah realitas ini sangat bergan-tung pada persepsi manusia, seperti yang dikatakan oleh kaum empirisisme, ataukah memang realitas fisik ini otonom dan bebas dari persepsi manusia. Meskipun begitu, cukuplah jika dikatakan bahwa realitas ini sangat commonsense, karena kebenaran dan konsistensi dari realitas ini, pada dasarnya, berlaku menyeluruh pada setiap persepsi inderawi manusia. Artinya setiap orang akan mempersepsikan hal yang sama dari suatu objek yang sama pula, sedan-gkan perbedaan atau relativitas persepsi baru akan muncul ketika ada usaha untuk menjelaskan objek tersebut.
Dunia pikiran manusia (mind). Di dalam bahasa Indonesia, belum ditemukan kata yang benar-benar tepat dalam meng-gambarkan ‘mind’ secara analogis, tetapi pada dasarnya hal ini cukup mudah untuk dipahami bahwa realitas kedua ini berkai-tan dengan apapun yang sedang dipikir-kan manusia. Dalam penelitian lebih lan-jut, amat dimungkinkan apabila realitas ini
007-[Canggih G. Farunik] Perna Media dalam membangun persona pemimpin di Indo.indd 104 4/24/2014 10:24:51 AM
Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia CANGGIH GUMANKY FARUNIK 105
akan mencakup segala aktivitas kognitif manusia.
Dunia hasil pemikiran manusia. Re-alitas ketiga ini merupakan hasil dari olah pikir manusia. Pada awalnya, Popper ha-nya mengatakan yang termasuk ke dalam dunia ketiga ini adalah tulisan, pengakuan, wacana, teori, dan bentuk lingustik lain-nya, namun dalam perkembangannya, Popper juga memasukkan karya manusia yang lain, yang pada dasarnya dapat di-sebut sebagai teknologi
Berdasarkan ilustrasi dari gambar 1 yang diambil dari knowledgejump.com, ditunjukkan bahwa dunia ketiga adalah pengetahuan virtual yang objektif. Selain itu, hubungan yang sangat penting adalah hubungan dunia ketiga dan dunia pertama.Hubungan diantara keduanya hanya bisa berinteraksi lewat bantuan dunia kedua melalui pengujian dan observasi.
yang berbeda dengan objek natural. Manu-sia hanya bisa mengawasi dan mengada-kan realitas fisik, sedangkan objekobjek artifisial itu diproduksi dan dikembangkan oleh pikiran manusia.
Persoalan lain terkait hubungan antara ‘pikiran manusia’ dengan ‘hasil pemiki-ran manusia’. Meskipun hasil pemikiran manusia bersifat otonom, tetapi pengem-bangan dari hasil pemikiran ini sangat bergantung pada subjektivitas pikiran ma-nusia. Bebe rapa orang yang mengembang-kan suatu objek artifisial yang sama, dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda juga, sehingga jika ada lima orang yang berpikir untuk mengembangkan televisi, maka akan ada lima jenis televisi yang berbeda. Media, baik elektronik maupun cetak, memiliki realitas yang berbeda dengan alam piki-ran manusia, jika dilihat dari pemahaman Karl Popper. Wacana hanya bisa dilengkapi atau direvisi, sehingga amat dimungkin-kan bahwa alur wacana dari suatu peris-tiwa dapat direkam dan setiap orang dapat meng arahkan pandangannya pada salah satu titik dari wacana tersebut. Jika halnya seperti itu, maka tidaklah mengherankan apabila ada suatu teori dalam sains yang sempat dianggap tidak lagi memadai un-tuk digunakan dalam normal science---se-perti teori evolusi Darwin---namun toh tetap saja ada beberapa peneliti yang masih tertarik menggeluti teori tersebut.
Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa keterangan berbentuk pernyataan, teori, argumentasi, dan pengakuan harus memiliki hubungan dengan realitas du-nia pertama yang diuji dan diobservasi oleh dunia kedua. Artinya seseorang tidak bisa begitu saja membuat keterangan yang terlepas dari realitas fisiknya, sehingga ada faktor yang koresponden dan koheren an-tara keterangan seseorang dengan realitas fisiknya. Hubungan yang koresponden
Gambar 1 (http://www.knowledgejump.com/knowl-edge/popper.html)
Pemikiran tiga dunia ini sangat mem-bantu untuk menjelaskan satu bagian yang hilang, bahwa sebenarnya perlu untuk membedakan objek yang berasal dari ma-nusia dan realitas fisik yang natural, karena campur tangan manusia atas objek-objek artifisial tersebut memiliki pola interaksi
007-[Canggih G. Farunik] Perna Media dalam membangun persona pemimpin di Indo.indd 105 4/24/2014 10:24:52 AM
106 Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia VOL II, 2014
dan koheren inilah yang menjadi acuan dari kebenaran suatu teori. Jadi, meskipun subjektivitas dari pikiran manusia sebagai dunia kedua dalam mengembangkan ha-sil pemikiran dalam dunia ketiga amatlah kuat namun ini tidak boleh terlepas dari realitas fisik sebagai dunia pertama. Hal inilah yang menentukan kebenaran dari suatu keterangan, baik berupa teori, argu-mentasi, pernyataan, atau pengakuan.
Peran Media dalam Pembentukan Persona Soeharto sebagai Pemimpin Indonesia
Konstelasi seperti diuraikan di ataslah yang akan dijadikan acuan oleh penulis untuk mengkritisi informasi yang beredar di dalam media. Sejak teknologi informa-si, seperti televisi, radio, dan media cetak dikembangkan, manusia semakin lemah dalam melakukan pengujian hubungan dari suatu informasi dengan realitas, ka-rena arus informasi yang sangat cepat yang berbanding terbalik dengan kemampuan manusia dalam melakukan pengujian in-formasi. Misalkan ada suatu keterangan yang direkayasa sehingga tidak korespon-den dengan realitasnya, atau yang biasa disebut ‘fiktif’, maka akan ada usaha untuk menutupi kebenaran dari keterangan terse-but. Kecenderungan untuk melakukan suatu keterangan yang fiktif pada dasarnya
memiliki tujuan dan kepentingan yang ter-balik dengan keterangan ilmiah yang fak-tual.Keterangan yang fiktif diciptakan un-tuk membuat suatu konstruksi yang surreal atau melampaui realitas yang sebenarnya, untuk memenuhi tujuan dan kepentingan tertentu dari suatu pihak. Perilaku fiktif ini sebenarnya sangat wajar untuk dilakukan manusia, karena berkaitan dengan imajina-si sebagai bagian dari proses berpikir ma-nusia. Hal inilah yang ditekankan Popper terkait dengan pengertian garis demarkasi antara hal ilmiah dan tidak ilmiah7, yaitu ketika suatu teori sesuai dengan realitas-nya, atau memiliki falsifiabilitas8 yang ting-gi, maka teori tersebut dapat dikatakan se-bagai ilmiah (Popper, 2002).
Dalam perkembangan informasi di dunia modern, terutama pada tahun 1965, televisi belum begitu banyak digunakan di Indonesia, sehingga berita yang beredar dianggap benar tanpa perlu pembuktian, meskipun tingkat kebenarannya sebena-rnya masih belum jelas.Kondisi tersebut memudahkan sekelompok orang yang me-miliki kepentingan tertentu untuk mem-berikan suatu keterangan yang mungkin saja jauh dari fakta sebenarnya. Selain itu, cara Soeharto menampilkan personanya sebagai penyelamat bangsa, meyakinkan rakyat Indonesia bahwa persona inilah yang dapat dipercayai.
7 Popper menyebutnya sebagai pseudoscience. Artinya kondisi ketika suatu teori dilandaskan pada suatu pemahaman yang bias dan bersifat ilusi atau khayalan belaka, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah. Salah satu contoh yang diambil Popper adalah teori psikoanalisis Sigmund Freud yang tidak bisa diuji dan diobservasi, karena para-doks yang dihasilkan dari teori alam bawah sadar.Selain itu, Popper juga menganggap teori Karl Marx mengenai persamaan kelas, juga dilandaskan pada sesuatu yang utopis dan doktriner, sehingga termasuk dalam pseudosci-ence.
8 Falsifiabilitas adalah sifat dari suatu teori yang terbuka pada suatu penyangkalan.Semakin banyak penyangkalan, maka teori tersebut dianggap falsifiable.Semakin falsifiablesuatu teori dan mampu bertahan dari penyangkalan, maka teori tersebut dianggap lebih mendekati kebenaran. Bagi Popper, perkembangan ilmiah suatu teori hanya dapat diuji melalui penyangkalan yang kritis. Jika suatu teori mampu bertahan, maka teori tersebut dapat dianggap mendekati kebenarannya; tetapi jika tidak mampu bertahan, maka teori yang lama akan digantikan dengan yang baru.
007-[Canggih G. Farunik] Perna Media dalam membangun persona pemimpin di Indo.indd 106 4/24/2014 10:24:52 AM
Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia CANGGIH GUMANKY FARUNIK 107
Gambar 2 (http://ceritaindonesia.wordpress.com/tag/soe-harto-ordebaru)
Gambar kedua diambil dari website ceritaindonesia.wordpress.com, yang isi-nya sebuah poster Soeharto sebagai bapak pembangunan. Persona Soeharto sebagai penyelamat bangsa dan seorang yang berjasa bagi pembangunan Indonesia me-negaskan bahwa dirinya bukan seorang fasis, dan hal tersebut dipercayai secara penuh oleh rakyat Indonesia. Sikap kritis dihalangi dan diredam dengan berbagai cara agar propaganda media menjadi ke-benaran tunggal. Soeharto juga menggu-nakan Pancasila sebagai langkah untuk mengantisipasi perlawanan dari simpati-san PKI, kalangan akademisi yang meneliti pemikiran Marx, dan termasuk seniman serta sastrawan yang bercorak Marxisme yang masih tersisa. Siapapun yang menye-barkan ajaran Marxisme akan dianggap sebagai musuh Pancasila dan negara Indo-nesia. Model dan strategi persona Soeharto ini berbeda dengan persona Pinochet yang berbentuk opresi terbuka, sehingga berita yang beredar adalah berita yang menegas-kan bahwa dirinya adalah seorang fasis yang menghambat kebebasan rakyat Chili. Opresi terbuka tersebut akan menimbul-kan suatu perlawanan, dan dianggap ber-
Melalui pemahaman tersebut, dapat di-simpulkan bahwa bukan masyarakat Indo-nesia yang bodoh, tetapi kecerdikan dan ke-mampuan Soeharto dalam memanfaatkan oposisi biner antara Pancasila dan PKI se-bagai cara untuk menjatuhkan musuh poli-tiknya. Jika kekuasaan Soeharto, diperkuat oleh suatu paham kenegaraan se perti Pan-casila, sedangkan Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tidak bisa diganti-kan, maka siapapun yang menyerang Soe-harto berarti menyerang Pancasila, begitu juga sebaliknya. Begitu juga apabila ada seseorang atau sekelompokorang yang ber-usaha menyebarkan paham komunisme,
tolak belakang dengan tujuan dan ideologi negara yang cenderung sosialis.
Gambar ketiga yang diambil dari store.tempo.com, juga menunjukkan pro-paganda anti PKI diperkuat dengan film yang menunjukkan kekejaman PKI, yang berisi pesan bahwa Resimen Cakrabirawa dan TNI Angkatan Udara yang melaku-kan penculikan para Jenderal merupakan bagian dari rencana PKI.Film ini selalu diputar selama masa pemerintahan Soe-harto setiap tanggal 30 Sptember sebagai hari peri ngatan G30S/PKI dan hari kesak-tian Pancasila pada tanggal 1 Oktober.
Gambar 3 (http://store.tempo.co/foto/detail/ P0508201100189/posterfilmpenumpasansi-sa-sisa-pki-di-blitar-selatan#.UxG9auOSxCA)
007-[Canggih G. Farunik] Perna Media dalam membangun persona pemimpin di Indo.indd 107 4/24/2014 10:24:52 AM
108 Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia VOL II, 2014
maka akan dianggap sebagai musuh neg-ara dan Pancasila. Kondisi inilah yang menjadi justifikasi bagi Soeharto untuk menekan lawan-lawan politiknya. Melalui cara seperti itu juga, masyarakat Indonesia merasa dibenarkan dengan pembunuhan massal para anggota dan pendukung dari PKI, sehingga tidak ada perasaan bersalah atas pembunuhan tersebut.
Hal tersebut juga digambarkan dengan baik dalam film The Art of Killing. Dalam film ini dituturkan bahwa para pelaku pembunuhan terhadap anggota PKI di Medan sama sekali tidak merasa bersalah, karena mereka menganggap PKI yang salah dan yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Para pelaku ini juga diang-gap sebagai pahlawan yang berjasa dalam melawan pemberontakan dan menjaga keutuhan negara Indonesia.Tentang hal ini Vltchek mengatakan:
”A few streets away, the newly rich, sit in their luxury SUV’s in epic traffic jams, watching tele-vision, going nowhere, but proud that they have moved up the rungs on their class ladder.What a success! What an absolute success of fascist, neo-colonial demagogy and the ‘market economy’!This ‘success’ was, of course, studied and analyzed in Washington, Canberra, London and elsewhere. It has been implemented all over the world, in differ-ent forms and variations, but with the same essence: strike and murder every thinking being, shock and brainwash… then rob the poor and reward a few criminals… from Chile to Argentina, Yeltsin’s Rus-sia and Rwanda, now again in Egypt.It has worked almost everywhere. “Jakarta was coming”, and it has been spreading its filth, its ignorance, brutality and compassionless way of ‘thinking’ all over the planet” (Vltchek, 2013).
Argumen tersebut memang menun-jukkan suatu kesuksesan yang bias, dan Vltchek menganggap bahwa istilah ‘Jakarta was coming’ menunjukkan contoh fasisme yang sukses. Sangat mudah dipahami bah-wa sikap sinis Vltchek lebih tertuju pada kemenangan fasisme, neo-kolonialisme,
dan ekonomi pasar. Hanya saja kesinisan Vltchek tersebut justru menutupi pandang-an yang objektif terhadap Indonesia. Indo-nesia seperti objek yang diteliti perilaku-nya dari dalam ruangan berkaca. Cara Vltchek menghakimi bangsa Indonesia dalam artikelnya menunjukkan sikap yang sama dengan masyarakat yang membenci PKI, yaitu sikap yang menganggap bahwa golongan yang berlawanan memiliki cara hidup yang salah, tidak bersifat konstruktif yang progresif, dan tidak mencerminkan orang yang layak untuk hidup sebagai ma-nusia yang beradab. Suatu cara pandang yang menyingkirkan data, dan informasi yang berkaitan dengan kondisi sebenarnya, dan hanya menggunakan informasi, dan data yang mendukung artikelnya tersebut. Dengan kata lain, Vltchek tidak melakukan suatu analisis yang objektif di dalam ar-tikelnya tersebut.
Kesimpulan
Artikel Vltchek yang menyebutkan bahwa rakyat Indonesia semata-mata bodoh, dan tidak peduli terhadap kejahatan kema-nusiaan tidak sepenuhnya benar, karena kompleksitas persoalan yang terjadi pada masa itu, ditambah kemampuan Soeharto dalam menampilkan persona yang berbeda dari pandangan seorang fasis. Kuatnya persona Soeharto itu juga yang menopang pandang an umum bahwa sistem Soeharto masih tetap bertahan, meskipun Soeharto sudah tidak lagi menjabat sebagai pre-siden Indonesia, dan era reformasi sudah menying sing. Bagi rakyat Indonesia, jasa Soeharto bagi kemajuan bangsa Indone-sia sangatlah besar. Jasa Soeharto tersebut mampu menutupi kenyataan bahwa ba-nyak rakyat Indonesia yang terbunuh se-lama periode kekuasa annya. Konteks Soe-harto sebagai seorang fasis juga tidak bisa dipahami apabila Soeharto dianggap se-
007-[Canggih G. Farunik] Perna Media dalam membangun persona pemimpin di Indo.indd 108 4/24/2014 10:24:52 AM
Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia CANGGIH GUMANKY FARUNIK 109
bagai seorang pahlawan bangsa. Ketegasan Soeharto dianggap lebih layak oleh rakyat Indonesia ketika itu daripada seorang yang demokratis dalam memimpin bangsa.
Hal inilah yang tidak dipahami Vltchek, bahwa penjajahan panjang, dan umur ne-gara Indonesia yang masih sangat muda menyebabkan kondisi Indonesia yang be-lum stabil, bahkan jika dibandingkan de-ngan Chili. Pendidikan yang belum merata bagi setiap penduduk Indonesia, karena ditinggalkan oleh golongan bangsawan ter-didik yang membuka akses pengetahuan secara kurang merata, menyebabkan seba-gian besar rakyat Indonesia mencari pendi-dikan alternatif melalui ajaran agama.
Melalui ajaran agama juga, rakyat In-donesia mempelajari tentang oposisi biner dari kerangka dan kaidah moralitas, an-tara baik dengan buruk, kebaikan dan ke-jahatan, sehingga sikap yang terbentuk adalah dikotomis secara absolut yaitu upa-ya meyakinkan diri mereka sendiri bahwa yang dilakukannya adalah benar dan perlu secara moral, sekaligus bahwa yang me-reka lawan adalah pihak yang salah. Si-kap seperti ini sudah tidak digunakan lagi di Eropa dan Ame rika, karena kesadaran HAM yang tinggi akibat perang yang ter-us terjadi di Eropa dan Amerika, sehingga wacana HAM bukan hanya tentang defi-nisi HAM itu sen diri, tetapi juga diiringi kesadaran untuk mencegah sekuat tenaga pelbagai aktivitas yang dikategorikan se-bagai pelanggaran HAM. Konteks kesadar-an HAM memang belum begitu banyak di-wacanakan di Indonesia, karena hal yang penting bagi Indonesia pada saat itu adalah stabilitas di segala bidang kehidupan, se-hingga rakyat Indonesia akan membela siapapun yang mampu membawa mereka keluar dari krisis, dan membawa Indonesia pada kondisi yang stabil.
Peran media sangat menentukan dalam hal menampilkan citra atau persona dari
seseorang ataupun kelompok. Berdasar-kan teori tiga dunia Popper, keterangan seseorang atau kelompok dapat dikatakan sebagai keterangan yang ilmiah, jika kores-ponden dengan realitas faktualnya. Na-mun, dalam perkembangannya, keterang-an yang berbentuk informasi tidak selalu sesuai dengan realitas sebenarnya, karena ada usaha untuk menjaga kepentingan per-sonal, baik untuk menutupi, memanipula-si, atau menciptakan sesuatu yang surreal. Suatu fakta juga dapat digiring pada wa-cana yang diinginkan kelompok tertentu untuk menghindari terwujudnya realitas yang tidak diinginkan atau justru untuk menciptakan suatu realitas tertentu. Butuh penelitian yang lebih seksama mengenai persepsi kebenaran dalam media, karena kecenderungan persepsi masyarakat In-donesia adalah gampang menyerahkan putusan tentang kebenaran pada media. Bahkan, ketika terjadi dua informasi yang berbeda, dan bertentangan terhadap suatu fakta dan realitasnya, masyarakat cende-rung percaya pada keduanya.
Keyakinan tersebut berkaitan juga de-ngan pemahaman bahwa informasi yang beredar di media tidak ada hubungan-nya dengan sikap moral dari realitas yang ditampakkan oleh informasi tersebut; ke-cuali informasi tersebut berhubungan de-ngan idola masyarakat, karena masyarakat akan cenderung membela idola mereka. Idola seperti menjadi bagian dari diri para penggemarnya, seolah-olah idola adalah milik para penggemar, dan mereka akan membelanya sepenuh hati.
Selain itu, peran dari informan yang bertugas mencari kebenaran realitasnya, memiliki kecenderungan yang bersifat in-duktif dengan penyimpulan yang sangat general, dan mudah dipahami dirinya sen-diri ataupun orang lain yang akan diinfor-masikan. Sebagai contoh, seseorang yang
007-[Canggih G. Farunik] Perna Media dalam membangun persona pemimpin di Indo.indd 109 4/24/2014 10:24:52 AM
110 Peran Media dalam Membangun Persona Pemimpin di Indonesia VOL II, 2014
berada di dalam bus, melihat pemuda de-ngan pakaian kasual secara tidak sengaja menyentuh celana seorang wanita, maka kesimpulan dari orang tersebut akan mengarah pada dugaan bahwa si pemu-da berpakaian kasual ini akan melakukan suatu kejahatan terhadap si wanita terse-but. Dugaan tersebut lebih dapat diterima umum daripada sekedar ‘kejadian yang ti-dak sengaja’, mengingat bahwa setiap tin-dakan seseorang pasti memiliki maksud dan tujuan, tidak mungkin hanya kebetu-lan. Maka dapat dibayangkan apabila si orang tersebut akan memberitahukan apa yang ia lihat kepada wanita tersebut se-perti apa yang dirinya pikirkan bahwa si pemuda berpakaian kasual akan melaku-kan suatu perbuatan jahat.
DAFTAR PUSTAKA
Caldwell, Malcolm dan Utrecht, Ernst. (2011). Sejarah Alternatif Indonesia. Yog-yakarta: Djaman Baru.
Popper, Karl R. (2002). Unended Quest: An Intellectual Autobiography. London dan New York: Routledge.
_____. (1978). Three World. University of Michigan: The Tanner Lecture of Hu-man Value.
Sumber Artikel dari InternetMinster, C. (2014). Chile’s MIR (The Revo-
lutionary Left Movement): Urban Guer-rillas Declare War on the Pinochet Dicta-torship. Artikel bisa diakses di http://latinamericanhistory.about.com/od/thehistoryofchile/a/09ChileMIR.htm
InterKnowledge Corp. (2010). Chile: His-tory and Culture. Artikel bisa diakses di http://www.geographia.com/chile/chil-ehistory.htm
Jurnal3. (2014). Hasil otopsi: 7 jenazah Pahla-wan Revolusi utuh semua. Artikel bisa diakses di http://www.jurnal3.com/hasil-otopsi-7-jenazah-pahlawan-rev-olusi-utuh-semua/
Vltchek, A. (2013). Chilean Socialism 1: In-donesian Facism 0. Artikel bisa diak-ses di http://www.counterpunch.org/2013/11/22/chilean-socialism-1-in-donesian-fascism-0/
Sumber GambarGambar 1 http://www.knowledgejump.
com/knowledge/popper.htmlGambar 2 http://ceritaindonesia.wordpress.
com/tag/soeharto-ordebaruGambar3 http://store.tempo.co/foto/detail/
P0508201100189/posterfilmpenump-asan-sisa-sisa-pki-di-blitar-selatan#.UxG9auOSxCA
007-[Canggih G. Farunik] Perna Media dalam membangun persona pemimpin di Indo.indd 110 4/24/2014 10:24:52 AM
Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, hal 111-123ISSN 2302-5719
Vol II, Nomor 1
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA
SURAJIYO1
Dosen Tetap pada Universitas Indraprasta PGRI, JakartaSurel: [email protected]
Diterima: 5 Januari 2014Disetujui: 28 Maret 2014
ABSTRACT
Essentially, Pancasila is the source of all moral and legal norms in Indonesia which are then applied nation-ally. Pancasila as political ethics is closely associated with the ethics of forms, objects, and political issues of material objects that covers the legitimacy of the state, law, power, and critical assessment for the said legitimacy. Based on MPR RI Decree Number: VI/MPR/2001, about national ethics, political ethics in the life of the nation, a concept that derived its legitimacy from religious values, especially values which are by nature universal, as well as cultural values originated from Indonesia, all those values are reflected in Pancasila as the basic reference in thinking, behaving, and acting in the spirit of nationalism. Pancasila as political ethics can be used as a tool to examine political behavior of a country, especially as a critical method to decide the truth or falsity of government’s actions and policies, by examining the implied correspondence between objective values with inter-subjective value. The results are then examined more thoroughly to weigh the synergy between government’s policies and actions with each principle of Pancasila. In politi-cal realm, a country should be based on democratic values which is then developed and actualized on its policies. In Indonesian context, these policies should be based on morality, divinity, humanity, and unity which bind the nation within the framework of Pancasila. This paper aims to expand the discussion on how Pancasila is applied as Indonesia’s most original and trustworthy political ethics.
Keywords: Nilai-nilai Pancasila, Etika, Moral, Etika Politik, Etika Kehidupan Berbangsa.
1 Dosen tetap pada Universitas Indraprasta PGRI, dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala. Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang. Alumnus Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta (S1) dan Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta.
Pendahuluan
Pancasila sebagai dasar negara pada ha-kikatnya merupakan sumber dari segala norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Nor-Nor-
ma hukum adalah suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di In-donesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara In-donesia. Norma moral berkaitan dengan
008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 111 4/24/2014 10:39:49 AM
112 PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA VOL II, 2014
tingkah laku manusia sebagai manusia un-tuk mengukur baik atau buruknya sebagai manusia. Dalam kapasitas inilah nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan dalam norma-norma moralitas atau norma-norma etika sehingga Pancasila merupakan sistem eti-ka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Jadi, sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan pedoman yang lang-sung bersifat normatif ataupun praktis me-lainkan sistem etika yang menjadi sumber norma moral maupun norma hukum, yang harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam ke-hidupan kenegaraan maupun kebangsaan.
Berdasarkan pandangan, keyakinan dan kesepakatan bersama para bapak pendiri bangsa bahwa Pancasila merupa-kan dasar negara (Philosophische grondslag) maka konsekuensinya Pancasila merupak-an sumber norma hukum, norma moral, dan norma kenegaraan lainnya. Dalam konteks Pancasila sebagai sumber norma moral inilah permasalahan muncul yak-ermasalahan muncul yak-ni sejauh mana Pancasila merupakan eti-ka politik di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan besar ini, permasalahan yang terkait dengan etika politik yakni tentang pengertian etika, nilai, moral, dan norma akan dibahas lebih dahulu. Kemudian, di-lanjutkan dengan pembahasan pengertian etika politik, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Re-publik Indonesia, nilai-nilai Pancasila seba-gai sumber etika, dan tulisan akan diakhiri dengan pelaksanaan etika politik Pancasila.
Pengertian Etika, Nilai, Moral, dan Norma
1. EtikaEtika secara etimologi berasal dari kata Yu-nani ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara terminologi etika adalah cabang filsafat yang membicarakan ting-kah laku atau perbuatan manusia dalam
hubungannya dengan baik-buruk. Yang dapat dinilai baik atau buruk adalah sikap manusia yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-gerakan, kata-kata dan sebagainya. Sedangkan motif, watak, suara hati sulit untuk dinilai. Perbuatan atau tingkah laku yang dikerjakan dengan kesadaran sajalah yang dapat dinilai, se-dangkan yang dikerjakan dengan tak sadar tidak dapat dinilai baik atau buruk.
Menurut Sunoto (1982: 5), etika dapat dibagi menjadi etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif hanya melukis-kan, menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya ber-buat. Contohnya sejarah etika. Sedangkan etika normatif sudah memberikan penilai-an yang baik dan yang buruk, yang harus dikerjakan dan yang tidak. Etika norma-tif dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan prinsip-prinsip umum, seperti penger-tian dan pemahaman tentang nilai, moti-vasi suatu perbuatan, suara hati, dan se-bagainya. Etika khusus adalah pelaksanaan prinsip-prinsip umum di atas, seperti etika pergaulan, etika dalam pekerjaan, dan se-bagainya.
Pembagian etika yang lain adalah etika individual dan etika sosial. Etika individual membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia sebagai individu. Misalnya tujuan hidup manusia. Etika sosial membi-carakan tingkah laku atau perbuatan ma-nusia dalam hubungannya dengan orang lain. Misalnya; baik/buruk dalam kehidup-an keluarga, masyarakat, negara. (Sunoto, 1982: 5-6)
Etika pada hakikatnya mengama-ti realitas moral secara kritis. Etika tidak mem berikan ajaran melainkan memeriksa ke biasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-nor ma dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menuntut pertanggung-
008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 112 4/24/2014 10:39:49 AM
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA SURAJIYO 113
jawaban yakni karena banyak sekali aja-ran moral dan pandangan moral seperti dalam kitab-kitab suci, petuah, wejangan dari para kyai, pendeta, orang tua dan sebagainya, dan manusia harus memilih dengan kritis dan meng ikuti ajaran moral tertentu sehingga bisa dipertanggungja-wabkan atas pilihannya. Etika tidak mem-biarkan pendapat-pendapat moral tidak dapat dipertanggungjawab an. Etika beru-saha untuk menjernihkan permasalahan moral. Misalnya seorang ibu yang mengan-dung dan difonis oleh dokter untuk memi-lih dua pilihan apakah bertahan tetap men-gandung sampai melahirkan dengan resiko jiwa ibu terancam karena kandungannya lemah atau menggugurkan dengan resiko tidak punya anak. Masalah-masalah seper-ti itu perlu tinjauan kritis untuk mengam-bil keputusan. Sedangkan kata moral sela-lu mengacu pada baik-buruknya manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia bila dilihat dari segi kebaikannya. Norma-norma moral adalah tolok ukur un-tuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Misalnya kalau seorang wartawan ternyata tidak bisa membuat berita dan ke-tika mencari warta juga tidak bisa maka se-bagai peran wartawan salah, tetapi sebagai manusia bisa juga seorang itu baik karena selalu berbuat jujur, adil, disiplin dan seba-gainya (Magnis-Suseno, 1987: 18).
Objek etika menurut Franz Magnis-Suseno (dalam Zubair, 1987: 18) adalah pernyataan moral. Apabila diperiksa se-gala macam moral, pada dasarnya hanya ada dua macam, yaitu: pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia seperti motif-motif, maksud, dan watak. Ada himpunan per-nyataan ketiga yang tidak bersifat mo ral, tetapi penting dalam rangka pernyataan tentang tindakan.
Berdasarkan pendapat Franz Magnis-Suseno tersebut Zubair (1987: 18) membuat skema sebagai berikut :
Etika
Pandangan Moral
Persoalan Moral
Pernyataan tentang tindakan manusia,Pernyataan tentang manusia sendiri
Pernyataan Moral
Pernyataan bukan moral.
Berdasarkan skema tersebut, Zubair (1987: 19) merincinya sebagai berikut :1. Dalam beberapa pernyataan kita me-
ngatakan bahwa suatu tindakan ter-tentu sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma moral dan oleh karena itu adalah betul, salah, dan atau wajib. Contoh: “Engkau seharusnya mengem-balikan uang itu”. “Mencuri itu salah”, “Perintah jahat tidak boleh ditaati” Ke-tiganya disebut sebagai pernyataan ke-wajiban.
2. Orang, kelompok orang dan unsur-un-sur kepribadian (motif, watak, maksud, dan sebagainya) kita nilai sebagai baik, buruk, jahat, mengagumkan, suci, me-malukan, bertanggung jawab, pantas ditegur, disebut sebagai pernyataan pe-nilaian moral.
3. Himpunan pernyataan ketiga yang ha-rus diperhatikan adalah penilaian bu-kan moral. Contoh: Mangga itu enak, Anak itu sehat. Mobil itu baik, Kertas ini jelek, dan sebagainya.
Perbedaan penting mengenai beberapa pernyataan di atas :1. Pernyataan kewajiban tidak mengenal
tingkatan. Wajib atau tidak wajib, betul atau salah Tidak ada tengahnya.
008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 113 4/24/2014 10:39:49 AM
114 PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA VOL II, 2014
2. Penilaian moral dan bukan moral me-ngenal tingkatan. Rasa dari sebuah mangga dapat agak enak atau enak sekali. Watak bersifat amat jahat atau agak jahat; dan lain sebagainya.
2. NilaiDi dalam Dictionary of Sociology and Related Science (dalam Kaelan, 2004: 87) dikemuka-kan bahwa nilai adalah kemampuan untuk dapat dipercayai yang ada pada suatu ben-da sehingga ia dapat memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu ob-jek, dan bukan objek itu sendiri. Jika sebuah objek mengandung nilai maka artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada objek itu.
Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dam-baan dan keharusan. Jika kita berbicara ten-tang nilai, maka sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan dambaan dan keharusan. Berbicara tentang nilai be-rarti berbicara tentang das Sollen, bukan das Sein, kita masuk ke dunia ideal dan bukan dunia riil. Meskipun demikian, di antara keduanya, antara das Sollen dan das Sein, antara dunia ideal dan dunia riil mereka saling berhubungan atau saling berkait secara erat. Artinya das Sollen seharusnya menjelma menjadi das Sein, yang ideal ha-rus menjadi real, dan hal yang bermakna normatif harus direalisasikan dalam per-buatan sehari-hari yang merupakan fakta. (Kaelan, 2004; 87-88)
3. MoralMoral berasal dari kata latin “mos” ja-maknya “mores” yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral mengandung mak-Etika dan moral mengandung mak-na yang sama, tetapi dalam penilaian seha-
ri-hari ada sedikit perbedaan. Moral dan moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada.
Magnis-Suseno (1987: 14) membedakan antara ajaran moral dengan etika. Ajaran moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-we-jangan, khotbah-khotbah, peraturan-pera-turan lisan atau tertulis tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung bagi ajaran moral adalah pelbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, juga tulisan para bijak. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral tetapi filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Hal yang mengajarkan bagai-mana kita seharusnya menjalani hidup bu-kanlah etika melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab dalam mengha-dapi pelbagai ajaran moral.
4. NormaPada mulanya norma berarti alat tukang batu atau tukang kayu yang berupa segiti-ga. Dalam perkembangannya norma berar-ti ukuran, garis pengarah, atau aturan, dan kaidah bagi pertimbangan serta penilaian. Nilai yang menjadi milik bersama di dalam satu masyarakat dan telah tertanam de-ngan emosi yang mendalam akan menjadi norma yang disepakati bersama.
Segala hal yang kita beri nilai baik, cantik atau berguna akan kita usahakan supaya diwujudkan kembali di dalam per-buatan kita. Sebagai hasil usaha itu maka timbul ukuran perbuatan atau norma tin-dakan. Norma yang diterima oleh anggota
008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 114 4/24/2014 10:39:49 AM
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA SURAJIYO 115
masyarakat selalu mengandung sanksi dan pahala.- Tidak dilakukan sesuai norma – hu-
kum an; celaan dan lain sebagainya.- Dilakukan sesuai dengan norma – pu-
jian; balas jasa dan sebagainya.
Jadi skemanya sebagai berikut :
gar norma hukum pasti dikenai sanksi. Tetapi norma hukum tidak sama de-ngan norma moral.
3. Norma Moral Norma moral adalah tolok ukur yang di-
pakai masyarakat untuk mengukur ke-baikan seseorang. Maka dengan nor ma moral, kita benar-benar dinilai. Itulah sebabnya penilaian moral selalu ber-bobot. Manusia tidak dilihat dari salah satu segi melainkan sebagai manusia. Apakah seseorang merupakan warga negara yang selalu taat, atau seorang munafik. Apakah kita ini baik atau bu-ruk, maka hal itulah yang menjadi per-masalahan moral.
Ketiga macam norma kelakuan itu, mana-kah yang mengalah apabila ada tabrak an di antara keduanya? Norma sopan santun mengalah baik terhadap norma-norma hukum maupun norma-norma moral. Ba-gaimana kalau norma hukum bertabrakan dengan norma moral? Misalnya, seorang ayah yang sama sekali tidak mempunyai uang lagi, di satu pihak ia berwajib (moral) untuk memberi makan anak serta istri, di lain pihak satu-satunya jalan yaitu dengan mengambil uang orang lain secara diam-diam. Thomas Aquinas berpendapat bah-wa suatu hukum yang bertentangan den-gan hukum moral (hukum kodrat) akan kehilangan kekuatannya. Norma-norma moral muncul sebagai kekuatan yang amat besar dalam hidup manusia, karena ber-ber-dasarkan norma morallah manusia benar-benar dinilai.
5. ����n�an etika, nilai, moral, dan nor�. ����n�an etika, nilai, moral, dan nor�ma
Agar nilai menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manu-sia, maka ia perlu lebih dikonkretkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objek-tif se hingga memudahkan manusia un-
Penilaian
Norma
Nilai
Ada banyak macam norma. Ada nor-ma-norma khusus, yaitu norma yang hanya berlaku dalam bidang dan situasi yang khusus, misalnya bola tidak boleh disentuh oleh tangan, hanya berlaku kalau dan sewaktu kita main sepak bola dan kita bukan kiper. Disamping norma khusus ada juga norma umum. Norma umum menurut Magnis-Suseno (1987: 19) ada tiga macam, yaitu :1. Norma Sopan Santun Norma ini menyangkut sikap lahiriah
manusia. Meskipun sikap lahiriah dapat mengungkapkan sikap hati dan karena itu mempunyai kualitas moral, namun sikap lahiriah sendiri tidak mempunyai kualitas moral. Orang yang melanggar norma kesopanan karena tidak menge-tahui tatakrama di daerah itu, atau di-tuntut oleh situasi, maka ia tidak dapat dianggap melanggar norma moral.
2. Norma Hukum Norma hukum adalah norma yang di-
tuntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselama-tan dan kesejahteraan umum. Norma hukum adalah norma yang tidak boleh dilanggar. Hukum tidak dipakai untuk mengukur baik buruknya seseorang se-bagai manusia, melainkan untuk men-jamin tertib umum. Jadi yang melang-
008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 115 4/24/2014 10:39:49 AM
116 PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA VOL II, 2014
tuk menjabarkannya dalam tingkah laku. Wujud yang lebih konkret dari nilai ada-lah norma. Terdapat berbagai macam nor-ma. Dari berbagai macam norma tersebut norma hukumlah yang paling kuat keber-lakuannya, karena dapat dipaksakan oleh kekuatan eksternal seperti penguasa atau penegak hukum.
Selanjutnya nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan marta-bat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang ter-kandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah maka kita me-masuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia (Kaelan, 2004: 92-93).
Pengertian Etika Politik
Dalam hubungan dengan etika politik pengertian politik harus dipahami da-lam pengertian yang lebih luas yaitu me-nyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara. Hukum dan kekuasaan negara merupakan aspek yang berkaitan langsung dengan etika politik. Hukum sebagai penataan masyarakat secara nor-matif, serta kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif pada hakikatnya sesuai dengan struktur sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.
Setiap ilmu terkandung dua macam ob-jek yakni objek forma dan objek material. Objek forma adalah sudut pandang subyek menelaah objek materialnya. Objek mate-rial adalah sasaran penyelidikan dari disi-plin ilmu. Etika politik berkaitan de ngan obyek forma etika, dan obyek material po-litik. Jadi etika politik mempelajari politik
dari sudut pandang etika, yang dalam po-litik mencakup masalah legitimai negara, hukum, kekuasaan serta penilaian kritis terhadap legitimasi-legitimasi tersebut.
Secara substansial pengertian etika po-litik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berda-sarkan kenyataan bahwa pengertian ‘mo-ral’ senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban mo-ral dibedakan dengan pengertian kewajib-an-kewajiban lainnya. Kewajiban moral adalah kewajiban yang dilakukan manusia sebagai manusia atas kesadarannya, se-dangkan kalau melakukan kewajiban atas dasar karena perintah di luar diri maka ke-wajiban itu bukan kewajiban moral. Misal-nya jika seorang pelatih memberikan pe-rintah kepada anak buahnya “besuk anda wajib latihan”. Kemudian anak buah itu besuk hadir latihan, namun karena anak buah itu menjalankan kewajiban atas dasar perintah di luar diri maka tidak termasuk kewajiban moral. Tetapi kalau ada orang dengan merasa wajib mengembalikan uang yang bukan haknya dan kewajiban ini dilkakukan atas dasar dari hati nurani maka inilah kewajiban moral. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantia-sa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia (Mag-nis-Suseno, 1987: 14-15).
Etika politik tidak langsung mencam-puri urusan politik praktis. Tugas etika po-litik ialah membantu agar pembahasan ma-salah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik dapat mem-berikan patokan orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manu-sia atau mempertanyakan legitimasi moral sebagai keputusan politik. Suatu keputus-
008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 116 4/24/2014 10:39:49 AM
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA SURAJIYO 117
an bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Prinsip-prinsip etika politik yang men-jadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, jami-nan hak-hak asasi manusia menurut paham kemanusiaan dan struktur sosial budaya masyarakat masing-masing serta keadilan sosial (Syarbaini, 2003: 29).
Pancasila sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara Republik Indone-sia
Dalam Dictionary of Sociology and Related Science (dalam Kaelan, 2004: 87), nilai se-cara sederhana dapat diartikan sebagai ke-mampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda itu yang menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai pada hakekatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai yang berarti ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu.
Notonagoro (dalam Kaelan, 2004; 89-90) membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu : 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu
yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material dari raga manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesua-tu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan menjadi empat macam :- Nilai kebenaran, yang bersumber
pada akal (ratio, budi, cipta) manu-sia.
- Nilai keindahan, atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasa-an (rasa) manusia.
- Nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehen-dak (karsa) manusia.
- Nilai religius, yang merupakan nilai korahian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada keper-cayaan atau keyakinan manusia.
Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kero-hanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital (Kaelan, 2004: 90).
Dalam kaitannya dengan derivasi atau penjabarannya, nilai dapat dikelompokkan menjadi tiga macam: a. Nilai Dasar Nilai dasar bersifat universal karena
menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu misalnya hakikat Tuhan, manusia atau yang lainnya. Nilai dasar dapat juga disebut sebagai sumber nor-ma yang pada gilirannya dijabarkan atau direalisasikan ke dalam kehidup-an yang bersifat praksis. Konsekuen-sinya aspek praksis dapat berbeda-be-da namun secara sistematis tidak dapat bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma serta realisasi praksis tersebut.
b. Nilai Instrumental Untuk dapat direalisasikan dalam suatu
kehidupan praksis maka nilai dasar harus memiliki formulasi serta parame-ter atau ukuran yang jelas. Nilai instru-mental inilah yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Nilai instrumental merupa-Nilai instrumental merupa-kan suatu pengejawantahan dari nilai dasar.
c. Nilai Praksis Nilai praksis pada hakikatnya merupa-
kan penjabaran lebih lanjut dari nilai
008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 117 4/24/2014 10:39:49 AM
118 PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA VOL II, 2014
instrumental dalam kehidupan yang nyata. Nilai praksis ini merupakan per-wujudan dari nilai instrumental.
Hubungan antara nilai dengan norma ialah norma merupakan wujud konkrit dari nilai. Selanjutnya nilai dan norma senantia-sa berkaitan dengan moral dan etika.
Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika
Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber bagi pera-turan perundangan, melainkan juga sum-ber moralitas terutama dalam hubungan-nya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu negara seharusnya sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan terutama hu-kum serta moral dalam kehidupan negara. Asas kemanusiaan seharusnya merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.
Dalam pelaksanaan dan penyeleng-garaan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan 1) Asas legalitas, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, 2) di-sahkan dan dijalankan secara demokratis, serta 3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral (legitimasi moral) (Kaelan, 2004: 101).
Legitimasi etis mempersoalkan keab-sahan kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi ini muncul da-lam konteks bahwa setiap tindakan negara baik dari legislatif maupun eksekutif da-pat dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Tujuannya agar kekuasaan dapat di-arahkan pada kebijakan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanu-siaan yang adil dan beradab.
Selain itu, pelaksanaan dan penyeleng-garaan negara harus berdasarkan legitimasi
hukum yaitu prinsip ‘legalitas’. Ne gara In-donesia adalah negara hukum. Oleh karena itu ‘keadilan’ dalam hidup bersama (keadi-lan sosial) sebagaimana terkandung dalam sila V merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Terkait dengan itu, dalam pelaksa-naan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenang an serta pembagiannya harus senantiasa berdasar-kan pada hukum yang berlaku. Pelang-garan atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam keberlang sung an kehidupan negara.
Etika Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di-nyatakan bahwa pengertian etika politik dalam kehidupan berbangsa merupakan ru-musan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan ni-lai-nilai luhur budaya bangsa yang tercer-min dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan ber tingkah laku dalam kehidupan berbangsa.
Pola berpikir untuk membangun ke-hidupan berpolitik secara jernih mutlak diperlukan. Pembangunan moral politik yang berbudaya mengandung tujuan un-tuk melahirkan kultur politik yang ber-dasarkan kepada iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, menggalang sua-sana kasih sayang sesama manusia Indone-sia, yang berbudi kemanusiaan luhur, yang mengindahkan kaidah-kaidah musyawarah secara kekeluargaan, yang bersih dan jujur, dan menjalin asas pemerataan keadilan di dalam menikmati dan menggunakan ke-kayaan negara. Membangun etika politik berdasarkan Pancasila akan diterima baik oleh segenap golongan dalam masyarakat (Syarbaini, 2010: 48).
008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 118 4/24/2014 10:39:49 AM
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA SURAJIYO 119
Pembinaan etika politik dalam kehidup-an berbangsa dan bernegara sangatlah mendesak untuk dilaksanakan. Langkah permulaan dimulai dengan membangun konstruksi berpikir dalam rangka menata kembali kultur politik bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara telah memiliki hak-hak politik, maka pelaksanaan hak-hak politik dalam kehidupan bernegara akan saling bersosialisasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan sesama warga negara dalam berbagai wadah, yaitu dalam wadah infrastruktur dan superstruktur (Syarbaini, 2003: 44).
Pada hakikatnya etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara leng-kap, tetapi melalui moralitas yang ber-sumber dari hati nurani, rasa malu kepada masyarakat, dan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Adanya kemauan dan itikad baik dalam hidup bernegara dapat diukur secara seimbang antara hak yang telah dimiliki dengan kewajiban yang telah ditunaikan, tidak mengandung ambisi yang berlebihan dalam merebut jabatan, namun membekali diri dengan kemampuan yang kompetitif serta terbuka untuk menduduki suatu jabatan, tidak melakukan cara-cara yang terlarang seperti penipuan untuk me-menangkan persaingan politik. Dengan kata lain, tidak menghalalkan segala ma-cam cara untuk mencapai suatu tujuan po-litik (Syarbaini, 2003: 46).
Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa di antaranya mengedepankan kejujuran, keteladanan, sportivitas, disip-lin, etos kerja, kemandirian, sikap toleran-si, rasa malu, tanggung jawab, menjaga ke-hormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.
Dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/ 2001 diuraikan enam etika kehidupan ber-bangsa yakni etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang
berkeadilan, etika keilmuan, dan etika ling-kungan. Berikut adalah uraian singkatnya:
1. Etika Sosial dan B�dayaEtika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan me-nampilkan kembali sikap jujur, saling pedu-li, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, kita perlu menumbuh-kembangkan kembali budaya malu, yakni: malu untuk berbuat kesalahan, semua yang bertentangan dengan moral agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu menumbuhkembangkan kem-bali budaya keteladanan yang harus diwu-judkan dalam perilaku para pemimpin for-mal maupun informal dalam setiap lapisan masyarakat.
Etika ini dimaksudkan untuk menum-buhkan dan mengembangkan kembali ke-hidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif yang sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemam-puan adaptasi, ketahanan, dan kreativitas budaya dari masyarakat.
2. Etika Politik dan PemerintahanEtika politik dan pemerintahan dimaksud-kan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuh-kan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, meng-haragai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan antara hak dengan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.
008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 119 4/24/2014 10:39:49 AM
120 PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA VOL II, 2014
Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pe-layanan kepada publik, siap mundur apa-bila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara. Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan serta per-tentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan sekaligus kebi-jaksanaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah.
Etika politik dan pemerintahan di-harapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar-pelaku dan antar-kekuatan sosial politik serta antar-kelompok kepen-tingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa maupun negara dengan mendahulukan kepentingan ber-sama daripada kepentingan pribadi dan golongan.
Etika politik dan pemerintahan me-ngandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memi-liki keteladanan, rendah hati, dan siap un-tuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti secara hukum melakukan kesalah-an dan secara moral kebijakannya berten-tangan dengan hukum serta rasa keadilan masyarakat.
Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang sesuai dengan tata krama da-lam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohong-an publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.
3. Etika Ekonomi dan BisnisEtika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan
bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bi-dang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan per-saingan yang jujur, berkeadilan, mendor-ong berkembangnya etos kerja daya tahan ekonomi dan saing, dan terciptanya suasa-na kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang meng-arah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan se-hat, keadilan, dan menghindarkan peri-laku menghalalkan segala cara dalam me-meroleh keuntungan.
4. Etika Pene�akan ��k�m yan� Berkea�dilan
Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesa-daran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan dalam hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan ter-hadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi serta kepastian hukum yang sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadil an yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.
Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama, tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, menghindar-kan penggunaan hukum secara salah se-bagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.
5. Etika Keilm�anEtika keilmuan dimaksudkan untuk men-junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar
008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 120 4/24/2014 10:39:50 AM
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA SURAJIYO 121
warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kema-juan yang sesuai dengan nilai-nilai agama maupun budaya. Etika ini diwujudkan se-cara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam pe-rilaku kreatif, inovatif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu penge-tahuan dan teknologi.
Etika keilmuan menegaskan penting-nya budaya kerja keras dengan menghar-gai dan memanfaatkan waktu, disiplin da-lam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan dalam menghadapi hambatan, rintangan, dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, tahan uji ser-ta pantang menyerah.
6. Etika Lin�k�n�anEtika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ru-ang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Dalam kehidupan politik Indone-sia, tidak sedikit suara masyarakat yang menuntut agar dibentuk dewan kehorma-tan dalam berbagai institusi kenegaraan dan kemasyarakatan, dengan harapan agar etika politik dapat terwujud dalam kehidup an bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, DPA, MA, dan BPK, dite-gaskan bahwa DPR perlu meningkatkan ki-nerja anggotanya dengan landasan moral,
etika, dan rasa tanggung jawab yang besar. Dalam pasal 6 Tata Tertib DPR mengenai kode etik DPR, diungkapkan dalam ayat (1) bahwa anggota DPR harus menguta-makan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi ke-wajibannya. Ayat (2) menegaskan bahwa ketidakhadiran anggota secara fisik seba-nyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis dan tanpa izin dari pimpinan fraksi merupakan pelanggaran kode etik.
Pelaksanaan Etika Politik Pancasila
Menurut Aryaning Arya Kresna dkk. (2012: 53-54) ada beberapa cara yang mu-dah untuk memahami politik Pancasila, yang dapat dipakai untuk mengajukan kritik terhadap praktik Pancasila. Pertama mempertanyakan tingkatan dijalankannya prinsip moral “menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia”. Apakah sebuah tindakan yang dilakukan sebuah lembaga pemerintahan telah menjunjung tinggi har-kat dan martabat manusia? Kedua, mem-pertanyakan tingkatan kesesuaian antara nilai obyektif dengan nilai intersubyektif. Apakah sebuah tindakan yang dilakukan lembaga pemerintahan yang berdasarkan prinsip nilai intersubjektif “keadilan” se-suai dengan nilai objektif “adil”?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu kiranya usaha untuk membuat se-buah rambu dan batasan dalam penilaian etika politik Pancasila, sehingga dari titik tersebut dapat ditarik kesimpulan logis, yaitu hal-hal mana saja yang dapat dipakai sebagai acuan penilaian yang lebih kon-kret. Rambu dan batasan tersebut dimulai dengan cara menentukan nilai objektif, ni-lai intersubjektif dan pemaknaannya dalam tiap-tiap sila:1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa , Nilai objektif: Tuhan; Nilai intersubjek-
tif: Ketuhanan; mengandung makna:
008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 121 4/24/2014 10:39:50 AM
122 PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA VOL II, 2014
keyakinan terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa sebagai Causa Prima
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Be-Sila Kemanusiaan yang Adil dan Be-radab
Nilai objektif: manusia; Nilai inter-subjektif: Kemanusiaan; mengandung makna: pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia, pe ng-akuan terhadap asas kesamaan dan ke-bebasan manusia
3. Sila Persatuan Indonesia Nilai objektif: satu; Nilai intersubjektif:
Persatuan; mengandung makna: pe-ngakuan terhadap perbedaan sebagai hakikat, dan pengakuan akan sifat ko-eksistensi manusia.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Per-musyawaratan / Perwakilan
Nilai objektif: rakyat; Nilai intersubjek-tif: Kerakyatan; mengandung makna: pengakuan bahwa kedaulatan negara di tangan rakyat, musyawarah un-tuk mufakat dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat, penjaminan tidak adanya tirani minoritas dan dominasi mayoritas
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Nilai objektif: adil; Nilai intersubjektif: Keadilan; mengandung makna: peng-akuan akan kesamaan hak dan kesem-patan bagi seluruh rakyat Indonesia di bidang agama, ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan.
Memperhatikan analisis singkat atas si-la-sila di atas, etika politik Pancasila da pat digunakan sebagai alat untuk menelaah perilaku politik negara, terutama sebagai metode kritis untuk memutuskan benar salahnya sebuah kebijakan serta baik bu-ruknya tindakan pemerintah dengan cara meneliti kesesuaian antara nilai objektif dengan nilai intersubjektifnya, kemudian
dilanjutkan de ngan menelaah kesesuaian antara kebijakan, dan tindakan pemerintah dengan makna dari sila-sila dalam Panca-sila tersebut.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan nilai sehingga ia menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya.
Etika politik berkaitan dengan objek formal etika, dan obyek material politik yang meliputi legitimasi negara, hukum, kekuasaan serta penilaian kritis terhadap legitimasi-legitimasi tersebut.
Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik yakni :
Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber bagi per-aturan perundangan, melainkan juga me-rupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasa-an, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.
Secara moralitas kehidupan negara - terutama hukum serta moral dalam ke-hidupan negara- harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan.
Asas kemanusiaan seharusnya menjadi prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.
Dalam pelaksanaan dan penyeleng-garaan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan: asas legalitas, disahkan dan di-jalankan secara demokratis, serta dilaksana-kan berdasarkan prinsip-prinsip moral.
Sila-sila Pancasila tersusun atas urut-urutan sistematis. Dalam politik negara seharusnya didasarkan pada prinsip ke-rakyatan (Sila IV). Adapun pengembangan, dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut moral Ketu-hanan (Sila I), moral kemanusiaan (Sila II),
008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 122 4/24/2014 10:39:50 AM
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DI INDONESIA SURAJIYO 123
dan moral persatuan yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa (Sila III). Adapun ak-tualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama (Sila V). Jadi, pengembang an poli-tik negara terutama dalam proses refor-masi seharusnya mendasarkan diri, dan aktualisasinya pada moralitas sebagaima-na tertuang dalam sila-sila Pancasila se-hingga, se bagai konsekuensinya, praktek politik yang menghalalkan segala cara de-ngan memfitnah, memprovokasi, mengha-sut rakyat yang tidak berdosa untuk diadu-domba, seharusnya segera diakhiri.
DAFTAR PUSTAKA
Fudyartanto. (1974). Etika, Cetakan Keempat. Yogyakarta: Warawidyani.
Hadiwijono, H. (1990). Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Cetakan Keempat. Yogyakarta: Kanisius.
Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi. Yogyakarta: Penerbit Para-digma.
Ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 2002. Jakarta: Sinar Grafika.
Kresna, Aryaning A., Agus Riyanto dan Hendar Putranto. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan (Civics). Tangerang: UMN Press.
Magnis-Suseno, F. (1987). Etika Dasar : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius.
_____. (1988). Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakar-ta: PT Gramedia.
Sunoto. (1982). Bunga Rampai Filsafat. Yog-yakarta: Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat UGM.
Syarbaini, S. (2003). Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: Ghalia Indo-nesia.
Syarbaini, S., Rusdiyanta, Fatkhuri. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan Implemen-tasi Karakter Bangsa. Jakarta: Hartomo Media Pustaka.
Zubair, Achmad C. (1987). Kuliah Etika. Ja-karta: Rajawali Pers.
008-[Surajiyo] PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK.indd 123 4/24/2014 10:39:50 AM
Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, hal 124-131ISSN 2302-5719
Vol II, Nomor 1
Kekerasan Media: Kapitalisme, Industri Hiburan, dan Masyarakat Tontonan
E K A N A D A S H O F A A L K H A J A R
Dosen dan Peneliti di Departemen Komunikasi, FISIP Universitas Sebelas MaretJl. Ir. Sutami 36A Kentingan, Surakarta 57126
Surel: [email protected]
Diterima: 21 Januari 2014Disetujui: 10 Maret 2014
ABSTRACT
There is no doubt that media violence poses a threat to public health. Violence is incompatible with human-ity as well as the true enemy of it, and violence does not recognize a religion. Ironically, violence often appears from the dialectic of human life. The tools for articulating violence are vary. One of them is media. Media as a powerful tool in cultivating messages were often included and participated to bring violence to audiences with economics logic and capital profit. This paper reveals an overview where violence is often used as a presentation and commodities that are sold through media in society. Violence is not only a com-mon matter of daily life but also an entertainment.
Keywords: Violence, Commodity, the Society of Spectacle, Media, Entertainment
Pendahuluan
Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menemui apa yang dinamakan kekerasan. Kekerasan itu sendiri mengandung pe-ngertian yang buruk. Oleh karena itu, kekerasan adalah sesuatu yang harus di-hindari karena mengandung unsur yang tidak sejalan dengan kemanusiaan. Jamil Salmi dalam bukunya Violence and Demo-cratic Society (1993) menilai kekerasan itu harus dihindari karena kekerasan memiliki wajah yang menyeramkan dan mengerikan (Salmi, 1993). Kekerasan itu sendiri sangat bertentangan dengan para pelaku, dan pe-mikir kemanusiaan semisal Mahatma Gan-dhi atau Martin Luther King Jr., yang telah
mengajarkan solidaritas, cinta, dan kasih sayang (Alkhajar, 2014: 65).
Namun, apa jadinya bila kekerasan malah sengaja diciptakan, bahkan diolah menjadi sebuah komoditas yang dapat di-jual dan laku di pasar? Sekali lagi orien-tasi pasar sebagai alasan utama berperan di sini. Tidak dapat dimungkiri bahwa media massa modern kerap menjadikan kekerasan sebagai barang dagangan. Ke-kerasan itu dikonstruksi, dan didekon-truksi untuk dapat diambil serta diangkat menjadi komoditas baik menjadi sebentuk bacaan ataupun tontonan.
Hal ini dapat dikatakan sebagai proses bersenyawanya kapitalisme dan media se-
009-[Eka Nada Shofa] Kekerasan Media.indd 124 4/24/2014 10:45:13 AM
Kapitalisme, Industri Hiburan, dan Masyarakat Tontonan EKA NADA SHOFA ALKHAJAR 125
hingga apapun dapat direduksi, dikemas serta disajikan sebagai hiburan dan ton-tonan. Hal ini senada dengan pandangan Gerald Sussman (1997: 34-35) yang menya-takan bahwa realitas yang terjadi saat ini merupakan sebuah gambaran mengenai industri yang di dalamnya segala sesuatu dapat dikomodifikasikan. Dengan kata lain, semua aspek kehidupan bisa menjadi komoditas menjanjikan bagi pemilik mo-dal. Maka tak salah apa yang dikatakan Jackman (2002) bahwa kita kerap menemui kekerasan, yang tentangnya kita tidak ha-nya menyaksikan atau mengalami secara langsung tetapi juga melalui media. Jadi, dari gejala, hasil amatan dan pandang-an para ahli ini, lalu muncullah istilah ke-kerasan media atau media violence, yang dapat dimaknai sebagai penggambaran ataupun penampilan kekerasan dari suatu sumber media, yang tentunya dapat mem-bawa efek negatif terhadap masyarakat.
Nalar Ekonomi Kapitalis, Komodifikasi dan Konstruksi Sosial
Salah satu kata kunci dari kapitalisme ada-lah keuntungan. Ini adalah sebuah cara pandang sejati yang selalu dijadikan para-digma bagi para pemilik modal yakni men-cari serta memeroleh keuntungan. Karl Marx (dalam Sanderson, 1999) mengurai-kan bahwa kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang memungkinkan be-berapa individu menguasai sumber daya produksi vital yang mereka gunakan untuk memeroleh keuntungan. Nalar ekonomi kapitalis merujuk pada makna yang men-cakup pengertian bahwa produksi dalam suatu pasar memiliki tujuan akhir yang memungkinkan produsen memeroleh ke-untungan yang sebesar-besarnya.
Kapitalisme dan komodifikasi meru-pakan jalinan yang erat. Jalinan ini akan senantiasa menghasilkan suatu komoditas
yang dapat dijual, dan disajikan ke pasar. Kapitalisme merupakan ruh sementara komodifikasi merupakan cara atau proses yang dijalankan. Merujuk pada Webster’s New World Encyclopedia (1992), komodifi-kasi memiliki akar kata ‘komoditas’ yakni ‘something produced to sale’. Pengertian ini menggambarkan komoditas merupakan suatu objek.
Merujuk pada Barker (2004), komodi-fikasi dapat dimaknai sebagai proses ke-tika objek, kualitas, dan penanda diubah menjadi komoditas yang tujuan utamanya adalah untuk dijual atau berorientasi pasar. Sementara itu, Vincent Mosco mengatakan bahwa komodifikasi merupakan suatu cara kapitalisme untuk mengakumulasi-kan modal. Dengan kata lain, komodifikasi adalah suatu transformasi atau perubahan dari nilai fungsi atau nilai guna menjadi nilai tukar (Mosco, 2009). Berpijak pada Stuart Hall, media massa merupakan in-strumen paling penting dari kapitalisme (Lury, 1996). Media massa memiliki logika tersendiri dalam menangkap “realitas”. Kekerasan melalui media massa ditang-kap untuk kemudian dihadirkan kembali sebagai bentuk komoditas. Hal ini senada dengan Inglis (1990), yang menuturkan bahwa kapitalisme era modern mengada-kan suatu industrialisasi terhadap area ke-hidupan yang tidak terbayangkan, namun tentu saja dengan logika mencari dan pe-menuhan pasar-pasar baru, termasuk di antaranya industrialisasi kekerasan. Lebih dari itu, Baudrillard dalam bukunya In the Shadow of the Silent Majorities (1983), men-jelaskan bahwa media memiliki logikanya sendiri terutama mengenai kemampuan-nya memproduksi “realitas kedua”. Reali-tas ini tidak dapat lepas dari berbagai ke-pentingan yang ada termasuk di dalamnya adalah pertimbangan mengenai orientasi keuntungan modal.
009-[Eka Nada Shofa] Kekerasan Media.indd 125 4/24/2014 10:45:13 AM
126 Kapitalisme, Industri Hiburan, dan Masyarakat Tontonan VOL II, 2014
Oleh karena itu, berbagai berita, teks, atau diskursus media yang hadir di hadap-an khalayak bukan merupakan suatu yang netral dan otonom pada dirinya, melaink-an realitas baru yang dihasilkan media me-lalui apapun itu bentuknya baik jurnalisme, surat kabar, film, televisi dan sebagainya.
Berpedoman pada uraian di atas, maka penulis dapat mengatakan bahwa kekeras-an dalam media merupakan sebentuk kon-struksi sosial dari berbagai pihak yang terlibat di belakangnya. Konstruksi sosial ini merujuk pada pandangan Berger dan Luckmann (1966), yang erat kaitannya de-ngan kesadaran manusia terhadap realitas sosial itu. Dengan kalimat lain, kesadaran merupakan bagian paling penting dalam konstruksi sosial.
Bagi kapitalisme, imaji kekerasan men-jadi suatu bahan yang potensial untuk di-jual kepada khalayak tentu saja dengan terlebih dahulu melakukan konstruksi so-sial terhadap kekerasan tersebut. Semua dibentuk sedemikian rupa agar dapat disa-jikan kepada pasar dalam bentuk-bentuk baru yang seolah-olah hal tersebut memi-liki alasan yang meyakinkan untuk disaji-kan. Dalam tataran ini, hal yang berbahaya tentu ketika kapitalisme mampu membeli dunia kesadaran sehingga menyebabkan realitas kekerasan tadi seakan menjadi ses-uatu yang biasa dan wajar adanya. Kita pun asyik larut dalam menikmati serta mengonsumsi kekerasan yang disajikan oleh media.
Mengenai hal ini, Chomsky (1997) pernah mengingatkan bahwa informasi atau fakta – termasuk di sini mengenai ke-kerasan yang ditampilkan di media – han-yalah hasil olahan semata yang tentunya sangat tergantung pada bagaimana orang di balik media melakukan kerja-kerjanya. Jika orang di balik media merupakan ka-langan yang berorientasi kepada modal, maka arah kerjanya adalah mendapatkan keuntungan dari apa yang diolahnya.
Industri Hiburan dan Masyarakat Tontonan
Berbagai materi dan aksi kekerasan dalam media kerap kali kita temui. Kekerasan menjelma ke dalam bentuk apapun yang mungkin untuk dibuat. Muaranya tak lain adalah untuk dapat dilempar ke pasar. Ke-tika dunia kesadaran berhasil dibeli oleh kapitalisme, maka sejatinya “darah” kapi-talisme telah mengalir ke segenap relung kehidupan sehingga cepat atau lambat akan menumpulkan daya kritis dari kha-layaknya.
Dengan maraknya muatan kekerasan yang diangkat oleh media khususnya tele-visi dan film dengan berbagai bentuk sajian-nya, penulis menengarai gejala kekerasan yang terasa semakin kental. Banyak sajian yang kerap atau bahkan sengaja disajikan tidak sebagai informasi yang konstruktif melainkan lebih menyiratkan harapan akan modal atau keuntungan yang tidak lain adalah bisnis. Khususnya mengenai televi-si, Fiske (1991: 55-56) pernah meng ingatkan bahwa televisi bukan sekadar memproduk-si dan mereproduksi komoditas melainkan yang lebih penting lagi adalah modal. Tele-visi tidak memproduksi realitas objektif tetapi memproduksi modal. Begitu halnya dengan film, Dominic Strinati (1995) meng-kritik bahwa film merupakan produk bu-daya yang telah menjadi produk komersil yang sudah tercerabut dari realitas sosial-nya. Tidak dapat dimungkiri, kekerasan di media telah menjelma menjadi sebuah bu-daya populer yang sarat mempertontonk-an makna hiburan sehingga menggeser makna sejati dari kekerasan yang berwajah menye ramkan. Hal ini dapat dirasional-isasi karena dalam dunia kapitalisme, hi-buran dan budaya telah berubah menjadi komoditas bagi dunia industri.
Kekerasan kini menjadi semacam in-dustri hiburan yang dikemas, diproduksi ulang, dikonstruksi dan disajikan. Melihat
009-[Eka Nada Shofa] Kekerasan Media.indd 126 4/24/2014 10:45:13 AM
Kapitalisme, Industri Hiburan, dan Masyarakat Tontonan EKA NADA SHOFA ALKHAJAR 127
realitas ini, dapat diasumsikan bahwa ke-kerasan mungkin merupakan suatu jalan paling praktis untuk mendapatkan perha-tian khalayak serta mencari keuntungan. Namun, hal yang patut diwaspadai ada-lah efeknya ketika hal tersebut hanya akan membuat suatu masyarakat menjadi rapuh sekaligus rusak. Jika hal ini tetap berlang-sung, maka benarlah asumsi awal tadi yaitu bahwa kekerasan merupakan salah satu formula yang ampuh dalam dunia tontonan.
Apabila kekerasan sudah lazim menja-di objek konsumsi ataupun objek tontonan, maka tak salah apabila akan muncul suatu masyarakat tontonan. Debord (1994) menu-turkan bahwa masyarakat tontonan adalah suatu masyarakat yang di dalamnya setiap sisi kehidupan menjadi komoditas, dan se-tiap komoditas tersebut menjadi tontonan. Oleh karena itu, tak heran apabila di dalam masyarakat tontonan, kekerasan menjadi objek tontonan itu sendiri.
Industri hiburan dapat dikatakan me-mang sarat dengan “manipulasi” untuk mendatangkan hal yang bersifat ekonomi bahkan melalui hal yang dapat dikatakan buruk sekalipun seperti kekerasan. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Hans Magnus Enzensberger (Dyer, 1992: 25):
The electronic media do not owe their irresistible power to any sleight-of-hand but to the elemental power of deep social needs that come through even in the present depraved form of these media.
Sebagaimana diutarakan sebelumnya, televisi dan film merupakan bagian dari media yang memiliki pengaruh yang demikian besar bagi masyarakatnya (Mc-Quail, 1987). Sementara itu, Abdullah meng-ungkapkan secara spesifik bahwa televisi merupakan kekuatan terpenting dewasa ini (2010: 59). Bahkan, televisi dapat ber-peran sebagai energi pembangun bangsa (Alkhajar, 2011).
Televisi membuat kita mampu melihat dan mengetahui berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dan menyuguh-kannya kepada kita tanpa harus bersusah payah. Selain itu, televisi memiliki salah satu fungsi yang luar biasa yakni: alih bu-daya (transmission of the culture) atau alih warisan sosial dari satu angkatan ke ang-katan berikutnya (transmission of the social heritage from one generation to the next) (Black dan Whitney, 1988).
Namun, fungsi yang baik ini akan men-jadi berbahaya apabila digunakan tidak se-cara semestinya, misalnya ketika televisi malah kerap menayangkan muatan ke-kerasan. Belum lagi ditambah dengan logi-ka industri yang menempatkan kekerasan sebagai komoditas. Melalui ideologi kapi-talisme, kekerasan kerap disuntikkan ke dalam berbagai program acara dalam tele-visi dengan tujuan keuntungan yang sebe-sar-besarnya.
Akan tetapi, seperti itulah realitasnya apabila kita ingin meniliknya dalam kon-teks Indonesia. Berbagai program acara semisal sinetron baik dewasa dan remaja, acara komedi, dan sebagainya kerap sekali mengangkat kekerasan sebagai isi serta menu dengan berbagai kemasan pesan yang dihadirkan kepada khalayak. Alasan-nya dalam industri hiburan, apapun dapat disajikan tak lain demi meraih keuntungan (Alkhajar, 2014: 7-8).
Keith Tester pun mengkritik perihal proses produksi yang senantiasa memper-timbangkan kepentingan material (modal) dan hiburan semata. Ia geram dan menyin-dir bahwa kondisi demikian layaknya ko-mersialisasi “sampah” yang berbahaya kar-ena memiliki dampak serius pada kualitas hidup manusia (Tester, 1994). Apabila hal tersebut dibiarkan terus berlangsung maka sejatinya proses dehumanisasi tengah ber-langsung secara masif di tengah khalayak masyarakat. Hal ini tentu sangat disayang-
009-[Eka Nada Shofa] Kekerasan Media.indd 127 4/24/2014 10:45:13 AM
128 Kapitalisme, Industri Hiburan, dan Masyarakat Tontonan VOL II, 2014
kan karena televisi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi sebagian besar masyarakat. Mulai dari kota hingga pelo-sok desa, rumah hunian liar, pinggiran kota bahkan masyarakat yang tinggal di bawah jembatan layang (Wirodono, 2005).
Tidak berbeda dengan televisi, muatan kekerasan juga kerap menjadi menu dalam berbagai film di Indonesia. Kekerasan da-lam kedua media tersebut kerap muncul baik berupa kekerasan secara langsung, tidak langsung, kekerasan visual maupun kekerasan simbolik yang diperankan oleh tokoh-tokoh yang hadir di dalam cerita dari media tersebut. Sudah jamak diketahui bahwa televisi dan film memiliki kelebihan dibandingkan media lainnya dalam hal au-dio visual sehingga pesan-pesannya, ter-masuk yang bermuatan kekerasan, begitu mudah ditangkap oleh khalayak pemirsa atau penontonnya.
Khususnya mengenai film, Christian Metz menyatakan bahwa kita mampu de-ngan mudah memahami film karena media ini telah menjelma menjadi bahasa kehidu-pan. Film mampu menyampaikan sebuah cerita yang sangat menarik. Metz menegas-kan demikian,
We understand a film not because we have a knowl-edge of its system: rather we achieve an understand-ing of its system because we understand the film put another way its not because the cinema its language that it can tell such fine stories, but rather it has be-come language because it has told such fine stories (Metz, 1974: 47).
Akan tetapi, realitas yang memuat ke-kerasan dan kerap dijadikan komoditas un-tuk dijual tidak hanya berlaku di Indonesia melainkan berlaku di mancanegara. Seba-gai contoh, eksplorasi berupa kengerian serta kekerasan berupa pembunuhan para pelacur London yang dilakukan oleh Jack The Ripper. Sosok ini pun sejatinya masih menjadi misteri namun nyatanya tetap di-
lakukan upaya komodifikasi untuk mem-bentuknya menjadi semacam komoditas yang laku untuk dijual. Kisah ini diangkat dalam film From Hell (2001) yang disutra-darai Albert Hughes dan Allen Hughes (Alkhajar, 2012: 46-47).
Hal ini setidaknya membuktikan bah-wa logika kapitalisme telah menghegemoni dan menyusup ke berbagai belahan dunia serta sendi kehidupan melalui fenomena globalisasi, yang beberapa kata kuncinya termasuk ekonomi dan budaya. Ferguson mendefinisikan globalisasi sebagai: “both a journey and destination: it signifies an histori-cal process of becoming, as well as an economic and cultural result; that is arrival at the global-ized state” (Ferguson, 2002: 239).
Efek Kekerasan Media
Hal yang dikhawatirkan dari berbagai saji-an kekerasan di media adalah terbentuknya suatu pemahaman bahwa kekerasan meru-pakan hal yang biasa karena semakin se-ring kekerasan ditampilkan, maka akan menimbulkan suatu persepsi bahwa ke-kerasan adalah lumrah, bahkan telah me-lekat dalam kehidupan masyarakat. Kamla Bhasin (1994) pernah menuturkan bahwa meningkatnya kekerasan dalam media akan membunuh rasa kepékaan (sensibili-tas) masyarakat, dan membuat kekerasan itu sendiri menjadi jalan hidup masyara-kat. Tak heran, apabila masyarakat kian tak segan untuk memilih cara atau pendekatan kekerasan guna menyelesaikan suatu per-masalahan. Bhasin mewanti-wanti sebagai berikut
Media have an element of propaganda and use monologue. They are wiping out dialogue, discus-sion, people’s participation and weakening civil society. People are becoming passive consumers of news and views rather than active citizens. Increas-ing violence in media is killing people’s sensibilities and making violence a way of life (Bhasin, 1994: 4-7).
009-[Eka Nada Shofa] Kekerasan Media.indd 128 4/24/2014 10:45:13 AM
Kapitalisme, Industri Hiburan, dan Masyarakat Tontonan EKA NADA SHOFA ALKHAJAR 129
Apa yang diungkapkan Bhasin di atas terasa tepat dan aktual karena kita tahu bahwa proses mengonsumsi media itu ten-tu bukan sekadar melihat, menonton atau menyorotkan mata ke media an sich me-lainkan dalam proses tersebut terkan dung berbagai dimensi yang kaya rupa serta warna. Oleh karena itu, penayangan be-ragam tindak kekerasan dengan ber bagai format dan intensitas yang sering tentu-nya malah dapat menciptakan realitas ke-kerasan dalam masyarakat.
Menurut pandangan teori pembela-jaran sosial (social learning theory), seperti model yang diajukan oleh Albert Bandura dari Stanford University dengan eksperi-men boneka Bobo pada 1961 (Bandura, dkk. 1961), masyarakat dapat belajar dari apa yang ditampilkan media semisal mo-dus operandi kriminalitas hingga cara-cara anarkis kekerasan dalam upaya menye-lesaikan berbagai masalah yang ada. Kita melihat bagaimana masyarakat melakukan aksi bakar hidup-hidup terhadap pelaku kriminalitas atau memukulinya hingga meninggal dunia.
Realitas tersebut sangat memprihatin-kan. Namun, tampaknya ideologi keuntung -an kerap menjadi pembenaran sebab di manapun media terus-menerus menayang-kan serta menyajikan kekerasan melalui isi dan kemasan yang memang menjadi kekuatan utama media. Media lupa bah-wa mereka termasuk institusi sosial yang turut berkewajiban memberikan wahana pendidikan terhadap masyarakatnya mela-lui informasi yang disajikan. Media telah berubah menjadi pencipta kekerasan, bah-kan dapat dikatakan sebagai penyebar ke-kerasan kepada masyarakat yang menjadi khalayaknya. Hal ini senada dengan apa yang dituturkan Anderson and Bushman (2002) bahwa tayangan kekerasan di me-dia akan memberikan efek yang signifikan
bagi masyarakat, terutama berkaitan de-ngan peningkatan agresi masyarakat.
Bahkan, merujuk kepada Wertham (1968) media tak ubahnya telah menjadi “school of violence”. Sekolah-sekolah ke-kerasan ini menampilkan kekerasan secara aktual dan visual dengan telanjang serta vulgar, yang biasanya kerap dilakukan oleh media elektronik. Media yang ideal-nya menjadi wajah saluran informasi kini telah berubah menjadi saluran pendidik-an kekerasan. Jika sudah demikian, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa berbagai wajah kekerasan kini telah disosialisasikan melalui dunia hiburan, film, iklan, lawakan atau dagelan di televisi. Jika tidak segera dilakukan pembenahan, maka dikhawatir-kan akan tercipta suatu budaya yang me-nyeramkan, yakni culture of violence yang di dalamnya kekerasan menjadi “bahasa” sehari-hari. Sekali lagi, ketika bisnis dan modal menjadi ideologi serta logika media maka tak heran akan terjadi penumpulan kepekaan terhadap kekerasan itu sendiri. Kekerasan tidak lagi dianggap sebagai hal yang luar biasa.
Storey (2009) pernah mengungkapkan bahwa ideologi menyiratkan adanya pe-nopengan, penyimpangan serta penyem-bunyian realitas tertentu. Ideologi akan memengaruhi teks dan praktik yang di-lakukan para pemilik modal untuk mema-nipulasi kesadaran demi mengeruk keun-tungan sebesar-besarnya.
Efek sajian kekerasan ini, di satu sisi, memang menjanjikan keuntungan yang luar biasa besar. Di sisi lain, efek terberat-nya adalah menghasilkan masyarakat yang rapuh serta rusak secara bangunan sosial. Efek lanjutannya lambat laun adalah ke-hancuran sebuah bangsa. Oleh karena itu, bukan saatnya lagi televisi dan film menya-jikan tayangan dan tontonan yang kerap hanya menawarkan mimpi, kekerasan ser-ta seks (Alkhajar, 2009: 27).
009-[Eka Nada Shofa] Kekerasan Media.indd 129 4/24/2014 10:45:13 AM
130 Kapitalisme, Industri Hiburan, dan Masyarakat Tontonan VOL II, 2014
Merujuk pada Latif (2010), media pada umumnya kini harus mulai memainkan peranan konstruktif yakni mengarahkan, membimbing serta memengaruhi sese-orang ke dalam pemahaman dan proses be-lajar sosial yang baik, dengan menyediakan acara-acara yang informatif, sehat, mengin-spirasi dan mencerahkan. Media seharus-nya tidak memainkan peranan destruktif dengan menampilkan muatan kekerasan serta berbagai hal lain yang akan mencipta-kan keburukan di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan media dengan segala daya tarik, daya jangkau serta efektivitasnya mempunyai kekuatan yang maha dahsyat untuk memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat.
Penutup
Menampilkan kekerasan dalam media se-cara membabi-buta tanpa melakukan fil-terisasi yang baik merupakan tindakan yang harus dihindari, apalagi menjadikan kekerasan sebagai bentuk komoditas un-tuk dijual ke khalayak sebagai pasar un-tuk dikonsumsi. Hal terakhir ini jelas-jelas merupakan suatu bentuk pendangkalan kemanusiaan. Tentunya, kita tidak meng-harapkan media ikut memproduksi, dan mengawetkan kekerasan di masyarakat melalui berbagai sajiannya. Terlebih, pendi-dikan literasi media belum memiliki gaung keras di negeri ini. Agenda pendidikan literasi sepertinya belum masif, dan ma-suk dalam ranah kebijakan yang ada. Oleh karena itu, para pelaku media harus mahir berikhtiar untuk berhenti menampilkan kekerasan baik di tayangan televisi mau-pun film meng ingat keburukan-keburuk-annya seperti sudah diuraikan di atas. Para pelaku media tidak boleh malah terjebak memopulerkan kekerasan itu sendiri kepa-da masyarakat. Hal semacam ini membu-tuhkan kemauan keras, ditopang dengan
pelbagai regulasi mengenai isi, dan mua-tan yang boleh ditayangkan atau tidak, yang sudah jelas dan legitimate. Sudah se-layaknya media mematuhi rambu-rambu serta peraturan yang ada demi kehidupan masyarakat yang berkualitas. Media yang berkualitas akan berdampak signifikan bagi terciptanya masyarakat yang berkualitas.
Daftar Pustaka
Abdullah, I. (2010). Konstruksi dan Reproduk-si Kebudayaan. Cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Alkhajar, E.N.S. (2009). “Televisi, Hipereal-itas Remaja dan Media Literacy,” dalam Eka Nada Shofa Alkhajar, et.al. Anomi Media Massa. Surakarta: Pascasarjana Ilmu Komunikasi UNS.
_____. (2011). “Televisi dan Energi Pem-bangun Bangsa,” Komunikasi Massa, 4(1): 107-118.
_____. (2012). Manusia-Manusia Paling Mis-terius di Dunia. Solo: Bukukatta.
_____. (2014). Media, Masyarakat dan Realitas Sosial. Surakarta: Sebelas Maret Univer-sity Press.
Anderson, C.A. dan Bushman, B.J. (2002). “The Effects of Media Violence on Soci-ety,” Science, 29 March: 2377-2379. Artikel bisa diakses di <http:/ /www.psychology.iastate.edu/faculty/caa/abstracts/2000-2004/02AB2.pdf>.
Bandura, A., Dorothea Ross, dan Sheila A. Ross. (1961). “Transmission of Aggres-sion through Imitation of Aggressive Models,” Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-582. Artikel bisa di-akses di http://psychclassics.yorku.ca/Bandura/bobo.htm
Barker, C. (2004). The SAGE Dictionary of Cultural Studies. London: Sage Publica-tions.
Baudrillard, J. (1983). In the Shadow of Silent Majorities. New York: Semiotext(e).
009-[Eka Nada Shofa] Kekerasan Media.indd 130 4/24/2014 10:45:14 AM
Kapitalisme, Industri Hiburan, dan Masyarakat Tontonan EKA NADA SHOFA ALKHAJAR 131
Berger, P. L. dan Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the
Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books.
Bhasin, K. (1994). “Women & Communi-cation Alternatives: Hope for the Next Century”. Media Development, 41(2): 4-7.
Black, J. dan Whitney, F.C. (1988). Introduc-tion to Mass Communication. Second Edition. Iowa: Wm. C. Brown Publis-her.
Chomsky, N. (1997). Media Control: The Spec-tacular Achievement of Propaganda. New
York: Seven Stories Press.Debord, G. (1994). The Society of the Specta-
cle. New York: Zone Books.Dyer, R. (1992). Only Entertainment. Lon-
don: Routledge.Ferguson, M. (2002). “The Mythology
About Globalization” dalam McQuail, D. (ed.) McQuail’s Reader in Mass Communication Theory. London: Sage Publication.
Fiske, J. (1991). “Postmodernism and Televi-sion,” dalam Curran, J. dan Gurevitch, M. (eds). Mass Media and Society. Lon-don: Edward Arnold.
Inglis, F. (1990). Media Theory: An Introduc-tion. Oxford: Basil Blackwell.
Jackman, M.R. (2002). “Violence in Social Life,” Annual Review of Sociology, 28(1): 387-414.
Latif, Y. (2010). “Peran Media dalam Pen-didikan Karakter,” dalam As’ad Said Ali, et.al. Nasionalisme dan Pembangu-
nan Karakter Bangsa. Yogyakarta: PSP Press.
Lury, C. (1996). Consumer Culture. New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press.
McQuail, D. (1987). Mass Communication-Theory: An Introduction. London: Sage
Publications.Metz, C. (1974). Film Language. New York:
Oxford University Press.Mosco, V. (2009). The Political Economy of
Communication. Second edition. London: Sage.
Salmi, J. (1993). Violence and Democratic Soci-ety. London: Zed Books.
Sanderson, S.K. (1999). Macrosociology: An Introduction to Human Societies. Fourth Edition. New York: Harper & Row.
Storey, J. (2009). Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. Fifth Edition. London: Longman.
Strinati, D. (1995). An Introduction to Theories of Popular Culture. London: Routledge.
Sussman, G. (1997). Communication, Technol-ogy, and Politics in the Information Age. Thousand Oaks, California: Sage Publi-cation.
Tester, K. (1994). Media, Culture and Moral-ity. London: Routledge.
Webster’s New World Encyclopedia. (1992). New York: Prentice Hall.
Wertham, F. (1968). “School of Violence,” dalam Larsen, O.N. (ed.). Violence and the Mass Media. New York: Harper & Row.
Wirodono, S. (2005). Matikan TV-Mu. Yog-yakarta: Resist Book.
009-[Eka Nada Shofa] Kekerasan Media.indd 131 4/24/2014 10:45:14 AM
Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, hal 132-135ISSN 2302-5719
Vol II, Nomor 1
[Resensi Buku]Bukan Sekedar Biografi: Menyelami Sisi Humanis Driyarkara
JUMAR SLAMET
Staf Perpustakaaan Universitas Sanata Dharma YogyakartaSurel: [email protected]
Diterima: 12 Februari 2014Disetujui: 24 Maret 2014
Judul : Driyarkara Si Jenthu: Napak Tilas Filsuf Pendidik (1913-1967)Penulis : Frieda TreuriniPenerbit : Penerbit Buku KompasCetakan : 2013Tebal : xxxvi + 252 halamanISBN : 978-979-709-755-4
(sumber gambar halaman sampul buku:http://stat.ks.kidsklik.com/statics/files/2013/11/13853733651391855807_300x400.jpg)
Buku dengan sampul warna hijau ini berisi biografi dan perjalanan hidup Driyarkara, seorang tokoh filsafat dan pendidikan di Indonesia. Beliau merupakan seorang to-koh yang memberi sumbangan pemikiran bagi Indonesia tentang Pancasila. Berbagai kesaksian dan kesan banyak disampaikan dalam buku ini. Pada awal tulisan yang
digarap oleh Frieda Treurini ini pembaca diajak sekilas menengok tentang apa yang dikatakan beberapa tokoh seperti Soed-jatmoko, Fuad Hasan, Arif Budiman, dan Franz Magnis-Suseno.
Jenthu--demikian nama Driyarkara ke-cil akrab dipanggil yang artinya ‘gemuk namun kekar’--adalah putra bungsu dari
010-[Jumar Slamet] Bukan Sekedar Biografi_ Menyelami Sisi Humanis Driyarkara.indd 132 4/24/2014 10:47:39 AM
Bukan Sekedar Biografi: Menyelami Sisi Humanis Driyarkara JUMAR SLAMET 133
Atmasenjaya dan Sinem, seorang petani yang mengandalkan hasil bumi dari tanah pegunungan Kedunggubah yang kering kerontang, sebuah desa terpencil di antara pegunungan Menoreh di Purworejo. Gam-bar tapal batas desa bertuliskan Kedung-gubah Gumregah yang disertai pengertian dalam bahasa Jawa (hlm. 5) seakan sengaja dihadirkan Frieda untuk menjelaskan sosok Jenthu dengan jiwa yang gumregah (bang-kit) dan bersemangat. Udara sejuk alam pegunungan, sebuah kedung atau waduk dengan air yang terlihat bening, dan kem-bang Suweg, sejenis bunga bangkai, kian menggambarkan sulitnya kehidupan dan mata pencaharian warga desa. Frieda me-nyuguhkan hasil penyelisikannya tentang silsilah keluarga Driyarkara untuk meleng-kapi buku ini.
Dikisahkan secara runtut perjalanan awal pendidikan si Jenthu dimulai semen-jak menempuh pendidikan di HIS, Pur-worejo, dengan nama Suhirman, kemudian berlanjut ke kota Malang, dan di sanalah akhirnya ia banyak membuka cakrawala dan pengetahuannya semakin luas pasca-pertemuannya dengan dua padri Yesuit dari Austria, yaitu Pater Henri van Driess-che dan Pater J.B. Prennthaler. Kedua sosok rohaniwan ini menguatkan niat Suhirman untuk menempuh pendidikan tinggi hing-ga mengabdikan dirinya sebagai rohani-wan. Proses Suhirman muda untuk me-nemukan dan melipatgandakan talentanya dimulai di Seminari Kecil di kawasan Ko-tabaru, sekitaran kali Code, Yogyakarta (hlm. 40).
Kemudian, ia menempa pendidikan askese (ulah tapa mati raga) di Girisonta, Ungaran, Semarang, sebagai perwujudan utuh atas pilihannya untuk bergabung se-bagai seorang Yesuit. Serikat Yesus (SY) menjadi wahana bagi pergulatan karya-karyanya. Di sini, Suhirman dikenal de-ngan nama Nicolaus Driyarkara. Pendidik-
an Yesuit yang ditempa, juga studi filsafat di Yogyakarta, membuat sosok Driyarkara menjadi semakin dewasa dan ia menun-jukkan sikap menggembala sebagai wujud hidup kerasulannya. Ia belajar tentang hu-maniora, kebudayaan, filsafat, teologi, dan praktik-praktik kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di masa kekuatan asing se-dang berkuasa di Indonesia.
***
Usai Proklamasi Kemerdekaan RI, jiwa kerasulannya memasuki babak baru. Di Semarang, Driyarkara ditahbiskan menjadi imam Yesuit pada awal tahun 1947 (hlm. 102). Kemudian, ia mulai banyak mem-persembahkan misa di berbagai kota, se-lain tugas hariannya mengajar filsafat di Seminari Tinggi St. Paulus dan di UGM, keduanya terletak di Yogyakarta (hlm. 105). Humanisme Driyarkara kembali terusik tatkala Pemerintah Hindia Belanda ber-usaha kembali menegakkan kekuatannya di Indonesia, sementara pada saat yang bersamaan ia ditugaskan pembesar Yesuit untuk belajar teologi di negeri penjajah, Be-landa. Hal ini sungguh memicu pergulatan batin dalam diri Driyarkara.
Driyarkara adalah pribadi yang unggul dan supel. Ia berusaha mengatasi kecema-san atas negerinya yang sedang meng alami situasi sulit. Di negeri Belanda, Driyarka-ra tetap mengikuti perkembang an poli-tik negeri kelahirannya. Setelah melewati pergulatan batin, ia mengikuti pemilihan umum (pemilu) parlemen Belanda dan me-mutuskan untuk mendukung Katholieke Volkspartij (KVP) --- partai kontestan pe-milu yang berpandangan Indonesia sepa-tutnya menjadi negara yang berdiri sendiri namun tetap ada keterikatan de ngan ne-geri Belanda. Driyarkara sangat terharu ke-tika partai yang didukungnya memenangi pemilu. Driyarkara meyakinkan dirinya
010-[Jumar Slamet] Bukan Sekedar Biografi_ Menyelami Sisi Humanis Driyarkara.indd 133 4/24/2014 10:47:39 AM
134 Bukan Sekedar Biografi: Menyelami Sisi Humanis Driyarkara VOL II, 2014
bahwa kekuasaan Belanda atas Indonesia akan sirna (hlm. 114).
Suatu ketika, ia dikagetkan oleh sebuah berita mengenai Yogyakarta diserbu Belan-da. Peristiwa ini sangat menyentuh hatinya, namun ia berusaha tetap tenang. Peristiwa tragis gugurnya serangkaian perunding-an Indonesia-Belanda yang disebabkan ulah Belanda ini mengusik kesadaran serta mentalitas para pemeluk Katolik, baik yang berkebangsaan Belanda maupun Indone-sia. Driyarkara kemudian berpandangan bahwa Republik Indonesia dapat dilenyap-kan, dikuasai, atau dijadikan apapun, akan tetapi Republik sebagai semangat masihlah tetap dan akan terus melahirkan diri lagi demi negara yang merdeka. Driyarkara mencatat hasil perenungannya sebagai berikut, “Janganlah kita putus asa. Ini me-rupakan proses menuju kesadaran bangsa manusia. Sadar akan kebenaran dan kebai-kan, sadar akan hidup sejati” (hlm. 117).
Pengalaman perjalanan pendidikan Driyarkara semakin sempurna tatkala ia menyelesaikan pendidikan lanjut olah ba-tin dan askese (masa Tersiat) di Drongen, Belgia, dan doktor filsafat dari Universi-tas Gregoriana, Italia. Melalui disertasi berjudul Participationis Cognitio In Existen-tia Dei Percipienda Secundum Malebranche utrum Partem Habeat (yang berarti “Peran-an Pengertian Partisipasi dalam Pengertian tentang Tuhan menurut Malebranche”), Driyarkara diangkat sebagai doktor dengan hasil cum laude. Sekembalinya ke Yogyakar-ta, ia kembali disibukkan dengan tugas-tu-gas pelayanan umat. Selain itu, Driyarkara kembali aktif mengajar dan meneruskan hobinya untuk menulis di banyak media.
Pada 17 Desember 1955, Driyarkara mempersembahkan sambutan pertamanya sebagai pimpinan PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru) Sanata Dharma di hadap-an jajaran pemerintah dan pejabat berba-gai lembaga, khususnya pejabat struktural
gereja keuskupan. PTPG mengemban misi untuk mendidik kaum muda guna mema-hami pentingnya pendidikan guru yang memiliki kepribadian yang luhur, memiliki semangat membangun, mengerti nilai-nilai luhur Pancasila, dan berwawasan kebu-dayaan lintas bangsa.
Driyarkara banyak berkecimpung dalam kegiatan sosial yang digerakkan oleh ba-nyak organisasi yang berasaskan Pancasila. Ia juga getol menyebarkan pemikiran-pe-mikiran filosofis ke khalayak melalui Ra-dio Republik Indonesia (RRI). Berkat kerja, pemikiran, hingga pengembaraan pela-yanannya ke berbagai negara, seorang Dri-yarkara dikenal luas oleh berbagai kalang-an baik di dalam maupun di luar negeri. Selain menjadi guru besar luar biasa dan tamu, antara lain di UI, Universitas Hasan-uddin (Makassar, Sulawesi Selatan), ALRI, dan Saint Louis University (Missouri, Amerika Serikat), Driyarkara juga sempat mengajar di SESKOAL dan SESKOAD. Driyarkara pun tercatat sebagai wakil ro-haniwan di MPRS sejak tahun 1960. Peran besar Driyarkara dalam memberikan lan-dasan pemikiran dan membina pendidikan di Indonesia diakui oleh Sarino Mangun-pranoto, Menteri Pendidikan dan Kebu-dayaan kala itu (1956 – 1957). Wakil Ketua MPRS (1966 – 1971), Melanchton Siregar, juga menyatakan bahwa Driyarkara adalah pejuang yang gigih mempertanggung-jawabkan isi Pancasila dan UUD 1945 se-bagai falsafah dan penghargaan hak asasi (hlm. 189).
***
Sepertiga halaman terakhir dari buku setebal 252 halaman ini mengisahkan pengabdian Driyarkara sebagai anak bang-sa. Banyak catatan, pesan-pesan tentang keprihatinan, dan hasil pergulatan batin Driyarkara pasca-peristiwa G30S. Sang
010-[Jumar Slamet] Bukan Sekedar Biografi_ Menyelami Sisi Humanis Driyarkara.indd 134 4/24/2014 10:47:39 AM
Bukan Sekedar Biografi: Menyelami Sisi Humanis Driyarkara JUMAR SLAMET 135
guru besar filsafat yang menguasai berba-gai bahasa itu menyelesaikan ziarahnya di dunia setelah beberapa waktu dirawat di RS. St Carolus. Dalam beberapa halaman akhir buku ini, Frieda menambahkan fea-ture kawan-kawan dan kolega Driyarkara, dan sekilas hikayat diarium (catatan keja-dian) Driyarkara yang banyak mewarnai buku ini.
Driyarkara telah banyak menelurkan pemikiran-pemikiran sebagai cendekiawan dan pendidik. Ia berwawasan jauh ke de-pan. Namanya tak hanya banyak dikenang, tetapi pemikirannya telah memberikan sumbangsih positif bagi warga bangsa. Se-menjak buku antologi gagasan Driyarkara diterbitkan, namanya kian menghiasi me-dia dan diskusi-diskusi di berbagai kalang-an. Pandangannya berhasil memengaruhi banyak orang, terutama di dunia pendidi-kan. Frieda telah menghadirkan sebuah inspirasi dengan menulis buku ini. Buku yang berjudul lengkap Driyarkara Si Jenthu: Napak Tilas Filsuf Pendidik tidak saja indah karena fisiknya, namun kehadiran sosok Jenthu pemuda asal Kedunggubah yang tumbuh menjadi Driyarkara hingga usia 54 tahun; selama 19 tahun sang profesor ber-hasil mengemban misi dan membawa pe-mahaman yang lebih luas dan mendalam
tentang nasionalisme, pendidikan dan hu-manisme.
Sebagai catatan atas buku bagus ini, Diarium Driyarkara sangat kental mewar-nai penulisan buku ini sehingga istilah “napak tilas” sebagaimana digunakan se-bagai judul belumlah sepenuhnya tercapai. Harapan “menapaki petilasan” melalui tulisan Frieda banyak tidak terjawab. Kha-layak pembaca tentu berharap mendapati lebih banyak pernyataan-pernyataan dan atau visualisasi perbandingan terkini de-ngan pengalaman Driyarkara dari lebih banyak narasumber, semisal kegiatannya di MPRS, sebagai anggota Dewan Per-timbangan Agung (1965 – 1966), di kota Malang, di Universitas Gregoriana, di Saint Louis University, atau dari tempat-tempat ia meng ajar dan singgah. Namun demiki-an de ngan kekuatan besar Romo Danu, –seorang Yesuit yang menjadi murid ke-sayangan Sang Filsuf atau si Meteor dari Menoreh ini, --yang memiliki segudang tal-enta, Frieda Treurini berhasil meramu per-jalanan napak tilasnya dengan catatan har-ian “Diari um” dan menyuguhkan secara runut nan jeli tentang sosok Driyarkara, pribadi gigih yang “bukan filsuf belaka.” Inilah khazanah perjuangan bangsa.
010-[Jumar Slamet] Bukan Sekedar Biografi_ Menyelami Sisi Humanis Driyarkara.indd 135 4/24/2014 10:47:39 AM
PEDOMAN PENULISAN JURNAL ULTIMA HUMANIORA
1. Artikel berupa hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun kajian pustaka atau yang setara dengan hasil penelitian, serta kajian konseptual di bidang rumpun ilmu humaniora, yaitu: Teologi, Filsafat, Hukum, Sejarah, Filologi, Bahasa, Budaya & Linguistik (Kajian bahasa), Kesusastraan, Kesenian, dan Psikologi.
2. Jurnal Ultima Humaniora memberikan perhatian dan porsi yang lebih khusus pada artikel, hasil penelitian, serta kajian konseptual seputar Pancasila dan Kewarganega-raan, Agama dan Religiositas, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris sebagai Bahasa As-ing, Metode Belajar dan Mengajar yang efektif di Perguruan Tinggi, Kepemimpinan dan Kewirausahaan.
3. Jurnal Ultima Humaniora terbit secara berkala, dua kali dalam setahun (Maret dan September).
4. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bila artikel menggu-nakan bahasa Indonesia abstraknya menggunakan bahasa Inggris, sedangkan bila artikel menggunakan bahasa Inggris, abstraknya berbahasa Indonesia
5. Panjang abstrak 150-200 kata, spasi 1, jenis huruf Times New Roman 10pt, ditulis de-ngan huruf miring serta dilengkapi dengan tiga sampai lima kata kunci.
6. Untuk artikel hasil penelitian lapangan, abstrak harus memuat latar belakang dan perumusan masalah,tujuan,metode,hasil atau kesimpulan penelitian
7. Panjang naskah antara 15-25 halaman, ukuran kertas Kwarto (A4), di luar bagan, gambar/foto dan daftar rujukan atau daftar pustaka (referensi)
8. Pengetikan naskah menggunakan program Microsoft Word, spasi 1.5, jenis huruf Times News Roman, 12pt. Marjin kanan-kiri, atas bawah 2.5 cm.
9. Gambar dan Tabela) Gambar yang akan ditampilkan dalam jurnal adalah gambar hitam-putih.b) Bila menginginkan, penulis dapat menyertakan gambar berwarna, namun penu-
lis akan dikenai biaya tambahan untuk pencetakan gambar berwarna tersebut.c) Gambar dan tabel diberi nomor sebagai berikut: Gambar 1, Gambar 2, dst. Tabel
1, Tabel 2, dst.d) Gambar dan tabel yang substansinya sama, ditampilkan salah satu.e) Tabel berbentuk pivot table.
10. Komposisi artikel hasil penelitian : (1) Judul dan sub-judul, (2) Nama Penulis (tan-pa gelar), di bawah nama penulis dicantumkan nama institusi/afiliasi/alumni, (3) abstrak, (4) kata kunci, (5) Pendahuluan (tanpa sub judul), (6) Tinjauan Pustaka/Kerangka Teori , (7) Metodologi Penelitian, (8) Hasil dan Pembahasan (9) Simpulan dan Saran, (10) Daftar Pustaka (hanya memuat kepustakaan yang dirujuk dalam ar-tikel)
11. Komposisi artikel konseptual: (1) Judul dan sub-judul, (2) Nama Penulis (tanpa ge-lar), (3) abstrak, (4) Kata kunci, (5) Pendahuluan (tanpa sub judul), (6) Sub judul- sub judul sesuai kebutuhan, (7) Penutup, (8) Daftar Pustaka (hanya memuat kepustakaan yang dirujuk dalam artikel).
011-pedoman.indd 136 4/24/2014 10:48:07 AM
12. Ucapan terima kasih: Penulis dapat menuliskan ucapan terima kasih kepada indi-vidu, lembaga pemberi dana penelitian, dan sebagainya. Ucapan terima kasih ditu-liskan sebelum Daftar Pustaka.
13. Penulisan sitasi dibuat dengan catatan perut (in-text references, APA style) yang me-muat nama belakang pengarang,tahun penulisan, dan halaman penulisan.Contoh: Satu penulis : (Siapera,2010:49) Dua penulis : (Kanpol dan McLaren, 1995:118) Lebih dari dua penulis : (Lister,dkk,2009:239)
14. Penulisan dalam Daftar Pustaka dapat dilakukan sebagai berikut:
Sumber buku:Kearney, R. (1999). Poetics of Modernity: Toward a Hermeneutic Imagination. New York:
Humanity Books. Killen, M. dan Smetana, J. G. (Tim Editor). (2006). Handbook of Moral Development.
Mahwah, New Jersey (USA) dan London (UK): Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Semi, G., Colombo, E., Camozzi, I. & Frisina, A. (2009). Practices of Difference: Analysing Multiculturalism in Everyday Life. Dalam Amanda Wise dan Selvaraj Velayutham. (Tim Editor). Everyday Multiculturalism (hlm. 66 – 84). Hampshire RG21 6XS (UK) dan New York (USA): Palgrave Macmillan.
Sumber jurnal: Mancini, S. (2009). Imaginaries of Cultural Diversity and the Permanence of the Reli-
gious. Diogenes 56 (4), 3 – 16.
Sumber prosiding seminar: Akbar, A. 2012. Adam, Atlantis, dan Piramida di Indonesia: Antara Fakta Arkeologi
dan Gegar Jati Diri. Artikel dipresentasikan dalam Konferensi Internasional Kajian Indonesia (ICSSIS) ke-4 yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia di Bali, 9 – 10 Februari. Dimuat dalam Prosiding The 4th Interna-tional Conference on Indonesian Studies (hlm. 96 – 107). ISSN 2087-0019.
Sumber internet: Harrington, A. M. (2010). Problematizing the Hybrid Classroom for ESL/EFL Stu-
dents. TESL-EJ, The Electronic Journal for English as a Second Language, Desember 2010, Volume 14 (3). Bisa diakses di http://www.tesl-ej.org/wordpress/issues/volume14/ej55/ej55a3/
Sumber disertasi/tesis: Sayles-Hannon, S. (2008). In search of multiculturalism: Uprooting ‘whiteness’ in curricu-
lum design and pedagogical strategies. Texas Woman’s University. ProQuest Disserta-tions dan Theses, n/a. Diakses dari http://search.proquest.com/docview/304326219?accountid=17242
011-pedoman.indd 137 4/24/2014 10:48:07 AM
15. Setiap naskah diserahkan dalam bentuk hard copy atau soft copy, dengan format .rtf atau .doc/.docx. Naskah dapat dikirimkan melalui pos surat biasa atau lewat surel (e-mail).
16. Hard copy artikel (dalam format RTF/doc/docx) bisa dikirimkan paling lambat satu bulan sebelum periode penerbitan kepada :
Redaksi Jurnal Ultima HumanioraGedung Rektorat Lantai 3UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA (UMN)Jalan Boulevard Gading Serpong, Desa Curug Sangereng, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15333Telp + 6221 5422 0808 ext. 3622
Atau format soft copy bisa dikirimkan lewat surel ke: Ketua Dewan Redaksi Jurnal Ultima Humaniora, Hendar Putranto, dengan alamat
surel: [email protected]. Sertakan juga carbon copy ke alamat surel kantor, [email protected]
17. Redaksi berhak memperbaiki gramatika (mistyping, misspelling, inaccuracy) penu-lisan naskah tanpa mengubah isi naskah tersebut. Semua pandangan, pendapat atau pernyataan (klaim) yang terdapat dalam naskah merupakan tanggungjawab penulis. Naskah yang tidak dimuat pada edisi Mei dapat dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi November tahun yang sama (atau yang tidak dimuat di edisi November dapat dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi Mei tahun berikutnya), dengan catatan bahwa penulis akan merevisi naskah tersebut sesuai saran dan rekomendasi Redaksi. Naskah yang tidak memenuhi ketentuan dan kebijakan Redaksi akan dikembalikan dengan catatan, lewat surel.
18. Penulis yang naskahnya diterima dan dipublikasikan dalam jurnal akan menda-patkan honorarium, setelah dipotong pajak 2.5% (dengan NPWP) atau 3% (tanpa NPWP). Honorarium akan ditransfer ke rekening dengan nama penulis (tidak boleh diwakilkan) paling lambat dua minggu setelah jurnal naik cetak dan siap didistri-busikan.
011-pedoman.indd 138 4/24/2014 10:48:07 AM