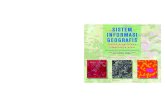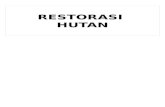hutan pendidikan
-
Upload
syahratulwilda -
Category
Documents
-
view
430 -
download
0
Transcript of hutan pendidikan

I. PENDAHULUAN
Hutan Pendidikan Unhas yang terletak di Bengo-Bengo Kabupaten Maros adalah laboratorium alam yang selama ini digunakan sebagai tempat praktek dan penelitian mahasiswa dan dosen dalam proses pendidikan kehutanan di Jurusan Kehutanan Unhas. Hutan Pendidikan tersebut memiliki potensi fisik, potensi biologi, dan potensi social yang strategis untuk dikelola sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pelayanan kehutanan di Sulawesi Selatan dan Regional Kawasan Timur Wilayah Indonesia.
Aktivitas pendidikan yang berlangsung di hutan pendidikan Unhas selama ini masih didominasi oleh kegiatan praktek dan penelitian yang terkait dengan ilmu-ilmu kehutanan dasar seperti inventarisasi, perencanaan, ilmu ukur tanah, manajemen hutan, silvika, silvikultur, dendrologi, ekologi, serta social ekonomi masyarakat di sekitar hutan pendidikan. Aktivitas tersebut sejalan dengan kurikulum Jurusan Kehutanan yang masih berorientasi kepada pengelolaan hutan konvensional. Sejak dua tahun terakhir, mahasiswa juga telah melaksanakan Praktek Umum dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi Kehutanan di Hutan Pendidikan dan desa-desa yang ada di sekitarnya, yang secara administratif berada di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba, dan Kecamatan Mallawa.
Aktivitas masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan Pendidikan Unhas adalah bersawah, berkebun, beternak, dan sebagian melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu seperti pengambilan kayu bakar, penyadapan getah pinus, penyadapan aren, pembuatan gula aren, pengambilan benih tanaman mahoni dan pinus, pemanfaatan tanaman obat-obatan, jamur, dan lain-lain. Aktivitas masyarakat tersebut membentuk agroekosistem yang dapat menjadi tempat belajar bersama stakeholder.
Seiring dengan paradigma pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat serta pengembangan Kurikulum Pendidikan Sarjana Kehutanan Unhas saat ini, maka Konsep Pengelolaan Hutan Pendidikan Berbasis Masyarakat menjadi tuntutan bagi penyelenggaraan pendidikan sarjana kehutanan. Oleh karena itu, Hutan Pendidikan Unhas akan dikelola dengan pendekatan ekosistem dan pendekatan social ekonomi budaya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan pendidikan.

II. PROFIL HUTAN PENDIDIKAN UNHAS
A. Faktor-faktor Strategis
Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin seluas 1.300 ha sangat strategis dan tepat untuk kegiatan pengembangan kehutanan, pusat pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pelayanan kehutanan karena 63 km dari Makassar, berada di pinggirletaknya relatif dekat yakni 40 km dari Bandara Internasional Hasanuddin Makassar,jalan propinsi berdekatan dengan Cagar Alam Karaenta dan Bantimurung, berdekatan dengan calon lokasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, serta dikelilingi oleh desa-desa hutan dimana sebagian masyarakatnya berinteraksi dengan hutan pendidikan. Dengan demikian, peninjauan ilmiah ke hutan pendidikan ini dapat dikemas dalam satu paket dengan wisata alam pada kawasan taman nasional Bantimurung Bulusaraung.
FUNGSI FISIK
Secara fisik hutan mangrove menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dan tebing sungai, mencegah terjadinya erosi laut serta sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah, mempercepat perluasan lahan, melindungi daerah di belakang mangrove dari hempasan dan gelombang dan angin kencang; mencegah intrusi garam (salt intrution) ke arah darat; mengolah limbah organik, dan sebagainya.
Hutan mangrove mampu meredam energi arus gelombang laut, seperti tergambar dari hasil penelitian Pratikto et al. (2002) dan Instiyanto et al. (2003). Pratikto et al. (2002) melaporkan bahwa di Teluk Grajagan – Banyuwangi yang memiliki tinggi gelombang tersebut sebesar 1,09 m, dan energi gelombang sebesar 1493,33 Joule, maka ekosistem mangrove di daerah tersebut mampu mereduksi energi gelombang sampai 60%, sehingga keberadaan hutan mangrove dapat memperkecil gelombang tsunami yang menyerang daerah pantai.
Istiyanto, Utomo dan Suranto (2003) menyimpulkan bahwa rumpun bakau (Rhizophora) memantulkan, meneruskan, dan menyerap energi gelombang tsunami yang diwujudkan dalam perubahan tinggi gelombang tsunami ketika menjalar melalui rumpun tersebut. Hasil pengujian tersebut dapat digunakan dalam pertimbangan awal bagi perencanaan penanaman hutan mangrove bagi peredaman penjalaran gelombang tsunami di pantai.
1

Pasca tsunami 26 Desember 2004 yang melanda Asia dengan pusat di pantai barat Aceh terdapat fakta bahwa hutan mangrove yang kompak mampu melindungi pantai dari kerusakan akibat tsunami (Istiyanto et al., 2003, Pratikto et al. 2002, Dahdouh-Guebas, 2005, Onrizal, 2005, Sharma, 2005). Demikian juga hal sama dijumpai pada kawasan pantai dengan hutan pantai yang baik mampu meredam dampak kerusakan tsunami (WIIP, 2005)
Vegetasi mangrove juga dapat menyerap dan mengurangi pencemaran (polutan). Jaringan anatomi tumbuhan mangrove mampu menyerap bahan polutan, misalnya seperti jenis Rhizophora mucronata dapat menyerap 300 ppm Mn, 20 ppm Zn, 15 ppm Cu (Darmiyati et al., 1995), dan pada daun Avicennia marina terdapat akumulasi Pb ³ 15 ppm, Cd ³ 0,5 ppm, Ni ³ 2,4 ppm (Saepulloh, 1995). Selain itu, hutan mangrove dapat mengendalikan intrusi air laut sebagaimana yang dilaporkan Hilmi (1998), yakni percepatan intrusi air laut di pantai Jakarta meningkat dari 1 km pada hutan mangrove selebar 0,75 km menjadi 4,24 km pada areal tidak berhutan.
FUNGSI BIOLOGIS
Secara biologi hutan mangrove mempunyai fungsi sebagai daerah berkembang biak (nursery ground), tempat memijah (spawning ground), dan mencari makanan (feeding ground) untuk berbagai organisme yang bernilai ekonomis khususnya ikan dan udang. Habitat berbagai satwa liar antara lain, reptilia, mamalia, hurting dan lain-lain. Selain itu, hutan mangrove juga merupakan sumber plasma nutfah.
Ekosistem hutan mangrove memiliki produktivitas yang tinggi. Produktivitas primer ekosistem mangrove ini sekitar 400-500 gram karbon/m2/tahun adalah tujuh kali lebih produktif dari ekosistem perairan pantai lainnya (White, 1987). Oleh karenanya, ekosistem mangrove mampu menopang keanekaragaman jenis yang tinggi. Daun mangrove yang berguguran diuraikan oleh fungi, bakteri dan protozoa menjadi komponen-komponen bahan organik yang lebih sederhana (detritus) yang menjadi sumber makanan bagi banyak biota perairan (udang, kepiting dan lain-lain) (Naamin, 1990).
Kerusakan mangrove di pantai Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdampak pada penurunan volume dan keragaman jenis ikan yang ditangkap (56,32% jenis ikan menjadi langka/sulit didapat, dan 35,36% jenis ikan menjadi hilang/tidak pernah lagi tertangkap). Konversi hutan mangrove di pantai Napabalano, Sulawesi Tenggara dilaporkan Amala (2004) menyebabkan berkurangnya secara nyara kelimpahan kepiting bakau (Scylla serrata). Hasil penelitian Onrizal et al.

(2008) menunjukkan bahwa semakin bertambah umur mangrove hasil rehabilitasi akan meningkatkan populasi dan keragaman biota pesisir pantai.
FUNGSI EKONOMI ATAU FUNGSI PRODUKSI
Mangrove sejak lama telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya (Saenger et al., 1983). Tercatat sekitar 67 macam produk yang dapat dihasilkan oleh ekosistem hutan mangrove dan sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya untuk bahan bakar (kayu bakar, arang, alkohol); bahan bangunan (tiang-tiang, papan, pagar); alat-alat penangkapan ikan (tiang sero, bubu, pelampung, tanin untuk penyamak); tekstil dan kulit (rayon, bahan untuk pakaian, tanin untuk menyamak kulit); makanan, minuman dan obat-obatan (gula, alkohol, minyak sayur, cuka); peralatan rumah tangga (mebel, lem, minyak untuk menata rambut); pertanian (pupuk hijau); chips untuk pabrik kertas dan lain-lain.
Menurut Saenger et al. (1983), hutan mangrove juga berperan dalam pendidikan, penelitian dan pariwisata. Bahkan menurut FAO (1982), di kawasan Asia dan Pasifik, areal mangrove juga digunakan sebagai lahan cadangan untuk transmigrasi, industri minyak, pemukiman dan peternakan.
Dari kawasan hutan mangrove dapat diperoleh tiga macam manfaat. Pertama, berupa hasil hutan, baik bahan pangan maupun bahan keperluan lainnya. Kedua, berupa pembukaan lahan mangrove untuk digunakan dalam kegiatan produksi baik pangan maupun non-pangan serta sarana/prasarana penunjang dan pemukiman. Manfaat ketiga berupa fungsi fisik dari ekosistem mangrove berupa perlindungan terhadap abrasi, pencegah terhadap rembesan air laut dan lain-lain fungsi fisik.
Kerusakan hutan mangrove di Secanggang, menyebabkan penurunan pendapatan sebesar 33,89% dimana kelompok yang paling besar terkena dampak adalah nelayan. Selain itu sekitar 85,4% masyrakat pesisir di kawasan tersebut kesulitan dalam berusaha dan mendapatkan pekerjaan dibandingkan sebelum kerusakan mangrove.

HUTAN MANGROVEhutan mangrove merupakan suatu tipe hutanyang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantaiyang terlindung, laguna dan muara sungai yangtergenang pada saat pasang dan bebas dari genanganpada saat surut yang komunitas tumbuhannyabertoleransi terhadap garam (Kusuma et al, 2003).Menurut FAO, Hutan Mangrove adalah Komunitastumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut.Kata mangrove merupakan kombinasi antarabahasa Portugis ”Mangue” dan bahasa Inggris ”grove”(Macnae, 1968). Dalam Bahasa Inggris kata mangrovedigunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuhdi daerah jangkauan pasang surut maupun untukindividu-individu jenis tumbuhan yang menyusunkomunitas tersebut. Hutan mangrove dikenal jugadengan istilah tidal forest, coastal woodland,vloedbosschen dan hutan payau (bahasa Indonesia).Selain itu, hutan mangrove oleh masyarakat Indonesiadan negara Asia Tenggara lainnya yang berbahasaMelayu sering disebut dengan hutan bakau.Penggunaan istilah hutan bakau untuk hutan mangrovesebenarnya kurang tepat dan rancu, karena bakauhanyalah nama lokal dari marga Rhizophora, sementarahutan mangrove disusun dan ditumbuhi oleh banyakmarga dan jenis tumbuhan lainnya. Oleh karena itu,penyebutan hutan mangrove dengan hutan bakausebaiknya dihindari (Kusmana et al, 2003).Tumbuhan mangrove bersifat unik karenamerupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidupdi darat dan di laut. Umumnya mangrove mempunyaisistem perakaran yang menonjol yang disebut akarnafas (pneumatofor). Sistem perakaran ini merupakansuatu cara adaptasi terhadap keadaan tanah yangmiskin oksigen atau bahkan anaerobMangrove tersebar di seluruh lautan tropik dansubtropik, tumbuh hanya pada pantai yang terlindungdari gerakan gelombang; bila keadaan pantaisebaliknya, benih tidak mampu tumbuh dengansempurna dan menancapkan akarnya.Mangrove tumbuh dan berkembang pada pantai-pantai

tepat di sepanjang sisi pulau-pulau yang terlindung dariangin, atau serangkaian pulau atau pada pulau di belakangterumbu karang di pantai yang terlindung (Nybakken, 1998).Indonesia memiliki sebanyak tidak kurang dari 89jenis pohon mangrove, atau paling tidak menurut FAOterdapat sebanyak 37 jenis. Dari berbagai jenis mangrovetersebut, yang hidup di daerah pasang surut, tahan airgaram dan berbuah vivipar terdapat sekitar 12 famili.Dari sekian banyak jenis mangrove di Indonesia,jenis mangrove yang banyak ditemukan antara lain adalahjenis api-api (Avicennia sp.), bakau (Rhizophora sp.),tancang (Bruguiera sp.), dan bogem atau pedada(Sonneratia sp.) merupakan tumbuhan mangrove utamayang banyak dijumpai. Jenis-jenis mangrove tersebut adalahkelompok mangrove yang menangkap, menahan endapandan menstabilkan tanah habitatnya.Jenis api-api (Avicennia sp.) atau di dunia dikenalsebagai black mangrove mungkin merupakan jenis terbaikdalam proses menstabilkan tanah habitatnya karenapenyebaran benihnya mudah, toleransi terhadap temperarturtinggi, cepat menumbuhkan akar pernafasan (akar pasak)dan sistem perakaran di bawahnya mampu menahanendapan dengan baik.Mangrove besar, mangrove merah atau Redmangrove (Rhizophora sp.) merupakan jenis kedua terbaik.Jenis-jenis tersebut dapat mengurangi dampak kerusakanterhadap arus, gelombang besar dan angin.
Hutan Mangrove memberikan perlindungan kepadaberbagai organisme baik hewan darat maupun hewanair untuk bermukim dan berkembang biak. HutanMangorove dipenuhi pula oleh kehidupan lain sepertimamalia, amfibi, reptil, burung, kepiting, ikan, primata,serangga dan sebagainya. Selain menyediakankeanekaragaman hayati (biodiversity), ekosistemMangorove juga sebagai plasma nutfah (geneticpool)dan menunjang keseluruhan sistem kehidupan disekitarnya. Habitat Mangorove merupakan tempatmencari makan (feeding ground) bagi hewan-hewantersebut dan sebagai tempat mengasuh danmembesarkan (nursery ground), tempat bertelur danmemijah (spawning ground) dan tempat berlindung yangaman bagi berbagai ikan-ikan kecil serta kerang(shellfish) dari predator.

Beberapa manfaat hutanmangrove dapat dikelompokan sebagai berikut:A. Manfaat / Fungsi Fisik :1. Menjaga agar garis pantai tetap stabil2. Melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosidan abrasi.3. Menahan badai/angin kencang dari laut4. Menahan hasil proses penimbunan lumpur,sehingga memungkinkan terbentuknya lahan baru.5. Menjadi wilayah penyangga, serta berfungsimenyaring air laut menjadi air daratan yang tawar6. Mengolah limbah beracun, penghasil O2 danpenyerap CO2.
B. Manfaat / Fungsi Biologik :1. Menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumbermakanan penting bagi plankton, sehingga pentingpula bagi keberlanjutan rantai makanan.2. Tempat memijah dan berkembang biaknya ikan-ikan,kerang, kepiting dan udang.3. Tempat berlindung, bersarang dan berkembang.biakdari burung dan satwa lain.4. Sumber plasma nutfah & sumber genetik.5. Merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota.
C. Manfaat / Fungsi Ekonomik :1. Penghasil kayu : bakar, arang, bahan bangunan.2. Penghasil bahan baku industri : pulp, tanin, kertas, tekstil,makanan, obat-obatan, kosmetik, dll3. Penghasil bibit ikan, nener, kerang, kepiting, bandengmelalui pola tambak silvofishery4. Tempat wisata, penelitian & pendidikan.Kerusakan mangrove dapat terjadi secara alamiah ataumelalui tekanan masyarakat. Secara alami umumnya kadarkerusakannya jauh lebih kecil daripada kerusakan akibatulah manusia. Kerusakan alamiah timbul karena peristiwaalam seperti adanya topan badai atau iklim keringberkepanjangan yang menyebabkan akumulasi garamdalam tanaman. Banyak kegiatan manusia di sekitarkawasan hutan mangrove yang berakibat perubahankarakteristik fisik dan kimiawi di sekitar habitat mangrovesehingga tempat tersebut tidak lagi sesuai bagi kehidupan

dan perkembangan flora dan fauna di hutan mangrove.Tekanan tersebut termasuk kegiatan reklamasi,pemanfaatan kayu mangrove untuk berbagai keperluan,misalnya untuk pembuatan arang dan sebagai bahanbangunan, pembuatan tambak udang, reklamasi dan tempatpembuangan sampah di kawasan mangrove yangmenyebabkan polusi dan kamatian pohon. Lokasi habitatmangrove yang terletak di kawasan garis pantai, laguna,muara sungai menempatkan posisi habitat tersebut rentanterhadap akibat negatif reklamasi pantai.Akibat yang terjadi bila hutan mangrove rusak adalah :• abrasi pantai• mengakibatkan intrusi air laut lebih jauh ke daratan• potensi perikanan menurun• kehidupan satwa liar terganggu• sumber mata pencaharian penduduk setempatberkurang OlehI r w a n t owww.irwantoshut.comirwantomangrove.webs.comAmbon, 2 0 0 8APA MANFAAT
EKOSISFUNGSI DAN PERANAN EKOSISTEM PADANG LAMUNPadang lamun merupakan ekosistem yang tinggi produktifitas organiknya, dengan keanekaragaman biota yang cukup tinggi. Pada ekosistem ini hidup beraneka ragam biota laut seperti ikan, Krustasea, Moluska ( Pinna sp., Lambis sp., dan Strombus sp.), Ekinodermata (Holothuria sp., Synapta sp., Diadema sp., Arcbaster sp., Linckia sp.) dan cacing ( Polichaeta) (Bengen, 2001). Menurut Azkab (1988), ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem di laut dangkal yang paling produktif. Di samping itu ekosistem lamun mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan dan perkembangan jasad hidup di laut dangkal, menurut hasil penelitian diketahui bahwa peranan lamun di lingkungan perairan laut dangkal sebagai berikut: 1. Sebagai produsen primer Lamun mempunyai tingkat produktifitas primer tertinggi bila dibandingkan dengan ekosistem lainnya yang ada di laut dangkal seperti ekosistem terumbu karang (Thayer et al. 1975). 2. Sebagai habitat biota

Lamun memberikan tempat perlindungan dan tempat menempel berbagai hewan dan tumbuh-tumbuhan (alga). Disamping itu, padang lamun (seagrass beds) dapat juga sebagai daerah asuhan, padang pengembalaan dan makan dari berbagai jenis ikan herbivora dan ikan– ikan karang (coral fishes) (Kikuchi & Peres, 1977). 3. Sebagai penangkap sedimen Daun lamun yang lebat akan memperlambat air yang disebabkan oleh arus dan ombak, sehingga perairan di sekitarnya menjadi tenang. Disamping itu, rimpang dan akar lamun dapat menahan dan mengikat sedimen, sehingga dapat menguatkan dan menstabilkan dasar permukaaan. Jadi padang lamun yang berfungsi sebagai penangkap sedimen dapat mencegah erosi ( Gingsburg & Lowestan 1958).
4. Sebagai pendaur zat hara Lamun memegang peranan penting dalam pendauran barbagai zat hara dan elemen-elemen yang langka di lingkungan laut. Khususnya zat-zat hara yang dibutuhkan oleh algae epifit. Sedangkan menurut Philips & Menez (1988), ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem bahari yang produktif. ekosistem lamun perairan dangkal mempunyai fungsi antara lain: 1. Menstabilkan dan menahan sedimen–sedimen yang dibawa melalui I tekanan–tekanan dari arus dan gelombang. 2. Daun-daun memperlambat dan mengurangi arus dan gelombang serta mengembangkan sedimentasi. 3. Memberikan perlindungan terhadap hewan–hewan muda dan dewasa yang berkunjung ke padang lamun. 4. Daun–daun sangat membantu organisme-organisme epifit. 5. Mempunyai produktifitas dan pertumbuhan yang tinggi. 6. Menfiksasi karbon yang sebagian besar masuk ke dalam sistem daur rantai makanan. Selanjutnya dikatakan Philips & Menez (1988), lamun juga sebagai komoditi yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara tradisional maupuin secara modern. Secara tradisional lamun telah dimanfaatkan untuk : 1. Digunakan untuk kompos dan pupuk 2. Cerutu dan mainan anak-anak 3. Dianyam menjadi keranjang 4. Tumpukan untuk pematang 5. Mengisi kasur 6. Ada yang dimakan 7. Dibuat jaring ikanPada zaman modern ini, lamun telah dimanfaatkan untuk: 1. Penyaring limbah 2. Stabilizator pantai 3. Bahan untuk pabrik kertas 4. Makanan 5. Obat-obatan dan sumber baha kimia6. Sumber bahan kimia.Lamun kadang-kadang membentuk suatu komunitas yang merupakan habitat bagi berbagai jenis hewan laut. Komunitas lamun ini juga dapat memperlambat gerakan air. bahkan ada jenis lamun yang dapat

dikonsumsi bagi penduduk sekitar pantai. Keberadaan ekosistem padang lamun masih belum banyak dikenal baik pada kalangan akdemisi maupun masyarakat umum, jika dibandingkan dengan ekosistem lain seperti ekosistem terumnbu karang dan ekosistem mangrove, meskipun diantara ekosistem tersebut di kawasan pesisir merupakan satu kesatuan sistem dalam menjalankan fungsi ekologisnya Habitat lamun dapat dipandang sebagai suatu komunitas, dalam hal ini suatu padang lamun merupakan kerangka struktur dengan tumbuhan dan hewan yang saling berhubungan. Habitat lamun dapat juga dipandang sabagai suatu ekosistem, dalam hal ini hubungan hewan dan tumbuhan tadi dipandang sebagai suatu proses tunggal yang dikendalikan oleh pengaruh-pengaruh interaktif dari faktor-faktor biologis, fisika, kimiawi. Lamun dapat hidup mulai dari rendah nutrien dan melimpah pada habitat yang tinggi nutrien. Keberadaan lamun pada kondisi habitat tersebut, tidak terlepas dan ganguan atau ancaman-ancaman terhadap kelansungan hidupnya baik berupa ancaman alami maupun ancaman dari aktivitas manusia. Banyak kegiatan atau proses, baik alami maupun oleh aktivitas manusia yang mengancam kelangsungan ekosistem lamun. Ekosistem lamun sudah banyak terancam termasuk di Indonesia baik secara alami maupun oleh aktifitas manusia. Besarnya pengaruh terhadap integritas sumberdaya, meskipun secara garis besar tidak diketahui, namun dapat dipandang di luar batas kesinambungan biologi. Perikanan laut yang meyediakan lebih dari 60% protein hewani yang dibutuhkan dalam menu makanan masyarakat pantai, sebagian tergantung pada ekosistem lamun untuk produktifitas dan pemeliharaanya. Selain itu kerusakan padang lamun oleh manusia akibat pemarkiran perahu yang tidak terkontrol (Sangaji, 1994). Limbah pertanian, industri, dan rumah tangga yang dibuang ke laut, pengerukan lumpur, lalu lintas perahu yang padat, dan lain-lain kegiatan manusia dapat mempunyai pengaruh yang merusak lamun. Di tempat hilangnya padang lamun, perubahan yang dapat diperkirakan menurut Fortes (1989), yaitu: 1. Reduksi detritus dari daun lamun sebagai konsekuensi perubahan dalam jaring-jaring makanan di daerah pantai dan komunitas ikan. 2. Perubahan dalam produsen primer yang dominan dari yang bersifat bentik yang bersifat planktonik. 3. Perubahan dalam morfologi pantai sebagai akibat hilangnya sifat-sifat pengikat lamun. 4. Hilangnya struktural dan biologi dan digantikan oleh pasir yang gundul
IRMAWAN SYAFITRIANTO
Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanhellae.
Hewan karang bentuknya aneh, menyerupai batu dan mempunyai warna dan bentuk beraneka rupa. Hewan ini disebut polip, merupakan hewan pembentuk utama terumbu karang yang menghasilkan zat kapur. Polip-polip ini selama ribuan tahun membentuk terumbu karang.
Zooxanthellae adalah suatu jenis algae yang bersimbiosis dalam jaringan karang. Zooxanthellae ini melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen yang berguna untuk kehidupan hewan karang
Di lain fihak, hewan karang memberikan tempat berlindung bagi zooxanthellae.
Gambar polip

Dalam ekosistem terumbu karang ada karang yang keras dan lunak. Karang batu adalah karang yang keras disebabkan oleh adanya zat kapur yang dihasilkan oleh binatang karang. Melalui proses yang sangat lama, binatang karang yang kecil (polyp) membentuk kolobi karang yang kental, yang sebenarnya terdiri atas ribuan individu polyp. Karang batu ini menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Walaupun terlihat sangat kuat dan kokoh, karang sebenarnya sangat rapuh, mudah hancur dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan.
Peran dan manfaat terumbu karang :> sebagai tempat hdiupnya ikan-ikan yang banyak dibutuhkan manusia untuk pangan, seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, dll.> sebagai benteng " pelindung pantai dari kerusakan yang disebabkan oleh gelombang atau ombak laut, sehingga

manusia dapat hidup di daerah dekat pantai.> sebagai tempat untuk wisata. Karena keindahan warna dan bentuknya, banyak orang berwisata bahari.
Luas terumbu karang Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 60.000 km2. Terumbu karang yang dalam kondisi baik hanya 6,2 %. Kerusakan ini pada umumnya disebabkan 3 faktor :
1. Keserakahan manusia2. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian3. Penegakan hukum yang lemah