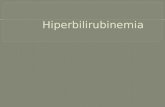hiperbilirubinemia
description
Transcript of hiperbilirubinemia
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
Ikterus terjadi apabila terdapat akumulasi bilirubin dalam darah. Pada
sebagian besar neonatus, ikterus akan ditemukan dalam minggu pertama
kehidupannya. Dikemukakan bahwa angka kejadian ikterus terdapat pada 60% bayi
cukup bulan dan 80% bayi kurang bulan.
Ikterus pada bayi baru lahir pada minggu pertama terjadi pada 60% bayi
cukup bulan dan 80% bayi kurang bulan. Hal ini adalah keadaan yang fisiologis.
Walaupun demikian, sebagian bayi akan mengalami ikterus yang berat sehingga
memerlukan pemeriksaan dan tata laksana yang benar untuk mencegah kesakitan dan
kematian.
Setiap bayi dengan ikterus harus mendapatkan perhatian, terutama apabila
ikterus ditemukan dalam 24 jam pertama kehidupan bayi atau bila kadar bilirubin
meningkat > 5 mg/dL (> 86mol/L) dalam 24 jam. Proses hemolisis darah, infeksi
berat, ikterus yang berlangsung lebih dari 1 minggu serta bilirubin direk >1 mg/dL
juga merupakan keadaan yang menunjukkan kemungkinan adanya ikterus patologis.
Dalam keadaan tersebut penatalaksanaan ikterus harus dilakukan sebaik-baiknya agar
akibat buruk ikterus dapat dihindarkan.
-
2
BAB II
LAPORAN KASUS
II.1. Identitas
Nama : Bayi K
Usia : 19 hari
Tanggal Lahir : x-x-2015
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Marital : Belum menikah
Pendidikan : Dibawah umur
Pekerjaan : Dibawah umur
Alamat : P 03/04 Bb, Kab. Semarang
No. RM : 077xxx-2015
Bangsal/Kelas : Seruni/II
Tanggal Masuk : 10 April 2015
II.2. Anamnesa
II.2.1. Keluhan Utama Badan kuning
II.2.2. Riwayat Penyakit Sekarang Pasien datang dibawa oleh ibunya dengan keluhan badan tampak
kuning. Ibu pasien mengetahui badan kuning sejak 2 hari lalu, yaitu saat
pasien berusia 19 hari. Kuning terdapat di seluruh tubuh, tampak pertama kali
di wajah yang semakin lama kuninga menyebar ke seluruh tubuh kecuali
telapak kaki. Pasien mulai batuk, disertai dengan dahak kuning dan sesak
sejak 1 hari. Keluhan juga ditambah dengan malas minum sejak 3 hari lalu,
menangis kurang kuat dan lebih jarang. Tidak ada perubahan warna pada
BAB, tidak seperti dempul, juga tidak ada perubahan warna BAK ke warna
teh pekat. Pasien diperiksakan ke bidan dan ditimbang berat badannya 2100
gram, menurun 200 gram dari berat lahir sebelumnya.
-
3
II.2.3. Riwayat Penyakit Dahulu Pasien belum pernah mengalami keluhan kuning sebelumnya. Tidak
ada riwayat kelainan kongenital pada pasien. Pasien lahir dengan BBLR.
II.2.4. Riwayat Penyakit Keluarga : Pasien memiliki 2 orang kakak yang memiliki riwayat penyakit kuning
yang sama dengan pasien. Kakak pertama lahir spontan di bidan saat usia
kehamilan 6 bulan, dengan berat lahir 1700 gram, seluruh badan kekuningan,
meninggal usia 10 hari dalam perawatan ruang perinatologi RSUD
Ambarawa.
Kakak kedua lahir spontan di bidan saat usia kehamilan 7 bulan,
dengan berat lahir 2200 gram. Usia 14 hari, kakak pasien juga mengalami
keluhan badan kuning, namun setelah perawatan selama 2 minggu, kondisi
membaik dan dipulangkan. Saat ini usia kakak pasien adalah 6 tahun.
II.2.5. Riwayat Kehamilan dan Kelahiran Pasien lahir spontan di bidan, usia kehamilan 7 bulan, jenis kelamin
perempuan, berat lahir 2300 gram, menangis cukup kuat segera setelah lahir
dan dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Ibu pasien periksa kehamilan di
bidan hanya 2 kali selama hamil dan tidak pernah di USG. Saat ANC di bidan
pasien diberikan tablet berisi zat berisi (warna merah) dan vitamin untuk
kehamilan. Tidak ada riwayat sakit kuning selama kehamilan, ibu pasien juga
tidak mengkonsumsi obat-obatan ataupun jamu selama hamil. Selama hamil
diakui janin bergerak aktif. Ibu pasien mengatakan terdapat keputihan yang
bau dan gatal namun tidak pernah diobati.
II.2.6. Riwayat Pengobatan dan Imunisasi : Pasien baru pertama kali dibawa untuk mengobati keluhan badan
kuning saat ini dan pasien tidak sedang dalam pengobatan lain. Menurut
pengakuan ibu, pasien baru menjalani 1 kali imunisasi saat lahir di bidan
(Hepatitis B 0).
-
4
II.2.7. Riwayat Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Pasien lahir dengan berat 2300 gram, PB 42 cm. Sejak lahir refleks
menghisap cukup kuat.
II.2.8. Riwayat Kebiasaan : Pasien sejak lahir diberi asupan ASI yang diberikan setiap pasien
menangis. Tidak ada makanan tambahan yang diberikan pada pasien.
II.3. Pemeriksaan Fisik
Keadaan Umum : Tampak kurang aktif, merintih
Kesadaran : CM
Tanda Vital :
Denyut jantung: 162 kali/menit
Resprasi : 18 kali/menit, dalam, tipe thoracoabdominal
Suhu : 37.3 oC
Status Gizi :
Umur : 19 hari
Berat badan : 2100 g
Panjang badan : 43 cm
Lingkar kepala: 31 cm
Lingkar dada : 30 cm
Lingkar lengan atas: 9.5 cm
Z-Score BB/U : SD < -3 : berat badan sangat kurang (severely underweight)
Z-Score PB/U : SD < -3 : sangat pendek (severely stunting)
Z-Score BB/PB : SD < -3 : gizi buruk (severely wasted)
BB/PB :
Kepala : Mesosefal, rambut hitam, ubun-ubun belum menutup,
tidak terdapat erosi ataupun laserasi
Mata : Terbuka spontan
Hidung : Tidak terdapat sekret atau napas cuping hidung
Telinga : Daun telinga normal
Mulut : Palatum mole dan palatum durun normal, lidah tampak
tidak membesar, tenggorokan tidak dapat dievaluasi
-
5
Leher : Bentuk simetris, tidak ada cekungan
Paru
Inspeksi : Dada simetris, tipe pernapasan diafragmatik, tidak ada retraksi dada
Auskultasi : Bronkovesikuler, tidak dtemukan ronki / wheezing Jantung
Auskultasi : irama sinus, tidak ditemukan murmur Abdomen
Inspeksi : Perut datar, tidak tampak hepar, lien atau usus pada dinding abdomen
Auskultasi : Bising usus (+) Perkusi : Bunyi timpani Palpasi : Supel, turgor kembali cepat, hepar teraba 2 cm BAC
Kelenjar Mammae : Tidak membesar, tidak ada sekret
Genitalia : Labia mayora menutupi labia minora, tidak terdapat
mucosal tag, tidak tampak sekret vagina
Anus dan Rektum : (+)
Kulit : Tampak kuning pada seluruh bagian tubuh kecuali
telapak kaki, tidak terdapat ptekie
KGB : Tidak terdapat pembesaran pada KGB inguinal
ataupun servikal
Anggota gerak : Tidak ditemukan anomali jari, akral hangat
Pemeriksaan Neurologis Neonatus
Tonus : Kurang kuat
Geraka n : Kurang aktif
Refleks : Refleks menghisap kurang kuat
Perilaku : Tenang
II.4. Pemeriksaan Penunjang (11 April 2015)
II.4.1. Darah Rutin Hemoglobin : 11.4 g/dl
Leukosit : 19.100 (H)
-
6
Eritrosit : 3.190.000 (L)
Hematokrit : 34.7 % (L)
MCV : 108.8 mikro (H)
MCH : 35.7 pg (H)
MCHC : 32.9 g/dl (H)
RDW : 14.9 % (H)
Trombosit : 301.000
Limfosit : 5.3 x 103/mikro
Monosit : 0.7 x 103/mikro
Eosinofil : 0.0 x 103/mikro (L)
Basofil : 0.2 x 103/mikro
Neutrofil : 12.8 x 103/mikro (H)
II.4.2. Morfologi Darah Tepi Eritrosit : Normositik, sedikit target, sferosit, normokromik,
polikromasi
Lekosit : Jumlah cukup, granulosit imatur (metamielosit 2%,
stab 14%), segmen 41%, limfosit 21%, monosit 22%,
granulosit toksik netrofil, vakuolisasi netrofil dan
monosit
Trombositt : Jumlsh cukup, morfologi dalam batas normal
Kesan : Gambaran proses infeksi bakterial dan viral
II.4.3. Kimia Klinik Bilirubin total : 14.80 mg/dL (H)
Bilirubin direk : 0.85 mg/dL (H)
Bilirubin indirek : 13.95 mg/dL (H)
-
7
II.5. Follow Up Harian
Tanggal Subjective Objective Assesment Planning 10 April 2015 06.45 15.30
Kuning pada seluruh tubuh kecuali di telapak kaki, malas minum, gerak kurang aktif, menangis kurang kuat Hasil lab keluar
SS : Kejang (-), demam (-), letargi (+) KV : Pucat (-), nadi cepat (+) HR 162x/menit, RS : Napas cepat (-) RR 18x/menit, napas cuping hidung (+), retraksi dada (-) GIS : Datar, BU (+) normal, muntah (-), intake ASI 50 cc Int : kulit tampak ikterik pada seluruh bagian tubuh kecuali telapak kaki, ptekie (-) Uro : BAK belum sejak 12 jam terakhir Hemoglobin : 11.4 g/dl Leukosit : 19.100 (H) Eritrosit : 3.190.000 (L) Hematokrit : 34.7 % (L) MCV : 108.8 mikro (H) MCH : 35.7 pg (H) MCHC : 32.9 g/dl (H) RDW : 14.9 % (H) Trombosit : 301.000 Kesan MDT : Gambaran proses infeksi bakterial dan viral Bilirubin total :14.80 mg/dL (H) Bilirubin direk :0.85 mg/dL (H) Bilirubin indirek : 13.95 mg/dL (H)
Ikterus neonatorum Hiperbilirubinemia Infeksi neonatorum
Cek darah rutin, MDT, bilirubin Infus D5 NS 300 cc/24 jam Pasang OGT (masukkan ASI perah) CPAP PEEP 5 FiO2 60% Cefotaxim 2 x 100 mg (IV) Fototerapi 2 x 24 jam
-
8
11 April 2015
Gerakan cukup aktif, menangis kurang kuat, menyusui via OGT, BAB (+), BAK (+)
SS : Kejang (-), demam (+) S : 38.3oC, letargi (-) KV : Pucat (-), nadi cepat (+) HR 162x/menit, RS : Napas cepat (-) RR 45x/menit, napas cuping hidung (+), retraksi dada (-), retraksi suprasternal (+) GIS : Datar, BU (+) normal, muntah (-), intake ASI 45 cc, BAB (+) 2x Int : kulit tampak ikterik pada kepala-leher-dada, ptekie (-) Uro : BAK (+) 2x
Hiperbilirubinemia Infeksi neonatorum
CPAP weaning FiO2 turun 40%, bila siang stabil ganti O2 nasal kanul 1 liter/menit Infus D5 NS 300 cc / 24 jam Inj Cefotaxim 2 x 100 mg IV Fototerapi 2 x 24 jam Berikan ASI
12 April 2015
Gerakan cukup aktif, menangis kurang kuat, menyusui via feeding cup, BAB (+), BAK (+)
SS : Kejang (-), demam (-) S : 36.8oC, letargi (-) KV : Pucat (-), nadi cepat (+) HR 170x/menit, RS : Napas cepat (-) RR 46x/menit, napas cuping hidung (-), retraksi dada (-), retraksi suprasternal (-) GIS : Datar, BU (+) normal, muntah (-), intake ASI 70 cc via feeding cup, BAB (+) 2x Int : kulit tampak ikterik pada kepala-leher, ptekie (-) Uro : BAK (+) 2x
Hiperbilirubinemia Infeksi neonatorum
Infus D5 NS 250 cc/24 jam Inj Cefotaxim 2 x 100 mg Menetek ASI
-
9
13 April 2015
Gerakan cukup aktif, menangis cukup kuat, menyusui via feeding cup, BAB (+), BAK (+)
SS : Kejang (-), demam (-) S : 36.5oC, letargi (-) KV : Pucat (-), nadi cepat (-) HR 146x/menit, RS : Napas cepat (-) RR 49x/menit, napas cuping hidung (-), retraksi dada (-), GIS : Datar, BU (+) normal, muntah (-), intake ASI 75 cc via feeding cup, BAB (+) 2x Int : kulit tampak ikterik pada kepala-leher, ptekie (-) Uro : BAK (+) 2x
Hiperbilirubinemia Infeksi neonatorum
Infus D5 NS 250 cc / 24 jam Inj Cefotaxim 2x100 mg Menetek ASI
14 April 2015
Gerakan aktif, menangis kuat, menyusui via feeding cup + menetek, BAB (+), BAK (+)
SS : Kejang (-), demam (-) S : 36.5oC, letargi (-) KV : Pucat (-), nadi cepat (+) HR 164x/menit, RS : Napas cepat (-) RR 52x/menit, napas cuping hidung (-), retraksi dada (-), GIS : Datar, BU (+) normal, muntah (-), intake ASI 75 cc via feeding cup + menetek, BAB (+) 2x Int : kulit tampak kemerahan, ptekie (-) Uro : BAK (+) 2x
Hiperbilirubinemia Infeksi neonatorum
Infus D5 NS Inj Cefotaxim 2x100 mg IM Menetek ASI
-
10
15 April 2015
Gerakan aktif, menangis kuat, menyusui via feeding cup + menetek, BAB (+), BAK (+)
SS : Kejang (-), demam (-) S : 36.7oC, letargi (-) KV : Pucat (-), nadi cepat (-) HR 130x/menit, RS : Napas cepat (-) RR 48x/menit, napas cuping hidung (-), retraksi dada (-), GIS : Datar, BU (+) normal, muntah (-), intake ASI 65 cc via feeding cup + menetek, BAB (+) 2x Int : kulit tampak kemerahan, ptekie (-) Uro : BAK (+) 2x
Hiperbilirubinemia Infeksi neonatorum
Pasien diperbolehkan pulang
II.6. Resume
Pasien datang dibawa oleh ibunya dengan keluhan badan tampak kuning. Ibu
pasien mengetahui badan kuning sejak 2 hari lalu, yaitu saat pasien berusia 19 hari.
Kuning terdapat di seluruh tubuh, tampak pertama kali di wajah yang semakin lama
kuninga menyebar ke seluruh tubuh kecuali telapak kaki. Pasien mulai batuk, disertai
dengan dahak kuning dan sesak sejak 1 hari. Keluhan juga ditambah dengan malas
minum sejak 3 hari lalu, menangis kurang kuat dan lebih jarang. Tidak ada perubahan
warna pada BAB, tidak seperti dempul, juga tidak ada perubahan warna BAK ke
warna teh pekat. Pasien diperiksakan ke bidan dan ditimbang berat badannya 2100
gram, menurun 200 gram dari berat lahir sebelumnya. Pasien belum pernah
mengalami keluhan kuning sebelumnya. Tidak ada riwayat kelainan kongenital pada
pasien. Pasien lahir dengan BBLR, 2300 gram, PB 42 cm. Sejak lahir refleks
menghisap cukup kuat. Pasien sejak lahir diberi asupan ASI yang diberikan setiap
pasien menangis. Tidak ada makanan tambahan yang diberikan pada pasien.
Pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya kejang, demam terjadi di hari
kedua perawatan dengan suhu 38.3oC, kondisi letargi. Pasien tidak pucat, nadi cepat
dengan HR 162x/menit, tidak terdapat napas cepat dengan RR 18x/menit di hari
pertama perawtan, ditemukan napas cuping hidung, dan terdapat retraksi suprasternal.
Pada pemeriksaan gastrointestinal, abdomen tampak datar dengan bising usus normal,
-
11
tidak muntah, dengan intake ASI. Pemeriksaan sistem integumen menunjukkan kulit
tampak ikter di seluruh bagian tubuh kecuali telapak kaki, tanpa adanya ptekie.
Hasil laboratorium menunjukkan Hb 11.4 g/dl, leukosit 19.100 yang
menunjukkan adanya infeksi, eritrosit 3.190.000, hematokrit 34.7%, trombosit
301.000, morfologi darah tepi menunjukkan gambaran proses infeksi bakterial dan
viral, kimia klinik menunjukkan bilirubin tial 14.80 mg/dl, bilirubin direk 0.85 mg/dl,
dan bilirubin indirek 13.95 mg/dl yang menandakan adanya peningkatan sehingga
bermanifestasi kulit ikterik.
Berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang
maka pasien didiagnosa dengan hiperbilirubinemia dengan infeksi neonatorum.
Pasien diberikan terapi berupa fototerapi 2 x 24 jam, pemasangan CPAP PEEP 5
FiO2 60%, infus D5 NS 300 cc / 24 jam, injeksi cefotaxim 2 x 100 mg (IV) selama
5 hari, dan diet ASI.
II.7. Diagnosa Kerja
1. Hiperbilirubinemia
2. Infeksi Neonatorum
II.8. Tatalaksana
1. Farmakologi
a. Infus KAEN D5 NS 300 cc / 24 jam selanjutnya 250 cc / 24 jam
b. Injeksi Cefotaxim 2 x 100 mg (IV) selama 5 hari
2. Nonfarmakologi
a. Diet ASI
b. CPAP PEEP 5 FiO2 60% dilanjutkan O2 nasal kanul 1 liter/menit
c. Fototerapi 2 x 24 jam
II.9. Prognosis
Ad vitam : baik
Ad sanam : baik
Ad fungsionam: baik
-
12
BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
III.1. Definisi Ikterus adalah menguningnya sklera, kulit atau jaringan lain akibat
penimbunan bilirubin dalam tubuh atau akumulasi bilirubin dalam darah lebih
dari 5 mg/dl dalam 24 jam, yang menandakan terjadinya gangguan fungsional
dari hepar, sistem biliary, atau sistem hematologi. Ikterus dapat terjadi baik
karena peningkatan bilirubin indirek (unconjugated) dan direk (conjugated).
Ikterus pada neonatus dapat bersifat fisiologis dan patologis. Ikterus
fisiologis adalah ikterus yang timbul pada hari kedua dan ketiga yang tidak
mempunyai dasar patologis, kadarnya tidak melewati kadar yang membahayakan
atau mempunyai potensi menjadi kernicterus dan tidak menyebabkan suatu
morbiditas pada bayi. Ikterus patologis ialah ikterus yang mempunyai dasar
patologis atau kadar bilirubinnya mencapai suatu nilai yang disebut
hiperbilirubinemia.
Ikterus Fisiologis
Dalam keadaan normal, kadar bilirubin indirek dalam serum tali pusat
adalah sebesar 1-3 mg/dl dan akan meningkat dengan kecepatan kurang dari 5
mg/dl/24 jam; dengan demikian ikterus baru terlihat pada hari ke 2-3, biasanya
mencapai puncaknya antara hari ke 2-4, dengan kadar 5-6 mg/dl untuk
selanjutnya menurun sampai kadarnya lebih rendah dari 2 mg/dl antara lain ke 5-
7 kehidupan. Ikterus akibat perubahan ini dinamakan ikterus fisiologis dan
diduga sebagai akibat hancurnya sel darah merah janin yang disertai pembatasan
sementara pada konjugasi dan ekskresi bilirubin oleh hati.
Diantara bayi-bayi prematur, kenaikan bilirubin serum cenderung sama
atau sedikit lebih lambat daripada pada bayi aterm, tetapi berlangsung lebih
lama, pada umumnya mengakibatkan kadar yang lebih tinggi, puncaknya dicapai
antara hari ke 4-7, pola yang akan diperlihatkan bergantung pada waktu yang
diperlukan oleh bayi preterm mencapai pematangan mekanisme metabolisme
ekskresi bilirubin. Kadar puncak sebesar 8-12 mg/dl tidak dicapai sebelum hari
ke 5-7 dan kadang-kadang ikterus ditemukan setelah hari ke-10.
-
13
Diagnosis ikterus fisiologik pada bayi aterm atau preterm, dapat
ditegakkan dengan menyingkirkan penyebab ikterus berdasarkan anamnesis dan
penemuan klinik dan laboratorium. Pada umumnya untuk menentukan penyebab
ikterus jika:
1. Ikterus timbul dalam 24 jam pertama kehidupan.
2. Bilirubin serum meningkat dengan kecepatan lebih besar dari 5 mg/dl/24 jam.
3. Kadar bilirubin serum lebih besar dari 12 mg/dl pada bayi aterm dan lebih
besar dari 14 mg/dl pada bayi preterm.
4. Ikterus persisten sampai melewati minggu pertama kehidupan, atau
5. Bilirubin direk lebih besar dari 1 mg/dl.
Ikterus Patologis
Ikterus patologis mungkin merupakan petunjuk penting untuk diagnosis
awal dari banyak penyakit neonatus. Ikterus patologis dalam 36 jam pertama
kehidupan biasanya disebabkan oleh kelebihan produksi bilirubin, karena klirens
bilirubin yang lambat jarang menyebabkan peningkatan konsentrasi diatas 10
mg/dl pada umur ini. Jadi, ikterus neonatorum dini biasanya disebabkan oleh
penyakit hemolitik.
- Ada beberapa keadaan ikterus yang cenderung menjadi patologik:
1. Ikterus klinis terjadi pada 24 jam pertama kehidupan
2. Peningkatan kadar bilirubin serum sebanyak 5mg/dL atau lebih setiap 24 jam
3. Ikterus yang disertai proses hemolisis (inkompatabilitas darah, defisiensi
G6PD, atau sepsis)
4. Ikterus yang disertai oleh:
a. Berat lahir 8 hari (pada NCB) atau >14
hari (pada NKB).
-
14
Kernicterus
Bahaya hiperbilirubinemia adalah kernikterus, yaitu suatu kerusakan otak
akibat perlengketan bilirubin indirek pada otak terutama pada korpus striatum,
talamus, nukleus subtalamus hipokampus, nukleus merah dan nukleus di dasar
ventrikel IV. Secara klinis pada awalnya tidak jelas, dapat berupa mata berputar,
letargi, kejang, tak mau menghisap, malas minum, tonus otot meningkat, leher
kaku, dan opistotonus. Bila berlanjut dapat terjadi spasme otot, opistotonus,
kejang, atetosis yang disertai ketegangan otot. Dapat ditemukan ketulian pada
nada tinggi, gangguan bicara dan retardasi mental.
III.2. Metabolisme bilirubin Untuk mendapat pengertian yang cukup mengenai masalah ikterus pada
neonatus, perlu diketahui tentang metabolisme bilirubin pada janin dan neonatus.
Perbedaan utama metabolisme adalah bahwa pada janin melalui plasenta dalam
bentuk bilirubin indirek.
Metabolisme bilirubin mempunyai tingkatan sebagai berikut :
I. Produksi
Sebagian besar bilirubin terbentuk sebagai akibat degradasi hemoglobin
pada sistem retikuloendotelial (RES). Tingkat penghancuran hemoglobin ini pada
neonatus lebih tinggi dari pada bayi yang lebih tua. Satu gram hemoglobin dapat
menghasilkan 35 mg bilirubin indirek. Bilirubin indirek yaitu bilirubin yang
bereaksi tidak langsung dengan zat warna diazo (reaksi hymans van den bergh),
yang bersifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam lemak.
II. Transportasi
Bilirubin indirek kemudian diikat oleh albumin sel parenkim hepar
mempunyai cara yang selektif dan efektif mengambil bilirubin dari plasma.
Bilirubin ditransfer melalui membran sel ke dalam hepatosit sedangkan albumin
tidak. Didalam sel bilirubin akan terikat terutama pada ligandin , glutation S-
transferase B) dan sebagian kecil pada(protein glutation S-transferase lain dan
protein Z. Proses ini merupakan proses dua arah, tergantung dari konsentrasi dan
afinitas albumin dalam plasma dan ligandin dalam hepatosit. Sebagian besar
bilirubin yang masuk hepatosit di konjugasi dan di ekskresi ke dalam empedu.
-
15
Dengan adanya sitosol hepar, ligadin mengikat bilirubin sedangkan albumin tidak
Pemberian fenobarbital mempertinggi konsentrasi ligadin dan memberi tempat
pengikatan yang lebih banyak untuk bilirubin.
III. Konjugasi
Dalam sel hepar bilirubin kemudian dikonjugasi menjadi bilirubin
diglukosonide. Walaupun ada sebagian kecil dalam bentuk monoglukoronide.
Glukoronil transferase merubah bentuk monoglukoronide menjadi diglukoronide.
Pertama-tama yaitu uridin di fosfat glukoronide transferase (UDPG : T) yang
mengkatalisasi pembentukan bilirubin monoglukoronide.
Sintesis dan ekskresi diglokoronode terjadi di membran kanilikulus.
Isomer bilirubin yang dapat membentuk ikatan hidrogen seperti bilirubin natural
IX dapat diekskresikan langsung kedalam empedu tanpa konjugasi. Misalnya
isomer yang terjadi sesudah terapi sinar (isomer foto).
IV. Ekskresi
Sesudah konjugasi bilirubin ini menjadi bilirubin direk yang larut dalam
air dan di ekskresi dengan cepat ke sistem empedu kemudian ke usus. Dalam usus
bilirubin direk ini tidak diabsorpsi; sebagian kecil bilirubin direk dihidrolisis
menjadi bilirubin indirek dan direabsorpsi. Siklus ini disebut siklus enterohepatis.
-
16
Pada neonatus karena aktivitas enzim B glukoronidase yang meningkat, bilirubin
direk banyak yang tidak dirubah menjadi urobilin. Jumlah bilirubin yang
terhidrolisa menjadi bilirubin indirek meningkat dan tereabsorpsi sehingga siklus
enterohepatis pun meningkat.
V. Metabolisme bilirubin pada janin dan neonatus
Pada likuor amnion yang normal dapat ditemukan bilirubin pada
kehamilan 12 minggu, kemudian menghilang pada kehamilan 36-37 minggu. Pada
inkompatibilitas darah Rh, kadar bilirubin dalam cairan amnion dapat dipakai
untuk menduga beratnya hemolisis. Peningkatan bilirubin amnion juga terdapat
pada obstruksi usus fetus. Bagaimana bilirubin sampai ke likuor amnion belum
diketahui dengan jelas, tetapi kemungkinan besar melalui mukosa saluran nafas
dan saluran cerna. Produksi bilirubin pada fetus dan neonatus diduga sama
besarnya tetapi kesanggupan hepar mengambil bilirubin dari sirkulasi sangat
terbatas. Demikian pula kesanggupannya untuk mengkonjugasi. Dengan demikian
hampir semua bilirubin pada janin dalam bentuk bilirubin indirek dan mudah
melalui plasenta ke sirkulasi ibu dan diekskresi oleh hepar ibunya. Dalam keadaan
fisiologis tanpa gejala pada hampir semua neonatus dapat terjadi akumulasi
bilirubin indirek sampai 2 mg%. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan
fetus mengolah bilirubin berlanjut pada masa neonatus. Pada masa janin hal ini
diselesaikan oleh hepar ibunya, tetapi pada masa neonatus hal ini berakibat
penumpukan bilirubin dan disertai gejala ikterus. Pada bayi baru lahir karena
fungsi hepar belum matang atau bila terdapat gangguan dalam fungsi hepar akibat
hipoksia, asidosis atau bila terdapat kekurangan enzim glukoronil transferase atau
kekurangan glukosa, kadar bilirubin indirek dalam darah dapat meninggi.
Bilirubin indirek yang terikat pada albumin sangat tergantung pada kadar albumin
dalam serum. Pada bayi kurang bulan biasanya kadar albuminnya rendah sehingga
dapat dimengerti bila kadar bilirubin indek yang bebas itu dapat meningkat dan
sangat berbahaya karena bilirubin indirek yang bebas inilah yang dapat melekat
pada sel otak. Inilah yang menjadi dasar pencegahan kernicterus dengan
pemberian albumin atau plasma. Bila kadar bilirubin indirek mencapai 20 mg%
pada umumnya kapasitas maksimal pengikatan bilirubin oleh neonatus yang
mempunyai kadar albumin normal telah tercapai.
-
17
III.3. Etiologi Penyebab ikterus pada bayi baru lahir dapat berdiri sendiri ataupun dapat
disebabkan oleh beberapa faktor. Secara garis besar etiologi ikterus neonatorum
dapat dibagi :
1. Produksi yang berlebihan
Hal ini melebihi kemampuan bayi untuk mengeluarkannya, misalnya pada
hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah Rh, AB0, golongan darah
lain, defisiensi enzim G-6-PD, piruvat kinase, perdarahan tertutup dan sepsis.
2. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar
Gangguan ini dapat disebabkan oleh bilirubin, gangguan fungsi hepar,
akibat asidosis, hipoksia dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glukoronil
transferase (sindrom criggler-Najjar). Penyebab lain yaitu defisiensi protein.
Protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake bilirubin ke sel
hepar.
3. Gangguan transportasi
Bilirubin dalam darah terikat pada albumin kemudian diangkat ke hepar.
Ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat misalnya salisilat,
sulfafurazole. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya
bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak.
4. Gangguan dalam ekskresi
Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau diluar hepar.
Kelainan diluar hepar biasanya disebabkan oleh kelainan bawaan. Obstruksi
dalam hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain.
Ikterus yang berhubungan dengan pemberian air susu ibu.
Diperkirakan 1 dari setiap 200 bayi aterm, yang menyusu, memperlihatkan
peningkatan bilirubin tak terkonjugasi yang cukup berarti antara hari ke 4-7
kehidupan, mencapai konsentrasi maksimal sebesar 10-27 mg/dl, selama minggu
ke 3. Jika mereka terus disusui, hiperbilirubinemia secara berangsur-angsur akan
menurun dan kemudian akan menetap selama 3-10 minggu dengan kadar yang
-
18
lebih rendah. Jika mereka dihentikan menyusu, kadar bilirubin serum akan
menurun dengan cepat, biasanya kadar normal dicapai dalam beberapa hari.
Penghentian menyusu selama 2-4 hari, bilirubin serum akan menurun dengan
cepat, setelah itu mereka dapat menyusu kembali, tanpa disertai timbulnya
kembali hiperbilirubinemia dengan kadar tinggi, seperti sebelumnya. Bayi ini
tidak memperlihatkan tanda kesakitan lain dan kernikterus tidak pernah
dilaporkan. Susu yang berasal dari beberapa ibu mengandung 5 -diol dan asam
lemak rantai panjang,, 2-pregnan-3 tak-teresterifikasi, yang secara
kompetitif menghambat aktivitas konjugasi glukoronil transferase, pada kira-kira
70% bayi yang disusuinya. Pada ibu lainnya, susu yang mereka hasilkan
mengandung lipase yang mungkin bertanggung jawab atas terjadinya ikterus.
Sindroma ini harus dibedakan dari hubungan yang sering diakui, tetapi kurang
didokumentasikan, antara hiperbilirubinemia tak-terkonjugasi, yang diperberat
yang terdapat dalam minggu pertama kehidupan dan menyusu pada ibu.
-
19
III.4. Patofisiologi Peningkatan kadar bilirubin tubuh dapat terjadi pada beberapa keadaan.
Kejadian yang sering ditemukan adalah apabila terdapat penambahan beban
bilirubin pada sel hepar yang terlalu berlebihan. Hal ini dapat ditemukan bila
terdapat peningkatan penghancuran eritrosit, polisitemia, memendeknya umur
eritrosit janin/bayi, meningkatnya bilirubin dari sumber lain, atau terdapatnya
peningkatan sirkulasi enterohepatik.
Gangguan ambilan bilirubin plasma juga dapat menimbulkan peningkatan
kadar bilirubin tubuh. Hal ini dapat terjadi apabila kadar protein Y berkurang atau
pada keadaan proten Y dan protein Z terikat oleh anion lain, misalnya pada bayi
dengan asidosis atau dengan anoksia/hipoksia. Keadaan lain yang memperlihatkan
peningkatan kadar bilirubin adalah apabila ditemukan gangguan konjugasi hepar
(defisiensi enzim glukoranil transferase) atau bayi yang menderita gangguan
ekskresi, misalnya penderita hepatitis neonatal atau sumbatan saluran empedu
intra/ekstra hepatik.
Pada derajat tertentu, bilirubin ini akan bersifat toksik dan merusak
jaringan tubuh. Toksisitas ini terutama ditemukan pada bilirubin indirek yang
bersifat sukar larut dalam air tapi mudah larut dalam lemak. Sifat ini
memungkinkan terjadinya efek patologik pada sel otak apabila bilirubin tadi dapat
menembus sawar darah otak. Kelainan yang terjadi pada otak ini disebut
kernikterus atau ensefalopati biliaris. Pada umumnya dianggap bahwa kelainan
pada susunan saraf pusat tersebut mungkin akan timbul apabila kadar bilirubin
indirek lebih dari 20 mg/dl. Mudah tidaknya bilirubin melalui sawar darah otak
ternyata tidak hanya tergantung dari tingginya kadar bilirubin tetapi tergantung
pula pada keadaan neonatus sendiri. Bilirubin indirek akan mudah melalui sawar
daerah otak apabila pada bayi terdapat keadaan imaturitas, berat lahir rendah,
hipoksia, hiperkarbia, hipoglikemia, dan kelainan susunan saraf pusat yang terjadi
karena trauma atau infeksi.
III.5. Manifestasi Klinis Pengamatan ikterus paling baik dilakukan dengan cahaya sinar matahari.
Bayi baru lahir (BBL) tampak kuning apabila kadar bilirubin serumnya kira-kira 6
mg/dl atau 100 mikro mol/L (1 mg mg/dl = 17,1 mikro mol/L). salah satu cara
-
20
pemeriksaan derajat kuning pada BBL secara klinis, sederhana dan mudah adalah
dengan penilaian menurut Kramer (1969). Caranya dengan jari telunjuk
ditekankan pada tempat-tempat yang tulangnya menonjol seperti tulang hidung,
dada, lutut dan lain-lain. Tempat yang ditekan akan tampak pucat atau kuning.
Penilaian kadar bilirubin pada masing-masing tempat tersebut disesuaikan dengan
tabel yang telah diperkirakan kadar bilirubinnya.
1. Kramer I. Daerah kepala
(Bilirubin total 5 7 mg).
2. Kramer II. Daerah dada pusat
(Bilirubin total 7 10 mg%)
3. Kramer III. Perut dibawah pusat s/d lutut
(Bilimbin total 10 13 mg)
4. Kramer IV. Lengan s/d pergelangan tangan tungkai bawah - pergelangan kaki
(Bilirubin total 13 17 mg%)
5. Kramer V. s/d telapak tangan dan telapak kaki
(Bilirubin total >17 mg%)
Disamping itu dapat pula disertai dengan gejala-gejala: 1. Dehidrasi
Asupan kalori tidak adekuat (misalnya: kurang minum, muntah-muntah)
2. Pucat
Sering berkaitan dengan anemia hemolitik (mis. Ketidakcocokan golongan
darah ABO, rhesus, defisiensi G6PD) atau kehilangan darah
ekstravaskular.
3. Trauma lahir
Bruising, sefalhematom (peradarahn kepala), perdarahan tertutup lainnya.
4. Pletorik (penumpukan darah)
Polisitemia, yang dapat disebabkan oleh keterlambatan memotong tali
pusat, bayi KMK
5. Letargi dan gejala sepsis lainnya
6. Petekie (bintik merah di kulit)
Sering dikaitkan dengan infeksi kongenital, sepsis atau eritroblastosis
7. Mikrosefali (ukuran kepala lebih kecil dari normal)
Sering berkaitan dengan anemia hemolitik, infeksi kongenital, penyakit
-
21
hati
8. Hepatosplenomegali (pembesaran hati dan limpa)
9. Omfalitis (peradangan umbilikus)
10. Hipotiroidisme (defisiensi aktivitas tiroid)
11. Massa abdominal kanan (sering berkaitan dengan duktus koledokus)
12. Feses dempul disertai urin warna coklat
Pikirkan ke arah ikterus obstruktif, selanjutnya konsultasikan ke bagian
hepatologi.3
III.6. Diagnosis Anamnesis ikterus pada riwayat obstetri sebelumnya sangat membantu
dalam menegakkan diagnosis hiperbilirubinemia pada bayi. Termasuk dalam hal
ini anamnesis mengenai riwayat inkompatabilitas darah, riwayat transfusi tukar
atau terapi sinar pada bayi sebelumnya. Disamping itu faktor risiko kehamilan dan
persalinan juga berperan dalam diagnosis dini ikterus/hiperbilirubinemia pada
bayi. Faktor risiko tersebut antara lain adalah kehamilan dengan komplikasi,
persalinan dengan tindakan/komplikasi, obat yang diberikan pada ibu selama
hamil/persalinan, kehamilan dengan diabetes melitus, gawat janin, malnutrisi
intrauterin, infeksi intranatal, dan lain-lain.
Secara klinis ikterus pada neonatus dapat dilihat segera setelah lahir atau
beberapa hari kemudian. Ikterus yang tampak pun sangat tergantung kepada
penyebab ikterus itu sendiri. Pada bayi dengan peninggian bilirubin indirek, kulit
tampak berwarna kuning terang sampai jingga, sedangkan pada penderita dengan
gangguan obstruksi empedu warna kuning kulit terlihat agak kehijauan. Perbedaan
ini dapat terlihat pada penderita ikterus berat, tetapi hal ini kadang-kadang sulit
dipastikan secara klinis karena sangat dipengaruhi warna kulit. Penilaian akan
lebih sulit lagi apabila penderita sedang mendapatkan terapi sinar. Selain kuning,
penderita sering hanya memperlihatkan gejala minimal misalnya tampak lemah
dan nafsu minum berkurang. Keadaan lain yang mungkin menyertai ikterus adalah
anemia, petekie, pembesaran lien dan hepar, perdarahan tertutup, gangguan nafas,
gangguan sirkulasi, atau gangguan syaraf. Keadaan tadi biasanya ditemukan pada
ikterus berat atau hiperbilirubinemia berat.
Waktu timbulnya ikterus mempunyai arti yang penting pula dalam
-
22
diagnosis dan penatalaksanaan penderita karena saat timbulnya ikterus
mempunyai kaitan yang erat dengan kemungkinan penyebab ikterus tersebut.
Ikterus yang timbul hari pertama sesudah lahir, kemungkinan besar disebabkan
oleh inkompatibilitas golongan darah (ABO, Rh atau golongan darah lain). Infeksi
intra uterin seperti rubela, penyakit sitomegali, toksoplasmosis, atau sepsis
bakterial dapat pula memperlihatkan ikterus pada hari pertama. Pada hari kedua
dan ketiga ikterus yang terjadi biasanya merupakan ikterus fisiologik, tetapi harus
pula dipikirkan penyebab lain seperti inkompatibilitas golongan darah, infeksi
kuman, polisitemia, hemolisis karena perdarahan tertutup, kelainan morfologi
eritrosit (misalnya sferositosis), sindrom gawat nafas, toksositosis obat, defisiensi
G-6-PD, dan lain-lain. Ikterus yang timbul pada hari ke 4 dan ke 5 mungkin
merupakan kuning karena ASI atau terjadi pada bayi yang menderita Gilbert, bayi
dari ibu penderita diabetes melitus, dan lain-lain. Selanjutnya ikterus setelah
minggu pertama biasanya terjadi pada atresia duktus koledokus, hepatitis
neonatal, stenosis pilorus, hipotiroidisme, galaktosemia, infeksi post natal, dan
lain-lain.
III.7. Diagnosis Banding Ikterus yang terjadi pada saat lahir atau dalam waktu 24 jam pertama
kehidupan mungkin sebagai akibat eritroblastosis foetalis, sepsis, penyakit inklusi
sitomegalik, rubela atau toksoplasmosis kongenital. Ikterus pada bayi yang
mendapatkan tranfusi selama dalam uterus, mungkin ditandai oleh proporsi
bilirubin bereaksi-langsung yang luar biasa tingginya. Ikterus yang baru timbul
pada hari ke 2 atau hari ke 3, biasanya bersifat fisiologik, tetapi dapat pula
merupakan manifestasi ikterus yang lebih parah yang dinamakan
hiperbilirubinemia neonatus. Ikterus nonhemolitik familial (sindroma Criggler-
Najjar) pada permulaannya juga terlihat pada hari ke-2 atau hari ke-3. Ikterus
yang timbul setelah hari ke 3, dan dalam minggu pertama, harus dipikirkan
kemungkinan septikemia sebagai penyebabnya; keadaan ini dapat disebabkan oleh
infeksi-infeksi lain terutama sifilis, toksoplasmosis dan penyakit inklusi
sitomegalik. Ikterus yang timbul sekunder akibat ekimosis atau hematoma
ekstensif dapat terjadi selama hari pertama kelahiran atau sesudahnya, terutama
pada bayi prematur. Polisitemia dapat menimbulkan ikterus dini.
-
23
Ikterus yang permulaannya ditemukan setelah minggu pertama kehidupan,
memberi petunjuk adanya, septikemia, atresia kongenital saluran empedu,
hepatitis serum homolog, rubela, hepatitis herpetika, pelebaran idiopatik duktus
koledoskus, galaktosemia, anemia hemolitik kongenital (sferositosis) atau
mungkin krisis anemia hemolitik lain, seperti defisiensi enzim piruvat kinase dan
enzim glikolitik lain, talasemia, penyakit sel sabit, anemia non-sperosit herediter),
atau anemia hemolitik yang disebabkan oleh obat-obatan (seperti pada defisiensi
kongenital enzim-enzim glukosa-6-fosfat dehidrogenase, glutation sintetase,
glutation reduktase atau glutation peroksidase) atau akibat terpapar oleh bahan-
bahan lain.
Ikterus persisten selama bulan pertama kehidupan, memberi petunjuk
adanya apa yang dinamakan inspissated bile syndrome (yang terjadi menyertai
penyakit hemolitik pada bayi neonatus), hepatitis, penyakit inklusi sitomegalik,
sifilis, toksoplasmosis, ikterus nonhemolitik familial, atresia kongenital saluran
empedu, pelebaran idiopatik duktus koledoskus atau galaktosemia. Ikterus ini
dapat dihubungkan dengan nutrisi perenteral total. Kadang-kadang ikterus
fisiologik dapat berlangsung berkepanjangan sampai beberapa minggu, seperti
pada bayi yang menderita penyakit hipotiroidisme atau stenosis pilorus.
Tanpa mempersoalkan usia kehamilan atau saat timbulnya ikterus,
hiperbilirubinemia yang cukup berarti memerlukan penilaian diagnostik yang
lengkap, yang mencakup penentuan fraksi bilirubin langsung (direk) dan tidak
langsung (indirek) hemoglobin, hitung leukosit, golongan darah, tes Coombs dan
pemeriksaan sediaan apus darah tepi. Bilirubinemia indirek, retikulositosis dan
sediaan apus yang memperlihatkan bukti adanya penghancuran eritrosit, memberi
petunjuk adanya hemolisis; bila tidak terdapat ketidakcocokan golongan darah,
maka harus dipertimbangkan kemungkinan adanya hemolisis akibat
nonimunologik. Jika terdapat hiperbilirubinemia direk, adanya hepatitis, kelainan
metabolisme bawaan, fibrosis kistik dan sepsis, harus dipikirkan sebagai suatu
kemungkinan diagnosis. Jika hitung retikulosit, tes Coombs dan bilirubin direk
normal, maka mungkin terdapat hiperbilirubinemia indirek fisiologik atau
patologik.
-
24
III.8. Penatalaksanaan I. Pendekatan menentukan kemungkinan penyebab
Menetapkan penyebab ikterus tidak selamanya mudah dan
membutuhkan pemeriksaan yang banyak dan mahal, sehingga dibutuhkan
suatu pendekatan khusus untuk dapat memperkirakan penyebabnya.
Pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan itu yaitu menggunakan saat
timbulnya ikterus seperti yang dikemukakan oleh Harper dan Yoon 1974,
yaitu :
A. Ikterus yang timbul pada 24 jam pertama
Penyebab ikterus yang terjadi pada 24 jam pertama menurut besarnya
kemungkinan dapat disusun sebagai berikut :
- Inkompatibilitas darah Rh, ABO atau golongan lain
- Infeksi intrauterin (oleh virus, toksoplasma, lues dan kadang-kadang
bakteri)
- Kadang-kadang oleh defisiensi G-6-PD
Pemeriksaan yang perlu diperhatikan yaitu :
- Kadar bilirubin serum berkala
- Darah tepi lengkap
- Golongan darah ibu dan bayi
- Uji coombs
- Pemeriksaan penyaring defisiensi enzim G-6-PD, biakan darah atau biopsi
hepar bila perlu.
B. Ikterus yang timbul 24- 72 jam sesudah lahir
- Biasanya ikterus fisiologis
- Masih ada kemungkinan inkompatibilitas darah ABO atau Rh atau
golongan lain. Hal ini dapat diduga kalau peningkatan kadar bilirubin
cepat, misalnya melebihi 5 mg%/24 jam.
- Defisiensi enzim G-6-PD juga mungkin
- Polisitemia
- Hemolisis perdarahan tertutup (perdarahan subaponeurosis, perdarahan
hepar subkapsuler dan lain-lain).
-
25
- Hipoksia.
- Sferositosis, eliptositosis dan lain-lain.
- Dehidrasi asidosis.
- Defisiensi enzim eritrosit lainnya.
Pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah bila keadaan bayi baik dan
peningkatan ikterus tidak cepat, dapat dilakukan pemeriksaan daerah tepi,
pemeriksaan kadar bilirubin berkala, pemeriksaan penyaring enzim G-6-PD
dan pemeriksaan lainnya bila perlu.
C. Ikterus yang timbul sesudah 72 jam pertama sampai akhir minggu pertama
- Biasanya karena infeksi (sepsis)
- Dehidrasi asidosis
- Difisiensi enzim G-6-PD
- Pengaruh obat
- Sindrom Criggler-Najjar
- Sindrom Gilbert
D. Ikterus yang timbul pada akhir minggu pertama dan selanjutnya
- Biasanya karena obstruksi
- Hipotiroidisme
- Breast Milk Jaundice
- Infeksi
- Neonatal hepatitis
- Galaktosemia
- Lain-lain
Pemeriksaan yang perlu dilakukan :
- Pemeriksaan bilirubin (direk dan indirek) berkala
- Pemeriksaan darah tepi
- Pemeriksaan penyaring G-6-PD
- Biakan darah, biopsi hepar bila ada indikasi
- Pemeriksaan lainnya yang berkaitan dengan kemungkinan penyebab
-
26
Penyinaran dapat dilakukan dengan:
1. Pertimbangkan terapi sinar pada:
- NCB (neonatus cukup bulan) SMK (sesuai masa kehamilan) sehat :
kadar bilirubin total > 12 mg/dL
- NKB (neonatus kurang bulan) sehat : kadar bilirubin total > 10 mg/dL
2. Pertimbangkan tranfusi tukar bila kadar bilirubin indirek > 20 mg/dL
3. Terapi sinar intensif
- Terapi sinar intensif dianggap berhasil, bila setelah ujian penyinaran
kadar bilirubin minimal turun 1 mg/dL.2
Dapat diambil kesimpulan bahwa ikterus baru dapat dikatakan fisiologis
sesudah observasi dan pemeriksaan selanjutnya tidak menunjukkan dasar
patologis dan tidak mempunyai potensi berkembang menjadi kernicterus. Ikterus
yang kemungkinan besar menjadi patologis yaitu :
1. Ikterus yang terjadi pada 24 jam pertama
2. Ikterus dengan kadar bilirubin melebihi 12,5 mg% pada neonatus cukup bulan
dan 10 mg% pada neonatus kurang bulan
3. Ikterus dengan peningkatan bilirubin-lebih dari 5 mg%/hari
4. Ikterus yang menetap sesudah 2 minggu pertama
5. Ikterus yang mempunyai hubungan dengan proses hemolitik, infeksi atau
keadaan patologis lain yang telah diketahui
6. Kadar bilirubin direk melebihi 1 mg%
II. Pencegahan
Ikterus dapat dicegah dan dihentikan peningkatannya dengan :
1. Pengawasan antenatal yang baik
2. Menghindari obat yang dapat meningkatkan ikterus pada bayi pada masa
kehamilan dan kelahiran, misalnya sulfafurazole, novobiosin, oksitosin dan
lain-lain
3. Pencegahan dan mengobati hipoksia pada janin dan neonatus
4. Penggunaan fenobarbital pada ibu 1-2 hari sebelum partus
5. Iluminasi yang baik pada bangsal bayi baru lahir
-
27
6. Pemberian makanan yang dini
7. Pencegahan infeksi
III. Mengatasi hiperbilirubinemia
Mempercepat proses konjugasi, misalnya dengan pemberian
fenobarbital. Obat ini bekerja sebagai enzyme inducer sehingga konjugasi
dapat dipercepat. Pengobatan dengan cara ini tidak begitu efektif dan
membutuhkan waktu 48 jam baru terjadi penurunan bilirubin yang berarti.
Mungkin lebih bermanfaat bila diberikan pada ibu kira-kira 2 hari sebelum
melahirkan.
Memberikan substrat yang kurang untuk transportasi atau konjugasi.
Contohnya yaitu pemberian albumin untuk mengikat bilirubin yang bebas.
Albumin dapat diganti dengan plasma dengan dosis 15-20 ml/kgBB. Albumin
biasanya diberikan sebelum tranfusi tukar dikerjakan oleh karena albumin
akan mempercepat keluarnya bilirubin dari ekstravaskuler ke vaskuler
sehingga bilirubin yang diikatnya lebih mudah dikeluarkan dengan tranfusi
tukar. Pemberian glukosa perlu untuk konjugasi hepar sebagai sumber energi.
Melakukan dekomposisi bilirubin dengan fototerapi. Walaupun
fototerapi dapat menurunkan kadar bilirubin dengan cepat, cara ini tidak dapat
menggantikan tranfusi tukar pada proses hemolisis berat. Fototerapi dapat
digunakan untuk pra dan pasca-tranfusi tukar.
Fototerapi
Penelitian Sarici mendapatkan 10,5% neonatus cukup bulan dan 25,5%
-
28
neonatus kurang bulan menderita hiperbilirubinemia yang signifikan dan
membutuhkan fototerapi.
Fototerapi diindikasikan pada kadar bilirubin yang meningkat sesuai
dengan umur pada neonatus cukup bulan atau berdasarkan berat badan pada
neonatus kurang bulan, sesuai dengan rekomendasi American Academy of
Pediatrics (AAP).
Sinar Fototerapi
Sinar yang digunakan pada fototerapi adalah suatu sinar tampak yang
merupakan suatu gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang
elektromagnetik bervariasi menurut frekuensi dan panjang gelombang, yang
menghasilkan spektrum elektromagnetik. Spektrum dari sinar tampak ini
terdiri dari sinar merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Masing masing
dari sinar memiliki panjang gelombang yang berbeda beda.
Panjang gelombang sinar yang paling efektif untuk menurunkan kadar
bilirubin adalah sinar biru dengan panjang gelombang 425-475 nm.Sinar biru
lebih baik dalam menurunkan kadar bilirubin dibandingkan dengan sinar biru-
hijau, sinar putih, dan sinar hijau. Intensitas sinar adalah jumlah foton yang
diberikan per sentimeter kuadrat permukaan tubuh yang terpapar. Intensitas
yang diberikan menentukan efektifitas fototerapi, semakin tinggi intensitas
sinar maka semakin cepat penurunan kadar bilirubin serum.Intensitas sinar,
yang ditentukan sebagai W/cm2/nm.
Intensitas sinar yang diberikan menentukan efektivitas dari fototerapi.
Intensitas sinar diukur dengan menggunakan suatu alat yaitu radiometer
fototerapi.28,36 Intensitas sinar 30 W/cm2/nm cukup signifikan dalam
menurunkan kadar bilirubin untuk intensif fototerapi. Intensitas sinar yang
diharapkan adalah 10 40 W/cm2/nm. Intensitas sinar maksimal untuk
fototerapi standard adalah 30 50 W/cm2/nm. Semakin tinggi intensitas
sinar, maka akan lebih besar pula efikasinya.
Faktor-faktor yang berpengaruh pada penentuan intensitas sinar ini
adalah jenis sinar, panjang gelombang sinar yang digunakan, jarak sinar ke
neonatus dan luas permukaan tubuh neonatus yang disinari serta penggunaan
-
29
media pemantulan sinar.
Intensitas sinar berbanding terbalik dengan jarak antara sinar dan
permukaan tubuh. Cara mudah untuk meningkatkan intensitas sinar adalah
menggeser sinar lebih dekat pada bayi.
Rekomendasi AAP menganjurkan fototerapi dengan jarak 10 cm
kecuali dengan menggunakan sinar halogen.Sinar halogen dapat menyebabkan
luka bakar bila diletakkan terlalu dekat dengan bayi. Bayi cukup bulan tidak
akan kepanasan dengan sinar fototerapi berjarak 10 cm dari bayi. Luas
permukaan terbesar dari tubuh bayi yaitu badan bayi, harus diposisikan di
pusat sinar, tempat di mana intensitas sinar paling tinggi.
Tabel Rekomendasi AAP penanganan hiperbilirubinemia pada neonatus sehat dan cukup bulan
Usia ( jam ) Pertimbangan
terapi sinar Terapi sinar
Transfusi
tukar
Transfusi tukar
dan terapi sinar
25-48 >12mg/dl
(>200 mol/L)
>15 mg/dl
( >250 mol/L)
>20 mg/dl
(>340 mol/L)
>25 mg/dl
(425 mol/L)
49-72 >15mg/dl
(>250 mol/L)
>18 mg/dl
(>300mol/L)
>25mg/dl
(425 mol/L)
>30 mg/dl
(510mol/L)
>72 >17 mg/dl
(>290 mol/L)
>20mg/dl
(>340mol/L
>25mg/dl
(>425 mol/L)
>30mg/dl
(>510 mol/L)
Tabel Tatalaksana hiperbilirubinemia pada Neonatus Kurang Bulan Sehat dan Sakit ( >37 minggu ) Neontaus kurang bulan sehat :
Kadar Total Bilirubin Serum
(mg/dl)
Neontaus kurang bulan sakit :
Kadar Total Bilirubin Serum
(mg/dl)
Berat Terapi sinar Transfusi tukar Terapi sinar Transfusi tukar
Hingga 1000 g 5-7 10 4-6 8-10
1001-1500 g 7-10 10-15 6-8 10-12
1501-2000 g 10 17 8-10 15
>2000 g 10-12 18 10 17
-
30
Kontraindikasi fototerapi adalah pada kondisi dimana terjadi
peningkatan kadar bilirubin direk yang disebabkan oleh penyakit hati atau
obstructive jaundice.
Komplikasi terapi sinar
Setiap cara pengobatan selalu akan disertai efek samping. Di dalam
penggunaan terapi sinar, penelitian yang dilakukan selama ini tidak
memperlihatkan hal yang dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang bayi,
baik komplikasi segaera ataupun efek lanjut yang terlihat selama ini ebrsifat
sementara yang dapat dicegah atau ditanggulangi dengan memperhatikan tata
cara pengunaan terapi sinar yang telah dijelaskan diatas.
Kelainan yang mungkin timbul pada terapi sinar antara lain :
1. Peningkatan insensible water loss pada bayi
Hal ini terutama akan terlihat pada bayi yang kurnag bulan. Oh dkk (1972)
melaporkan kehilangan ini dapat meningkat 2-3 kali lebih besar dari keadaan
biasa. Untuk hal ini pemberian cairan pada penderita dengan terapi sinar perlu
diperhatikan dengan sebaiknya.
2. Frekuensi defekasi yang meningkat
Banyak teori yang menjelaskan keadaan ini, antara lain dikemukankan karena
meningkatnya peristaltik usus (Windorfer dkk, 1975). Bakken (1976)
mengemukakan bahwa diare yang terjadi akibat efek sekunder yang terjadi
pada pembentukan enzim lactase karena meningkatnya bilirubin indirek pada
usus. Pemberian susu dengan kadar laktosa rendah akan mengurangi
timbulnya diare. Teori ini masih belum dapat dipertentangkan (Chung dkk,
1976)
3. Timbulnya kelainan kulit yang sering disebut flea bite rash di daerah muka,
badan dan ekstremitas. Kelainan ini segera hilang setelah terapi dihentikan.
Pada beberapa bayi dilaporkan pula kemungkinan terjadinya bronze baby
syndrome (Kopelman dkk, 1976). Hal ini terjadi karena tubuh tidak mampu
mengeluarkan dengan segera hasil terapi sinar. Perubahan warna kulit yang
bersifat sementara ini tidak mempengaruhi proses tumbuh kembang bayi.
4. Gangguan retina
-
31
Kelainan retina ini hanya ditemukan pada binatang percibaan (Noel dkk
1966). Pnelitain Dobson dkk 1975 tidak dapat membuktikan adanya
perubahan fungsi mata pada umumnya. Walaupin demikian penyelidikan
selanjutnya masih diteruskan.
5. Gangguan pertumbuhan
Pada binatang percobaan ditemukan gangguan pertumbuhan (Ballowics 1970).
Lucey (1972) dan Drew dkk (10976) secara klinis tidak dapat menemukan
gangguan tumbuh kembang pada bayi yang mendapat terapi sinar. Meskipun
demikian hendaknya pemakaian terapi sinar dilakukan dengan indikasi yang
tepat selama waktu yang diperlukan.
6. Kenaikan suhu
Beberapa penderita yang mendapatkan terapi mungkin memperlihatkan
kenaikan suhu, Bila hal ini terjadi, terapi dapat terus dilanjutkan dengan
mematikan sebagian lampu yang dipergunakan.
7. Beberapa kelainan lain seperti gangguan minum, letargi, iritabilitas kadang-
kadang ditemukan pada penderita. Keadaan ini hanya bersifat sementara dan
akan menghilang dengan sendirinya.
8. Beberapa kelainan yang sampai saat ini masih belim diketahui secara pasti
adalah kelainan gonad, adanya hemolisis darah dan beberapa kelainan
metabolisme lain.
Sampai saat ini tampaknya belum ditemukan efek lanjut terapi sinar
pada bayi. Komplikasi segera juga bersifat ringan dan tidak berarti
dibandingkan dengan manfaat penggunaannya. Mengingat hal ini, adalah
wajar bila terapi sinar mempunyai tempat tersendiri dalam penatalaksanaan
hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir.
Tranfusi tukar
Pada umumnya tranfusi tukar dilakukan dengan indikasi sebagai
berikut :
- Pada semua keadaan dengan kadar bilirubin indirek 20 mg%
- Kenaikan kadar bilirubin indirek yang cepat, yaitu 0,3-1 mg%/jam.
-
32
- Anemia yang berat pada neonatus dengan gejala gagal jantung.
- Bayi dengan kadar hemoglobin talipusat < 14 mg% dan uji Coombs direk
positif.
Sesudah tranfusi tukar harus diberi fototerapi. Bila terdapat keadaan
seperti asfiksia perinatal, distres pernafasan, asidosis metabolik, hipotermia,
kadar protein serum kurang atau sama dengan 5 g%, berat badan lahir kurang
dari 1.500 gr dan tanda-tanda gangguan susunan saraf pusat, penderita harus
diobati seperti pada kadar bilirubin yang lebih tinggi berikutnya.
Adapun teknik transfusi tukar yang digunakan adalah :
1. SIMPLE DOUBLE VOLUME
Push-Pull tehnique : jarum infus dipasang melalui kateter vena
umbilikalis/ vena saphena magna. Darah dikeluarkan dan dimasukkan
bergantian.
2. ISOVOLUMETRIC
Darah secara bersamaan dan simultan dikeluarkan melalui arteri
umbilikalis dan dimasukkan melalui vena umbilikalis dalam jumlah yang
sama.
3. PARTIAL EXCHANGE TRANFUSION
Tranfusi tukar sebagian, dilakukan biasanya pada bayi dengan polisitemia
Indikasi Transfusi Tukar Berdasarkan Kadar Bilirubin Serum
Usia Bayi Cukup Bulan Sehat Dengan Faktor Risiko
Hari mg/dL mg/Dl
Hari ke-1 15 13
Hari ke-2 25 15
Hari ke-3 30 20
Hari ke-4 dan
seterusnya
30 20
-
33
Indikasi Transfusi Tukar pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah
Berat badan (gram) Kadar Bilirubin (mg/dL)
>
-
34
dilakukan pemeriksaan berkala, baik dalam hal pertumbuhan fisis dan motorik,
ataupun perkembangan mental serta ketajaman pendengarannya.
-
35
BAB IV
PEMBAHASAN
Pasien datang dibawa oleh ibunya dengan keluhan badan tampak kuning. Ibu
pasien mengetahui badan kuning sejak 2 hari, yaitu saat usia pasien 19 hari.
Anamnesis ini bertujuan untuk menilai etiologi ikterus yang terjadi pada pasien.
Berdasarkan waktu timbulnya, yaitu lebih dari hari ke-10, maka etiologi yang
mungkin adalah atresia biliaris, hipotiroidisme, breast milk jaundice, galaktosemia,
hepatitis neonatal, kista koledokus, sepsis atau infeksi neonatorum, dan stesonis
pilorus. Kuning terdapat di seluruh tubuh pasien, tampak pertama kali di wajah yang
semakin lama semakin kuning kemudian menyebar ke seluruh tubuh kecuali telapak
kaki. Anamnesis ini ditanyakan untuk melihat penyebaran ikterus, sehingga dapat
dilakukan penilaian derajat ikterus menurut Kramer. Cara ini dapat mememperkirakan
secara kasar kadar bilirubin serum dan untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap
bilirubin indirek bebas atau direk secara laboratorium. Pasien dinilai masuk dalam
Kramer IV dengan perkiraan bilirubin total 13 -17 mg%. Keluhan kuning disertai
dengan malas minum sejak 3 hari, sering cegukan, menangis kurang kuat dan lebih
jarang. Anamnesis ini bertujuan untuk menilai apakah telah terjadi komplikasi kern
ikterus yang memiliki gejala awal berupa menurunnya aktivitas bayi, peningkatan
iritabilitas, dan kesukaran minum. Pada pasien ditemukan adanya gejala prodromal
dari kern ikterus yaitu penederita tampak lesu, mengantuk, dan malas minum. Buang
air besar tidak tampak seperti dempul dan buang air kecil tidak berwarna teh pekat.
Pada penderita ini kemungkinan ikteruk terjadi prehepatik karena tidak ada tanda-
tannda yang mengarahkan kepada ikterus intrahepatik atau post hepatik. Pasien
diperiksakan ke bidan dan ditimbang berat badannya 2100 gram. Pasien belum pernah
mengalami keluhan kuning sebelumnya. Tidak ada riwayat kelainan kongenital pada
pasien. Pasien lahir kurang bulan dengan BBLR, yaitu 2300 gram, PB 42 cm, lahir di
bidan. Dari anamnesis didapatkan bahwa penderita lahir prematur yang mungkin
dapat menyebabkan pasien rentan terhadap ikterus neonatorum melalui mekanisme
campuran yaitu terjadinya produksi bilirubin yang berlebihan dan sekresi yang
menurun, dan juga risiko persalinan yang kurang higienis yang dapat meningkatkan
kejadian infeksi neonatorum. Pasien sejak lahir diberi asupan ASI yang diberikan
setiap pasien menangis. Tidak ada makanan tambahan yang diberikan pada pasien.
-
36
Tidak ada riwayat sakit kuning, kelainan darah, atau kekurangan darah dalam
keluarga pasien sehingga melemahkan kemungkinan adanya penyakit hepatitis B pada
ibu yang dapat ditularkan ke janin dan menimbulkan ikterus neonatorum. Selama
hamil, ibu pasien tidak mengkonsumsi obat-obatan atau jamu dari bidan sehingga
kemungkinan ikterus disebabkan oleh obat yang menghambat daya ikat albumin dan
daya kerja glukoronil transferase sehingga menyebabkan peningkatan kadar bilirubin
serum dapat dilemahkan.
Pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya kejang, demam terjadi di hari
kedua perawatan dengan suhu 38.3oC, kondisi letargi. Hasil pemeriksaan ini
menunjukkan adanya infeksi neonatorum yang mungkin juga merupakan gejala
prodormal dari kernikterus. Pasien tidak pucat, nadi cepat dengan HR 162x/menit,
tidak terdapat napas cepat dengan RR 18x/menit di hari pertama perawatan,
ditemukan napas cuping hidung, dan terdapat retraksi suprasternal. Pada pemeriksaan
gastrointestinal, abdomen tampak datar dengan bising usus normal, tidak muntah,
dengan intake ASI. Pemeriksaan sistem integumen menunjukkan kulit tampak ikter di
seluruh bagian tubuh kecuali telapak kaki, tanpa adanya ptekie. Berat badan pasien
saat pemeriksaan adalah 2100 gram menunjukkan kemungkinan adanya dehidrasi.
Hasil laboratorium menunjukkan Hb 11.4 g/dl, leukosit 19.100 yang
menunjukkan adanya infeksi, eritrosit 3.190.000, hematokrit 34.7%, trombosit
301.000, morfologi darah tepi menunjukkan gambaran proses infeksi bakterial dan
viral, kimia klinik menunjukkan bilirubin total 14.80 mg/dl, sesuai dengan perkiraan
kadar bilirubin berdasarkan indeks Kramer, bilirubin direk 0.85 mg/dl, dan bilirubin
indirek 13.95 mg/dl yang menandakan adanya peningkatan sehingga bermanifestasi
kulit ikterik.
Berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang maka
pasien didiagnosa dengan hiperbilirubinemia dengan infeksi neonatorum. Pasien
diberikan terapi berupa pemasangan fototerapi 2 x 24 jam, CPAP PEEP 5 FiO2 60%,
infus D5 NS 300 cc / 24 jam, injeksi cefotaxim 2 x 100 mg (IV) selama 5 hari, dan
diet ASI. Ibu dianjurkan untuk menyusui bayinya paling sedikit 8-12 kali per hari, dan
pasien tidak diberikan cairan tambahan rutin seperti dekstrose atau air. Pemberian
infus didasarkan pada penurunan berat badan yang terjadi pada pasien yang mungkin
menandakan adanya dehidrasi. Pada bayi dengan dehidrasi, dianjurkan untuk lebih
sering diberikan ASI atau bahkan cairan intravena.
-
37
Sinar fototerapi akan mengubah bilirubin yang ada di dalam kapiler-kapiler
superfisial dan ruang-ruang usus menjadi isomer yang larut dalam air yang dapat
diekstraksikan tanpa metabolisme lebih lanjut oleh hati. Bila fototerapi menyinari
kulit, akan memberikan foton-foton diskrit energi, sama halnya seperti molekul-
molekul obat, sinar akan diserap oleh bilirubin dengan cara yang sama dengan
molekul obat yang terikat pada reseptor. Molekul-molekul bilirubin pada kulit yang
terpapar sinar akan mengalami reaksi fotokimia yang relatif cepat menjadi isomer
konfigurasi, dimana sinar akan merubah bentuk molekul bilirubin dan bukan
mengubah struktur bilirubin. Bentuk bilirubin 4Z, 15Z akan berubah menjadi bentuk
4Z,15E yaitu bentuk isomer nontoksik yang bisa diekskresikan. Isomer bilirubin ini
mempunyai bentuk yang berbeda dari isomer asli, lebih polar dan bisa diekskresikan
dari hati ke dalam empedu tanpa mengalami konjugasi atau membutuhkan
pengangkutan khusus untuk ekskresinya. Bentuk isomer ini mengandung 20% dari
jumlah bilirubin serum. Eliminasi melalui urin dan saluran cerna sama-sama penting
dalam mengurangi muatan bilirubin. Reaksi fototerapi menghasilkan suatu
fotooksidasi melalui proses yang cepat.
-
38
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
V.1 Kesimpulan
Hiperbilirubinemia merupakan salah satu fenomena klinis yang paling sering
ditemukan pada bayi baru lahir. Lebih dari 85% bayi cukup bulan yang kembali
dirawat dalam minggu pertama kehidupan disebabkan oleh keadaan ini.
Hiperbilirubinemia menyebabkan bayi terlihat berwarna kuning, keadaan ini timbul
akibat akumulasi pigmen bilirubin (4Z, 15Z bilirubin IX alpha) yang berwarna ikterus
pada sklera dan kulit.
Pada masa transisi setelah lahir, hepar belum berfungsi secara optimal,
sehingga proses glukuronidasi bilirubin tidak terjadi secara maksimal. Keadaan ini
akan menyebabkan dominasi bilirubin tak terkonjugasi di dalam darah. Pada
kebanyakan bayi baru lahir, hiperbilirubinemia tak terkonjugasi merupakan fenomena
transisional yang normal, tetapi pada beberapa bayi, terjadi peningkatan bilirubin
secara berlebihan sehingga bilirubin berpotensi menjadi toksik dan dapat
menyebabkan kematian dan bila bayi tersebut dapat bertahan hidup pada jangka
panjang akan menimbulkan sekuele neurologis. Dengan demikian, setiap bayi yang
mengalami kuning, harus dibedakan apakah ikterus yang terjadi merupakan keadaan
yang fisiologis atau patologis serta dimonitor apakah mempunyai kecenderungan
untuk berkembang menjadi hiperbilirubinemia yang berat.
V.2. Saran
Setiap bayi dengan ikterus harus mendapatkan perhatian, terutama apabila
ikterus ditemukan dalam 24 jam pertama kehidupan bayi atau bila kadar bilirubin
meningkat > 5 mg/dL (> 86mol/L) dalam 24 jam. Ibu-ibu dianjurkan untuk
menyusui bayinya paling sedikit 8-12 kali per hari untuk beberapa hari pertama serta
tidak memberikan cairan tambahan rutin seperti dekstrosa atau air pada bayi yang
mendapat ASI dan tidak mengalami dehidrasi. Sebagai pencegahan sekunder, semua
wanita hamil harus diperiksakan golongan darah ABO dan rhesus serta penyaringan
serum antibodi isoimun yang tidak biasa. Pastikan bahwa semua bayi secara rutin
dimonitor terhadap timulnya ikterus.
-
39
DAFTAR PUSTAKA
1. Damanik, Sylvia. Pedoman Diagnosis dan Terapi Bagian Ilmu Kesehatan
Anak. Edisi III. 2008. Rumah Sakit dokter Soetomo. Hiperbilirubinemia.
Hal : 17-21.
2. Etika, Risa dkk. Hiperbilirubinemia pada Neonatus. Divisi Neonatologi
Bagian Ilmu Kesehatan Anak. FK Unair/RSU Dr. Soetomo Surabaya.
3. Sukadi, Abdulrahman. Buku Ajar Neonatologi. Ikatan Dokter Anak
Indonesia. Edisi I. 2010. IDAI. Hal 147-169.
4. Anonymous, Ikterus pada Anak, available at: http://medlinux.blogspot.com/
2007/09/ikterus-pada-anak.html
5. Klik Dokter, Ikterus Neonatorum, available at: http://www.klikdokter.com/
illness/detail/212.
6. Glaser, K.L., Jaundice and Hyperbilirubinemia in the Newborn, available
at: http://www.medstudents.com.br/pedia/pedia3.html.