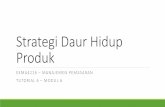fistan 6
Transcript of fistan 6
LAPORAN PRAKTIKUMFISIKA TANAH
Oleh:Yarsitri
NIM A1H012066
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS PERTANIANPURWOKERTO
2014
LAPORAN PRAKTIKUM
FISIKA TANAH
PENETAPAN TEKSTUR TANAH METODE PIPET
Oleh:Yarsitri
NIM A1H012066
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS PERTANIANPURWOKERTO
2014
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan
organik. Tanah sangat penting peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena
tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air
sekaligus sebagai penopang akar. Tanah merupakan campuran bahan atau
partikel-partikel bahan organik yang telah melapuk, udara dan air. Materi kasar
seperti pasir biasanya ditutupi oleh material halus. Ukuran dari partikel-partikel
tanah relatif tidak berubah. Karena itu, tekstur tanah dikategorikan sebagai sifat
dasar tanah.
Tekstur tanah menunjukkan kasar atau halusnya suatu tanah. Tekstur
merupakan perbandingan relatif pasir, debu dan liat. Kasar dan halusnya tanah
dalam klasifikasi tanah (taksnomi tanah) ditunjukkan dalam sebaran butir yang
merupakan penyederhanaan dari kelas tekstur tanah dengan memperhatikan pula
fraksi tanah yang lebih kasar dari pasir (lebih besar 2 mm), sebagian besar butir
untuk fraksi kurang dari 2 mm meliputi berpasir lempung, berpasir, berlempung
halus, berdebu kasar, berdebu halus, berliat halus, dan berliat sangat halus.
Penentuan kelas tekstur suatu tanah secara teliti harus dilakukan analisa
tekstur di laboratorium yang disebut analisa mekanik tanah. Dalam menetapkan
tekstur tanah ada tiga metode yang digunakan yaitu metode lapang, hydrometer,
dan pipet. Sedangakan metode yang digubakan pada praktikum kali ini adalah
metode pipet.
B. Tujuan
1. Mahasiswa dapat mengetahui batas cair tanah (BC).
2. Mahasiswa dapat mengetahui batas lekat tanah (BL).
3. Mahasiswa dapat mengetahui batas gulung tanah (BG).
4. Mahasiswa dapat mengetahui batas berubah warna (BBW).
II. TINJAUAN PUSTAKA
Tanah merupakan suatu sistem mekanik yang kompleks terdiri dari tiga fase
yakni bahan-bahan padat, cair dan gas. Fase padat hampir menempati 50 %
volume tanah sebagian besar terdiri dari bahan mineral dan sebagian lainnya
adalah bahan organik. Sisa volume selebihnya merupakan ruang pori yang
ditempati sebagian oleh fase cair dan fase gas yang perbandingannya dapat
bervariasi menurut musim dan pengelolaan tanah.. Tanah berfungsi sebagai
tempat tumbuhnya tanaman yang menangkap sinar matahari.. Di samping itu
kebanyakan unsur-unsur dalam usaha memelihara kehidupan berada pada siklus
yang lebih berat ke tanah dalam hubungan ini tanah menyediakan lingkungan
yang cocok untuk terlaksananya pelapukan bahan-bahan mati dengan cukup cepat
melalui aktivitas mikroorganisme terhadap senyawa-senyawa dasar untuk dapat
segera menyusul memasuki kembali siklus, terutama melalui vegetasi.
Tekstur tanah menunjukkan komposisi partikel penyusun tanah (separat)
yang dinyatakan sebagai perbandingan proporsi (%) relatif antara fraksi pasir,
fraksi debu dan fraksi liat (Hanafiah, 2008).
Tekstur merupakan sifat kasar-halusnya tanah dalam percobaan yang
ditentukan oleh perbandingan banyaknya zarah-zarah tunggal tanah dari berbagai
kelompok ukuran, terutama perbandingan antara fraksi-fraksi lempung, debu, dan
pasir berukuran 2 mm ke bawah (Notohadiprawito, 1978).
Tanah terdiri dari butir-butir yang berbeda dalam ukuran dan bentuk,
sehingga diperlukan istilah-istilah khusus yang memberikan ide tentang sifat
teksturnya dan akan memberikan petunjuk tentang sifat fisiknya. Untuk ini
digunakan nama kelas seperti pasir, debu, liat dan lempung. Nama kelas dan
klasifikasinya ini, merupakan hasil riset bertahun-tahun dan lambat laun
digunakan sebagai patokan. Tiga golongan pokok tanah yang kini umum dikenal
adalah pasir, liat dan lempung(Buckman dan Brady, 1992)
Pembagian kelas tekstur yang banyak dikenal adalah pembagian 12 kelas
tekstur menurut USDA.Nama kelas tekstur melukiskan penyebaran butiran,
plastisitas, keteguhan, permeabilitas kemudian pengolahan tanah, kekeringan,
penyediaan hara tanah dan produktivitas berkaitan dengan kelas tekstur dalam
suatu wilayah geogtrafis (A.K. Pairunan, dkk, 1985).
Tekstur tanah dapat menentukan ssifat-sifat fisik dan kimia serta mineral
tanah. Partikel-partikel tanah dapat dibagi atas kelompok-kelompok tertentu
berdasarkan ukuran partikel tanpa melihat komposisi kimia, warna, berat, dan sifat
lainnya. Analisis laboratorium yang mengisahkan hara tanah disebut analisa
mekanis. Sebelum analisa mekanis dilaksanakan, contoh tanah yang kering udara
dihancurkan lebih dulu disaring dan dihancurkan dengan ayakan 2 mm.
Sementara itu sisa tanah yang berada di atas ayakan dibuang. Metode ini
merupakan metode hidrometer yang membutuhkan ketelitian dalam
pelaksanaannya. Tekstur tanah dapat ditetapkan secara kualitatif dilapangan
(Hakim, 1986).
Tekstur tanah dibagi menjadi 12 kelas seperti yang tertera pada diagram
segitiga tekstur tanah USDA yang meliputi pasir, pasir berlempung, lempung
berpasir, lempung, lempung liat berpasir, lempung liat berdebu, lempung
berliat, lempung berdebu, debu, liat berpasir, liat berdebu, dan liat (Lal, 1979).
Tanah terdiri dari butir-butir pasir, debu, dan liat sehingga tanah
dikelompokkan kedalam beberapa macam kelas tekstur, diantaranya kasar, agak
kasar, sedang, agak halus,dan hancur (Hardjowigeno, 1995).
Kasar dan halusnya tanah dalam klasifikasi tanah (taksnomi tanah)
ditunjukkan dalam sebaran butir yang merupakan penyederhanaan dari kelas
tekstur tanah dengan memperhatikan pula fraksi tanah yang lebih kasar dari pasir
(lebih besar 2 mm), sebagian besar butir untuk fraksi kurang dari 2 mm meliputi
berpasir lempung, berpasir, berlempung halus, berdebu kasar, berdebu halus,
berliat halus, dan berliat sangat halus (Hardjowigeno, 1995).
Sifat-sifat fisik tanah diketahui sangat mempengaruhi pertumbuhan
dan produksi tanaman. Kondisi fisik tanah menentukan penetrasi akar di
dalam tanah,retensi air, drainase, aerasi, dan nutrisi tanaman. Tekstur tanah
penting untuk kitaketahui karena komposisi ketiga fraksi butir-butir tanah tersebut
(fraksi padat,cair, dan gas) akan menentukan sifat-sifat fisika, dan kimia tanah.
Sifat fisik yang dipengaruhi tekstur antara lain daya dukung tanah, daya
serap atau daya simpan air, permeabilitas, erodibilitas (kemudahan tanah tererosi),
kemudahan penetrasi akar tanaman, drainase atau pengatusan, kemudahan terolah,
plastisitas, dan kelekatan. Tekstur tanah selain dapat menentukan sifat-sifat fisik
tanah, juga dapat menentukan sifat kimia dan mineral tanah. Perbedaan komposisi
fraksi dan pengaruhnya terhadap sifat fisik tanah adalah sebagai berikut:
1. Kemudahan pengolahan tanah atau lahan
Tanah yang didominasi fraksi pasir akan lebih mudah diolah, sedangkan
tanah yang didominasi fraksi lempung akan lebih sulit diolah karena
bertekstur keras dan liat.
2. Daya serap atau daya simpan air
Fraksi tanah yang berupa lempung akan sangat mudah menyerap dan
menyimpan air karena memiliki kemampuan menyerap air tinggi, sedangkan
tanah berpasir akan lebih sulit dalam menyimpan air karena memiliki pori
yang besar.
3. Erodibilitas (kemudahan tanah tererosi)
Tanah dengan tekstur pasir akan mudah tererosi karena memiliki tekstur
yang lepas-lepas dan memiliki pori-pori yang besar, sedangkan tanah
bertekstur lempung akan lebih sulit tererosi karena memiliki tekstur yang liat
dan keras.
4. Kemudahan penetrasi akar tanaman
Tanah dengan kandungan silt (debu) dan clay (lempung) yang tinggi
sangat sulitditembus oleh akar-akar tanaman sehingga percabangan dan
perkembangan akar terhambat. Hal ini akan berpengaruh pada daerah yang
mempunyai iklim kering panjang. Tanaman yang masih berumur muda sangat
peka terhadap tekstur tanah sehingga dapat menghasilkan tanaman dewasa
yang berbeda.
III. METODOLOGI
A. Alat dan Bahan
1. Gelas piala
2. Gelas beker 1000 ml
3. Gelas ukur
4. Kertas lakmus biru
5. Kompor
6. Pipet
7. Oven
8. Thermometer
9. Stopwatch
10. Timbangan analitik
11. Ayakan dan cawan porselin
12. Tanah kering udara
13. Larutan H2O2
14. Larutan HCl
15. Larutan NaOH
16. Aquades
B. Prosedur Kerja
1. Mengeringkan tanah dengan cara diangin-anginkan
2. Menambahkan 25 ml H2O2 selama 24 jam untuk menghilangkan
mikroorganisme.
3. Memanaskan tanah kering udara diatas kompor dan menambahkan H2O2
sampai buih hilang (75).
4. Mendinginkan larutan yang sudah terbentuk.
5. Menambahkan 15 ml HCl kemudian dipanaskan hingga mendidih.
6. Menambahkan air hingga 500 ml.
7. Memindahkan ke gelas beker dan menambahkan 10 ml NaOH, diaduk
selama 15 menit kemudian ditambah air sampai 1000 ml.
8. Memasukkan air ke gelas piala untuk memisahkan pasirnya.
9. Larutan dalam gelas piala didiamkan hingga liat dan debu memisah.
10. Mengukur suhu pada gela spiala dan mencocokkan dengan tabel.
11. Mengambil air yang mengandung debu menggunakan pipet 25 ml
sebanyak 20 ml pada kedalaman 20 ml.
12. Memasukkan ke cawan porselin.
13. Menimbang cawan yang berisi air dan debu dan memasukkannya ke oven
dimana cawan yang digunakan sebelumnya sudah ditimbang.
14. Tiga jam kemudian , mengambil air yang mengandung liat pada
kedalaman 5 ml sebanyak 20 ml.
15. Ditimbang dan dimasukkan ke oven. Setelah 24 jam dari memasukkan
cawan ke oven, maka ambil cawan dan ditimbang kemudian dicatat
hasilnya.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
Tabel 1. Hasil pengamatan
Nama CawanBerat Cawan Kosong (a)
gram
Berat Cawan + isi setelah dioven
(b) gram
A (pasir) 42,32 43,86
B (debu liat) 47,12 47,33
C (liat) 43,85 44,03
Penetapan Tekstur
1. Gram pasir (P) = b – a gram
= 43,86 – 42,32 gram
= 1,54 gram
2. Gram debu+liat (D+L) = b – a gram
= 47,33 – 47,12 gram
= 0,21 gram
3. Gram liat (L) = b – a gram
= 44,03 – 43,85 gram
= 0,18 gram
4. Gram debu (D) = (D+L) - L
= 0,21 – 0,18 gram
= 0,03 gram
Jumlah pasir, debu dan liat adalah 1,75 gram
1. Persen pasir = gram pasir
∑ PDL x 100%
= 1,541,75
x 100%
= 88 %
2. Persen debu = gram debu
∑ PDL x 100%
= 0,031,75
x 100%
= 1,71%
3. Persen liat = gram liat
∑ PDL x 100%
= 0,181,75
x 100%
= 10,28%
B. Pembahasan
Praktikum kali ini membahas tentang tekstur tanah dengan menggunakan
metode pemipetan. Tekstur tanah, biasa juga disebut besar butir tanah, termsuk
salah satu sifat tanah yang paling sering ditetapkan. Hal ini disebabkan karena
tekstur tanah berhubungan erat dlam pergerakan air dan zat terlarut, udara,
pergerakan panas, berat volume tanah, luas permukaan spesifik (specific surface),
kemudahan tanah memadat (compressibility), dan lain-lain (Hillel, 1982).
Tekstur tanah menunjukkan komposisi partikel penyusun tanah (separat)
yang dinyatakan sebagai perbandingan proporsi (%) relatif antara fraksi pasir,
fraksi debu dan fraksi liat (Hanafiah, 2008). kelompok ukuran, terutama
perbandingan antara fraksi-fraksi lempung, debu, dan pasir berukuran 2 mm ke
bawah (Notohadiprawito, 1978).
Tekstur merupakan sifat kasar-halusnya tanah dalam percobaan yang
ditentukan oleh perbandingan banyaknya zarah-zarah tunggal tanah dari berbagai
kelompok ukuran, terutama perbandingan antara fraksi-fraksi lempung, debu, dan
pasir berukuran 2 mm ke bawah (Notohadiprawito, 1978).
Tanah terdiri dari butir-butir yang berbeda dalam ukuran dan bentuk,
sehingga diperlukan istilah-istilah khusus yang memberikan ide tentang sifat
teksturnya dan akan memberikan petunjuk tentang sifat fisiknya. Untuk ini
digunakan nama kelas seperti pasir, debu, liat dan lempung. Nama kelas dan
klasifikasinya ini, merupakan hasil riset bertahun-tahun dan lambat laun
digunakan sebagai patokan. Tiga golongan pokok tanah yang kini umum dikenal
adalah pasir, liat dan lempung (Buckman dan Brady, 1992)
Kemampuan tanah ditentukan oleh sifat fisik dan sifat kimianya maka
penting untuk mengetahui sifat fisik dan kimianya. Pertumbuhan tanaman sangat
dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik tanah seperti tekstur, struktur dan kekuatan tanah.
Kemampuan tanah untuk menahan air harus mendapatkan perhatian serius agar
tidak mengganggu ketersediaan air tanah dalam upaya mendapatkan produksi
tanaman yang optimum. Untuk memperbaiki kemampuan tanah dalam menahan
air salah satunya dengan memperbaiki struktur, distribusi ukuran partikel serta
tekstur tanah.
Pengetahuan akan tekstur tanah sangat bermanfaat di berbagai bidang,
terutama di bidang pertanian. Kegunaan tekstur tanah adalah sebagai bahan
informasi dalam dalam menentukan tanaman budidaya apa yang cocok pada
daerah tersebut dengan jenis tekstur tertentu. Selain itu, tekstur tanah juga
berkaitan erat dengan sifat fisik tanah karena komposisi fraksi-fraksi tanah yang
berlainan dapat mempengaruhi sifat fisik tanah lainnya.
Tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena
terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu dan liat yang
terkandung pada tanah (Badan Pertanahan Nasional). dari ketiga jenis fraksi
tersebut partikel pasir mempunyai ukuran diameter paling besar yaitu 2 – 0.05
mm, debu dengan ukuran 0.05 – 0.002 mm dan liat dengan ukuran < 0.002 mm
(penggolongan berdasarkan USDA). Keadaan tekstur tanah sangat berpengaruh
terhadap keadaan sifat-sifat tanah yang lain seperti struktur tanah, permeabilitas
tanah, porositas dan lain-lain. Berbagai lembaga penelitian atau intuisi
mempunyai criteria sendiri untuk pembagian fraksi partikel tanah. Sebagai
contoh, pada akan diperlihatkan sistem klasifikai fraksi partikel menurut
International Soil Science Society (ISSS), United States Department of
Agriculture (USDA), dan United States Public Roads Administration (USPRA).
Tabel 2. Klasifikasi tekstur tanah menurut beberapa sistem (Hillel, 1982)ISSS USDA USPRA
Diameter
(mm)Fraksi
Diameter
(mm)Fraksi
Diameter
(mm)Fraksi
>2 Kerikil >0,02 Kerikil >2 Kerikil
0,02 - 2 Pasir 0,05 – 2 Pasir 0,05 – 2 Pasir
0,2 – 2
0,02 – 0,2
Kasar
Halus
1-2
0,5 – 1
0,25 – 0,5
0,1 – 0,25
0,05 - 0,1
Sangat
Kasar
Kasar
Sedang
Halus
Sangat
halus
0,25 – 2
0,05 – 0,25
Kasar
Halus
0,002 –
0,02Debu
0,002 –
0,05Debu 0,005 – 0,05 Debu
< 0,002 Liat <0,005 Liat <0,005 Liat
Segitiga tekstur merupakan suatu diagram untuk menentukan kelas-kelas
tekstur tanah. ada 12 kelas tekstur tanah yang dibedakan oleh jumlah persentase
ketiga fraksi tanah tersebut, misalkan hasil analisis lab menyatakan bahwa
persentase pasir (X) 32%, liat (Y) 42% dan debu (Z) 26%, berdasarkan diagram
segitiga tekstur maka tanah tersebut masuk kedalam golongan tanah
bertekstur pasir.
Menurut Hardjowigeno (1992) tekstur tanah menunjukkan kasar halusnya
tanah. Tekstur tanah merupakan perbandingan antara butir-butir pasir, debu dan
liat. Tekstur tanah dikelompokkan dalam 12 klas tekstur. Kedua belas klas tekstur
dibedakan berdasarkan prosentase kandungan pasir, debu dan liat seperti yang
digambarkan pada segitiga tekstur.
Gambar 1. Segitiga Tekstur
Ada beberapa metode dalam menententukan tekstur tanah, yaitu secara
kualitatif (dilakukan di lapang) dan kuantitatif (di laboratorium dengan
menggunakan analisis mekanis), secara kualitatif yaitu dapat dilakukan di
lapangan, berikut penjelasannya :
1. Penetapan di lapang dilakukan dengan membasahi tanah kering atau lembab,
kemudian dispirit diantara ibu jari dan telunjuk, sehingga membentuk pita
lembab, sambil diperhatikan adanya rasa kasar atau licin, dapat ditentukan
kelas tekstur lapang, atau dapat diamati bila memiliki cirri-ciri seperti ini :
a. Apabila rasa kasar terasa sangat jelas, tidak melekat, dan tidak dapat
dibentuk bola dan gulungan, maka tanah tersebut tergolong bertekstur
Pasir.
b. Apabila rasa kasar terasa jelas, sedikit sekali melekat, dan dapat dibentuk
bola tetapi mudah sekali hancur, maka tanah tersebut tergolong bertekstur
Pasir Berlempung.
c. Apabila rasa kasar agak jelas, agak melekat, dan dapat dibuat bola tetapi
mudah hancur, maka tanah tersebut tergolong bertekstur Lempung
Berpasir.
d. Apabila tidak terasa kasar dan tidak licin, agak melekat, dapat dibentuk
bola agak teguh, dan dapat sedikit dibuat gulungan dengan permukaan
mengkilat, maka tanah tersebut tergolong bertekstur Lempung.
e. Apabila terasa licin, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dan
gulungan dengan permukaan mengkilat, maka tanah tersebut tergolong
bertekstur Lempung Berdebu.
f. Apabila terasa licin sekali, agak melekat, dapat dibentuk bola teguh, dan
dapat digulung dengan permukaan mengkilat, maka tanah tersebut
tergolong bertekstur Debu.
g. Apabila terasa agak licin, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh,
dan dapat dibentuk gulungan yang agak mudah hancur, maka tanah
tersebut tergolong bertekstur Lempung Berliat.
h. Apabila terasa halus dengan sedikit bagian agak kasar, agak melekat, dapat
dibentuk bola agak teguh, dan dapat dibentuk gulungan mudah hancur,
maka tanah tersebut tergolong bertekstur Lempung Liat Berpasir.
i. Apabila terasa halus, terasa agak licin, melekat, dan dapat dibentuk bola
teguh, serta dapat dibentuk gulungan dengan permukaan mengkilat, maka
tanah tersebut tergolong bertekstur Lempung Liat Berdebu.
j. Apabila terasa halus, berat tetapi sedikit kasar, melekat, dapat dibentuk
bola teguh, dan mudah dibuat gulungan, maka tanah tersebut tergolong
bertekstur Liat Berpasir.
k. Apabila terasa halus, berat, agak licin, sangat lekat, dapat dibentuk bola
teguh, dan mudah dibuat gulungan, maka tanah tersebut tergolong
bertekstur Liat Berdebu.
l. Apabila terasa berat dan halus, sangat lekat, dapat dibentuk bola dengan
baik, dan mudah dibuat gulungan, maka tanah tersebut tergolong
bertekstur Liat.
2. Penetapan tekstur tanah di laboratorium, biasanya menggunakan analisis
mekanis proses ini terdiri dari pendispersian agregat tanah menjadi butir-butir
tunggal dan kemudian diikuti dengan sedimentasi. Dispersi dan sedimentasi
merupakan proses penting sebelum tekstur tanah ditentukan dengan salah satu
metode, metode hydrometer tau metode pipet. Dengan proses pendispersian,
butir-butir tanah yang biasanya lengket satu sama lain dalam suatu agregat
akan dipisahkan dengan cara membuang zat perekatnya dengan
menambahkan zat anti flokulasi. Zat perekat yang umum didalam tanah
adalah bahan organic (dihancurkan dengan hydrogen peroksida), kalsium
karbonat (asam klorida) dan oksida besi (Hillel, 1982). Sedangkan
sedimentasi digunakan untuk memisahkan partikel yang mempunyai ukuran
yang berbeda.
a. Metode hydrometer ”Bouyoucos”, (lebih teliti), yang didasarkan pada
perbedaan kecepatan jatuhnya partikel-partikel tanah di dalam air dengan
asumsi bahwa kecepatan jatuhnya partikel yang berkerapatan (density)
sama dalam suatu larutan akan meningkat secara linear apabila radius
partikel bertambah secara kuadratik (Hanafiah, 2005). Berikut prosedur
singkat menggunakan hydrometer :
Nilai RL adalah pembacaan kalibrasi hidrometer yang didapatkan dengan
prosedur sebagai berikut:
a) Tambahkan 50 ml 10% (NaPO3)6 ke dalam silinder sedimentasi yang
kosong.
b) Tambahkan aquades sehingga volume akhir larutan menjadi 1.000 ml.
c) Aduk dengan sempurna.
d) Celupkan hidrometer dan catat pembacaan (RL).
Pembacaan hidrometer dilakukan pada miniskus bagian atas suspensi
(larutan).
b. Metode pipet merupakan metode langsung pengambilan contoh partikel
tanah dari dalam suspense dengan menggunakan pipet pada kedalaman h
dan waktu t. pada kedalaman h dan waktu t tersebut partikel dengan
diameter >x sudah berada pada kedalaman h.
Pada praktikum penetapan tekstur tanah menggunakan metode pipet
digunakan beberapa larutan untuk analisis tekstur yaitu H2O2, NaOH dan HCl.
Penambahan H2O2 berfungsi untuk menghancurkan agregasi tanah-tanah yang
kaya akan bahan organik. Sedangkan NaOH merupakan senyawa kimia yang
berguna sebagai pendispersi. Dimana dengan penambahan NaOH ini larutan tanah
akan lebih mudah homogen dan dapat diketahui kadar lengasnya. Adapun fungsi
dari penambahan HCl yaitu sebagai penghilang kapur. Analisis tanah dengan
menggunakan larutan-larutan tersebut dilakukandengan harapan agar tekstur tanah
yang dihasilkan dari hasil analisis lebih alami atau mendekati keadaan tanah yang
sebenarnya dilapangan.
Hasil dari praktikum fisika tanah pada acara tentang penetapan tekstur
tanah dengan menggunakan metode pipet ini didapat hasil yaitu presentase pasir
sebesar 88%, presentase debu sebesar 1,71 % dan presentase liat sebesar 10,28 %.
Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui tekstur tanah dengan melihat
pada segitiga tekstur. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tanah yang digunakan
sample merupakan tanah bertekstur pasir. Jika dilihat dari jumlah banyaknya
presentase tiap fraksi, hasil yang didapatkan juga menunjukkan bahwa tanah yang
digunakan sample merupakan tanah bertekstur pasir karena memenuhi syarat
dimana tanah bertekstur pasir merupakan tanah yang kandungan pasirnya lebih
dari 75%.
Kandala pada praktikum kali ini adalah terbatasnya alat dan bahan yang
digunakan sehingga tidak semua praktikan dapat mengetahui cara penetapan
tekstur tanah dengan menggunakan metode pipet. Selain itu, pembagian shift yang
terlalu besar sehingga praktikum tidak berjalan secara kondusif dan banyak
praktikan yang kurang memperhatikan jalannya praktikum serta banyaknya
praktikan yang bercanda sendiri. Kendala lain yaitu kurang tepatnya waku pada
saat proses penimbangan sampel setelah dioven selaa 24 jam.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Tekstur tanah adalah perbandingan relatif (dalam bentuk persentase) fraksi-
fraksi pasir, debu, dan liat.
2. Ada tiga metode yang digunakan untuk menentukan tekstur tanah yaitu
metode lapang, hydrometer, dan pipet. Metode lapang biasanya disebut
dengan metode kualitatif, sedangkan hydrometer dan pipet termasuk pada
metode kuantitatif yang menggunakan proses analisis mekanis yaitu disperse
dan sedimentasi.
3. Menurut hasil yang didapat maka dapat menentukan tekstur tanah, dengan
hasil 88 % pasir, 1,71% debu, dan 10,28% liat, maka tekstur yang didapat
adalah tanah bertekstur pasir.
B. Saran
Pada praktikum kali ini sudah berjalan cukup baik, namun akan lebih baik
apabila pembagian shift tidak terlalu besar karena peralatan yang digunakan
sedikit dan pada saat pelaksanaan praktikum seharusnya semua praktikan
memperhatikan sehingga jalannya praktikum dapat kondusif.
DAFTAR PUSTAKA
Buckman, Harry O. 1982. Ilmu Tanah. PT Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
Foth, Henry D. 1986. Fundamental of Soil Science. Gajah Mada University. Yogyakarta.
Hakim, N, dkk. 1986. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Hanafiah, Kemas. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Hardjowigeno, Sarwono. 1987. Ilmu Tanah. Mediyatama Sarana Perkasa. Jakarta.
Poerwowidodo. 1991. Ganesha Tanah. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.
Sutedjo, M.M. 2002. Pengantar Ilmu Tanah Terbentuknya Tanah dan Tanah Pertanian. PT Rineka Cipta. Jakarta.
Utomo, Wani Hadi. 1985. Dasar-dasar Fisika Tanah. Universitas Brawijaya. Malang