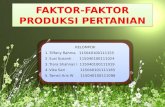Faktor produksi alam
-
Upload
helenapakpahann -
Category
Documents
-
view
10.865 -
download
4
Transcript of Faktor produksi alam

FAKTOR PRODUKSI ALAM DALAM PERTANIAN

FAKTOR PRODUKSI ALAM DALAM PERTANIAN
Faktor produksi alam adalah segala yang disediakan alam baik langsung maupun tidak langsung dapat digunakan manusia dalam kegiatannya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran.
Faktor produksi alam terdiri dari terdiri dari : Udara, Iklim, Lahan, Flora dan Fauna. Tanpa faktor produksi alam tidak ada produk pertanian. Tanpa tanah/ lahan, sinar matahari, udara dan cahaya tidak ada hasil pertanian. Orang yang kurang memahami proses produksi pertanian menganggap faktor produksi yang tidak langka atau tidak terbatas (unscarcity) seperti udara, cahaya adalah tidak termasuk faktor produksi. Tanah/lahan yang bersifat langka/terbatas (scarcity) adalah sebagai faktor produksi. Pada era sebelum Masehi tanah ini juga belum bersifat scarcity, sama halnya dengan udara dan cahaya. Air di beberapa daerah masih bersifat unscarcity, namun di beberapa daerah sudah scarcity, karena itu dibangun irigasi, sprinkle dan kadang-kadang harus diciptakan hujan buatan.
Nelayan menangkap ikan di laut, perusahaan jungle log menebang kayu di hutan. Pernahkah nelayan memberi makan ikan di laut, pernahkah penebang kayu memberi pupuk kayu di hutan?? Ikan dan kayu itu adalah termasuk fauna dan flora. Analisis terhadap fauna dan flora sangat kurang sehingga terlupakan. Analisis terhadap faktor unscarcity banyak disoroti oleh orang-orang dalam bidang biologi dan lingkungan. Pada zaman kehidupan manusia masih berburu, faktor lahan malah belum penting tetapi faktor flora dan fauna sebagai faktor utama. Setelah terjadi kehidupan menetap dan mulai bercocok tanam, tanah sudah menjadi faktor produksi penting, tetapi modal dan manajemen saat itu belum berfungsi.

Pada saat perekonomian terbuka,. Sebagian flora diimprove, sebagian fauna didometifikasi oleh manusia untuk memperoleh hasilyang lebih baik dan lebih banyak, sebagian lagi flora/fauna sama sekali belum dijamah manusia.
Flora/tumbuhan sebagai pabrik primer pertanian. Dia ambil CO dari udara melalui
stomata di daun (bagi flora yang berstomata), dia hisap H O dan zat-zat kimia seperti: N,Ca, Mg, Cl, Fe dan lain-lain dari tanah. Bahan-bahan ini dengan bantuan energi
sinar matahari diproses untuk menghasilkan karbohidrat, lemak, vitamine, serat dan lain – lain yang berguna bagi manusia dan hewan. Hanya flora di dunia ini yang mampu menghisap CO dan merubahnya ke bahan yang berguna, bila manusia atau hewan menghisap CO ini maka tammatlah riwayatnya.
Fauna/binatang sebagai pabrik sekunder pertanian. Ada fauna memakan flora (jenis
herbivora) ada juga memakan fauna (jenis omnivora), kemudian menghasilkan daging,
susu, telor, kulit yang berguna bagi manusia.
Pada awalnya kehidupan flora dan fauna di alam berlangsung tanpa campur tangan
manusia. Beribu jenis flora dan fauna telah mengalami evolusi sepanjang abad di
berbagai bagian dunia yang berlainan reaksinya terhadap adanya perbedaan-perbedaan dalam penyinaran matahari, suhu, jumlah air, kelembaban, sifat tubuh tanah dan lain-lain. Setiap jenis flora/fauna membutuhkan syarat-syarat tumbuh tersendiri. Akhirnya terdapatlah berbagai kombinasi tertentu flora dan fauna di berbagai bagian di dunia ini.
Pertanian timbul ketika manusia mulai mengendalikan atau menguasai atau campur
tangan dalam pertumbuhan flora/fauna, dengan mengaturnya sedemikian rupa sehingga lebih bermanfaat. Beda antara pertanian primitif dengan pertanian ilmiah terletak pada taraf pengendalian/pengusahaan tersebut yang telah terlaksana.

Pada pertanian yang sangat primif orang menerima tubuh tanah, jenis tanaman/hewan seadanya. Pertanian ilmiah telah memakai kekuatan otak untuk meningkatkan pengendalian terhadap semua faktor yang mempengaruhi produksi tanaman/hewan. Pada tahap awal timbulnya pertanian, faktor lahan bersifat unscarcity, makin lama sifatnya menjadi scarcity. Tuhan hanya sekali menciptakan lahan/tanah, manusia bertambah banyak, lahan menjadi barang rebutan. Orang yang kuat merebut atau berkemampuan tinggi memiliki lahan luas, orang yang lemah memiliki lahan sempit. Inilah awal dari timbulnya ketimpangan pemilikan lahan. Tanah/lahan dalam arti sesungguhnya bukan termasuk modal, karena tanah bukan buatan manusia atau hasil produksi. Orang awam menganggap tanah sebagai modal utama atau satu-satunya modal bagi petani. Hal ini karena tanah mempunyai fungsi ekonomi.
Fungsi ekonomi dari tanah adalah:
1. Dapat diperjual belikan
2. Dapat disewakan,
3. Dapat dijadikan jaminan kredit.
Areal tanah di pinggiran kota atau di dekat proyek industri/pemukiman, saat ini sudah
banyak diperjual belikan yang kemudian lahan pertanian beralih fungsi ke lahan non pertanian. Harga tanah per m² di lokasi tersebut cukup tinggi dan menggiurkan,
sehingga petani pemilik tanah menjualnya. Petani menganggap lebih beruntung tanah itu
dijual daripada diusahakan sebagai lahan pertanian. Bila tanah sudah beralih fungsi, maka
tingkat kesuburan tubuh tanah tidak berarti lagi. Tidak ada atau sangat langka tanah/lahan
non pertanian beralih fungsi ke tanah/lahan pertanian.
.

Antar sesama petani juga sering terjadi transaksi jual beli tanah yang belum beralih fungsi. Menyusul ada pula penduduk kota membeli lahan pertanian, ini juga menambah ketimpangan pemilikan lahan. Ada petani yang dulunya memiliki lahan beberapa hektar,
akhirnya dia berubah status menjadi petani penyewa atau buruh tani.
Mengapa orang kota mau membeli lahan ke desa karena:
1. Sifat berjaga-jaga.
2. Sifat harga tanah makin lama makin tinggi.
3. Jumlah/luas lahan bersifat scarcity.
4. Menyimpan harta, tanah tidak dapat terbakar, mudah mengurusnya, sulit
dicuri orang.
5. Meningkatkan status sosial/gengsi/ dan kesejahteraan rohaninya.
Tanah dapat disewakan misalnya dengan bagi hasil atau bentuk-bentuk lain.
UUPH (Undang2 Pokok Bagi Hasil) sejak tahun 1960 menganjurkan agar perjanjian
sewa-menyewa tanah dibuat secara tertulis agar supaya:
1. Ada jaminan dalam waktu penyakapan
2. Dapat ditentukan secara tegas hak dan kewajiban pemilik dan penyewa tanah
3. Pembagian hasil bersifat adil, tidak ada pihak ditekan.

Ciri-ciri faktor produksi alam:
1. tersebar tidak merata
2. jumlahnya terbatas
3. kondisi alam tidak dapat dikendalikan
4. barang tersebut ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat di Perbaharui.
KEADAAN LAHAN PERTANIAN
Kondisi yang memprihatinkan tanah di Indonesia khususnya dipulau jawa karena kondisi kandungan C-organic sudah sangat rendah, rata rata kurang dari 2% padahal kondisi yang seharusnya adalah 5% Kondisi tanah yang bagus terdiri dari udara 25%, Bahan Organik 5%, Air 25%, mineral 45%. Kondisi kandungan C-organik lahan pertanian kita yang sangat rendah karena akibat dari lahan lahan yang dikelola secara intensif tanpa memperhatikan kelestarian kesehatan tanah (tanpa usaha pengembalian bahan organic ke dalam tanah). Hal ini menjadi salah satu sebab terjadinya pelandaian produktivitas meskipun jenis dan dosis pupuk kimia ditingkatkan, karena tanah telah menjadi sakit. Bahan organic tanah merupakan bagian dari tanah dan mempunyai fungsi yaitu: Meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan micro hara dan factor-faktor pertumbuhan lainnya yang biasanya tidak disediakan oleh pupuk kimia (anorganik) tanah dengan bahan organic yang rendah, mempunyai daya daya sangga hara yang rendah, sehingga pemupukan kurang efisien.Tanah yang subur mengandung bahan
Organic sekitar 3-5%.

Sedangan bahan organic tanah merupakan hasil dari pelapukan sisa sisa tanaman dan atau binatang yang bercampur dengan bahan mineral lain didalam tanah pada lapisan atas tanah, yang mempunyai fungsi yaitu:
1. fisika : memperbaiki struktur tanah, memperbaiki aerasi tanah, meningkatkan daya penyangga air tanah, menekan laju erosi.2. Kimia : menyangga dan menyediakan hara tanaman, meningkatkan efisiensi pemupukan, menetralkan sifat racun Al dan Fe.3. Biologi : sumber energi bagi jasad renik / microba tanah yang mampu melepaskan hara bagi tanaman.
4. Bahan organic tanah merupakan penyangga biologis tanah yang mampu menyeimbangkan hara dalam tanah dan menyediakan hara bagi tanaman secara efisien. Bahan organic adalah bahan yang berasal dari limbah tumbuhan atau hewan atau produk sampingan seperti pupuk kandang atau unggas pupuk hijau dll.

KONDISI LAHAN PERSAWAHAN
Kondisi lahan sawah di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan sudah termasuk kategori sakit dan kelelahan (sick soils and fatigue). Sekitar 70 % dari lahan sawah telah memiliki kandungan C-organik yang rendah (<2% ) akibat intensifnya pemberian pupuk anorganik dan eksploitasi yang berlebihan (input < output). Konsekuensinya lahan tidak responsif lagi terhadap pupuk (levelling off) dan meningkatkan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Hal ini disebabkan oleh tidak seimbangnya input dengan output pada lahan sawah (terjadi eksploitasi). Sebenarnya, produk utama bertanam padi adalah pupuk organik berbentuk jerami (sekitar 1,5 x hasil gabah). Hanya saja jerami sebagai pupuk organik yang sangat murah dan multi manfaat, umumnya belum dimanfaatkan, bahkan dibakar atau diangkut untuk keperluan lainnya. Akibatnya, output yang keluar dari lahan semakin besar sehingga mempercepat terjadinya penurunan kesehatan lahan dan pengurasan nutrisi yang sangat penting untuk padi yaitu silika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini disebagian besar lahan sawah di Indonesia kandungan silikanya sudah semakin kritis. Silika diserap tanaman padi dalam jumlah besar dan berperan penting dalam meningkatkan kesehatan tanaman dan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit (blast) maupun hama (wereng).

Upaya pemulihan kesehatan lahan sawah dan peningkatan produktivitas padi dapat dilakukan dengan pengelolahan lahan sawah terpadu secara berkelanjutan (sustainable of integrated paddy soil management). Salah satu diantaranya adalah (Intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik(IPAT – BO). IPAT-BO adalah sistem produksi holistik terpadu berbasis input lokal (kompos jerami, pupuk hayati, dan input lainnya ) dengan konsep LEISA (Low External Input Sustaibale Agriculture) dan managemen tata air, tanaman dan pemupukan untuk memanfaatkan kekuatan biologis tanaman (potensi sistem perakaran dan jumlah produktif) maupun kekuatan biologis tanah atau soil biological power (kelimpahan organisme tanah menguntungkan). Teknologi IPAT-BO dikembangkan sejak tahun 2007 oleh Tim peneliti Fakultas Pertanian Unpad bekerjasama dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Adopsi IPAT-BO dengan memanfaatkan jerami (kompos jerami) pada berbagai provinsi di Indonesia (Jabar, Banten, Jateng, Jatim, Sulsel, Sumut, NTT, dll) hingga awal 2011, mampu menghasilkan padi 8-12 ton/ha (peningkatan hasil rata-rata berkisar 50-150%).

Trimakasih