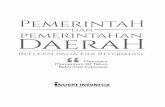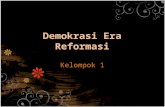ERA Reformasi
-
Upload
fajar-jayusman -
Category
Documents
-
view
36 -
download
2
Transcript of ERA Reformasi

ERA reformasi, yang terhitung sejak jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998, telah memunculkan banyak fenomena dalam kesusastraan Indonesia. Di antara fenomena-fenomena tersebut, terangkat dan tergalinya kembali jenis-jenis dan karya-karya sastra yang selama ini terpinggirkan, termasuk sastra populer.
Fenomena yang terkait dengan sastra populer dan ditunjukkan pada era ini adalah maraknya keberadaan sastra yang menjadi ciri penting kesusastraan pasca-Orba. Selain marak, sastra populer era ini juga menunjukkan keberagaman dan secara mencolok memperlihatkan karakteristik yang berbeda dengan sastra populer di era sebelumnya. Fenomena ini tentunya mengusik kita untuk memikirkan persoalan seputar pemetaan sastra populer.
Pasca-Orde Baru, yang sering disebut era reformasi, berkembang pesat karya-karya sastra populer dengan motif-motif keagamaan atau yang diistilahkan Moh. Irfan Hidayatullah sebagai Ispolit-Islam Popular Literature (jenis ini telah dirintis sejak sebelum reformasi). Berkembang pula novel dan cerpen-cerpen remaja yang menceritakan perempuan kosmopolitan dengan keseharian kehidupan perkotaan dalam karya-karya chicklit dan teenlit. Jenis-jenis cerita yang ada pada era sebelumnya memang masih berkembang sekali pun tidak mendominasi. Namun, pada periode ini sastra populer tidak banyak diwarnai tema-tema kekerasan (kriminalitas). Hal itu terjadi barangkali karena tayangan-tayangan berita kriminal di televisi telah cukup "memuaskan" masyarakat.
Sastra adalah roh kebudayaan. Ia lahir dari proses yang rumit kegelisahan sastrawan atas kondisi masyarakat dan terjadinya ketegangan atas kebudayaannya. Sastra sering juga ditempatkan sebagai potret sosial. Ia mengungkapkan kondisi masyarakat pada masa tertentu. Ia dipandang juga memancarkan semangat zamannya. Dari sanalah, sastra memberi pemahaman yang khas atas situasi sosial, kepercayaan, ideologi, dan harapan-harapan individu yang sesungguhnya merepresentasikan kebudayaan bangsanya. Dalam konteks itulah, mempelajari sastra suatu bangsa pada hakikatnya tidak berbeda dengan usaha memahami kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, mempelajari kebudayaan suatu bangsa tidak akan lengkap jika keberadaan kesusastraan bangsa yang bersangkutan diabaikan. Di situlah kedudukan kesusastraan dalam kebudayaan sebuah bangsa. Ia tidak hanya merepresentasikan kondisi sosial yang terjadi pada zaman tertentu, tetapi juga menyerupai pantulan perkembangan pemikiran dan kebudayaan masyarakatnya.
sejak kelahirannya Kesusastraan Indonesia atau kesusastraan bangsa mana pun juga di dunia ini pada dasarnya merupakan potret sosial budaya masyarakatnya. Ia berkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa itu. Ia merupakan refleksi kegelisahan kultural dan sekaligus juga merupakan manifestasi pemikiran bangsa yang bersangkutan. Periksa saja perjalanan kesusastraan Indonesia sampai kini.
Kejutan lain yang juga penting terjadi menjelang berakhir abad ke-20. Ayu Utami melalui novelnya, Saman (1998) mengejutkan banyak pihak terutama keberaniannya dalam

mengungkapkan persoalan seks. Selepas itu, bermunculan sastrawan wanita yang dalam beberapa hal justru lebih berani dibandingkan Ayu Utami. Sebutlah misalnya, Dinar Rahayu (Ode untuk Leopold, 2002), Djenar Maesa Ayu (Mereka Bilang, Saya Monyet! 2003, dan Jangan Main-Main (dengan Kelaminmu) 2004), Maya Wulan (Swastika, 2004).
Jauh sebelum Ayu Utami, sejumlah sastrawan wanita sesungguhnya telah menunjukkan prestasi yang cukup penting, seperti Nh Dini, Titis Basino, Marianne Katoppo, Leila Chudori, Ratna Indraswari, Abidah El-Khalieqy, Helvy Tiana Rosa, atau Dorothea Rosa Herliani. Meskipun begitu, kemunculannya makin semarak justru selepas Ayu Utami itu. Boleh jadi, kondisi itu dimungkinkan oleh runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang ketika itu banyak melakukan represi. Maka, begitu ada saluran pembebasan, berlahiranlah pengarang-pengarang wanita dengan keberanian dan kekuatannya masing-masing. Tercatat, beberapa di antaranya, Fira Basuki, Anggie D. Widowati, Naning Pranoto, Ana Maryam, Weka Gunawan, Agnes Jesicca, Ani Sekarningsih, Ratih Kumala, Asma Nadia, Nukila Amal dan Dewi Sartika.
Yang menarik dari sejumlah karya yang ditulis para pengarang wanita ini adalah usahanya untuk tidak lagi terikat oleh problem domestik. Karya-karya mereka tidak lagi berbicara tentang problem rumah tangga –suami-istri, melainkan problem seorang perempuan dalam berhubungan dengan masyarakat kosmopolitan. Maka, di sana, tokoh-tokoh wanita yang menjadi pelaku utamanya, seenaknya bergentayangan ke mancanegara atau berhubungan dengan masyarakat dunia.
SEJARAH kesusastraan abad ke-20 sangat dipengaruhi interaksinya dengan kolonialisme. Pada dasawarsa pertama Orde Lama, sastra Indonesia diwarnai sikap yang mendua: Sikap antara keharusan mengembangkan nilai-nilai lokal dan kekhawatiran terhadap identitas di baliknya. Ini berbeda dengan kenyataan yang terjadi di India dan Afrika, di mana sastra lokal pada 1950--1960-an menjadi strategi perlawanan terhadap kanon sastra Eropa.
Berbeda dengan Orde Lama kelemahan Orde Baru yang kelemahan mendasar dari Orde Baru adalah kegagalan nyadalam merangsang partisipasi Rakyat, pola Pembangunanyang dilakukan oleh Orde Baru hanya TOP DOWN bukan TOPDOWN yang merangsang BOTTOM UP, sehingga , ORDE BARUtidak mampu merangsang agar Rakyat bias BERDIKARI, ORDE BARU tidak mampu merangsang musyawarah untukmufakat diantara para pemimpin Rakyat, inilah yangdisebut Penyalahgunaan Kekuasaan dari Orde Baru yangkita kenal dengan sebutan Korupsi, peringatan kepadaORDE BARU atas penyelewengan kekuasaannya sudahdilakukan oleh mahasiswa sejak tahun 1971, 1974, 1977/78 dan puncaknya terjadi di 21 Mei 1998, dengan
lengsernya pak Harto yang kita kenal dengan sebutan reformasi