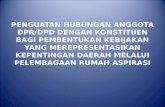Desentralisasi Di Indonesia
-
Upload
nur-azizah -
Category
Documents
-
view
36 -
download
3
description
Transcript of Desentralisasi Di Indonesia
DESENTRALISASI DI INDONESIA
1. Pengantar Indonesia merupakan salah satu dari sebelas negara di kawasan Negara-negara Asia Tenggara dalam zona Asia Tenggara Maritim. Berada di kawasan yang diapit dua benua, Benua Asia dan Benua Australia, dan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki pulau sejumlah 17.508 (Portal Nasional Republik Indonesia 2010). Luas wilayah Indonesia mencapai 3.977 mil ditambah dengan luas perairan Indonesia menjadi 1.9 juta mil persegi dengan 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dengan luas wilayah yang sangat besar tersebut, secara administratif Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dan setiap Provinsi terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kotaberkembang dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk maupun permasalahan yang dihadapi masyarakat di suatu terkait. Berikut detail perkembangan jumlah propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Tabel 1. Perkembangan Jumlah Daerah Administratif di Indonesia tahun 1996-2008TahunJumlah ProvinsiJumlah Kabupaten/KotaTahunJumlah ProvinsiJumlah Kabupaten/Kota
1996272872003 Juni31416
1997272912003 Desember30440
1998 awal27293200433440
1998 akhir273142005 Juni33440
1999263412005 Desember33440
200032341200633450
200130353200733475
2002 Juni303772008 Juni33483
2002 Desember313912008 Desember33489
Sumber: Badan Pusat Statistik 2008Data di atas memperlihatkan adanya penambahan jumlah Kabupaten/Kota secara signifikan mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 1999. Penambahan jumlahg Kabupaten/Kota di Indonesia yang pesat pada kurun waktu tersebut merupakan dampak dari diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi penanda atas apa yang disebut sebagai Decentralization Big Bang[footnoteRef:2] di Indonesia. [2: Big bang decentralization adalah sebuah proses perubahan dalam tata hubungan pusat dan daerah yang dilakukan pemerintah pusat mulai dari perubahan ke desentralisasi, pengesahan undang-undang, transfer kewenangan dan kekuasaan ke level lokal dalam tempo yang singkat (2007:10-11).]
Indonesia mengalami dua kali gelombang Decentralisation Big Bang. Big bang yang pertama ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang relatif besar kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu, dalam undang-undang ini, daerah diberi peluang untuk membentuk Kabupaten/Kota baru jika telah memenuhi persyaratan tertentu[footnoteRef:3]. Ruang untuk mengakui kekhasan suatu daerah juga terbuka, yang memungkinkan bagi diberlakukannya desentralisasi berbasis konteks atau karakter suatu Daerah (baca: Desentralisasi Asimetris). [3: Persyaratan untuk membentuk Provinsi/Kabupaten/Kota baru berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 diantaranya adalah: jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi daerah, dll.]
Kabupaten/Kota yang semula diatur dalam pola yang sentralistis, secara cepat berubah haluan kearah yang desentralistis. Perubahan tersebut ditandai dengan penyerahan sebagian besar urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Penyerahan urusan tersebut pada gilirannya memindahkan tanggung jawab penyediaan pelayanan publik, termasuk untuk sektor dasar seperti pendidikan dan, dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal inilah yang menjadikan Indonesia masuk dalam catatan World Bank sebagai salah satu dari empat negara[footnoteRef:4] yang mengalami Decentralization Big Bang (Wasistiono 2010: 1). [4: Tiga negara lain yang juga mengalami Big Bang ini adalah Filipina, Pakistan, dan Ethiopia.]
Gelombang kedua big bang ditandai dengan adanya peningkatan aliran Dana Alokasi Umum (DAU - General Alocation Grand) hingga mencapai 64% dari total APBN (Fengler, Hofman 2009). Di era sebelumnya, pemerintah daerah belum pernah mendapatkan dana sebesar itu untuk dikelola. Situasi ini menjadi tantangan sekaligus jebakan maut bagi pemerintah daerah untuk mengelola dana DAU secara efektif, transparan dan akuntabel sehingga dapat menjalankan kewenangannya untuk menyediakanpelayanan publik kepada masyarakat.Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami perubahan dalam hal bentuk negara maupun pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam hal bentuk negara, Indonesia pernah mengalami bentuk negara kesatuan maupun federal (dengan nama Republik Indonesia Serikat). Bentuk negara kesatuan digunakan dalam dua periode, yaitu pada 1945 1949 dan 1950 sekarang, sedangkan bentuk negara federal dijalankan kurang lebih selama dua tahun pada 1949 1950.Bentuk negara federal diterapkan di Indonesia sebagai strategi politik pada masa tersebut untuk mendapatkan pengakuan kemerderkaan dari kalangan internasional. Hal ini terjadi karena Pemerintah Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945. Setelah melalui kesepakatan yang alot dalam Konferensi Meja Bundar antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda dan pemerintah boneka bentukan Belanda (Bijeenkomst voor Federaal Overleg/BFO)[footnoteRef:5], pada tanggal 27 Desember 1949 berdirilah Republik Indonesia Serikat (RIS)[footnoteRef:6]. Hanya saja, RIS tidak berusia panjang karena kuatnya tuntutan dari berbagai daerah di Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. [5: Pasca 1945, Pemerintah Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Strategi yang kemudian digunakan adalah membujuk pemimpin-pemimpin politik diluar Jawa untuk membentuk negara bagian yang terpisah dari Republik Indonesia yang baru merdeka tersebut. Negara-negara bagian inilah yang kemudian disebut sebagai negara boneka.] [6: Republik Indonesia Serikat terdiri dari tujuh negara bagian dan 9 daerah otonom yang tidak tergabung dalam federasi. Tujuh negara bagian tersebut adalah Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan termasuk distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur dan Negara Sumatera Selatan. Sementara 9 wilayah yang berdiri sendiri adalah Jawa Tengah, Kalimantan Barat dengan status istimewa, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung dan Riau. Selain berimplikasi terhadap nama negara, pembagian daerah/negara bagian, perubahan menjadi negara federal membawa konsekuensi yuridis. Yaitu adanya konstitusi Republik Indonesia Serikat yang ditandatangani oleh 16 negara bagian/daerah (Muslimin, Amrah 1960; Kaho,J.R. 2012).]
Sedangkan dalam hal pola relasi antara pusat dan daerah, Indonesia secara de yure lebih banyak menganut prinsip desentralisasi. Namun, secara de facto, prinsip sentralisasi lah yang muncul lebih dominan, hingga munculnya UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004. Dua undang-undang inilah yang secara de yure memberikan landasan bagi desentralisasi di Indonesia yang kemudian de facto diterapkan sesuai dengan aturan.Perjalanan desentalisasi di Indonesia sebelum dan sesudah reformasi tahun 1999 inilah yang akan menjadi misi utama tulisan ini. Terlebih lagi karena Indonesia adalah negara yang semula memiliki tata hubungan pusat dan daerah yang paling sentralistis di dunia berubah secara drastis menjadi negara paling terdesentralisasi di dunia(Guess 2005).2. Desentralisasi di Indonesia sebelum era reformasi (1945 1998)Sistem pemerintahan desentralisasi diperkenalkan di Indonesia saat pemerintahan kolonial Belanda melalui Regering Reglement (RR) yang ditetapkan tahun 1854. Peraturan ini menegaskan bahwa Hindia Belanda[footnoteRef:7] tidak mengenal sistem desentralisasi namun sistem sentralisasi dengan asas dekonsentrasi.[footnoteRef:8]Konsekuensinya, Hindia Belanda dibentuk wilayah-wilayah administratif yang diatur secara hirarkis mulai dari gewest (residentie), Afdeling Distrik dan Onderdistric (Asshiddiqqie, J. 2006). [7: Nama Indonesia di masa penjajahan Belanda] [8: Dekonsentrasi merupakan salah satu variasi dalam teorisasi Desentralisasi menurut Rondinelli dan Cheema (1983).]
Tahun 1903, ditetapkanDecentralisatie Wet tanggal 23 Juli 1903. Decentralisatie Wet ini memuat beberapa pasal baru yang memungkinkan daerah otonom (gewest) memiliki kewenangan untuk mengurus keuangan. Tahun 1925, Pemerintah Belanda melengkapi peraturan pusat dan daerah dengan mengeluarkan aturan[footnoteRef:9] yang berimplikasi pada berimplikasi pada pembagian Pulau Jawa menjadi beberapa Provincies (propinsi), regent (karesidenan) dan stad. Selain itu, berdasarkan peraturan ini pemerintahan Hindia Belanda mulai melibatkan orang pribumi, Indonesia, terutama kaum ningrat/bangsawan untuk masuk ke jajaran birokrasi pemerintahan(kabupaten/kotamadya) (Yani, A. 2002; Kaho, J.R. 2012). [9: Aturan tersebut adalah Wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indie atau biasa disebut dengan Indische Staatsregeling (IS). Penerapan IS tersebut diatur dalam dua peraturan baru yaitu Regentschap ordonantie dan Provincies ordonantie.]
Sistem pemerintahan desentralisasi dengan konsep otonomi daerah mulai diperkenalkan di tahun 1937. Dimana daerah memiliki hak untuk membantu pelaksanaan pemerintah pusat dimana kepala daerahnya adalah orang pusat yang di kirim ke daerah sebagai pemegang jabatan pemerintahan tertinggi di daerah dan diawasi oleh Gubernur Jenderal (Yani, A. 2002). Pada zaman penjajahan Jepang (1942 1945), sistem desentralisasi dihapuskan dan diganti dengan sistem sentralisasi yang dikendalikan oleh militer. Sejak Indonesia merdeka, pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia sangat tergantung pada rezim yang berkuasa. Dari tahun 1945 hingga tahun 1998, terdapat 5 undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.[footnoteRef:10]Dari kelima perundangan tersebut, empat perundangan diundangkan pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia I, Soekarno[footnoteRef:11]. Sementara satu perundangan yaitu UU No. 5 tahun 1974 pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia II, Soeharto, yang berlaku dari tahun 1974 hingga 1998[footnoteRef:12]. [10: Perundangan tersebut adalah UU No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintah Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Penpres NO. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU. No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.] [11: Masa pemerintahan Presiden RI I adalah tahun 1945 1966. Periode ini selanjutnya disebut sebagai Era Orde Lama.] [12: Periode ini kemudian disebut sebagai Era Orde Baru.]
2.1. Desentralisasi di era Orde Lama (1945 1965)Empat perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah di era Orde Lama memiliki latar belakang dan implikasi yang berbeda-beda terhadap hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Regulasi pemerintahan daerah yang pertama kali diundangkan pasca Indonesia merdeka adalah UU No. UU No. 1 Tahun 1945. Dalam undang-undang ini, muncul semangat untuk melaksanakan desentralisasi di Indonesia melalui pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Lembaga ini merupakan cikal bakal terbentuknya lembaga perwakilan di daerah. Artinya, peluang bagi terciptanya demokrasi di tingkat daerah mulai dibuka, dengan dibentuknya lembaga legislatif daerah yang berfungsi untuk menjadi mitra eksekutif daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari didaerah. Selain itu, undang-undang ini membagi pemerintahan daerah dalam tiga level, yaitu karesidenan, kabupaten dan kota. Ketiga pemerintahan di level lokal tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri-sendiri. Namun, tidak semua pemerintahan daerah di Indonesia dapat membentuk KNID, sehingga di tahun 1945 sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu pemerintahan daerah yang memiliki KNID dan pemerintahan yang tidak memiliki KNID. Pemerintahan yang memiliki KNID adalah pemerintahan daerah yang diberi kewenangan otonom untuk mengatur rumah tangga sendiri. Sementara pemerintahan yang tidak memiliki KNID adalah daerah yang diperlakukan sebagai wilayah administratif. Kelemahan dari undang-undang ini adalah pertama tidak mengatur secara tegas batas dan ruang lingkup urusan rumah tangga. Kedua, terjadi dualistik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yaitu pemerintahan yang diselenggarakan bersama-sama antara KNID, badan eksekutif dan kepala daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala daeah yang terlepas KNID dan badan eksekutif. Kelemahan yang ada dalam UU No. 1 tahun 1945 tersebut berusaha diperbaiki oleh Pemerintah Orde Lama dengan mengeluarkan UU No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini memiliki empat tujuan yaitu pertama melakukan uniformitas pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, kedua menghapuskan dualisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketiga memberikan hak otonomi kepada daerah, keempat memberikan medebewind (tugas pembantuan) seluas-luasnya kepada badan-badan pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan pertama terkait tingkat pemerintahan di daerah yang berubah menjadi provinsi, kabupaten (kota besar) dan swatantra (menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang meliputi desa, nagari, marga, gampong dll). Perubahankedua, perubahan dalam konfigurasi pemerintah daerah, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Ketua/anggota DPD memegang jabatan kepala daerah. Kepala daerah tersebut diangkat oleh Pemerintah Pusat dan dapat dihentikan oleh DPRD sebagai salah satu implementasi hak DPRD dalam melakukan sistem kontrol dan pengawasan. Semangat UU No. 22 tahun 1948 ini adalah memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah. Hal ini ditandai dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai wewenang politik yang relatif besar. Selain itu, undang-undang ini juga mengakui otonomi asli (self governing community) yang ada di tingkat desa di Indonesia. Hanya saja, implementasi undang-undang ini tidak berjalan dengan baik, karena konteks sosial dan politik pada saat itu.Pada tahun 1957, pemerintah Orde lama mengeluarkan kembali Undang-undang Pemerintah Daerah yang baru yaitu UU. No. 1 Tahun 1957 yang berinduk kepada UUDS 1950 yang menganut azaz otonomi yang seluas-luasnya (UUDS Pasal II , UU No. 1 Tahun 1957 Pasal 31 ayat (1)) dengan menganut sistem otonomi riil. Implikasi dari implementasi undang-undang ini adalah pertama adanya semangat untuk menghilangkan prinsip azaz dekonsentrasi di daerah-daerah dengan menentang adanya kedudukan Pamong Praja, kedua DPRD dipilih oleh rakyat, DPD dipilih oleh DPRD dan kepala daerah dipilih DPRD, ketiga DPD bertanggung jawab kepada DPRD, keempat DPRD bertugas untuk mengangkat Sekretaris Daerah. Kelima, Kepala Daerah dapat dijatuhkan sewaktu-waktu oleh DPRD dengan mosi tidak percaya. Perundang-undangan yang baru ini membuat kondisi daerah menjadi tidak kondusif karena keluasan otonomi yang diberikan dan kurangnya kontrol dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini diperkeruh dengan kondisi perpolitikan nasional yang sedang memanas dimana saat itu hubungan Presiden dengan DPR/MPR sedang tidak harmonis (Mahfud, M. 1987).Seiring dengan perubahan ideologi yang dianut oleh Orde Lama dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin,[footnoteRef:13] maka UU No. 1 Tahun 1957 yang kental dengan demokrasi liberal diganti dengan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 dengan nuansa demokrasi terpimpin yang kuat. Implikasi dari perubahan fundamental tersebut adalah pertamakewenangan-kewenangan pusat yang diberikan ke daerah ditarik kembali ke pusat karena Presiden Soekarno berargumen bahwa otonomi luas mengancam keutuhan bangsa (Raharusun, Y.A. 2009). Dengan kata lain, ada perubahan prinsip dari desentralisasi menjadi prinsip sentralisasi. Kedua adanya pemusatan pimpinan pemerintahan di satu tangan yaitu Kepala Daerah. Kepala Daerah tidak saja memimpin pemerintahan namun juga mengetuai lembaga legislatif yaitu DPRD. Sementara dalam menyelenggarakan pemerintahan Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH). [13: Demokrasi terpimpin adalah salah satu variasi demokrasi yang pernah dijalankan di Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, seluruh keputusan politik dibuat oleh Presiden, yang harus diikuti sampai level Gubernur/Bupati di Daerah.]
Ketiga penghapusan DPD dan diganti dengan BPH yang berfungsi sebagai penasehat Kepala Daerah. Keempat, posisi Kepala Daerah sangat kuat dimana tidak dapat diberhentikan oleh DPRD dan berwenang untuk menunda pemberlakukan keputusan-keputusan daerah. Pemberhentian Kepala Daerah hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai konsekuensi dari perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. Kelima, adanya protes keras dari partai politik karena kekuasaan partai di daerah dikurangi (Asshiddiqqie, Jimly 2006; Raharusun, Y.A. 2009).Salah satu dampak sampingan dari diberlakukan UU ini adalah bertambahnya jumlah provinsi dari 12 di tahun 1950 (10 provinsi ditambah 2 daerah istimewa) menjadi 20 provinsi di tahun 1958. Namun sisi fiskal peraturan desentralisasi tsb masih sangat terpusat sehingga mengakibatkan banyak daerah tetap bergantung pada pusat. Tetapi sayangnya desentralisasi belum sempat berakar akibat dari pemberontakan-pemberontakan daerah di Sumatera dan Sulawesi menentang Jakarta, pengumuman UU darurat perang, meningkatnya pengaruh militer, sehingga menggugurkan eksperimen singkat desentralisasi di Indonesia. Kemudian UU ini dicabut dengan menggunakan Dekrit Presiden 1959, yang merupakan penanda dari munculnya Demokrasi Terpimpin. Undang-undang terakhir tentang Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam periode Orde Lama yaitu UU. No. 18 Tahun 1965, tidak mengalami perubahan signifikan dari perundangan sebelumnya. Hal ini dikarenakan UU No. 18 Tahun 1965 hanya mengadopsi dari Penpres No. 6 tahun 1959 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan DPR GR. Meski pun demikian, terdapat beberapa hal positif dari Undang-undang ini yaitu pertama susunan DPRD dipimpin oleh Ketua dan wakil ketua dari partai-partai dan golongan karya (pasal 7-9), kedua sumber pendapatan daerah didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, pajak negara, subsidi, sumbangan serta bea dan cukai, hasil perusahaan negara dan ganjaran (Pasal 69-73). Ketiga, adanya pemberian hak petisi kepada DPRD untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat ke serta untuk mencegah kesewenang-wenangan pemerintah pusat (Pasal 55).
2.2. Era Orde Baru (1996 1998)Berbeda dengan era Orde Lama yang memiliki banyak perundangan tentang pemerintah daerah, era Orde Baru hanya memiliki satu perundangan yaitu UU. No 5 Tahun 1974. Perundangan ini memperkenalkan sebuah dimensi baru dalam tata kelola otonomi daerah yaitu otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Penerapan tata kelola otonomi daerah ini disesuaikan dengan trilogi pembangunan Orde Baru yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya.Menurut Kaloh, J. (2002), pengaruh dari trilogi pembangunan dalam UU No. 5 Tahun 1974 tersebut adalah pertama, konsentrasi kekuasaan terletak di lembaga eksekutif (Kepala Daerah), kedua dihapusnya lembaga BPH (Badan Pelaksana Harian) sebagai perwakilan parpol di dalam Pemerintahan Daerah. Ketiga, tidak dilaksanakannya hak angket DPRD yang dapat menganggu keutuhan Kepala Daerah, keempat Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD tetapi langsung kepada Presiden dan kelima, Kepala Daerah hanya memberi keterangan kepada DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sekali dalam setahun. UU No. 5 Tahun 1965 memiliki tiga prinsip dasar yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Secara ideal, tiga prinsip dasar tersebut bersifat komplementer dan berjalan dengan seimbang dalam mengatur hubungan pusat dan daerah. Namun dalam pelaksanaannya, prinsip dekonsentrasi lebih mendominasi. Hal ini terlihat dengan sentralisasi pemerintah Orde Baru yang melakukan penarikan kembali urusan-urusan daerah menjadi urusan dekonsentrasi tanpa melalui prosedur yang jelas dan penempatan aparat dekonsentrasi yang semakin banyak di daerah (Kaloh, J. 2002). Misalnya saja dalam pemilihan kepala daerah. Meskipun DPRD yang memilih, namun keputusan akhirnya ada di Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pun diserahkan kepada Presiden melalui Mendagri bukan DPRD. Demikian juga yang terjadi di level kebijakan, dimana semuanya disiapkan oleh Pemerintah Pusat secara seragam tanpa memperhitungkan kebutuhan, karakteristik daerah, kultur dari daerah-daerah di Indonesia (Hoessein, B. 1995). Implikasi dari hal ini adalah terbatasnya ruang daerah dan daerah terbebani oleh biaya aktivitas dekonsentrasi yang dibiayai oleh APBD Pada masa pemerintahan Orde Baru, sistem pemerintahan disusun secara bertingkat, propinsi menjadi Daerah Tingkat I dan kabupaten/kotamadya sebagai Daerah Tingkat II. Kecamatan menjadi daerah administratif yang membawahi beberapa desa (untuk tingkat kabupaten) dan kelurahan (untuk tingkat kotamadya dan kota administratif). Untuk menjaga stabilitas pembangunan, pemerintah Orde Baru menempatkan militer sebagai kepala daerah-kepala daerah baik di level daerah tingkat I, daerah tingkat II hingga ke level pemerintahan terkecil, desa. Kebijakan pemerintah Orde Baru terkait dengan otonomi daerah ini masih diwarnai oleh colonial flavour (Legge, J.D. 1963).Atas dasar tersebut, desentralisasi yang dihadirkan melalui UU No. 5 Tahun 1974 ini bukanlah bentuk desentralisasi yang sebenarnya. Dengan sedikitnya kewenangan yang dimiliki Daerah untuk menyusun dan melaksanakan perencanaan kebijakan daerah serta kuatnya dominasi Presiden atas Kepala Daerah, maka desentralisasi pada periode ini baru pada tahap legal formal belaka. Prakteknya, prinsip sentralisasi kekuasaan ditangan Pemerintah Pusat (Presiden) lah yang menjadi prinsip utama dalam pola relasi hubungan Pusat dan Daerah pada periode ini.
3. Desentralisasi di Indonesia di Era Reformasi (1999 sekarang)Setelah berada dalam praktek sentralisasi Pemerintah Pusat selama 32 tahun, pada tahun 1998 dimulailah upaya untuk menata ulang polahubungan pusat dan daerah. Upaya perubahan ini dipicu oleh dua konteks besar.Setting politik pertama adalah merebaknya protes daerah yang semakin sulit dikendalikan oleh pemerintah pusat. Setelah hampir tiga dekade tidak terusik oleh kenakalan daerah sebagaimana yang terjadi pada periode 1950-1960, Indonesia di akhir abad 20 ini harus mengalami kembali kenakalan-kenakalan itu. Dengan mengecualikan Timor-Timur, protes berbasis kedaerahan yang terjadi pada penghujung 1998 secara tegas mengindikasikan ketidakpuasan terhadap kebijakan desentralisasi pemerintahan dan keuangan pada masa Orde Baru sebagai pemicu utamanya. Tuntutan terhadap otonomi yang lebih luas, bahkan tuntutan federasi maupun merdeka, terutama datang dari daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya alam yang kuat, seperti Aceh, Irian Jaya dan Riau, yang memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan nasional, namun tidak memperoleh alokasi keuntungan yang berarti.Setting politik yang kedua adalah semangat demokratisasi yang menuntut ruang partisipasi politik yang luas. Akumulasi kekecewaan terhadap sistem politik monolitik yang dibangun Presiden Suharto kemudian muncul dalam bentuk tuntutan terhadap liberalisasi politik yang menuntut kebebasan berorganisasi, berpartai-politik, berpendapat, dan beroposisi. Selain itu, tuntutan untuk melakukan pemilu yang jujur dan adil dan untuk membangun pemerintahan yang representatif sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan.Dengan latar belakang sosial politik seperti itu, bisa dipastikan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, secara sengaja maupun tidak dimotivasi dua misi utama.Pertama, untuk memuaskan semua daerah dengan memberikan ruang partisipasi politik yang tinggi di tingkat daerah. Hal ini diwujudkan dengan desentralisasi politik dari pusat kepada daerah, dan memberikan kesempatan dan kepuasan politik kepada masyarakat daerah dengan memberikan kesempatan untuk menikmati simbol-simbol utama demokrasi lokal (misal pemilihan Kepala Daerah). Dan kedua, untuk memuaskan daerah-daerah kaya sumberdaya alam yang memberontak dengan memberikan akses yang lebih besar untuk menikmati sumberdaya alam yang ada di daerah mereka masing-masing.Gambaran kontekstual yang telah diuraikan di atas membantu kita untuk memamahi pemahaman tekstual yang dirumuskan dalam UU No. 22 Tahun 1999. UU ini melakukan desentralisasi sekaligus demokratisasi. Sebagai contoh, istilah pemerintah daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999 digunakan untuk merujuk pada Badan Eksekutif Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat Daerah Otonom. Hal ini berbeda dengan UU No. 5 Tahun 1974 yang menggunakan istilah pemerintah daerah yang meliputi pula DPRD, dan menempatkan DPRD sebagai mitra eksekutif. Perubahan pengertian yang dilakukan UU No. 22 Tahun 1999 ini membawa implikasi pada keterpisahan secara tegas antara badan eksekutif dan legislatif, dan penempatan fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif daerah.Perlu untuk dicatat, terdapat perbedaan substansial antara tingkat desentralisasi kepada Daerah Propinsi dengan tingkat desentralisasi kepada Daerah Kabupaten dan Kota. UU No. 22 Tahun 1999 ini memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi yang dibatasi hanya sampai pemerintahan Propinsi. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 ini, titik berat otonomi daerah memang berada di Kabupaten/Kota. Dari sisi provinsi, memang tidak ada perubahan yang berarti. Gubernur tetap menjadi wakil pusat dan sekaligus Kepala Daerah, dan Kanwil (instrumen Menteri) tetap ada. Gubernur bukan lagi menjadi atasan dari Bupati/Walikota. Dengan titik berat otonomi di Kabupaten/Kota, hal ini berarti bahwa pemerintahan Kabupaten dan Kota telah terbebas dari intervensi pusat yang dulu dilakukan melalui perangkapan jabatan Kepala Daerah Otonom dan Kepala Wilayah Administratif (wakil pusat). Bupati dan Walikota adalah Kepada Daerah Otonom saja. Sementara itu jabatan Kepala Wilayah pada kabupaten dan Kota (dulu Kotamadya) sudah tidak dikenal lagi. Konsekuensinya, tidak ada lagi instansi Pusat di level Kabupaten/Kota dan instansi teknis yang ada hanyalah Dinas-Dinas Daerah Otonom. Bahkan, UU ini juga menempatkan pemerintahan kecamatan sebagai kepanjangan tangan pemerintahan daerah otonom Kabupaten/Kota (desentralisasi), dan bukan sebagai aparat Pusat / Provinsi (dekonsentrasi) .Selain itu, melalui UU No. 22 Tahun 1999 ini, otonomi daerah Kabupaten dan Kota yang tinggi ini kemudian dibarengi dengan peluang partisipasi politik yang tinggi pula. Beberapa hal yang cukup menonjol diantaranya adalah dalam hal pemilihan Bupati/Walikota dan dikenalkannya Badan Perwakilan Desa.Bupati dan Walikota dipilih secara mandiri oleh DPRD Kabupaten/ Kota tanpa melibatkan pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Bupati/Walikota harus bertanggung jawab kepada dan bisa diberhentikan oleh DPRD sebelum masa jabatannya usai. Sementara itu, pemerintah pusat (Presiden) hanya diberi kekuasaan untuk memberhentikan sementara seorang Bupati/Walikota jika dianggap membahayakan integrasi nasional. Namun, pembuktian terhadap tuduhan Presiden ini tetap harus diuji oleh proses peradilan. Sedangkan di tingat desa, dibentuklah Badan Perwakilan Desa yang menjadi lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa. Hal ini merupakan perkembangan baru bagi kehidupan demokrasi di tingkat desa.Kabupaten/Kota diberikan kewenangan politik yang tinggi yang mencakup jenis urusan yang cukup luas. Misalnya saja, UU ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom yang meliputi seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Namun, definisi kewenangan bidang lain ini ternyata masih sangat luas, sebab mencakup perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM, pendaya gunaan SDA serta teknologi tinggi strategis, koservasi dan standarisasi nasional. Ketentuan terakhir ini memberikan peluang kepada pemerintah pusat untuk melakukan sentralisasi administrasi di tengah desentralisasi politik yang kuat.Sementara itu, keuangan daerah juga mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah. Regulasi ini menyediakan seuatu kerangka fiskal bagi pemerintah lokal, serta memberi penekanan pada pembuatan-keputusan finansial lokal. Berdasarkan UU ini penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah harus dibiayai dari dana APBN dan penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya. Di samping itu kewenangan untuk memanfaatkan keuangan sendiri didukung perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang dilakukan dengan pembagian kewenangan atau money follow function yang artinya daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya dan dengan kewenangan itu maka Daerah akan menggunakannya untuk menggali sumber dana keuangan yang sebesar-besarnya sepanjang bersifat legal dan diterima oleh segenap lapisan masyarakat.Melalui UU No.25/1999 secara makro sumber-sumber keuangan daerah diperbesar, sejalan dengan dikembangkannya prinsip perimbangan. Sebagai contoh, penerimaan negara dari SDA sektor kehutanan, pertambangan umum dan perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Sementara itu, pemerintah pusat memperoleh alokasi yang lebih besar untuk sektor pertambangan minyak bumi (85%) dan gas alam (70%). Namun demikian masih terdapat limitasi terhadap regulasi ini yang menyangkut perdebatan soal pemasukan (pendapatan) bagi pemerintah lokal, penentuan subsidi pemerintah pusat, serta pembagian penghasilan yagn didapat dari industri berbasis sumberdaya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Hal tersebut tentu sangat penting bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumberdaya alam seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan Papua.Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ini memang telah memberikan arah perubahan mendasar dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Ada beberapa catatan dalam implementasinya. Pertama, merebaknya ketegangan daerah, yang nampak dalam hal pembagian Dana Alokasi Umum dan dana pemekaran wilayah. Kedua, munculnya bibit ketegangan antar daerah sebagai akibat dari perbedaan Sumber Daya Alam (daerah kaya vs daerah miskin) dan perbedaan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing daerah dapat menimbulkan kesenjangan antar daerah. Ketiga, munculnya ketegangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya terkait dengan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Provinsi yang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota seringkali diabaikan atau dianggap mengintervensi otonomi daerah yang mereka miliki. Dan keempat, masalah keuangan daerah, yakni menyangkut apakah masing-masing daerah mampu menggali sumber daya alamnya untuk menghasilkan dana dan mampu mengelola dana tersebut secara akuntabel dan transparan.Berbagai persoalan tersebut kemudian memunculkan upaya untuk melakukan revisi atas UU No. 22 Tahun 1999. Dan pada 15 oktober 2004, lahirlah UU no 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999.Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini, sebagian besar masih melanjutkan banyak hal dalam UU sebelumnya, misalnya saja dalam hal kewenangan daerah, yang tetap sama. Pembeda terbesar antara UU NO. 32 Tahun 2004 dengan UU sebelumnya adalah dalam hal pemilihan Kepala Daerah. Jika dalam UU. No 22 Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, maka dalam UU. No 32 Tahun 2004 ini Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat (one man one vote). Dengan sendirinya, Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada masyarakat (konstituen), ditambah pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat (laporan) dan DPRD (keterangan).Pemilihan Kepala Daerah Langsung memang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan kepala daerah, baik Bupati/Walikota maupun Gubernur. Dengan demikian, UU No. 32 Tahun 2004 ini telah memberikan ruang besar bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal melalui mekanisme pemilihan langsung. Namun, ada beberapa catatan dalam pelaksanaannya.Pertama, terjadi beberapa beberapa kerusuhan pelaksanaan pilkada langsung di berbagai daerah. Misal saja, kerusuhan di Tuban, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Depok, dan kerusuhan massa di Banyuwangi. Meskipun jumlahnya tidak banyak, berbagai konflik di masyarakat pra dan paska pelaksanaan Pilkada langsung di beberapa daerah telah mencoreng wajah demokrasi pada level lokal.Persoalan kedua terkait Pilkada adalah tumpang-tindih peraturan-peraturan yang terkait satu sama lain dalam momentum pilkada. Misalnya saja pengaturan tentang partisipasi politik tentara dan Pegawai negeri Sipil. Pengaturan tentang keduanya tersebar diberbagai peraturan perundangan-undangan. Dan ketiga, persoalan yang muncul menyangkut persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pasangan calon Kepala Daerah. Misalnya saja, ditemukan adanya manipulasi persyaratan administrasi oleh pasangan calon Pilkada, perbedaan penafsiran antara beda penafsiran antara Komite Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas, dan pihak calon terhadap ketentuan-ketentuan persyaratan administrasi.Selain persoalan yang terkait dengan Pilkada tersebut, implementasi UU No. 32 Tahun 2004 juga dibayangi oleh kuatnya anggapan upaya resentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Salah satu indikasi dari asumsi ini adalah adanya ketentuan yang mengharuskan adanya konsultasi kepada level Pemerintah atasan untuk pengisian jabatan eselon II di daerah (dengan Gubernur untuk Daerah Kabupaten/Kota dan dengan Mendagri untuk Daerah Provinsi). Hal yang sama juga terjadi pada evaluasi APBD, yang meski sudah disahkan oleh Kepala Daerah dan DPRD masih harus disahkan oleh pejabat tingkat atasnyaSecara umum, dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia paska pemerintahan Orde Baru, masih ada beberapa limitasi yang ditemukan. Pertama, terkait dengan persaingan menyangkut kontrol atas otoritas dan sumberdaya, yang seringkali dimanipulasi dengan menggunakan simbol-simbol lokal seperti bahasa kebanggaan lokal, identitas etnis atau regional. Kedua, perpindahan persoalan korupsi dari tingkat nasional ke tingkat lokal. Sebagian besar pejabat lokal memanfaatkan kesempatan dalam rantai rent seeking (seorang penanam modal harus memberi imbalan kepada individu-individu & kantor-kantor di tingkat yang berbeda dari birokrasi Indonesia) untuk masuk ke dalam industri yg menguntungkan tsb, yang sebelumnya menjadi lahan pemerintah pusat di Jakarta.Desentralisasi memungkinkan munculnya berbagai jaringan patronase yang lebih terlokalkan yang berbeda dari masa Soeharto, relatif otonom dari otoritas pusat negara. Yang paling menonjol dari konstelasi tsb adalah berbagai kepentingan predator yang dibesarkan dibawah sistem patronase rezim Soeharto yang begitu luas dan terpusat (yang menjalar dari istana Kepresidenan di Jakarta hingga ke provinsi-provinsi, kota-kota dan desa-desa) sebagian besar masih terus hidup & berpengaruh. Fenomena inilah yang kemudian disebut sebagai pembajakan proses desentralisasi (Hadiz dan Robinson, 2002).
4. Masa depan desentralisasi & Otonomi Daerah di IndonesiaDesentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia khususnya paska 1999 memang telah menunjukkan kemajuan, khususnya dari sisi besaran kewenangan dan sumber daya finansial yang ditransfer Pusat kepada Daerah. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk memikirkan ulang pola hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia ini. Pertama, keragaman kultur, suku, bahasa dan budaya di Indonesia yang sangat beragam. Kondisi ini menjadikan setiap upaya untuk menata Derah secara seragam di seluruh Indonesia dipastikan tidak akan berjalan optimal. Kedua, ketimpangan pembangunan antara Jawa dengan Luar Jawa yang masih saja tinggi paska 1999. Hal ini mengisyaratkan perlunya memikirkan pola desentralisi dan otonomi daerah yang sensitif terhadap persoalan ini.Salah satu yang ditawarkan adalah pelaksanaan pola desentralisasi asimetris. Desain desentralisasi asimetris sebenarnya bukanlah barang baru bagi Indonesia. Pemberian otonomi khusus kepada Aceh dan Papua serta diberlakukannya kawasan pengembangan ekonomi terpadu di Batam adalah beberapa bentuk asimetrisme yang pernah dipraktekkan di Indonesia. Demikian pula dengan adanya status Daerah Istimewa bagi Yogyakarta maupun pengaturan khusus bagi Provinsi DKI Jakarta menjadi bukti bahwa asimetrisme secara sadar dijadikan pilihan bagi pengelolaan hubungan antara Pusat dengan Daerah d Indonesia. Hanya saja, pengalaman Indonesia mempraktekkan desain asimetrime juga belum menunjukkan hasil yang diharapkan, khususnya yang terkait dengan kesejahteraan dan demokrasi. Laporan dari Kemitraan tahun 2008 tentang Kinerja Otonomi Khusus Papua menyebutkan bahwa desain asimetri yang diberikan kepada Provinsi Papua dalam bentuk Otonomi Khusus belum juga berhasil menyelesaikan problem kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami sebagian besar rakyat di Papua.Tragisnya, yang menggejala kemudian adalah pembagian kue kesejahteraan yang berasal dari Dana Otonomi Khusus pada beberapa kelompok yang awalnya diharapkan dapat menjadi ujung tombak majunya pembangunan dan pemerataan di Provinsi Papua ini. Elit politik lokal, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Birokrasi lokal, serta kalangan swasta yang berasal dari luar Papua ditengarai menjadi penikmat terbesar dari aliran Dana Otsus yang besar ini (lihat dalam Kemitraan 2008). Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.Persoalan mendasar pelaksanaan desentralisasi asimetris di kedua provinsi tersebut terletak pada niat pemberian asimetrisme itu sendiri. Bukan rahasia lagi jika desain otonomi khusus di kedua wilayah tersebut lebih dilandasi oleh motif mencegah separatisme, dibandingkan dengan motif peningkatan kesejahteraan dan demokrasi. Hal ini terlihat dari lambannya instrumentasi otonomi khusus dari Pemerintah Pusat yang baru belakangan muncul.Selain itu, karena motifnya adalah untuk meredam konflik, pasca pemberian status otonomi khusus Pemerintah Pusat nampak tidak lagi mempunyai daya untuk mengawal implementasi dari kekhususan yang diberikan. Akibatnya, instrumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kebijakan dibuat seragam dengan daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk dalam pengaturan kewenangan daerah (PP No. 38 Tahun 2007). Terlebih lagi, kekhususan yang diberikan kemudian diwujudkan dalam bentuk alokasi dana otonomi khusus, tanpa disertai dengan porsi kewenangan yang kuat untuk menjalankan otonomi khusus yang diberikan. Fakta ini menjelaskan bahwa asimetrisme sekedar dimaknai sebagai alat tawar-menawar saja, tanpa lebih lanjut mengkerangkainya sebagai metode penyerahan kewenangan (method of devolution) maupun sebagai metode untuk mengelola pemerintahan (method of governance).Sebagai metode penyerahan kewenangan, desain desentralisasi asimetris yang ditawarkan melihat bagaimana pola penyerahan kewenangan dari Pusat ke Daerah yang berbeda dengan yang ada dalam desain desentralisasi yang berjalan saat ini. Titik mendasar yang akan diambil adalah pola pembagian kewenangan antara Pusat dengan Daerah yang lebih deliberatif sehingga ruang bagi daerah untuk menentukan kewenangan sesuai dengan kontekstualitas daerah yang bersangkutan. Kewenangan dasar yang harus ada di setiap daerah tentu saja akan tetap dan harus ada. Misalnya untuk kewenangan yang terkait dengan pemenuhan hak dasar, sebagai bentuk dari kesejahteraan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Namun tentu saja, pada saat yang sama, hal ini juga akan menuntut peran Pemerintah Pusat yang kuat, khususnya di daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Dengan demikian, keseimbangan capaian kesejahteraan antara satu daerah dengan daerah lain akan lebih merata. Dan sebagai metode untuk mengelola pemerintahan, khususnya relasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, desain asimetrisme ini ditawarkan untuk merekatkan kembali relasi dan trust antara Pusat dengan Daerah.Alasan bagi pelaksanaan desentralisasi asimetris di banyak negara umumnya dilandasi oleh dua alasan besar. Pertama adalah alasan politis, untuk memberikan ruang bagi keragaman maupun untuk meredam isu separatisme (Wehner 2000: h. 250). Alasan inilah yang kemudian memunculkan otonomi khusus bagi Aceh dan Papua. Alasan kedua terkait dengan persoalan kapasitas, dimana pemberian kewenangan asimetris kepada suatu daerah lebih didasarkan pada pertimbangan penataan makro ekonomi dan keselarasan administratif (Wehner 2000: h. 250). Dalam konteks ini, asimetrisme juga diberikan berdasarkan kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih efisien. Bagi daerah yang telah mampu, maka peran pusat akan semakin berkurang, dan sebaliknya bagi daerah yang kurang mampu, peran pusat dimungkinkan untuk bertambah besar sampai daerah tersebut mempunyai sumber daya memadai untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih mandiri.Dengan kata lain, asimetrisme akan berhasil saat dapat dikombinasikan dengan insentif bagi daerah terkait untuk mengambil alih fungsi/pelayanan, yang akan lebih efektif saat daerah tsb mempunyai kapasitas yang memadai. Dilain pihak, perlu ada insentif bagi pemerintah pusat agar bersedia mengidentifikasi dan kemudian mentransfer fungsi-fungsi yang akan lebih efektif jika dilakukan oleh daerah ketimbang oleh pusat (Wehner 2000: h. 253).Alasan tersebut diatas mempertegas adanya peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mencapai derajat kesejahteraan bagi seluruh warga daerah. Peluang ini tercipta sebagai akibat dari adanya keseimbangan antara ruang politik dan kapasitas setempat yang terbuka dengan hadirnya desain desentralisasi asimetris.Titik inilah yang membedakannya dengan praktek desentralisasi yang selama ini berjalan di Indonesia. Persoalan kesenjangan antar daerah dan ketidakmerataan pembangunan sebagian besar bersumber pada desain desentralisasi yang sekedar memberikan ruang politik tanpa disertai dengan pertimbangan kapasitas daerah yang bersangkutan.Dengan menyeimbangkan aspek politik dan kapasitas inilah akan terbuka dua ruang asimetrisme sekaligus. Pertama adalah desain asimetrime yang berbasis pada kekuatan kapasitas daerah. Kapasitas disini mencakup seluruh kemampuan yang dimiliki daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, untuk dapat menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dengan cara inilah, Pemerintah Pusat dapat menagih tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.Dan kedua, asimetrime yang didasarkan pada keterbatasan daerah. Pada pola asimetrisme ini, peran Pemerintah Pusat untuk meredistribusi sumber daya nasional untuk daerah-daerah yang secara riil masih mengalami problem kesejahteraan, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, justru diperlukan. Hal ini penting untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan dan menjadi instrumen untuk memastikan kesejahteraan yang lebih merata untuk semua masyarakat.
Daftar PustakaAsshiddiqqie, Jimly 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, JakartaBappenas 2012, Kapet, diunduh tanggal 12 Juli 2012, http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=94Bayo, L.N. et.al 2012, Seminar Lokakarya Desentralisasi Pelayanan Publik dan Tantangan Integritas, Laporan Penelitian, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM kerja sama dengan Kemitraan, Yogyakarta. Dwipayana, A.; Lay, C.; Santoso, P. 2012, Policy Brief: Desentralisasi Asimetris yang Menyejahterakan Aceh dan Papua, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM kerja sama dengan Tifa Foundation, Yogyakarta. G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries, London, Sage Publications, 1983.Hadiz, R. Vedi, Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto, LP3ES, Jakarta, 2005.Hariss John, dkk, Politisasi Demokrasi, Politik Lokal Baru, Demos, Jakarta, 2004. Hoessein, B. 1995, Sentralisasi dan Desentralisasi: Masalah dan Prospek dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi (ed.), Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru, hal. 58-74.JPP Fisipol UGM 2010, Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi, Laporan Penelitian, JPP Fisipol UGM bekerja sama dengan Tifa Foundation, Yogyakarta. Kaho, J.R. 2012, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Polgov, Yogyakarta. Kaho, Josef Riwu 2002, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Rajawali Press, Yogyakarta.Kaloh, J. 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, PT Rineka Cipta, JakartaKemitraan (2008), Kinerja Otonomi Khusus Papua (Cetakan I), Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.Legge, J.D. 1963, Central Authority and Regional Autonomy in Indonesia: A Study in Local Administration 1950-1960, Cornell University Press, Ithaca, NYMahfud, M. 1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, YogyakartaMuslimin, Amrah 1960, Ichtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958, Djambatan, Jakarta. Permendagri No. 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Portal Nasional Republik Indonesia 2010, Geografi Indonesia, http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia.htmlRaharusun, Y.A. 2009, Daerah Khusus dalam Perspektif NKRI, Konstitusi Press, Jakarta. Syaukani, Affan Gaffar, Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.Wasistiono, Sadu, Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan, dimuat dalam Jurnal Ilmu Politik AIPI Nomor 21 Tahun 2010 dengan tema Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah : Evaluasi dan Prospek. Diunduh melalui http://www.ipdn.ac.id/wakilrektor/wp-content/uploads/MAKALAH-MENUJU-DESENTRALISASI-BERKESEIMBANGAN-UTK-JURNAL-AIPI1.pdf pada 8 November 2012.Watts, Ronald L. (2004), Asymmetrical Decentralization: Functional or Dysfunctional, Indian Journal of Federal Studies 1/2004, Diunduh dari (http://www.jamiahamdard.edu/cfs/jour4-1_1.htm pada 17 Januari 2011.Wehner, Joachim HG (2000), Asymmetrical Devolution, Journal of Developmeny Southern Africa Vol. 17, No. 2, June 2000.Yani, A. 2002, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta