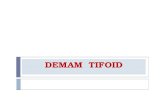Demam Tifoid BAB I
-
Upload
sylvana-kusumaningrum -
Category
Documents
-
view
642 -
download
0
Transcript of Demam Tifoid BAB I
BAB I LAPORAN KASUS A. IDENTITAS PASIEN Nama pasien Jenis kelamin Tempat tanggal lahir Umur Berat badan Tinggi badan Alamat No. RM Tanggal masuk RS Tanggal keluar RS : An. A : Laki-laki : 9 April 2009 : 15 bulan : 10,8 kg : + 70 cm : Jl. Dieng 27 Garung : 47.24.74 : 18/07/2010 : 22/07/2010
Nama ayah Umur Pekerjaan Agama
: Tn. H : 35 tahun : Wiraswasta : Islam
Nama ibu Umur Pekerjaan Agama
: Ny. H : 34 tahun : Wiraswasta : Islam
B. ANAMNESIS Alloanamnesis dilakukan dengan orang tua pasien pada 20 Juli 2010. Keluhan Utama : panas tinggi, kejang selama 8 menit. Keluhan Tambahan : anak rewel, gelisah, belum BAB selama 3 hari, batuk, muntah 2x. Riwayat Penyakit Sekarang Pada 18 July 2010 pukul 16.06 pasien datang melalui IGD dengan keterangan panas selama 3 hari dan kejang selama 8 menit. Panas tidak mendadak tinggi, tapi diawali dengan suhu badan pasien yang hangat. Panas terjadi terus-menerus dan suhu dirasakan turun naik. Saat malam hari panas meninggi, lalu suhu menurun di pagi hari. Sebelum masuk RS pasien hanya mendapatkan obat-obatan yang dibeli orang tua pasien di warung dan belum pernah dibawa berobat. Setiap kali minum obat, panas turun lalu naik lagi. Pasien belum BAB sejak awal panas, yaitu 3 hari SMRS. Buang air kecil lancar, nafsu makan pasien berkurang, minum biasa, muntah 2x. Pasien dibawa ke IGD RSUD Wonosobo karena pasien mengalami kejang yang diawali dengan panas yang meninggi. Pasien tidak memiliki riwayat bepergian ke daerah endemik malaria, tidak ada riwayat kontak dengan penderita TB. Riwayat Penyakit Dahulu Sering pilek, terutama pada saat udara dingin. Pasien belum pernah mondok di rumah sakit. Riwayat Penyakit Keluarga Di keluarga tidak ada yang menderita demam. Kakak dari ibu pasien pernah kejang. Putra dari kakak ibu pasien juga pernah kejang. Kakak kandung pasien sehat.
Riwayat Kehamilan Ibu Pasien lahir spontan dari seorang G2P1A0 saat ibu berusia 33 tahun, usia kehamilan 39 minggu. Ibu rajin ANC di bidan dan posyandu. Riwayat muntah-muntah di awal kehamilan diakui, tapi tidak sampai mengganggu aktivitas. Penyulit lain selama kehamilan disangkal. Riwayat Kelahiran Pasien lahir pada 9 April 2009, ditolong bidan dirumah, dan dilahirkan secara spontan. Kehamilan cukup bulan (39 minggu), berat lahir 3300 gram, pasien langsung menangis saat dilahirkan. Riwayat bayi kuning atau biru disangkal, ibu sehat. Riwayat Post Partum Pasien rutin diperiksakan ibunya ke posyandu untuk ditimbang dan diimunisasi. Berat badan pasien bertambah setiap bulannya. Kesimpulan : Riwayat kehamilan baik Riwayat persalinan baik Riwayat pasca persalinan baik Riwayat Makanan Pasien masih mengkonsumsi ASI sampai sekarang. Konsumsi ASI eksklusif sampai dengan pasien berusia 6 bulan, mulai usia 6 bulan pasien diberi makanan tambahan bubur bayi. Kemudian pada usia 8 bulan pasien mengkonsumsi ASI dan bubur saring. Saat ini konsumsi sehari-hari pasien adalah ASI dan nasi. Kesimpulan : kualitas dan kuantitas makanan cukup baik.
Riwayat Imunisasi Pasien rutin dibawa ke posyandu untuk diimunisasi. Imunisasi hepatitis saat berusia 1 minggu, BCG saat berusia 1 minggu, polio saat berusia 0 bulan. 2 bulan, 6 bulan.DPT saat berusia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Imunisasi campak saat usia 9 bulan. Kesimpulan: imunisasi dasar lengkap sesuai umur. Pertumbuhan dan Perkembangan Pertumbuhan Berat badan pasien selalu bertambah setiap bulannya, mulai bayi sampai sekarang. Berat badan pasien saat ini 10,8 dengan tinggi badan + 70 cm. Perkembangan-
Motorik kasar : duduk pada usia 6 bulan, berdiri pada usia 9 bulan, mulai belajar jalan pada usia 11 bulan
-
Motorik halus : mulai memegang alat tulis dan mencoret-coret pada usia 11 bulan Bahasa : mulai bicara jelas pada usia 10 bulan Personal sosial : biasa bermain dengan kakaknya dan anak-anak tetangga yang seusia.
Sosial Ekonomi dan Lingkungan Pasien adalah anak ke dua, ayah dan ibu adalah wiraswasta, memiliki salon dan toko di rumah dengan pendapatan perbulan sekitar 1,5 2 juta rupiah. Pasien tinggal bersama ayah, ibu dan seorang kakak di sebuah rumah dengan 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dan ruang masak. Rumah merupakan rumah permanen, terbuat dari batako, lantai ubin, beratap genteng, jendela sering dibuka, cahaya matahari yang masuk dirasa cukup. Sumber air untuk kebutuhan sehari-hari berasal dari PAM. Ibu sering memberi makan anak sambil
berjualan di toko kelontongnya, ibu sering member makan pasien dengan tangan yang belum dicuci setelah menerima uang dari pelanggan. Anamnesis Sistem System cerebrospinal : pasien tampak lemas System kardiovaskular : tidak ada keluhan System respiratorius : pasien sering pilek bila udara dingin System gastrointestinal : pasien belum BAB sejak mulai panas yaitu 3 hari SMRS, sebelumnya pasien BAB 1 hari 1 kali System urogenital : BAK dirasa normal System integumentum : tidak ada keluhan System muskuloskeletal : gangguan gerak disangkal, kelemahan otot disangkal C. PEMERIKSAAN FISIK Status Generalisata Keadaan umum : pasien tampak lemah Kesadaran : CM Vital sign Nadi Respiratory Rate Suhu Status Gizi Berat badan Tinggi badan : 10,8 kg : + 70 cm 86 x/menit, isi dan teganagan cukup, teratur 22 x/menit 38C
Pemeriksaan Kepala
Kepala Wajah Mata
: Bentuk mesochepal, rambut hitam, distribusi merata : Simetris, pigmentasi (-), tanda-tanda radang (-) : Konjungtiva anemis (-/-), sclera ikterik (-/-), udem (-/-), hiperemis (-/-), pupil isokor (+/+)
Hidung Mulut Telinga
: deformitas (-), sekret (-), nafas cuping hidung (-) : bibir dbn, mukosa basah, coated tounge (+), faring hiperemi (-) : discharge (-), nyeri tekan tragus (-), pendengaran normal
Pemeriksaan Leher Pembesaran limfonodi kanan kiri (-)
Pemeriksaan Thorax Inspeksi Palpasi Perkusi : deformitas (-), simetris, sikatrik (-), ketinggalan gerak saat nafas (-), retraksi (-) : iktus cordis teraba di SIC 4-5 : lapang paru sonor, cor redup
Auskultasi : pulmo SD vesikuler (+/+) ST (-/-) Pemeriksaan Abdomen Inspeksi : dinding dada // dinding perut, massa (-), sikatrik (-)
Auskultasi : peristaltic (+) Perkusi Palpasi : timpani (+) : supel, massa tumor (-), hepar ttb, lien ttb, turgor elastisitas baik
Pemeriksaan Ekstrimitas Simetris, kelainan kulit (-), refleks fisiologis (+), kekuatan otot 5/5
D. PEMERIKSAAN PENUNJANG Pemeriksaan Lab. (18 juli 2010) WBC LYM MID GRA LY% MI% GR% RBC HGB HCT : 17,83 x 103 /L : 5,65 x 103 /L : 0,48 x 103 /L : 11,70 x 103 /L : 31,7% : 2,7% : 65,5% : 5,20 x 106 /L : 10,1 g/dl : 32,67% MCV MCH MCHC PLT Malaria : 63 fl : 19,4 pg : 30,9 g/dl : 319 x 103 /L : (-) negatif
Widal Ty H: + 1/80 Widal Ty O: + 1/320 SGOT SGPT GDS : 27 : 15 : 81
E. Follow Up tanggal 20 Juli 2010 Vital sign : Nadi Respiratory Rate Suhu 86 x/menit, isi dan teganagan cukup, teratur 22 x/menit 38C
S/ panas (-), BAB (-) sudah 3 hari, mual (-), muntah (-) O/ KU : CM, lemas Kepala : mata CA (-/-) SI (-/-), lidah kotor (+) Leher : lnn membesar (-) Thorax : pulmo SD vesikuler (+/+), ST (-/-) Abd : peristaltik (+), timpani (+), supel, hepar ttb, lien ttb
Ekst. : akral hangat A/ demam tifoid dan kejang demam P/ O2 1-2 liter, Ka en 4B 1000 ml/24jam, Cefotaxim 3 x 325, Luminal 2 x 25 mg , Gerdilium drop 3 x 0,8 ml, paracetamol 3 x 1 cth, Ambroxol Hcl 3 x 1 cth
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. DEFINISI : Demam tifoid (tifoid abdominalis, enteric fever) merupakan penyakit infeksi akut yang biasanya terdapat pada saluran pencernaan dengan gejala demam lebih dari satu minggu, gangguan pada saluran pencernaan dan gangguan kesadaran.1 B. ETIOLOGI : Demam tifoid disebabkan oleh Salmonella thypi dan Salmonella parathypi. Salmonela merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Salmonella memiliki karakteristik memfermentasikan glukosa dan mannose tanpa memproduksi gas, tetapi tidak memfermentasikan laktosa atau sukrose. Seperti Enterobacteriaceae yang lain Salmonella memiliki tiga macam antigen yaitu antigen O (tahan panas, terdiri dari lipopolisakarida), antigen Vi (tidak tahan panas, polisakarida), dan antigen H (dapat didenaturasi dengan panas dan alkohol). Biasanya dalam serum penderita terdapat zat anti terhadap ketiga macam antigen tersebut. Salmonella hampir selalu masuk melalui makanan dan minuman yang terkomtaminasi. Reservoir kuman ini antara lain unggas, babi, hewan pengerat, sapi, dan hewan peliharaan.3 C. EPIDEMIOLOGI : Demam tifoid merupakan masalah kesehatan yang penting di negara-negara berkembang. Penyakit ini dikenal memiliki gejala dengan spectrum klinis yang sangat luas. Diperkirakan angka kejadiannya 150/100.000 per tahun di Amerika Serikat dan 900/100.000 per tahun di Asia2. Di Indonesia (daerah endemis), penderita yang ditemukan biasanya berumur diatas
satu tahun. Insiden infeksi salmonella tertinggi terjadi pada usia 1-4 tahun. Angka kematian lebih tinggi pada bayi, orang tua dan pada orang dengan system kekebalan tubuh yang menurun (HIV, keganasan)4. D. PATHOGENESIS Bakteri masuk melalui saluran cerna, dibutuhkan 105-109 bakteri untuk dapat menimbulkan infeksi. Sebagian besar bakteri mati oleh asam lambung. Bakteri yang tetap hidup akan masuk ke dalam ileum melalui mikrovili dan mencapai plak peyeri, selanjutnya masuk ke dalam pembuluh darah (bakteremia primer). Basil yang tidak dihancurkan tadi akan berkembang biak pada hati dan limpa sehingga organ-organ tersebut akan membesar disertai nyeri pada perabaan. Kemudian basil akan masuk kedalam darah lagi dan menyebar ke seluruh tubuh terutama ke kelenjar limfoid usus halus dan dapat menimbulkan tukak berbentuk lonjong pada mukosa diatas plak peyeri. Tukak tersebut dapat menyebabkan perdarahan dan perforasi usus. Gejala demam disebabkan oleh endotoksin, sedangkan gejala pada saluran cerna disebabkan oleh kelainan pada usus1. E. TEMUAN KLINIS Gejala klinis : 1. Demam 3 minggu, bersifat febris remitten. Pada kasus khas terdapat demam remitten pada minggu pertama, biasanya menurun pada pagi hari dan suhu naik pada sore dan malam hari. Pada minggu kedua, pasien terus-menerus dalam keadaan demam yang berangsur-angsur turun pada minggu ketiga. 2. Gangguan pada saluran pencernaan : pada mulut terdapat gejala nafas berbau tidak sedap, bibir kering dan pecah-pecah, lidah ditutupi selaput putih kotor, ujung dan tepinya kemerahan, jarang disertai tremor. Pada abdomen kemungkinan dapat dijumpai perut
kembung (meteorismus), hati dan limpa membesar disertai nyeri pada perabaan, bisa tedapat konstipasi, bisa juga diare. 3. Gangguan kesadaran biasanya apatis sampai somnolen, jarang terjadi sopor ataupun koma. Disamping gejala tersebut dapat pula dijumpai gejala lain seperti dijumpainya rose spot, berupa ruam makulopapuler berwarna merah dengan ukuran 1-5 mm akibat emboli basil dalam kapiler kulit yang biasa didapat pada anggota gerak4. Relaps Yaitu keadaan berulangnya gejala penyakit tifus abdominalis, akan tetapi manifestasinya lebih ringan dan lebih singkat. Terjadi dalam minggu kedua setelah suhu badan normal kembali. Menurut teori, relaps terjadi karena terdapatnya basil dalam organ-organ yang tidak dapat dimusnahkan baik oleh obat maupun zat anti. Mungkin pula relaps terjadi saat penyembuhan tukak, terjadi invasi basil bersamaan dengan pembentukan jaringan-jaringan fibroblast1. Temuan Laboratorium Pemeriksaan laboratorium sebagai berikut : 1. Pemeriksaan Rutin -Anemia normositik normokromik terjadi sebagai akibat perdarahan usus atau supresi pada sumsum tulang. -Leukopenia, namun jarang kurang dari 3000/uL. -Limfositosis relatif dan anaeosinofilia pada permulaan sakit. -Trombositopeni terutama pada demam tifoid berat2.
2. Pemeriksaan serologi -Serologi Widal dilakukan dengan mencampur serum yang sudah diencerkan dengan suspensi salmonella mati yang mengandung antigen O (somatik) dan H (flagella). Titik akhir dari pemeriksaan adalah pengenceran tertinggi serum pasien yang menyebabkan aglutinasi makroskopik suspensi salmonella5. -Kadar Ig M dan Ig G (Typhi-dot). -tes TUBEX -metode enzyme immunoassay (EIA) -metode enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), dan -pemeriksaan dipstik. 3. Biakan Salmonela -Biakan darah terutama pada minggu I perjalanan penyakit. -Kultur tinja terutama pada minggu II perjalanan penyakit. 4. Identifikasi kuman secara molekuler : Mendeteksi DNA (asam nukleat) gen flagellin bakteri S. typhi dalam darah dengan teknik hibridisasi asam nukleat atau amplifikasi DNA dengan cara polymerase chain reaction (PCR) melalui identifikasi antigen Vi yang spesifik untuk S. typhi5. F. DIAGNOSIS Diagnosis Kerja Diagnosis dugaan demam tifoid dibuat berdasarkan gejala klinis berupa demam, gangguan gastrointestinal, dan mungkin disertai gangguan kesadaran, atau ditemukannya respon antibody yang spesifik terhadap S. thypi2.
Menurut WHO, demam tifoid dipertimbangkan jika anak demam dan mempunyai salah satu tanda berikut ini6 : -Demam (biasanya lebih dari 7 hari) -Terlihat jelas sakit dan kondisi serius tanpa sebab yang jelas -Nyeri perut, kembung, mual, muntah, diare, atau konstipasi -Delirium -Hepatosplenomegali -Pada demam tifoid berat dapat dijumpai penurunan kesadaran, kejang, dan ikterus- Dapat timbul dengan tanda yang tidak tipikal terutama pada bayi muda sebagai demam
akut disertai dengan syok dan hipotermi. Diagnosis kerja lain Pada kasus ini pasien masuk ke rumah sakit disebabkan kejang oleh karena pasien mengalami panas tinggi, dimana pada saat pertama kali datang panas tubuh pasien mencapai 41C. G. DIAGNOSIS BANDING : Pada stadium dini demam tifoid, beberapa penyakit kadang secara klinis dapat menjadi diagnosis bandingnya, yaitu influenza, gastroenteritis, bronchitis, dan bronkopneumonia. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme intraseluler seperti malaria, Tuberkulosis, infeksi jamur sistemik, bruselosis, tularemia, shigellosis, dan leptospirosis juga perlu dipikirkan. Pada demam tifoid yang berat, sepsis, leukemia, limfoma, dan penyakit Hodgkin dapat sebagai diagnosis banding.2 H. PENATALAKSANAAN : 1. Isolasi penderita dan desinfeksi pakaian penderita.
2. Perawatan yang baik mengingat akan komplikasi, sakit yang lama dan anoreksia pada pasien demam tifoid. 3. Istirahat selama demam sampai dengan 2 minggu normal kembali, yaitu istirahat mutlak, berbaring terus di tempat tidur. Seminggu kemudian boleh duduk dan selanjutnya berdiri dan berjalan. 4. Diet makanan yang dikonsumsi harus mengandung cukup protein, cairan dan berkalori tinggi. Bahan makanan tidak boleh mengandung serat, tidak merangsang dan tidak menimbulkan banyak gas 5. Obatobat pilihan pertama adalah kloramfenikol, ampisilin / amoxicillin dan kotrimoksasol. Obat pilihan kedua adalah sefalosporin generasi III. Obat-obat pilihan ketiga adalah meropenem, azithromisisn dan florokuinolon. Kloramfenikol diberikan dengan dosis 50 mg/ kg/ BB/ hari, terbagi dalam 3-4 x pemberian. Pemberian intravena saat belum dapat minum obat, selama 21 hari, atau amoxicillin dengan dosis 100 mg/ kg/ BB/ hari, terbagi dalam 3-4 kali. Pemberian oral/ intravenaselama 21 hari kotrimoksasol dengan dosis (tmp) 8 mg/ kgBB/ hari terbagi dalam 2-3 kali pemberian, oral, selama 14 hari. Evaluasi kloramfenikol harus dilakukan setelah 1 minggu, karena efek kloramfenikol dapat mendepresi sum-sum tulang. Cara mengetahui apabila ada depresi adalah apabila Hb < 7 atau AL 2 minggu. Pasien tidak ikterik pada sclera dan membrane mukosa, seperti pada penyakit hepatitis. Pemeriksaan SGOT SGPT menunjukkan angka normal. Pola demam dengan suhu naik di sore dan malam hari, dan turun di pagi hari merupakan pola yang biasanya ada pada demam tifoid. Obstipasi yang terjadi pada pasien menunjukkan
adanya gangguan gastrointestinal. Penegakan diagnosis didukung oleh uji serologis widal dengan hasil titer agglutinin H 1/80 dan titer agglutinin O 1/320 membantu penegakan diagnosis demam tifoid. Rencana pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis pasti demam tifoid adalah dengan melakukan kultur dari specimen darah (minggu pertama demam), specimen feses (minggu kedua demam), atau specimen urin (minggu ketiga demam). Faktor resiko untuk menderita demam tifoid pada pasien ini berupa ibu yang sering memberi makan dengan tangan sambil berjualan, saat ibu menerima uang dari pelanggan ibu tidak mencuci tangan terlebih dahulu pada saat akan menyuapi si anak yang memungkinkan makanan terkontaminasi S.thypi. Terapi pada pasien ini meliputi: a. Terapi Kausatif Cefotaxime iv 3 x 325 mg b. Terapi Suportif Luminal 2 x 25 mg, Gerdilium drop 3 x 0,8 ml, Paracetamol 3 x 1 cth, Ambroxol Hcl 3 x 1 ml c. Terapi dietika Pertama-tama diberikan bubur saring yang kemudian diganti dengan bubur kasar, dapat juga diberikan makanan rendah serat sehingga mudah dicerna dan juga susu. d. Edukasi Edukasi kepada pasien dan keluarga untuk memperhatikan pola, kualitas, dan kuantitas makanan, menjaga self hygiene seperti mencuci tangan sebelum makan dan memasak,
menjaga kebersihan makanan dan minuman. Selama perawatan di pusat pelayanan kesehatan, pengunjung dibatasi untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial.
DAFTAR PUSTAKA1. Staff Pengajar Ilmu Kesehatan Anak FK UI. 1985. Buku Kuliah Ilmu Kesehatan Anak jilid 2. Penerbit FK UI : Jakarta2. Soedarmo, SSP. Garna, H. Hadinegoro, SRS. Satari, HI. Demam Tifoid. Buku Ajar
Infeksi & Pediatri Tropis. Edisi Kedua. Ikatan Dokter Anak Indonesia. Badan Penerbit IDAI. Jakarta. 2008. p. 338-346 3. Jawetz, Melnick & Adelburg. 1996. Mikrobiologi Kedokteran ed.20. penerbit Buku Kedokteran ECG : Jakatra4. Parry CM, Hien TT, Dougan G, White NJ, Farrar JJ. Review Article : Typhoid Fever.
New Eng. J of Med. 2002;347(22):1770-82 5. Sacher, R.A. McPherson, R.A. Diagnosis Serologik Penyakit Infeksi. Tinjauan Klinis Hasil Pemeriksaan Laboratorium, ed. 11. EGC. Jakatta. 2004. p. 454-455. 6. Tim Adaptasi Indonesia. Demam Tifoid. Buku Saku Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit Pedoman bagi Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama di Kabupaten/Kota. WHO Indonesia. Jakarta.2008.