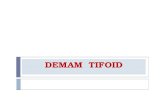demam tifoid
Transcript of demam tifoid

LI 1 : Memahami dan menjelaskan tentang demam
LO 1.1 : Definisi
Demam pada umumnya diartikan suhu tubuh di atas 37.2oC. biasanya terdapat perbedaan antara pengukuran suhu di aksila dan oral maupun rektal. Dalam keadaan biasa perbedaan ini berkisar sekitar 0.5oC. suhu rektal lebih tinggi daripada suhu oral.
LO 1.2 : Penyebab
Penyebab demam selain infeksi juga dapat disebabkan oleh keadaan toksemia, karena keganasan atau reaksi terhadap pemakaian obat. Juga gangguan pada pusat regulasi suhu sentral dapat menyebabkan peninggian temperature seperti pada heat stroke, perdarahan otak, koma atau gang-guan sentral lainnya. Pada perdarahan internal pada saat terjadinya reabsorbsi darah dapat pula menyebabkan peningkatan temperature.
LO 1.3 : Jenis-jenis
1. Demam septikPada tipe demam septik, suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali ke tingkat di atas normal pada pagi hari. Sering disertai keluhan mengigil dan berkeringat. Bila demam yang tinggi tersebut turun ke tingkat yang normal dinamakan juga demam hektik.
2. Demam remitenPada tipe demam remiten, suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah mencapai suhu badan normal. Perbedaan suhu yang mungkin tercatat dapat mencapai dua derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang dicatat pada demam septik.
3. Demam intermitenSuhu badan turun ke tingkat yang normal selama beberapa jam dalam satu hari. Bila demam seperti ini terjadi setiap dua hari sekali disebut tersiana dan bila terjadi dua hari bebas demam di antara serangan demam disebut kuartana.
4. Demam kontinyuPada tipe demam kontinyu, variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari satu derajat. Pada tingkat demam yang terus-menerus tinggi sekali disebut hiperpireksia.
5. Demam siklikTerjadi kenaikan suhu badan selama beberapa hari yang diikuti oleh periode bebas demam untuk beberapa hari yang kemudian diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula.

LI 2 : Memahami dan menjelaskan Salmonella
LO 2.1 : Jenis-jenis
1. Salmonella typosaGenus bacteria enterobacteria gram negatife berbentuk tongkat yang mengakibatkan penyakit paratifus, tifus dan food borne. Spesies-spesies salmonella dapat bergerak bebas dan menghasilkan hydrogen sulfide(Jawetz, 2005).Salmonella merupakan kuman gram negative, tidak berspora dan panjangnya berfariasi. Kebanyakan spesies bergerak dengan flagel peritrih. Salmonella tumbuh cepat pada pembenihan biasa tetapi tidak meragikan sukrosa dan laktosa. Kuman ini merupakan asam dan beberapa gas dan glukosa dan manosa. Kuman ini dapat hidup dalam air yang dibekukan dengan masa yang lama. Salmonella resisten terhadap zat-zat kimia tertentu misalnya hijau brilliant, natrium tetrationat dan natrium dioksikholat. Senyawa ini menghambat kuman koliform dan karena itu bermanfaat untuk isolasi salmosella dari tinja(Lay bco, 1994)
2. Salmonella thypimoriumMorfologi spesies ini adalah batang lurus pendek dengan panjang 1-1,5 mikrometer. Tidak berbentuk spora, gram negatife dan ciri-ciri morfologi dan fisiologi sangat erat hubungannya dengan genus lain dalam family enterobacteriaceae. Biasanya bergerak motil dengan menggunakan peritrichous flagella, dan kadang terjadi bentuk non motilnya. Memproduksi asam dan gas dari glukosa, maltose, mannitol dan sorbitol, tetapi tidak memfermentasi laktosa, sukrosa atau salian tidak membentuk indol, susu koagulat atau gelatin cair (Robinson, 1998).
3. Salmonella entereditisSalmonella entereditis adalah penyebab penyakit usus, gejalanya berupa sakit atau kejang-kejang pada bagian perut, demam, hilangnya nafsu makan, mual, dan diare. Pada enteriditis akut, meskipun berlangsung singkat dan tidak begitu serius, dapat sangat menguras tenaga bayi dan orang dewasa yang mengidapnya. Memasak telur dan daging ayam dengan sempurna dapat mematikan bakteri salmonella(Lay bco, 1994)
4. Salmonella Choleraesuis5. Salmonella Dublin6. Salmonella Gallinarum7. Salmonella Hadar8. Salmonella Heidelberg9. Salmonella Infantis10. Salmonella Paratyphi11. Salmonella Typhi12. Salmonella Genrus

LO 2.2 : Struktur
LO 2.3 : Sifat
Bentuk batang, gram negatif, bergerk dengan flagel peritrich, mudah tumbuh pada perbenihan biasa dan tumbuh baik pada perbenihan yang mengandung empedu,sebagian besar salmonella sp bersifat patogen pada binatang dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Binatang itu antara lain tikus, ternak, anjing, kucing, di alam bebas salmonella dapat tahan hidup lama dalam air, tanah atau pada bahan makanan.
LO 2.4 : Siklus hidup
- Infeksi terjadi dari memakan makanan yang tercontaminasi dengan feses yang terdapat bakteri Salmonella dari organisme pembawa (hosts).
- Setelah masuk dalam saluran pencernaan maka dia menyerang dinding usus yang menyebabkan kerusakan dan peradangan.
- Infeksi dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah karena dapat menembus dinding usus tadi ke organ-organ lain seperti hati, paru-paru, limpa, tulang-tulang sendi, plasenta dan dapat menembusnya sehingga menyerang fetus pada wanita atau hewan betina yang hamil, dan ke membran yang menyelubungi otak.
- Subtansi racun diproduksi oleh bakteri ini dan dapat dilepaskan dan mempengaruhi keseimbangan tubuh.
- Di dalam hewan atau manusia yang terinfeksi, pada fesesnya terdapat kumpulan Salmonella yang bisa bertahan sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
- Bakteri ini tahan terhadap range yang lebar dari temperature sehingga dapat bertahan hidup berbulan-bulan dalam tanah atau air.
LI 3: Memahami dan menjelaskan demam tifoid
LO 3.1 : Definisi
Demam tifoid (typhoid fever) atau yang lebih dikenal dengan penyakit tifus ini merupakan suatu penyakit pada saluran pencernaan yang sering menyerang anak-anak bahkan juga orang dewasa. Penyebab penyakit tersebut adalah bakteri Salmonella typhi. Selama terjadi infeksi, kuman

tersebut bermultiplikasi dalam sel fagositik mononuklear dan secara berkelanjutan dilepaskan ke aliran darah.
LO 3.2 : Etiologi
Demam tifoid disebabkan oleh jenis Salmonella tertentu yaitu S. Typhi, S. Paratyphi A, dan S. Paratyphi B dan kadang-kadang jenis Salmonella yang lain. Demam yang disebabkan oleh S. Typhi cendrung untuk menjadi lebih berat daripada bentuk infeksi Salmonella yang lain. (Ashkenazi et al, 2002). Bakteri tifoid ditemukan dalam tinja dan air kemih penderita. Penyebaran bakteri ke dalam makana atau minuman bisa terjadi akibat pencucian tangan yang kurang bersih setelah buang air besar maupun buang air kecil. Lalat bisa menyebarkan bakteri secara langsung dari tinja ke makanan. Bakteri masuk ke saluran pencernaan dan bisa masuk ke peradaran darah. Hal ini akan diikuti oleh terjadinya peradangan pada usus halus dan usus besar. Pada kasus yang berat, yang bisa berakibat fatal, jaringan bisa mengalami perdarahan dan perforasi (perlubangan).
LO 3.3 : Patogenesis
Masuknya kuman Salmonella typhi dan Salmonella parathypi ke dalam tubuh manusia terjadi melalui makanan yang terkontaminasi kuman. Sebagian kuman dimusnahkan dalam lambung, sebagian lolos masuk ke dalam usus dan selanjutnya berkembang biak. Bila respons imunitas humoral mukosa (IgA) usus kurang baik maka kuman akan menembus sel-sel epitel dan selanjut-nya ke lamina propia. Di sana kuman berkembang biak dan difagosit oleh sel-sel fagosit. Kuman dapat hidup dan berkembang biak di dalam makrofag dan selanjutnya di bawa ke plak Peyeri ileum distal dan kemudian ke kelenjar getah bening mesentrika. Selanjutnya melalui duktus torasikus kuman yang terdapat dalam makrofag ini masuk ke sirkulasi darah dan menyebar ke seluruh organ retikuloendotelial tubuh terutama hati dan limpa. Di organ ini, kuman meninggalkan sel fagosit dan berkembang biak di luar sel dan selanjutnya masuk ke dalam sirkulasi darah lagi mengakibat-kan bacteremia yang kedua dengan disertai tanda-tanda dan gejala penyakit infeksi sistemik.
Dalam hati, kuman masuk ke dalam kantung empedu, berkembang biak, dan bersama cairan empedu diekskresikan ke lumen usus. Sebagian kuman dikeluarkan melalui feses dan sebagian lagi masuk lagi ke dalam sirkulasi setelah menembus usus.
LO 3.4 : Patofisiologi
Sel fagosit masuk berkembang biak di ekstrasel atau organ sinusoid sirkulasi darah (baktermeia II) tanda dan gejala sistemik.
Setelah berkembang biak di ekstrasel hati kandung empedu dan berkembang biak lumen usus sebagian ke feses sebagian menembus usus lagi makrofag sudah teraktivasi hiperaktif melepas sitokin reaksi inflamasi sistemik gejala.
Hiperaktif reaksi hyperplasia plek pyeri / erosi pembuluh darah menyebabkan perdarahan saluran cerna/ proses berjalan terus menembus lapisan mukosa dan otot sehingga terjadi proliferasi

Makrofag yang sudah teraktivasi reaksi hipersensitivitas tipe lambat hiperplasi nekrosis reaksi hiperplasi plek pyeri.
Pada minggu pertama, gejalanya adalah demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare, perasaan tidak enak di perut, batuk, dan epistaksis. Sifat demamnya meningkat perlahan-lahan dan terutama pada sore hingga malam hari.
Dalam minggu ke dua gejala-gejala menjadi lebih jelas berupa demam, bradikardia relative ( pe-ningkatan suhu 1 derajat Celcius tidak diikuti peningkatan denyut nadi 8 kali per menit), lidah yang berselaput (kotor di tengah, tepid an ujung merah serta tremor), hepatomegaly, splenomegaly, meteroismus, gangguan mental berupa somnolen, stupor, koma, delirium, atau psikosis.
LO 3.5 : Epidemiologi
Surveilans Departemen Kesehatan RI, frekuensi kejadian demam tifoid di Indonesia pada tahun 1990 sebesar 9.2 dan pada tahun 1994 terjadi peningkatan frekuensi menjadi 15.4 per 10.000 penduduk. Dari survey berbagai rumah sakit di Indonesia dari tahun 1981 sampai dengan 1986 memperlihatkan peningkatan jumlah penderita sekitar 35.8%, yaitu dari 19.596 menjadi 26.606 kasus.
Insiden demam tifoid bervariasi di tiap daerah dan biasanya terkait dengan sanitasi lingkungan. Di daerah rural (Jawa Barat) 157 kasus per 100.000 penduduk, sedangkan di daerah urban ditemukan 760-810 per 100.000 penduduk. Perbedaan insiden di perkotaan berhubungan erat dengan penye-diaan air bersih yang belum memadai serta sanitasi lingkungan dengan pembuangan sampah yang kurang memenuhi syarat kesehatan lingkungan.
Case fatality rate demam tifoid di tahun 1996 sebesar 1.08% dari seluruh kematian di Indonesia. Namun demikian bersadarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga Departemen Kesehatan RI tahun 1995 demam tifoid tidak termasuk dalam 10 penyakit dengan mortalitas tertinggi.
LO 3.6 : Diagnosis
Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala-gejala dan hasil pemeriksaan fisik. Untuk memperkuat diagnosis, dilakukan biakan darah tinja, air kemih, atau jaringan tubuh lainnya guna menemukan bakteri penyebabnya.
LO 3.7 : Pemeriksaan fisik dan penunjang
Pemeriksaan fisik bisa dilakukan dengan melihat tanda dan gejala fisik dari pasien. Pemeriksaan penunjang meliputi:
1. Pemeriksaan rutinWalaupun pada pemeriksaan darah perifer lengkap sering ditemukan leukopenia, dapat pula terjadi kadar leukosit normal atau leukositosis.
2. Uji widalUji widal dilakukan untuk deteksi antibody terhadap kuman S. typhi. Pada uji widal terjadi suatu reaksi aglutinasi antara antigen kuman S. typhi dengan antibody yang

disebut agglutinin. Antigen yang digunakan pada uji widal adalah suspense Salmonella yang sudah dimatikan dan diolah di laboratorium. Maksud uji widal adalah untuk menentukan adanya agglutinin dalam serum penderita tersangka demam tifoid yaitu: Aglutinin O (dari tubuh kuman, Aglutinin H (flagella kuman), Aglutinin Vi (simpai kuman). Dari ketiga agglutinin tersebut hanya aglutinin O dan H yang digunakan untuk diagnosis demam tifoid. Semakin tinggi titernya semakin besar kemungkinan terinfeksi kuman ini.
3. Uji TUBEXUji TUBEX merupakan uji semi-kuantitatif kolometrik yang cepat (beberapa menit) dan mudah untuk dikerjakan. Uji ini mendeteksi antibody anti-S. thypi O9 pada serum pasien, dengan cara menghambat ikatan antara IgM anti-O9 yang terkonjugasi pada partikel latex yang berwarna dengan lipopilisakarida S. typhi yang terkonjugasi pada partikel magnetic latex. Hasil positif uji tubex ini menunjukkan terdapat infeksi Salmonellae serogrup D walau tidak secara spesifik menunjuk pada S. typhi. Infeksi oleh S. paratyphi akan mem-berikan hasil negative.
4. Uji TyphidotUji typhidot dapat mendeteksi antibody IgM dan IgG yang terdapat pada protein membrane luar Salmonella typhi. Hasil positif pada uji typhidot didapatkan 2-3 hari setelah infeksi dan dapat mengidentifikasi secara spesifik antibody IgM dan IgG terhadap antigen S. typhi seberat 50 kD, yang terdapat pada strip nitroselulosa.
5. Uji IgM DipstickUji ini secara khusus mendeteksi antibody IgM spesifik terhadap S. typhi pada specimen serum atau whole blood.
6. Kultur DarahHasil biakan darah yang positif memastikan demam tifoid, akan tetapi hasil negative tidak menyingkirkan demam tifoid, karena mungkin disebabkan beberapa hal sebagai berikut:1) Telah mendapat terapi antibiotic. Bila pasien sebelum dilakukan kultur darah telah
mendapat antibiotic, pertumbuhan kuman dalam media biakan terhambat.2) Volume darah yang kurang. Bila darah yang dibiakkan terlalu sedikit, hasil biakan
bisa negative.3) Riwayat vaksinasi. Vaksinasi di masa lampau menimbulkan antibody dalam darah
pasien dan dapat menekan bacteremia.4) Saat pengambilan darah setelah minggu pertama, pada saat aglutinin semakin
meningkat.
LO 3.8 : Penatalaksanaan
1. Istirahat dan perawatan, dengan tujuan mencegah komplikasi dan mempercepat penyem-buhan.
2. Diet dan terapi penunjang, dengan tujuan mengembalikan rasa nyaman dan kesehatan pasien secara optimal.
3. Pemberian antimikroba, dengan tujuan menghentikan dan mencegah penyebaran kuman. Obat-obat antimikroba yang sering digunakan untuk mengobati demam tifoid adalah:

- Kloramfenikol. Dosis yang diberikan adalah 4 x 500 mg per hari dapat diberikan per oral atau intravena. Diberikan sampai dengan 7 hari bebas panas.
- Tiamfenikol. Dosisnya 4 x 500 mg, demam rata-rata menurun pada hari ke-5 sampai ke-6.
- Kotrimoksazol. Dosis untuk orang dewasa adalah 2 x 2 tablet diberikan selama 2 minggu.- Ampisilin dan amoksisilin. Kemampuannya menurunkan demam lebih rendah dari
kloramfenikol, dosisnya 50-150 mg/kgBB dan digunakan selama 2 minggu.- Sefalosporin Generasi Ketiga. Golongan obat ini yang terbukti efektif untuk demam
tifoid adalah seftriakson, dosisnya 3-4 gr dalam dekstrosa 100 cc diberikan selama 0.5 jam per-infus sekali sehari, diberikan selama 3 hingga 5 hari.
- Golongan Fluoroquinolon. Ada beberapa jenis yang dipakai: norfloksasin, siprofloksasin, ofloksasin, pefloksasin, fleroksasin.
- Azitromisin. Dosisnya 2 x 500 mg, dibandingan dengan fluorokuinolon, azitromisin secara signifikan mengurangi kegagalan klinis dan durasi rawat inap.
LO 3.9 : Prognosis
Prognosis demam tifoid tergantung dari umur, keadaan umum, derajat kekebalan tubuh, jumlah dan virulensi Salmonella serta cepat dan tepatnya pengobatan. Angka kematian pada anak-anak 2,6% dan pada orang dewasa 7,4%, rata-rata 5,7%.
LO 3.10 : Pencegahan
Vaksin tipus per oral memberikan perlindungan sebesar 70%. Vaksin ini hanya diberikan kepada orang-orang yang telah terpapar bakteri Salmonella typhi dan orang-orang yang memiliki risiko tinggi. Sebaiknya menghindari makan sayuran mentah dan makanan lainnya yang disimpan atau disajikan pada suhu ruangan. Sebaiknya memilih makanan yang masih panas atau makanan yang dibekukan, minuman kaleng, dan buah berkulit yang bisa dikupas.
Daftar pustaka:
http://suhenik.blogspot.com/2010/03/salmonella-typhi.html
Sudoyo, dkk. Ilmu Penyakit Dalam jilid 3. Jakarta: EGC. Hal 2797-2804
http://medicastore.com/penyakit/10/Demam_Tifoid.html