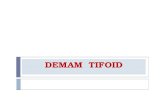DEMAM TIFOID
-
Upload
dindavalupi -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
description
Transcript of DEMAM TIFOID
DEMAM TIFOIDPENDAHULUAN Demam tifoid merupakan penyakit endemik di Indonesia. Penyakit ini termasuk penyakit menular yang tercantum dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1962 tentang wabah. Kelompok penyakit menular ini merupakan penyakit yang mudah menular dan dapat menyerang banyak orang sehingga dapat menimbulkan wabah.1EPIDEMIOLOGI
Surveilands Departemen Kesehatan RI,frekuensi kejadian demam tifoid di Indonesia pada tahun 1990 sebesar 9,2 dan pada tahun 1994 terjadi peningkatan frekuensi menjadi 15,4 per 10.000 penduduk. Dari survei berbagai rumah sakit di Indonesia dari tahun 1981 sampai dengan 1986 memperlihatkan peningkatan jumlah penderita sekitar 35,8% yaitu 19.596 menjadi 26.606 kasus.1
Penelitian di RSUD Persahabatan Jakarta, memperlihatkan kasus demam tifoid angka kejadian demam tifoid dari tahun 1997 hingga 1999 adalah berkisar antara 5-18 kasus setiap bulan. Pada tahun 1997 jumlah penderita demam tifoid adalah 40 kasus, pada tahun 1998 adalah 40 kasus, sedangkan pada tahun 1999 adalah 37 kasus.2TINJAUAN PUSTAKA
DEFINISI
Demam tifoid disebut juga dengan typus abdominalis atau typhoid fever. Demam tifoid ialah penyakit infeksi akut yang biasanya terdapat pada saluran pencernaan (usus halus) dengan gejala demam satu minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran pencernaan dan dengan atau tanpa kesadaran terganggu.
ETIOLOGIDemam tifoid disebabkan oleh bakteri salmonella typhi atau salmonella paratyphi dari genus salmonella. Bakteri ini berbentuk batang gram negatif, tidak berbentuk spora, motil, berkapsul dan mempunyai flagella (bergerak dengan rambut getar). Bakteri ini dapat hidup sampai beberapa minggu di alam bebas seperti di dalam air, es, sampah dan debu. Bakteri ini dapat mati dengan pemanasan suhu 60 C selama 15-20 menit, pasteurisasi, pendidihan dan khlorinisasi
Salmonella typhi mempunyai 3 macam antigen, yaitu :
1. Antigen O (antigen somatik), yaitu terletakpada lapisan luar dari tubuh kuman. Bagian ini mempunyai strukturkimia lipopolisakarida atau disebut endotoksin. Antigen ini tahan terhadap panas dan alkohol tetapi tidak tahan terhadap formaldehid2. Antigen H (antigen flagella), yang terletak pada flagella, fimbriae, atau pili dari kuman. Antigen ini mempunyai struktur kimia suatu protein dan tahan terhadap formaldehid tetapi tidak tahan terhadap panas dan alkohol3. Antigen Vi yang terletak pada kapsul (envelope) dari kuman yang dapat melindungi kuman dari fagositosis.
Ketiga macam antigen tersebut di atas di dalam tubuh penderita akan menimbulkan pula pembentukan 3 macam antibodi yang lazim disebut antibodi.
PATOGENESIS
Penularan kuman salmonella typhi (S.typhi) dan Salmonella paratyphi (S.paratyphi) terjadi melalui makanan dan minuman yang tercemar yang tertelan melalui mulut. Sebagian kuman, oleh asam lambung, dimusnahkan dalam lambung. Kuman dapat melewati lambung selanjutnya masuk ke dalam usus dan selanjutnya berkembang biak. Bila respons imunitas humoral mukosa (IgA) usus kurang baik maka kuman akan menembus sel-sel epitel (terutama sel-M) dan selanjutnya ke lamina propia. Di lamina propia kuman berkembang biak dan difagosit oleh sel-sel fagosit terutam makrofag. Kuman dapat hidup dan berkembang biak di dalam makrofag dan selanjutnya dibawa ke plague peyeri ileum distal dan kemudian ke kelenjar gentah bening mesenterika.
Selanjutnya melalui duktus torasikus kuman yang terdapat di dalam makrofag ini masuk ke dalam sirkulasi darah (mengakibatkan bakteremia pertama yang asimptomatik) dan menyebar ke seluruh organ retikuloendotelial tubuh terutama hati dan limpa. Di organ-organ ini kuman meninggalkan sel-sel fagosit dan kemudian berkembang biak di luar sel atau ruang sinusoid dan selanjutnya masuk lagi ke dalam sirkulasi darah dan mengakibatkan bakteremia kedua dengan tanda-tanda dan gejala penyakit infeksi sistemik.Didalam hati, kuman masuk ke dalam kandung empedu, berkembang biak, dan di sekresikan ke dalam lumen usus melalui cairan empedu. Sebagian kuman ini dikeluarkan melalui feses dan sebagian lainnya menembus usus lagi. Proses yang sama kemudian terjadi lagi, tetapi dalam hal ini makrofag telah teraktivasi. Kuman salmonella di dalam makrofag yang sudah teraktivasi ini akan merangsang makrofag menjadi hiperaktif dan melepaskan beberapa mediator (sitokin) yang selanjutnya akan menimbulakan gejala reaksi inflamasi sistemik seperti demam, malaise, mialgia, sakit kepala, sakit perut, instabilitas vaskular, gangguan mental, dan koagulasi. Sepsis dan syok sepetik dapat terjadi pada stadium ini.
Di dalam plaque peyeri makrofag hiperaktif menimbulkan reaksi hiperplasia jaringan. S.typhi di dalam makrofag dapat merangsang reaksi hipersensitivitas tipe lambat yang dapat menimbulkan hiperplasia dan nekrosis organ.
Pendarahan saluran cerna dapat terjadi akibat erosi pembuluh darah palqua peyeri yang mengalami hiperplasia dan nekrosis atau akibat akumulasi sel-sel mononuklear di dinding usus. Proses patologis jaringan limfoid ini dapat berkembang hingga ke lapisan otot, serosa usus dan dapat mengakibatkan perforasi
Endotoksisn dapat menempel di reseptor sel endotel kapiler dengan akibat timbulnya komplikasi seperti gangguan neuropsikiatrik, kardiovaskular, pernafasan, dan gangguan organ lainnya. 1,3,4,5,6,7
GAMBAR 2. Patofisiologi demam tifoid1
GAMBAR 3. Patofisiologi demam tifoid
DIAGNOSIS
MANIFESTASI KLINIS
Masa tunas demam tifoid berlangsung antara 10-14 hari. Gejala-gejala klinis yang timbul sangat bervariasi dari ringan sampai dengan berat, dari tidak terdiagnosis hingga gambaran penyakit yang jelas dengan komplikasi hingga kematian.1 Dari laporan penelitian retrospektif di jakarta ditemukan penderita berusia 74 tahun dengan diagnosis awal pneumonia, ternyata pada pemeriksaan kultur darah ditemukan kuman Salmonella typhi.8 Data tersebut memperlihatkan salah satu variasi gejala klinis dari demam tifoid.Secara umum gejala klinis penyakit ini pada minggu pertama di temukan keluhan dan gejala yang serupa dengan penyakit infeksi sistemik akut pada umumnya, yaitu demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare, perasaan tidak enak di perut, batuk, dan epitaksis. Pada pemeriksaan fisik hanya didapatkan suhu tubuh yang meningkat.1 Sifat demam adalah meningkat perlahan-lahan dan terutama pada sore hingga malam hari.8 Dalam minggu kedua gejala-gejala menjadi lebih jelas berupa demam, bradikardi relatif, lidah berselaput/coated tongue (kotor ditengah, tepi dan ujung merah serta tremor), hepatomegali, splenomegali, meteroismus (kembung), gangguan mental berupa somnolen, stupor, koma, delirium, atau psikosis, roseolae jarang ditemukan pada orang Indonesia.1 bradikardi relatif adalah peningkatan suhu 1C tidak diikuti peningkatan denyut nadi 8 kali permenit.9PEMERIKSAAN LABORATORIUM
Pemeriksaan Darah Perifer Lengkap
Pada pemeriksaan darah perifer lengkap dapat ditemukan leukopenia, dapat pula terjadi kadar leukosit normal atau leukositosis.8 leukositosis dapat terjadi walaupun tanpa disertai infeksi sekunder.1 Selain itu juga dapat ditemukan anemia ringan dan trombositopenia.1,8 Pada pemeriksaan hitung jenis leukosit dapat terjaid aneosinofilia maupun limfonia.10 Laju endap darah pada demam tifoid dapat meningkat.
Pemeriksaan SGOT dan SGPT
SGOT dan SGPT seringkali meningkat, tetapi akan kembali menjadi normal setelah sembuh. Kenaikan SGOT dan SGPT tidak memerlukan penanganan khusus.1,8Pemeriksaan lain yang rutin dilakukan adalah uji widal dan kultur organisme (standart baku dalam penegakan diagnosis).1Uji Widal
Uji widal dilakukan untuk deteksi antibodi terhadap salmonella typhi. Pada uji widal terjadi suatu reaksi aglutinasi antara antigen kuman Salmonella typhi dengan antibodi yang disebut aglutinin.11 Antigen yang digunakan pada uji widal adalah suspensi salmonella yang sudah dimatikan dan diolah di laboratorium. Maksud uji widal adalah untuk menentukan adanya glutinin dalam serum penderita demam tifoid.1 Akibat infeksi oleh Salmonella typhi, pasien membuat antibodi aglutinin yaitu: 1
1. Aglutinin O, yang dibuat karena rangsangan antigen O (berasal dari tubuh kuman)2. Aglutinin H, karena rangsangan antigen H (berasal dari simpai kuman)
3. Aglutinin Vi, karena rangsangan antigen Vi (berasal dari simpai kuman)
Dari ketiga aglutinin tersebut hanya aglutinin O dan H yang digunakan untuk diagnosis demam tifoid. Makin tinggi titernya makin besar kemungkinan menderita demam tifoid.1
Pembentukan aglutinin mulai terjadi pada akhir minggu pertama demam kemudian meningkat secara cepat dan mencapai puncak pada minggu ke-empat dan tetap tinggi selama beberapa minggu.pada fase akut mula-mula timbul aglutinin O, kemudian diikuti aglutinin H.pada orang yang telah sembuh aglutinin O masih tetap dijumpai setelah 4-6 bulan,sedangkan aglutinin H menetap lebih lama antara 9-12 bulan. Oleh karena itu uji widal bukanlah untuk menetukan kesembuhan penyakit.11,12,13Faktor-faktor yang Mempengaruhi uji widal
Ada 2 faktor yang mempengaruhi uji widal yaitu faktor yang berhubungan dengan penderi dan faktor teknis.1
Faktor yang berhubungan dengan penderita, yaitu :1,12
1. Pengobatan dini dengan antibiotik
2. Pemberikan kortikosteroid
3. Gangguan pembentukan antibodi
4. Saat pengambilan darah
5. Daerah endemik atau non-endemik
6. Riwayat vaksinasi
7. Reaksi anamnestik, yaitu peningkatan titer aglutinin pada infeksi bukan demam tifoid akibat infeksi demam tifoid masa lalu atau vaksinasi
Faktor teknik :1
1. Akibat aglutinasi silang
2. Strain Salmonella yang digunakan untuk suspensi antigen
3. Teknik pemeriksaan antar laboratorium
Saat ini belum ada kesamaan pendapat mengenai titer aglutinin yang bermakna diagnostik untuk demam tifoid. Batas titer yang sering dipaki hanya kesepakatan saja, hanya berlaku setempat dan batas ini bahkan dapat berbeda di berbagai laboratorium setempat.1Reaksi Widal tunggal dengan titer antibodi O 1/320 atau titer antibodi H 1/640 menyokong diagnosis demam tifoid pada pasien dengan gambaran klinis yang khas.1Penelitian di RSUP Persahabatan Jakarta terhadap penderita demam tifoid yang terbukti dari kultur darah menunjukan sekitar 30-50% uji widal menunjukan hasil negatif pada pemeriksaan pertama maupun kedua.
Kultur Darah
Hasil biakan darah yang positif memastikan demam tifoid, akan tetapi hasil negatif tidak menyingkirkan demam tifoid, karena mungkin disebabkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Telah mendapat terapi antibiotik. Bila pasien sebelum dilakukan kultur darah telah mendapat antibiotik, pertumbuhan kuman dalam media biakan terhambat dan hasil mungkin negatif2. Volume darah yang kurang (diperlukan kurang lebih 5 cc darah). Bila darah yang dibiak terlalu sedikit, hasil biakan bisa negatif
3. Riwayat vaksinasi. Vaksinasi dimasa lampau menimbulkan antibodi dalam darah pasien. Antibodi (aglutinin) ini dapat menekan bakteremia hingga biakan darah dapat negatif
4. Saat pengambilan darah setelah minggu pertama, dimana pada saat itu aglutinin semakin meningkat
Uji TubexMerupakan uji semi-kuantitatif kolometrik yang cepat (beberapa menit) dan mudah untuk dikerjakan. Uji ini mendeteksi antibodi anti-S.typhi O9 pada serum pasien, dengan cara menghambat ikatan antara IgM anti O9 yang terkonjugasi pada partikel latex yang berwarna dengan lipopolisakarida S.typhi yang terkonjugasi pada partikel magentik latex. Hasil positif uji tubex ini menunjukkan terdapat infeksi salmonellae serogroup D walau tidak spesifik menunjuk pada S.typhi . infeksi oleh S.paratyphi akan memberikan hasil negatif.1 Uji Typhidot
Uji typhidot dapat mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang terdapat pada protein membran luar Salmonella typhi. Hasil positif pada uji typhoid didapatkan 2-3 hari setelah infeksi dan dapat mengidentifikasi secara spesifik antibodi IgM dan IgG terhadap antigen S.typhi seberat 50 kD, yang terdapat pada strip nitroselulosa.1Uji IgM Dipstick
Uji ini secara khusus mendeteksi antibodi igM spesifik terhadap S.typhi pada spesimen serum atau whole blood. Uji ini menggunakan strip yang mengandung antigen lipopolisakarida (LPS) S.typhoid dan anti IgM (sebagai kontrol), reagen deteksi yang mengandung antibodi anti IgM yang dilekati lateks pewarna, cairan yang membasahi strip sebelum diinkubasi dengan reagen dan serum pasien, tabung uji. TATALAKSANA Sampai saat ini masih dianut trilogi penatalaksaan demam tifoid yaitu: 14
1. istirahat dan perawatan, dengan tujuan mencegah komplikasi dan mempercepat penyembuhan
2. diet dan terapi penunjang (simtomatik dan suportif), dengan tujuan mengembalikan rasa nyaman dan kesehatan pasien secara optimal
3. pemberian antimikroba, dengan tujuan menghentikan dan mencegah penyebaran kuman
1. istirahat dan perawatan
tirah baring dan perawatan bertujuan untuk mencegah komplikasi. Tirah baring dengan perawatan sepenuhnya di tempat tidur seperti makam, minum, mandi, buang air kecil, dan buang air besar akan membantu dan mempercepat masa penyembuhan.12. diet dan terapi penunjangdiet merupakan hal yang cukup penting dalam proses penyembuhan penyakit demam tifoid, karena makanan yang kurang akan menurunkan keadaan umumdan gizi penderita sehingga masa penyembuhan semakin lama. Diet yang diberikan pada pasien demam tifoid adalah makanan yang lunak, seperti bubur saring atau bubur kasar. Pemberian bubur saring dimaksudkan agar tidak terjadi komplikasipendarahan saluran cerna atau perforasi usus.1 beberapa peneliti mengatakan pemberikan nasi dengan lauk pauk rendah selulosa (hindari makanan berserat) dapat diberikan secara aman pada pasien demam tifoid.1 dan cairan dan elektrolit perlu dimonitor setiap harinya.PEMBERIAN ANTIMIKROBA
Obat antimikroba yang sering digunakan untuk mengobati demam tifoid adalah :1
1. kloramfenikol
dosis 4 x 500 mg per hari dapat diberikan secara oral atau intravena. Diberikan samapai dengan 7 hari bebas panas.12. tiamfenikol
hampir sama dengan kloramfenikol, akan tetapi komplikasi hematologi seperti kemungkinan terjadi anemia aplastik lebih rendah dibanding denga kloramfenikol. Dosis 4 x 500 mg
3. ampisilin dan amoksisilin
4. kotrimoksazol
dosis untuk orang dewasa 2 x 2 tablet (1 tablet mengandung sulfametoksazol 400mg dan 80mg trimetropim) selama 2 minggu.1, 145. sefalosporin generasi ke- 3
yang terbukti efektif untuk demam tifoid pada golongan sefalosporin generasi 3 adalah ceftriaxone 3-4 gram dalam dextrosa 100 cc diberikan selama jam per infus sekali sehari diberikan selama 3 hingga 5 hari.16. golongan fluorokuinolon
1. norfloksasin dosis 2 x 400 mg/hari selama 14 hari
2. siprofloksasin dosis 2 x 500mg/hari selama 6 hari
3. ofloksasin dosis 2 x 400mg/hari selama 7 hari
4. pefloksasin dosis 400mg/hari selama 7 hari
5. fleroksasin dosis 400 mg/hari selama 7 hari
kombinasi obat antimikroba
kombinasi 2 antibiotik atau lebih diindikasikan hanya pada keadaan tertentu saja antara lain toksik tifoid,15 peritonitis atau perforasi, septik syok, dimana pernah terbukti ditemukan 2 macam organisme dalam kultur darah selain kuman Salmonella.Kortikosteroid
Penggunaan steroid hanya diindikasikan pada toksik tifoid atau demam tifoid yang mengalami syok septik. Dosis 3x5 mg.15
Pengobatan demam tifoid pada wanita hamil
Kloramfenikol tidak dianjurkan pada trimester ke-3 kehamilan karen dikhawatirkan dapat terjadi partus prematur, kematian fetus intrauterin, dan grey sindrome pada neonatus. Tiamfenikol tidak dianjurkan digunakan pada trimester pertama karena kemungkinan teratogenik. Obat yang dianjurkan adalah ampisilin, amoksilin, dan seftriason.Komplikasi
Komplikasi demam tifoid dapat dibagi atas dua bagian, yaitu :
Komplikasi Intestinala. Perdarahan Usus
Sekitar 25% penderita demam tifoid dapat mengalami perdarahan minor yang tidak
membutuhkan tranfusi darah. Perdarahan hebat dapat terjadi hingga penderita
mengalami syok. Secara klinis perdarahan akut darurat bedah ditegakkan bila terdapat perdarahan sebanyak 5 ml/kgBB/jam.
b. Perforasi Usus
Terjadi pada sekitar 3% dari penderita yang dirawat. Biasanya timbul pada minggu ketiga namun dapat pula terjadi pada minggu pertama. Penderita demam tifoid dengan perforasi mengeluh nyeri perut yang hebat terutama di daerah kuadran kanan bawah yang kemudian meyebar ke seluruh perut. Tanda perforasi lainnya adalah nadi cepat, tekanan darah turun dan bahkan sampai syok.
Komplikasi Ekstraintestinal
1. Komplikasi kardiovaskuler : kegagalan sirkulasi perifer (syok, sepsis), miokarditis, trombosis dan tromboflebitis.
2. Komplikasi darah : anemia hemolitik, trombositopenia, koaguolasi intravaskuler diseminata, dan sindrom uremia hemolitik. 3. Komplikasi paru : pneumoni, empiema, dan pleuritis 4. Komplikasi hepar dan kandung kemih : hepatitis dan kolelitiasis 5. Komplikasi ginjal : glomerulonefritis, pielonefritis, dan perinefritis 6. Komplikasi tulang : osteomielitis, periostitis, spondilitis, dan artritis 7. Komplikasi neuropsikiatrik : delirium, meningismus, meningitis, polineuritis perifer, psikosis, dan sindrom katatonia.