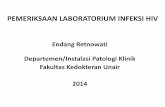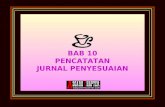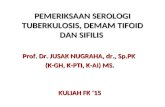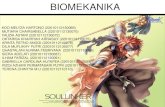Content Jurnal FK (10)
-
Upload
adib-mustofa -
Category
Documents
-
view
182 -
download
5
Transcript of Content Jurnal FK (10)

Pengaruh Diet Vegan Terhadap Insiden Terjadinya Kanker Payudara
Oleh
Loo Hariyanto Raharjo
Departemen Biokimia
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: [email protected]
I. ABSTRAK Tujuan penulisan : Untuk menambah pengetahuan mengenai peranan diet vegan didalam mengurangi resiko terjadinya kanker payudara. Metoda penulisan: melakukan suatu tinjauan pustaka dari beberapa studi yang dimuat didalam jurnal internasional mengenai peranan diet vegan didalam mengurangi resiko terjadinya kanker payudara. Pembahasan: Diet vegan menyebabkan kadar fitoestrogen dalam darah yang lebih tinggi sehingga dapat menghambat ikatan antara estrogen dengan reseptornya. Ikatan estrogen dengan reseptornya dapat meningkatkan proliferasi dari sel-sel payudara yang cenderung menimbulkan suatu keganasan. Kesimpulan : Diet vegan yang merupakan sumber fitoestrogen dapat menekan resiko terjadinya kanker payudara. Kata kunci : diet vegan, fitoestrogen, estrogen, kanker payudara.
Vegan Diet Effect Against Breast Cancer Incidence occurrence
By
Loo Hariyanto Raharjo
Biokimia Department
Lecturer Faculty of Medicine, University of Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: [email protected]
ABSTRACT Background: This article to increase knowledge about influence of vegan to reduce risk of breast cancer Method: the book observation from some international journal about role of vegan to reduce risk of breast cancer Results: vegan diet can increase blood phytoestrogen level and then inhibit estrogen-receptor bind. When estrogen binding to the receptor then increase proliferation of breast cells which tend to malignation. Conclusion: vegan is source of phytoestrogen which can reduce risk of breast cancer. Key words: vegan, phytoestrogen, estrogen, breast cancer
II. PENDAHULUAN Kanker payudara merupakan suatu penyakit keganasan yang sering terjadi pada wanita dan sering menimbulkan kematian akibat derajat keganasan yang sudah lanjut pada saat terdeteksi. Melalui karya tulis ini, kami ingin memberikan wawasan mengenai pentingnya pencegahan terjadinya kanker payudara melalui pemberian diet vegan yang pada beberapa penelitian dibuktikan mampu
menurunkan insiden kanker payudara. Selain itu pada wanita yang terdeteksi menderita kanker payudara dengan pemberian diet rendah lemak / diet vegan akan memberikan survival rate yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian diet tinggi lemak / diet omnivora (Verreault R, 1988 dan Hebert JR, 1989). Selain itu juga terdapat hubungan yang terbalik antara insiden kanker payudara dengan konsumsi serat dan makanan yang
1

kaya serat (Shanker,1991).
III. BAHAN DAN METODAPada penulisan artikel ilmiah ini kami
melakukan tinjauan pustaka yang kami kumpulkan dari beberapa jurnal ilmiah internasional yang berhubungan dengan masalah terjadinya kanker payudara, pandangan mengenai diet vegetarian menurut American Dietetic Association (ADA), serta beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan pemberian diet vegetarian untuk menekan insiden terjadinya kanker payudara.
IV. PEMBAHASANDIET VEGETARIAN
Vegetarianisme merupakan suatu pola diet yang tidak mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan, baik hewan yang ada di darat, air, maupun udara. Ada beberapa macam tipe vegetarianisme, yaitu:
1. Lacto-ovo-vegetarian: pola diet yang tidak mengkonsumsi sumber makanan hewani, tetapi masih mengkonsumsi telur, susu, serta produk olahannya.
2. Lacto-vegetarian: pola diet yang tidak mengkonsumsi sumber makanan hewani, tetapi masih mengkonsumsi susu dan produk olahannya.
3. Ovo-vegetarian: pola diet yang tidak mengkonsumsi sumber makanan hewani, tetapi masih mengkonsumsi telur dan produk olahannya.
4. Strict vegetarian (vegan): pola diet yang tidak mengkonsumsi sumber makanan hewani termasuk tidak mengkonsumsi susu, telur, serta pro-duk olahannya.
Diet vegetarian berhubungan dengan sejumlah kondisi kesehatan yang menguntungkan seperti kadar kolesterol yang rendah, resiko penyakit jantung yang rendah, resiko hipertensi dan diabetes tipe 2 yang rendah. Selain itu diet vegetarian cenderung menimbulkan Body Mass Index (BMI) yang rendah dan resiko untuk terjadinya kanker yang rendah. Diet vegetarian cenderung mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang rendah serta banyak mengandung serat, magnesium dan potassium, vitamin C dan E, folat, karotenoid, flavonoid serta fitokimia lainnya (American Dietetics Association, 2009).
Obesitas merupakan faktor yang signifikan
untuk meningkatkan resiko terjadinya kanker. Pada orang yang bervegetarian cenderung mempunyai Body Mass Index yang lebih kecil dibandingkan dengan orang yang non-vegetarian, sehingga dengan berat badan yang lebih ringan mungkin merupakan faktor yang penting untuk menurunkan insiden kanker.
Pada beberapa studi epidemiologi menunjukkan bahwa konsumsi buah dan sayuran secara teratur mempunyai korelasi yang signifikan terhadap penurunan resiko terjadinya beberapa kanker.
Buah dan sayuran mengandung beraneka ragam fitokimia yang kompleks, yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan yang poten, antiproliferatif, serta aktivitas protektif terhadap kanker. Fitokimia-fitokimia inilah yang berpengaruh terhadap proses beberapa sel yang mengalami keganasan sehingga dapat ditekan progresivitasnya. Mekanismenya meliputi inhibisi terhadap proliferasi sel, inhibisi terhadap pembentukan DNA-adduct, inhibisi terhadap signal transduction pathways dan ekspresi onkogen, induksi terhadap penghentian siklus sel dan apoptosis, menghambat aktivasi Nuclear Factor Kappa Beta (NFk) serta menghambat proses angiogenesis (Liu RH, 2004).
ESTROGEN DAN KANKER PAYUDARAHormon estrogen diperlukan untuk
perkembangan seksual dan fungsional organ-organ kewanitaan secara normal terutama yang berhubungan dengan kemampuan melahirkan anak seperti uterus dan ovarium. Estrogen juga berperan terhadap siklus menstruasi dari wanita, pertumbuhan payudara secara normal dan juga berperan terhadap pemeliharaan jantung dan tulang yang sehat.
Estrogen juga berpengaruh terhadap terjadinya kanker payudara yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Estrogen berperan sebagai stimulator pembelahan sel payudara.
2. Estrogen bekerja pada periode kritis (critical period) dari pertumbuhan dan perkembangan payudara.
3. Estrogen mempengaruhi kerja hormon lain yang berperan dalam pembelahan sel payudara.
4. Estrogen dapat memacu pertumbuhan tumor-tumor yang responsif terhadap estrogen.
Wanita sepanjang hidupnya selalu terpapar dengan estrogen sehingga wanita ini
2

mempunyai kemungkinan lebih besar untuk terjadinya kanker payudara.Gaya hidup dapat berpengaruh terhadap kadar estrogen didalam tubuh melalui beberapa hal, yaitu:1. Diet: makanan yang dikonsumsi oleh seorang wanita dapat mempengaruhi kadar estrogen dalam tubuhnya. Pemberian diet yang rendah lemak dan tinggi serat dapat mengurangi kadar estrogen dalam tubuh. Sebaliknya diet yang tinggi lemak dan rendah serat dapat meningkatkan resiko kanker payudara yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan kadar estrogen dan secara tidak langsung berhubungan dengan terjadinya obesitas. Obesitas dapat meningkatkan resiko kanker payudara pada wanita post menopause.2. Diet yang mengandung fitoestrogen: fitoestrogen adalah estrogen yang ditemukan dalam makanan nabati seperti kacang kedelai, tofu, gandum,buah-buahan dan sayuran. Kata “Phyto” berasal dari bahasa latin yang berarti tumbuh-tumbuhan. Pemberian diet yang kaya fitoestrogen merupakan cara untuk mengurangi insiden kanker payudara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita yang diberikan diet tinggi fitoestrogen, termasuk vegan, dan wanita yang banyak mengkonsumsi kedelai dan produk olahannya, mempunyai resiko kanker payudara yang lebih rendah. Kebanyakan fitoestrogen tidak disimpan dalam tubuh, tetapi langsung dipecah. Fitoestrogen merupakan estrogen yang lemah, tetapi dapat mencegah ikatan antara estrogen manusia yang lebih kuat dengan reseptornya. Jika estrogen yang lemah berikatan dengan reseptor estrogen, sebagai pengganti estrogen yang kuat, maka akan mengurangi proses pembelahan sel payudara. Wanita yang diberikan diet tinggi fitoestrogen juga akan mengekskresi estrogen lebih banyak didalam urinnya, dan mempunyai kadar estrogen dalam darah lebih rendah. Beberapa studi menunjukkan bahwa wanita yang diberikan diet tinggi fitoestrogen mempunyai waktu menstruasi lebih panjang, karena itu siklus menstruasinya lebih sedikit. Semua faktor tersebut diatas dapat mengurangi resiko terjadinya kanker payudara.3. Berat badan: beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelebihan berat badan pada orang dewasa, terutama sebelum dan sesudah menopause, meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. Setelah wanita
menopause, ovarium akan menghentikan produksi estrogen dan sumber primer untuk produksi estrogen pada wanita ini berasal dari lemak tubuh. Oleh karena itu pada wanita dengan kadar lemak tubuh yang tinggi selama masa menopause diperkirakan akan mempunyai kadar estrogen dalam tubuh yang lebih besar daripada wanita yang kurus. Salah satu cara untuk mengurangi resiko terjadinya kanker payudara pada wanita adalah dengan membatasi pertambahan berat badan pada lanjut usia dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan melakukan olah raga setiap hari dengan rutin.4. Olah raga: beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita yang berolah raga secara teratur mempunyai resiko kanker payudara lebih rendah. Hal tersebut didukung beberapa data yang menunjukkan kadar estrogen dalam sirkulasi darah yang lebih rendah pada wanita yang berolah raga secara teratur. Lemak tubuh biasanya berkurang pada wanita yang berolah raga dan disertai penurunan kadar estrogen dalam tubuh.Waktu menstruasi yang lebih panjang akan menyebabkan jumlah siklus menstruasi yang lebih sedikit sepanjang hidup, akibatnya paparan estrogen pada tubuh juga lebih sedikit sepanjang hidupnya.5. Alkohol: beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum alkohol dapat meningkatkan resiko kanker payudara dan peningkatan resiko ini juga berkaitan dengan jumlah alkohol yang dikonsumsi.6. Pil kontrasepsi: terdapat perdebatan mengenai efek pemakaian pil kontrasepsi terhadap timbulnya kanker payudara. Hal ini dipengaruhi oleh kadar estrogen yang terdapat dalam pil kontrasepsi, lamanya pemakaian, dan usia wanita mulai pakai pil kontrasepsi.7. Terapi hormon pada wanita post menopause (terapi sulih hormon): sesudah memopause, ovarium tidak memproduksi estrogen lagi. Hilangnya produksi estrogen ini berhubungan dengan resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah, osteoporosis dan sejumlah keadaan tidak nyaman yang bersifat temporer yang berhubungan dengan menopause.Untuk mengatasi hal tersebut maka diberikan terapi dengan estrogen. Terapi hormon dengan hanya memberikan estrogen saja dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker uterus, maka perlu ditambahkan hormon progesteron untuk menekan terjadinya hal tersebut. Terapi
3

hormon estrogen saja diberikan pada wanita yang mengalami histerektomi dan tidak mempunyai rahim. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terapi hormon pada wanita post menopause dengan estrogen dan progresteron dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara.
fitoestrogenFitoestrogen adalah estrogen lemah
yang didapatkan pada tanaman. Istilah fitoestrogen berhubungan dengan beberapa kelas senyawa kimia seperti flavones, flavanones, isoflavones, coumestans, dan lignans. Senyawa-senyawa tersebut memiliki struktur yang mirip dengan estrogen endogen, tetapi memberikan efek campuran antara efek estrogenik dan efek anti-estrogenik.
Beberapa studi menunjukkan bahwa isoflavones mempunyai konsentrasi yang tinggi pada kacang kedelai dan daun semanggi merah (red clover), selanjutnya yang lebih rendah konsentrasinya yaitu flavones, kemudian coumestans. Lignan lebih banyak didapatkan pada buah-buahan dan sayuran
Fitoestrogen mempunyai afinitas terhadap reseptor estrogen 1.000 – 10.000 kali lebih kecil daripada estradiol. Fitoestrogen dapat menstimulasi sintesa sex-hormone binding globulin di dalam liver dan menimbulkan inhibisi kompetitif terhadap ikatan antara estrogen dan reseptornya, maka ia memegang peranan untuk menurunkan resiko terjadinya kanker payudara dan penyakit-penyakit hormonal lainnya. Kelompok polong-polongan banyak mengandung fitoestrogen. Fitoestrogen diekskresikan melalui urin, dimana diet vegetarian dan makrobiotik berhubungan dengan tingginya kadar lignan dalam urin.
Metabolisme fitoestrogen pada wanita premenopause juga dipengaruhi secara hormonal. Puncak dari ekskresi lignan didapatkan pada fase luteal dari siklus menstruasi dan peningkatan ekskresi juga terjadi pada awal kehamilan.
Pada percobaan yang dilakukan oleh Pamela L. Dan kawan-kawan, insiden kanker payudara pada wanita muda lebih banyak didapatkan pada kelompok wanita afro-amerika daripada kelompok wanita kulit putih atau wanita latin. Pada kelompok wanita afro-amerika ini didapatkan kadar estrogen yang diekskresikan lebih rendah, hal ini berkaitan dengan hipotesa bahwa peningkatan resiko
kanker payudara disebabkan kurangnya paparan terhadap efek antipromosi dari fitoestrogen.
Mekanisme kerja fitoestrogen untuk menurunkan resiko kanker payudara.
Beberapa percobaan in vitro menunjukkan bahwa fitoestrogen dapat menghambat aktifitas enzim pengendali proses steroidogenesis (enzim aromatase) sehingga dapat menghambat sintesa estradiol dari androgen dan estrogen sulfat. Dari semua kelompok fitoestrogen, flavones dan flavanones merupakan inhibitor potent terhadap enzim aromatase.
Isoflavones merupakan inhibitor yang lemah terhadap aktifitas aromatase pada cell-free maupun pada whole-cell preparations (Le Bail, et al. 2000; Lacey, et al. 2005). Almstrup, et al. (2002) menyatakan bahwa formononetin, biochanin A, dan ekstrak dari daun semanggi merah dapat menghambat aktivitas enzim aromatase pada dosis rendah (< 1 µM), tetapi mempunyai aktivitas estrogenik pada dosis tinggi.
Flavones mempunyai kemampuan inhibisi terhadap aromatase lebih baik daripada isoflavones, yang disebabkan karena mempunyai struktur kimia yang berbeda. Pada suatu studi mutagenesis, Kao, et.al. (1998) menyatakan apabila 4-hydroxyphenol group masuk ke cincin C2 dari isoflavones dan flavones, maka cincin A dan C dari fitoestrogen tersebut akan bereaksi mirip seperti cincin C dan D dari substrat androgen.
Isoflavones juga menghambat 17-hidroksisteroid dehidrogenase tipe-1, enzim yang merubah estrone menjadi estradiol. Pada sel granulosa dan sel kanker payudara, produksi estradiol meningkat beberapa kali lebih tinggi bila dipakai androstenedion sebagai substrat dibandingkan dengan testosteron, serta perubahan estrone menjadi estradiol lebih tinggi daripada perubahan androstenedion atau testosteron menjadi estradiol.
Fitoestrogen juga dapat meningkatkan sex-hormones binding globulin yang mengakibatkan berkurangnya kadar hormon “aktif” di dalam sirkulasi darah.
Fitoestrogen dapat berperan sebagai antioksidan sehingga dapat menghambat Reactive Oxygen Species (ROS) yang memegang peranan dalam terjadinya kanker payudara.
4

V. KESIMPULANData-data epidemiologi menunjukkan
bahwa pemberian fitoestrogen dengan konsentrasi tinggi pada masa pertumbuhan atau bahkan sejak usia dini merupakan hal yang penting untuk mencegah terjadinya resiko keganasan pada usia lanjut. Fitoestrogen merupakan senyawa kimia yang ada pada tumbuh-tumbuhan, oleh karena itu pada beberapa penelitian didapatkan bahwa pada orang yang mengkonsumsi diet vegan mempunyai resiko terjadinya kanker payudara yang lebih rendah daripada orang dengan diet omnivora.
DAFTAR PUSTAKAClark R. A., Snedeker S., Devine C., 2002. Estrogen and Breast Cancer Risk: What Factors Might Affect a Woman’s Exposure to Estrogen?. Fact sheet of the Cornell University Program on Breast Cancer and Environmental Risk Factors in New York State (BCERF);10:1-4.Hebert JR, Toporoff E., 1989. Dietary exposures and other factors of possible prognostic significance in relation to tumour size and nodal involvement in early-stage breast cancer. International Journal Epidemiology;18:518-26.Kao Y-C, Zhou C, Sherman M, Laughton CA & Chen S.1998. Molecular basis of the inhibition of human aromatase (oestrogen synthetase) by flavone and isoflavone phytoestrogens: a site directed mutagenesis study. Environmental Health Perspectives; 106: 85–92.Lacey M, Bohday J, Fonseka S, Ullah A & Whitehead SA.2005. Dose–response effects on phytoestrogens on the activity and expression of 3b-hydroxsteroid dehydrogenase and aromatase in human granulosa-luteal cells. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology; 96: 279–286.
Le Bail JC, Champavier Y, Chulia AJ & Habrioux G. 2000. Effects on phytoestrogens on
aromatase 3 and 17-hydroxysteroid dehydrogenase activities and human breast cancer cells. Life Sciences 66 1281–1291.Liu RH., 2004. Potential synergy of phytochemicals in cancer prevention: Mechanism of action. Journal Nutritional.;134(suppl):3479S-3485S.Pamela L., et.al. 1997. Urinary Phytoestrogen Levels in Young Women from a Multiethnic population. Cancer Epidemiology, Biomarkers and prevention;6 :339-45.Position of the American Dietetic Association:Vegetarian Diets. 2009. Journal of the AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION;109: 1266-82.Rice S., Whitehead S.A.,2006. Phytoestrogens and breast cancer – promoters or protectors?. Endocrine related cancer; 13: 995-1015.Shanker S., Lanza E., 1991. Dietary fiber and cancer prevention. Hematology Oncology Clinical North American; 5:25-41.Verreault R., et.al. 1988. Dietary fat in relation to prognostic indicators in breast cancer. Journal National Cancer Instute;80:819-25.
5

DIPYLIDIASIS
Bagus Uda Palgunadi
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
AbstrakDipylidiasis merupakan penyakit cacing pita pada anjing yang bersifat zoonosis dan disebabkan oleh Dipylidium caninum. Sebagai Definitif host selain anjing adalah kucing dan carnivora lain sedangkan manusia adalah occasional host. Cacing ini menular dari hewan yang terinfeksi ke manusia melalui intermediate host yaitu flea (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis dan Pulex irritans) ataupun kutu (Trichodectes canis). Kejadian dypilidiasis pada manusia sangat tergantung pada kejadian dyplidiasis pada hewan dan ada tidaknya intermediate host. Pernah ada penelitian terjadinya kasus dipylidiasis pada anjing di Indonesia walaupun belum ada penelitian mengenai kejadian dipylidiasis pada manusia di Indonesia. Potensi terjadinya penyakit ini sangat dimungkinkan mengingat anjing dan kucing adalah hewan peliharaan yang umum pada sebagian orang.
Kata kunci : Dipylidiasis, zoonosis
DIPYLIDIASIS
Bagus Uda Palgunadi
Lecturer Faculty of Medicine, University of Wijaya Kusuma Surabaya
Abstract
Dipylidiasis a tapeworm disease in dogs that are zoonotic and are caused by Dipylidium caninum. As a Definitive hosts are cats and dogs than other Carnivora, while humans are occasional hosts. This worm is transmitted from infected animals to humans through the intermediate hosts of flea (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis and Pulex irritans) or lice (Trichodectes canis). Dypilidiasis incidence in humans is highly dependent on the incident dyplidiasis on animals and whether there is an intermediate host. Been no studies of dipylidiasis cases in dogs in Indonesia, although there has been no research on the incidence dipylidiasis in humans in Indonesia. The potential occurrence of this disease is very possible considering dogs and cats are common pets in some people.
Keywords: Dipylidiasis, zoonotic
PENDAHULUAN Dipylidiasis merupakan penyakit cacing pita yang secara primer terjadi pada anjing. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis karena dapat ditularkan kepada manusia melalui hospes perantara berupa pinjal atau kutu anjing. Di Indonesia kasus dypilidiasis pada manusia belum pernah dilaporkan. Dari Laporan hasil penelitian terjadinya dipylidiasis pada anjing Bali disebutkan bahwa 18% dari anjing yang diperiksa , positif terinfeksi Dipylidium caninum ( Dharmawan NS dkk, 2003)ETIOLOGI Dipylidiasis merupakan penyakit cacing pita pada anjing yang disebabkan oleh Dipylidium caninum. Selain anjing, hospes definitif lainnya adalah kucing dan karnivora liar. Manusia terutama anak – anak dapat sebagai occasional host . Sebagai intermediate hostnya (hospes perantara) adalah flea (pinjal) anjing
(Ctenocephalides canis) , pinjal kucing (Ctenocephalides felis). Selain itu Pulex irritans dan kutu / tuma anjing (Trichodectes canis) juga diduga sebagai intermediate host. (Levine ND,1994)Morfologi dan siklus hidup :Cacing dewasa dari Dipylidium caninum yang predeleksinya pada usus halus ini panjangnya berkisar antara 15 sampai 70 cm dan mempunyai sekitar 60 sampai 175 proglottid. Scolex cacing ini berbentuk belah ketupat (rhomboidal) dan mempunyai 4 buah sucker yang menonjol dan berbentuk oval. Sucker dilengkapi dengan rostellum yang retraktil dan berbentuk kerucut serta dilengkapi dengan sekitar 30 sampai 150 kait (hook) berbentuk duri mawar yang tersusun melengkung transversal. Proglottid mature berbentuk seperti vas bunga dan Tiap segmennya mempunyai 2 perangkat alat reproduksi serta 1 lubang kelamin di tengah –tengah sisi
6

lateralnya. Proglottid gravid penuh berisi telur yang berada di dalam kapsul / selubung (kantung). Tiap kantung berisi sekitar 15 sampai 25 telur. Fenomena inilah yang disebut sebagai eggball. Tiap butir telur berdiameter sekitar 35 sampai 60 µ dan berisi oncosphere yang mempunyai 6 kait. Proglottid gravid dapat terpisah dari strobila satu demi satu atau berkelompok 2 sampai 3 segmen. Segmen – segmen tersebut dapat bergerak aktif beberapa inci per jam dan keluar melewati anus atau bersama feces.Pinjal (flea) dari anjing (Ctenocephalides canis) dan kucing ( Ctenocehalides felis) atau kutu / tuma anjing (Trichodectes canis) merupakan intermediate host ( hospes perantara ) dari Dipylidium caninum ini. Apabila telur Dipylidium caninum tertelan oleh larva dari hospes perantara, maka oncosphere akan keluar dari telur dan menembus dinding usus hospes perantara dan selanjutnya akan berkembang menjadi larva infektif yang disebut larva cysticercoid. Apabila hospes perantara yang mengandung larva cysticercoid tersebut tertelan oleh hospes definitive, maka larva cysticercoid akan menembus keluar dan masuk ke dalam usus halus hospes definitive serta tumbuh dan berkembang menjadi cacing dewasa setelah kurun waktu sekitar 20 hari. ( Soulsby,1982 ; Brown,1975)
EPIDEMIOLOGI :Dipylidiasis pada manusia umumnya dilaporkan terjadi pada anak – anak usia di bawah 8 tahun. Penularan biasanya terjadi per oral malalui makanan , minuman atau tangan yang tercemar pinjal anjing atau kucing serta kutu anjing yang mengandung cysticercoid . (Soedarto,2003). Orang yang mempunyai resiko tinggi adalah yang mempunyai hewan peliharaan anjing atau kucing yang menderita dipylidiasis. Rupanya orang – orang yang menyayangi hewan peliharaannya pasti selalu kontak dan adakalanya menciumi atau membawa hewan tersebut ke kamar tidur, sehingga ada kemungkinan terjadi infeksi dipylidiasis melalui tertelannya pinjal dari hewan tersebut. Terdapat kemungkinan lain mengenai tertelannya pinjal tersebut yaitu melalui tangan yang tercemar pinjal ke mulut.Penyebaran penyakit ini pada hewan maupun manusia sangat tergantung pada ada atau tidaknya hospes perantara karena
perkembangan telur Dipylidium caninum untuk menjadi larva yang infektif yaitu cysticercoid harus di dalam tubuh hospes perantara yaitu pinjal atau kutu anjing. PATOGENESIS DAN GEJALA KLINIS :Pada anjing atau kucing yang terinfeksi ringan tidak terlihat gejala yang jelas, hanya tampak gelisah dan menggosok – gosokkan anusnya ke tanah. Pada infeksi berat terlihat diare , konstipasi dan obstruksi usus. (Soulsby, 1982)Infeksi pada manusia umumnya sangat ringan , kadang – kadang terjadi nyeri epigastrium, diare atau reaksi alergi disertai penurunan berat badan ( Soedarto,2008)
DIAGNOSA:Berdasarkan anamnesa yaitu perilaku keeratan hubungan dengan anjing atau kucing peliharaannya dan status kesehatan anjing atau kucing peliharaannya serta gejala klinis yang tampak dapat diprediksi kemungkinan menderita dipylidiasis. Pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan untuk kepastian diagnosa dengan cara memeriksa adanya telur dalam feces atau adanya segmen proglottid yang keluar bersama feces. Kadang – kadang ditemukan sejumlah eggball pada perianal penderita.
PENGOBATAN : Anthelmintik yang dapat digunakan untuk dipylidiasis adalah praziquantel 600 mg dosis tunggal, niclosamide (Yomesan) dosis tunggal 2 gr untuk dewasa atau 1,5 gr untuk anak dengan berat badan lebih dari 34 kg atau 1 gr untuk anak dengan berat badan 11-34 kg. Selain itu Quinakrin (atabrin) dapat juga digunakan. ( Natadisastra D & Agoes R, 2009; Markell EK, et al, 1992)Pada anjing dan kucing anthelmimtik yang digunakan adalah arecoline hydrobromide, arecolineacetasol, Bithional, Niclosamide atau Praziquantel (Soulsby EJL,1982)
PENCEGAHANPenularan dan infeksi dapat dicegah dengan cara menghindari kontak antara anak – anak dengan anjing atau kucing. Anjing atau kucing penderita dipylidiasis harus diobati. Selain itu perlu dilakukan pemberantasan pinjal atau kutu dengan insektisida ( Soedarto,2007)
KESIMPULAN DAN SARANMengingat bahwa anjing dan kucing merupakan hewan peliharaan yang semakin
7

banyak diminati , maka perlu diwaspadai adanya kemungkinan penularan dipylidiasis dari hewan peliharaan kepada manusia.Sebelum memelihara anjing ataupun kucing, perlu memilih dengan seksama dan memperhatikan status kesehatannya misalnya telah divaksinasi, bebas penyakit baik yang zoonosis maupun yang bukan zoonosis.Selama pemeliharaan hendaknya selalu menjaga kesehatan anjing atau kucing peliharaannya dengan secara teratur memeriksakan kepada dokter hewan untuk diberikan anthelmintik.Menjaga kebersihan lingkungan ataupun kandang hewan peliharaan dengan penyemprotan insektisida untuk memberantas pinjal dan kutu juga perlu dilakukan untuk mencegah reinfeksi.
DAFTAR PUSTAKABROWN HW, 1975. Basic Clinical Parasitology.4thEd.Appleton Century Crofts. 185-187.DHARMAWAN NS. SURATMA NA, DAMRIYASA M, MERDANA IM.2003. Infeksi Cacing Pita pada Anjing Bali dan Gambaran Morfologinya.Jvet.Vol 4(1).LEVINE ND.1994. Buku Pelajaran Parasitologi Veteriner. Gajah Mada University Press.163-164,480.MARKELL EK, VOGE M, JOHN DT. 1992.Medical Parasitology.7thEd.WB Saunders Company.254-255.NATADISASTRA D, AGOES R. 2009.Parasitologi Kedokteran : Ditinjau dari Organ Tubuh yang Diserang. EGC.122-123.SOEDARTO.2003.Zoonosis Kedokteran.Airlangga University Press.67.SOEDARTO.2007.Sinopsis Kedokteran Tropis.Airlangga University Press.75-76.SOEDARTO.2008.Parasitologi Klinik.Airlangga University Press.37-39.SOULSBY EJL.1982.Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7thEd.Bailliere Tindal London. 105.
8

TERAPI TERKINI UNTUK KANKER OVARIUM
Oleh
Harry Kurniawan Gondo
Program Pendidik Dokter Specialis (PPDS) 1 Obstetri & Ginekologi
Fakultas Kedokteran Udayana – RS Sanglah
Denpasar – Bali
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
AbstrakWalaupun penyakit tumor ovarium biasanya menunjukkan gejala yang serupa, diagnosis awal kanker ovarium lebih menekankan pada penemuan secara klinis bukan pada metode ilmiah yang canggih. Begitu terjadi pembesaran, ada kompresi yang progresif pada struktur pelvik disekitarnya, yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada abdomen, dispepsia, peningkatan frekuensi buang air kecil, dan tekanan dalam pelvik. Variabel yang paling penting yang mempengaruhi terapi dan prognosis pada kasus kanker ovarium adalah stadium atau luasnya penyakit. Sistem staging yang dipakai adalah memungkinkan perbandingan hasil terapi diantara pada masing – masing institusi berbeda, oleh karena itu terapi kanker ovarium sebaiknya dilakukan berdasarkan stadium. Survival tergantung pada stadium lesi, grade diferensiasi lesi, temuan gross makroskopik saat operasi, jumlah tumor residu setelah operasi dan terapi tambahan setelah operasi. Pada banyak institusi, pilihan terapi untuk kanker ovarium adalah total abdominal hysterectomy dan bilateral salpingo-oophorectomy (TAH-BSO), omentektomi dan pemberian kemoterapi intraabdominal (32P). Pusat penelitian lain memilih irradiasi pelvik dan abdominal sebagai terapi pasca operasi. Institusi lain menunjukkan kesuksesan dengan kombinasi irradiasi pelvik dan kemoterapi sistemik. Secara umum radioisotope dan terapi iiradiasi bukanlah terapi lini pertama untuk karsinoma ovarium. Biasanya dilakukan operasi dan kemudian diikuti dengan kemoterapi, biasanya terapi kombinasi yang berbasis Platinum.
THE LATEST THERAPY FOR OVARIAN CANCER
By
Harry Kurniawan Gondo
Physician Educator Program Specialist (PPDS) 1 Obstetrics & Gynecology
Faculty of Medicine Udayana - Sanglah
Denpasar - Bali
Lecturer Faculty of Medicine, University of Wijaya Kusuma Surabaya
AbstractAlthough disease of ovary tumor usually show the similar symptom, diagnosed early ovary cancer more emphasizing at invention by klinis non sophisticated erudite method. That so happened magnification, there is progressive compressive at structure pelvik, causing to feel is not balmy at abdomen, dyspepsia, frequency urinate, and pressure in pelvik Variable influencing therapy and prognosis of case of ovary cancer is stadium or disease broadness. System Staging weared enable the comparison of result of therapy among institution differ, therefore therapy of ovary cancer better be done by pursuant to stadium. Survival depend on peaky stadium, peaky grade diferensiasi, macroscopic gross finding moment operate for the, amount of tumor residu after additional therapy and operation after operation A lot of institution, therapy choice for the cancer of ovary is totally abdominal hysterectomy and bilateral
salpingo-oophorectomy (TAH-BSO), omentektomy and gift of kemoterapi intraabdominal (32P). Other research center chosen the irradiasi pelvik and abdominal as therapy pasca operate for the. Other institution show the successfulness with the combination of systematical irradiasi pelvik and kemoterapi. In general radioisotope and therapy iiradiasi is not first therapy lini for the karsinoma of ovary. Usually operated and later then followed by kemoterapi, usually combination therapy being based on Platinum.
9

I. PILIHAN TERAPI PRIMER
I.1 Neoplasma Epithelial Maligna Borderline
Pada 3 dekade terakhir, ada bukti jelas yang telah menunjukkan adanya tumor ovarium epithelial yang gambaran histologi dan biologinya berada diantara tumor yang jinak dan neoplasma ovarium yang maligna. Neoplasma maligna borderline ini, yang mencakup kurang lebih 15% dari semua kanker ovarium epithelial, seringkali dimasukkan ke dalam kategori cystadenoma proliferative, tumor dengan low malignant potential. Dibandingkan dengan neoplasma ovarium epithelial yang ganas, tumor epithelial borderline cenderung lebih banyak ditemukan pada populasi yang lebih muda. Survival rate 10 tahun untuk penyakit ini mencapai kurang lebih 95%. Namun, rekurensi simtomatis dan kematian mungkin terjadi dalam waktu 20 tahun setelah terapi
Pada beberapa pasien, neoplasma ini lebih tepat disebut dengan low malignant potential. Berdasarkan sifatnya yang paling jinak, banyak ahli ginekologi memberikan terapi konservatif, terutama pada pasien yang masih ingin memiliki keturunan dan memiliki penyakit stadium Ia. Mayoritas pasien dengan borderline serous tumor memiliki tumor stadium I (70%-85%). Sekitar 30% pasien memiliki tumor diluar ovarium (bukan berasal dari ovarium, extra-ovarian) pada saat diagnsosis, dengan jumlah pasien yang memiliki tumor stadium II dan III, hampir sama. Sebagian besar kematian akibat tumor terjadi pada pasien dengan neoplasma stadium II atau III, namun ada beberapa perbedaan yang penting dari adenocarcinoma ovarium. Lebih dari 50% pasien dengan tumor ekstra-ovarium bertahan walaupun reseksi tidak komplit.
Perjalanan penyakit tumor yang panjang menyebabkan follow up yang panjang, merupakan komponen penting dari penyelidikan ilmiah. Waktu survival yang panjang dan penyembuhan yang jelas pada pasien dengan advanced-stage proliferating serous tumor masih belum jelas dan mengarah pada spekulasi bahwa beberapa pasien memiliki proliferasi multifocal pada epitel selomik yang melibatkan pada satu atau dua ovarium dan lokasi ekstra-ovarium, termasuk beberapa lokasi yang tidak biasa, seperti dalam
pelvik dan limfonodi abdominal. Baik bukti klinis dan patologis tersedia untuk mendukung hipotesis bahwa tumor ekstra-ovarium, setidaknya pada beberapa pasien, mewakili proliferasi multifocal bukannya implantasi atau metastasis.
Terapi operasi standar yang ada saat ini adalah Total Abdominal Hysterectomy dan Bilateral Salpingo-Oophorectomy (TAH-BSO). Banyak ahli percaya bahwa terapi ajuvan belum terjamin tanpa memperhatikan stadium penyakit karena neoplasma ekstra-ovarium apapun harus dilihat sebagai multifocal dan insitu, bukan metastasis. Isu ini jelas memerlukan studi lebih lanjut yang mencakup evaluasi yang teliti dalam grading deposit tumor ekstra-ovarium, dan juga pada neoplasma ovarium, dan hubungan antara munculnya dan hasil akhirnya.
Lesi berulang mungkin terjadi setelah interval laten kurang lebih 20-50 tahun. Setelah follow-up yang panjang, kurang lebih 25% pasien yang diteliti meninggal. Rekurensi biasanya memiliki gambaran histologi yang serupa dengan tumor primer, yang menunjukkan bahwa sel-sel tumor borderline tidak mengalami anaplasia progresif dengan berjalannya waktu. Metastase ke limfonodi terkadang muncul, namun metastase hematogenus dan perluasan keluar rongga peritoneal jarang ditemukan.
Terapi tumor stadium III masih belum ditentukan. Banyak dokter yang percaya bahwa terapi radiasi atau kemoterapi efektif terhadap populasi slow-dividing cell ini. Tidak ada studi prospektif atau yang terkontrol dengan baik terhadap penyakit stadium lanjut yang telah dilakukan, walaupun ada banyak laporan tentang respon penyakit terhadap kemoterapi. Fort, melaporkan pengalaman dari Memorial Sloan-Kettering Cancer Center dengan tumor ovarium epithelial dengan low malignant potential diterapi dengan kemoterapi. Studi ini mencakup 29 pasien dengan penyakit stadium I, 5 pasien stadium II, 11 pasien stadium III, dan 1 pasien stadium IV. Sembilan belas pasien memiliki residu penyakit setelah operasi. Kesembilan belas pasien tersebut mendapat kemoterapi ajuvan, terapi radiasi atau kombinasi. Dua belas pasien dengan penyakit residu ditemukan bebas penyakit pada penilaian operasi kedua setelah terapi ajuvan. Review ini mengindikasikan bahwa terapi ajuvan mengeradikasi penyakit
10

residu pada beberapa pasien dengan tumor ovarium epithelial dengan low malignant potential. Ditemukan operasi eksisi pada tumor merupakan terapi yang paling efektif dan dari eksplorasi berulang ditemukan bahwa kemoterapi diberikan pada pasien dengan ascites atau yang gambaran histologis tumornya berubah atau menunjukkan pertumbuhan yang cepat.
I.2 Terapi neoplasma epithelial malignaKanker epithelial pada ovarium yang
paling sering terjadi dikategorikan secara histologi menjadi serous, musinus, endometrioid, dan tipe clear cell (mesonephroid). Walaupun ada beberapa kontroversi di masa lalu, dimana sekarang varietas histologi yang berbeda ini bersifat serupa baik dalam stadium maupun grade. Beberapa tipe, seperti musinus dan endometrioid, lebih sering ditemukan pada stadium awal.
Satu teori pertumbuhan kanker epithelial ovarium menunjukkan bahwa penyakit ini awalnya tumbuh lokal, dan menginvasi kapsul dan mesovarium, dan kemudian menginvasi organ disekitarnya dan menyebar melalui aliran limfa. Pada saat neoplasma maligna mencapai permukaan eksternal kapsul, sel-sel mengalami eksfoliasi ke rongga peritoneal, dimana sel ini bebas untuk bersirkulasi dan kemudian berimplantasi. Metastasis limfatik local dan regional mungkin melibatkan uterus, tuba fallopii, dan limfonodi pelvik. Keterlibatan limfonofi para-aortik pada ligament infundibulopelvik juga sering terjadi.
Woodruff, menyebutkan mekanisme lain penyebaran penyakit yang mungkin terjadi pada kanker epithelial ovarium, bahwa seluruh epitel selomik dapat menimbulkan lesi ini dibawah pengaruh agen karsinogenik yang mungkin memiliki akses ke rongga peritoneal dari vagina melalui tuba fallopii. Bahkan lesi mungkin berasal dari distribusi multifocal, dengan banyaknya porsi epitel selomik. Teori ini menjelaskan observasi penyakit stadium lanjut pada pasien yang diperiksa dengan teliti dalam waktu tidak lama sebelumnya dan bebas dari penyakit tanpa massa pelvik yang teraba.
Stadium Ia, Ib, dan IcTerapi yang terbaik untuk lesi stadium
I adalah total abdominal hysterectomy dan bilateral salpingo-oophorectomy (TAH-BSO)
dengan staging operasi yang akurat. Pada banyak institusi, omentectomy adalah bagian dari staging untuk lesi stadium I. Omentum adalah organ yang tampaknya menarik sel-sel tumor (absorsi) dan menunjukkan penyakit mikroskopik pada pasien dengan lesi stadium I yang jelas. Nilai omentektomi sebagai modalitas terapi untuk lesi stadium I masih belum ditegakkan.
Limfonodi pelvik dan peraaortik mungkin terlibat dalam 10-20% penyakit stadium I, dan limfadenektomi diperkirakan merupakan prosedur diagnostik dan terapeutik yang penting. Burghardt dkk, menyebutkan tentang 23 pasien dengan kanker epithelial ovarium stadium I, dimana semua menjalani limfadenektomi komplit, dan 7 pasien menunjukkan keterlibatan limfonodi (30%).
Buchsbaum dkk, melaporkan insiden keterlibatan limfonodi pelvik yang lebih rendah dari studi the Large Gynecologic Oncology Group (GOG) (0% untuk stadium I, 19,5% untuk stadium II, dan 11,1% untuk stadium III). Studi GOG hanya memasukkan pasien dengan lesi metastase dengan diameter < 3 cm. Burghardt dkk, melaporkan sejumlah pasien dengan semua ukuran lesi yang menjalani limfadenektomi pelvik dan peraaortik komplit, dan keterlibatan limfonodi pelviknya diketahui lebih tinggi (15% untuk stadium I, 57% untuk stadium II, and 64% untuk stadium III).
Baiocchi dkk, mereview pengalaman mereka pada 242 wanita yang menjalani limfadenektomi pelvik dan paraaortik yang lesi kankernya ditemukan hanya pada ovarium (stadium I). Metastasis nodal ditemukan pada 32 pasien (13,2%). Adenokarsinoma serous memiliki insiden metastasis ke limfonodi yang tertinggi (27 dari 106, 25,4%). Mereka dengan lesi grade 3 mengalami 38,5% metastasis (15 dari 39) dibandingkan dengan 5,8% (9 dari 155) lesi grade 1 dan 2. Ada 33 wanita dengan tumor low malignant potential dan 7 diantaranya (21%) mengalami metastasis nodal. Bila hanya satu dari tiga limfonodi yang terlibat, metastasis biasanya terjadi ipsilateral, namun pasien ini juga mengalami metastasis ke limfonodi illiaka komunis atau paraaorta. Limfonodi paraaorta terlibat tanpa ada metastase pelvik. Keterlibatan limfonodi pelvik bilateral terutama ditemukan bila limfonodi multiple mengalami metastasis. Pada analisis multivariate, stadium, tipe histologi dan grade bukan merupakan alat
11

prediktif survival. Creasman dkk, mendeskripsikan
empat pasien dengan kanker ovarium yang setelah kemoterapi atau imunokemoterapi kombinasi, ditemukan mengalami penyakit retroperitoneal pada saat laparotomi eksploratif kedua, walaupun tidak ada bukti adanya residu kanker intraabdominal. Kanker ovarium dapat bermetastase ke limfonodi pelvik dan paraaorta, sehingga area ini harus dievaluasi untuk penilaian yang lebih teliti untuk mencari luasnya penyakit pasien kanker ovarium. Tanpa operasi staging yang menyeluruh, metastasis tersembunyi mungkin terjadi dan tidak disadari.
Penggunaan terapi ajuvan dan peranannya pada kanker ovarium stadium I masih terus diteliti. Dalam sebuah studi retrospektif dari Inggris. Ahmed dkk, mereview sebuah kasus pada 194 pasien dengan panyakit stadium I, dimana 103 pasien diperkirakan di staging dengan “baik” (low malignant potential dieksklusi). Tidak satupun dari pasien tersebut mendapat terapi pasca operasi. Ada banyak faktor yang dievaluasi sehubungan dengan prognosis, dan dalam analisis multivariate, hanya grade (grade 1 atau grade 2 hingga grade 3), adanya asites dan tumor permukaan ovarium yang bermakna untuk relaps namun tidak memiliki dampak pada survival. Angka relaps penyakit ini adalah 6,5%, 24,7%, dan 38,1% untuk stadium Ia, Ib, dan stadium Ic. Pasien yang megalami relaps diterapi secara eksklusif dengan Carboplatin atau Cisplatin dengan angka respon 44%.
Beberapa institusi memilih memberikan kemoterapi sebagai terapi pasca operasi untuk stadium Ib dan Ic dan untuk tipe histologi undifferentiated. Pada era terakhir, ajuvan terapi yang dipilih biasanya analog Platinum atau dalam kombinasi dengan agen Alkylating atau Paclitaxel (Taxol). Pada penanganan lesi grade rendah (grade 1). Dokter harus memperhitungkan kemungkinan manfaat kemoterapi ajuvan dibandingkan dengan resikonya, tidak direkomendasikan pemberian kemoterapi ajuvan pada pasien stadium Ia, Ib, lesi grade 1 dan 2. Pasien stadium I, lesi grade 3 adalah masalah yang sulit diputuskan. Insiden rekurensi pada grup ini mencapai 50%, pada kasus dalam grup ini harus diberi kemoterapi ajuvan multiagen walaupun tidak ada data jelas yang menunjukkan hasil yang superior
dibandingkan dengan terapi agen tunggal. Terapi ajuvan yang paling sesuai untuk
pasien dengan lesi stadium I dimana telah dilakukan total abdominal hysterectomy dan bilateral salpingo-oophorectomy (TAH-BSO) masih kontroversi. Beberapa peneliti menyebutkan tidak perlu pemberian terapi ajuvan. Sedangkan yang lain mengusulkan irradiasi seluruh abdomen dengan atau tanpa kemoterapi, tetapi dapat dipilih kemoterapi multiagen yang berbasis Platinum untuk grup pasien resiko tinggi ini.
Studi oleh the GOG dan The Ovarian Cancer Study Group telah melaporkan bahwa pasien stadium Ia dan Ib dan grade penyakit 1 atau grade 2 diacak untuk mendapat Melphalan (0,2 mg/m2/hari per oral selama 5 hari) selama 12 siklus dan mereka yang tidak mendapat terapi lanjutan. Survival 5 tahun pada kedua kelompok studi sangat baik (>90%). Dengan mempertimbangkan toksisitas, biaya, ketidaknyamanan pasien, dan resiko neoplasma maligna sekunder yang diasosiasikan dengan terapi agen Alkylating , maka menentukan pasien yang tidak memerlukan terapi tambahan perlu dipertimbangkan. Uji GOG Ovarian Cancer Study Group lainnya memasukkan semua pasien yang memiliki penyakit stadium Ic tanpa residu mikroskopik, pasien stadium Ia dan stadium Ib dengan ruptur kapsul, pasien yang mengalami lesi stadium Ia dan Ib grade 3, dan pasien yang memiliki penyakit stadium II yang tidak menunjukkan bukti adanya residu makroskopik. Pasien tersebut dikelompokkan secara acak untuk mendapat melphalan atau 15 mCi koloid 32P intraperitoneal. Survival dan disease free survival pada kedua kelompok serupa (kurang lebih 80%). Frekuensi efek samping berat adalah rendah pada kedua kelompok. Namun, 32P diasosiasikan dengan efek samping yang lebih sedikit daripada Melphalan, dan hanya 25% pasien yang diterapi dengan 32P mengalami toksisitas. Pada follow-up, GOG mempelajari populasi stadium awal yang beresiko tinggi yang sama dan membandingkan kombinasi kemoterapi Siklofosfamid plus Cisplatin, dengan koloid 32P intraperitoneal. Angka kematian pasien yang diterapi dengan kemoterapi 17% lebih rendah daripada koloid radioaktif. Saat ini tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam survival, namun angka rekurensi yang lebih rendah pada kelompok yang mendapat kemoterapi dan angka
12

komplikasi yang lebih tinggi pada kelompok koloid 32P mengarah pada kesimpulan bahwa kemoterapi yang berbasis Platinum lebih dianjurkan.
Sebuah studi terhadap 271 pasien kanker ovarium stadium I oleh The Intalian Gynecologic Group dikelompokkan menjadi 2 uji. Pasien dimasukkan menjadi kelompok stadium Ia dan Ib, grade 2 atau grade 3, kemudian diacak untuk mendapat Cisplatin (6 seri) dan kelompok yang tidak mendapat terapi. Angka relaps berkurang secara signifikan pada kelompok Cisplatin, namun angka survival pada kedua kelompok tidak berbeda secara bermakna (88% pada kelompok cisplatin vs 82% pada kelompok tanpa terapi) pada median 76 bulan follow-up). Pada pasien yang dikelompokkan kedalam kelompok stadium Ia2, stadium Ib2, dan stadium Ic, diacak untuk mendapat Cisplatin dan 32P (intraperitoneal). Angka relaps pada kelompok cisplatin lebih rendah, namun secara keseluruhan survival 5-tahun kedua kelompok serupa.
The European Gynecologic Group melaporkan suatu analisis kombinasi uji ICON 1 dan ACTION. Lebih dari 900 pasien dengan kanker ovarium stadium awal yang mendapat baik kemoterapi ajuvan berbasis platinum atau observasi hingga kemoterapi diindikasi. Setelah median follow-up lebih dari 4 tahun, keseluruhan survival pada saat 5 tahun adalah 82% untuk pasien dengan kemoterapi primer dan 74% pada pasien kelompok observasi. Disease-free survival pada 5 tahun adalah 76% versus 65%. Disimpulkan bahwa recurrence-free survival dan keseluruhan survival pada 5 tahun meningkat pada kemoterapi yang berbasis Platinum. Pada uji European Organization for Research and Treatment Group of Cancer (EORTC)-ACTION lain terhadap 448 pasien, mereka menemukan bahwa manfaat kemoterapi terbatas pada pasien yang kurang mendapat operasi staging yang komprehensif, sehingga memunculkan perlunya terapi ajuvan pada pasien dengan karsinoma ovarium stadium awal yang distaging dengan baik.
Karena protokol terapi untuk penyakit stadium lanjut telah menunjukkan peningkatan survival dengan menggantikan Siklofosfamid dengan Paclitaxel, GOG mengevaluasi Carboplatin (AUC 7,5) dan Paclitaxel (175 mg/m2) pada penyakit stadium awal resiko tinggi. Uji ini membandingkan 3 siklus
kemoterapi dengan kemoterapi 6 siklus. Setelah lebih dari 3 tahun interval, 457 pasien direkrut dan dievaluasi setelah median follow-up 6,8 tahun. Sementara angka rekurensi pada kelompok 6 siklus 24% lebih rendah (P=0,18), keseluruhan angka kematian pada kedua kelompok serupa (hazard ratio 1,02). Studi ini menyimpulkan bahwa tambahan 3 siklus menyebabkan peningkatan toksisitas (11% neurotoksisitas grade 3 dan atau 4 versus 2% pada kelompok 3 siklus) tanpa hasil akhir yang terlalu bermakna.
Pada wanita muda dengan penyakit stadium Ia yang menginginkan memiliki keturunan dikemudian hari, unilateral salpingo-oophorectomy (USO) diasosiasikan dengan peningkatan resiko rekurensi minimal, dan menyediakan prosedur staging yang teliti dan berdasarkan pertimbangan untuk melakukan grading dan self-containment neoplasma yang ada.
Stadium IIa, IIb, dan IIcPada banyak institusi, pilihan terapi
untuk penyakit stadium IIa dan IIb adalah total abdominal hysterectomy dan bilateral salpingo-oophorectomy (TAH-BSO), omentectomy dan pemberian 32P. Pusat penelitian lain memilih irradiasi pelvik danabdominal sebagai terapi pasca operasi. Institusi lain menunjukkan kesuksesan dengan kombinasi irradiasi pelvik dan kemoterapi sistemik. Secara umum radioisotope dan terapi iiradiasi bukanlah terapi lini pertama untuk karsinoma ovarium. Biasanya dilakukan operasi dan kemudian diikuti dengan kemoterapi, biasanya terapi kombinasi yang berbasis Platinum. Sedangkan pada penyakit stadium I nilai omentektomi masih belum jelas. Namun, banyak pihak yang setuju bahwa pada semua stadium omentektomi bertindak sebagai alat diagnostik yang berharga. Operasi staging yang baik sangat penting artinya bagi kesuksesan rencana terapi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pasien dengan penyakit stadium II diterapi dengan cara yang serupa dengan penyakit stadium III yang optimal debulked.
Stadium IIISetiap usaha harus dilakukan untuk
membuat operasi usus mayor untuk mengeluarkan massa tumor (bulk) termasuk omentum yang cukup luas setelah dilakukan TAH-BSO. Studi retrospektif menyebutkan
13

bahwa angka survival pasien dengan penyakit stadium III berhubungan dengan jumlah residu tumor pasca operasi, dimana pasien dengan residu tumor yang lebih sedikit memiliki prognosis yang lebih baik dengan terapi ajuvan. Pasien dengan penyakit stadium III harus diterapi dengan kemoterapi. Sebagian besar pusat kanker kini memilih kemoterapi agen multiple yang berbasis Platinum seperti Carboplatin dan Paclitaxel, karena grup pasien ini memiliki angka respon yang baik.
Durasi terapi agen multiple biasanya 6-8 siklus. Bila pasien selamat selama periode waktu ini dan tidak menunjukkan bukti klinis adanya penyakit, biasanya dipertimbangkan untuk melakukan prosedur operasi kedua. Namun kemudian hal ini mengalami transisi dimana banyak peneliti tidak menganjurkan untuk melakukan laparotomi kedua kecuali pasien masuk dalam suatu studi. Saat ini, analisis sekunder terhadap studi GOG #158 menunjukkan tidak ada manfaat pada hasil akhir dengan melakukan operasi kedua. Namun, laparotomi kedua merupakan suatu alat diagnostik sehingga mungkin bermanfaat bagi pasien yang sebelumnya belum mendapat intervensi pembedahan yang adekuat.
Sebelumnya ada laporan bukti yang menunjukkan bahwa grup optimal (pasien dengan diameter residu yang kurang dari 1-2 cm), angka survival dan respon terhadap kemoterapi setara dengan irradiasi abdominal dan pelvik. Namun, morbiditas jangka panjang pada terapi irraadiasi lebih besar dan faktor ini mempengaruhi terapi pasca operasi untuk penyakit stadium III sehingga sebagian besar pusat memberikan kemoterapi agen multiple sebagai terapi primer bukan terapi irradiasi. Studi prospektif awal pada beberapa grup pasien yang diacak untuk mendapat kemoterapi agen tunggal dan mereka yang mendapat agen multipel, dan sebagian besar menyimpulkan (sehubungan dengan respon tumor) bahwa polikemoterapi memiliki keuntungan yang bermakna dibandingkan dengan regimen tunggal pada penyakit stadium lanjut, non-optimally debulked. Isu ini sangat penting karena morbiditas pada polikemoterapi lebih besar daripada regimen tunggal aen Alkylating.
Stadium IVPenanganan ideal untuk stadium IV
adalah mengeluarkan sebanyak mungkin kanker dan memberikan kemoterapi setelah
operasi. Keseluruhan survival pada stadium ini lebih rendah daripada pasien stadium lain. II. USAHA OPERASI MAKSIMAL
Ada axiom diantara banyak ahli ginekologi onkologi bahwa adalah bijaksana untuk mengeksisi sebanyak mungkin tumor yang dapat dieksisi bila ditemukan penyebaran penyakit pada saat operasi primer untuk kanker ovarium. Telah diketahui bahwa terapi yang bermakna dapat dicapai dengan reduksi atau mengurangi beban tumor yang berat.
Munnell, melaporkan angka survival 5 tahun sebesar 28% pada pasien yang menjalani “usaha operasi maksimal” dibandingkan dengan angka survival 5 tahun sebesar 9% pada pasien yang menjalani reseksi parsial dan 3% pada pasien yang hanya menjalani biopsy. Pada 14 pasien yang bertahan pada Munnell’s, usaha operasi maksimal yang terdiri dari histerektomi, bilateral salpingo-oophorectomy, dan omentectomy (TAH-BSO Omentektoy)
Aure dkk, menunjukkan peningkatan survival yang signifikan diantara pasien penyakit stadium III yang semua tumornya diangkat. Hasil yang serupa diperoleh oleh Griffiths dkk, yang menggunakan multiple linear regression equation dengan survival sebagai variabel dependen untuk mengontrol terapiutik multiple dan faktor biologis yang mempengaruhi hasil akhir pasien secara simultan. Faktor yang paling penting adalah grade histologi tumor dan ukuran massa residu terbesar setelah operasi primer. Operasi sendiri tidak mempengaruhi survival kecuali mempengaruhi reduksi ukuran massa residu terbesar tumor hingga dibawah batas 1,6 cm.
Prosedur debulking saat ini mendapat perhatian lebih dalam penanganan kanker ovarium. Konsep yang ada adalah mengurangi atau menghilangkan residu tumor hingga ukuran dimana terapi ajuvan dapat bekerja secara efektif. Semua bentuk terapi ajuvan akan lebih efektif bila residu tumor yang tersisa minimal. Hal ini terutama berlaku untuk karsinoma ovarium, yang merupakan salah satu tumor solid yang sensitif terhadap kemoterapi. Sebuah operasi yang teliti dan persisten dapat mengangkat massa tumor yang besar yang pada kesan pertama tidak dapat direseksi. Dengan menggunakan area retroperitoneal yang bersih, dokter dapat mengidentifikasi ligamentum infundibulopelvik dan suplai darah ovarium. Begitu pembuluh darah ini dikenali dan ditranseksi, pengangkatan massa ovarium yang
14

besar secara retrograde menjadi lebih mudah dan lebih aman. Ureter sedapat mungkin harus dilindungi dari diseksi sehingga kemungkinan trauma struktur pelvik ini dapat diminimalisir. Area yang bersih biasanya ditemukan pada kolon transversum dimana area omentum yang besar pada kanker ovarium diangkat setelah pembuluh darah gastroepiploic kanan dan kiri diligasi.
Pengangkatan massa tumor yang besar dan omentum yang terlibat sering mereduksi beban tumor hingga 80-99%. Nilai teoretikal dari prosedur debulking ada pada reduksi jumlah sel dan keuntungan hal ini dalam terapi ajuvan. Hal ini terutama relevan pada bulky solid tumor seperti kanker ovarium, dimana pengangkatan sel dalam jumlah yang besar pada fase istirahat (G0) menggerakkan sel residu ke fase proliferatif yang lebih rentan.
Beberapa studi retrospektif menunjukkan peningkatan angka survival pada pasien yang berada dalam status beban tumor minimal melalui operasi. Laporan dari MD Anderson Hospital and Tumor Innstitute menunjukkan suatu peningkatan angka lini kedua yang signifikan pada pasien dengan kanker epithelial stadium II dan III dimana operasi awal tanpa ada residu tumor atau tidak ada residu massa tumor tunggal yang berdiameter lebih dari 1 cm. Laporan ini merefleksikan angka survival 2 tahun sebesar 70% pada pasien kanker stadium III dimana tidak ada penyakit makroskopis yang tersisa dan angka survival sebesar 50% bila nodul residu berdiameter kurang dari 1 cm. Hal ini lebih baik daripada angka survival biasa. GOG ingin meneliti lebih dalam tentang operasi sitoreduksi primer dengan analisis yanhg lebih detil mengenai hasil operasi pada pasien stadium lanjut. Pada studi awal, dibandingkan survival pasien stadium III yang memiliki penyakit abdominal ≤ 1 cm dengan pasien yang memiliki penyakit > 1 cm namun setelah sitoreduksi tumor menjadi berdiameter ≤ 1 cm. Apabila operasi merupakan satu-satunya faktor yang penting, survival mungkin akan ditemukan serupa pada kedua kelompok.
Pasien yang memiliki penyakit dengan volume lebih kecil bertahan lebih lama daripada mereka yang menjalani sitoreduksi hingga volume tumor menjadi lebih kecil, yang menunjukkan bahwa biologi tumor juga memiliki signifikansi prognosis. Pada studi kedua, GOG mengevaluasi efek diameter terbesar tumor terhadap survival pasien
dengan sitoreduksi suboptimal. Studi ini menunjukkan bahwa sitoreduksi hingga residu massa terbesar yang ada berukuran ≤ 2 cm menunjukkan hasil survival yang signifikan, namun semua residu yang berukuran > 2 cm juga memberikan survival yang ekuivalen. Sehingga kecuali massa dapat direduksi menjadi ≤ 2 cm, diameter residu tidak mempengaruhi survival. Dalam mengevaluasi sitoreduksi optimal dan suboptimal, penelitian oleh GOG menunjukkan bahwa ada tiga grup yang berbeda muncul : residu mikroskopik, residu massa < 2 cm, dan residu > 2 cm. Dari studi ini jelas diketahui bahwa pasien dengan penyakit mirkoskopik memiliki angka survival 4 tahun sebesar 60%, sedangkan pasien dengan penyakit makroskopik ≤ 2 cm memiliki angka survival 4 ahun sebesar 35%. Di sisi lain, pasien yang tumornya tidak disitoreduksi hingga ≤ 2 cm memiliki angka survival 4 tahun sebesar <20%. Namun yang lebih mengejutkan adalah kegagalan sitoreduksi tidak memiliki efek terhadap survival kecuali residu penyakit ≤ 2 cm.
Sebuah laporan pada tahun 2005 menganalisis dampak pembedahan sitoreduksi terhadap progression-freesurvival. Diadakan sebuah analisis retrospektif terhadap 889 pasien pada 1077 pasien yang direkrut dalam the Scottish Randomised Trial in Ovarian Cancer (SCOTROC-1). Analisis ini menunjukkan bahwa debulking optimal (<2 cm) lebih sering dicapai pada pasien yang berasal dari Amerika Serikat, Eropa, dan Australia daripada pasien yang direkrut dari Inggris (71% vs 58%). Progression-free survival (PFS) ditemukan lebih baik pada pasien yang menjalani debulking optimal bila penyakit mereka tidak seluas pada saat awal direkrut (P=0,003). Perbandingan antara pasien Inggris dan non-Inggris yang tidak memiliki residu penyakit yang terlihat menunjukkan survival yang lebih baik pada pasien non-Inggris, dan peneliti memperkirakan hal ini disebabkan oleh pasien non-Inggris lebih sering menjalani limfadenektomi primer.
Peranan debulking pada tumor stadium IV masih dipertanyakan. Ada 3 studi yang menyebutkan bahwa debulking optimal dapat dilakukan pada sebagian besar pasien tersebut dengan efek yang baik. Liu dkk, menyebutkan 47 pasien dengan kanker stadium IV, dimana 14 (30%) menjalani debulking optimal hingga residu <2 cm. Median survival pada pasien
15

tersebut adalah 37 bulan, dibandingkan dengan median 17 bulan pada mereka yang menjalani debulking suboptimal. Sebuah studi oleh Memorial Sloan-Kettering mengidentifikasi 92 pasien dimana debulking optimal dicapai pada 45% pasien dengan median survival 40 bulan dibandingkan dengan 18 bulan pada mereka yang mendapat debulking suboptimal.
The MD Anderson Group mendeskripsikan 100 pasien yang menjalani debulking. Mereka dengan debulking optimal memiliki median survival 25 bulan, dibandingkan dengan median survival 15 bulan pada mereka yang mendapat debulking suboptimal. Efek operasi sitoreduksi primer dapat dilihat pada persentase prosedur negative second-look. Walaupun operasi sitoreduksi primer tampaknya memiliki nilai terapeutik, namun masih ada kontroversi yang muncul. Isu utama yang belum terselesaikan disebabkan oleh adanya peningkatan beban tumor (pada kasus dimana operasi sitoreduksi memberi manfaat yang potensial) atau apakah hal ini berhubungan dengan perbedaan biologi tumor atau penurunan sensitifitas terhadap regimen kemoterapi (apabila hal tersebut yang kemungkinan menyebabkan, operasi sitoreduksi mungkin tidak memiliki dampak utama terhadap survival). Maka implikasi yang muncul adalah bahwa pasien yang memiliki penyakit yang dapat disitoreduksi adalah grup tertentu dengan prognosis baik tergantung pada faktor-faktor independen operasi sitoreduksi. Belum jelas seberapa banyak pasien dengan penyakit bulky yang dapat dengan sukses menjalani sitoreduksi massa tumor hingga kurang dari 2 cm dan pada seberapa banyak pasien operasi yang agresif ini merupakan kontraindikasi secara klinis. Dan, bila kemoterapi terlambat karena komplikasi pembedahan, akan memberikan efek yang buruk terhadap survival jangka panjang pasien.
Waktu sitoreduksi yang paling tepat masih belum ditentukan, sebelum kemoterapi atau setelah satu sampai tiga induksi kemoterapi, atau setelah selesainya siklus kemoterapi 6 hingga 12 bulan. Persentase pasien dengan kanker ovarium stadium lanjut yang dapat menjalani operasi sitoreduksi secara efektif berkisar antara 43-87%, tergantung pada laporan yang direview. Perbedaan ini mungkin merefleksikan kemampuan ahli bedah, namun hal ini lebih mungkin mewakili pola rujukan yang berbeda
dan faktor seleksi lainnya. Dalam studi The Southwest Oncology Group-GOG terhadap terapi intraperitoneal dengan terapi intravena pada kanker stadium III optimal, median survivalnya adalah 76 bulan, 42 bulan dan 32 bulan bila ditemukan residu mikroskopik saja, residu <0,5 cm, dan residu 0,5-2 cm.
Eisenkop dkk, menyebutkan 163 pasien stadium IIIc dan stadium IV. Sitoreduksi komplit berhasil dilakukan pada 86% pasien. Keseluruhan median survival adalah 54 bulan, namun didapatkan survival 64 bulan pada mereka yang tumornya menjalani debulking optimal. Peranan limfadenektomi pada pasien dengan penyakit stadium lanjut masih terus didebatkan. Semua studi menunjukkan keterlibatan limfonodi yang signifikan pada penyakit stadium lanjut (>50%).
Burghardt, ahli yang pertama menunjukkan manfaat terapeutik tindakan ini. Data yang didapatkan menunjukkan bahwa bahkan dengan limfonodi positif, pasien dengan penyakit stadium lanjut memiliki survival yang lebih baik daripada pasien yang serupa yang tidak menjalani evaluasi limfonodi. Telah disebutkan bahwa beberapa metastase pada limfonodi tidak merespon kemoterapi begitu juga dengan metastasis intraperitoneal sehingga sebaiknya limfonodi diangkat. Pernyataan yang berlawanan muncul pada kasus pasien yang mengalami kekambuhan, yang juga terjadi di intraperitoneal dan jarang hanya terjadi di rongga retroperitoneal, sehingga status limfonodi hanya memiliki sedikit dampak pada perjalanan alamiah penyakit. Dua studi dari Italia, walaupun tidak identik dalam hal desain, mengungkapkan temuan yang berbeda.
Parazzini dkk, mengevaluasi 456 wanita dengan penyakit stadium III-IV dalam sebuah uji kemoterapi randomisasi prospektif. Ada 161 pasien dengan limfonodi positif. Mereka menemukan bahwa tumor grade 3 lebih banyak menunjukkan status limfonodi positif dibandingkan dengan tumor grade 1 dan 2. Hal ini juga berlaku bagi penyakit stadium IV dibandingkan dengan stadium III. Mereka tidak menemukan perbedaan dalam hal survival antara mereka yang memiliki limfonodi positif atau negatif; apakah pengangkatan limfonodi positif dengan operasi mempengaruhi survival masih belum diketahui.
Scarabelli dkk, mengevaluasi status
16

limfonodi 98 pasien kanker stadium IIIc-IV yang tidak memiliki residu massa makroskopik setelah operasi dibandingkan dengan 44 pasien yang tidak menjalani limfadenektomi. Survival ditemukan meningkat secara signifikan pada mereka yang menjalani limfadenektomi. Studi ini menunjukkan bahwa pada sekelompok tertentu pasien, limfadenektomi memiliki efek terapeutik. Analisis uji SCOTROC-1 sebelumnya juga menunjukkan bahwa limfadenektomi mungkin memiliki manfaat terapeutik.
Dalam praktek, sebaiknya dilakukan limfadenektomi pelvik dan paraaorta secara rutin bila tumor pasien dapat didebulking secara optimal. Manfaat limfadenektomi pada pasien dengan residu bulky masih dipertanyakan. Saat ini tampaknya sesuai bila pasien dengan diagnosis kanker ovarium stadium lanjut harus menjalani reseksi semua massa yang terlihat secara teknis. Antusiasme debulking kanker ovarium mengarah pada berbagai teknik yang berkembang untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa dokter telah mengusulkan penggunaan ultrasound surgical aspirator. Yang lain mengusulkan electrosurgical debulking dengan sinar argon sebagai koabulator. Lainnya mengusulkan bahwa reseksi peritoneum atau otot diafragma mungkin berperan dalam sitoreduksi.
Ada peningkatan usaha dalam mengevaluasi pasien kanker ovarium dengan laparoskopi bukan laparotomi. Secara teknis hal ini dapat dilakukan, walaupun kebijaksanaan mengangkat massa adnexa yang besar dengan laparoskopi masih dipertanyakan. Rekurensi kanker pada lokasi insisi operasi juga pernah terjadi namun jarang walaupun ada kanker intrabdominal.
Wang dkk, mereview literature untuk menentukan faktor resiko yang mungkin berperan dalam kekambuhan dini pada lokasi kanker ginekologi, kanker ovarium adalah neoplasma maligna yang paling sering menimbulkan metastasis pada lokasi utama kanker tumbuh. Hal ini terjadi pada pasien dengan atau tanpa asites, pada pasien dengan tumor makroskopik dalam rongga abdominal, pada pasien yang menjalani prosedur diagnostik atau paliatif, dan pada penyakit stadium dini.
Metastasis pada lokasi kanker juga ditemukan pada pasien dengan tumor low malignant potential. Metastasis pada lokasi
port lebih sering ditemukan bila terjadi asites dan bila terjadi karsinomatosis intraperitoneal. Waktu terpendek munculnya metastasis lokasi kanker dengan laparoskopi adalah 8 hari. Beberapa teori mengenai mekanisme metastasis lokasi port telah disebutkan, antara lain implantasi sel kanker yang menyebar karena trauma operasi pada saat operasi pengangkatan tumor primer, implantasi langsung dengan instrument dan pembentukan perbedaan tekanan oleh pneumoperitoneum, dengan aliran keluar gas mengalirkan sel-sel tumor melalui lokasi kanker. Walaupun laparoskopi telah dilakukan dengan sukses dalam penanganan massa adnexa benigna, tetapi lebih dipilih melakukan laparotomi terbuka untuk kanker ovarium. Bila ditemukan kanker secara tidak sengaja pada saat laparoskopi, biasanya langsung dilakukan laparotomi.
Peranan prosedur second-look laparotomy masih kontroversial, walaupun lebih jarang digunakan kecuali bila pasien direkrut dalam sebuah protokol penelitian. Sebagian besar setuju bahwa tidak ada atau hanya ada sedikit dampak prosedur ini terhadap survival, walaupun status penyakit pada beebrapa titik waktu tertentu dapat dipastikan. Beberapa yang mendukung prosedur second-look laparotomy menyebutkan bahwa bahwa debulking sekunder mungkin bermanfaat dan meningkatkan survival. Setidaknya ada lima studi yang mengevaluasi peranan debulking sekunder pada pasien-pasien dengan penyakit klinis yang ada setelah kemoterapi. Dari total 193, hanya 11 (5,6%) mengalami reduksi penyakit hingga tidak ada penyakit residu dan hanya 3 (37%) yang bertahan sampai pada waktu publikasi dengan 19% dengan penyakit residu sebesar 1-2 cm dan 6% dengan penyakit residu >2 cm. ada 1207 pasien (pada semua stadium) yang diidentifikasi pada 16 artikel yang menjalani laparotomi second-look yang tidak menunjukkan gejala klinis penyakit setelah kemoterapi. Ada 600 pasien dengan penyakit makroskopik; pada 118, dilakukan debulking hingga penyakit mikroskopik, dan 31% bertahan. Bila debulking dilakukan hingga <5 mm, survival terjadi sebesar 22%; dari 420 pasien dengan penyakit residu >5 mm, hanya 14% yang bertahan. Yang menarik adalah, pada kasus debulking hingga penyakit mikroskopik, ada 31% yang bertahan dibandingkan dengan 47% pasien yang
17

memiliki penyakit mikroskopik hanya pada saat laparotomi second-look. Walaupun mungkin ada manfaat bila debulking dapat dilakukan hingga tersisa tingkat mikroskopik saja, dimana dari review sebuah pustaka hal ini dapat dicapai pada <10% pasien yang bersih dari penyakit secara klinis dan menjalani laparotomi second-look.
Grup the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) telah melaporkan pengalamannya dengan operasi debulking intervensional pada pasien-pasien dengan karsinoma ovarium stadium lanjut. Pasien mendapat 3 siklus Cisplatin dan Siklofosfamid dan kemudian diacak untuk mendapat operasi debulking intervensional atau tidak dioperasi. Semua pasien mendapat enam siklus kemoterapi. Ada 278 pasien yang dievaluasi, dan median survival adalah 26% vs 20% (operasi vs tanpa operasi, P=0,012). Operasi debulking adalah faktor prognostik independen dalam analisis multivarian. Setelah penyesuaian terhadap semua faktor prognostik, operasi diketahui mengurangi resiko kematian sebesar 33% (P=0,008).
The GOG juga melakukan studi yang serupa. Studi ini dilaporkan pada tahun 2004 dan merekrut 550 pasien. Pasien yang tidak mendapat debulking secara optimal (residu tumor >1 cm) mendapat tiga siklus Paclitaxel plus Cisplatin. Pasien diacak untuk melanjutkan kemoterapi atau menjalani operasi sitoreduksi sekunder dan kemudian melanjutkan kemoterapi. Baik PFS maupun resiko relatif kematian meningkat pada tambahan interval operasi. Peneliti memperkirakan bahwa pasien pada studi GOG juga menjalani operasi yang lebih agresif daripada pasien dalam studi EORTC, hal ini mungkin menyebabkan hasil yang berbeda. Yang terpenting, yang dapat disimpulkan dari kedia studi ini adalah bahwa pasien dengan kanker ovarium stadium lanjut harus mendapat setidaknya satu usaha maksimal dalam hal sitoreduksi, yang dilakukan oleh ahli ginekologi onkologi.
Sementara usaha operasi primer maksimal tampaknya merupakan bagian yang penting dalam potensi survival jangka panjang, waktu untuk melakukan usaha operasi masih merupakan fokus perdebatan. Pada pasien dengan status penyakit borderline, didasarkan pada usia, penyakit medis yang menyertai, efusi ekstensif (terutama pleural atau perikardial), dan pada pasien dengan penyakit
abdominal ekstensif, tidak efektif untuk dilakukan debulking dan sebaiknya dipikirkan untuk memberikan kemoterapi neoajuvan. Setelah 2 sampai 4 siklus biasanya terjadi respon klinis yang baik yang memungkinkan untuk melakukan operasi debulking yang efektif dengan angka komplikasi yang cukup rendah.
Sebelum memulai kemoterapi, sebaiknya ditegakkan diagnosis kanker ovarium, tuba, atau peritoneal berdasarkan sitologi atai operasi invasif minimal. Kini, hasil kemoterapi neoajuvan (yang diikuti dengan operasi debulking) telah dilaporkan dalam sebuah laporan retrospektif pada 20-90 pasien. Studi ini menunjukkan bahwa hasil akhir penyakit serupa dengan yang terjadi pada pasien yang diberikan intervensi operasi primer. Saat ini diadakan sebuah uji klinis oleh EORTC dan NCI-Kanada terhadap lebih dari 700 pasien pada tahun 2006.
III, PERANAN TERAPI RADIASITeknik terapi radiasi mencakup
instilasi kromium fosfat radioaktif ke intraperitoneal dan radiasi external-beam ke abdomen dan pelvis. Pasien dengan karsinoma epithelial ovarium yang dipilih untuk mendapat irradiasi pasca operasi harus mendapat terapi pada seluruh abdomen dan juga radiasi padapelvis. Lapangan terapi yang luas ini didasarkan pada analisis terhadap kekambuhan pasca irradiasi pada tumor stadiumI dan II, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kekambuhan atau rekurensi terjadi diluar pelvis. Tidak ada penutup pada pelvis, dan sel-sel maligna akan meluruh dari tumor ovarium primer dan bersirkulasi melalui seluruh rongga abdomen. Penyebaran limfatik juga mungkin terjadi.
Dua teknik terapi radiasi yang berbeda telah digunakan untuk irradiasi abdomen. Biasanya digunakan portal yang besar, dengan dosis 2500-3000 cGy diberikan selama 4-5 minggu ke seluruh abdomen. Ginjal dan kemungkinan lobus kanan hepar dilindungi untuk membatasi dosis hingga 2000-25000 cGy. Biasanya prosedur ini menyebabkan mual dan muntah, dan terapi biasanya terganggu. Pada beberapa pusat irradiasi abdomen dilakukan dengan teknik moving-strip. Baik teknik seluruh abdomen dan moving-strip biasanya diakhiri dengan boost pelvik dengan dosis mendekati 2000-3000 cGy.
Karena pemahaman terhadap
18

kemoterapi pada kanker ovarium semakin mendalam, peranan radiasi dalam terapi penyakit ini semakin berkurang. Pola penyebaran kanker ovarium dan beda jaringan normal yang terlibat dalam terapi neoplasma inilah yang mempersulit terapi radiasi efektif. Bila residu tumor setelah laparotomi adalah bulky, maka terapi radiasi tidak efektif. Seluruh abdomen harus dianggap berisiko, sehingga dibutuhkan volume irradiasi yang besar, dan menyebabkan limitasi multiple pada ahli radioterapi.
GOG menguji kelayakan penggunaan terapi radiasi bersama dengan kemoterapi. Sebuah studi randomisasi prospektif dengan menggunakan 4 kelompok yang menilai terapi radiasi saja, terapi radiasi sebelum kemoterapi (Melphalan), kemoterapi saja, dan kemoterapi sebelum terapi radiasi tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara keempat kelompok tersebut.
Dembo dkk, melaporkan sebuah studi randomisasi prospektif terhadap 231pasien dengan kanker stadium I dan II, dan III asimtomatis yang mendapat terapi radiasi dengan atau tanpa Klorambusil. Klorambusil, 6 mg perhari, diberikan selama 2 tahun, dan pasien mendapat radiasi abdomen dan pevik sebesar 2250 cGydalam 10 fraksike portal pelvik yang kemudian sege diikuti dengan 2250 cobalt dalam 10 fraksi dengan teknik downward moving abdominal pelvik strip. Untuk pasien stadium I atau II, diberikan irradiasi pelvik saja dengan dosis 4500 cGy. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk pasien stadium Ib, II atau stadium III asimtomatis, operasi pelvik inkomplit pada awal berhubungan dengan survival yang buruk. Untuk pasien yang operasinya komplit, irradiasi abdomen dan pelvik lebih superior dibandingkan dengan irradiasi pelvik saja atau irradiasi pelvik diikuti dengan Klorambusil, dalam hal survival jangka panjang dan kontrol penyakit abdominal. Keefektifan irradiasi abdomen dan pelvic tidak tergantung pada stadium dan gambaran histologi penyakit. Nilai irradiasi abdomen dan pelvik lebih ekstrim terlihat pada pasien yang tidak memiliki residu tumor. Peneliti-peneliti tersebut juga menyimpulkan bahwa irradiasi pelvik saja tidak adekuat dan merupakan terapi pasca operasi yang tidak sesuai untuk pasien stadium Ib atau II. Irradiasi abdomen dan pelvik yang meliputi kedua kubah diafragma tanpa perlindungan hepar akan mengurangi
kegagalan tumor di luar pelvik dan meningkatkan survival.
Namun, kemoterapi ajuvan dengan klorambusil harian setelah irradiasi pelvik tidak efektif dalam penanganan pasien ini. Peneliti juga menyimpulkan bahwa dalam memilih terapi pasca operasi, adanya jumlah penyakit yang sedikit pada abdomen bagian atas bukan merupakan alasan memilih kemoterapi dibandingkan dengan radioterapi. Mereka yakin bahwa terapi radiasi efektif, bahkan bila ada jumlah kecil penyakit yang ada pada abdomen bagian atas.
Studi oleh Dembo dkk, melaporkan angka survival 5 tahun yang baik, seperti 85% untuk pasien kanker stadium II dan 43% pada pasien stadium III. Martinez dkk, melaporkan angka survival 5 tahun sebesar 54% pada 42 pasien dengan kanker ovarium stadium II dan III. Peranan terapi radiasi terhadap penyakit yang terlokalisir juga masih membutuhkan diskusi lebih lanjut.
Sebuah studi randomisasi prospektif terhadap kanker ovarium stadium I yang diadakan oleh GOG menunjukkan hasil sebagai berikut. Pasien dikelompokkan menjadi 3, yaitu : tanpa terapi tambahan, Melphalan (Alkeran), dan irradiasi pelvik. Pasien yang mendapat Melphalan mendapat manfaat yang besar, dan mereka yang mendapat irradiasi pelvik tidak mendapat manfaat. Peranaan irradiasi pelvik pada kanker ovarium stadium II belum dipastikan. Beberapa institusi menggunakan irradiasi pelvik bersama dengan kemoterapi sistemik pelvik meningkatkan survival dibandingkan dengan dengan operasi saja. Efikasi irradiasi pelvik dibandingkan dengan kemoterapi pada penyakit stadium II masih belum diuji dengan studi prospektif.
Studi GOG yang dilaporkan oleh Young dkk, membandingkan kemoterapi dengan koloip 32P intraperitoneal. Sehingga bila dilakukan terapi radiasi pasca operasi, tampaknya lebih tepat bila teknik dilakukan kepada seluruh permukaan abdomen dan pelvik. Tidak ada data fase III yang membandingkan kemoterapi yang berbasis Platinum dengan terapi radiasi pada pasien kanker epithelial ovarium resiko rendah dan intermediate. Limitasi perbandingan terapi radiasi dengan kemoterapi disebabkan oleh banyaknya studi retrospektif. Pada berbagai kondisi, studi terapi radiasi lebih lama, dan prosedur staging tidak dilakukan dengan
19

akurasi yang sama dengan sekarang. Studi prospektif gagal karena akrual yang rendah. Kedua metode terapi sangat berbeda sehingga bias peneliti biasanya mencegah akrual pada pasien. Teknik terapi radiasi kini semakin canggih, dengan toksisitas yang lebih rendah. Hal ini dikombinasikan dengan seleksi data pasien dengan lebih baik akan memberikan bahan uji fase III modalitas ini dalam terapi karsinoma ovarium.
Terapi radiasi sebagai terapi lini kedua pada pasien dengan kemoterapi persisten atau kanker oarium rekuren semakin banyak pendukungnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terapi radiasi sebagai bagian dari terapi inisial telah ditinggalkan dan lebih dipilih kemoterapi. Yang mendorong ketertarikan kembali pada terapi radiasi lini kedua adalah bahwa kemoterapi lini kedua tidak bermanfaat. Cmelak dan Kapp melaporkan, pengalamannya dengan 41 pasien yang gagal merespon kemoterapi. Semua diterapi dengan irradiasi seluruh abdomen, biasanya dengan boost pelvik. Actuarial disease-spesific survival 5 tahun adalah 40% dan 50 % pada pasien yang refrakter terhadap Platinum. Bila residu tumor adalah <1,5 cm, disease-free survival 5 tahun adalah 53%, namun 0% pada pasien dengan penyakit >1,5 cm. Hampir sepertiga pasien yang gagal menyelesaikan irradiasi seluruh abdomen disebabkan oleh toksisitasnya. Tiga pasien memerlukan operasi untuk mengkoreksi masalah traktus gastrointestinal. Sedlacek dkk, mendeskripsikan 27 pasien yang diterapi dengan irradiasi seluruh abdomen, semua telah menjalani kemoterapi yang berbasis Platinum. Semua pasien menyelesaikan radiasi. Angka survival pada5 tahun adalah 15%. Pasien dengan penyakit mikroskopik bertahan rata-rata 63 bulan, namun bila penyakit >2 cm, maka rata-rata survival adalah 9 bulan. Empat pasien membutuhkan operasi untuk mengoreksi masalah gastrointestinal.
Mungkin ada peranan radiasi seluruh abdomen pada pasien yang telah mendapat kemoterapi bila residu tumor kecil. Sedlacek, dalam sebuah review literature menemukan bawha 47 dari 130 (36%) bertahan jangka panjang jika hanya penyakit mirkoskopik yang ada pada saat radiasi seluruh abdomen namun hanya 15 dari 218 (6,8%) bila ada penyakit makroskopik.
IV. TERAPI ISOTOPE
Radioisotope telah banyak digunakan dalam terapi kanker ovarium. Baik beta emitter radioactive chromium phosphate (waktu paruh 14,2 hari) dan radioactive gold (waktu paruh 2,7 hari) telah digunakan. Isotop ini mengemisi radiasi dengan penetrasi maksimal efektif 4-5 mm sehingga hanya bermanfaat pada penyakit minimal. Kedua agen diambil oleh makrofag serosa dan ditransportasikan ke limfonodi retroperitoneal dan mediastinal. Kemungkinan bahwa koloid radioaktif akan mengeradikasi metastasis limfonodi dengan uptake limfatik selektif masih diragukan karena studi-studi menunjukkan bahwa limfonodi maligna tidak mengambil isotop, namun tumor dengan limfonodi bersih mengambil isotop. Telah diperkirakan bahwa 6000 cGy dikirim ke omentum dan permukaan peritoneal dan 7000 cGy pada beebrapa struktur retroperitoneal.
Beberapa uji telah dilakukan untuk membandingkan 32P intraperitoneal dengan atau tanpa irradiasi pelvik dengan radiasi seluruh abdomen atau kemoterapi agen tunggal dalam berbagai kondisi klinis kanker ovarium. Karena 32P intraperitoneal gagal menunjukkan peningkatan hasil akhir dan sulit secara teknis, pilihan ini dikeluarkan dari rencana terapi yang ada.
V. KEMOTERAPI KANKER OVARIUMEvolusi kemoterapi pada kanker
ovarium stadium lanjut selama lebih dari 30 tahun semakin bermanfaat. Kanker ovarium adalah satu tumor maligna solid pertama yang menunjukkan respon terhadap kemoterapi. Efektifitas berbagai kemoterapi telah ditunjukkan dalam bentuk angka respon (biasanya respon komplit atau parsial), angka second-look negatif, dan median survival. Semua ukuran hasil akhir tersebut adalah subyek error dan walaupun yang paling reliable adalah median progression-free survival dan median overall survival.
Agen kemoterapi yang awalnya digunakan dalam terapi kanker ovarium (1970-1990) sebgaian besar terdiri dari Alkylating agen Melphalan (yang juga dikenal dengan Phenylalanine mustard, Alkeran, L-PAM dan L-sarcolysin), Siklofosfamid. Klorambusil dan Tiotepa. Angka respon biasanya dilaporkan dalam kisaran 20-60%, namun angka median survival untuk pasien dengan kanker ovarium stadium lanjut biasanya berkisar antara 10-18 bulan, cukup rendah dibandingkan dengan
20

hasil uji klinis akhir-akhir ini. Antimetabolit, seperti 5-Fluorouracil dan Metotrexat, banyak digunakan pada uji klinis, terutama dalam kombinasi dengan agen Alkylating. Penggunaan sementara agen-agen tersebut pada kanker epitelial ovarium sangat jarang.
Pada akhir 1970an dan 1980an ada perkenalan regimen kemoterapi kombinasi, Hexa CAF-Hexamethylmelamine, Cyclophosphamide, Doxorubicin dan 5-Fluorouracil; dan CAP-Cyclophosphamide, Doxorubicin dan Cisplatin, yang merupakan dua kombinasiyang paling sering digunakan. Pada awal 1980an, terapi kombinasi adalah terapi standar untuk sebagian besar pasien. Pada tahun 1980an juga terjadi perkenalan Cisplatin dan kemudian Carboplatin. Perkenalan senyawa Platinum meningkatkan angka respon menjadi kisaran 50-80% dan peningkatan median survival hingga 12-30 bulan pada sebagian besar studi. Kisaran yang luas ini seringkali disebabkan oleh pemilihan pasien yaitu pasien yang mendapat debulking suboptimal 30 bulan. Senyawa Platinum masih merupakan komponen integral dalam terapi hingga kini.
Pada tahun 1990an terjadi perkenalan Paclitaxel, suatu agen yang awalnya diekstraksi dari Taxus brevifolia. Paclitaxel, yang kini disintesis secara kimiawi menunjukkan mekanisme kerja yang baru dengan memicu perakitan mikrotubular dan menstabilkan pembentukan polimer tubulin, sehingga menghambat pembelahan sel yang cepat dalam menyelesaikan proses mitosis. Respon terhadap agen tunggal Paclitaxel inisial pada pasien-pasien dengan kanker ovarium refrakter berkisar 25-35%. Perkembangan sementara obat-obatan kini berkisar pada formulasi berbagai grup Taxane. Sebuah studi oleh SCOTROC menunjukkan substitusi Paclitaxel dengan Docetaxel memberikan hasil operasi yang serupa, dan profil toksisitas yang lebih unggul pada Docetaxel. Modifikasi Taxane lainnya masih dalam penelitian lebih lanjut, contoh CT-2103 (Xyotax) dan Abraxane, yang memungkin memberikan manfaat lebih atau toksisitas yang lebih rendah dibandingkan pendahulunya.
Lima hingga 10 tahun terakhir juga tetlah diperkenalkan agen aktif lain dalam terapi kanker ovarium, yang paling terlihat adalah Topotecan, sebuah Topoisomerase I-inhibitor; suatu bentuk pegylated liposomal encapsulated dari Doxorubicin (Doxil), dan
Gemcitabine, sebuah obat yang pertama kali diuji pada kankar pancreas. Ketiga obat ini diuji dalam sebuah uji klinis oleh GOG 182/ICON-5. Beberapa fokus terapeutik baru dalam uji klinis terakhir adalah menguji agen yang menargetkan pada target molekular spesifik. Salah satu agen yang mendapat perhatian tersebut adalah Bevacizumab.
Uji klinisAngka respon yang relatif rendah
terhadap sebagian besar agen kemoterapi tunggal menstimulasi penelitian untuk mencari kombinasi agen. Saat ini, kombinasi yang berbasis Platinum telah terbukti menjadi obat kombinasi yang paling sukses. Sebuah studi oleh GOG (GOG#47) membandingkan Doxorubicin (Adriamycin) dan Cyclophosphamide (AC) dengan AC dan Cisplatin (CAP) yang mengindikasikan kemajuan dengan kombinasi tiga regimen. Dengan AC ditemukan 26% respon komplit, dan pada CAP ditemukan 51% respon komplit. Durasi respon berkisar antara 9 bulan hingga 15 bulan, dan progression-free interval adalah 7 bulan hingga 13 bulan. Median survival dalam uji ini adalah 16 bulan hingga 19 bulan untuk CAP pada semua pasien, namun tidak ada signifikansi statistical dalam hal survival pada kedua kelompok. Bila pasien dengan penyakit yang dapat diukur dievaluasi secara terpisah (227 dari 440 pasien yang dapat dinilai), statistik berbeda bermakna untuk survival ditemukan pada kelompok CAP. Tidak ada signifikansi survival yang ditemukan pada penyakit residual yang tidak dapat diukur. Studi ini menunjukkan manfaat pada pasien kelompok Platinum yang memiliki penyakit residual yang dapat diukur setelah menjalani operasi debulking yang suboptimal.
Studi lain pada saat itu menemukan bahwa agen Alkylating seefektif regimen kombinasi (termasuk Platinum) yang terdiri dari hingga 4 obat. Pada studi lain oleh GOG (GOG #52) terhadap pasien dengan kanker ovarium stadiumIII yang sudah menjalani debulking optimal hingga ukuran penyakit residu ≤1 cm, CAP dibandingkan dengan Cyclophosphamide dan Cisplatin. Progression-free interval dan survival tidak banyak berbeda antara kedua kelompok. Sehingga kombinasi Cyclophosphamide dan Cisplatin, menjadi kelompok standar untuk banyak uji klinis pada akhir 1980an dan awal 1990an.
21

Ada empat studi yang dimasukkan dalam metaanalisis untuk menjawab pertanyaan tentang peranan Doxorubicin dalam kanker ovarium. Dengan hanya mempertimbangkan respon komplit patologi, studi ini menunjukkan suatu manfaat kecil yang konstan pada CAP, dan lebih tinggi pada studi The North-West Oncology Group (DACOVA). Dengan menyatukan data-data tersebut dalam metaanalisis, sangat mungkin untuk mendeteksi suatu signifikansi statistik sebesar 6% pada persentase respon komplit patologi dengan CAP. Dan metaanalisis ini menunjukkan signifikansi survival sebesar 7% pada 6 tahun dengan CAP. Namun, karena dalam 3 uji intensitas dosis CAP lebih besar daripada Cyclophosphamide dan Cisplatin, maka apakah hasil CAP yang lebih besar disebabkan oleh dosis yang lebih besar atau karena Doxorubicin itu sendiri masih belum diketahui. Sebuah studi oleh GOG (GOG#132) mengevaluasi 614 pasien dengan kanker yang tidak dilakukan debulking secara optimal yang diterapi dengan protokol 3 kelompok yang membandingkan pemberian Cisplatin saja, Paclitaxel saja, dan kombinasi kedua obat. Progression free survival atau survival pada ketiga kelompok obat serupa. Beberapa menginterpretasikan bahwa hasil studi ini mengindikasikan agen Platinum harus menjadi komponen terapi primer.
Studi GOG (GOG#111) telah mengacak pasien dengan penyakit volume besar untuk mendapat 6 siklus Cisplatin 75 mg/m2 plus Cyclophosphamide 750 mg/m2
setiap 3 minggu atau Paclitaxel 135 mg/m2
selama 24 jam kemudian diikuti dengan Cisplatin 75 mg/m2 setiap 3 minggu. Pada kelompok Paclitaxel, pemberian Paclitaxel sebelum Cisplatin sangat penting untuk mengoptimalkan respon dan meminimalkan toksisitas. Ada total 386 pasien yang dapat dinilai dalam studi ini. Dalam hal efikasi terapeutik, kelompok Paclitaxel memberi keseluruhan respon yang lebih baik (73% hingga 60%) dan respon klinis komplit, dimana frekuensi respon patologi komplit serupa antara kedua kelompok. Persentase pasien yang mencapai status tanpa residupenyakit markoskopis lebih tinggi pada kelompok Paclitaxel (41%) dibandingkan dengan kelompok kontrol (25%). Progression-free survival pada kelompok paclitaxel lebih besar (18 hingga 13bulan). Resiko pregresifitas 32% lebih rendah pada mereka
yang diterapi dengan Paclitaxel daripada regimen Cyclophosphamide. Survival lebih lama pada kelompok Paclitaxel (38 hingga 24 bulan). Resiko kematian 39% lebih rendah pada mereka yang diterapi dengan regimen paclitaxel. Suatu uji European-Canadian Intergroup (OV-10) memiliki studi desain yang serupa dengan GOG #111, yang menguji penggantian Cyclophosphamide dengan Paclitaxel. Studi ini memasukkan penyakit stadium III optimal dan stadium IIB-C. Respon klinis dalam uji ini ditemukan lebih besar pada kelompok Paclitaxel (45% vs 59%). Kombinasi Paclitaxel dengan Cisplatin dianggap sebagai kombinasi standar untuk kemoterapi lini pertama dalam terapi kanker ovarium.
Bila dikombinasikan dengan Cisplatin, Paclitaxel memerlukan interval infus yang panjang (24 jam) untuk mencegah neuropati yang tidak diharapkan. Pemberian ini memberi rasa tidak nyaman pada pasien dan karena itu banyak pusat yang menggantikan Cisplatin dengan Carboplatin, sehingga GOG mengadakan studi ekuivalen untuk mengetahui efikasi serupa dari Paclitaxel (175-185 mg/m2) yang dikombinasikan dengan Carboplatin (AUC 5-7,5). GOG mengadakan GOG# 158 pada populasi pasien optimal (<1 cm) sebagai uji non-infreioritas. Resiko relatif progresifitas pada kelompok Paclitaxel plus Carboplatin adalah 0,88 (95% CI 0,75-1,03). Toksisitas kelompok Paclitaxel plus Cisplatin lebih tinggi. Suatu laparotomi second-look juga merupakan bagian dari protocol.
Pada studi The International Collaborative Ovarian Neoplasm (ICON2), 1526 pasien kanker ovarium diacak untuk mendapat carboplatin dan CAP. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal survival pada kedua kelompok. Usia, stadium, residu penyakit, diferensiasi, dan gambaran hsitologi tidak mempengaruhi survival pada kedua kelompok.
Untuk menginterpretasikan respon harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena merupakan indikator kecenderungan dalam angka survival. Seringkali regimen kemoterapeutik memberikan angka respon yang sangat baik namun tidak memberi efek terhadap angka survival. Sehingga dokter harus menunggu studi yang lebih panjang tentang kemoterapi kombinasi yang berbasis Cisplatin untuk memahami dengan lebih akurat mengenai dampaknya terhadap survival
22

pasien. Omura dkk, melaporkan analisis terhadap dua studi GOG terhadap kemoterapi multistadium pada kanker epithelial ovarium.dalam analisis terhadap 726 wanita dengan stadium III atau IV, telah dilakukan follow-up yang baik. Peneliti menyimpulkan bahwa dampak kemoterapi kini berada dalam tingkat sedang. Kurang dari 10% dari pasien dalam studi ini bebas progresifitas dalam waktu 5 tahun, dan kegagalan tertunda masih muncul, bahkan sebelum 7 tahun. Sutton dkk, melaporkan 7% disease-free survival pada10 tahun.namun superioritas kombinasi agen kemoterapi manapun dalam hal survival jangka panjang pasih belum terbukti.
REFERENSI
1. Bartlett JM. Ovarian Cancer Method and Protocol. Humana Press, Tokowa
2. Britow RE, Karlan BY. Surgical For Ovarian Cancer Principle And Practice. Informa Healtcare Taylor and Francis, London, 2006.
3. Choy H. Chemoradiation In Cancer Ther-apy. Humana Press, New Jersey, 2003.
4. Copeland LJ. Epithelial Ovarian Cancer, In Clinial Gynecology Oncology 7th edition page 313 - 68, Eds : DiSaia PJ, William WT. Mosby Elsevier, Philadelphia, 2007.
5. Davellar EM. Serum Tumor Marker In Ovarian And Cervical Cancer. Vrije Uni-versiteit, Amsterdam, 2008.
6. DiSaia PJ. The Adnexal Mass And Early Ovarian Cancer, In Clinial Gynecology Oncology 7th edition page 283 - 312, Eds : DiSaia PJ, William WT. Mosby Elsevier, Philadelphia, 2007.
7. Donato ML, Wang X, Kavanagh VV, et al. Chemotherapy For Epithelial Ovarian Cancer, In Gynecologic Cancer page 188
– 206, Eds :Buzdar AU, Freedman MS. Springer Science, United Stated Of Amer-ica, 2006.
8. Hesley ML, Alektiar KM, Chi DS. Ovar-ian And Fallopian Tube Cancer, In Hand-book Gynecologic Oncology 2nd edition page 243 – 64, Eds : Barakat RR, Bevers MW,Gersheson DM. Martin Dunitz Pub-lisher, London, 2001.
9. Leung PC, Adasi EY. The Ovary. Elsevier, London, 2004.
10. Piso P, Dahlke MH, Loss M, et al. Cytore-ductive surgery and hyperthermic in-traperitoneal chemotherapy in peritoneal carcinomatosis from ovarian cancer. World Journal Of Surgical Oncology, Biomed Central, 2004.
11. Penson RT, Gynecologic Oncology Ovar-ian Cancer, In Horrison Manual Of Oncol-ogy page 485 -96, eds Chabner BA, Lynch TJ, Longo DL. McGrawHill Medical,United Stated Of America, 2008.
12. Shorge JO, Schaffer JI, Holvorson LM, et al. Epithelial Ovarian Cancer, In William Gynecology. McGrawHill, China, 2008.
13. Tinnelli A, Tinnelli R, Tinneli FG, et al. Conservative Surgery For Borderline Ovarian Tumor : Review. Jurnal Gy-neclogy Oncology (100) 181 - 91, Else-vier, 2006.
14. Wright C. Ovarian Malignancies, In Handbook Of Gynecologic Management page 462 – 7, ed Rosevear SK. Blackwell Science, London, 2002.
23

HUBUNGAN ANTARA FUNGSI KELUARGA DENGAN KEPATUHAN BEROBAT
PASIEN
PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON RSU DR. SOETOMO
SURABAYA
Agung Budi Setyawan
Bagian Psikiatri
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya kusuma Surabaya
AbstrakDari hasil pengamatan dalam penelitian ini secara keseluruhan didapatkan perbedaan yang bermakna
dalam fungsi keluarga antara keluarga sampel yang patuh dibanding dengan yang tidak patuh. Dalam hal ini keluarga sampel yang patuh menunjukkan fungsi keluarga yang lebih baik dibanding keluarga sampel yang tidak patuh.Dari semua skala yang ada, skala 2 (komunikasi keluarga) menunjukkan skala yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan pasien-pasien ketergantungan opioid yang berobat di URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya. Urutan berikutnya adalah peran, keterlibatan afektif, respon afektif, kontrol perilaku, dan kemampuan problem solving keluarga tersebut.Dengan demikian hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini dapat diterima yaitu bahwa : ‘Didapatkan hubungan antara disfungsi keluarga dengan kepatuhan berobat pasien-pasien ketergantungan opioid yang berobat di URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya.
Kata kunci : fungsi keluarga, kepatuhan berobat, dan komunikasi
RELATIONSHIP BETWEEN THE FUNCTIONS OF A FAMILY WITH PATIENT
TREATMENT COMPLIANCE
METHADONE MAINTENANCE THERAPY PROGRAM RSU DR. SOETOMO
SURABAYA
Agung Budi Setyawan
Psychiatry Section
Lecturer Faculty of Medicine, University of Wijaya Kusuma Surabaya
AbstractFrom the observation in this study as a whole found significant differences in family functioning between families who are obedient samples compared with non-compliance. In this case the sample families who dutifully show family functions better than samples of families who do not patuh.Dari all the existing scale, scale 2 (family communication) indicates the scale of the most influential to adherence opioid dependent patients seeking treatment at public hospitals URJ PTRM dr. Soetomo. The next sequence is the role, affective involvement, affective responses, behavioral control, and problem solving abilities tersebut.Dengan family so the hypothesis made in this study can be accepted namely that: 'It was found the relationship between family dysfunction with treatment compliance of patients seeking treatment of opioid dependence at URJ PTRM Dr. Soetomo.
Key words: family functioning, treatment compliance, and communication
BAB IPENDAHULUANI.1. Latar Belakang Masalah
Penyalahgunaan zat merupakan suatu masalah yang memiliki dimensi yang cukup komplek, terkait dengan berbagai segi
kehidupan serta berdampak negatif, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat, bahkan dapat pula membahayakan masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) menunjukkan kecenderungan peningkatan
24

yang cukup pesat, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. United Nations Drug Control Programme (UNDCP) melaporkan bahwa kurang lebih 200 juta orang di seluruh dunia ini telah menjadi pengguna NAPZA, dan tiga juta diantaranya berada di Indonesia (BNN,2003). Pusat data dan informasi Departemen Kesehatan melaporkan bahwa 98,2 % pengguna NAPZA adalah pengguna opioid, dan 89,9 % diantaranya adalah generasi muda yang berusia antara 15 – 29 tahun (DepKes RI, 2004).
Menurut the Office of National Drug Control Policy (ONDCP), diperkirakan hampir 1 juta pengguna opiat dalam jangka lama berada di USA. Demikian pula, kematian oleh karena overdosis seringkali/paling banyak terjadi akibat zat opioid. Selain hal tersebut diatas, para pengguna opioid banyak yang menggunakan jarum suntik dengan cara yang salah, sehingga dengan demikian akan menambah meningkatnya risiko infeksi HIV, hepatitis, cellulitis, endocarditis serta tuberculosis.
Berfungsi atau tidaknya suatu keluarga telah terbukti mempunyai pengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan mental seseorang. Adanya gangguan dalam fungsi keluarga dapat menjadi salah satu faktor yang berperan dalam mendorong seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan zat. Gerber dkk (1983) telah membuktikan bahwa penyalahgunaan zat secara bermakna berkaitan dengan disfungsi dalam sistim keluarga, yang mencerminkan adanya gangguan psikopatologik dari salah satu atau lebih anggota keluarga tersebut. Namun demikian, mengingat masih terbatasnya penelitian yang mencari hubungan antara fungsi keluarga dengan kepatuhan berobat pada para pengguna NAPZA, khususnya opioid, maka diperlukan adanya penelitian yang bertujuan untuk menjawab suatu pertanyaan apakah fungsi keluarga juga ada hubungannya dengan kepatuhan para pengguna opioid tersebut dalam proses terapi/pengobatan mereka. Selama ini upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, khususnya zat opioid telah banyak dilakukan, termasuk diantaranya melalui program terapi rumatan metadon. Jumlah kasus baru ketergantungan opioid yang berobat di Unit Rawat Jalan Program Terapi Rumatan Metadon (URJ PTRM) RSU Dr. Soetomo Surabaya
cenderung mengalami peningkatan. Pada awal Februari 2006 pasien baru sebanyak 18 orang dan setiap bulan bertambah rata rata 16 orang. Pada bulan Februari 2007 pasien berjumlah 218 orang, namun demikian yang tetap aktif mengikuti PTRM hanya sebanyak 109 orang. Dari semua pasien yang ada 35% drop out (DO) dalam 6 bulan pertama dan 53% DO dalam 12 bulan pertama. Sedangkan menurut War, Matik & Hall (1992) angka DO pada pasien-pasien PTRM adalah berkisar antara 7% - 64%. Sementara itu, di RSKO Jakarta dilaporkan 43% dari pasien yang ada DO pada Agustus 2004 dan 75%nya DO sebelum 5 bulan pertama terapi.
Menurut Newcomb dkk (1986), Vaillant & Milofsky (1982), Zucher & Gomberg (1986) menyatakan sejumlah risiko yang terlibat dalam penyalahgunaan zat antara lain keluarga penyalahguna alkohol dan zat, tekanan kelompok sebaya, fungsi keluarga, harga diri yang rendah, kepribadian antisosial, depresi & kecemasan, keagamaan yang rendah, serta pengaruh kultural & etnis.
Sejauh ini belum ada data yang menggambarkan hubungan antara fungsi keluarga dengan kepatuhan berobat pada pasien ketergantungan opioid yang berobat di Unit Rawat Jalan Program Terapi Rumatan Metadon RSU Dr. Soetomo Surabaya, hal inilah yang mendorong untuk dilakukannya penelitian ini.
I.2. Rumusan Masalah- Apakah fungsi keluarga berhubungan
dengan kepatuhan pasien-pasien kergantungan opioid yang berobat di URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya ?
I.3. Tujuan Penelitian- Dari penelitian ini akan dapat
diketahui adanya hubungan antara jenis disfungsi keluarga tertentu pada pasien-pasien kergantungan opioid dengan ketidakpatuhan mereka dalam mengikuti proses pengobatan di URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya, sehingga dapat menjadi data dasar untuk optimalisasi penatalaksanaan pasien-pasien tersebut baik saat ini maupun di masa-masa yang akan datang.
25

I.4. Manfaat Penelitian- Dalam pelayanan kesehatan:
Peningkatan strategi pelayanan dengan optimalisasi perawatan psikiatrik sebagai bagian dari pelayanan holistik bio-psiko-sosial.
- Dalam bidang akademik : Menambah data dan wacana adanya jenis disfungsi keluarga tertentu yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pasien-pasien kergantungan opioid yang berobat di URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya.
- Dalam bidang penelitian : Dapat dijadikan data awal dan pembanding untuk penelitian sejenis diwaktu yang akan datang.
BAB IITINJAUAN PUSTAKA
Penyalahgunaan NAPZA terjadi oleh adanya interaksi berbagai faktor, yakni faktor predisposisi, kontribusi, dan pencetus. Faktor predisposisi adalah faktor yang membuat individu cenderung menyalahgunakan NAPZA, yang tergolong faktor ini antara lain gangguan kepribadian antisosial, kecemasan, dan depresi. Sedangkan yang tergolong cukup dominan sebagai faktor kontribusi dalam terjadinya penyalahgunaan NAPZA adalah faktor keluarga, baik kondisi keluarga, keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, maupun hubungan interpersonal dalam keluarga tersebut. Kondisi keluarga yang mengalami gangguan/disfungsi merupakan faktor potensial dalam mendorong terjadinya penyalahgunaan NAPZA. Anak-anak yang bertumbuh dan berkembang dalam keluarga yang mengalami disfungsi memiliki peluang 7,9 kali untuk terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA. Sementara itu faktor pencetus adalah faktor yang mendorong sehingga penyalahgunaan NAPZA terjadi, dan yang tergolong dominan dalam hal ini adalah pengaruh teman kelompok sebaya (Hawari,2001).
Opioid adalah istilah yang digunakan untuk segolongan zat, baik yang alamiah, semisintetik, maupun yang sintetik dari opium. Opioid alamiah berasal dari getah seperti susu yang keluar dari kotak biji yang belum masak atau getah kepala bunga tanaman Papaversomniferum (poppy). Senyawa ini memiliki sifat mematikan rasa, analgesik, sedatif dan depresan umum. Opioid memiliki
lebih dari 20 jenis alkaloid, yang salah satu dari alkaloid memiliki efek yang dapat memberikan rasa nyaman dan mengurangi penderitaan sehingga diberi nama morfin, nama dari dewa mimpi Yunani Morpheus. Di dalam opioid mentah mengandung 4 – 21 % morfin dan 0,7 – 2,5 % kodein (Fisher,1997;Bigelow,1995).
Opioid adalah jenis NAPZA yang mempunyai potensi ketergantungan paling kuat. Golongan ini terdiri dari berbagai turunan dan zat sintesisnya. Turunan tersebut antara lain : opium, morfin, diasetilmorfin/ diamorfin (heroin, smack, horse, dope), metadon, kodein, oksikodon (percodan, percocet), hidromorfon (dilaudid), levorfanol (levo-dromoran), pentazosin (talwin), meperidin (demerol), propeksipen (dorvon) (Kosten,2002). Golongan opioid mampu melewati sawar darah otak. Dalam hal ini heroin memiliki kemampuan 100 kali dibandingkan dengan kemampuan morfin, oleh karena itu heroin dinamakan ”hero drug”, dan oleh karena alasan ini pula, heroin menduduki peringkat tertinggi untuk disalahgunakan, terutama dengan menggunakan jarum suntik yaitu sebesar 75,63 % (PPIKB/CME,2002).
Pada saat opioid melewati aliran darah otak kemudian berikatan dengan reseptor µ opiat yang terdapat pada permukaan neuron sel otak, hubungan khemikal tersebut akan mencetuskan biokhemikal otak yang sama untuk memproses reward pada seseorang dengan perangsangan kesenangan alami seperti makan, minum dan seksual. Ketika zat menstimuli reseptor µ opiat di otak maka sel pada ventral tegmental area (VTA) akan memproduksi dopamin (DA) dan dilepaskan ke dalam Nucleus Acumben (NAc) untuk memberikan perasaan senang. Perubahan sistem reward dopamin (DA) pada VTA tidak sepenuhnya dimengerti (Clark,200). Prinsip kesenangan dari sistem reward alami tersebut akan meningkatkan aktivitas opiat untuk pemakaian awal yang akan berlanjut pada adiksi. Pemakaian opioid dalam waktu lama akan merubah fungsi otak dan akan memperpanjang waktu kesenangan, hal ini yang mendasari perilaku kompulsif mencari zat. Apabila pemakaian opioid berlanjut akan menginduksi mekanisme ketergantungan di otak, sehingga memerlukan pemakaian tiap hari untuk mencegah craving dan gejala withdrawal. Penelitian lebih baru
26

secara umum menjelaskan beberapa model tentang pembiasaan pemakaian opioid mengakibatkan perubahan pada otak dan proses adiksi yang kemungkinan melibatkan komponen dari masing-masing model dengan ciri-ciri yang berbeda (Kosten,2002).
Toleransi, kecanduan, dan ketergantungan opioid merupakan manifestasi perubahan otak yang diakibatkan dari penyalahgunaan opioid yang kronis. Abnormalitas otak akan menghasilkan ketergantungan dan hal ini akan melibatkan efek dari interaksi dengan lingkungan seperti stres, keadaan sosial yang mengawali penggunaan opiat, kondisi psikologi, faktor predisposisi genetik serta jalur otak yang abnormal sebelum pemakaian opioid pada dosis awal. Abnormalitas tersebut akan menimbulkan kekambuhan berikutnya setelah beberapa bulan atau tahun (Cami,2003). Ketergantungan opioid menurut definisi WHO adalah sekumpulan gejala kognitif, perilaku dan fisiologis yang dapat terjadi bersama-sama, dimana memerlukan pemakaian opioid yang berulang ulang dengan dosis yang lebih besar (Jaffe in Kaplan, 9ed). Kriteria diagnosa ketergantungan opioid menurut DSM IV apabila memenuhi ≥ 3 dari yang tersebut di bawah ini selama periode 12 bulan : 1. Toleransi2. Withdrawal3. Penggunaan opioid dalam jumlah besar
atau waktu yang lebih lama daripada se-harusnya.
4. Keinginan yang kuat untuk berhenti, na-mun berulang kali gagal.
5. Hampir seluruh waktu dalam hidup digu-nakan untuk mendapatkan opioid, meng-gunakan opioid, atau menyembuhkan dampaknya.
6. Berkurangnya aktivitas penting lainnya dalam hal sosial, pekerjaan, atau rekreasi karena ditukar dengan penggunaan opi-oid.
7. Menggunakan opioid meskipun tahu merugikan fisik atau menimbulkan masalah psikologis (Atkison,2003).
Metadon merupakan salah satu farmakoterapi untuk manajemen ketergantungan opioid. Dengan Program Terapi Rumatan Metadon telah terbukti dapat menurunkan angka kematian pada pasien-pasien penyalahgunaan opioid. Penelitian di Amerika Serikat menjelaskan bahwa pecandu
heroin yang tidak diobati mempunyai angka kematian sebesar 8,3%, sedangkan yang mengikuti Program Terapi Rumatan Metadon angka kematian turun menjadi sebesar 0,8% (Vocci,2005).
Penelitian di Swedia, menyebutkan sebesar 6 kali lipat penurunan angka kematian pecandu opioid pada Program Terapi Rumatan Metadon, sedangkan pada penelitian orang Australia terdapat 4 kali penurunan risiko kematian untuk pasien Program Terapi Rumatan Metadon (Batki,2005). Program Terapi Rumatan Metadon juga dapat menurunkan angka kesakitan serta risiko penyakit infeksi. Pada penelitian sebelumnya, mengatakan lamanya Program Terapi Rumatan Metadon berbanding terbalik dengan prevalensi HIV dan pada penelitian prospective terdapat 7 kali penurunan insiden HIV pada kelompok Program Terapi Rumatan Metadon dibanding pasien yang tidak mengikuti program (Luty,2004).
Keberhasilan suatu terapi dipengaruhi oleh seberapa jauh gangguan itu diketahui penyebabnya, ada atau tidaknya metode yang efektif, serta faktor-faktor yang berpengaruh lainnya. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut, akan dapat dikembangkan suatu intervensi yang lebih efektif. Seperti yang sudah dijelaskan diawal BAB II dalam tulisan ini, faktor keluarga telah menjadi bagian yang cukup dominan dalam memberikan kontribusi penyalahgunaan NAPZA, setidaknya sejak tahun 1954, Fort telah mengulas tentang masalah ini, dan setelah itu, literatur tentang variabel-variabel yang berpengaruh dalam proses perawatan masalah ketergantungan zat ini menunjukkan akumulasi yang semakin meningkat dan tetap.
Hubungan yang kurang dekat antara orang tua dengan anak menyebabkan anak akan mencari pengganti dan kompensasi ke dalam teman kelompok sebaya (Moesono, 2003). Selain itu Naratman (1981) dalam penelitiannya terhadap penyalahgunaan zat di Malaysia, juga telah menyatakan bahwa disfungsi keluarga yang ditandai dengan buruknya hubungan antara orang tua dan anak merupakan faktor yang berperan serta yang secara potensial dapat mendorong anak kepada penyalahgunaan zat.
Pandangan awal tentang individu-individu ketergantungan obat cenderung untuk mencirikan mereka sebagai para penyendiri –
27

yaitu orang-orang yang terisolasi dari hubungan primer dan menjalani kehidupan “alley cat”. Sampai para peneliti mulai menyelidiki tentang tata kehidupan dan kontak keluarga para pecandu, pandangan itu mulai bergeser. Sebagai contoh, Vaillant (1996), dalam sebuah follow up dari para pecandu NAPZA New York yang kembali dari rumah sakit rehabilitasi NAPZA Federal di Kentucky, menemukan bahwa 90% dari orang-orang berusia 22 tahun yang ibunya masih hidup, kemudian tinggal dengan ibu mereka, sementara 59% dari orang-orang berusia 30 tahun yang ibunya masih hidup, tinggal dengan ibu mereka atau dengan kerabat darah perempuan lainnya seperti nenek atau saudara perempuan.
Apakah para pecandu obat-obatan benar-benar hidup dengan orang tua mereka atau tidak, bukti yang telah terakumulasi menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka berhubungan erat dengan para keluarga mereka. Sebagai contoh, dalam melacak para pecandu untuk follow up jangka panjang, Bale dan rekan-rekan (1977) mencatat bahwa para klien ini biasanya memiliki contact person akrab seperti orang tua atau kerabat dekat lainnya, namun menurut Goldstein dan rekan-rekan (1977) para pecandu tersebut “cenderung untuk memanfaatkan rumah tangga yang ada (biasanya orang tua mereka) sebagai titik referensi konstan dalam kehidupan mereka”.
Lebih jauh lagi, Coleman (personal communication, March 1979), dalam sebuah ulasan dari grafik 30 pecandu pria, mencatat bahwa orang yang mereka minta untuk dihubungi dalam kasus darurat hampir selalu ibu mereka, dan hampir tidak pernah orang dengan siapa mereka tinggal (yaitu istri atau pacar) bagi para klien yang tidak tinggal dengan para ibu mereka.
Para pecandu seringkali terikat pada sistem keluarga pada banyak titik, sehingga komunikasi diantara mereka dan para anggota lainnya seringkali berjalan melalui saudara kandung, kerabat, dan suami/istri. Dari 26 laporan yang menguatkan, semuanya menunjukkan bahwa mayoritas dari para pasien seperti itu sedikitnya memiliki kontak mingguan, sementara (bergantung pada lokasi geografis dan variabel-variabel lainnya) dari 35% hingga 80% tinggal dengan atau bertemu dengan satu atau lebih orang tua tiap harinya. Tentu saja, tinggal dengan atau secara reguler
menghubungi orang tua tidak dengan sendirinya bersifat pathognomonic. Bahkan, praktik-praktik seperti itu bisa jadi adalah peraturan/budaya dalam beberapa kelompok etnis tertentu.
Dalam sebuah studi terhadap orang Australia, Schweitzer dan Lawton (1989) meminta para pasien pria dan wanita poli ketergantungan obat-obatan dan opium untuk melengkapi Parental Bonding Instrument. Para subjek menilai orang tua mereka, terutama ayah mereka, memiliki sifat yang lebih dingin, acuh tak acuh, intrusif, dan menghalangi kemandirian dibandingkan penilaian dari kelompok kontrol.
Telah diketahui secara umum bahwa prosentase para pasien dengan masalah ketergantungan atau penyalahgunaan obat-obatan adalah sangat kecil dalam kepatuhan berobatnya. Nathan (1990) memperkirakan bahwa angka ini adalah 5%, sementara Frances dan rekan-rekan (1989) menetapkannya pada 10%. Sebuah studi epidemiologi oleh Kessler dan rekan-rekan (1994) menunjukkan bahwa hanya 8% diantara para pecandu tersebut yang berusaha dengan sungguh-sungguh mencari pertolongan/ pengobatan. Dengan besarnya populasi yang tidak terawat dan meningkatnya kontribusi dari penyalahgunaan obat-obatan (melalui penggunaan intravena dan prostitusi) pada penyebaran acquired immunodeficiency syndrom (AIDS), cara-cara untuk mengikutsertakan keluarga dalam perawatan mulai diasumsikan sebagai hal yang penting. Memang, Frances dan Miller (1991) telah menyatakan bahwa “tantangan utama bidang kecanduan adalah membantu para pecandu zat tersebut untuk menerima dan meneruskan perawatan”.
Pendekatan-pendekatan melalui keikutsertaan seluruh anggota keluarga maupun orang lain (significant figure) menjadi hal yang penting dalam mempertahankan kepatuhan berobat para pasien ketergantungan zat. Berikutnya menurut Collins dan Allison (1983), salah satu dari metode yang paling efektif/manjur dalam mengatasi ketidakpatuhan mereka adalah melalui orang lain yang berarti/signifikan, seperti suami/istri, orang tua, saudara kandung, anak-anak, teman, pendeta, atasan, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Resnick dan Resnick (1984), “… keluarga dapat
28

seringkali menjadi kunci untuk memaksa pasien agar berhenti menyangkal/menghindar, dan mulai dengan serius menangani masalah ketergantungannya”.
Pada mulanya dikembangkan pada tahun 1960an oleh Johnson (1973, 1986) di the Johnson Institute di Minneapolis, sebuah metode/intervensi untuk memobilisasi dan melatih para anggota keluarga, teman, dan rekan-rekan untuk menghadapi para pecandu dengan kepedulian-kepedulian mereka, agar dengan keras mendorong para pecandu tersebut untuk memasuki perawatan, dan menjabarkan konsekuensi-konsekuensi (seperti perceraian, hilangnya pekerjaan, dll) jika mereka tidak patuh dalam proses perawatan.
Community Reinforcement Training (CRT) adalah program yang melibatkan anggota keluarga agar mereka segera menelpon untuk mendapatkan bantuan apabila ada anggota keluarga mereka yang mengalami masalah dalam hal ketergantungan zat. Program ini meliputi sejumlah sesi dengan keluarga para pasien dimana mereka diajari bagaimana cara untuk menghindari kekerasan fisik, mendorong ketenangan hati, mendorong pencarian perawatan, dan bantuan dalam proses perawatan. Pendekatan ini pada umumnya adalah non konfrontasional dan berusaha untuk mengambil kesempatan dari sebuah saat ketika para pecandu tersebut mulai termotivasi untuk mendapatkan perawatan dengan cara mendorong agar segera meminta pertemuan di klinik dengan konselor, bahkan jika hal ini terjadi di tengah malam (Sisson dan Azrin, 1993).
Sebuah metode untuk mengikutsertakan para pecandu remaja (dan keluarga mereka) telah dikembangkan oleh Szapocznik dan rekan-rekan (1988). Dengan menggunakan metode ini, Szapocznik dan rekan-rekan mampu untuk mendapatkan 93% remaja yang ditargetkan untuk datang ke klinik dengan para keluarga mereka untuk sebuah pertemuan intake, dibandingkan dengan 42% untuk keikutsertaan dalam situasi dan kondisi yang tidak melibatkan keluarga mereka.
The Albany-Rochester Interventional Sequence for Engagement (ARISE) dirancang oleh Garrett dari program Al-Care (sebuah fasilitas rawat jalan yang cukup besar untuk para pecandu zat di Albany, NY), ARISE membawa beberapa tahap dalam mobilisasi
keluarga dan orang-orang lainnya yang signifikan menuju masuknya pasien dalam proses perawatan (Garrett et al.,). Metode ini mengkombinasikan intervensi formal (Johnson, 1973, 1986), terapi jaringan social (Speckand Attneave, 1973), dan pendekatan terhadap keluarga (Rochester danLandau-Stanton, 1990; Landau-Stanton dan Clements, 1993; Seaburn et al. 1995; Stanton, 1984; Stanton dan Landau-Stanton, 1990).
Masalah keluarga (yang secara tidak sengaja, biasanya dihubungkan dengan kejadian siklus hidup keluarga) juga dapat mendorong para pecandu obat-obatan untuk kambuh atau meninggalkan perawatan. Sebagai contoh, ada bukti bahwa permulaan dari penyalahgunaan obat-obatan dan over dosis dapat ditimbulkan oleh gangguan keluarga, stres, dan kehilangan (Duncan, 1978; Krueger, 1981; Noone, 1980). Lebih jauh lagi, gangguan-gangguan ini mungkin tidak secara nyata melibatkan klien secara langsung, tetapi mugkin bersifat lebih tidak langsung (seperti ketika ibunya kehilangan pacarnya, atau ketika ayahnya kehilangan pekerjaannya).
Persepsi fungsi keluarga adalah persepsi dari anggota keluarga/pasien mengenai kemampuan keluarga dalam hal pemecahan masalah, komunikasi, peran, respon afektif, keterlibatan afektif, dan pengendalian tingkah laku. Fungsi keluarga ini dapat dinilai dengan menggunakan The McMaster Family Assessment Divice (FAD), yang menilai persepsi dari pasien mengenai kemampuan keluarga dalam hal-hal sebagai berikut :
Pemecahan masalah Komunikasi Peran Respon afektif Keterlibatan afektif Pengendalian tingkah laku Fungsi umum
Hasil penelitian reliabilitas pada uji ulang FAD menunjukkan nilai reliabilitas yang cukup tinggi ( alpha = 0,70). Sedang studi validitas FAD pada kelomppok klinik dan non klinik menunjukkan perbedaan yang bermakna ( p < 0,02 ). Sementara itu penggunaan FAD bersama-sama dengan Locke Wallace Marital Satisfaction Scale memberikan hasil analisis yang sejajar.
BAB III
29

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN
III.1. Kerangka konseptual
Keterangan : : Jalur yang diteliti: Jalur yang tidak diteliti
III.2. Hipotesis PenelitianDidapatkan hubungan antara disfungsi
keluarga dengan kepatuhan pasien-pasien ketergantunagan opioid yang berobat ke URJ PTRM RSU Dr. Soetomo.
BAB IV METODE PENELITIAN
IV .1. Jenis PenelitianPenelitian ini adalah studi analitik
observasional dengan bentuk cross-sectional untuk mengetahui adanya hubungan antara fungsi keluarga tertentu dengan kepatuhan berobat pasien ketergantungan opioid di URJ Program Terapi Rumatan Metadon RSU Dr. Soetomo Surabaya..
IV. 2. Tempat dan WaktuTempat dilakukannya penelitian ini
adalah di Unit Rawat Jalan Program Terapi Rumatan Metadon RSU Dr. Soetomo Surabaya. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan kalender, mulai bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007. IV. 3. Sampel Penelitian
Sampel penelitian adalah pasien Unit Rawat JalanProgram Terapi Rumatan Metadon RSU Dr. Soetomo Surabaya. Cara pengambilan sampel adalah dengan cara systematic random sampling.
IV. 4. Kriteria inklusi dan eksklusiIV. 4. 1. Kriteria inklusi
Kriteria inklusi : Harus memenuhi kriteria DSM-IV
untuk ketergantungan opioid Bersedia dengan sukarela
menandatangani informed consent dan berpartisipasi dalam penelitian
Pasien-pasien yang tercatat berobat di URJ PTRM RSDS sampai dengan bulan Agustus 2007
Usia lebih dari 17 tahun sampai dengan 40 tahun
Telah mengikuti PTRM minimal sudah 1 bulan.di URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya
IV. 4. 2. Kriteria eksklusiKriteria eksklusi :
Pasien dengan psikosis yang jelas Retardasi mental yang jelas Kelebihan dosis atau intoksikasi
opioid Pasien dengan penyakit fisik berat Mengikuti Program Terapi
Rumatan Metadon < 1 bulanIV. 5. Jumlah Sampel
Sampel diambil dari pasien-pasien yang berobat ke URJ PTRM RSDS sampai bulan Agustus 2007 secara systematic random
30
Pasien yg berobat ke URJ PTRM RSDS
Kepatuhan Dalam Berobat ke URJ PTRM RSDS
Fungsi Keluarga
Faktor lain : KepribadianPendidikanUmurPekerjaanBudayaKeterlibatan dalam masalah hukumPengaruh lingkungan

sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dengan besar sampel didapat melalui
rumus :
n1 = n2 =
Z1/2 0,05 = 1,96Z 0,20 = 0,842p1 = Proporsi kepatuhan berobat pasien
ketergantungan opioid dengan fungsi keluarga yang baik.
p2 = Proporsi ketidak-patuhan berobat pasien ketergantungan opioid dengan disfungsi keluarga.
Oleh karena belum ditemukan penelitian sejenis maka besar sampel ditetapkan berdasarkan teori limit pusat dengan masing-masing kelompok sebesar 30 pasien patuh dan 31 pasien tidak patuh.
IV. 6. Variabel Penelitiana. Variabel bebas adalah fungsi keluargab. Variabel tergantung adalah kepatuhanc. Variabel luar adalah faktor kepribadian,
pendidikan, jenis kelamin,umur, norma agama, budaya, ketergantuangan ekonomi pada orang tua, dan lingkungan.
IV. 7. Definisi OperasionalA. Ketergantungan NAPZA : adalah
pasien yang oleh psikiater telah didiagnosis sebagai ketergantungan NAPZA. Sesuai dengan pedoman PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya keadaan ketergantungan merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh paling sedikit tiga atau lebih kondisi di bawah ini yang dialami dalam masa setahun sebelumnya : Adanya keinginan yang kuat
atau dorongan yang memaksa (kompulsi) untuk menggunakan zat
Kesulitan dalam mengendalikan perilaku menggunakan zat sejak awal, usaha untuk penghentian atau tingkat penggunaannya
Keadaan putus zat secara fisiologis ketika penghentian penggunaan atau pengurangan zat, terbukti orang tersebut menggunakan zat atau golongan
zat sejenis dengan tujuan menghilangkan atau menghindari terjadinya gejala putus zat
Adanya bukti toleransi, berupa peningkatan dosis zat yang diperlukan guna memperoleh efek yang sama yang biasanya diperoleh dengan dosis yang lebih rendah
Secara progresif mengabaikan alternatif menikmati kesenangan atau minat lain karena penggunaan zat, meningkatnya jumlah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan atau menggunakan zat atau untuk pullih dari akibatnya
Tetap menggunakan zat meskipun ia menyadari adanya akibat yang merugikan kesehatannya, seperti gangguan fungsi hati, keadaan depresi, atau hendaya fungsi kognitif akibat penyalahgunaan zat tersebut
B. Persepsi Fungsi Keluarga : adalah persepsi dari pasien mengenai kemampuan keluarga dalam hal-hal sebagai berikut :
Pemecahan masalah Komunikasi Peran Respon afektif Keterlibatan afektif Pengendalian tingkah
laku Fungsi umum
Fungsi keluarga ini dapat dinilai dengan menggunakan The McMaster Family Assessment Divice (FAD).
C. Ketergantungan opioid : Sesuai dengan DSM IV disebut
ketergantungan opioid apabila memenuhi ≥ 3 dari yang tersebut di bawah ini selama periode 12 bulan :
31
(Z1/22.p.q + Zp1.q1+p2.q2)2
(p1 - p2)2

1. Toleransi, seperti yang dipastikan dengan adanya salah satu tersebut di bawah ini : kebutuhan akan penambahan dosis yang mencolok agar diperoleh efek yang diinginkan atau berkurangnya efek secara mencolok akibat penggunaan berulang dengan dosis yang sama.
2. Withdrawal, yang dipastikan dengan adanya salah satu yang tersebut di bawah ini : sindroma putus zat yang khas untuk zat tersebut atau zat yang sama harus digunakan untuk menyembuhkan/menghindari gejala putus zat.
3. Penggunaan opioid dalam jumlah besar atau waktu yang lebih lama dari-pada seharusnya.
4. Keinginan yang kuat untuk berhenti, namun berulang kali gagal.
5. Hampir seluruh waktu dalam hidup digunakan untuk mendapatkan opioid, menggunakan opioid, atau menyembuhkan dampaknya.
6. Berkurangnya aktivitas penting lainnya dalam hal sosial, pekerjaan, atau rekreasi karena ditukar dengan penggunaan opioid.
7. Menggunakan opioid meskipun tahu merugikan fisik atau menimbulkan masalah psikologis.
D. Disebut patuh apabila minimal enam bulan berturut-turut pasien rajin kontrol setiap hari sesuai dengan buku panduan berobat URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya.
E. Disebut tidak patuh apabila pasien berobat secara tidak teratur (tidak kontrol selama lebih dari 3 hari berturut-turut), atau berobat teratur tetapi sebelum enam bulan pasien sudah menghentikan proses perawatan selanjutnya.
32

IV. 8. Cara KerjaIV. 8. 1. Prosedur
IV. 8. 2. Alat ukurPersepsi fungsi keluarga
adalah persepsi dari pasien mengenai kemampuan keluarga dalam hal pemecahan masalah, komunikasi, peran, respon afektif, keterlibatan afektif, dan pengendalian tingkah laku. Persepsi fungsi keluarga ini dapat dinilai dengan menggunakan The McMaster Family Assessment Divice (FAD), yang merupakan kwesioner terdiri dari enam puluh item dan terbagi dalam 7 skala sebagai berikut :
Skala 1 : Pemecahan masalah (Problem Solving/PS), yang menilai kemampuan keluarga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mengancam integritas dan kapasitas fungsional keluarga.
Skala 2 : Komunikasi (Communication/Co), yang menilai
bagaimana pertukaran informasi antar anggota keluarga terutama ditekankan pada kejelasan dari isi pesan-pesan verbal dan ditujukan kepada siapa.
Skala 3 : Peran (Roles/Ro), yang menilai kemampuan keluarga menetapkan pola tingkah laku dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga sehari-hari yang meliputi fungsi keluarga sebagai sumber penyediaan perbekalan, pendukung perkembangan individu, dan sebagainya.
Skala 4 : Respon afektif (Affective Responsiveness/AR), yang menilai tentang kemampuan keluarga dalam memberikan reaksi afektif yang sesuai terhadap berbagai macam rangsang.
Skala 5 : Keterlibatan afektif (Affective Involvement/AI), yang menilai sejauh mana anggota keluarga
33
Pengolahan data
Sampel Penelitian
Kriteriainklusi
Kriteriaeksklusi
Berobat ke URJ PTRM
RSDS
Pasien Ketergantungan
opioid
Pengukuran dengan FADPengukuran dengan FAD
Patuh Tidak Patuh
Laporan

memberikan perhatian dan melibatkan diri pada kegiatan anggota keluarga yang lain. Suatu keluarga akan dinilai sehat apabila tingkat keterlibatannya cukup sedang saja, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak melibatkan diri.
Skala 6 : Pengendalian tingkah laku (Behavior Control/BC), yang menilai tentang bagaimana keluarga mengekspresikan serta mempertahankan tingkah laku-tingkah laku standard.
Skala 7 : Fungsi umum (General Functioning/GF), yang menilai keseluruhan dari fungsi keluarga baik yang sifatnya patologis maupun yang sehat, dan hal ini merupakan gabungan dari skala 1 sampai dengan skala 6.
Skor FAD berkisar antara 1,00 – 4,00; nilai rendah berarti sehat, sedangkan nilai tinggi berarti tidak sehat. Hasil penelitian reliabilitas pada uji ulang FAD menunjukkan nilai reliabilitas yang cukup tinggi ( alpha = 0,70). Sedang studi validitas FAD pada kelompok klinik dan non klinik menunjukkan perbedaan yang bermakna (p < 0,02). Sementara itu penggunaan FAD bersama-sama
dengan Locke Wallace Marital Satisfaction Scale memberikan hasil analisis yang sejajar. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini dicoba untuk mencari hubungan antara persepsi mengenai fungsi keluarga dengan kepatuhan berobat pasien-pasien URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya.
IV. 8. 3. Analisis dataData dikumpulkan dan diolah
secara deskriptif. Untuk membandingkan fungsi keluarga antara pasien patuh dan tidak patuh digunakan analisis statistik Mann-Whitney.
BAB VHASIL PENELITIAN
5.1 Gambaran Sampel Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Unit Rawat Jalan Program Terapi Rumatan Metadon RSU Dr. Soetomo Surabaya, mulai bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007. Dari data yang diperoleh pada periode waktu diatas, didapatkan 61 pasien yang memenuhi kriteria inklusi dengan rincian 31 pasien tidak patuh, dan 30 pasien patuh.
Patuh Tak patuh Total0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
20-24 thn25-29 thn30-34 thn>= 35 thn
Gambar 5.1 : Distribusi sampel berdasarkan umur
34

Patuh Tak patuh Total0
0.050.1
0.150.2
0.250.3
0.350.4
0.450.5
SDSLTPSLTAPT
Gambar 5.2 : Distribusi sampel berdasarkan pendidikan
Patuh Tak patuh Total0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
BekerjaTidak
Gambar 5.3 : Distribusi sampel berdasarkan pekerjaan
Patuh Tak patuh Total0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Masalah hukumTidak
Gambar 5.4 : Distribusi sampel berdasarkan keterlibatan dalam masalah hukum
35

Patuh Tak patuh Total0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
DisosialTidak
Gambar 5.5 : Distribusi sampel berdasarkan kepribadian disosial
Patuh Tak patuh Total0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
Mdh terpengaruhTdk mudahSeries3
Gambar 5.6 : Distribusi sampel berdasarkan mudah/tidaknya dipengaruhi
Patuh Tak patuh Total0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
PS baikPS jelekSeries3
Gambar 5.7 : Distribusi sampel berdasarkan Problem Solving keluarga
36

Patuh Tak patuh Total0.00%
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%
100.00%
Co baikCo jelekSeries3
Gambar 5.8 : Distribusi sampel berdasarkan Communication keluarga
Patuh Tak patuh Total0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
Ro baikRo jelekSeries3
Gambar 5.9 : Disribusi sampel berdasarkan Roles keluarga
Patuh Tak patuh Total0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
AR baikAR jelekSeries3
Gambar 5.10 : Distribusi sampel berdasarkan AR keluarga
37

Patuh Tak patuh Total0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
AI baikAI jelekSeries3
Gambar 5.11 : Distribusi sampel berdasarkan AI keluarga
Patuh Tak patuh Total0.00%
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%
BC baikBC jelekSeries3
Gambar 5.12 : Distribusi sampel berdasarkan BC keluarga
Patuh Tak patuh Total0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
GF baikGF jelekSeries3
Gambar 5.13 : Distribusi sampel bardasarkan GF keluarga
38

Patuh Tak patuh Total0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
FAD baikFAD jelekSeries3
Gambar 5.14 : Distribusi sampel berdasarkan FAD5.2 Analisis Hasil Penelitian Tabel 5.1 Uji homogenitas variabel penelitian
Kepatuhan
Variabel Tidak patuh
n=31
Patuh n=30
Harga p
Umur [rerata±SD] 27,8±5,6 27,1±3,2 0,549
Tingkat pendidikan 0,339
SD 1 (3,2) 0 (0,0)
SLTP 4 (12,9) 2 (6,7)
SLTA 15 (48,4) 15 (60,0)
PT 11 (35,5) 13 (43,3)
Bekerja 23 (74,2) 27 (90,0) 0,203
Menikah 11 (35,5) 8 (26,7) 0,641
Terlibat masalah hukum 19 (61,3) 13 (43,3) 0,251
Kepribadian disosial 19 (61,3) 13 (43,3) 0,251
Mudah dipengaruhi teman 18 (58,1) 19 (63,3) 0,874
Variabel umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, keterlibatan dalam masalah hukum dan kepribadian disosial merupakan variabel yang berpotensi sebagai variabel perancu terhadap kepatuhan pasien. Hasil uji homogenitas menunjukkan
bahwa tidak ada perbedaan bermakna semua variabel yang berpotensi sebagai variabel perancu terhadap kepatuhan (harga p>0,05). Oleh karena sudah homogen maka variabel tersebut di atas tidak dilibatkan dalam analisis selanjutnya (Tabel 5.1).
39

Tabel 5.2 : Fungsi keluarga terhadap kepatuhan pasien berobat di URJ PTRM
Kepatuhan
Fungsi keluarga Tidak patuh
n=31(%)
Patuh n=30 (%)
Harga p OR CI95%
Problem solving 0,252 2,08 0,74 – 5,81
Jelek 20 (64,5) 14 (46,7)
Baik 11 (35,5) 16 (53,3)
Communication <0,0001 45,00 5,39 – 375,67
Jelek 30 (96,8) 12 (40,0)
Baik 1 (3,2) 18 (60,0)
Roles <0,0001 20,80 5,61 – 77,10
Jelek 26 (83,9) 6 (20,0)
Baik 5 (16,1) 24 (80,0)
Affective Responsiveness 0,007 5,14 1,69 – 15,68
Jelek 24 (77,4) 12 (40,0)
Baik 7 (22,6) 18 (60,0)
Affective Involvement 0,001 8,03 2,55 – 25,31
Jelek 22 (71,0) 7 (23,3)
Baik 9 (29,0) 23 (76,7)
Behavior Control 0,035 4,50 1,25 – 16,17
Jelek 27 (97,1) 18(60,0)
Baik 4 (12,9) 12 (40,0)
General Functioning <0,0001 22,28 5,79 – 85,79
Jelek 24 (77,4) 4 (13,3)
Baik 7 (22,6) 26 (86,7)
Total Fungsi Keluarga <0,0001 4,44 2,50 – 7,87
Jelek 31 (100,0) 9 (30,0)
Baik 21 (70,0)
Hasil analisis statistik menunjukkan secara keseluruhan fungsi keluarga berhubungan dengan kepatuhan. Fungsi keluarga yang jelek berisiko terhadap ketidak patuhan sebesar 4,44 kali dibanding fungsi keluarga yang baik. Dari ketujuh sub-variabel peran keluarga, hanya problem solving yang tidak berhubungan dengan kepatuhan. Komunikasi, fungsi umum dan peran merupakan faktor risiko yang dominan sedangkan keterlibatan afektif, respon afektif
dan pengendalian tingkah laku bukan faktor risiko yang dominan.
BAB VIPEMBAHASAN
Penelitian ini adalah studi analitik observasional dengan bentuk cross-sectional yang dirancang untuk menjelaskan hubungan antara persepsi fungsi keluarga dengan kepatuhan berobat pasien-pasien ketergantungan opioid di Unit Rawat Jalan
40

Program Terapi Rumatan Metadon RSU Dr. Soetomo Surabaya (URJ PTRM RSDS). Sampel penelitian adalah pasien-pasien ketergantungan opioid di URJ PTRM RSDS yang memenuhi kriteria inklusi-eksklusi dan telah dengan sukarela menandatangani informed consent untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Cara pengambilan sampel adalah dengan cara systematic random sampling.
Berdasarkan distribusi umur didapatkan bahwa pengguna opioid paling banyak berusia 25-29 tahun (49,2%) (Gambar 5.1). Dari proporsi ini tampak bahwa usia terbanyak para pasien ketergantungan opioid yang berobat di URJ PTRM RSDS adalah usia-usia produktif. Untuk itu diperlukan penanganan yang eklektik holistik dan sedini mungkin untuk mencegah dampak negatif sosio-ekonominya baik bagi pasien, keluarga dan masyarakat. Kalau tidak, keadaan sosio-ekonomi yang buruk tersebut akan menurunkan kapasitas fungsi keluarga dan pada gilirannya akan meningkatkan risiko anggota keluarga untuk menggunakan NAPZA. Hal ini sesuai dengan penelitian Reinherz yang menyatakan bahwa keadaan sosio ekonomi yang rendah akan meningkatkan risiko penyalahgunaan NAPZA pada anak-anaknya.
Variabel umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, keterlibatan sampel dalam masalah hukum dan kepribadian disosial merupakan variabel yang berpotensi sebagai variabel perancu terhadap kepatuhan pasien. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna semua variabel yang berpotensi sebagai variabel perancu terhadap kepatuhan (harga p>0,05) (Tabel 5.1). Oleh karena sudah homogen maka variabel tersebut di atas tidak dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.
Skor FAD pada semua skala dalam penelitian ini didapatkan angka yang lebih tinggi pada kelompok sampel yang tidak patuh dibandingkan dengan kelompok sampel yang patuh.
Pada skala Pemecahan Masalah (Problem Solving), skor yang lebih tinggi memberikan kesan bahwa kemampuan keluarga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mengancam integritas dan kapasitas fungsional keluarganya kurang memadai.
Pada skala Komunikasi
(Communication), skor yang lebih tinggi memberikan kesan bahwa pertukaran informasi antar anggota keluarga terutama ditekankan pada kejelasan dari isi pesan-pesan verbal dan ditujukan langsung kepada siapa kurang memadai.
Pada skala Peran (Roles), skor yang lebih tinggi memberikan kesan bahwa kemampuan keluarga menetapkan pola tingkah laku dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga sehari-hari yang meliputi fungsi keluarga sebagai sumber penyediaan perbekalan, pendukung perkembangan individu, dan sebagainya kurang memadai.
Pada skala Respon Afektif (Affective Responsiveness), skor yang lebih tinggi memberikan kesan bahwa kemampuan keluarga dalam memberikan reaksi afektif yang sesuai terhadap berbagai macam rangsang kurang memadai atau kurang lemah lembut, kurang menunjukkan kasih sayang.
Pada skala Keterlibatan Afektif (Affective Involvement), skor yang lebih tinggi memberikan kesan bahwa kemampuan keluarga dalam memberikan perhatian dan melibatkan diri pada kegiatan anggota keluarga yang lain kurang atau berlebihan. Suatu keluarga akan dinilai sehat apabila tingkat keterlibatannya cukup sedang saja, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak melibatkan diri.
Pada skala Pengendalian Tingkah Laku (Behavior Control), skor yang lebih tinggi memberikan kesan bahwa kemampuan keluarga dalam mengekspresikan serta mempertahankan standard/batasan tingkah laku masing-masing anggota keluarga kurang memadai.
Pada skala Fungsi Umum (General Functioning), skor yang lebih tinggi memberikan kesan bahwa keseluruhan dari fungsi keluarga tersebut adalah kurang baik.
Skor FAD berkisar antara 1,00 – 4,00; nilai rendah berarti sehat, sedangkan nilai tinggi berarti tidak sehat. Hasil penelitian reliabilitas pada uji ulang FAD menunjukkan nilai reliabilitas yang cukup tinggi ( alpha = 0,70). Sedang studi validitas FAD pada kelompok klinik dan non klinik menunjukkan perbedaan yang bermakna ( p < 0,02 ). Sementara itu penggunaan FAD bersama-sama dengan Locke Wallace Marital Satisfaction Scale memberikan hasil analisis yang sejajar.
Dari hasil analisis statistik penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan
41

fungsi keluarga berhubungan secara bermakna dengan kepatuhan berobat pasien-pasien URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya. Fungsi keluarga yang jelek berisiko terhadap ketidak patuhan sebesar 4,44 kali dibanding fungsi keluarga yang baik (Tabel 5.2). Keadaan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hawari D, yang menyatakan bahwa ada hubungan antara penyalahgunaan NAPZA dengan fungsi keluarga, artinya makin buruk fungsi keluarga kemungkinan terjadi penyalahgunaan NAPZA semakin besar.
Dari ketujuh sub-variabel peran keluarga, hanya problem solving yang tidak berhubungan secara bermakna dengan kepatuhan sampel dalam berobat di URJ PTRM RSDS (Tabel 5.2). Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan referensi yang ada. Ketidaksesuaian ini kemungkinan disebabkan karena kurang optimalnya peneliti memberikan penjelasan mengenai maksud pertanyaan-pertanyaan dalam FAD yang terkait dengan skala 1 (problem solving) tersebut. Hal ini merupakan kekurangan dari penelitian ini. Situasi dan kondisi yang tenang serta waktu yang tidak terburu-buru akan berpengaruh terhadap hasil pengisian formulir FAD.
Komunikasi, fungsi umum dan peran merupakan faktor risiko yang dominan, sedangkan affective involvement, affective responsiveness dan behavior control bukan faktor risiko yang dominan. Diantara yang dominan komunikasi merupakan skala yang paling dominan/berpengaruh kepatuhan berobat pasien-pasien URJ PTRM RSDS. Hal ini sesuai dengan literatur dan berbagai penelitian terkait seperti yang dilakukan Stanton dan rekan-rekan yang menyatakan bahwa komunikasi yang baik dalam keluarga menurunkan tingkat ketidakpatuhan dari 44% menjadi 24%.
Penemuan dari studi ini diharapkan dapat dipakai sebagai data dasar penelitian serupa selanjutnya dan juga untuk peningkatan usaha program terapi rumatan metadon secara eklektik holistik khususnya di URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya baik saat ini maupun dimasa yang akan datang. Dengan diketahuinya bahwa faktor komunikasi keluarga adalah skala paling berpengaruh terhadap kepatuhan berobat pasien-pasien ketergantungan opioid (Tabel 5.2), maka hal ini dapat dipakai acuan dalam usaha meningkatkan efektifitas psikoterapi keluarga
sehingga meningkatkan pula kepatuhan dan keberhasilan proses PTRM khususnya di URJ PTRM RSDS.
Psikoterapi keluarga yang efektif adalah setiap intervensi yang dapat merubah interaksi dan komunikasi antar anggota keluarga sedemikan rupa sehingga memperbaiki fungsi keluarga sebagai unit dan fungsi anggotanya sebagai individu. Konsep dasar psikoterapi keluarga dimulai dengan melihat perilaku dan gangguan psikiatrik setiap anggota keluarga khususnya dalam konteks relasi dan komunikasi interpersonal dalam keluarga tersebut, untuk selanjutnya dilakukan intervensi sesuai dengan tujuan terapi tersebut.
Secara umum fungsi keluarga adalah sebagai suatu organisasi sosial, seperti yang dikatakan Nathan Ackerman:
”None of us lives this life alone. Those who try are foredoomed; they disintegrate as human beings. Some aspects of life experience are, to be sure, more individual than social, others more social than individual; but life nonetheless is a shared and sharing experience. In the early years this sharing occurs almost exclusively with members of our family. The family is the basic unit of growth and experience, fulfillment or failure. It is also the basic unit of illness and health”.Ciri-ciri keluarga sehat yang berfungsi
dengan baik antara lain adalah adanya relasi antar anggota yang hangat dan afektif, menerima dan menghargai aturan bersama yang secara explisit mengatur tingkah/perilaku (conduct) anggota keluarga, mampu menghadapi tantangan dan perubahan, komunikasi yang jelas, terbuka dan langsung antar anggota keluarga, toleransi terhadap konflik, dan adanya kebersamaan dalam menghadapi konflik yang timbul.
BAB VIIKESIMPULAN DAN SARANVII.1. Kesimpulan
Dari hasil pengamatan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :
Secara keseluruhan didapatkan per-bedaan yang bermakna dalam fungsi keluarga antara keluarga sampel yang patuh dibanding dengan yang tidak patuh. Dalam hal ini keluarga
42

sampel yang patuh menunjukkan fungsi keluarga yang lebih baik di-banding keluarga sampel yang tidak patuh.
Dari semua skala yang ada, skala 2 (komunikasi keluarga) menunjukkan skala yang paling berpengaruh te-rhadap kepatuhan pasien-pasien ke-tergantungan opioid yang berobat di URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Sur-abaya. Urutan berikutnya adalah peran, keterlibatan afektif, respon afektif, kontrol perilaku, dan ke-mampuan problem solving keluarga tersebut.
Dengan demikian hipotesis yang di-buat dalam penelitian ini dapat dite-rima yaitu bahwa : ‘Didapatkan hu-bungan antara disfungsi keluarga dengan kepatuhan berobat pasien-pasien ketergantungan opioid yang berobat di URJ PTRM RSU Dr. Soe-tomo Surabaya.
VII.2. SaranDalam usaha meningkatkan kepatuhan
berobat pasien-pasien ketergantungan opioid di URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya perlu dipikirkan usaha peningkatan kualitas fungsi keluarga mereka terutama pada skala/kemampuan komunikasi interpersonal masing-masing anggota keluarga tersebut, baik dengan cara edukasi dan informasi melalui media masa yang ada maupun dengan melakukan psikoterapi keluarga yang eklektik, holistik, efektif dan berkesinambungan langsung kepada keluarga para pasien tersebut. Untuk hal tersebut diperlukan adanya tambahan tenaga/sumber daya manusia baik tenaga profesional medis maupun non medis di URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya agar dapat melaksanakan program psikoterapi keluarga ataupun pelayanan lain dengan lebih optimal dan terpadu.
Selain itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan alat ukur atau aspek-aspek berpengaruh lain yang berbeda untuk melengkapi hasil penelitian yang sudah ada, sehingga menambah wawasan dalam menangani secara terpadu terhadap permasalahan ketidakpatuhan pasien-pasien ketergantungan opioid terutama yang berobat ke Unit Rawat Jalan Program Terapi Rumatan Metadon RSSU Dr. Soetomo Surabaya.
KEPUSTAKAAN
1. Atkison RM, Substance Abuse in Cummings JL, Textbook of Geriatric Neuropsychiatry, 2ed , American Psy-chiatric Press, Washington DC, 2000, 369, 388-390.
2. Badan NAPZA Nasional (BNN), 2004. Perkembangan Kasus Narkoba di Indonesia. Jakarta: 8-10.
3. Batki SL et al, Medication-Assisted Treatment For Opioid Addiction in opioid Treatment Programs, A Treat-ment Improvement Protocol 43, US Departement of Health and Human Services, 2005, 1-240.
4. Bigelow GE and Preston KL. 1995. Opioid. Dalam Bloom, Floyd E and Kupfer, David J. Psychopharmacol-ogy. New York : Raven Press. 1731-1743.
5. Buku Panduan URJ PTRM RSU Dr. Soetomo Surabaya, 2007.
6. Cami J and Farre M, Drug Addiction in The New England Journal of Medicine, Volume 349 : 975-986, Sep-tember 2003.
7. Clark W et al, Substance-Related Dis-orders: Alcohol & Drugs in Review in General Psychiatry, Goldman H, 5 ed, Lange Medical Books, New York, 2000, 215, 220.
8. Departemen Kesehatan RI, 2004. Pe-doman Terapi Pasien Ketergantungan NAPZA dan Zat Adiktif Lainnya. Jakarta : 23-29.
9. Fisher GL, Harrison TC, 1007. Sub-stance Abuse : Information for School Counselors, Social Workers, Thera-phists and Counselors. USA : Allyn & Bacon, 13-34.
10. Hapsari HI, Muljoharjono H, Haniman F, 2000. Persepsi Mengenai Fungsi Keluarga dari Penderita Ketergantun-gan NAPZA. Laporan Penelitian. Lab/SMF Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unair/RSUD Dr. Soetomo. Surabaya.
11. Hawari D, 2001. Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA. Jakarta : FK UI. 103-123.
12. Jaffe JH and Strain EC, Opioid-Re-lated Disorders in Kaplan and Sad-
43

docks, Comprehensive Textbook Psy-chiatry, 9 ed, Volume 1, 1265-1288.
13. Josephson, Allan M, MD, Family Therapy, Comprehensive Textbook of Psychiatry, Section Child Psychiatry: Psychiatric Treatment, Vol.II.
14. Josephson, Allan M., M.D., Family Therapy, Comprehensive Textbook of Psychiatry, Section Child Psychiatry: Psychiatric Treatment, Vol.II,
15. Kosten TR and George TP, Research Review - the Neurobiology of Opioid Dependence: Implication for Treat-ment, Yale University School of Medicine New Haven, July 2002.
16. Luty J, Treatment Preferences of Opi-ate-Dependent Patients, Psychiatric Bulletin (2004) 28 : 47-50 © 2004 The Royal College of Psychiatrists
17. Moesono A, 2003. Peran Keluarga dan Masyarakat sebagai Penangkal Penyalagunaan Narkoba. Dalam Penanggulangan Narkoba. Jakarta : FK UI. 49-58
18. NIDA, 2003. Stanton Duncan. Re-seacch, Beyond the Therapeutic Al-lianci : Keeping the Drug-Dependent Individual in Treatment. University of Rocherster School of Medicine and Dentistry, New York.
19. PPIKB/CME, 2002. Konsensus FKUI tentang Opiat, Masalah Medis dan Pe-natalaksanaannya. Jakarta : FK UI. 10—33.
20. Reinherz,HZ: General and Specific Child Risk Factors for Depression and Drug Disorders by Early Adulthood. Journal of American Academic of Child and Adolescent Psychiatry, Feb.2000,39(2):223-231.
21. Shovelar, G. Pirooz, M.D., Family Therapy, Textbook of Child and Ado-lescent Psychiatry, 3rd Edition, Edited by Jerry M.Wiener, M.D., Mina K.-Dulcan, M.D. the American Psychi-atric Publishing, 2004.
22. Shovelar, G. Pirooz, M.D., Family Therapy, Textbook of Child and Ado-lescent Psychiatry, 3rd Edition, Edited
by Jerry M.Wiener, M.D., Mina K.-Dulcan, M.D. the American Psychi-atric Publishing, 2004.
23. Sidney Bloch, Julian Hafner, Edwin Harari, and George I. Szmukler, The Fakily in Clinical Psychiatry, Oxford Medical Publications, Oxford Univer-sity Press, 1994.
24. Stanton D, The Role of Family and Significant Others in the Engagement and Retention of Drug-Dependent In-dividuals, at Spalding University in Louisville, Published 12/27/2005
25. Vocci FJ et al, Medication Develop-ment for Addictive Disorders : The State of the Science, American Journal Psychiatry 162 : 1432-1440, August 2005.
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NEONATUS DISMATUR
Anna Lewi Santoso
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
44

ABSTRAK“Neonatus Dismatur” atau insufisiensi plasenta adalah suatu komplikasi yang terjadi pada kehamilan di
mana plasenta mengalami gangguan atau hambatan sehingga bayi yang di dalam kandungan tidak dapat cukup oksigen dan nutrisi, karena hal itu, maka bayi mengalami gangguan pertumbuhan. Plasenta adalah organ yang sangat penting dalan perkembangan tumbuh kembang bayi dalam kandungan, nama lain dari insufisiensi plasenta aadalah disfungsi plasenta. Penyebab terjadinya neonatus dismatur bisa di karenakan penyakit yang di derita ibu ( diabetes melitus, hipertensi ), kebiasaan ibu ( merokok ). Bisa di karenakan plasenta tidak dapat berkembang dengan baik, bila bayi kembar, atau plasenta tidak melekat erat pada dinding rahim, karena terlepas atau ada bekuan darah.
Kata kunci : kekurangan oksigen dan nutrisi, keadaan dan tingkah laku, tidak melekat erat.
PREVENTION AND RESPONSE NEONATES DISMATUR
Anna Levi Santoso
Lecturer Faculty of Medicine, University of Wijaya Kusuma Surabaya
ABSTRACT“Neonatus Dismatur” or Placental insufficiency is a complication of pregnancy in which the placenta
cannot bring enough oxygen and nutrients to a baby growing in the womb. The placenta is the organ that develops during pregnancy to feed a developing baby, is also by name “placental dysfunction”. Causes by certain medical conditions and habits in the mother can lead to placental insufficiency, for example: Diabetes, high blood pressure, smoking. In same case, the placenta may not grow big enough, expecially if you are carrying twins or more. Placental insufficiency may also accur if the placenta does not attach correctly to the surface of the womb, or if it breaks away from this surface or bleeds.
Key words: insufficiency oxygen and nutrients, conditions and habits, not attach correctly.
PENDAHULUANNeonatus Dismatur adalah bayi baru
lahir yang berat badan waktu lahirnya kurang dibandingkan dengan berat badan seharusnya untuk masa gestasi bayi itu, nama lain untuk neonatus dismatur adalah Kecil Masa Kehamilan ( KMK ) (1,3,5,6)
Pada umumnya neonatus dismatur mengalami retardasi pertumbuhan intra uterin, kasus neonatus dismatur paling banyak ditemukan pada golongan sosial ekonomi rendah, bentuk ibu yang kecil, adanya komplikasi kehamilan, kelainan kromosom dan kelainan bawaan pada fetus, bisa juga dikarenakan kehamilan multipara dan ibu yang merokok.(2,3,5,6)
Dismaturitas dapat terjadi “preterm”, “term”, atau “postterm”. Nama lain yang sering digunakan juga adalah insufisiensi plasenta. Untuk dismaturitas “postterm” sering disebut “postmaturity”. Penyebab dismaturitas adalah setiap keadaan yang mengganggu pertukaran zat antara ibu dan janin.(1,3)
Untuk mengetahui adanya dismaturitas, diperlukan perhitungan umur gestasi yang tepat. Karena itu penting untuk penatalaksanaan neonatus dismatur dan membedakan dengan neonatus prematur.(1,3,4,5,8)
Tujuan dari penyusunan jurnal ini, agar kita dapat lebih waspada akan adanya neonatus dismatur dan dapat melakukan perawatan dan mencegah terjadinya komplikasi pada neonatus dismatur.
Neonatus dismatur adalah bayi lahir yang berat badan lahirnya kurang dibandingkan dengan berat badan seharusnya untuk masa gestasi bayi itu.(1,3,5,8)
Pengertian berat badan kurang dari berat badan lahir yang seharusnya untuk masa gestasi tertentu adalah kalau berat badan lahirnya di bawah persentil 10 menurut kurva pertumbuhan intra uterin “Lubchenco” atau di bawah 2SD menurut kurva pertumbuhan intrauterin “Usher” dan “McLean”.(1,3,8) Nama lain yang sering digunakan adalah kecil untuk masa kehamilan ( KMK ), insufisiensi plasenta.(1,3,8)
Neonatus dismatur merupakan bagian dari Bayi Berat Lahir Rendah ( BBLR ). Bayi Berat Lahir Rendah adalah: bayi baru lahir yang berat badan lahirnya pada saat kelahirannya kurang dari 2.500 gram ( sampai dengan 2.499 gram ). BBLR dibagi menjadi dua golongan yaitu Prematuritas murni, dengan batasan masa gestasinya kurang dari 37 minggu dan berat
45

badannya sesuai dengan berat badan untuk masa gestasi itu atau biasa disebut neonatus kurang bulan sesuai untuk masa kehamilan ( NKB-SMK).Dan Dismaturitas, adalah bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan seharusnya untuk masa gestasi itu. Berarti bayi mengalami retardasi pertumbuhan intra uterin dan merupakan bayi yang kecil untuk masa kehamilan ( KMK ). (1,3,8)
Insidens untuk BBLR mulai 1985 : 6,7%, insiden ini dicatat di USA, dan rata-rata menurun 14% sejak 1970 dibandingkan dengan 50% penurunan infant mortality rate.Mendekati 30% BBLR di USA adalah retardasi intra uterin yang berumur lebih dari 37 minggu. BBLR meningkat lebih besar 10% dengan pembagian, dismaturitas meningkat dan prematuritas menurun. Pada negara berkembang, dismaturitas mendekati 70%. Neonatus dismatur memiliki angka kesakitan dan kematian yang lebih besar dibandingkan dengan neonatus yang berat badan sesuai masa kehamilan. (3)
Keadaan-keadaan yang merupakan predisposisi gangguan pada besarnya janin:1. Ibu yang kecil. Karena faktor genetik, maka seorang ibu yang kecil biasanya mempunyai bayi yang kecil. Pada keadaan di mana ibunya kecil, kelahiran bayi yang beratnya ditentukan secara genetik berada di bawah rata-rata populasi, tidak perlu merupakan hal yang merisaukan. (3,5,6)
2. Pertambahan berat yang jelek pada ibu. Bila ibu mempunyai berat badan rata-rata atau lebih kecil, kegagalan pertambahan berat badan atau terhentinya pertambahan berat badan selama trimester kedua kehamilan kemungkinan disebabkan bayi yang terhambat pertumbuhannya. Pada umumnya bila kalori dibatasi 1500 setiap hari selama beberapa waktu, akan menyebabkan hambatan pertumbuhan janin yang nyata. (3,5,6,7,8)
3. Penyakit vaskuler.Penyakit vaskuler yang kronis, terutama bila juga mengalami komplikasi superimposed-preeklampsia dan proteinuria, biasanya menyebabkan hambatan pertumbuhan. Hipertensi akibat kehamilan yang terjadi pada akhir kehamilan tanpa penyakit vaskuler kronis atau penyakit ginjal yang mendasarinya, biasanya tidak menyebabkan hambatan pertumbuhan janin yang nyata. (2,3,5,6,7,8)
4. Penyakit ginjal kronisPenyakit ginjal kronis dengan penurunan klirens ginjal biasanya disertai dengan
hambatan pertumbuhan janin. (3,5,6,8)
5. Hipoksia kronisJanin pada ibu yang tinggal pada tempat yang tinggi seringkali mempunyai berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah yang lebih rendah. Demikian pula janin pada wanita dengan penyakit jantung sianotik dan insufisiensi paru. (3,5,8)
6. Anemia ibu.Konsentrasi haemoglobin ibu yang rendah berpengaruh pada terjadinya hambatan pertumbuhan janin. Tetapi biasanya hanya terjadi pada janin dengan ibu yang menderita penyakit anemia sel bulan sabit atau anemia yang disebabkan penyakit ibu yang berat. (3,5,8)
7. Merokok.Merokok tembakau mengganggu pertumbuhan janin, lebih banyak sigaret yang dihisap, makin besar gangguan tersebut. (2,3,5,6,8)
8. Obat-obat keras.Pemakaian heroin dan hampir dipastikan obat-obat keras lainnya pada waktu hamil mengganggu pertumbuhan janin. (2,3,5,8)
9. Konsumsi kronis alkohol dalam jumlah besar oleh ibu pada waktu hamil menyebabkan hambatan pertumbuhan janin, seringkali disertai malformasi fisik dan gangguan intelektual di kemudian hari. (2,3,5,8)
10. Kelainan plasenta dan tali pusat.Lesi plasenta termasuk solutio plasenta fokal yang kronis, infark yang luas, atau chorioangioma, dapat menyebabkan semakin besar resiko pertumbuhan janin terhambat. Suatu plasenta sirkumvalata atau plasenta previa dapat mengganggu pertumbuhan tetapi biasanya janin tidak jauh lebih kecil daripada normal. Tali pusat dengan insertio marginalis dan terutama insertio velamentosa sering disertai dengan janin yang pertumbuhannya terhambat. (3,5)
11. Janin multipel.Adanya dua atau lebih janin dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan salah satu atau kedua janin bila dibandingkan dengan kehamilan tunggal. (3,5,8)
12. Infeksi janin.Penyakit virus cythomegalo, virus rubella dan mungkin penyakit infeksi kronis janin yang lain dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan yang berat. (2,3,5,6,8)
13. Malformasi janin.Pada umumnya makin berat malformasi, makin besar kemungkinan janin menjadi kecil untuk masa kehamilan. Hal ini terutama nyata
46

pada janin dengan kelainan kromosom atau dengan malformasi kardiovaskuler yang berat. (2,3,5,8)
14. Kahamilan extra uterin.Biasanya janin yang tidak berada dalam uterus akan mengalami hambatan pertumbuhan ( dismaturitas ). (3,5)
Faktor-faktor penyebab diatas memungkinkan terdapatnya neonatus dismatur. Hal ini dapat terjadi karena fungsi plasenta yang insufisiensi sebagai akibat gangguan perfusi maternal maupun terhalangnya fungsi plasenta atau keduanya. (3,5,8) Juga dapat menyebabkan kelainan denyut jantung janin dan adanya mekonium di dalam cairan amnion, yang disebut distress janin. (3,5)
Cairan amnion yang minimal tanpa bukti adanya pecah selaput janin merupakan tanda yang membahayakan, tak peduli kapan hal tersebut ditemukan pada kehamilan. Keadaan tersebut sering dijumpai pada kasus hambatan pertumbuhan yang berat, dimana janin terhambat pertumbuhannya karena faktor ibu. Bukti yang nyata tentang adanya oligohidramnion dan adanya tanda lain mengenai hambatan pertumbuhan yaitu:dengan menghitung perkiraan umur gestasi yang teliti dan evaluasi besar uterus secara konsisten pada waktu kunjungan-kunjungan antenatal (3,5,8)
Dismaturitas dapat terjadi “preterm”, “term”, “postterm”. Pada “preterm” akan terlihat gejala fisik bayi prematur murni ditambah dengan gejala dismaturitas. Dalam hal ini berat badan kurang dari 2.500 gram, karakteristik fisik sama dengan bayi prematur dan mungkin ditambah dengan retardasi pertumbuhan dan wasting. Pada bayi cukup bulan dengan dismaturitas, gejala yang menonjol adalah wasting, demikian pula pada “postterm” dengan dismaturitas. (1,3,6)
Gruenwald ( 1967 ) mengatakan bahwa tidak semua kekurangan makanan pada janin diakibatkan oleh insufisiensi plasenta. Gejala insufisiensi plasenta timbulnya tergantung pada berat dan lamanya bayi menderita defisit. Menurut Gruenwald defisit yang menyebabkan retardasi pertumbuhan biasanya berlangsung kronis. Menurut sarjana tersebut, sebagai akibat defisit itu akan terjadi fetal distress. (1,3,8)
Dalam arti luas fetal distress dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :
1. Acute fetal distress yaitu defisit atau fetal deprivation yang hanya
mengakibatkan perinatal distress tetapi tidak mengakibatkan retardasi pertumbuhan dan wasting.
2. Subacute fetal distress yaitu bila fetal deprivation tersebut menunjukan tanda wasting tetapi tidak retardasi pertumbuhan.
3. Chronic fetal distress yaitu bila bayi jelas menunjukkan retardasi pertumbuhan. (1,3)
Bayi dismatur dengan tanda wasting atau insufisiensi plasenta dapat dibagi dalam tiga ( 3 ) stadium menurut berat ringannya wasting tersebut ( clifford ) yaitu:
1. Stadium pertama: Bayi tampak kurus dan relatif lebih panjang, kulitnya longgar, kering seperti perkamen tetapi belum terdapat noda mekonium.
2. Stadium kedua: Didapatkan tanda stadium pertama ditambah dengan warna kehijauan pada kulit, plasenta dan umbilikus. Hal ini disebabkan oleh mekonium yang tercampur dalam amnion yang kemudian mengendap ke dalam kulit, umbilikus dan plasenta sebagai akibat anoksia intrauterin.
3. Stadium ketiga: Ditemukan tanda stadium kedua ditambah dengan kulit yang berwarna kuning, demikian pula kuku dan tali pusat. Ditemukan juga tanda anoksia intra uterin yang lama. (1,3)
Identifikasi melalui pengambilan riwayat penderita yang teliti, tentang adanya faktor-faktor etiologi merupakan predisposisi gangguan pertumbuhan janin. Selain itu, perkiraan umur gestasi yang teliti dan evaluasi besar uterus secara konsisten pada waktu kunjungan antenatal, dalam banyak hal akan menemukan adanya hambatan janin. (3,5)
Pengukuran tinggi fundus uteri harus didukung dengan pemeriksaan sonografi, dimana ditemukan:
Hambatan pertumbuhan simetris, terdapat menyeluruh, termasuk kepala.
Hambatan pertumbuhan asimetris, dimana kepala tidak ikut serta. (3,5)
Untuk bayi yang baru lahir perlu diketahui dengan tepat lamanya masa gestasi untuk menentukan maturitas bayi tersebut. Ada beberapa cara untuk menaksir umur atau lamanya masa gestasi bayi pada saat bayi
47

dilahirkan.Cara yang sampai sekarang digunakan ialah1.Perhitungan “hari pertama haid terakhir” ( HPHT )Biasanya masih ada kesalahan ± 1 minggu, karena selalu ada variasi waktu antara HPHT dan ovulasi, kemungkinan terjadi “time log” antara koitus yang menyebabkan kehamilan dan ovulasi atau antara ovulasi dan koitus. (1,3,4,5,8)
2. Penilaian ukuran antropometrik :A. Berat badan lahir ( BBL )BBL merupakan indeks yang terburuk untuk menentukan masa gestasi neonatus. Hal ini disebabkan BBL sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. BBL kurang atau sama dengan 2.500 gram tidak dapat dipandang sebagai unit yang homogen. Bayi BBLR dapat merupakan bayi prematur murni atau dismatur. Jadi lama masa gestasi untuk BBLR sangat bervariasi.(1,3,4,5,6,8)
B. Crown heel lengthLingkaran kepala, diameter oksipito-frontal, diameter bipariental dan panjang badan. Menurut Finnstrom ( 1971 ), dari semua ukuran tersebut di atas hanya ukuran lingkaran kepala yang mempunyai korelasi yang baik dengan lamanya masa gestasi. Untuk ini ia menemukan “confidence limit” kira-kira 26,1 hari. (1) Selain itu ia mengajukan rumus sebagai berikut:Y = 11,03 + 7,75xY = masa gestasix = lingkaran kepala.
3. Pemeriksaan radiologisDengan pemeriksaan ini dapat
diketahui lamanya masa gestasi dengan meneliti pusat epifisis. (1,3,4,5)
4. “Motor conduction velocity”
Pemeriksaan ini adalah dengan mengukur “motor conduction velocity” dari nervus ulnaris. (1,3,4,5)
5. Pemeriksaan elektro ensefalogram ( EEG ). (1,3,4,5)
6. Penilaian karakteristik fisik luar dari beberapa alat tubuh ternyata mempunyai hubungan dengan maturitas bayi. Dari semua kriteria external yang dapat dinilai untuk menentukan masa gestasi neonatus, kriteria yang disebutkan di bawah ini adalah yang terbaik mempunyai hubungan dengan masa gestasi. Kriteria tersebut adalah bentuk puting susu, ukuran payudara, “plantar creases”, rambut kepala, transparansi kulit, membran pupil, alat kelamin, kuku dan tulang rawan telinga.Hasil penelitian kriteria external ini bervariasi, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, beberapa sarjana mengadakan skor terhadap kriteria external ini dan korelasi antara skor dengan masa gestasinya. Lihat tabel 1. (1,3,4,5)
7. Penilaian Kriteria NeurologisTelah lama diketahui bahwa beberapa kriteria neurologis atau reflek tertentu baru timbul pada suatu masa gestasi. Cara penilaian masa gestasi dengan kriteria external dan neurologis merupakan maturitas yang paling mendekati kebenaran. Kombinasi penilaian karakteristik external, kriteria neurologis dan lingkaran kepala adalah cara yang paling mendekati kebenaran. Lihat tabel 2. (1,3,4,5)
8. Penilaian menurut DubowitzMenggabungkan hasil penilaian fisik
external dan neurologis. Kriteria neurologis diberikan skor, demikian pula kriteria fisik external. Jumlah skor fisik dan neurologis dipadukan, kemudian dengan menggunakan grafik linier dicari masa gestasinya. Lihat tabel 3. (1,3,4,5,8)
48

TABEL 1: HUBUNGAN ANTARA MASA GESTASI DAN BEBERAPA KRITERIA EXTERNA PADA BAYI BARU LAHIR.
Kriteria Masa gestasi
Sampai 36 minggu 37-38 minggu 39 minggu
Plantar Creases Bagian anterior: hanya ada transverse creases
Meliputi 2/3 anterior Seluruh telapak kaki
Diameter nodul mammae
2mm 4mm 7mm
Rambut kepala Halus Halus Kasar
Daun telinga Lentur, tidak bertulang rawan Sedikit tulang rawan Kaku, tulang rawan tebal
Testis dan scrotum Testis di kanal bawah. Scrotum kecil, ruga sedikit
Intermedia Testis pendulum. Scrotum penuh, ruga extensif
TABEL 2 : KRITERIA NEUROLOGIS UNTUK MENENTUKAN MATURASI NEONATUS
24 minggu 28 minggu 32 minggu 34 minggu 37 minggu 41 minggu
Posisi Lateral dekubitus
Extensi total (hipotoni)
E.A:extensiE.B:tonus meningkat
E.A:extensiE.B:flexi (frog)
Fleksi pd E.A dan E.B
Flexi total
Popliteal angle 180 0 180 0 180 0 120 0 90 0 90 0
Head to ear manouvre
Tanpa tahanan
Tanpa tahanan
Sedikit tahanan
Susah Hampir tidak mungkin
Tidak mungkin
Berjalan otomatik
0 0 0 Minimal Jalan pada ujung jari
Jalan pada tumit
Reflek Moro Belum jelas Lemah Baik Baik Baik Baik
Reflek menghisap
Lemah Lemah Lemah Lemah Baik Baik
Reflek cahaya pupil
- 29 minggu (+)
(+) (+) (+) (+)
Glabellar tap reflek
- - (+) (+) (+) (+)
Neck traction reflek
- - - (+) (+) (+)
Neck righting reflek
- - - (+) (+) (+)
Head turning to light
- - - (+) (+) (+)
E.A = Extremitas Atas E.B = Extremitas Bawah
TABEL 3: KRITERIA FISIK LUAR
KRITERIA S K O R
0 1 2 3 4
Edema - edema jelas pada tangan dan kaki
Edema tidak jelas pada tangan dan kaki
Tanpa edema - -
49

-Pretibia: 'Piting' Pretibia: piting
Jaringan kulit Tipis sekali seperti gelatin
Tipis dan licin Licin, sedikit menebal terdapat erupsi kecil atau mengelupasan
-Penebalan sedang-Pecah-pecah supefisial-Pengelupasan terutama tangan + kaki
-Tebal dan kering-Terdapat pecahan superfisial dan dalam
Warna kulit Merah Merah muda menyeluruh
Merah muda pucat, bervariasi pada seluruh tubuh
Pucat, hanya merah muda pada telinga, bibir, telapak tangan dan kaki
-
Dibawah kulit Terlihat banyak vena, besar-kecil, terutama didinding perut
Terlihat vena dan cabang-cabangnya
Beberapa pembuluh besar jelas terlihat pada dinding abdomen
Beberapa pembuluh darah besar samar terlihat pada dinding abdomen
Tidak terlihat pembuluh darah
Lanugo (dipunggung) Tidak ada Banyak:panjang dan tebal diseluruh punggung
Rambut menipis terutama pada punggung bawah
Terdapat sedikit lanugo dan daerah tak berambut
Kira-kira setengah dari punggung tidak ada lanugo
Garisan telapak kaki Tidak terdapat garisan
Pada ½ anterior telapak kaki ada garis merah yang samar-samar
Garis merah yg jelas pada lebih ½ anterior indentasi pd 1/3 anterior
Indentasi pada lebih 1/3 anterior
Indentasi jelas dalam pada > 1/3 anterior
Perkembangan puting susu
Puting baru terlihat samar-samar tanpa areola
Puting berbatas tegas, areola licin dan datar, diameter < 0,75cm
Areola bertitik-titik pinggir datar, diameter < 0,75cm
Areola bertitik-titik, pinggir tinggi. Diameter < 0,75cm
-
Besarnya mammae Tidak teraba jaringan mammae
Teraba jaringan mammae pada satu atau dua sisi, diameter < 0,5cm
Jaringan mammae pada dua sisi, diameter 0,5-1,0cm
Jaringan mammae pada kedua sisi, diameter1cm.Lipatan pada pinggiran
-
Bentuk telinga Pinna datar, tidak berbentuk. Tidak ada lipatan atau sangat sedikit
Terdapat lipatan pada sebagian tepi pinna
Pelipatan tak sempurna pada semua pinna bagian atas
Pelipatan yang jelas pada semua pinna bagian atas
-
Elastisitas telinga Pinna lembek, mudah dilipat, rekoil (-)
Pinna lembek, mudah dilipat, rekoil-pelan
Terdapat tulang rawan pada pinggir pinna. Bagian lain lembek. Rekoil-baik
Pinna keras, tulang rawan pada pinggiran, rekoil-cepat
-
50

Genetalia pria Desensus testis (-)
Sekurang-kurangnya satu testis masih tinggi pada scrotum
Sekurang-kurangnya satu testis turun dengan baik
- -
Genetalia wanita Labia mayora terbuka lebar, labia minora menonjol
Labia mayora hampir menutupi labia minora
Labia mayora menutupi seluruh labia minora
- -
Bila sudah didiagnosa neonatus dismatur, perlu antisipasi terhadap komplikasi yang mungkin timbul pada bayi tersebut. Adapun komplikasi yang dapat terjadi adalah sebagai berikut.1. Sindrom aspirasi mekonium
Kesulitan pernapasan yang sering ditemukan pada bayi dismatur adalah sindrom aspirasi mekonium. Keadaan hipoksia intra uterin akan mengakibatkan janin mengadakan gasping dalam uterus. Selain itu mekonium akan dilepaskan ke dalam likuor amnion seperti yang sering terjadi pada subacute fetal distress. Akibatnya cairan yang mengandung mekonium yang lengket itu masuk ke dalam paru janin karena inhalasi. Pada saat lahir bayi akan menderita gangguan pernapasan yang sangat menyerupai sindrom gangguan pernapasan idiopatik. Pengobatannya sama dengan pengobatan sindrom gangguan pernapasan idiopatik di tambah dengan pemberian antibiotik. (1,3,4,6,8)
2. Hipoglikemia simptomatikKeadaan ini terutama terdapat pada
bayi laki-laki. Penyebabnya belum jelas, tetapi mungkin sekali disebabkan oleh persediaan glikogen yang sangat kurang pada bayi dismaturitas. Gejala klinisnya tidak khas, tetapi umumnya mula-mula bayi tidak menunjukkan gejala, kemudian dapat terjadi Jitteriness ( tampak seperti kaget ), twitching, serangan apneu, sianosis, pucat, tidak mau minum, lemas, apatis dan kejang ( fit ). Diagnosa dapat digunakan dengan melakukan pemeriksaan gula darah. Bayi cukup bulan dinyatakan menderita hipoglikemia bila kadar gula darahnya kurang dari 30mg %
Sedangkan bayi BBLR bila kadar gula darahnya kurang dari 20mg%. Pengobatannya adalah dengan menyuntikkan glukosa 20%, 4 ml/kgBB, kemudian disusul dengan pemberian infus glukosa 10%. (1,2,3,6,7,8,10)
3. Asfiksia neonatorumBayi dismatur lebih sering menderita
asfiksia neonatorum dibandingkan dengan bayi normal. (1,2,3,6,8,9,10)
4. Penyakit membran hialin.Penyakit ini terutama mengenai bayi
dismatur yang preterm. Hal ini karena surfaktan paru belum cukup sehingga alveoli selalu kolaps. Sesudah bayi mengadakan inspirasi, tidak tertinggal udara residu dalam alveoli, sehingga selalu dibutuhkan tenaga negatif yang tinggi pada pernapasan berikutnya. Akibatnya akan tampak dispneu yang berat, retraksi epigastrium, sianosis dan pada paru terjadi atelektasis dan akhirnya terjadi eksudasi fibrin dan lain-lain serta terbentuknya membran hialin. Penyakit ini dapat mengenai bayi dismatur yang preterm, terutama bila masa gestasinya kurang daripada 35 minggu. (1,3,4,6,7,8,9)
5. HiperbilirubinemiaBayi dismatur lebih sering mendapat
hiperbilirubinemia dibandingkan dengan bayi yang sesuai dengan masa kehamilannya. Hal ini mungkin disebabkan gangguan pertumbuhan hati. Menurut Gruenwald, hati pada bayi dismatur beratnya kurang dibandingkan dengan bayi biasa. (1,2,3,4,6,7,8,10)
6. InfeksiPerkembangan sistem imun belum
lengkap maka bayi dismatur lebih mudah terkena infeksi dibandingkan dengan bayi normal. (3,4,8,10)
Bayi dismatur biasanya aktif, reflek baik, menghisap secara aktif tampak haus dan harus diberikan makanan dini ( early feeding ). Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya hipoglikemia. Maka untuk penatalaksanaan bayi dismatur adalah : kadar gula darah harus diperiksa setiap 8 – 12 jam. Sebaiknya sebelum dilakukan pemeriksaan “true glukosa” dilakukan lebih dahulu pemeriksaan penyaring dengan dextrostix. Jika dengan cara ini ternyata kadar glukosa 45 mg
51

% atau kurang, harus dilakukan pemeriksaan “true glukosa”. (1,2,3,8) Frekwensi pernapasan terutama dalam 24 jam pertama selalu harus diawasi untuk mengetahui adanya sindrom aspirasi mekonium atau sindrom gangguan pernapasan idiopatik. Sebaiknya setiap jam dihitung frekwensi pernapasan dan bila frekwensi pernapasan lebih dari 60x/mnt dibuat foto thorax. (1,2,3,8) Pencegahan terhadap infeksi sangat penting, karena bayi sangat rentan terhadap infeksi, yaitu karena pemindahan IgG dari ibu ke janin terganggu. (1,2,3,8)
Temperatur harus dikelola, jangan sampai kedinginan karena bayi dismatur lebih mudah menjadi hipotermik. Hal ini disebabkan oleh karena luas permukaan tubuh bayi relatif lebih besar dan jaringan lemak subkutan kurang. (1,3,8)
Harus waspada pula terhadap kelainan kongenital dibandingkan dengan bayi normal. Pentingnya membedakan bayi dismatur dengan bayi prematur murni.Bayi BBLR seperti telah diuraikan, dapat berupa bayi prematur murni atau bayi dismatur.Hal ini sangat penting dibedakan karena:
1. Morbiditas yang berlainan, misalnya prematuritas murni mudah menderita komplikasi seperti membran hialin, pendarahan intraventrikular, pneumonia aspirasi.
2. Bayi dismatur mudah menderita sindrom aspirasi mekonium, hipoglikemia simptomatik dan hiperbilirubinemia.
3. Pada bayi dismatur yang preterm, dengan sendirinya komplikasi bayi prematuritas murni juga dapat terjadi.
4. Membedakan hal ini penting pula sebab bayi dismatur harus mendapat makanan dini daripada bayi permatur. (1,3)
Dasar perawatan yang penting1. Pengawasan dan perawatan khusus in
utero ( waktu hamil dan selama persalinan.1. Nutrisi dan keseimbangan cairan
dan elektrolit ibu harus dijaga baik agar fungsi plasenta terjamin.
2. Obat-obatan pada ibu harus diperhatikan betul sehingga dengan masuknya obat-obat itu
melalui plasenta ke janin, terutama obat-obat sedativa, harus kita awasi. Mengingat rapuhnya tubuh bayi dismatur, harus dihindari/dibatasi trauma waktu persalinan dengan episiotomi, dan sebagainya. “Minimal handling” juga harus diterapkan pada bayi itu setelah kelahirannya. (3,8)
2. Pernapasan harus segera dibenahiBayi dismatur sering
dilahirkan dalam keadaan asfiksia. Menjadi prioritas untuk segera resusitasi. (1,3,8)
3. Pertahanan suhu tubuh.Bayi dismatur sukar
mempertahankan suhu tubuhnya, mudah hipotermia.Untuk itu perlu dilakukan :
Segera setelah lahir bayi dikeringkan dan dibungkus dengan selimut yang telah dihangatkan. Jangan dimandikan terutama bila lahir dalam keadaan asfiksia.
Masukkan bayi dalam inkubator atau perhatikan suhu bayi secara berkala. (1,3,8)
4. Berikan nutrisi yang sesuai puasa 2-3 jam. Frekwensi pemberian minum per os
BBL kurang dari 1250 gram : 24 x minum/hr
BBL 1250-2000 gram : 12 x minum/hr
BBL lebih dari 2000 gram : 8 x minum/hr
Jumlah cairan : Hari I : 60 cc/kg/24 jam Hari II : 90 cc/kg/24 jam Hari III : 120 cc/kg/24 jam Hari IV : 150 cc/kg/24 jam
Kemudian ditambah sedikit-sedikit setiap hari sampai mencapai 180-200 cc/kg/24 jam pada waktu bayi berumur 10-12 hari.
Kalori : 67-75 cal/100 cc Macam minuman:
ASI Humanized Milk
Pengenceran perlu untuk PASI terutama pada bayi dismatur dan menderita komplikasi, sebaiknya ditambah glukosa 5% agar kebutuhan kalori dapat dipenuhi. (8)
5. Cegah atau bertindak sedini mungkin semua penyulit yang timbul. (1,3,8)
6. Cegah infeksi dengan cara yang
52

aseptik.Mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang / memeriksa tiap bayi. (1,3,8)
Perkembangan selanjutnya bayi baru lahir yang mengalami hambatan pertumbuhan tidak dapat diramalkan berdasarkan ukuran-ukuran pada waktu lahir. Bayi yang kecil pada masa kehamilannya dapat menunjukkan berbagai variasi pertumbuhan pada waktu masa bayi dan masa anak. Hambatan pertumbuhan simetris, atau menyeluruh, yang lama dalam uterus biasanya diikuti pertumbuhan yang lambat setelah lahir, sedangkan janin yang mengalami hambatan pertumbuhan yang asimetris biasanya lebih dapat mengejar pertumbuhannya setelah lahir. Bayi yang panjang ( tinggi ) nya pada waktu lahir normal tetapi beratnya kurang dapat diharapkan akan tumbuh dengan normal. Bila panjangnya juga kurang, biasanya akan tetap kecil.
Kemampuan neurologik dan intelektual selanjutnya pada bayi yang mengalami hambatan pertumbuhan in utero tidak dapat diramalkan dengan tepat. Tetapi Fancourt dkk, mendapatkan bahwa pada anak yang terbukti secara sonografik pertumbuhan kepalanya lambat sejak sebelum trimester ketiga, perkembangan neurologik dan intelektual selanjutnya juga lambat. (3,5,8)
SimpulanNeonatus dismatur adalah bayi baru
lahir yang berat badan lahirnya kurang dibandingkan dengan berat badan seharusnya untuk masa gestasi bayi itu.
Insidens angka kesakitan dan kematian neonatus dismatur lebih besar dibandingkan neonatus yang berat badan sesuai masa kehamilan.
Faktor predisposisi untuk neonatus dismatur adalah ibu yang kecil, pertambahan berat yang jelak pada ibu, penyakit vaskuler, penyakit ginjal kronis, anemia ibu, merokok, obat-obat keras, konsumsi kronis alkohol dalam jumlah besar, kelainan plasenta dan tali pusat, janin multiple, infeksi janin, malformasi janin dan kehamilan extra uterin
Terjadinya neonatus dismatur disebabkan oleh fungsi plasenta yang insufisien sebagai akibat gangguan perfusi maternal maupun terhalangnya fungsi plasenta atau keduanya.
Gejala klinis ditentukan berdasarkan
stadium menurut berat ringannya wasting.Identifikasi melalui pengambilan
riwayat penderita yang teliti, perkiraan gestasi dapat mendiagnosis adanya neonatus dismatur.
Komplikasi yang dapat terjadi pada neonatus dismatur adalah sindrom aspirasi mekonium, hipoglikemia simptomatik, asphyxia neonatorum, penyakit membran hialin, hiperbilirubinemia.
Bayi dismatur harus diberikan makanan dini, untuk mencegah hipoglikemia, pengawasan frekwensi pernapasan untuk mencegah komplikasi, diperlukan juga pencegahan terhadap infeksi dan pengaturan suhu tubuh.
Perkembangan selanjutnya bayi baru lahir yang mengalami dismaturitas tidak dapat diramalkan berdasarkan ukuran-ukuran waktu lahir. Bayi yang kecil pada masa kahamilannya dapat menunjukkan berbagai variasi pertumbuhan pada waktu masa bayi dan masa anak.
Daftar pustaka
1. Abdoerachman. M. H., dkk, Perinatologi, dalam : Ilmu Kesehatan Anak, Editor : Hassan. R, Dr., dkk, jilid III, Jakarta : Percetakan infomedika Jakarta, 1985 : 1055 – 1065.
2. Damanik. S. M, Dr., dkk, Masa Perinatal, Titik Tolak Menuju Anak Sehat, dalam : Continuing Education Ilmu Kesehatan Anak, Editor : Sarwan. E, Dr., dkk, no 12, FK Unair / R. S. U. D Dr. Soetomo, Surabaya, Desember 1985 : 57 – 66.
3. Gotoff. S. P, The Fetus and The Neonatal Infant, dalam : Nelson Textbook of Pediatrics, Editor : Bralow. L., 14th ed, W. B. Sounders Company, Philadelphia, 1992 : 439 – 449.
4. Pernoll. M. J. B., The Infant, dalam : Handbook of Obstetrics and Gynecology, Editor : Govert. G., Bolger. G., P. P., 9th ed, Mc Growhill Inc., 1994 : 242 – 268.
5. Pritchard. J. A. M. D., eds, Kehamilan Preterm dan Postterm dan Hambatan Pertumbuhan Janin, dalam : Obstetrics Williams, Alih Bahasa : Hariadi. H, Prof. Dr., dkk, Edisi 17, Surabaya :
53

Airlangga University Press, 1991 : 869 – 889.
6. Rangkuti. S. M., dkk, Perinatal Mortality Rate dan Penyebab Kematian BBLR pada tahun 1978 di RS Dr. Pirngadi Medan, dalam, Majalah Obstetrics dan Gynecology Indonesia, vol 6, No 3 : Perkumpulan Obstetrics dan Gynecology Indonesia ( POGI ), Jakarta, Juli 1980 : 126 – 128.
7. Robie. G, eds, Newborn, dalam : Current Therapy in Obstetrics and Gynecology, Editor : Quilligan. E. J, M. D., W. B., Sounders Company, Philadelphia, 1980 : 77 – 90.
8. Sarwono. E., dkk, Bayi Berat Lahir Rendah, dalam : Continuing Education Ilmu Kesehatan Anak, Editor : Sarwono. E., Dr., dkk, No 6, FK Unair/ R. S. U. D Dr., Soetomo, Surabaya, Desember 1982 : 65 – 78.
9. Sarwono. E., Strategi Pendekatan Diagnosis pada Neonatus dengan Masalah Pernapasan, dalam : Continuing Education Ilmu Kesehatan Anak, Editor : Soegijanto. S., Prof. Dr. dr. DSAK, dkk, No 27, FK Unair/ R. S. U. D Dr., Soetomo, Surabaya, November 1997 : 63 – 78.
10. Sarwono. E., dkk, Neonatologi, dalam : Pedoman Diagnosis dan Terapi. Lab/ UPF Ilmu Kesehatan Anak, Editor : Soemarto. R., Prof. Dr., R. S. U. D. Dr. Soetomo, Surabaya, 1994 : 165 – 183.
PERBANDINGAN KEPEKAAN PEMERIKSAAN KUMAN BTA DARI DAHAK SPONTAN DENGAN DAHAK INDUKSI SALIN 0,9% PADA AKHIR TERAPI FASE
INTENSIF DOTSFarida A. Soetedjo
54

Bag/SMF Ilmu Penyakit Paru FK Unair – RSU Dr. Soetomo SurabayaDosen Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Abstrak Latar Belakang: Cara terbaik untuk mengevaluasi respon terapi pasien dengan TB paru adalah pemberantasan basil TB dari dahak pasien. Biasanya, pasien TB paru yang sudah mendapat satu bulan terapi OAT gejala batuk akan berkurang atau hilang. Jadi, pada akhir fase intensif akan ada masalah untuk mendapatkan spesimen dahak yang baik untuk memeriksa AFB, pasien tidak dapat menghasilkan dahak secara spontan karena tidak ada gejala batuk lagi. Seringkali spesimen hanya air liur, yang membuat sulit untuk mengevaluasi konversi BTA, apakah ada benar-benar sudah terjadi? induksi dahak adalah salah satu cara yang mudah, murah, dan non-invasif untuk mendapatkan spesimen dahak. Metode: Menjadi dilakukan pap AFB dahak pada akhir fase intensif dari spesimen dahak spontan (pasien yang diajarkan cara membuat batuk efektif dan fisioterapi dada), dan normal saline spesimen induksi dahak terhadap 35 pasien TB paru dengan BTA dahak BTA positif sebelum terapi, yang berada di bawah kendali terapi OAT di TB - DOTS klinik pasien rawat jalan RSU. Dr Soetomo Surabaya, mulai dari 31 Mei sampai 31 Agustus 2005. Hasil: hapusan BTA dari dahak spontan mendapatkan hasil yang negatif pada 34 sampel (97,1%), sedangkan induksi dahak normal saline mendapatkan pada 31 sampel (88,6%). Dengan menggunakan Mc. uji Nemar, tidak ada perbedaan yang signifikan (p> 0.05) antara dahak BTA spontan dan normal saline hasil induksi BTA. Empat BTA positif BTA dari spesimen dahak induksi saline normal dapat disebabkan oleh basil tuberkulosis mati, karena kita membuat budaya M. tuberculosis dari semua spesimen dahak induksi, dan hasilnya tidak ada pertumbuhan mikobakteri. Kesimpulan: Tidak ada peningkatan kepekaan signifikan antara pemeriksaan BTA dari dahak induksi saline normal dengan dahak spontan diajarkan oleh batuk efektif dan fisioterapi dada spesimen. Penggunaan 4 macam OAT (RHZE) selama dua bulan intensif membuktikan cukup potensial untuk membunuh M. tuberculosis yang dapat membuat konversi BTA dari positif ke negatif.
Kata kunci: BTA dahak, dahak spontan, induksi dahak
COMPARATION OF AFB SMEAR EXAMINATION SENSITIVITY FROM SPONTANEOUS SPUTUM AND NORMAL SALINE SPUTUM INDUCTION AT THE
END OF DOTS INTENSIVE PHASEFarida A. Soetedjo
Bag / SMF Airlangga University Faculty of Medicine Pulmonary Pathology - Dr. Soetomo
Lecturer Faculty of Medicine, University of Wijaya Kusuma SurabayaAbstractBackground: The best way to evaluate the therapeutic response of patient with pulmonary TB is the eradication of tuberculosis bacillus from patient’s sputum. Usually, pulmonary TB patient who has got one month OAT therapy the cough symptom will relieved or disappeared. So, at the end of intensive phase there will be a problem to get a good sputum specimen to examine the AFB, the patient can’t produce the sputum spontaneously because of no cough symptom anymore. Often the specimen is only saliva, that makes difficult to evaluate the conversion of AFB, is there really already happened ? Sputum induction is one of the easy, cheap, and non-invasive ways to get sputum specimen.Method: Being done the AFB sputum smear at the end of intensive phase from spontaneous sputum specimen (the patient being teached how to make effective cough and chest physiotherapy), and normal saline sputum induction specimen toward 35 pulmonary TB patients with positive AFB sputum smear before therapy, who are under control of OAT therapy in TB – DOTS outpatients clinic of RSU. Dr. Soetomo Surabaya, starting from 31st May until 31st August 2005. Result: AFB smear from spontaneous sputum get a negative result on 34 samples (97.1%), while normal saline sputum induction get on 31 samples (88.6%). By using Mc. Nemar test, there is no significance difference (p>0.05) between AFB spontaneous sputum and normal saline sputum induction smear results. Four positive AFB sputum smear from normal saline sputum induction specimens can cause by dead tuberculosis bacillus, because we made M. tuberculosis culture from all of the sputum induction specimens, and the result is no growth of mycobacteria. Conclusion: There is no increasing of significance sensitivity between AFB smear examination from normal saline sputum induction with spontaneous sputum teached by effective cough and chest physiotherapy specimens. The use of 4 kinds OAT (RHZE) for two months intensively prove potential enough to kill the M.
55

tuberculosis that can make AFB conversion from positive into negative.
Key word: AFB sputum smear, spontaneous sputum, sputum induction
PENDAHULUAN Penyakit tuberkulosis (TB) sampai saat ini tetap menjadi masalah di seluruh dunia. Setiap tahun, 8,74 juta orang menderita TB aktif dan sekitar 2 juta orang meninggal karenanya. Pada tahun 1993, WHO mencanangkan kedaruratan global penyakit TB karena pada sebagian besar negara di dunia penyakit TB tidak terkendali, ini ditunjukkan dengan banyaknya penderita yang tidak berhasil disembuhkan terutama penderita dengan BTA positif yang potensial menular. Lebih dari 90% kasus TB dan kematian akibat TB terjadi di negara berkembang, 75% penderita berada pada usia produktif (15 – 50 tahun) (Dep Kes RI, 2002; Kumaresan, 2002; Blanc, 2003). Indonesia merupakan penyumbang penderita TB terbesar ketiga di dunia setelah India dan Cina, dan menurut data Survei Kesehatan Rumah Tangga tahun 1995 TB merupakan penyebab kematian ketiga terbesar setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit infeksi lainnya (Dep Kes RI, 2002). Untuk menanggulangi masalah tersebut, sejak tahun 1995 WHO merekomendasikan penggunaan strategi DOTS (Directly Observed Treatment, Shortcourse) dalam program Pemberantasan Penyakit TB. Dalam strategi DOTS, pemeriksaan laboratorium untuk menemukan adanya kuman TB dalam dahak dengan cara pemeriksaan hapusan langsung (direct smear) merupakan sarana utama untuk menegakkan diagnosa dan menilai kemajuan terapi penyakit TB paru. Untuk menilai kemajuan terapi cukup dilakukan 2 pemeriksaan (Sewaktu dan Pagi) dan bila salah satu spesimen positif maka hasil pemeriksaan follow-up dahak tersebut dinyatakan positif (Dep Kes RI, 2002; Blanc, 2003). Beberapa keadaan klinis dapat digunakan untuk memantau kemajuan terapi seperti demam, batuk, dan peningkatan berat badan. Tetapi penilaian terbaik respons terapi penderita TB paru adalah eradikasi basil tuberkulosis dari dahak penderita. Beberapa peneliti mendapatkan penurunan yang cepat dari jumlah kuman BTA yang sensitif setelah mendapat terapi OAT selama lebih kurang 2
minggu. Faktor-faktor yang mempengaruhi saat terjadinya konversi dahak pada penderita TB paru BTA positif adalah status imun penderita, tingkat infeksi, kepatuhan minum obat, bioavilabiliti dan suseptibiliti obat (Soedarsono, 2003; Garay, 2004). Oleh karena itu pemeriksaan follow-up dahak pada akhir terapi fase intensif sangat penting dilakukan karena akan menentukan kebijakan penanganan selanjutnya. Pada umumnya penderita TB paru yang telah mendapat terapi lebih dari satu bulan gejala batuk dan produksi dahak akan berkurang sehingga penderita akan sulit untuk mengeluarkan dahaknya secara spontan. Keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya false-negative, dimana sebenarnya dahak penderita masih mengandung kuman BTA tetapi karena penderita tidak dapat mengekspektorasikan dahaknya maka hanya akan didapatkan spesimen saliva yang memberikan hasil BTA negatif. Hasil hapusan dahak BTA yang false-negative ini membuat klinisi berpikir bahwa terapi yang diberikan telah adekuat dan tidak ada kemungkinan adanya MDR-TB. Bila keadaan ini berlanjut terus dikuatirkan akan semakin meningkatkan angka resistensi kuman TB terhadap OAT. Induksi dahak merupakan salah satu cara alternatif yang sederhana, aman, tidak invasif, dan lebih dapat diterima oleh penderita anak guna memperoleh spesimen dahak yang layak untuk pemeriksaan bakteriologis pada penderita-penderita yang sulit mengeluarkan dahak secara spontan (Menzies, 2003; Fireman, 2003; Garay, 2004). Induksi dahak dapat dilakukan dengan cara nebulisasi aerosol air suling yang dihangatkan atau larutan salin isotonik (0,9%) atau hipertonik. Beberapa penelitian mendapatkan hasil positif yang tinggi dari pemeriksaan dahak induksi yaitu berkisar antara 70 – 90%, dan sebanding dengan hasil pemeriksaan yang menggunakan bronkoskopi (Garay, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa induksi dahak dengan nebulisasi larutan salin 0,9% dapat meningkatkan kepekaan pemeriksaan kuman BTA dari dahak penderita TB paru (kasus baru) dengan BTA positif sebelum terapi pada
56

akhir terapi fase intensif DOTS.
BAHAN DAN CARA Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni dengan desain penelitian berupa time series, before and after. Penelitian eksperimental murni disini merupakan penelitian eksperimental fungsional dimana variabel bebas dapat dimanipulasi dengan sempurna. Sebagai variabel bebas adalah induksi dahak dengan nebulisasi salin 0,9% sebanyak 4 ml dan edukasi cara batuk efektif, sedang BTA dahak merupakan variabel tergantung.Hipotesis Dahak induksi dengan nebulisasi larutan salin 0,9% dapat meningkatkan kepekaan pemeriksaan kuman BTA dibandingkan dengan dahak spontan dari penderita TB paru (kasus baru) dengan BTA positif sebelum terapi pada akhir terapi fase intensif DOTS.Batasan operasional Larutan salin 0,9% adalah larutan elektrolit yang mengandung Natrium Klorida (NaCl) steril yang kadarnya 0,9%. Nebulisasi salin 0,9% adalah upaya mengubah larutan salin 0,9% menjadi bentuk aerosol yang partikel-partikelnya berukuran mikron dengan perantaraan alat nebuliser. Pada penelitian ini digunakan alat nebuliser jet. Dahak adalah sekret saluran napas yang meningkat yang menunjukkan adanya kelainan patologis. Dahak spontan adalah dahak yang diperoleh tanpa induksi salin, sedangkan dahak induksi adalah dahak yang didapatkan setelah dilakukan induksi dengan nebulisasi salin 0,9%. BTA (Batang Tahan Asam) adalah kuman M. tuberculosis yang merupakan penyebab tuberkulosis paru, didapatkan pada dahak penderita TB paru, denga pengecatan kuman menurut metode Ziehl-Neelsen tampak kuman berbentuk batang berwarna kemerahan dibawah pemeriksaan mikroskop cahaya. Penderita TB paru (kasus baru) BTA positif adalah penderita TB paru dengan hapusan BTA dahak spontan positif dan belum pernah atau pernah mendapat terapi OAT tetapi kurang dari satu bulan. Pembacaan sediaan dahak menggunakan skala IUATLD (International Union Against Tuberculosis Lung Disease) sebagai berikut:
Tidak ditemukan BTA dalam 100 lapang pandang, disebut negatif
Ditemukan 1–9 BTA dalam 100 la-pang pandang, ditulis jumlah kuman yang ditemukan. Bila ditemukan 1–3 BTA dalam 100 lapang pandang, pemeriksaan harus diulang dengan spesimen dahak yang baru. Bila hasilnya tetap 1–3 BTA, hasilnya dilaporkan negatif. Bila ditemukan 4–9 BTA, dilaporkan positif.
Ditemukan 10–99 BTA dalam 100 lapang pandang, disebut + atau (1+).
Ditemukan 1–10 BTA dalam 1 la-pang pandang, disebut ++ atau (2+).
Ditemukan >10 BTA dalam 1 la-pang pandang, disebut +++ atau (3+). Penelitian dilakukan di Insta-lasi Rawat Jalan Poli TB - DOTS Bag/SMF Ilmu Penyakit Paru RSU Dr. Soetomo Surabaya. Subyek penelitian adalah semua penderita TB paru (kasus baru) dengan dahak BTA positif sebelum terapi yang menjalani pengobatan di Poli TB – DOTS Bag/SMF Ilmu Penyakit Paru RSU Dr. Soetomo Surabaya, dan pada akhir terapi fase intensif pada pemeriksaan dahak spontan tanpa diajarkan cara batuk efektif didap-atkan hasil BTA negatif, serta memenuhi kriteria inklusi dan ek-sklusi. Sampel diambil secara total sampling selama 3 bulan mulai 31 Mei 2005 sampai dengan 31 Agus-tus 2005, dan setiap penderita men-jadi kontrol untuk dirinya sendiri. Sebagai kriteria inklusi, pen-derita TB paru (kasus baru) laki-laki atau wanita dengan dahak spontan BTA positif sebelum mendapat ter-api dan pada akhir terapi fase inten-sif didapatkan hasil BTA dahak spontan tanpa diajarkan batuk efek-tif negatif, berumur antara 13-65 tahun, mendapat OAT sesuai pro-gram DOTS, tidak pernah men-galami drug-induced hepatitis se-lama mendapat OAT dalam terapi fase intensif, tidak menderita penyakit lain seperti asma bronkiale atau PPOK, tidak sedang hamil, ko-operatif, dan menandatangani in-
57

formed consent. Kriteria eksklusi meliputi penderita yang sudah men-dapat terapi mukolitik atau ekspek-toransia, datang dalam keadaan darurat atau keadaan umum yang jelek, dan hemoptisis. Semua penderita yang memenuhi syarat penelitian dia-jarkan cara batuk efektif untuk memudahkan keluarnya dahak. Pen-derita diminta untuk membatukkan dahaknya ke dalam pot steril yang telah disediakan untuk pemeriksaan BTA dahak spontan. Dilakukan pen-gukuran PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) sebagai baseline faal paru. Induksi dahak dilakukan den-gan nebulisasi larutan salin 0,9% se-banyak 4 ml yang menggunakan nebuliser jet, kemudian penderita diminta membatukkan dahaknya ke dalam pot steril yang telah disedi-akan untuk pemeriksaan BTA dahak induksi salin 0,9%. Dari sampel da-hak induksi selain dilakukan pe-meriksaan hapusan dahak BTA juga dilakukan kultur M. tuberculosis. Bila pada saat dilakukan nebulisasi penderita mengeluh sesak nebulisasi dihentikan dan dilakukan pengukuran PEFR. Bila terjadi penurunan PEFR 20% induksi di-hentikan, pada penderita diberikan bronkodilator short acting 2 agonis
MDI (Ventolin MDI) dan O2 nasal 2-4 l/m, dan penderita drop out. Tetapi bila PEFR tetap atau menu-run < 20% penderita diistirahatkan sebentar dan bila keluhan sesak menghilang serta PEFR kembali ke baseline induksi dilanjutkan sampai didapatkan sampel dahak induksi. Bila pada saat dilakukan nebulisasi terjadi komplikasi batuk darah in-duksi juga dihentikan dan penderita drop out.
Pemeriksaan hapusan dahak BTA menggunakan metode pengecatan Ziehl- Neelsen dan kultur M. tuber-culosis (sampel dahak induksi) den-gan media telur metode Ogawa di-lakukan di Balai Besar Laborato-rium Kesehatan Daerah Surabaya. Untuk membandingkan hasil kuman BTA pada dahak spontan dan in-duksi dilakukan analisa statistik den-gan uji Mc. Nemar.
HASIL PENELITIAN
Karakteristik penderita Selama 3 bulan masa peneli-tian terdapat 35 orang penderita yang memenuhi syarat penelitian, terdiri dari 24 orang laki-laki dan 11 orang perempuan berumur antara 15-65 tahun dengan umur rata-rata 37,3 14,2 tahun.
Tabel 1. Karakteristik umur dan jenis kelamin
Kelompok
Umur
Jenis Kelamin
Total
(n)
%Laki-laki Perempuan
n % n %
15-24
25-34
3
6
8,6
17,1
6
1
17,1
2,9
9
7
25,7
20,0
58

35-44
45-54
55-64
>=65
5
5
3
2
14,3
14,3
8,6
5,7
3
1
0
0
8,6
2,9
0
0
8
6
3
2
22,9
17,1
8,6
5,7
Total (n) 24 68,6 11 31,4 35 100,0
Penyakit penyerta Beberapa subyek penelitian mempunyai penyakit penyerta, dan penyakit penyerta terbanyak adalah DM.
Tabel 2. Penyakit penyerta pada subyek penelitian
Penyakit Penyerta n %
Tidak ada
DM
Jantung
Alergi
28
6
0
1
80,0
17,1
0
2,9
Total 35 100,0
Tingkat kepositifan dahak BTA sebelum terapi
Tingkat kepositifan kuman BTA pada dahak spontan penderita sebelum mendapat terapi OAT terdapat pada tabel 3. Semua subyek penelitian mempunyai dahak BTA positif yang tersebar diantara 1+ sampai 3+.
Tabel 3. Tingkat kepositifan dahak BTA sebelum terapi
Tingkat Kepositifan n %1+2+3+
1313 9
37,137,125,7
Total 35 100,0
Hasil pemeriksaan dahak BTA pada akhir terapi fase intensif Sampel dahak spontan berhasil didapatkan pada semua subyek penelitian (100%) setelah diajarkan cara batuk efektif. Sampel dahak induksi juga berhasil didapatkan pada semua subyek penelitian (100%) setelah dilakukan nebulisasi dengan larutan salin 0,9% sebanyak 4 ml. Hasil pemeriksaan dahak BTA secara keseluruhan terdapat pada tabel 4 dan 5.
Tabel 4. Hasil pemeriksaan BTA dahak spontan dan induksi
BTA Dahak n %
Spontan+-
134
2,997,1
Total 35 100,0
Induksi+-
431
11,488,6
Total 35 100,0
59

Hasil pemeriksaan BTA dahak spontan didapatkan BTA positif 1 orang (2,9%), sedangkan dengan induksi didapatkan BTA positif lebih banyak yaitu 4 orang (11,4%).
Tabel 5. Cross tabulation BTA dahak spontan dan BTA dahak induksi
BTA InduksiTotal+ -
BTA spontan + -
13
031
134
Total 4 31 35 Uji Mc. Nemar; p = 0,250
Ada 3 orang yang dinyatakan BTA positif dengan induksi namun dengan dahak spontan dinyatakan BTA negatif. Hasil uji Mc. Nemar menunjukkan p > 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan yang bermakna antara hasil pemeriksaan dahak BTA melalui induksi maupun spontan.
Hasil kultur mikobakteria dari sampel dahak induksi
Dari 35 sampel dahak induksi selain dilakukan pemeriksaan hapusan BTA juga dilakukan kultur mikobakteria dengan media telur metode Ogawa. Semua sampel (100%) memberikan hasil negatif atau tidak ada pertumbuhan kuman.
Komplikasi Pada semua subyek penelitian tidak terjadi komplikasi bronkospasme ataupun batuk darah selama dan pasca induksi.
DISKUSI Dari 35 subyek penelitian, penderita terbanyak terdapat pada kelompok umur 15-24 tahun menca-pai 9 orang (25,71%), diikuti kelom-pok umur 35-44 tahun sebanyak 8 orang (22,86%) dan 25-34 tahun se-banyak 7 orang (20%). Hasil ini sesuai dengan laporan WHO bahwa 75% penderita TB di negara berkembang mengenai usia produk-tif yaitu 15-50 tahun (Dep.Kes. RI, 2002; Blanc, 2003).
Penyakit penyerta yang terbanyak adalah DM yang terdapat pada 6 subyek penelitian (17,1%). Dari 6 subyek penelitian dengan penyakit penyerta DM, hanya 1
penderita yang memberikan hasil BTA dahak spontan negatif tetapi BTA dahak induksi positif. Kelima penderita lainnya benar-benar telah mengalami konversi BTA dari positif sebelum terapi menjadi negatif pada akhir terapi fase intensif. Penderita TB paru dengan DM sering mengalami kelambatan konversi BTA, terutama bila kadar gula darah tidak teregulasi dengan baik.
Sampel dahak spontan berhasil didapatkan pada semua subyek penelitian (100%) setelah terlebih dahulu diajarkan cara batuk efektif. Pada pemeriksaan hapusan BTA dahak spontan didapatkan 1 sampel (2,9%) yang memberikan hasil positif (1+) dan 34 sampel (97,1%) lainnya memberikan hasil negatif. Sampel dahak induksi berhasil didapatkan pada semua subyek penelitian (100%) setelah dilakukan nebulisasi dengan larutan salin 0,9% sebanyak 4 ml. Pada pemeriksaan hapusan BTA dahak induksi didapatkan 4 sampel (11,4%) yang memberikan hasil positif (1+) dan 31 sampel (88,6%) memberikan hasil negatif. Hanya ada 1 sampel yang memberikan hasil hapusan BTA positif (1+) pada spesimen dahak spontan maupun induksi. Pada analisa statistik dengan uji Mc. Nemar menunjukkan p = 0,250 (p > 0,05) yang berarti tidak ada perbedaan bermakna antara pemeriksaan hapusan BTA dahak spontan yang diajarkan cara batuk efektif dan fisioterapi dada dengan dahak induksi salin 0,9%.
Tingginya hasil negatif dari pemeriksaan hapusan BTA baik dari sampel dahak spontan maupun induksi kemungkinan dapat disebabkan karena masih sensitifnya
60

kuman M. tuberculosis terhadap OAT yang diberikan sehingga sebagian besar kuman mati atau sampel dahak yang didapat baik secara spontan atau induksi masih banyak tercampur saliva. Sulit untuk mendapatkan sampel dahak yang benar-benar berasal dari sekret di saluran napas besar dan kecil. Hapusan BTA positif pada 4 sampel dahak induksi kemungkinan dapat disebabkan oleh kuman M. tuberculosis yang telah mati, karena pada semua sampel dahak induksi dilakukan kultur M.tuberculosis dan semuanya memberikan hasil negatif atau tidak ada pertumbuhan kuman. Hasil kultur yang negatif dari spesimen yang mengandung kuman M. tuberculosis dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pada penderita yang mendapat terapi OAT, kuman M. tuberculosis dapat kehilangan kemampuan untuk tumbuh pada media kultur atau kuman telah mati. Beberapa penelitian melaporkan bahwa penderita yang telah mendapat terapi OAT dengan regimen yang mengandung rifampicin, seringkali hasil kultur menjadi negatif setelah pengobatan 3 minggu tetapi pemeriksaan hapusan dahak masih positif, ini berarti basil tuberkulosis telah mati (Toman, 2004). Hasil kultur yang negatif juga dapat disebabkan oleh kurang tepatnya penanganan sampel dahak dan atau prosedur pembuatan kultur. Penanganan sampel dahak kurang tepat bila sampel dahak terpapar dengan sinar matahari atau temperatur yang tinggi, disimpan terlalu lama, mengering, atau terkontaminasi. Prosedur dekontaminasi yang berlebihan sebelum dilakukan inokulasi, pemanasan yang berlebihan selama sentrifugasi, media kultur yang tidak adekuat, dan kurangnya masa inkubasi merupakan beberapa keadaan yang dapat menyebabkan hasil kultur negatif (Toman, 2004).
Untuk keamanan penderita, dilakukan pemeriksaan faal paru dengan PEFR sebelum dilakukan tindakan induksi dahak dengan nebulisasi larutan salin 0,9%, tetapi ternyata selama dan sesudah tindakan induksi tidak ada subyek penelitian yang mengeluh sesak. Induksi dahak harus dihentikan bila ada keluhan sesak dan terjadi penurunan PEFR 20% (Paggiaro, 2002; Pizzichini, 2002).
Obstruksi saluran napas
akibat induksi dahak dapat terjadi terutama pada penderita-penderita asma bronkiale dan emfisema paru serta pemakaian salin konsentrasi tinggi. Karena itu konsentrasi salin untuk induksi dahak dibatasi hingga 3% untuk penderita-penderita tersebut (Pizzichini, 2002). Jika dengan salin 0,9% induksi dahak berhasil, tidak perlu menggunakan konsentrasi salin yang lebih tinggi untuk mendapatkan dahak, disamping itu induksi dahak dengan salin 0,9% lebih dapat ditoleransi penderita, khususnya bagi mereka dengan penyakit obstruksi saluran napas. Larutan salin 0,9% lebih mudah didapat dan lebih murah dibandingkan salin 3%, karena itu larutan ini merupakan pilihan untuk induksi dahak (Paggiaro, 2002; Pizzichini, 2002; Fireman, 2003).
Dalam penelitian ini semua subyek penelitian mempunyai Pengawas Minum Obat (PMO), tetapi seberapa jauh peran PMO tidak diteliti dan semua subyek penelitian dianggap telah minum OAT secara teratur selama masa terapi fase intensif 2 bulan.
Dalam penelitian ini, semua penderita mengalami batuk spontan selama dan sesudah induksi, tidak ada yang mengalami komplikasi bronkospasme ataupun batuk darah. KESIMPULAN
Tidak terdapat peningkatan kepekaan yang bermakna antara pemeriksaan hapusan BTA dahak induksi salin 0,9% dengan dahak spontan yang diajarkan cara batuk efektif pada penderita TB paru (kasus baru) dengan BTA positif sebelum terapi pada akhir terapi fase intensif DOTS. Dengan memberikan edukasi cara batuk efektif, dapat diperoleh spesimen dahak spontan yang laik periksa.
Induksi dahak dengan larutan salin 0,9% tidak menyebabkan terjadinya komplikasi bronkospasme. Prosedur induksi dahak perlu dipahami dengan benar dan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan
61

sehingga tidak memberikan efek samping yang berarti. Induksi dahak perlu dilakukan pada penderita TB paru yang sulit mengekspektorasikan dahak.
Hasil positif pada hapusan dahak BTA pada akhir fase intensif kemungkinan dapat disebabkan oleh kuman M. tuberculosis yang telah mati. Dari besarnya sampel yang memberikan hasil hapusan BTA negatif baik dari spesimen dahak spontan maupun dahak induksi salin 0,9%, secara tidak langsung dapat diasumsikan bahwa pemberian OAT kategori I yang terdiri dari rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan ethambutol secara intensif selama 2 bulan pada penderita TB paru (kasus baru) BTA positif terbukti cukup poten dalam membunuh kuman M. tuberculosis sehingga terjadi konversi kuman BTA dari positif menjadi negatif. Keadaan ini akan menurunkan tingkat infeksiusiti dan mortaliti penderita.
DAFTAR PUSTAKA
1. Blanc L, Chaulet P, Espinal M, et al (2003). Treatment of tuberculosis. Guidelines for national programmes 3rd ed. World Health Organization, Geneva.
2. Departemen Kesehatan Republik In-donesia (2002). Pedoman nasional penanggulangan tuberkulosis, cetakan VI, Jakarta.
3. Fireman E (2003). Induced sputum as a diagnostic tactic in pulmonary dis-eases. IMAJ;5:524-7.
4. Garay SM (2004). Pulmonary tubercu-losis. In: Rom WN, Garay SM eds. Tuberculosis, 2nd ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia:345-94.
5. Kumaresan J (2002). Epidemiology. In: Narain JP ed. Tuberculosis. Epi-
demiology and control, 1st ed. World Health Organization, India:15-33.
6. Menzies D (2003). Sputum induction: Simpler, cheaper, and safer – but is it better? Am J Respir Crit Care Med; 167:676-7.
7. Paggiaro PL, Chanez P, Holz O, et al (2002). Sputum induction. Eur Respir J; 20:3S-8S.
8. Pizzichini E, Pizzichini MM, Leigh R, et al (2002). Safety of sputum induc-tion. Eur Respir J; 20:9S-18S.
9. Soedarsono (2003). Evaluasi terapi tu-berkulosis: klinis dan program. Da-lam: TB Update – II Simposium Na-sional, Lab-SMF Ilmu Penyakit Paru FK Unair / RSUD dr. Soetomo, Surabaya:49-68.
10. Toman K (2004). What is the proba-bility of obtaining a negative culture from a sputum specimen found posi-tive by smear microscopy?. In: Frieden T (editor). Toman’s Tubercu-losis Case detection, treatment, and monitoring – questions and answers, 2nd ed. World Health Organization, Geneva:44-45.
ANTROPOMETRI ANAK SEKOLAH DASAR UNTUK MENENTUKAN BANGKU
YANG ERGONOMIS
DI SEKOLAH DASAR KOTA SURABAYA
62

Ira Idawati
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dimensi antropometri dari bahasa Indonesia siswa sekolah dasar dan interlationship mereka untuk sekolah desain furniture, terutama desain bangku sekolah siswa SD. pengukuran antropometri sangat penting untuk desain ruang kerja yang benar ergonomis. Hal ini terutama berlaku untuk anak-anak shool, yang menghabiskan sebagian besar kursi dan meja, dan sebagainya yang seharusnya mampu mengadopsi pasture.of tubuh nyaman 735 siswa yang pertama untuk tahun keenam (378 laki-laki dan 357 perempuan) terlibat sebagai sampel populasi. Dalam studi ini dilakukan di tiga sekolah dasar yang berbeda yaitu: atas, tengah dan bawah sosial dan ekonomi status sekolah dasar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini wiich uji t dimaksudkan untuk menemukan perbedaan yang signifikan dari variabel-variabel yang diukur antara sekolah - anak laki-laki dan sekolah - anak perempuan di kelas yang sama. The Anova dan uji Manova bekerja untuk menemukan perbedaan yang signifikan dari variabel interclass. Sebuah analisis deskriptif juga dilakukan untuk menentukan desain meja siswa. Hasil t - test tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dari desain meja siswa antara sekolah - anak laki-laki dan sekolah - gadis. Sementara hasil Anova dan Manova menunjukkan perbedaan yang signifikan dari desain meja siswa di kelas masing-masing. Ini dianjurkan untuk memiliki tiga jenis mahasiswa desain meja di setiap kelas, yaitu 25% dari desain meja untuk siswa bentuknya kecil, 50% dari desain meja untuk siswa menengah berbentuk dan 25% bagi siswa besar-bentuk.
Kata Kunci: siswa sekolah dasar meja, Ergonomi
Anthropometric Elementary School Children to determine the Ergonomic benches
surabaya city in Primary Schools
Ira Idawati
Lecturer Faculty of Medicine, University of Wijaya Kusuma Surabaya
ABSTRACTThe purpose of this research is to find the anthropometric dimensions of Indonesian elementary school students and their interlationship for school furniture design, especially the design of the elementary school students desks. Anthropometric measurements are essential for correct design of ergonomic work spaces. This is especially true for shool children, who spend most of their chairs and desks, and so who ought to able to adopt comfortable body pasture.of 735 students of the first to the sixth year (378 boys and 357 girls ) were involved as a sample population.The reaseach was conducted at three different elementary schools : namely upper, middle and lower social and economic status elementary school. Data analysis employed in this research the t test wiich is meant to find the significant difference of the measured variables between the school – boys and school - girls in the same class. The Anova and Manova test are employed in order to find any significant difference of the interclass variables. A descriptive analysis was also conducted to determine the design of the students desks.The result of the t – test doesn’t indicate any significant difference of the students desk design between the school – boys and the school – girls. Meanwhile the Anova and Manova results indicate significant difference of the student desk design in each class.It’s advisable to have three types of student desk design in each class, namely 25% of desk design for small shape students, 50% of desk design for medium-shaped students and 25% for big-shape students.
Key Words : the elementary school students desks, Ergonomic
1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
63

Negara-negara industri sudah lebih sadar tentang pentingnya perbedaan etnis, populasi dan rasial pada manusia sesudah mendapat pengalaman dari hasil pemakaian senjata dan produksi industri lainnya yang diekspor ke negara-negara lain. Hal ini sebetulnya mudah dimengerti oleh orang awam, tetapi kadang-kadang luput dri perhatian para akademisi.
Peralatan sekolah perlu disesuaikan dengan ukuran dan bentuk tubuh anak-anak oleh karena masih dalam masa pertumbuhan, sehingga ketidaksesuaian akan berpengaruh buruk pada sikap badan dan tulang belakang. Sikap yang salah ini sering terlihat pada anak-anak sekarang serta karyawan- karyawan kantor seperti dilaporkan oleh beberapa ahli.
Diantara peralatan sekolah yang penting adalah bangku, karena anak-anak memakai bangku untuk sebagian besar kegiatannya, lebih kurang selama tiga sampai enam jam sehari, bahkan lebih apabila mereka bersekolah di sekolah full day, yang akhir-akhir ini digemari oleh orang tua murid.
Di Negara yang sudah maju ada empat sampai dua belas jenis bangku, mengingat ukuran anak-anak yang sebaya dapat cukup berbeda secara bermakna. “Bahaya-bahaya akibat posisi duduk” seyogyanya mendapat perhatian kita semua.
B. Permasalahan
Pada saat ini belum banyak dilakukan pengukuran antoprometri dari murid-murid Sekolah Dasar, padahal data antopometris ini sangat penting untuk memper-baiki desain bangku supaya lebih sesuai dengan kaidah-kaidah ergonomis.
C. Tujuan penelitian
Tujuan penelitian ini ialah mendapatkan data-data antropometris pada murid Sekolah Dasar di Surabaya yang dapat dipakai sebagai rujukan dalam merencana-kan desain perabot sekolah terutama bangku sekolah.
2. OBYEK DAN METODE PENELITIAN
a. Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah murid kelas I sampai dengan kelas VI SD negeri dan swasta di kota Surabaya yang berjumlah 280.428 anak. Berbentuk normal dan tidak cacat.
Populasi dikategorikan menjadi 3 yaitu :Kategori I : Sekolah Dasar dengan orang tua yang pada umumnya berstatus sosial tinggi,Kategori II : Sekolah Dasar dengan orang tua yang pada umumnya berstatus sosial menengah,Kategori III : Sekolah Dasar dengan orang tua yang pada umumnya berstatus sosial Rendah.
Dengan confidence coefficient 95% dipilih 384 siswa sebagai sampel.Sampel diambil dari masing-masing kategori social –ekonomi dan batas obyek 20 orang siwa laki-laki dan 20 orang siswa perempuan sehingga jumlahnya sebesar 360 siswa laki-laki dan 360 siswa perempuan. Tetapi dalam pelaksanaannya yang tercata 735 siswa terdiri atas 378 siswa laki-laki dan 357 siswa perempuan.
b. Prosedur Pengukuran
Pengukuran Antropometri dilakukan sesuai dengan variable yang telah ditentukan. Pada waktu pengukuran subyek penelitian memakai baju olah raga tipis saku kosong dan duduk pada posisi tegak.
c. Variabel yang diukur1. Tinggi siku duduk2. Tinggi siku lantai3. Lebar siku ke siku4. Lebar pinggul duduk5. Tebal paha duduk6. Tinggi poplitea duduk7. Jarak pantat poplitea8. Lebar bahu9. Tinggi bahu
d. Analisa data
1. Analisa data untuk mengetahui adanya perbedaan antropometri siswa laki-laki dan perempuan menggunakan uji t2. Analisa data untuk menguji adanya perbedaan antroprometri siswa atas kategori sosial-ekonomi
64

menggunakan uji Anova dan Manova3. Analisa data untuk menguji adanya perbedaan antropometri siswa Antar kelas menggunakan uji Anova dan Manova4. Analisa diskriptif dilakukan untuk mengelompokan antropometri yang berbeda dalam masing-masing kelas dengan asumsi bahwa ada ukuran kecil sebanyak 25% ( persentil 25 ), ukuran sedang 50% ( persentil 26-75 ) dan ukuran besar sebanyak 25% (persentil > 75 )
b. Rancang Bangun
Penelitian ini merupakan penelitian desktriptif dengan cara survey.
c. Sumber Data
Murid-murid Sekolah Dasar di Kotamadya Surabaya dari kelas I sampai kelas VI.
d. Kriteria Subyeki. Murid yang tercatat dari kelas I sampai
dengan kelas VI.ii. Murid yang bentuk tubuhnya normal dan
tidak mempunyai cacat fisik.e. Kriteria Sekolah
Dengan pertimbangan bahwa usuran antopometri dipengaruhi oleh faktor gizi dan ras, maka sekolah dasar yang ada dibagi dalam tiga kategori berdasatrkan daerahnya dan status social ekonomi wali murid pada umumnya.
Kategori 1: Sekolah Dasar didaerah sosial kategori tinggiKategori 2: Sekolah Dasar didaerah sosial kategori menengahKategori 3: Sekolah Dasar didaerah sosial kategori rendah
f. Besar Sampel
Menurut data dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surabaya, Jumlah murid Sekolah Dasar dari 19 kecamatan berjumlah 280.428 orang.
Maka untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus :
N . Za² . p . qn = -------------------------------------- d² . [ N – 1 ] + Za . p . q
n = Jumlah / besar Sample
p = Estimator proposi populasi
q = 1 – p
Za = Harga standart normal , tergantung harga yang digunakan
N = Jumlah unit populasi
Jika harga p dianggap sama dengan 0,5 maka harga n menjadi maksimal. Bila harga p belum diketahui, dapat digunakan harga p = 0,5 agar diperoleh n yang terbesar. Jika penyimpangan proporsi pada confidence coeficient 0,95 adalah 5% maka d = 5% = 0,05 pada harga 1 – 0,95 = 0,05 .
P = 0,5 maka q = 1 – 0,5 = 0,5.Z = 1,96. 280.428 . [1,96] . [0,5] . [0,5]n = ------------------------------------------------- [0,05] . [280.428 – 1]+[1,96] . [0,5] .[0,5]
296.323,0512n = ----------------------- 701,0675 + 0,49
296.323,0512n = ------------------- = 383,893054 ≈ 384 701,5575
n = 384
2.6. Cara Pengambilan Sample
Di Kotamadya Surabaya terdapat 280.428 murid Sekolah Dasar Negeri dari 178.639 murid Sekolah Dasar Negeri dan 101.789 murid Sekolah Dasar swasta. Dari sini ditentukan 3 kategori sekolah dasar berdasarkan daerahnya, yaitu Sekolah Dasar dengan status ekonomi dan sosial tinggi,
65

sedang dan rendah. Kemudian dari kategori diambil satu sampel Sekolah Dasar.
Dari setiap sekolah diambil sampel secara acak dengan cara diundi dari kelas I sampai kelas VI dimana setiap kelas diambil 20 murid laki-laki dan 20 murid perempuan.
g. Prosedur Pengukuran
i. Pada waktu diukur subyek memakai baju olah raga yang tipis serta saku baju kosong
ii. Tidak memekai alas kakiiii. Pada waktu diukur pada posisi tegak
h. Variabel yang diukur
Tinggi badan, tinggi siku dan duduk.
Tinggi siku, lantai, tinggi duduk normal, lebar siku ke siku, lebar panggul, duduk, tabal paha, duduk, tinggi poplitea, duduk, jarak pantat poplitea, lebar bahu.
66

67

i. Analisa Data
Dilakukan uji t untuk mengetahui apakah ada perbedaan usuran yang bermakna antara murid laki-laki dan murid perempuan dikelas yang sama.
Dilakukan uji Anova dan Manova untuk mengetahui apakah ada perbedaan ukuran yang bermakna dari setiap variasi dalam setiap tipe sekolah. Juga untuk mengetahui perbedaan ukuran yang bermakna dari setiap
variable antar kelas (kelas I sampai dengan kelas VI).
Dilakukan analisa deskriptif untuk menentukan 25 persentil serta 75 persentil di setiap kelas dari setiap variable. Mengingat disetiap kelas tentunya ada murid yang kecil, sedang dan besar usuran tubuhnya, maka dihitung nilai rata-rata dibawah atau lebih kecil dari 25 persentil, nilai rata-rata 25 persentil samapi dengan 75 persentil serta ditambah dan dikurangi [±] dengan Standard error (SE) dengan rumus:
Standard error = Standard Devíasi :
√Jumlah data
( ∑ fx )²
∑ fx² - --------------
Standard Deviasi = ______ N
√----------------------------------
N - 1
f : frekwensiN : Jumlah Datax : Besarnya tiap-tiap data
Kemudian dilakukan penghalusan data yang didapat dengan metode Aproksimasi Gaus-Doolitle (Glinka, 1990).
i. Perbedaan murid laki-laki dan murid perempuan
Terdapat perbedaan pada ukuran murid laki-laki dan murid perempuan tetapi setelah dilakukan uji t ternyata hanya ada sedikit perbedaan yang bermakna dari ukuran variabel antara murid laki-laki dan perempuan dikelas yang sama.
ii. Perbedaan Desain bangku antar tipe sekolah
Dari hasil uji Anova maupun Manova , pada
sekolah dengan status social dan ekonomi yang berbeda , berbeda juga desain bangkunya, yang berbeda ádalah lebar dan dalamnya serta tinggi sandarannya.
iii. Perbedaan bangku antar kelas
Hasil uji Anova dan Manova hampir semua variabel berbeda bermakna, berarti desain bangku setiap kelas seharusnya berbeda-beda.
68

iv. Perbedaan ukuran variabel di kelas
Mengingat didalam satu kelas juga terdapat murid yang ukuran tubuhnya kecil, sedang dan besar untuk itu diperlukan tiga desain bangku.
2.8.4.i. Model I
Ukuran desin ini didapat dengancara menghitung nilai rata-rata 25 persentil ± standart error. Desain ini diperuntukan bagi individu yang mempunyai ukuran nilai dibawah rata-rata. Sebaiknya di dalam kelas disediakan desain ini sebanyak 25%.
2.8.4.ii. Model II
Ukuran desain ini didapat dengan cara menghitung nilai rata-rata antara 25 persentil sampai dengan 75 persentil ± standart error. Desain ini diperuntukan bagi individu yang mempunyai ukuran rata-rata. Sebaiknya disediakan desain ini sebanyak 50%.
2.8.4.iii. Model III
Ukuran desin ini didapat dengan cara menghitung nilai rata-rata diatas 75 persentil ± standart error. Desain ini diperuntukan bagi individu mempunyai kuran nilai rata-rata. Model III ini sebaiknya disediakan sebanyak 25%.
Tabel 1 Norma data kelas IVariable < 25 persentil ± SE 25 -75 persentil ±
SE>75 persentil ± SE
Tinggi Siku duduk 12.0 ± 0.1 14.1 ± 0.1 17.2 ± 0.3Tinggi Siku lantai 82.8 ± 0.1 84.9 ± 0.1 87.5 ± 0.1Lebar siku ke siku 23.5 ± 0.2 26.9 ± 0.1 32.3 ± 0.3Lebar panggul duduk 20.8 ± 0.1 23.0 ± 0.1 26.8 ± 0.4Tabal paha duduk 8.7 ± 0.0 9.9 ± 0.0 12.0 ± 0.1Tinggi poplitea duduk 26.0 ± 0.3 29.7 ± 0.1 32.5 ± 0.2Jarak pantat poplitea 29.6 ± 0.3 33.3 ± 0.3 37.1 ± 0.3Lebar bahu 24.9 ± 0.3 26.4 ± 0.1 29.5 ± 0.3Tinggi bahu 35.8 ± 0.1 38.4 ± 0.1 42.1 ± 0.3
Tabel 2 Norma data kelas IIVariabel < 25 persentil ± SE 25 -75 persentil ±
SE>75 persentil ± SE
Tinggi Siku duduk 12.4 ± 0.1 14.6 ± 0.1 17.4 ± 0.1Tinggi Siku lantai 83.4 ± 0.1 85.6 ± 0.1 88.2 ± 0.1Lebar siku ke siku 23.4 ± 0.6 26.9 ± 0.1 32.3 ± 0.6Lebar panggul duduk 21.4 ± 0.3 23.5 ± 0.1 27.2 ± 0.3Tabal paha duduk 9.0 ± 0.0 10.4 ± 0.1 12.3 ± 0.8Tinggi poplitea duduk 28.1 ± 0.3 31.3 ± 0.1 34.2 ± 0.2Jarak pantat poplitea 31.5 ± 0.3 34.9 ± 0.1 39.0 ± 0.4Lebar bahu 25.6 ± 0.1 27.8 ± 0.1 31.4 ± 0.5Tinggi bahu 37.2 ± 0.2 40.1 ± 0.1 44.0 ± 0.6
Tabel 3 Norma data kelas IIIVariabel < 25 persentil ± SE 25 -75 persentil ±
SE>75 persentil ± SE
Tinggi Siku duduk 13.0 ± 0.1 15.3 ± 0.1 17.8 ± 0.2Tinggi Siku lantai 83.9 ± 0.1 86.3 ± 0.1 88.9 ± 0.2Lebar siku ke siku 23.5 ± 0.2 26.9 ± 0.1 32.7 ± 0.6Lebar panggul duduk 22.2 ± 0.1 24.2 ± 0.1 28.0 ± 0.4Tabal paha duduk 9.4 ± 0.1 10.9 ± 0.1 12.8 ± 0.2Tinggi poplitea duduk 29.9 ± 0.1 32.9 ± 0.1 36.0 ± 0.2Jarak pantat poplitea 33.4 ± 0.2 36.6 ± 0.1 40.8 ± 0.2Lebar bahu 26.4 ± 0.1 29.3 ± 0.1 33.3 ± 0.3
69

Tinggi bahu 38.8 ± 0.3 42.1 ± 0.1 46.2 ± 0.2
70

Tabel 4 Norma data kelas IVVariabel < 25 persentil ± SE 25 -75 persentil ±
SE>75 persentil ± SE
Tinggi Siku duduk 13.5 ± 0.2 16.0 ± 0.1 18.6 ± 0.1Tinggi Siku lantai 84.2 ± 0.5 86.9 ± 0.1 89.7 ± 0.2Lebar siku ke siku 23.9 ± 0.2 27.2 ± 0.1 33.5 ± 0.4Lebar panggul duduk 23.1 ± 0.1 25.3 ± 0.1 29.2 ± 0.2Tabal paha duduk 9.9 ± 0.1 11.4 ± 0.0 13.4 ± 0.1Tinggi poplitea duduk 31.5 ± 0.2 34.5 ± 0.1 37.8 ± 0.2Jarak pantat poplitea 35.2 ± 0.1 38.4 ± 0.1 42.7 ± 0.2Lebar bahu 27.5 ± 0.1 30.9 ± 0.1 35.1 ± 0.3Tinggi bahu 40.6 ± 0.4 44.3 ± 0.1 48.6 ± 0.2
Tabel 5 Norma data kelas VVariabel < 25 persentil ± SE 25 -75 persentil ±
SE>75 persentil ± SE
Tinggi Siku duduk 14.2 ± 0.1 16.8 ± 0.1 20.8 ± 0.3Tinggi Siku lantai 84.2 ± 0.1 87.6 ± 0.1 91.4 ± 0.2Lebar siku ke siku 24.5 ± 0.2 27.5 ± 0.2 36.3 ± 0.7Lebar panggul duduk 24.2 ± 0.2 26.7 ± 0.1 33.0 ± 0.5Tabal paha duduk 10.5 ± 0.1 12.0 ± 0.1 15.1 ± 0.2Tinggi poplitea duduk 32.8 ± 0.5 36.0 ± 0.1 41.6 ± 0.3Jarak pantat poplitea 37.0 ± 0.2 40.4 ± 0.1 46.3 ± 1.2Lebar bahu 28.6 ± 0.1 32.5 ± 0.4 38.6 ± 0.3Tinggi bahu 42.5 ± 0.3 46.7 ± 0.1 51.2 ± 0.8
Tabel 6 Norma data kelas VIVariabel < 25 persentil ± SE 25 -75 persentil ±
SE>75 persentil ± SE
Tinggi Siku duduk 15.0 ± 0.2 17.7 ± 0.1 20.8 ± 0.2Tinggi Siku lantai 83.9 ± 1.3 88.4 ± 0.1 91.4 ± 0.3Lebar siku ke siku 25.4 ± 0.5 27.9 ± 0.2 36.3 ± 0.7Lebar panggul duduk 25.4 ± 0.2 28.4 ± 0.1 33.0 ± 0.3Tabal paha duduk 11.1 ± 0.1 12.6 ± 0.1 15.1 ± 0.2Tinggi poplitea duduk 33.9 ± 0.2 37.5 ± 0.1 41.6 ± 0.2Jarak pantat poplitea 38.7 ± 0.3 42.5 ± 0.1 46.3 ± 0.2Lebar bahu 29.9 ± 0.2 34.2 ± 0.1 38.6 ± 0.3Tinggi bahu 44.7 ± 0.2 49.3 ± 0.2 54.0 ± 0.3
e. KESIMPULAN DAN SARANa. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan guna mendapatkan ukuran bangku skolah yang berdasarkan data antopometris bagi murid Sekolah Dasar di Kotamadya Surabaya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :
1. Desain bangku sekolah perlu berbeda untuk setiap kelas. Hal ini dapat dibuktikan dari uji anova dimana hampir setiap variabel berbeda makna pada setiap kelas (p <0,05 ).
2. Disetiap kelas minimal dibuatkan 3 desain bangku yang berbeda, dengan perbandingan sebagai berikut :
2.1. Sebanyak 25% desain bangku model I untuk individu dengan ukuran dibawah ukuran rata-rata.
2.2. Sebanyak 50% desain bangku untuk individu model II dengan ukuran rata-rata.
2.3. Sebanyak 25% desain bangku untuk individu model III dengan usuran diatas ukuran rata-rata.
71

3. Berdasarkan penelitian ini nampaknya usuran bangku untuk Sekolah Dasar murid laki-laki dan perempuan di kelas yang sama tidak perlu dibedakan, karena hanya ada sedikit perbedaan usuran variable yang bermakna antara murid laki-laki dan perempuan.
4. Desain bangku sekolah untuk sekolah dengan status social yang berbeda, agar diperhatikan lebar dan dalamnya bangku serta tinggi sandarannya karena dengan uji anova ternyata terdapat perbedaan yang bermakna dari variable-variabel tersebut (p <0,05 ).
3.2. Saran
3.2.1. Mengingat murid Sekolah Dasar masih dalam usia pertumbuhan serta banyak waktunya dihabiskan dibangku sekolah sebaiknya desain bangku sekolah setiap kelas berbeda.
3.2.2. Apabila memungkinkan sebaiknya dilakukan pengukuran variabel minimal 10 tahun sekali agar dapat dievaluasi ukuran bangkunya masih sesuai atau tidak.
3.2.3. Apabila memungkinkan diperlukan sampel yang besar agar dipeoleh hasil yang lebih representatif.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
1. Allen, Lee, 1988, The Concept of Er-gonomic, Professional Safety, Desember :
i. 30-31.2. Byung Y. J. and Kyung S.P., 1990, Sex Differences in Antopometry for School
i. Furniture Design, Ergonomic, 33: 1551 – 1524.
3. Glinka, J. SVD., 1987, Antropologi Ragawi, Fisip Unair4. Glinka, J. SVD., 1990, Antropometri dan Antroskopi, Fisip Unair.5. Jacob T., Antropologi Teknik, B. Bioantrop. Indon., 1980, 1 : 7 – 16.6. Sander M. & Cormick, E., 1987, Hu-man Factor in Engineering and Design, Mc. Graw Hill, Inc.7. Thimbleby, H., 1991, Can Human Think? Ergonomic Society Lecture, Er-gonomic, 10 : 1269 – 12878. Toetik, K., 1992, Ukuran-ukuran An-thropometris yang Berpengaruh Terhadap be-rat Badan, Pertemuan Ilmiah Nasional Perkumpulan Ahli Anatomi Indonesia, Malang.9. Vanworterghem, K., 1992, Representa-tive Strain Injuries, Konggres Ikatan Ahli Faal Indonesia, Yogyakarta.
INISIASI MENYUSU DINI UNTUK AWALI ASI
EKSKLUSIF
Atik Sri Wulandari
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ABSTRAK
72

Praktek pemberian ASI di Indonesia masih sangat kurang baik, untuk menuju Asi eksklusif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, faktor sosial budaya, susu formula, dukungan petugas kesehatan, kesehatan ibu dan bayi, dan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberian ASI secara eksklusif dengan Inisiasi Menyusui Dini.
Dengan memberikan inisiasi dini juga menurunkan resiko kematian bayi, Ddiantaranya ada yang menyebutkan samapi sebanyak 21%. Tak terpikirkan bahwa aneka ragam penyakit yang sering menyerang seseorang di usia 30, 40 dan 50 dapat disebabkan karena pemberian ASI yang kurang optimal saat masih bayi. IMD juga merupakan metode KB paling aman, ekonomis, dan menghemat waktu. Berat badan dan rahim (uterus) pun lebih cepat kembali normal.Inisiasi
Menyusu Dini atau yang dikenal sekarang dengan IMD merupakan langkah awal menuju kesuksesan menyusui.Dengan demikian tujuan penuruna Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) dapat ditekan dan tujuan menghasilkan generasi muda yang sehat akan tercapai.
INITIATION OF BREAST FEEDING EARLY FOR BEGINS
EXCLUSIVE
Atik Sri Wulandari
Lecturer Faculty of Medicine, University of Wijaya Kusuma Surabaya
ABSTRACTBreastfeeding practices in Indonesia is still very poor, to go to this exclusive Asi influenced by several factors including, socio-cultural factors, infant formula, health support, maternal and infant, and one of the govern-ment's efforts to increase exclusive breastfeeding with Early Initiation of Breastfeeding. By providing early initiation also reduce the risk of infant mortality, there is mention Ddiantaranya till as much as 21%. It was unthinkable that a variety of diseases that often strike anyone at age 30, 40 and 50 can be caused by a lack of optimal breastfeeding in infancy. IMD is also the most secure method of family planning, economical, and saves time. Weight and womb (uterus) is more rapid return normal.Inisiasi
Early feeding or known now with the IMD is the first step toward success thus menyusui.Dengan penu-runa purpose or the Infant Mortality Rate Infant Mortality Rate (IMR) can be suppressed and the goal of produc-ing a healthy younger generation will be achieved.
PENDAHULUANIndikator utama derajat kesehatan
masyarakat adalah angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR). Dari hasil penelitian yang ada, angka kematian bayi ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan faktor-faktor lain, terutama gizi. Status gizi ibu pada waktu melahirkan, dan gizi bayi itu sendiri sebagai faktor tidak langsung maupun langsung sebagai penyebab kematian bayi. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi bayi sangat perlu mendapat perhatian yang serius. Gizi untuk bayi yang paling sempurna dan paling murah adalah ASI atau Air Susu Ibu.(1)
Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah program yang sedang gencar dianjurkan oleh Pemerintah. Dengan melakukan inisiasi menyusui dini bayi belajar beradaptasi dengan kelahirannya didunia, selain itu kedekatan antara ibu dan bayinya akan terbentuk dalam proses tersebut. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi merupakan cara terbaik bagi
peningkatan kualitas SDM sejak dini yang akan menjadi penerus bangsa. ASI merupakan makanan yang paling sempurna bagi bayi. Pemberian ASI berarti memberikan zat-zat gizi yang bernilai gizi tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan saraf dan otak, memberikan zat-zat kekebalan terhadap beberapa penyakit dan mewujudkan ikatan emosional antara ibu dan bayinya.
Mengingat pentingnya pemberian ASI bagi tumbuh kembang yang optimal baik fisik maupun mental dan kecerdasannya, maka perlu perhatian agar dapat terlaksana dengan benar.
Faktor keberhasilan dalam menyusui adalah dengan menyusui secara dini dengan posisi yang benar, teratur, dan eksklusif. Oleh karena itu, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana ibu yang bekerja dapat tetap memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berumur 2 (dua) tahun.(2)
73

Bayi yang baru lahir ternyata tidak selemah yang diperkirakan orang selama ini. Jika dituntun dengan cara yang benar, maka dalam satu jam pertama kehidupan bayi, dia dapat mencari sendiri cara untuk menyusu kepada ibunya. Hal itu dikenal dengan istilah Inisiasi Menyusu Dini (IMD).(3,4)
Inisiasi Menyusu Dini atau yang dikenal sekarang dengan IMD merupakan langkah awal menuju kesuksesan menyusui, salah satu faktor penting dari pembangunan sumber daya manusia kedepan. Hal ini menunjukan bahwa mortalitas dapat ditekan dengan efektif saat kita memberikan kesempatan pada bayi untuk bersama ibunya, dengan kontak kulit dan membiarkan mereka bersamasama minimal 1 jam.
TINJAUAN PUSTAKAASI merupakan makanan bayi yang paling
penting terutama pada bulan-bulan pertama kehidupan. Pemberian ASI eksklusif adalah Air Susu Ibu yang diberikan kepada bayi berusia 0-6 bulan tanpa diberikan makanan dan minuman tambahan lain kecuali vitamin, mineral dan obat-obatan.
Berdasarkan stadium laktasi komposisi ASI dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: Kolostrum, ASI masa transisi, ASI mature.(2,4)
Manfaat ASI adalah memberi segala kebutuhan bayi, baik dari segi gizi, imunologis, maupun psikologis. ASI bersifat species-specific dan lebih unggul dibandingkan dengan makanan pengganti untuk bayi. ASI merupakan makanan alamiah dengan komposisi nutrisi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI mudah dicerna dan diserap, jarang menyebabkan konstipasi.(5,7)
Dari penelitian Dinas Kesehatan Surabaya disebutkan bahwa dengan memisahkan si ibu dengan si bayi ternyata sdaya tahan tubuh si bayi akan drop hingga mencapai 25%. Ketika ibu si ibu bersama dengan si bayi daya tahan si bayi akan berada dalam kondisi prima, dan si ibu bisa melakukan proteksi terhadap si bayi jika memang perlu.ASI mengandung substansi yang menunjang perkembangan system saraf dan pertumbuhan otak. ASI kaya akan antibodi untuk melawan infeksi. ASI dapat membantu bayi untuk merespon secara baik terhadap vaksin mengingat jumlah antibodi yang tinggi pada bayi usia 7-12 bulan yang menyusui. Bayi yang menyusui lebih sedikit mengalami alergi.
Cara pemberian ASI eksklusif adalah sejak lahir, sesegera mungkin (setengah-l jam sejak lahir). Pada jam pertama bayi menemukan payudara ibunya, ini merupakan awal dari inisiasi menyusu dini dan hubungan menyusui berkelanjutan dalam kehidupan antara ibu dan bayi. Prosesnya setelah melakukan inisiasi menyusu dini maka dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan hingga dua tahun.(9,10)
Inisiasi Menyusu Dini atau yang dikenal sekarang dengan IMD merupakan langkah awal menuju kesuksesan menyusui, salah satu faktor penting dari pembangunan sumber daya manusia kedepan.
Selain manfaat WD seperti diatas dapat dirasakan manfaat yang seperti : mampu mengurangi pendarahan pasca melahirkan (karena pengeluaran hormon oksitosin), mencegah kanker payudara dan kanker indung telur, dan mampu mengurangi pengeroposan tulang. IMD juga merupakan metode KB paling aman, ekonomis, dan menghemat waktu. Berat badan dan rahim (uterus) pun lebih cepat kembali normal.
Indikasi IMD, Ibu dan bayi harus dalam keadaan yang stabil. Artinya, ibu dan bayi tidak memerlukan perawatan atau tindakan medis paska pesalinannya, apabila memerlukan perawatan medis (resusitasi) IMD harus dihentikan atau tidak dilakukan.
PEMBAHASANWHO merekomendasikan pemberian ASI
eksklusif bagi bayi sejak lahir, sesegera mungkin (setengah-1 jam sejak lahir) sampai setidaknya usia 4 bulan dan bila mungkin hingga usia 6 bulan. Yang dimaksud dengan ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa disertai makanan atau minuman tambahan yang lain kecuali vitamin, mineral dan obat-obatan. ASI harus diberikan sebanyak dan sesering yang diinginkan bayi, siang maupun malam, setidaknya 8 kali.(7)
Pemberian ASI secara eksklusif sangat mendukung tumbuh kembang bayi lebih optimal. Sayangnya, pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Akibat dari pemberian ASI dan pemberian makanan tambahan yang salah, masih banyak balita di Indonesia menderita kurang gizi dan bahkan menderita gizi buruk.(11)
Maksud dari pemberian ASI eksklusif ialah bayi hanya diberikan ASI tanpa adanya tambahan cairan lain ataupun makanan
74

padat hingga enam bulan lamanya. Setelah enam bulan, baru bayi mulai diberi makanan pendamping ASI, dan ASI dapat diberikan sampai dua tahun. Sosialisasi ASI eksklusif, harus terus dilakukan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti PKK agar bisa memberi informasi kepada masyarakat dan keluarga serta para suami untuk memacu dan memberikan dorongan ibu-ibu untuk bisa menyusui bayinya. Sedang bagi yang telah berhenti menyusui dapat dilaksanakan relaktasi dan memberikan makanan pendamping yang baik.(7,9)
Dengan memberikan inisiasi dini juga menurunkan resiko kematian bayi sebanyak 21%. Tak terpikirkan bahwa aneka ragam penyakit yang sering menyerang seseorang di usia 30, 40 dan 50 dapat disebabkan karena pemberian ASI yang kurang optimal saat masih bayi.
Menurut paparan Dr. Utami Roesli, SpA,MBA,IBCLC sebagai ketua umum sentra laktasi Indonesia, Inisiasi dilakukan ketika bayi lahir, tali pusat dipotong, lalu di lap ker-ing dan langsung diberikan pada ibu. Harus ada sentuhan skin to skin contact, dimana bayi tidak boleh dipisahkan dulu dari ibu. Yang perlu di jaga adalah suhu ruangan, dan se-baiknya bayi memakai topi bayi karena disitu banyak keluar panas. Suhu yang tepat adalah 28-29 derajat C.(8)
Sampai disitu biarkan bayi di dada ibu min-imal 30 menit sampai bayi mencari sendiri putting susu ibunya dan langsung diminum. Masa ini bisa sampai 2 jam dan hal ini tidak menjadi masalah. Bila bayi kedinginan dada sang ibu akan meningkat hangat sampai 2 der-ajat, jika bayi kepanasan otomatis suhu dada ibu menurun sampai 1 derajat. Dengan inisiasi dini memberikan motivasi yang sangat besar untuk ibu menyusui bayi.(8)
Inisiasi dini juga berlaku untuk bayi yang lahir dengan cara sesar, vakum, kelahiran tidak sakit atau episiotomi. Hanya peluang untuk menemukan sendiri putting ibu akan berku-rang sampai 50%. Ini juga berlaku untuk bayi yang begitu lahir dipisahkan untuk ditimbang, disinar dan lain-lain.
Anak yang dapat menyusui dini dapat mu-dah sekali menyusu kemudian, sehingga kega-galan menyusui akan jauh sekali berkurang. Selain mendapatkan kolostrum yang berman-faat untuk bayi, pemberian ASI ekslusif akan menurunkan kematian.(8,9)
ASI adalah cairan kehidupan, yang selain mengandung makanan juga mengandung penyerap. Susu formula tak diberi enzim se-hingga penyerapannya tergantung enzim di usus anak. Sehingga ASI tidak ‘merebut’ en-zim anak.
Inti dari semua itu adalah, ASI ekslusif merupakan makanan terbaik bagi bayi. Namun karena informasi ASI yang kurang, tanpa kita sadari sudah menggangu proses kehidupan manusia mamalia. Inisiasi menyusui dini me-mang hanya 1 jam, tapi mempengaruhi bayi seumur hidupnya.(8)
IMD merupakan pemberian kesempatan pada bayi untuk langsung menyusui dengan mencari puting ibunya sendiri setelah lahir. Beragam manfaat IMD yang dapat dirasakan diantaranya, mampu mengurangi pendarahan pasca melahirkan, mencegah kanker payudara dan kanker indung telur, dan mampu mengurangi keropos tulang.
Dengan melaksanakan IMD, tentunya angka kematian bayi akan menurun. Tak hanya itu, IMD juga besar manfaatnya terhadap keberhasilan menyusui dan memberi bayi kesempatan untuk belajar menemukan puting susu ibunya. IMD pun membantu bayi untuk menjaga kemampuan bertahan hidup secara alami. Pada jam pertama bayi menemukan payudara ibunya, ini awal hubungan menyusui berkelanjutan dalam kehidupan antara ibu dan bayi menyusu. Prosesnya setelah melakukan inisiasi menyusu dini maka dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan diteruskan hingga dua tahun.
Berdasar data terbaru Departemen Kesehatan, angka kematian bayi dan balita di Indonesia semakin meningkat. Setidaknya, tiap 6 menit bayi baru lahir di Indonesia meninggal. Dr.Utami Rusli SpA, dokter RS. St Carolus mengatakan angka kematian bayi dan balita yang tinggi itu bisa ditekan dengan melakukan IMD dan memberikan ASI eklusif. Berdasarkan
75

penelitian jika bayi yang baru lahir dipisahkan dengan ibunya maka hormon stres akan meningkat 50%. Otomatis, hal tersebut akan menyebabkan kekebalan atau daya tahan tubuh bayi menurun. Bila dilakukan kontak antara kulit ibu dan bayi maka hormon stres akan kembali turun. Sehingga bayi menjadi lebih tenang, tidak stres, pernafasan dan detak jantungnya lebih stabil.
Hasil penelitian hubungan persepsi ibu-ibu tentang inisiasi menyusui dini dengan praktek pemberian ASI Eksklusif dengan uji korelasi pearson prudact moment tidak didapatkan hubungan yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara persepsi ibu-ibu tentang inisiasi menyusui dini dengan praktek pemberian ASI Eksklusif di Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.(12)
Ibu yang melakukan perawatan payudara dan melakukan tindakan IMD ternyata semua menunjukkan produksi ASI kategori cukup mencapai 100 %.Ada hubungan antara perawatan payudara (P<0,05) dan IMD (P<0,05) dengan produksi ASI. Disarankan untuk memberikan pelatihan perawatan payudara dan konseling tentang perawatan payudara dan IMD (13) Sentuhan dari bayi juga merangsang horman lain yang membuat ibu jadi tenang, relaks dan mencintai bayi, serta merangsang pengaliran ASI dari payudara.
Menurut penelitian dengan memisahkan si ibu dengan si bayi ternyata sdaya tahan tubuh si bayi akan drop hingga mencapai 25%. Lembaga internasional Unicef memperkirakan, pemberian ASI eksklusif sampai usia enam bulan dapat mencegah kematian 1,3 juta anak berusia di bawah lima tahun. Suatu penelitian di Ghana yang diterbitkan jurnal Pediatrics menunjukkan, 16% kematian bayi dapat dicegah melalui pemberian ASI pada bayi sejak hari pertama kelahirannya. Angka ini naik menjadi 22% jika pemberian ASI dimulai dalam satu jam
pertama setelah kelahiran bayi.Sayangnya, di Indonesia hanya 8% ibu
memberi ASI eksklusif kepada bayinya sampai berumur enam bulan dan hanya 4% bayi disusui ibunya dalam waktu satu jam pertama setelah kelahirannya. Padahal, sekitar 21.000 kematian bayi baru lahir (usia di bawah 28 hari) di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian ASI pada satu jam pertama setelah lahir.
Kontak dengan bayi sejak dini itu membuat menyusui menjadi dua kali lebih lama, bayi lebih jarang infeksi, dan pertumbuhannya lebih baik. Pemberian ASI dini meningkatkan kemungkinan 2-8 kali lebih besar untuk ibu yang memberi ASI eksklusif.
KESIMPULANPemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi
merupakan cara terbaik bagi peningkatan kualitas SDM sejak dini yang akan menjadi penerus bangsa. ASI merupakan makanan yang paling sempurna bagi bayi.
Faktor keberhasilan dalam menyusui adalah dengan menyusui secara dini dengan posisi yang benar, teratur, dan eksklusif Oleh karena itu, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana cara memberikan ASI kepada bayinya secara eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berumur 2(dua) tahun.
Inisiasi Menyusu Dini atau yang dikenal sekarang dengan IMD merupakan langkah awal menuju kesuksesan menyusui. Sebaiknya IMD dilakukan sejak lahir sebagai awal dari hubungan menyusui berkelanjutan. Mengenai pelaksanaan IMD masih jarang dilakukan di Indonesia karena kurangnya informasi tentang betapa pentingnya IMD sehingga diharapkan adanya peningkatan penyuluhan mengenai pentingnya IMD.
DAFTAR PUSTAKA
1. Wardani lusie,Dinas Kesehatan Surabaya,2009 dikutip dari www.surabaya-ehealth.org
2. 1999. Pedoman Penyuluhan Cara Menyusui yang Baik. Depertemen Kesehatan RI, Jakarta
3. 2006. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.
4. Soetjiningsih, dr, DSAK. 1997. ASI Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan. Penerbit Buku Kedokteran EGC.Jakarta.
76

5. Nindya S. Dampak pemberian ASI eksklusif terhadap penurunan kesuburan seorang wanita. Cermin Dunia Kedokteran 2001; 133: 44-47.
6. Suririnah. Air Susu Ibu (ASI) memberi keuntungan ganda untuk ibu dan bayi. 2004. Dikutip dari www. infoibu. com
7. American Academy of Pediatrics. Breast-feeding and the use of human milk. Pe-diatrics 2005; 115: 496-506. Dikutip dari aap.policy. aappublications. org
8. Roesli, Utami SpA, MBA, IBCLC Inisiasi Menyusu Dint Untuk Awali ASI Eksklusif, 16 September 2008, dikutip
dari www.republika- newsroom.com .
9. Dewi Sartika, S. Pd, M. Si, Sosialisasi ASI Eksklusif dan IMD, 17 January 2009, dikutip dari www.jurnal bogor. com
10. Selasi , Inisiasi Menyusu Dini, 19 Juni 2009, dikutip dari www.selasih.net
11. Dito Anurogo, Rahasia di Balik Keajaiban ASI, 6 Agustus 2009, dikutip dari www. zahraaulia.blogdetik. com
12. Fatmawati, Ari, Persepsi dan Praktek Pemberian ASI Ekslusif.Child Health Srvices, 2010
13. Rohaeti, Ety, Hubungan Perwtan Payudara dan Praktek Inisiasi Menyusui Dini Terhadap Ibu Pasca Bersalin Spontan di Rumah Sakit Annisa, Boyolali,2009.
MODELS of CARDIORESPIRATORY CONTROL(JENIS KONTROL KARDIORESPIRASI)
Akmarawita kadirHeru Setiawan
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma SurabayaAbstrakRespon sistem kardiovaskuler tergantung pada tipe dan intensitas dari aktivitas cabang olahraganya. Misalnya, selama olahraga dengan kontraksi statis (isometric contraction) akan meningkatkan tekanan darah arteri, latihan ini akan memperbesar otot-otot yang aktif dan berkontraksi secara maksimal. Sedangkan latihan dinamik, akan meningkatkan cardiac output, oksigen uptake pada otot yang berkontraksi (aktif). Respon kardiovaskuler pada latihan statik dan dinamik ini karena peningkatan aktivitas simpatis dan penurunan aktivitas Parasimpatis.
MODELS of CARDIORESPIRATORY CONTROL(TYPE OF CONTROL CARDIORESPIRATORY)
Akmarawita KadirHeru Setiawan
Lecturer Faculty of Medicine, University of Wijaya Kusuma SurabayaAbstractCardiovascular system response depends on the type and intensity of exercise branch activity. For example, during exercise with static contraction (isometric contraction) will increase arterial blood pressure, this exercise will enlarge the active muscles and contracting to the fullest. Meanwhile, dynamic exercise, will improve cardiac output, oxygen uptake in muscle contraction (active). Cardiovascular response to static and dynamic exercise is due to increased sympathetic activity and decreased parasympathetic activity.
PendahuluanPada gambar.1 dapat
dijelaskan mengenai pentingnya regulasi sistem kardiovaskuler selama latihan statik dan dinamik dimana keduanya secara langsung mempengaruhi kontrol neuron dan kontrol refleks neuron. Pengendali sentral, kita sebut sebagai “central command” yang memberikan impuls dari higher motor center di cerebrum (otak) ke cardiovascular center di medulla oblongata (batang otak). Ketika seseorang mengawali latihan (start), keadaan ini menyebabkan timbulnya impuls yang dikirimkan ke motor unit untuk menimbulkan
kontraksi otot, juga ada impuls yang dikirimkan ke cardiovascular center, dan segera menyebabkan keluarnya saraf simpatis menuju SA nodus di jantung. Pengeluaran NE dan E di SA nodus meningkatkan HR. Sedangkan rangsangan Parasimpatis yang mengeluarkan Acetylcholine ke SA nodus akan menyebabkan peningkatan HR pada detik awal latihan. Pengeluaran NE ke ventrikel dan ke beberapa daerah jantung, akan meningkatkan kontraksi otot jantung serta memperbesar stroke volume yang menyebabkan meningkatnya cardiac output, kombinasi peningkatan ini dengan kontraksi
77

pembuluh darah pada otot yang aktif akan menyebabkan meningkatnya tekanan darah sistolik yang disebut sebagai “Exercise pressor reflex”.
Ada impuls lain menuju ke Cardiovascular center (CVS) setelah otot mulai berkontraksi dan gerakan lain atau static tension. Impuls ini berasal dari reseptor spesial yang di temukan pada otot dan tendon yang disebut sebagai ergoreceptors. Salah satu tipe ergoreceptors yang sensitif terhadap efek mekanik kontraksi otot yaitu
mechanoreceptors. Serabut otot afferent untuk mechanoreceptors adalah serabut otot tipe III, yang memiliki paciniform corpuscles pada sensory ending. Serabut saraf ini melalui dorsal root menuju ke medulla spinalis dan kemudian menuju ke CVC. Mechanoreceptors bersama dengan impuls dari cerebral motor, memberikan informasi ke CVC. Impuls dari central command dan mechanoreceptors ke CVC menyebabkan respon kardiovaskuler berupa aktivitas sistem saraf otonom yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah.
Gambar 1. Kontrol kardiovaskuler sistem selama latihan. Ada dua jalur impuls, yaitu yang turun dari motor region di cerebrum (central command) dan impuls yang ke atas dari muscle receptors (ergoreceptors command) yang akan menuju ke kardiovaskuler area (Cardiovascular center / CVC) di medulla. Yang kemudian menghasilkan penurunan aktivitas Parasimpatis ke jantung dan meningkatnya aktivitas simpatis ke jantung, pembuluh darah, dan medulla adrenalis. Dan akhirnya akan meningkatkan cardiac output dan meningkatkan tekanan darah. Kombinasi dari peningkatan keduanya disebut sebagai “exercise pressor reflex”
Tipe kedua dari ergoreceptors adalah metaboreceptors, reseptor ini akan memberikan arus balik (feedback) ke CVC di batang otak untuk kemudian mengatur secara tepat peningkatan kebutuhan metabolik. Ujung reseptor ini bebas (free nerve ending) yang
disebut nociceptor (diaktifkan oleh rangsangan noxious dan bertanggungjawab untuk nyeri otot. Serabut afferent nya tidak bermeylin, sehingga hantaran konduksi nya lambat, dan digolongkan dalam serabut saraf sensoris tipe IV. Jalur hantarannya pun sama dengan serabut
78

saraf tipe III yaitu dari mechanoreceptors ke medulla spinalis kemudian ke CVS. Bedanya pada latihan dinamik dengan intensitas rendah mekanisme refleks neural mungkin tidak teraktivasi, tapi latihan dinamik dengan intensitas yang tinggi, atau selama latihan statik, refleks neural dengan cepat memberikan signal untuk meningkatkan aliran darah. Impuls ini dikirim ke CVS dan memberikan jawaban pengaturan jantung dan pembuluh darah sesuai dengan kebutuhan jaringan.
Pengaturan respon kardiovaskuler terhadap latihan diatur oleh beberapa mekanisme kontrol saraf. Ada mekanisme pengaturan yang independent yang mempengaruhi respon kardiovaskuler, dan tidak dibantu oleh pengaruh dari otak. Pada gambar. 2, terlihat bahwa respon terhadap frekuensi, tekanan darah adalah sama pada kontraksi statik yang dirangsang oleh rangsangan listrik (tidak ada pengaruh central, hanya ergoreceptors saja) dengan kontraksi volunter yang dipengaruhi oleh central
command dan ergoreceptors. Fakta ini membuktikan bahwa otot dapat berkontraksi tanpa selalu dipengaruhi oleh central command (otak). Pada penelitian lain, dilakukan blok anasthesi spinal terhadap latihan statik dan dinamik, dengan maksud menghilangkan efek neural reflex command dari ergoreceptors, hasilnya juga terjadi peningkatan cardiac output selama latihan dinamik karena adanya efek dari central command.
Gambar 2. A. Heart rate, B. Systolic blood pressure. C. Diastolic blood pressure response to static exercise voluntary contraction and electrical induced contraction.
Bukti lebih jauh untuk ke efektifan central command telah didapatkan dari penelitian fungsi neuromuscular dengan cara memblok sebagian / partial dengan decamethonium. Hasilnya ternyata lebih banyak motor impuls yang dikirim ke motor neuron yang menyebabkan motor unit cukup menghasilkan tegangan statis, katakanlah 10-30% dari kontraksi volunter maksimum. Mekanisme sentral maupun refleks saraf menghasilkan respon kardiovaskuler karena sama-sama mempengaruhi jalur saraf di sistem saraf sentral. Jika ada signal yang tidak proporsional dari mekanisme saraf pusat, maka akan digabungkan dengan pengaturan mekanisme refleks saraf, semakin besar keduanya menunjukkan respon terhadap HR dan BP.
Mekanisme kontrol untuk pulmonal atau sistem ventilasi selama latihan tampak pada gambar.3, pada respiratory system dan kardiovaskuler sistem di medulla oblongata mendapat descending impuls dari higher motor neuron di cerebrum dan ascending impuls dari mechano - metaboreseptor dari otot yang aktif,
di
samping kedua impuls itu ada impuls ketiga yaitu dari paru sendiri. Sensor di paru mendeteksi perubahan CO2 flow yang didapat dari cardiac output dan CvCO2 (konsentrasi CO2 dalam vena), yang mengatur C-fiber ending di n. vagus yang akan membawa informasi tentang meningkat/menurunnya CO2
flow ke paru. Selama istirahat atau latihan dengan intensitas yang rendah. Pengaturan frekuensi dan dalamnya pernapasan dilakukan oleh peningkatan aktivitas otot intercostalis dan diaphragma.
Tampak pada gambar.3, adanya impuls ke respiratory center, yaitu terdapat
79

beberapa reseptor, yakni reseptor yang berasal dari paru-paru dan reseptor di jalan napas, interkostal dan diaphragma muscle spindle, reseptor perifer di carotid body dan central chemoreseptor di medulla sendiri. Dan ada mekanisme feedback yang berasal dari paru-paru, receptor di jalan napas dan receptor di
otot-otot pernapasan, yang juga mempengaruhi arus, tekanan, volume dan tegangan yang berhubungan dengan kontrol pernapasan dan volume paru. Peripheral chemoreseptor akan peka terhadap perubahan pO2 dan ion H+, dan central chemoreseptor akan peka terhadap penurunan pH di cairan ekstraseluler cerebral.
Gambar 3. Kontrol sistem ventilasi selama latihan. Respiratory center menerima impuls dari motor region di otak, dari central chemoreseptor yang sensitif terhadap perubahan ion H+ dan menerima impuls dari reseptor spesial, termasuk paru-paru, reseptor jalan napas, reseptor CO2 paru, reseptor di otot-otot intercostalis dan diaphragma, metabo dan mechanoreceptors di otot-otot yang aktif dan kemoreseptor perifer. Kesemuanya ini akan menghasilkan penurunan aktivitas Parasimpatis di bronchioles dan meningkatkan impuls ke diaphragma dan otot intercostalis melalui nervous phrenicus dan intercostalis. Yang akhirnya akan menyebabkan exercise induced hyperpnea, peningkatan frekuensi dan dalamnya napas dan regulasi PO2, PCO2, serta pH.
Konsep yang berlaku pada regulasi neurohumoral exercise induced hyperpnea ini sesuai dengan model konsep ini (gambar), misalnya CO2 flow sebagai faktor humoral dapat mengendalikan ventilasi dalam berbagai macam kondisi pada saat istirahat atau gerakan yang kecil. Sedangkan pada saat latihan, akan dihasilkan neural impuls dari cerebral motor center untuk mengatur ventilasi guna
menghasilkan kekuatan otot dan laju metabolik. Dan jika latihan dilanjutkan, maka central neural regulation akan dibantu dengan pengendalian neural dari mechanoreceptor dan metaboreceptors.
Efektifitas pengaturan ventilasi dapat dilihat dari hasil antara produksi CO2 oleh otot yang aktif dan pengaruh yang kuat dari hyperpnea sebagai hasil dari regulasi PCO2
80

arteri dan konsentrasi ion H+. Tampaknya ini tidak sesuai antara stimulus pertama untuk bernapas selama latihan dengan respon yang ideal seperti regulasi penuh pCO2 arteri, yang mana akan menghasilkan isocapnic hyperpnea. Chemo-feedback dari perifer dan central reseptor akan memberikan tambahan stimulus ketika stimulus pertama tidak adekuat, dan menyebabkan hiperventilasi lebih kuat lagi. Ketepatan pengaturan lewat chemoreseptor feedback adalah kurang lebih 5 – 10 %, tapi ketidaktepatan tergantung pada individu selama melakukan latihan dengan intensitas yang tinggi.
Ada suatu bukti mengenai kontrol pada over ventilasi, karena respiratory center dapat mengatur keseimbangan selama latihan berat. Misalnya hyperventilation dan penurunan kadar CO2, respiratory center berusaha mengatur agar tidak terjadi efek metabolic acidosis, dan disaat yang sama juga melindungi efek hypoxemia dengan meningkatkan pengambilan oksigen dari udara ke alveoli.
Dalam latihan fisik yang terprogram (training) kontrol kardiovaskuler dan respirasi sangat penting, misalnya bradikardia pada orang yang terlatih disebabkan karena adanya perbedaan mekanisme kontrol saat istirahat dan selama latihan. Respon bradikardia saat istirahat disebabkan oleh perubahan kontrol Parasimpatis, dan penurunan pengendalian simpatis. Training mempunyai pengaruh terhadap muscle receptor yang kemudian menyebabkan terjadinya bradikardia. Orang yang terlatih ketika melakukan latihan yang berat akan menyebabkan respon terhadap frekuensi nadinya (takikardia) akibat efek feedback selama latihan. Perbedaannya antara orang yang terlatih dengan orang yang tidak terlatih tampak pada kontrol area ventilasi, dimana orang yang terlatih memiliki VE
increases per unit of metabolic rate yang rendah seperti VO2 uptake atau VCO2
production. Bisa dikatakan respon ventilasi terhadap rangsangan kimia relatif rendah. Hal lain yaitu pengendalian ventilasi terhadap hipoksia dan hiperkapnea dapat dilihat pada hasil pengukuran VO2 max.
Mekanisme Kontrol yang lain
Kontrol saraf pada sistem kardiorespiratori terutama bertujuan untuk efisiensi seluruh fungsi tubuh. Maka itu
kontrol ini tidak hanya diatur oleh central nervous system, tetapi juga diatur oleh peningkatan suhu darah (blood temperature), keasaman dan pergeseran ke kanan kurva HbO2 disosiasi selama latihan. Di samping itu, dengan faktor yang sama ditambah dengan pO2
yang rendah akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah arteri pada otot-otot yang aktif. Akibat dari hal ini akan menyebabkan respon perubahan antara lain peningkatan venous return akibat dari aktivitas mekanik otot dan pompa respirasi, dan adanya hemoconcentrasi yang disebabkan oleh perpindahan cairan antara otot-otot yang aktif dan darah. Kesemuanya ini guna untuk efisiensi sistem kardiovaskuler, khususnya selama latihan.
Tipe-tipe latihan
Seal dan Victor menambahkan adanya pengaturan dari “muscle sympathetic nerve activity” (MSNA) pada beberapa tipe latihan yang berbeda. Kontraksi otot dinamik maupun statik akan menyebabkan Rangsangan pada MSNA, yang menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah pada otot-otot yang tidak aktif. Intinya adanya vasokonstriksi menyebabkan darah mengalir ke tempat otot-otot yang aktif.
1. Penurunan vasokonstriksi pembuluh darah pada otot yang tidak aktif se-lama exercise akibat respon dari MSNA dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : jenis kerja yaitu kon-traksi dinamik atau statik, intensitas dan lamanya kontraksi, tingkat kondisi fisik dari otot, dan kecepatan ter-jadinya kelelahan otot.
2. Meningkatnya MSNA (pembuluh darah yang vasokonstriksi) selama latihan yang berat akan menyebabkan perubahan kadar norepinephrine, tahanan vaskuler, dan tekanan darah arteri. (merupakan respon fisiologis)
3. Respon MSNA pada level latihan yang sama menandakan kesehatan seseo-rang.
4. Selama kontraksi statik pada otot manusia, mekanisme pertama yang merangsang MSNA adalah metabore-ceptors command.
5. Stimulus MSNA dari metaboreflex otot, dapat terlihat pada latihan di-
81

namik baik yang sedang, maupun den-gan intensitas yang submaximal, tetapi tidak terjadi rangsangan pada intensi-tas yang rendah.
6. Peningkatan MSNA dari metaboreflex otot, juga terjadi pada latihan yang be-rat yang menyebabkan turunnya sim-panan glikogen otot (glycogenolysis) dan penumpukan ion hidrogen di dalam sel otot.
7. Pengaruh MSNA dalam penurunan ali-ran darah pada otot yang tidak aktif selama latihan isometric pada orang sehat tidak berkurang akibat pengaruh hambatan dari vagal reflex (parasym-pathetic of ANS), tetapi menghambat baroreflex arteri.
KESIMPULAN
Selama istirahat dan latihan, kontrol sistem kardiorespirasi sangat komplek. Kontrol ini terutama terdapat pada batang otak (brain steam) yaitu area respirator dan area sirkulator Adanya rangsangan humoral dan neural ke tempat area ini sangat penting untuk regulasi sistem kardiorespirasi, misalnya perubahan dari PO2, PCO2, dan konsentrasi H+.
Regulasi ini menyebabkan perubahan pada frekuensi nadi, kontraksi otot jantung, frekuensi dan dalamnya pernapasan, pengaturan aliran pembuluh darah melalui vasokonstriksi dan vasodilatasi.
Persarafan kardiorespirasi diatur oleh voluntary nervous system (mensuplai otot-otot respirasi) dan involuntary nervous system (yang mensuplai jantung dan pembuluh darah).
Pada saat istirahat, faktor penting dalam memelihara keseimbangan fungsi tubuh adalah perubahan tekanan darah, PO2, PCO2, dan konsentrasi H+. (adanya negative feedback)
Selama latihan, ada rangsangan predominan yang muncul : (1) peningkatan aktivitas motor Korteks, (2) kontraksi otot dan gerakan tubuh atau gerakan statis, (3) peningkatan konsentrasi ion H+ dan aliran CO2 di paru-paru, (4) peningkatan suhu darah, dan (5) sekresi norepinephrine dan epinephrine dari medulla adrenalis. Mekanisme lain adalah adanya pergeseran HbO2 dissociation curve dan vasodilatasi lokal pada otot.
Keduanya yaitu central command dan ergoreceptors command bekerja dalam
mengatur fungsi kardiorespirasi selama latihan. Metaboreceptors penting dalam keadaan vasokonstriksi aliran darah di otot-otot yang tidak aktif selama kontraksi isometric. Vasokonstriksi ini terjadi akibat dari MSNA dalam respon nya terhadap penurunan glikogen otot dan penumpukan ion H+ dalam otot. MSNA dipengaruhi oleh latihan dinamik yang sedang sampai berat, besarnya ukuran otot, latihan yang ritmik.
RUJUKAN
Fox E.L., Bowers R.W., Foss M.L. 1993. The Physiological Basis for Exercise and Sport, 5th. Ed. Boston-USA. WCB/McGraw-Hill. p. 275-282
Guyton A.C. 2000. Text Book of Medical Physiology, 10th. Ed. USA. W.B. Saunders Co.
82

PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID PADA TUBERKULOSAOleh :
Muzaijadah Retno ArimbiDosen Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ABSTRAKPenanganan tuberkulosa yang penting adalah diagnose dini dan pemberian kemoterapi yang
sesuai.Gambaran perjalanan penyakit dan gejala klinis tuberkulosa cenderung tergantung pada respon imun tubuh, bila dibanding virulensi kuman penyebabnya.
Imunitas pada tingkat seluler merupakan suatu keadaan dari tingkat dimana makrofag teraktifasi dan pengerahan makrofag pada lesi serta kemanpuan makrofag untuk menghancurkan kuman M.TB.
Kortikosteroid mempunyai kemanpuan mencegah atau menekan berkembangnya manifestasi inflamasi dan juga mempunyai nilai yang tinggi pada pengobatan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reaksi imun , baik kondisi yang berhubungan dengan imnunitas humoral maupun seluler.
Dari pengalaman dan penelitian yang pernah dilakukan, tidak semua infeksi tuberkulosa perlu mendapat tambahan kortikosteroid. Beberapa keadaan dimana kortikosteroid perlu dipertimbangkan pemakaiannya pada keadaan: Penderita tuberkulosa paru dengan keadaan penyakit berat dan tanda toksik ,TB Millier, efusi Pleura dan Pericarditis tuberculosa.
Kata Kunci : TB , Imunitas seluler / Humoral, Kortikosteroid, TB yang memerlukan Kortikosteroid.
USE CORTICOSTEROIDS IN TUBERCULOSISBy:
Retno Muzaijadah ArimbiLecturer Faculty of Medicine, University of Wijaya Kusuma Surabaya
ABSTRACTThe important Therapy of Tuberculosis, is early diagnosis and adeqwat chemotheraphy. History of
disease and clinical simptom of tuberculousa, not only depend on the bacterial virullency, but also depend on bodys immune respons.
In Cellular imunity, condition where actives of macrofag and work of macrofag in infected area, so power of macrofag to destroyed of MTB.
Corticosteroid can prevent or inhibit manifestation of inflamation,so have power to teraphy imunitys disease in cellular or humoral immunity.
From history and experiments study, Corticosteroid not for all M TB infection cases.Several condition use of Corticosteroid likes: Toxic or Severe Pulmonary TB, Milliary TB, Pleural effusion and TB Pericarditis.
Key words: TB , Cellular / Humoral Immunity, Corticosteroid, TB with corticosteroid
PEDAHULUAN Penyakit tuberkulosa sampai saat ini masih merupakan suatu masalah dalam kesehatan terutama di negara berkembang, karena masih menunjukkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Pada tahun 1993 WHO menyatakan bahwa di dunia terdapat 8 juta kasus baru per tahun, hal ini didukung oleh adanya epidemi infeksi terhadap AIDS (HIV). Penanganan tuberkulosa yang penting adalah diagnose dini dan pemberian kemoterapi yang sesuai.Lesi di paru sering dijumpai, meskipun lesi di tempat lain dapat terjadi misalnya di kelenjar
getah bening, selaput otak dan menyebar ke seluruh tubuh. Gambaran perjalanan penyakit dan gejala klinis tuberkulosa cenderung tergantung pada respon imun tubuh, bila dibanding virulensi kuman penyebabnya.Penggunaan kortikosteroid pada penyakit tuberkulosa hingga saat ini masih kontroversial. Pada penelitian terdahulu disebutkan bahwa penggunaan kortikosteroid pada tuberkulosa menyebabkan progresifitas penyakit, sehingga penggunaannya merupakan kontraindikasi. Sesuai dengan data-data terbaru menunjukkan bahwa dengan pemberian kortikosteroid yang digabung
83

dengan kemoterapi yang sesuai mempunyai manfaat pada keadaan tertentu pada tuberkulosa.Dalam tinjauan kepustakaan ini akan dibahas tentang imunologi tuberkulosa, daya kerja kortikosteroid dan penggunaannya pada tuberkulosa.
IMUNOLOGI TUBERKULOSAKuman tuberkulosa yang terkumpul dalam alveoli atau bronchioli terminalis jaringan paru membentuk proses keradangan yang dinamakan fokus primer (Ghon fokus), selanjutnya proses meluas ke kelenjar getah bening regional, sehingga terbentuklah komplek primer.Pada kebanyakan kasus keradangan primer ini dapat diatasi oleh sistim imun “host”, namun bila sistim imun tidak baik maka akan terjadi perluasan proses ke tempat lain seperti ke rongga pleura, maka terjadi pleuritis atau bila proses meluas ke kelenjar getah bening dihilus sehingga menekan bronchus maka terjadi kolaps paru (ateletasis) atau apabila meluas ke pericardium akan terjadi pericarditis dan dapat pula terjadi penyebaran secara sistemik sehingga terjadi meningitis tuberkulosa.Lesi yang telah sembuh pada suatu saat dapat terjadi ”reaktifasi” dan menampilkan bentuk klinis tuberkulosa post primer, dimana proses nekrosis lebih menonjol bila dibandingkan dengan tuiberkulosa primer.Pada awal kejadian infeksi tuberkulosa adalah setelah kuman terutama di alveoli akan segera diikuti oleh reaksi keradangan yang tersusun dari sel-sel darah putih terutama sel PMN, tapi peristiwa ini hanya berjalan singkat karena kemanpuan “fagositosis” PMN tidak memadai untuk kuman M.TB, meskipun makrofag mengambil alih tugas sel PMN, aqkibatnya terjadi peristiwa infiltrasi sel-sel makrofag ke dalam sel, sehingga bayak sel-sel makrofag yang didapatkan pada lesi keradangan, dimana secara patologi anatomi akan menunjukkan gambaran radang akut dan kronis.Pada tahap selanjutnya kuman M.TB. difagosit oleh makrofag jaringan dan pada saat inilah dimulai perjuangan mempertahankan hidup bagi kuman M. TB. Kuman ynag berada pada sel jaringan pelan-pelan dihancurkan secara proses biokimia (oksidasi dan Enzimatik). Dalam peristiwa ini lesi dapat sembuh sempurn atau sebaliknya bahwa kuman bertahan dan memperbanyak diri dalam makrofak.
Daya tahan “host” terhadap kuman M.TB. terutama terletak pada makrofak, sehingga bila daya tahan “host” tidak baik, maka akan menimbulkan mekanisme atau respon hipersentivity (imunitas) seluler yang terbentuk dalam kurun waktu 4 – 6 minggu setelah terinfeksi kuman M. TB.Pada penyakit tuberkulosa, hipersetivitas seluler merupaka bentuk statu imunologi yang meunjukkan bahwa sel-sel tubuh telah sensitif terhadap tuberkulin, dimana secara klinis dapat ditunjukkan dengan pemberian suntikan tuberkulin secara Mantoux, diman reaksi terhadap tuberkulin tersebut menunjukkan reaksi positif.Imunitas pada tingkat seluler merupakan suatu keadaan dari tingkat dimana makrofagteraktifasi dan pengerahan makrofag pada lesi serta kemanpuan makrofag untuk menghancurkan kumanM.TB.Makrofag dapat menghancurkan kuman dengan mengurng kuman tersebut dalam fagosom, selanjutnya fagosom bergabung dengan kantongan-kantongan lisosom yang mengandung enzim-enzim pencernaan didalam sitoplasma makrofag yang disebut fagolisosom, yang mampu menghancurkan kuman secara oksidatif dan enzimatik. Berkaitan dengan imunitas seluler tersebut, maka makrofag berdiferensiasi menjadi sel-sel epiteloid yang selanjutnya disebut granuloma. Sel-sel makrofag yang teraktifasi menbutuhkan banyak oksigen, dengan demikian bag terbebani oleh bebean antigen ian sentral granuloma akan mengalami anoksia, sehingga mengakibatkan sel-sel jaringan mengalami nekrosisyang bersifat asam yang disebut nekrosis kaseosa. Banyak oksigen dari fraksi molekul kuman ikut ikut menentukan bentuk imun seluler kearah bentuk yang menguntungkan atau merugikan untuk “host”. Bila produk dari kuman yang menyerupai tuberkulin terlalu banyak, maka akan menyebabkan terbentuknya nekrosis kaseosa, karena makrofag terbebani oleh beban antigen antigen yang berlebihan akan mengeluarkan mediator-mediator seperti TNF dan INF gama berlebihan seta sekresi enzim proteolitik meningkat, akibatnya jaringan sekitatnya akan mengalami “apoptosis” (Program Cell Death) dipercepat. Disamping itu terjadinya nekrosis jaringan dapat di sebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan akibat reaksi imflamasi yaitu reaksi lokal yang lambat karena terjadinya infiltrasi
84

selul antigen er pada pembuluh-pembuluh darah kecil.Pada umum perkenalan imun (imun recognition) pada tuberkulosa serupa dengan penyakit infeksi lainnya, yaitu APC (Anti Presenting Cell) akan memproses antigen untuk disajikan pada T limfosit. Makrofag yang teraktifasi akan mengeluarkan IL1 (Interleukin 1) dan TNF (Tumor Necrotizing Factor). Dibawah pengaruh IL1, resting T menjadi T yang teraktifasi selanjutnya akan mensekresi sitoksin, antra lain IFN (Interferon) gama dan IL2 melalui IL6 dan bersama MIF (Migration Inhibitory Factor) dapat memperkuat sel mediator respon INF gamma dapat mengaktifkan makrofag dengan menginduksi enzim pada mikrofag yang dapat merubah vitamin D3 menjadi calcitriol yang aktif, sehingga makrofag menjadi peka terhadap rangsang lipoarabinomanan untuk membebaskan TNF . TNF ini dalam keadaan normal bersifat protektif, karena dapat mengaktifkan sel fagosit dan membantu pembentukan granuloma.,namun apabila bila kadar TNF berlebihan mengakibatkan meluasnya proses tuberkulosa dan terjadilah kaheksia.
DAYA KERJA KORTIKOSTEROIDKortikosteroid mempunyai kemanpuan mencegah atau menekan berkembangnya manifestasi inflamasi dan juga mempunyai nilai yang tinggi pada pengobatan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reaksi imun , baik kondisi yang berhubungan dengan imnunitas humoral maupun seluler.Penggunaan kortikosteroid memberi semacam-macam efek, tetapi yang penting dalam kaitannya dengan infeksi khususnya tuberkulosa adalah sifat anti inflamasi dan anti alerginya. Pengertian yang berkaitan dengan anti inflamasi dan imunosupresi dari kortikosteroid masih merupakan permasalahan, namun akhir-akhir ini dapat dibedakan.Mekanis kerja korikosteroid adalah dengan menembus membran sel, kemudian didalam sitoplasma berikatan dengan suatu reseptor protein interseluler spesifik. Komplek reseptor steroid selanjutnya meninggalkan sitoplasma dan menuju inti sel, didalam inti sel mensintesa suatu protein baru yang mempengaruhi transkripsi dan translasi asam inti, sehingga terjadi perubahan inti sel. Kortikosteroid tidak hanya menghambat
fenomena awal dari inflamasi, tetapi juga mampu menghalau manifestasi lanjutannya. Dalam proses inflamasi bahan ini selain mampu mempertahankan tonus pembuluh darah. Agar peristiwa diapedesis leukosit, ekstravasasi cairan yang menyebabkan terjadinya odema setempat, serta migrasi sel-sel leukosit ke lokasi radang dapat dihambat. Proliverasi sel-sel vibroblas yang merupakan bagian dari proses reparasi juga dihambat oleh kortikosteroid. Hambatan ini pada satu sisi dapat mencegah pembentukan jaringan vibotik yang berlebihan, namun di sisi lain mempermudah terjadinya penyebaran kuman, hal ini tergantung pada dosis yang diberikan. Penggunaan kostikosteroid akan merubah kinetika dan jumlah leukosit dalam peredaran darah, dimana efek maksimum dicapai dalam 4-6 jam setelah pemberian dan kembali normal dalam 24 jam.Kortikosteroid akan meningkatkan jumlah sel netrofil dalam aliran darah oleh banyak netrofil baru yang dilepas dari sumsum tulang, disamping itu karena bertambah panjangnya umur netrofil dalam peredaran darah serta sedikitnya akumulasi netrofil di lokasi radang karena berkurannya perlekatan sel endotel pada vaskuler.Penggunaan kortikosteroid dapat menginduksi terjadinya limvopenia oleh karena banyaknya sel-sel limfosit dari peredaran darah menuju ke jaringan limfoid. Dua per tiga dari jumlah sel-sel limfosit dalam sirkulasi termasuk dalam kelompok limfosit re-sirkulasi yakni limfosit yang mudah untuk keluar dan masuk ke dalam sirkulasi. Di luar sirkulasi sel-sel ini berada dalam duktus thoraksikus, limfa, kelenjar limfe, dan sumsum tulang. Kortikosteroid lebih banyak mempengaruhi limfosit T untuk bermigrasi ke jaringan limfoid daripada limfosit B. Mekanisme tepat mengenai pengaruh kortikosteroid pada redistribusi limfosit ini masih belum jelas.Penggunaan kortikosteroid juga menginduksi terjadinya monositopenia, hal ini disebabkan oleh mekanisme redistribusi dan berkurangnya akumulasi sel monosit di tempat radang. Jumlah eosinofil dan basofil juga menurun dengan alasan yang sama dengan monosit. Efek kerja kortikosteroid pada sel-sel monosit dan manofag adalah dengan menurunkan efek endositosis dan kliren RES serta menghambat aktivitas bakterisidalnya. Kortikosteroid mempengaruhi makrofag dengan cara menghambat kerja MIF (Migrasi Inhibitory
85

Factor), sehingga makrofag mudah keluar dari jaringan yang dipengaruhinya, disamping itu kortikosteroid bekerja dengan cara meredam sintesa dan sekresi INF gamma dan IL1, dimana IL1 lebih dikenal sebagai pirogen endogen yang bertanggungjawab terhadap kenaikan suhu tubuh, sehingga kortikosteroid mampu menurunkan suhu tubuh. Kortikosteroid memberi efek stabilisasi terhadap membran lisosom yang dapat mencegah pelepasan enzim-enzim hidralase, sehingga daat mengurangi kerusakan jaringan. Kortikosteroid juga menekan perluasan CMI (Cell Mediated Imune) dengan cara menghambat respirasi gen IL2 dalam sel-sel T dan menghalangi interaksi IL2 dengan reseptornya didalam sel T.
PENGGUNAAN KORTIKOSTEROID PADA TUBERKULOSADari pengalaman dan penelitian yang pernah dilakukan, tidak semua infeksi tuberkulosa perlu mendapat tambahan kortikosteroid. Beberapa keadaan dimana kortikosteroid perlu dipertimbangkan pemakaiannya sebagai berikut:
1. Penderita tuberkulosa paru dengan keadaan penyakit berat dan tanda toksik.Dikatakan bahwa pemberian kortikosteroid mempercepat perbaikan klinis dan radiologis, tetapi kesembuhan tetap terantung obat anti tuberkulosa dan penggunaan kortikosteroid tidak dilakukan secara rutin, kecuali dalam keadaan berat yang memerlukan pengobatan suportif sampai obat anti tuberkulosa bekerja secara efektif.
2. Tuberkulosa MilierDikatakan bahwa angka kematian bisa mencapai 100% bila tidak diberikan pengobatan adekwat dan hal ini terjadi dalam 4-12 minggu dimulai timbulnya gejala klinis, kebanyakan disebabkan oleh karena penyebaran kuman ke susunan saraf pusat dan yang sering terjadi adalah meningitis tuberkulosa.Ada pendapat lain yang tidak menyetujui pemberian kortikosteroid oleh karena sebagian besar penderita tuberkulosa milier bila telah sembuh maka tidak meninggalkan gejala sisa, sehingga penggunaan kortikosteroid tidak dilakukan secara rutin.
3. Efusi pleuraDikatakan bahwa terapi pada pleuritis tuberkulosa bermanfaat mencegah terjadinya efusi pleura, memperpendek gejala klinis yang timbul dan mencegah kerusakan pleura, dimana penebalan pleura dan penurunan fungsi paru merupakan gejala sisa dari efusi pleura. Dikatakan bahwa terutama pada anak, bila terjadi komplikasi, maka fungsi parunya akan turun dan kortikosteroid tidak akan memperbaruhi fungsi parunya.Sejak pertengahan abad dilaporkan tentang manfaat pemberian kortikosteroid per oral dan intra pleura, khususnya dalam mempercepat penyerapan cairan pleura.Berger dan Meiji tahun 1993 melaprkan bahwa tidak ditemukan adanya penyerapan cairan pleura total, tanpa silakukan torakosintesis dan terapi obat anti tuberkulosa, disamping itu pemberian kortikosteroid tidak memberikan manfaat jangaka panjang serta tidak pernah dilaporkan adanya manfaat kortikosteroid dalam mencegah penebalan pleura dan penurunan faal paru.Dalam penyelidikan terbaru tahun 1996 dilaporkan bahwa kortikosteroid mempercepat penurunan panas badan pada penderita dengan kortikosteroid, dengan perbandingan 2,4 hari dan 9,2 hari dan mempercepat penyerapan cairan pleura dengan perbandingan pemakai kortikosteroid dan plasebo adalah 54,4 hari 132,2 hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan kortikosteroid dengan kombinasi OAT mempercepat perbaikan klinis dan penyerapan cairan pleura, tetapi tidak dapat memperbaiki faal parunya bila terjadi komplikasi.
4. Perikarditis tuberkulosaPerikarditis tuberkulosa merupakan hal yang jarang terjadi, dilaporkan terdapat 44 kasus 3002 penderita tuberkulosa di inggris dalam penelitian selama 6 bulan.Strang dan kawan-kawan pada tahun 1972 melaporkan bahwa dari 143 penderita OAT dengan kombinasi kortikosteroid atau placebo 30 mg yang diberikan secara randomm
86

selama 4 minggu, diteruskan 15 mg per hari selama 2 minggu dan diturunkan secara bertahap sampai 5 mg per hari sampai hari ke sebelas. Dikatakan selama follow up ditemukan 2 dari 53 penderita dengan kortikosteroid dan 7 dari 61 penderita dengan placebo, meninggal dengan pericarditis tuberkulosa, serta 11 penderita dengan kortikosteroid dan 18 penderita dengan placebo menjalani kardiotomi.Alzer dkk pada tahun 1993 melaporkan pula bahwa 170 penderita dengan pericarditis tuberkulosa yang di terapi dengan OAT yang dikombinasi dengan kortikosteroid dan placebo, didapatkan 2 dari 76 penderita dengan kortikosteroid serta 10 dari 24 penderita dengan placebo, meninggal dunia serta 7 dari 17 penderita dengan atau tanpa kortikosteroid menjalani kardiosentesis terbuka, sehingga dikatakan bahwa “drainage” perikard terbuka tetap diperlukan untuk mempercepat kardiosentesis.
5. Meningitis tuberkulosameskipun ada beberapa tuberkulosa SSP, namun meningitis tuberkulosa insidenya menduduki tempat tertinggi dengan angka kematian (20-50%).Pada penelitian awal sekitar tahun 1976 dikatakan bahwa kortikosteroid secara “parenteral “dan “intrakekal” memberi manfaat, dimana efeknya mengurangi peradangan, menurunkan tekanan intrakranial, mengurangi odema otak, menghambat terbentuknya jaringan fibrous, mempercepat perbaikan konsentrasi protein serta jumlah sel darah putih pada cairan cerebro spinal.Toole dan kawan-kawan pada tahun 1961 mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna dalam hal menurunkan odem cerebri pada pemakaian kortikosteroid ataupun placebo. Dalam penyelidikan ini kortikosteroid 2,5 mg diberikan secara intravena setiap 6 jam selama 1 minggu dan diturunkan secara bertahap selama 3 minggu. Escobar dan kawan-kawan pada tahun 1991 melaporkan bahwa tidak ada
perbedaan bermakna antara pemakai kortikosteroid 10 mg/Kg bb/ hari dalam terapi meningitis tuberkulosa. Humpries dan kawan-kawan pada atahun 1995 melaporkan bahwa angka kematian penderita miningitis tuberkulosa yang menggunakan kortikosteroid pada stadium II 4,9% dan stadium III 30%, dibanding penderita dengan placebo yakni dengan angka kematian pada stadium II sebesar 11% sedangkan stadium III sebesar 60,9%. Dikatakan bahwa pemberian kortikosteroid pada meningitis tuberkulosa stadium I kurang bermanfaat, sebab kerja kortikosteroid baru nampak bila sudah terjadi “blok” pada saraf spinal.Kortikosteroid yang cukup banyak dipakai adalah golongan trednison, namun dapat pula dipakai preparat lain dengan dosis ekuivalen 1 mg/Kg bb/hari. Pada umumnya pretnison yang diberikan sebesar 40-60 mg/hari selama 4-7 hari, dilanjutkan dengan dosis 30-50mg/hari selama 4-7 hari, kemudian diberikan dosis 10-30mg/hari selama 5-8 minggu yang diturunkan terus sampai habis.Dosis ekuivalen beberapa preparatkortikosteroid adalah sebagai berikut:- kortisol (hidrokortisol) : 20mg- metilprednisolon : 4mg- kotison : 20mg - triamisolon : 4mg- prednison : 5mg- betametason : 0,60mg- dexametason : 0,75m
KESIMPULANHingga saat ini pengunaan kortikosteroid pada tuberkulosa masih kontroversial. Dahulu pengobatan dan kortikosteroid menyebabkan progesifitas penyakit dasarnya. Tetapi ada beberapa peneliti yang melaporkan adanya manfaat penggunaan kortikosteroid disertai terapi anti tuberkulosa yang adekwat.Pengguanan kortikosteroid pada tuberkulosa banyak dapat dipertimbangkan pada keadaan tertentu dari penyakit-penyakit seperti tuberkulosa yang berat disertai tanda-tanda tiksik, tuberkulosa millier, efusi pleura, perikarditis tuberkulosa dan meningitis tuberkulosa.
87

Penghentian pemakaian kortikosteroid hendaknya dilakukan secara bertahap, sedangka yang perlu diperhatikan selama penurunan bertahap tersebut adalah eksaserbasi penyakit dasarnya.
DAFTAR PUSTAKAAlgostini C, Chilosi M,Zambello R,et al.
1993.Pulmonary Immune Cell in health and disease limfosit. Eur.Resp.J
Millier therapy. Tubercle and Lung Disease.Barnes PJ, adcock IM. 1997. Glucocorticoid
Receptor, in Lung Scientific Foundation.Lippincott Raven Publisher.Philadelphia.
Baxter JD, Forsham MA. 1972. Tissue effect of glucocorticoids. Am.Jour.Med.Christopher, Gerhard W. 1996. Corticosteroid andf treatment of Tuberculosis Pleurisy. Chest.Colton SJ, Douglas A. 1981. Respiratory disease. Singapore,Hongnkong,New dwlhi.Danberg AM. 1985. Celluler Hypersensitivity
and celluler Immunity in the pathogenesis of Tuberculose, Spesificity, systemic, and local nature also assosiated macrofag enzymes. Bacteriology Cal. Rev
Fauci AS, dale DC, Ballow JM. 1976. Glucocorticoi Theraphy. Mechanism of action and clinical consideration. Ann. Intern med.
Galarza I, Canete C, Granados A. 1995. Randomized Trial of Corticosteroid in the treatment of Tubercolous Pleurisy. Thorax.
Gilmans and Goodman. 1991. ACTH, Adrenocorticosteroid,inhibitor of syntesis.In: The Farmacological Basis of therapeutics.New York,Oxford.
Grabner W. 1072. Corticosteroid Long Term therapy. The medical clinic with polyclinic of the University Erlangen- neurenberg.
Humpries MJ, Teoh R, Lau J, et al. 1991. Factors of Prognostic Significancy in Chinese Children with tuberculosis Meningitis.
Kendig EL, Selman LS. 1990. Tuberculosis .In: Disorders of the Respiratorytract infection in Children. WB Saunders Company.Philadelphia.London.
Sahn S, Neff TA. 1990.Millier Tuberculosis.Am,Jour.Med.
Steeteen DHP, Phill MBD.1975. Corticosteroid therapy in: Pharmacological Properties and Principles of Corticosteroid use. Jama
Thomas Kardjito. 1991. Host defence Against tuberculosis, departement of pulmonogy of Medical School Airlangga University.Surabaya
Thomas Kardjito.1992. Imunologi Tuberkulosa. Dalam: pendidikan Kedokteran berkelanjutan Ilmu Penyakit paru. Universitas Airlangga, Surabaya
Thomas kardjito. 1982. Pengertian dasar Imunologi Tuberkulosa. Dalam: Simposium tuberkulosa. Surabaya
88

89