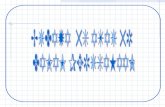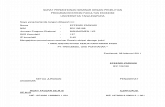CONCEPT_PAPER_PENCEGAHAN_BENCANA_BANJIR_YLI_OXFAM.pdf
-
Upload
endang-seolehudin -
Category
Documents
-
view
14 -
download
0
Transcript of CONCEPT_PAPER_PENCEGAHAN_BENCANA_BANJIR_YLI_OXFAM.pdf
-
Page 1 of 20
CONCEPT PAPER
Perencanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir
Berbasis Wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai)
Untuk Mewujudkan
VISI INDONESIA BEBAS BANJIR
Disusun oleh:
Yayasan Lestari Indonesia
(Gunawan, Aris Sustiyono, Anggoro, M)
Direvisi oleh:
1. Prof. Dr. Ir. Naik Sinukaban, M.Sc
2. Dr. Al. Sentot Sudarwanto, S.H. M.Hum.
3. Lukman Hakim, Msi.
Kerjasama,
YOGYAKARTA, Oktober 2014
-
Page 2 of 20
CONCEPT PAPER
Perencanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir
Berbasis Wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai)
Abstrak
Maksud dan tujuan penulisan Concept Papaer ini adalah untuk menyamakan
persepsi stakeholders terkait sebab akibat dan proses terjadinya bencana banjir. Dan
merumuskan rekomendasi penyusunan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan
bencana banjir berbasis wilayah daerah aliran sungai (DAS) dan penguatan kapasitas
penyelenggara penanggulangan bencana di daerah, penguatan kapasitas kelembagaan
pengelola DAS. Idea penyusunan Concept Paper ini berawal dari pernyataan para pihak
yang hadir dalam Workshop Meningkatkan Koordinasi Kesiapsiagaan Terhadap
Ancaman Banjir Sungai Bengawan Solo, yang dilaksanakan pada Bulan Desember
Tahun 2013 di Surakarta. Dalam workshop tersebut disepakati bahwa penanggulangan
bencana banjir selain dengan kesiapsiagaan juga harus dilakukan upaya pencegahan
secra terpadu dan terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir.
Untuk memahami keterkaitan banjir dengan wilayah DAS dan permasalahan yang
ada di dalamnya, kemudian diselenggarakan Simposium Regional Revitalisasi Sungai
Bengawan Solo; Menyelaraskan Tata Kehidupan dan Ekosistem di Surakarta dan
dilanjutkan di Jakarta dengan Simposium Nasional Membangun Sinergi Antar
Multistakeholder Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Hidrologi di Indonesia. Dari
kedua simposium tersebut diperoleh gambaran umum sebab akibat bencana banjir, serta
gambaran hambatan dan kendala yang dialami stakeholders dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana banjir.
Untuk melengkapi informasi yang sudah di hasilkan dalam workshop dan
simposium, kemudian dilakukan kajian literatur dengan pendekatan induktif dan
deduktif melalui kegiatan desk review dan focus group discusion (FGD) yang
melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan representatif dari unsur masyarakat sipil
(CSO), lembaga swadaya masyarkat (LSM) dan akademisi. Kajian literatur ditujukan
kepada peraturan perundang-undangan, hasil kajian lain, dan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang sudah diterapkan.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah: (1) bencana banjir sangat terkait erat dengan
kondisi wilayah DAS; (2) penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di daerah
-
Page 3 of 20
belum sesuai seperti yang di mandatkan dalam UU PB, khususnya pada tahapan
prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana; (3) ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana tidak cukup
untuk menjawab permasalahan bencana banjir di wilayah DAS lintas provinsi dan DAS
lintas kabupaten/ kota.
Dalam concept paper ini, berdasarkan hasil workshop, simposium dan kajian
literatur, direkomendasikan perlu penyusunan perencanaan penanggulangan bencana
banjir berbasis wilayah DAS dan penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara
penanggulangan bencana di daerah.
Kata kunci: Kebijakkan, Perencanaan, Penanggulangan Bencana, Banjir, Daerah
Aliran Sungai (DAS)
I. LATAR BELAKANG
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis,
geologis, hidrologis, dan demografis yang unik dan spesifik yang tidak ada di
wilayah lain di dunia. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di daerah
khatulistiwa di antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik
dan Hindia, berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan
wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi,
dan letusan gunung api. Selain itu, Indonesia yang beriklim tropis dengan dua
musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau juga sangat rawan terjadinya
bencana yang terkait hidroklimatologis seperti angin puting beliung, banjir,
kekeringan dan kebakaran hutan.
Dengan sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang mencpai
237,6 juta jiwa dengan penyebaran tidak merata serta ketimpangan sosial dan
masalah penyimpangan pemanfaatan kekayaan alam dapat meningkatkan eskalasi
dan macam bencana. Bencana yang muncul tidak hanya bersumber dari gejala
alam tapi juga berkaitan dengan prilaku manusia terhadap alam/ lingkungan.
Iklim sudah dan akan terus berubah, perubahan iklim ini menimbulkan
potensi bencana di Indonesia1. Dari laporan para ahli di dunia, iklim global
1Nurhayati. (2014). Peran BMKG dalam menghadapi Bencana Hidrometeorologi. Presentasi dalam Simposium Nasional, Yayasan Lestari Indonesia Oxfam, Jakarta.
-
Page 4 of 20
mengalami perubahan yang cukup signifikan dan Indonesia sebagai negara
kepulauan juga terpengaruh dengan adanya perubahan iklim tersebut. Hasil
kajian yang dilakukan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
sebuah panel ahli internasional yang ditunjuk untuk mengkaji aspek-aspek
ilmiah tentang perubahan iklim dan memberikan masukan kepada Unaited
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), bahwa dampak
perubahan iklim di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia,
diperkirakan akan meningkatkan ancaman terhadap ketahanan pangan,
kesehatan manusia, ketersediaan air, keragaman hayati, dan kenaikan muka
air laut2.
Cuaca ekstrim seperti curah hujan yang tinggi memang menjadi faktor
pemicu terjadinya banjir. Tetapi selain itu masih ada penyebab lain yang
mengakibatkan terjadinya banjir. Perubahan iklim memicu lebih banyak cuaca
ekstrem yang menghasilkan bencana, seperti yang terjadi di Daerah Khusus
Ibukota (DKI) Jakarta pada Januari hingga Februari 2013.3 Pemerhati sekaligus
pakar lingkungan dari Universitas Riau, Tengku Ariful Amri, mengatakan, cuaca
ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah Tanah Air adalah dampak dari
terhambatnya siklus hidrologi4. Berubahnya pola siklus hidrologi ini menurut
Tengku Ariful Amri disebabkan karena adanya perubahan kondisi wilayah DAS.
Menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (DIBI-BNPB) kejadian banjir di Indonesia yang dicatat
mulai Tahun 1815 2014 sebanyak 5,541 kejadian, atau sebanyak 37 % dari
seluruh kejadian jenis bencana. Sedangkan sebaran jumlah kejadian bencana
banjir terbanyak berada di pulau Jawa. Kemudian melihat data jumlah penduduk
hasil sensus penduduk Tahun 2010, penduduk pulau Jawa mendominasi dengan
jumlah mencapai 58 % dari 237,6 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa
kerusakan wilayah DAS sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir lebih
banyak dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan.
2http://www.wwf.or.id/?29541/Laporan-IPCC-ke-5-Kelompok-Kerja-I-Perubahan--Iklim--Nyata--Umat
Manusia-Menghadapi-Ancaman-Serius diakses pada tanggal 07 Oktober 2014 pukul 14:19 WIB
3http://sains.kompas.com/read/2013/01/20/17502648/Enam.Dampak.Perubahan.Iklim.pada.Hidup.Kita
diakses pada tanggal 06 Oktober 2014 pukul 14:47 WIB
4http://www.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/12/01/06/lxcuef-ini-dia-faktor-penyebab cuaca-
ekstrem-di-indonesia diakses pada tanggal 07 Oktober 2014 pukul 14:13 WIB
-
Page 5 of 20
II. TUJUAN
Penyusunan Concept Paper ini bertujuan untuk:
1. Menyamakkan persepsi stakeholders terkait sebab akibat bencana banjir;
2. Merumuskan rekomendasi penyusunan perencanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana banjir berbasis wilayah daerah aliran sungai
(DAS);
Keluaran yang diharapkan adalah:
1. Adanya kesamaan persepsi dari stakeholders terhadap penyebab dan
akibat bencana banjir;
2. Adanya rekomendasi penyusunan perencanaan penyelenggaraan
penanggulangan bencana banjir berbasis DAS;
Kajian ini difokuskan pada aspek non teknis. Untuk mempertajam analisis,
ruang lingkup kajian ini dibatasi pada: (1) pengumpulan dan analisis data
sekunder tentang sebab akibat dan proses terjadinya banjir; (2) analisis kebijakan
penyelenggaraan penangulangan bencana banjir; (3) penyusunan rekomendasi
penyusunan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir
berbasis wilayah DAS.
III. METODOLOGI
Dalam penyusunan Concept Paper ini menggunakan dua pendekatan, yaitu
dengan pendekatan induktif dan pendekatan deduktif.
1. Pendekatan induktif dilakukan dengan cara analisis pengalaman empirik
berkenaan dengan penanggulangan bencana banjir. Untuk mengeksplorasi
dan mencari data melalui kegiatan Desk Review, workshop, simposium dan
focus group dicussion (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak yang
berkompeten dan representatif. Pihak yang terlibat adalah masyarakat sipil
(CSO), lembaga swadaya masyarkat (LSM), akademisi dan pemerintah.
2. Pendekatan deduktif dikerjakan dengan cara analisis perspektif dan
konseptual dari buku-buku yang membahas mengenai DAS dan bencana
alam, khususnya bencana banjir, analisis regulasi dan kebijakan.
-
Page 6 of 20
Penyusunan Concept Paper ini berpijak dari pernyataan para pihak yang
hadir dalam Workshop Meningkatkan Koordinasi Kesiapsiagaan Terhadap
Ancaman Banjir Sungai Bengawan Solo, yang dilaksanakan pada Bulan
Desember Tahun 2013 di Surakarta. Dalam workshop tersebut disepakati bahwa
penanggulangan bencana banjir selain dengan kesiapsiagaan juga harus dilakukan
upaya pencegahan untuk pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan
pihak yang terancam bencana.
Untuk memahami keterkaitan banjir dan wilayah DAS serta untuk memahami
permasalahan yang ada di Sungai Bengawan Solo kemudian diselenggarakan
Simposium Regional Revitalisasi Sungai Bengawan Solo; Menyelaraskan Tata
Kehidupan dan Ekosistem di Surakarta dan dilanjutkan di Jakarta dengan
Simposium Nasional Membangun Sinergi Antar Multistakeholder Dalam
Menghadapi Ancaman Bencana Hidrologi di Indonesia. Dari kedua simposium
tersebut diperoleh gambaran umum sebab akibat bencana banjir, serta gambaran
hambatan dan kendala yang dialami pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana banjir.
A. KERANGKA ANALISIS
1. Sebab Akibat Banjir
Banjir didefinisikan sebagai peristiwa atau keadaan dimana
terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang
meningkat. (Pusat Data dan Informasi, BNPB, 2008). Secara alamiah
banjir, adalah proses alam yang biasa dan merupakan bagian penting dari
mekanisme pembentukkan dataran di bumi. Proses terjadinya banjir
dibagi dua yaitu proses yang terjadi secara alamiah dan non alamiah.
Proses terjadinya banjir secara alamiah seperti, air hujan yang turun
sebagian tidak terserap oleh tanah dan menjadi aliran permukaan (run
off) kemudian menggenang di dataran yang lebih rendah. Sedangkan
proses terjadinya banjir secara non alamiah, karena ulah manusia sebagai
contoh adalah prilaku manusia membuang sampah ke sungai dan
mendirikan bangunan di sepadan sungai mengakibatkan terhambatnya
aliran air dan kemudian melimpas ke daratan.
Terjadinya banjir sangat terkait erat dengan siklus hidrologi yang
terjadi di wilayah DAS sebagaimana yang digambarkan pada Gambar 1.
-
Page 7 of 20
Gambar 1.
Siklus Hidrologi
(Sumber : Rahayu dkk., Banjir dan Upaya Penanggulangannya,)
Siklus hidrologi menggambarkan mekanisme pendistribusian
massa air yang bergerak melalui berbagai media dan dalam berbagai
bentuk karena adanya pengaruh radiasi matahari dan gravitasi bumi.
Banjir terjadi pada saat pergerakan massa air dalam bentuk aliran
permukaan terhambat oleh rendahnya kapasitas pembuangan sehingga
terjadi genangan di wilayah yang lebih rendah5.
Kategori atau jenis banjir terbagi berdasarkan lokasi sumber aliran
permukaannya dan berdasarkan mekanisme terjadinya banjir.
Berdasarkan sumber aliran permukaannya, banjir ada dua jenis, yaitu
banjir kiriman dan banjir lokal. Sedangkan berdasarkan mekanisme
terjadinya, banjir bisa dibedakan antara banjir yang diakibatkan oleh
hujan dan banjir yang diakibatkan oleh selain hujan, seperti tsunami,
gelombang pasang (ROB) dan banjir akibat rusaknya bendungan
(Rahayu dkk, 2009).
2. Manajemen Bencana
Momentum upaya penanggulangan bencana di tingkat global
terjadi pasca bencana besar berupa gempa bumi dan tsunami yang
melanda beberapa negara di asia tenggara, termasuk Indonesia pada
tahun 2004. Setahun kemudian pada bulan Januari 2005, lahirlah
5 P. Rahayu, H. et al (2009) Banjir dan Upaya Penanggulangannya. ......
-
Page 8 of 20
kesepakatan global tentang Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework
for Action/HFA). Kerangka Aksi ini ditandatangani oleh 168 negara
(termasuk Indonesia) di Kobe, Jepang pada World Conference on
Disaster Reduction. Jauh sebelum adanya kesepakatan tersebut,
sebetulnya sudah ada perhatian dari salah satu badan PBB (Perserikatan
Bangsa-Bangsa) tentang bencana. Pada tahun 1990-an Unaited Nations
Development Programe (UNDP) dan Unaited Nation Disaster Risk
Organization (UNDRO) sudah menjalankan program pelatihan
manajeman bencana, dalam program ini kemudian menerbitkan modul
dasar untuk pelatihan manajemen bencana.
Dalam Modul Dasar yang diterbitkan oleh UNDP/UNDRO dengan
judul Tinjauan Umum Manajemen Bencana edisi ke 2 pada tahun 1992
untuk Program Pelatihan Manajemen Bencana, Bencana adalah
gangguan yang serius dari berfungsinya satu masyarakat, yang
menyebabkan kerugian-kerugian yang besar terhadap lingkungan,
material dan manusia, yang melebihi kemampuan dari masyarakat yang
tertimpa bencana untuk menanggulangi dengan hanya menggunakan
sumber-sumber daya masyarakat itu sendiri. Bencana sering
diklasifikasikan sesuai dengan cepatnya serangan bencana tersebut
(secara tiba-tiba atau perlahan-lahan) atau sesuai dengan penyebab
bencana itu (secara alami atau karena ulah manusia).
Proses terjadinya bencana tidak terlepas dengan adanya bahaya,
kerentanan dan kapasitas yang ada di masyarakat. Bencana terjadi saat
bahaya muncul dalam lingkungan masyarakat dengan kerentanan yang
tinggi sementara kapasitasnya rendah. Faktor-faktor penyebab bencana
antara lain; kemiskinan, pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang cepat,
transisi-transisi di dalam praktek-praktek kultural, degradasi lingkungan,
kurangnya kesadaran dan informasi, perang dan kerusuhan sipil
(UNDP/UNDRO, 1992).
Pengertian bencana secara normatif tercantum dalam Pasal 1 UU
PB disebutkan; Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor
-
Page 9 of 20
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia,kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Definisi manajemen bencana menurut UNDP/UNDRO adalah
sekumpulan kebijakan dan keputusan- keputusan administratif dan
aktivitas-aktivitas operasional yang berhubungan dengan berbagai
tahapan dari semua tingkatan bencana. Di Indonesia, dalam UU PB tidak
menggunakan istilah manajemen bencana, tetapi dengan istilah
penanggulangan bencana yang pengertiannya disebutkan dalam Pasal
1, Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan
rehabilitasi.
Seiring meningkatnya perhatian dan kesadaran manusia terhadap
permasalahan bencana, kemudian muncul konsep pengurangan risiko
bencana (PRB). Salah satu peneliti yang mengenalkan konsep ini adalah
John Twigg dari University College London pada tahun 2007. Sedangkan
pengertian PRB adalah sebuah pendekatan sistematis untuk
mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko bencana (Jhon Twigg,
2009).
Istilah PRB kemudian digunakan oleh berbagai lembaga NGO
(Non Goverment Organization) sebagai istilah yang memayungi untuk
membantu mengintegrasikan bencana dan pekerjaan pembangunan. Para
penggagas konsep ini berpandangan bahwa dalam mengatasi
permasalahan bencana, faktor bahaya, baik bahaya alamiah atau bahaya
akibat prilaku manusia tidak bisa sama sekali dihilangkan. Usaha yang
bisa dilakukan dengan mengurangai kerentanan dan meningkatkan
kapasitas lingkungan dan masyarakat dengan mengintegrasikannya
dalam proses pembangunan. Proses pembangunan selain berdampak
positif bagi perkembangan masyarakat, disisi lain juga menciptakan
kerentanan-kerentanan. Pada Gambar 2 berikut ini bisa dilihat hubungan
antara bencana dengan pembangunan.
-
Page 10 of 20
Gambar 2.
Hubungan Bencana dengan Pembangunan
(Sumber: UNDP/UNDRO, Tinjauan Umum Manajemen Bencana)
Dalam proses PRB bahaya yang ada di identifikasi dan dihitung
risiko-risiko yang mungkin muncul di masa yang akan datang. Tugas
keseluruhan dari manajemen risiko harus mencakup baik estimasi dari
besarnya risiko khusus dan juga evaluasi terhadap betapa pentingnya
risiko. Proses manajemen risiko mempunyai dua bagian: penilaian risiko
dan evaluasi risiko. Penilaian risiko memerlukan penghitungan risiko dari
data dan pemahaman proses-proses yang terlibat. Evaluasi risiko adalah
penilaian bahwa satu masyarakat menempatkan risiko-risiko yang
menghadang mereka dalam menentukan apa yang harus dilakukan
terhadap risiko-risiko tersebut (UNDP/UNDRO, 1992)
3. Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik diartikan sebagai
pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang
keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat
melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut
merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang
merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.
Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan
-
Page 11 of 20
sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian
kerja pejabat publik.6
Namun dalam hal ini kebijakan diartikan dalam arti sempit, yaitu
kebijakan yang masih harus dijabarkan terlebih dahulu di dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 1 Undang Undang
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan,
kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/
Daerah untuk mencapai tujuan.
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) disebutkan jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : a.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.
Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c.
Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah.
B. DATA
Dalam kajian ini menjaring informasi tentang penyebab dan dampak
banjir, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, hambatan dan
kendala yang dihadapi, pada tahapan prabencana ketika tidak terjadi bencana.
Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, sedangkan workshop dan
simposium dilakukan dengan melibatkan stakeholders dari unsur
decision/policy maker di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,
terutama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), instansi yang
menangani pengelolaan wilayah sungai (WS) dan instansi yang berwenang
dalam pengelolaan DAS. Dari unsur intermediaries, FGD dilakukan dengan
pakar dari perguruan tinggi, profesional dan pemerhati bidang sumberdaya air
dan DAS, serta LSM yang peduli terhadap masalah banjir dan pengelolaan
DAS.
6 Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik
yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003,
-
Page 12 of 20
IV. HASIL KAJIAN
A. Temuan Hasil Workshop, Simposium, dan Penelusuran Data Sekunder
Dari hasil workshop dan simposium, terungkap penyebab banjir di
wilayah DAS Bengawan Solo antara lain: (1) tingginya curah hujan dengan
durasi yang panjang; (2) berkurangnya daerah tangkapan air di wilyah hulu
karena alih fungsi lahan, sementara upaya penghijauan belum optimal; (3)
terjadinya pendangkalan di waduk dan sungai dari sedimen yang menumpuk
karena tingkat erosi yang cukup tinggi; (4) daya tampung sungai dan drainase
yang tidak memadai dan kurang terpelihara; (5) banyak sampah padat yang
dibuang ke sungai maupun drainase dan masih ada bangunan yang didirikan
di bantaran sungai sehingga menghambat aliran air, dalam hal ini kesadaran
masyarakat masih rendah. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil
dikumpulkan, dan dilihat dari proses terjadinya banjir yang terjadi di wilayah
DAS Bengawan Solo lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non alam, yaitu
karena faktor manusia.
Sedangkan akibat atau dampak banjir di DAS Bengawan Solo yaitu; (1)
adanya korban jiwa baik yang meninggal atau sakit; (2) terganggunya
aktifitas sosial ekonomi dan proses pendidikan di masyarakat; (3)
terganggunya akses transportasi antar daerah; (4) terganggunya ases air bersih
bagi masyarakat; (5) menurunnya produktifitas hasil pertanian; (6) kerusakan
infrastruktur di wilayah sekitar sungai; (7) munculnya bahaya sekunder
seperti menyebarnya wabah penyakit.
Melihat persebaran wilayah yang terdampak banjir Sungai Bengawan
Solo dan penyebab terjadinya banjir, dalam kajian ini juga mengidentifikasi
stakeholders dari unsur decision/policy maker terkait pemanfaatan dan
pengelolaan wilayah DAS lintas provinsi. Dari identifikasi dan penelusuran
data sekunder, stakeholders tersebut yaitu: (1) BP DAS (Balai Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai), di koordinasikan oleh Kementerian Kehutanan; (2)
BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), di koordinasikan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum; (3) pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang ada, Stakeholders inilah yang memiliki kewenangan dan tanggung
jawab dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan di
wilayah DAS.
-
Page 13 of 20
Kemudian sektor-sektor yang mempengaruhi kondisi wilayah DAS,
antara lain; (1) sektor kehutanan; (2) sektor pertanian; (3) sektor SDA
(sumber daya air); dan (4) sektor pemukiman. Ke 4 (empat) sektor tersebut
masing-masing memiliki regulasi dan kebijakan sendiri-sendiri dalam
mengimplemntasikan program kerjanya. Meskipun dalam peraturan
perundang-undangan mengintruksikan untuk melakukan koordinasi dan
sinkronisasi dalam menerapkan kebijakannya, tetapi pada kenyataannya hal
tersebut belum dilakukan secara optimal.
Usaha penanggulangan banjir sudah dilakukan baik oleh pemerintah
daerah maupun pemerintah pusat mulai pada tahapan prabencana, saat
terjadinya bencana dan setelah terjadinya bencana. Berdasarkan informasi
yang terhimpun, penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir pada
tahapan ketika terjadinya bencana atau pada saat tanggap darurat, pemerintah
daerah dan masyarakat terlihat lebih siap. Sedangkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana banjir pada tahapan prabencana belum
menunjukkan hasil yang optimal. Pemerintah daerah selaku penanggung
jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah mengahadai
berbagai hambatan dan kendala, antar lain: a) tidak adanya aturan hukum
yang spesifik mengatur tentang penanggulangan bencana banjir; b)
kewenangan pemerintah daerah terbatas pada wilayahnya masing-masing,
sementara persolaan banjir faktor penyebabnya tidak selalu berada di
wilayahnya; c) belum memadainya kapasitas penyelenggara penanggulangan
bencana yang ada di daerah.
Kebijakan pemerintah terkait penanggulangan bencana banjir yang
kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain; (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, dengan
istilah daya rusak air; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
Tentang Sungai (PP 34/2011); (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangan Bencana; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Umum Mitigasi Bencana; (6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor.
-
Page 14 of 20
B. Analisis
1. Penyebab dan Proses Terjadinya Banjir
Dari data sekunder dan informasi yang terkumpul, penyebab banjir
pada dekade sebelum tahun 1970-an lebih disebabkan oleh faktor alam,
yaitu dari curah hujan. Seperti banjir besar yang pernah terjadi di Sungai
Bengawan Solo pada Tahun 1966. Seiring pesatnya proses pembangunan
dan pesatnya pertambahan jumlah penduduk, penyebab banjir setelah
tahun 1970-an lebih disebabkan oleh faktor non alam, yaitu karena
prilaku manusia yang kurang bijak dalam memanfaatkan lingkungan.
Aktifitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan dalam beberapa
dekade terakhir telah mengubah kondisi wilayah DAS secara massif,
terutama di Pulau Jawa. Hal ini terbukti dari data kejadian bencana banjir
yang sebagian besar terjadi di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk
mencapai 58 % dari total jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010.
Untuk menemukan pemahaman yang utuh, perlu dilihat juga
keterkaitan bencana banjir dengan wilayah DAS. Pengertian DAS
menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (UU SDA) dan Pasal 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai, yaitu;
Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal
dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
DAS sebagai suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari wilayah
daratan, sungai dan anak sungainya yang berfungsi menampung,
menyimpan dan mengalirkan air hujan merupakan bagian dari siklus
hidrologi. Terhambatnya siklus hidrologi akan memicu terjadinya cuaca
ekstrim seperti curah hujan yang tinggi. Hal ini seperti yang disampaikan
-
Page 15 of 20
Tengku Ariful Amri, pemerhati sekaligus pakar lingkungan dari
Universitas Riau7.
Perubahan kondisi wilayah DAS sangat dipengaruhi oleh kinerja
beberapa sektor yang ada di dalam wilayah DAS. Sektor-sektor yang
memiliki pengaruh kuat antara lain, sektor kehutanan, sektor pertanian,
sektor sumber daya air dan sektor pemukiman. Selain ke 4 (empat) sektor
tersebut juga masih ada sektor yang lain seperti sektor pertambangan.
Tetapi untuk konteks di Jawa, sektor ini tidak terlalu signifikan dalam
mempengaruhi kondisi DAS.
2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir
Jauh sebelum lahirnya UU PB, permasalahan banjir sebetulnya
sudah disinggung dalam UU SDA dengan istilah daya rusak air yang
dalam hal ini bisa dikatakan sebagai banjir. Dalam UU SDA ini daya
rusak air di definisikan sebagai daya air yang dapat merugikan
kehidupan. Kemudian pada bab V (lima) tentang pengendalian daya
rusak air sudah diatur secara detail siapa yang bertanggung jawab dan
bagaimana strategi pengendalian daya rusak air, yang diatur mulai Pasal
51 sampai Pasal 58. Sedangkan dalam PP 38/2011 Tentang Sungai
diataur dalam Pasal 34 sampai Pasal 48.
Pendekatan yang digunakan dalam UU SDA dan PP 34/2011 ini
sudah lebih tepat dengan berbasis pada kesatuan wilayah sungai (WS).
Pengertia WS menurut UU SDA adalah kesatuan wilayah pengelolaan
sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau
pulau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
Dengan pengertian tersebut WS bisa berupa; WS dalam satu kabupaten/
kota, WS lintas kabupaten/kota, WS lintas provinsi, WS lintas negara,
dan WS strategis nasional. Pendekatan ini masih perlu dikaji lebih dalam
seberapa efektif dalam pengendalian daya rusak air atau bencana banjir,
pada kenyataannya kejadian bencana banjir masih terus terjadi dan
cenderung meningkat. Mengingat bahwa kejadian bencana banjir sangat
7 http://www.republika.co.id/berita/nasional/lingkungan/12/01/06/lxcuef-ini-dia-faktor-
penyebab cuaca-ekstrem-di-indonesia diakses pada tanggal 07 Oktober 2014 pukul 14:13 WIB
-
Page 16 of 20
terkait dengan siklus hidrologi dan kesatuan ekosistem wilayah DAS,
pendekatan yang lebih tepat dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana banjir adalah berbasiskan wilayah kesatuan ekosistem DAS. Hal
ini juga mengingat dalam penentuan batas WS tidak ada dasar ilmih
seperti halnya dalam penentuan batas wilayah DAS.
Selain menggunakan UU SDA, PP 34/2011 pemerintah daerah
dalam upaya penanggulangan bencana banjir juga berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Umum Mitigasi Bencana. Dalam pedoman ini ruang
lingkupnya sudah lengkap meliputi kebijakan, strategi, manajemen,
upaya-upaya dan aspek koordinasi mitigasi bencana. Terkait kebijakan
disebutkan dalam pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara
terpadu dan terkoordinir. Dalam salah satu strateginya sudah memasukan
prosedur kajian resiko bencana ke dalam perencanan tata ruang/tata guna
lahan. Dari segi langkah-langkah yang dilakukan dalam mitigasi bencana
banjir juga sudah cukup lengkap. Tetapi jika pedoman tersebut
dilaksankan dengan berbasis administratif sesuai dengan batas-batas
wilayah pemerintah daerah tentu tidak cukup untuk mengatasi
permasalahan bencana banjir yang terjadi di wilayah DAS lintas
pemerintah daerah.
UU PB yang lahir atas kesadaran betapa pentingnya peraturan
perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam penanggulangan
bencana memberikan dimensi baru dalam usaha penanggulangan
bencana. Namun dalam UU PB ini juga belum muncul kesadaran bahwa
bencana banjir sangat terkait dengan siklus hidrologi yang terjadi dalam
wilayah DAS. Sehingga dalam UU PB ini tidak ada ketentuan yang
mengatur usaha pencegahan dan mitigasi bencana banjir yang berbasis
wilayah kesatuan ekosistem DAS. Kemudian untuk mengisi kekosongan
hukum terkait penanggulangan bencana banjir, pada tahun 2012 Presiden
Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Banjir Dan
Tanah Longsor. Dalam Inpres ini disebutkan beberapa kementerian dan
lembaga negara yang di instruksikan untuk melakukan penanggulangan
bencana banjir dan tanah longsor mulai dari status siaga darurat, tanggap
-
Page 17 of 20
darurat, transisi darurat ke pemulihan dan pasca bencana. Inpres ini juga
belum cukup untuk dijadikan landasan hukum dalam penyelnggaraan
penanggulangan bencana banjir pada tahapan prabencana.
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Berdasarkan informasi, data dan literatur yang telah dikumpulkan dan
dianalisis menggunakan kerangka teori sebagaimana dijelaskan diatas, maka
dalam concept paper ini kesimpulannya sebagai berikut :
1. Penyebab bencana banjir lebih banyak disebabkan karena faktor non
alam, yaitu karena aktifitas manusia yang telah merubah kondisi wilayah
DAS. Proses pembangunan yang dilakukan di dalam DAS yang tidak
memperhatikan kelestarian ekosistem telah menimbulkan kerentanan-
kerentanan.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di daerah belum sesuai
seperti yang diamanatkan dalam UU PB, khususnya pada tahapan
prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana.
3. Tidak adanya aturan hukum yang secara lengkap dan spesifik mengatur
penanggulangan bencana banjir. Sedangkan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan
bencana yang sudah ada tidak cukup untuk menjawab permasalahan
bencana banjir di wilayah DAS lintas provinsi dan DAS lintas kabupaten/
kota.
B. Rekomendasi
Permasalahan bencana merupakan permasalahan yang komplek
menyangkut semua unsur dalam masyarakat. Maka dari itu, urusan bencana
juga merupakan urusan bersama, dan membutuhkan keterlibatan semua pihak
dalam penyelesaiannya. Dalam negara hukum seperti di Indonesia kebijakan
pemerintah yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan mutlak
diperlukan dalam rangka mencapai tujuan bangsa. Dengan banyaknya
kejadian bencana baik secara langsung maupun tidak langsung akan
menghambat proses pembangunan. Sedangkan proses pembangunan yang
-
Page 18 of 20
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan juga
berpotensi menimbulkan kerentanan-kerentanan baru di masyarakat.
Dalam semangat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan
pengurangan risiko bencana banjir, concept paper ini merekomendasikan
kepada semua pihak terutama kepada pemerintahan baru yang sedang
berproses dalam penyusunan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional) 2014 2019 sebagai berikut:
1. Bencana banjir merupakan dampak dari terganggunya sistem hidrologi di
dalam DAS, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir
dilakukan dengan berbasis wilayah daerah aliran sungai (DAS),
khususnya perencanan pada tahapan prabencana. Dokumen perencanaan
yang dimaksud antara lain; RENAS-PB (Rencana Nasional
Penanggulangan Bencana), RAN-PRB (Rencana Aksi Nasional
Pengurangan Risiko Bencana), RPBD (Rencana Penanggulangan
Bencana Daerah), RAD-PRB (Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko
Bencana) dan Rencana Kontijensi Bencana Banjir.
2. Untuk memantapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di
daerah, perlu adanya penguatan kapasitas penyelenggara penanggulangan
bencana di daerah. Sedangkan dalam upaya pencegahan dan pengurangan
risiko bencana banjir yang terkait dengan wilayah DAS, perlu dilakukan
penguatan kelembagaan pengelola DAS dengan membentuk badan
otonom yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan
DAS. Pengelola DAS saat ini adalah Balai Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (BP DAS) yang menginduk pada Kementerian Kehutanan.
3. Dalam upaya pencegahan kerusakan ekosistem DAS/ lingkungan,
idealnya perencanaan pencegahan dilakukan secara terintegrasi dan
terpadu mulai dari hulu sampai hilir. Kebijakan yang perlu di
integrasikan antara lain ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 UU 7/2004
PSDA, Pasal 34 Pasal 47 UU 24/2007 PB, Pasal 14 Pasal 52 UU
32/2009 PPLH dan PP 37/2012 Tentang Pengelolaan DAS. Kemudian
hasil inventarisasi SDA, kajian analisis resiko bencana, inventarisasi
lingkungan hidup dan inventarisasi DAS disusun dalam satu dokumen
sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan.
-
Page 19 of 20
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum
Mitigasi Bencana
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan
Bencana Banjir Dan Tanah Longsor
Buku dan Makalah
Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam
Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta,
Lukman Offset dan YPAPI, 2003
Lassa Jonatan. (2008) Kajian Disaster Risk Governance in Indonesia. PRIME
Project. Dapat di akses di http://www.zef.de/module/register/media/8b80_Lassa-
rise-of-risk.pdf
Nurhayati. (2014). Peran BMKG dalam menghadapi Bencana Hidrometeorologi.
Presentasi dalam Simposium Nasional, Yayasan Lestari Indonesia Oxfam,
Jakarta.
Harkunti P. Rahayu et al Banjir dan Upaya Penanggulangannya, Bandung, PROMISE
Indonesia (Program for Hydro - Meteorological Risk Mitigation Secondary
Cities in Asia). 2009.
Program Pelatihan Manajemen Bencana (1992) Tinjauan Umum Manajemen Bencana
(edisi ke 2), Unaited Nations Development Programe dan Unaited Nation
Disaster Risk Organization UNDP/UNDRO.
-
Page 20 of 20
Dr John Twigg, (2009) Karakteristik Masyarakat Tahan Bencana (edisi ke 2) dapat di
akses di www.proventionconsortium.org/?pageid=90