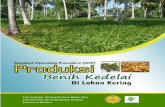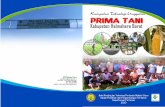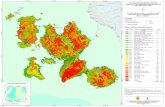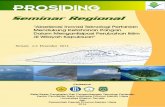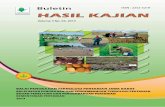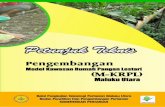BULETIN -...
Transcript of BULETIN -...


BULETIN Pengkajian Pertanian
Vol. 7, No. 1, 2018
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian

BULETIN PENGKAJIAN PERTANIAN
@ 2018, BPTP MALUKU UTARA
Volume 7, No. 1, 2018.
Penanggung Jawab :
Bram Brahmantiyo
Dewan Redaksi :
Wawan Sulistiono, A. Yunan Arifin, Chris Sugihono, Slamet Hartanto
Redaksi Pelaksana :
Herwan Junaidi
Himawan Bayu Aji
Bayu Suwitono
Penerbit :
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara,
Komplek Pertanian Kusu No. 1 Oba Utara Kota, Tidore Kepulauan
Fax : (021) 29490482
email : [email protected]
PRAKATA
Buletin Vol. 7, No. 1, 2018. merupakan buletin hasil pengkajian yang
diterbitkan oleh BPTP Maluku Utara, yang memuat makalah review dan hasil
pengkajian/penelitian primer yang dilakukan tahun 2013-2018. Makalah tersebut
telah diseleksi dan dikoreksi oleh tim redaksi baik dari segi bahasa maupun bentuk
penyajiannya.
Penerbitan buletin Vol. 7, No. 1, 2018. ini diterbitkan dengan memuat
artikel yang tidak harus berasal dari penyajian dalam suatu seminar, tetapi lebih
ditentukan oleh ketanggapan penulis dan kelayakan ilmiah tulisan.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak peneliti dan penyuluh, tim
redaktur, aparat penunjang lainnya yang telah membantu memperlancar proses
penerbitan. Semoga media ini bermanfaat bagi khalayak. Kritik dan saran dari
pembaca selalu kami nantikan.
Redaksi
Tulisan yang dimuat adalah yang telah diseleksi dan disunting oleh tim redaksi dan belum pernah
dipublikasikan pada media cetak manapun. Tulisan hendaknya mengikuti Pedoman Bagi Penulis
(lihat halaman sampul dalam). Redaksi berhak menyunting makalah tanpa mengubah isi dan makna tulisan atau menolak penerbitan suatu makalah.

BULETIN Pengkajian Pertanian
Vol. 7, No. 1, 2018
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian

BULETIN PENGKAJIAN PERTANIAN
@ 2018, BPTP MALUKU UTARA
Volume 7, No. 1, 2018.
Penanggung Jawab :
Bram Brahmantiyo
Dewan Redaksi :
Wawan Sulistiono, A. Yunan Arifin, Chris Sugihono, Slamet Hartanto
Redaksi Pelaksana :
Herwan Junaidi
Himawan Bayu Aji
Bayu Suwitono
Penerbit :
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara,
Komplek Pertanian Kusu No. 1 Oba Utara Kota, Tidore Kepulauan
Fax : (021) 29490482
email : [email protected]
PRAKATA
Buletin Vol. 7, No. 1, 2018. merupakan buletin hasil pengkajian yang
diterbitkan oleh BPTP Maluku Utara, yang memuat makalah review dan hasil
pengkajian/penelitian primer yang dilakukan tahun 2013-2018. Makalah tersebut
telah diseleksi dan dikoreksi oleh tim redaksi baik dari segi bahasa maupun bentuk
penyajiannya.
Penerbitan buletin Vol. 7, No. 1, 2018. ini diterbitkan dengan memuat
artikel yang tidak harus berasal dari penyajian dalam suatu seminar, tetapi lebih
ditentukan oleh ketanggapan penulis dan kelayakan ilmiah tulisan.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak peneliti dan penyuluh, tim
redaktur, aparat penunjang lainnya yang telah membantu memperlancar proses
penerbitan. Semoga media ini bermanfaat bagi khalayak. Kritik dan saran dari
pembaca selalu kami nantikan.
Redaksi
Tulisan yang dimuat adalah yang telah diseleksi dan disunting oleh tim redaksi dan belum pernah
dipublikasikan pada media cetak manapun. Tulisan hendaknya mengikuti Pedoman Bagi Penulis
(lihat halaman sampul dalam). Redaksi berhak menyunting makalah tanpa mengubah isi dan makna tulisan atau menolak penerbitan suatu makalah.

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara Vol. 7, No. 1, 2018
1
PENGARUH PEMUPUKAN NPK TERHADAP KOMPONEN HASIL UMBI BEBERAPA
VARIETAS UBI KAYU DI LAHAN KERING BACAN, HALMAHERA SELATAN
Wawan Sulistiono dan Bram Brahmantiyo
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku Utara
Kompleks Pertanian Kusu NO. 1 Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.
ABSTRAK
Budidaya ubi kayu di Maluku Utara secara umum menggunakan varietas lokal dan tidak dipupuk.
Pengaruh pemupukan terhadap peningkatan produktivias umbi belum banyak diketahui oleh petani.
Tujuan percobaan ini adalah mengetahui pengaruh pemupukan terhadap produksi umbi klon lokal
Bacan yaitu jumlah umbi per tanaman, bobot umbi pertanaman dan produktivitas dibanding varietas
nasional. Penelitian ini dilakukan di lahan kering desa Tuokona, Bacan, Kabupaten Halmahera Seletan
pada bulan September 2017-Juni 2018. Rancangan percobaan menggunakan rancangan acak
kelompok faktorial. Faktor pertama adalah jenis ubi kayu, terdiri 4 jenis yaitu lokal Bacan, Adira-1,
Mentega, Ubi Kuning. Faktor kedua adalah dosis pemupukan NPK, terdiri 3 jenis taraf dosis yaitu
100% dosis, 50% dosis, dan kontrol-nol dosis- (tanpa pemupukan). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemupukan NPK dengan dosis 100% tidak nyata meningkatkan bobot umbi per tanaman pada
semua varietas. Namun demikian klon lokal Bacan, memiliki respon tertinggi terhadap pemupukan
yang menaikkan jumlah umbi per tanaman sebesar 23,8 % dibanding perlakuan hanya pupuk kandang.
Kata Kunci: Ubi kayu, pemupukan NPK, umbi, lahan kering, Bacan
PENDAHULUAN
Ubi kayu merupakan tanaman pangan penting di Halmahera Selatan-Maluku Utara. Produksi
ubi kayu di Maluku Utara sebagian besar, 33,85% dihasilkan dari luas panen ubi kayu Halmahera
Selatan (BPS, 2017). Secara umum, di Maluku Utara ubi kayu dihasilkan dari sistem pertanaman
konvensional yang salah satu cirinya tanaman tidak dipupuk (Sulistiono dkk, 2010). Hasil ubi kayu di
Maluku Utara dengan sistem tanam konvensional tersebut masih mencapai 12, 21 ton/ha (BPS, 2017).
Hasil ini masih dibawah rata-rata produktivitas nasional dengan pengelolaan optimal mencapai 30-40
ton/ha (Suryana, 2007; Badanlitbang, 2008). Oleh karena itu diperlukan teknologi budidaya yang
dapat meningkatkan produktivitas umbi pada teknologi yang belum petani terapkan yaitu pemupukan.
Hasil pengkajian BPTP Malut pada pengelolaan PTT ubi kayu menunjukkan bahwa
pemupukan meningkatkan berat umbi. Klon Ternate dan Tidore menghasilkan produktivitas tinggi
berturut turut 48,37 ton/ha dan 62,10 ton/ha pada umur panen 7 bulan dengan pengelolaan tanaman
terpadu (Sulistiono dkk, 2008). Pemupukan Urea, SP-36 dan KCl masing-masing dengan dosis 100
kg:100 kg, dan 100 kg, meningkatkan produktivitas umbi lokal di bacan mencapai 76,9 ton/ha
(Sulistiono dkk, 2010). Wahyuningsih dan sundari (2013) melaporkan bahwa pemupukan ubi kayu
dengan dosis Urea, SP-36, dan KCl berturut-turut sebesar 200 kg/ha, 100 kg/ha, 100 kg/ha
menghasilkan produktivitas 39,4-49,2 ton/ha. Dosis Urea yang lebih tinggi diberikan pada varietas
Adira 1 sebanyak 200 kg/ha sedangkan pupuk SP-36 dan KCl untuk memunculkan potensi genetisnya
yaitu 40 ton/ha (Sutrisno dan Sundari, 2013).
Berdasarkan hasil peningkatan umbi segar pada pengaruh pemupukan. Diperlukan upaya
teknologi peningkatan produktivitas ubi kayu di Maluku Utara, Bacan. Salah satu teknologinya adalah
pemupukan. Perlakuan pemupukan diharapkan secara nyata meningkatkan umbi segar. Oleh kerena
itu dilakukan penelitian pengaruh pemupukan NPK hasil umbi lokal Bacan Halmahera Selatan. Tujuan
penelitian ini disamping untuk mengingkatan produktivitas umbi segar juga mengetahui dosis yang
tepat untuk budidaya ubi kayu di Maluku Utara.

2 Pengaruh pemupukan NPK terhadap komponen hasil umbi beberapa varietas ubi kayu di lahan kering Bacan,
Halmahera Selatan
BAHAN DAN METOIDE
Penelitian ini dilakukan di Desa Tuokona Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi
Maluku Utara. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2017-Juli 2018. Tanah lokasi
penelitian adalah jenis tanah Andosol dengan pH 5,5-7. Curah hujan tahunan dua tahun berturut-turut
adalah 1.286-2.274 mm/tahun (2016-2017). Suhu harian berkisar 25-30°C.
Penelitian dilakukan menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap Faktorial. Faktor
pertama adalah jenis ubi kayu yang terdiri atas empat (4) jenis yaitu: (1) Adira 1, (2) Mentega, (3) Ubi
Kuning, dan (4) Lokal Bacan. Faktor ke dua adalah dosis pupuk an organik yaitu Urea, SP-36, KCl
dengan 3 taraf: (1) dosis 100% yaitu 100:100:100kg/ha, (2) dosis 50% yaitu 50:50:50kg/ha, (3) tanpa
pemupukan pupuk an organik (kontrol). Terdapat 12 kombinasi perlakuan. Tiap kombinasi perlakuan
menggunakan luas petak 5x6m dengan jarak tanam antar stek tanam 1x0,9m. Tiap kombinasi
perlakuan diulang tiga (3) kali.
Pengamatan dilakukan pada jumlah umbi pertanaman, bobot umbi pertanaman dan diameter
umbi. Pengamatan dilakukan pada saat panen pada umur 10 bulan. Pengamatan dilakukan dengan
menimbang umbi, mengitung umbi pada tanaman contoh masing-masing unit perlakuan 3 tanaman
dan menghitung produktivitas rerata secara total per ha. Data paremeter pengamatan yang dihasilkan
dianalisis menggunakan analysis of variance (ANOVA) pada faktor perlakuan rancangan acak
lengkap kelompok menggunakan SAS 9.4 program for windows. Jika terdapat interaksi perlakuan
antar faktor, dilakukan pembandingan pengaruh antar interaksi. Kemudian pengaruh perlakuan
tersebut dibandingkan berdasarkan uji Tukey’s studentized range (HSD) test dengan p ≤0.05.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Bobot umbi per tanaman
Berdasarkan sidik ragam bobot umbi per tanaman nyata ditentukan oleh perlakuan perbedaan
dosis pupuk Urea, SP-36, dan KCl (p<0,01) serta jenis varietas pada umur 9 bulan (p <0,01) (Tabel
1). Tanah yang tidak diberi perlakuan pupuk Urea, SP-36, dan KCl pada lokasi penelitian,
menghasilkan bobot umbi yang tetap tinggi (Tabel 2).
Tabel 1. Sidik ragam pengaruh pemupukan terhadap bobot umbi basah, jumlah umbi per tanaman, dan
diameter umbi umur 9 bulan di lahan kering Bacan, Halmahera Selatan
Sumber db Beda nyata F Tabel pada komponen hasil umbi
keragaman Bobot umbi
basah/tanaman
Jumlah umbi/tanaman Diameter umbi
Blok 2 0,9378 0,6464 0,8279
Varietas 3 0,0022 0,0003 0,0162
Dosis 2 0,0048 0,0314 0,1242
Interaksi 6 0.0511 0,0341 0,0008
KK (%) 33,0 14,31 13,28
Angka beda nyata uji F tabel: < 0,050 = nyata, < 0,010 = sangat nyata
Secara genetis varietas lokal Bacan memiliki bobot umbi per tanaman terendah berbeda
dengan varietas Ubi Kuning dan Mentega (Tabel 2). Jenis lokal Bacan termasuk jenis ubi kayu yang
menghasilkan potensi hasil mirip dengan varietas Adira 1. Hasil ini menunjukkan bahwa ubi kayu
lokal Bacan termasuk memiliki potensi genetik berupa komponen hasil umbi yang rendah. Sementara
itu, jenis ubi kayu Mentega, Adira 1 serta Ubi kuning yang merupakan jenis introduksi terlihat
adaptif. Hal ini diketahui pada hasil bobot umbi per tanaman tertinggi.

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara Vol. 7, No. 1, 2018
3
Tabel 2. Pengaruh dosis pemupukan Urea, SP-36, dan KCl dan varietas terhadap bobot umbi per
tanaman umur 9 bulan di lahan kering Bacan, Halmahera Selatan.
Bobot umbi per tanaman (kg) umur 9 bulan pada beberapa
varietas Perlakuan
Dosis pupuk Urea, SP-36 dan KCl
100:100:100kg/ha 2,64 b
50:50:50kg/ha 2,67 b
0 (Tanpa pemupukan) 4,00 a
Varietas
Adira 1 2,67 bc
Ubi Kuning 3,62 ab
Mentega 4,03 a
Lokal Bacan 2,08 c
Ket.: Angka yang diikuti huruf sama pada perlakuan dosis pemupukan dan varietas tidak berbeda
nyata pada uji Tukey 5%. (+) menunjukkan terdapat interaksi antar perlakuan berdasarkan
analisis sidik ragam.
Jumlah umbi per tanaman
Berdasarkan sidik ragam jumlah umbi per tanaman nyata ditentukan oleh interaksi dosis Urea,
SP-36, dan KCl dan varietas pada umur 9 bulan (p<0,05) (Tabel 1). Jumlah umbi varietas lokal Bacan
menunjukkan terendah berbeda nyata dengan jenis Mentega tanpa pemupakan.
Tabel 3. Pengaruh dosis pemupukan Urea, SP-36, dan KCl terhadap jumlah umbi per tanaman umur 9
bulan di lahan kering Bacan, Halmahera Selatan.
Jumlah umbi per tanaman umur 9 bulan pada beberapa varietas
Dosis pupuk/varitas Adira 1 Ubi Kuning Mentega Lokal Bacan
Dosis pupuk Urea, SP-36
dan KCl
100:100:100kg/ha 7,0 b 8,67 ab 8,00 ab 8,33 ab
50:50:50kg/ha 6,3 b 9,33 ab 7,33 b 6,33 b
0 (Tanpa pemupukan) 7,3 b 9,67 ab 11,00 a 2,37 bc
(+)
Ket.: Angka yang diikuti huruf sama pada semua kombinasi perlakuan tidak berbeda nyata pada uji
Tukey 5%. (+) menunjukkan terdapat interaksi antar perlakuan berdasarkan analisis sidik
ragam.
Diameter umbi per tanaman
Berdasarkan sidik ragam jumlah umbi per tanaman nyata ditentukan oleh interaksi dosis
pupuk (urea, SP-36, dan KCl) dan varietas pada umur 9 bulan (p<0,01) (Tabel 1). Ubi kayu mentega
memiliki potensi berdiameter lebih besar. Jenis Mentega menunjukkan ukuran diameter nyata lebih
besar jika dibanding varietas Adira 1 oleh pengaruh semua perlakuan dosis pupuk, Ubi Kuning oleh
pengaruh dosis pupuk 50% dosis (Urea, SP-36, KCl), serta lokal Bacan oleh pengaruh pemupukan
50% dosis Urea, SP-36, dan KCl (Tabel 4).

4 Pengaruh pemupukan NPK terhadap komponen hasil umbi beberapa varietas ubi kayu di lahan kering Bacan,
Halmahera Selatan
Tabel 4. Pengaruh dosis pemupukan Urea, SP-36, dan KCl terhadap diameter umbi per tanaman umur
9 bulan di lahan kering Bacan, Halmahera Selatan.
Diameter umbi per tanaman umur 9 bulan pada beberapa varietas
Dosis pupuk/varietas Adira 1 Ubi Kuning Mentega Lokal Bacan
Dosis pupuk Urea, SP-36
dan KCl
100:100:100kg/ha 5,83 b 6,67 ab 5,00 b 6,33 ab
50:50:50kg/ha 6,17 b 6,17 b 7,33 ab 5,00 b
0 (Tanpa pemupukan) 5,00 b 6,33 ab 8,67 a 6,67 ab
(+)
Ket.: Angka yang diikuti huruf sama pada semua kombinasi perlakuan tidak berbeda nyata pada uji
Tukey 5%. (+) menunjukkan terdapat interaksi antar perlakuan berdasarkan analisis sidik
ragam.
Pembahasan
Bobot umbi, jumlah umbi, dan diameter umbi adalah komponen hasil umbi ubi kayu. Bobot
umbi sangat nyata ditentukan oleh faktor dosis pemupukan kimia (NPK) dan jenis varietas (Tabel 1).
Pada faktor tanah, bobot umbi tertinggi nyata dihasilkan dari tanah tanpa pemupukan kimia. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian Edet et al. (2013) bahwa pada penanaman ubi kayu tanpa pemberian
pupuk, namun berdasarkan residu pupuk tanam pertama (Organomineral Fertilizer: 2,5-6 ton/ha)
memberikan hasil umbi/ha sama dengan musim tanam sebelumnya. Tanah di lokasi penelitian tersebut
menunjukkan pH netral yaitu 5,5-7,0. Kisaran pH tersebut memberikan pertumbuhan yang optimal
untuk perkembangan ubi kayu karena unsur hara optimal tersedia (Ande, 2011). Faktor lingkungan
menurut Danquah et al. (2017) berperan menentukan berat umbi segar sebesar 37 %, sedangkan
menurut Aina et al. (2009) sebesar 70,3%.
Faktor genetis berupa jenis varietas ubi kayu sangat nyata menentukan bobot umbi per
tanaman (Tabel 1). Jenis ubi kayu Mentega menunjukkan jenis ubi kayu yang secara genetis memiliki
bobot umbi tertinggi berbeda nyata dengan varietas Adira 1 dan lokal Bacan. Hal ini mengindikasikan
klon lokal Bacan merupakan jenis ubi kayu yang potensi hasilnya sedang seperti Adira 1 yaitu sekitar
30-45 ton /ha (Badan Libang: Balitkabi, 2008). Faktor genetis tersebut yang menentukan bobot umbi
sejalan dengan hasil penelitian Denquah et al. (2017) bahwa peran genotif ubi kayu menentukan berat
umbi segar sebesar 51 %.
Jumlah umbi nyata ditentukan oleh interaksi varietas dan dosis pemupukan NPK (p<0,05).
Jenis ubi kayu Mentega yang tidak diberi pupuk menghasilkan jumlah umbi tertinggi (Tabel 3).
Jumlah umbi jenis Mentega tanpa pemupukan berbeda nyata dengan varietas Adira 1 pada semua
perlakuan dosis pemupukan. Demikian juga klon lokal Bacan pada dosis pupuk 50 % dan kontrol.
Hasil ini menunjukkan bahwa jenis ubi kayu Mentega secara genetis memiliki potensi jumlah umbi
yang tinggi. Faktor genetis yang berinteraksi dengan lingkungan sangat menentukan dalam
menentukan jumlah umbi pada semua varietas yang ditanam. Hal ini sejalan dengan apa yang
disampaikan oleh Mwila et al. (2018) bahwa klon-klon ubi kayu memiliki kemampuan genetis untuk
berinteraksi dengan lingkungan tumbuh yang merupakan kenerja dari metebolik sekunder seperti
kapasitas antioksidatin dan mekanisme ketahanan terhadap penyakit-cassava musaic disease- (Mwila
et al. 2018; Adriko et al., 2011).
Jenis lokal Bacan memiliki ketanggapan terhadap pemupukan yang lebih tinggi dibanding
varietas lainnya terhadap jumlah umbi. Peningkatan jumlah umbi tersebut tidak berbeda nyata
dibanding pemberian dosis pupuk yang lebih tinggi. Namun demikian terdapat peningkatan jumlah
umbi sebesar 23,8 % dibanding tanpa pemupukan. Peningkatan hasil umbi oleh pengaruh pemupukan
NPK juga dilaporkan oleh Munyahali et al. (2017) dengan besarnya kenaikan berat segar umbi 19,9
%. Macalon et al. (2018) menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang nyata (r = 0,653) dengan
pemupukan NPK terhadap berat segar umbi ubi kayu.
Jumlah umbi varietas Adira 1 tidak nyata ditentukan oleh dosis pemupukan, 100 kg/ha (Urea,
SP-36 dan KCl). Hasil ini menunjukkan varietas Adira 1 memiliki kemampuan menghasilkan umbi
stabil dan ditentukan oleh genetis. Menurut Aina et al. (2009) terdapat klon atau varietas ubi kayu

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara Vol. 7, No. 1, 2018
5
yang stabil di beberapa lingkungan tumbuh. Faktor lingkungan tumbuh yang menentukan hasil ubi
kayu seperti ketinggian tempat, suhu, serta curah hujan (Noerwijayanti and Budianto, 2015).
Ubi kayu jenis Mentega memiliki potensi untuk meningkatkan diameter umbi pada tingkat
kesuburan tanah yang sesuai (Tabel 4). Sementara itu klon lokal Bacan memiliki potensi mengalami
peningkatan daya hasil umbi berupa jumlah umbi per tanaman pada perlakuan pemupukan. Peran
kesuburan tanah tersebut, berupa pemberian pupuk kimia atau alami, sangat penting menentukan
pertumbuhan tanaman ubi kayu (Abah and Petja, 2017). Tanah yang optimal menentukan
pertumbuhan tanaman ubi kayu terutama pada umur 4-6 bulan setelah tanam yang nyata meningkatkan
berat segar umbi saat panen di umur 12 bulan (Edet et al., 2015). Peran kesuburan tanah tersebut
dilaporkan juga oleh (Njoku et al., 2010) bahwa tanah yang subur dan gembur yang terdapat tanaman
legum, sangat nyata memberikan hasil umbi pada perlakuan pemupukan.
KESIMPULAN
Pemberian pupuk kimia Urea-SP36 dan KCL hingga 100 kg/ha tidak nyata meningkatkan
komponen hasil umbi pada semua jenis varietas di tanah jenis Andosol Bacan. Namun pada klon lokal
Bacan perlakuan pemupukan tersebut menghasilkan peningkatan jumlah umbi tertinggi sebesar 23,8
%. Klon Mentega menunjukkan potensi hasil umbi tertinggi dan dapat beradaptasi lebih baik. Varietas
Adira 1, memiliki kestabilan hasil umbi tertinggi.
UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada Haryanti Koostanto SP selaku fasilitator
CIAT/FoodSTAR+ dan Mansur Arif, S.P di Dinas Pertanian Halamhera Selatan.
DAFTAR PUSTAKA
Abah R. C., and Petja B.M. 2016. Crop Suitability Mapping for Rice, Cassava, and Yam in North
Central Nigeria. Journal of Agricultural Science 9(1): 96-108.
Adriko J., Sserubombwe W.S., Adipala E., Bua A., Thresh J. M., and Edema R. 2011. Response of
improved cassava varieties in Uganda to cassava mosaic disease (CMD) and their inherent
resistance mechanisms. African Journal of Agricultural Research 6(3):521-531.
Aina O.O., Dixon A.G.O., Paul I., and Akinrinde E.A. 2009. G×E interaction effects on yield and
yield components of cassava (landraces and improved) genotypes in the savanna regions of
Nigeria. African Journal of Biotechnology 8 (19):4933-4945.
Ande O.T. 2011. Soil suitability evaluation and management for cassava production in the derived
savanna area of Southwestern Negeria. International Journal of Soil Science 6 (2): 142-149.
Badan Litbang. Balitkabi. 2008. Prospek dan arah pengembangan agribisnis ubi kayu. Jakarta.
BPS 2017. Maluku Utara dalam angka. Badan Pusat Statistik. Ternate. 408 hal.
Danquah J.A., Aduening J.A., Gracen V.E., Asante I.K., and Offei S.K. AMMI Stability Analysis and
Estimation of Genetic Parameters for Growth and Yield Components in Cassava in the Forest
and Guinea Savannah Ecologies of Ghana. International Journal of Agronomy 2017: 1-16.
Edet M.A., Tijani-Eniola H., Lagoke S.T.O.,Tarawali G. 2015. Relationship of Cassava Growth
Parameters with Yield, Yield Related Components and Harvest Time in Ibadan, Southwestern
Nigeria. Journal of Natural Sciences Research 5 (9): 87-92.
Edet M.A, Tijani-Eniola H., and Okechukwu R. 2013. Residual effects of fertilizer application on
growth and yield of two cassava varieties in Ibadan, South-Western Nigeria. African Journal of
Root and Tuber Crops, 10(1): 33-40.

6 Pengaruh pemupukan NPK terhadap komponen hasil umbi beberapa varietas ubi kayu di lahan kering Bacan,
Halmahera Selatan
Macalou S., Mwonga S., Musandu A. 2018. Performance of Two Cassava (Manihot Escculenta
Crantz) Genotypes to NPK Fertilizer in Ultisols of Sikasso Region. International Journal of
Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)38 (2):189-206 .
Munyahalia B.W., Pypersc P., Swennend E.R., Walangululub J., Vanlauwec B., Merckxa R. 2017.
Responses of cassava growth and yield to leaf harvesting frequency and NPK fertilizer in South
Kivu, Democratic Republic of Congo. Field Crops Research 214:194-201.
Mwila N., Nuwamanya E, Odong T .L., Badji A., Agbahoungba S, Ibanda P.A., Mwala M., Sohati P.,
yamanywa S., Rubaihayo P.R. 2018. Genotype by Environment Interaction Unravels Influence
on Secondary Metabolite Quality in Cassava Infested by Bemisia tabaci. Journal of Agricultural
Science 10(8): 192-209.
Njoku D.N., Afuape S.O., and Ebeniro, C.N. 2010. Growth and yield of cassava as influenced by
grain cowpea population density in Southeastern Nigeria. African Journal of Agricultural
Research 5(20): 2778-2781.
Noerwijati K., and Rohmad Budiono R., 2014. Yield and Yield Components Evaluation of Cassava
(Manihot esculenta Crantz) Clones In Different Altitudes. Conference and Exhibition Indonesia
- New, Renewable Energy and Energy Conservation. (The 3rd Indo-EBTKE ConEx 2014).
Energy Procedia 65:155 – 161.
Sulistiono W., Kulle M.S.S., Hidayat Y., Sugihono C., Saleh R., Marliani, Heru I., Ode H.R.,
Musyadik, Ponco H.W. 2010. Uji Kemantapan genetik ubi kayu varietas lokal Ternate dan
Tidore pada 3 Agroekosistem yang berbeda di Maluku Utara. Laporan Akhir Tahun.
Balitbangda Prov. Maluku Utara dan BPTP Maluku Utara. Sofifi. 55 hal.
Sulistiono W., Mejaya J.M., Syahbudin H., Ponco W., Sugihono C., Musyadik. 2008. Pengkajian
introduksi varietas unggul nasional UJ-5 dan varietas lokal Ternate dan Tidore dengan sistem
pengelolaan tanam terpadu (PTT) di Tidore. BPTP Maluku Utara. Sofifi. 30 hal.
Suryana A. 2007. Kebijakan penelitian dan pengembangan ubi kayu untuk agroindustri dan ketahanan
pangan. Prosiding: Prospek strategi dan teknologi pengembangan ubi kayu untuk agroindustri
dan ketahanan pangan. Badan Litbang Deptan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman
Pangan. Bogor.
Sutrisno dan Sundari T. 2013. Potensi hasil klon harapan ubi kayu pada tiga umur panen berbeda.
Peningkatan daya saing dan implementasi pengembangan komoditas kacang dan umbi
mendukung pencapaian empat sukses pengembangan pertanian. Prosiding seminar nasional
hasil penelitian tanaman aneka kacang dan umbi tahun 2012: 537-544.
Wahyuningsih S., dan Sundari T. 2013. Evaluasi klon-klon harapan ubi kayu untuk karakter hasil
umbi dan pati. Peningkatan daya saing dan implementasi pengembangan komoditas kacang dan
umbi mendukung pencapaian empat sukses pengembangan pertanian. Prosiding seminar
nasional hasil penelitian tanaman aneka kacang dan umbi tahun 2012: 528-536.

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara Vol. 7, No. 1, 2018
7
KELAYAKAN USAHA INTEGRASI KELAPA-JAGUNG MANIS-SAPI DI LAHAN KERING
MALUKU UTARA
Slamet Hartanto dan Yayat Hidayat
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara
ABSTRAK
Integrasi kelapa dengan tanaman pangan dan ternak diperlukan untuk mengurangi risiko usaha
monokultur kelapa. Pengkajian sistem integrasi kelapa dilaksanakan pada tahun 2014 di desa
Tafasoho, kecamatan Malifut, kabupaten Halmahera Utara. Satu hektar tanaman kelapa berumur 15
tahun diintegrasikan melalui penanaman jagung manis (Zea mays L. Saccharata) dilahan sela
dibandingkan dengan 1 hektar tanaman kelapa monokultur. Tiga ekor sapi berumur 1,2-1,5 tahun
diberi pakan 1 kg dedak dan limbah tebon jagung manis 3% dari bobot badan. Analisis input-output
(B/C) dan nisbah peningkatan keuntungan bersih (NKB) digunakan menguji kelayakan usaha integrasi
tanaman kelapa dengan jagung manis dan ternak sapi. Hasil yang diperoleh menunjukan produksi
tanaman jagung manis dibawah naungan kelapa teridenfikasi mengalami penurunan, akan tetapi
penanaman jagung manis mampu meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sebesar 50%. Selain itu,
pemanfaatan limbah tebon jagung manis dapat meningkatkan produktivitas ternak sapi yang dipelihara
secara intensif. Berdasarkan analisis finansial, sistem integrasi kelapa-jagung manis-sapi mampu
meningkatkan 60,58% keuntungan yaitu 2.984.000,- per tahun dibandingkan tanaman monokultur
kelapa dengan nilai B/C 1,38 dan nilai NKB 1,15. Sistem integrasi tanaman kelapa-jagung manis-sapi
menunjukan hasil yang positif, tetapi untuk pengembangan dalam skala besar diperlukan pengkajian
menyeluruh dan multi-lokasi di Maluku Utara.
Kata kunci: integrasi, kelapa, jagung, sapi, kelayakan usaha
PENDAHULUAN
Sektor pertanian merupakan penggerak utama perekonomian di Maluku Utara dengan
sumbangan terhadap distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar di Maluku Utara yaitu
36,37 %. Pertanian lahan kering berkontribusi paling besar dalam pembangunan sektor pertanian di
Maluku Utara. Tanaman perkebunan kelapa, cengkeh dan pala merupakan usahatani lahan kering yang
banyak dilakukan oleh petani di Maluku Utara. Maluku Utara merupakan salah satu sentra produksi
kelapa di Indonesia dengan luas lahan 223.108 Ha. Luas lahan perkebunan kelapa sebesar 69% dari
total luas lahan perkebunan di Maluku Utara (BPS Maluku Utara, 2014).
Tanaman kelapa merupakan komoditas unggulan di Maluku Utara tetapi nilai ekonomi dari
tanaman kelapa masih rendah karena produktivitas rendah dan diusahakan secara monokultur (BPTP
Maluku Utara, 2015). Produktivitas rata-rata tanaman kelapa di Maluku Utara 1,2 ton/ha/tahun (BPS
Maluku Utara, 2014). Sebagian besar lahan di antara tanaman kelapa di Maluku Utara merupakan
lahan marginal dan petani umumnya belum melakukan upaya untuk meningkatkan kesuburan tanah.
Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas kelapa masih rendah. Usaha agribisnis pertanian yang
bersifat monokultur juga telah terbukti rentan mengalami kerugian, karena harga jual produk pertanian
bersifat fluktuatif dari waktu ke waktu.
Diversifikasi (penganekaragaman) usaha secara vertikal maupun horisontal diperlukan untuk
mengurangi resiko terhadap usaha monokultur. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut perlu inovasi
teknologi yang sesuai untuk diintegrasikan dalam usaha pokok, dengan mengoptimalkan sumberdaya
yang tersedia, dan secara teknis, ekonomi dan sosial budaya layak dan dapat diterima oleh masyarakat
pelaku usaha secara berkelanjutan. Crops Livestock System (CLS) atau Sistem Integrasi Tanaman
Ternak (SITT) merupakan pola diversifikasi usaha yang diperkirakan bisa sebagai solusi jangka

8 Kelayakan usaha integrasi kelapa-jagung manis-sapi di lahan kering Maluku Utara
panjang yang harus dikembangkan sebagai kunci menemukan pakan ternak dari beragam limbah
pertanian dan sumberdaya tanaman tahunan, bukan untuk mengganti pakan konvensional, melainkan
untuk memperkuat ketahanan pangan dalam ekosistem lahan kering (Nataatmaja, 2004).
SITT dengan pola Kelapa – Jagung Manis - Sapi merupakan usaha yang sangat layak
dikembangkan sebagai solusi untuk pengembangan peternakan dan perkebunan serta menjaga
ketahanan pangan lahan kering di Maluku Utara. Manfaat SITT Kelapa-Jagung Manis- Sapi yaitu
dengan adanya jagung manis sebagai tanaman sela diperkirakan mampu meningkatkan produktivitas
tanaman kelapa, meningkatkan pendapatan petani, dan menyediakan hijauan pakan ternak dari limbah
tanaman jagung (zero waste). Perlakuan pengolahan tanah dan pemupukan untuk usaha tanaman
jagung pada lahan marginal diantara tanaman kelapa dapat meningkatkan kesuburan tanah sehingga
produktivitas kelapa meningkat. Malia et. al. (2010) menyatakan produktivitas kelapa di Desa
Tawaang meningkat dari 6 menjadi 12 butir per tandan pada integrasi kelapa dengan jagung Srikandi
kuning. Jagung manis juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan cocok dikembangkan di Maluku
Utara sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani diluar usaha perkebunan kelapa. Manfaat lain
SITT yaitu ternak sapi akan menghasilkan berlimpah kotoran yang dapat diolah menjadi kompos dan
sumber energi berupa sumber biogas (Hasnudi, 1991 dalam Elly et al., 2008).
Pengkajian SITT Kelapa- Jagung Manis- Sapi dengan tujuan untuk mendapatkan paket
teknologi SITT Kelapa- Jagung Manis- Sapi dan menguji kelayakan sistem integrasi tanaman dengan
ternak.
BAHAN DAN METODE
(a) Lokasi dan Waktu Pengkajian
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Waktu pelaksanaan Januari – Desember
2014. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive), yaitu berdasarkan
pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Lokasi yang dipilih adalah desa Tafasoho,
Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dengan pertimbangan wilayah yang masyarakatnya
banyak membudidayakan tanaman kelapa, beternak sapi dan tanaman jagung.
(b) Tanaman Kelapa
Dua hektar tanaman kelapa berumur 15 tahun didesain untuk mendapatkan perlakuan
pengkajian dengan 1 hektar untuk sistem integrasi dan 1 hektar untuk usaha monokultur. Paket
teknologi yang diintroduksikan pada tanaman kelapa adalah penanaman jagung manis diantara
tegakan kelapa.
(c) Jagung Manis (Zea mays L. Saccharata)
Varietas yang digunakan adalah varietas unggul Bonanza F1. Penanaman dilakukan dengan
cara ditugal ditugal 2-3 cm, dengan jarak tanam 75x40 cm (2 biji/lubang). Dosis pupuk yang
diberikan yaitu 300 kg/ ha urea, 400 kg/ ha NPK dan 1.000 kg/ ha pupuk kandang. Pemupukan
pertama (saat tanam), ditugal dekat barisan tanaman ( + 5 cm dari batang tanaman dengan kedalaman
5-7 cm. Pada pemupukan pertama, pupuk urea dan NPK diberikan ½ dosis dari pupuk yang
digunakan. Pemupukan kedua dilakukan pada saat 14 HST. Pemupukan kedua dengan cara membuat
larikan 5 cm diantara tanaman dan diberikan ½ dosis atau ½ dari kekurangan. Pupuk kandang
diberikan sekali pada saat penanaman dan sebagai penutup lubang tanam dengan dosis 1.000 kg/ ha.
(d) Ternak Sapi
Tiga ekor sapi Bali betina umur 1,2-1,5 tahun. Sapi dikandangkan secara intensif pada
kandang individu. Pakan yang diberikan 1 kg dedak halus dan limbah tebon jagung diberikan 3% dari
bobot badan. Air minum diberikan secara adlibitum.
(e) Pengumpulan Data
Data pengamatan jumlah butir kelapa dilaksanakan 2 kali setiap 4 bulan. Jumlah butir dihitung
secara manual dengan pengamatan visual setiap pohon. Pertambahan bobot badan dilakukan dengan

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara Vol. 7, No. 1, 2018
9
menghitung selisih bobot badan setiap bulan selama 4 bulan. Perhitungan bobot badan dilakukan
dengan estimasi bobot badan dengan metode perhitungan lingkar dada (Zurahmah dan The, 2011).
Data tanaman jagung manis yang diamati jumlah tongkol, berat batang dan daun (limbah) jagung.
Data usaha tani yang diambil adalah biaya input usahatani dan besarnya output usahatani.
(f) Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode input-output analysis (B/C) (Price, 1972)
untuk menguji kelayakan usahatani.
NPT
B/C =--------
BT
Dimana:
B/C = Nisbah penerimaan dan biaya, NPT = Nilai produksi kotor (Rp/ha/th), BT = Nilai biaya total
(Rp/ha/th), Dengan keputusan:
B/C>1, usahatani secara ekonomi menguntungkan; B/C=1, usahatani secara ekonomi berada pada titik
impas (BEP); B/C<1, usahatani secara ekonomi tidak menguntungkan (rugi).
Untuk melihat perbandingan keuntungan usahatani dengan penerapan teknologi yang berbeda
atau seberapa jauh teknologi introduksi mampu meningkatkan keuntungan petani digunakan tolok
ukur Nisbah Peningkatan Keuntungan Bersih (NKB) (Adnyana dan Kariyasa 1995) dengan rumus:
KBTI
NKB = --------------
KBTP
Dimana:
NKB = Nilai peningkatan keuntungan bersih, KBTI = Keuntungan bersih dari penerapan teknologi
introduksi, KBTP = Keuntungan bersih dari penerapan teknologi petani
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik wilayah pengkajian
Kecamatan Malifut termasuk dalam di desa lahan kering adalah dataran rendah iklim basah.
Kecamatan Malifut memiliki kondisi agroekologi tipe IV/ B f e atau tipe lahan kering yang sesuai
dengan pengembangan tanaman perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura dengan luas lahan
potensial 10.596 ha serta didukung dengan adanya kelembagaan kelompok tani (BPTP Maluku
Utara, 2009). Karakteristik petani di kecamatan Malifut yaitu kisaran umur petani 34-71 tahun dengan
rata-rata pendidikan formal setingkat sekolah dasar. Pekerjaan utama sebagai petani tanaman pangan,
sebagian diantaranya memiliki pekerjaan sampingan baik di sektor pertanian pangan (buruh tani),
usaha ternak, perkebunan maupun di luar usaha tani (jasa, angkutan, dan dagang). Ternak yang
dijumpai ada tiga jenis yakni sapi, kambing dan ayam. Rata-rata pemilikan sapi 1 - 2 ekor, rata-rata
pemilikan kambing 1 - 7 ekor, dengan rataan 4 ekor, rata-rata pemilikan ternak ayam 10-11 ekor.
Andalan dalam usahatani di lahan kering adalah jagung, kelapa, pala dan cengkeh dengan pola tanam
yang dominan adalah jagung-jagung.
Keragaan tanaman jagung manis, kelapa dan ternak sapi
Keragaan tanaman jagung manis dan tanaman kelapa meliputi jumlah buah kelapa pertandan,
jumlah tongkol jagung, PBBH sapi dan berat limbah jagung yang disajikan pada Tabel 1. Terjadi
penurunan jumlah tongkol jagung manis dibawah naungan kelapa dibandingkan produksi jagung
manis yang ditanam tidak dibawah naungan. Dilaporkan Zuraida (2010), bahwa produksi jagung
manis yang ditanam dilahan tadah hujan di Kalimantan Selatan yaitu 20.000 tongkol/ha. Ditambahkan
Rustan Hadi (2009) bahwa hasil panen jagung yang ditanam di antara kelapa adalah 2,70 t/ha lebih
rendah dari jagung monokultur yaitu 3,87 t/ha. Hal ini disebabkan oleh rendahnya jumlah cahaya
matahari yang diserap tanaman jagung selama masa pembungaan karena ternaungi tanaman kelapa.
Tollenaar (1977) dalam Fisher dan Palmer (1984) menyatakan bahwa tanaman jagung yang ternaungi

10 Kelayakan usaha integrasi kelapa-jagung manis-sapi di lahan kering Maluku Utara
hingga 45% akan terjadi penurunan hasil. Limbah brangkas (daun dan batas) yang dihasilkan oleh
jagung manis juga cukup tinggi yaitu 1.120 kg/ ha.
Jumlah buah kelapa per tandan meningkat 50 % setelah adanya tanaman jagung manis, yaitu
dari 6 buah per tandan menjadi 8-9 buah pertandan. Hal ini sesuai Kaat dan Dawis (1986) yang
menyatakan penanaman tanaman sela mampu meningkatkan jumlah bunga betina dan buah kelapa tiap
pohon. Dilaporkan Paat et. al. (2006), bahwa penerapan sistem integrasi kelapa dengan jagung di
Kabupaten Minahasa Utara berkorelasi positif terhadap peningkatan produksi kelapa per tandan dari 5
buah menjadi 9 buah per tandan.
Tabel 1. Keragaan tanaman jagung manis, ternak sapi dan tanaman kelapa
No Parameter Volume
1. Tanaman jagung manis:
- Jumlah tongkol (buah/ ha)
- Berat limbah/ brangkasan (kg/ ha)
8.240
1.120
2. Kelapa:
- Jumlah buah pertandan (buah/
tandan)
8-9
3. Sapi:
- PBBH1) (kg/ hari)
0,416 1)PBBH, pertambahan bobot badan harian
Sistem pemeliharaan sapi secara intensif pada SITT juga meningkatkan PBBH yaitu 0,416
kg/ekor/hari, lebih tinggi dibandingkan dengan pemeliharaan semi intensif dan ektensif. Dilaporkan
Hendaru et. al. (2011), PBBH sapi Bali yang dipelihara secara semi intensif 0,221 kg/ekor/hari,
sedangkan secara ekstensif menjadi 0,126 kg/ekor/hari.
Kelayakan usahatani SITT kelapa- jagung manis- sapi
Untuk melakukan usahatani terintegrasi kelapa-jagung manis-sapi, diperlukan biaya tetap
sebesar Rp 2.832.000,- untuk membeli sapi, susut kandang dan susut peralatan. Modal kerja sebagai
biaya variabel sebesar Rp. 17.935.000,- diasumsikan hanya 2 musim tanam jagung per tahun.
Keuntungan dengan penerapan SIIT, tidak ada modal kerja untuk pembersihan lahan karena dengan
adanya pemeliharaan tanaman sela lahan diantara tanaman kelapa terlihat bersih. Untuk usahatani
kelapa monokultur, modal kerja yang dibutuh Rp. 1.075.000,- untuk upah tenaga panen dan
pembersihan lahan sebanyak 2 kali dalam setahun.
Penerapan SITT kelapa-jagung manis-sapi mampu meningkatkan 60,58% pendapatan petani
yaitu sebesar Rp. 2.984.000,-/ tahun dibandingkan system usaha tani monokultur. Berdasarkan analisis
finansial, keuntungan dari SITT yaitu Rp. 7.909.000,-/ha/tahun dengan nilai B/C 1,38. Keuntungan
dari usahatani monokultur hanya sebesar Rp. 4.925.000,-. Penerimaan SITT diperoleh dari penjualan
jagung manis sebanyak 16.480 buah dengan harga jual Rp. 1.000,-/ buah, penjualan sapi, pejualan
kopra sebanyak 2.000 kg dengan harga Rp. 3.000/ kg dan penjualan pupuk kandang sebanyak 2.880
kg dengan harga jual Rp. 200,-/ kg.
Tabel 2. Analisis kelayakan usahatani kelapa-jagung manis-sapi
Uraian SITT Kelapa-Jagung
Manis-Sapi Monokultur
(Rp.) (Rp.)
A. BIAYA TETAP 2.832.000 -
Tanah - -
Bibit sapi 2.622.000 -
Susut kandang 100.000 -
Susut peralatan 10.000 -

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara Vol. 7, No. 1, 2018
11
Peralatan olah pakan 100.000 -
B. MODAL KERJA 17.935.000 1.075.000
Saprodi:
Benih jagung (25 kgx 2 musim) 2.500.000 -
Pupuk urea (300 kgx 2 musim) 2.100.000 -
Pupuk NPK (400 kgx 2 musim) 3.600.000 -
Pupuk kandang (1.000 kgx 2 musim) 400.000 -
Obat-obatan/ herbisida dll (2 musim) 300.000 -
Pakan tambahan dan obat
( Dedak halus+ obat) 360.000 -
Upah tenaga kerja:
Olah tanah (2 musim) 1.800.000 -
Penanaman (2 musim) 1.000.000 -
Pemupukan (2 musim) 600.000 -
Pemeliharaan (2 musim) 1.600.000 -
Panen dan pasca panen (2 musim) 1.800.000 -
Pemeliharaan sapi (pengolahan
pakan
dan pemeliharaan) 1.200.000 -
Pembersihan lahan (2 kali) - 400.000
Panen dan pascapanen kelapa (3 x
150 pohon) 675.000 675.000
C. PENERIMAAN 28.676.000 6.000.000
Penjualan jagung manis 16.480.000 -
Penjualan sapi 5.620.000 -
Penjualan kopra 6.000.000 6.000.000
Penjualan pupuk kandang 576.000 -
PENDAPATAN BERSIH 7.909.000 4.925.000
B/C 1,38
NKB 1,15
Nilai NKB dari penerapan SITT kelapa-jagung manis-sapi yaitu 1,15. Ini berarti penerapan
SITT mampu meningkatkan keuntungan petani kooperator. Dengan demikian, secara finansial
teknologi SITT kelapa-jagung manis-sapi layak diterapkan karena nilai B/C dan NKB lebih dari 1.
KESIMPULAN
Sistem integrasi tanaman kelapa-jagung manis-sapi menunjukan hasil yang positif, tetapi
untuk pengembangan dalam skala besar diperlukan pengkajian menyeluruh dan multi-lokasi di
Maluku Utara.

12 Kelayakan usaha integrasi kelapa-jagung manis-sapi di lahan kering Maluku Utara
DAFTAR PUSTAKA
Adnyana, M.O. dan K. Kariyasa. 1995. Model Keuntungan Kompetitif Sebagai Alat Analisis Dalam
Memilih Komoditas Unggulan Pertanian. Informatika Penelitian. Vol 5(2): 251-258
BPS. 2014. Maluku Utara dalam Angka. Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku Utara.
BPTP Maluku Utara. 2009. Gelar Teknologi Jagung Hibrida Bima 5 di Maluku Utara. Laporan Akhir.
BPTP Maluku Utara. 2015. Kajian Agribisnis Tanaman Kelapa (Teknologi Budidaya, Pengendalian
OPT, dan Produk Olahan Kelapa). Laporan Akhir.
Elly, FH., Sinaga, BM., Sri Utami Kuntjoro, AU., dan Nunung Kusnadi. 2008. Pengembangan Usaha
Ternak Sapi Rakyat Melalui Integrasi Sapi Tanaman di Sulawesi Utara. Jurnal Litbang
Pertanian, 27(2), 2008. Tersedia pada:
http://www.pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/p3272084.pdf
Fisher, K.S. dan A.F.E. Palmer. 1984. Jagung Tropik. CIMMYT, Mexico. Dalam R. Goigworthy dan
N.M. Fisher (Ed.).Terjemahan Tohari, Penyunting Soedharoedjian. Fisiologi Tanaman
Budidaya Tropika. Gadjah Mada University Press. hlm. 305-307.
Hadi, Rustan. 2009. Teknik Optimalisasi Pemanfaatan Lahan di Antara Tanaman Kelapa di Daerah
Pasang Surut Jambi. Buletin Teknik Pertanian Vol. 14 No. 1, 2009: 40-43.
Hendaru, Indra H. et. al. 2011. Laporan Akhir Kegiatan Prima Tani Kabupaten Halmahera Barat.
BPTP Maluku Utara.
Kaat, H dan S.N. Dawis. 1986. Pengaruh Tanaman Sela Terhadap Produksi Kelapa. Jurnal Penelitian
Kelapa (1): 34-36.
Malia, IE., Paat, PC., Aryanto, dan Bahtiar. 2006. Kelayakan Sistem Usahatani Jagung-Ternak Sapi-
Kelapa di Sulawesi Utara. Prosiding Pekan Serealia Nasional, 2010. Ha; 607-618. ISBN : 978-
979-8940-29-3.
Nataatmaja, H. 2004. Studi Pelaksanaan Pengembangan Sistem “Crop-Livestock” melalui BLM.
Zurahman, N dan The, E. 2011. Pendugaan Bobot Badan Calon Pejantan Sapi Bali Menggunakan
Dimensi Ukuran Tubuh. Buletin Peternakan Volume 35(3): 160-164.
Paat, PC., dan Taulu, LA. 2006. Potensi dan Peluang Pengembangan Sistem Integrasi Jagung – Sapi di
Sulawesi Utara. Lokakarya Nasional Pengembangan Jejaring Litkaji Sistem Integrasi
Tanaman –Ternak. Hal 99-106.
Price GJ 1972, Economic analysis of agricultural project. The economic development institute,
Interbational Bank for reconstruction and development, The John Hopkins University Press,
Baltimore and London. 221 p.
Zuraida, R. 2010. Usaha tani Padi dan Jagung Manis pada Lahan Tadah Hujan untuk Mendukung
Ketahanan Pangan di Kalimantan Selatan
(Kasus di Kec. Landasan Ulin Kotamadya Banjarbaru). Prosiding Pekan Serealia Nasional,
2010. Hal; 597-601. ISBN : 978-979-8940-29-3.

13
STATUS PERKEMBANGAN PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
MALUKU UTARA
Ahmad Yunan Arifin
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara.
Jl. Komp. Pertanian Kusu Kec. Oba Utara Kota idore Kepulauan Maluku Utara
Email: [email protected]
ABSTRAK
Saat ini telah terjadi kecenderungan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap struktur
perekonomian di setiap wilayah. Kondisi ini disebabkan adanya fokus kebijakan dan implementasi
pada kegiatan non pertanian pada struktur pembangunan wilayah. Kajian ini bertujuan untuk a).
Mengidentifikasi karakteristik subsektor pertanian dalam pembangunan wilayah dan b). Menyusun
strategi dalam mengoptimalisasi peran subsektor pertanian dalam pembangunan wilayah. Kajian
dilakukan pada bulan Januari – April 2009 di provinsi Maluku Utara menggunakan data sekunder
yang tersedia. Data dianalisis menggunakan pendekatan Shift Share Analysis (SSA) dan tipologi
Klassen untuk mengidentifikasi kontribusi subsektor pertanian dalam pembangunan wilayah serta
analisis deskriptif untuk mengetahui situasi dan permasalahan pembangunan pertanian. Hasil kajian
menunjukkan adanya 7 (tujuh) akar permasalahan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap
struktur perekonomian wilayah, yaitu a). keterbatasan infrastruktur dasar dan pertanian; b). Rendahnya
produktivitas usaha tani; c). Rendahnya kapasitas kolektif petani; d). Rendahnya produktivitas kerja
petani akibat akses pendidikan dan kesehatan yang rendah; e). Minimnya lapang usaha dan
keterbatasan kemampuan pemanfataan peluang usaha; f). Pendekatan pembangunan birokratik dan
sentralistik; dan g). Pelaksanaan manajemen pembangunan perdesaan bersifat egosektoral. Dalam hal
ini, pendekatan kawasan berbasis gugus pulau diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan
sumberdaya alam dan penyediaan sumberdaya buatan untuk peningkatan produktivitas usaha
pertanian. Pengembangan gugus pulau memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan ekologis,
karakterisitik dan potensi pertanian wilayah, pengembangan pusat pertumbuhan dan pelayanan sarana
ekonomi sosial, serta keterkaitan potensi masing-masing pulau secara fungsional dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan kehidupan ekonomi masyarakat pada suatu gugus pulau.
PENDAHULUAN
Hingga saat ini, pertanian dipandang sebagai suatu subsektor yang memilki kemampuan
khusus dalam memadukan pertumbuhan dan pemerataan (growth with equity) di tingkat wilayah.
Dalam hal ini, kesejahteraan masyarakat perdesaan dapat ditingkatkan dan kesenjangan perdesaan-
perkotaan dapat dikurangi melalui optimalisasi pembangunan subsektor pertanian. Dengan demikian,
keberhasilan pembangunan subsektor pertanian memiliki peran vital dalam mengurangi kemiskinan
dan kesenjangan antar wilayah. Hal ini disebabkan pertumbuhan sektor pertanian memiliki
kemampuan khusus untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan estimasi lintas negara menunjukkan
bahwa pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang dipicu oleh subsektor pertanian, minimal
memiliki dua kali lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan daripada pertumbuhan yang disebabkan
oleh sektor di non pertanian (Bank Dunia, 2008). Pertumbuhan di sektor pertanian diyakini pula
memiliki efek pengganda (multiplier effects) yang tinggi karena pertumbuhan di sektor ini mendorong
pertumbuhan yang pesat di sektor-sektor perekomonian lain, misalnya di sektor pengolahan (agro-
industry) dan jasa pertanian (agro-services).
Ironisnya, saat ini telah terjadi kecenderungan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap
struktur perekonomian di Maluku Utara. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya beberapa titik lemah
dalam kebijakan dan implementasi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi (termasuk
pertanian). Pemerintah telah melakukan berbagai pendekatan pembangunan sektor pertanian seperti

14
pembangunan pertanian terpadu, pembangunan pertanian berwawasan lingkungan, dan pembangunan
pertanian berwawasan agroindustri. Namun, upaya tersebut sampai saat ini belum menghasilkan
pencapaian yang optimal. Dengan demikian, diperlukan sebuah pendekatan pemberdayaan alternatif
yang mampu memberdayakan masyarakat pedesaan secara holistik dan sinergis. Berimbang antara
aspek ekonomi, infrastruktur, sosial dan kelembagaan serta lingkungan hidup lewat pengembangan
kawasan yang melingkupinya yang mampu membuka peluang melakukan sinergitas beragam kegiatan
lebih yang dinamis dan produktif yang melibatkan partisipasi berbagai pihak dalam merespon
ketidakberdayaan dan kemiskinan akut. Asumsi ini sejalan dengan pandangan dan pengalaman
empirik bahwa partisipasi adalah jalan mencapai pemberdayaan (Sajogyo, 1977) yang tentu akan lebih
efektif apabila didekati melalui kebijakan pengembangan kawasan perdesaan berbasis komunitas atau
masyarakat.
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan kajian ini sebagai berikut: a).
Mengidentifikasi karakteristik subsektor pertanian dalam pembangunan wilayah dan b). Menyusun
strategi dalam mengoptimalisasi peran subsektor pertanian dalam pembangunan wilayah.
METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat
Kajian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan April 2009 dengan menganalisis data
sekunder terkait di wilayah Maluku Utara.
Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder yang terdiri dari dokumen instansi terkait
dan data Biro Pusat Statistik.
Analisa Data
Shift Share Analysis (SSA) merupakan suatu analisis ekonomi wilayah yang mengidentifikasi potensi
dan daya saing perkembangan suatu program pembangunan wilayah. Persamaan yang digunakan
adalah:
∆ 𝑌𝑖 = 𝑃𝑅𝑖𝑗 + 𝑃𝑃𝑖𝑗 + 𝑃𝑃𝑊𝑖𝑗
Atau secara rinci dapat dinyatakan;
𝑌′𝑖𝑗 − 𝑌𝑖𝑗 = ∆𝑌𝑖𝑗 = 𝑌𝑖𝑗 (𝑅𝑎 − 1) + 𝑌𝑖𝑗(𝑅𝑖 − 𝑅𝑎) + 𝑌𝑖𝑗 (𝑟𝑖 − 𝑅𝑖)
∆𝑌𝑖𝑗 = 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑖 𝑘𝑒 − 𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑘𝑒 − 𝑗
Yij = PDRB subsektor pertanian ke-i pada provinsi ke-j pada tahun dasar analisis
Y’ij = PDRB subsektor pertanian ke-i pada provinsi ke-j pada tahun akhir analisis
Yi = PDRB subsektor pertanian ke i di seluruh wilayah penelitian pada tahun dasar
analisis
Y’i = PDRB subsektor pertanian ke i di seluruh wilayah penelitian pada tahun akhir
analisis
Y.. = PDRB seluruh subsektor pertanian pada tahun dasar analisis
Y’.. = PDRB seluruh subsektor pertanian pada tahun akhir analisis
Ra = Y’.. / Y..
Ri = Y’i. / Yi.
ri = Y’ij / Yij
Tipologi Klassen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola pertumbuhan
ekonomi daerah dengan klasifikasi sebagai berikut: (a) wilayah maju dan tumbuh cepat (ri > r dan yi <
y); (b) wilayah maju dan tertekan (ri < r dan yi > y); (c) wilayah sedang tumbuh (ri > r dan yi < y); dan
(d) wilayah yang relatif tertinggal (ri < r dan yi < y).
Keterangan:
ri = Laju pertumbuhan ekonomi PDRB wilayah i
yi = PDRB perkapita wilayah i

15
r = Laju pertumbuhan PDRB wilayah referensi
y = PDRB perkapita wilayah referensi
HASIL PEMBAHASAN
Kebijakan Pembangunan Maluku Utara
Pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhannya merupakan salah satu kebutuhan dalam
rangka membangun perekonomian di daerah. Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) merupakan
salah satu indikator yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi wilayah.
Maluku Utara memiliki nilai PDRB sebesar 2.6 trilyun dengan rata-rata laju pertumbuhan selama
periode tahun 2001 – 2008 yang cukup tinggi, yaitu 5,9%/th. Namun demikian, laju pertumbuhan ini
tidak diiringi dengan perkembangan kualitas pembangunan ekonomi dan manusia yang cukup baik.
Hal ini terlihat adanya ketimpangan ekonomi dan efisiensi pengelolaan sumber daya dalam
pelaksanaan pembangunan di wilayah Maluku Utara.
Ketimpangan Pembangunan
Dalam hal distribusi ketimpangan pembangunan ekonomi, dapat diidentifikasi menurut
aspeknya, yaitu dimensi sektoral, spasial, distribusi pendapatan dan pengeluaran. Dari dimensi
sektoral, pada tahun 2008, sektor pertanian mampu memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB
Maluku Utara, yaitu sebesar 39,5 %. Namun demikian, sebagian besar laju pertumbuhan ini
disumbang oleh sektor pertambangan (10.8%), bangunan (10.3%), serta pengangkutan dan komunikasi
(8.9%). Sektor pertanian hanya memiliki laju pertumbuhan sebesar 4.7%. Seiring dengan tingginya
jumlah keluarga pra sejahtera di perdesaan yang mencapai 96% dari total keluarga pra sejahtera (BPS,
2008), fenomena ini menunjukkan adanya indikasi perhatian pemerintah daerah yang lebih besar pada
subsektor non-pertanian, khususnya pertambangan, perdagangan, bangunan, serta pengangkutan dan
komunikasi.
Beradasarkan aspek spasial, kota Ternate merupakan penyumbang sumbangan terbesar dalam
pembentukan PDRB Maluku Utara Tahun 2007 (19,3%), diikuti dengan kabupaten Halmahera Selatan
(19,2%), Halmahera Utara (16,7%), Kep. Sula (11,4%), Tidore Kep. (9,1%), Halmahera Timur
(8,3%), Halmahera Barat (8,0%), dan Halmahera Tengah (7,9%).
Senada dengan hal tersebut, tipologi Klassen berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan per kapita memberikan informasi terkait pola pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Hasil
analisis memberikan gambaran bahwa tingginya ketimpangan pertumbuhan antar kabupaten/kota.
Hanya Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Timur yang masuk dalam Wilayah Maju dan Tumbuh
Cepat sedangkan Halmahera Tengah, Selatan, Utara, dan Tidore Kepulauan (Wilayah Maju Tetapi
Tertekan) serta Halmahera Barat dan Kep Sula (Wilayah Relatif Tertinggal). Dalam teori ekonomi,
adanya perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar kabupaten/kota yang besar menyebabkan pengaruh
yang merugikan (backwash effects) terhadap pertumbuhan wilayah provinsi Maluku Utara. Perbedaan
pertumbuhan wilayah yang cukup besar menyebabkan adanya perbedaan ketersediaan sumber daya
yang dimiliki setiap wilayah sehingga pemilik modal (investor) cenderung memilih wilayah dengan
pertumbuhan cepat karena tersedinya berbagai fasilitas pendukung usaha, meliputi prasarana
perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, dan ketersediaan tenaga
terampil.
Efisiensi Pembangunan Sumberdaya
Pembangunan ekonomi dalam kerangka otonomi daerah menghendaki adanya pengelolaan dan
penggunaan sumberdaya yang efisien untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi daerah
berdasarkan potensi dan karakteristik. Efisiensi pengelolaan sumberdaya dapat diuraikan dari efisiensi
pendayagunaan sumberdaya fisik dan manusia serta sumberdaya alam.
Penilaian efisiensi pendayagunaan aspek sumberdaya fisik menggunakan metode Shift Share
Analysis (SSA) untuk memperoleh gambaran secara umum terkait efisiensi pendayagunaan
sumberdaya fisik dan manusia di tingkat wilayah (Tabel 1). Metode SSA mengukur kegiatan ekonomi

16
pada seluruh sektor dengan memberikan asumsi adanya perubahan pendapatan dan produksi wilayah
menurut tiga komponen pertumbuhan, yaitu pertumbuhan regional, proporsional, dan pangsa pasar.
Tabel 1. Hasil Analisis SSA Wilayah Pusat Pertumbuhan Maluku Utara (Kota Ternate)
N
o
Sektor Ternate Maluku Utara Pertumbuhan Pertum
b
Pangsa
Pasar
Th
2005
Th
2007
Th
2005
Th
2007
Region
-al
Propor
si-onal
1 Pertanian 55.717 61.745 792.67 870.19 6.585 -1.137 580
2 Pertambangan
dan Penggalian
3.807 4.512 106.62 123.40 450 149 106
3 Industri
Pengolahan
26.731 29.388 343.32 370.48 3.159 -1.045 542
4 Listrik, Gas,
dan Air
6.447 6.725 11.177 12.625 762 73 -557
5 Bangunan 13.662 16.657 33.574 40.704 1.615 1.287 94
6 Perdagangan,
Hotel, dan
Resto
141.25 161.08 540.69 619.28 16.695 3.837 -701
7 Pengangkutan
dan Kominukasi
57.660 76.728 157.73 185.63 6.815 3.384 8.869
8 Keuangan &
Persewaan
29.869 32.560 74.071 83.695 3.530 351 -1.190
9 Jasa-jasa 79.941 89.260 176.92 195.14 9.448 -1.215 1.086
TOTAL 415.08 478.65 2.236.
8
2.501.
1
49.060 5.684 8.828
Sumber: BPS, 2008
Kota Ternate, sebagai wilayah pusat pertumbuhan di Maluku Utara, memiliki pertumbuhan
regional dan proporsional paling tinggi berada pada sektor perdagangan-perhotelan-restoran. Namun
demikian, sektor pertanian termasuk dalam kategori pertumbuhan regional yang cepat tetapi masuk
dalam kategori pertumbuhan proporsional yang tidak maju. Kedepannya, diperlukan pembenahan dan
penguatan sistem agribisnis yang didukung dengan kebijakan yang kondusif, meliputi aspek
pemasaran, kelembagaan, perpajakan dan subsidi untuk memajukan sektor pertanian Maluku Utara.
Penilaian efisiensi pengelolaan aspek sumberdaya alam, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
di Maluku Utara telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam dan
kualitas lingkungan akibat kurang diperhatikannya faktor produksi, sosial, dan ekologi dalam
pengelolaan SDA. Sebagai gambaran dapat diuraikan pengurasan tambang (dalam hal ini nikel) dan
kayu sebagai primadona sumberdaya alam Maluku Utara. Berdasarkan Laporan Triwulan IV Bank
Indonesia, terdapat peningkatan ekspor tambang nikel yang cukup signifikan selama tahun 2009
hingga mencapai 43% di Maluku Utara. Diperkirakan ekspor ini akan terus meningkat seiring
masuknya invetasi baru maupun ekspansi usaha dari dua perusahaan tambang besar yang ada, yaitu
PT. NHM dan PT. Antam. Kedepannya, pertanian di kedua wilayah tersebut akan dihadapkan dengan
permasalahan meningkatnya kerusakan lahan, menurunnya kesuburan dan produktivitas lahan,
meluasnya lahan kritis, serta berkurangnya daya dukung lingkungan.
Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai
pelaksana dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan
pembangunan wilayah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Strategi
pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada karakteristik yang dimiliki daerah sehingga
mampu mendayagunakan potensi sumber daya manusia, sumber-sumber fisik serta kelembagaan local,
baik formal maupun non formal.

17
Permasalahan Pembangunan Perdesaan
Pada dasarnya, pembangunan yang efisien dan efektif dapat tercapai apabila mampu
memanfaatkan sumberdaya yag terbatas untuk memberikan hasil yang maksimal, bermanfaat bagi
masyarakat, dan merupakan upaya pemecahan masalah yang mendasar dan permanen sehingga dapat
landasan yang kuat untuk pembangunan ke depan. Dalam hal ini, pembangunan di subsektor pertanian
menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, meliputi aspek sumberdaya alam, ekonomi, sosial,
budaya, kelembagaan, pendidikan, kesehatan, dan politik. Atas dasar hal ini, perlu dilakukan
penelusuran akar permasalahan dan kemudian membangun mulai dari akar permasalahan.
Membangun dari akar permasalahan diharapkan dapat mengoptimalkan sumberdaya yang terbatas
secara tepat untuk mendukung prioritas pembangunan yang memberikan manfaat secara luas.
Menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di “permukaan” hanya bersifat sementara dan
tidak menyelesaikan akar permasalahan sehingga cenderung menimbulkan masalah baru yang lebih
kompleks. Mengingat kompleksitas permasalahan, maka permasalahan pembangunan perdesaan
dikelompokkan berdasarkan unsur-unsur di dalamnya, yaitu petani, pertanian, dan pelaksanaan
pembangunan perdesaan.
Petani
• Sektor pertanian sebagai sumber penghasilan 82% keluarga di Maluku Utara belum mampu secara
optimal memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani. Terbukti, hampir
sebagian besar jumlah penduduk miskin di Maluku Utara (73% dari total penduduk miskin) berada
di desa (BPS, 2007). Selain itu, terdapat kecenderungan tingginya rata-rata angka pengangguran
di tingkat desa, yaitu sebesar 30 orang/desa (BPS, 2003).
• Sektor pertanian yang identik sebagai sumber penghasilan utama di perdesaan, tidak mampu
memberikan jaminan kelangsungan hidup bagi masyarakat. Data menunjukkan bahwa rata-rata
jumlah penduduk yang “keluar” desa (urbanisasi) sebanyak 3 orang/desa/tahun. Kota Ternate
sebagai wilayah pusat pertumbuhan di Maluku Utara, merupakan daerah tujuan utama urbanisasi
dengan rata-rata jumlah penduduk yang datang per kelurahan di kota Ternate, sebanyak 22 org
dalam kurun waktu 1 tahun (2008). Hal ini menggambarkan sektor pertanian tidak mampu
memberikan jaminan kelangsungan lapangan kerja sehingga seiring dengan terjadinya urbanisasi,
maka terjadi perubahan sumber penghasilan utama masyarakat dari petani ke non pertanian (BPS,
2008).
• Kualitas SDM dapat diukur melalui Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan
mempertimbangkan hubungan antara faktor penghasilan dan kesejahteraan. Nilai Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara selama kurun waktu 3 tahun (2006-2008) cukup
rendah, yaitu 67,82-68,8 dengan rata-rata nasional sebesar 70,1-71,2 (BPS, 2008). Kondisi ini
menjadi penyebab rendahnya produktivitas kerja sebagian besar masyarakat, termasuk didalamnya
petani, cukup rendah.
• Tingkat produktivits kerja dipengaruhi oleh status kesehatan dan kemampuan askses masyarakat
terhadap pendidikan. Dalam hal ini, masyarakat Maluku Utara memiliki tingkat kerentanan yang
tinggi terhadap berbagai wabah penyakit (muntaber,demam berdarah, dan TBC) dengan rata-rata
penderita berjumlah 2,5 orang/desa/th (BPS, 2008). Selain itu, berdasarkan pola pengeluaran
pendapatan masyarakat, hanya sebagian kecil pendapatan masyarakat di perdesaan yang
dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, yaitu sebesar 4.4%. Dengan
demikian, perlu adanya upaya peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka mewujudkan
peningkatan kualitas sumberdaya manusia di tingkat masyarakat, khususnya di perdesaan (Susenas,
2005).
Produktivitas Pertanian
• Keragaan produktivitas seluruh komoditas pertanian di Maluku Utara masih jauh dibawah standar
nasional, kecuali tanaman cengkeh. Standar produktivitas nasional tanaman cengkeh adalah 480 –
800 kg/ha sedangkan tingkat produktivitas cengkeh di Maluku Utara sebesar 547 kg/ha. Ironisnya,
produktivitas cengkeh yang merupakan tanaman asli Maluku Utara ini memiliki nilai yang lebih
rendah dibandingkan provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yaitu sebesar 632 kg/ha.

18
• Hal yang sama terlihat dari rendahnya pola diversifikasi usaha tani. Secara nasional. Rata-rata
jumlah industri pengolahan makanan skala kecil/rumah tangga di tingkat desa sangat rendah, yaitu
3 vs 9 industri/desa (BPS, 2008) . Dengan demikian, produktivitas usaha tani yang rendah diikuti
dengan aktivitas nilai tambah yang juga rendah akibat kegiatan agroindustri di perdesaan yang
belum optimal.
• Produktivitas usaha tani memerlukan kemudahan akses terhadap invasi teknologi di wilayah
perdesaan sehingga mampu membuka kesempatan bagi penyaluran informasi ke komunitas
pedesaan, memperbaiki hubungan antar penelitian dan penyuluhan, serta mendukung
pengembangan daerah pedesaan. Ketersediaan kelembagaan petani dan media informasi
masyarakat desa yang relatif rendah, yang terlihat dengan keberadaan kegiatan penyuluhan yang
hanya berada di 137 desa (17,8%); keberadaan kelompok tani 412 desa (53,6%); dan keberadaan
kegiatan sosial-keagamaan 474 desa (61,7%) (BPS, 2003). Kondisi ini berakibat lemahnya upaya
dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan dan peluang di tingkat
desa. Selain itu, masih minimnya penerapan inovasi teknologi pertanian memerlukan upaya khusus
peningkaatan adopsi inovasi teknologi melalui berbagai saluran diseminasi yang tersedia di tingkat
wilayah.
Pembangunan Perdesaan
• Terdapat indikasi perhatian pemerintah yang lebih besar pada sektor non-pertanian, khususnya
pertambangan, bangunan, serta pengangkutan dan komunikasi. Provinsi Maluku Utara memiliki
nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 2.6 trilyun pada tahun 2008 dengan
subsektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 37,5%. Namun demikian, sebagian besar laju
pertumbuhan ini disumbang oleh sektor pertambangan (10.8%), bangunan (10.3%), serta
pengangkutan dan komunikasi (8.9%). Subsektor pertanian hanya memiliki laju pertumbuhan
sebesar 4.7%.
• Keterbatasan infrasturktur dasar dan infrastruktur pertanian (jaringan irigasi, modal dan pemasaran
produksi) mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat petani secara ekonomi. Kondisi
infrastruktur dasar, dalam hal ini jalan dan listrik di tingkat perdesaan menunjukkan hanya sebesar
62% jenis jalan utama desa merupakan jalan aspal dan 38% merupakan jenis jalan batu maupun
tanah. Jumlah keluarga yang mampu mengakses listrik untuk mendukung kegiatan ekonomi dan
kebutuhan dasar keluarga hanya sebesar 59%. Kondisi infrastruktur pertanian, dalam hal ini
jaringan irigasi, hanya sebesar 20% lahan sawah merupakan lahan berpengairan teknis. Kondisi ini
menunjukkan minimnya ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas ekonomi
masyarakat.
• Kemampuan dan kemudahan akses petani terhadap permodalan dan pasar juga cukup rendah, yang
ditunjukkan dengan kecilnya jumlah desa yang menerima fasilitas kredit untuk petani (KKP, KUK,
KPR, dll), yaitu hanya sebesar 36% dari seluruh desa yang ada; kecilnya jumlah keberadaan
lembaga keuangan di tingkat desa, yaitu 8% dari seluruh desa yang ada; dan rata-rata jarak desa ke
pasar cukup jauh, yaitu sebesar 26,3 km (BPS, 2008). Dari aspek sarana produksi (mesin produksi),
rata-rata jumlah kepemilikan mesin pengolah hasil pertanian di tiap desa (mesin pengolah padi,
jagung, dan atau ubi kayu) hanya sebesar 2 unit/desa (BPS, 2003).
• Tersebarnya program/kegiatan antar sektor di berbagai wilayah desa di Maluku Utara sehingga
dampak masing-masing program/kegiatan terhadap pertumbuhan wilyah/desa tidak optimal.
Berbagai program/kegiatan telah masuk di tingkat desa, dengan rincian program/kegiatan dari
pemerintah kabupaten/kota; pemerintah pusat; serta sumber dana luar negeri, swasta dan sumber
lainnya masing-masing 90%; 33%; 43%; serta 27% dari seluruh desa yang ada di Maluku Utara
(BPS, 2008).
Strategi Optimalisasi Subsektor Pertanian
Merujuk kondisi diatas, dapat dipastikan masyarakat dan desa akan terus menghadapi
ketidakberdayaan dalam pembangunan pertanian. Dalam hal ini, pembangunan di subsektor pertanian
menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, meliputi aspek sumberdaya alam, ekonomi, sosial,
budaya, dan kelembagaan. Atas dasar hal ini, maka strategi optimalisasi subsektor pertanian dalam
pembangunan wilayah diharapkan mampu mempertimbangkan akar permasalahan pembangunan

19
pertanian dan perdesaan. Menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di “permukaan” hanya
bersifat sementara sehingga cenderung menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Oleh karena
itu, membangun dari akar permasalahan diharapkan dapat mengoptimalkan sumberdaya yang terbatas
secara tepat untuk mendukung prioritas pembangunan yang memberikan manfaat secara luas.
• Pertama, masyarakat dan desa menghadapi terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar dan
infrastruktur pertanian sehingga masyarakat relatif kurang mampu memanfaatkan peluang usaha
yang ada. Diperlukan upaya pemberdayaan wilayah berbasis gugus pulau dalam penyediaan
infrastruktur pendukung usaha di tiap wilayah.
• Kedua, produktivitas dan produksi usaha tani di tingkat petani sangat rendah di seluruh subsektor
pertanian. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat penerimaan pendapatan petani yang
diterima oleh petani. Diperlukan upaya peningkatan produktivitas usaha tani melalui penerapan
inovasi teknologi dan peningkatan nilai tambah petani melalui pemanfaatan peluang diversifikasi
usaha. Peningkatan adopsi inovasi teknologi dilakukan dengan mengintensifkan penyuluhan
berbasis potensi dan permasalahan pertanian di tiaap wilayah.
• Ketiga, masyarakat petani di perdesaan dengan kondisi perekonomian yang belum baik, sangat
rentan terhadap berbagai penyakit, gizi buruk dan sekarang semakin sangat tidak berdaya untuk
akses kepada pendidikan dan kesehatan dasar. Kondisi ini berpengaruh terhadap kinerja dan
produktivitas petani di perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelayanan pendidikan
dan kesehatan yang baik hingga ke tiap wilayah. Seiring dengan meningkatnya aksesibilitas antar
wilayah melalui pendekatan pembangunan berbasis gugus pulau maka layanan pendidikan dan
kesehatan dapat disediakan pada pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat pada setiap gugus pulau.
• Keempat, kapasitas kolektif masyarakat desa terus menurun dalam merespon tantangan dan
memanfaatkan peluang yang ada di desa. Gejala yang tumbuh adalah kecenderungan masyarakat
tidak berminat menemukenali dan mengelola potensi sumberdaya yang ada di desa tempat
tinggalnya secara kreatif dan produktif untuk kesejahteraan bersama. Masyarakat cenderung
meninggalkan desa menuju wilayah perkotaan yang berimplikasi pada perubahan sumber
penghasilan dari pertanian sebagai basis keahlian ke non pertanian. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan kelembagaan petani melalui pemberdayaan kelompok tani yang telah tumbuh di tingkat
masyarakat, seperti kelompok pengajian, perkumpulan PKK, dan kelembagaan adat. Dalam hal ini,
peningkatan kemampuan petani dilakukan secara kolektif agar mampu memahami potensi dan
permasalahan serta rencana aksi secara bersama dalam meningkatkan produktivitas usaha pertanian
di tiap wilayah.
• Kelima, terjadi degradasi sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi
sumberdaya alam. Kondisi ini berakibat menurunnya daya dukung wilayah dalam memenuhi
kebutuhan hidup dan kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Diperlukan upaya program pertanian
padat karya yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja di perdesaan. Hal ini diharapkan
dapat mengurangi tingkat urbanisasi yang relatif tinggi di Maluku Utara.
• Keenam, pendekatan pembangunan birokratik dan sentralistik melalui bantuan program/kegiatan
di tingkat desa, menyebabkan masyarakat desa memiliki ketergantungan pada pihak luar dalam
melaksanakan aktivitas usaha. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, pola pembangunan ini telah
melemahkan kearifan lokal dan pranata sosial (kelembagaan adat) yang mampu memberikan solusi
dalam pemecahan berbagai persoalan di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan
pembangunan pertanian partisipatif sehingga petani dapat melaksanakan program pembangunan
pertanian sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat serta monitoring pelaksanaan kegiatan
melalui kelembagaan lokal yang ada di tingkat masyarakat.
• Ketujuh, pelaksanaan manajemen pembangunan perdesaan masih bersifat egosektoral. Belum
adanya mekanisme pengaturan intervensi berbagai pihak dalam mendukung pengembangan
perdesaan, khususnya untuk subsektor pertanian. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan
pertanian berbasis gugus pulau diharapkan dapat mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya yang
ada pada instansi yang berbeda. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai efisiensi pemanfataan
sumberdaya utama dan pendukung dalam mendukung kegiatan pertanian di tiap wilayah.

20
KESIMPULAN
Kualitas dan kuantitas pertumbuhan ekonomi wilayah cenderung mengalami penurunan akibat
terjadi penurunan kontribusi subsektor pertanian terhadap struktur perekonomian di wilayah Maluku
Utara. Kondisi ini disebabkan adanya kelemahan dalam kebijakan dan implementasi yang berkaitan
dengan pembangunan ekonomi, termasuk subsektor pertanian. Dengan demikian, diperlukan sebuah
pendekatan pemberdayaan alternatif yang mampu memberdayakan masyarakat pedesaan secara
sinergis antara aspek ekonomi, infrastruktur, sosial dan kelembagaan melalui pengembangan kawasan
sehingga petani mampu mengoptimalkan peluang usaha pertanian yang produktif. Dalam hal ini,
pendekatan kawasan berbasis gugus pulau diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya
alam dan penyediaan sumberdaya buatan untuk peningkatan produktivitas usaha pertanian.
Pengembangan gugus pulau memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan ekologis, karakterisitik
dan potensi pertanian wilayah, pengembangan pusat pertumbuhan dan pelayanan sarana ekonomi
sosial, serta keterkaitan potensi masing-masing pulau secara fungsional dalam rangka memenuhi
kebutuhan dan kehidupan ekonomi masyarakat pada suatu gugus pulau.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS), 2012. Maluku Utara Dalam Angka. BPS. Ternate.
Badan Pusat Statistik (BPS), 2011. Potensi Desa. BPS. Jakarta.
Badan Pusat Statistik (BPS), 2003. Potensi Desa. BPS. Jakarta.
Bulohlabna, C. 2008. Tipologi dan pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan
timur indonesia. Departemen Ilmu Ekonomi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Chambers, R. 1995. “Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?” IDS Discussion Paper 347,
1995.
Cheyne, Christine, Mike O’Brien dan Michael Belgrave. 1998. Social Policy in Aotearoa New
Nealand: A Critical Introduction, Auckland: Oxford University Press. Hal 91 dan 97).
Delis, A. 2008. Peran infrastruktur sebagai pendorong dinamika ekonomi sektoral dan regional
berbasis pertanian. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor
Edi Suharto. “Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Konsep dan Strategi
Pengentasan Kemiskinan menurut Perspektif Pekerjaan Sosial”.
(http://www.policy.hu/suharto/makIndo15.html, 11 april 2005).
Hardono, S.G., 2002. Dampak perubahan faktor-faktor ekonomi terhadap ketahanan pangan rumah
tangga pertanian. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
La Ode Samsul Barani. 2009. Analisis Spasial Untuk Perumusan Kebijakan Pengembangan Kawasan
Pulau-Pulau Kecil. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
Manafi R. 2003. Rancangbangun pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis pemanfaatan ruang. Program
Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
Renata Lok-Dessallien. “Review of Poverty Concepts and Indicators”.
(http://www.undp.org/poverty/publications/pov_red/Review_of_Poverty_Concepts.pdf., 11 Mei
2005).
Rustiadi, E. 2001. Perencanaan Wilayah Di Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Dan Disparitas
Antar Wilayah Di Era Otonomi Daerah1. Makalah. Diskusi Program Certification, Environment
Justice And Natural Asset. Lembaga Alam Tropika Indonesia. Bogor.
Sajogyo. 1977. Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa. Majalah Prisma No. 3
Maret 1977. Hal. 10-17.
Sumarto, Sudarno, Syaikhu Usman, and Sulton Mawardi (1997) Peran Sektor Pertanian dalam
Penanggulangan Kemiskinan: Mengikutsertakan Petani dalam Proses Penyusunan Kebijakan;
dalam Agriculture Sector Strategy Review. Jakarta: Ministry of Agriculture Republic of Indonesia

home | Error! No text of specified style in document. 21
PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI MELALUI OPTIMALISASI
LAHAN PEKARANGAN
DI KELURAHAN SASA, KOTA TERNATE
Agus Hadiarto1) dan Chris Sugihono1)
1)Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku Utara
Komplek Pertanian Kusu No. 1, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Kota Ternate sebagai Kota perdagangan dan merupakan salah satu daerah di Provinsi Maluku Utara
yang membutuhkan perhatian yang sangat serius untuk mengatasi ketergantungan pangan yang tinggi
seperti daging ayam, telur, sayuran, dan beras dari wilayah lain. konsidi cuaca yang buruk di lautan
mengakibatkan pasokan komoditas pangan terganggu dan berdampak pada kenaikan harga pangan
yang tinggi, sehingga dapat memicu gangguan stabilitas pangan di Kota Ternate. Model Kawasan
Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan salah satu program Kementerian Pertanian yang dapat
mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga.
Kegiatan pengembangan KRPL Kota Ternate berlangsung pada bulan Januari - Desember 2012.
Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Ruang
lingkup kegiatan meliputi: (1) Persiapan dengan melakukan survey dan koordinasi kegiatan dengan
instansi terkait; (2) Sosialisasi Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL); (3) Pembentukan
kelompok dan pemilihan komoditas secara partisipatif; (4) Pembangunan kebun bibit desa (KBD) dan
pembuatan media tanam di KBD; (5) Pembuatan media tanam untuk pekarangan RPL; (6) Pelatihan
teknis budidaya; (7) Penataan landscape pekarangan RPL berdasarkan strata; (8) Pendampingan
perawatan tanaman dan lahan pekarangan; (9) Musyawarah untuk mengatasi masalah dan menemukan
solusi bersama; (10) Pendampingan pemasaran hasil pertanian; (11) Replikasi model.
Pola pengembangan kegiatan terbagi menjadi tiga kelompok sasaran yaitu rumah tangga dengan luas
pekarangan kurang dari 120 m2, antara 120 sampai 400 m2, dan lebih dari 400 m2. Kegiatan KRPL
Ternate 2012 diikuti oleh 25 orang petani kooperator yang rumahnya saling berdekatan dalam satu
kawasan RT 003, Kelurahan Sasa. Hasil survey penentuan lokasi, RT 003 Kelurahan Sasa terpilih
sebagai tempat lokasi, karena masyarakatnya memiliki kemauan yang tinggi untuk mengembangkan
pola KRPL. Kebun bibit KRPL Kota Ternate seluas 3,5 x 7 m2 digunakan secara maksimal dengan
rumah naungan pembibitan seluas 3 x 4 m2. Tanaman yang diusahakan oleh RPL terdiri dari 12 jenis
komoditas tanaman sayuran, 3 komoditas tanaman pangan, 10 komoditas tanaman buah, dan 2
komoditas peternakan.
Tiga masalah utama yang membatasi kegiatan dan telah diatasi adalah (1) adanya kambing yang
berkeliaran di sekitar pekarangan; (2) Curah hujan terlalu banyak yang menyebabkan banyak penyakit;
dan (3) kesulitan mendapatkan tanah sebagai media tanam di polibag. Hama dan penyakit yang
umumnya menyerang adalah hama ulat penggorok daun, hama thrips dan tungau, hama ulat grayak,
penyakit bercak daun akibat jamur, dan penyakit akibat virus. KRPL Kota Ternate telah tereplikasi
secara luas di Kota Ternate yang didukung dengan Surat Keputusan Walikota Ternate No. 1 Tahun
2012 dan adanya kunjungan Menteri Pertanian RI.
Kata kunci: Optimalisasi lahan, KRPL, Kebun bibit, pekarangan
PENDAHULUAN
Kota Ternate merupakan salah satu daerah di Provinsi Maluku Utara yang membutuhkan
perhatian untuk mengatasi masalah pangan. Sebagai Kota perdagangan, saat ini Ternate masih sangat
tergantung dari daerah atau wilayah lainnya untuk ketersediaan daging ayam, telur, sayuran, dan beras.
Pasokan komoditas pangan tersebut diperoleh melalui jalur transportasi laut yang sangat dipengaruhi

oleh faktor cuaca dan musim. konsidi cuaca yang buruk di lautan mengakibatkan pasokan komoditas
pangan terganggu dan berdampak pada kenaikan harga pangan yang tinggi, bahkan ketersediaan suatu
komoditas dapat mencapai titik nol.
Menurut BPS Maluku Utara (2008), sektor pertanian di Kota Ternate hanyalah sektor pendukung
bagi struktur perekonomian Kota Ternate yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa yang
berkontribusi sebesar 32,06 % dan 19,75%, sedangkan sektor pertanian menempati posisi ke-4
sebesar 13,14%. Walaupun hanya sektor pertanian sebagai sektor pendukung, gangguan pada
ketersediaan komoditas pangan dapat mengakibatkan gangguan stabilitas ekonomi secara keseluruhan,
karena berkaitan dengan permasalahan pangan dan kehidupan masyarakat Kota Ternate.
Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan salah satu program Kementerian
Pertanian yang merupakan solusi untuk mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga.
Melalui pemanfaatan pekarangan yang ada disekitar rumah dengan komoditas pangan seperti sayuran,
buah-buahan, peternakan ayam, perikanan kolam, serta tanaman obat diharapkan mampu
meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
Budaya bertanam di pekarangan rumah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi
keluarga. Pemanfaatan pekarangan untuk bertanam sayuran maupun pangan lainnya juga menambah
estetika rumah. Selain itu, hasil panen di pekarangan rumah dapat mengurangi belanja rumah tangga,
bahkan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Jika pemanfaatan pekarangan dikelola secara
kelompok melalui kelembagaan yang ada, maka secara tidak langsung dalam jangka panjang produksi
pangan di pekarangan dapat memenuhi kebutuhan pangan di Kota Ternate (Agus Hadiarto dkk, 2012).
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku Utara pada Tahun 2011 melaksanakan
kegiatan M-KRPL di Kota Tidore Kepulauan. Tahun 2012 kegiatan M-KRPL dikembangkan menjadi
8 lokasi terdiri dari Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, Kab.
Halmahera Barat, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Selatan, dan
Kab. Morotai. Model KRPL di Kota Ternate secara khusus ditempatkan di Kelurahan Sasa, di
Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate yang secara teknis sumberdaya lahan masih relatif cukup
baik untuk dikembangkan kawasan rumah pangan lestari agar mendukung ketahanan pangan serta
peningkatan gizi dan pendapatan rumah tangga.
Konsep dan Pemahaman
Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL)
M-KRPL adalah sebuah model pengembangan himpunan rumah pangan lestari (RPL). RPL
merupakan rumah penduduk yang memanfaatkan lahan pekarangan secara intensif dengan prinsip
ramah lingkungan dan berkelanjutan. RPL dirancang untuk menjamin penyediaan bahan pangan
keluarga yang bergizi dan beragam serta untuk mengurangi pengeluaran belanja rumah tangga dan
sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
Untuk mencapai kesinambungan pemanfaatan pekarangan, kawasan tersebut dilengkapi dengan
Kebun Bibit Desa (KBD) untuk menyediakan bibit bagi RPL yang dikelola oleh masyarakat secara
partisipatif dengan dukungan kelembagaan KBD, unit pengolahan hasil, dan unit pemasaran.
Kawasan Rumah Pangan Lestari menganut prinsip-prinsip yaitu pemanfaatan lahan pekarangan
sesuai dengan kondisi lahan setiap rumah tangga, pemanfaatan potensi kawasan yang belum digarap,
namun secara teknis menguntungkan, mengintroduksikan teknologi baru untuk mengatasi beberapa
keterbatasan tertentu yang ada pada rumah tangga, selain diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
pangan dan gizi keluarga, pengembangan RPL tetap mempertimbangkan efisiensi. Sebab, jika efisiensi
diabaikan, dikhawatirkan faktor “lestari” akan sulit dicapai, atau secara laten merugikan rumah
tangga/masyarakat dalam kawasan, arahan pemanfaatan lahan pekarangan yang diberikan bersifat
dinamis, partisipatif dan berwawasan kawasan, disesuaikan dengan keinginan atau pandangan
anggota rumah tangga, serta dinamika sosial-ekonomi setempat, dan perlu dibarengi dengan
pembangunan/penguatan infrastruktur sosial (kelompok, forum, dan pemasaran hasil).
Tujuan pengembangan model KRPL adalah: (a) Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi
keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfataan pekarangan secara lestari; (b)
Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di
perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat

home | Error! No text of specified style in document. 23
keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah
tangga menjadi kompos; (c) Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan
pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan dan; (d)
Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan
keluarga dan menciptakan lingkungan hijau, bersih, dan sehat secara mandiri. Sementara sasaran yang
ingin dicapai model KRPL ini adalah peningkatan kemampuan keluarga dan masyarakat secara
ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari, menuju keluarga dan
masyarakat yang sejahtera (Kementerian Pertanian, 2011).
METODOLOGI
Kegiatan pengembangan kawasan RPL dilaksanakan selama Januari - Desember 2012. Lokasi
kegiatan dilaksanakan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada suatu kelurahan yang akan
ditetapkan setelah melakukan survey dan penetapan calon anggota RPL dan calon lokasi kegiatan.
Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini terbagi dalam 4 bagian besar yaitu benih, pupuk,
obat-obatan, dan bambu atau kayu. Benih yang digunakan ditentukan oleh calon anggota RPL secara
partisipatif. Pupuk yang digunakan terdiri dari urea, NPK, pupuk organik, zat pengatur tumbuh (ZPT),
dan pupuk cair. Obat-obatan yang digunakan ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan konsep
pengendalian hama terpadu (PHT). Bambu atau kayu digunakan untuk membuat vertikultur, kebun
bibit desa (KBD), dan pagar pekarangan.
Peralatan yang digunakan seperti parang, cangkul, handsprayer, minisprayer, gergaji, paku,
meteran, paranet atau kofo, meteran, GPS, kamera, cetok, ember, dan alat tulis kantor.
Ruang lingkup kegiatan meliputi: (1) Persiapan dengan melakukan survey dan koordinasi
kegiatan dengan instansi terkait; (2) Sosialisasi Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL);
(3) Pembentukan kelompok dan pemilihan komoditas secara partisipatif; (4) Pembangunan kebun bibit
desa (KBD) dan pembuatan media tanam di KBD; (5) Pembuatan media tanam untuk pekarangan
RPL; (6) Pelatihan teknis budidaya; (7) Penataan landscape pekarangan RPL berdasarkan strata; (8)
Pendampingan perawatan tanaman dan lahan pekarangan; (9) Musyawarah untuk mengatasi masalah
dan menemukan solusi bersama; (10) Pendampingan pemasaran hasil pertanian; (11) Replikasi model.
Persiapan Kegiatan
Persiapan kegiatan meliputi Survey lokasi, koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, dan
penentuan calon kawasan. Survey di Kota Ternate dilakukan di enam tempat, yaitu Kel. Jambula, Kel.
Sasa, Kel. Gambesi, Kel. Tobololo, Kel. Tarau, dan Kel. Salero. Seluruh tempat yang telah disurvey
menunjukkan rumah yang memiliki karakteristik pekarangan dengan strata rata-rata tidak lebih dari
120 m2. Penduduk di Kota Ternate tidak selalu memiliki pagar untuk membatasi pekarangan
rumahnya. Akan tetapi pekarangan rumah-rumah di Ternate terlihat bersih dan rapih.
Dari keenam lokasi yang disurvey, Kel. Sasa memiliki potensi lahan untuk dimanfaatkan
sebagai tempat kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Di Kel. Sasa, ada gabungan
kelompok tani (Gapoktan) Tumpang Sari yang memiliki anggota berjumlah 300 orang. Di antaranya
terdapat 61 orang petani yang bergabung mengelola usahatani sayuran (bayam, caisim, dan kangkung)
dalam satu hamparan lahan seluas 4 ha.
Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan pada empat institusi yaitu (1) Dinas Pertanian,
Perkebunan, dan Kehutanan Kota Ternate, (2) Tim Penggerak PKK Pokja III Kota Ternate yang
memiliki program yang sama menyangkut optimalisasi lahan pekarangan di tiap rumah, (3) Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) Kota Ternate sekaligus Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP) Ternate Selatan, Kota Ternate, (4) Pemerintah Kelurahan Sasa, Kota
Ternate. Seluruh instansi tersebut mendukung KRPL Kota Ternate dilaksanakan di Kelurahan Sasa,
Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate.
Berdasarkan hasil survey lokasi dan dukungan instansi terkait, Kelurahan Sasa, Kecamatan
Ternate Selatan, Kota Ternate ditetapkan sebagai Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kota
Ternate Tahun 2012 dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Kelurahan Sasa memiliki letak

yang mudah dijangkau dengan akses jalan dan sarana transportasi yang memadai; (2) Seluruh rumah
memiliki pekarangan dengan pendekatan berbasis perdesaan berdasarkan luas pekarangan; (3)
Antusiasme masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pekarangannya; (4) Lokasi yang dipilih berada
pada satu kawasan yang berada di RT 003, Kelurahan Sasa, Kota Ternate; (5) Sebagian besar
pekarangan sudah dibuatkan pagar yang dapat melindungi tanaman pekarangan dari gangguan
binatang ternak; (6) Masyarakat yang belum memiliki pagar pada lahan pekarangannya bersedia untuk
membuat pagar sendiri; (7) Adanya dukungan yang besar dari instansi terkait; dan (8) Adanya
dukungan kelembagaan, seperti gapoktan, toko saprodi milik gapoktan, pedagang pengumpul, dan
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
Karakteristik Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kota Ternate Tahun 2012 berada di
RT 003, Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Kelurahan Sasa dengan luas
wilayah 436,48 km2 berbatasan sebelah timur dengan Selat Ternate, sebelah barat dengan Gunung
Gamalama, sebelah Utara dengan Kelurahan Gambesi, dan sebelah Selatan dengan Kelurahan
Jambula.
Kelurahan Sasa didominasi oleh tanah jenis regosol dan tekstur tanah vulkanis dan ketinggian
sampai 700 m dpl. Kedalaman air tanah cukup dangkal antara 2 sampai 10 m. Curah hujan tergolong
tinggi sebanyak 1798 mm per tahun dan curah hujan yang tertinggi terjadi pada bulan Januari
sebanyak 263 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebanyak 77 mm.
Gambar 1. Grafik Curah Hujan Kelurahan Sasa Tahun 2011
Sumber : Monografi Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian Kel. Sasa, Ternate, 2012
Total Luas Lahan di Kelurahan Sasa yang digunakan adalah seluas 417,48 Ha. Sejumlah lahan
tersebut digunakan untuk pekarangan dan bangunan 60 Ha, ladang & tegalan 127,75 Ha, tanaman
hutan 20 Ha, perkebunan 155 ha, dan lain-lain 54,73 Ha.
Penduduk Kelurahan Sasa berjumlah 4187 jiwa yang terdiri dari 2031 jiwa laki-laki dan 2156
jiwa perempuan. Penduduk berusia 17-30 tahun mendominasi Kelurahan Sasa yang menandai di
wilayah ini terdapat banyak mahasiswa yang tinggal sementara untuk pendidikan, karena di kelurahan
ini terdapat 2 perguruan tinggi. Penduduk yang bekerja, sebagian besar memiliki mata pencaharian
sebagai pegawai pemerintah (PNS/TNI/Polri), berikutnya sebagai buruh bangunan, petani, dan
pengusaha.
Petani di Kelurahan Sasa tergabung dalam keanggotaan Gapoktan Tumpang Sari dengan ketua
Haidir Ola dan keanggotaan Gapoktan terbagi menjadi 4 kelompok tani, yaitu Kelompok tani Tanjung
Selatan I dengan komoditas perikanan, Tanjung Selatan II dengan komoditas hortikultura, Campang
Sari dengan komoditas hortikultura, dan Ake Sanoto dengan komoditas perkebunan.
Kelembagaan di Kelurahan Sasa cukup banyak, yaitu kios saprodi milik Gapoktan Tumpang
Sari, BRI unit desa, kelompok capir, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Ternate Selatan, UPP
263
100
182210 200
12177
113 98 82
237
115
0
50
100
150
200
250
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des
Cu
rah
hu
jan
(m
m)
Bulan

home | Error! No text of specified style in document. 25
Peternakan, Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan), dan 2 perguruan Tinggi swasta (Universitas
Muhammadiyah Maluku Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Ternate). Kios
saprodi milik Gapoktan selain berfungsi menyediakan kebutuhan saprodi juga berfungsi sebagai
lembaga keuangan, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi petani untuk membayar saprodi setelah
petani memanen hasil pertanian.
Sarana dan prasarana di Kelurahan Sasa dinilai cukup baik. Kondisi jalan aspal halus yang
menghubungkan Kelurahan Sasa dengan ibukota kecamatan bahkan pusat kota Ternate sangat baik.
Sarana komunikasi berupa telephone ataupun handphone sudah hampir dimiliki oleh seluruh
masyarakat, sehingga tidak ada batas masyarakat untuk komunikasi dengan pihak luar. Prasarana
untuk pemasaran juga sangat baik. Pasar untuk tempat menjual hasil pertanian masih mudah
dijangkau oleh penduduk, bahkan petani dapat dengan mudah menjual hasil pertaniannya pada
pedagang pengumpul (dibo-dibo) dengan harga yang wajar.
Sosialisasi M-KRPL
Sosialisasi kegiatan MKRPL diberikan kepada masyarakat khususnya calon anggota RPL
sebanyak 25 orang. Kegiatan ini juga dihadiri oleh PPL Pendamping kelurahan Sasa, Ketua Gapoktan
Tumpang Sari Kelurahan Sasa, dan Ketua RT 003 sebagai tuan rumah tempat pertemuan.
Usia rata-rata wanita tani adalah 45 tahun, terbanyak berusia 37 tahun, termuda berusia 26
tahun, dan tertua berusia 79 tahun. Tingkat pendidikan petani kooperator terbanyak adalah setingkat
SLTA sebanyak 10 orang, bahkan di antara wanita tani, ada 2 orang anggota KRPL Ternate yang
sudah wisuda sarjana S1. Akan tetapi, terjadi kesenjangan dengan wanita tani yang tidak sekolah
sebanyak 8 orang dan hanya berpendidikan SLTP sebanyak 5 orang. Beragamnya tingkat pendidikan
ini akan menjadi kendala pada saat penyuluhan, pemberian materi, dan pelatihan diberikan.
Pendidikan SLTA ke atas akan mudah memahami materi atau konsep yang diberikan, tetapi
pendidikan SLTA ke bawah akan mengalami kesulitan.
Pada acara sosialisasi kegiatan, peserta yang hadir diberikan pemahaman tentang konsep
Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Selain itu, peserta yang hadir juga diberikan contoh-contoh
lokasi KRPL yang telah berhasil di daerah lainnya dengan alat media presentasi yang menggunakan
layar LCD. Secara khusus calon anggota RPL diberikan pemahaman secara mendalam tentang
pentingnya pembangunan kebun bibit desa (KBD), model penanaman vertikultur dan dengan
menggunakan media tanam polibag, serta teknologi budidaya tanaman pekarangan.
Pembentukan Kelompok dan Pemilihan Komoditas
Bimbingan teknis dan pembinaan kelompok dilakukan untuk menjaga kelestarian kegiatan
pemanfaatan pekarangan yang telah berjalan. Bimbingan dan pembinaan dilakukan dengan
pendampingan, pembentukan kelompok, dan pemberian pelatihan teknis budidaya tanaman
pekarangan.
Pendampingan kegiatan dilakukan oleh peneliti BPTP Maluku Utara beserta dengan penyuluh
pertanian lapangan dan ketua Gapoktan Kelurahan Sasa dan Ketua RT 003. Pendampingan kegiatan
diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dalam hal pemanfaatan pekarangan, pengelolaan kebun
bibit desa, dan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dan pengurangan
pengeluaran rumah tangga.
Pembentukan organisasi kelembagaan Kawasan Rumah Pangan Lestari diperlukan untuk
memudahkan koordinasi antar anggota kelompok. Kelembagaan yang dibentuk adalah kelompok
wanita tani RT 003, Kelurahan Sasa dan pengurus kebun bibit desa. Petani kooperator KRPL RT 003,
Kel. Sasa dibagi menjadi 3 kelompok untuk memudahkan koordinasi dan pertemuan. Pembagian ini
didasarkan pada lokasi rumah masing-masing anggota yang berdekatan.
Organisasi yang telah terbentuk perlu diperkuat dengan pembinaan dan pendampingan agar
kelompok memiliki kemampuan untuk memutuskan keputusan secara mandiri, kemudian mentaati apa
yang telah menjadi keputusan. Selain itu, kelompok juga dapat membantu terciptanya suasana gotong
royong di antara masyarakat, memudahkan akses informasi yang bermanfaat, dan dapat bekerja sama
dengan organisasi lainnya.

Pemilihan komoditas dilakukan secara partisipatif. Petani kooperator diberikan keleluasan
untuk memilih sendiri komoditas yang akan ditanam. RPL Kelurahan Sasa menanam beragam
komoditas yang terdiri dari tanaman sayuran, tanaman pangan, tanaman buah-buahan, dan peternakan.
Tanaman sayuran adalah komoditas terbanyak yang diusahakan oleh RPL Kel. Sasa.
Tanaman sayuran yang diusahakan oleh RPL terdiri dari 12 jenis komoditas, yaitu tanaman terong,
tomat, cabai keriting, cabai rawit, buncis, pare, seledri, kangkung, bawang merah, ketimun, sawi, dan
sayur lilin. Tanaman pangan yang diusahakan oleh RPL terdiri dari 3 jenis komoditas, yaitu jagung,
ubi kayu, dan kacang panjang. Tanaman Buah-buahan yang diusahakan oleh RPL terdiri dari 10, yaitu
pisang, pepaya, jeruk manis, jambu air, jambu biji, mangga, lemon ikan, nangka, alpukat, dan kelapa.
Peternakan yang diusahakan oleh RPL terdiri dari 2 jenis komoditas, yaitu ternak ayam buras dan ikan
kolam.
Pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD)
Kebun bibit desa (KBD) merupakan jantung KRPL, menjadi tempat produksi benih dan bibit
untuk memenuhi kebutuhan pekarangan dalam membangun RPL dan kawasan. Benih/bibit hasil
produksi KBD juga dijual untuk masyarakat (Badan Litbang Pertanian, 2011). Kebun bibit dibangun
di lahan milik ketua RT 003 Kel. Sasa, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate yaitu Bapak Safrudin
(Udin). Pak Udin adalah sebagai salah satu pembina kegiatan KRPL Kota Ternate yang membina
langsung ibu-ibu anggota petani binaan KRPL Kota Ternate. Kebun pekarangan seluas 3,5 x 7 m2
digunakan secara maksimal untuk dibangun kebun bibit dengan rumah naungan seluas 3 x 4 m2.
Rumah naungan dilapisi dengan jaring-jaring kopo untuk melindungi tanaman bibit dari curah
hujan yang berlebihan, sinar matahari yang berlebihan, maupun serangan serangga. Rumah naungan
bibit terdapat bedengan persemaian di bawahnya dan rak untuk tempat koker (polibag kecil) di
atasnya. Pupuk kandang dan tanah dimasukkan ke dalam koker untuk media tanam bibit. Tanaman
yang disemai adalah tomat, cabai merah keriting, cabai rawit, dan terong. Bibit di kebun bibit
dipindahkan ke pekarangan RPL setelah satu bulan semai.
Ada juga benih yang langsung diberikan kepada petani binaan tanpa melalui kebun bibit.
Benih tersebut adalah benih kangkung, benih caisim, benih petsai, dan benih paria. Benih yang telah
disemai pada rumah naungan bibit akan dipindahkan ke dalam koker (pada rak di atasnya). Bibit di
kebun bibit dipindahkan ke pekarangan RPL setelah satu bulan semai.
Pelatihan Teknis dan Pendampingan
Pelatihan teknis budidaya dan pemasaran pendampingan ditujukan untuk pengurus KBD dan
petani kooperator RPL. Pelatihan yang diberikan meliputi (1) pembuatan media tanam berupa koker,
polibag, vertikultur, dan bedengan; (2) Persemaian dengan koker di KBD dan langsung tanam di
bedengan pekarangan RPL; (3) Penataan landscape pekarangan RPL; (4) perawatan tanaman masa
vegetatif dan generatif; (5) mengendalikan hama dan penyakit secara terpadu; (6) pendampingan
pemasaran; (7) musyawarah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada.
Media tanam berupa koker, polibag, vertikultur, ataupun bedengan terdiri dari campuran tanah
dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1 : 1. Koker adalah media tanam yang terbuat dari
plastik panjang transparan dengan diameter 5 cm. Setelah diisi dengan campuran tanah dan pupuk
kandang, koker dipotong-potong sepanjang 10 cm yang digunakan untuk media persemaian.
Setelah lewat masa persemaian, tanaman ditanam pada media polibag, vertikultur, bedengan
ataupun gabungan polibag dan vertikultur. Masyarakat diberikan contoh pembuatan vertikultur dan
cara untuk menggunakannya. Kaum lelaki dilibatkan untuk pembuatan vertikultur dan penataan
pekarangan. Vertikultur yang menggunakan bahan baku lokal (bambu) telah dibuat dengan
bermacam-macam model, seperti model segitiga, tegak, dan rak bersusun. Masyarakat lebih banyak
memilih membuat vertikultur model rak bersusun yang dinilai mudah untuk dibuat. Pada pekarangan
dengan luas di atas 120 m2 dapat menggunakan media tanam bedengan ataupun gabungan bedengan,
polibag, dan vertikultur.

home | Error! No text of specified style in document. 27
Penataan landscape pekarangan dibuat berdasarkan strata luas pekarangan. Pekarangan di
lokasi KRPL Kota Ternate 2012 menunjukan karakteristik perdesaan dengan basis komoditas
berdasarkan strata luas pekarangan yaitu strata sempit (<120 m2), strata sedang (120 – 400 m2) dan
strata luas (>400 m2) dengan ditunjukkan dengan tabel berikut.
Tabel 1. Basis Komoditas Berdasarkan Strata Pekarangan KRPL
Kota Ternate
No Kelompok sasaran Basis komoditas Model usaha
1 Pekarangan sempit
(< 120m2)
Sayuran : Cabai, Tomat, Terong,
bawang daun, pare, seledri, buncis
Pot polibag / Vertikultur
2 Pekarangan sedang
(120 – 400 m2)
Sayuran : Cabai, Tomat, Terong,
bawang daun, pare, seledri, buncis
Pot polibag / Vertikultur
Sayuran : kangkung, sawi, ketimun,
sayur lilin
Bedengan
Tanaman pangan : jagung, ubi kayu,
kacang panjang
Bedengan
Tanaman buah : pisang, jeruk manis,
jambu air, jambu biji, mangga, lemon
ikan, nangka, alpukat, kelapa
Multistrata
Ternak : ayam buras dan ikan air tawar Kandang/kolam
3 Pekarangan luas
(>400 m2)
Sayuran : Cabai, Tomat, Terong,
bawang daun, pare, seledri, buncis
Pot polibag / Vertikultur
Sayuran : kangkung, sawi, ketimun,
sayur lilin
Bedengan
Tanaman pangan : jagungn, ubi kayu,
kacang panjang
Bedengan
Tanaman buah : pisang, jeruk manis,
jambu air, jambu biji, mangga, lemon
ikan, nangka, alpukat, kelapa
Multistrata
Ternak : ayam buras dan ikan air tawar Kandang/kolam
Perawatan tanaman pada masa vegetatif berbeda dengan masa generatif. Perawatan tanaman
terutama dilakukan dengan penyiraman pada pagi dan sore hari. Pemupukan dengan kandungan
nitrogen lebih utama dilakukan pada masa masa vegetatif karena kandungan nitrogen dapat
meningkatkan daya tumbuh tanaman, sedangkan pemupukan dengan kandungan sulfat dan kalium
lebih utama dilakukan pada masa generatif untuk membantu pembentukan bunga dan buah.
Perawatan dilakukan juga dengan mengamati tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Secara
umum organisme pengganggu tanaman (OPT) yang menyerang tanaman pekarangan di Kelurahan
Sasa, Kota Ternate adalah lalat penggorok daun, karat daun, kutu daun, tungau, lalat buah, jamur, ulat
grayak, dan virus. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan
pengendalian non kimiawi. Pengendalian secara kimia dilakukan jika serangan hama dan penyakit
sudah melewati ambang batas.
Musyawarah, Pemasaran, dan Replikasi
Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan mengalami kendala dan permasalahan.
Permasalahan muncul setelah dilakukan musyawarah. Tiga masalah utama yang membatasi kegiatan
adalah (1) adanya kambing yang berkeliaran di sekitar pekarangan; (2) Curah hujan terlalu banyak
yang menyebabkan banyak penyakit; dan (3) kesulitan mendapatkan tanah sebagai media tanam di
polibag.

Ketiga masalah tersebut telah dapat dicarikan solusinya berupa (1) membuat pagar pekarangan
rumah untuk mengatasi kambing; (2) penyuluhan pengendalian penyakit terutama penyakit busuk
pada tanaman akibat jamur; (3) mendatangkan tanah dari daerah lain sebagai media tanam di polibag.
Pemasaran hasil pertanian tidak menjadi kendala dalam kegiatan RPL. Hasil panen di tiap
pekarangan RPL dikumpulkan oleh salah satu anggota RPL, kemudian dijual di Pasar Gamalama.
Hasil panen yang dikumpulkan tersebut menghemat ongkos kirim dari tiap anggota RPL, dengan
demikian keuntungan lebih besar didapatkan.
Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) Kelurahan Sasa, Kota Ternate telah
tereplikasi pada wilayah lainnya di Kota Ternate. M-KRPL RT 003 Kelurahan Sasa telah dapat
tereplikasi pada Kelurahan Sasa secara keseluruhan melalui Tim Penggerak PKK Kelurahan Sasa. M-
KRPL juga telah diterapkan pada kelurahan Soa melalui kegiatan utama kelurahan, sehingga sudah
terbentuk suatu kawasan pemanfaatan pekarangan rumah secara optimal yang menjadikan kawasan ini
hijau dan berbuah. M-KRPL juga tereplikasi pada Kelurahan Pasar Gamalama.
Secara umum M-KRPL Kota Ternate pada tahun 2012 telah tereplikasi dengan adanya
kunjungan kerja Menteri Pertanian pada tanggal 14 September 2012. Kunjungan Menteri Pertanian RI
ini di KRPL Kota Ternate merupakan bagian dari acara untuk menghadiri Sail Indonesia Morotai
2012. Pemerintah Kota Ternate juga mendukung repliklasi KRPL dengan adanya Surat Keputusan
Walikota Ternate No. 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan pemanfaatan secara optimal pekarangan
rumah. Secara tidak langsung seluruh kelurahan yang ada di Ternate akan melihat contoh nyata
kawasan rumah pangan lestari yang ada di Kelurahan Sasa.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kelurahan Sasa dengan kawasan rumah pekarangannya berhasil dan lestari dengan memenuhi
upaya (1) pengelolaan kebun bibit desa yang selalu menyediakan bibit bagi RPL, (2) Bimbingan
kelompok dan pendampingan dari BPTP Maluku Utara, penyuluh pertanian, dan tokoh masyarakat,
(3) Kelompok yang aktif untuk menyelesaikan masalah bersama dan selalu mencari solusi, (4)
Dukungan Pemerintah Kota Ternate baik secara fisik maupun finansial.
Tanaman yang diusahakan oleh RPL terdiri dari 12 jenis komoditas tanaman sayuran, 3
komoditas tanaman pangan, 10 komoditas tanaman buah, dan 2 komoditas peternakan. Tanaman
pekarangan di Kelurahan Sasa secara umum terserang hama ulat penggorok daun, hama thrips dan
tungau, hama ulat grayak, penyakit bercak daun akibat jamur, dan penyakit akibat virus.
KRPL Kota Ternate telah tereplikasi secara luas di Kota Ternate yang didukung dengan Surat
Keputusan Walikota Ternate No. 1 Tahun 2012 tentang optimalisasi lahan pekarangan dan juga
didukung dengan keberhasilan KRPL Kota Ternate di Kelurahan Sasa serta kunjungan Menteri
Pertanian RI pada tanggal 14 September 2012.
BPTP Maluku Utara bersama-sama dengan penyuluh pertanian dan tokoh masyarakat
sebaiknya senantiasa memberikan pembinaan kelompok dan pendampingan KRPL Kota Ternate
Kelurahan Sasa terutama membimbing masyarakat untuk selalu mengelola dengan baik kebun bibit
desa. Dukungan Pemerintah Kota Ternate sebaiknya lebih nyata dalam hal penganggaran lokasi
KRPL agar dapat membantu secara fisik maupun finansial.
DAFTAR PUSTAKA
Anonimous. 2002. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
Astuti, Pudji Umi. 2011. Laporan Akhir Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) di
Provinsi Bengkulu.
http://bengkulu.litbang.deptan.go.id/ind/images/dokumen/LAPKHIR2011/mkrpl.pdf.
Diakses tanggal 3 Desember 2012.
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. 2011. Model Kawasan Rumah
Pangan Lestari dan Pengembangannya ke seluruh Provinsi di Indonesia. Warta Penelitian
dan Pengembangan Pertanian. Vol. 33 No. 6, 2011.

home | Error! No text of specified style in document. 29
http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/wr336111.pdf. Diakses tanggal 3 Desember
2012.
BPS. Maluku Utara Dalam Angka 2009. Badan Pusat Statistik. Ternate.
Badan Litbang Pertanian. 2012. Penggembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.
BPTP NTB. Petunjuk Teknis Kawasan Rumah Pangan Lestari di Nusa Tenggara Barat.
http://ntb.litbang.deptan.go.id/ind/pu/krpl/juknis.pdf. Diakses tanggal 3 Desember 2012.
BPTP Bengkulu. Laporan Spektrum Diseminasi Multi Channel (SDMC) Model Kawasan Rumah
Pangan Lestari (MKRPL) BPTP Bengkulu.
http://bengkulu.litbang.deptan.go.id/ind/images/dokumen/SDMC/MKRPL-1.pdf. Diakses
tanggal 3 Desember 2012.
BPTP Jatim. Serba-Serbi Kawasan Rumah Pangan Lestari di Jawa Timur.
http://www.litbang.deptan.go.id/KRPL/MKRPL-BPTP-Jatim.pdf. Diakses tanggal 3
Desember 2012.
Darwin, Muhammad dan R. Teguh Wijanarko. 2012. Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui
Pengembangan Model – Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) di Kelurahan
Wandoka, Wakatobi. Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sulawesi Tenggara Volume 8, Tahun 2012.
Hadiarto, Agus, Chris Sugihono, Wawan Sulistriyono, Hermawati, La Salihi. 2012. Laporan Akhir
Tahun 2012: Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) di Kota
Ternate. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara.
Hendoko, Roy, Liwang, Salafudin, Praptiningsih, G.A., L.O. Nelwan, Yosephianus Sakri, dan Satriyo
K. Wahono. Sinergi Bio-Metana Berbahan Baku Limbah Jatropha Curcas L. Dan Pangan
Dalam Penerapan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari
http://xa.yimg.com/kq/groups/23465704/1916771723/name/makalahIPB.Roy.Rev280412.pd
f. Diakses tanggal 3 Desember 2012.
Kementerian Pertanian RI. 2011. Pedoman Umum Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jakarta.
Muchtar. 2011. Pengembangan Inovasi Teknologi Pengelolaan Lahan Kering Masam Untuk
Meningkatkan Produktivitas > 20% Dan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Laporan
Akhir. Balai Penelitian Tanah. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian.
http://balittanah.litbang.deptan.go.id/dokumentasi/lapakhir2011/Isi Laporan Akhir 2011
muhtar.pdf. Diakses tanggal 3 Desember 2012.
Rauf, AW. dan Lestari, MS. 2009. Pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai sumber pangan
alternatif di Papua. Jurnal Litbang Pertanian 28(2): 54-62
Saptana, Saktyanu, KD. Wahyuni, S. Ariningsih, E. Darwis, V. 2004. Integrasi kelembagaan forum
KASS dan program agropolitan dalam rangka pengembangan agribisnis sayuran sumatera.
Analisis Kebijakan Pertanian 2(3): 257-276
Sayaka, B. et al. 2005. Analisis pengembangan agroindustri berbasis pangan lokal dalam
meningkatkan keanekaragaman pangan dan pengembangan ekonomi pedesaan. Laporan
Akhir. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
Saliem, Handewi Purwati. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebagai Solusi Pemantapan
Ketahanan Pangan.
http://www.opi.lipi.go.id/data/1228964432/data/13086710321319802404.makalah.pdf.
Diakses tanggal 3 Desember 2012
Sugiman, Sri Bananiek dan M. Taufik Ratule. 2012. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL) Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan Rumah Tangga. Buletin Teknologi dan
Informasi Pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara Volume 8,
Tahun 2012.

Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang
30
KLASIFIKASI TANAH BERDASARKAN
SISTEM TAKSONOMI TANAH DI DESA TARO,
KECAMATAN TEGALLALANG, GIANYAR
Himawan Bayu Aji
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku Utara,
Komplek Pertanian Kusu No. 1 Oba utara, Kota Tidore Kepulauan
E-mail : [email protected]
ABSTRAK
Penelitian di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten
Gianyar ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi tanah-tanah di Desa Taro
berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah hingga kategori famili tanah dan
memetakan tanah berdasarkan hasil klasifikasi. Penelitian ini menggunakan
dua metode, yaitu survai tanah di lapang dan analisis tanah di laboratorium.
Klasifikasi tanah dikerjakan sampai kategori famili tanah, kemudian
dilanjutkan dengan pembuatan peta tanah dengan skala 1 : 25.000. Hasil
pengklasifikasian tanah menunjukkan bahwa tanah-tanah di Desa Taro
diklasifikasikan ke dalam ordo Inceptisols, sub ordo Udepts dan Aquepts,
greatgroup Dystrudepts, Epiaquepts dan Eutrudepts, subgroup Ruptic-Alfic
Dystrudepts, Aeric Epiaquepts, Humic Eutrudepts dan Typic Eutrudepts.
Untuk kategori famili tanah terdapat empat famili tanah yaitu : (1) Ruptic-
Alfic Dystrudepts, berlempung kasar, campuran, isotermik; (2) Aeric
Epiaquepts, berlempung kasar, campuran, isotermik; (3) Humic Eutrudepts,
berlempung kasar, campuran, isotermik; (4) Typic Eutrudepts, berlempung
kasar, campuran, isotermik. Tanah-tanah yang diwakili oleh profil P1, P2, P3,
dan P4 sesuai sebagai lahan pertanian. Namun demikian masih memerlukan
penanganan intensif terhadap adanya faktor-faktor pembatas.
Kata kunci : Klasifikasi tanah, Sistem Taksonomi Tanah, peta tanah, lahan
pertanian
PENDAHULUAN
Peningkatan pembangunan disegala bidang khususnya bidang
pertanian, membutuhkan pemikiran, perencanaan dan pelaksanaan yang
matang, sehingga akan diperoleh hasil seperti harapan. Tanah merupakan
satu dari beberapa sumberdaya alam yang mempunyai peranan sangat vital

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara
31
bagi kehidupan manusia, karena hampir seluruh kegiatan kehidupan
ditunjang oleh keberadaannya.
Tanah adalah bahan mineral yang terkonsolidasi pada permukaan
bumi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang meliputi bahan
induk, iklim, mikroorganisme, dan topografi. Faktor-faktor tersebut bekerja
selama suatu periode waktu dan menghasilkan tanah (Foth, 1994). Tanah
yang telah berkembang dengan berbagai proses mempunyai sifat yang
berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut meliputi
sifat-sifat profil tanah seperti jenis dan susunan horison, kedalaman solum
tanah, kandungan bahan organik, kandungan liat, kandungan air, dan
sebagainya.
Keragaman sifat yang memperumit dalam menggolongkan jenis-
jenis tanah menjadi dasar terkuat untuk mengklasifikasikan tanah lengkap
dengan peta penyebaran tanahnya. Ini diperlukan agar lebih mempermudah
dalam penggunaan dan penanganannya. Untuk memecahkan masalah
tersebut masing-masing jenis tanah perlu diberi nama sesuai dengan
karakteristik yang dimiliki.
BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat
Penelitian dimulai dari bulan November 2003 sampai dengan bulan
Maret 2004, terhitung dari pengumpulan literatur sampai selesai analisis
tanah di laboratorium. Penelitian dilaksanakan di Desa Taro, Kecamatan
Tegallalang, Kabupaten Gianyar.
Bahan dan Alat
Bahan-bahan yang akan diperlukan dalam penelitian ini adalah :
1. Contoh tanah yang diambil dari masing-masing lapisan pada profil
pewakil.
2. Berbagai bahan kimia yang diperlukan untuk keperluan analisis di
lapangan yaitu ; H2O2 untuk menguji ada tidaknya bahan organik,
NAF untuk menguji ada tidaknya bahan alofan atau sifat andik
terutama di daerah vulkanik, HCl untuk menguji ada tidaknya sifat
kalkarius dan α,α-dipyridyl untuk menguji sifat aquik. Sedangkan
untuk uji di laboratorium ialah K2Cr2O7 sebagai pengekstrak tanah
untuk mengetahui kadar C-organik, NH4OAc 1N sebagai
pengekstrak tanah untuk mengetahui nilai Kapasitas Tukar Kation
dan Kejenuhan basa serta zat-zat kimia lainnya.
3. Bahan-bahan survai lainnya untuk pencatatan data tanah dan
informasi lainnya.

Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang
32
Alat-alat yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :
1. Peta Rupa Bumi Pulau Bali skala 1 : 25.000.
2. Peta Geologi Pulau Bali skala 1 : 250.000 (Hadiwidjojo, 1971).
3. Untuk pekerjaan lapang diperlukan cangkul, meteran, abney level,
pisau lapang, kantong plastik, pH teskit, bor tanah, altimeter,
kompas, sekop, buku Munsell Soil Colour Chart, kamera, spidol
permanen dan daftar isian.
4. Untuk analisis tanah di laboratorium diperlukan alat-alat yaitu
ayakan 0.51 mm, 0.5 mm dan 2 mm, tabung reaksi, gelas ukur,
pipet, kompor listrik, pH meter, Erlenmeyer, pengocok elektris,
timbangan dan lain-lain.
Metode Penelitian
Penelitian dilaksanakan dengan metode survai tanah di lapangan dan
ditunjang dengan analisis tanah di laboratorium.
Analisis Laboratorium
Tahapan dalam analisis laboratorium meliputi sifat fisik, kimia dan
morfologi tanah.
Analisis sifat fisik tanah :
1. Tekstur tanah dengan metode pipet (Soil Conservation Service,
1972).
2. Berat per volume/bulk density tanah dengan metode gravimetrik
(Soil Conservation Service, 1972).
3. Permeabilitas tanah dengan metode De Boodt, berdasarkan hukum
Darcy.
Analisis sifat kimia tanah :
1. Karbon organik dengan ekstrak K2Cr2O7 (Walkley dan Black, 1934
dalam Soil Conservation Service, 1972).
2. Reaksi tanah (pH) = pH dengan H2O (1 : 2,5) dan pH NaF 1N pH 7
(1 : 50) (Soil Conservation Service, 1972).
3. Kapasitas Tukar Kation (KTK) dengan pengekstrak NH4OAc 1N pH
7 (Peech et al, 1974 dalam Soil Conservation Service, 1972).
4. Kejenuhan basa (KB) dengan ekstrak NH4OAc 1N pH7 (Soil
Conservation Service, 1972).
Analisis mineralogi fraksi pasir dan liat
1. Mineral pasir ditetapkan dengan menggunakan metode sebaran
hitung yang dibantu dengan menggunakan mikroskop binokuler.
2. Analisis mineral liat ditetapkan dengan menggunakan gejala
pengeringan dan reaksi warna.

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara
33
Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah
Interpretasi data dilakukan berdasarkan data hasil dari pengamatan
yang telah diperoleh baik hasil pengamatan di lapangan maupun hasil
analisis tanah di laboratorium. Setelah data diinterpretasi selanjutnya tanah
di lokasi penelitian diklasifikasikan menurut Sistem Taksonomi Tanah
dengan menggunakan Kunci Taksonomi Tanah 1998 (Soil Survey Staff,
1998). Klasifikasi tanah dilakukan dari kategori tinggi sampai kategori
rendah yaitu dari ordo, subordo, greatgroup, subgroup, dan famili.
Pembuatan Peta Tanah
Hasil klasifikasi tanah di daerah penelitian akan dituangkan ke
dalam bentuk peta jenis tanah dengan skala semi-detail yaitu 1 : 25.000.
Sehingga diharapkan dengan pembuatan peta ini akan memudahkan dalam
penggunaan tanahnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Daerah Penelitian
Secara geografis, lokasi penelitian terletak antara 080 20’ 16” sampai
dengan 080 22’ 30” LS dan antara 1150 16’ 26” sampai dengan 1150 18’ 25”
BT. Lokasi penelitian memiliki luas wilayah 565.3 ha. Secara administratif
daerah penelitian termasuk ke dalam wilayah Desa Taro, Kecamatan
Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Desa Taro berturut-turut dibatasi oleh;
sebelah utara Desa Abuan, selatan Desa Brasela, barat Desa Puhu dan
sebelah timur Desa Sebatu. Peta lokasi penelitian disajikan pada gambar 2.
Berdasarkan peta geologi Pulau Bali (Hadiwidjojo, 1971), bahan
induk di lokasi penelitian tersusun atas tufa vulkan intermedier. Lokasi
penelitian memiliki kemiringan lereng dalam kisaran antara 2% sampai
dengan 65% dengan bentuk wilayah landai sampai dengan bergunung.
Sedangkan ketinggian tempat berkisar antara 700 sampai dengan 1300 meter
di atas permukaan laut.
Sesuai dengan data Balai Meteorologi dan Geofisika Wilayah III
Denpasar dari tahun 1993 sampai dengan 2002, menunjukkan bahwa curah
hujan dan hari hujan rata-rata pertahun di lokasi penelitian adalah 2347.35
mm/tahun dan 135 hari. Berdasarkan tipe iklim di lokasi penelitian termasuk
ke dalam tipe A (daerah sangat basah) dengan vegetasi hutan hujan tropis.
Penyebanya adalah karena terdapat delapan bulan basah (> 100 mm/bulan)
dan tanpa bulan kering (< 60 mm/bulan). Rejim kelembaban tanah yang
diwakili oleh profil P1, P3, dan P4 termasuk udik karena rejim kelembaban
tanah tidak kering selama 90 hari kumulatif dalam tahun-tahun normal.
Sedangkan untuk tanah-tanah yang diwakili oleh profil P2 mempunyai rejim
kelembaban tanah akuik karena tanah selalu jenuh air.

Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang
34
Tabel 1. Kiteria iklim menurut Schmidth-Ferguson Kriteria Nilai Q (%) Tipe Iklim Vegetasi Keterangan
0 ≤ Q < 14.3 A Hutan hujan tropis Sangat basah
14.3 ≤ Q < 33.3 B Hutan hujan tropis Basah
33.3 ≤ Q < 60 D Hutan rimba Agak basah
60 ≤ Q < 100 E Hutan musiman Sedang
100 ≤ Q < 167 F Hutan sabana Agak kering
167 ≤ Q < 300 G Hutan sabana Kering
300 ≤ Q < 700 H Padang ilalang Sangat kering
Q ≥ 700 I Padang ilalang Ekstrim kering
Temperatur tanah tahunan rata-rata adalah 21.070C dan selisih antara
suhu tanah musim panas rata-rata dan musim dingin rata-rata adalah kurang
dari 60C, sehingga rejim temperatur tanah digolongkan ke dalam isotermik.
Tabel 2. Data rata-rata curah hujan (mm), hari hujan (hari), suhu
udara (0C) dan suhu tanah (0C) Bulan Curah Hujan
(mm)
Hari Hujan
(hari)
Suhu Udara
(0C)
Suhu Tanah
(0C)
Januari 402.5 17.3 19.02 21.52
Februari 327.6 16.7 19.06 21.56
Maret 219.4 14.1 18.82 21.32
April 146.2 11.2 18.89 21.39
Mei 80.85 6.5 18.33 20.83
Juni 116.2 9.1 18.09 20.59
Juli 81.7 8.6 19.43 19.93
Agustus 81.6 6.1 19.34 19.84
Septembr 90.0 4.5 18.85 21.35
Oktober 252.6 10.4 18.68 21.18
November 275.2 15.1 19.21 21.71
Desember 273.5 15.2 19.23 21.73
Jumlah 2347.35 134.8 222.95 252.95
Rata-rata 195.61 11.23 18.57 21.07
Keterangan :
1. Data rata-rata curah hujan, hari hujan dan suhu udara didapatkan dari catatan
pengamatan Balai Meteorologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar, selama 10 tahun
(1993-2002). Tinggi tempat 350 m dpl
2. Suhu udara diperoleh berdasarkan pencatatan suhu di Balai Meteorologi dan Geofisika
Wilayah III Denpasar, selama 10 tahun (1993-2002)
t = (26.3-0.6 h)
t = suhu udara rata-rata tahunan (0C)
h = ketinggian tempat dari permukaan laut (hm)
3. Suhu tanah didapat dari suhu rata-rata tahunan + 2.50C (Hardjowigeno, 1985)

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara
35
Morfologi, Sifat Fisik dan Kimia Tanah
Hasil pengamatan morfologi, analisis sifat fisik dan kimia tanah
disajikan pada Tabel 3, 4, dan 5. Ketebalan kedua horizon teratas pada
keempat profil rata-rata berkisar antara 20-40 cm (Tabel 3). Ditemukannya
horizon B setelah horizon C pada profil P1, karena adanya endapan akibat
letusan gunung berapi. Meskipun demikian kasus ini bukan merupakan
diskontinuitas litologi karena tidak adanya perubahan yang nyata dalam
besar butir atau dalam susunan mineralogi dan atau perbedaan umur yang
mencerminkan perbedaan litologi dalam suatu tanah.
Pada Tabel 3 ditunjukkan bahwa warna matrik tanah rata-rata cukup
gelap disemua profil, hanya beberapa horizon yang tampak agak terang
khususnya pada profil P1 dan P4. Warna tanah yang gelap sering
menunjukkan penumpukan bahan organik. Sesuai data kandungan bahan
organik pada lapisan teratas tiap profil hampir sama, semuanya mempunyai
kisaran nilai antara 3.524 sampai dengan 5.545% (Tabel 5).
Tabel 3. Data Morfologi Tanah
Pro fil
Hori son
Dalam (cm)
Batas
Hori
son
Warna Matriks Kelas Tekstur
Struk tur
Kon
Sis
tensi
Peraka ran
Frag
men
Batuan Lembab Kering
P1
Ap 0-20/27 c,w 7.5 YR 3/4 10 YR 5/3 SCL sb,m,m ss/sp m c x -
Bw1 20/27-47 c,s 7.5 YR 4/6 10 YR 5/4 SiL sb,m,m ss/sp m c x -
Bw2 47-80 c,s 7.5 YR 5/6 10 YR 6/4 SiCL sb,m,m ss/sp c x x -
C1 80-107 c,s 7.5 YR 3/2 10 YR 5/3 SCL cr,c,w ss/sp x x x -
C2 107-128 c,s 7.5 YR 3/4 10 YR 6/4 SC cr,c,w ss/sp x x x -
Bw3 128-133 c,s 7.5 YR 5/6 10 YR 6/6 SiCL sb,m,m ss/sp x x x -
C3 133-200 - 7.5 YR 5/8 10 YR 7/6 SCL cr,c,w ss/sp x x x -
P2
Ap 0-34 c,s 10 YR 3/4 10 YR 5/4 SiL ab,c,h ss/sp m c x -
Bw1 34-59/62 g,w 10 R 4/8 2.5 YR 5/8 L sb,m,m ss/sp c c x -
Bw2 59/62-87 c,s 10 YR 3/4 10 YR 6/3 L sb,m,m ss/sp f x x -
Bw3 87-120 c,s 10 YR 2/1 10 YR 5/2 SL sb,c,m ss/sp f x x -
C 120-200 - 10 YR 4/6 10 YR 5/3 SL cr,c,w ss/sp x x x -
P3
Ap 0-37/42 g,w 10 YR 3/1 10 YR 5/3 SiL sb,m,m so/op m x x -
Bw1 37/42-50 c,s 10 YR 2/1 10 YR 4/2 SL cr,m,m so/op c x x -
Bw2 50-85/94 g,w 10 YR 3/3 10 YR 5/4 SL sb,m,m ss/sp f x x -
Bw3 85/94-123 c,s 10 YR 3/4 10 YR 6/6 SL g,m,m ss/sp f f x -
C 123-200 - 10 YR 5/4 10 YR 7/6 SL cr,c,w ss/sp x f x -
P4
A 0-39/48 g,i 10 YR 3/4 10 YR 6/4 SiL sb,m,m ss/sp c c x -
Bw1 39/48-71 c,s 10 YR 4/6 10 YR 7/4 SL g,m,m s/sp f f x 5
Bw2 71-87 c,s 10 YR 4/4 10 YR 6/3 SL cr,m,m ss/sp f f x 2
Bw3 87-123/130 g,w 10 YR 5/8 10 YR 8/4 SL sb,m,m s/sp f f x 2
C 123/130-
200
- 10 YR 6/8 10 YR 8/3 SL cr,c,w ss/sp x x x 1
Khusus Profil P2 Horison Bw1 warna matrik karatan lembab 10 R 4/8, kering 2,5 YR 5/8, jumlah karatan
10%, reaksi warna dengan α,α dipyridil merah

Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang
36
Keterangan :
Batas Horison : cs = jelas dan rata, gw = berangsur dan berombak, cw = jelas dan berombak, gi =
berangsur dan tidak teratur; Tekstur : S = pasir, SL = lempung berpasir, SiL = lempung berdebu, L = lempung, SCL = lempung liat berpasir, SC = liat berpasir, SiCL = lempung liat berdebu, SiL = lempung
berdebu; Struktur : ab = gumpal menyudut, sb = gumpal membulat, g = berbutir, cr = remah; Ukuran
Struktur : m = sedang, c = kasar; Tingkat Perkembangan Struktur : w = lemah, m = cukup, h = kuat; Konsistensi : so = tidak lekat, ss = agak lekat, s = lekat; Konsistensi Plastisitas : op = tidak plastis, sp =
agak plastis; Ukuran Perakaran : f = halus, m = sedang, c = kasar; Jumlah Perakaran : x = tidak ada, c
= cukup, f = sedikit, m = banyak.
Data warna tanah dan bahan organik pada profil P3 menunjukkan
bahwa tanah di lokasi penelitian memenuhi syarat untuk dimasukkan ke
dalam epipedon molik. Pada profil P1, P2, dan P4 memenuhi kriteria epipedon
okrik apabila ditinjau dari sisi warna kroma. Karatan di temukan tetapi
hanya pada profil P2 horison Bw1, yaitu pada tanah persawahan di mana
sering terjadi reaksi redoks. Warna karatan dalam keadaan lembab adalah
coklat kemerahan (10 R 4/8).
Tekstur tanah pada profil P3 dan P4 hampir semua didominasi oleh
lempung berpasir, sedangkan untuk profil P1 dan P2 cukup bervariasi (Tabel
4). Data tekstur ini menunjukkan bahwa lokasi penelitian didominasi tanah-
tanah bertekstur kasar. Keadaan ini merupakan salah satu penyebab nilai
bulk density atau berat per satuan volume tanah kering oven yang dinyatakan
dalam g/cm3 di masing-masing profil tergolong rendah dengan kisaran antara
0,635-1,115.
Tanah bertekstur kasar mempunyai kemampuan menahan air dan
hara rendah, airase baik dan tingkat permeabilitas yang cepat sedangkan
permeabilitas berkaitan dengan pori total, distribusi ukuran dan kemampuan
pori. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi prosentase pasir di dalam
tanah akan semakin banyak ruang pori makro di dalam tanah yang akan
memperlancar pergerakan air dan udara, khususnya pergerakan dari atas ke
bawah (Hakim dkk, 1986). Pergerakan inilah yang menyebabkan liat, bahan
organik dan bahan-bahan halus lainnya bergerak ke lapisan di bawahnya.
Hasil pengamatan terhadap struktur tanah di lokasi penelitian (Tabel
3), menunjukkan bahwa struktur gumpal membulat mendominasi hampir di
setiap profil. Beberapa struktur juga terbentuk pada beberapa horizon di
beberapa profil, seperti struktur berbutir dan remah pada profil P1, P3, dan P4.
Sedangkan struktur gumpal menyudut terdapat pada profil P2. Selain itu
tanah mempunyai ukuran struktur dengan kisaran sedang sampai dengan
kasar dan tingkat perkembangan tanah lemah sampai dengan kuat.
Tabel 4. Data Analisis Sifat Fisik Tanah
Pro fil
Dalam (cm)
Hori
son
Tekstur Kelas
Tekstur Bulk
Density
Permeabi
litas
(cm/jam)
Kelas
Permeabi
litas Lain (%) Debu (%) Pasir (%)
P1 0-20/27 Ap 11.28 27.583 61.133 SCL 0.869 93.199 SC
20/27-47 Bw1 6.285 42.735 50.980 SiL 0.908 5.511 S

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara
37
47-80 Bw2 6.483 44.087 49.429 SiCL 0.908 5.511 S
80-107 C1 3.601 36.006 60.394 SCL 0.980 6.648 AC
107-128 C2 6.297 30.227 63.476 SC 0.980 6.648 AC
128-133 Bw3 12.315 35.577 52.107 SiCL 0.843 11.401 AC
133-200 C3 1.285 38.560 60.154 SCL 0.810 311.151 SC
P2
0-34 Ap 4.697 56.370 38.933 SiL 1.115 1.383 AL
34-59/62 Bw1 12.458 47.065 40.476 L 0.799 11.932 AC
59/62-87 Bw2 10.992 48.852 40.156 L 0.841 87.499 SC
87-120 Bw3 9.304 34.556 56.140 SL 0.717 62.442 SC
120-200 C 3.695 46.798 49.507 SL 0.702 155.111 SC
P3
0-37/42 Ap 6.857 13.714 79.430 SiL 0.913 213.577 SC
37/42-50 Bw1 8.294 33.175 58.531 SL 0.834 79.544 SC
50-85/94 Bw2 6.731 29.618 63.651 SL 0.803 6.602 AC
85/94-123 Bw3 1.505 24.082 74.413 SL 0.635 30.094 SC
123-200 C 9.854 28.153 61.993 SL 0.810 95.453 SC
P4
0-39/48 A 12.032 29.412 58.556 SiL 0.836 295.507 SC
39/48-71 Bw1 9.755 30.658 59.588 SL 0.793 206.815 SC
71-87 Bw2 6.937 30.522 62.542 SL 0.894 83.522 SC
87-123/130 Bw3 15.502 28185 56.313 SL 0.804 46.533 SC
123/130-
200
C 4.512 33.970 61.518 SL 0.873 26.515 SC
Keterangan :
1. Analisis sifat fisik tanah dilakukan di laboratorium Ilmu Tanah Jurusan Ilmu Tanah Fakultas
Petanian Universitas Udayana. 2. Kelas tekstur tanah : Tekstur : S = pasir, SL = lempung berpasir, SiL = lempung berdebu, L
= lempung, SCL = lempung liat berpasir, SC = liat berpasir, SiCL = lempung liat berdebu, SiL
= lempung berdebu; Kelas Permeabilitas : SC = sangat cepat, AC = Agak cepat, S = sedang, AL = agak lambat
Konsistensi tanah ditunjukkan oleh derajat kohesi dan adhesi yang di
tentukan dalam keadaan basah. Pada profil P1 dan P2 semua horizon
mempunyai tingkat konsistensi agak lekat dan agak plastis. Sedangkan pada
profil P3, konsistensi tidak lekat dan tidak plastis menempati dua horizon
teratas. Untuk profil P4, konsistensi lekat dan agak plastis terdapat pada
horison Bw1 dan Bw3 serta sisanya mempunyai konsistensi agak lekat dan
agak plastis.
Pada tabel 5 rendahnya nilai pH tanah di masing-masing profil
berhubungan dengan jumlah dan jenis mineral liat, bahan organik serta
tingginya curah hujan di lokasi penelitian. Jumlah mineral liat yang banyak
ditemukan di lokasi penelitian adalah haloisit di mana haloisit mempunyia
kandungan Al+ dan H+. Sedangkan bahan organik merupakan penyumbang
ion H+ yang bersifat masam. Tingginya curah hujan juga menyebabkan
adanya pencucian basa-basa, sehingga yang tertinggal adalah ion-ion
bermuatan positif seperti Al3+ dan H+ sehingga tanah cenderung masam.
Pada kondisi masam larutan tanah lebih banyak mengandung ion hydrogen
(H+) daripada ion hidroksil (OH-) (Foth, 1994).

Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang
38
Hasil analisis pH tanah dalam larutan H2O disemua profil
menunjukkan nilai yang lebih besar daripada pH tanah dalam larutan KCl.
Perbedaan nilai antara kedua pH tanah di dalam larutan H2O dan KCl atau
biasa disebut ΔpH menunjukkan nilai positif dari seluruh horison pada setiap
profil. Nilai ΔpH positif mengidikasikan bahwa tanah di lokasi penelitian
masih didominasi oleh bahan amorf.
Tabel 5. Data Analisis Sifat Kimia Tanah
Pro
fil Dalam (cm)
Hori
son
C.
Organik
(%)
B.
Organik
KTK
(me/100
g tanah)
pH Tanah pH NaF
H2O KCl 2 mnt 4 mnt
P1
0-20/27 Ap 2.044/S 3.524/S 11.333/R 5.61/AM 5.08 10.45 10.56
20/27-47 Bw1 1.725/R 2.973/R 13.953/R 5.67/AM 5.05 10.41 10.60
47-80 Bw2 1.197/R 2.063/R 14.754/R 5.50/M 5.01 10.28 10.43
80-107 C1 0.842/SR 1.451/SR 14.946/R 5.41/M 4.87 9.89 10.50
107-128 C2 0.851/SR 1.467/SR 14.208/R 5.69/AM 4.93 9.64 9.78
128-133 Bw3 0.895/SR 1.543/SR 21.150/S 5.83/AM 4.93 9.64 9.48
133-200 C3 0.437/SR 0.753/SR 13.034/R 5.51/M 4.99 9.23 9.36
P2
0-34 Ap 2.893/S 4.987/S 15.842/R 5.23/M 4.92 9.91 10.09
34-59/62 Bw1 2.129/S 3.670/S 21.639/S 5.27/M 5,01 10.08 10.23
59/62-87 Bw2 0.834/SR 1.438/SR 18.629/S 5.42/M 5.15 10.05 10.25
87-120 Bw3 0.139/SR 0.239/SR 19.612/S 5.49/M 5.43 10.17 10.39
120-200 C 0.143/SR 0.246/SR 21.436/S 5.63/AM 5.53 10.22 10.42
P3
0-37/42 Ap 3.216/T 5.545/T 16.114/R 5.39/M 5.32 10.12 10.23
37/42-50 Bw1 2.438/S 4.203/S 19.513S 5.37/M 5.34 10.38 10.56
50-85/94 Bw2 2.150/S 3.706/S 18.322/S 5.38/M 5.30 10.54 10.73
85/94-123 Bw3 0.829/SR 1.429/SR 21.088/S 5.20/M 5.14 10.33 10.46
123-200 C 0.316/SR 0.544/SR 20.496/S 5.51/M 5.16 9.94 10.09
P4
0-39/48 A 2.468/S 4.254/S 17.372/S 5.23/M 4.66 9.55 9.68
39/48-71 Bw1 2.606/S 4.492/S 17.837/S 5.38/M 4.89 9.46 9.54
71-87 Bw2 1.255/R 2.164/R 16.326/R 5.60/AM 4.88 9.40 9.50
87-123/130 Bw3 1.296/R 2.234/R 18.182/S 5.47/M 4.78 9.38 9.51
123/130-
200
C 0.429/SR 0.740/SR 16.318/R 5.69/AM 4.63 9.23 9.29
Keterangan :
1. Analisis sifat fisik tanah dilakukan di laboratorium Ilmu Tanah Jurusan Ilmu Tanah Fakultas
Pertanian Universitas Udayana.
2. Kriteria C. Organik : SR = sangat rendah, R = rendah, S = sedang; Kriteria B.Organik : SR =
sangat rendah, R = rendah, S = sedang; Kriteria KTK : R = rendah, S = sedang; Kriteria KB : S = sedang, T = tinggi, ST = sangat tinggi, Kriteria pH (H2O) : M = masam, AM = agak
masam Nilai pH tanah juga diukur dengan menggunakan larutan NaF, nilai
ini ditetapkan untuk menduga kandungan mineral liat amorf atau alofan yang
biasanya menurun sejalan dengan menurunnya ketinggian tempat.
Kandungan mineral ini biasanya terdapat pada tanah dari abu vulkan di
daerah humid. Selain itu tanah yang kaya alofan dan terbentuk dari abu
vulkan mempunyai profil tanah yang dalam, lapisan atas gembur, bulk

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara
39
density rendah dan perkembangan struktur tanah baik tetapi agak lemah dan
porous (Hardjowigeno, 1993).
Hasil analisis pH NaF berkisar antara 9.2-10.7, nilai pH ini
mengindikasikan adanya mineral liat amorf/alofan (tabel 5). Pada lokasi
penelitian ditemukan dominasi liat haloisit yang berasal dari pelapukan atau
alterasi Al-silikat amorf seperti alofan. Selain adanya alofan, tingginya
konsentrasi ion H+ di dalam tanah juga menjadi faktor yang sangat
menentukan dalam proses pembentukan liat haloisit (Tabel 6).
Rendahnya pH ternyata berkorelasi positif dengan rendahnya
kapasitas tukar kation (KTK). Nilai KTK ditentukan oleh bahan organik,
jumlah dan jenis mineral liat serta tekstur tanah. Bahan organik
mempengaruhi KTK dengan melepaskan ion H+ dalam proses
dekomposisinya sehingga berakibat pada rendahnya nilai kemasaman tanah.
Tinggi rendahnya nilai KTK juga ditentukan oleh jenis mineral liat yang
mempunyai muatan beragam. Semakin kecil jumlah liat dan semakin kasar
tekstur tanah karena rendahnya koloid liat dan koloid organik, menyebabkan
nilai KTK semakin rendah.
Keempat profil mempunyai prosentase kejenuhan basa yang
bervariasi dengan kisaran 37.036 sampai dengan 95.779 (Tabel 5).
Prosentase kejenuhan basa merupakan petunjuk bagi horison penciri, seperti
molik, di mana profil P3 memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam
epipedon molik karena nilainya di atas 50%.
Mineral Faksi Pasir
Hasil analisis mineral fraksi pasir pada tabel 7, menunjukkan bahwa
jumlah mineral mudah lapuk (olivine, piroksin, plagioklas, ortoklas, biotit,
glas vulkan, weatherd mineral, hornblende) lebih tinggi dibandingkan
mineral sukar lapuk (kuarsa, kalsit, muskovit dan fraksi batuan). Tingginya
mineral mudah lapuk disebabkan karena bahan induk berkembang dari tufa
vulkan intermedier. Selain itu tingginya mineral mudah lapuk juga
menunjukkan bahwa proses pelapukan bahan induk masih belum lanjut. Hal
ini bisa disebabkan karena faktor pembentuk tanah kurang mendukung
proses perkembangan tanah lanjut. Kondisi inilah yang mengindikasikan
bahwa tanah masih kaya unsur-unsur mineral yang belum terbebaskan
sehingga tanah masih subur.
Mineralogi Liat
Mineral liat umumnya terbentuk dari hasil pelapukan fisik dan kimia
bahan induk atau mineral primer. Hasil pengamatan mineralogi liat
menunjukkan bahwa tanah liat silikat tipe haloisit cukup mendominasi
tanah-tanah di lokasi penelitian (Tabel 6). Keadaan ini bisa terjadi karena

Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang
40
adanya pelapukan liat amorf atau alofan yang berkembang dari abu vulkan
(Hardjowigeno, 1993). Sehingga dapat dikemukakan bahwa tanah-tanah di
lokasi penelitian tergolong tanah yang baru berkembang atau tanah muda.
Tabel 6. Data Analisis Mineralogi Liat Profil Kaolinit Haloisit Montmorilonit Illit Vermikulit Keterangan
P1
- xxx - xx - Campuran
x xxxx - x - Haloisit
x xxxx - x - Haloisit
- xxxx x x - Haloisit
P2
- - x xxxx x Illit
- - x xxxx x Illit
x xxx - xx - Campuran
x xxx - xx - Campuran
P3
x xxx - xx - Campuran
x xxxx - x - Haloisit
x xxx - xx - Campuran
- x x xxx x Campuran
P4
- xx x xxx - Campuran
- x x xxx x Campuran
- xxxx x x - Haloisit
- xxxx x x - Haloisit
Keterangan :
Analisis mineralogi liat dilakukan di laboratorium Ilmu Tanah Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian
Universitas Udayana.
xxxx : Dominan, xxx : Banyak, xx : Sedang, x : Sangat Sedikit
Illit yang juga dijumpai di lokasi penelitian bisa terbentuk dari
proses alterasi, artinya bahwa Illit bisa terbentuk dari montmorilonit bila di
lingkungan kaya unsur K. Di samping itu juga dapat terbentuk karena
rekristalisasi hasil pelapukan K-feldspar dalam larutan yang kaya K. Mineral
liat yang lain seperti montmorilonit, kaolinit, dan vermikulit mempunyai
jumlah yang lebih kecil dibandingkan kedua mineral di atas.
Montmorilonit bisa terbentuk dari rekristalisasi hasil pelapukan
bermacam-macam mineral bila kedaan lingkungan sesuai (drainase/tata air
kurang baik dan proses pencucian lambat). Selain itu juga ditemukan di
tempat-tempat di mana terjadi pelapukan mineral silikat yang banyak
mengandung Mg dan Fe.
Kaolinit terbentuk setelah mineral primer terdekomposisi, di mana
Al, dan Si yang larut akan berkristalisasi membentuk kaolinit. Sedangkan
vermikulit mempunyai kandungan K yang lebih rendah daripada Illit karena
sebagian besar atau seluruh K-interlayer telah diganti H+. Di samping itu
interlayer juga mengandung Ca dan Mg yang mudah disubstitusi oleh H+
sehingga KTK menjadi rendah.

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara
41
Tabel 7. Hasil Analisis Mineral Fraksi Pasir untuk Kelas Ukuran Butir Berpasir, Skeletal Berpasir dan Skeletal
Berlempung
Jenis
Mineral
Profil
P1 P2 P3 P4
Ap Bw1 Bw2 C1 C2 Bw3 C3 Ap Bw1 Bw2 Bw3 C Ap Bw1 Bw2 Bw3 C A Bw1 Bw2 Bw3 C
Olivin 6.17 12.10 7.94 12.46 11.04 2 12.81 10.34 2 6.95 6.48 9.40 13.71 6.85 2 2 6.50 12.65 9.41 5.89 10.44 15.71
Piroksin 9.98 7.51 5.43 8.30 8.41 9.72 9.61 11.4 14.42 10.42 10.53 7.05 11.5 15.85 12.03 13.66 5.28 2 9.41 12.77 2 7.64
Plagioklas 8.55 2 5.43 6.75 11.40 8.64 8.54 8.71 6.46 6.95 2 6.26 212.8 5.57 12.03 5.22 6.50 2 16.74 5.89 15.41 5.52
Kuarsa 2 2 5.43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.22 2 2 2 2 2 2
Kalsit 6.17 2 2 6.75 6.83 7.02 6.94 2 2 2 7.29 2 2 2 6.01 2 5.28 6.32 2 5.89 12.92 5.56
Ortoklas 9.98 11.26 2 16.09 20.50 19.44 15.48 15.78 15.91 11.29 25.93 14.10 2 6.85 8.79 2 13.82 13.14 2 4.25 2 5.79
Biotit 6.17 10.82 2 9.34 6.83 2 8.54 2 2 5.64 5.26 7.05 7.96 6.85 7.40 2 10.57 2 6.80 2 6.46 2
Muskovit 6.17 7.93 2 8.30 2 10.26 6.94 8.71 2 12.59 2 9.40 2 2 2 2 7.72 7.78 2 2 2 8.92
Glas Vulkan 2 7.51 6.69 2 2 10.26 2 2 2 5.64 11.34 8.22 15.03 2 2 6.42 5.28 6.32 9.41 16.04 10.44 5.52
Fraksi
Batuan
23.76 12.10 5.43 16.61 20.50 7.02 9.61 18.50 14.42 16.07 7.29 7.05 12.38 20.14 13.42 7.23 18.70 27.74 20.40 21.28 10.44 11.04
Weatherd
Mineral
12.83 14.6 50.18 9.34 2 10.26 15.48 11.43 12.92 10.42 7.29 21.15 12.82 12.42 14.81 45 10.97 9.24 17.79 12.77 15.41 20.38
Hornblende 6.17 6.67 5.43 2 6.83 11.34 2 7.07 10.44 9.12 2 6.26 5.75 5.57 6.01 7.23 7.31 8.76 2 9.17 10.44 8.92
Keterangan : Analisis fraksi liat dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanah Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Udayana

Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang
42
Klasifikasi Tanah
Hasil klasifikasi tanah berdasarkan morfologi, sifat fisik, kimia dan
mineralogi tanah dengan menggunakan Kunci Taksonomi Tanah 1998 Soil
Suevey Staff, 1998), yang dimulai dari kategori ordo sampai famili tanah
disajikan pada tabel 8.
Tabel 8. Klasifikasi Tanah dari Tingkat Ordo sampai Famili di Desa
Taro Profil Lokasi Ordo Subordo Greatgroup Subgroup Famili
P1
Pisang kaja, Pakuseba,
Sengkaduan, Tebuana
Incepti
sols
Udepts Dystrudepts Ruptic-Alfic
Dystrudepts
Ruptic-Alfic Dystrudepts,
berlempung kasar, campuran, isotermik
P2 Belong, Pakuseba Incepti
sols
Aquepts Epiaquepts Aeric
Epiaquepts
Aeric Epiaqupts, berlempung
kasar, campuran isotermik
P3
Alaspujung, Belong, Let, Patas, Pisang
Kaja, Puakan,
Sengkaduan, Tebuana
Inceptisols
Udepts Eutrudepts Humic Eutrudepts
Humic Eutrudepts, berlempung kasar, campuran
isotermik
P4 Patas, Pisang Kelod, Puakan
Inceptisols
Udepts Eutrudepts Typic Eutrudepts
Typic Eutrudepts, berlempung kasar, campuran,
isotermik
Epipedon dan Endopedon Penciri
Berdasarkan hasil pengamatan morfologi tanah di lapangan serta
analisis sifat fisik dan kimia tanah profil P1, P2, P4 mengindikasikan epipedon
okrik dan endopedon kambik. Dimasukkan ke epipedon okrik karena warna
value ≥ 4 (lembab) atau ≥ 6 (kering), kroma ≥ (lembab), mempunyai 1
horison A atau Ap, ketebalan 18 cm dan tidak memenuhi salah satu dari
tujuh epipedon yang lain. Sedangkan untuk profil P3 mengindikasikan
epipedon molik dan endopedon kambik. Epipedon molik dicirikan oleh
tanah yang tersusun dari bahan tanah mineral, kelas resistensi pecah agak
keras/lebih lunak, jumlah struktur batuan < 5 mm kurang dari ½ volume.
Selain itu warna value ≤ 3 (lembab) atau ≤ 5 (kering), kroma ≤ 3 (lembab),
memiliki value warna minimal 1 unit atau kroma 2 unit Munsell lebih rendah
baik lembab maupun kering dibandingakan horison C, kandungan C-
organik 0,6% lebing tinggi daripada horison C, KB > 50%, tebal ≥ 25 cm,
kandungan P larut dalam 1% asam sitrat < 1.500 mg/kg, sebagian epipedon
lembab selama ≥ 90 hari kumulatif, nilai -n < 0.7.
Lebih lanjut (Soil Survey Staff, 1998) menyatakan, endopedon
kambik sebagai horison penciri dicirikan oleh Tebal ≥ 15 cm, tekstur pasir
sangat halus, pasir sangat halus berlempung atau lebih halus, tidak
mempunyai kondisi akuik atau telah didrainase, memiliki struktur
tanah/tidak memiliki struktru batuan > ½ volume tanah, hue lebih merah,
kroma dan value atau kandungan liat lebih tinggi daripada horison di bawah

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara
43
atau di atasnya, memiliki sifat-sifat yang tidak memenuhi syarat hampir
semua epipedon, duripan atau fragipan dan semua endopedon, bukan bagian
horison Ap dan tidak rapuh.
Ordo
Ordo tanah di lokasi penelitian dengan profil pewakil P1, P2, P3, dan
P4, diklasifikasikan ke dalam ordo Inceptisols. Pada profil P1, P2, dan P4,
mempunyai epipedon okrik dan endopedon kambik sehingga termasuk pada
ordo Inceptisols. Sedangkan untuk profil P3, walaupun mempunyai epipedon
molik, tetapi karena gelas vulkanik atau abu vulkanik dan horison kambik
yang masam lebih berpengaruh terhadap profil tanah daripada epipedon
molik sehingga profil ini juga dimasukkan ke dalam ordo Inceptisols
(Hardjowigeno, 1993).
Subordo
Untuk kategori subordo, tanah di lokasi penelitian diklasifikasikan
ke dalam subordo aquepts dan udepts. Subordo aquepts diwakili oleh profil
P2 sedangkan subordo udepts diwakili oleh profil P1, P3 dan P4.
Pengklasifikasian profil P2 ke dalam subordo aquepts karena tanah memiliki
kondisi akuik selama sebagian waktu pada tahun-tahun normal (atau telah di
drainase) di kedalaman antara 40 – 50 cm dari permukaan tanah mineral.
Mengandung cukup besi feroaktif untuk dapat memberikan reaksi positif
terhadap α,α-dipyridil ketika tanah tidak sedang diirigasi pada kedalaman 50
cm dari permukaan tanah mineral.
Profil P1, P3, dan P4 diklasifikasikan ke dalam subordo udepts karena
memiliki rejim kelembaban tanah udik. Hal ini karena lokasi penelitian
beriklim basah dengan total curah hujan tahunan sebesar 2347,35 mm/tahun,
dengan 8 bulan basah dan tanpa adanya bulan kering. Rejim kelembaban
udik merupakan rejim kelembababan di mana penampang kontrol
kelembaban tanah tidak kering sebarang bagiannya, selama 90 hari
kumulatif di dalam tahun-tahun normal. Rejim kelembaban udik bisa
dijumpai pada tanah-tanah di daerah beriklim humid yang mempunyai curah
hujan dengan penyebaran merata (Soil Survey Staff, 1998).
Greatgroup
Tanah-tanah di daerah penelitian diklasifikasikan ke dalam
greatgroup dystrudepts yang diwakili profi P1. Hal ini karena tidak
memenuhi untuk kejenuhan basa sebesar ≥ 60% pada satu horison atau lebih
di antara kedalaman 25 cm dan 75 cm dari permukaan tanah mineral, jika
dimasukkan ke dalam eutrudepts. Profil P2 dimasukkan ke dalam epiaquepts,
karena tanah pada profil tersebut mempunyai episaturasi yaitu tanah sawah
yang diirigasi, tidak mempunyai epipedon histik, melanik, molik atau
umbrik. Tidak mempunyai rejim suhu cryik dan tanah tidak mempunyai
fragipan. Profil P3 dan P4, diklasifikasikan ke dalam great group eutrudepts,

Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang
44
karena kejenuhan basa > 60% serta tidak mempunyai horison sulfurik pada
kedalaman 50 cm, tidak mempunyai duripan dan fragipan pada kedalaman
100 cm dari permukaan tanah mineral sehingga tidak dapat dimasukkan ke
dalam greatgroup yang lain
Subgroup
Kategori subgroup di lokasi penelitian diklasifikasikan ke dalam
subgroup Ruptic-Alfic Dystrudepts untuk profi P1, Aeric Epiaquepts untuk
profil P2 dan Humic Eutrudepts untuk profil P3 dan Typic Eutrudepts untuk
profil P4. Profil P1 dimasukkan ke dalam Ruptic-Alfic Dystrudepts karena
mempunyai horison kambik, 10-50% berdasar volume terdapat bagian
iluvial yang tidak memenuhi persyaratan horison argilik, kandik atau natrik
dan kejenuhan basa lebih dari 35% pada kedalaman 125 cm dari bahan atas
horison kambik. Profil P2 diklasifikasikan ke dalam subgroup Aeric
Epiaquepts karena pada 50% atau lebih matriksnya mempunyai hue 10 YR
atau lebih kuning dan mempunyai warna value dan kroma dalam keadaan
lembab 3 atau lebih.
Profil P3 di masukkan ke dalam subgroup Humic Eutrudepts karena
mempunyai epipedon molik. Sedangkan profil P4 diklasifikasikan ke
dalamTypic Eutrudepts karena memiliki epipedon okrik bukan umbrik atau
molik, memiliki rejim kelembaban udik, kejenuhan basa lebih dari 50%
tidak memiliki sifat tanah fragik dan andik sehingga tidak memenuhi kriteria
subgroup yang lain.
Famili
Sifat pembeda yang digunakan untuk memisahkan atau
membedakan antara satu famili dengan famili yang lain adalah kelas ukuran
butir, kelas mineralogi dan temperatur tanah. Berdasarkan sifat-sifat tanah
tersebut, maka pada kategori famili, tanah-tanah di lokasi penelitian
diklasifkasikan ke dalam empat famili tanah yaitu : (1) Ruptic-Alfic
Dystrudepts, berlempung kasar, campuran, isotermik yang diwakili oleh
profil P1; (2) Aeric Epiaquepts, berlempung kasar, campuran, isotermik yang
diwakili profil P2; (3) Humic Eutrudepts, berlempung kasar, campuran,
isotermik yang diwakili oleh profil P3; (4) Typic Eutrudepts berlempung
kasar, campuran, isotermik yang diwakili oleh P4. Karena sifat pembeda
untuk kategori famili sama, maka yang dijadikan pembeda dalam kategori
famili adalah kategori subgroup.
Semua profil mempunyai kelas ukuran butir yang sama berlempung
kasar, karena fase halus atau lebih kasar ≥ 15% dan kandungan liat < 18%
(Tabel 9). Selain itu juga mempunyai kelas mineralogi campuran, karena
berdasarkan hasil analisis di masing-masing horison dan pada masing-
masing profil ditemukan jenis mineralogi yang heterogen dan tidak satupun
dari jenis mineral pasir tersebut yang dominan (Tabel 7). Temperatur tanah

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara
45
masing-masing profil juga sama, yaitu isotermik, ini disebabkan karena
temperatur tanah tahunan rata-rata 21.070C dan perbedaan antara temperatur
tanah musim panas rata-rata dengan musim dingin rata-rata adalah < 60C.
Tabel 9. Berat Rata-rata Tanah Tertimbang untuk Kelas Ukuran Butir Profil Liat (%) Debu (%) Pasir (%) Fragmen Batuan (%) Kelas Ukuran Butir
P1 5.789 41.131 53.078 - Berlempung kasar
P2 10.491 46.609 42.899 - Berlempung kasar
P3 6.508 25.955 67.542 - Berlempung kasar
P4 10.848 29.818 59.334 2 Berlempung kasar
Sumber : Laboratorium Ilmu Tanah Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
Famili tanah yang diwakili oleh keempat profil mengindikasikan
bahwa tanah masih muda dengan tingkat pelapukan masih rendah.
Rendahnya tingkat pelapukan tanah menunjukkan bahwa tanah di lokasi
penelitian secara potensial sangat subur karena unsur hara masih belum
terbebaskan. Tingkat pelapukan tanah yang belum lanjut juga menyebabkan
kasarnya tekstur tanah. Tekstur tanah yang kasar menjadi penyebab
rendahnya kemampuan tanah dalam menyediakan, menahan serta menyerap
air dan unsur hara.
Tingginya mineral liat haloisit yang berkembang dari alofan
menyebabkan tanah mempunyai pH yang rendah begitu juga dengan KTK.
Kapasitas tukar kation dapat ditingkatkan dengan beberapa cara seperti
pemupukan dan meningkatkan tingkat kemasaman tanah dengan pengapuran
(hakim dkk, 1986). sedangkan untuk reaksi tanah yang agak masam hingga
masam dapat diatasi dengan pemberian kapur.
Tabel 10. Satuan Peta Tanah di Desa Taro
SPT Satuan Peta Tanah Relief
Le
reng (%)
Bahan
Induk
Bentuk
Lahan
Penggunaan
Lahan
Luas
Ha %
1
Ruptic-Alfic
Dystrudept, berlempung kasar,
campuran,
isotermik
Berom
bak
3-8 Tufa
vulkan intermedier
Lereng
bawah vulkan
Tegalan 114.56 20.26
2
Aeric-Epiaquepts, berlempung kasar,
campuran,
isotermik
Landai 0-3 Tufa
vulkan
intermedier
Lereng
bawah
vulkan
Sawah 36.03 6.37
3
Humic Eutrudepts, berlempung kasar,
campuran,
isotermik
Landai 0-3 Tufa
vulkan
intermedier
Lereng
bawah
vulkan
Tegalan 233.08 41.23
4 Typic Eutrudepts, Berge 8-15 Tufa Lereng Belukar 15.41 2.72

Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang
46
berlempung kasar, campuran
isotermik
lombang vulkan
intermedier
bawah
vulkan
5
Typic Eutrudepts,
berlempung kasar,
campuran, isotermik
Berbukit
kecil
15-30 Tufa
vulkan
intermedier
Lereng
bawah
vulkan
Belukar 30.25 5.35
6
Typic Eutrudepts
berlumpur kasar,
campuran, isotermik
Berbukit 30-45 Tufa
vulkan
intermedier
Lereng
bawah
vulkan
Belukar 23.11 4.08
7
Typic Eutrudepts,
berlempung kasar,
campuran, isotermik
Bergu
nung
45-65 Tufa
vulkan
intermedier
Lereng
bawah
vulkan
Belukar 112.86 19.96
Tanah-tanah di lokasi penelitian juga mempunyai potensi untuk
dijadikan lahan pertanian. Untuk tanah-tanah yang diwakili oleh profil P1,
P3, dan P4 sesuai digunakan sebagai lahan perkebunan walaupun masih
memerlukan penanganan yang intensif dalam pengelolaan maupun tata
airnya. Selain itu juga masih memerlukan masukan yang cukup tinggi baik
bahan organik (pencampuran sisa-sisa panen dengan tanah yang diolah,
penambahan pupuk kandang dan pupuk hijau) maupun anorganik
(pemupukan yang berimbang antara N, P, K). Khusus untuk tanah-tanah
yang diwakili profil P4 yang perlu dilakukan adalah mencegah terjadinya
erosi melalui pencegahan secara mekanis dengan cara terasiring, guludan,
pengolahan tanah minimum dan menurut kontur. Untuk cara biologis dapat
diusahakan dengan penghutanan dan penanaman tanaman penutup
sedangkan cara kimia dengan menggunakan PAM, PVA, Bitumen dan
Krilium karena lahan di areal ini tergolong curam.
Untuk tanah-tanah yang diwakili oleh profil P2, sesuai sebagai lahan
persawahan dengan perlakuan yang hampir sama dengan lahan perkebunan.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pH tanah yang telalu masam,
kandungan bahan organik dan tingkat kesuburan tanah.
PetaTanah
Peta tanah yang dihasilkan dari penelitian ini adalah peta tanah semi
detail dengan skala 1 : 25.000. Unsur-unsur satuan penyusun suatu peta
terdiri dari topografi, bahan induk, kemiringan lereng, penggunaan lahan
serta famili tanah. Atas dasar beberapa unsur penyusun satuan peta tersebut,
maka tanah-tanah di lokasi penelitan dibedakan menjadi tujuh satuan peta
tanah.
Satuan Peta Tanah 1 : Ruptic-Alfic Dystrudepts, berlempung kasar,
campuran, isotermik. Tanah mempunyai relief berombak, dengan

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara
47
kemiringan lereng 3% sampai dengan 8% dan berkembang dari bahan induk
tufa vulkan intermedier. Ketinggian tempat berkisar antara 820 meter sampai
dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Total lokasi satuan peta ini
hampir seluruhnya digunakan sebagai lahan tegalan dengan tanaman pisang,
ilalang dan kelapa.
Satuan Peta Tanah 2 : Aeric Epiaquepts, berlempung kasar, campuran,
isotermik. Tanah mempunyai relief landai, dengan kemiringan lereng 0%
sampai dengan 3% dan berkembang dari bahan induk tufa vulkan
intermedier. Ketingian tempat berkisar antara 765 meter sampai dengan 920
meter di atas permukaan laut. Penggunaan lahan satuan peta ini hampir
seluruhnya untuk persawahan dengan tanaman utama padi sawah.
Satuan Peta Tanah 3 : Humic Eutrudepts, berlempungk kasar, campuran,
isotermik. Tanah dengan relief landai, kemiringan lereng 0% sampai dengan
3% dan berkembang dari bahan induk tufa vulkan intermedier. Ketinggian
tempat berkisar antara 1100 meter sampai dengan 1220 meter di atas
permukaan laut. Penggunaan lahan pada areal satuan peta ini adalah berupa
tegalan dengan tanaman kelapa, bambu dan ilalang.
Satuan Peta Tanah 4 : Typic Eutrudepts, berlempung kasar, campuran,
isotermik. Tanah dengan relief bergunung, kemiringan lereng berkisar antara
45% sampai dengan 65% dan berkembang dari bahan induk tufa vulkan
intermedier. Ketinggian tempat mempunyai kisaran antara 990 meter sampai
dengan 1140 meter di atas permukaan laut. Areal pada satuan peta ini
merupakan lahan belukar dengan tanaman semak belukar dan ilalang.
Satuan Peta Tanah 5 : Typic Eutrudepts, berlempung kasar, campuran,
isotermik. Tanah dengan relief bergelombang, kemiringan lereng berkisar
antara 8% sampai dengan 15%. Berkembang dari bahan induk tufa vulkan
intermedier, ketinggian tempat mempunyai kisaran antara 850 meter sampai
dengan 1210 meter di atas permukaan laut. Areal pada satuan peta ini
merupakan lahan belukar dengan tanaman semak belukar, ilalang dan
bambu.
Satuan Peta Tanah 6 : Typic Eutrudepts, berlempung kasar, campuran,
isotermik. Tanah dengan relief berbukit kecil, kemiringan lereng berkisar
antara 15% sampai dengan 30%. Berkembang dari bahan induk tufa vulkan
intermedier, dengan ketinggian tempat berkisar antara 760 meter sampai
dengan 1115 meter di atas permukaan laut. Areal pada satuan peta ini
merupakan lahan belukar dengan tanaman ilalang dan semak belukar.
Satuan Peta Tanah 7 : Typic Eutrudepts, berlempung kasar, campuran,
isotermik. Tanah dengan relief berbukit, dengan kemiringan lereng berkisar
antara 30% sampai dengan 45% dan berkembang dari bahan induk tufa
vulkan intermedier, ketinggian tempat berkisar antara 780 meter sampai

Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang
48
dengan 1040 meter di atas permukaan laut. Areal pada satuan peta ini
merupakan lahan belukar dengan tanaman ilalang dan semak belukar.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Tanah-tanah di lokasi penelitian diklasifikasikan ke dalam ordo
intceptisols, subordo Aquepts dan Udepts, greatgroup Epiaquepts,
Dystrudepts dan Eutrudepts subgroup Ruptic-Alfic Dystrudepts,
Aeric Epiaquepts, Humic Eutrudepts dan Typic Eutrudepts
2. Untuk kategori famili tanah terdapat empat famili tanah yaitu :
a. Ruptic-Alfic Dystrudepts, berlempung kasar, campuran,
isotermik
b. Aeric Epiaqupts, berlempung kasar, campuran, isotermik
c. Humic Eutrudepts, berlempung kasar, campuran, isotermik
d. Typic Eutrudepts, berlempung kasar, campuran, isotermik
3. Lokasi penelitian terdiri dari tujuh SPT (Satuan Peta Tanah) dengan
skala 1 : 25.000
4. Secara potensial tanah di lokasi penelitian tergolong cukup subur
untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian.
Saran
Mengacu pada data morfologi, sifat fisik, kimia dan mineralogi
tanah menunjukkan adanya beberapa faktor pembatas seperti pH tanah
cukup masam, tekstur kasar, KTK dan bahan organik. Untuk memperbaiki
kondisi tersebut maka diperlukan penambahan bahan organik, pengapuran
dan pemupukan. Jika lahan tegalan dengan komoditi tanaman tahunan akan
dikonversi menjadi lahan perkebunan dengan tanaman semusim dibutuhkan
pengelolaan yang tepat, perbaikan tata air dan penambahan bahan organik
serta unsur hara dari pemupukan.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kecamatan Tegallalang, 1997. Tegallalang dalam
angka. Tidak dipublikasikan.
Balai Meteorologi dan Geofisika Wilayah III. 2003. Laporan Curah Hujan
Rata-rata dan Suhu Udara Rata-rata Tahunan Daerah Bali. Tidak
dipubliksikan

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara
49
Foth, H.D. 1994. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Terjemahan E.D. Purbayanti,
dkk. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Hadiwidjojo, M.M.P. 1971. Peta Geologi pulau Bali. Skala 1 : 250.000.
Direktorat Geologi, Bandung.
Hakim N., Nyakpa Y.m., Lubis A.M., Nugroho G.S., Saul R.M., Diha A. M.,
Hong B.G., Bailey H.H. 1986. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Univeritas
lampung.
Hardjowigeno, S. 1993. Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis. Akademi
pressindo. Jakarta.
Soil Conservation Service. 1972. Soil Survey Laboratory Methods and
Procedures for Collecting Soil Samples. USDA, US. Govt. printy
Office. Washington. USA.
Soil Survey Staff. 1998. Kunci Taksonomi Tanah. Edisi kedua. Bahasa
Indonesia, 1999. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat., Badan
Penelitian dan pengembangan Pertanian.

Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang
50
Gambar 1. Satuan Peta Tanah Tentatif dan Lokasi Pengambilan Profil dan Minipit Desa
Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Bali, Skala 1 : 25.000

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara
51
0 1 2 3 4 5
1.25
Sumber Geologi : Peta Landform, Peta Lereng,
Peta Penggunaan Lahan
dan Peta Geologi
Disusun oleh : Himawan Bayu Aji
NIP. 19790521 201403 1 001
Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Maluku Utara
SATUAN PETA TANAH TENTATIF DAN LOKASI PENGAMBILAN
PROFIL DAN MINIPIT DESA TARO, KECAMATAN TEGALLALANG,
KABUPATEN GIANYAR
BALI Skala 1 : 25.000
Ket : Lokasi minipit .. .. .. Batas Kodya/Kabupaten
Lokasi Profil Batas Satuan Peta Tanah
Permukiman Sungai
…. …. Batas Desa Sungai Intermiten
… … Batas Kecamatan Jalan
Legenda Satuan Peta Tanah Desa Taro
Unit
Lhn Relief Lereng Bahan Induk Bentuk Lahan
Pengguna
an Lahan
1 Berombak 3 - 8 Tufa vulkan intermedier Lereng bawah vulkan Tegalan
2 Landai
0 - 3 Tufa vulkan intermedier Lereng bawah vulkan Sawah
3 Landai 0 - 3 Tufa vulkan intermedier Lereng bawah vulkan Tegalan
4 Bergelombang 8 -15 Tufa vulkan intermedier Lereng bawah vulkan Belukar
5 Berbukit kecil 15 - 30 Tufa vulkan intermedier Lereng bawah vulkan Belukar
6 Berbukit 30 - 45 Tufa vulkan intermedier Lereng bawah vulkan Belukar
7 Bergunung 45 - 65 Tufa vulkan intermedier Lereng bawah vulkan Belukar
Lokasi penelitian
P. Bali

Klasifikasi Tanah Berdasarkan Sistem Taksonomi Tanah Di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang
52
Gambar 2. Peta Tanah Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Bali,
Skala 1 : 25.000

Buletin Pengkajian Pertanian BPTP Maluku Utara
53
0 1 2 3 4 5
1.25
Sumber : Peta Landform, Peta Lereng,
Peta Penggunaan Lahan
dan Peta Geologi
Disusun oleh : Himawan Bayu Aji
NIP. 19790521 201403 1 001
Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Maluku Utara
Gambar 2. Peta Tanah Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Bali,
Skala 1 : 25.000
PETA TANAH
DESA TARO, KECAMATAN TEGALLALANG,
KABUPATEN GIANYAR
BALI Skala 1 : 25.000
Ket : Permukiman Batas Satuan Peta Tanah
…. …. Batas Desa Sungai
… … Batas Kecamatan Sungai Intermiten
.. .. .. Batas Kodya/Kabupaten Jalan
Legenda Satuan Peta Tanah Desa Taro
SPT Famili Relief Lereng
(%)
Bahan
Induk Bentuk Lahan
Penggu
na
an
Lahan
Luas
Ha %
1 Ruptic-Alfic Dystrudepts,
berlempung kasar, campuran
isotermik
Berombak 3 - 8 Tufa vulkan
intermedier
Lereng bawah
vulkan Tegalan
114.5
6
20.26
2 Aeric Epiaquepts, berlempung
kasar, campuran, isotermik
Landai 0 - 3 Tufa vulkan
intermedier
Lereng bawah
vulkan
Sawah 36.03 6.37
3 Humic Etrudepts, berlempung
kasar, campuran, isotermik
Landai 0 - 3 Tufa vulkan
intermedier
Lereng bawah
vulkan
Tegalan 233.0
8
41.23
4 Typic Eutrudepts, berlempung
kasar, campuran, isotermik
Bergelom
bang
8 -15 Tufa vulkan
intermedier
Lereng bawah
vulkan
Belukar 15.41 2.72
5 Typic Eutrudepts, berlempung
kasar, campuran, isotermik
Berbukit
kecil
15 - 30 Tufa vulkan
intermedier
Lereng bawah
vulkan
Belukar 30.25 5.35
6 Typic Eutrudepts berlempung
kasar, campuran, isotermik
Berbukit 30 - 45 Tufa vulkan
intermedier
Lereng bawah
vulkan
Belukar 23.11 4.08
7 Typic Eutrudepts berlempung,
kasar, campuran, isotermik
Bergunung 45 - 65 Tufa vulkan
intermedier
Lereng bawah
vulkan
Belukar 112.8
6
19.96
Lokasi penelitian
P. Bali

PEDOMAN BAGI PENULIS BULETIN BPTP MALUKU UTARA Naskah hasil pengkajian maupun yang berupa review ditulis dalam bahasa Indonesia atau
Inggris dengan urutan pembagian bab sebagai berikut :
JUDUL & NAMA PENULIS ditulis dengan huruf besar pada awal setiap kata dan disertai
catatan kaki yang ditulis lengkap (tidak disingkat) tentang profesi/jabatan dan nama instansi
tempat penulis bekerja. Judul hendaknya singkat (tidak lebih dari 14 kata) dan mampu
menggambarkan isi pokok tulisan.
Contoh : ANALISIS USAHATANI PALA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN
ABSTRAK ditulis dalam bahasa Indonesia, sebanyak-banyaknya 150 kata yang dituangkan
pada satu alinea dengan susunan : Judul, nama (-nama) penulis dan ringkasan isi. ABSTRAK
merupakan inti seluruh tulisan dan harus mampu memberikan uraian yang tepat, jelas tapi
singkat tentang latar belakang, tujuan yang ingin dicapai, metodologi yang digunakan dalam
pencapaian tujuan, hasil penelitian yang terpenting dan kesimpulan (apabila memungkinkan).
Contoh : ABSTRAK <Judul> <Nama -[nama] penulis> < Abstrak isi>.
KATA KUNCI terdiri dari beberapa kata atau gugus kata yang menggambarkan isi naskah.
Demi keseragaman format dan kemudahan dalam pen-database-an, dianjurkan untuk diawali
dengan <nama komoditas> (apabila jenis komoditasnya tidak terlalu banyak).
Contoh : Padi, Benih unggul, Sekolah lapang.
ABSTRACT & KEY WORDS ditulis dengan bahasa Inggris dengan ketentuan seperti pada
ABSTRAK & KATA KUNCI. Pada naskah berbahasa Inggris, bab ini mendahului
ABSTRAK & KATA KUNCI.
PENDAHULUAN (nama bab tidak ditulis), mencakup latar belakang masalah, alasan
pentingnya penelitian itu dilakukan, temuan terdahulu yang akan disanggah atau
dikembangkan (termasuk di dalamnya telusuran pustaka terkait), pendekatan umum dan
tujuan penulisan. Nama jasad hidup yang menjadi topik penelitian harus disertai nama
ilmiahnya.
Contoh : Kedelai (Glycine max L. [Merrill]).
BAHAN & METODE berisi penjelasan ringkas tentang waktu dan tempat penelitian, bahan
dan teknik yang digunakan, rancangan percobaan dan analisis data. Teknik yang dirujuk tidak
perlu diuraikan (kecuali apabila dimodifikasi), tetapi cukup disebut nama sumbernya dan
tahun atau metodenya. Nama piranti lunak komputer yang digunakan untuk menganalisis
data seyogyanya disebutkan.
HASIL & PEMBAHASAN merupakan kupasan penulis tentang hasil, menerangkan arti
hasil penelitian, persamaan dan perbedaan hasil penelitian ini dibandingkan dengan
penelitian terdahulu (baik dari dalam maupun luar negeri), peran hasil penelitian terhadap
pemecahan masalah yang disebutkan di bab pendahuluan, hubungan antara parameter yang
satu dengan yang lain, dan kemungkinan pengembangannya.
KESIMPULAN (apabila memungkinkan) merupakan hasil kongkrit atau keputusan yang
diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran. Informasi yang bersifat
faktual (e.g. umur tanaman, dll) bukanlah kesimpulan, sehingga tidak perlu dimasukkan ke
dalam bab kesimpulan.
UCAPAN TERIMA KASIH (apabila dianggap perlu) berisi penghargaan singkat kepada
pihak-pihak yang telah berjasa selama penelitian (3-5 kalimat ringkas).

PUSTAKA disusun menurut abjad. Secara umum, setiap pustaka hendaknya terdiri atas
nama penulis, tahun, judul, halaman dan penerbit. Pustaka seyogyanya dipilih yang masih
mempunyai kaitan dengan topik penelitian dan ditulis sebagai berikut :
Untuk Artikel di dalam Buku : Nama (-nama) penulis, tahun penerbitan, judul artikel,
halaman, nama penyunting, judul publikasi atau buku, nama dan tempat penerbit. Contoh :
Nugraha, U.S., Subandi, dan A. Hasanuddin. 2003. Perkembangan Teknologi Budidaya dan
Industri Benih Jagung. Ekonomi Jagung Indonesia. Badan Litbang Pertanian: 37-72. Jakarta.
Untuk Terbitan Berkala : Nama (-nama) penulis, tahun penerbitan, judul artikel, nama
terbitan (disingkat, apabila dianjurkan), volume dan nomor, dan nomor halaman (dianjurkan).
Contoh :
Bachrein, S. 2005. Keragaan dan Pengembangan Sistem Tanam Legowo 2:1 pada Padi
Sawah di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Jawa Barat. JPPTP Valome 8 Nomor 1,
Maret 2005. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Untuk Buku : Nama (-nama) penulis, tahun penerbitan, judul buku, edisi dan tahun revisi,
nama dan tempat penerbit, dan jumlah halaman. Contoh :
Soekartawi. 2002. Analisis Usahatani. Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS). Jakarta.
110 hlm.
PERSIAPAN TULISAN
Persiapan Tulisan. Naskah diketik 1 spasi pada kertas ukuran A4, satu muka, tipe huruf
baku Times New Roman ukuran 11 cpi dan tidak lebih dari 15 halaman (termasuk tabel,
gambar dan pustaka). Badan naskah dicetak dengan ketentuan batas pinggir kertas 3 cm dari
atas, bawah, dan kanan, dan 4 cm dari kiri.
Tabel ‘masuk’ ke dalam teks, tidak dikumpulkan di bagian akhir makalah sebagaimana
halnya lampiran.
Judul tabel terletak di atas tabel yang bersangkutan dan hendaknya berupa satu kalimat yang
singkat dan jelas (termasuk keterangan tempat dan waktu).
Angka desimal ditandai dengan koma (bahasa Indonesia) atau titik (bahasa Inggris).
Besaran ditulis menurut standar internasional, bukan besaran lokal (e.g. kuintal, are) dan
mengikuti kaidah Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (misalnya g, l, kg, bukan gr,
ltr, atau Kg).
Catatan kaki pada tabel ditandai dengan huruf atau angka dengan posisi agak naik
(superscript).
Gambar & Grafis hendaknya dibuat dengan piranti lunak komputer berikut ini : Excel,
SPSS, Corel Draw, dll. Foto hendaknya kontras, tajam dan jelas.
Penyerahan softcopy Penulis yang makalahnya akan segera diterbitkan agar menyerahkan
softcopy file teks dan gambar (format seperti tertera sebelumnya) dengan flashdisk yang
diserahkan ke Sdr. Hermawati Cahyaningrum di Ruang Editor Buletin Pengkajian BPTP
Maluku Utara, Komplek Pertanian Kusu No. 1 Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, atau via
email melalui: [email protected]

DAFTAR ISI
PENGARUH PEMUPUKAN NPK TERHADAP KOMPONEN
HASIL UMBI BEBERAPA VARIETAS UBI KAYU DI
LAHAN KERING BACAN, HALMAHERA SELATAN
( Wawan Sulistiono dan Bram Brahmantiyo) …………………...........................................
1 - 6
KELAYAKAN USAHA INTEGRASI KELAPA-JAGUNG
MANIS-SAPI DI LAHAN KERING MALUKU UTARA (Slamet Hartanto dan Yayat Hidayat).........................................................................
7 - 12
STATUS PERKEMBANGAN PERTANIAN DALAM
PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU UTARA
(Ahamd Yunan Arifin) .............................……………….................................................
13 - 20
PENGEMBANGAN KAWASAN RUMAH PANGAN
LESTARI MELALUI OPTIMALISASI LAHAN
PEKARANGAN
DI KELURAHAN SASA, KOTA TERNATE ( Agus Hadiarto dan Chris Sugihono) ..........................................................................
21 - 29
KLASIFIKASI TANAH BERDASARKAN SISTEM
TAKSONOMI TANAH DI DESA TARO, KECAMATAN
TEGALLALANG, GIANYAR (Himawan Bayu Aji)………………...................................................................................
30 - 53