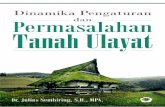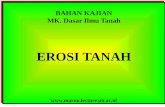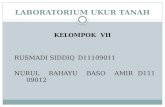bahan tanah ulayat....
-
Upload
muhammad-yani -
Category
Documents
-
view
49 -
download
0
Transcript of bahan tanah ulayat....
BAB I PENDAHULUAN Setelah melalui perdebatan panjang dan proses berliku, akhirnya pada tanggal 22 Juli 2008 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Secara eksplisit, Perda No. 6 tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan . Kemudian, sasaran utama pemanfaaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat . Lebih lanjut dinyatakan juga bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data/informasi pertanahan, tanah ulayat dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota . Pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya dalam Perda Provinsi, tentu menimbulkan dampak terhadap eksistensi hak ulayat di Sumatera Barat pada masa mendatang. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah pengaturan tanah ulayat dan kemungkinan penyertipikatannya oleh Perda No. 6 tahun 2008 akan menjamin eksistensi tanah ulayat di Sumatera Barat? Pertanyaan ini perlu direnungkan dan ditelaah secara mendalam.
BAB II TANAH ULAYATA. Pengertian Tanah Ulayat Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
B. Status Tanah Dalam Konsepsi Hukum Pertanahan Indonesia Menurut Maria SW Sumardjono, secara konseptual status tanah dapat dibedakan atas 3 (tiga) entitas, yakni tanah negara, tanah hak, dan tanah (hak) ulayat . Tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak. Dengan demikian, tanah-tanah yang dilekati dengan sesuatu hak atas tanah yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA, demikian pula tanah (hak) ulayat dan tanah wakaf tidak termasuk dalam pengertian tanah negara . Tanah hak adalah tanah yang dilekati dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Sedangkan tanah (hak) ulayat pada prisipnya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Dalam hal ini, pembicaraan mengenai hak ulayat tidak hanya mengenai tanahnya saja, melainkan juga meliputi segala isinya.
Tanah negara mengandung aspek publik. Artinya, aspek yang menonjol di sini adalah aspek kewenangan mengatur dan menguasai tanah oleh negara. Ada pun ruang lingkup tanah negara tersebut meliputi (a) tanah-tanah yang diserahkan secara suka rela oleh pemiliknya; (b) tanahtanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi; (c) tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris; (d) tanah-tanah yang diterlantarkan; dan (e) tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sebagaimana yang diatur oleh Perpres No. 36 tahun 2005 yang kemudian diubah oleh Perpres No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum . Tanah hak mengandung aspek keperdataan. Aspek yang menonjol adalah aspek hubungan hukum orang dengan tanah. Berdasarkan Pasal 16 UUPA, yang termasuk hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai (HP), hak Sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. Menurut Maria SW Sumardjono, secara implisit UUPA membedakan 2 (dua) kelompok hak atas tanah. Kelompok pertama adalah hak milik, sedangkan kelompok kedua adalah HGU, HGB, HP . Berikut adalah persandingan 2 (dua) kelompok tersebut. Di samping 3 (tiga) jenis status tanah tersebut di atas, dikenal juga tanah hak pengelolaan (HPL). HPL secara implisit pengertiannya diturunkan dari Pasal 2 ayat (4) UUPA dan Penjelasan Umum II (2) UUPA. Istilah HPL muncul pertama kali dalam Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan KetentuanKetentuan Tentang Kebijaksanaan selanjutnya. Menurut Maria SW Sumardjono, HPL merupakan bagian dari hak menguasai negara yang (sebagian) kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang HPL . Bagian-bagian tanah HPL tersebut dapat diberikan kepada pihak lain dengan hak milik, HGB, atau hak pakai . Tinjauan Singkat Pendaftaran Tanah menurut PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dalam PP No. 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah: a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah . Ada pun yang menjadi obyek pendaftaran tanah menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997, meliputi: a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai b. Tanah HPL c. Tanah wakaf d. Hak milik atas satuan rumah susun e. Hak tanggungan f. Tanah negara Dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) di atas, tanah ulayat tidak termasuk ke dalam obyek pendaftaran tanah. Terhadap tidak dimasukkannya tanah ulayat sebagai obyek pendaftaran tanah, Boedi Harsono berpendapat: hak ulayat tidak akan didaftar. UUPA tidak memerintahkan pendaftarannya, dan dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hak ulayat secara sadar tidak dimasukkan dalam
obyek pendaftaran tanah. Secara teknis tidak mungkin, karena batas-batas tanahnya tidak mungkin dipastikan tanpa menimbulkan sengketa antarmasyarakat hukum yang berbatasan. UUPA mengakui adanya keberadaan hak ulayat. Hal ini menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri agraria tersebut mengatur mengenai kriteria ada atau tidaknya keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Setelah melalui penelitian yang melibatkan stakeholders, keberadaan hak ulayat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah . Dalam hal ini, tanah ulayat tersebut tidak diterbitkan sertipikat. C. Pendaftaran Tanah Ulayat Versi Perda No. 6 tahun 2008 Perda No. 6 tahun 2008 mengklasifikasikan tanah ulayat di Sumatera Barat atas 4 (empat) jenis tanah ulayat, yakni tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo . Tanah-tanah ulayat tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Bila didaftarkan, tanah ulayat nagari diberi status Hak Guna Usaha (HGU), hak pakai atau hak pengelolaan (HPL). Tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum diberi status hak milik. Sedangkan tanah ulayat rajo diberi status hak pakai dan hak kelola. Dari ketentuan tersebut di atas, dipahami bahwa jika tanah ulayat didaftarkan pada Kantor Pertanahan, maka statusnya diubah menjadi HGU, hak pakai, HPL, hak milik dan hak kelola. HGU, hak pakai, HPL dan hak milik merupakan status tanah yang dikenal dalam hukum pertanahan Indonesia. Sedangkan hak kelola merupakan istilah baru, atau jangan-jangan yang dimaksud adalah HPL? HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan . Bila tanah ulayat nagari di daftarkan pada Kantor Pertanahan dan pada pemegang haknya diberikan HGU, maka status hukum tanah ulayat nagari tersebut dapat dipastikan telah berubah menjadi tanah negara. Dalam hal ini, pemegang HGU tidak begitu leluasa memanfaatkan tanah yang dikuasainya. Peruntukannya dibatasi pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan. Pemanfaatannya pun juga dibatasi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun . Selain itu, pemegang HGU diwajibkan membayar uang pemasukan pada negara Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah negara, tanah hak milik atau tanah HPL . Artinya, hak pakai hanya dapat diberikan di atas tanah negara, tanah hak milik atau tanah HPL. Bila tanah ulayat didaftarkan, tentu status hukumnya berubah menjadi salah satu di antara 3 (tiga) jenis tanah tersebut. Kemungkinan terbesarnya, tanah ulayat itu berubah menjadi tanah negara. Hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun atau dapat diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu . HPL adalah hak menguasai negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya. Pemegang HPL dapat memberikan hak atas tanah pada pihak lain. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang dapat menjadi pemegang HPL adalah: (1) Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah; (2) BUMN; (3) BUMD; (4) PT. Persero; (5) Badan Otorita; (6) Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah. Dalam praktiknya, terdapat berbagi jenis HPL, yakni: (a) HPL
Pelabuhan, (b) HPL Otorita, (c) HPL Perumnas, (d) HPL Pemerintah Daerah, (e) HPL Transmigrasi, (f) HPL Instansi Pemerintah, dan (g) HPL Industri/pertanian/pariwisata/Perkeretaapian. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah . Terkuat dan terpenuh maksudnya disini adalah pemegang hak milik itu dapat berbuat apa saja terhadap miliknya itu, misalnya memakai/menguasainya sendiri maupun menjual, menyewakan, meminjamkan hak miliknya itu kepada pihak lain. Secara teoritis, hak milik dengan hak menguasai berbeda. Pemegang hak milik atas suatu benda pastilah pemilik dari benda tersebut sedangkan pemegang hak menguasai belum tentu pemilik dari benda itu . Bila dikaitkan dengan hak ulayat, maka hak ulayat termasuk ke dalam kategori hak menguasai. Karena hak ulayat merupakan kepunyaan bersama masyarakat hukum adat di mana penguasaannya dipimpin oleh Penguasa Adat. D. Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kepentingan Investasi dan Pembanguna Lahirnya Perda No.6 tahun 2008 tidak hanya semata ditujukan untuk melindungi eksistensi tanah ulayat di sumatera Barat, namun juga hadir untuk kepentingan investasi dan pembangunan . Untuk itu, melalui Pasal 3 ayat (2), Perda No. 6 tahun 2008 membuka ruang bagi dimanfaatkannya tanah ulayat oleh pihak lain dengan kaedah adat diisi limbago dituang melalui musyawarah mufakat . Secara eksplisit, Perda No.6 tahun 2008 menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan Badan Hukum dan perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan tanah ulayat dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil dan/atau bentuk lain yang disepakati . Kemudian, Perda No. 6 tahun 2008 juga memungkinkan investor memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikutsertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian . Apabila perjanjian penyerahan hak penguasan dan/atau hak milik untuk pengusahaan dan pengelolaan tanah yang diperjanjikan berakhir, maka status pengusahaan dan/atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula . Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain tersebut, dimungkinkan tidak hanya berdasarkan perjanjian saja. Perda No. 6 tahun 2008 juga memberi peluang untuk didaftarkannya tanah ulayat tersebut dengan hak-hak tertentu . Jikalau tanah ulayat didaftarkan, niscaya mekanismenya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perda No.6 tahun 2008. Bila dilaksanakan, status hukum tanah ulayat akan berubah. Sebab, dalam hukum tanah Indonesia tidak ada pemberian HGU, HGB, dan hak pakai di atas tanah ulayat. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) Perda No.6 tahun 2008 mengatur bahwa bila perjanjian tanah ulayat yang terdaftar tersebut berakhir, maka pengaturan pemanfaatan tanah selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada penguasa dan/atau pemilik tanah ulayat semula. Bila perjanjian berakhir, mengapa tanah ulayat tersebut tidak langsung diserahkan pada masyarakat hukum adat dan harus melalui perantaraan Pemerintah Kabupaten/ Kota? Tidak mungkin ketentuan ini dibuat tanpa ada pertimbangan tertentu yang melatarbelakanginya. Tawaran Solusi Mekanisme pendaftaran tanah ulayat yang diatur oleh Perda No.6 tahun 2008 berimplikasi terhadap berubahnya status hukum tanah ulayat. Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan asas utama tanah ulayat sebagaimana diusung oleh Pasal 2 ayat (1) Perda No.6 tahun 2008, yaitu jua ndak dimakan bali, gadai ndak makan sando . Hal ini merupakan kerugian besar bagi
keberlangsungan tanah ulayat di Sumatera Barat. Di samping itu, pengaturan pemanfaatan maupun pendaftaran tanah ulayat tersebut, ditenggarai dapat pula memicu konflik antara Pemerintah Nagari dengan KAN. Dalam Perda Provinsi No.2 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dinyatakan bahwa tanah ulayat nagari merupakan harta kekayaan nagari. Pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan peraturan nagari . Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (2) menyebutkan, sebelum peraturan nagari untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari ditetapkan, Pemerintah Nagari melakukan konsultasi/koordinasi dengan KAN. Jadi yang bertindak mengatur dan mengelola tanah ulayat nagari adalah Pemerintah Nagari, sedangkan KAN merupakan mitra dari Pemerintah Nagari, yaitu sebatas lembaga konsultasi/koordinasi. Berbeda dengan Perda No. 2 tahun 2007, Perda No.6 tahun 2008 menyatakan bahwa penguasa dan pemilik tanah ulayat nagari adalah Ninik Mamak KAN . Pengaturan dari dua Perda ini saling tabrak dan bertolak belakang. Dalam rangka menjamin eksistensi tanah ulayat, pemetaan tanah ulayat merupakan keniscayaan. Penentuan batas-batas tanah ulayat tidak cukup hanya berdasarkan peta ingatan dari penguasapenguasa adat. Perlu kejelasan siapa pemilik/penguasa tanah ulayat beserta dengan batas-batas yang melingkupinya. Ketidakjelasan tersebut, cenderung akan menjadi sumber konflik dan menjadi bom waktu yang siap meledak di kemudian hari. Ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan dalam memetakan tanah ulayat. Pertama, tetap menempuh mekanisme sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 5 tahun 1999. Kedua, mendaftarkan tanah ulayat kepada kepada Kantor Pertanahan dengan cara membukukan bidang tanah ulayat dalam daftar tanah sesuai dengan mekanisme pendaftaran tanah negara sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997. Mengenai dua tawaran solusi ini, Penulis lebih cenderung memilih tawaran yang kedua. Karena, prosedurnya tidak rumit dan tidak memerlukan biaya yang besar.
Bab III Penutup Dari uraian di atas, dipahami bahwa pendaftaran tanah ulayat sebagaimana diatur oleh Perda No. 6 tahun 2008 pada hakekatnya mengancam eksistensi tanah ulayat di Sumatera Barat. Terlihat tidak ada korelasi antara tujuan dengan substansi pengaturannya dalam Perda No. 6 tahun 2008. Tanah ulayat bukan merupakan momok untuk masuknya investasi jikalau keberadaan tanah ulayat diakui dan dihormati eksistensinya. Merupakan suatu realitas bahwa HGU, HGB dan hak pakai yang notabene adalah pintu masuknya investasi tidak bisa diberikan di atas tanah ulayat. Perlu kiranya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten/Kota maupun BPN melakukan langkah progresif dengan menyatakan bahwa HGU, HGB dan hak pakai dapat diberikan di atas tanah ulayat. Disadari hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan UUPA, namun demi menjaga keberadaan tanah ulayat dan masuknya investasi tidak ada salahnya langkah ini dilakukan. Sebetulnya, penyimpangan ketentuan UUPA secara sadar telah terjadi di Sumatera Barat. Dari hasil penelitian Kurnia Warman, hak ganggam bauntuak tidak lantas menjadi hak pakai sebagaimana dirumuskan UUPA, tapi ia cenderung menjadi hak milik . Penyimpangan tersebut secara formil dibenarkan oleh BPN dengan terbitnya serpikat hak milik.
DAFTAR PUSTAKA Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, isi dan Pelaksanaannya, Penerbit Djambatan, Jakarta Kurnia Warman, 1998, Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak Menurut UUPA di Sumatera Barat, Tesis, Sekolah PPs UGM, Yogyakarta Maria SW Sumardjono, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta , 2005, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1986, Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran: Tinjauan Falsafah HUkum, Penerbit Balai Aksara, Jakarta Bonnie Setiawan, (2006). Ekonomi Pasar Yang Neo-Liberalistik Versus Ekonomi Berkeadilan Sosial, Disampaikan pada Diskusi Publik Ekonomi Pasar yang Berkeadilan Sosial yang diadakan oleh Forum Komunikasi Partai Politik dan Politisi untuk Reformasi tanggal 12 Juni 2006 di DPR-RI, Jakarta. Hal 4-5 Budi Harsono, (2003). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta. Herman Soesangobeng, (2000). Pendaftaran Tanah Ulayat Di Sumatera Barat dengan Contoh Pilot Proyek Pendaftaran Tanah di Desa Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Makalah dalam Lokakarya di Padang, 23-24 Oktober 2000. John Griffiths, (2005). Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual, dalam Buku Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner, HuMa, Jakarta. Kurniawarman, (2006). Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik, Andalas University Press, Padang.