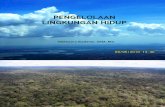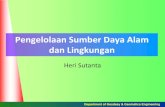Bab IV Pengelolaan Lingkungan
-
Upload
imran-natsir -
Category
Documents
-
view
18 -
download
0
description
Transcript of Bab IV Pengelolaan Lingkungan
54
BAB IV PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Pengelolaan lingkungan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan, mencegah pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan biotik, abiotik dan sosial. Pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan penanggulangan dan pencegahan. Penanggulangan pencemaran merupakan suatu usaha untuk mengelola limbah yang telah dihasilkan. Pencegahan adalah usaha menahan atau meniadakan zat pencemar dalam kegiatan industri tapi karena tersedia teknologi pengolahan produksi yang lebih baik maka bahan pencemar bisa dicegah sehingga memungkinkan tidak memerlukan teknologi pengolahan limbah. Usaha pencegahan dilakukan pada proses produksi sedangkan penanggulangan dilakukan setelah proses produksi berlangsung. Upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan berupa penerapan konsep produksi bersih dan pengolahan limbah cair dalam IPAL (MASITHOH, 2008).Alternatif pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan oleh industri kecil tahu Sumber Rezeki adalah dengan penerapan produksi bersih, Penerapan Sanitasi dan pengolahan limbah padat serta pembuatan Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai untuk limbah cair namun dengan biaya yang murah, dan pengolahan sanitasi industri.
4.1 Penerapan Produksi Bersih
Strategi pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan oleh industri tahu Sumber Rezeki sebelum alternatif pengolahan limbah yaitu dengan penerapan produksi bersih. Penerapan produksi bersih dapat meningkatkan efesiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya, sehingga dapat meminimisasi dampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Upaya penerapan produksi bersih yang dapat dilakukan di industri tahu Sumber Rezeki adalah sebagai berikut:a. Proses produksi1. PerendamanDeskripsi proses: Proses perendaman memerlukan waktu 3 jam. Perbandingan air dengan bahan saat perendaman adalah 1 : 3. Proses akhir yang terjadi adalah diperolehnya kedelai melar yang kemudian dibersihkan dari kotoran yang masih tersisa dan juga kulit kedelai.Identifikasi terbentuknya Limbah: Pada tahap perendaman, air sisa perendaman dibuang. Air sisa pembuangan masih mengandung zat- zat organik seperti protein, lemak, dan suspensi padatan. Alternatif produksi bersih: Menggunakan air perendaman untuk pencucian, sehingga mengurangi penggunaan air. Alternatif ini dapat memanfaatkan air sisa perendaman sebesar 40 %.2. Pencucian kedelaiDeskripsi proses: pencucian dilakukan dengan cara mencuci kedelai dengan air sampai bersih, sehingga kotoran- kotoran yang ada pada kedelai hilang baik itu pasir, tanah dan lain- lain.Identifikasi terbentuknya Limbah: pada tahap ini, sisa air cuci masih mengandung sisa bahan kedelai, akan tetapi loss yang terjadi dianggap tidak signifikan, kotoran yang terbawa dalam air berisi komponen zat organik yang dapat menyebabkan air menjadi hitam dan berbau busuk jika dibiarkan. Pemborosan penggunaan air untuk pencucian kedelai.Alternatif produksi Bersih : Tahap pencucian kedelai tidak dilakukan dengan air mengalir, pencucian dilakukan didalam wadah atau bak secara bertahap. Air hasil pencucian pertama langsung dibuang. Sementara air pencucian kedua dapat digunakan kembali. Alternatif ini dapat mengurangi penggunaan air sebanyak 30 %.3. PenggilinganDeskripsi proses: Kedelai basah yang sudah ditiriskan kemudian digiling dengan mesin penggiling. Selama penggilingan berlangsung di tambahkan air sehingga memudahkan proses. Hasil gilingan berupa bubur kedelai yang ditampung dalam wadah.Identifikasi terbentuknya limbah: pada saat penggilingan ada kedelai yang tercecer, karena corong mesin penggiling yang kelebihan beban kedelai.Alternatif produksi bersih: Tidak memasukkan kedelai berlebih kedalam corong mesin penggiling. Alternatif ini dapat mengurangi ceceran sebesar 5%.4. Pemasakan Deskripsi proses: Bubur kedelai dimasukkan kedalam tangki pemasakan dan ditambahkan air dan diaduk terus- menerus. Pemaskan terus- menerus bertujuan untuk memperoleh ekstrak protein yang optimum, mencegah kegosongan dan meluapnya buih akibat naiknya suhu pemasakan.Identifikasi terbentuknya limbah: a. Pembakaran kayu dapat menyebabkan terjadinya jelaga pada langit atau genteng rumah.b. Air tercecer saat pengadukan.Alternatif produksi bersih:Menjaga kondisi api agar suhu pemasakn tidak terlalu tinggi, untuk menhindari melubernya bubur kedelai yang dimasak. Menghindari air yang tumpah saat pengadukan dengan pengadukan yang lebih hati- hati serta bahan yang tidak melebihi kapasitas tangki pemasakan. Alternatif ini dapat mengurangi air yang tumpah pada proses pemasakan sebesar 40%.5. Penyaringan Deskripsi proses: Ekstraksi dilakukan dengan menyaring bubur kedelai menggunakan kain blacu. Ampas tertinggal pada kain pres.Identifikasi terbentuknya limbah: Terbentuknya ampas tahu dari proses penyaringan. Apabila dibiarkan akan menimbulkan bau yang tidak enak, serta menjadi limbah semi padat yang mencemari lingkungan.Alternatif produksi bersih: Ampas tahu yang terbentuk bisa dijadikan pakan ternak, kerupuk ampas tahu, dll.6. PenggumpalanDeskripsi proses: Protein dalam susu kedelai selanjutnya diendapkan dengan penambahan koagulan ( bahan penggumpal). Identifikasi terbentuk limbah: Terbentuknya Whey sari kedelai yang tidak menggumpal yaitu cairan basi yang bisa menimbulkan pencemaran bau apabila Whey dibiarkan atau dibuang kesungai.Alternatif produksi bersih: a. pekerja berhati-hati pada saat memasukkan bibit/ biang ke dalam sari kedelai maupun pada saat melakukan pengadukan. Alternatif ini dapat mengurangi tumpahan sebesar 20%.b. Whey bisa dimanfaatkan menjadi nata de soya dengan perlakuan penambahan starter bakteri Acetobacter xylinum. Alternatif ini dapat mengurangi pembuangan whey sebesar 95 %.7. Pencetakan dan Pengepresan.Deskripsi Proses: Gumpalan yang terbentuk dimasukkan kedalam cetakan yang telah dialasi kain blacu, kemudian di- press sampai terbentuk tahu cetak.Identifikasi terbentuknya limbah: Limbah cair yang berasal dari proses pencetakan dan pengepresan tahu.Alternatif produksi bersih: Pembuatan selokan dekat dengan tempat pengepresan agar limbah cair tidak berceceran dilantai. Perhitungan NPO sebelum dan setelah diterapkan produksi bersih dapat dilihat pada Lampiran 4 b. Penggunaan EnergiIndustri tahu sebaiknya menggunakan gas sebagai bahan bakar sehingga emisi jelaga dan asap dapat diminimisasi. Tetapi jika masih menggunakan kayu bakar maka dibuat gudang atau tempat penyimpanan yang memadai agar kayu tidak terkena air hujan. Pekerja diharapkan menggunakan kayu bakar secara efisien. Selain itu, dapat pula memanfaatkan batok dan sabut kelapa sebagai bahan bakar tambahan agar menghemat penggunaan kayu.Penghematan listrik dapat dilakukan dengan mematikan lampu pada siang hari, jika ruang produksi cukup terang untuk mengurangi biaya listrik. Untuk efisiensi penggunaan air, dilakukan perbaikan kran dan pipa air yang bocor, dan tidak mengisi bak terlalu penuh. Menghemat penggunaan air pada proses pencucian sebaiknya dengan tidak menggunakan air langsung dari kran tetapi menggunakan sistem pencucian dengan bak. Kedelai dimasukkan ke dalam bak yang telah berisi air dan dipindahkan ke dalam bak selanjutnya. Sisa air pencucian kedua dapat dimanfaatkan untuk pencucian kedelai selanjutnya. Pekerja sebaiknya segera mematikan kran air apabila bak penampung telah penuh.c. Lay Out Pabrik dan PeralatanBangunan dan peralatan diusahakan didesain mudah dipelihara, selalu bersih dan siap dipakai sehingga lebih tahan lama dan tidak mudah aus. Efisiensi lay out pabrik dilakukan dengan penerapan GHK. Hal ini dilaksanakan dengan menyingkirkan barangbarang yang tidak di gunakan atau rusak, pengelompokkan barang, serta merawat peralatan produksi. Selain itu dilakukan pembersihan berkala pada lantai, langit-langit, dan dinding dari jelaga dan debu. d. Proses Produksi dan Kebiasaan PekerjaProsedur kerja dibuat tertulis agar memudahkan para pekerja dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga kegagalan produksi dapat dihindari jika pekerja terpaksa diganti karena sakit. Hal ini tentunya dapat menghindari hilangnya biaya pengeluaran tambahan. Meningkatkan kesadaran pekerja mengenai efisiensi produksi dan pentingnya penerapan produksi bersih. e. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerjaPeralatan yang tidak berhubungan dengan proses produksi sebaiknya dipindahkan dari ruang produksi agar karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan memperluas ruang produksi. Ruang produksi sebaiknya diatur dengan memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan oleh pekerja. Industri sebaiknya menyediakan obatobatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
4.2 Penerapan Sanitasi
Pengelolaan sanitasi dapat membantu untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada produk yang dihasilkan. Pengelolaan sanitasi dapat diterapkan pada beberapa aspek sanitasi, antara lain:4.2.1 Sanitasi Bahan1. Bahan baku dan bahan penolong yang digunakan aman dikonsumsi manusia.2. Bahan baku dibeli dari toko atau supplier yang dapat dipercaya.3. Menyiapkan tempat khusus untuk penyimpanan bahan baku dan bahan penolong yang bersih, jauh dari jangkauan anak-anak, tidak lembab dan kapasitas yang cukup.4. Periksa kondisi bahan yang dibeli untuk memastikan bahan yang dibeli memiliki mutu yang baik.5. Bahan penolong seperti asam cuka hendaknya dibeli dalam kondisi masih terkemas dalam kemasan asal. Perhatikan kondisi kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Kondisi kemasan harus bersih dan utuh (tidak terbuka).6. Air yang digunakan harus bersih.
4.2.2 Sanitasi Peralatan1. Peralatan yang tidak dibutuhkan dalam proses produksi tidak diletakkan di ruang produksi karena mengganggu estetika dan kenyamanan karyawan.2. Tidak menggunakan bak yang sudah mengelupas untuk pemansan. Bak untuk pemanasan sebaiknya menggunakan bak yang dilapisi keramik dan bak dibersihkan secara teratur. Menggunakan ember yang tahan panas pada proses penyaringan jika memungkinkan.3. Peralatan seperti ember, baskom, sendok, kain penyaringan dan mesin penggilingan harus selalu diperhatikan kondisi dan kebersihannya. Peralatan tersebut juga harus bebas karat, jamur, minyak, cat yang terkelupas, dan kotoran-kotoran lainnya (sisa pengolahan sebelumnya, dan lain lain).4. Wadah atau baskom dan peralatan lain yang mempunyai mulut besar dan terbuka harus dilindungi dari kontaminasi (terutama berupa jatuhan dari atap atau langit-langit ruangan.
4.2.3 Sanitasi Pekerja
1. Pekerja yang menangani pangan (kontak langsung dengan pangan di ruangan penanganan, penyimpanan, dan proses produksi) harus dalam kondisi sehat. Pekerja yang sakit atau baru sembuh dari penyakit-penyakit infeksi tidak boleh bekerja di ruang produksi2. Setiap pekerja harus menjaga kebersihan badannya dan mandi sebelum melakukan proses produksi3. Pekerja sebaiknya menggunakan pakaian pada saat bekerja. 4. Kuku pekerja harus selalu dalam keadaan bersih, dipotong pendek dan tidak memakai cat kuku. Keracunan pangan seringkali disebabkan oleh tangan kotor yang kontak dengan pangan atau peralatan pengolahan5. Pekerja diharuskan untuk mencuci tangan setiap kali akan memulai pekerjaan, setelah menggunakan toilet, menangani bahan mentah atau bahan kotor, dan pada kondisi lainnya yang dianggap perlu mencuci tangan6. Mencuci tangan harus dilakukan secara benar dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir (jika memungkinkan menggunakan air hangat)7. Pada saat sedang menangani pangan, pekerja tidak boleh melakukan kegiatan yang berpotensi untuk menyebabkan kontaminasi pada pangan seperti mengunyah, makan dan minum, merokok, bersin atau batuk ke arah pangan. Jika pekerja tidak bisa menahan batuk atau bersin yang datang secara tiba-tiba, maka mulut harus ditutup dengan tangan dan segera mencuci tangan sesudahnya8. Pekerja tidak mengenakan perhiasan (cincin, gelang, kalung), arloji, peniti atau perlengkapan lain yang jika terlepas dan jatuh ke dalam pangan yang diproduksi dapat menyebabkan pencemaran pada produk 4.2.4 Sanitasi Lingkungan Produksi
Beberapa aspek yang harus diperhatikan pada sanitasi lingkungan industri dapat dilihat pada Lampiran 5. Dari daftar checklist dapat diketahui bahwa terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki antara lain:1. Lingkungan Luar/ Halaman Perapihan dan penataan halaman luar industri dengan mengatur tumpukan kayu bakar di tempat yang terlindung dari potensi air hujan sehingga menghindari tumbuhnya jamur. Membersihkan halaman dari rumput liar dan genangan air serta menyarankan pekerja untuk membersihkan halaman seminggu sekali agar industri bebas dari serangga dan binatang pengerat yang dapat membawa kuman penyakit sehingga dapat mencemari produk tahu yang dihasilkan. Selain itu, menyediakan tempat sampah yang tertutup dan terpisah antara sampah organik dan anorganik. 2. Ruang dan Bangunan Bangunan merupakan satu kesatuan tempat yang terdiri dari dinding, lantai, atap/langit-langit, dan memiiki ruang. Ruang yang dimaksud adalah ruangan yang dilengkapi dengan ventilasi di dalamnya. Industri tahu Sumber Rezeki memiliki bangunan permanen namun tidak dirawat dengan baik. Pada lantai seharusnya dibuat saluran aliran limbah dan selokan agar air limbah mengalir lancar dan menghindari kondisi becek dan lantai licin. Atap pabrik dibersihkan dari jelaga, debu, dan sarang laba-laba. Kebocoran atap pabrik segera diperbaiki karena jika terjadi hujan makan air hujan akan masuk ke dalam pabrik dan menyebabkan genangan. Sebagian atap menggunakan atap yang transparan agar membantu pencahayaan pada proses produksi. Sebaiknya dipasang langit-langit untuk menghindari kontaminasi debu dari atap. Perawatan terhadap bangunan dilakukan dengan menjaga kebersihan pabrik dan melakukan piket kebersihan secara rutin. 3. Penyehatan Udara RuangDi lingkungan pabrik terdapat bau menyengat yang berasal dari limbah cair dan ampas tahu yang didiamkan. Gas atau bau yang ditimbulkan tidak hanya mencemari pabrik saja, tetapi mencemari rumah pemilik, tetangga dan sungai yang berada sekitar industri. Setelah dilakukan wawancara terhadap pekerja, mereka mengaku bahwa bau yang dihasilkan awalnya mengganggu namun karena sudah terbiasa maka bau tersebut tidak menjadi masalah lagi. Hal ini tentunya tetap berpengaruh terhadap kesehatan, sehingga sebaiknya pekerja menggunakan masker untuk melindungi pekerja dari bau dan debu yang berasal dari asap. Sebaiknya ampas tahu tidak disimpan lama didalam ruangan karena ampas tahu yang basi menjadi sumber bau busuk.4. Pengendalian Vektor PenyakitBerdasarkan hasil observasi, terdapat hewan ternak ayam pemilik dan tetangga yang berkeliaran di sekitar pabrik. Hewan ternak tersebut selalu diusir jika memasuki tempat produksi, tetapi kotorannya terlihat di halaman dan menimbulkan bau dan perasaan tidak nyaman. Tidak hanya hewan ternak, lalat pun banyak ditemukan karena sampah berserakan dan bau dari limbah.Industri seharusnya menyingkirkan hewan ternak di samping halaman yang berpotensi sebagai vektor penyakit, merapikan penyimpanan peralatan dan bahan baku agar tidak menjadi sarang tikus, membersihkan peralatan produksi dan peralatan makan segera setelah digunakan untuk menghindari adanya lalat dan kecoa, serta menghimbau pekerja untuk membuang ampas tahu dan sampah dalam waktu tidak lebih dari 24 jam.5. InstalasiKondisi instalasi listrik tidak memenuhi syarat estetika. Kabel-kabel listrik tidak tertata dengan rapi. Sebaiknya kabel-kabel listrik yang sudah tidak layak pakai diganti dengan yang baru untuk menghindari terjadinya hubungan arus pendek.6. Pemeliharaan ToiletKondisi yang terjadi di industri ini adalah toilet yang tersedia tidak memenuhi persyaratan. Industri dengan pekerja berjumlah 3 orang tersebut memiliki satu kamar mandi dan satu jamban yang bersatu dengan rumah pemilik, tidak ada wastafel, serta tidak memiliki peturasan. Pemeliharaan toilet dilakukan dengan penyediaan sikat dan desinfektan serta menyingkirkan baju yang tergantung di toilet karena dapat menjadi sarang pertumbuhan bakteri. Kebersihan toilet dijaga teratur agar tidak bau dan licin.
4.3 Pengolahan Limbah Padat
Limbah padat industri kecil tahu Sumber Rezeki mengandung bahan-bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak, serat kasar dan air. Bahan-bahan ini mudah terdegradasi secara biologis dan menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama menimbulkan bau busuk. Limbah padat tahu dapat diolah melalui beberapa cara, antara lain:1. Pembuatan Tepung Serat Ampas TahuAmpas tahu dapat dibuat tepung yang disebut dengan tepung serat ampas tahu. Bentuk tepung seperti ini mempunyai sifat tahan lama, dan dapat menjadi bahan baku pengganti tepung terigu atau tepung beras untuk berbagai makanan. Penambahan bahan lain disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan produk apa yang akan dibuat. Tepung serat ampas tahu dimanfaatkan untuk mengganti 2 (dua) hingga 3 (tiga) bagian dari tepung terigu yang diresepkan untuk membuat kue kering. Selain kue kering, tepung ini dapat pula digunakan untuk membuat lauk pauk seperti kerupuk ampas tahu, perkedel, resoles, kroket dan donat (KASWINARNI, 2007). 2. Pembuatan Tempe GambusMenurut SARWONO dan SARAGIH (2003), proses pembuatan tempe gambus sama dengan pembuatan oncom hanya saja dalam peragiannya digunakan ragi tempe. Bahan baku pembuatan tempe gembus adalah ampas tahu, tahap pertama ampas tahu direndam dalam air selama 12 jam. Setelah itu ampas tahu dipres dengan mesin pres sehingga airnya keluar. Tahap selanjutnya adalah fermentasi, ampas tahu yang sudah bersih, kemudian ditaburi dengan ragi tempe dan diaduk-aduk sampai rata. Setelah itu ampas tahu dimasukkan ke dalam plastik kemudian diletakkan di rak-rak agar terhindar dari serangga dan cahaya matahari langsung selama 4-5 hari hingga kapang yang terbentuk cukup tebal dan menutupi seluruh tempe gembus.3. Pakan TernakAmpas tahu selain dibuat tempe gembus juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Produk sampingan produksi tahu ini apabila telah mengalami fermentasi dapat meningkatkan kualitas pakan dan memacu pertumbuhan ayam pedaging. Namun karena kandungan air dan serat kasarnya yang tinggi, maka penggunaannya menjadi terbatas dan belum memberikan hasil yang baik. Guna mengatasi tingginya kadar air dan serat kasar pada ampas tahu maka dilakukan pengeringan.Limbah padat industri tahu tidak hanya berupa ampas tahu saja, tetapi juga kulit ari kedelai sisa proses perendaman. Kulit ari kedelai ini dapat dimanfaatkan untuk campuran pakan ternak. Pembuatannya cukup mudah, yaitu kulit ari yang sudah dibersihkan dari berbagai kotoran dicampur dengan air dan bahan campuran lain seperti bakatul dan tepung ikan. Kemudian diaduk rata dan siap diberikan ke ternak.
4.4 Pengolahan Limbah Cair
Pengolahan limbah cair dilakukan untuk menurunkan kadar bahan pencemar yang terkandung dalam air limbah agar dapat dibuang dengan aman ke lingkungan. Pengolahan ini meruapakan langkah akhir dalam upaya pengelolaan lingkungan setelah dilakukan upaya-upaya pencegahan dan minimisasi limbah melalui produksi bersih. Pengolahan dilakukan dalam suatu instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dibangun dengan memperhatikan segi biaya, ketersediaan lahan, sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana.Perencanaan dalam pengelolaan limbah cair harus memperhatikan kualitas dan kuantitas limbah yang akan diolah. Karakteristik limbah cair yang dihasilkan industri tahu Sumber Rezeki yaitu TSS sebesar 30 g/kg bahan baku kedelai, KOB 65 g/kg bahan baku kedelai dan KOK 130 g/kg bahan baku kedelai, pH 3,5-5 dan suhu operasi 30C - 35C (EMDI & BAPEDAL, 1994). Karakteristik limbah cair yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu di IKM Sumber Rezeki dapat dilihat pada Tabel 4.Tabel 4. Karakteristik Limbah Produk Hasil Olahan KedelaiBeban pencemaran limbah cair
Kuantitas Bahan baku (kedelai)Kuantitas limbah cairParameterKuantitas (jumlah)
LiteraturKonversiLiteraturKonversi
100 kg/hari20 L/ 1 kg kedelai2000 L/hari atau 2 m3 /hariTSS30000 mg/kg kedelai1500 mg/L
KOB65000 mg/kg kedelai3250 mg/L
COD130000mg/kg kedele6500 mg/L
pH3,5-5,5-
Sumber: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT DEVELOPMENT IN INDONESIA, 1994.
Karakteristik yang dihasilkan memiliki kadar bahan organik tinggi dengan nilai indikator BOD dan COD yang tinggi. Kadar padatan (TSS) dalam air cukup tinggi mennjukkan bahwa sebagian besar padatan tersebut merupakan bahan organik yang dapat diuraikan secara biologis dengan memanfaatkan mikroorganisme. Desain IPAL yang direncanakan meliputi tiga tahap pengolahan yaitu pengolahan pendahuluan, pengolahan pertama dan pengolahan kedua. Pengolahan pendahuluan bertujuan untuk menyisihkan kotoran dan benda padat yang ikut bersama aliran limbah. Pengolahan pertama melakukan bertujuan untuk Kadar padatan yang tinggi perlu diturunkan. Pengolahan tahap kedua berupa pengolahan biologi untuk menurunkan kadar bahan organik yang terkandung dalam limbah. Pengolahan biologi menggunakan sistem anaerob karena harga pengolahannya dapat dijangkau oleh industri kecil tahu Sumber Rezeki. Dari karakteristik limbah yang dihasilkan, maka IPAL industri tahu Sumber Rezeki direncanakan sebagai berikut:1. Bak Ekualisasi sekaligus Bak NetralisasiEkualisasi bukan merupakan suatu proses pengolahan tetapi merupakan suatu cara/teknik untuk meningkatkan efektivitas dari proses pengolahan selanjutnya. Keluaran dari bak ekualisasi adalah parameter operasional bagi unit pengolahan selanjutnya. Air limbah yang berasal dari industri tahu sebelum masuk ke bak ekualisasi (bak penampungan) harus melalui saringan (bar screen) terlebih dahulu untuk memisahkan kotoran-kotoran yang terikut, sehingga tidak mengganggu proses selanjutnya. Pada bak ekualisasi dapat pula dilengkapi dengan pembubuhan bahan kimia untuk mengkondisikan sifat air limbah yang diinginkan.
2 m Penggabungan bak ekualisasi dan netralisasi berdasarkan pertimbangan biaya pada industri kecil pembuatan tahu, Sehingga pada bak ekualisasi ini juga dilakukan penambahan kapur Ca(OH)2 untuk menetralkan karena air limbah tahu bersifat asam. Dosis kapur yang ditambahkan harus melalui pengujian jar test terlebih dahulu. Perhitungan jumlah kapur yang dibutuhkan dapat dilihat pada Lampiran 6. Fungsi lain dari bak ekualisasi adalah meratakan variabel dan fluktuasi dari beban organik untuk menghindari shock loading pada sistem pengolahan biologi sehingga perlu dilakukan pengadukan. Penurunan kadar COD mencapai 50% dan penurunan kadar TSS mencapai 20-30%. Perhitungan untuk bak ekualisasi sekaligus netralisasi dapat dilihat pada Lampiran 7. Ukuran bak ekualisasi dan netralisasi sapat dilihat pada Gambar 19.
0,3 m
1,5 m
2 m
Gambar 19. Bak Ekualisasi dan Netralisasi2. Bak anaerobPenguaraian polutan dilakukan oleh mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen bebas atau secara anaerob. Penguraian tersebut dapat berjalan walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Supaya proses pengolahan dapat berjalan lebih efektif, maka perlu dicari kondisi yang paling baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme dapat hidup dengan baik pada kondisi pH limbah cair sekitar 7 atau pada keadaan normal. Limbah cair industri tahu bersifat asam sehingga sebelum diolah perlu dinetralkan terlebih dahulu dengan kapur di bak ekualisasi agar kerja mikroorganisme berlangsung dengan baik.Bak ini dibuat dengan sistem kolam anaerob yaitu salah satu cara pengolahan limbah cair yang berlangsung tanpa adanya oksigen. Limbah pangan dengan volume kecil sampai sedang tetapi berkadar bahan organik tinggi dapat diolah dengan sistem ini termasuk tahu. Pada bak ini juga terjadi pengendapan oleh padatan tersuspensi. Sistem kolam ini harus didesain dan dioperasikan secara benar agar tidak mencemari air dan tanah di sekitarnya.
d= 2 mBeberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain dan mengoperasikan kolam ini adalah dinding kolam harus kedap air, saluran air masuk harus lebih tinggi dari saluran air keluar ( perbedaan tinggi minimum 3 cm), kolam harus tertutup dan dilengkapi lubang untuk pembuangan gas yang terbentuk, dan kolam harus dilengkapi lubang control. Pengolahan biologi yang dilakukan dengan kolam anaerob ini mampu menurunkan kandungan KOB, KOK, dan TSS mencapai 70% - 90% (JENIE dan RAHAYU, 1993). Perhitungan dan ukuran untuk bak anaerob dapat dilihat pada Lampiran 7 Gambar 20.
0,3 m
2m
Gambar 20. Bak Anaerob3. Bak StabilisasiBak stabilisasi untuk pengolahan limbah tahu ini dibuat tanpa aerasi dan dengan kedalaman maksimal 2 m dan waktu tinggal 5 20 hari. Pembuatan kolam ini didasarkan atas estimasi masih tingginya kandungan pencemar setelah pengolahan dengan kolam anaerob. Penurunan kadar polutan baik BOD, COD dan TSS bisa mencapai 90% (JENIE dan RAHAYU, 1993). Bak stabilisasi ini menggunakan eceng gondok dengan kepadatan 50 % . Semakin padat eceng gondok, maka efisiensinya semakin besar (SUARDANA, 2009). Perhitungan bak stabilisasi dapat dilihat pada Lampiran 7 Gambar 21.
4 m0,3 m
2 m
3 m Gambar 21. Bak Stabilisasi4. Bak KontrolAir limbah yang sudah dikelola terlebih dahulu di kontrol kualitas airnya sebelum dibuang ke sungai. Kontrol ini berguna untuk mengetahui pengaruh air limbah terhadap biota air. Pada bak kontrol terdapat ikan air tawar, apabila ikan yang berada di dalam kolam kontrol dapat bertahan hidup, berarti air limbah cukup baik dan dapat dibuang ke sungai. Namun apabila ikan mati, berarti proses yang berlangsung di IPAL ada yang kurang sempurna.Seluruh parameter pada limbah cair industri tahu yang telah diolah berada di bawah baku mutu lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 tahun 2008, tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan pengolahan kedelai, sehingga limbah industri tahu sudah layak dibuang ke lingkungan. Desain IPAL industri kecil tahu Sumber Rezeki yang direncanakan dapat dilihat pada Lampiran 8.40