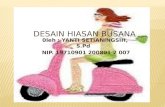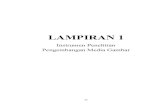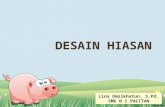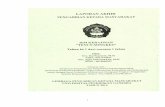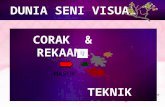BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Pembelajaran ...eprints.uny.ac.id/21885/2/BAB II.pdf ·...
Transcript of BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori 1. Pembelajaran ...eprints.uny.ac.id/21885/2/BAB II.pdf ·...

11
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan
a. Pembelajaran
Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru secara
terprogram dalam disain instruksional yang menciptakan proses interaksi
antara sesama peserta didik, guru dengan peserta didik dan dengan sumber
belajar. Pembelajaran bertujuan untuk menciptakan perubahan secara terus-
menerus dalam perilaku dan pemikiran siswa pada suatu lingkungan belajar.
Sebuah proses pembelajaran tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar.
Menurut Syaiful Sagala (2013:61) pembelajaran merupakan proses
komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik,
sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Sedangkan
menurut Dimyati dan Mudjiono (2013:157) pembelajaran adalah proses yang
diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar
bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan,
dan sikap. Menurut Zainal Arifin(2011:10) pembelajaran adalah suatu proses
atau kegiatan yang sistematis, dan sistemik yang bersifat interaktif dan
komunikatif antara pendidik (guru) dengan peserta didik, sumber belajar, dan
lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya
tindakan belajar peserta didik, baik di kelas maupun luar kelas, dihadiri guru
secara fisik atau tidak, untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan.
Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah
adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku

12
tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif),
keterampilan (psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif).
Belajar tidak hanya meliputi mata pelajaran, tetapi juga penguasaan,
kebiasaan, persepsi, kesenangan, kompetensi, penyesuaian sosial,
bermacam-macam keterampilan, dan cita-cita.
Dari beberapa pendapat tentang pembelajaran diatas dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi belajar
mengajar antara pendidik dengan peserta didik untuk memperoleh
pengetahuan, keterampilan, dan sikap baik di kelas maupun luar kelas untuk
menguasai kompetensi yang telah ditentukan.
Menurut Asep dan Abdul (2012:13-14) mengemukakan rancangan
pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Pembelajaran diselenggarakan dengan pengalaman nyata dan
lingkungan otentik.
2) Isi pembelajaran harus didesain agar relevan dengan karakteristik siswa.
3) Menyediakan media dan sumber belajar yang dibutuhkan.
4) Penilaian hasil belajar terhadap siswa dilakukan secara formatif sebagai
diagnosis untuk menyediakan pengalaman belajar secara
berkesinambungan dan dalam bingkai belajar sepanjang hayat(life long
contiuning education).
Berdasarkan penjelasan diatas, komponen pembelajaran dapat
diartikan sebagai seperangkat alat atau cara dari berbagai proses yang
kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sebuah pembelajaran
demi tercapainya suatu tujuan diantaranya, peserta didik, guru, tujuan
pembelajaran, materi/isi, metode, media pembelajaran, dan evaluasi. Oleh

13
karena itu pembelajaran menaruh perhatian pada ”bagaimana
membelajarkan siswa”, dan bukan pada”apa yang dipelajari siswa”. Dengan
demikian perlu diperhatikan bagaimana cara mengorganisasi sebuah
pembelajaran agar dapat dirancang dan direncanakan secara optimal untuk
memenuhi harapan dan tujuan.
b. Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bentuk satuan pendidikan
kejuruan sebagaimana yang ditengaskan dalam penjelasan Pasal 15
Sisdiknas N0.20 Tahun 2003 yang merupakan pendidikan menengah yang
mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
Menurut House Committee on Education and Labour (HCEL) dalam (Oemar
H.Malik,2003:94) bahwa: “Pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk
pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan, dan kebiasaan-
kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan
keterampilan”.Sementara Slamet (http://http:/konsep-pendidikan-
kejuruan.diakses tanggal 07/02/2015), menyatakan: ”Pendidikan kejuruan
adalah pendidikan untuk suatu pekerjaan atau beberapa jenis pekerjaan yang
disukai individu untuk kebutuhan sosialnya”.
Adapun tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan menengah
kejuruan menurut Sisdiknas N0.20 Tahun 2003 antara lain :
1) Tujuan umum
a) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peseta didik kepada Tuhan Yang
Maha Esa.

14
b) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan
bertanggung jawab.
c) Mengembangkan potensi peserta didik agar memililki potensi peserta
didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai
keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.
d) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap
lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan
lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif
dan efisien.
2) Tujuan khusus
a) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu
bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha
dan dunia industi sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan
kompetensi dan program keahlian yang dipilih.
b) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam
berkompetensi, beradaptasi dilingkungan kerja, dan mengembangkan
sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya.
c) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,
agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri
maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
d) Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi sesuai dengan
progam keahlian yang dipilih.

15
Dengan demikian, secara esensial dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran di sekolah menengah kejuruan memungkinkan untuk
keterlaksanaan pembekalan keterampilan pada para siswa. Keterampilan
inilah yang membedakan utama dengan sekolah menengah umum.
Kenyataannya, lulusan sekolah menengah kejuruan lebih siap di dunia kerja
dibandingkan lulusan sekolah umum.
2. Kompetensi Pola Dasar di SMK
a. Kompetensi Keahlian Busana Butik
Kompetensi diartikan sebagai kecapakan yang memadahi untuk
melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki ketrampilan dan kecakapan
yang disyaratkan (suhaenah Suparno,2001:27). Menurut Hamzah (2007:78)
kompetensi sebagai karakteristik yang menonjol dari seorang individu yang
berhubungan dengan kinerja atau superior dalam suatu pekerjaan atau
situasi. Sedangkan menurut Robert A. Roe (2001:73) kompetensi dapat
digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas, peran
atau pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai pribadi, dan
kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang
didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sebagai
kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas mengintegrasikan
pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk membangun kinerja yang
didasarkan pada pengalaman serta pembelajaran yang dilakukan. Profil
kompetensi lulusan SMK terdiri dari kompetensi umum, dan kompetensi
kejuruan. Masing-masing telah mengacu pada tujuan pendidikan nasional,
sedangkan kompetensi kejuruan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja

16
Nasional Indonesia (SKKNI). Setiap keahlian mempunyai tujuan untuk
menyiapkan peserta didik bekerja dalam bidang tertentu yang sudah dipilih
dan digeluti selama pendidikan.
SMK terbagi beberapa bidang keahlian, salah satunya adalah bidang
keahlian Busana Butik.Secara khusus tujuan program keahlian busana butik
adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan
sikap yang berkompeten. Pada bidang keahlian busana butik diperlukan
target pencapaian kompetensi (TPK) untuk mempertimbangkan tingkat
kemampuan rata-rata peserta didik serta sumber daya pendukung dalam
penyelenggaraan pembelajaran. Untuk mencapai hasil target pencapaian
kompetensi ini program keahlian busana butik kemudian membagi menjadi
beberapa standar kompetensi (SK) yang kemudian dikerucutkan pada
kompetensi dasar (KD). Berikut tabel 1 yang menjelaskan standar
kompetensu dan kompetensi dasar pada bidang keahlian busana butik
berdasarkan Spectrum 2009 :
Tabel 1. Kompetensi Kejuruan Bidang Keahlian Busana Butik
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
1) Menggambar
busana
(fashion drawing)
a) Memahami bentuk bagian-bagian busana
b) Mendiskripsikan bentuk proporsi tubuh anatomi
beberapa tipe tubuh manusia
c) Menerapkan teknik pembuatan desain busana
d) Penyelesaian pembuatan gambar busana
2) Pola Dasar
(Pattern making)
a) Menguraikan macam-macam teknik pembuatan pola
(teknik konstruksi dan teknik drapping)
b) Membuat pola
3) Membuat busana
wanita
a) Mengelompokkan Macam-Macam Busana Wanita
b) Memotong bahan
c) Membuat krah wanita
d) Menyelesaikan busana wanita dengan jahitan tangan
e) Menghitung harga jual
f) Melakukan pengepresan

17
4) Membuat busana
pria
a) Mengelompokkan macam-macam busana pria
b) Memotong bahan
c) Membuat krah pria
d) Menyelesaikan busana pria dengan jahitan tangan
e) Menghitung harga jual
f) Melakukan pengepresan
5) Membuat busana
anak
a) Mengelompokkan macam-macam busana anak
b) Memotong bahan
c) Membuat krah anak
d) Menyelesaikan busana dengan jahitan tangan
e) Menghitung harga jual
f) Melakukan pengepresan
6) Membuat busana
bayi
a) Mengelompokkan busana bayi
b) Memotong bahan
c) Menyelesaikan busana dengan jahitan tangan
d) Menghitung harga jual
e) Melakukan pengepresan
7) Memilih bahan baku
busana
a) Mengidentifikasi jenis bahan utama dan bahan pelapis
b) Mengidentifikasi pemeliharaan bahan tekstil
c) Menentukan bahan pelengkap
8) Membuat hiasan
pada busana
a) Mengidentifikasi hiasan busana
b) Membuat hiasan pada kain atau bahan
9) Mengawasi mutu
busana
a) Memeriksa kualitas bahan utama
b) Memeriksa kualitas bahan pelengkap
c) Memeriksa mutu pola
d) Memeriksa mutu potongMemeriksa hasil jahit
b. Kompetensi Pola Dasar
Pola busana merupakan suatu sistem dalam membuat busana yang
digambar dengan benar berdasarkan ukuran badan seseorang yang diukur
secara cermat baik melalui pola konstruksi, pola standar,dan pola
draping(Ernawati,2008:246). Sedangkan menurut Ida saraswati (2013:11)
pola atau patern dalam menjahit adalah potongan kain atau kertas yang
mengikuti ukuran desain kostum bentuk badan dan model tertentu sebagai
contoh untuk membuat baju. Menurut Novi kurnia (2012:18) pola adalah
beberapa potongan bahan(kain, kertas, karton, dan kertas mika) yang
digunakan sebagai contoh membuat busana pada saat kain busana digunting
berdasarkan ukuran badan pemakai.

18
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pola
busana adalah potongan kertas untuk memotong kain sesuai dengan ukuran
badan. Pola terdiri dari berbagai bagian, seperti pola badan, pola lengan,
pola krah, pola rok, pola celana, yang masing-masing pola tersebut dapat
dirubah sesuai model yang dikehendaki.
Ada beberapa macam pola yang dapat digunakan dalam membuat
busana (Ernawati, 2008:246) yaitu :
1) Pola kontruksi Pola konstruksi adalah pola dasar yang dibuat berdasarkan ukuran
badan sipemakai, dan digambar dengan perhitungan secara matematika sesuai dengan sistem pola konstruksi masing-masing. Pembuatan pola konstruksi lebih rumit dari pada pola standar disamping itu juga memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi hasilnya lebih baik dan sesuai dengan bentuk tubuh sipemakai. Ada beberapa macam pola konstruksi antara lain : pola sistem Dressmaking, pola sistem So-en , pola sistem Charmant, pola sistem Aldrich, pola sistem Meyneke dan lain-lain sebagainya. 2) Pola standar
Pola standar adalah pola yang dibuat berdasarkan daftar ukuran umum atau ukuran yang telah distandarkan, seperti ukuran Small (S), Medium (M), Large (L), dan Extra Large (XL). Pola standar di dalam pemakaiannya kadang diperlukan penyesuaian menurut ukuran sipemakai. Jika sipemakai bertubuh gemuk atau kurus, harus menyesuaikan besar pola, jika sipemakai tinggi atau pendek diperlukan penyesuaian panjang pola.
Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini difokuskan pada
pembuatan pola dasar rok secara konstruksi dengan Sistem Cuppens Geurs.
Menurut Ida Saraswati (2013:76) rok adalah bagian dari pakaian yang biasa
dipakai mulai dari pinggang melewati panggul sampai kebawah sesuai
keinginan. Biasanya rok dipakai sebagai pasangan blus. Desain rok cukup
bervariasi baik dilihat dari ukuran panjang rok maupun dari siluet rok.
Menurut Novi Kurnia dan Mia Siti (2013:27) rok adalah bagian busana yang
dipakai dibagian bawah dengan mengukur dari garis lingakar pinggang,
lingkar panggul, tinggi panggul panjang rok, dan panjang sisi rok. Sedangkan
menurut Ernawati,dkk (2008:240) rok adalah bagian pakaian yang berada

19
pada bagian bawah badan. Umumnya rok dibuat mulai dari pinggang sampai
ke bawah sesuai dengan model yang diinginkan. Berdasarkan ukuran rok,
rok dapat dikelompokkan atas rok mini, rok kini. rok midi, rok maxi dan
longdress.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rok adalah
berupa bagian pakaian luar yang bebas tergantung dari pinggang ke bawah
dengan mengambil ukuran lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi panggul,
panjang rok, dan panjang sisi. Dibawah ini merupakan gambar pola dasar
rok:
Gambar 1. Pola Dasar Rok Skala 1:8
Sistem Cuppens Geurs
Dalam membuat pola macam-macam rok diperlukan pola dasar rok
yang kemudian dikembangkan sesuai dengan disain rok yang diinginkan.
Menurut Sri Wening (1996: 47) aspek penilaian pembuatan pola terdiri
atas :
1) Persiapan (kelengkapan alat dan bahan).

20
2) Proses (faham gambar, ketepatan ukuran, ketepatan sistem pola,
merubah model).
3) Hasil (ketepatan tanda pola, gambar pola, kerapian dan kebersihan).
Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini difokuskan pada pembuatan
pola dasar rok secara konstruksi yang dikerjakan siswa yaitu persiapan,
proses, dan hasil unjuk kerja.
Adapun aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah:
1) Persiapan
Aspek persiapan yang dinilai adalah kelengkapan alat dan bahan. Untuk alat
yaitu mesin disediakan oleh pihak sekolah, jadi peneliti menilai kelengkapan
alat dan bahan sebagai berikut :
Alat :
a) Penggaris
b) Skala
c) Pensil
d) Penghapus
e) Pensil merah biru
Bahan :
a) Buku kostum/buku pola
b) Kertas merah biru
c) Kertas payung
2) Proses
Ketepatan ukuran pola menjadi bagian yang sangat penting dalam
proses pembuatan pola, apabila terjadi kesalahan pengukuran maka akan
berpengaruh besar pada busana yang akan dijahit. Untuk menghindari itu,

21
maka pada proses pembuatan pola apabila selesai perlu pengecekan pola
dengan ukuran.
3) Hasil
a) Kelengkapan tanda pola
b) Tanda-tanda pola adalah beberapa macam garis warna yang dapat
menunjukkan keterangan dan gambar pola. Macam-macam tanda pola
antara lain :
: Letak arah serat vertikal, atau horizontal
: Potong kain serong
: Garis pola asli dengan warna hitam
: Garis lipatan
: Garis penyelesaian
: Garis merah untuk pola bagian muka
: Garis biru untuk pola bagian belakang
: Garis lipatan/ploi
: Garis siku 90°
Gambar 2 . Macam-Macam Tanda Pola(Ida saraswati,2013:25-26)
c) Kerapian dan kebersihan
Apabila pola dibuat dengan rapi dan bersih maka dapat mudah
terbaca atau lebih mudah memahami bagian-bagian pola seperti garis pola
tegas, garis bantu pola.
Pada hasil pembuatan pola, penilaian dilakukan pada ketepatan dan
kelengkapan tanda-tanda pola, yakni sesuai dengan fungsi tanda pola.

22
Keluwesan bentuk pada gambar polarok yakni pada garis lengkung rok.
Kebersihan serta kerapihan pola, dalam arti apabila pola dibuat dengan rapi
dan bersih maka dapat mudah terbaca atau lebih mudah memahami bagian-
bagian pola dan memperjelas saat memotong pola sampai merader.
3. Hasil Belajar
Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku
mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris (Nana Sudjana, 2011:3).
Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2013:3) hasil belajar merupakan
hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Menurut Asep
dan Abdul(2012:14) hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan
perilaku cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif,dan psikomotor dari
proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu.
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
merupakan hasil atas pencapaian belajar melalui perlakuan yang
mencangkup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang dilakukan dalam
waktu tertentu.
Menurut Nana Sudjana (2011:23-31) ada beberapa unsur-unsur yang
terdapat dalam ketiga aspek hasil belajar yaitu :
a. Tipe hasil belajar bidang kognitif.
Dalam tipe hasil belajar bidang kognitif dapat dibagi menjadi
beberapa tipe yaitu :
1) Tipe hasil belajar pengetahuan(knowledge).
2) Tipe hasil belajar pemahaman.
3) Tipe hasil belajar aplikasi.

23
4) Tipe hasil belajar analisis.
5) Tipe hasil belajar sintesis.
6) Tipe hasil belajar evaluasi.
b. Tipe hasil belajar bidang afektif.
Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai.
c. Tipe hasil belajar psikomotor.
Hasil belajar psikomotor tampak pada bentuk ketrampilan (skill), dan
kemampuan bertindak individu (seseorang).
Sedangkan menurut Agus Suprijono (2010:6) klasifikasi hasil belajar
secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga ranah antara lain :
a. Ranah kognitif
Ranah ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menguasai
pemahaman konsep atau isi bahan pembelajaran yang telah diterimanya.
Dominan kognitif antara lain:Pengetahuan, ingatan, memahami, menjelaskan,
contoh, menerapkan, menganalisis, mengorganisasikan, merencanakan, dan
menilai.
b. Ranah afektif
Ranah afektif berkenaan dengan sikap, minat, nilai, dan konsep diri.
Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku,
menghargai seperti perhatian terhadap pelajaran, disiplin, menghargai orang
lain, dan lain-lain. Dominan ranah afektif meliputi: menerima, menjawab,
menilai, pengorganisasian, dan pengkarakteran.
c. Ranah psikomotor
Hasil belajar pada ranah psikomotor tampak dalam bentuk
keterampilan (skill), dan kemampuan bertindak individu. Ranah psikomotor

24
terdiri dari empat dominan yaitu: gerakan, manipulasi, komunikasi, dan
menciptakan.
Sedangkan untuk mencapai hasil belajar pada pencapaian tujuan
pembelajaran di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi
hasil belajar itu sendiri. Sugihartono, dkk. (2007:76-77), menyebutkan faktor-
faktor yang mempengaruhi hasil belajar, sebagai berikut:
a. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang
belajar. Faktor internal meliputi: faktor jasmaniah dan faktor psikologis.
b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal
meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.
Sedangkan menurut Syaiful Bahri dan Aswan Zain (2002:120), yang
menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil
antara lain:
a. Daya serap terhadap pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi,
baik secara individu maupun kelompok.
b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran instruksional khusus
(TIK) telah dicapai siswa, baik secara individu maupun kelompok.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil
yang dicapai siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang tampak dari
hasil evaluasi pada awal dan akhir pembelajaran. Semakin baik proses
pembelajaran dan aktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, maka
seharusnya hasil belajar yang diperoleh siswa akan semakin tinggi sesuai
dengan tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Sehingga tujuan pendidikan
dalam tiga bidang yakni bidang kognitif (penguasaan intelektual), bidang
efektif (berhubungan dengan sikap dan nilai), dan bidang psikomotor

25
(kemampuan/ketrampilan/berperilaku) dapat dicapai dengan hasil yang baik.
Dan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di atas,
peneliti menggunakan faktor eksternal berupa penggunaan model
pembelajaran kooperatif STAD.
Pada prinsipnya pengungkapan hasil belajar meliputi segenap ranah
psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar
siswa. Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa
adalah mengetahui garis besar indikator dikaitkan dengan jenis prestasi yang
ingin diukur. Berikut adalah tabel jenis, indikator, dan cara evaluasi prestasi
menurut Muhibbin Syah (2007:151) :
Tabel 2. Jenis, Indikator, dan Cara Evaluasi Prestasi
Ranah/Jenis Prestasi Indikator Cara Evaluasi
a. Ranah Kognitif
1) Pengamatan 1) Dapat menunjukkan
2) Dapat membandingkan
3) Dapat menghubungkan
1) Tes lisan
2) Tes tulis
3) Observasi
2) Ingatan 1) Dapat menyebutkan
2) Dapat menunjukkan
kembali
1) Tes lisan
2) Tes tulis
3) Observasi
3) Pemahaman 1) Dapat menjelaskan
2) Dapat mendefinisikan
dengan lisan sendiri
1) Tes tulis
2) Tugas
4) Penerapan 1) Dapat memberikan contoh
2) Dapat menggunakan
secara tepat
1) Tes tulis
2) Tugas
5) Analisis (pemeriksaan
dan pemilihan secara
teliti)
1) Dapat menguraikan
2) Dapat mengklasifikasikan/
memilah-milah
1) Tes tulis
2) Tugas
6) Sintetis (membuat
paduan baru dan
utuh)
1) Dapat menghubungkan
2) Dapat menyimpulkan
3) Dapat melealisasikan
(membuat prinsip umum)
1) Tes tulis
2) Tugas

26
Ranah/Jenis
Prestasi
Indikator Cara Evaluasi
b. Ranah Afektif
1) Penerimaan 1) Menunjukkan sikap
menerima
2) Menunjukkan sikap
menolak
1) Tes sikap
2) Tes tulis
3) Observasi
2) Sambutan 1) Kesediaan
berpartisipasi/terlibat
2) Kesediaan memanfaatkan
1) Tes sikap
2) Tugas
3) Observasi
3) Apresiasi (sikap
menghargai)
1) Menganggap penting dan
bermanfaat
2) Menganggap indah dan
harmoni
1) Tes sikap
2) Tugas
3) Observasi
4) Internalisasi
(pendalaman)
1) Mengakui dan meyakini
2) Mengingkari
1) Tes sikap
2) Tugas
3) Observasi
5) Karakteristik
(penghayatan)
1) Mengakui dan meyakini
2) Mengingkari
1) Tes lisan
2) Tes tulis
3) Observasi
c. Ranah psikomotor
1) Keterampilan
bergerak dan
bertindak
1) Mengkoordinasikan gerak,
mata, tangan, kaki, dan
anggota tubuh lainnya.
1) Observasi
2) Tes
tindakan
2) Kecakapan
ekspresi verbal
dan non verbal
1) Mengucapkan
2) Membuat mimik dan gerak
jemari
1) Observasi
2) Tes lisan
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa cara mengevaluasi
dipengaruhi oleh indikator dan ranahnya. Misalnya pada ranah kognitif, jika
ingin mengetahui kemampuan siswa dalam pengamatan, indikator dapat
menunjukkan dengan evaluasi lisan, sedangkan untuk menilai siswa dalam
membandingkan dapat dilakukan dengan evaluasi tes, dan untuk mengetahui
apakah siswa dapat menghubungkan siswa dapat dilakukan dengan evaluasi
observasi.

27
4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams-Achievement
Division (STAD)
a. Pembelajaran Kooperatif
Robert E. Slavin (2005:3) menjelaskan bahwa pembelajaran
kooperatif adalah model pembelajaran dimana siswa akan duduk bersama
dalam kelompok untuk menguasai materi yang disampaikan oleh guru.
Menurut Artz dan Newman (Miftahul Huda,2013:32) pembelajaran koorperatif
merupakan kelompok kecil pembelajar / siswa yang bekerja sama dalam satu
tim untuk mengatasi suatu masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau
mencapai satu tujuan bersama. Menurut Isjoni (2010:14), pembelajaran
kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai
anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda.
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa
berupa pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan
siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar anggota lainnya dalam
kelompok tersebut melalui belajar secara kelompok, peserta didik
memperoleh kesempatan untuk saling berinteraksi dengan teman-temannya.
Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif (Asep Jihad,2012:30) antara lain:
a. Untuk menuntaskan materi materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif.
b. Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah.
c. Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku, budya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar dalam tiap kelompokpun terdiri dari suku, budya, jenis kelamin yang berbeda pula.
d. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan.

28
Sedangkan menurut Isjoni (2010:27) ada beberapa ciri-ciri dari
pembelajaran kooperatif adalah:
a. Setiap anggota memiliki peran.
b. Terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa.
c. Setiap anggota kelompok bertanggungjawab atas belajarnya, dan juga
teman-teman sekelompoknya.
d. Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan personal
kelompok, dan
e. Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan.
Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pembelajaran
kooperatif siswa harus memiliki peran didalam kelompok untuk membangun
sebuah kerjasama, dan guru hanya mampu mengembangkan keterampilan
siswa dengan memberikan penghargaan untuk memberikan semangat siswa.
Menurut Sadker dalam Miftahul huda (2011:66) menjabarkan
beberapa manfaat pembelajaran kooperatif. Selain itu, meningkatkan
keterampilan kognitif dan afektif siswa, pembelajaran kooperatif juga
memberikan manfaat-manfaat besar lain seperti berikut ini :
a. Siswa yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif akan
memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi;
b. Siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki
sikap harga-diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk
belajar;
c. Dengan pembelajaran kooperatif, siswa menjadi lebih peduli pada teman-
temannya, dan di antara mereka akan terbangun rasa ketergantungan
yang positif (interdependensi positif) untuk proses belajar mereka nanti;

29
d. Pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan siswa terhadap
teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan etnik yang
berbeda-beda.
Prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif (Muslimin dkk, 2000:46)
yaitu :
a. Setiap anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya.
b. Setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama.
c. Setiap anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggungjawab yang sama di antara anggota kelompoknya.
d. Setiap anggota kelompok (siswa) akan dievaluasi. e. Setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan
membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya.
f. Setiap anggota kelompok (siswa) akan diminta untuk mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.
Sedangkan menurut Nur Asma (2006:14-16) menyatakan ada 5
prinsip dalam cooperative learning, yaitu :
a. Belajar siswa aktif yaitu berpusat pada siswa, yang dominan dilakukan
siswa dalam membangun dan menemukan pengetahuan dengan belajar
bersama-sama secara berkelompok.
b. Belajar bekerjasama dalam kelompok untuk membangun pengetahuan
yang sedang dipelajari. Prinsip pembelajaran inilah yang melandasi
keberhasilan penerapan model pembelajaran kooperatif
c. Belajar patrisipatorik yaitu siswa belajar dengan melakukan sesuatu
(learning by doing) secara bersama-sama untuk menemukan dan
membangun pengetahuan yang menjadi tujuan pembelajaran.
d. Mengajar reaktif yaitu guru perlu menciptakan strategi yang tepat agar
seluruh siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Guru harus

30
mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik
serta dapat meyakinkan siswanya akan manfaat dari pembelajaran
tersebut.
e. Pembelajaran yang menyenangkan dan tidak ada lagi suasana
pembelajaran yang membuat siswa merasa tertekan.
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar berupa
prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan pengembangan
keterampilan sosial. Untuk mencapai hasil belajar itu model pembelajaran
kooperatif menuntut kerjasama dan interdependensi peserta didik dalam
struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur reward-nya. Struktur tugas
berhubungan dengan bagaimana tugas yang diberikan dapat diorganisir
dengan baik oleh peserta didik. Struktur tujuan dan reward mengacu pada
kerja sama dalam kelompok atau kompetisi yang dibutuhkan untuk mencapai
tujuan yang diinginkan maupun reward.
Menurut Robert Slavin (2005:11-26), ada beberapa macam-macam
metode pembelajaran Kooperatif antara lain :
a. Student Teams-Achievement Division (STAD)
Dalam STAD, para siswa dibagi dalam tim belajar secara heterogen
yang terdiri dari empat sampai lima siswa dengan berbeda-beda tingkat
kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etnicnya. Model ini menuntut
siswa untuk bekerjasama dalam satu tim sampai seluruh anggota tim dapat
fokus pada pemaknaan bukan penghafalan dalam belajar materi
pelajaran.Model ini juga mengadakan reward atau penghargaan untuk

31
mendorong siswa bersaing meningkatkan prestasi. Kelebihan model STAD
ini dapat dipakai pada mata pelajaran teori maupun praktikum.
b. Team Game Tournament (TGT)
Para siswa ditugaskan untuk membaca sub bab, buku kecil, atau
materi lain yang bersifat terperinci. Dari pembagian tim, setiap anggota tim
ditugaskan secara acak untuk menjadi “ ahli “ dalam aspek tertentu dari tugas
membaca tersebut, lalu mereka kembali kepada timnya untuk mengajar topik
mereka kepada teman satu timnya. Kelebihan pada model ini dapat
diterapkan pada pelajaran langsung praktikum.
c. Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)
CIRC merupakan program komperhensif untuk mengajarkan
membaca dan menulis. Para siswa ditugaskan untuk berpasangan dua siswa
dalam tim mereka untuk belajar dalam serangkaian kegiatan yang bersifat
kognitif. Penghargaan untuk tim dan sertifikat akan diberikan kepada tim
berdasarkan kinerja rata-rata dari semua anggota tim dalam semua kegiatan
membaca dan menulis. Model ini cocok untuk membimbing pada sekolah
jurusan bahasa.
d. Team Assisted Individualization (TAI)
Model pembelajaran kooperatif tipe TAI merupakan strategi pembelajaran
yang berpusat pada siswa. Pada model pembelajaran kooperatif ini, siswa
biasanya belajar menggunakan LKS (lembar kerja siswa) secara
berkelompok. Mereka kemudian berdiskusi untuk menemukan atau
memahami konsep-konsep. Setiap anggota kelompok dapat mengerjakan
satu persoalan (soal) sebagai bentuk tanggungjawab bersama. Penerapan
model pembelajaran kooperatif TAI lebih menekankan pada penghargaan

32
kelompok, pertanggungjawaban individu dan memperoleh kesempatan yang
sama untuk berbagi hasil bagi setiap anggota kelompok. Model ini juga dapat
diterapkan pada pelajaran langsung praktikum.
e. Group Investigation
Group Investigation merupakan perencanaan pengaturan kelas yang
umum di mana para siswa bekerja dalam kelompok kecil mengunakan
pertanyaan koorperatif, diskusi kelompok, serta perencanaan dan proyek
koorperatif. Dalam metode ini kelemahannya, para siswa dibebaskan dalam
membentuk kelompoknya sendiri yang terdiri dari dua orang sampai dengan
enam orang anggota. Sehingga apabila dalam satu tim tingkat
kemampuannya rendah maka yang ada tingkat prestasi siswa akan turun,
dan konsentrasi siswa saat mengerjakan materi kurang maksimal.
f. Learning Together
Metode ini melibatkan siswa yang dibagi dalam kelompok yang terdiri atas
empat atau lima kelompok dengan latar belakang berbeda mengerjakan
lembar tugas. Kelompok-kelompok ini menerima satu lembar tugas, dan
menerima pujian dan penghargaan berdasarkan hasil kerja kelompok. Tetapi,
model ini hanya cocok diterapkan di kelas tinggi karena lebih didominasi
kegiatan diskusi dan presentasi. Memakan waktu cukup lama dan sedikit
membosankan serta guru tidak bisa melihat kemampuan tiap-tiap siswa
karena mereka bekerja dalam kelompok.
Dari pendapat diatas maka pada penelitian ini peneliti meneliti
memilih model pembelajaran koopertatif tipe Student Teams Achievement
Division (STAD) dikarenakan model pembelajaran didalam STAD, para siswa
dibagi dalam tim belajar yang terdiri atas empat kelompok yang berbeda-

33
beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etnicnya. Model
pembelajaran STAD ini juga dapat diterapkan pada mata pelajaran produktif
yang mengacu pada materi teori seperti mata pelajaran pola dasar. Dengan
begitu diharapkan ada kerjasama yang baik dalam sebuah tim untuk
mendapatkan sebuah prestasi disetiap materi yang disampaikan.
b. Model Pembelajaran Koorperatif Tipe STAD
Dalam penelitian ini menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe
Student Teams Achievement Division (STAD) yang akan di implementasikan
di kelas. Menurut Robert Slavin (2005:11) Student Teams Achievement
Division (STAD) merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling
sederhana, dan banyak digunakan dalam pembelajaran kooperatif. Menurut
Isjoni (2007:74) merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan
pada adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi
dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai
prestasi yang maksimal. Menurut Trianto (2010:68) pembelajaran kooperatif
tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) merupakan salah satu
tipe dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-
kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara
heterogen.
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, disimpulkan bahwa
pengertian model pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement
Division (STAD) adalah model pembelajaran dimana siswa belajar dalam
kelompok-kelompok yang heterogen (tingkat prestasi, jenis kelamin, budaya,
dan suku) yang terdiri dari 4-5 siswa. Kegiatan pembelajarannya diawali
dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan

34
kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Ciri terpenting dalam model
pembelajaran kooperatif STAD adalah kerja tim.
Menurut Agus Suprijono (2009:65) langkah-langkah pengajaran
STAD ini terdiri dari enam fase seperti yang disajikan pada Tabel berikut:
Tabel 3.Fase-Fase Pembelajaran Tipe STAD
Fase Kegiatan Guru
Fase I Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa
Menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar
Fase II Menyajikan atau menyampaikan informasi
Menyajikan informasi pada siswa dengan jalan mendemonstrasikan atau lewat bahan bacaan
Fase III Mengorganisasikan siswa pada kelompok-kelompok belajar
Menjelaskan pada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien
Fase IV Membimbing kelompok bekerja dan belajar
Membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka bekerja dan belajar
Fase V Evaluasi
Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah diajarkan dan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya
Fase VI Memberikan penghargaan
Mengali cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu
a. Fase Pertama
Pada fase ini guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa siap dalam mengikuti
pembelajaran dengan sungguh-sungguh agar mencapai hasil belajar yang
baik.

35
b. Fase Kedua
Pada fase ini guru menyampaikan materi pelajaran dengan jalan
mendemostrasikan melalui bahan bacaan maupun media pembelajaran.
c. Fase Ketiga Fase
kedua ini guru membagi tim yang terdiri dari empat atau lima siswa
yang mewakili seluruh bagian kelas dalam hal kinerja akademik, jenis
kelamin, ras maupun etnis. Fungsi utama dari tim ini adalah semua anggota
tim harus benar-benar belajar, khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan
anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dnegan baik. Tim adalah yang
paling penting dalam STAD.
d. Fase Keempat
Pada fase ini guru perlu mendampingi tim-tim belajar, mengingat
tentang tugas-tugas yang dikerjakan siswa dan waktu yang dialokasikan.
Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, pengarahan, atau
meminta beberapa siswa mengulangi hal yang sudah ditunjukkan. Sebelum
siswa diberikan tugas secara kelompok guru memberikan penjelasan materi
didepan kelas.
e. Fase Kelima
Guru melakukan evaluasi dengan menggunakan stratergi evaluasi
konsisten dengan tujuan pembelajaran.
f. Fase Keenam
Setelah evaluasi dilaksanakan maka guru mempersiapkan struktur
reward yang akan diberikan kepada siswa. Struktur reward kooperatif
diberikan kepada siswa meskipun anggota timnya harus saling bersaing.

36
Sedangkan menurut Robert Slavin (2010:134) Adapun sintak dari
metode pembelajaran kooperatif tipe Students Teams Achievement Divisions
(STAD) adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Sintak Pembelajaran STAD
Fase-Fase Perlakuan Guru
Fase1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik
Menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik siap belajar.
Fase 2. Menyajikan atau
menyampaikan informasi Memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari
Fase 3. Mengondisikan kelas dan membagi kelompok secara heterogen
Membagi kelompok dengan perbedaan jenis, kepandaian
Fase 4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar
Mengamati, memberikan motivasi dan membantu siswa apabila kesulitan.
Fase 5. Mengevaluasi dan memberikan penghargaan
Menguji pengetahuan peserta didik mengenai berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.
Menurut Robert Slavin (2010:138) langkah-langkah pembelajaran
kooperatif tipe Students Teams Achievement Divisions (STAD) adalah
sebagai berikut :
a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa.
b. Guru membentuk beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari empat
sampai lima siswa dengan kemampuan yang heterogen.
c. Guru menyampaikan materi pelajaran secara garis besar.
d. Bahan atau materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok
untuk mencapai kompetensi dasar.
e. Guru memanggil salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya.
f. Perwakilan siswa dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.

37
g. Guru memfasilitasi siswa dalam bentuk rangkuman, mengarahkan, dan
memberikan penegasan pada materi pelajaran yang telah dipelajari.
h. Guru memberiakan tes/kuis kepada siswa secara individu.
i. Guru memberikan pujian/penghargaan kepada kelompok berdasarkan
perolehan nilai hasil belajar individu dari skor kuis berikutnya.
Keunggulan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe
STAD (Robert Slavin,2010:139) adalah :
a. Keunggulan 1) Dapat diterapkan pada setiap mata pelajaran. 2) Setiap siswa dituntut untuk selalu siap dan bertanggung jawab penuh
terhadap suatu konsep ataupun masalah yang diajukan oleh guru. 3) Siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi dapat membantu siswa
yang memiliki kemampuan akademik kurang tinggi. b. Kelemahan 1) Siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi dapat mendominasi
kelompoknya. 2) Dalam penentuan anggota kelompok yang akan mempresentasikan hasil
diskusinya, dimungkinkan siswa yang mememiliki kemampuan akademik tinggi dapat mendominasi diskusi/presentasi kelas.
Dengan memahami dan mengetahui model pembelajaran
cooperative learning model STAD pada teori yang sudah dikemukakan pada
beberapa ahli, maka peneliti menggunakan model pembelajaran cooperative
learning model STAD menggunakan sintak STAD dengan teori dasar Agus
Suprijono. Guru dapat merubah paradigma mengajar dari konvensional ke
model pembelajaran STAD sehingga memotivasi siswa untuk aktif, kreatif,
inovatif dan menyenangkan. Pembelajaran STAD ini hampir sama dengan
pembelajaran kooperatif lainnya namun yang membedakan adalah tipe STAD
ini menggunakan kuis-kuis individual pada tiap akhir pelajaran. Para siswa
tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam mengerjakan kuis
sehingga tiap siswa bertanggung jawab secara individual untuk memahami
materinya. Dalam STAD ini terdiri atas enam sintak utama di antaranya

38
adalah penyampaian tujuan dan motivasi pembelajaran, menyajikan
menyampaikan informasi, mengoganisasi kegiatan belajar dalam tim (kerja
tim), membimbing kelompok bekerja dan belajar, kuis (evaluasi), dan
penghargaan prestasi tim.
Menurut Robert E.Slavin (2005:143) tipe pembelajaran kooperatif
STAD pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di dalam kelas. Dalam
presentasi ini bisa juga memasukkan presentasi audiovisual. Dengan cara ini,
para siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-benar memberi
perhatian penuh selama presentasi kelas, karena dengan demikian akan
sangat membantu mereka mengerjakan kuis-kuis, dan skor kuis mereka
menentukan skor tim mereka.
Sehingga dari pendapat tersebut peneliti menyempurnakan sebuah
model pembelajaran ini dengan alat pembantu media powerpoint. Media
berbasis powerpoint merupakan pembelajaran yang digunakan dalam proses
pembelajaran dengan menggunakan software komputer. Media berbasis
powerpoint ini memiliki kelebihan yaitu menggabungkan unsur media seperti
teks, video, animasi, image, dan sound didalam presentasi powerpoint
sehingga dapat dibuat semenarik mungkin.
5. Microsoft Power Point
a. Pengertian Microsoft Power Point
Menurut Musliadi KH (2013:1) microsoft power point adalah bagian
dari microsoft office yang digunakan untuk keperluan presentasi dalam
bentuk slide, outline presentasi, presentasi elektronika, menampilkan slide
yang dinamis, termasuk clip art yang menarik, yang semuanya itu mudah
ditampilkan di layar monitor komputer. Menurut Abdul kadir (2011:2) microsoft

39
power point adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun
sebuah presentasi yang efektif, professional, dan juga mudah. Menurut
Wahana komputer (2011:2) microsoft power point merupakan salah satu
aplikasi presentasi yang banyak digunakan pada saat ini, hal ini dikarenakan
banyak sekali kemudahan dan kelebihan yang disediakan sehingga pelaku
bisnis dapat menyampaikan presentasi kerja secara profesional dan menarik.
Berdasarkan pengertian microsoft power point yang telah dipaparkan
oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa microsoft office power point
merupakan perangkat lunak (software) yang mampu menampilkan program
multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan dan penggunaannya
relatif murah. Microsoft power point memiliki kemampuan untuk
menggabungkan berbagai unsur media, seperti pengolahan teks, warna,
gambar, dan grafik, serta animasi.
b. Pembuatan Animation Of Shapes
Animation of shapes merupakan bagian dari suatu presentasi yang
terdapat pada microsoft power point. “Animation“ dalam bahasa indonesia
mempunyai arti animasi atau gerakan. Menurut Musliadi KH (2013:75)
fasilitas shapes digunakan untuk menambahkan objek gambar pada slide
presentasi, sedangkan menurut Abdul kadir (2011:2) fasilitas shapes
digunakan untuk membuat berbagai bentuk gambar dasar, dan
memungkinkan untuk menyisipkan tulisan didalamnya, selain itu dapat
dengan mudah mengganti warna gambar. Menurut Wahana komputer
(2011:32) shapes terdiri dari kotak, lingkaran, calout balloons, lines, dan
block arrows. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
Animasi yang akan diterapkan untuk presentasi pada penelitian ini adalah

40
custom animations yang merupakan animasi dengan beragam variasi
animasi yang ada pada toolbar animations. Sedangkan “shapes” mempunyai
arti bentuk. Shapes digunakan membuat berbagai bentuk gambar yang terdiri
dari kotak, lingkaran, garis, arah, dan lain-lain.
Menurut banyak orang yang menyukai power point sebagai media
pembelajaran presentasi dikarenakan program ini memiliki beberapa
keunggulan, salah satunya custom animation of shapes. Dengan fasilitas ini
presentasi dapat menjadi lebih hidup, menarik, dan interaktif. Dalam
pembuatan animation of shapes ada beberapa langkah yang harus dilakukan
yaitu :
a. Membuka aplikasi microsoft power point dengan tampilan sebagai berikut.
Gambar 3. Halaman Awal Microsoft Power Point
(Abdul Kadir,2011:3)
b. Kemudian membuka bagian Insert, pilih apilkasi Shapes sebagai
pembuatan garis sesuai pola.
Gambar 4. Apilkasi Shapes

41
c. Pada Bagian shapes akan muncul berbagai garis yang akan membantu
dalam pembuatan pola dasar.
Gambar 5. Macam-macam Garis pada Apilkasi Shapes
(Abdul Kadir,2011:96 )
d. Dalam pembuatan ilustrasi gambar pola, ada beberapa garis yang
digunakan yaitu :
1) Line ( ) digunakan untuk membuat garis lurus.
2) Double Arrow ( ) digunakan untuk membuat garis dengan dua ujung
panah. Pada pembuatan pola garis ini digunakan sebagai arah serat.
3) Curve ( ) digunakan untuk membuat kurva. Pada pembuatan
pola garis ini digunakan sebagai garis lengan.
4) Arc ( ) digunakan untuk membuat garis busur. Pada
pembuatan pola garis ini digunakan sebagai garis lengkung pada
panggul. (Abdul Kadir,2011:96)
e. Setelah selesai pembuatan garis-garis pola dan langkahnya, selanjutnya
adalah memberi Animasi pada setiap garis dengan cara :
1) Mengklik kanan text atau objeknya
2) Mengklik Custom Animation

42
3) Memilih effects untuk memberikan animasi pada text atau objek yang
diinginkan dengan memilih pada icon.
4) Setelah memilih effects yang diinginkan maka akan nampak sebagai
berikut :
Gambar 6. Custom Animation
a) Mengatur Start berdasarkan pada saat apa animasi ini dilakukan.
b) Mengatur Direction berdasarkan arah yang diinginkan.
c) Mengatur Speed berdasarkan seberapa cepat animasi tersebut dilakukan
d) Menyesuaikan urutan tampilan animasi sesuai keinginan dengan
mengatur order.
e) Menekan play untuk melihat tampilan preview hasil pengaturan yang
dilakukan.
f) Sehingga akan nampak hasil akhirnya sebagai berikut :

43
Gambar 7. Hasil Jadi Job sheet berbasis animation of shapes.
B. Kajian Penelitian yang Relevan
Beberapa hasil penelitian relevan yang terkait dengan penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Nur Ikomah (2007) dengan judul “ Pengaruh Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD)
Berbantuan Job Sheet Terhadap Hasil Belajar Membuat Pola Celana
Anak Kelas X Busana 2 Di SMK N 6 Purworejo”.
2. Siti Chaeriyah (2010) dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) Untuk
Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa
Kelas VII Di SMP Negeri 2 Depok Pada Materi Bangun Segiempat”.
3. Septi Dwi Dayati (2011) dengan judul “ Pengaruh Model Pembelajaran
Cooperative Learning Tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD)
Pada Pencapaian Kompetensi Membuat Pola Blazer Di SMK N 1 Sewon
Bantul”.
Dari beberapa hasil penelitian yang relevan diatas, akan diuraikan
dalam tabel 5 untuk mengetahui relevansi penelitian

44
Tabel 5. Penelitian Yang Relevan
Uraian penelitian Nur Ikomah (2007)
Siti Chaeriyah (2010)
Septi Dwi Dayati (2011)
Apris Sarah Wijayanti (2014)
Tujuan Pencapaian kemampuan pemecahan masalah
√
Pencapaian kompetensi
√
Pencapaian hasil belajar
√ √
Tempat penelitian
SD
SMP √
SMA
SMK √ √ √
Jenis Penelitian
Deskriptif
Kualitatif
R&D
PTK √ √
Quasi eksperimen √ √
Teknik analisis data
Angket √ √ √ Observasi √ √ √ Wawancara √ √ Catatan lapangan √
Analisis data Statistik deskriptif √ √
Analisis deskriptif √ √
Materi Matematika √
Pola Celana √
Pola Blazer √
Pola dasar √
Media Buku pedoman √
Job sheet √ √ √
Riil object
Powerpoint √
Model pembelajaran
STAD √ √ √ √
Hasil penelitian ini digunakan sebagai dasar acuan Penelitian
Tindakan kelas (PTK) yang menerapkan metode Student Team Achievement
Division (STAD). Dari uraian penelitian relevan diatas, yang membedakan
dari ketiga penelitian dengan penelitian ini adalah tempat penelitian, materi
pembelajaran, dan penggunaan dari media powerpoint berbasis animation of
shapes.

45
C. Kerangka Pikir
Dalam berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, proses sangatlah
berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Berhasil atau tidaknya hasil
belajar peserta didik sangat bergantung pada keefektifan metode
pembelajaran yang digunakan saat menyampaikan suatu meteri pelajaran
pada peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran yang efektif adalah
penyampaian materi pembelajaran dengan berbagai metode dan media
pembelajaran untuk menarik perhatian dan minat peserta didik dalam belajar,
serta dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
Guru memiliki peranan utama di dalam proses pembelajaran.
Keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung dari segi strategi
pembelajaran yang digunakan oleh guru. Penggunaan metode Student Team
Achievement Division (STAD) adalah satu tipe dalam metode pembelajaran
kooperatif yang dapat digunakan sebagai alternatif guru untuk mengajar.
Model pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) ini memiliki
keistimewaan yaitu selain siswa dapat mengembangkan kemempuan secara
individu, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan kelompoknya.
Adanya keaktifan siswa ini maka diharapkan akan meningkatkan hasil belajar
siswa dalam mempelajari mata pelajaran yang diberikan guru karena siswa
akan lebih dapat memahami materi membuat pola busana secara konstruksi
dengan mempelajari secara bersama-sama daripada hanya dijelaskan oleh
guru. Mata diklat membuat pola busana akan lebih mudah dimengerti oleh
siswa apabila mereka bersama-sama memecahkan masalah daripada
dijelaskan oleh guru dengan model pembelajaran konvensional. Sehingga
kompetensi belajar membuat pola busana dapat meningkat. Dan dengan

46
didukung media powerpoint berbasis animation of shapes yang digunakan
pada saat pembelajaran dasar pola maka dapat membantu siswa mengatasi
masalah-masalah belajar sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan 1.
Kerangka Pikir
Bagan 1. Kerangka Pikir
Pengamatan : Kompetensi Membuat Pola Rendah
Perencanaan tindakan: Model Cooperative Learning tipe STAD
Penerapan Tindakan model kooperatif STAD : 1. Pendahuluan : a. Salam b. Presensi c. Apersepsi materi dan menyajikan informasi d. Memotivasi siswa 2. Kegiatan Inti : a. Menyampaikan tujuan pembelajaran. b. Membagi jobsheet c. Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD : 1) Mengelompokkan siswa menjadi 4 kelompok untuk saling bekerja sama 3) Guru menjelaskan materi pembelajaran. d. Pemberian tugas pola dasar rok dari pengukuran hingga hasil jadi dan dikumpulkan e. Evaluasi pekerjaan siswa f. Tes uraian
Mengobservasi dan
mengevaluasi proses
dan hasil
tindakan
Peningkatan Hasil Belajar Membuat Pola
Dasar Rok
Motivasi dan Minat Belajar
Meningkat REFLEKSI

47
D. Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang dikemukan
diatas, dirumuskan hipotesis tindakan sebagai dugaan awal penelitian
sebagai berikut :
1. Penerapan pembelajaran membuat pola dasar rok menggunakan model
pembelajaran tipe STAD berbasis media power point dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK Pelita Buana Bantul.
2. Penerapan model pembelajaran tipe STAD berbasis media power point
pada pembelajaran pola dasar rok dapat meningkatkan hasil belajar
siswa lebih dari 80% di SMK Pelita Buana Bantul.