BAB 4 MALA
-
Upload
mala-syahril -
Category
Documents
-
view
25 -
download
0
Transcript of BAB 4 MALA

Lembar KerjaMATA KULIAH; ETIKA DAN LOGIKA
Nama Mahasiswa : NurmalaNIM :10640407
Dosen: Dr. Maharuddin Pangewa, M.SiProdi : PEND.IPS TERPADU
RESUME MATERI PEMBAHASAN
BAB IV PERSOALAN DALAM ETIKA
A. Persoalan tentang Nilai Etika
B. Etika Deskriptif dan Normatif
C. Kesadaran Moral (Hati Nurani)
A. Persoalan tentang Nilai Etika
Kattsoff (1996:349), etika merupakan cabang aksiologi yang pada
pokoknya membicarakan masalah predikat-predikat nilai “betul” (“right”) dan
“salah” (“wrong”) dalam arti “susila” (“moral”) dan “tidak susila” (“immoral”).
Popkin dan Stroll dalam Sudarsono (2001), menguraikan perbedaan
antara etika, metafisika lalu masuk logika sebagai bagian dari filsafat. Bila
seseorang memikirkan persoalan tingkah laku, maka ia akan masuk filsafat
dalam bidang etika; bila yang menjadi perhatian baginya adalah alam semesta,
maka ia masuk filsafat dalam bidang metafisika, akan tetapi bila ia
memperhatikan tentang cara berpikir itu sendiri, maka yang dimasukinya adalah
dunia filsafat dalam bidang logika. Dengan itulah Popkin dan Stroll
membedakan tiga jenis cabang filsafat itu dengan memperhatikan arah
pemikiran.
Ilmu pengetahuan dalam perkembangannya dewasa ini nampaknya
semakin jauh dari makna, hakikat, dan tujuannya (bebas nilai) dalam hidup dan
kehidupan manusia. Mengapa demikian?, karena pengembangan pengetahuan
pada umumnya dan ilmu pada khususnya dilandasi pada suatu keyakinan bahwa
ilmu pengetahuan adalah suatu kekuatan (power). Sehingga dewasa ini
keyakinan inilah yang memacu perkembangan pengetahuan manusia untuk
menguasai, mamanipulasi, dan mengelola alam semesta demi kepentingan umat
manusia.

Watloly (2001:119), pengetahuan apa pun bentuk dan jenisnya selalu
mendasarkan dirinya pada dua landasan pokok, selain landasan epistemologi,
yaitu: pertama, landasan ontologi yang mengkaji hal-hal mengenai “apa” yang
mengandaikan adanya pengetahuan itu; kedua, landasan aksiologi, yaitu
mengenai “untuk apa” pengetahuan itu diusahakan. Landasan aksiologi ini
menunjukkan pula bahwa pengembangan epistemologi selalu berkaitan dengan
etika atau nilai.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, ketiga landasan pengetahuan
ini saling berkaitan dalam rangka pengembangan pengetahuan. Epistemologi
misalnya, tidak dapat dilepaskan dari dasar ontologi pengetahuan yaitu
mengenai dasar-dasar keberadaan (manusia) yang mengandaikan adanya
pengetahuan. Epistemologi juga tidak dapat memisahkan dirinya dengan dasar
aksiologi yang memberikan landasan (nilai-nilai kemanusiaan) bagi
pengembangan dan pengamalan pengetahuan.
Jelaslah bahwa manusia dengan daya pengetahuannya harus dapat
menegaskan cita-citanya untuk dapat menyumbang pada pemenuhan kodrat
keagungan manusia. Ciri pengembangan epistemologi menegaskan pula bahwa
manusia adalah makhluk berkepribadian, bermartabat, dan menolak untuk
diperlakukan sebagai benda atau dipergunakan sebagai alat, bahkan merupakan
objek eksperimentasi keilmuan. Berkat kodratnya sendirilah, maka manusia
bersifat membudaya, sehingga bila dalam pengembangan pengetahuannya
karena suatu kecelakaan manusia tidak dapat mencapai kebudayaan, maka dia
dikucilkan dari kebudayaan. Bukan itu saja, bahkan dengan daya
pengetahuannya pun manusia tidak akan pernah mencapai kodrat
manusiawinya. Kondisi demikian tidak akan pernah menuntun manusia untuk
mencapai tingkat kebebasan dan tanggung jawab moral. Hal ini disebabkan
karena pikiran atau pengetahuan yang berciri kultural itu tidak dapat lahir dari
dirinya.
Moore dalam Kumorotomo (2008:11-15), secara sederhana, nilai dapat
dirumuskan sebagai objek dari keinginan manusia. Nilai menjadi pendorong
utama bagi tindakan manusia dari pelbagai macam nilai yang mempengaruhi
kompleksitas tindakan manusia. Moore membedakan enam macam nilai, :

1. Nilai Primer, Sekunder, dan Tertier: yang membedakan adanya nilai primer,
sekunder, dan nilai tertier adalah pada kerangka berpikir yang menentukan
usaha, angan-angan, atau kepuasan seseorang.
2. Terdapat perbedaan antara nilai semu (quasi values) dan nilai riil (real
values). Seseorang yang memiliki nilai semu apabila dia bertindak seolah-
olah berpedoman kepada suatu nilai sedangkan ia sesungguhnya tidak
menganut nilai tersebut.
3. Ada nilai terbuka dan ada pula yang tertutup. Suatu nilai disebut terbuka
bila tidak terdapat rentang waktu yang membatasinya.
4. Pembedaan dapat digariskan antara nilai-nilai negatif dan positif. Suatu nilai
negatif terjadi bila proposisi yang mendasari suatu keinginan bersifat
negatif, kebalikan dari nilai negatif adalah nilai positif.
5. Suatu nilai dapat pula dibedakan menurut orde atau urutannya. Maka
terdapat nilai orde pertama (first order values), order kedua (second order
values), atau orde-orde selanjutnya yang lebih tinggi (higher order values).
Nilai pertama terjadi jika benar-benar tidak ada nilai yang lainnya. Nilai
orde kedua terjadi jika tidak terdapat nilai lain kecuali nilai orde pertama
tadi, demikian seterusnya.
6. Pembedaan yang cukup sering disebutkan dalam kaitannya dengan nilai
ialah pembedaan antara nilai relatif dan nilai absolut. Suatu nilai bersifat
relatif bila merujuk kepada orang yang memiliki spesifikasi nilai tersebut.
Kebalikannya adalah nilai absolut, tidak merujuk kepada orang dan dianut
secara mutlak.
Dari kutipan panjang tersebut, dapat dikatakan bahwa dari keenam dasar
pembedaan yang diuraikan tersebut pada dasarnya merupakan psikologi teoretis
dengan memperoleh serangkaian pembedaan dari nilai-nilai yang beraneka
ragam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap perilaku manusia dalam
hidup dan kehidupannya ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut serta adanya
prinsip-prinsip moral yang dipegangnya. Sehingga, moral itu sendiri merupakan
suatu sistem nilai yang menjadi dasar bagi adanya dorongan atau
kecenderungan untuk berbuat atau bertindak, nilai-nilai yang terdapat pada
moral maupun etika adalah masuk dalam norma, sedangkan norma mengacu

kepada peraturannya sendiri beserta sanksi-sanksinya, baik itu bermula dari
dorongan batin, dari rasa susila, maupun paksaan fisik.
B. Etika Deskriptif dan Normatif
1. Etika Deskriptif
Etika deskriptif memberikan gambaran tentang tingkah laku moral dalam
arti yang luas, seperti berbagai norma dan aturan yang berbeda dalam suatu
masyarakat atau individu yang berada dalam kebudayaan tertentu atau yang
berada dalam kurun atau periode tertentu. Norma atau aturan tersebut ditaati
oleh individu atau masyarakat yang berasal dari kebudayaan atau kelompok
tertentu. Sebagai contoh, masayarakat Jawa mengajarkan bertatakrama
terhadap orang yang lebih tua dengan menghormatinya, bahkan dengan
sapaan yang halus merupakan ajaran yang harus diterima. Apabila
seseorang menolak melakukan hal itu, maka masyarakat menganggapnya
aneh, ia dianggap bukan orang Jawa. Norma-norma tersebut berisi ajaran
atau semacam konsep etis tentang yang baik dan tidak baik, tindakan yang
diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, etika deskriptif
mengkaji berbagai bentuk ajaran-ajaran moral yang berkaitan dengan “yang
baik” dan “yang buruk”. Ajaran tersebut lazim diajarkan oleh para pemuka
masyarakat pada masyarakatnya ataupun individu tertentu dan nampaknya
sering terdapat pada suatu kebudayaan manusia. Mempelajari etika orang
Jawa ataupun etika orang Bugis adalah suatu contoh dari bentuk etika
deskriptif.
2. Etika Normatif
Bagian yang dianggap penting dalam studi etika adalah etika normatif.
Mengapa? Karena ketika mempelajari etika normatif muncul berbagai studi
atau kasus yang berkaitan dengan masalah moral. Etika normatif merupakan
etika yang mengkaji tentang apa yang harus dirumuskan secara rasional dan
bagaimana prinsip-prinsip etis dan bertanggung jawab itu dapat digunakan
oleh manusia. Di dalam etika normatif hal yang paling menonjol adalah
munculnya penilaian tentang norma-norma tersebut. Penilaian tentang

norma-norma tersebut sangat sangat menentukan sikap manusia tentang
“yang baik’ dan “yang buruk”. Dalam mempelajari etika normatif, dijumpai
etika yang bersifat umum dan etika yang bersifat khusus. Etika umum
memiliki landasan dasar seperti norma etis/norma moral, hak dan
kewajiban, hati nurani, dan tema-tema itulah yang menjadi kajiannya.
Sedang etika khusus berupaya menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum
atas perilaku manusia yang khusus. Lama kelamaan etika khusus tersebut
berkembang menjadi etika terapan (applied etics). Etika khusus
mengembangkan dirinya menjadi etika individual dan etika sosial. Etika
individual menyangkut kewajiban dan sikap individu terhadap dirinya
sendiri. Sedang etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola
perilaku manusia sebagai anggota umat manusia atau masyarakat. Bentuk
etika sosial yang diterapkan pada berbagai bentuk memunculkan kajian-
kajian mengenai etika keluarga, etika profesi (etika biomedis, etika
perbankan, etika bisnis dan sebagainya), etika politik, etika lingkungan
hidup.
Kant (dalam Abdullah, 2006:594) merumuskan pandangannya tentang etika
normatif dalam tiga prinsip,
a.supaya tindakan manusia mempunyai nilai etika baik, tindakan itu haruas
dijalankan berdasarkan kewajiban;
b. nilai etika dari tindakan itu tidak tergantung pada tercapainya tujuan dan
tindakan itu, melainkan hanya tergantung pada kemauan baik;
c.konsekuensi kewajiban dari tindakan yaang dilaksanakan, harus
berdasarkan sikap hormat menghormati dan menjunjung tinggi aturan
hukum.
Selanjutnya, Abdullah (2006:595) mengemuka bahwa etika normatif
mempunyai tugas khusus, yaitu:
a. berusaha menuangkan berbagai norma peraturan, peringatan, kewajiban
dan nilai etika yang membentuk norma-norma masyarakat
b. berusaha dengan berbagai cara untuk membenarkan prinsip dasar etika
kepada suatu masyarakat agar memiliki norma etika yang konsisten,

c. meta-etika, ini erat hubungannya dengan studi tentang etika normatif. Ia
disebut sebagai etika analisis, karena menganalisis meta-etika, mengkaji
makna istilah-istilah etika dan logika dari penalaran tingkah laku
manusia.
C. Persoalan Kesadaran Moral (Hati Nurani)
1. Pengertian Kesadaran Moral (Hati Nurani)
Setiap manusia dalam hatinya memiliki suatu kesadaran tentang apa yang
menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Kesadaran itu tidak selalu
diperhatikan. Kalau hati setuju dengan pendapat moral lingkungannya, maka
suara hati tidak menampak. Tetapi kalau bertentangan dan tidak menyetujuinya,
maka hati nurani dalam kondisi itu menyatakan diri, dan inilah hakikatnya
manusia. Magniz, (1987:53) mengatakan suara hati adalah kesadaran moral kita
dalam situasi konkret dan selalu harus ditaati karena suara hati merupakan
kesadaran kita yang langsung tentang apa yang menjadi kewajiban kita.
Immanuel Kant (ibid) menyatakan tuntutan suara hati itu bersifat mutlak, yaitu
memuat tuntutan untuk selalu bertindak dengan baik, jujur, wajar dan adil,
apapun biayanya dan apa pun pendapat “lembaga-lembaga normatif”.
Kesadaran moral (suara hati) merupakan suatu faktor penting untuk
memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula
tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku. Kesadaran moral
didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial, fundamental. Perilaku
manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya akan selalu
direalisasikan sebagaimana yang seharusnya, kapan saja dan di mana saja.
Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, tindakan yang bermoral akan
selalu dilakukan. Sebab tindakannya berdasarkan atas kesadaran, bukan
berdasar pada suatu kekuasaan apa pun dan juga bukan karena paksaan, tetapi
berdasar “kekuasaan” kesadaran moral itu sendiri.

2. Unsur-unsur Kesadaran Moral
Zubair, (1987:54) mengemukakan empat pendapat ahli yang berhubungan
dengan unsur-unsur kesadaran moral.
a. Von Magnis, menyebutkan 3 unsur kesadara moral, yaitu: Perasaan Wajib,
Rasional, dan Kebebasan.
1) Perasaan Wajib, atau keharusan untuk melakukan tindakan yang
bermoral itu ada, dan terjadis di dalam setiap hati sanubari manusia,
siapapun, dimanapun dan kapan pun..
2) Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional, karena berlaku
umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan.
3) Kebebasan. Atas kesadaran moralnya seseorang bebas untuk
menaatinya. Bebas dalam menentukan perilakunya dan di dalam
penentuan itu sekaligus terpampang pula nilai manusia itu sendiri.
b. Poedjawijatna, berpendapat kata hati (istilah lain bagi kesadaran moral)
bertindak sebagai berikut:
1) Index atau petunjuk. Memberi petunjuk tentang baik-buruknya sesuatu
tindakan yang mungkin akan dilakukan sessorang.
2) Iudex atau Hakim. Sesudah tindakan dilakukan, kata hati menentukan
baik-buruknya tindakan.
3) Vindex atau penghukum. Jika ternyata tindakan itu buruk, maka
dikatakan dengan tegas dan berulangkali bahwa buruklah itu.
c. Notonagoro,
1) Sebelum melakukan tindakan, kata hati sudah memutuskan satu diantara
4 hal, yait: memerintahkan, melarang, menganjurkan, dan atau
membiarkan.
2) Sesudah melakukan tindakan, bila bermoral diberi penghargaan, bila
tidak bermoral dicela, atau dihukum.
d. Vernon J. Bourke menampilkan bagan tentang petunjuk rasional mengenai
proses penalaran yang praktis dalam tindakan manusia yaitu: sampai pada
tahap conscience (kesadaran kata hati) tahap mana merupakan prinsip
keempat dari norma dasar bagi pertimbangan moral, dilihat atas kedudukan
akal manusia di dalam konteks semestalainnya, yaitu dalam urutan jenjang

dari makhluk alami yang paling rendah sampai pada suatu yang tertinggi,
dari makhluk alami sampai akal abadi – Tuhan. Dengan melihat bagan
tersebut, ternyata dapat pula ditunjukkan adanya unsur-unsur kesadaran
moral yaitu: adanya kewajiban, rasional, objektif dan adanya kebebasan,
3. Kaidah Dasar Moral
Istilah kaidah disebut juga dengan prinsip. Zubair (1987:71)
menggunakan kaidah dasar moral dan menyatakan bahwa apabila kita
memperhatikan keseluruhan teori etika, kita akan sampai pada kesimpulan
bahwa manusia menjadi manusia yang “sebenarnya” jika ia menjadi manusia
yang etis.
Magnis Suseno (1987:129) menggunakan istilah prinsip-prinsip moral
dasar dan mengemukakan tiga prinsip dasar moral yaitu: prinsip sikap baik,
prinsip keadilan, dan prinsip hormat terhadap diri sendiri.
a. Kaidah sikap baik
Kaidah sikap baik dimaksudkan bahwa kita wajib bertindak sedemikan rupa
sehinga ada kelebihan dari akibat baik dibandingkan akibat buruk
(maksimalisasi).
Kaidah sikap baik pada dasarnya mendasari semua norma moral. Orang
yang mempunyai etika baik dapat bergaul dengan masyarakat secara luwes,
karena dapat melahirkan sifat saling cinta mencintai dan saling tolong-
menolong. Kita pada dasarnya – kecuali kalau ada alasan khusus – mesti
bersikap baik terhadap apa saja. Sikap baik dalam arti: memandang
sesorang/sesuatu tidak hanya sejauh berguna bagi saya menghendaki,
menyetujui, membenarkan, mendukung, membela, membiarkan
seseorang/sesuatu berkembang demi dia itu sendiri. Bagaimana sikap baik
itu harus dinyatakan secara konkret tergantung dari apa yang baik dalam
situasi konkret itu.
b. Kaidah keadilan
Keadilan dalam membagikan yang baik dan yang buruk. Kita berbicara
tentang ketidakadilan apabila dari dua orang yang sifat-sifatnya cukup mirip
dan yang berada dalam ssituasi yang mirip juga, yang satu diperlakukan

denga lebih baik atau dengan lebih buruk dari yang lain.
c. Kaidah hormat terhadap diri sendiri
Kaidah ketiga ini mengatakan bahwa manusia wajib untuk selalu
memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri.
Kaidah ini berdasarkan paham bahwa manusia adalah person, pusat
berpengertian dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati,
makhluk berakal budi.

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. Yatimin.2006. Pengantar Studi Etika. Rajawali Pers. Jakarta
Kattsoff, Louis O. 1996. Pengantar Filsafat. Tiara Wacana. Yogyakarta.
Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Etika Administrasi Negara. RajaGrafindo
Persada. Jakarta
Watloly, Aholiab. Tanggung Jawab Pengetahuan. Mempertimbangkan
Epistemologi secara Kultural. Penerbit Kani
Zubair, Achmad Charis. 1987. Kuliah Etika. Rajawali Pers. Jakarta
http://ms.wikipedia.org/wiki/Etika_normatif
http://susipurwati.blogspot.com/2010/10/metaetika-dan-etika-deskriptif.html
Catatan: 1. Kumpulkan lembar kerja Anda setelah perkuliahan bab ini selesai
2. Tidak mengumpulkan/tidak mengisi lembaran kerja ini dianggap tidak hadir dalam perkuliahan
Nilai dosen
1, 2, 3, 4






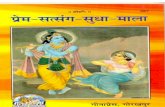







![JURNAL Puspa Dewi Ainul Mala [11050724057]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6157e1c2e12232611568b9d5/jurnal-puspa-dewi-ainul-mala-11050724057.jpg)







