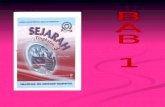bab 1-3
-
Upload
chaca-dian-catur-permatasari -
Category
Documents
-
view
32 -
download
8
description
Transcript of bab 1-3
KEANEKARAGAMAAN MIKROALGA DI HULU DAN HILIR PERAIRAN HUTAN MANGROVE, TAMAN NASIONAL ALAS PURWO JAWA TIMUR SERTA HUBUNGANNYA DENGAN BEBERAPA FAKTOR LINGKUNGAN
Laporan PenelitianKuliah Kerja LapanganTaman Nasional Alas PurwoKabupaten Banyuwangi, Jawa TimurTanggal 7-14 April 2013
Disusun Oleh:Dian C Permatasari140410100080
JURUSAN BIOLOGIFAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAMUNIVERSITAS PADJADJARANJATINANGOR2013BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangMikroalga merupakan bentuk tumbuhan yang paling primitif. Umumnya mikroalga lebih dikenal sebagai fitoplankton atau ganggang yang hidupnya melayang-layang di permukaan air laut ataupun air tawar. Secara umum mikroalga dikelompokkan dalam divisi Chlorophyta (alga hijau), Cyanophyta (alga hijau-biru), Euglenophyta, Rhodophyta (alga merah), Phaeophyta (alga cokelat), Chrysophyta (alga keemasan) dan Pyrrophyta (alga pirang) (Sze, 1986). Pertumbuhan, kelangsungan hidup dan keanekaragaman mikroalga dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor fisika, kimia dan biologi seperti temperatur, salinitas, derajat keasaman, cahaya, nutrisi dan faktor lainnya.Ekosistem mangrove merupakan ekoton yang unik, yang menghubungkan antara kehidupan biota daratan dengan lautan, fungsi ekologis ekosistem mangrove sangat khas dan kedudukannya tidak dapat digantikan oleh ekosistem lain (Nugroho, Setiawan, dan Harianto, 1991).Dalam ekosistem perairan seperti halnya ekosistem mangrove, mikroalga berperan sebagai produsen primer karena dapat menangkap dan memanfaatkan energi matahari dan CO2 untuk keperluan fotosintesis. Produsen primer merupakan salah satu komponen penting dalam rantai makanan.Tumbuhan, hewan dan jasa renik beserta lingkungan fisik hutan mangrove berhubungan secara timbal balik dalam suatu proses pertukaran materi dan estimilasi (Soedarma, 1990). Pentingnya hutan mangrove terhadap berbagai biota telah banyak diketahui orang. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat penelitian yang mengkaji mengenai mikroalga baik itu dalam hal distribusi, kelimpahan dan potensial. Namun penelitian mengenai keanekaragaman mikroalga di perairan hutan mangrove belum banyak dilaporkan khusunya di Alas Purwo, Jawa Timur. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan keanekaan mikroalga dengan faktor lingkungan di hutan mangrove.
1.2 Identifikasi MasalahAdapun identifikasi masalah dalam laporan ini yaitu:1. Bagaimana keanekaragaman mikroalga di perairan hulu dan hilir hutan mangrove Taman Nasional Alas Jawa Timur2. Bagaimana indeks nilai penting (INP) mikroalga di perairan hutan mangrove Taman Nasional Alas Purwo Jawa Timur3. Sejauh mana hubungan anatara keanekaragaman jenis mikroalga dengan faktor lingkungan yang mempengaruhinya
1.3 Maksud dan TujuanMaksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari keanekaragaman mikroalga dan hubungannya dengan faktor lingkungan yang mempengaruhinya di hutan mangrove Taman Nasional Alas Purwo Jawa Timur.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis mikroalga dan mengetahui nilai indeks diversitasSimpson dan nilai indeks nilai penting (INP) mikroalga di hutan mangrove serta mengetahui hubungan antara keanekaragaman jenis mikroalga dengan faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
1.4 Metodologi PenelitianMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode suvei. Pengambilan data lapangan dilakukan pada daerah yang representatif dengan menentukan tiga titik sampling yang berbeda pada tiap hulu dan hilir hutan mangrove. Spesimen yang ditemukan diidentifikasi dengan Buku The Marine Plankton of Japan tahun 1979, The Structure and Reproduction of the Algae tahun 1997 dan Identifying Marine Fitoplankton tahun 1997. Dilakukan analisis data berupa indeks diversitasSimpson dan nilai indeks nilai penting (INP).
1.5 Kegunaan PenelitianKegunaan dari penelitian ini antara lain untuk pengembangan ilmu di bidang taksonomi khususnya kriptogamae serta memberikan informasi data terbaru mengenai keanekaragaman mikroalga bagi masyarakat khusunya pihak Alas Purwo Jawa Timur.
1.6 Lokasi dan Waktu PenelitianPenelitian ini dilakukan pada tanggal 7-14 April 2013 di Hutan Mangrove Taman Nasional AlasPurwo Jawa Timur.
BAB IITINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Lokasi2.1.1 Sejarah KawasanBerdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Replubik Indonesia No.283/Kpts-II/92 tanggal 26 Februari 1992, Taman Nasional Alas Purwo merupakan kawasan konservasi kedua yang dikelola olah Taman Nasional Baluran dengan luas 43.420 ha. Semenanjung blambangan yang dikenal dengan sebutan Alas Purwo merupakan tempat yang dianggap memiliki banyak misteri, sehingga tidak mengherankan apabila banyak pengunjung yang datang untuk melakukan semedi atau nyepi terlebih pada bulan Muharram / Syuro, mereka berkumpul pada tempat yang dianggap mempunyai kekuatan supra natural misalnya Pancur, Gua Istana, Gua Padepokan.Dikawasan ini terdapat sebuah pura yang merupakan tempat peribadatan pemeluk agama hindu, biasa dipakai untuk merayakan upacara Pagar Besi yang dilaksanakan setiap tujuh bulan sekali. Masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Alas Purwo kebanyakkan merupakan pendatang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian barat.
2.1.2 Letak, Status dan Luas WilayahTaman Nasional Alas Purwo secara geografis terletak di antar 114o 115o BT dan 8o 9o LS. Adapun batas-batas kawasan ini adalah sebagai berikut :1. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan selat Bali2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia3. Sebelah Barat berbatasan dengan kawasan hutan produksi Perum Perhutani BKPH Kalipahit dan BKPH benculu.Berdasarkan pengelolaannya Alas Purwo termasuk ke dalam wilayah kerja Taman Nasional Baluran, sesuai SK Dirjen PHPH No. 46/Kpts/VI-Set/1984. Taman Nasional Alas Purwo ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kehutanan No. 283/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 dengan luas 43.420 ha. Sedangkan menurut administrasi pemerintahannya termasuk kedalam lima kecamatan yaitu kecamatan Muncar, kecamatan Tegal Dlimo, kecamatan Purwoharjo, kecamatan Bangorejo dan kecematan Pesanggrahan, kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
2.1.3 Topografi, Tanah, dan GeologiSecara umum Kawasan Taman Nasional Alas Purwo mempunyai topografi landai yang membentang dari ketinggian mulai dari 0 322 m dpl dan memiliki puncak tertinggi yang terdapat di Gunung Lingganis (322 m dpl), kemudian diikuti dengan Gunung Sembulungan (204 m dpl) dan Gunung Geger.Jenis tanah di kawasan Taman Nasional Alas Purwo terdiri atas 4 kelompok, yaitu tanah komplek Mediteran Merah-Litosol, tanah Regosol Kelabu, tanah Grumosol Kelabu, dan tanah Alluvial Hidromorf. Jenis tanah Alluvial hidromorf merupakan jenis tanah yang mendominasi di Taman Nasional Alas Purwo. Jenis tanah ini mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permiabilitas (water run off) lambat.Geologi pembentuk kawasan Taman Nasional Alas Purwo sebagian besar dari batuan sedimen Meosen atas yang terdiri dari batuan berkapur dan batuan berasam. Pada batuan berkapur terjadi proses karstifikasi yang tidak sempurna, karena faktor iklim yang kurang mendukung (relatif kering) dan sebagian kecil pantai bagian selatan berupa batuan sedimen alluvium undak dan terumbu koral.
2.1.4 IklimKawasan Taman Nasional Alas Purwo dan sekitarnya memiliki curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Hari hujan berkisar dari tidak ada hari hujan hingga lebih dari 15 hari hujan. Curah hujan tahunan mencapai 1.079 mm 2.147 mm, dengan hari hujan sebanyak 55 112 hari. Menurut sistem klasifikasi Schmidth dan Ferguson daerah sekitar Taman Nasional Alas Purwo memiliki tipe iklim sekitar D (agak lembab) sampai E (agak kering). Secara umum, bulan basah terjadi pada bulan Nopember sampai April, dan bulan kering terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Kisaran penyinaran matahari bulanan di Banyuwangi dan sekitarnya adalah 52% (bulan Januari) hingga 89% (bulan September), dengan rata-rata sebesar 75%.
2.1.5 HidrologiJaringan sungai di kawasan Taman Nasional Alas Purwo berpola radial karena leher semenanjungnya menyempit. Aliran airnya langsung mengarah ke laut (Samudera Hindia dan Selat Bali). Sungai di kawasan Alas Purwo, secara umum berupa sungai-sungai kecil (aliran kurang dari 10 m dengan panjang kurang dari 5 Km), namun jumlahnya sangat banyak (sekitar 70 buah). Beberapa sungai, seperti Sunglon Ombo dan Sungai Pancur, berhubungan dengan sungai bawah tanah yang mengalir di bawah kompleks perbukitan atau lipatan kapur (daerah karst).Areal Banyuwangi Selatan merupakan tanjung yang menjorok ke laut dan terisolasi, sedangkan pemukiman penduduk dengan berbagai aktivitasnya berada di sebelah barat. Oleh karena itu, sungai-sungai yang terdapat di areal tersebut sebagian besar langsung ke laut tanpa melalui pusat aktivitas penduduk, terutama sungai-sungai yang bermuara ke pantai sebelah utara, timur dan selatan.
2.1.6 VegetasiDalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo terdapat lima vegetasi yaitu tipe vegetasi hutan bakau (mangrove), vegetasi hutan pantai, vegetasi hutan sawo kecik, vegetasi hutan hujan dataran rendah dan vegetasi padang rumput.a. Vegetasi hutan bakau (Mangrove)Vegetasi hutan bakau terdapat di daerah Segara Anakan, jenis tumbuhan yang terdapat dalam mangrove ini didominasi oleh jenis bakau (Rhizophora sp.), api-api (Avicenia sp.), dan pedada (Sonneratia sp.). kondisi hutan bakau di daerah ini masih cukup baik.b. Vegetasi hutan pantaiVegetasi hutan pantai terdapat di sepanjang pantai, jenis tumbuhan yang terdapat di dalamnya di dominasi oleh jenis waru laut (Hibiscus tiliaceus), ketapang (Terminalia catapa), nyemplung (Calophylum inophylum) dan keben (Baringtonia sp.). pada beberapa tempat dalam hutan pantai ini telah ditumbuhi semak belukar.c. Vegetasi hutan sawo kecikVegetasi hutan sawo kecik merupakan hutan murni sawo kecik (Manilkara kauki) yang tumbuh secara alami, terdapat di bagian barat kawasan yaitu sekitar Pancur sampai Plengkung.d. Vegetasi hutan dataran rendahVegetasi hutan dataran rendah terdapat dibagian tengah semenanjung Purwo, dimana didalamnya terdapat hutan bambu. Jenis tumbuhan yang terdapat didalamnya didominasi oleh jenis bendo (Artocarpus elasticus), ketangi (Lagerstromia sp.), dan kesambi (Schleichera oleosa).e. Vegetasi padang rumputVegetasi padang rumput terdapat di dua lokasi yaitu di Sembulungan dan Sadengan. Jenis rumput yang terdapat di vegetasi tersebut antara lain lamuran (Polytrias amaura), alang-alang (Imperata cylindrica), dan rumput gajah (Penisetum purpureum).
2.1.7 FaunaTaman Nasional Alas Purwo merupakan habitat dari beberapa satwa liar seperti lutung budeng (Trachypithecus auratus auratus), banteng (Bos javanicus javanicus), ajag (Cuonalpinus javanicus), burung merak (Pavo muticus), ayam hutan (Gallus gallus), rusa (Cervus timorensis russa), macan tutul (Panthera pardus melas), dan kucing bakau (Prionailurus bengalensis javanensis). Satwa langka dan dilindungi seperti penyu lekang (Lepidochelys olivacea), penyu belimbing (Dermochelys coriacea), penyu sisik (Eretmochelys imbricata), dan penyu hijau (Chelonia mydas).
2.1.8 FloraTumbuhan khas dan endemik pada taman nasional ini yaitu sawo kecik (Manilkara kauki) dan bambu manggong (Gigantochloa manggong). Tumbuhan lainnya adalah ketapang (Terminalia cattapa), nyamplung (Calophyllum inophyllum), kepuh (Sterculia foetida), keben (Barringtonia asiatica), dan 13 jenis bambu.
2.1.9 Objek WisataDisamping sebagai tempat penelitian dan menunjang kebudayaan kawasan Taman Nasional Alas Purwo juga merupakan tempat rekreasi dan pariwisata alam yang menarik. Beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi antara lain :a. Pantai PlengkungTerletak sekitar 24 km dari pintu masuk (Pasar Anyar) dan merupakan tempat terbaik untuk berselancar (surfing). Kawasan Pantai Plengkung mempunyai gelombang untuk berselancar yang sangat memikat dengan ketinggian gelombang rata-rata 4-6 m dan panjang gelombang sejauh 2 km bergerak susul menyusul sejauh 7 gelombang. Bagi pengunjung yang menginap pada pagi hari akan dihibur oleh kicauan berbagai jenis burung sedangkan pada malam hari menyajikan kesunyian hutan rimba.b. TrianggulasiTerletak 12 km dari pintu masuk (Pasar Anyar). Di kawasan ini pengunjung dapat menikmati pemandangan alam dengan pantai pasir putihnya serta deburan ombak laut selatan yang memikat.c. SadenganMerupakan tempat padang penggembalaan berbagai jenis satwa, sehingga dengan adanya menara pandang (Tower) dapat melihat beberapa atraksi satwa seperti banteng, kijang, babi hutan, merak dan ayam hutan serata beberapa jenis burung yang sedang mencari makan.d. NgagelanTerletak 7 km ke arah barat dari Pantai trianggulasi, terdapat tempat penetasan telur penyu dan tempat pemeliharaan anak penyu (tukik). Tempat ini merupakan pusat penelitian penyu yang ada di Taman Nasional Alas Purwo.
e. RowobendoTerletak 10 km dari pintu masuk (Pasar Anyar) terdapat penginggalan sejarah berupa Pura Agung yang menjadi tempat upacara pagar wesi bagi umta hindu yang diadakan dalam 210 hari sekali.f. PancurTerletak 3 km dari Pantai Trianggulasi dan dapat di tempuh dengan berjalan kaki. Di sepanjang Pantai Pancur akan disuguhi panorama yang cukup menarik dengan hamparan formasi karang hitan dan pasir gotri.g. Goa IstanaTerletak 2 km dari arah timur Pantai Pancur terdapat goa yang cukup terkenal yaitu Goa Istana yang pada umumnya digunakan sebagai tempat semedi. Selain itu juga terdapat goa-goa lainnya seperti Goa Padepokan dan Goa Putri.
2.2 Tinjauan Pustaka2.2.1 Ekosistem MangroveHutan mangrove seringkali disebut dengan hutan bakau. Akan tetapisebenarnya istilah bakau hanya merupakan nama dari salah satu jenis tumbuhanpenyusun hutan mangrove, yaitu Rhizopora spp. Oleh karena itu, istilah hutanmangrove sudah ditetapkan sebagai nama baku untuk mangrove forest (Dahuri, 1996). Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa Portugis mangue danbahasa Inggris grove. Kata mangrove dalam bahasa Inggris digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu spesies tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Sedangkan dalam bahasa Portugis, kata mangrove digunakan untuk menyatakan individu spesies tumbuhan, dan kata mangal untuk mengatakan komunitas tumbuhan tersebut (Macnae 1968 diacu dalam Kusmana et al. 2005). Mangrove merupakan pohon yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut (intertidal trees), ditemukan di sepanjang pantai tropis di seluruh dunia. Pohon mangrove biasanya dipengaruhi oleh pasang sehingga mangrove memiliki adaptasi fisiologis secara khusus untuk menyesuaikan diri dengan garam yang ada di dalam jaringannya. Mangrove juga memiliki adaptasi melalui sistem perakaran untuk menyokong dirinya di sedimen lumpur yang halus dan mentransportasikan oksigen dari atmosfer ke akar. Sebagian besar mangrove memiliki benih terapung yang diproduksi setiap tahun dalam jumlah besar dan terapung hingga berpindah ke tempat baru untuk berkelompok (Lewis 2004). Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis yang didominasi oleh beberapa jenis mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur (Bengen 2001). Taman Nasional Alas Purwo merupakan salah satu dari kawasan konservasi yang memiliki hutan mangrove, bahkan hutan mangrove yang ada adalah yang terutuh di Jawa Timur. Zona penyangga seluas 1.203 Ha, yang terbagi menjadi dua wilayah konservasi yaitu 803 Ha untuk Seksi Konservasi wilayah I (SKW) rowobendo, dan 400 Ha untuk Seksi Konservasi wilayah II (SKW) Muncar, diantaranya terdapat hutan mangrove (Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2001).Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landai. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung 6lumpur. Sedangkan di wilayah pessisir yang tidak terdapat muara sungai, hutanmangrove pertumbuhannya tidak optimal. Mangrove tidak atau sulit tumbuh di wilayah yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut kuat karenakondisi ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur, substrat yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Hal ini terbukti dari daerah persebaran mangrove di Indonesia yang umumnya terdapat di Pantai Timur Sumatera, Kalimantan, Pantai Utara Jawa dan Irian Jaya. Penyebaran hutan mangrove juga dibatasi oleh letak lintang karena mangrove sangat sensitif terhadap suhu dingin (Dahuri 1996).Bangen (2001) menyebutkan karakteristik hutan mangrove sebagaiberikut:a. Umumnya tumbuh pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung atau berpasir.b. Daerahnya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun yang hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan menentukan komposisi vegetasi hutan mangrove.c. Menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat.d. Terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Air bersalinitas payau (2-22 permil) hingga asin (mencapai 38 permil).
2.2.2 Struktur Vegetasi MangroveVegetasi hutan mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman jenisyang tinggi, dengan jumlah jenis tercatat sebanyak 202 jenis yang terdiri dari 89 jenis pohon, 5 jenis palem, 19 jenis liana, 44 jenis epifit dan 1 jenis sikas. Hanya terdapat kurang lebih 47 jenis tumbuhan yang spesifik hutan mangrove. Di dalam hutan mangrove, paling tidak terdapat salah satu jenis tumbuhan sejati penting/dominan yang termasuk ke dalam 4 famili: Rhizoporaceae (Rhizopora, Bruguiera dan Ceriops), Sonneratiaceae (Sonneratia), Avicenniaceae (Avicennia) dan Meliaceae (Xylocarpus) (Bengen 2001).Secara sederhana, mangrove umumnya tumbuh dalam 4 zona (Noor et al. 1999), yaitu:a. Mangrove terbukaDaerah yang paling dekat dengan laut, dengan substrat agak berpasir, sering ditumbuhi oleh Avicennia spp. Pada zonasi ini, biasanya berasosiasi dengan Sonneratia spp. yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang kaya bahan organik (Bengen 2001).
b. Mangrove TengahMangrove di zona ini terletak di belakang mangrove zona terbuka. Di zona ini umumnya didominasi oleh Rhizopora spp. Selain itu sering juga dijumpai Bruguiera spp. dan Xylocarpus spp. (Noor et al. 1999 dan Bengen 2001).c. Mangrove payauZona ini berada di sepanjang sungai berair payau sampai tawar. Zona ini biasanya didominasi oleh komunitas Nypa dan Sonneratia (Noor et al.1999).d. Mangrove daratanMangrove berada di zona perairan payau atau hampir tawar di belakang jalur hijau mangrove yang sebenarnya. Jenis-jenis yang utama ditemukan pada zona ini termasuk Ficus microcarpus, Intsia bijuga, N. fruticans, Lumnitzera racemosa, Pandanus sp. dan Xylocarpus moluccensis. Zona ini memiliki kekayaan jenis tinggi daripada zona lainnya (Noor et al.1999).Berdasarkan geomorfologi jenis hutan mangrove dapat diklasifikasikan sebagai berikut:1. Overwash mangrove forestMangrove merah merupakan jenis yang dominan yang sering dibanjiri dan dibilas oleh air pasang, menghasilkan ekspor bahan organik dengan tingkat yang tinggi. Tinggi pohon maksimal adalah sekitar 7 m.2. Fringe mangrove forestMangrove fringe ini ditemukan sepanjang terusan air, digambarkan sepanjang garis pantai yang tingginya lebih dari rata-rata pasang naik. Ketinggian mangrove maksimum adalah sekitar 10 m.3. Riverine mangrove forestKelompok ini mungkin adalah hutan yang tinggi letaknya sepanjang daerah pasang surut sungai dan teluk, merupakan daerah pembilasan reguler. Ketiga jenis bakau, yaitu putih (Laguncularia racemosa), hitam (Avicennia germinans) dan mangrove merah (Rhizophora mangle) yang terdapat di dalamnya. Tingginya rata-rata dapat mencapai 18-20 m.4. Basin mangrove forestKelompok ini biasanya adalah jenis yang kerdil terletak di bagian dalam rawa karena tekanan runoff terestrial yang menyebabkan terbentuknya cekungan atau terusan ke arah pantai. Bakau merah terdapat dimana ada pasang surut yang membilas tetapi ke arah yang lebih dekat pulau, mangrove putih dan hitam lebih mendominasi. Pohon dapat mencapai tinggi 15 m.5. Hammock forestBiasanya serupa dengan tipe (4) di atas tetapi mereka ditemukan pada lokasi sedikit lebih tinggi dari area yang melingkupi. Semua jenis ada tetapi tingginys jarang lebih dari 5 m.6. Scrub or dwarf forestJenis komunitas ini secara khas ditemukan di pinggiran yang rendah. Semua dari tiga jenis ditemukan tetapi jarang melebihi 1,5 m (4,9 kaki). Nutrien merupakan faktor pembatas ( Hutching, Saenger, 1987).
2.2.3 Keragaman Hayati di Hutan MangroveIndonesia terdapat perbedaan dalam hal keanekaragaman jenis mangrove antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Dari 202 jenis yang telah diketahui, 166 jenis terdapat di Jawa, 157 jenis di Sumatera, 150 jenis di Kalimantan, 142 jenis di Irian Jaya, 135 jenis di Sulawesi, 133 jenis di Maluku dan 120 jenis di Kepulauan Sunda Kecil. Pengecualian untuk di Pulau Jawa, meskipun memiliki keragaman jenis yang paling tinggi akan tetapi sebagian besar dari jenis-jenis yang tercatat berupa jenis gulma (seperti Chenopdiaceae, Cyperaceae, Poaceae).
2.2.4 Fungsi MangroveHutan mangrove menyediakan sejumlah manfaat secara ekologi meliputi stabilisasi sepanjang pantai, pereduksi ombak dan gelombang yang menyerang pantai dan perlindungan struktur pulau, pendukung perikanan laut (ikan dan kerang) secara langsung dan tidak langsung, penyedia makanan dan habitat dan 10pendukung populasi satwaliar meliputi burung penyeberang maupun burung air (Lewis 2004).Bengen (2001) menyebutkan fungsi dan manfaat mangrove sebagai berikut:a. Sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung dari abrasi, penahan lumpur dan penagkap sedimen.b. Penghasil sejumlah besar detritus dari daun dan dahan pohon mangrovec. Daerah asuhan (nursery grounds), daerah mencari makanan (feeding grounds) dan daerah pemijahan (spamming grounds) berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya.d. Penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku arang dan bahan kertas (pulp).e. Pemasok larva ikan, udang dan biota laut lainnya.f. Sebagai tempat pariwisata.
2.2.5 MikroalgaMikroalga merupakan bentuk tambahan yang palingprimitif. Tumbuhan ini umumnya hanya terdiri dari satu sel atau berbentuk seperti benang. Tumbuhan ini tampak warna-warni indah sesuai dengan zat warna atau pigmen yang dikandungnya. Umumnya lebih dikenal sebagai fitoplankton atau ganggan yang hidupnya melayang-layang di permukaan air laut ataupun air tawar.Berdasarkan pigmen spesifik yang terdapat dalam butir plastida, alga dikelompokkan dalam divisi Chlorophyta (alga hijau), Cyanophyta (alga hijau-biru), Euglenophyta, Rhodophyta (alga merah), phaeophyta (alga cokelat), Chrysophyta (alga emas) dan Pyrrophyta (alga pirang) (Sze, 1986).
a. Phylum ChlorophytaMenurut Herawati (1989), ciri-ciri chlorophyta, antara lain : Berwarna hijau karena proporsi pigmen pada chloroplas jauh lebihbanyak. Kebanyakan bersifat epiphytic sessik, comensalisme, atau simbiotiksebagian besar yang hidup di danau atau kolam bersifat sebagai planktondi laut, tidak ada yang bersifat pelagik. Dinding sel sebagian dalam terdiri dari 2 lapisan utama. Sering menyebabkan blooming perairan. Hidup melayang pada atau dekat permukaan air. Hidup secara koloni. Jika mati menghasilkan bau busuk.Menurut Alvyanto (2009), Chlorophyta (ganggang hijau) adalah salah satu kelas dari ganggang yang sel-selnya bersifat eukariotik (materi inti dibungkus oleh membran inti). Pigmen klorofil terdapat dalam jumlah banyak sehingga ganggang ini berwarna hijau. Pigmen lain yang dimiliki adalah korotan dan Nantafil.Alga hijau merupakan alga yang memiliki bentuk sel tunggal. Bentuk filament dari alga hijau adalah filament terapung atau terikat serta bentuk koloninya juga terapung. Chlorophyta berwarna hijau karena klorofil tidak tertutup pigmen lain. Alga hijau dapat ditemukan di air tawar maupun air laut dan beberapa lagi di darat. Sebagian besar alga hijau mengandung satu kloroplas per sel yang acapkali berisikan pusat-pusat pembentukan pati yang dinamakan pirenoid. Banyak alga hijau uniseluler dapat bergerak-gerak karena adanya flagella. Beberapa spesies dilengkapi alat pelekat yang menjangkarnya pada benda-benda yang terendam air atau tumbuhan air (Pelczar, 1986).Divisi Cholorophyta dibagi ke dalam dua kelas, yaitu kelas Chlorophyceae dan kelas Charophyceae.
a. ChlorophyceaeAlga ini merupakan kelompok terbesar dari vegetasi alga. Perbedaan dengan divisi lainnya karena memiliki warna hijau yang jelas seperti pada tumbuhan tingkat tinggi karena mengandung pigmen klorofil a dan klorofil b lebih dominan dibandingkan karotin dan xantofil. Hasil asimilasi dari beberapa amilum, penyusunnya sama pula seperti pada tumbuhan tingkat tinggi yaitu amilose dan amilopektin (Nontji, 1993).Menurut Taylor (1960) susunan tubuh bervariasi baik dalam ukuran, bentuk maupun susunannya. Untuk mencakup sejumlah besar variasi tersebut, maka alga hijau dikelompokkan sebagai berikut:1. Sel tunggal (uniseluler) dan motil, ex: Chlamydomonas2. Sel Tunggal (uniseluler) dan non motil, ex: Chorella3. Sel senobium, ex: Volvox dan Pandorina4. Koloni tak beraturan, ex: Tetraspora5. Filamen tak bercabang, ex: Ulotrix, Oedogonium6. Filamen bercabang, ex: Cladiphora, pithophora7. Heterotrikus, ex: Stigeoclonium8. Tubular, ex: Caulerpab. CharophyceaeCiri-ciri jenis alga Charophyceae, bentuk thallusnya menyerupai dan tumbuhan tinggi terdiferensiasi menjadi akar, batang dan daun.b. Phylum CyanophytaCyanophyta atau alga biru hijau dalah kelompok alga yang paling primitif dan memiliki sifat-sifat bakterial dan alga. Kelompok ini adalah organisme prokariot yang tidak memiliki struktur-struktur sel seperti yang ada pada algalainnya, contohnya nukleus dan chloroplast. Mereka hanya memiliki chlorophil , namun mereka juga memiliki variasi phycobilin seperti halnya carotenoid. Pigmen-pigmen ini memiliki beragam variasi sehingga warnanya bisa bermacam-macam dari mulai hijau sampai ungu bahkan merah. Alga biru hijau tidak pernah memiliki flagell, namun beberapa filamen membuat mereka bergerak ketika berhubungan dengan permukaan (Teguh, 2008).Menurut Herawati (1989), menyatakan bahwa ciri-ciri Cyanophyta adalah : Mengandung warna disebabkan oleh klorofil dan kadang juga oleh pigmen sel serta reaksi warna oleh pseudaracuce. Tidak mempunyai membran dan nucleolus Reproduksi secara aseksual. Sering menyebabkan blooming perairan. Dinding sel terdiri dari lapisan utama, bagian dalam dan luar Hidup melayang-layang dekat permukaan air Hidup berkoloni Jika mati menghasilkan bau busukDivisi Cyanophyta terdiri dari satu kelas yaitu Cyanophyceae yang terbagi menjadi tiga ordo yaitu Chroococcales, Oscillatoriales dan Chamaesiphona.a. Ordo ChroococcalesTidak menghasilkan spora, ciri-ciri tubuhnya unicell atau koloni. Reproduksinya dengan pembelahan sel bagi yang unicell dan fragmentasi untuk yang berkoloni. Terdapat 1 famili yaitu Chroococcaeae. Contoh genus yaitu Chroococcus, Merismopedia, Gleocapsa dan Microcystis.b. Ordo OscillatorialesTidak menghasilkan spora, seluruhnya berupa filament. Sebagian memiliki heterocyst dan sebagian lainnya tidak. Umumnya bereproduksi secara fragmentasi dan terkadang dengan akineta. Terdapat tiga famili, yaitu:1 Oscillatoriaceae: tidak memiliki heterocyst dan contoh genusnya adalah Oscilllatoria, Lyngbya, Spirullina, Arthrospira.2 Nostocaceae: memiliki heterocyst dan memproduksi akineta dan contoh genusnya adalah Anabaena, Nostoc.3 Rivulariaceae: memiliki heterocyst dan sebagian memproduksi akineta dan contoh genusnya adalah Rivularia, Gleotrichia.c. Ordo ChamaesiphonalesMenghasilkan spora, ciri tubuhnya unicell dan filament. Terdapat dua famili yaitu Chamaesiphonaceae dan Dernocarpaceae. Contoh genusnya ialah Chamaesiphon dan Dermocarpa (Anonim, 2009).c. Phylum EuglenophytaEuglenophyta merupakan organisme uniseluler yang bersifat autotrof, karena memiliki klirofil a dan b, karoten dan xanthofil yaitu astaxanthin yang dikenal juga sebagai euglenorodhon atau haematokrom. Kloroplast berbentuk bulat, seperti pita, binatang atau menyerupai jala. Mempunyai pirenoid. Cadangan makanan berupa paramilum (1-3 polimer glukosa) yang terletak di dalam sitoplasma. Euglenophyta disebut juga Euglenoidina, merupakan organisme yang mitl karena memiliki 1-3 flagell di bagian anteriornya. Sel organisme yang motil karena memiliki 1-3 flagella di bagian anteriornya. Sel organisme ini tidak memiliki dinding, tubuh hanya diliputi pellicle yang sering disebut periplas yang terletak tepat di bawah plasmalemma (Anonim, 2008).Phylum Euglenophyta terdiri dari satu kelas yaitu Euglenophyceae dengan ordo Euglenales, Peranemales/Eutreptiales dan Rhabdomonadales.a. Ordo EuglenalesPada ordo Euglenales terdapat satu famili yaitu Euglenaceae yang memiliki ciri-ciri sel uniseluler, mempunyai pembungkus yang terbuat dari gelatin disebut lorica, mempunyai cytoplasmic granula atau butir mucus yang berperan dalam pembentukkan kista serta memiliki cytosome dan bleplaroplast. Contoh genusnya adalah Euglena, Phacus, Trachelomonas.b. Ordo EutreptialesTerdapat satu famili yaitu Eutreptiaceae dimana contoh genusnya ialah Astacia (morfologi sama seperti Euglena), Peranema, Hyalophacus (Polunin, 1960).d. Phylum ChrysophytaMenurut Herawati (1989), ciri-ciri Chrysophyta , yaitu : Dapat berkembang cepat sebagai hava plankter Merupakan tanaman satu sel Value mengandung silika Reproduksi dengan sang pembelahan sel dan pembentukan spesies Reproduksi seksual dengan pembentukan auxosphoraChrysophyta / ganggang keasaman memiliki pigmen dominan hasoter berupa klorofil yang memberikan warna keasaman. Pigmen lainnya adalah yang uniseluler soliter (contohnya: ochromonas) ada juga yang berkoloni tidak bertogillum dan ada juga yang multiseluler (Herawati,1989).Berdasarkan Susunan dan bentuk serta kandungan zatnya, Chrysophyta terbagi menjadi kelas Xanthophyceae, Chrysophyceae dan Bacillariophyceae (Diatome).a. XanthophyceaeGanggang ini banyakditemukan hidup di air tawar, air laut dan tanah. Susunan tubuhnya mempunyai 3 bentuk yaitu berbentuk sel tunggal contohnya Botrydiopsis, berbentuk filament contohnya Tribonema, dan yang berbentuk tubular contohnya Vaucheria. Umumnya ganggang ini tidak mempunyai dinding sel, biasanya terdiri dari pectin dan silica. Terdiri dari 2 bagian yang saling menutupi, seperti halnya pada Tribonema sp. Ganggang jenis ini mempunyai alat gerak yang berupa 2 buah flagella yang tidak sama panjangnya, satu bagian terletak di ujung atau apical dan bagian yang lain terletak pada bagian anteriornya. Cadangan makanan berupa krisolaminarin yaitu lutein.b. Chrysophyceae atau alga coklat keemasanGanggang ini kebanyakan hidup di air laut atau air tawar. Susunan tubuhnya ada yang berbentuk sel tunggal, contohnya Chromonas dan ada yang berbentuk koloni, contohnya Synura. Umumnya ganggang ini tidak mempunyai dinding sel. Bila mempunyai dinding sel biasanya terdiri dari lokaria atau bisa juga tersusun dari lempengan silicon atau bisa juga dari cakram kalsium karbonat. Ganggang jenis ini mempunyai alat gerak yang berupa flagella yang tidak sama jumlahnya tiap marga. Cadangan makanan berupa tepung krisolaminarin.c. Bacillariophyceae atau alga diatomaeGanggang ini banyak ditemukan, hidup di air tawar, air laut dan tanah-tanah yang lembab. Susunan tubuhnya ada yang berbentuk sel tunggal dan ada juga yang berbentuk koloni dengan bentuk tubuh simetri bilateral (Pennales) dan simetri radial (Centrals). Terdapat dinding sel yang disebut frustula yang tersusun dari bagian dasar yang dinamakan hipoteka dan bagian tutup dinamakan epiteka dan juga sabuk atau singulum. Frustula ini tersusun oleh zat pectin yang dilapisi oleh silicon. Cadangan makanan berupa tepung krisolaminarin (Zaif,2009).e. Phylum RhodophytaMenurut Herawati (1989), menyatakan bahwa ciri-ciri Rhodophyta, antara lain : Hidup di laut Tubuh bersel banyak Mengandung pigmen pikoasilin Bentuk tubuh seperti rumput lautDalam sebagian besar ganggang merah (rhodophyta) telur berupa phyta/filament bercabang. Namun beberapa species ada yang berbentuk lembaran seperti porphyta/berbentuk sel tunggal. Beberapa ganggang merah dapat mengapur misalnya Corallina spp. Plasmoyesmata tampaknya tidak ada. Tapi banyak ganggang merah multikelula memuat koneksi (Chapman, V.J. and D.J. Chapman, 1980).f. Phylum Phyrrhophyta Phyrrhophyta atau ganggang api disebut juga Dinoflagelata karena memiliki alat gerak berupa flagella. Ganggang ini termasuk dalam calon kingdom Alveolata dalam sistem klasifikasi tiga dominan. Ganggang ini umumnya bersifat autotrof, namun ada sebagian spesies yang bersifat heterotrof parasitic (Sharma, 1992).Menurut Sze (1986), menyatakan bahwa Phyrrhophyta berasal dari lautan (dominan) tetapi ada beberapa ratus spesies yang lain yang berada di air segar. Phyrrhophyta memiliki variasi nutrisi yang besar dari autotropik ke bentuk heterotropik yang mana terdapat vertebrata parasit dan ikan atau alga phagocytiza yang lain.Phylum Phyrrhophyta terdiri dari dua kelas yaitu Desmophyceae dan Dinophyceaea. Kelas DesmophyceaeMemiliki flagel yang keluar dari ujung anterior (apikal, subapikal), pergerakan motil dan memiliki satu ordo yaitu Prorocentrales. Desmophyceae memiliki dinding sel yang tebal, tersusun atas dua belahan (theca). Bentuk tubuhnya speris, oval atau tetes air mata dan terdapat di air tawar, payau dan laut. Contohnya pada Prorocentrum.b. Kelas DinophyceaeFlagelnya keluar dari posisi ventral. Selain itu, salah satu flagella terdapat pada bagian transversal dan yang lainnya pada bagian longitudinal. Dinophyceae memiliki enam ordo antara lain Dinophysiales, Gymnodiniales, Noctilucales, Peridiniales, Gonyaulucales dan Pyrocystales.2.2.6 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan MikroalgaBermacam faktor fisik, komia dan biologi dapat mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup dan keanekaragaman mikroalga antara lain:1. Parameter fisika. CahayaFotosintesis hanya dapat berlangsung bila intensitas cahaya yang sampai ke suatu sel alga lebih besar daripada suatu intensitas tertentu. Hal ini berarti bahwa fitoplankton yang produktif hanyalah terdapat di lapisan-lapisan air teratas dimana intensitas cahaya cukup bagi kelangsungan fotosintesis. Kedalaman penetrasi cahaya di dalam perairan, yang merupakan kedalaman dimana produksi fitoplankton masih dapat berlangsung, bergantung pada beberapa faktor, antara lain absorpsi cahaya oleh air, panjang gelombang cahaya, kecerahan air, pemantulan cahaya oleh permukaan laut, lintang geografi dan musim.
BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN
3.1 Alat dan Bahan3.1.1 AlatPada penelitian ini dipergunakan beberapa alat bantu untuk mengambil sampel mikroalga dan pengukuran data fisik. Alat bantu tersebut antara lain botol film yang digunakan untuk menyimpan sampel mikroalga, botol semprot sebagai tempat aquades, buku identifikasi mikroalga sebagai panduan mengidentifikasi jenis mikroalga yang ditemukan, gayung dipergunakan untuk mengambil sampel air laut, kamera sebagai alat dokumentasi mikroalga yang ditemukan, kertas label untuk memberi keterangan pada botol sampel, mikroskop digunakan untuk melihat sampel mikroalga, pH meter dipergunakan untuk mengukur kadar keasaman air laut, pipet tetes diperlukan untuk mengambil sampel dari botol sampel, plankton net digunakan untuk menyaring dan mengumpulkan mikroalga, salinometer/SCT meter untuk mengukur kadar garam , segwidck rafter digunakan untuk melihat mikroalga pada sampel air di bawah mikroskop dan termometer untuk mengukur suhu air dan suhu udara.3.1.2 BahanAdapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah aquadesyang digunakan untuk membersihkan mikroalga yang tertinggal pada plankton net, CuSO4 untuk mempertahankan warna mikroalga, formalin 4% untuk mengawetkan mikroalga dan sampel air sebagai bahan yang akan diamati.3.2 Metode PenelitianMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan pengambilan sampel air yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan plankton net di lokasi hutan mangrove. 3.2.1 Metode Pengumpulan DataJenis mikroalga yang ditemukan di lapangan diidentifikasi dengan menggunakan buku identifikasi, yaitu The Marine Plankton of Japan tahun 1997, The Structure and Reproduction of the Algae tahun 1977 dan Identifying Marine Fitoplankton tahun 1997.
Gambar 3.1 Peta Lokasi PenelitianSumber Google Earth 2013Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jenis vegetasi yang tumbuh merupakan jenis vegetasi yang sanggup beradaptasi dengan perubahan kondisi yang berubah-ubah (Anwar, et al., 1984). Secara ekologis hutan mangrove berfungsi sebagai daerah pembesaran berbagai jenis ikan, udang, kerang-kerangan, dan spesies lainnya. Selain itu mangrove yang jatuh di perairan menjadi sumber pakan biota perairan dan unsur hara yang sangat menentukan produktivitas perikanan di perairan pesisir dan laut.
3.3 Analisis DataData yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan Indeks Kesamaan. Indeks Kesamaan yaitu parameter yang digunakan untuk membandingkan dua komunitas berbeda. Indeks yang digunakan adalah Indeks Simpson dan nilai indeks nilai penting (INP) dengan rumus sebagai berikut (Waite, 2000):3.3.1 Indeks DiversitasSimpsonIndek diversitas ini biasanya digunakan untuk plankton, yaitu dengan anggapan bahwa nilai diversitas Simpson yang lebih besar dari 0,6 merupakan ekosistem yang belum mengalami pencemaran oleh bahan organik.Rumus Indeks Diversitas Simpson:I = 1 DD = (ni/N)2Keterangan :I = indeks diversitas SimpsonD = resiprok indeks diversitas simpsonni = Jumlah individu jenis ke-iN = Jumlah total individu seluruh jeniskeanekaragaman Simpson dalam Odum (1971), yaitu:I = > 0,8, keanekaragaman tergolong tinggiI = 0,6 0,8, keanekaragaman tergolong sedangI = < 0,6, keanekaragaman tergolong rendah.
3.4 Prosedur Penelitian3.4.1 Penentuan Titik Pengamatan Memilih lokasi sampling pada dua lokasi perairan hulu dan hilir hutan mangrove. Menentukan 3 titik sampling pada masing-masing hulu dan hilir hutan mangrove dengan jarak yang berbeda-beda. Pada masing-masing titik sampling dilakukan pengambilan sampel mikroalga sebanyak 1 kali selama 2 hari.
3.4.2 Pengambilan Data Mikroalga Mengambil sampel mikroalga pada titik lokasi di hutan mangrove dengan menggunakan plankton net. Menyaring air sebanyak 50 L ke dalam plankton net. Menyiram permukaan dalam plankton net dengan akuades untuk melarutkan mikroalga yang menempel pada plankton net. Memberi formalin 4% dan CuSO4 pada sampel yang sudah diambil agar sampel tidak rusak dan diberi label. Mengambil sampel air sebanyak dua kali dengan interval waktu dua hari pada tempat yang sama.
3.4.3 Pengambilan Data Fisik Lapangan3.4.3.1 Suhu Air dan UdaraPengambilan data suhu air dilakukan dengan langkah-langah sebagai berikut: Mengikat termometer pada tali sepanjang kira-kira 60 cm. Mencelupkan ke dalam perairan sampai thermometer terendam. Menunggu hingga beberapa saat (5 menit) untuk mengukur suhu air. Mencatat suhu air yang tertera pada thermometer.
Pengambilan data suhu udara dilakukan dengan langkah sebagai berikut: Mengikat thermometer pada tali sepanjang kira-kira 60 cm Menggantungkan atau dibiarkan menggantung dalam waktu tertentu (5 menit) untuk mengukur suhu udara. Mencatat suhu udara yang tertera pada thermometer.
3.4.3.2 Salinitas Menyiapkan alat SCT meter sedemikian rupa sehingga alat tersebut siap digunakan. Mencelupkan elemen pengukur dalam air. Menunggu hingga muncul angka pada layar. Mencatat angka yang tertera pada layar.
3.4.3.3 Derajat Keasaman Menyiapkan alat pH meter sedemikian rupa sehingga alat tersebut siap digunakan. Mencelupkan elemen pengukur dalam air. Menunggu hingga muncul angka pada layar. Mencatat angka yang tertera pada layar.
3.4.3.4 Pengidentifikasian Sampel Mengidentifikasi mikroalga yang ditemukan dengan menggunakan Segwidck rafter yang diletakkan di bawah mikroskop. Mengambil foto mikroalga yang didapatkan. Memberi penamaan mikroalga dengan menggunakan kunci determinasi mikroalga.
DAFTAR PUSTAKAAlvyanto, Nugroho.2009.Algae.http://alvyanto.blogspot.com/2009/. Diakses tanggal 31 Januari 2013 pukul 19.00 WIB.Bengen DG; L Adrianto. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove. [makalah pad a Lokakarya Jaringan Kerja Pelestarian Mangrove]. Yogyakarta : Institut Pertanian Stiper.Chapman, V.J. and D.J. Chapman. 1980.Seaweed and Their Uses. Third edition.Chapman and Hall, New York: 30 - 97. Dahuri, R. 1996. An analysis of Enviromental Threath to Marine Fisheries inIndonesia. Paper Submited for Asia Pasific Fisheries Commision (APFIC) Symposium on Enviromental Aspects of Responsible Fisheries, Soul Republic of Korea. 15-18 Oct 1996.Herawati.1989.Pengantar Diklat Planktonologi.UI Press.JakartaSharma, OP. 1992. Text Book of Algae. TataMcGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi: 73 - 79. Sze, Philip. 1986.A Biology of the Algae. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, IA, pp. 143-169.Trono, G.C., Jr. and E.T.G. FORTES. 1988.Philippine Seaweeds. National Book Store, Inc. Publishers, Metro Manila, Philippines: 199-225.