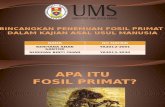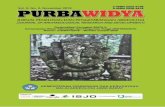Arkeologi pancasila
-
Upload
aufi-filla -
Category
Documents
-
view
258 -
download
1
description
Transcript of Arkeologi pancasila
-
1. KOMPETENSI DASAR1.1.Tujuan Umum Pembelajaran
Mengetahui proses pembentukan Pancasila Mengerti sejarah pemikiran dalam perumusan Pancasila Menerapkan nilai-nilai kearifan dalam dunia akademik
1.2 Tujuan Khusus Pembelajaran Memahami definisi arkeologi pancasila Mampu berpikir analitis Mengetahui fase pembuahan, perumusan dan pengesahan
Pancasila Mampu mengaplikasikan nilai kearifan dalam aktivitas ilmiah
2. PENDAHULUANDalam persilangan budaya nusantara, dikenal ada
empat era kultural. 1. Era pra-Hindu, era yang paling genuine dari
nusantara. Di era ini nusantara belum bersentuhandengan kebudayaan lain di luar dirinya. Era inimemuat nilai solidaritas, gotong royong dankekeluargaan.
2. Era Kerajaan Majapahit; era di mana nusantaramampu menjadi diri yang kuat, sebuah kepercayaandiri, keberanian dan kemandirian.
3. Era Kerajaan-kerajaan Islam. Di samping masihterpengaruh dari karakter-karakter era sebelumnya,di era ini juga muncul proses penggabungan unsur-unsur lokal dengan unsur Islam menjadi sebuah polabudaya baru, atau yang sering disebut dengan nalarsintesis.
4. Era Kolonial, sebuah era yang menindas,menghegemonik secara terstruktur. Pada masa initerjadi pemutusan mata rantai ekonomi, perdagangan,maritim, sikap hidup, serta nilai-nilai ketimuran.Muncul pula kolonialisme nalar dan mental;pembunuhan karakter dan identitas bangsa.
Era pra-Hindu, era kerajaan Majapahit dan era kerajaan-kerajaan Islam,menjadi pijakan historis para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila. Dariera-era tersebut digali dan disarikan kebudayaan yang kuat dan menjadipenggerak zaman di era masing-masing. Penemuan substansi kebudayaan itulahyang mendasari setiap sila dari Pancasila yang kemudian menjadi falsafah hidupbangsa Indonesia.
Sasaran akhir dari pokok pembahasan ini adalah pengungkapan danpemahaman akan proses pembentukan Pancasila, pemahaman nilai-nilai kearifandari pendiri bangsa, serta model baru pembacaan Pancasila.
3. Arkeologi Pancasila3.2 Definisi Arkeologi Pancasila
Arkeologi adalah proses kerja melalui arsip-arsip sejarah dari berbagaimasyarakat untuk menjelaskan pembentukan wacana yang telahmenghasilkan bidang-bidang pengetahuan dan pembentukan wacana dari
-
berbagai zaman atau era. Objek arkeologi adalah episteme: a). kerangkapemikiran khas suatu jaman. b) struktur pemikiran cara memberi maknapada dunia. Sementara mekanisme kerjanya adalah mengisolasi berbagaitatanan wacana yang mendasari syarat-syarat mengartikulasikan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan, proposisi dan pernyataan yang digunakanmasyarakat untuk memberi makna kepada sejarah.
Arkeologi Pancasila berarti proses kerja mengungkap arsip-arsip sejarahterbentuknya Pancasila dari berbagaro ragam pemikiran dari pendiribangsa yang telah menghasilkan bidang pengetahuan, nilai, dan kearifan.Dari model arkeologi ini, akan terlihat kekhasan pemikiran yang mewarnaiproses pembentukan Pancasila. Misalnya, sistem pemikiran Marxis,Islamis, hingga Nasionalis. Ketiga arus pemikiran ini begitu dominan danmembentuk suatu kerangka pemikiran khas di zamannya, pemikiran khastersebut adalah Pancasila itu sendiri.
3.3 Proses Pembentukan Pancasila
3.3.1 Fase PembuahanPada fase awal ini, menurut Soekarno, muncul tiga model paham
kebangsaan yang dominan, yakni:1. Nasionalistis 2. Islamistis3. Marxistis
Pada kenyataannya, ketiga paham pergerakan tersebut tidak salingmendominasi dan tidak pula menunjukkan keegoan masing-masing. Justrusejarah mencatat, terjadi sintesis ketiganya yang terangkum dalam SumpahPemuda: tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan. Hal ini menandakanbahwa fase ini telah mampu menemukan kode kebangsaan bersama (civicnationalism). Kode kebangsaan ini sangatlah penting sebagai tonggak awalpenyatuan berbagai ragam paham pergerakan yang selama waktu penjajahanberserakan dan berjalan sendiri-sendiri yang bercorak kedaerahan.
3.3.2. Fase PerumusanPerumusan dasar Negara Indonesia merdeka mulai dibicarakan pada masa
persidangan pertama BPUKP (29 Mei 1 Juni 1945). Anggota BPUPKI: 69 orang,Jepang membagi anggota BPUK menjadi lima golongan pergerakan, golonganIslam, golongan birokrat (kepala jawatan), wakil kerajaan (kooti), pangreh praja(residen/wakil residen, bupati, wali kota), dan golongan peranakan: peranakanTionghoa (4 orang), peranakan Arab (1 orang) dan peranakan Belanda (1 orang).Tidak semua anggota BUPK beranggotakan laki-laki, dua di antaranya adalahNy.Maria Ulfa Santoso dan Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito, yang ternyataadalah perempuan, sehingga istilah founding fathers tidak tepat.
Dalam Perumusan dasar negara, anggota-anggota BPUPK memunculkanpentingnya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasipermusyawaratan, nilai keadilan/kesejahteraan sosial.Prinsip-prinsip di atas dianggap masih serabutan, belum ada yang merumuskansecara sistematis dan holistic sebagai dasar Negara yang koheren. Mr. Yamin danSoepomo barangkali yang mendekati permintaan Radjiman sebagai ketuaBPUPK, namun dalam kategorisasi yang dikemukakan Yamin tidak semuadimasukkan sebagai dasar negara. Guna menjawab permintaan Radjiman Wediodiningrat, tanggal 1 Juni 1945, BungKarno berpidato tentang falsafah negara atau dasar negara yang berisi:
-
1. Kebangsaan; tidak menolak perbedaan.2. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan; tidak ekploitatif; 3. Mufakat atau Demokrasi; tidak tirani mayoritas atas minoritas.4. Kesejahteraan Sosial; yang berbasis pada kekeluargaan, bukan berbasis
individualistik.5. Ketuhanan yang Berkebudayaan; yang toleran
Soekarno memunculkan istilah PANCA SILA, pilihan bilangan limamencerminkan bahwa bilangan tersebut mempunyai nilai keramat bagiantropologi masyarakat Indonesia. Pada umat Islam sendiri, lima merupakanrukun Islam, sementara dalam tradisi Jawa ada lima larangan sebagai kode etik ,yang disebut istilah Mo-limo. Taman Siswa dan Chuo Sangi In juga memilikiPanca Dharma.
Selain itu menurut Soekarno, urutan kelima sila itu sebagi urutansequential, bukan urutan prioritas. Bahwa dalam suatu majelis yang terdiri darikeragaman elemen, seruan kea rah titik persetujuan itu harus dimulai denganmengangkat keragaman ke dalam suatu kode kemunitas politik bersama, yaknientitas kebangsaan. Tetapi, tidaklah berarti bahwa sila-sila berikutnya sebagaiderivasi dari sila kebangsaan. Masing-masing sila Pancasila merupakan satukesatuan integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci.
Sungguhpun Soekarno telah mengajukan lima sila dari dasar Negara, diajuga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya ada yang tidak menyukaibilangan lima, sekaligus juga cara Soekarno menunjukkan dasar dari segaladasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bisa diperas menjadi Tri Sila bahkan bisadikerucutkan lagi menjadi Eka Sila.Dasar dari semua sila Pancasila adalah gotong-royong, maknanya adalah:
1. Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong-royong (ketuhanan yangberkebudayaan, yang lapang dan toleran), bukan ketuhanan yang salingmenyerang dan mengucilkan.
2. Prinsip internasionalismenya harus berjiwa gotong-royong (yangberperikemanusiaan dan berperikeadilan), bukan internasionalisme yangmenjajah dan eksploitatif.
3. Prinsip kebangsaannya berjiwa gotong-royong (mampu mengembangkanpersatuan dari aneka perbedaan, bhineka tunggal ika), bukanperbedaan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan.
4. Prinsip demokrasi juga harus berjiwa gotong-royong (mengembangkanmusyawarah mufakat), bukan demokrasi yang didikte oleh suaramayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elit penguasa-pemodal(minorokrasi).
5. Prinsip kesejahteraannya harus berjiwa gotong-royong (mengembangkanpartisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangatkekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualism-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu sepertidalam sistem etatisme.
3.3.3 Fase PengesahanSoekarno mengambil inisiatif informal dengan membentuk Panitia Kecil
(tidak resmi) yang beranggotakan 9 yang kemudian dikenal panitia Sembilan.Panitia ini bertugas menyusun rancangan Pembukaan Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia, yang di dalamnya memuat Dasar Negara. PanitiaSembilan ini pun diketuai oleh Soekarno, yang dibentuk sebagai ikhtiar untukmempertemukan pandangan antara dua golongan yang menyangkut dasarkenegaraan. Panitia Sembilan ini pun akhirnya berhasil menyetujui rancangan
-
pembukaan UUD yang kemudian ditandatangani oleh setiap anggota PanitiaSembilan pada 22 Juni. Oleh Soekarno rancangan Pembukaan UUD ini diberinama Mukaddimah, oleh M. Yamin dinamankan Piagam Jakarta, dan olehSukiman Wirjosandjojo disebut Gentlemens Agreement
Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mencerminkan usaha kompromi antaragolongan Islam dan kebangsaan. Titik temu antara kedua golongan tersebutdiikat pada alenia ketiga Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengandidorong oleh keinginan yang luhur, supaya bekehidupan kebangsaan yangbebas Alinea ini mencerminkan pandangan golongan kebangsaan yangmenitikberatkan kebangsaan yang bebas dan golongan Islam yangmelandaskan perjuangannya atas rahmat Allah. Menurut Muhammad Yamin,dengan menyebut Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, KonstitusiRepublik Indonesia berlindung kepada Allah, dan dengan itu maka syaratagama dipenuhi dan rakyat pun tentu menimbulkan perasaan yang baikterhadap dasar Negara ini.
Ujung dari kompromi ini bermuara pada alinea terakhir yang mengandungrumusan dasar negara berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila Islam tidakdijadikan dasar Negara (dan agama negara), tetapi terjadi perubahan tata urutPancasila dari susunan yang dikemukakan Soekarno pada 1 Juni. PrinsipKetuhanan dipindah dari sila terakhir ke sila pertama, ditambah dengan anakkalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tambahan inilah yang kemudian dikenal dengan tujuhkata. Bagi golongan Islam, penambahan tujuh kata itu dianggap pentingsebagai bentuk politik pengakuan. Seperti dinyatakan oleh PrawotoMangkoesasmito, golongan Islam sepakat dengan semua sila Pancasila, namunmenuntut penambahan tujuh kata dari sila Ketuhanan karena hal itu menandaihal yang penting. Bahwa Islam yang selama zaman kolonial terus dipinggirkanakan mendapat tempat yang layak dalam negara Indonesia.
Selain itu, prinsip internasionalisme atau peri-kemanusiaan tetapdiletakkan pada sila kedua, namun redaksinya mengalami penyempurnaanmenjadi Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip Mufakat ataudemokrasi berubah posisinya dari sila keempat menjadi sila kelima. Bunyinyamenjadi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Respon tajam dari Latuharhary soal tujuh kata, tambahan anak kalimat,dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyadianggap diskriminatif sehingga harus dicoret. Tentang pencoretan tujuh katatersebut, Mohammad Hatta punya andil besar, seperti yang diakui sendiri dalamotobiografinya Memoir Mohammad Hatta (1979). Pagi hari menjelang dibukanyarapat PPKI, Hatta mendekati tokoh-tokoh agar bersedia mengganti kalimatKetuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyadalam rancangan Piagam Jakarta dengan kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa.Alasannya demi menjaga persatuan bangas. Atas usulan tersebut tokoh-tokohIslam akhirnya menyetujui pencoretan tujuh kata tersebut.
3.4. NIlai Kearifan dari Perumus PancasilaDari proses pembentukan Pancasila yang sungguh melibatkan segala
emosi, pengetahuan, hasrat dan sebagainya dari para pendiri bangsa ini, dapatditemukan nilai-nilai kearifan yang bisa diambil:
Pertama, kesediaan berdialog dan terbuka terhadap semua golongan,agama, etnis, paham kebangsaan yang berbeda tanpa bersikap hegemonik(memaksakan pendapat) apalagi anarkhis. Ini merupakan lompatan demokrasiyang mendahului zaman, di mana dalam proses dialektika yang panjang dan
-
berliku para pendiri bangsa dengan tangguh dan penuh kesabaran mampumengelola perbedaan untuk mencapai titik temu.
Kedua, dalam perbedaan pendapat apapun, yang paling ekstrim sekalipun,terutama terkait dengan persoalan yang mendasar harus diperlukan peranantara (liminal) untuk menjadi jembatan dan sekaligus menjembatani dua titikperbedaan. Peran antara harus aktif untuk turun-naik, kanan-kiri atau bahkanmondar-mandir dalam mempertemukan perbedaan pandangan.
Ketiga, hal menarik yang dapat ditarik dari proses pembentukan Pancasilaadalah penemuan hal yang baru. Meskipun merupakan karya bersama, tetapiPancasila dan segenap nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya semuanyaadalah origin dan kreasi baru dari para pendiri bangsa ini. Penting untukditekankan dalam dunia akademik, bahwa pengulangan sebuah pendapat atausebuah teori telah mambawa civitas akademik yang berhenti pada kejumudanberpikir, kemalasan, dan bahkan menandakan kemunduran peradaban sebuahbangsa. Diperlukan nalar imaginatif untuk menghasilkan sebuah karya barusehingga tidak selalu terjadi pengulangan-pengulangan karya-karya ilmiah. 3.4 Ziarah Ilmiah-Filosofis Pancasila
Sebagaimana diketahui bahwa pemahaman Pancasila selama ini lebihmenekankan pada negara, artinya penekanan pada membangun negara(state building) dan mendukung penguatan koorporatis negara. Smentarapada level warga negara lebih diarahkan pada kepatuhan terhadap rezimatau penguasa dan mendukung pada status-quo. Kuatnya peran negaradalam menjadikan Pancasila sebagai ideology tertutup dan legitimasipenguasa Orde Baru waktu itu terlihat dari nilai moral P4 sebagai tafsirantunggal penguasa, sementara corak pedidikannya bersifat indoktrinasidan hegemonik. Intervensi rezim untuk menitipkan kepentingannyasangat kuat sehingga rentan terhadap perubahan rezim atau mengikutiselera kepentingan penguasa. Di samping itu, selama ini dalammemahami Pancasila tidak jelas akar keilmuan (body of knowledge) yangdigunakan. Kajian ilmiah terhadap Pancasila harus bersifat interdisiplin,artinya berbagai ragam keilmuan bisa saling terkoneksi untuk memahamiPancasila. Misalnya, pendekatan filosofis menggunakan ilmu filsafat,sementara pendekatan ilmiah dapat digunakan ilmu hukum, sosial danhumaniora.
Perjalanan meletakkan Pancasila sebagai dasar, episteme, pengarahdan sekaligus pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara hinggasekarang masih mengalami persoalan. Problem-problem tersebut diantaranya adalah pembelokan tafsir sebuah rezim, disensus sebagaiideologi negara dari kelompok tertentu, hingga kesenjangan yang begitutajam antara gagasan ideal Pancasila berupa praktek kebangsaan yangkorup, kehidupan beragama yang tidak toleran bahkan cenderung anarkis,kapitalisasi pendidikan dan seterusnya. Kita lalu bertanya, di mana basiskarakter, kepribadian, etika, kemanusiaan dan keadaban yang selama inidiagungkan?
Pancasila memang bukan teks suci, sakral, layaknya wahyu yangturun dari langit, Pancasila adalah teks kultural, teks kebudayaan, iaadalah hasil pergumulan dan dialektika panjang para pendiri bangsadengan kearifan-kearifan nusantara dan teori-teori modern. Sebagai tekskebudayaan, Pancasila harus menjadi teks terbuka untuk ditafsirkan
-
ulang, tak boleh ada monopoli tafsir sebab hal ini rentan denganpembatasan kebenaran dan kepentingan untuk legitimasi kekuasaan olehrezim tertentu. Sebuah rezim kuasa bisa saja mengartikan Pancasilasebagai senjata untuk menciptakan kepatuhan dan penyeragaman atasnama pragmatisme sebuah rezim.
Pluralitas dalam sebuah penafsiran bukanlah mengandaikanrelativitas nilai, di mana setiap orang mengklaim kebenaran masing-masing, akan tetapi dalam perbedaan sebuah interpretasi harus terusmenerus didiskursuskan di ruang-ruang publik sehingga ditemukansebuah konsesus bersama, interpretasi baru, hingga temuan baru.Sebagai ideologi terbuka, Pancasila sangat terbuka untuk didialogkandengan ideologi lain yang kini masih saja berambisi menggeserPancasila. Tak perlu apriori dengan mengatakan Pancasila sudah tak saktilagi, justru Pancasila memberi ruang pada kita untuk tidak hanya sekedartahu, tetapi untuk lebih mengerti (tafsir produktif) atas nilai-nilaikeagamaan, kemanusiaan, keadilan, keragaman, dan kesejahteraan yangkemudian diimplementasikan dalam tindakan nyata.
Ringkasnya, menurut Yudi Latief, ada tiga langkah untukmembumikan Pancasila dalam konteks sekarang;
1. Historis, pijakan tradisi dan local wisdom2. Rasionalitas (dielaktika dengan filsafat dan etika politik
kontemporer)3. Aktualisasi
REFERENSI
Kaelan, 1998, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Yogyakarta: ParadigmaLatief, Yudi, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan
Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia
Notonegoro, 1975, Pancasila Ilmiah Populer, Jakarta: Pantjuran TujuhSutrisno, Slamet, 2006, Filsafat dan Ideologi Pancasila, Yogyakarta:
Penerbit AndiRandhal dan Bucher, 1986, Philosophy an Introduction, 11th printing,
Oxford University., New York.