APLIKASI KLINIS.doc
-
Upload
rizkirijatullah -
Category
Documents
-
view
15 -
download
3
Transcript of APLIKASI KLINIS.doc

A. APLIKASI KLINIS
1. Atherosklerosis
Atherosklerosis salah satu bentuk dari arteriosklerosis yaitu berarti pengerasan
dinding arteri yang terjadi penebalan dan kehilangan elastisitas dindingnya (Sarjadiet
al., 2008). Atherosklerosister bentuk dari lesiintisel yang disebut atheromas (biasa
disebut atheromatous atau plak atherosklerotik) yang menghambat pada lumen
pembuluh darah. Plak atheromatous terdiri dari lesi yang lunak, berwarna kuning, inti
berasal dari lipid (biasanya kolesterol dan kolesterol ester) yang tertutup oleh jaringan
ikat fibrous putih.Secara pembentukan obstruksi dari aliran darah, atherosklerotik
dapat rupture, menuju pembuluh darah kecil dan terjadi thrombosis; plak juga akan
melunakkan bagian dalam dan akan menjadi aneurisma (Kumar et al., 2010).
Menurut Studi Jantung dan resiko atherosclerosis dari Framingham, ketika ketiga
faktor resiko dating bersamaan (hiperlipidemia, hipertensi dan merokok), resiko dari
infark myokard meningkat 7 kali lipat. Ada 3 faktor resiko yang tidak dapat diubah,
yaitu umur, jenis kelamin, dan genetik. Untuk faktor resiko yang dapat diubah, yaitu
hiperlipidemia, hipertensi, merokok, Diabetes melituster masuk hiperkolesterolemia.
Dan beberapa faktor resiko lainnya adalah inflamasi, hiperkromosistinemia,
sindromametabolik, lipoprotein (a), faktor yang mempengaruhi hemostasis (Kumar et
al., 2010).
Patogenesis dari atherosclerosis sendiri berdasar akan respon dari cedera, dimana
akan terjadi inflamasi kronik dan respon dari penyembuhan dari dinding arteri pada
cedera endotel. Lesi akan progresif menuju lipoprotein yang termodifikasi, PMN,
limfosit T danselsel lain yang bergabung pada dinding arteri (Kumar et al., 2010).
Arterosklerosis berupa penebalan lapisan intima pembuluh darah karena adanya
deposit lemak dan jaringan ikat, yang bisa berakibat fatal apabila mengenai pembuluh
darah yang mendarahi organ vital. Tahap awal kelainan berupa “foam cells” yang
berkembang menjadi “fatty streak” (garis lemak. Dengan adanya respon radang yang
menyertai, maka terjadilah suatu plak aterom. Pada plak aterom mudah terjadi
kalsifikasi maupun ulserasi dinding pembuluh darah. Plak aterom yang banyak akan
menyebabkan terjadinya penyempitan dan kekakuan pembuluh darah (Sarjadiet al.,
2008).
.

Gambar 2.1 Patogenesis Atheroskelrosis
Dari gambar di atas dapat dilihat atherosclerosis diproduksi dari beberapa gejala
patologik:
1. Cedera endotel, menyebabkan kenaiakan permeabilitas pembuluh darah,
adesileukosit, dantrombosis
2. Akumulasi dari lipoprotein (biasanya LDL dan bentuk teroksidasinya) pada
pembuluh darah.
3. Adesi Monosit ke endotel, diikuti dengan migras imenuju tunika intima dan
berubah menjadi makrofag dan sel foam.
4. Adesi platelet

5. Faktor-faktor, seperti dari aktivasi platelet, makrofag dan dinding vaskular yang
akan menginduksi sel otot polos.
6. Proliferasi sel otot polos dan produksi ECM
7. Akumulasi lipid dari ekstraselullar dan antara sel (makrofag dan sel otot polos)
(Kumar et al., 2010)
Konsekuensi dari aetherosklerosis biasanya menginduksi banyak organ target
diantaranya otak, jantung, ginjal, dan ekstremitas bawah. Infark Miokard (serangan
jantung), infark pada cerebral (stroke), aneurisma aorta, gangrene ekstremitas bawah
(Kumar et al., 2010).
2. Hipertensi
a. Definisi
Tekanan darah adalah desakan darah terhadap dinding-dinding arteri ketika
darah tersebut dipompa dari jantung ke jaringan. Tekanan darah merupakan gaya
yang diberikan darah pada dinding pembuluh darah. Tekanan ini bervariasi sesuai
pembuluh darah terkait dan denyut jantung. Tekanan darah pada arteri besar
bervariasi menurut denyutan jantung. Tekanan ini paling tinggi ketika ventrikel
berkontraksi (tekanan sistolik) dan paling rendah ketika ventrikel berelaksasi
(tekanan diastolik) (Kaplan, 2008)
Tekanan darah digolongkan normal jika tekanan darah sistolik tidak
melampaui 140 mmHg dan tekanan darah diastolik tidak melampaui 90 mmHg
dalam keadaan istirahat, sedangkan hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang
bersifat abnormal. Tekanan darah normal bervariasi sesuai usia, sehingga setiap
diagnosis hipertensi harus bersifat spesifik usia. Secara umum, seseorang dianggap
mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya lebih tinggi dari 140 mmHg
sistolik atau 90 mmHg diastolik (ditulis 140/90) (Gunawan, 2011)
Hipertensi adalah desakan darah yang berlebihan dan hampir konstan pada
arteri. Hipertensi juga disebut dengan tekanan darah tinggi, dimana tekanan
tersebut dihasilkan oleh kekuatan jantung ketika memompa darah sehingga
hipertensi ini berkaitan dengan kenaikan tekanan sistolik dan tekanan diastolik.
Standar hipertensi adalah sistolik ≥ 140 mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg
(Gunawan, 2011).
b. Etiologi
Berdasarkan penyebab, hipertensi dibagi menjadi dua golongan yaitu
hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya

dijumpai lebih kurang 90 % dan hipertensisekunder yang penyebabnya diketahui
yaitu 10 % dari seluruh hipertensi (Suyono, 2011; Gunawan-Lany, 2005)
Menurut Sunarta Ann dan peneliti lain, berdasarkan penyebabnya hipertensi
dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu (WHO, 2005; Gunawan,
2011; Sheps, 2005; Mansjoer-Arif et all):
1) Hipertensi Primer
Artinya hipertensi yang belum diketahui penyebabnya dengan jelas.
Berbagai faktor yang diduga turut berperan sebagai penyebab hipertensi primer
seperti bertambahnya umur, stress psikologis, dan hereditas (keturunan). Sekitar
90 % pasien hipertensi diperkirakan termasuk dalam kategori ini. Pengobatan
hipertensi primer sering dilakukan adalah membatasi konsumsi kalori bagi
mereka yang kegemukan (obes), membatasi konsumsi garam, dan olahraga.
Obat antihipertensi mungkin pula digunakan tetapi kadang-kadang
menimbulkan efek samping seperti meningkatnya kadar kolesterol, menurunnya
kadar natrium (Na) dan kalium (K) didalam tubuh dan dehidrasi.
2) Hipertensi Sekunder
Artinya penyebab boleh dikatakan telah pasti yaitu hipertensi yang
diakibatkan oleh kerusakan suatu organ. Yang termasuk hipertensi sekunder
seperti : hipertensi jantung, hipertensi penyakit ginjal, hipertensi penyakit
jantung dan ginjal, hipertensi diabetes melitus, dan hipertensi sekunder lain
yang tidak spesifik
c. Klasifikasi
1) Klasifikasi tekanan darah berdasarkan JNC 7:
Tabel 1 klasifikasi tekanan darah (JNC 7, 2003)

2) Klasifikasi menurut WHO
Tabel 2 Klasifikasi tekanan darah (WHO, 2004)
d. Faktor resiko
1) Faktor yang tidak dapat diubah/dikontrol
a) Umur
Hipertensi erat kaitannya dengan umur, semakin tua seseorang
semakin besar risiko terserang hipertensi. Umur lebih dari 40 tahun
mempunyai risiko terkena hipertensi. Dengan bertambahnya umur,
risiko terkena hipertensi lebih besar sehingga prevalensi hipertensi
dikalangan usia lanjut cukup tinggi yaitu sekitar 40 % dengan kematian
sekitar 50% diatas umur 60 tahun (Yundini, 2006).
Arteri kehilangan elastisitasnya atau kelenturannya dan tekanan
darah seiring bertambahnya usia, kebanyakan orang hipertensinya
meningkat ketika berumur lima puluhan dan enam puluhan (Staessen et
all, 2013). Hal ini disebabkan juga oleh perubahan alami pada jantung,
pembuluh darah dan hormon. Tetapi bila perubahan tersebut disertai
faktor-faktor lain maka bisa memicu terjadinya hipertensi (Gunawan,
2011).
b) Jenis Kelamin
Ahli lain mengatakan pria lebih banyak menderita hipertensi
dibandingkan wanita dengan rasio sekitar 2,29 mmHg untuk
peningkatan darah sistolik. Sedangkan menurut Arif Mansjoer, dkk,
pria dan wanita menapouse mempunyai pengaruh yang sama untuk
terjadinya hipertensi. Menurut MN. Bustan bahwa wanita lebih banyak

yang menderita hipertensi dibanding pria, hal ini disebabkan karena
terdapatnya hormon estrogen pada wanita (Bustan, 2007).
c) R i w a y a t Keluarga
Menurut Nurkhalida, orang-orang dengan sejarah keluarga yang
mempunyai hipertensi lebih sering menderita hipertensi. Riwayat
keluarga dekat yang menderita hipertensi (faktor keturunan) juga
mempertinggi risiko terkena hipertensi terutama pada hipertensi
primer (Nurkhalida, 2013). Keluarga yang memiliki hipertensi dan
penyakit jantung meningkatkan risiko hipertensi 2-5 kali lipat (Chunfang
Qiu, 2013).
d ) G e n e t i k
Peran faktor genetik terhadap timbulnya hipertensi terbukti
dengan ditemukannya kejadian bahwa hipertensi lebih banyak pada
kembar monozigot (satu sel telur) daripada heterozigot (berbeda sel
telur). Seorang penderita yang mempunyai sifat genetik hipertensi
primer (esensial) apabila dibiarkan secara alamiah tanpa intervensi terapi,
bersama lingkungannya akan menyebabkan hipertensinya berkembang
dan dalam waktu sekitar 30-50 tahun akan timbul tanda dan gejala
(Chunfang Qiu, 2013).
2) Faktor yang dapat diubah/dikontrol
a) Kebiasaan Merokok
Rokok juga dihubungkan dengan hipertensi. Hubungan antara rokok
dengan peningkatan risiko kardiovaskuler telah banyak dibuktikan. Selain
dari lamanya, risiko merokok terbesar tergantung pada jumlah rokok yang
dihisap perhari. Seseoramg lebih dari satu pak rokok sehari menjadi 2
kali lebih rentan hipertensi dari pada mereka yang tidak merokok
(Price, 2005).
Zat-zat kimia beracun, seperti nikotin dan karbon
monoksida yang diisap melalui rokok, yang masuk kedalam aliran darah
dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri dan mengakibatkan
proses aterosklerosis dan hipertensi (Nurkhalida, 2013).
Nikotin dalam tembakau merupakan penyebab meningkatnya
tekanan darah segara setelah isapan pertama. Seperti zat-zat kimia lain

dalam asap rokok, nikotin diserap oleh pembuluh-pembuluh darah amat
kecil didalam paru-paru dan diedarkan ke aliran darah. Hanya dalam
beberapa detik nikotin sudah mencapai otak. Otak bereaksi terhadap
nikotin dengan memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas
epinefrin (adrenalin). Hormon yang kuat ini akan menyempitkan
pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat karena
tekanan yang lebih tinggi (Sheps, 2005).
b) Konsumsi Asin/Garam
Secara umum masyarakat sering menghubungkan antara konsumsi
garam dengan hipertensi. Garam merupakan hal yang sangat penting
pada mekanisme timbulnya hipertensi. Pengaruh asupan garam
terhadap hipertensi melalui peningkatan volume plasma (cairan
tubuh) dan tekanan darah. Keadaan ini akan diikuti oleh peningkatan
ekskresi kelebihan garam sehingga kembali pada keadaan hemodinamik
(sistem pendarahan) yang normal. Pada hipertensi esensial mekanisme ini
terganggu, di samping ada faktor lain yang berpengaruh (Radecki, 2010).
Garam merupakan faktor yang sangat penting dalam patogenesis
hipertensi. Hipertensi hampir tidak pernah ditemukan pada suku bangsa
dengan asupan garam yang minimal. Asupan garam kurang dari 3 gram
tiap hari menyebabkan prevalensi hipertensi yang rendah, sedangkan jika
asupan garam antara 5-15 gram perhari prevalensi hipertensi meningkat
menjadi 15-20 %. Pengaruh asupan terhadap timbulnya hipertensi terjadi
melalui peningkatan volume plasma, curah jantung dan tekanan darah
(Radecki, 2010; Gunawan, 2005).
c) Konsumsi Lemak Jenuh
Kebiasaan konsumsi lemak jenuh erat kaitannya dengan peningkatan
berat badan yang berisiko terjadinya hipertensi. Konsumsi lemak jenuh
juga meningkatkan risiko aterosklerosis yang berkaitan dengan
kenaikan tekanan darah. Penurunan konsumsi lemak jenuh, terutama
lemak dalam makanan yang bersumber dari hewan dan peningkatan
konsumsi lemak tidak jenuh secukupnya yang berasal dari minyak
sayuran, biji-bijian dan makanan lain yang bersumber dari tanaman
dapat menurunkan tekanan darah (Gunawan, 2005).

d) Kebiasaan Konsumsi Minum Minuman Beralkohol
Alkohol juga dihubungkan dengan hipertensi. Peminum alkohol
berat cenderung hipertensi meskipun mekanisme timbulnya hipertensi
belum diketahui secara pasti. Orang- orang yang minum alkohol terlalu
sering atau yang terlalu banyak memiliki tekanan yang lebih tinggi dari
pada individu yang tidak minum atau minum sedikit (Suyono, 2011; Hull-
Alison, 2006).
e) Obesitas
Obesitas atau kegemukan dimana berat badan mencapai indeks
massa tubuh > 25 (berat badan (kg) dibagi kuadrat tinggi badan (m)) juga
merupakan salah satu faktor risiko terhadap timbulnya hipertensi. Obesitas
merupakan ciri dari populasi penderita hipertensi. Curah jantung
dan sirkulasi volume darah penderita hipertensi yang obesitas lebih
tinggi dari penderita hipertensi yang tidak obesitas. Pada obesitas
tahanan perifer berkurang atau normal, sedangkan aktivitas saraf simpatis
meninggi dengan aktivitas renin plasma yang rendah (Teodosha S, 2010).
f) Olahraga
Olahraga banyak dihubungkan dengan pengelolaan hipertensi, karena
olahraga isotonik dan teratur dapat menurunkan tahanan perifer yang
akan menurunkan tekanan darah. Olahraga juga dikaitkan dengan
peran obesitas pada hipertensi. Kurang melakukan olahraga akan
meningkatkan kemungkinan timbulnya obesitas dan jika asupan
garam juga bertambah akan memudahkan timbulnya hipertensi (Teodosha
S, 2010).
g) Stres
Hubungan antara stres dengan hipertensi diduga melalui aktivitas
saraf simpatis, yang dapat meningkatkan tekanan darah secara bertahap.
Apabila stress menjadi berkepanjangan dapat berakibat tekanan darah
menjadi tetap tinggi. Hal ini secara pasti belum terbukti, akan tetapi pada
binatang percobaan yang diberikan pemaparan tehadap stress
ternyata membuat binatang tersebut menjadi hipertensi (Ferketich et Al,
2010)
h) Penggunaan esterogen

Estrogen meningkatkan risiko hipertensi tetapi secara epidemiologi
belum ada data apakah peningkatan tekanan darah tersebut disebabkan
karena estrogen dari dalam tubuh atau dari penggunaan kontrasepsi
hormonal estrogen (Runo R, 2013) MN Bustan menyatakan bahwa
dengan lamanya pemakaian kontrasepsi estrogen (± 12 tahun berturut-
turut), akan meningkatkan tekanan darah perempuan (Bustan, 2007).
e. Patofisiologi hipertensi
Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah
terletak di pusat vasomotor, pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula
jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar dari
kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan
pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui
saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion melepaskan
asetilkolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh
darah, dimana dengan dilepaskannya norepinefrin mengakibatkan konstriksi
pembuluh darah (corwin, 2007).
Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi
respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokontriktor. Individu dengan
hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun tidak diketahui dengan
jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi (corwin,2007).
Pada saat bersamaan dimana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh
darah sebagai respon rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang
mengakibatkan tambahan aktivitas vasokontriksi. Medula adrenal mengsekresi
epinefrin yang menyebabkan vasokontriksi. Korteks adrenal mengsekresi kortisol
dan steroid lainnya, yang dapt memperkuat respon vasokontriktor pembuluh darah.
Vasokontriksi yang mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal, menyebabkan
pelepasan renin. Renin merangsang pembentukan angiotensin I yang kemudian
diubah menjadi angiotensin II, suatu vasokonstriktor kuat, yang pada gilirannya
merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan
retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume
intravaskuler. Semua faktor tersebut cenderung mencetus keadaan hipertensi
(corwin, 2007).

Perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh darah perifer
bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada lanjut usia.
Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan
penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah, yang pada gilirannya
menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh darah.
Konsekuensinya, aorta dan arteri besar berkurang kemampuannya dalam
mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung (volume sekuncup),
mengakibatkan penurunan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer
(Corwin,2007).
f. Penegakkan diagnosis hipertensi
1) Anamnesis
Anamnesis dilakukan untuk mengetahui faktor resiko dari pasien. Gejala
yang sering muncul (Panggabean, 2009) :
a) Gejala yang sering dikeluhkan :
i) Sakit kepala/migraine
ii) Rasa berat/tegang pada bagian tengkuk
iii) Takikardia
iv) Dada terasa berat/sesak
v) Mudah lelah
vi) pusing
vii) Epistaksis
b) Riwayat Penyakit Dahulu :
i) Riwayat hipertensi
ii) Riwayat penggunaan OAH
iii) Obesitas, DM, Penyakit Jantung Koroner, penyakit ginjal
c) Riwayat Penyakit Keluarga
Riwayat keluarga mengalami hipertensi ataupun penyakit
kardiovaskular lain.
2) Pemeriksaan Fisik (Panggabean, 2009) :
a) Vital sign (Tek. darah, Denyut nadi, RR, Suhu)
Tekanan darah diukur sebanyak 2-3 kali dalam keadaan pasien istirahat
atau relaks.
b) Antropometri (BB, TB, Lingkar pinggang)
c) Kepala dan leher

d) Toraks
i) Inspeksi : melihat bentuk dada, ictus cordis
ii) Palpasi : menilai denyut iktus kordis
iii) Perkusi : menentukan batas jantung
iv) Auskultasi : mendengarkan bunyi jantung normal (S1, S2, S3, S4)
atupun bunyi jantung tambahan serta suara napas
e) Abdomen : hati, lien, ginjal
f) Ekstremitas : sianosis, clubbing finger
3) Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk dapat mengetahui ada tidaknya
penyakit yang mendasari kejadian hipertensi dari pasien, meliputi (Panggabean,
2009):
a) Pemeriksaan darah rutin
b) Pemeriksaan darah khusus
c) Urinalisis (protein, leukosit, eritrosit)
d) Elektrolit darah
e) Ureum/kreatinin
f) Pemeriksaan Gula darah
g) Pemeriksaan profil lipid
h) EKG
3. Atrial Flutter
a. Definisi
Atrial flutter adalah takikardi yang dihasilkan oleh rapid electrical circuit
di atrium. Atrial flutter secara tipikal berasal dari atrium kanan dan seringkali
melibatkan large circuit yang melintasi seluruh area valva tricuspidalis antara
atrium kanan dan ventrikel kanan, atrial flutter ini disebut typical atrial flutter.
Terkadang atrial flutter dihasilkan oleh sirkuit di area lain dari atrium kanan atau
kiri yang menyebabkan takikardi, atrial flutter ini disebut atypical atrial flutter
(Dhar et al, 2009).
b. Etiologi
Beberapa hal yang bisan menyebabkan AFL adalah (Boyer dan Koplan,
2005):
1) Coronary Artery Disease (CAD)

CAD merupakan kausa utama AFL. CAD terjadi ketika arteri coronaria
terblok oleh plak. Akumulasi kolesterol bisa menyebabkan kekakuan pada
arteri sehingga memperlambat bahkan menghambat total sirkulasi darah. Hal
tersebut bisa merusak miokardium, atrium atau ventrikel dan pembuluh darah.
2) Open-Heart Surgery
Open-heart surgery bisa meninggalkan luka parut di jantung. Hal ini
menyebabkan obstruksi impuls.
3) Stress
Stress meningkatkan heart rate.
c. Faktor Risiko
Faktor risiko AFL di antaranya (Dhar et al, 2009):
1) Merokok
2) Penyakit jantung
3) Hipertensi
4) Penyakit katup jantung
5) Penyakit paru
6) Depresi
7) Obat-obatan
d. Patofisiologi
Typical Atrial flutter (AFL) adalah masuknya kembali irama atrium kanan
yang dibatasi oleh annulus tricuspidalis (anterior) dan crista terminalis dan valva
Eustachii (posterior). AFL bisa mengalir dengan searah (clockwise) atau
berlawanan (counterclockwise) jarum jam. Pada counterclockwise AFL,
gelombang berjalan di sekeliling annulus tricuspid di bidang frontal. Gelombang
aktif akan turun melalui anterolateral atrium kanan dan naik melalui dinding
atrium kanan (counterclockwise rotation in the left anterior oblique view),
ditambah lagi dengan adanya passing antara vena cava inferior dan cincin
trikuspid, area ini disebut sebagai cavotricuspid isthmus (CTI). Lama siklus ini
secara tipikal 200-240 ms (Dhar et al, 2009).
Reverse atau clockwise rotation (naik ke anterolateral atrium kanan dan
turun melaui dinding atrium kanan), bisa dikenali dengan defleksi positif yang
lebar pada sadapan inferior. Atypical atrial flutter adalah jenis lain dari takikardi
dengan kriteria EKG yang tidak sesuai dengan typical (counterclockwise) and

reverse typical (clockwise) flutter patterns. Atypical AFL menghasilkan lebih
banyak pola EKG dan lebih dari satu sirkuit. AFL butuh barrier anatomi atau
fungsional untuk aktivasi siklus (Dhar et al, 2009).
Gambar II.1 Patofisiologi Atrial Flutter (Iwasaki et al, 2011)

Iwasaki Y, dkk. 2011. “Atrial Fibrillation Pathophysiology”. Circulation American Heart Association. 124: 2264-2274.
Dhar, Sunnil, dkk. 2009. “Current Concepts and Management Strategies in Atrial Flutter”. Southern Medical Journal. Vol 102: 9.
Boyer, Melissa dan Bruce A. Koplan. 2005. “Atrial Flutter”. Circulation American Heart Association. 112: e334-e336.
Corwin, Elizabeth J. 2007. Buku Saku Patofisiologi Edisi 3 Revisi. Jakarta: Penerbit
Buku Kedokteran EGC. bagian fisiologi fakultas kedokteran universitas
Sumatra utara.
Departemen Kesehatan RI. 2006. Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Hipertensi.
Jakarta: Bakti Husada.
Djarwoto, B. 2012. Penangan Hipertensi Terkini, Yogyakarta: FK UGM.
Gunawan. 2011. Hipertensi. Jakarta: PT Gramedia.
Jakarta: Perhimpunan Hipertensi Indonesia (Perhi).
Kaplan M. Norman. 2008. Measurenment of Blood Pressure and Primary Hypertension:
Pathogenesis in Clinical Hypertension: Seventh Edition. Baltimore, Maryland
USA: Williams & Wilkins. H:28-46.
Kumar, V., Abbas, AK., Fausto, N., & Aster, JC. 2010. Robbins and Cotran Phatologic
Basis of Disease, Eigth Edition. Philadelphia: Saunders, an imprint of Elsevier,
Inc.
Management of High Blood Pressure in Adults: Report From the Panel Members
Appointed to the Eight Joint National Committtee (JNC 8). 2014 Guideline for
Management of High Blood Pressure, pp. 1-14.
Nurkhalida. 2013. Warta Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Depkes RI.
Panggabean MM. 2009. Penyakit Jantung Hipertensi. Buku Ajar ilmu Penyakit Dalam
Edisi V, Jilid II. Jakarta : Interna Publishing

Sarjadi, Putranto, BE.,Sadhana, U., Wijaya, I. 2008.
PanduanPraktikumPatologiAnatomi II. Semarang:
BadanPenerbitUniversitasDiponegoro.
Sheps, Sheldon G. 2005. Mayo Clinic Hipertensi: Mengatasi Tekanan Darah Tinggi.
Jakarta: PT Intisari Mediatama.
Yundini. 2006. Faktor Risiko Hipertensi. Jakarta: Warta Pengendalian Penyakit
Tidak Menular.
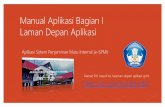


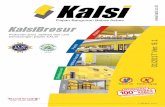





![tugas aplikasi komputer [aplikasi perpustakaan]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/5571fa56497959916991df34/tugas-aplikasi-komputer-aplikasi-perpustakaan.jpg)











