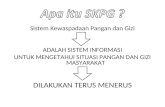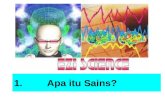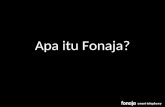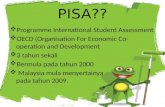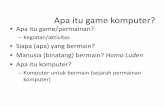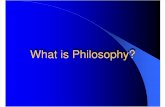Apa itu Artritis gout.docx
-
Upload
dina-mailana -
Category
Documents
-
view
153 -
download
3
Transcript of Apa itu Artritis gout.docx
Apa itu Artritis gout
Arthritis pirai atau gout adalah suatu proses inflamasi yang terjadi karena deposisi kristal asam urat pada jaringan sekitar sendi. gout juga suatu istilah yang dipakai untuk sekelompok gangguan metabolik yang ditandai dengan meningkatnya konsentrasi asm urat (hiperurisemia). Gout dapat bersifat primer maupun sekunder. Gout primer merupakan akibat langsung pembentukan asam urat tubuh yang berlebihan atau ekskresi asam urat yang berkurang akibat proses penyakit lain atau pemakaian obat tertentu. Ada sejumlah faktor yang agaknya mempengaruhi timbulnya penyakit gout, termasuk diet, berat badan, dan gaya hidup. ( Misnadiarly, 2009 )
Arthritis pirai (gout) adalah penyakit yang sering ditemukan dan tersebar diseluruh dunia. Artitis pirai merupakan kelompok penyakit heterogen sebagai akibat deposisi Kristal monosodium urat pada jaringan atau akibat supersaturasi asam urat di dalam ekstraseluler. Manifestasi klinis deposisi urat meliputi artitis gout akut, akumulasi kristal pada jaringan yang merusak tulang, batu asam urat dan yang jarang adalah gagal ginjal. Gangguan metabolisme yang mendasarkan gout adalah hiperurisemia yang didefinisikan sebagai peninggian kadar urat lebih dari 7,0 ml/dl dan 6,0 mg/dl. ( Edward Stefanus, 2010 )
Gout merupakan penyakit dominan pada pria dewasa. Sebagai mana yang disampaikan oleh Hipocrates bahwa gout jarang pada pria sebelum masa remaja sedangkan pada wanita jarang sebelum menopause. Pada tahun 1986 dilaporkan prevalensi gout di Amerika Serikat adalah 13,6/1000 pria dan 6,4/1000 perempuan. Prevalensi gout bertambah dengan meningkatnya taraf hidup. Prevalensi diantara pria African American lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok pria Caucasian. ( Edward Stefanus, 2010 )
Di Indonesia belum banyak publikasi epidemiologi tentang artitis pirai (AP). Pada tahun 1935 seorang dokter kebangsaan belanda bernama Van der Horst telah melaporkan 15 pasien artitis pirai dengan kecacatan dari suatu daerah di Jawa Tengah. Penilaian lain mendapatkan bahwa pasien gout yang berobat rata-rata sudah mengidap penyakit selama lebih dari 5 tahun. Hal ini mungkin disebabkan banyak pasien gout yang mengobati sendiri. Satu study yang lama di Massachusetts mendapat lebih dari 1% dari populasi dengan kadar asam urat kurang dari 7 mg/100ml pernah mendapat serangan artitis gout akut.
2.2 Definisi Artritis Pirai ( Gout )
Berikut ini pengertian Gout dari beberapa ahli, diantaranya:
a. Artritis pirai ( Gout ) adalah kelompok penyakit heterogen sebagai akibat deposisi kristal monosodium urat pada jaringan atau akibat supersaturasi asam urat didalam cairan ekstraselular. (Edward Stefanus, 2010 )
b. Gout merupakan kelainan metabolisme purin bawaan yang ditandai dengan peningkatan kadar asam urat serum dengan akibat penimbunan kristal asam urat di sendi.( Syamsuhidayat dan Wim de Jong, 2004 )
c. Arthritis pirai atau gout adalah suatu proses inflamasi yang terjadi karena deposisi kristal asam urat pada jaringan sekitar sendi. ( Misnadiarly, 2009 )
d. Arthritis gout adalah penyakit dimana terjadi penumpukan asam urat ( uric acid ) dalam tubuh secara berlebihan. ( VitaHealth, 2007 )
2.3 Etiologi Artritis Pirai ( Gout)
Faktor-faktor yang berpengaruh sebagai penyebab gout adalah:
a. Faktor keturunan dengan adanya riwayat gout dalam silsilah keluarga
b. Meningkatnya kadar asam urat karena diet tinggi protein dan makanan kaya senyawa purin lainnya. Purin adalah senyawa yang akan dirombak menjadi asam urat dalam tubuh
c. Konsumsi alkohol berlebih, karena alkohol merupakan salah satu sumber purin yang juga dapat menghambat pembuangan urin melalui ginjal.
d. Hambatan dari pembuangan asam urat karena penyakit tertentu, terutama gangguan ginjal. Pasien disarankan meminum cairan dalam jumlah banyak . minum air sebanyak 2 liter atau lebih tiap harinya membantu pembuangan urat, dan meminimalkan pengendapan urat dalam saluran kemih.
e. Penggunaan obat tertentu yang meningkatkan kadar asam urat, terutama diuretika ( furosemid dan hidroklorotiazida )
f. Penggunaan antibiotika berlebihan yang menyebabkan berkembangnya jamur, bakteri dan virus yang lebih ganas.
g. Penyakit tertentu dalam darah ( anemia kronis ) yang menyebabkan terjadinya gangguan metabolism tubuh, missal berupa gejala polisitomia dan leukemia.
h. Faktor lain seperti stress, diet ketat, cidera sendi, darah tinggi dan olahraga berlebihan.( VitaHealth, 2007 )
2.4 Faktor Resiko Artritis Pirai ( Gout )
Faktor resiko arthritis pirai antara lain:
a. Riwayat keluarga atau genetic
b. Asupan senyawa purin berlebih dalam makanan
c. Konsumsi alkohol berlebihan
d. Berat badan berlebihan ( obesitas )
e. Hipertensi, penyakit jantung
f. Obat-obatan tertentu ( terutama diuretika )
g. Gangguan fungsi ginjal
h. Keracunan kehamilan ( preeklampsia ) ( VitaHealth, 2007 )
2.5 Macam-macam Arthritis Pirai ( Gout )
Pembagian arthritis gout terdiri dari arthritis gout akut, interkritikal gout dan gout menahun dengan tofi. Ketiga stadium ini merupakan stadium yang klasik dan didapat deposisi progesif kristal urat.
a. Stadium arthritis gout akut
Radang sendi pada stadium ini sangat akut dan yang timbul sangat cepat dalam waktu singkat. Pasien tidur tanpa ada gejala apa-apa, pada saat bangun pagi terasa sakit yang hebat dan tidak dapat berjalan. Biasanya bersifat monoartikuler dengan keluhan utama berupa nyeri, bengkak, terasa hangat, merah dengan gejala sistemik berupa demam, menggigil dan merasa lelah. Lokasi yang paling sering pada MTP-1 yang biasanya disebut podagra. Apabila proses penyakit berlanjut, dapat terkena sendi lain yaitu pergelangan tangan atau kaki, lutut dan siku. Pada serangan akut yang tidak berat, keluhan-keluhan dapat hilang dalam beberapa jam atau hari. Pada serangan akut berat dapat sembuh dalam beberapa hari sampai beberapa minggu.
Faktor pencetus serangan akut antara lain berupa trauma local, diet tinggi purin, kelelahan fisik, stress, tindakan operasi, pemakaian obat diuretic, atau penurunan dan peningkatan asam urat. Penurunan asam urat darah secara mendadak dengan alopurinol atau obat urikosurik dapat menebabkan kekambuhan.
b. Stadium interkritikal
Stadium ini merupakan kelanjutan dari stadium akut dimana terjadi periode interkritik asimptomatik. Walaupun secara klinik tidak didapatkan tanda-tanda radang akut namun pada aspirasi sendi ditemukan Kristal urat. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradangan tetap berlanjut, walaupun tanpa keluhan. Keadaan ini dapat terjadi satu atau beberapa kali pertahun, atau dapat sampai 10 tahun tanpa serangan akut. Apabila tanpa penanganan yang baik dan pengaturan asam urat yang tidak benar, maka dapat timbul serangan akut lebih sering yang dapat mengenai beberapa sendi dan biasanya lebih berat. Manejemen yang tidak baik, maka keadaan interkritik akan berlanjut menjadi stadium menahun dengan pembentukan tofi.
c. Stadium arthritis gout menahun
Stadium ini umumnya pada pasien yang melakukan pengobatan sendiri (self medication) sehingga dalam waktu lama tidak berobat secara teratur pada dokter. Arthritis gout menahun biasanya disertai tofi yang banyak dan terdapat poliartikular. To fi ini sering pecah dan sulit sembuh dengan obat, kadang-kadang dapat timbul infeksi sekunder. Pada tofus yang besar dapat dilakukan ekstirpasi, namun hasilnya kurang memuaskan. Lokasi tofi yang paling sering pada cuping telinga, MTP-1, olekranon, tendon Achilles dan jari tangan. Pada stadium ini kadang-kadang disertai batu saluran kemih sampai penyakit ginjal menahun.
2.6 Patogenesis Artritis Pirai ( Gout )
Awitan (onset) serangan gout akut berhubungan dengan perubahan kadar asam urat serum, meninggi ataupun menurun. Pada kadar urat serum yang stabil, jarang mendapat serangan. Pengobatan dini dengan alopurinol yang menurunkan kadar urat serum dapat mempresipitasi serangan Gout akut. Pemakaian alkohol berat pada pasien gout dapat menimbulkan fluktuasi konsentrasi urat serum.
Penurunan urat serum dapat mencetuskan pelepasan Kristal monosodium urat dari depositnya dalam tofi ( crystals shedding ). Pada beberapa pasien gout atau yang dengan hiperurisemia asimptomatik Kristal urat ditemukan pada sendi metatarsofalangeal dan lutut yang sebelumnya tidak pernah mendapat serangan akut. Dengan demikian, gout seperti juga pseudogout, dapat timbul pada keadaan asimptomatik. Pada penelitian didapat 21% pasien gout dengan asam urat normal. Terdapat peranan temperature, pH, dan kelarutan urat untuk timbul seranga gout akut. Menurunnya kelarutan sodium urat pada temperature lebih rendah pada sendi perifer seperti kaki dan tangan, dapat menjelaskan mengapa Kristal MSU diendapkan pada kedua tempat tersebut. Predileksi untuk pengendapan Kristal
MSU pada metatarsofalangeal- 1 (MTP-1) berhubungan juga dengan trauma ringan yang berulang-ulang pada daerah tersebut.
Penelitian Simkin didapatkan kecepatan difusi molekul urat pada ruang sinovia kedalam plasma hanya setengah kecepatan air. Dengan demikian konsentrasi urat cairan sendi seperti MTP-1 menjadi seimbang dengan urat dalam plasma pada siang hari selanjutnya bila cairan sendi direabsorbsi waktu berbaring, akan terjadi peningkatan kadar urat local. Fenomena ini dapat menerangkan terjadinya awitan (onset) gout akut pada malam hari pada sendi yang bersangkutan. Keasaman dapat meninggikan nukleasi urat in vitromelalui pembentukan dari protonated solid phases. Walaupun kelarutan sodium urat bertentangan terhadap asam urat, biasanya kelarutan ini meninggi, pada penurunan pH dari 7,5 menjadi 5,8 dan pengukuran pH serta kapasitas buffer pada sendi dengan gout, gagal untuk menentukan adanya asidosis. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pH secara akut tidak signifikan mempengaruhi pembentukan Kristal MSU sendi.
Peradangan atau inflamasi merupakan reaksi penting pada arthritis gout terutama pada gout akut. Reaksi inni merupakan reaksi pertahanan tubuh non spesifik untuk menghindari kerusakan jaringan akibat agen penyebab. Tujuan dari proses inflamasi adalah:
a. Menetralisir dan menghancurkan agen penyebab;
b. Mencegah perluasan agen penyebab kejaringan yang lebih luas.
Peradangan pada arthritis gout akut adalah akibat penumpukan agen penyebab yaitu Kristal monosodium urat pada sendi. Mekanisme peradangan ini belum diketahui secara pasti. Hal ini diduga oleh peranan mediator kimia dan selular. Pengeluaran berbagai mediator peradangan akibat aktivasi melalui berbagai jalur, antara lain aktivitas komplemen (C) dan selular. ( Edward Stefanus, 2010 )
2.7 Patofisiologi arthritis pirai ( Gout )
Banyak faktor yang berperan dalam mekanisme serangan gout. Salah satunya yang telah diketahui peranannya adalah kosentrasi asam urat dalam darah. Mekanisme serangan gout akut berlangsung melalui beberapa fase secara berurutan.
a. Presipitasi kristal monosodium urat.
Presipitasi monosodium urat dapat terjadi di jaringan bila kosentrasi dalam plasma lebih dari 9 mg/dl. Presipitasi ini terjadi di rawan, sonovium, jaringan para- artikuler misalnya bursa, tendon, dan selaputnya. Kristal urat yang bermuatan negatif akan dibungkus (coate) oleh berbagai macam protein. Pembungkusan dengan IgG akan merangsang netrofil untuk berespon terhadap pembentukan kristal.
b. Respon leukosit polimorfonukuler (PMN)
Pembentukan kristal menghasilkan faktor kemotaksis yang menimbulkan respon leukosit PMN dan selanjutnya akan terjadi fagositosis kristal oleh leukosit.
c. Fagositosis
Kristal difagositosis olah leukosit membentuk fagolisosom dan akhirnya membram vakuala disekeliling kristal bersatu dan membram leukositik lisosom.
d. Kerusakan lisosom
Terjadi kerusakn lisosom, sesudah selaput protein dirusak, terjadi ikatan hidrogen antara permukan kristal membram lisosom, peristiwa ini menyebabkan robekan membram dan pelepasan enzim-enzim dan oksidase radikal kedalam sitoplasma.
e. Kerusakan sel
Setelah terjadi kerusakan sel, enzim-enzim lisosom dilepaskan kedalam cairan sinovial, yang menyebabkan kenaikan intensitas inflamasi dan kerusakan jaringan.
( Khaidir Muhaj, 2010 )
2.8 Pathway Artritis Pirai ( Gout )
Terlampir
2.9 Manifestasi Klinik Artritis Pirai ( Gout )
Tanda dan gejala arthritis gout secara umum adalah sebagai berikut:
a. Nyeri hebat yang tiba-tiba menyerang sendi pada saat tengah malam, biasanya pada ibu jari kaki ( sendi metatarsofalangeal pertama ) atau jari kaki ( sendi tarsal )
b. Jumlah sendi yang meradang kurang dari empat ( oligoartritis ) dan serangannya pada satu sisi ( unilateral )
c. Kulit berwarna kemerahan, terasa panas, bengkak, dan sangat nyeri
d. Pembengkakan sendi umumnya terjadi secara asimetris ( satu sisi tubuh )
e. Demam, dengan suhu tubuh 38,30C atau lebih, tidak menurun lebih dari tiga hari walau telah dilakukan perawatan
f. Ruam kulit, sakit tenggorokan, lidah berwarna merah atau gusi berdarah
g. Bengkak pada kaki dan peningkatan berat badan yang tiba-tiba
h. Diare atau muntah. ( VitaHealth, 2007 )
2.10Komplikasi Pasien dengan Artritis Pirai ( Gout )
Komplikasi yang muncul akibat arthritis pirai antara lain:
a. Gout kronik bertophus
Merupakan serangan gout yang disertai benjolan-benjolan (tofi) di sekitar sendi yang sering meradang. Tofi adalah timbunan kristal monosodium urat di sekitar persendian seperti di tulang rawan sendi, sinovial, bursa atau tendon. Tofi bisa juga ditemukan di jaringan lunak dan otot jantung, katub mitral jantung, retina mata, pangkal tenggorokan.
b. Nefropati gout kronik
Penyakit tersering yang ditimbulkan karena hiperurisemia. terjadi akibat dari pengendapan kristal asam urat dalam tubulus ginjal. Pada jaringan ginjal bisa terbentuk mikrotofi yang menyumbat dan merusak glomerulus.
c. Nefrolitiasi asam urat (batu ginjal)
Terjadi pembentukan massa keras seperti batu di dalam ginjal, bisa menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Air kemih jenuh dengan garam-garam yang dapat membentuk batu seperti kalsium, asam urat, sistin dan mineral struvit (campuran magnesium, ammonium, fosfat).
d. Persendian menjadi rusak hingga menyebabkan pincang
e. Peradangan tulang, kerusakan ligament dan tendon
f. Batu ginjal ( kencing batu ) serta gagal ginjal ( Emir Afif, 2010 )
BAB III
MANAJEMEN KLIEN DENGAN GOUT
3.1 Penatalaksanaan Medis
Pengobatan dilakukan secara dini agar tidak terjadi kerusakan sendi atau komplikasi lain misalnya pada ginjal. Pengobatan arthritis gout akan bertujuan menghilangkan keluhan nyeri sendi dan peradangan dengan obat-obatan, antara lain:
a. Kolkisin
1) Indikasi : penyakit gout (spesifik)
2) Mekanisme kerja : Menghambat migrasi granulosit ke tempat radang menyebabkan mediator berkurang dan selanjutnya mengurangi peradangan. Kolkisin juga menghambat pelepasan glikoprotein dari leukosit yang merupakan penyebab terjadinya nyeri dan radang sendi pada gout.
3) Dosis : 0,5 – 0,6 mg tiap satu jam atau 1,2 mg sebagai dosis awal dan diikuti 0,5 – 0,6 mg tiap 2 jam sampai gejala penyakit hilang atau mulai timbul gejala saluran cerna, misalnya muntah dan diare. Dapat diberikan dosis maksimum sampai 7 – 8 mg tetapi tidak melebihi 7,5 mg dalam waktu 24 jam. Untuk profilaksis diberikan 0,5 – 1,0 mg sehari.
4) Pemberian IV : 1-2 mg dilanjutkan dengan 0,5 mg tiap 12 – 24 jam dan tidak melebihi 4 mg dengan satu regimen pengobatan. Indikasi pemberian secara intravena :terjadi komplikasi saluran cerna, serangan akut pada pasca operatif, bila pemberian oral pasca akut tidak menunjukkan perubahan positif.
5) Efek samping : muntah, mual, diare dan pengobatan harus dihentikan bila efek samping ini terjadi walaupun belum mencapai efek terapi. Bila terjadi ekstravasasi dapat menimbulkan peradangan dan nekrosis kulit dan jaringan lemak. Pada keracunan kolkisin yang berat terjadi koagulasi intravascular diseminata.
b. Obat Anti Inflamasi Non Steroid (OAINS)
1) Indometasin
a) Indikasi : penyakit arthritis reumatid, gout, dan sejenisnya.
b) Mekanisme kerja : efektif dalam pengobatan penyakit arthritis reumatid dan sejenisnya karena memiliki efek anti-inflamasi dan analgesik-antipiretik yang sebanding dengan aspirin. Indometasin
dapat menghambat motilitas leukosit polimorfonuklear (PMN). Absorpsi indometasi cukup baik dengan pemberian oral dengan 92 – 99% terikat pada protein plasma. Metabolismenya terjadi di hati dan diekskresi dalam bentuk asal maupun metabolit lewat urin dan hempedu. Waktu parah plasma kira-kira 2 – 4 jam.
c) Dosis : 2 – 4 kali 25 mg sehari
d) Kontra indikasi : anak, wanita hamil, pasien gangguan psikiatri, pasien dengan penyakit lambung
e) Efek samping : amat toksik sehingga dapat menyebabkan nyeri abdomen, diare, pendarahan lambung, pancreatitis, sakit kepala yang hebat disertai pusing, depresi, rasa bingung, halusinasi, psikosis, agranulositosis, anemia aplastik, trombositopena, hiperkalemia, alergi
2) Fenilbutazon
a) Dosis : bergantung pada beratnya serangan. Pada serangan berat : 3 x 200 mg selama 24 jam pertama, kemudian dosis dikurangi menjadi 500 mg sehari pada hari kedua, 400 mg pada hari ketiga, selanjutnya 100 mg sehari sampai sembuh.Pemberian secara suntikan adalah 600 mg dosis tunggal. Pemberian secara ini biasanya untuk penderita dioperasi.
3) Kortikosteroid
a) Indikasi : penderita dengan arthritis gout yang recurrent, bila tidak ada perbaikan dengan obat-obat lain, dan pada penderita intoleran terhadap obat lain.
b) Dosis : 0,5 mg pada pemberian intramuscular. Pada kasus resisten, dosis dinaikkan antara 0,75 – 1,0 mg dan kemudian diturunkkan secara bertahap samapi 0,1 mg. Efek obat jelas tampak dalam 3 hari pengobatan.
c. Golongan urikosurik; untuk menurunkan kadar asam urat
1) Allopurinol
a) Penggunaan jangka panjang dapat mengurangi frekuensi serangan, menghambat pembentukan tofi, memobilisasi asam urat dan mengurangi besarnya tofi. Dapat juga digunakan untuk pengobatan pirai sekunder akibat polisitemia vera, metaplasia myeloid, leukemia, limfoma, psoriasis, hiperurisemia akibat obat dan radiasi.
b) Mekanisme kerja : menghambat xantin oksidase agar hipoxantin tidak dikonversi menjadi xantin dan selanjutnya menjadi asam urat. Mengalami biotransformasi oleh enzim xantin oksidase menjadi aloxantin yang mempunyai masa paruh yang lebih panjang.
c) Efek allopurinol dilawan oleh salisilat, berkurang pada insufficient ginjal, dan tidak menyebabkan batu ginjal.
d) Dosis :
Ø pirai ringan : 200 – 400 mg sehari
Ø pirai berat : 400 – 600 mg sehari
Ø Pasien dengan gangguan fungsi ginjal : 100 – 200 mg sehari
Ø Anak (6 – 10 tahun) : 300 mg sehari
2) Probenesid
a) Indikasi : penyakit gout stadium menahun, hiperurisemia sekunder
b) Mekanisme kerja : mencegah dan mengurangi kerusakan sendi serta pembentukan tofi pada penyakit gout, tidak efektif untuk mengatasi serangan akut. Probenasid tidak efektif bila laju filtrasi glomerulus.
c) Dosis : 2 x 250 mg/hari selama seminggu diikuti dengan 2 x 500 mg/hari.
d) Kontra indikasi : adanya riwayat batu ginjal, penderita dengan jumlah urin yang berkurang, hipersensitivitas terhadap probenesid.
e) Efek samping : gangguan saluran cerna yang lebih ringan, nyeri kepala, reaksi alergi.
3) Sulfipirazon
a) Mekanisme kerja : mencegah dan mengurangi kelainan sendi dan tofi pada penyakit pirai kronik, berdasarkan hambatan reabsorpsi tubular asam urat. Kurang efektif untuk menurunkan asam urat dan tidak efektif untuk mengatasi serangan pirai akut, meningkatkan frekuensi serangan pada fase akut.
b) Dosis : 2 x 100 – 200 mg sehari, ditingkatkan sampai 400 – 800 mg kemudian dikurangi sampai dosis efektif minimal
c) Kontra indikasi : pasien dengan riwayat ulkus peptic
d) Efek samping : gangguan cerna yang berat, anemia, leukopenia, agranulositosis (Emir Afif, 2010 )
3.2 Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan penunjang yang digunakan pada kasus gout antara lain:
a. Pemeriksaan Radiologi
1) Foto Konvensional (X-Ray)
a) ditemukan pembengkakan jaringan lunak dengan kalsifikasi (tophus) berbentuk seperti topi terutama di sekitar sendi ibu jari kaki.
b) tampak pembengkakan sendi yang asimetris dan kista arthritis erosif.
c) peradangan dan efusi sendi.
b. Pemeriksaan laboratorium
1) Asam Urat (Serum)
a) dijalankan untuk memantau asam urat serum selama pengobatan gout.
b) 3-5 ml darah vena dikumpulkan dalam tabung tabung berpenutup merah. Diusahakan supaya tidak terjadi hemolisis.
c) elakkan dari memakan makanan tinggi purin seperti jeroan (hati, ginjal, otak, jantung), remis, sarden selama 34 jam sebelum uji dilakukan.
d) nilai normal : Pria Dewasa : 3,5 – 8,0 mg/dL, Perempuan Dewasa : 2,8 – 6,8 mg/dL
e) peningkatan kadar asam urat serum sering terjadi pada kasus gout, alkoholisme, leukimia, limfoma, diabetes mellitus (berat), gagal jantung kongestif, stress, gagal ginjal, pengaruh obat : asam askorbat, diuretic, tiazid, levodopa, furosemid, fenotiazin, 6-merkaptopurin, teofilin, salisilat.
2) Asam Urat (Urine 24 jam)
a) Untuk mendeteksi dan/atau mengonformasi diagnosis gout atau penyakit ginjal.
b) sampel urine 24 jam ditampung dalam wadah besar, ditambahkan pengawet dan didinginkan.
c) pengambilan diet makanan yang mengandung purin ditangguhkan selama penampungan.
d) tidak terdapat pembatasan minuman.
e) nilai normal :250 – 750 mg/24 jam
f) Peningkatan terjadi pada kasus gout, diet tinggi purin, leukemia, sindrom Fanconi, terapi sinar–X, penyakit demam, hepattis virus, pengaruh obat: kortikosteroid, agens sitotoksik (pengobatan kanker), probenesid (Benemid), salisilat (dosis tinggi).
g) Kadar pH urine diperiksa jika terdapet hiperuremia. Batu urat terjadi pada pH urine rendah (asam).
c. Pemeriksaan cairan sendi
1) Tes makroskopik
a) Warna dan kejernihan
Ø Normal : tidak berwarna dan jernih
Ø Seperti susu : gout
Ø Kuning keruh : inflamasi spesifik dan nonspesifik karena leukositosis
Ø Kuning jernih : arthritis reumatoid ringan, osteo arthritis
b) Bekuan
Ø Normal : tidak ada bekuan
Ø Jika terdapat bekuan menunjukkan adanya peradangan. Makin besar bekuan makin berat peradangan
c) Viskositas
Ø Normal : viskositas tinggi (panjangnya tanpa pututs 4-6 cm)
Ø Menurun (kurang dari 4 cm : inflamatorik akut dan septik)
Ø Bervariasi : hemoragik
d) Tes mucin
Ø Normal : terlihat stu bekuan kenyal dalam cairan jernih
Ø Mucin sedang : bekuan kurang kuat dan tidak ada batas tegas : rheumatoid arthritis
Ø Mucin jelek : bekuan berkeping-keping : infeksi
2) Tes mikroskopik
a) Jumlah leukosit
Ø Jumlah normal leukosit : kurang 200/mm3
Ø 200 – 500/mm3 → penyakit non inflamatorik
Ø 2000 – 100 000/mm3 → penyakit inflamatorik akut. Contoh : arthritis gout, arthritis reumatoid
Ø 20 000 – 200 000/mm3 → kelompok septik (infeksi). Contoh : arthritis TB, arthritis gonore
Ø 200 – 1000/mm3 → kelompok hemoragik
b) Hitung jenis sel
Ø Jumlah normal neutrofil : kurang dari 25%
Ø Jumlah neutrofil pada akut inflamatorik: Arthritis gout akut : rata-rata 83%
Ø Faktor rematoid : rata-rata 46%, Artrhritis rematoid : rata-rata 65%
c) Kristal-kristal
Ø Normal : tidak ditemukan kristal dalam cairan sendi
Ø Arthritis gout : ditemukan kristal monosodium urat (MSU) berbentuk jarum memiliki sifat birefringen ketika disinari cahaya polarisasi
Ø Arthritis rematoid : ditemukan kristal kolestrol
d. Tes kimia
1) Tes glukosa
Ø Normal : perbedaan antara glukosa serum dan cairan sendi adalah kurang dari 10mg%
Ø Pada kelompok inflammatorik : Arthritis gout : perbedaan rata-rata 12 mg%
Ø Faktor rematoid : perbedaan 6 mg%
2) Laktat Dehidrogenase
Ø Normal : 100 – 190 IU/l, 70 – 250 U/l
Ø Meningkat : rematoid arthritis, gout, arthritis karena infeksi
3) Tes mikrobiologi
Ø untuk kelainan sendi yang disebabkan infeksi
Ø hasil negatif pada kultur bakteri cairan sendi ( Joyce LeFever, 2008 )
3.3 Penatalaksanaan Keperawatan Penunjang Medis
a. Memberikan kompres hangat pada pasien yang mengalami serangan arthritis gout
b. Melaksanakan dan mengajarkan teknik managemen nyeri non farmakologis dengan nafas dalam dan distraksi ( pengalihan )
c. Menjelaskan dan memantau pembatasan gerak dan aktivitas fisik berat bagi pasien agar radang sendi tidak bertambah kronik.
3.4 Manajemen Diet
Tujuan utama diet adalah menurunkan kadar asam urat darah dan juga agar berat badan tidak melebihi ukuran ideal yang disarankan. Diet yang dianjurkan bagi penderita arthritis gout antara lain:
a. Menghindari makanan berlemak kaya purin tinggi
1) Purin Tinggi (100 – 1000 mg purin dalam 100 gr bahan ) sebaiknya dihindari : otak, hati, ginjal, jeroan, ekstrak daging, bebek, ikan sardin, makarel dan kerang.
2) Purin sedang (900 – 100 mg purin dalam 100 gr bahan ) sebaiknya dibatasi : daging, ikan, unggas, ayam, udang, kepiting atau rajungan, tahu, tempe, kacang kering, bayam, asparagus, daun singkong, kangkung, daun dan biji mlinjo
3) Purin rendah ( dibawah 50 mg purin dalam 100 gr bahan ) sebaiknya dibatasi: gula, telur, dan susu.
b. Perbanyak minum air, 8 sampai 10 gelas setiap hari untuk memperlancar pembuangan asam urat melalui ginjal. Hindari minuman yang mengandung alkohol, kopi, bir karena banyak mengandung senyawa purin yang dapat memperberat fungsi ginjal.
c. Perbanyak konsumsi makanan yang mengandung asam lemak omega-3 dan omega-6, misalnya flax seed oil dan minyak ikan ( fish oil ), yang dapat mengurangi radang dan mencegah serangan berikutnya.
d. Konsumsi buah-buahan dan sayuran yang berfungsi menurunkan tingkat keasaman tubuh, sehingga baik untuk mencegah peningkatan kadar asam urat. Buah yang mengandung vitamin C dan bioflavonoid dapat mencegah radang, seperti: jeruk, stroberi, tomat, paprika hijau dan sayuran berdaun hijau, terutama buah ceri yang merupakan nutrisi penyembuh dan pengurang kadar asam urat. Selain itu konsumsi sayuran seperti: wortel, bayam, piterseli, seledri juga dapat menurunkan kadar asam urat. ( VitaHealth, 2007 )
Pengobatan untuk reumatik dan encok
3
11
2008
Rheumatik adalah penyakit yang termasuk golongan penyakit tulang dan sendi yang berciri rasa nyeri, bengkak, kekakuan, dan terganggunya fungsi alat-alat penggerak tubuh, yaitu sendi dan tulang. Selain rheumatik, ada juga penyakit tulang dan sendi lain yang hampir mirip gejalanya dan sering kali saling tertukar pengertiannya. Untuk itu, di awal makalah ini, akan diperjelas kembali perbedaan beberapa gangguan tulang dan sendi tersebut. Hal ini penting karena perbedaan tersebut akan mempengaruhi penatalaksanaannya.
Penyakit sendi dikenal dengan istilah arthritis, dari kata “arth” = sendi, dan “itis”= radang/inflamasi. Arthritis Society (2002) mengelompokkan penyakit radang sendi ini ke dalam berbagai jenis penyakit berdasarkan penyebab dan patogenesisnya, namun yang paling sering dijumpai di masyarakat dan akan diliput dalam makalah ini adalah rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dan gout.
Diantara tulang dengan tulang, terdapat ruang sendi yang memungkinkan tulang untuk bergerak. Daerah sendi antara dua tulang dilindungi oleh semacam kapsula yang fleksibel, yang cukup kuat untuk melindungi tulang dari kemungkinan dislokasi (bergeser). Di bagian dalam kapsula ini, yang disebut sinovium, diproduksi suatu cairan sinovial yang akan melubrikasi sendi. Pada kebanyakan bentuk radang sendi, sinovium ini mengalami inflamasi dan menebal, memproduksi ekstra cairan yang mengandung banyak sel-sel inflamasi. Sel-sel inflamasi ini kemudian dapat merusak tulang rawan dan tulang yang ada di sekitarnya.
Penyakit radang sendi sangat bermacam-macam, tetapi yang banyak dijumpai pada masyarakat adalah rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dan gout.
Rheumatoid arthritis atau kita kenal sebagai penyakit rematik adalah gangguan sendi yang dicirikan adanya inflamasi dan merupakan penyakit auto imunitas. Sistem imun di dalam tubuhnya gagal membedakan jaringan sendiri dengan benda asing, sehingga sistem imunnya akan menyerang jaringan tubuh sendiri, khususnya jaringan sinovial dan jaringan ikat. Penyakit ini bersifat menahun dan sistemik, dan seringkali progresif. Sebagian besar pasien dengan rematik artritis ini tubuhnya membentuk antibodi yang disebut rheumatoid factor (faktor rematoid). Faktor ini menentukan agresivitas/keganasan dari penyakit.
Osteoarthritis adalah gangguan sendi juga, tetapi bukan gangguan imun. Penyebabnya bisa bermacam-macam, seringkali bersifat idiopatik, dengan ciri terjadinya degenerasi tulang rawan. Pada penyakit ini terjadi ketidak-seimbangan antara pembentukan dan perusakan/degradasi tulang rawan. Penyakit ini tidak bersifat sistemik seperti rematik artritis, umumnya terjadi pada usia di atas 45 tahun. Sifat inflamasinya umumnya lebih ringan dan lebih terlokalisir dibandingkan rematik artritis. Sendi yang terpengaruhi umumnya yang sering harus mengampu beban berat.
Gout atau encok adalah gangguan sendi yang disebabkan oleh gangguan pada metabolisme purin sehingga berakibat terganggunya keseimbangan antara sintesis zat asam urat dengan ekskresinya melalui ginjal. Pada pasien gout seringkali dijumpai bahwa kadar asam urat dalam darahnya terlampau tinggi (hiperurikemia). Gangguan yang dapat terjadi dengan kadar asam urat yang tinggi antara lain adalah nyeri sendi (artritis), batu ginjal akibat terbentuknya batu asam urat (nefrolitiasis), dan gangguan ginjal (nefropati).
Tatalaksana terapi
Karena berbeda secara patofisiologinya, maka terapi terhadap ketiga gangguan sendi ini juga berbeda. Untuk itu akan dipaparkan tatalaksana untuk masing-masing penyakit sendi.
1. Terapi untuk artritis rematik (AR)
Tujuan terapi rematik utamanya adalah untuk meningkatkan atau memelihara status fungsionalnya sehingga meningkat kualitas hidup pasien. Pengatasan rematik harus merupakan pendekatan multifaset yang melibatkan terapi farmakologi dan nonfarmakologi. Terapi nonfarmakologi antara lain meliputi: istirahat, fisioterapi, penggunaan alat bantu, penurunan berat badan, atau pembedahan. Sedangkan terapi farmakologi adalah terapi menggunakan obat-obatan.
Obat-obat untuk rematik dikenal dengan istilah DMARD (disease-modifying antirheumatic drug). Obat-obat yang biasa digunakan dalam penanganan rematik adalah:
1. NSAIDs (Non-steroid antiinflammatory drugs)
2. Metotreksat
3. Leflunomid
4. Hidroksiklorokuin
5. Sulfazalazin
6. Kortikosteroid
7. Agen biologis : Etanercept, Infliximab, Adalimumab, Anakinra
8. Lain-lain : Garam emas, azathioprine, d-penisilamin, siklosporin, siklofosfamid, dan minoksilin
Pada bagian ini akan dipaparkan keterangan singkat tentang masing-masing obat.
1. NSAIDs
Obat-obat NSAID umumnya dipakai sebagai terapi komplementer, jarang digunakan secara tunggal/monoterapi pada AR. Obat ini bekerja menghambat sintesis prostaglandin yang merupakan mediator inflamasi dengan menekan kerja enzim siklooksigenase. Penghambatan ini tidak selektif sehingga obat-obat ini menyebabkan efek samping gastrointestinal. Golongan penghambat selektif siklooksigenase-2 (COX-2) memiliki efikasi yang sebanding dengan NSAIDs tetapi efek samping gastrointerstinalnya lebih ringan.
2. Methotrexate (MTX)
Saat ini MTX dianggap sebagai obat DMARD pilihan oleh banyak rematologis untuk mengatasi AR. MTX bekerja dengan menghambat produksi sitokin (cytokines), menghambat biosintesis purin, dan mungkin menstimulasi pelepasan adenosin, yang semuanya dapat mengarah pada kerja antiinflamasi. Obat ini memiliki onset yang agak cepat, hasil dapat dilihat kurang lebih 2-3 minggu setelah dimulainya terapi. Obat bisa diberikan secara i.m., s.c., atau p.o.
Efek samping atau gejala toksisitas MTX adalah gangguan gastrointestinal, hematologi, pulmonar, dan hepatik. Test terhadap fungsi liver perlu dilakukan untuk memantau penggunaan obat ini. MTX dikontraindikasikan untuk kehamilan dan menyusui, gangguan liver kronis, defisiensi imun, leukopenia, trombositopenia, gangguan darah, serta pasien yang kreatin klirens-nya kurang dari 40
mL/min. Karena MTX adalah antagonis asam folat, maka ia juga dapat menyebabkan defisiensi asam folat. Untuk itu suplementasi asam folat diperlukan untuk mengurangi efek samping ini (Schuna, 2005).
3. Leflunomid
Leflunomid memiliki efikasi yang mirip dengan MTX dalam mengatasi AR. Ia bekerja dengan menghambat sintesis pirimidin, sehingga dapat menurunkan proliferasi limfosit dan menghambat inflamasi. Obat ini diberikan dengan loading dose 100 mg sehari untuk 3 hari, dan dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 20 mg sehari. Seperti MTX, obat ini cukup toksis terhadap hati, sehingga dikontraindikasikan bagi pasien yang punya riwayat gangguan liver. Selain itu obat ini juga teratogenik, sehingga tidak boleh digunakan pada wanita hamil atau yang merencanakan hamil. Bedanya, leflunomid jarang menyebabkan gangguan darah, sehingga memungkinakan untuk dipakai pada pasien dengan gangguan darah.
4. Hidroksklorokuin
Obat ini dikenal sebagai antimalaria, tetapi juga dapat menekan sistem imun, sehingga seringkali digunakan pada penyakit gangguan imun. Kelebihan obat ini adalah ia tidak toksis terhadap hepar atau renal. Toksisitasnya bersifat jangka pendek, meliputi: gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah atau diare.
5. Sulfasalazin
Sulfasalazin adalah suatu prodrug yang akan diuraikan oleh bakteria di usus menjadi sulfapiridin dan asam 5-aminosalisilat. Sulfapiridin inilah yang diduga bertanggung-jawab terhadap aktivitas antirematiknya. Penggunaan sulfasalazin agak terbatas karena menyebabkan beberapa efek samping antara lain efek gastrointestinal (mual, muntah, diare dan anoreksia), alergi, leukopenia, alopesia, dan peningkatan enzim hepatik. Obat ini berinteraksi dengan antibiotik yang membunuh bakteri kolon, dapat mengikat suplemen besi, dan meningkatkan efek warfarin.
6. Kortikosteroid
Kortikosteroid digunakan pada AR karena efek antiinflamasi dan imunosupresifnya. Obat ini bisa menghambat sintesis prostagandin dan leukotrien, menghambat reaksi radikal superoksida netrofil dan monosit, mencegah migrasi sel monosit, limfosit, dan monosit, sehingga dapat mencegah respon imun.
7. Agen biologis
Golongan obat ini termasuk obat baru hasil rekayasa genetik, seperti : etenercept, infliximab, adalimumab, dan anakinra. Obat ini mungkin efektif, jika obat lain tidak berhasil. Harganya masih mahal, dan belum ada di Indonesia. Tidak ada resiko toksisitas yang membutuhkan pemantauan lab, tetapi ada laporan bahwa obat ini sedikit meningkatkan resiko infeksi. Untuk itu, pasien yang sedang infeksi sebaiknya tidak menggunakan obat ini. Berikut ini adalah keterangan singkat tentang agen biologis tersebut.
Etanercept adalah suatu protein yang terdiri dari reseptor TNF (tumor necrosis factor) yang berikatan dengan antibodi IgG. Obat ini akan mengikat TNF sehingga secara biologis menjadi inaktif dan tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Seperti diketahui, TNF adalah salah satu sitokin yang terlibat dalam patogenesis AR.
Infliximab merupakan anti TNF, ia juga akan mengikat TNF sehingga tidak bis aberikatan dengan reseptornya.
Adalimumab juga merupakan antibodi terhadap TNF.
Anakinra adalah antagonsi reseptor inteleukin-1 (IL-1). Diketahui bahwa IL-1 sangat terlibat dalam patogenesis AR. Obat ini akan mengikat reseptor IL-1, sehingga mencegah IL-1 untuk berikatan dengan reseptornya.
2. Terapi untuk osteoartritis (OA)
Tujuan utama terapi OA adalah untuk mengurangi nyeri dan gejala lain, dan meningkatkan fungsinya. Terapi non-farmakologi merupakan dasar dari penatalaksanaan OA, meliputi: edukasi pada pasien, memperkuat dan memperbanyak latihan gerakan, penggunaan alat bantu (jika perlu), perlindungan terhadap sendi, dan penurunan berat badan jika dibutuhkan. Sedangkan terapi farmakologi biasanya diawali dengan pemberian analgesik non-opiat seperti parasetamol, diikuti dengan penggunaan NSAID, atau inhibitor selektif COX-2, dan analgesik topikal. Jika terapi ini kurang efektif, penggunaan injeksi glukokortikoid atau asam hialuronat secara intra-artikular serta penggunaan analgesik opiat dapat membantu.
a. Terapi non-farmakologi
Terapi nonfarmakologi untuk OA meliputi : diet, terapi fisik, dan pembedahan. Pengaturan diet diperlukan untuk mencegah kelebihan berat badan yang seringkali menjadi penyebab memburuknya nyeri sendi, terutama pada sendi-sendi yang harus menopang berat badan. Terapi fisik bisa dilakukan dengan berendam pada air hangat, atau alat penghangat lain, untuk mengurangi nyeri dan kaku pada sendi. Selain itu juga dapat dilakukan program-program latihan untuk melatih fungsi persendian. Jika terapi konservatif tidak efektif, maka pembedahan bisa direkomendasikan.
b. Terapi farmakologi
Target utama terapi OA adalah menghilangkan atau mengurangi nyeri. Terapi ini umumnya dilakukan jangka panjang, untuk itu perlu dipilih terapi yang cukup aman digunakan dalam jangka panjang. Beberapa obat yang digunakan dalam OA umumnya merupakan golongan analgetik dan NSAID. Selain itu, ada terapi topikal yang dapat digunakan bersama-sama dengan terapi oral dengan analgesik atau NSAID, misalnya krim capsaicin.
Saat ini sedang dikembangkan pula penggunaan glukosamin dan kondroitin sebagai terapi, karena dapat menstimulasi sintesis proteoglikan dan juga dilaporkan memiliki efek analgesik dibandingkan dengan plasebo. Sebagai pilihan pada terapi yang tidak responsif, dapat diberikan injeksi hialuronat secara intra artikular. Obat ini bisa menggantikan cairan sinovial dan mengurangi gejala.
3. Terapi untuk gout
Tujuan terapi gout adalah untuk menghentikan serangan akut gout, mencegah kekambuhan serangan gout, dan mencegah komplikasi yang terkait dengan meningkatnya deposisi kristal urat secara kronis pada jaringan. Selain itu, pasien harus diingatkan untuk mengurangi makanan-makanan yang mengandung purin (daging, jeroan, dll).
Untuk mengatasi serangan artritis gout, obat-obat NSAID dan colchicine umumnya cukup efektif. Masalah utama penggunaan obat-obat tersebut adalah gangguan gastrointestinal. Colchicine merupakan pilihan jika terjadi kontraindikasi terhadap NSAID. Untuk menghindari gangguan GIT, dapat dilakukan pemberian secara intravena. Colchicine dikontraindikasikan bagi pasien leukopenia, gangguan ginjal yang berat (klirens kreatinin < 10 mL/min), atau ada kombinasi gangguan ginjal dan liver.
Untuk pasien yang tidak dapat mentoleransi colchicine dan NSAID, dapat digunakan inhibitor selektif COX-2 seperti celecoxib, rofecoxib atau valdecoxib. Sebagai pilhan akhir jika pasien resisten terhadap pengobatan di atas, dapat digunakan kortikosteroid.
Untuk mencegah dan mengatasi nefrolitiasis (batu ginjal), dapat dilakukan dengan hidrasi (minum banyak-banyak) agar volume urin mencapai 2-3 L/hari, pembasaan urin, dan menghindari makanan mengandung purin. Pembasaan urin dapat dilakukan dengan pemberian larutan sodium bikarbonat. Jika pasien kontraindikasi terhadap garam Na, dapat diganti dengan Kalium sitrat. Selain itu, dapat diberikan acetazolamid, suatu inhibitor karbonat anhidrase, untuk alkalinisasi urin.
Terapi utama untuk litiasis asam urat yang kambuhan adalah alopurinol. Obat ini efektif mengurangi kadar asam urat pada serum maupun urin, sehingga mencegah pembentukan kristal asam urat. Setelah serangan akut yang pertama atau pengeluaran batu ginjal yang pertama, perlu dilakukan terapi profilaksis untuk pencegahan kekambuhan. Terapi profilaksis dapat dilakukan dengan pemberian colchicin atau allopurinol.
Demikianlah terapi untuk gangguan artritis yang umum dijumpai, yaitu rematik artritis, osteoartritis, dan gout. Semoga bermanfaat.
(tulisan ini pernah penulis sampaikan pada Seminar nasional yang diselenggarakan oleh ISFI Kab Banyumas di Purwokerto, September 2005)
Rheumatoid Arthritis
Rheumatoid Arthritis adalah penyakit arthritis yang sering dijumpai di masyarakat. Merupakan penyakit autoimun kronik yang ditandai dengan kerusakan sendi sehingga menimbulkan kecacatan, bahkan kematian. Penyakit ini banyak dampak yang ditimbulkan selain nyeri dan kecacatan, yang berdampak pada kualitas hidup penderita. Selain itu membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk mengendalikan penyakitnya.
Rheumatoid Arthritis merupakan penyakit autoimun yang merusak sinovium (bagian dari sendi) yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pelumas sendi supaya sendi mudah bergerak. Umumnya menyerang sendi-sendi kecil, jari-jari tangan, kaki pada kedua sisi dan simetris.
Gejala klinis biasanya ditandai dengan bengkak pada jari-jari tangan, pergelangan tangan, kedua siku, bahu, lutut, pergelangan kaki. Selain bengkak juga nyeri terutama pagi hari. Selain gejala nyeri sendi biasanya juga disertai demam, nafsu makan menurun, berat badan menurun dan gejala anemia. Penyakit ini bila tidak ditangani sedini mungkin akan menimbulkan kerusakan tulang sekitar sendi sehingga menimbulkan kecacatan.
Manifestasi Rheumatoid Arthritis diluar sendi yaitu konjungtivitis, perikarditis, felty’s syndrome. Komplikasi yang sangat membahayakan adalah adanya radang pada tulang servikal C1 yang bisa subluksasi yang bisa menyebabkan kondisi yang fatal.
Untuk dapat mengobati penyakit autoimun, maka kita harus tahu secara detail proses terjadinya penyakit (patogenesis) autoimun. Pada kondisi normal, respon imun yang bertanggung jawab pada terjadinya inflamasi akan diatur ketat oleh sistem imun baik melibatkan sistem imun alamiah maupun yang didapat melalui mediator inflamasi. Pada penyakit inflamasi kronik terjadi ketidakseimbangan antara mediator inflamasi dan anti inflamasi yang akibatnya menimbulkan kerusakan sendi atau jaringan. Pada rheumatoid arthritis akibat inflamasi yang berkepanjangan menimbulkan kerusakan cartilage dan tulang daerah sekitarnya.
Pemeriksaan laboratorium
Pemeriksaan laboratorium tidak ada yang spesifik, biasanya hanya ditandai dengan anemia dan laju endap darah serta C-Reactive Protein (CRP) yang meningkat. Rematoid Faktor (RF) bukan spesifik untuk penyakit Rheumatoid Arthritis, tetapi merupakan marker untuk memperkirakan berat tidaknya penyakit Rheumatoid Arthritis.
Dalam usaha untuk menghentikan suatu proses inflamasi, maka harus dimengerti peran mediator dalam patogenesis rheumatoid arthritis sehingga bisa dilakukan terapi dengan tepat sasaran, karena terapi DMARD dianggap kurang efektif dan banyak efek samping.
Rheumatoid Arthritis harus diterapi sedini mungkin untuk mencegah kecacatan, berikut adalah terapi yang diberikan pada penyakit rheumatoid arthritis berdasarkan standar internasional:
1. NSAID (non steroid anti inflamasi) dimana fungsi kerja obat ini adalah menghambat sintesa prostaglandin yang menimbulkan nyeri. Obat ini menghambat COX1 dan COX2, dimana COX1 sangat penting untuk fungsi pertahanan mukosa lambung, sehingga obat ini mempunyai efek samping pada lambung. Kerusakan pada ginjal disebabkan adanya nekrosis unit fungsional dari ginjal, dengan pemakaian yang hati-hati dan pertimbangan yang cukup bijaksana, maka pemakaian NSAID ini tidak perlu dikhawatirkan. Saat ini sudah ada obat yang selektif hanya menghambat COX2 sehingga aman digunakan jangka panjang. Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa anti nyeri ini sama dengan “anti rematik”.
2. DMARD (disease modyfing anti rheumatic drug): obat ini bertujuan untuk mengendalikan sel kekebalan tubuh yang merusak synovial, namun obat ini tidak jelas bagaimana mekanisme kerjanya. Untuk itu pada akhir-akhir ini berkembang obat rematik yang disebut biologic agent yang terdiri dari antibody monoclonal dengan tujuan mentarget molekul tertentu yang berperanan dalam mekanisme penyakit, misalnya TNF alfa, IL-1, IL-6, sel B. beberapa obat DMARD yang digunakan pada RA yaitu metrotrexate, leflunomide, sulfasalazine, azatioprine, siklosporin, kloroquin. Obat ini bisa digunakan tunggal atau kombinasi, bila dosis yang digunakan dengan tepat, maka efek samping dapat diminimalisasi. Bila tidak respon dengan DMARD, maka terapi saat ini adalah kombinasi antara DMARD dan biologic agent. Kombinasi DMARD tidak boleh lebih dari tiga macam obat (cocktail), ini sangat berbahaya efek sampingnya sangat tinggi.
3. Biologic agent: macamnya adalah anti TNFalfa (etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab), anti CD20, anti IL-6, anti IL-1 (anakinra).
Terapi DMARD bisa dalam bentuk monoterapi atau single DMARD dan bisa dikombinasi dengan DMARD yang lain, artinya terapi kombinasi. Bila tidak respon, maka diperlukan terapi Biologic
Agent. Bila sejak awal RA sangat berat, maka sebaiknya terapi dilakukan dengan DMARD + Biologic Agent.
Tanda-tanda RA terkontrol
Secara klinis tidak ada nyeri sendi, bengkak sendi maupun kaku sendi, dan tahun ke tahun tidak ada kecacatan yang bertambah. Secara laboratorium LED, CRP dalam batas normal. Gambaran radiologi tidak ada destruksi sendi baru.
Artritis Gout
a) Defenisi
Adalah suatu peradangan sendi sebagai manifestasi dari akumulasi andapan kristal monosodium urat, yang terkumpul di dalam sendi sebagai akibat dari tingginya kadar asam urat dalam urat (hiperurisemia). Meskipun begitu, tidak semua orang yang memiliki hiperurisemia adakah penderita artrhitis gout.
b) Insiden
Artritis gout umumnya dijumpai pada laki-laki dari semua usia, paling sering pada dekade kelima atau keenam, namun pada perempuan umumnya dijumpai pada usia lanjut (lansia) atau sesudah menopause. Faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya artritis gout antara lain: penyakit komorbiditas seperti kegemukan, tekanan darah tinggi (hipertensi), dan diet tinggi purin serta konsumsi alkohol. Di samping itu obat-obatan tertentu dapat menyebabkan penurunan ekskresi asam urat. (contohnya: obat diuretik yang digunakan pada penderita sakit jantung atau pirazinamid yang digunakan pada penderita TBC).
c) Etiologi
Dalam keadaan normal, beberapa asam urat (yang merupakan hasil pemecahan sel) ditemukan dalam darah karena tubuh terus menerus memecahkan sel dan membentuk sel yang baru dan karena makanan yang dikonsumsi mengandung cikal bakal asam urat. Kadar asam urat menjadi sangat tinggi jika ginjal tidak dapat membuangnya melalui air kemih. Tubuh juga bisa menghasilkan sejumlah besar asam urat karena adanya kelainan enzim yang sifatnya diturunkan atau karena suatu penyakit (misalnya kanker darah), dimana sel-sel berlipat ganda dan dihancurkan dalam waktu yang singkat. Beberapa jenis penyakit ginjal dan obat-obatan tertentu mempengaruhi kemampuan ginjal untuk membuang asam urat.
d) Faktor Resiko
Selama ini gout hanya dikaitkan dengan masalah diet dan konsumsi jenis obat tertentu yang dapat menyebabkan hiperurisemia, tetapi ternyata terdapat berbagai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko gout. Penggunaan diuretik thiazide, cyclosporine, dan asam asetilsalisilat dosis rendah (<1 g per hari) dapat menyebabkan hiperurisemia, sedangkan asam asetilsalisilat dosis tinggi (≥ 3 g per hari) bersifat urikosurik. Faktor-faktor yang berkaitan dengan hiperurisemia dan asam urat antara lain adalah: resistensi insulin, sindrom metabolik, obesitas,insufisiensi ginjal, hipertensi, gagal jantung kongestif, transplantasi organ.
Risiko kejadian gout meningkat pada orang yang banyak mengonsumsi makanan dengan kandungan purin tinggi (terutama daging dan makanan laut), etanol (terutama alkohol), minuman ringan, dan
fruktosa. Risiko kejadian gout menurun pada mereka yang banyak mengonsumsi kopi, produk susu, dan vitamin C (yang menurunkan kadar asam urat). Faktor pemicu untuk flare (eksaserbasi akut) berulang meliputi penggunaan diuretik, konsumsi alkohol, menjalani rawat inap, dan menjalani tindakan operasi. Terapi untuk menurunkan kadar asam urat (misal: allopurinol) mungkin dapat memicu timbulnya serangan gout akut, mungkin disebabkan oleh perpindahan asam urat yang disimpan dalam jaringan tubuh (terjadi fluktuasi kadar asam urat).
e) Patofisiologi
Pada penyakit gout-arthritis, terdapat gangguan kesetimbangan metabolisme (pembentukan dan ekskresi) dari asam urat tersebut, meliputi:
1. Penurunan ekskresi asam urat secara idiopatik
2. Penurunan eksreksi asam urat sekunder, misalnya karena gagal ginjal
3. Peningkatan produksi asam urat, misalnya disebabkan oleh tumor (yang meningkatkan cellular turnover) atau peningkatan sintesis purin (karena defek enzim-enzim atau mekanisme umpan balik inhibisi yang berperan).
4. Peningkatan asupan makanan yang mengandung purin
• Peningkatan produksi atau hambatan ekskresi akan meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh.
• Asam urat ini merupakan suatu zat yang kelarutannya sangat rendah sehingga cenderung membentuk kristal.
• Penimbunan asam urat paling banyak terdapat di sendi dalam bentuk kristal mononatrium urat. Mekanismenya hingga saat ini masih belum diketahui.
Adanya kristal mononatrium urat ini akan menyebabkan inflamasi melalui beberapa cara:
1. Kristal bersifat mengaktifkan sistem komplemen terutama C3a dan C5a.
• Komplemen ini bersifat kemotaktik dan akan merekrut neutrofil ke jaringan (sendi dan membran sinovium).
• Fagositosis terhadap kristal memicu pengeluaran radikal bebas toksik dan leukotrien, terutama leukotrien B.
• Kematian neutrofil menyebabkan keluarnya enzim lisosom yang destruktif.
2. Makrofag yang juga terekrut pada pengendapan kristal urat dalam sendi akan melakukan aktivitas fagositosis, dan juga mengeluarkan berbagai mediator proinflamasi seperti IL-1, IL-6, IL-8, dan TNF.
• Mediator-mediator ini akan memperkuat respons peradangan, di samping itu mengaktifkan sel sinovium dan sel tulang rawan untuk menghasilkan protease.
• Protease ini akan menyebabkan cedera jaringan.
Penimbunan kristal urat dan serangan yang berulang akan menyebabkan terbentuknya endapan seperti kapur putih yang disebut tofi/tofus (tophus) di tulang rawan dan kapsul sendi. Di tempat tersebut
endapan akan memicu reaksi peradangan granulomatosa, yang ditandai dengan massa urat amorf (kristal) dikelilingi oleh makrofag, limfosit, fibroblas, dan sel raksasa benda asing. Peradangan kronis yang persisten dapat menyebabkan fibrosis sinovium, erosi tulang rawan, dan dapat diikuti oleh fusi sendi (ankilosis). Tofus dapat terbentuk di tempat lain (misalnya tendon, bursa, jaringan lunak). Pengendapan kristal asam urat dalam tubulus ginjal dapat mengakibatkan penyumbatan dan nefropati gout.
f) Manifestasi Klinik
Manifestasi Klinis untuk artritis Gout dibagi berdasarkan 4 stadium :
1. Hiperurisemia Asimptomatik
Hiperurisemia asimptomatik adalah keadaan hiperurisemia (kadar asam urat serum tinggi) tanpa adanya manifestasi klinik gout. Fase ini akan berakhir ketika muncul serangan akut arthritis gout, atau urolitiasis, dan biasanya setelah 20 tahun keadaan hiperurisemia asimptomatik. Terdapat 10-40% subyek dengan gout mengalami sekali atau lebih serangan kolik renal, sebelum adanya serangan arthritis.
2. Artritis Gout Akut
Serangan pertama biasanya terjadi antara umur 40-60 tahun pada laki-laki, dan setelah 60 tahun pada perempuan. Onset sebelum 25 tahun merupakan bentuk tidak lazim arthritis gout, yang mungkin merupakan manifestasi adanya gangguan enzimatik spesifik, penyakit ginjal atau penggunaan siklosporin.
Pada 85-90% kasus, serangan berupa arthritis monoartikuler dengan predileksi MTP-1 yang biasa disebut podagra. Gejala yang muncul sangat khas, yaitu radang sendi yang sangat akut dan timbul sangat cepat dalam waktu singkat. Pasien tidur tanpa ada gejala apapun, kemudian bangun tidur terasa sakit yang hebat dan tidak dapat berjalan.
Keluhan monoartikuler berupa nyeri, bengkak, merah dan hangat, disertai keluhan sistemik berupa demam, menggigil dan merasa lelah, disertai lekositosis dan peningkatan laju endap darah. Sedangkan gambaran radiologis hanya didapatkan pembengkakan pada jaringan lunak periartikuler. Keluhan cepat membaik setelah beberapa jam bahkan tanpa terapi sekalipun.
Pada perjalanan penyakit selanjutnya, terutama jika tanpa terapi yang adekuat, serangan dapat mengenai sendi-sendi yang lain seperti pergelangan tangan/kaki, jari tangan/kaki, lutut dan siku, atau bahkan beberapa sendi sekaligus. Serang-an menjadi lebih lama durasinya, dengan interval serangan yang lebih singkat, dan masa penyembuhan yang lama. Faktor pencetus serangan akut antara lain trauma lokal, diet tinggi purin, minum alkohol, kelelahan fisik, stress, tindakan operasi, pemakaian diuretik, pemakaian obat yang meningkatkan atau menurunkan asam urat. Diagnosis yang defini-tif/gold standard, yaitu ditemukannya kristal urat (MSU) di cairan sendi atau tofus.
3. Stadium Interkritikal
Stadium ini merupakan kelanjutan stadium gout akut, dimana secara klinik tidak muncul tanda-tanda radang akut, mes-kipun pada aspirasi cairan sendi masih ditemukan kristal urat, yang menunjukkan proses kerusakan sendi yang terus berlangsung progresif. Stadium ini bisa berlangsung bebe-rapa tahun sampai 10 tahun tanpa serangan akut. Dan tanpa tata laksana yang adekuat akan berlanjut ke stadium gout kronik.
4. Artritis Gout Kronik = Kronik Tofaseus Gout
Stadium ini ditandai dengan adanya tofi dan terdapat di poliartikuler, dengan predileksi cuping telinga, MTP-1, olekranon, tendon Achilles dan jari tangan. Tofi sendiri tidak menimbulkan nyeri, tapi mudah terjadi inflamasi di sekitarnya, dan menyebabkan destruksi yang progresif pada sendi serta menimbulkan deformitas. Selain itu tofi juga se-ring pecah dan sulit sembuh, serta terjadi infeksi sekunder. Kecepatan pembentukan deposit tofus tergantung beratnya dan lamanya hiperurisemia, dan akan diperberat dengan gangguan fungsi ginjal dan penggunaan diuretik.
Pada beberapa studi didapatkan data bahwa durasi dari serang-an akut pertama kali sampai masuk stadium gout kronik berkisar 3-42 tahun, dengan rata-rata 11,6 tahun. Pada stadium ini sering disertai batu saluran kemih sampai penyakit ginjal menahun/gagal ginjal kronik. Timbunan tofi bisa ditemukan juga pada miokardium, katub jantung, system konduksi,beberapa struktur di organ mata terutama sklera, dan laring.
Pada analisa cairan sendi atau isi tofi akan didapatkan Kristal MSU, sebagai kriteria diagnostik pasti. Gambaran radiologis didapatkan erosi pada tulang dan sendi dengan batas sklerotik dan overhanging edge.
g) Diagnosis
Untuk memudahkan penegakan diagnosis arthritis gout akut, dapat digunakan kriteria dari ACR (American College of Rheumatology) tahun 1977:
a. Ditemukannya kristal urat di cairan sendi, atau
b. Adanya tofus yang berisi kristal urat, atau
c. Terdapat 6 dari 12 kriteria klinis, laboratoris dan radiologis berikut :
1) Terdapat lebih dari satu kali serangan arthritis akut
2) Inflamasi maksimal terjadi dalam waktu satu hari
3) Arthritis monoartikuler
4) Kemerahan pada sendi
5) Bengkak dan nyeri pada MTP-1
6) Artritis unilateral yang melibatkan MTP-1
7) Artritis unilateral yang melibatkan sendi tarsal
8) Kecurigaan adanya tofus
9) Pembengkakan sendi yang asimetris (radiologis)
10) Kista subkortikal tanpa erosi (radiologis)
11) Kultur mikroorganisme negative pada cairan sendi
h) PEMERIKSAAN PENUNJANG
a. Analisis Cairan Sinovial
Ketika seorang pasien terindikasi arthritis monoarticular akut radang, aspirasi cairan synovial sendi yang terlibat sangat penting untuk menyingkirkan suatu infeksi radang sendi dan untuk mengkonfirmasi diagnosis gout lewat identifikasi kristal. Lihat gambar cairan asam urat tophaceous bawah ini.
Kristal urat yang berbentuk seperti jarum atau tusuk gigi dengan ujung runcing. Dalam polarisasi mikroskop cahaya, kristal urat berwarna kuning ketika selaras sejajar dengan sumbu kompensator merah dan biru saat sejajar di arah polarisasi (yaitu, menunjukkan birefringence negatif). Kristal urat birefringent negatif tegas menetapkan diagnosis arthritis gout.
Selama serangan akut, cairan sinovial adalah inflamasi, dengan jumlah WBC lebih besar dari 2000/μL (kelas II cairan) dan mungkin lebih besar dari 50.000 / uL, dengan dominasi neutrofil polimorfonuklear. Tingkat cairan sinovial glukosa biasanya normal, sedangkan mungkin menurun pada arthritis septik dan kadang-kadang di rheumatoid arthritis. Pengukuran protein cairan sinovial tidak memiliki nilai klinis.
b. Asam Urat Serum
Pengukuran asam urat serum adalah tes yang paling disalahgunakan dalam diagnosis gout. Kehadiran hiperurisemia dengan tidak adanya gejala tidak diagnostik gout. Selain itu, sebanyak 10% pasien dengan gejala karena asam urat yang normal mungkin memiliki kadar serum asam urat pada saat serangan mereka. Dengan demikian, diagnosis yang benar gout dapat terjawab jika cairan sendi tidak diambil. situasi yang menurunkan kadar asam urat dapat memicu serangan gout.
Sekitar 5-8% penduduk telah meningkatkan kadar asam urat serum (> 7 mg / dL), tetapi hanya 5-20% pasien dengan hyperuricemia terkena gout. Dengan demikian, tingkat asam urat tinggi serum tidak menunjukkan atau memprediksi asam urat. Seperti disebutkan di atas, asam urat didiagnosis berdasarkan penemuan kristal urat dalam cairan sinovial atau jaringan lunak. Lebih penting lagi, beberapa pasien dengan radang sendi ini menular dengan sendi bengkak panas dan tingkat asam urat serum tinggi dan beresiko jika salah mendiagnosis dari cairan sinovial dengan tidak menyingkirkan artritis septik.
c. Asam Urat dalam Urin
Sebuah evaluasi 24-jam asam urat dalam urin umumnya dilakukan jika terapi uricosuric sedang dipertimbangkan. Jika pasien mengeluarkan lebih dari 800 mg asam urat dalam 24 jam saat makan diet biasa, mereka overexcretors dan dengan demikian overproducers asam urat. Pasien-pasien ini (sekitar 10% pasien dengan gout) membutuhkan allopurinol bukan probenesid untuk mengurangi kadar asam urat. Pasien yang mengekskresikan lebih dari 1100 mg dalam 24 jam harus menjalani pemantauan fungsi ginjal dekat karena risiko batu dan nefropati urat.
d. Pemeriksaan Darah
Pengukuran glukosa berguna karena pasien dengan gout berada pada peningkatan risiko diabetes mellitus. Hati studi fungsi penting karena hasil abnormal dapat mempengaruhi pemilihan terapi. Pemeriksaan leukosit akan menunjukkan peningkatan yang signifikan mencapai 20.000/mm3 selama serangan akut. Selama periode asimtomatik angka leukosit masih dalam batasnormal yaitu 5000 - 10.000/mm3.
e. Radiografi
Foto polos mungkin menunjukkan temuan yang konsisten dengan gout, tapi temuan ini tidak diagnostic utama. Pada awal penyakit, radiografi seringkali normal atau hanya menunjukkan pembengkakan jaringan lunak. Temuan radiografi karakteristik asam urat, yang umumnya tidak muncul dalam tahun pertama onset penyakit, terdiri dari menekan-out erosi atau daerah litik dengan pinggiran menggantung.
Karakteristik erosi yang khas dari gout tetapi tidak rheumatoid arthritis meliputi :
· Pemeliharaan ruang sendi
· Tidak adanya osteopenia periarticular
· Lokasi di luar kapsul sendi
j) Penatalaksanaan
Terapi Farmakologis
Manajemen Artritis Gout serangan akut :
(1) sendi yang terkena harus diistirahatkan dan terapi obat antiinflamasi analgesik dimulai segera, dan berlanjut selama 1-2 minggu
(2) NSAID oral short-acting pada dosis maksimum adalah obat pilihan ketika tidak ada kontraindikasi
(3) Pada pasien dengan peningkatan risiko tukak lambung, pendarahan atau perforasi, co-reseptor agen pelindung lambung harus mengikuti pedoman standar untuk penggunaan NSAID dan coxib.
(4) Colchicine dapat menjadi alternatif yang efektif tetapi lambat untuk bekerja daripada NSAID. Untuk mengurangi risiko efek samping (terutama diare) harus digunakan dalam dosis 500 mg / hari.
(5) Allopurinol tidak boleh dimulai selama serangan akut tetapi pada pasien yang sudah boleh menggunakan allopurinol, harus dilanjutkan dan serangan akut harus ditangani secara konvensional
(6) analgesik opiat dapat digunakan sebagai tambahan.
(7) kortikosteroid intraartikular sangat efektif dalam monoarthritis gout akut, baik dalam bentuk oral, im atau iv kortikosteroid bisa efektif pada pasien yang tidak dapat mentoleransi NSAID, dan pada pasien yang refrakter terhadap pengobatan lain.
(8) Jika digunakan obat diuretik untuk mengobati hipertensi, dan agen anti-hipertensi, terapi alternatif harus dipertimbangkan, tetapi pada pasien dengan gagal jantung, terapi diuretik tidak harus dihentikan.
Manajemen Artritis Gout yang Berulang, Interkritikal dan Kronis.
(1) Kadar Asam Urat plasma harus dijaga dibawah, 300mol / L.
(2) Dalam kasus yang berbahaya, terapi harus dimulai setelah serangan kedua, atau bila serangan lebih lanjut terjadi dalam 1 tahun.
(3) obat juga harus ditawarkan kepada pasien dengan tophi, pasien insufisiensi ginjal pasien dengan batu asam urat untuk pasien yang perlu untuk melanjutkan pengobatan dengan diuretik.
(4) menunda untuk menurunkan obat asam urat sampai 1-2 minggu setelah peradangan akut.
(5) pengobatan jangka panjang untuk gout yang berulang biasanya harus dengan allopurinol, dimulai pada dosis 50-100 mg / hari dan meningkat 50-100 mg bertahap setiap beberapa minggu, disesuaikan jika perlu untuk perbaikan fungsi ginjal, sampai terapi Target (SUA <300mol / l) tercapai (dosis maksimum 900 mg).
(6) agen uricosuric dapat digunakan sebagai obat lini kedua pada pasien yang kadar asam uratnya dibawah standar atau pada pasien yang tidak tolerir dengan allopurinol. Obat-obatan yang bisa diberikan adalah sulphinpyrazone (200-800 mg / hari) pada pasien dengan fungsi ginjal normal atau benzbromarone (50-200 mg / hari) pada pasien dengan ringan / sedang insufisiensi ginjal.
(7) Colchicine 0,5 mg harus diikuti dengan pemberian obat allopurinol atau uricosuric, terus sampai 6 bulan. Pada pasien yang tidak dapat mentoleransi colchicine, NSAID atau coxib dapat diganti asalkan tidak ada kontraindikasi, tapi durasi NSAID atau coxib harus dibatasi sampai 6 minggu.
(8) Aspirin dalam dosis rendah (75-150 mg / hari) memiliki efek signifikan pada asam urat plasma, dan bisa digunakan untuk profilaksis kardiovaskular. Namun, aspirin dalam dosis analgesik (600-2400 mg / hari) mengganggu ekskresi asam urat dan harus dihindari. [10]
Terapi non-Farmakologis
Terapi non‐obat merupakan strategi esensial dalam penanganan gout. Gout adalah gangguan metabolik, yang dipengaruhi oleh diet, asupan alkohol, hiperlipidemia dan berat badan. Intervensi seperti istirahat yang cukup, penggunaan kompres dingin, modifikasi diet, mengurangi asupan alkohol dan menurunkan berat badan pada pasien yang kelebihan berat badan terbukti efektif.
Nutrisi untuk penderita artritis gout
1. Pembatasan purin
2. Kalori sesuai dengan kebutuhan
3. Tinggi karbohidrat
4. Rendah protein
5. Rendah lemak
6. Tinggi cairan
7. Tanpa alkohol
i) Komplikasi
Bila Diobati, Artritis Gout jarang menimbulkan ancaman kesehatan jangka panjang. Bila tidak diobati, asam urat bisa berkembang menjadi gangguan kronis menyakitkan dan melumpuhkan. Serangan gout kronis dapat merusak tulang rawan dan tulang, menyebabkan disfungsi sendi ireversibel dan cacat.
Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2006 gout menunjukkan bahwa 66 % orang dengan gout dianggap rasa sakit menjadi yang terburuk yang pernah mereka alami, sementara sekitar 75 % mengklaim bahwa suar-up membuat berjalan sangat sulit dan sekitar 70 persen melaporkan masalah bermain olahraga atau bahkan menempatkan di kaus kaki dan sepatu.
Jika gout tidak diobati, tophi (gumpalan kristal urat) dapat tumbuh sampai berukuran sebesar bola golf dan menyebabkan berbagai masalah pada sendi dan organ. Batu ginjal terjadi pada 10-40 persen pasien gout dan sekitar 25 persen dari mereka dengan hyperuricemia kronis mengembangkan penyakit ginjal, yang kadang-kadang berujung pada gagal ginjal.
Meskipun perlu dicatat bahwa dalam kebanyakan kasus penyakit ginjal datang pertama dan menyebabkan konsentrasi tinggi asam urat sekunder karena berkurangnya penyaringan. Kondisi lain yang berkaitan dengan gout jangka panjang termasuk katarak, sindrom mata kering dan komplikasi paru-paru.
j) Prognosis
Rata rata, setelah serangan awal, diramalkan 62 % yang tidak diobat akan mendapat serangan ke 2 dalam 1 tahun, 78 % dalam 2 tahun, 89 % dalam 5 tahun serta 93 % dalam 10 tahun. Seiring perjalanan waktu, pasien yang tidak diobati dengan serangan berulang akan mempunyai periode interkritikal yang lebih pendek, meningkatnya jumlah sendi yang terserang, dan meningkatkan disability. Diperkirakan 10-20 % pasien dengan pengendalian yang jelek atau tidak diobati akan mengalami perkembangan tofi dan 29 % nefrolitiasis pada kurang lebih 11 tahun setelah serangan awal.
Tata Laksana Terapi Hiperurisemia dan Gout
I. DEFINISI
Hiperurisemia adalah keadaan dimana terjadi peningkatan kadar serum asam urat (hingga di atas
7,0 mg/dl untuk pria dan 6,0 mg/dl untuk wanita.) dalam tubuh. Hiperurisemia disebabkan oleh
kelainan genetik dalam sistem metabolisme tubuh yang menyebabkan tubuh menghasilkan asam urat
lebih banyak dan atau disebabkan karena tubuh tidak dapat mengeliminasi asam urat dari
tubuh. Meskipun hiperurisemia merupakan dasar untuk pengembangan gout, keberadaannya justru
sering tidak menimbulkan gejala. Gout merupakan suatu keadaan dimana kadar asam urat terlalu
tinggi dalam cairan tubuh sehingga terbentuk kristal monosodium urat pada cairan sinovial, yang
menyebabkan terjadinya nyeri dan inflamasi (Ernst et al., 2008).
II. ETIOLOGI
Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko terjadinya gout erat hubungannya
dengan usia, kadar kreatinin dalam serum, kadar BUN (Blood Urea Nitrogen), jenis kelamin (pria),
tekanan darah, berat badan, stress, trauma,dislipidemia, pasien dengan kerusakan ginjal, dan konsumsi
alkohol.Penggunaan beberapa obat seperti diuretik, niasin, pirazinamide, levodopa, etambutol,
siklosporin, aspirin dosis rendah dan obat sitotoksik juga dapat memicu terjadinya hiperurisemia dan
gout. Pada penderita gout, kadar asam urat dalam serum rata-rata adalah 6,8 mg/dl untuk pria dan 6,0
mg/dl untuk wanita. Resiko pria menderita gout 10 kali lebih sering dibandingkan wanita (Burns et
al., 2008).
III. PATOFISIOLOGI
Pada manusia, asam urat merupakan produk akhir dari degradasi purin. Pada kondisi normal,
jumlah asam urat yang terakumulasi sekitar 1200 mg pada pria dan 600 mg pada wanita. Akumulasi
yang belebihan tersebut dapat dikarenakan over produksi atau under-eksresi asam urat
1. Over-produksi Asam Urat
Asam urat dibentuk oleh purin, yang berasal dari tiga sumber yaitu: makanan yang mengandung
purin, perubahan asam nukleat jaringan menjadi nukleotida purin, dan sistesis de novo dari basa purin.
Pada kondisi normal, asam urat dapat terakumulasi secara berlebihan jika produksi asam urat tersebut
berlebihan.Rata-rata produksi asam urat manusia per harinya sekitar 600-800 mg. Modifikasi diet
penting bagi pasien dengan beberapa penyakit yang dapat meningkatkan gejala hiperurisemia. Asam
urat juga dapat diproduksi berlebihan sebagai konsekuensi dari peningkatan gangguan dari jaringan
asam nukleat dan jumlah yang berlebihan dari sel turnover, penyakit myeloproliferative dan
lymphoproliferative, polycythemia, psoriasis, dan beberapa tipe anemia. Penggunaan obat sitotoksik
juga dapat menyebabkan overproduksi asam urat. Dua enzim abnormal yang menyebabkan
peningkatan produksi asam urat digambarkan pada gambar berikut.
Gambar 1. Metabolisme purin (HGPRT, hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase; PRPP, phosphoribosyl pyrophosphate (Ernst et al., 2008)
Pertama adalah peningkatan aktifitas sintesis phosphoribosyl pyrophosphate (PRPP) yang
memicu peningkatan konsentrasi PRPP. PRPP adalah kunci yang menentukan sintesis purin dan
produksi asam urat. Yang kedua adalah kekurangan hypoxanthine-guanine
phosphoribosyltransferase (HGPRT). HGPRT bertanggungjawab dalam merubah guanin menjadi
asam guanilic dan hipoxantin menjadi asam inosinik. Kekurangan enzim HGPRT memicu
peningkatan metabolisme dari guanin dan hipoxantin menjadi asam urat. Ketiadaan HGPRT
menghasilkan Lesch-Nyhan syndrome ditandai dengan choreoathetosis, spasticity, retardation mental,
yang secara nyata meningkatkan asam urat (Ernst et al., 2008).
2. Undereksresi Asam Urat
Sebagian besar pasien dengan gout mengalami penurunan fungsi ginjal dalam ekskresi asam urat
dengan alasan yang tidak diketahui. Normalnya, asam urat tidak terakumulasi didalam tubuh. Sekitar
2-3 produksi asam urat setiap hari dieksresikan melalui urin. Eliminasi dilakukan melalui saluran
pencernaan setelah degradasi enzim oleh bakteri. Penurunan asam urat melalui urin memicu
hiperuresimia dan meningkatkan endapan asam urat. Sebagian besar asam urat secara bebas terfiltrasi
melalui glomerulus. Konsentrasi asam urat muncul pada urin ditentukan dengan transport multiple
renal tubular dan menambah beban filtrasi. Sekitar 90% hasil filtrasi asam urat direabsorbsi pada
tubulus proximal, dengan mekanisme transport aktif atau pasif. Faktor-faktor yang dapat menurunkan
klirens asam urat atau meningkatkan produksi asam urat akan mengakibatkan peningkatan konsentrasi
asam urat dalam serum yaitu primary gout, diabetik ketoasidosis, gangguan mieloproliferatif, anemia
hemolitik kronik, obesitas, gagal jantung kongestif, gagal ginjal, down syndrome, hiperparatiroid,
hipoparatiroid, alkoholisme akut, akromegali, hipotiroid, dan lain-lain. Obat-obat yang dapat
menurunkan klirens asam urat di ginjal melalui modifikasi beban yang disaring (filtered load) atau
salah satu proses transport tubular diantaranya diuretik, asam nikotinat, salisilat (< 2 g/hari), etanol,
pirazinamid, levodopa, etambutol, obat sitotoksik, dan siklosporin (Ernst et al., 2008).
IV. GEJALA DAN PRESENTASI KLINIK
1. Artritis Gout Akut
Serangan arthritis gout akut ditandai dengan onset yang cepat dari terjadinya nyeri yang
menyiksa, pembengkakan, dan inflamasi. Serangan tersebut awalnya muncul monoartikular, dan
pertama lebih sering mempengaruhi sendi metatarsophalangeal (pembengkakan jari) dan kemudian
berlanjut mempengaruhi instep, pergelangan kaki, tumit, lutut, pergelangan tangan, jari, dan
siku (Hawkins and Rahn, 2005).
Kebanyakan tipe dari gout akut ini menyerang sendi periferal ekstremitas bawah yang mungkin
dikarenakan sendi tersebut memiliki suhu rendah yang dikombinasikan dengan konsentrasi asam urat
intraartrikular. Cairan sinovial ditemukan menyebabkan terjadinya gout sementara pada bantalan
sendi yang berhubungan dengan berat badan dalam melakukan aktivitas rutin sepanjang hari. Pada
malam hari, air direabsorbsi dari ruang sendi, dan menjadi larutansupersaturated monosodium urat,
yang dapat memicu serangan arthritis akut. Serangan umumnya terjadi pada malam hari yang
mengganggu waktu istirahat pasien akibat nyeri yang hebat. Untuk mengevaluasi hiperurisemia,
diperlukan pendekatan patofisiologi apakah pasien mengalami overproduksi atau underekskresi asam
urat. Pada keadaan diet yang teratur, jika terjadi ekskresi asam urat lebih dari 1000 mg dalam 24 jam
maka menunjukkan overproduksi asam urat, dan kurang dari jumlah ini kemungkinan
normal (Hawkins and Rahn, 2005).
2. Asam Urat Nefrolitiasis
Nefrolitiasis terjadi pada 10-25% pasien yang mengidap gout. Beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi individu mengidap asam urat nefrolitiasis yaitu ekskresi asam urat yang berlebihan
dalam urin, urin yang asam, dan konsentrasi urin yang pekat. Risiko batu ginjal (renal calculi)
mencapai 50% pada individu yang mengekskresikan asam urat dalam jumlah berlebih melalui ginjal
hingga 1100 mg/hari. Sebagai tambahan selain batu asam urat murni, pada individu hiperurikosurik
juga terjadi peningkatan resiko batu akibat campuran asam urat-kalsium oksalat dan batu kalsium
oksalat murni (Hawkins and Rahn, 2005).
3. Gout Nefropati
Terdapat dua tipe gout nefropati yaitu asam urat nefropati akut dan kronis. Pada asam urat
nefropati akut, terjadi gagal ginjal akut sebagai akibat penyumbatan aliran urin dan pengendapan
kristal asam urat pada saluran pengumpul dan ureter. Terdapat dua tipe gout nefropati yaitu asam urat
nefropati akut dan kronis. Pada asam urat nefropati akut, terjadi gagal ginjal akut sebagai akibat
penyumbatan aliran urin dan pengendapan kristal asam urat pada saluran pengumpul dan ureter.
Gejala ini merupakan komplikasi yang sering terjadi pada pasien mieloproliferatif atau
limfoproliferatif dan merupakan akibat dari pergantian sel malignan (ganas) secara besar-besaran,
terutama setelah inisiasi kemoterapi. Sedangkan pada asam urat nefropati kronis disebabkan karena
pengendapan kristal asam urat jangka panjang dalam parenkim ginjal.Sedangkan pada asam urat
nefropati kronis disebabkan karena pengendapan kristal asam urat jangka panjang dalam parenkim
ginjal (Hawkins and Rahn, 2005).
4. Tophaceous Gout
Tofi (deposit asam urat) jarang terjadi pada pasien gout dan merupakan komplikasi hiperurisemia
yang lambat. Tempat yang paling umum terjadi deposit asam urat (tophaceous deposits) pada pasien
dengan arthritis gout akut kambuhan adalah pangkal ibu jari kaki, helix telinga, tonjolan tulang
siku,achilles tendon, lutut, pergelangan tangan, dan tangan. Pada akhirnya pinggul, bahu, dan tulang
belakang juga terpengaruh (Hawkins and Rahn, 2005).
V. DIAGNOSIS
Aspirasi cairan sendi yang terkena adalah penting untuk definitive diagnosis. Cairan sendi yang
mengandung negatif birefringent kristal monosodium urat akan menegaskan diagnosis. Cairan sendi
memiliki jumlah WBC yang tinggi dengan neutrofil mendominasi. Meskipun jarang dilakukan,
pengumpulan urin 24 jam dapat digunakan untuk menentukan apakah pasien adalah overproducer
atau underexcretor asam urat. Individu yang mengekskresikan lebih dari 800 mg asam urat dalam
pengumpulan urin 24jam ini akan dianggap overproducers. Pasien dengan hyperuricemia yang
mengekskresikan kurang dari 600 mg/hari diklasifikasikan sebagai underexcretor asam urat (Burns et
al., 2008)
VI. PENATALAKSANAAN TERAPI
Tujuan dari terapi gout dan hiperurisemia adalah sebagai berikut:
1. Menghentikan serangan akut.
2. Mencegah serangan kembali dari arthritis gout.
3. Mencegah komplikasi yang berkaitan dengan deposit kristal asam urat kronis di jaringan1.
Sangat penting bagi pasien untuk memahami diagnosis gout dan pentingnya pengobatan. Terapi
jangka panjang biasanya dianjurkan untuk menindaklanjuti serangan akut yang parah. Untuk serangan
akut dan pencegahan berulangnya serangan dibutuhkan terapi obat. Banyak brosur dan tulisan-tulisan
tentang gout yang dapat dibaca pasien. Perubahan gaya hidup, dapat digunakan sebagai pilihan-
pilihan dalam pengobatan.
(Depkes RI, 2006)
A. Terapi Nonfarmakologi
Berikut ini contoh-contoh tindakan yang dapat berkontribusi dalam menurunkan kadar asam
urat :
1. Penurunan berat badan (bagi yang obes).
2. Menghindari makanan (misalnya yang mengandung purin tinggi) dan minuman tertentu yang dapat
menjadi pencetus gout.
3. Mengurangi konsumsi alkohol (bagi peminum alkohol).
4. Meningkatkan asupan cairan.
5. Mengganti obat-obatan yang dapat menyebabkan gout (misal diuretik tiazid).
6. Terapi es pada tempat yang sakit.
Intervensi dengan diet dengan mengurangi karbohidrat menurunkan kadar urat sampai 18% dan
frekuensi serangan gout sampai 67%. Sudah lama buah cherry dilaporkan membantu menurunkan
serangan gout. Dugaan karena kandungan antosianin dalam cherry mempunyai sifat inhibitor COX 2.
Studi mutakhir membuktikan juga cherry menurunkan kadar asam urat. Diet rendah purin pada masa
lalu dianggap menurunkan kadar asam urat, ternyata keberhasilannya mempunyai batas. Walau terapi
non obat ini sederhana, tetapi dapat mengurangi simtom gout apabila digunakan bersama dengan
terapi obat.
(Depkes RI, 2006)
Modifikasi gaya hidup
Banyak pasien gout mempunyai berat badan berlebih. Hiperurisemia dan gout adalah
komponen dari sindrom resisten insulin. Diet dan cara lain untuk menurunkan insulin dalam serum
dapat menurunkan kadar urat dalam serum, sebab insulin tinggi akan mengurangi ekskresi asam urat.
Alkohol meningkatkan produksi urat dan menurunkan ekskresi urat dan dapat mengganggu ketaatan
pasien. Sebab iti secara rutin membahas diet dengan pasien dengan gout, dan mengajak pasien
merubah gaya hidup yang praktis yang dapat mengurangi risiko gout, akan sangat berarti.
Biasanya diet sebaiknya diawali hanya pada saat inflamasi telah terkendali secara total, karena
diet ketat akan memperparah hiperurisemia dan menyebabkan serangan akut gout. Hal yang sama
untuk mencegah serangan gout dengan minum kolkhisin atau NSAID pada saat upaya serius
penurunan berat badan. Separuh dari asam urat dalam tubuh di dapat dari asupan makanan yang
mengandung purin. Diet ketat purin sulit diikuti. Lagi pula walau diet ketat diikuti, urat dalam serum
hanya turun 1mg/dL dan ekskresi urat lewat urin hanya turun 200mg/hari. Tetapi sayangnya kalau
asupan makanan purin dan alkohol diumbar maka kadar urat dalam serum dapat melonjak, tidak
jarang sampai 12-14mg/dL.
Tabel 1. Panduan Diet Pasien Gout Arthritis (GA)
(Depkes RI, 2006)
B. TERAPI FARMAKOLOGI
1. Arthritis Gout Akut
Tujuan terapi serangan arthritis gout akut adalah menghilangkan simptom. Penting untuk
menghindarkan fluktuasi konsentrasi urat dalam serum karena dapat memperpanjang serangan atau
memicu episoda lebih lanjut. Sebab itu hipourisemik seperti alopurinol tidak diberikan sampai paling
sedikit tiga minggu setelah serangan akut berhenti dan diteruskan pada pasien yang mengalami
serangan. Sendi yang sakit harus diistirahatkan dan terapi obat dilaksanakan secepat mungkin untuk
menjamin respons yang cepat dan sempurna.
Ada tiga pilihan obat untuk arthritis gout akut: NSAID, kolkhisin, kortikosteroid. Setiap obat ini
memiliki keuntungan dan kerugian. Pemilihan untuk pasien tetentu tergantung pada beberapa faktor,
termasuk waktu onset dari serangan yang berhubungan dengan terapi awal, kontraindikasi terhadap
obat karena adanya penyakit lain, efikasi versus resiko potensial. Adapun algoritme terapi gout akut
sebagai berikut.
Gambar 2. Algoritma terapi arthritis gout akut (Depkes RI, 2006)
Adapun obat-obat untuk penanganan arthritis gout akut adalah sebagai berikut:
a. NSAID
NSAID biasanya lebih dapat ditolerir dibanding kolkhisin dan lebih mempunyai efek yang
dapat diprediksi. NSAID tidak mempengaruhi kadar urat dalam serum. Ada beberapa NSAID yang
sering diperuntukan untuk arthritis gout. Diklofenak, indometasin, ketoprofen, naproksen, piroxikam,
sulindak. Indometasin cenderung paling sering digunakan, walau tidak ada perbedaan yang signifikan
antara obat ini dengan obat NSAID lain. Pemakaian aspirin harus dihindarkan sebab mengakibatkan
retensi asam urat, kecuali kalau digunakan dalam dosis tinggi.
Tergantung pada keparahan serangan dan waktu antara onset dan permulaan terapi, dosis 50-
100 mg indometasin oral akan menghilangkan nyeri dalam dua-empat jam. Dapat diikuti menjadi
150-200 mg sehari, dengan dosis dikurangi bertahap menjadi 25 mg tiga kali sehari untuk 5 sampai 7
hari, hingga nyeri hilang. Cara ini dapat mengurangi toksisitas gastrointestinal. NSAID biasanya
dibutuhkan antara 7 sampai 14 hari tergantung respons pasien, walau pasien dengan kronik atau gout
tofi membutuhkan terapi NSAID lebih lama untuk mengendalikan gejala.
Pemanfaatan NSAID menjadi terbatas karena efek sampingnya, yang menimbulkan masalah
terutama pada manula dan pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Pada manula, atau mereka dengan
riwayat PUD (Peptic Ulcer Disease), harus diikuti dengan H2 antagonis, misoprostol atau PPI (Proton
Pump Inhibitor) 21. Untuk Misoprostol, perlu kehati-hatian dalam pemakaiannya, kontraindikasi
untuk wanita hamil, dan penggunaannya masih sangat terbatas di Indonesia. Untuk pasien dengan
gangguan ginjal, NSAID harus dihindarkan sedapat mungkin, atau diberikan dengan dosis sangat
rendah, apabila keuntungan masih lebih tinggi dibanding kerugian. Apabila demikian maka harus
dilakukan pemantauan creatinin clearance, urea, elektrolit secara reguler.
b. Kolkhisin
Kolkhisin digunakan untuk Arthritis gout akut, sebagian rematologis menganggap tidak efektif,
karena cenderung menyebabkan diare berat terutama bagi pasien dengan mobilitas terbatas.
Sebaiknya digunakan untuk pencegahan saja atau sebagai pilihan terakhir. Kolkhisin telah digunakan
sejak tahun 1920. Kolkhisin adalah antimitotik, menghambat pembelahan sel, dan diekskresi melalui
urin. Tidak menurunkan kadar urat dalam serum, dan kalau menjadi pilihan maka harus diberikan
secepat mungkin saat serangan terjadi agar efektif. Kolkhisin dapat juga digunakan untuk mencegah
serangan, dan direkomendasikan untuk diberikan dalam dosis rendah sebelum memulai obat penurun
urat, kemudian dilanjutkan sampai 1 tahun setelah urat dalam serum menjadi normal.
Bila diberikan secara oral maka diberikan dosis awal 1 mg, diikuti dengan dosis 0,5 mg. Walau
BNF menganjurkan diberikan setiap 2 jam sampai timbul diare atau total pemberian 8 mg, kenyataan
jarang diikuti. Kebanyakan pasien merespons dalam waktu 18 jam dan inflamasi menghilang pada 75-
80% pasien dalam 48 jam. Reaksi yang tidak dikehendaki dari kolkhisin adalah gangguan
gastrointestinal, disfungsi sumsum tulang belakang, dan disfungsi neuromuskular. Hal ini lebih sering
terjadi pada pasien dengan gangguan ginjal atau hati dan manula. Kolkhisin sebagai vasokonstriktor
dan mempunyai efek stimulasi pada pusat vasomotor, sebab itu hati-hati bagi pasien dengan gagal
jantung kronis.
c. Kortikosteroid
Injeksi intra-artikular kortikosteroid sangat berguna bila NSAID atau kolkhisin bermasalah,
misalnya pada pasien dengan gagal jantung kronis atau gangguan ginjal atau hati. Ini juga sangat
berguna untuk arthritis gout akut yang terbatas hanya sendi tunggal. Bagaimanapun harus dipastikan
bahwa penyakit ini bukan arthritis septik, sebelum menyuntikkan steroid.
Kortikosteroid dapat diberikan secara oral dalam dosis tinggi (30-40 mg) atau intramuskular,
berangsur-angsur diturunkan selama 7-10 hari, terapi ini baik untuk pasien yang tidak dapat
mentolerir NSAID, kolkhisin ataupun gagal dengan terapi ini, juga bagi mereka dengan serangan
poliartikular. Hati-hati bagi pasien dengan gagal jantung.
(Depkes RI, 2006)
2. Gout Kronis
Pengobatan gout kronis membutuhkan waktu jangka panjang untuk mereduksi serum urat
sampai di bawah normal. Harus dijaga agar tidak terjadi serangan gout akut, mengurangi volume tofi,
mencegah perusakan selanjutnya. Terapi penurunan urat hendaknya tidak direkomendasikan saat
terjadi serangan akut. Sebelum memberi pasien alopurinol, beberapa hal harus dipertimbangkan
apakah pasien adalah kandidat yang tepat untuk urikosurik.
Obat penurun urat diindikasikan untuk:
- Pasien dengan serangan lebih dari 2 kali setahun
- Gout tofi yang kronis
- Produksi berlebih asam urat (primary dan purin enzyme defect)
- Gout kronis yang berkaitan dengan kerusakan ginjal atau batu ginjal urat
- Tambahan terapi sitotoksik untuk hematological malignancy
Obat ini dibagi menjadi 3 kategori, antara lain:
- Urikostatik (xantin oksidase inhibitor) misalnya alopurinol
- Urikosurik misalnya benzbromaron, sulfinperazon, probenesid
- Urikolitik misalnya urat oksidase
(Depkes RI, 2006)
Adapun obat-obat yang digunakan dalam penanganan gout kronis adalah sebagai berikut:
a. Urikostatik (Xantin oxidase inhibitor)
Alopurinol adalah drug of choice untuk menurunkan urat dalam serum. Alopurinol
menghambat pembentukan asam urat. Risiko untuk menimbulkan serangan goutakut pada awal
pengobatan dapat dihindarkan dengan memakai dosis awal yang rendah (50-100 mg), dan
ditingkatkan bila perlu. Kolkhisin atau NSAID ditambahkan sebagai pencegahan terjadinya episode
akut. Dosis 50-600 mg sehari untuk mengurangi kadar urat. Normalisasi kadar urat dalam serum
biasanya terlihat dalam 4 minggu dan serangan gout akut berhenti dalam 6 bulan dengan terapi yang
kontinyu. Reduksi tofi memakan waktu tahunan. Kadang-kadang dosis dibutuhkan sampai 900 mg.
Dalam penggunaannya perlu diwaspadai, antara lain, banyak interaksi, terutama dengan antikoagulan
oral, teofilin, azatioprin; efek samping utama : ruam (2%) reaksi hipersensitif: (0.4%), meningkat bila
digunakan bersama ampisilin (20%), tiazid; reaksi hipersensitif dapat mengakibatkan mortalitas; dan
karena ekskresi hanya lewat ginjal, hati-hati bagi yang mengalami kerusakan ginjal, sebab itu dosis
harus disesuaikan dengan creatinin clearance.
b. Urikosurik
Obat urikosurik meningkatkan ekskresi urat di ginjal dengan menghambat reabsorpsi pada
proksimal tubule. Karena mekanisme ini ada kemungkinan terjadi batu ginjal atau batu di saluran
kemih. Untuk mencegah risiko ini dosis awal harus rendah ditingkatkan perlahan-lahan, dan hidrasi
yang cukup. Tidak boleh digunakan pada kondisi overproduction atau nefrolitiasis ginjal. Obat ini
ternyata dapat digunakan untuk hiperurisemia yang disebabkan diuretik.
Probenesid dan sulfinpirazon sebaiknya tidak digunakan untuk pasien dengan kerusakan ginjal.
Benzbromaro suatu alternatif dari alopurinol, untuk pasien normal danpasien dengan fungsi ginjal
yang terganggu, hasilnya bagus. Telah digunakan pula untuk pasien yang tidak mengalami kemajuan
dengan pengobatan alopurinol, dan pada pasien transplan ginjal dalam terapi siklosporin. Ada
kekhawatiran tentang hepatoksisitas, dan pemakaiannya pada pasien yang alergi alopurinol dengan
gangguan ginjal belum diteliti lebih lanjut.
Losartan dengan dosis 25- 15 mg, suatu angiotensin II converting enzyme inhibitor (ACE
inhibitor) yang digunakan untuk terapi hipertensi, menghambat reabsorpsi tubular ginjal sebab itu
bekerja sebagai urikosurik. Losartan juga menunjukkan penurunan urat dalam serum yang meningkat
akibat diuretik. Obat ini berguna sebagai terapi tambahan pada pasien dengan hipertensi dan gout atau
hiperurisemia. sulfinpirazon, benzbromaron, belum ada di Indonesia saat ini.
Fenofibrat, obat penurun lipid, ternyata mempunyai efek urikosurik juga. Penurunan sebesar
20-35% terjadi. Akan berguna bagi pasien dengan hiperlipidemia dan gout/hiperurisemia. Terapi
kombinasi dari fenofibrat atau losartan dengan obat anti-hiperurisemik, termasuk benzbromaron
(50mg sekali sehari) atau alopurinol (200 mg dua kali sehari), secara signifikan mengurangi urat
dalam serum sesuai dengan peningkatan ekskresi asam urat. Kombinasi ini adalah pilihan yang baik
untuk terapi pasien gout dengan hipertrigliseridamia dan/atau hipertensi, walau efek tambahan
hipourisemik sifatnya sedang.
c. Urikolitik
Sebagai katalisator, urat oxidase merubah asam urat menjadi alantoin pada binatang tingkat
rendah. Manusia tidak memiliki enzim ini. Bila digunakan secara parentral urikase adalah penurun
urat yang lebih cepat dibanding alopurinol. Urat oxidase mencegah terbentuknya urat dan juga
menguraikan asam urat yang telah ada, tidak seperti alopurinol.
(Depkes RI, 2006)
3. Arthritis Gout Interkitikal
Pasien dengan arthritis gout, pada saat ada periode bebas simptom di antara serangan-serangan
disebut interkritikal gout. Hiperurisemia mungkin masih menetap dan kristal mungkin ada dalam
cairan sinovial. Interkritikal gout adalah saat dimana pasien harus proaktif mengendalikan kadar asam
urat dan mengambil langkah lain untuk menurunkan risiko serangan gout lain. Evaluasi kondisi pasien
yang berkaitan dengan dasar penyebab disorder (misalnya: peminum alkohol dengan gout, dll)
identifikasi dan obati penyakit yang berkaitan dengan gout bila ada: hipertensi, obesitas, peminum
alkohol, pemakaian diuretik, hipotiroid, hiperkoleterolemia, dan intoksikasi timbal (Depkes RI, 2006).
VII. PROGNOSIS
Adapun prognosis untuk pasien arthritis gout, antara lain:
Rata-rata, setelah serangan awal, diramalkan 62% yang tidak diobati akan mendapat serangan ke 2 dalam 1 tahun, 78% dalam 2 tahun, 89% dalam 5 tahun, 93% dalam 10 tahun
Informasikan kepada pasien dengan hiperurisemia asimtomatik, bahwa risiko untuk arthritis gout di masa depan proporsional dengan kadar asam urat dalam darah dan masalah kesehatan lain, terutama hipertensi, obesitas, kadar kolesterol dalam darah, asupan alkohol.
Dalam perjalanan waktu, pasien yang tidak diobati dengan serangan berulang akan mempunyai perioda interkritikal yang lebih pendek, meningkatnya jumlah sendi yang terserang, dan meningkatnya disability.
Diramalkan 10-22% pasien dengan pengendalian yang jelek atau tidak diobati akan mengalami perkembangan tofi dan 20% nefrolitiasis pada kurang lebih 11 tahun setelah serangan awal.
Bila memprediksi pasien dengan penyakit sendi karena kristal, pertimbangkan juga efek komorbiditas (contoh hipertensi atau alkoholisme pada gout dll).
Kaitan antara gout dengn hipertensi, aterosklerosis, hipertrigliseridemia, dan diabetes melitus mungkin ada hubungannya dengan sindrom resistensi insulin (obesitas-insulin insesitifitas, sindrom metabolik).
(Depkes, 2006)
DAFTAR PUSTAKA
Burns, M.A.C., B.G. Wells., T.L. Schwinghammer., P.M.Malone., J.M. Kolesar., J.C. Rotschafer and J.T. Dipiro. 2008. Pharmacotherapy: Principles and Practice. USA: The McGraw-Hill Companies. P. 932-939.
DepKes, 2006. Pharmaceutical Care Untuk Pasien Penyakit Arthritis Rematik. Jakarta: Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan. P. 66-80.
Ernst, M.E., Clark, E.C., and Hawkins, D.W. 2008. Gout and Hyperuricemia. 2008. In: Dipiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzke, G.R., Wells, A.G., Posey, L.M. editors. Pharmacotherapy: a Pathophysiologic Approach, 7thed. USA: McGraw-Hill Companies. P. 1539-1550.
Hawkins, D. W. and Rahn, D. W. 2005. Gout and Hyperuricemia. In: Dipiro, J.T., Talbert, R.L., Yee, G.C., Matzke, G.R., Wells, A.G., Posey, L.M. editors. Pharmacotherapy: a Pathophysiologic Approach, 6th ed. USA:McGraw-Hill. P. 1705-1711.
RHEUMATOID ARTHRITIS
EMIRZA NUR WICAKSONO, S.KED JANUARI 10, 2013[0] COMMENTS
Rheumatoid arthritis (RA) adalah jenis arthritis kronis. Gejala awal RA meliputi kelelahan, nyeri sendi, dan kekakuan. Gejala lain rheumatoid arthritis mungkin merasa seperti flu, dengan perasaan sakit, nyeri otot, dan kehilangan nafsu makan. Penyebab rheumatoid arthritis tidak diketahui, walaupun mungkin ada komponen genetik. Pengobatan awal arthritis, dapat efektif meningkatkan prognosis dan dapat membantu mencegah kerusakan tulang sendi yang terkait dengan RA.
Etiologi
Penyebab pasti reumatod arthritis tidak diketahui. Biasanya merupakan kombinasi dari faktor genetic, lingkungan, hormonal dan faktor system reproduksi. Namun faktor pencetus terbesar adalah faktor infeksi seperti bakteri, mikoplasma dan virus (Lemone & Burke, 2001).
Penyebab utama kelainan ini tidak diketahui. Ada beberapa teori yang dikemukakan mengenai penyebab artritis reumatoid, yaitu :
1. Infeksi streptokokus hemolitikus dan streptokokus non-hemolitikus
2. Endokrin
3. Autoimun
4. Metabolik
5. Faktor genetik serta faktor pemicu lainnya.
Pada saat ini, artritis reumatoid diduga disebabkan oleh faktor autoimun dan infeksi. Autoimun ini bereaksi terhadap kolagen tipe II; faktor infeksi mungkin disebabkan oleh karena virus dan organisme mikoplasma atau grup difterioid yang menghasilkan antigen tipe II kolagen dari tulang rawan sendi penderita.
Manifestasi Klinis
Pola karakteristik dari persendian yang terkena :
1. Mulai pada persendian kecil ditangan, pergelangan , dan kaki.
2. Secara progresif menenai persendian, lutut, bahu, pinggul, siku, pergelangan kaki, tulang belakang serviks, dan temporomandibular.
3. Awitan biasnya akut, bilateral, dan simetris.
4. Persendian dapat teraba hangat, bengkak, dan nyeri ; kaku pada pagi hari berlangsung selama lebih dari 30 menit.
5. Deformitasi tangan dan kaki adalah hal yang umum.
Gambaran Ekstra-artikular :
1. Demam, penurunan berat badan, keletihan, anemia.
2. Fenomena Raynaud.
3. Nodulus rheumatoid, tidak nyeri tekan dan dapat bergerak bebas, di temukan pada jaringan subkutan di atas tonjolan tulang.
Rheumatoid arthritis ditandai oleh adanya gejala umum peradangan berupa :
1. demam, lemah tubuh dan pembengkakan sendi.
2. nyeri dan kekakuan sendi yang dirasakan paling parah pada pagi hari.
3. rentang gerak berkurang, timbul deformitas sendi dan kontraktur otot.
4. Pada sekitar 20% penderita rheumatoid artritits muncul nodus rheumatoid ekstrasinovium. Nodus ini erdiri dari sel darah putih dan sisia sel yang terdapat di daerah trauma atau peningkatan tekanan. Nodus biasanya terbentuk di jaringan subkutis di atas siku dan jari tangan.
Komplikasi
Kelainan sistem pencernaan yang sering dijumpai adalah gastritis dan ulkus peptik yang merupakan komlikasi utama penggunaan obat anti inflamasi nonsteroid (OAINS) atau obat pengubah perjalanan penyakit ( disease modifying antirhematoid drugs, DMARD ) yang menjadi faktor penyebab morbiditas dan mortalitas utama pada arthritis reumatoid.
Komlikasi saraf yang terjadi memberikan gambaran jelas , sehingga sukar dibedakan antara akibat lesi artikuler dan lesi neuropatik. Umumnya berhubungan dengan mielopati akibat ketidakstabilan vertebra servikal dan neuropati iskemik akibat vaskulitis.
Patofisiologi
Membran syinovial pada pasien reumatoid artritis mengalami hiperplasia, peningkatan vaskulariasi, dan ilfiltrasi sel-sel pencetus inflamasi, terutama sel T CD4+. Sel T CD4+ ini sangat berperan dalam respon immun. Pada penelitian terbaru di bidang genetik, reumatoid artritis sangat berhubungan dengan major-histocompatibility-complex class II antigen HLA-DRB1*0404 dan DRB1*0401. Fungsi utama dari molekul HLA class II adalah untuk mempresentasikan antigenic peptide kepada CD4+ sel T yang menujukkan bahwa reumatoid artritis disebabkan oleh arthritogenic yang belum teridentifikasi. Antigen ini bisa berupa antigen eksogen, seperti protein virus atau protein antigen endogen. Baru-baru ini sejumlah antigen endogen telah teridentifikasi, seperti citrullinated protein dan human cartilage glycoprotein 39.
Antigen mengaktivasi CD4+ sel T yang menstimulasi monosit, makrofag dan syinovial fibroblas untuk memproduksi interleukin-1, interleukin-6 dan TNF-α untuk mensekresikan matrik metaloproteinase melalui hubungan antar sel dengan bantuan CD69 dan CD11 melalui pelepasan mediator-mediator pelarut seperti interferon-γ dan interleukin-17. Interleukin-1, interlukin-6 dan TNF-α merupakan kunci terjadinya inflamasi pada rheumatoid arthritis.
Arktifasi CD4+ sel T juga menstimulasi sel B melalui kontak sel secara langsung dan ikatan dengan α1β2 integrin, CD40 ligan dan CD28 untuk memproduksi immunoglobulin meliputi rheumatoid faktor. Sebenarnya fungsi dari rhumetoid faktor ini dalam proses patogenesis reumatoid artritis tidaklah diketahui secara pasti, tapi kemungkinan besar reumatoid faktor mengaktiflkan berbagai komplemen melalui pembentukan immun kompleks.aktifasi CD4+ sel T juga mengekspresikan osteoclastogenesis yang secara keseluruhan ini menyebabkan gangguan sendi. Aktifasi makrofag, limfosit dan fibroblas juga menstimulasi angiogenesis sehingga terjadi peningkatan vaskularisasi yang ditemukan pada synovial penderita reumatoid artritis.
Pemeriksaan Penunjang
Tidak banyak berperan dalam diagnosis reumatoid, namun dapat menyokong bila terdapat keraguan atau untuk melihat prognosis gejala pasien.
1. Pemeriksaan laboratorium
Beberapa hasil uji laboratorium dipakai untuk membantu menegakkan diagnosis artritis reumatoid. Sekitar 85% penderita artritis reumatoid mempunyai autoantibodi di dalam serumnya yang dikenal sebagai faktor reumatoid. Autoantibodi ini adalah suatu faktor anti-gama globulin (IgM) yang bereaksi terhadap perubahan IgG. Titer yang tinggi, lebih besar dari 1:160, biasanya dikaitkan dengan nodula reumatoid, penyakit yang berat, vaskulitis, dan prognosis yang buruk.
Faktor reumatoid adalah suatu indikator diagnosis yang membantu, tetapi uji untuk menemukan faktor ini bukanlah suatu uji untuk menyingkirkan diagnosis reumatoid artritis. Hasil yang positif dapat juga menyatakan adanya penyakit jaringan penyambung seperti lupus eritematosus sistemik, sklerosis sistemik progresif, dan dermatomiositis. Selain itu, sekitar 5% orang normal memiliki faktor reumatoid yang positif dalam serumnya. Insidens ini meningkat dengan bertambahnya usia. Sebanyak 20% orang normal yang berusia diatas 60 tahun dapat memiliki faktor reumatoid dalam titer yang rendah.
Laju endap darah (LED) adalah suatu indeks peradangan yang bersifat tidak spesifik. Pada artritis reumatoid nilainya dapat tinggi (100 mm/jam atau lebih tinggi lagi). Hal ini berarti bahwa laju endap darah dapat dipakai untuk memantau aktifitas penyakit. Artritis reumatoid dapat menyebabkan anemia
normositik normokromik melalui pengaruhnya pada sumsum tulang. Anemia ini tidak berespons terhadap pengobatan anemia yang biasa dan dapat membuat penderita cepat lelah. Seringkali juga terdapat anemia kekurangan besi sebagai akibat pemberian obat untuk mengobati penyakit ini. Anemia semacam ini dapat berespons terhadap pemberian besi.
Pada Sendi Cairan sinovial normal bersifat jernih, berwarna kuning muda hitung sel darah putih kurang dari 200/mm3. Pada artritis reumatoid cairan sinovial kehilangan viskositasnya dan hitungan sel darah putih meningkat mencapai 15.000 – 20.000/ mm3. Hal ini membuat cairan menjadi tidak jernih. Cairan semacam ini dapat membeku, tetapi bekuan biasanya tidak kuat dan mudah pecah. Pemeriksaan laboratorium khusus untuk membantu menegakkan diagnosis lainya, misalnya : gambaran immunoelectrophoresis HLA (Human Lymphocyte Antigen) serta Rose-Wahler test.
2. Pemerikasaan Gambaran Radiologik
Pada awal penyakit tidak ditemukan, tetapi setelah sendi mengalami kerusakan yang berat dapat terlihat penyempitan ruang sendi karena hilangnya rawan sendi. Terjadi erosi tulang pada tepi sendi dan penurunan densitas tulang. Perubahan ini sifatnya tidak reversibel. Secara radiologik didapati adanya tanda-tanda dekalsifikasi (sekurang-kurangnya) pada sendi yang terkena.
Diagnosa rheumatoid arthritis (RA), pada tahap awal, bisa sulit. Tidak ada tes tunggal yang dapat dengan jelas mengidentifikasi rheumatoid arthritis. Sebaliknya, dokter mendiagnosis rheumatoid arthritis berdasarkan faktor-faktor yang sangat terkait dengan penyakit ini. American College of Rheumatology menggunakan daftar kriteria Untuk mcnegakkan diagnosis Artritis Reumatoid harus didapati 4 atau lebih kriteria berikut ini :
1. Kekakuan pagi hari di dalam dan sekitar sendi minimal satu jam.
2. Pembengkakan atau cairan di sekitar tiga atau lebih sendi secara bersamaan.
3. Setidaknya satu bengkak di daerah pergelangan tangan, tangan, atau sendi jari.
4. Arthritis melibatkan sendi yang sama di kedua sisi tubuh (arthritis simetris).
5. Rheumatoid nodul, benjolan pada kulit penderita rheumatoid arthritis. Nodul ini biasanya di titik-titik tekanan dari tubuh, paling sering siku.
6. Jumlah faktor rematoid dalam darah abnormal.
7. X-ray tampak perubahan di tangan dan pergelangan tangan khas dari rheumatoid arthritis, dengan kerusakan tulang di sekitar sendi yang terlibat.
Obat apa yang digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis?
NSAID
Sebagai bagian dari perawatan rheumatoid arthritis Anda, dokter Anda mungkin akan memberikan resep obat anti-inflamasi nonsteroid (NSAID). Obat ini mengurangi rasa sakit dan inflamasi tetapi tidak memperlambat kemajuan RA. Oleh karena itu, orang dengan RA sedang sampai parah seringkali membutuhkan obat tambahan untuk mencegah kerusakan sendi lebih lanjut.
DMARDs
Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) membantu memperlambat atau menghentikan perkembangan RA. DMARD yang paling umum digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis adalah metotreksat. DMARDs lainnya termasuk Arava, Azulfidine, Cytoxan, Imuran, Neoral, dan Plaquenil.
Biologis
Pengobatan yang terbaru dan paling efektif untuk rheumatoid arthritis adalah terapi biologis. Terapi biologis secara genetik direkayasa protein. Mereka dirancang untuk menghambat komponen spesifik sistem kekebalan tubuh yang memainkan peran penting dalam peradangan, komponen kunci dalam rheumatoid arthritis.
TNF blocker membantu mengurangi rasa sakit dan kerusakan sendi dengan memblokir sebuah protein inflamasi disebut tumor necrosis factor (TNF). Ada beberapa bukti bahwa TNF blocker dapat menghentikan perkembangan rheumatoid arthritis. Penelitian terbaru telah menunjukkan manfaat ketika mereka menggabungkan dengan methotrexate. TNF blocker mencakup Enbrel, Humira, Remicade, Cimzia, dan Simponi.
Penanganan dan Obat Rematoid Artritis
Artritis Reumatoid (AR) merupakan suatu penyakit inflamasi sistemik kronik yang walaupun manifestasi utamanya adalah poliartritis yang progesif, akan tetapi penyakit ini juga melibatkan seluruh organ tubuh. Terlibatnya sendi pada pasien artritis reumatoid terjadi setelah penyakit ini berkembang lebih lanjut sesuai dengan sifat progesifitasnya. Pada umumnya selain gejala artikular, AR dapat pula menunjukkan gejala konstitusional berupa kelemahan umum, cepat lelah atau gangguan organ non artikular lainnya.
Artritis Reumatoid ditandai dengan adanya peradangan dari lapisan selaput sendi (sinovium) yang mana menyebabkan sakit, kekakuan, hangat, bengkak dan merah. Peradangan sinovium dapat menyerang dan merusak tulang dan kartilago. Sel penyebab radang melepaskan enzim yang dapat mencerna tulang dan kartilago. Sehingga dapat terjadi kehilangan bentuk dan kelurusan pada sendi, yang menghasilkan rasa sakit dan pengurangan kemampuan bergerak.
Artritis adalah inflamasi dengan nyeri, panas, pembengkakan, kekakuan dan kemerahan pada sendi. Akibat artritis, timbul inflamasi umum yang dikenal sebagai artritis reumatoid yang merupakan penyakit autoimun.
Manifestasi tersering penyakit ini adalah terserangnya sendi yang umumnya menetap dan progresif. Mula-mula yang terserang adalah sendi kecil tangan dan kaki. Seringkali keadaan ini mengakibatkan deformitas sendi dan gangguan fungsi disertai rasa nyeri.
Setelah diagnosis AR dapat ditegakkan, pendekatan pertama yang harus dilakukan adalah segera berusaha untuk membina hubungan yang baik antara pasien dengan keluarganya dengan dokter atau tim pengobatan yang merawatnya. Tanpa hubungan yang baik ini agaknya akan sukar untuk dapat memelihara ketaatan pasien untuk tetap berobat dalam suatu jangka waktu yang cukup lama.
Pendidikan pada pasien mengenai penyakitnya dan penatalaksanaan yang akan dilakukan sehingga terjalin hubungan baik dan terjamin ketaatan pasien untuk tetap berobat dalam jangka waktu yang lama.
OAINS diberikan sejak dini untuk mengatasi nyeri sendi akibat inflamasi yang sering dijumpai. OAINS yang dapat diberikan:
Aspirin Pasien dibawah 50 tahun dapat mulai dengan dosis 3-4 x 1 g/hari, kemudian dinaikkan 0,3-0,6 g per minggu sampai terjadi perbaikan atau gejala toksik. Dosis terapi 20-30 mg/dl.
Ibuprofen, naproksen, piroksikam, diklofenak, dan sebagainya.
DMARD digunakan untuk melindungi rawan sendi dan tulang dari proses destruksi akibat artritis reumatoid. Mula khasiatnya baru terlihat setelah 3-12 bulan kemudian. Setelah 2-5 tahun, maka efektivitasnya dalam menekan proses reumatoid akan berkurang. Keputusan penggunaannya bergantung pada pertimbangan risiko manfaat oleh dokter. Umumnya segera diberikan setelah diagnosis artritis reumatoid ditegakkan, atau bila respon OAINS tidak baik, meski masih dalam status tersangka.
Jenis-jenis yang digunakan adalah:
Klorokuin, paling banyak digunakan karena harganya terjangkau, namun efektivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Dosis anjuran klorokuin fosfat 250 mg/hari hidrosiklorokuin 400 mg/hari. Efek samping bergantung pada dosis harian, berupa penurunan ketajaman penglihatan, dermatitis makulopapular, nausea, diare, dan anemia hemolitik.
Sulfasalazin dalam bentuk tablet bersalut enteric digunakan dalam dosis 1 x 500 mg/hari, ditingkatkan 500 mg per minggu, sampai mencapai dosis 4 x 500 mg. Setelah remisi tercapai, dosis dapat diturunkan hingga 1 g/hari untuk dipakai dalam jangka panjang sampai tercapai remisi sempurna. Jika dalam waktu 3 bulan tidak terlihat khasiatnya, obat ini dihentikan dan diganti dengan yang lain, atau dikombinasi. Efek sampingnya nausea, muntah, dan dyspepsia.
D-penisilamin, kurang disukai karena bekerja sangat lambat. Digunakan dalam dosis 250-300 mg/hari, kemudian dosis ditingkatkan setiap 2-4 minggu sebesar 250-300 mg/hari untuk mencapai dosis total 4x 250-300 mg/hari. Efek samping antara lain ruam kulit urtikaria atau mobiliformis, stomatitis, dan pemfigus.
Garam emas adalah gold standard bagi DMARD. Khasiatnya tidak diragukan lagi meski sering timbul efek samping. Auro sodium tiomalat (AST) diberikan intramuskular, dimulai dengan dosis percobaan pertama sebesar 10 mg, seminggu kemudian disusul dosis kedua sebesar 20 mg. Seminggu kemudian diberikan dosis penuh 50 mg/minggu selama 20 minggu. Dapat dilanjutkan dengan dosis tambahan sebesar 50 mg tiap 2 minggu sampai 3 bulan. Jika diperlukan, dapat diberikan dosis 50 mg setiap 3 minggu sampai keadaan remisi tercapai. Efek samping berupa pruritis, stomatitis, proteinuria, trombositopenia, dan aplasia sumsum tulang. Jenis yang lain adalah auranofin yang diberikan dalam dosis 2 x 3 mg. Efek samping lebih jarang dijumpai, pada awal sering ditemukan diare yang dapat diatasi dengan penurunan dosis.
Obat imunosupresif atau imunoregulator. Metotreksat sangat mudah digunakan dan waktu mula kerjanya relatif pendek dibandingkan dengan yang lain. Dosis dimulai 5-7,5 mg setiap minggu. Bila dalam 4 bulan tidak menunjukkan perbaikan, dosis harus ditingkatkan. Dosis jarang melebihi 20 mg/minggu. Efek samping jarang ditemukan. Penggunaan siklosporin untuk artritis reumatoid masih dalam penelitian.
Kortikosteroid hanya dipakai untuk pengobatan artritis reumatoid dengan komplikasi berat dan mengancam jiwa, seperti vaskulitis, karena obat ini memiliki efek samping yang sangat berat. Dalam
dosis rendah (seperti prednison 5-7,5 mg satu kali sehari) sangat bermanfaat sebagai bridging therapy dalam mengatasi sinovitis sebelum DMARD mulai bekerja, yang kemudian dihentikan secara bertahap. Dapat diberikan suntikan kortikosteroid intraartikular jika terdapat peradangan yang berat. Sebelumnya, infeksi harus disingkirkan terlebih dahulu.
Riwayat Penyakit alamiah
Riwayat penyakit alamiah AR sangat bervariasi. Pada umumnya 25% pasien akan mengalami manifestasi penyakit yang bersifat monosiklik (hanya mengalami satu episode AR dan selanjutnya akan mengalami remisi sempurna). Pada pihak lain sebagian besar pasien akan menderita penyakit ini sepanjang hidupnya dengan hanya diselingi oleh beberapa masa remisi yang singkat (jenis polisiklik). Sebagian kecil lainnya akan menderita AR yang progresif yang disertai dengan penurunan kapasitas fungsional yang menetap pada setiap eksaserbasi.
Penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa dengan pengobatan yang digunakan saat ini, sebagian besar pasien AR umumnya akan dapat mencapai remisi dan dapat mempertahankannya dengan baik pada 5 atau 10 tahun pertamanya. Setelah kurun waktu tersebut, umumnya pasien akan mulai merasakan bahwa remisi mulai sukar dipertahankan dengan pengobatan yang biasa digunakan selama itu. Hal ini mungkin disebabkan karena pasien sukar mempertahankan ketaatannya untuk terus berobat dalam jangka waktu yang lama, timbulnya efek samping jangka panjang kortikosteroid. Khasiat DMARD yang menurun dengan berjalannya waktu atau karena timbulnya penyakit lain yang merupakan komplikasi AR atau pengobatannya. Hal ini masih merupakan persoalan yang banyak diteliti saat ini, karena saat ini belum berhasil dijumpai obat yang bersifat sebagai disease controlling antirheumatic therapy (DC-ART).
Rehabilitasi pasien AR
Rehabilitasi merupakan tindakan untuk mengembalikan tingkat kemampuan pasien AR dengan cara:
Mengurangi rasa nyeri
Mencegah terjadinya kekakuan dan keterbatasan gerak sendi
Mencegah terjadinya atrofi dan kelemahan otot
Mencegah terjadinya deformitas
Meningkatkan rasa nyaman dan kepercayaan diri
Mempertahankan kemandirian sehingga tidak bergantung kepada orang lain.
Rehabilitasi dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain dengan mengistirahatkan sendi yang terlibat, latihan serta dengan menggunakan modalitas terapi fisis seperti pemanasan, pendinginan, peningkatan ambang rasa nyeri dengan arus listrik. Manfaat terapi fisis dalam pengobatan AR telah ternyata terbukti dan saat ini merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam penatalaksanaan AR.
Pembedahan
Jika berbagai cara pengobatan telah dilakukan dan tidak berhasil serta terdapat alasan yang cukup kuat, dapat dilakukan pengobatan pembedahan. Jenis pengobatan ini pada pasien AR umumnya
bersifat ortopedik, misalnya sinovektoni, artrodesis, total hip replacement, memperbaiki deviasi ulnar, dan sebagainya.
ASAM URAT (GOUT)
EMIRZA NUR WICAKSONO, S.KED JANUARI 10, 2013[163] COMMENTS
DEFINISI
Gout adalah suatu penyakit yang ditandai dengan serangan mendadak dan berulang dari artritis yang terasa sangat nyeri karena adanya endapan kristal monosodium urat, yang terkumpul di dalam sendi sebagai akibat dari tingginya kadar asam urat di dalam darah (hiperurisemia).
Peradangan sendi bersifat menahun dan setelah terjadinya serangan berulang, sendi bisa menjadi bengkok.
Hampir 20% penderita gout memiliki batu ginjal.
PENYEBAB
Dalam keadaan normal, beberapa asam urat (yang merupakan hasil pemecahan sel) ditemukan dalam darah karena tubuh terus menerus memecahkan sel dan membentuk sel yang baru dan karena makanan yang dikonsumsi mengandung cikal bakal asam urat.
Kadar asam urat menjadi sangat tinggi jika ginjal tidak dapat membuangnya melalui air kemih.
Tubuh juga bisa menghasilkan sejumlah besar asam urat karena adanya kelainan enzim yang sifatnya diturunkan atau karena suatu penyakit (misalnya kanker darah), dimana sel-sel berlipatganda dan dihancurkan dalam waktu yang singkat.
Beberapa jenis penyakit ginjal dan obat-obatan tertentu mempengaruhi kemampuan ginjal untuk membuang asam urat.
GEJALA
Serangan gout (artritis gout akut) terjadi secara mendadak.
Timbulnya serangan bisa dipicu oleh:
– luka ringan
– pembedahan
– pemakaian sejumlah besar alkohol atau makanan yang kaya akan protein
– kelelahan
– stres emosional
– penyakit.
Nyeri yang hebat dirasakan oleh penderita pada satu atau beberapa sendi, seringkali terjadi pada malam hari; nyeri semakin memburuk dan tak tertahankan.
Sendi membengkak dan kulit diatasnya tampak merah atau keunguan, kencang dan licin, serta teraba hangat. Menyentuh kulit diatas sendi yang terkena bisa menimbulkan nyeri yang luar biasa.
Penyakit ini paling sering mengenai sendi di pangkal ibu jari kaki dan menyebabkan suatu keadaan yang disebut podagra; tetapi penyakit ini juga sering menyerang pergelangan kaki, lutut, pergelangan tangan dan sikut.
Kristal dapat terbentuk di sendi-sendi perifer tersebut karena persendian tersebut lebih dingin daripada persendian di pusat tubuh dan urat cenderung membeku pada suhu dingin.
Kristal juga terbentuk di telinga dan jaringan yang relatif dingin lainnya.
Sebaliknya, gout jarang terjadi pada tulang belakang, tulang panggul ataupun bahu.
Gejala lainnya dari artritis gout akut adalah demam, menggigil, perasaan tidak enak badan dan denyut jantung yang cepat.
Gout cenderung lebih berat pada penderita yang berusia dibawah 30 tahun.
Biasanya pada pria gout timbul pada usia pertengahan, sedangkan pada wanita muncul pada saat pasca menopause.
Serangan pertama biasanya hanya mengenai satu sendi dan berlangsung selama beberapa hari.
Gejalanya menghilang secara bertahap, dimana sendi kembali berfungsi dan tidak timbul gejala sampai terjadi serangan berikutnya.
Tetapi jika penyakit ini semakin memburuk, maka serangan yang tidak diobati akan berlangsung lebih lama, lebih sering terjadi dan mengenai beberapa sendi. Sendi yang terkena bisa mengalami kerusakan yang permanen.
Bisa terjadi gout menahun dan berat, yang menyebabkan terjadinya kelainan bentuk sendi.
Pengendapan kristal urat di dalam sendi dan tendon terus berlanjut dan menyebabkan kerusakan yang akan membatasi pergerakan sendi.
Benjolan keras dari kristal urat (tofi) diendapkan dibawah kulit di sekitar sendi. Tofi juga bisa terbentuk di dalam ginjal dan organ lainnya, dibawah kulit telinga atau di sekitar sikut.
Jika tidak diobati, tofi pada tangan dan kaki bisa pecah dan mengeluarkan massa kristal yang menyerupai kapur.
PATOFISIOLOGI
Gambaran klasik artritis gout yang berat dan akut ada kaitan langsung dengan hiperurisemia (asam urat serum tinggi). Gout mungkin primer atau sekunder. Gout primer merupakan akibat langsung pernbentukan asam urat tubuh yang berlebihan atau akibat penurunan ekskresi asam urat. Gout sekunder disebabkan an karena pembentukan asam urat yang berlebihan atau ekskresi asam urat yang berkurang akibat proses penyakit lain atau pemakaian obat tertentu.
Endapan urat dalam sendi atau traktus urinarius dialkibatkan: karena, asam urat yang rendah daya larutnya dan akibat garam-garainnya. Asam. Urat yang berlebihan dan garam-garam tersebut keluar dari serum dan urin masing-masing mengendap dalam sendi dan traktus urinarius.
Patofisiologi gout arthritis
Peningkatan kadar asam urat serum dapat disebabkan oleh pembentukan berlebihan atau penurunan eksresi asam urat, ataupun keduanya. Asam urat adalah produk akhir metabolisme purin. Secara normal, metabolisme purin menjadi asam urat dapat diterangkan sebagai berikut:
Sintesis purin melibatkan dua jalur, yaitu jalur de novo dan jalur penghematan (salvage pathway).
1. Jalur de novo melibatkan sintesis purin dan kemudian asam urat melalui prekursor nonpurin. Substrat awalnya adalah ribosa-5-fosfat, yang diubah melalui serangkaian zat antara menjadi nukleotida purin (asam inosinat, asam guanilat, asam adenilat). Jalur ini dikendalikan oleh serangkaian mekanisme yang kompleks, dan terdapat beberapa enzim yang mempercepat reaksi yaitu: 5-fosforibosilpirofosfat (PRPP) sintetase dan amidofosforibosiltransferase (amido-PRT). Terdapat suatu mekanisme inhibisi umpan balik oleh nukleotida purin yang terbentuk, yang fungsinya untuk mencegah pembentukan yang berlebihan.
2. Jalur penghematan adalah jalur pembentukan nukleotida purin melalui basa purin bebasnya, pemecahan asam nukleat, atau asupan makanan. Jalur ini tidak melalui zat-zat perantara seperti pada jalur de novo. Basa purin bebas (adenin, guanin, hipoxantin) berkondensasi dengan PRPP untuk membentuk prekursor nukleotida purin dari asam urat. Reaksi ini dikatalisis oleh dua enzim: hipoxantin guanin fosforibosiltransferase (HGPRT) dan adenin fosforibosiltransferase (APRT).
Asam urat yang terbentuk dari hasil metabolisme purin akan difiltrasi secara bebas oleh glomerulus dan diresorpsi di tubulus proksimal ginjal. Sebagian kecil asam urat yang diresorpsi kemudian diekskresikan di nefron distal dan dikeluarkan melalui urin.
Pada penyakit gout-arthritis, terdapat gangguan kesetimbangan metabolisme (pembentukan dan ekskresi) dari asam urat tersebut, meliputi:
1. Penurunan ekskresi asam urat secara idiopatik
2. Penurunan eksreksi asam urat sekunder, misalnya karena gagal ginja
3. Peningkatan produksi asam urat, misalnya disebabkan oleh tumor (yang meningkatkan cellular turnover) atau peningkatan sintesis purin (karena defek enzim-enzim atau mekanisme umpan balik inhibisi yang berperan)
4. Peningkatan asupan makanan yang mengandung purin
Peningkatan produksi atau hambatan ekskresi akan meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Asam urat ini merupakan suatu zat yang kelarutannya sangat rendah sehingga cenderung membentuk kristal. Penimbunan asam urat paling banyak terdapat di sendi dalam bentuk kristal mononatrium urat. Mekanismenya hingga saat ini masih belum diketahui.
Adanya kristal mononatrium urat ini akan menyebabkan inflamasi melalui beberapa cara:
1. Kristal bersifat mengaktifkan sistem komplemen terutama C3a dan C5a. Komplemen ini bersifat kemotaktik dan akan merekrut neutrofil ke jaringan (sendi dan membran sinovium). Fagositosis terhadap kristal memicu pengeluaran radikal bebas toksik dan leukotrien, terutama leukotrien B. Kematian neutrofil menyebabkan keluarnya enzim lisosom yang destruktif.
2. Makrofag yang juga terekrut pada pengendapan kristal urat dalam sendi akan melakukan aktivitas fagositosis, dan juga mengeluarkan berbagai mediator proinflamasi seperti IL-1, IL-6, IL-8, dan TNF. Mediator-mediator ini akan memperkuat respons peradangan, di samping itu mengaktifkan sel sinovium dan sel tulang rawan untuk menghasilkan protease. Protease ini akan menyebabkan cedera jaringan.
Penimbunan kristal urat dan serangan yang berulang akan menyebabkan terbentuknya endapan seperti kapur putih yang disebut tofi/tofus (tophus) di tulang rawan dan kapsul sendi. Di tempat tersebut endapan akan memicu reaksi peradangan granulomatosa, yang ditandai dengan massa urat amorf (kristal) dikelilingi oleh makrofag, limfosit, fibroblas, dan sel raksasa benda asing. Peradangan kronis yang persisten dapat menyebabkan fibrosis sinovium, erosi tulang rawan, dan dapat diikuti oleh fusi sendi (ankilosis). Tofus dapat terbentuk di tempat lain (misalnya tendon, bursa, jaringan lunak). Pengendapan kristal asam urat dalam tubulus ginjal dapat mengakibatkan penyumbatan dan nefropati gout.
DIAGNOSA
Diagnosis seringkali ditegakkan bedasarkan gejalanya yang khas dan hasil pemeriksan terhadap sendi.
Ditemukannya kadar asam urat yang tinggi di dalam darah akan memperkuat diagnosis.
Tetapi pada suatu serangan akut, kadar asam urat seringkali normal.
Pada pemeriksaan terhadap contoh cairan sendi dibawah mikroskop khusus akan tampak kristal urat yang berbentuk seperti jarum.
Kristal asam urat
PENGOBATAN
Langkah pertama untuk mengurangi nyeri adalah mengendalikan peradangan.
Pengobatan tradisional untuk gout adalah kolkisin.
Biasanya nyeri sendi mulai berkurang dalam waktu 12-24 jam setelah pemberian kolkisin dan akan menghilang dalam waktu 48-72 jam.
Kolkisin diberikan dalam bentuk tablet, tetapi jika menyebabkan gangguan pencernaan, bisa diberikan secara intravena.
Obat ini seringkali menyebabkan diare dan bisa menyebabkan efek samping yang lebih serius (termasuk kerusakan sumsum tulang).
Saat ini obat anti peradangan non-steroid (misalnya ibuprofen dan indometasin) lebih banyak digunakan daripada kolkisin dan sangat efektif mengurangi nyeri dan pembengkakan sendi.
Kadang diberikan kortikosteroid (misalnya prednison).
Jika penyakit ini mengenai 1-2 sendi, suatu larutan kristal kortikosteroid bisa disuntikkan langsung ke dalam sendi. Pengobatan ini sangat efektif untuk mengakhiri peradangan yang disebabkan oleh kristal urat.
Kadang obat pereda nyeri ditambahkan untuk mengendalikan nyeri (misalnya kodein dan meperidin).
Untuk mengurangi nyeri, sendi yang meradang sebaiknya diistirahatkan dahulu.
Obat-obat seperti probenesid atau sulfinpirazon berfungsi menurunkan kadar asam urat dalam darah dengan jalan meningkatkan pembuangan asam urat ke dalam air kemih.
Aspirin menghambat efek probenesid dan sulfinpirazon, sehingga sebaiknya tidak digunakan pada saat yang bersamaan. Jika diperlukan obat pereda nyeri, lebih baik diberikan asetaminofen atau obat anti peradangan non-steroid (misalnya ibuprofen).
Jika pembuangan asam urat meningkat, dianjurkan untuk minum banyak air (minimal 2 liter/hari) untuk membantu mengurangi resiko kerusakan sendi dan ginjal.
Allopurinol merupakan obat yang menghambat pembentukan asam urat di dalam tubuh.
Obat ini terutama diberikan kepada penderita yang memiliki kadar asam urat yang tinggi dan batu ginjal atau mengalami kerusakan ginjal.
Allopurinol bisa menyebabkan gangguan pencernaan, timbulnya ruam di kulit, berkurangnya jumlah sel darah putih dan kerusakan hati.
Sebagian besar tofi di telinga, tangan atau kaki akan mengecil secara perlahan jika kadar asam urat dalam darah berkurang; tetapi tofi yang sangat besar mungkin harus diangkat melalui pembedahan.
Orang yang memiliki kadar asam urat yang tinggi tetapi tidak menunjukkan gejala-gejala gout, kadang mendapatkan obat untuk menurunkan kadar asam uratnya.
Tetapi karena adanya efek samping dari obat tersebut, maka pemakaiannya ditunda kecuali jika kadar asam urat di dalam air kemihnya sangat tinggi.
Pemberian allopurinol bisa mencegah pembentukan batu ginjal.
PENCEGAHAN
Penyakitnya sendiri tidak bisa dicegah, tetapi beberapa faktor pencetusnya bisa dihindari (misalnya cedera, alkohol, makanan kaya protein).
Untuk mencegah kekambuhan, dianjurkan untuk minum banyak air, menghindari minuman beralkohol dan mengurangi makanan yang kaya akan protein.
Banyak penderita yang memiliki kelebihan berat badan, jika berat badan mereka dikurangi, maka kadar asam urat dalam darah seringkali kembali ke normal atau mendekati normal.
Beberapa penderita (terutama yang mengalami serangan berulang yang hebat) mulai menjalani pengobatan jangka panjang pada saat gejala telah menghilang dan pengobatan dilanjutkan sampai diantara serangan.
Kolkisin dosis rendah diminum setiap hari dan bisa mencegah serangan atau paling tidak mengurangi frekuensi serangan.
Mengkonsumsi obat anti peradangan non-steroid secara rutin juga bisa mencegah terjadinya serangan.
Kadang kolkisin dan obat anti peradangan non-steroid diberikan dalam waktu yang bersamaan. Tetapi kombinasi kedua obat ini tidak mencegah maupun memperbaiki kerusakan sendi karena pengendapan kristal dan memiliki resiko bagi penderita yang memiliki penyakit ginjal atau hati.
Referensi:
Kumar V, Cotran R, Robbins S. Buku Ajar Patologi. 7th ed. Jakarta: EGC; 2000. p. 864-8
www.kalbe.co.id/…/09DiagnosisdanPenatalaksanaanArtritisPirai129…/09DiagnosisdanPenatalaksanaanArtritisPirai129.html
Artritis Infeksiosa : Infeksi Pada Cairan & Jaringan sendi
Artritis Infeksiosa adalah infeksi pada cairan (cairan sinovial, cairan rongga sendi) dan jaringan dari suatu sendi.
PENYEBAB
Organisme penyebab infeksi (terutama bakteri), biasanya mencapai sendi melalui aliran darah, tetapi suatu sendi bisa terinfeksi secara langsung melalui pembedahan, penyuntikan atau suatu cedera.
Bakteri apa yang paling sering menyebabkan infeksi tergantung kepada usia penderita.
Bayi dan anak kecil sering terinfeksi oleh stafilokokus, Hemophilus influenza dan bakteri basilus gram negatif.
Dewasa dan anak yang lebih tua sering terinfeksi oleh gonokokus (bakteri penyebab gonore), stafilokokus dan streptokokus.
Virus (misalnya HIV, parvovirus dan virus penyebab rubella, gondongan dan hepatitis B) bisa menginfeksi sendi pada berbagai usia.
Infeksi sendi menahun sering disebabkan oleh tuberkulosis atau infeksi jamur.
GEJALA
Manifestasi klinis
• Onset akut artritis monoartikular (>80%) dengan rasa nyeri, pembengkakan, dan hangat pada sendi
• Lokasi : lutut (paling sering), panggul, pergelangan tangan, bahu, pergelangan kaki, pada IVDA, cenderung untuk melibatkan daerah lain seperti sendi sakroiliaka, simfisis pubis, sternoklavikular dan sendi manubrium sterni
• Pada lutut, bursitis pra-patela septik harus dibedakan dengan efusi lutut intra-artikular septik
jangkauan gerak nyeri ekstrem bila fleksi dan Infeksi intra-artikular
pembengkakan berbentuk kubah diatas patela, tanpa efusi intra-artikularBursitis pra-patela
• Gejala konstitusional : demam, menggigil, berkeringat, malaise, mialgia, nyeri
• Infeksi dapat dilacak dari tempat awal untuk membentuk fistula, abses, osteomielitis.
Pada anak yang lebih tua dan orang dewasa yang mengalami infeksi bakteri atau virus, gejala biasanya dimulai sangat tiba-tiba.
Sendi tampak merah dan teraba hangat, pergerakan dan perabaan akan terasa sangat nyeri.
Cairan yang terkumpul dalam sendi yang terinfeksi, menyebabkan sendi membengkak dan kaku.
Penderita juga bisa mengalami demam dan menggigigil.
Sendi-sendi yang sering terkena adalah lutut, bahu, pergelangan tangan, panggul, jari dan sikut.
Jamur atau mikobakteria (bakteri penyebab tuberkulosis dan infeksi sejenis) biasanya menyebabkan gejala yang tidak terlalu berat.
Sebagian besar infeksi bakteri, jamur dan mikobakteria, hanya mengenai satu sendi atau kadang-kadang mengenai beberapa sendi.
Contohnya, bakteri yang menyebabkan penyakit Lyme paling sering menyerang sendi lutut, bakteri gonokokus dan virus bisa menyerang beberapa sendi pada saat yang sama.
DIAGNOSA
• Leukositosis dengan pergeseran ke kiri
• Artrosentesis sebaiknya dilakukan secepatnya bila dicurigai
Hati-hati untuk tudak melakukan punksi melalui daerah yang terinfeksi karena dapat memasukkan infeksi ke dalam rongga sendi
Cairan sinovial: hitung sel Leukosit biasanya >50.000, > tidak menyingkirkan artritis septik)90% PMN (catatan : kristal
50% infeksi batang gram negatif kultur 75% infeksi stafilokokus, pada Pewarnaan gram >90% kasus
pada• Kultur darah : >50% kasus
2 minggu setelah infeksi, pada saat itu dapat melihat erosi tulang, penyempitan rongga sendi, osteomielitis, periositisis• Radiografi konvensional seperti biasanya jarang membantu sampai
• CT dan MRI berguna terutama terhadap infeksi panggul yang dicurigai atau abses epidural.
Anak-anak biasanya mengalami demam dan nyeri dan cenderung rewel.
Biasanya anak tidak mau menggerakkan sendi yang terkena karena pergerakan dan perabaan menyebabkan nyeri.
PENGOBATAN
Antibiotik diberikan segera setelah dicurigai suatu infeksi, meskipun belum diperoleh hasil laboratorium yang mengidentifikasi kuman penyebabnya.
Pada awalnya diberikan antibiotik yang bisa membunuh hampir semua bakteri. Jika diperlukan, antibiotik lainnya diberikan kemudian.
Pada awalnya antibiotik diberikan secara intravena (melalui pembuluh darah), agar tercapai jumlah obat yang cukup, yang sampai ke sendi yang terinfeksi.
Meskipun jarang, antibiotik bisa disuntikkan langsung ke dalam sendi yang terinfeksi.
Jika antibiotiknya tepat, biasanya perbaikan akan terjadi dalam waktu 48 jam.
Untuk mencegah pengumpulan nanah, yang bisa merusak sendi, nanah dikeluarkan melalui bantuan sebuah jarum. Jika sendi tidak dapat dijangkau dengan jarum, kadang-kadang dimasukkan suatu selang untuk mengeluarkan nanahnya.
Jika pengaliran nanah dengan jarum atau selang tidak berhasil, dilakukan artroskopi atau pembedahan.
Pada awalnya penggunaan bidai bisa membantu meringankan nyeri, tetapi bisa menyebabkan kekakuan dan kehilangan fungsi yang menetap.
Infeksi yang disebabkan jamur diobati dengan obat anti jamur.
Infeksi yang disebabkan tuberkulosis diobati dengan kombinasi antibiotik.
Infeksi virus biasanya akan membaik dengan sendirinya. Yang diperlukan hanya pengobatan untuk nyeri dan demam.
Jika infeksi mengenai sendi buatan, pemberian antibiotik saja biasanya tidak cukup. Setelah pemberian antibiotik selama beberapa hari, diperlukan pembedahan untuk mengganti sendi terinfeksi dengan sendi buatan yang baru.
OSTEOARTITIS
EMIRZA NUR WICAKSONO, S.KED JANUARI 10, 2013[93] COMMENTS
Definisi Osteoarthritis
Osteoarthritis atau juga disebut dengan penyakit sendi degeneratif yaitu suatu kelainan pada kartilago (tulang rawan sendi) yang ditandai perubahan klinis, histologi dan radiologis (Kuntono,2005). Osteoarthritis secara patologis dicirikan dengan penurunan secara progresif dan akhirnya hilangnya kartilago sendi dengan perubahan reaktif pada batas-batas sendi dan pada tulang subkondral (Garrison, 1996).
Osteoarthritis merupakan bentuk radang sendi yang serius, salah satu jenis rematik atau rasa sakit di tulang. Osteoartritis bermula dari kelainan pada tulang rawan sendi, seperti kolagen dan proteoglikan. Akibat dari kelainan pada sel-sel tersebut, tulang rawan akhirnya menipis dan membentuk retakan-retakan pada permukaan sendi. Rongga kecil akan terbentuk di dalam sumsum dari tulang di bawah tulang rawan tersebut, sehingga tulang yang bersangkutan menjadi rapuh. Tubuh kita akan berusaha memperbaiki kerusakan tersebut, tetapi perbaikan yang dilakukan oleh tubuh tidak memadai, mengakibatkan timbulnya benjolan pada pinggiran sendi atau osteofit yang terasa nyeri. Pada akhirnya, permukaan tulang rawan akan berubah menjadi kasar dan berlubang-lubang sehingga sendi tidak lagi bisa bergerak secara halus. Semua komponen yang ada pada sendi mengalami kegagalan dan terjadi kekakuan sendi.
Sendi yang biasanya menjadi sasaran penyakit ini adalah sendi yang sering digunakan sebagai penopang berat badan seperti sendi lutut, sendi tulang belakang, dan sendi panggul. Selain itu juga pada sendi tangan/kaki. Jika tidak diobati, sakit akan bertambah sampai tidak bisa berjalan. Selain itu, tulang bisa mengalami perubahan bentuk atau deformity. Jika dibiarkan, osteoarthritis dapat menyebabkan cacat permanen pada tulang. Bentuk tulang bisa berubah menjadi bengkok baik ke dalam maupun keluar. Untuk itu penyakit tersebut perlu diwaspadai karena mempunyai dampak jangka panjang. Dampak tersebut baru dirasakan penderita 10 tahun kemudian. Untuk mengetahui gejalanya, harus lewat pemeriksaan laboratorium dan rontgen. Bila ada laju endap darah dan kolesterol meningkat maka dapat diidentifikasi sebagai gejala osteoarthitis sehingga perlu segera diobati.
Osteoarthritis adalah suatu penyakit degeneratif. Ini merupakan aging process yang biasanya terjadi pada mereka yang berada di kelompok usia 50 tahun ke atas. Namun penyakit ini juga bisa menyerang segala usia, termasuk 300 ribu anak di Amerika Serikat menderita penyakit ini.
Ada dua macam Osteoarthritis :
1. Osteoarthritis Primer : dialami setelah usia 45 tahun, sebagai akibat dari proses penuaan alami, tidak diketahui penyebab pastinya, menyerang secara perlahan tapi progresif, dan dapat mengenai lebih dari satu persendian. Biasanya menyerang sendi yang menanggung berat badan seperti lutut dan panggul, bisa juga menyerang punggung, leher, danjari-jari.
2. Osteoarthritis Sekunder: dialami sebelum usia 45 tahun, biasanya disebabkan oleh trauma (instabilitas) yang menyebabkan luka pada sendi (misalnya patah tulang atau permukaan sendi tidak sejajar), akibat sendi yang longgar, dan pembedahan pada sendi. Penyebab lainnya adalah faktor genetik dan penyakit metabolik.
Etiologi/Penyebab Osteoarthritis
Etiologi/ penyebab dari penyakit degeneratif pada sendi ini belum diketahui dengan pasti tetapi banyak faktor yang mungkin dapat menyebabkan timbulnya penyakit ini, antara lain:
a. Usia, merupakan faktor resiko tertinggi untuk osteoarthritis. Peningkatan prevalensi osteoarthritis dijumpai seiring dengan peningkatan usia. Pada survey radiografik terhadap perempuan berusia kurang dari 45 tahun, hanya 2 % menderita osteoarthritis; namun, antara usia 45 tahun dan 65 tahun prevalensinya 30 %, sedangkan untuk yang berusia lebih dari 65 tahun angkanya 68 %. Pada laki-laki, angkanya serupa tetapi sedikit lebih rendah pada kelompok usia tua (Cash, 2000).
b. Obesitas, pada keadaan normal berat badan akan melalui medial sendi lutut dan akan diimbangi otot paha bagian lateral sehingga resultan gaya akan melewati bagian tengah/ sentral sendi lutut. Sedangkan pada orang yang mengalami obesitas, resultan gaya akan bergeser ke medial sehingga beban gaya yang diterima sendi lutut tidak seimbang (Parjoto, 2000). Pada orang yang memiliki indeks massa tubuh berada di quintile tertinggi pada pemeriksaan dasar, resiko relatif mengalami OA lutut dalam 36 tahun mendatang adalah 1,5 untuk laki-laki dan 2,1 untuk perempuan. Untuk OA lutut yang parah, resiko relatif meningkat menjadi 1,9 untuk laki-laki dan 3,2 untuk perempuan, yang mengisyaratkan bahwa kegemukan berperan lebih besar dalam etiologi kasus OA lutut yang parah (Brandt, 2000).
c. Pekerjaan aktivitas fisik yang banyak membebani sendi lutut akan mempunyai resiko terserang OA lebih besar (Parjoto, 2000). Osteoarthritis lebih sering terjadi pada sendi yang digerakkan secara berulang daripada sendi lain di tangan. Laki-laki yang pekerjaannya memerlukan penekukan lutut dan
paling sedikit tuntutan fisik tingkat sedang lebih sering memiliki tanda radiografik OA lutut, dan gambaran radiografiknya cenderung lebih berat daripada laki-laki yang pekerjaannya tidak memerlukan keduanya (Kalim, 1996).
d. Jenis kelamin, wanita lebih banyak daripada pria (Parjoto, 2000). Wanita lebih sering terkena OA lutut dan OA banyak sendi, dan laki-laki lebih sering terkena OA paha, pergelangan tangan dan leher. Secara keseluruhan, di bawah 45 tahun frekuensi OA kurang lebih sama pada laki-laki dan wanita, tetapi di atas 50 tahun (setelah menopause) frekuensi OA lebih banyak pada wanita daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya peran hormonal pada patogenesis OA (Kalim, 1996).
e. Faktor hormonal/ metabolisme, diabetes melitus berperan sebagai predisposisi timbulnya OA. Meskipun belum ada bukti yang jelas bahwa faktor hormonal terlibat sebagai penyebab OA. Bagaimanapun, perubahan degeneratif di lutut dan spine pada umumnya terjadi pada pasien dengan penyakit diabetes. Pasien yang mengalami hypothyroid biasanya/ sering mengeluh nyeri pada otot, tapi angka kejadian OA tidak meningkat pada kasus ini (Moll, 1987).
f. Suku bangsa, prevalensi dan pola terkenanya sendi pada OA tampaknya terdapat perbedaan di antara masing-masing suku bangsa. Misalnya OA paha lebih jarang diantara orang-orang kulit hitam dan Asia daripada Kaukasia. OA lebih sering dijumpai pada orang-orang Amerika asli (Indian) daripada orang-orang kulit putih. Hal ini mungkin berkaitan dengan perbedaan cara hidup maupun perbedaan pada frekuensi kelainan kongenital dan pertumbuhan (Kalim, 1996).
g. Riwayat imobilisasi.
h. Riwayat trauma atau radang di persendian sebelumnya
i. Adanya stress pada sendi yang berkepanjangan, misalnya pada olahragawan.
j. Adanya kristal pada cairan sendi atau tulang rawan
k. Densitas tulang yang tinggi
l. Neurophaty perifer
Patofisiologi Kartilago hyaline (jaringan rawan sendi)
Adalah jaringan elastis yang 95 persen terdiri dari air dan matrik ekstra selular, 5 persen sel kondrosit. Fungsinya sebagai penyangga atau shock breaker, juga sebagai pelumas, sehingga tidak menimbulkan nyeri pada saat pergerakan sendi.
Apabila kerusakan jaringan rawan sendi lebih cepat dari kemampuannya untuk memperbaiki diri, maka terjadi penipisan dan kehilangan pelumas sehingga kedua tulang akan bersentuhan. Inilah yang menyebabkan rasa nyeri pada sendi lutut.
Setelah terjadi kerusakan tulang rawan, sendi dan tulang ikut berubah. Pada permukaan sendi yang sudah aus terjadilah pengapuran. Yaitu tumbuhnya tulang baru yang merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk menjadikan sendi kembali stabil, tapi hal ini justru membuat sendi kaku.
Sendi yang sering menjadi sasaran penyakit ini adalah sendi yang sering digunakan sebagai penopang tubuh seperti lutut, tulang belakang, panggul, dan juga pada sendi tangan/kaki. Jika tidak diobati sakit akan bertambah dan tidak bisa berjalan. Selain itu, tulang bisa mengalami perubahan bentuk atau
deformity bersifat permanen. Bengkok pada kaki bisa ke dalam maupun keluar. Dampak kelainan ini muncul perlahan 10 tahun kemudian untuk itu perlu waspada.
Patologi Osteoarthritis
Pada OA terdapat proses degenerasi, reparasi dan inflamasi yang terjadi dalam jaringan ikat, lapisan rawan, sinovium dan tulang subkondral. Pada saat penyakit aktif, salah satu proses dapat dominan atau beberapa proses terjadi bersama dalam tingkat intensitas yang berbeda. OA lutut berhubungan dengan berbagai defisit patofisiologi seperti instabilitas sendi lutut, menurunnya lingkup gerak sendi (LGS) lutut, nyeri lutut sangat kuat berhubungan dengan penurunan kekuatan otot quadriceps yang merupakan stabilisator utama sendi lutut dan sekaligus berfungsi untuk melindungi struktur sendi lutut. Pada penderita usia lanjut kekuatan quadriceps bisa menurun 1/3 nya dibandingkan dengan kekuatan quadriceps pada kelompok usia yang sama yang tidak menderita OA lutut. Penurunan kekuatan terutama disebabkan oleh atrofi otot tipe II B yang bertanggungjawab untuk menghasilkan tenaga secara cepat.
Perubahan – perubahan yang terjadi pada OA adalah sebagai berikut:
a. Degradasi rawan. Perubahan yang mencolok pada OA biasanya dijumpai di daerah tulang rawan sendi yang mendapatkan beban. Pada stadium awal, tulang rawan lebih tebal daripada normal, tetapi seiring dengan perkembangan OA permukaan sendi menipis, tulang rawan melunak, integritas permukaan terputus dan terbentuk celah vertikal (fibrilasi). Dapat terbentuk ulkus kartilago dalam yang meluas ke tulang. Dapat timbul daerah perbaikan fibrokartilaginosa, tetapi mutu jaringan perbaikan lebih rendah daripada kartilago hialin asli, dalam kemampuannya menahan stres mekanik. Semua kartilago secara metabolis aktif, dan kondrosit melakukan replikasi, membentuk kelompok (klon). Namun, kemudian kartilago menjadi hiposeluler (Brandt, 2000). Proses degradasi yang timbul sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara regenerasi (reparasi) dengan degenerasi rawan sendi melalui beberapa tahap yaitu fibrilasi, pelunakan, perpecahan dan pengelupasan lapisan rawan sendi. Proses ini dapat berlangsung cepat atau lambat. Yang cepat dalam waktu 10 – 15 tahun, sedang yang lambat 20 – 30 tahun. Akhirnya permukaan sendi menjadi botak tanpa lapisan rawan sendi (Parjoto, 2000).
b. Osteofit. Bersama timbulnya dengan degenerasi rawan, timbul reparasi. Reparasi berupa pembentukan osteofit di tulang subkondral (Parjoto, 2000).
c. Sklerosis subkondral. Pada tulang subkondral terjadi reparasi berupa sclerosis (pemadatan/ penguatan tulang tepat di bawah lapisan rawan yang mulai rusak) (Parjoto, 2000).
d. Sinovitis.
Sinovitis adalah inflamasi dari sinovium dan terjadi akibat proses sekunder degenerasi dan fragmentasi. Matriks rawan sendi yang putus terdiri dari kondrosit yang menyimpan proteoglycan yang bersifat immunogenik dan dapat mengaktivasi leukosit. Sinovitis dapat meningkatkan cairan sendi. Cairan lutut yang mengandung bermacam-macam enzim akan tertekan ke dalam celah-celah rawan. Ini mempercepat proses pengerusakan rawan. Pada tahap lanjut terjadi tekanan tinggi dari cairan sendi terhadap permukaan sendi yang botak. Cairan ini akan didesak ke dalam celah-celah tulang subkondral dan akan menimbulkan kantong yang disebut kista subkondral
. GEJALA OA
Penyakit ini bisa tanpa gejala (asimptomatik) artinya walaupun menurut hasil X-ray hampir 70 persen manula lebih 70 tahun dideteksi menderita penyakit OA, tetapi hanya setengahnya mengeluh, sedangkan selebihnya normal. Berikut ini tanda tanda serangan OA :
o Persendian terasa kaku dan nyeri apabila digerakkan .Pada mulanya hanya terjadi pagi hari, tetapi apabila dibiarkan akan bertambah buruk dan menimbulkan rasa sakit setiap melakukan gerakan tertentu , terutama pada waktu menopang berat badan, namun bisa membaik bila diistirahat kan . Pada beberapa penderita , nyeri sendi dapat timbul setelah istirahat lama,misalnya duduk di kursi atau di jok mobil dalam perjalanan jauh. Terkadang juga dirasakan setelah bangun tidur di pagi hari.
o Adanya pembengkakan/peradangan pada persendian (Heberden’s dan Bouchard’s nodes)
Persendian yang sakit berwarna kemerah-merahan.
o Kelelahan yang menyertai rasa sakit pada persendian
o Kesulitan menggunakan persendian
o Bunyi pada setiap persendian(crepitus). Gejala ini tidak menimbulkan rasa nyeri, hanya rasa tidak nyaman pada setiap persendian (umumnya lutut)
o Perubahan bentuk tulang.Ini akibat jaringan tulang rawanyang semakin rusak, tulang mulai berubah bentuk dan meradang , menimbulkan rasa sakit yang amat sangat.
FAKTOR RESIKO;
o Usia diatas 50 tahun.
o wanita
o Kegemukan
o Riwayat immobilisasi
o Riwayat trauma atau radang di persendian sebelumnya.
o Adanya stress pada sendi yang berkepanjangan,misalnya pada olahragawan.
o Adanya kristal pada cairan sendi atau tulang .
o Densitas tulang yang tinggi
o Neurophaty perifer
o faktor lainnya : ras, keturunan dan metabolik.
PENCEGAHAN OA
Dengan mengeleminir faktor predisposisi di atas. Sebagai tips, lakukan hal-hal berikut untuk menghindari sedini mungkin anda terserang OA atau membuat OA anda tidak kambuh yaitu dengan;
o Menjaga berat badan
o Olah raga yang tidak banyak menggunakan persendian
o Aktifitas Olah raga sesuai kebutuhan
o Menghindari perlukaan pada persendian.
o Minum suplemen sendi
o Mengkonsumsi makanan sehat
o Memilih alas kaki yang tepat dan nyaman
o Lakukan relaksasi dengan berbagai tehnik
o Hindari gerakan yang meregangkan sendi jari tangan.
o Jika ada deformitas pada lutut, misalnya kaki berbentuk O, jangan dibiarkan. hal tersebut akan menyebabkan tekanan yang tidak merata pada semua permukaan tulang.
Bagaimana Mendiagnosis Osteoatritis ?
Diagnosis dari osteoartritis dapat ditegakan berdasarkan gejala penyakit dan dengan melakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan yang dimaksud dapat berupa :
• Röntgen tulang
Dengan pemeriksaan ini dapat diketahui kerusakan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada tulang rawan atau tulang yang mengindikasikan adanya osteoartritis.
• MRI (Magnetic Resonance Imaging)
Pada MRI dapat pula dilihat kelainan-kelainan yang terjadi pada tulang rawan dan tulang dengan detail yang lebih baik daripada pemeriksaan röntgen tulang.
• Aspirasi sendi (arthrocentesis)
Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengambil sedikit cairan yang ada di dalam sendi untuk diperiksa di laboratorium berkenaan dengan adanya kelainan pada sendi.
Terapi Osteoatritis ?
Sampai saat ini masih belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan osteoartritis hingga tuntas. Pengobatan yang ada hingga saat ini hanya berfungsi untuk mengurangi nyeri dan mempertahankan fungsi dari sendi yang terkena. Ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai dalam proses terapi osteoartritis, yaitu untuk mengontrol nyeri dan gejala lainya, untuk mengatasi gangguan pada aktivitas sehari-hari, dan untuk menghambat proses penyakit.
Pilihan pengobatan dapat olahraga, kontrol berat badan, perlindungan sendi, terapi fisik, dan obat-obatan. Bila semua pilihan terapi tersebut tidak memberikan hasil, dapat dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan operasi pada sendi yang terkena.
Glucosamine dan Chondroitine Sulfate
Glucosamine merupakan suatu gula amino yang berfungsi untuk pembentukan dan perbaikan kartilago. Chondroitin sulfate merupakan bagian dari molekul protein besar (proteoglycan) yang memberikan elastisitas dari kartilago. Studi menunjukkan bahwa penderita osteoartritis yang
mengonsumsi suplemen glucosamine dan chondroitin sulfate mengalami pengurangan rasa nyeri dalam intensitas yang sama seperti bila seseorang mengonsumsi obat AINS (Anti Inflamasi Non-Steroid). Selain itu kedua zat tersebut juga dipercaya dapat memperlambat kerusakan kartilago pada pederita osteoartritis.
Penatalaksanaan Osteoporosis Berdasarkan National Osteoporosis Guideline Group (NOGG)
Oleh admin kalbemed
August 26, 2013 06:30
Osteoporosis merupakan penyakit skeletal sistemik progresif, ditandai oleh massa tulang yang rendah dan kerusakan mikroarsitektur jaringan tulang sehingga meningkatkan fragilitas tulang dan kecenderungan untuk terjadinya fraktur/patah. Pada osteoporosis ini, tulang direabsorpsi terlalu cepat oleh osteoclast dibandingkan penggantiannya oleh osteoblast sehingga tulang menjadi lemah dan mudah fraktur.
The National Osteoporosis Guideline Group (NOGG) telah memperbaharui guideline 2009 pada hal penegakan diagnosis dan tatalaksana osteoporosis wanita postmenopause dan pria usia sekurang-kurangnya 50 tahun di Inggris. Sejak tahun 2009 telah terjadi banyak pembaharuan di lapangan terutama dalam tatalaksana osteoporosis yang diinduksi glukokortikoid, lalu peran calcium dan vitamin D serta keuntungan dan risiko terapi bisphosphonate, seperti yang dikatakan oleh J. Compston, MD dari the University of Cambridge School of Clinical Medicine, United Kingdom, dan kolega dari the NOGG.
Beberapa hal yang disorot dalam guideline NOGG 2013:
• Terapi farmakologi yang dapat menurunkan risiko terjadinya fraktur vertebra (dan beberapa kasus fraktur tulang panggul) seperti bisphosphonate, denosumab, rekombinan hormon parathyroid, raloxifene, dan strontium ranelate. Pada NOGG 2009, terapi yang diakui untuk kasus fraktur vertebra, non vertebra dan fraktur tulang panggul hanya alendronate, risedronate, zoledronate dan terapi sulih hormon.
• Alendronate generik direkomendasikan sebagai terapi lini pertama karena kerja spektrum luasnya sebagai agen antifraktur dengan harga terjangkau.
• Ibandronate, risedronate, zoledronic acid, denosumab, raloxifene atau strontium ranelate digunakan sebagai terapi pilihan jika alendronate dikontraindikasikan atau tidak dapat ditoleransi dengan baik oleh pasien.
• Karena harga yang mahal, maka rekombinan hormon parathyroid hanya diberikan pada pasien dengan risiko sangat tinggi fraktur terutama pada vertebra.
• Wanita postmenopause dapat mendapatkan manfaat dari calcitriol, etidronate, dan terapi hormon pengganti.
• Terapi untuk pria dengan risiko tinggi terjadi fraktur harus dimulai dengan alendronate, risedronate, zoledronate, atau teriparatide.
• Bagi wanita post menopause, terapi yang diakui untuk pencegahan dan pengobatan osteoporosis akibat glukokortikoid yaitu alendronate, etidronate dan risedronate, sementara itu terapi pilihan yang diakui baik untuk wanita dan juga pria adalah teriparatide dan zoledronate.
• Suplemen calcium dan vitamin D secara luas direkomendasikan untuk para lansia dan sebagai terapi osteoporosis.
• Efek potensial pada kardiovaskuler akibat pemberian suplemen calcium masih kontroversial, namun sangat bijaksana jika asupan calcium melalui makanan ditingkatkan dan menggunakan suplemen vitamin D saja daripada mengkonsumsi suplemen calcium dan vitamin D bersamaan.
• Penghentian mendadak bisphosphonate dihubungkan dengan penurunan BMD dan bone turn over setelah 2 – 3 tahun diterapi dengan alendronate dan risedronate.
• Terapi bisphosphonate dilanjutkan meskipun tanpa evaluasi lebih lanjut terutama pada pasien dengan risiko sangat tinggi terjadi fraktur, dimana review terapi dan evaluasi fungsi ginjal cukup dilakukan tiap 5 tahun sekali.
• Jika bisphosphonate dihentikan, risiko fraktur dievaluasi ulang tiap kali setelah terjadinya fraktur baru, atau setelah 2 tahun jika tidak terjadi fraktur baru.
• Setelah 3 tahun diterapi dengan zoledronate, manfaat yang timbul pada BMD akan tetap ada sampai dengan 3 tahun setelah terapi dihentikan. Kebanyakan pasien harus menghentikan pengobatan
setelah terapi selama 3 tahun, dan dokter harus melakukan evaluasi ulang akan kebutuhan untuk melanjutkan terapi dalam 3 tahun mendatang.
• Pasien dengan fraktur vertebra sebelumnya atau terapi awal osteoporosis tulang panggul dengan skor T BMD ≤ -2,5 SD dapat mengalami peningkatan risiko fraktur vertebra jika zoledronate dihentikan.
Rekomendasi pada guideline ini dimaksudkan untuk membantu dalam keputusan tatalaksana osteoporosis dengan tidak mengenyampingkan keputusan klinik bagi pasien.
Kesimpulan:
• Pada guideline NOGG 2013 tatalaksana osteoporosis ini masih tetap mengacu pada guideline 2009 sebelumnya, dimana terapi lini pertama bagi pasien dengan risiko fraktur vertebra dan non vertebra adalah alendronate. Jika penggunaan alendronate memberikan hasil yang kurang memuaskan atau pasien intoleransi terhadap alendronate maka dapat diberikan ibandronate, risedronate, zoledronic acid, denosumab, raloxifene dan strontium ranelate.
• Tetap direkomendasikan konsumsi calcium (dalam makanan maupun suplemen) dan vitamin D yang dapat memberikan manfaat bagi mereka dengan risiko fraktur pada osteoporosis.
• Penegakan osteoporosis juga mengacu pada penemuan kasus fraktur dan mempertimbangkan adanya faktor risiko pada pasien tersebut.(PDP)
Referensi:
1. Barclay L. Osteoporosis Management Guidelines Updated for Women and Men. (Internet) 2013 (Cited 2013 August 19). Available from : http://www.medscape.com/viewarticle/807140.
2. Compston J, Bowring C, Cooper A, Davies C, Francis R, et al. Diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women and older men in the UK: National Osteoporosis Guideline Group (NOGG) update 2013. Maturitas 2013 August;75(4):392-6.
3. Compston J, Cooper A, Cooper C, Francis R, Kanis JA. Guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women and men from the age of 50 years in the UK. Maturitas 2009 February;62(2):105-8.