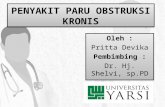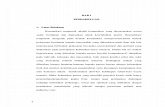Anemia Pada Penyakit Kronis
-
Upload
zha-zha-marza -
Category
Documents
-
view
32 -
download
2
description
Transcript of Anemia Pada Penyakit Kronis
ANEMIA PADA PENYAKIT KRONISMartholiza1, Dani Rosdiana21 Fakultas Kedokteran, Universitas Abdurrab2 Bagian Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran, Universitas Riau
ABSTRAKAnemia pada penyakit kronis merupakan suatu bentuk anemia yang terjadi akibat: infeksi atau inflamasi kronis, trauma maupun penyakit neoplastik yang telah berlangsung selama 1-2 bulan dan tidak disertai penyakit hati, ginjal dan endokrin. Kami melaporkan sebuah kasus anemia pada penyakit kronis.PBM via IGD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau pada tanggal 3 September 2014, seorang laki-laki (57 tahun) datang dengan keluhan badan lemas sejak 1 hari SMRS, keluhan ini didahului dengan sinkop dan disertai dengan sesak, batuk dan dahak kronis sejak 7 tahun SMRS. Dari pemeriksaan fisik ditemukan konjungtiva anemis dengan kelainan paru (pelebaran sela iga, hipersonor dan vesikuler melemah). Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan kesan anemia mikrositik hipokrom dan pada hasil pemeriksaan radiologi didapatkan kesan sugestif TB paru.Laporan kasus ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penegakan diagnosis anemia pada penyakit kronis dan penatalaksanaannya.Kata kunci: anemia, penyakit kronis
CASE REPORT
5 | Anemia pada Penyakit Kronis
PENDAHULUANAnemia pada penyakit kronis merupakan suatu bentuk anemia yang terjadi akibat: infeksi kronis seperti penyakit tuberkulosis, abses paru, endokarditis bakteri subakut, osteomielitis, infeksi jamur kronis, pneumonia, sifilis, hiv-aids; inflamasi kronis seperti artritis reumatoid dan juga pada penyakit lain seperti limfoma Hodgkin atau kanker yang telah berlangsung selama 1-2 bulan dan tidak disertai penyakit hati, ginjal dan endokrin.1,2PatogenesisPatogenesis anemia pada penyakit kronis adalah sebagai berikut (dikutip dari Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam FKUI):11. Pemendekan Masa Hidup EritrositDiduga anemia yang terjadi merupakan bagian dari sindrom stres hematologik (haematological stress syndrome), dimana terjadi produksi sitokin yang berlebihan karena kerusakan jaringan akibat infeksi, inflamasi atau kanker. Sitokin tersebut dapat menyebabkan sekuestrasi makrofag sehingga mengikat lebih banyak zat besi, meningkatkan destruksi eritrosit di limpa, menekan produksi eritropoietin oleh ginjal, serta menyebabkan perangsangan yang inadekuat pada eritropoiesis di sumsum tulang. Pada keadaan lebih lanjut, malnutrisi dapat menyebabkan penurunan transformasi T4 (tetraiodothyronine) menjadi T3 (tri-iodothyronine), menyebabkan hipotiroid fungsional dimana terjadi penurunan kebutuhan Hb yang mengangkut O2 sehingga sintesis eritropoietin pun akhirnya berkurang.2. Penghancuran EritrositBeberapa penelitian membuktikan bahwa masa hidup eritrosit memendek pada sekitar 20-30% pasien. Defek ini terjadi di ekstrakorpuskular, karena bila eritrosit pasien ditransfusikan ke resipien normal, maka dapat hidup normal. Aktivasi makrofag oleh sitokin menyebabkan peningkatan daya fagositosis makrofag tersebut dan sebagai bagian dari filter limpa (compulsive screening), menjadi kurang toleran terhadap perubahan/kerusakan minor dari eritrosit.3. Produksi EritrositGangguan metabolisme besi. Kadar besi yang rendah meskipun cadangan besi cukup menunjukkan adanya gangguan metabolisme zat besi pada penyakit kronis. Hal ini memberikan konsep bahwa anemia disebabkan oleh kemampuan Fe dalam sintesis Hb. Penelitian akhir menunjukkan parameter Fe yang terganggu mungkin lebih penting untuk diagnosis daripada patogenesis anemia tersebut (Tabel 1).Tabel 1. Perbedaan parameter Fe pada orang normal, anemia defisiensi besi dan anemia penyakit kronisNormalAnemia defisiensi besiAnemia penyakit kronis
Fe plasma (mg/L)70-903030
TIBC250-400>450288-28
TIBC-total iron binding capacityPengukuran kecepatan penyerapan zat besi oleh saluran cerna pada beberapa kasus dengan kelainan kronis memberikan hasil yang sangat bervariasi, sehingga tidak dapat disimpulkan. Pada umumnya memang terdapat gangguan absorpsi, walaupun ringan. Ambilan zat besi ke sel-sel usus dan pengikatan oleh apoferitin intrasel masih normal, sehingga defek agaknya terjadi saat pembebasan Fe dari makrofag dan sel-sel hepar pada pasien penyakit kronis.Fungsi sumsum tulang. Meskipun sumsum tulang yang normal dapat mengkompensasi pemendekan masa hidup eritrosit, diperlukan stimulus eritropoietin oleh hipoksia akibat anemia. Pada penyakit kronis, kompensasi yang terjadi kurang dari yang diharapkan akibat berkurangnya penglepasan atau menurunnya respons terhadap eritropoietin menunjukkan hasil yang berbeda-beda; pada beberapa penelitian kadar eritropoietin tidak berbeda bermakna pada pasien anemia tanpa kelainan kronis, sedangkan penelitian lain menunjukkan penurunan produksi eritropoietin sebagai respons terhadap anemia sedang-berat. Agaknya hal ini disebabkan oleh sitokin, seperti IL-1 dan TNF- yang dikeluarkan oleh sel-sel yang cedera. Penelitian in vitro pada sel hepatoma menunjukkan bahwa sitokin-sitokin ini mengurangi sintesis eritropoietin.Terdapat 3 jenis sitokin yakni TNF-, IL-1, IFN- yang ditemukan dalam plasma pasien dengan penyakit inflamasi atau kanker dan terdapat hubungan secara langsung antara kadar sitokin ini dengan beratnya anemia. TNF- dihasilkan oleh makrofag aktif dan bila disuntikkan pada tikus menyebabkan anemia ringan dengan gambaran khas seperti anemia penyakit kronis. Pada kultur sumsum tulang manusia ia akan menekan eritropoiesis pada pembentukan BFU-E dan CFU-E. Penelitian terkini menunjukkan bahwa efek TNF- ini melalui IFN- yang diinduksi oleh TNF dari sel stroma.IL-1 berperan dalam berbagai manifestasi inflamasi, juga terdapat dalam serum penderita penyakit kronis. IL-1, seperti halnya TNF, akan menginduksi anemia pada tikus dan menekan pembentukan CFU-E pada kultur sumsum tulang manusia.Kedua interferon tadi diduga dapat langsung menghambat CFU-E tanpa melalui efek TNF-, serta dapat menekan progenitor non-eritroid. Walaupun demikian, bagaimana peranannya dalam patogenesis anemia secara pasti belum dapat dijelaskan, karena masih banyak faktor-faktor lain yang tak terduga yang mungkin berperan penting dalam patogenesis anemia jenis ini.DiagnosisGejala anemia pada penyakit kronis umumnya asimtomatik karena kadar Hb sekitar 7-11 g/dL. Meskipun demikian apabila demam atau debilitas fisik meningkat, pengurangan kapasitas transpor O2 jaringan akan memperjelas gejala anemianya atau memperberat keluhan sebelumnya.1Tanda anemia pada penyakit kronis hanya dijumpai konjungtiva yang pucat tanpa kelainan yang khas dari anemia jenis ini.1Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan kadar Hb berkisar 7-11 g/dL, selularitas sumsum tulang normal, kadar Fe serum menurun disertai TIBC yang rendah, cadangan Fe yang tinggi di jaringan serta produksi sel darah merah berkurang.1,3PenatalaksanaanPenatalaksanaan anemia pada penyakit kronis adalah mengobati penyakit dasarnya. Namun, terdapat beberapa pilihan, antara lain:11. Transfusi2. Preparat besi3. Eritropoietin
ILUSTRASI KASUSNy. J (53 tahun) merupakan PBM via IGD RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan pucat sejak 1 minggu SMRS, pucat secara perlahan-lahan. Pasien mengeluh badan lemas, lemas dirasakan terus menerus, semakin lama semakin berat. BAB hitam bercampur darah segar, nafsu makan berkurang, BB pasien dirasakan turun ( 8 kg) selama sakit. Pasien tidak mengeluh mual, muntah, demam, nyeri kepala, nyeri dada dan nyeri perut. Gangguan BAK disangkal. Pasien dirawat di RSUD Bangkinang dan telah ditransfusi darah 4 kantong sebelum dirujuk ke RS Arifin Achmad. Sejak 1 tahun SMRS, pasien mengeluh BAB berwarna hitam seperti aspal, BAB hitam dirasakan 1-2 kali /hari dan terjadi setiap hari. Volume BAB 1 gelas aqua kecil tiap kali BAB dan konsistensi BAB lunak. Pasien mengaku kadang-kadang BAB hitam yang dirasakan disertai darah segar 1 sendok makan tiap kali BAB. Pasien mengaku makan 2x sehari dengan porsi 1 piring. Pasien merasakan nyeri sebelum dan setelah makan. Pasien tidak mengeluh mual, muntah, demam, nyeri kepala, nyeri dada dan nyeri perut. Gangguan BAK disangkal. 9 bulan SMRS, pasien merasakan makin lama makin pucat dan dibawa ke RSUD Bangkinang. Pasien mendapatkan transfusi darah 5 kantong dan membaik pasien pulang. Keluhan pucat berulang dikeluhkan pasien sebanyak 3 kali dalam tahun ini dan selalu dilakukan transfusi 5 kantong tiap transfusi. Keluhan BAB hitam tidakb berkurang. Riwayat maag 2 tahun yang lalu. Riwayat asma disangkal, riwayat hipertensi tidak diketahui, riwayat DM tidak diketahui. Tidak ada keluarga dengan keluhan yang sama.Pasien tidak bekerja sejak 1 tahun terakhir. Pasien tergolong ekonomi menengah ke bawah. Kehidupan ekonomi disokong oleh istri pasien yang memiliki pekerjaan sebagai penyadap karet. Pasien tinggal di lingkungan yang padat. Pasien tidak merokok sejak 7 tahun terakhir, sebelumnya pasien merokok 1 bungkus sehari selama 30 tahun. Pasien sesekali mengkonsumsi alkohol di masa muda. Pasien mengaku memiliki kebiasaan minum 1,5-2 L per hari dan makan makanan biasa 3 kali sehari dengan porsi sedikit, sejak 7 tahun terakhir nafsu makan semakin berkurang. Pasien mengalami penurunan berat badan sejak 7 tahun terakhir, dari 50-60 kg menjadi 39 kg.Hasil dari pemeriksaan umum yang dilakukan pada pasien ini pada tanggal 4 September 2014 adalah kesadaran apatis, keadaan umum tampak sakit sedang, keadaan gizi: buruk (IMT 15,62 kg/m2 dengan berat 39 kg dan tinggi 158 cm), tekanan darah 100/70 mmHg, frekuensi nadi 88 kali per menit reguler, frekuensi nafas 28 kali per menit reguler dan suhu 36,7C.Pada pemeriksaan fisik ditemukan konjungtiva anemis, mata tidak cekung, bibir tidak kering, pembesaran KGB leher (-), JVP normal 5-2 cmH2O. Pada pemeriksaan toraks (status lokalis) ditemukan pada paru: gerakan dinding dada simetris, tidak ada penggunaan otot bantu pernafasan, pelebaran sela iga (+), bentuk dada barrel chest (-), tipe pernafasan torakoabdominal, vokal fremitus melemah pada seluruh lapangan paru, hipersonor pada seluruh lapangan paru, vesikuler melemah pada seluruh lapangan paru dan jantung: iktus kordis tidak terlihat, iktus kordis teraba pada SIK V linea mid klavikula, batas jantung sulit dinilai, bunyi jantung I & II reguler melemah, murmur (-), gallop (-). Pemeriksaan abdomen dan ekstremitas dalam batas normal.Pada pemeriksaan laboratorium (darah, kimia darah, fungsi hati, fungsi ginjal dan feses) ditemukan eritrosit 4.750.000/L, leukosit 7.770/L, trombosit 214.000/L, hemoglobin 8,7 g/dL, hematokrit 27,5%, LED 2 mm, MCV 57,9 fl, MCH 18,3 pg, MCHC 31,6 g/dL, hitung jenis: basofil 0,1%, eosinofil 0,1%, neutrofil 52,4%, limfosit 37,5%, monosit 9,9%; GDS 123 mg/dL; faal hati (SGPT) dan ginjal (kreatinin) dalam batas normal; elektrolit: Na+ 144 mmol/L, K+ 3,3 mmol/L 2,78 mmol/L, Cl- 107 mmol/L.Pada pemeriksaan radiologi (rontgen toraks) ditemukan cor CTR>50%; pulmo corakan bronkovaskuler meningkat, tampak infiltrat di parakardial kanan, kedua hilus tidak menebal, kedua sinus dan diafragma baik. Kesan: cor tidak tampak kelainan radiologis, sugestif TB paru.Terapi non-farmakologis pada pasien ini adalah tirah baring dan diet tinggi kalori tinggi protein. Untuk terapi farmakologisnya, pada pasien ini diberikan IVFD NaCl 0,9%, pemberian O2 4 L per menit melalui nasal kanul, transfusi 2 labu PRC dan sulfas ferrosus 1x1 tablet.Setelah transfusi dilakukan pemeriksaan ulang darah, didapatkan hasil eritrosit 5.217.000/L, leukosit 6.590/L, trombosit 150.700/L, hemoglobin 10,47 g/dL, hematokrit 32,67%, MCV 62,63 fl, MCH 20,07 pg, MCHC 32,05 g/dL. Pasien kemudian dipulangkan dan diberikan obat selama 5 hari berupa sulfas ferrosus 1x1 tablet dan vitamin b kompleks 1x1 tablet.
DISKUSIKeluhan utama pada pasien adalah badan lemas. Diketahui keluhan ini didahului dengan sinkop atau kehilangan kesadaran sesaat. Penegakan penyebab sinkop sebaiknya dilakukan dengan menggunakan anatomi dan fisiologi. Seperti halnya konvulsi, sinkop disebabkan oleh berkurangnya pasokan oksigen dan glukosa dalam sel otak. Segala sesuatu yang menimbulkan hipoglikemia dapat menyebabkan episode sinkop.4 Hipoglikemia sebagai penyebab sinkop pada pasien ini disingkirkan dengan pemeriksaan GDS 123 mg/dL (N: 70-199 mg/dL). Selain hipoglikemia, penyebab lain yang dapat dipikirkan adalah obstruksi jalan nafas. Obstruksi jalan nafas dapat menyebabkan anoksia dan sinkop.4 Kemungkinan obstruksi jalan nafas perlu dipikirkan mengingat keluhan penyerta pasien adalah sesak, batuk dan dahak kronis selama 7 tahun. Selain itu, pasien juga memiliki riwayat batuk berdarah 7 tahun yang lalu. Diagnosis pada pasien ini mengarah pada sindrom obstruktif paska tuberkulosis. Untuk penegakan diagnosis perlu disingkirkan kemungkinan adanya asma bronkial dan gagal jantung kongestif. Asma bronkial disingkirkan karena dari anamnesis dapat disimpulkan bahwa karakteristik sesak pada pasien adalah sesak yang tidak dicetuskan oleh suatu keadaan hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu. Gagal jantung kongestif disingkirkan karena tidak terpenuhinya kriteria Framingham.Kriteria Framingham untuk diagnosis gagal jantung kongestif (minimal 1 kriteria major dan 2 kriteria minor:1Kriteria major:1. Paroksismal nokturnal dispnea2. Distensi vena leher3. Ronki paru4. Kardiomegali5. Edema paru akut6. Gallop S37. Peninggian tekanan vena jugularis8. Refluks hepatojugulerKriteria minor:1. Edema ekstremitas2. Batuk malam hari3. Dispnea deffort4. Hepatomegali5. Efusi pleura6. Penurunan kapasitas vital 1/3 dari normal7. Takikardia (>120 kali per menit)Dari pemeriksaan fisik ditemukan keadaan gizi buruk (IMT 15,62 kg/m2), konjungtiva anemis, status lokalis (paru): frekuensi nafas 28 kali per menit, pelebaran sela iga (+), hipersonor dan vesikuler melemah. Ini menunjukkan adanya kelainan pada paru pasien.Dari pemeriksaan penunjang ditemukan Hb 8,7 g/dL, hematokrit 27,5%, MCV 57,9 fl, MCH 18,3 pg anemia mikrositik hipokrom. Kesan pada rontgen toraks sugestif TB paru.Daftar masalah pada pasien ini adalah malnutrisi, takipnea dan anemia pada penyakit kronis suspek sindrom obstruktif paska tuberkulosis. Malnutrisi pada pasien ditatalaksana dengan pemberian diet tinggi kalori tinggi protein, takipnea dengan pemberian O2 4 L per menit dan tatalaksana anemianya dengan transfusi 2 labu PRC dan pemberian sulfas ferrosus 1x1 tablet. Kebutuhan nutrisi pada pasien berdasarkan BB ideal pasien ((TB-100)x1kg) yaitu 58 kg, jadi kebutuhan kalori (30kkal/kgBB) pada pasien adalah 1.740 kkal per hari. Rumus transfusi PRC HbxBBx4ml, sesuai dengan keadaan pasien didapatkan kebutuhan PRC pasien adalah 202,8 ml. Sulfas ferrosus mengandung Fe sulfat heptahidrat 300 mg.Pemeriksaan kadar Fe serum, TIBC dan feritin serum secara teori perlu diperiksa dalam penegakan diagnosis anemia pada penyakit kronis.1 Untuk menentukan etiologi penyakit pada pasien ini perlu diperiksa BTA sputum untuk kecurigaan tuberkulosis paru kronis yang mungkin telah dialami pasien selama > 7 tahun.Diagnosis tuberkulosis paru dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis (gejala lokal: batuk >2 minggu, batuk darah, sesak nafas, nyeri dada; gejala sistemik: demam, malaise, keringat malam, anoreksia, berat badan menurun), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.5 Hal ini sesuai dengan yang ditemukan pada pasien yaitu batuk kronis, batuk darah, sesak nafas, keringat malam dan berat badan menurun.Klasifikasi tuberkulosis paru berdasarkan BTA sputum:1. Tuberkulosis paru BTA (+) ditegakkan apabila sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak menunjukkan hasil BTA positif, hasil pemeriksaan satu spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan kelainan radiologik menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif atau hasil pemeriksaan satu spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan biakan positif.2. Tuberkulosis paru BTA (-) ditegakkan apabila hasil pemeriksaan dahak 3 kali menunjukkan BTA negatif, gambaran klinik dan kelainan radiologik menunjukkan tuberkulosis aktif atau hasil pemeriksaan dahak 3 kali menunjukkan BTA negatif dan biakan M. tuberkulosis positif.5Penatalaksanaan tuberkulosis paru dalam program nasional adalah berdasarkan 6 kategori, yaitu:51. Kategori I TB paru BTA (+), BTA (-), lesi luas: 2 RHZE / 4 RH atau 2 RHZE / 6 HE atau 2 RHZE / 4R3H32. Kategori II kambuh, gagal pengobatan: 2 RHZES / 1 RHZE / 5 RHE atau 2 RHZES lalu sesuai hasil uji resistensi atau 2 RHZES / 1 RHZE / 5 R3H3E33. Kategori III TB paru lalai berobat: 2 RHZES / 1 RHZE / 5 R3H3E34. Kategori IV TB paru BTA (-) lesi minimal: 2 RHZ / 4 RH atau 6 RHE atau 2 RHZ / 4 R3H35. Kategori V kronik: sesuai uji resistensi (minimal 3 obat sensitif dengan H tetap diberikan) atau H seumur hidup6. Kategori VI MDR TB: sesuai uji resistensi + kuinolon atau H seumur hidupKeterangan:R = RifampisinH = INHZ = PirazinamidE = EtambutolS = Streptomisin
KESIMPULANAnemia pada penyakit kronis merupakan suatu bentuk anemia yang terjadi akibat: infeksi atau inflamasi kronis, trauma maupun penyakit neoplastik yang telah berlangsung selama 1-2 bulan dan tidak disertai penyakit hati, ginjal dan endokrin.Diagnosis anemia pada penyakit kronis ditegakkan hanya jika anemia dengan kadar Hb berkisar 7-11 g/dL, selularitas sumsum tulang normal, kadar Fe serum menurun disertai TIBC yang rendah, cadangan Fe yang tinggi di jaringan serta produksi sel darah merah berkurang.Penatalaksanaan anemia pada penyakit kronis selain mengobati penyakit dasarnya adalah transfusi, preparat besi dan eritropoietin.
DAFTAR PUSTAKA1. Sudoyo AW et al. Buku ajar ilmu penyakit dalam. Jakarta: Interna Publishing; 2009.2. Lee GR. The anemia of chronic disorders. Semin Haematology; 1983.3. Muhammad A dan Sianipar O. Penentuan defisiensi besi anemia penyakit kronis menggunakan peran indeks STfR-F. Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory Vol 12; 2005.4. Collins RD. Diagnosis banding di layanan primer. Jakarta: EGC; 2010.5. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Tuberkulosis: pedoman diagnosis dan penatalaksanaan di Indonesia; 2002.

![[1] konsep penyakit kronis](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/55687c53d8b42a3b7b8b53bd/1-konsep-penyakit-kronis.jpg)