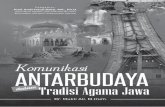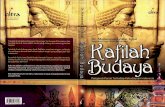10_pariwisata budaya.pdf
-
Upload
surya-diarta -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of 10_pariwisata budaya.pdf

1
PARIWISATA BUDAYA: PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
(draft buku)
Oleh: I Ketut Surya Diarta, SP, MA

2
BAB 2
PENGERTIAN PARIWISATA BUDAYA
2.1 PARIWISATA, BUDAYA, DAN PARIWISATA BUDAYA
2.1.1 PARIWISATA
Pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional. Tak bisa dihindari
beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh praktisi dengan tujuan dan perspektif
yang berbeda-beda sesuai tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, beberapa ahli
mendefinisikan pariwisata sebagai:
The study of man away from his usual habitat, of the industry which responds to his needs, and of the impacts that both he and the industry have on the host’s socio-cultural, economic, and physical environments (Jafari, 1977 dalam Richardson & Flicker, 2004: 5).
Tourism comprises the ideas and opinions people hold which shape their decisions about going on trips, about where to go (and where not to go) and what to do or not to do, about how to relate to other tourists, locals and service personnel. And it is all the behavioural manifestations of those ideas and opinions (Leiper, 1995 dalam Richardson & Flicker, 2004: 6).
The activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes (WTO dalam Richardson & Flicker, 2004: 6).
Konsep ’usual environment’ menjadi konsep yang sangat penting sebab hal ini
menjadi kriteria pertama yang membedakan pariwisata dari tipe perjalanan lainnya.
Penglaju misalnya, mereka pergi ke tempat kerja, sekolah, atau universitas walaupun
hal tersebut menempuh jarak yang cukup jauh namun masih terkait dengan lingkungan
sehari-harinya tidak dapat dikategorikan ke dalam kegiatan pariwisata. Menurut WTO
konsep usual environment mengandung dua dimensi sebagai berikut.

3
a. Dimensi frekuensi
Tempat yang secara rutin atau teratur dikunjungi oleh seseorang adalah bagian dari
’usual environment’ dari orang tersebut. Meskipun, tempat ini terletak sangat jauh
dari tempat tinggal/rumah orang tersebut. Oleh karenanya, kategori ini tidak dapat
dikategorikan dalam pengertian pariwisata.
b. Dimensi jarak
Tempat atau lokasi yang terletak dekat dengan tempat tinggal seseorang adalah
‘usual environment’ meskipun lokasi tersebut sangat jarang dikunjungi.
Oleh karenanya, konsep ini mengandung pengertian tempat tertentu yang terletak di
sekitar tempat tinggal orang tersebut dan tempat-tempat yang dikunjunginya secara
rutin atau teratur.
Namun demikian, pendapat Smith (2004) dapat dijadikan acuan dalam memilih
pengertian standar yang relatif bisa diaplikasikan dan dipertanggungjawabkan secara
akademis. Menurut Smith (2004: 28), pengertian pariwisata haruslah: (a) dapat
diterima dan diterapkan secara global, (b) sesederhana dan sejelas mungkin, (c) dapat
diaplikasikan secara statistik, dan (d) sedapat mungkin konsisten dengan standar
internasional. Salah satu definisi yang dicontohkan oleh Smith (ibid) yaitu definisi
WTO tahun 1994 dimana pariwisata didefinisikan sebagai berikut.
…the set of activities engaged in by persons temporarily away from their usual environment, for a period not more than one year, and for a broad range of leisure, business, religious, health, and personal reasons, excluding the pursuit of remuneration from within the place visited or long-term change of residence (Smith, 2004: 29)
Tidak seperti pengertian wisatawan, pada pengertian pariwisata di atas lebih
ditekankan pada segi aktifitas atau kegiatan wisatawannya. Ada beberapa elemen dari
definisi WTO tersebut.
a. Definisi tersebut lebih bersifat demand-side. Dalam konteks ini pariwisata
dipandang sebagai sesuatu yang orang (wisatawan) lakukan, bukan sebagai sesuatu
yang dihasilkan oleh aktifitas bisnis (businesses produce). Konsekuensinya, ketika
mengukur magnitud pariwisata sebagai aktifitas ekonomi kita harus fokus pada
pengeluaran wisatawan dalam perjalanan wisatanya. Bukan sebaliknya, dengan
memasukkan aktifitas bisnis oleh hotel dan tur operator yang menjual sebuah
paket wisata siap jual. Konsekuensinya, hal-hal yang tidak terhitung dalam definisi
tersebut sebenarnya sama pentingnya dengan hal-hal yang dimasukkan dalam

4
perhitungan. Investasi pemerintah, bisnis di bidang penyediaan infrastruktur,
penyedia layanan pariwisata, biaya konstruksi kapal, gaji karyawan pada
perusahaan penyelenggara usaha pariwisata tidak tercakup dalam definisi
pariwisata ini.
b. Definisi WTO tersebut merujuk pada usual environment. Dalam konteks
pariwisata internasional, hal ini didefinisikan sebagai melewati perbatasan
internasional yang memisahkan dua negara. Jarak aktual dari perjalanan menjadi
tidak relevan sebab penekanan pada perbatasan nasional sebagai karakteristik
definisi pariwisata menjadi problematik di Uni Eropa di mana formalitas batas
nasional sudah “hilang” bagi penduduk Uni Eropa yang tiap hari ulang alik
melintasi batas nasional negaranya dengan negara tetangganya.
c. Definisi WTO tersebut tidak menyebutkan secara spesifik lama tinggal di tempat
tujuan. Menurut definisi WTO ini, bisa saja perjalanan dalam sehari adalah
perjalanan wisata sebagaimana perjalanan beberapa bulan sampai kurang dari
setahun (Smith, 2004: 29-30). Sebagai solusinya, WTO merevisi perngertian
wisatawan dalam konsep pariwisata dengan mengklasifikasikan menjadi visitor
(orang yang terlibat dalam pariwisata sebagai konsumer), tourist (visitor yang
tinggal lebih dari semalam/menginap), dan same-day visitor (visitor yang tidak
menginap).
Menurut WTO (Theobald, 2005: 18-19), terdapat tiga elemen dasar dalam
pengertian pariwisata secara holistik sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 yaitu:
• domestic tourism (residen/penduduk yang mengunjungi/mengadakan perjalanan
wisata dalam wilayah negaranya)
• inbound tourism (non residen/bukan penduduk yang mengadakan perjalanan
wisata masuk ke negara tertentu)
• outbound tourism (residen/penduduk yang melakukan perjalanan wisata ke
negara lain).
Ketiga bentuk pariwisata ini dapat dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dapat
diturunkan tiga kategori lagi yaitu:
• internal tourism (termasuk domestic tourism dan inbound tourism).
• national tourism (termasuk domestic tourism dan outbound tourism).
• international tourism (termasuk inbound dan outbound tourism).

5
Gambar 1. Bentuk-bentuk pariwisata
Perlu dipahami bahwa walaupun Gambar 1 di atas merujuk kepada sebuah negara
tertentu, tetapi dapat diterapkan pada setiap unit geografis.
2.1.2 BUDAYA
Budaya merupakan sebuah konsep yang lebih kompleks dibandingkan dengan
pariwisata. Hal ini dibuktikan oleh berkembangnya selama bertahun-tahun debat
mengenai definisi budaya dari berbagai disiplin ilmu. Buku ini tidak dimaksudkan untuk
me-review berbagai macam definisi tersebut. Namun, lebih ditekankan pada
bagaimana pendefinisian budaya tersebut dipergunakan dalam konteks pariwisata.
Berdasarkan bagaimana definisi budaya dipergunakan, maka dapat
dikategorikan ke dalam tiga kategori utama sebagai berikut.
(i) as a general process of intellectual, spiritual and aesthetic development; (ii) as indicative of a particular ‘way of life’; and (iii) as the works and practices of intellectual and artistic activity (William dalam McDonald, 2004: 19)
Menurut kategori di atas, ranah penggunaan pengertian ‘budaya’ mencakup ranah
kognitif (serangkaian pengetahuan) berupa proses intelektual, spiritual dan estetika.
Selanjutnya, mencakup ranah afektif (serangkaian sikap) berupa tatanan hidup dan
Sumber: WTO (Theobald, 2005: 18)
Domestic
Inbound Outboundd
international
National Internal

6
terakhir mencakup ranah psikomotorik (serangkaian keterampilan) berupa hasil karya
atau produk yang menjadi ‘wujud’ dari kedua ranah di atas.
Seiring perjalanan waktu, terjadi pergeseran pemahaman ‘budaya’ dari konsep
budaya sebagai ‘proses’ ke arah konsep budaya sebagai ‘produk.’ Pertama, budaya
sebagai proses umumnya menjadi pendekatan dalam kajian Antropologi dan Sosiologi
yang menekankan pengertian budaya sebagai konsep sistem simbolik atau code of
conduct yang menjadi wahana masyarakat memproduksi dan mereproduksi nilai,
kepercayaan, dann perilaku yang memungkinkan masyarakat pendukungnya memaknai
keberadaan dan pengalamannya sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut.
Culture...is seen as a set of practices, based on forms of knowledge, which encapsulate common values and act as general guiding principles. It is through these forms of knowledge that distinctions are creaed and maintained, so that, for example, one culture is marked off as different from another (Meethan dalam McDonald, 2004: 20).
Budaya menurut pemahaman di atas merupakan seperangkat kebiasaan
berdasarkan pengetahuan yang berasal dari kristalisasi nilai-nilai yang disepakati
bersama sebagai prinsip-prinsip atau tuntunan hidup bersama. Karena budaya
disususn dari pengetahuan lokal atau kearifan lokal yang beragam, maka sebuah
budaya dapat dibedakan dengan budaya yang lainnya. Misalnya, budaya orang Bali
dapat dibedakan dengan budaya orang Sunda.
Kedua, pendekatan budaya sebagai produk merujuk pada hasil karya dari
aktifitas individu atau masyarakat dimana makna tertentu melekat pada produk
tersebut. Dalam pendekatan ini, sering dikategorikan lagi menjadi high culture dan low
culture. High culture termasuk di dalamnya seperti theater, museum, arsitektur yang
mengimplikasikan ’elitisme’ dan memerlukan apresiasi estetika yang tinggi. Dalam
tataran ini, budaya berkaitan dengan kemampuan sensibilitas estetika yang
memungkinkan seseorang mengapresiasi sebuah produk (seni) dan selanjutnya
memungkinkannya untuk menilainya sebagai sesuatu yang ’bagus’ atau ’jelek’
berdasarkan pengetahuan memadai yang dimilikinya. Sebaliknya low culture atau
budaya massal merupakan lawan dari pengertian sebelumnya yang bisa mencakup
musik pop, opera sabun, sinetron, Disneyland, Dufan Ancol, dan sejenisnya. Low
culture tidak dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang elit, tidak juga mensyaratkan
pengetahuan memadai sebelumnya untuk bisa menikmatinya. Konsep budaya sebagai
produk juga bersifat deskriptif dan preskriptif. Deskriptif berarti budaya

7
memberitahukan apa yang dicakup didalamnya, sedangkan preskriptif mensyaratkan
penilaian sebagai wahana untuk memberitahu kita apa yang boleh dan apa yang tidak
boleh dilakukan.
2.1.3 PARIWISATA BUDAYA
Berdasarkan dua pendekatan budaya di atas, pariwisata budaya juga dapat
didekati melalui pendekatan proses dan pendekatan produk. Pertama, menurut
Bonink (dalam McDonald, 2004: 22) pariwisata budaya berdasarkan pendekatan
proses mengacu pada pendekatan konseptual atau pendekatan eksperiensial.
Penekanannya pada motivasi dan pengalaman. Berdasarkan pendekatan proses ini,
beberapa definisi pariwisata budaya dapat disusun sebagai berikut.
The movement of persons to cultural attractions away from their normal place of residence, with the intention to gather new information and experiences to satisfy their cultural needs (European Association for Tourism and Leisure Educations (ATLAS) dalam McDonald, 2004: 22).
Posisi definisi ATLAS di atas sangat sentral dan sangat menekankan komponen
pendidikan dan pembelajaran yang dianggap sangat penting dalam pariwisata budaya.
Definisi lainnya yang menekankan pentingnya komponen motivasi adalah definisi
pariwisata budaya oleh The Canadian Tourism Commission (CTC) sebagai berikut.
Cultural...tourism occuurs when participation in a cultural or heritage activity is a significant factor of traveling (CTC dalam McDonald, 2004: 22).
Definisi CTC ini menempatkan komponen motivasi wisatawan untuk berpartisipasi
dalam kegiatan budaya dan/atau motivasi mengunjungi tempat peninggalan budaya
sebagai sentral dari perjalanan wisata yang dilakukan.
Sisi lain, definisi pariwisata budaya yang menekankan sisi pengalaman sebagai
sentralnya diajukan oleh ahli lain sebagai berikut.
…that activity which enables people to explore or experience the different ways of life of other people, reflecting the social customs, religious traditions and the intellectual ideas of a cultural heritage which may be unfamiliar (Borley dalam MacDonald, 2004: 22)
Dari definisi di atas, terlihat bahwa pariwisata budaya menekankan aktifitas wisatawan
untuk mengekplorasi cara dan kebiasaan hidup masyarakat lain yang merefleksikan
tradisi, budaya, dan kehidupan releginya termasuk di dalamya beragam ide dan
peninggalan budaya yang mungkin saja tidak familiar bagi wisatawan dari tempat lain.

8
Mengingat sebagian pariwisata bisa dianggap sebagai kegiatan budaya dalam
derajat tertentu (dimana beberapa perjalanan atau kunjungan yang dilakukan
melibatkan pengalaman untuk mengetahui dan memahami budaya lain), melibatkan
motivasi dalam melakukan wisata sebagai elemen pokok dalam pengertian pariwisata
budaya menjadi sangat penting. Oleh karenanya, ketika memahami pariwisata budaya
maka kegiatan mengunjungi sebuah museum tidak cukup dikatakan sebagai sebuah
pengalaman dalam pariwisata budaya. Namun, yang terpenting adalah adanya
‘motivasi’ untuk mengunjungi museum tersebut dalam memenuhi hasrat dan
kebutuhan untuk ikut merasa ‘terlibat’, ‘mengkonsumsi’, dan ‘mengalami’ budaya yang
diminati sebagai bagian terpenting dari dan kepada wisatawan.
Kedua, konsep pariwisata budaya yang berhubungan dengan pendekatan
produk (ibid, hal. 21-22) mengacu pada pendekatan deskriptif (’situs dan monumen’
ketimbang ’motivasi dan pengalaman’). Pendekatan produk ini lebih menekankan pada
berbagai tipe atraksi wisata budaya yang dikunjungi oleh wisatawan. Menurut World
Tourism Organization (WTO) pariwisata budaya dalam pendekatan produk
didefinisikan sebagai berikut.
Cultural tourism refers to a segment of the industry that places special emphasis on cultural attractions. These attractions are varied, and include performances, museums, displays, and the like. In developed areas, cultural attractions museums, plays, and orchestral and other musical performances….In less developed areas, they might include traditional religious practices, handicrafts, or cultural performances (dikutip McDonald, 2004: 21).
Sebagaimana dapat disimak definisi WTO di atas, pariwisata budaya dikategorikan
sebagai sebuah segmen industri yang sama seperti industri lainnya tetapi produk yang
dihasilkan dan dijual menekankan pada atraksi budaya. Atraksi budaya yang dimaksud
bisa beragam mulai dari pertunjukan seni, museum, pameran, permainan rakyat,
orkestra, musik, ritual agama, kerajinan, dan pertunjukan budaya lainnya. Pendekatan
produk dalam pariwisata budaya sangat berguna bagi penelitian kuantitatif mengingat
memungkinkan kita untuk mengidentifikasi, menghitung dan mewawancarai
pengunjung pada atraksi wisata tertentu.
Pertanyaan berikutnya adalah definisi pariwisata mana yang dianut dalam buku
ini? Untuk menyediakan bingkai berpikir mengenai pariwisata budaya dalam

9
memahami uraian selanjutnya dalam buku ini, akan dielaborasi kedua pendekatan
tersebut di atas menjadi sebagai berikut.
Cultural tourism is a segment of the industry occurring when people are motivated wholly or in part to explore or experience the different ways of life and/or ideas of other people, reflecting the social customs, religious traditions and cultural heritage which may be unfamiliar (Borley dalam McDonald, 2004: 23).
Jadi, pariwisata budaya harus menyangkut pendekatan proses dan produk sekaligus.
Pariwisata budaya adalah sebuah segmen industri pariwisata yang terjadi
ketika wisatawan yang terlibat digerakkan oleh motivasinya untuk
mengekslorasi atau menikmati atau mengkonsumsi cara hidup, ide,
tradisi, relegi dan warisan budaya yang mungkin kurang familiar dari
kesehariannya yang dimiliki oleh masyarakat lainnya.
Ahli lain, Gee dan Fayos-Sola (1997: 3-9) mengatakan bahwa pendefinisian
pariwisata budaya tidaklah mudah agar bisa memuaskan semua pihak. Bahkan
ICOMOS (The International Council on Monuments and Sites) berpendapat bahwa
”pariwisata budaya sebagai sebuah nama yang berarti banyak hal dengan segala
kekuatan dan kelemahan makna yang melekat padanya.” Umumnya orang akan
memakai definisi tertentu yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.
Namun, dari studi literatur yang dilakukan oleh Gee dan Fayos-Sola (ibid: 3) definisi
pariwisata budaya dapat digolongkan ke dalam empat kategori yaitu: tourism derived,
motivational, experiential dan operational. Beberapa definisi bersifat komprehensif
sementara yang lainnya bersifat sederhana dan praktis.
a. Tourism-derived definition
Definisi dalam konteks ’tourism-derived definition’ menempatkan pariwisata
budaya dalam kerangka pariwisata dan manajemen pariwisata yang lebih luas. Sebagai
contoh, pariwisata didefinisikan sebagai ’sebuah bentuk pariwisata dengan minat
khusus, dimana budaya dengan segala bentuk atau manifestasinya menjadi dasar baik
dlam menarik wisatawan atau memotivasi orang untuk melakukan perjalanan wisata’
(McIntosh & Goeldner 1990; Zeppel 1992; Ap 1999 dalam McKercher & du Cros,
2002: 4).
Definisi lain menempatkan pariwisata budaya dalam konteks sistem budaya
dimana pariwisata budaya merupakan pariwisata yang melibatkan orang, tempat, dan
warisan budaya (Zeppel & Hall 1991 dalam McKercher & du Cros, 2002: 4) atau

10
menempatkannya dalam konteks pergerakan sementara orang (Richards 1996 dalam
McKercher & du Cros, 2002: 4).
Pengertian pariwisata budaya dalam perspektif bisnis melibatkan
pengembangan dan pemasaran dari beragam situs atau atraksi budaya kepada
wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik (Goodrich 1997 dalam
McKercher & du Cros, 2002: 4).
b. Motivational definition
Beberapa ahli melihat bahwa sebagian wisatawan mempunyai motivasi
tertentu yang berbeda dengan wisatawan lainnya dan oleh karenanya faktor motivasi
harus dipandang sebagai elemen penting ketika mendefinisikan pariwisata budaya.
WTO mendefinisikan pariwisata budaya sebagai berikut.
Movement of persons essentially for cultural motivations such as study tours, performing arts and cultural tours, travel to festivals and other events, visit to sites and monuments, travel to study nature, folkflore or art, and pilgrimages (WTO 1985 dalam McKercher & du Cros, 2002: 4). Dari definisi WTO di atas sangat jelas bahwa pariwisata budaya dimulai dari
adanya motivasi atau alasan-alasan budaya yang menyebabkan wisatawan melakukan
perjalanan wisatanya ke daerah tujuan wisata yang diinginkan. Motivasi budaya
tersebut dapat beragam bentuknya seperti pertunjukan seni, studi tur, festival,
berziarah dan sebagainya.
Senada dengan definisi WTO di atas, Provinsi Ontario di Kanada
mendefiniskan pariwisata budaya sebagai berikut.
Visits by persons from outside the host community motivated wholly or in part by interest in the historical, artistic, scientific, or lifestyle/heritage offerings of the community, region, group, or institution (Silberberg 1995 dalam McKercher & du Cros, 2002: 4)
Berdasarkan definisi di atas, wisatawan melakukan perjalanan dalam konteks
pariwisata budaya juga dipicu oleh adanya motivasi/hasrat baik secara keseluruhan
maupun sebagian oleh alasan-alasan budaya misalnya gaya hidup masyarakat yang
dituju, kesenian artistic atau situs bersejarah dan sebagainya.
c. Experiential/Aspirational definition
Motivasi, kalau tanpa pengaruh faktor lain, tidak akan mampu menggambarkan
magnitud pariwisata budaya secara utuh. Pariwisata budaya juga menyangkut aktifitas
eksperiensial dan elemen aspirasi. Setidaknya, pariwisata budaya melibatkan
pengalaman khusus atau kontak dengan intensitas tertentu dengan sistem sosial lain di

11
daerah tujuan wisata, warisan budaya, dan karakter khusus dari tempat atau daerah
tujuan wisata tersebut (Blackwell 1997; Schweitzer 1999 dalam McKercher & du
Cros, 2002: 5). Dengan konsep ini, dengan mengalami dan bersentuhan langsung
dengan budaya lain diharapkan wisatawan semakin mendapat pembelajaran dari
pengalamannya disamping juga semakin merasa terhibur, mempunyai kesempatan
untuk belajar tentang komunitas yang dikunjunginya, atau memiliki kesempatan
mempelajari arti penting suatu tempat atau kawasan dan bagaimana hubungan
kawasan tersebut dengan komunitas yang mendiaminya, peninggalan yang dimilikinya,
budaya, dan lingkungan di sekitarnya. Beberapa wisatawan bahkan menilai pariwisata
budaya sebagai wahana untuk menumbuhkan rasa saling memahami dengan budaya
dan peradaban masyarakat lainnya.
d. Operational definition
Pendekatan definisi pariwisata budaya yang paling umum dipakai adalah definisi
operasional. Menurut pendekatan operasional, pariwisata budaya diartikan sebagai
berikut.
Cultural tourism is defined by participation in any one of an almost limitless array of activities or experiences. Indeed, it is common to avoid defining cultural tourism, instead stating that “cultural tourism includes visits to…” By inference, if someone visits of these attractions, that person must be a cultural tourist; thus the activity must be a cultural tourism activity. Motivation, purpose or depth of experience count less than participation (McKercher & du Cros, 2002: 5) Menurut definisi di atas, pariwisata budaya mencakup semua aktitifitas
pariwisata berupa partisipasi pada hampir semua kegiatan atau pengalaman wisata.
Luasnya cakupan definisi pariwisata budaya tersebut dimaksudkan justru untuk
menghindari pendefinisian pariwisata budaya itu sendiri. Argumentasinya adalah,
daripada mendefinisikan “pariwisata budaya mencakup kunjungan ke….” Maka secara
tersirat jika seseorang mengunjungi atau berpartisipasi pada semua kegiatan wisata,
mengunjungi atraksi wisata dapat dikatakan wisatawan tersebut melakukan kegiatan
pariwisata budaya sehingga kegiatan tersebut otomatis dapat dikatakan sebagai
kegiatan pariwisata budaya. Motivasi, tujuan, atau kedalaman pengalaman dari
kegiatan tersebut haruslah didasari oleh adanya partisipasi aktif wisatawan.
Literatur pariwisata mengidentifikasi beberapa contoh kegiatan atau aktifitas
dalam pariwisata budaya termasuk di dalamnya penggunaan asset warisan budaya
termasuk situs arkeologi, museum, kastil, istana, pura, masjid, gereja, tempat suci,
bangunan bersejarah, bangunan terkenal, barang seni, patung, kerajinan, festival, even,

12
musik dan tari, seni tradisional, theater, budaya primitif, komunitas etnik, dan semua
hal yang mewakili dan menggambarkan hugungan suatu komunitas dengan budayanya
(Richards 1996, Goodrich 1997, Miller 1997 dan Jamieson 1994 dalam McKercher &
du Cros, 2002: 5).
Definisi operasional menyoroti semua potensi cakupan dari aktifitas
pariwisata namun saat bersamaan mengandung potensi masalah yaitu bagaimana
menentukan suatu parameter apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk ke
dalam pariwisata budaya. Pariwisata budaya mempunyai batas-batas yang tidak jelas
sehingga hampir mustahil menjelaskan parameter absolutnya atau menentukan
sumberdaya apa saja yang dipergunakan atau digunakan oleh wisatawan dalam
pariwisata budaya. Sejatinya, pariwisata budaya telah menjadi istilah payung dari
aktifitas pariwisata yang sangat luas termasuk dan tak terbatas di dalamnya seperti
pariwisata etnik, pariwisata sejarah, pariwisata seni, pariwisata museum, dan
sebagainya.
2.2 ELEMEN-ELEMEN DALAM PARIWISATA BUDAYA
Berbagai pendekatan definisi pariwisata budaya seperti telah dibahas
sebelumnya bukannya tanpa kelemahan. Definisi pariwisata budaya tersebut bukannya
jelek, tetapi lebih diakibatkan karena hampir mustahil untuk merekam semua esensi
dari pariwisata budaya dalam sebuah atau dua buah kalimat dalam definisi tertentu.
Oleh karenanya, daripada menambah daftar panjang definisi pariwisata budaya yang
akan jatuh pada kelemahannya sendiri atas batasan definisi yang diberikan, lebih baik
menempatkan pada beberapa tema umum yang tercakup dalam beberapa definisi yang
telah ada yang membangun pengertian kita tentang pariwisata budaya.
Menutut McKercher & du Cros (2002: 6), pariwisata budaya mencakup empat
elemen sebagai berikut.
a. Pariwisata
Untuk mengatakan bahwa pariwisata budaya merupakan bagian dari pariwisata
kelihatannya tidak akan menjelaskan apa-apa karena sudah benar dengan sendirinya.
Tetapi kalau dianalisa padanan kata ‘pariwisata budaya’ terdiri dari kata ‘pariwisata’
yang merupakan kata benda dan ‘budaya’ sebagai kata sifat yang menjelaskan tipe
‘pariwisata’ yang dijelaskannya. Namun, bagaimanapun juga sebagai salah satu bentuk
pariwisata maka seharusnya penekanannya pada pariwisatanya terlebih dahulu baru
diikuti oleh penekanan budayanya. Lebih spesifik, keputusan yang akan diambil dalam

13
kerangka pariwisata budaya harus berdasarkan alasan-alasan pariwisata baru alasan-
alasan lainnya termasuk alasan budaya.
Alasan penekanan alasan pariwisata terlebih dahulu kadang tidak mendapat
apresiasi dari beberapa komunitas. Bagi yang konsen di bidang budaya yang mungkin
memandang pariwisata sebagai wahana untuk mencapai agenda lain termasuk di
dalamnya pelestarian budaya sehingga penekanan pada pariwisata menjadi kurang
tepat. Atau, pihak yang kurang mengerti bagaimana mengelola sebuah aset budaya
sehingga bisa bekerja sebagai atraksi wisata. Sebagai sebuah aktifitas pariwisata,
pariwisata budaya akan menarik wisatawan dari luar yang melakukan perjalanan
utamanya untuk menyenangkan diri dengan dana yang terbatas dan mungkin
mengetahui sedikit hal tentang pentingnya aset wisata yang akan dikunjunginya.
Suksesnya produk pariwisata budaya haruslah diletakkan pada konsep berpikir akan
’apa yang dipikirkan wisatawan’.
b. Penggunaan aset/warisan budaya
Secara prinsip, bangun pariwisata budaya menggunakan aset budaya suatu
komunitas atau bahkan suatu negara. The International Council on Monuments and
Sites (ICOMOS) mendefinisikan warisan budaya sebagai sebuah konsep yang luas yang
mencakup aset warisan budaya yang terlihat dan nyata (tangible) seperti lingkungan
alam dan budaya, tempat bersejarah, lanskap, situs, bangunan dan sejenisnya.
Berikutnya adalah aset warisan budaya yang tidak dapat terlihat tetapi dapat dirasakan
seperti tata nilai, norma, pengetahuan, pengalaman hidup, legenda, dan sejenisnya.
Aset warisan budaya ini mula-mula biasanya diidentifikasi dan dikonservasi
karena nilai intrinsiknya atau arti pentingnya bagi suatu komunitas dibandingkan
dengan nilai ekstrinsiknya sebagai atraksi wisata. Biasanya, potensi pariwisata dari
suatu aset budaya jarang disadari ketika pertama kali ditemukan. Pada titik ini,
umumnya dokumentasi arti penting aset budaya terkonsentrasi pada nilai estetikanya,
bentuk arsitekturnya, sejarahnya, fungsi sosialnya, nilai spiritualnya, nilai
pendidikannya dimana unsur pariwisata menempati bagian yang kurang penting di
bawah subset nilai pendidikan atau subset nilai sosial.
Salah satu paradok dari pariwisata budaya adalah di satu sisi keputusan untuk
pengembangan sektor ini harus dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan pariwisata,
tetapi di sisi lain aset budaya yang dijadikan modal dasarnya justru sering dikelola
dengan prinsip-prinsip manajemen warisan budaya. Konsekuensinya, sering muncul

14
ketidaksinkronan antara manajemen pariwisata dengan manajemen perlindungan aset
budaya. Berbagai kelompok masyarakat (termasuk wisatawan, etnis lokal dan
penduduk lokal lainnya) memandang aset budayanya dari berbagai perspektif dengan
beragam alasan tertentu dan oleh karenanya mengambil manfaat yang berbeda pula.
Konsekuensinya, usaha untuk memadukan konsep manajemen pariwisata dengan
manajemen perlindungan aset budaya menjadi lebih rumit. Pendekatan yang berlainan
ini dapat menjadi sumber masalah di lapangan.
c. Konsumsi produk dan pengalaman
Semua kegiatan pariwisata melibatkan aktifitas konsumsi baik berupa
’konsumsi pengalaman/kegiatan wisata’ atau ’konsumsi produk wisata’ (Urry 1990;
Richards 1996 dalam McKercher & du Cros, 2002: 8) dan pariwisata budaya dalam
hal ini tidak ada bedanya. Wisatawan yang terlibat dalam pariwisata budaya
menginginkan menikmati beragam pengalaman budaya. Untuk menfasilitasi hal ini, aset
dan warisan budaya harus ditransformasi ke dalam produk pariwisata. Proses
transformasi ini memerlukan sebuah proses mengubah atau mengkonversi sebuah
aset yang potensial menjadi sesuatu yang dapat berguna atau dapat dinikmati oleh
wisatawan.
Proses transformasi ini merupakan bagian integral dari keberhasilan dan
keberlanjutan dari produk pariwisata budaya. Tegasnya, transformasi ini perlu karena
terdapat perbedaan substantif antara aset budaya/warisan budaya dengan produk
pariwisata budaya. Aset budaya/warisan budaya merupakan aset yang belum
mengalami komodifikasi atau komersialisasi yang masih berupa aset mentah (bahan
baku) yang dapat diidentifikasi karena nilai intrinsiknya. Di sisi lain, produk pariwisata
budaya merupakan aset yang sudah ditransformasi atau dikomodifikasi secara spesifik
untuk dapat dikonsumsi atau dinikmati oleh wisatawan.
d. Wisatawan
Elemen terakhir dalam konsep pariwisata budaya adalah wisatawan. Beberapa
definisi pariwisata budaya menyangkut elemen wisatawan yang mempunyai
karakteristik khusus dimana motivasi utamanya dalam melakukan perjalanan wisata
adalah untuk mempelajari, memahami, mengalami, atau mengekplorasi budaya lain.
Beberapa pihak menyadari bahwa motivasi wisatawan dalam melakukan kegiatan
dalam pariwisata budaya terletak dari kontinum secara khusus memang untuk alasan-

15
alasan seperti di atas sampai pada kondisi dimana pariwisata budaya ’secara tidak
sengaja’ menjadi bagian elemen tertentu dari paket wisata yang diikutinya.
Kualitas pariwisata budaya sangat tergantung pada bagaimana kita menangani
elemen wisatawan ini. Harapan dan bayangan yang ada di pikiran wisatawan sebelum
mereka melakukan perjalanan wisata budaya sangat menentukan bagaimana
perilakunya terhadap budaya atau warisan budaya di tempat yang ingin dikunjunginya.
Oleh karenanya, penyediaan informasi yang benar, jujur, akurat dan handal mengenai
segala aspek yang menyangkut pariwisata budaya kepada calon wisatawan menjadi
sangat penting. Jika hal ini dilakukan dengan baik, terkadang justru memainkan peran
lebih penting dibandingkan keberadaan aset budaya itu sendiri. Hal inilah yang sering
dilakukan oleh pengelola pariwisata di luar negeri padahal aset budaya yang dijadikan
modal dalam industri pariwisata budayanya tidaklah selalu lebih baik dari yang kita
miliki karena pada hakekatnya setiap budaya memiliki kehususan dan sangat bersifat
unik.
2.3 PARIWISATA DAN BUDAYA: KOLABORATOR ATAU KOMPETITOR?
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata budaya adalah
mencari keseimbangan antara manajemen pariwisata dengan manajemen
budaya/warisan budaya. Lebih operasional, bagaimana memadukan sisi konsumsi akan
nilai ekstrinsik oleh wisatawan dengan upaya konservasi nilai intrinsik dari aset
budaya tersebut. Konflik kadang terjadi mengingat kedua aspek tersebut
menggunakan satu sumber daya yang sama yaitu aset budaya/warisan budaya.
Dalam bangun yang ideal, pariwisata budaya hanya bisa dibangun dengan baik
jika ada kolaborasi yang saling menguntungkan antara kedua elemen tersebut.
ICOMOS menyadari hal ini melalui statemennya sebagai berikut.
Tourism can capture the economic characteristics of heritage and harness these for conservation by generating funding, educating the community and influencing policy (ICOMOS 1999).
Dalam prakteknya, kemitraan antara elemen pariwisata dan elemen budaya bukanlah
sesuatu yang mudah terkadang bahkan tidak kompatibel. Kemitraan umumnya akan
berhasil ketika pemangku kepentingan yang terlibat terbatas dan mempunyai
pemahaman dan nilai yang sama akan permasalahan yang dihadapinya. Sebaliknya,

16
konflik atau potensi konflik lebih cenderung terjadi ketika begitu banyaknya
pemangku kepentingan terlibat dan mempunyai pemahaman beragam atau tindakan
salah satu pemangku kepentingan yang tidak diinginkan oleh yang lainnya karena
menghambat kemajuan atau merugikan pihak lain.
Berkaitan dengan pariwisata budaya, menurut Kerr (1994 dalam McKercher &
du Cros, 2002: 12), ketidaksinkronan antara kepentingan pariwisata dan kepentingan
konservasi sering terjadi sebagaimana tersirat sebagai berikut, ”what is good for
conservation is not necessarily good for tourism and what is good fo tourism is rarely good
for conservetion.” Dalam prakteknya, nilai-nilai budaya telah banyak yang
dikompromikan untuk keuntungan komersial dimana asset-aset budaya disajikan
sebagai produk-produk pariwisata yang bersifat komersial agar dapat dengan mudah
dikonsumsi oleh wisatawan. Sebaliknya, nilai-nilai pariwisata dikompromikan untuk
kepentingan konservasi asset budaya ketika nilai-nilai pariwisata dianggap akan
merusak eksistensi asset budaya tersebut. Menurut McKercher & du Cros (2002: 12),
dalam sejarah pariwisata budaya lebih banyak diwarnai oleh kompetisi pemakaian
sumberdaya yang sama dibandingkan dengan kolaborasi untuk mencapai keuntungan
bersama. Hal ini bersumber dari perbedaan substantif antara manajemen pariwisata
yang dianut dalam pengelolaan pariwisata budaya dengan manajemen warisan budaya
sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut.
Tabel 1. Perbandingan Manajemen Warisan Budaya dengan Manajemen Pariwisata
No Issues Cultural Heritage Management
Tourism Management
1 Structures • Public sector oriented
• Not for profit
• Private sector oriented
• Profit making 2 Goals • A broader social goal • Commercial goals 3 Key stakeholders • Community groups
• Heritage groups
• Minority ethnic/indigenious groups
• Local residents
• Organizations for heritage professional/local historical/religious leaders
• Business groups
• Nonlocal residents
• National tourism trade association, other industries bodies
4 Economic attitude to assets
• Existence values
• Conserve for their intrinsic values
• Use values
• Consume for their intrinsic or extrinsic appeal
5 Key user groups • Local residents • Non local residents
6 Employment background
• Social science/arts degrees • Business/marketing degrees
7 Use of asset • Value to community as a representation of tangible and intangible heritage
• Value to tourist as product or activity that can help brand a destination

17
8 International political bodies/NGOs
• ICOMOS/UNESCO (promote conservation of culture)
• WTO/WTTC (promote development of tourism)
Sumber: diadopsi dari McKercher & du Cros (2002: 14),
Berdasarkan perbandingan di atas, terlihat bahwa manajemen warisan budaya
bertujuan untuk melindungi dan memproteksi budaya/warisan budaya sebagai
representasi dari suatu komunitas tertentu untuk kepentingan masa depan. Tujuannya
adalah untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas. Manajemen budaya/
warisan budaya biasanya dikelola oleh organisasi nirlaba (misalnya oleh dinas
kebudayaan) yang dijalankan oleh pemerintah, kelompok masyarakat atau kelompok
etnik tertentu yang memperlakukan aset budaya lebih karena nilai intrinsik aset
budaya tersebut bagi masyarakat dibandingkan dengan pertimbangan komersial.
Sebaliknya, dalam manajemen pariwisata, kegiatan yang dilakukan lebih berupa
aktifitas-aktifitas komersial yang didominasi oleh sektor swasta yang didorong oleh
hasrat mendapatkan keuntungan atau keinginan pemerintah untuk mencapai tujuan-
tujuan ekonomi tertentu. Oleh karenanya, dalam manajemen pariwisata lebih
cenderung menggunakan nilai aset budaya untuk tujuan komersial.
Hubungan antara manajemen budaya/warisan budaya dengan manajemen
pariwisata memungkinkan beberapa kemungkinan. Menurut Budowksi (1977 dalam
McKercher & du Cros, 2002: 15) terdapat tiga kemungkinan hubungan yaitu:
1. Coexistence
Hubungan ini cenderung terjadi pada tahap awal pengembangan pariwisata
ketika hanya beberapa operator pariwisata membawa wisatawan dalam jumlah kecil.
Karena jumlah wisatawan masih sedikit maka kontak antara wisatawan dengan
kebudayaan lokal juga kurang intensif dan masif. Konsekuensinya, pariwisata
dipandang sebagai aktifitas yang tidak mengandung potensi ancaman yang besar.
2. Conflict
Seiring bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan, potensi konflik mulai
nampak terutama jika tidak adanya perencanaan manajemen pariwisata dan
manajemen pengelolaan budaya/warisan budaya yang terpadu. Konflik mulai
meningkat eskalasinya ketika pariwisata dianggap mulai mempunyai potensi merusak
atau mengancam keberadaan budaya/warisan budaya suatu komunitas.

18
3. Symbiotic
Hubungan ini muncul ketika pariwisata dipandang sebagai bagian
komplementer yang tidak terpisahkan dari manajemen pengelolaan budaya/warisan
budaya untuk mencapai tujuan manajemen secara terpadu. Hubungan yang simbiotik
ini jarang terjadi walau bukan mustahil dan terjadi sebagai hasil dari campur tangan
manajemen secara langsung dan terpadu.
Kemitraan antara sisi pariwisata denan sisi konservasi budaya tidaklah terjadi
secara spontan dan begitu saja melainkan mesyaratkan intervensi dari penentu
kebijakan baik dari sisi pariwisata maupun dari sisi konservasi budaya. Sebaliknya,
absennya sisi manajemen yang baik cenderung menjadi pemicu hubungan yang
konfliktual antara pariwisata dengan budaya.
Menurut McKercher & du Cros (2002: 17-21), terdapat tujuh tahapan sifat
hubungan antara pariwisata dengan budaya bergerak dari kontinum full parthnership
ke kontinum open conflict sebagai berikut.
1. Full cooperation
Kondisi ini merupakan kondisi ideal dimana pariwisata dan budaya saling
mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Umumnya lebih mudah dicapai jika
pemangku kepentingan tidak terlalu banyak, baik dalam jumlah maupun dalam
melakukan persaingan. Tujuan manajemen, baik dari sisi manajemen pariwisata
maupun manajemen konservasi budaya dapat didefiniskan dengan jelas dan bersifat
saling dukung dan disetujui oleh semua pihak. Tujuan-tujuan ekonomi dihargai dan
berjalan secara harmonis dengan tujuan-tujuan konservasi.
Hirarki manajemen didefinisikan dengan jelas sehingga menjamin tujuan kedua
belah pihak tercapai secara seimbang. Kemitraan yang sungguh-sungguh antara
manajemen pariwisata dengan manajemen budaya/warisan budaya sangat sulit
diwujudkan tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Dalam beberapa kasus, salah
satunya—apakah dari sisi pariwisata atau sisi budaya—harus mendominasi dari sisi
manajemen sehingga sisi yang lain harus dimodifikasi untuk mendukung tercapainya
tujuan manajemen secara keseluruhan.
Di satu sisi, manajemen pariwisata menjamin sedemikian rupa sehingga semua
fasilitas pendukung pariwisata (termasuk aset budaya) tersedia untuk dapat
dikonsumsi wisatawan. Di sisi lain manajemen konservasi budaya menjaga agar

19
konsumsi oleh wisatawan tersebut diijinkan sebatas pada konsumsi yang tidak
menimbulkan degradasi atau kerusakan pada aset budaya yang dilindungi.
2. Working relationship
Baik pemangku kepentingan dari manajemen pariwisata maupun dari
manajemen warisan budaya menyadari mereka berbagi aset bersama. Masing-masing
menyadari walau mereka di satu sisi mempunyai visi yang berbeda juga memiliki
banyak persamaan. Seiring perjalanan waktu, working relationship terbentuk diantara
keduanya dengan masing-masing pemangku kepentingan mencoba mengakomodasi
kepentingan pihak lain agar saling menguntungkan.
3. Peaceful coexistence
Bentuk hubungan ini timbul jika pemangku kepentingan baik untuk
kepentingan manajemen pariwisata maupun manajemen warisan budaya menggunakan
sumberdaya yang sama tetapi belum merasakan perlunya bekerjasama. Kondisi ini
memungkinkan terjadi jika kunjungan wisatawan masih rendah atau wisatawan
menkonsumsi produk wisata masih di bawah ambang kapasitas maksimumnya. Atau,
aktivitas manajemen warisan budaya tidak bertentangan dengan penggunaannya untuk
pariwisata. Misalnya, suatu peninggalan budaya berupa bangunan bersejarah yang
dikunjungi wisatawan dalam jumlah besar. Disini, kunjungan wisatawan berdampak
kecil terhadap upaya pelestariannya. Sebaliknya, adanya kunjungan wisatawan justru
dijadikan justifikasi untuk keberlanjutan perlindungan dan pelestariannya. Hal ini
memungkinkan karena manajemen warisan budaya mempunyai larangan yang minimal
bagi wisatawan di obyek wisata tersebut.
4. Parallel existence
Tipe hubungan ini terjadi ketika pariwisata dan manajemen warisan budaya
berjalan secara independen atau mandiri. Di sisi lain, wisatawan memiliki minat yang
kecil terhadap aset budaya di wilayah obyek wisata berada. Situasi ini berjalan jika
aktifitas pariwisata masih sedikit atau jika aktifitas pariwisata terfokus pada atribut
selain aset budaya seperti pantai, resor, rekreasi, judi, pemandangan alam dan
sejenisnya. Pariwisata budaya tidak dianggap sebagai produk pariwisata sehingga tidak
dipromosikan sehingga aset budaya tersebut sangat kecil dimanfaatkan.
5. Mild annoyance
Hal ini terjadi jika tindakan satu pemangku kepentingan konta-produktif
terhadap tujuan pemangku kepentingan lainnya. Situasi ini kemungkinan akan berakhir

20
pada situasi konflik. Jika situasi ini terjadi tidak membuat seseorang menghentikan
aktifitas wisatanya tetapi tingkat kepuasan yang didapat sangat rendah. Pemangku
kepentingan merasa perkembangan situasi mengarah pada keadaan yang tidak
diinginkan. Misalnya, jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu obyek wisata atau
aset budaya semakin banyak sedangkan dilain pihak mulai mengganggu kenyamanan
yang dirasakan oleh masyarakat setempat.
6. Nascent conflict
Merupakan situasi antara mild annoyance dan open conflict. Situasi ini terjadi jika
aktifitas satu pemangku kepentingan yang terlibat mempunyai dampak negatif atau
bahkan menghancurkan eksistensi pihak lain. Situasi ini juga dipicu jika hubungan
antara manajemen pariwisata dan manajemen warisan budaya berubah secara
fundamental. Misal, keputusan untuk memasukkan suatu warisan budaya dalam paket
wisata budaya tanpa konsultasi dengan pengelolanya akan memicu situasi nascent
conflict. Demikian juga jika keputusan suatu pihak untuk melakukan atau tidak
melakukan suatu tindakan yang nampaknya menguntungkan pihaknya menjadi biaya
langsung yang harus ditanggung pihak lainnya. Hal ini juga akan memicu kondisi
nascent conflict.
7. Full-scale/open conflict
Merupakan situasi yang menjadi puncak pertentangan antara dua kepentingan
pariwisata dan warisan budaya. Konflik cenderung terjadi ketika terdapat perbedaan
cara pandang (baik yang nyata maupun yang diyakini ada) bagaimana seharusnya
mereka mengelola aset yang ada. Hal lain yang memicu konflik diantaranya perbedaan
cara pandang mengenai hal eksklusifitas atas aset budaya, perbedaan bentuk aktifitas
yang dilakukan, dan perbedaan niat dan motivasi dalam menjalankan suatu aktifitas.
Kebangkitan pariwisata sebagai pemakai dominan dari suatu aset budaya yang
cenderung mengalahkan kepentingan manajemen warisan budaya juga cenderung
memicu konflik. Sebaliknya, pembatasan kunjungan wisatawan yang terlalu ketat pada
suatu obyek budaya sebagai daya tarik wisata juga cenderung memicu konflik.