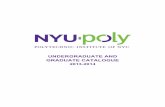UNIMED Undergraduate 22550 5 BAB II
Transcript of UNIMED Undergraduate 22550 5 BAB II
4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tumbuhan Ranti (Solanum nigrum L.)
Ranti atau leunca (Solanum nigrum L.) adalah tumbuhan anggota suku
terung-terungan (Solanaceae) yang buahnya dikenal sebagai sayuran dan juga
menjadi bahan pengobatan. Tumbuhan ini berasal dari Asia Barat, dibawa ke
Indonesia melalui Malaysia dan telah menyebar ke seluruh penjuru dunia karena
mampu hidup dalam kondisi tertekan. Dalam bahasa Inggris ia paling banyak
dikenal sebagai (European) black nightshade (Anonim (1), 2012).
2.1.1. Nama Umum
Indonesia : Ranti
Sunda : Leunca
Inggris : Black nightshade
Melayu : Ranti
Filipina : Kama-kamatisan
Cina : Long Kui (Anonim (2), 2012).
2.1.2. Sistematikan Tumbuhan
Kingdom : Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)
Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)
Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)
Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil)
Sub Kelas : Asteridae
Ordo : Solanales (suku terung-terungan)
Famili : Solanaceae
Genus : Solanum
Spesies : Solanum nigrum L. (Prima, 2012).
5
2.1.3. Morfologi Tumbuhan
Tanaman ini termasuk ke dalam golongan semak, dengan tinggi lebih
kurang 1,5 m. Memiliki akar tunggang dengan warna putih kocoklatan. Batang
tegak, berbentuk bulat, lunak, dan berwarna hijau. Berdaun tunggal, lonjong, dan
tersebar dengan panjang 5-7,5 cm ; lebar 2,5-3,5 cm. Pangkal dan ujung daun
meruncing dengan tepi rata. Pertulangan daun menyirip. Daun mempunyai
tangkai dengan panjang ± 1 cm dan berwarna hijau. Bunga berupa bunga
majemuk dengan mahkota kecil, bangun bintang, berwarna putih, benang sari
berwarna kehijaunan dengan jumlah 5 buah. Tangkai bunga berwarna hijau pucat
dan berbulu. Buah berbentuk bulat, jika masih muda berwarna hijau, dan
berwarna hitam mengkilat jika sudah tua ukurannya kira-kira sebesar kacang kapri
Biji berbentuk bulat pipih, kecil-kecil, dan berwarna putih. (Prima, 2012).
Gambar 2.1. Tumbuhan ranti
2.1.4. Kandungan Kimia dan Manfaat Ranti (Solanum nigrum L.)
Leunca (Solanum nigrum L.) mengandung solanine, solasonine,
solamargine dan chaconine. Serta diketahui pada buah leunca yang belum matang
mengandung steroidal alkaloid solasodine serta steroidal sapogenin diosgenin dan
tigogenin. Serta terdapat kandungan signifikan dari diosgenin (1,2%) dan
6
solasodine (0,65%) pada buah leunca (Solanum nigrum L.) yang masih hijau
(belum matang) (Prima, 2012).
Struktur berbagai macam metabolit yang dihasilkan dari tumbuhan
Solanum nigrum L. adalah sebagai berikut:
Gambar 2.2. Struktur Kimia α-Solanine, solasonine, solamargine, α-
chaconine, solasodine, diosgenin dan tigogenin
Disamping penggunaannya sebagai ramuan tradisional, beberapa studi
ilmiah menunjukkan, leunca memiliki aktivitas antiulserogenik yang berhubungan
dengan lambung, sistem saraf pusat dan sebagai agen antineoplastik dan
memiliki peran sitoprotektif melawan kerusakan sel ginjal. Rebusan air daunnya
juga dapat melancarkan buang air kecil, menyembuhkan sakit perut, batuk dan
mampu pula menurunkan tekanan darah tinggi serta bermanfaat mengurangi
jumlah sel darah putih dalam tubuh (Johan, 2005).
Kandungan metabolit sekundernya seperti Solasodine mempunyai efek
menghilangkan sakit (analgetik), penurunan panas, antiradang, dan antishok.
7
Solamargine dan solasonine mempunyai efek antibakteri, sedangkan solanine
sebagai antimitosis. Senyawa-senyawa itu bisa mengatasi gangguan kanker, yakni
kanker payudara, leher rahim, lambung dan saluran pernapasan (Kabayan, 2009).
2.2. Imunostimulan
Imunostimulan atau imunomodulator adalah senyawa tertentu yang dapat
meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh baik secara spesifik maupun non
spesifik. Yang terutama terjadi adalah induksi non spesifik baik mekanisme
pertahanan seluler maupun humoral. Pertahanan non spesifik terhadap antigen ini
disebut paraimunitas, dan zat bersangkutan disebut penginduksi paraimunitas.
Induktor semacam ini biasanya tidak atau sedikit sekali kerja antigennya, bahkan
sebagian bekerja sebagai mitogen yaitu menaikkan proliferasi sel yang berperan
pada imunitas. Sel tujuan adalah makrofag, granulosit, limfosit T dan B; karena
induktor paramunitas ini terutama menstimulasi mekanisme pertahanan seluler.
Mitogen ini dapat bekerja langsung maupun tak langsung (misalnya melalui
sistem komplemen atau limfosit, melalui produksi interferon atau enzim
lisosomal) untuk meningkatkan fagositosis mikro dan makro. Mekanisme
pertahanan spesifik maupun non spesifik umumnya saling berpengaruh. Dalam
hal ini pengaruh pada beberapa sistem pertahanan mungkin terjadi, hingga
mempersulit penggunaan imunomodulator ini dalam praktek (Widianto, 1987).
Imunomodulator tampak menjadi bagian terpenting dalam dunia
pengobatan. Imunomodulator membantu tubuh untuk mengoptimalkan fungsi
sistem imun yang merupakan sistem utama yang berperan dalam pertahanan tubuh
di mana kebanyakan orang mudah mengalami gangguan sistem imun.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Maratani, (2006) dikatakan
bahwa dalam daun mahkota dewa terkandung alkaloid, saponin dan polyfenol.
Flavonoid memiliki bermacam-macam efek, antara lain sebagai imunostimulan.
Penelitian ini juga dilakukan oleh Sanjaya, (2006) terhadap buah mahkota dewa
(Phaleria macrocarpa). Dikatakan bahwa buah mahkota dewa mengandung
saponin dan flavonoid, kedua senyawa tersebut dipercaya paling berperan sebagai
8
imunostimulan sehingga dapat menurunkan jumlah koloni kuman pada organ
yang terinfeksi, terutama hepar.
Penelitian lain terkait imunostimulan juga telah dilakukan oleh Tyastuti,
dkk., (2006) yang mengatakan bahwa kemampuan propolis dalam melawan
mikrobia dan menstimulasi imun karena kandungan flavonoidnya yang tinggi.
Penelitian oleh Jenn-Haung, (2002) dikatakan bahwa alkaloid memiliki peran
dalam peningkatan respon iminunitas tubuh. Suhirman dan winarti, (2009) juga
mengatakan bahwa, komponen aktif metabolit sekunder dalam meniran adalah
flavonoid, lignan, isolignan, dan alkaloid. Komponen yang bersifat
imunomodulator adalah dari golongan flavonoid, yang mampu meningkatkan
sistem kekebalan tubuh hingga mampu menangkal serangan virus, bakteri atau
mikroba lainnya.
2.3. Ekstraksi
Ekstraksi adalah penyarian zat-zat aktif dari bagian tumbuhan. Adapun
tujuan dari ekstraksi yaitu untuk menarik komponen kimia yang terdapat dalam
suatu sampel. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat
padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka,
kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut.
Secara umum, terdapat beberapa keadaan dalam menentukan tujuan
ekstraksi, yaitu:
1. Senyawa kimia telah diketahui identitasnya untuk diekstraksi dari tumbuhan.
Dalam kasus ini, prosedur yang telah dipublikasikan dapat diikuti dan dibuat
modifikasi yang sesuai untuk mengembangkan proses atau menyesuaikan
dengan kebutuhan pemakai.
2. Bahan diperiksa untuk menemukan kelompok senyawa kimia tertentu,
misalnya terpenoid, alkaloid, flavanoid atau saponin, meskipun struktur kimia
sebetulnya dari senyawa ini bahkan keberadaannya belum diketahui. Hal ini
diikuti dengan uji kimia atau kromatografik yang sesuai untuk kelompok
senyawa kimia tersebut.
9
3. Sifat senyawa yang akan diisolasi belum ditentukan sebelumnya dengan cara
apapun. Situasi ini (utamanya dalam program skrining) dapat timbul jika
tujuannya adalah untuk menguji organisme, baik yang dipilih secara acak atau
didasarkan pada penggunaan tradisional untuk mengetahui adanya senyawa
dengan aktivitas biologi khusus (Sudjadi dalam Maniur, 1986).
Penyarian zat-zat aktif tumbuhan dengan metode ekstraksi dapat
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
1. Maserasi
Maserasi merupakan proses perendaman sampel menggunakan pelarut
organik pada temperatur ruangan. Dengan perendaman sampel, akan terjadi
pemecahan dinding sel dan membran sel karena perbedaan tekanan antara di
dalam dan luar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan
terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat
diatur lama perendaman yang dilakukan.
2. Perkolasi
Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan
cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Kekuatan yang
berperan pada perkolasi antara lain: gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan
permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler dan daya geseran (friksi). Cara
perkolasi lebih baik dibandingkan dengan cara maserasi karena:
a. Aliran cairan penyari menyebabkan adanya pergantian larutan yang terjadi
dengan larutan yang konsentrasinya lebih rendah, sehingga meningkatkan
derajat perbedaan konsentrasi.
b. Ruangan diantara serbuk-serbuk simplisia membentuk saluran tempat
mengalir cairan penyari.karena kecilnya saluran kapiler tersebut,maka
kecepatan pelarut cukup untuk mengurangi lapisan batas,sehingga dapat
meningkatkan perbedaan konsentrasi (Irwanto, 2010).
Perkolasi dengan cara panas dapat dilakukan dengan beberapa cara
sebagai berikut:
10
a. Refluks
Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya
selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan
adanya pendingin balik.
b. Sokletasi
Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru,
umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan
jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.
c. Digesti
Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada
temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu pada temperatur 40-
50°C.
d. Infudasi
Infuudasi adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas
air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur 96-98°C)
selama waktu tertentu (15-20 menit).
e. Dekok
Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama dan temperatur sampai
titik didih air (Saridewi, 2011).
Proses ekstraksi didasarkan pada kelarutan komponen terhadap
komponen lain dalam campuran. Kelarutan suatu komponen tergantung pada
derajat kepolarannya. Tingkat polaritas pelarut dapat ditentukan dari nilai
konstanta dielektrik pelarut (Saridewi, 2011). Urutan tingkat kepolaran beberapa
pelarut organik berdasarkan nilai konstanta dieletriknya dapat dilihat pada tabel
2.1 berikut.
11
Tabel 2.1. Nilai Konstanta Dieletrik Berbagai Pelarut Organik
No Pelarut Rumus kimia Titik didih Konstanta dieletrik
1. Heksana CH3-CH2-CH2-CH2-
CH2-CH3
690C 2,0
2. Benzena C6H6 800C 2,3
3. Toluena C6H5-CH3 1110C 2,4
4. Dietil eter CH3CH2-O-CH2-CH3 350C 4,3
5. Kloroform CHCl3 610C 4,8
6. Etil asetat CH3-C(=O)-O-CH2-
CH3
770C 6,0
7. n-butanol CH3-CH2-CH2-CH2-
OH
1180C 18
8. n-propanol CH3-CH2-CH2-OH 970C 20
9. Etanol CH3-CH2-OH 790C 30
10. Metanol CH3-OH 650C 33
11. Air H-O-H 1000C 80
Sumber : Anonim (3), 2012
2.4. Uji Fitokimia
Fitokimia merupakan suatu disiplin ilmu yang bidang perhatiannya
adalah aneka ragam senyawa organik yang dibentuk oleh tumbuhan meliputi
struktur kimianya, biosintesisnya, perubahan serta metabolismenya, penyebaran
secara ilmiah dan fungsi biologisnya. Setiap tahap pengerjaan fitokimia
merupakan bagian intergral dari seluruh rangkaian pengerjaan dan merupakan
aspek yang berhubungan. Hasil setiap tahap berkaitan satu sama lain, oleh
karenanya harus dilakukan dengan cara yang tepat dan teknik yang benar.
Penapisan fitokimia dimulai dengan pengumpulan sampel sebanyak
mungkin. Oleh karena kegiatan ini memakan waktu cukup lama maka penapisan
12
fitokimia memegang peranan terbesar dari kegiatan kimia bahan alam. Sekalipun
kegiatan ini bertitik tolak pada daya tarik kimiawi, hal ini tidaklah mengurangi
manfaat hasil penelitian. Spesies-spesies yang telah dianalisis secara fitokimia
akan diinventarisasi untuk ditelaah lebih lanjut mengenai struktur kimia senyawa-
senyawa aktifnya.
2.5. Senyawa Alkaloid, Flavonoid dan Terpenoid
2.5.1. Senyawa Alkaloid
Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang terbanyak
ditemukan di alam. Hampir seluruh senyawa alkaloid berasal dari tumbuh-
tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan. Semua alkaloid
mengandung paling sedikit satu atom nitrogen yang biasanya bersifat basa dan
dalam sebagian besar atom nitrogen ini merupakan bagian dari cincin heterosiklik.
Hampir semua alkaloida yang ditemukan di alam mempunyai keaktifan
biologis tertentu, ada yang sangat beracun tetapi ada pula yang sangat berguna
dalam pengobatan. Misalnya kuinin, morfin dan stiknin adalah alkaloida yang
terkenal dan mempunyai efek sifiologis dan psikologis. Alkaloida dapat
ditemukan dalam berbagai bagian tumbuhan seperti biji, daun, ranting dan kulit
batang. Alkaloida umumnya ditemukan dalam kadar yang kecil dan harus
dipisahkan dari campuran senyawa yang rumit yang berasal dari jaringan
tumbuhan (Lenny, 2006).
Gambar 2.3. Piridin
Kebanyakan alkaloid yang telah diisolasi berupa padatan kristal dengan
titik lebur yang tertentu atau mempunyai kisaran dekomposisi. Sedikit alkaloid
yang bersifat amorf dan beberapa seperti nikotin dan koniin berupa cairan
(Sastrohamidjojo, 1996).
13
2.5.2. Senyawa Flavonoid
Senyawa flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar
yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu
dan biru dan sebagai zat warna kuning yang ditemukan pada tumbuhan (Lenny,
2006). Flavonoid merupakan kandungan khas tumbuhan hijau dengan
mengecualikan alga dan hornwort. Flavonoid sebenarnya terdapat pada semua
bagian tubuh tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nektar,
bunga, buah buni dan biji ( Markham, 1988).
Senyawa Flavonoid adalah senyawa yang mengandung C15 terdiri atas
dua inti fenolat yang dihubungkan dengan tiga satuan karbon. Cincin A memiliki
karakterisasi bentuk hidroksilasi phloroglusinol atau resorsinol, dan cincicn B
biasanya 4,3,4- atau 3,4,5-terhidroksilasi (Sastrohamidjojo, 1996).
Gambar 2.4. Struktur Flavonol
Senyawa-senyawa flavonoid terdiri dari beberapa jenis tergantung pada
tingkat oksidasi dari rantai propana dari sistem 1,3-diarilpropana. Flavon, flavonol
dan antosianidin adalah jenis yang banyak ditemukan di alam sehingga sering
disebut sebagai flavonoida utama. Banyaknya senyawa flavonoida ini disebabkan
oleh berbagai tingkat hidroksilasi, alkoksilasi atau glikosilasi dari struktur tersebut
(Lenny, 2006).
2.5.3. Senyawa Terpenoid
Terpenoida adalah merupakan komponen tumbuh-tumbuhan yang
mempunyai bau dan dapat diisolasi dari bahan nabati dengan penyulingan disebut
sebagai minyak atsiri. Minyak atsiri yang berasal dari bunga pada awalnya dikenal
dari penentuan struktur secara sederhana, yaitu dengan perbandingan atom
hidrogen dan atom karbon dari suatu senyawa terpenoid yaitu 8 : 5 dan dengan
14
perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut adalah golongan
terpenoid.
Gambar 2.5. Skualenadan Ursana
Sebagian besar terpenoid mempunyai kerangka karbon yangg dibangun
oleh dua atau lebih unit C5 yang disebut isopren. Unit C5 ini dinamakan demikian
karena kerangka karbonnnya sama seperti senyawa isopren (Lenny, 2006).
Senyawa Saponin
Saponin merupakan senyawa glikosida triterpenoida ataupun glikosida
steroida yang merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun
serta dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan
menghemolisa sel darah merah. Pola glikosida saponin kadang-kadang rumit,
banyak saponin yang mempunyai satuan gula sampai lima dan komponen yang
umum ialah asam glukuronat (Harborne dalam Yenni, 1996). Saponin merupakan
senyawa berasa pahit menusuk dan dapat menyebabkan bersin dan bersifat racun
bagi hewan berdarah dingin, banyak di antaranya digunakan sebagai racun ikan
(Gunawan dan Mulyani, 2004).
Gambar 2.6. Sapogenin Triterpenoida
Dikenal ada dua jenis saponin yaitu, glikosida triterpenoid alkohol dan
glikosida struktur steroid tertentu. Kedua jenis saponin ini larut dalam air dan
etanol, tetapi tidak larut dalam eter (Patmawinata, 1995).
15
2.6. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik pemisahan komponen-
komponen campuran senyawa-senyawa yang melibatkan partisi suatu senyawa di
antara padatan penyerap (adsorbent, fasa diam) yang dilapiskan pada pelat kaca
atau plastik kaku dengan suatu pelarut (fasa gerak) yang mengalir melewati
adsorbent (padatan penyerap). Pengaliran pelarut dikenal sebagai proses
pengembangan oleh pelarut (elusi). Karena kesederhaan dan kecepatan
analisisnya, KLT mempunyai peranan penting dalam pemisahan senyawa-
senyawa yang volatilitasnya relatif rendah, baik senyawa organik maupun
senyawa anorganik.
Di dalam analisis dengan KLT, suatu contoh dalam jumlah yang sangat
kecil ditempatkan (sebagai titik noda) di atas permukaan pelat tipis fasa diam
(adsorbent), kemudian pelat diletakkan dengan tegak dalam bejana pengembang
yang berisi sedikit pelarut pengembang. Oleh aksi kapiler, pelarut mengembang
naik sepanjang permukaan lapisan pelat dan membawa komponen-komponen
contoh. Komponen-komponen contoh memanjat pelat KLT dengan kecepatan
yang berbeda-beda, tergantung pada kelarutan komponen dalam pelarut dan
derajat kekutan komponen teradsorbsi pada fasa diam. Hasilnya adalah sederetan
bercak-becak (noda-noda) yang tegak lurus terhadap permukaan pelarut dalam
bejana (Firdaus, 2011).
Kecepatan senyawa-senyawa sebagai komponen-komponen contoh
memanjat pelat dibandingkan dengan kecepatan pelarut yang mendahuluinya.
Harga perbandingan ini dikenal sebagai harga Rf, dan didefisikan sebagai:= ℎ ℎℎ ℎ