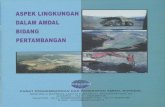PENGEMBANGAN KEBIJAKAN AMDAL DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
-
Upload
panduaninstalasi -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of PENGEMBANGAN KEBIJAKAN AMDAL DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN AMDAL
DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN
PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
YUSNI YETTI
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2008
2
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI
Saya yang tertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi yang berjudul Pengembangan Kebijakan AMDAL dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir disertasi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Bogor, April 2008
Yusni Yetti P062040304
3
ABSTRACT
Yusni Yetti. 2008. Policy Development of EIA in Protecting Environmental Damage on Oil and Gas Activities. Under Advisory Committee of Syamsul Ma’arif as Chairman. Surjono Hadi Sutjahjo and Imam Santosa as Members. Environment Impact Assessment (EIA) is a study for high and important impact any development process. The objectives of the research were to formulate the EIA policy to protect the negative impact on the environment in the oil and gas activities. The methods of the research were: 1) principle component analysis, 2) analytical hierarchy process, 3) focus group discussion and 4) total economic valuation. The results of the research was found that the important components to develop EIA policy of oil and gas were arranging efficiency, completing of document, document substantial, community involvement mechanism, compiler team of EIA, developing of EIA method, environment economic value, emergency, waste management technology, simplification of arrangement, increasing of human resources, law enforcement and contribution of oil and gas activities. Formulation to policy development on effective and efficient of EIA to environment damage protection on oil and gas activities consist of, 1) strategy to quality improvement of EIA document with developing EIA method including ecology, economic and social aspects. Method of main issue on Term of Reference of Environmental Impact Analysis, method of estimation and impact evaluation on Environmental Impact Analysis document, alternative technology on Environmental Management Planning and institution on Environmental Monitoring Planning. Complier quality improving EIA consist of independent, competence, and composition aspects, and then necessary integration of emergency on technical guide of arrangement of EIA, 2) strategy to law enforcement and institution consist of quality improving of human resources, center EIA commission specially (environmental ministry ), and technical team (energy and resources ministry), implementation of administration and punishment sanction (c.g Law No. 23/1997 about is Environmental Management), community involvement mechanism improving, and supervise institution of environmental management planning and environmental monitoring planning implementation 3) strategy to arrangement procedure completing of EIA oil and gas consist of time of arrangement to document agreement, time of community publication and agreement to EIA study arrangement by independent institution. Key words: Policy, EIA, Oil and Gas
4
RINGKASAN Yusni Yetti. 2008. Pengembangan Kebijakan AMDAL dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas. Di bawah bimbingan Syamsul Ma’arif, Surjono Hadi Sutjahjo dan Imam Santosa. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut. AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan perencanaan usaha atau kegiatan serta merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha. AMDAL di Indonesia telah diterapkan lebih dari 20 tahun, namun demikian berbagai hambatan dan masalah dalam penerapannya masih terjadi. Kualitas komisi penilai AMDAL yang sangat beragam kemampuannya sangat berpengaruh terhadap proses penilaian dokumen AMDAL selama ini, tidak adanya kriteria dan indikator penilaian yang standar, menjadikan proses penilaian AMDAL menjadi sangat subyektif. Tujuan penelitian adalah merumuskan kebijakan AMDAL yang efektif dan efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan tahapan penelitian sebagai berikut: review kebijakan AMDAL saat ini, analisis kualitas dokumen AMDAL migas, analisis kinerja lingkungan implementasi AMDAL kegiatan migas, analisis kebutuhan stakeholders terhadap kebijakan AMDAL migas dimasa mendatang dan merumuskan strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas.
Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari sampai September 2007. Penelitian dilakukan pada tujuh lokasi kegiatan usaha migas, yakni: 1) Pertamina Plaju Palembang Sumatera Selatan, 2) PT. CPI Duri Riau, 3) Suryaraya Teladan Muara Enim Sumatera Selatan, 4) Lapindo Berantas Sidoarjo Jawa Timur, 5) Expan Toili Morowali Sulawesi Tengah, 6) BP Tangguh Sorong Papua dan 7) Hess Pangkah Gresik Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian terdiri atas: 1) principle component analysis, 2) analytical hierarchy process, 3) focus group discussion dan 4) total economic valuation.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan AMDAL saat ini memiliki beberapa kelemahan dalam hal pedoman dan petunjuk teknis penyusunan AMDAL, PP No.27 tahun 1999, Permen LH No.11 tahun 2006, Permen LH No.08 tahun 2006, Kepmen ESDM No.1457 tahun 2000, Kepdal No.229 tahun 1996 dan Kepdal No.08 tahun 2000, antara lain: penentuan dampak penting, efisiensi dalam penyusunan, kedudukan komisi AMDAL, metode pelingkupan dan metode studi yang digunakan, aspek sosial ekonomi, mekanisme keterlibatan masyarakat, serta belum diaplikasikannya analisis valuasi ekonomi lingkungan dan pengkajian keadaan darurat. Hasil analisis kualitas dokumen diperoleh enam dokumen dikategorikan kurang baik yakni dokumen AMDAL PT.CPI Duri, Pertamina Plaju, Suryaraya Teladan, Lapindo Brantas, BP Tangguh dan Hess Pangkah, serta satu dokumen dikategorikan cukup baik yakni dokumen AMDAL Expan Toili, sedangkan hasil analisis kinerja lingkungan implementasi AMDAL pada enam lokasi kegiatan usaha migas diperoleh kualitas limbah cair, kualitas udara dan kebisingan di bawah baku mutu, untuk aspek sosial ekonomi menunjukkan peningkatan yang signifikan khususnya kontribusi PDRB,
5
sementara pendidikan dan kesehatan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.
Kebutuhan stakeholders AMDAL migas di masa mendatang antara lain: RKL/RPL secara dinamis dapat diperbaharui seiring dengan perubahan teknologi yang digunakan, simplifikasi pembahasan dan persetujuan dokumen AMDAL migas, peningkatan SDM komisi AMDAL pusat, mekanisme keterlibatan masyarakat lokal yang jelas, AMDAL sebagai dokumen yang berkekuatan hukum, pengembangan metodologi AMDAL migas, perlu akreditasi lembaga penyusun AMDAL migas, pengkajian nilai ekonomi lingkungan, serta perlunya mengintegrasikan kajian keadaan darurat dengan dokumen AMDAL.
Pengembangan kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas dirumuskan kebijakan AMDAL yang efektif dan efisien meliputi: a) Peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas dengan memperbaiki metode-metode di dalam penyusunan AMDAL untuk aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Metode penentuan isu pokok untuk kerangka acuan, metode prakiraan dan evaluasi dampak untuk dokumen ANDAL, teknologi alternatif untuk RKL dan institusi/kelembagaan untuk RPL. Selain itu juga diperlukan peningkatan kualitas penyusun AMDAL migas yang mencakup independensi, kompotensi dan komposisi serta perlunya pengintegrasian kajian keadaan darurat/emergency di dalam AMDAL dan dicantumkan dalam pedoman teknis penyusunan AMDAL migas. b) Penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL migas meliputi penguatan sumberdaya manusia, khususnya komisi AMDAL pusat (KLH) dan tim teknis AMDAL migas, penerapan sanksi administrasi dan pidana sesuai UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbaikan mekanisme keterlibatan masyarakat dan kelembagaan pengawas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan usaha migas. c) Penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL meliputi waktu penyusunan persetujuan dokumen, waktu pengumuman masyarakat serta penunjukan pelaksana studi AMDAL oleh lembaga independen.
6
© Hak cipta milik IPB, tahun 2008
Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya
tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
7
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN AMDAL
DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN
PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
Oleh:
Yusni Yetti P062040304
Disertasi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2008
8
Penguji Ujian Tertutup : Dr. Ir. Etty Riani, MS. (Sekretaris PS. PSL SPs IPB)
Penguji Ujian Terbuka : Prof. Dr. Ir. H. Kahar Mustari, MS. (Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNHAS) : Dr. Ir. Irwandi Idris, M.Si. (Sekretaris Direktorat Jenderal KP3K DKP.RI)
9
Judul Disertasi : Pengembangan Kebijakan AMDAL dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas
Nama : Yusni Yetti
NIM : P062040304
Program Studi : Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Disetujui,
Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Ir. Syamsul Ma’arif, M.Eng. Ketua
Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS. Dr. Ir. Imam Santosa, MS. Anggota Anggota
Diketahui,
Ketua Program Studi Dekan SPs
Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS. Prof. Dr. Khairil Anwar Notodiputro, MS.
Tanggal ujian: 29 Februari 2008 Tanggal lulus:
10
KATA PENGANTAR
Disertasi ini merupakan penelitian kebijakan (policy research) dengan metode deskriptif dan teknik analisis decission making. Obyek penelitian adalah kebijakan AMDAL pada kegiatan usaha migas. Melalui bidang kebijakan publik diterangkan dan dievaluasi peran AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas.
Untuk menentukan alternatif kebijakan yang efektif dan efisien dilakukan melalui aplikasi analytical hierarchy process. Deskripsi ringkas dari konteks bidang dan fokus obyek dan tujuan penelitian tercermin dalam judul disertasi “Pengembangan Kebijakan AMDAL dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas”. Karya ilmiah yang dipublikasikan adalah: Analisis kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas (Jurnal Ilmiah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2008); Pengembangan kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas (Jurnal LEMIGAS, 2008); Analisis Valuasi Ekonomi Lingkungan dalam pengembangan kebijakan AMDAL migas (Jurnal Ilmiah PPLH UGM, 2008).
Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ketua komisi pembimbing Prof. Dr. Ir. Syamsul Ma’arif, M.Eng, dan anggota komisi pembimbing Prof. Dr. Ir. Surjono Hadi Sutjahjo, MS, dan Dr. Ir. Imam Santosa, MS yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam melaksanakan penelitian dan penulisan disertasi ini. Begitu pula kepada Ketua Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang banyak memberikan arahan dan bantuan selama penulis menempuh studi hingga akhir penulisan disertasi. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Suryo Suwito. P, Pertamina Direktorat Eksplorasi dan Produksi, pimpinan Ditjen Migas dan staf Lindungan Lingkungan Ditjen Migas, pimpinan dan staf PT.CPI, pimpinan dan staf Amerada Hess, pimpinan dan staf INRR yang telah banyak memberikan bantuan dan data untuk keperluan penelitian. Terima kasih pula kepada ananda Amanda tersayang yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta segenap keluarga atas doa dan motivasi selama ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membatu, semoga amal ibadahnya mendapat ridho ALLAH SWT. Amin.
Akhirnya penulis berharap bahwa dengan penelitian ini diperoleh outcomes berupa kebijakan AMDAL yang lebih efektif dan efisien pada kegiatan usaha migas di masa datang.
Bogor, April 2008
Yusni Yetti
11
RIWAYAT HIDUP
Yusni Yetti. Penulis lahir di Padang Sumatera Barat, menyelesaikan pendidikan SD, SMP dan SMA di Sumatera Barat, yang kemudian dilanjutkan di jurusan biologi fakultas MIPA Universitas Andalas Padang Sumatera Barat dan memperoleh gelar sarjana (S1) pada tahun 1983. Penulis menyelesaikan pendidikan magister (S2) pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan tahun 2000. Pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Doktor (S3) Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor.
Penulis juga mengikuti pendidikan informal antara lain: Oil Spill Preventing and Combating Technology Course IMO-Marpol Asia Pacific (1990), Environmental Impact Assesment UI (1991), Technology Management Oil Field Corrosion Control PT.CPI (1991), Oil Drift Modelling ASCOPE (1993), Environmental Audit ITB (1994), Exploration and Production Health, Safety and Environment Training, Texaco dan Chevron, USA (1994-1995), Fire Fighting Program, Texas A&M University System, USA (1995), Oil Spill Control Course, Centre for Marine Training and Safety Galveston Island, Texaco, USA (1995), Intensive English Program for 314 hours, Caltex Pacific Indonesia (1995), Environmental Segment of Safety Health and Environmental Training Train The Trainers, Caltex Pacific Indonesia (1997), The Safety and Industrial Hygiene Segment of Safety Health, Caltex Pacific Indonesia (1997), ISO 14000 Training Course Environmental International and Industry Lestari Environmental (1997), Indonesia Society of Technolgy Course, UNPAD (1999), Training Course on Challenge to Environmental Pollution Control in Refineries, Japan Cooperation Centre Petroleum, Jepang (2001), Condensate/Oil Spill Response Training Course Level I, Global Alliance EARL (2003), Studi banding pemotongan kepala sumur, Norwegia (2005), Studi banding bioremediasi pengelolaan limbah minyak dan tanah terkontaminasi oleh Minyak Bumi, Perancis (2007). Selain itu penulis juga mengikuti beberapa seminar yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain: National Seminar Coservation Technology, Jakarta (1996), International Seminar on Sustainable Development of Coastal and Marine Resources, Bogor (1996) dan National Seminar Toxicology, Jakarta (1997).
Mendapat penugasan di bidang lingkungan antara lain: Inspeksi pengujian bejana tekan, Perancis (2003), Inspeksi kompresor gas, USA (2004), Inspeksi bejana tekan, USA (2004), Inspeksi pengujian bejana tekan, Korea (2004), Inspeksi pengujian bejana tekan, Jepang (2004), Inspeksi barge, Singapura (2004), Inspeksi barge, New Zealand (2005), Inspeksi barge, Singapura (2005), Pengujian bejana tekan peralatan pemurnian gas, Perancis (2007).
Riwayat pekerjaan penulis yaitu sebagai Dosen di Fakultas MIPA jurusan Biologi Universitas Pakuan Bogor dari tahun 1983 sampai 1995. Mulai bekerja di Migas tahun 1989 sampai sekarang. Saat ini, penulis menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Lindungan Lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Migas Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. Penulis pernah mendapatkan tanda jasa dan penghargaan antara lain Satya Lancana Karya Satya Pengabdian 10 tahun.
Bogor, April 2008 Yusni Yetti
12
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI.................................................................................................... x DAFTAR TABEL............................................................................................ xii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xiv I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1 1.2 Kerangka Pemikiran............................................................................ 6 1.3 Perumusan Masalah ........................................................................... 8 1.4 Tujuan Penelitian ................................................................................ 11 1.5 Manfaat Penelitian ............................................................................. 11 1.6 Kebaruan Penelitian ............................................................................ 11
II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 12
2.1 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup ........................................ 12 2.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan .......................................... 17 2.2.1 Definisi AMDAL ....................................................................... 17 2.2.2 Landasan Hukum Pelaksanaan AMDAL................................... 20 2.2.3 Prosedur Pelaksanaan AMDAL ................................................. 21 2.3 Kegiatan Minyak dan Gas Bumi ........................................................ 30 2.4 Konsep Valuasi Ekonomi.................................................................... 31 2.5 Hasil Penelitian Terdahulu.................................................................. 36
III. KEGIATAN MIGAS DI INDONESIA .................................................... 41
3.1 Sejarah Kegiatan Migas di Indonesia ................................................. 41 3.2 Potensi Minyak dan Gas Bumi Indonesia ........................................... 43 3.3 Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia......................................... 44 3.4 Kontribusi Migas terhadap Devisa Negara ........................................ 46 3.5 Permasalahan dalam Kegiatan Migas ................................................ 49
IV. METODOLOGI PENELITIAN ................................................................ 53
4.1 Waktu dan Lokasi Penelitian ............................................................. 53 4.2 Tahapan Penelitian .............................................................................. 54 4.3 Jenis dan Sumber Data ....................................................................... 55 4.4 Rancangan Penelitian ......................................................................... 56 4.4.1 Metode Pengumpulan Data ........................................................ 56 4.4.2 Metode Analisis Data ................................................................ 57 4.4.2.1 Analisis Komponen Utama ............................................ 57 4.4.2.2 Analytical Hierarchy Process ........................................ 58 4.4.2.3 Focus Group Discussion ................................................ 58 4.4.2.4 Analisis Total Economic Valuation ............................... 59
13
V. HASIL DAN PEMBAHASAN................................................................... 63 5.1 Kebijakan AMDAL............................................................................. 63 5.1.1 Peraturan Pemerintah tentang AMDAL...................................... 63 5.1.2 Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup ...................................................................... 72 5.1.3 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan... 75 5.2 Kualitas Dokumen AMDAL Migas .................................................... 79 5.3 Kinerja Lingkungan Kegiatan Usaha Migas ....................................... 106 5.3.1 Tumpahan Minyak ..................................................................... 107 5.3.2 Kualitas Limbah Cair ................................................................. 110 5.3.3 Kualitas Udara dan Kebisingan.................................................. 115 5.3.4 Aspek Sosial Ekonomi ............................................................... 120 5.3.5 Nilai Ekonomi Lingkungan........................................................ 128 5.4 Kebutuhan Stakeholders ..................................................................... 137 5.5 Komponen Utama Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas.......... 142 5.6 Strategi Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas.......................... 148 5.6.1 Peningkatan Kualitas Dokumen AMDAL Migas ....................... 149 5.6.2 Penyempurnaan Prosedur Penyusunan AMDAL Migas............. 153 5.6.3 Penguatan Hukum dan Kelembagaan AMDAL Migas............... 156 5.7 Prioritas Strategi Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas ............ 160 5.8 Rumusan Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas ........................ 166
VI. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 169 6.1 Kesimpulan ........................................................................................ 169 6.2 Saran.................................................................................................... 170
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 172 LAMPIRAN..................................................................................................... 178
14
DAFTAR TABEL Tabel Teks Halaman 1 Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan AMDAL dan valuasi
ekonomi................................................................................................... 36 2 Cadangan minyak bumi dan kondesat Indonesia tahun 2006 ................. 43 3 Cadangan gas bumi Indonesia tahun 2006.............................................. 44 4 Kegiatan usaha migas yang berpotensi menimbulkan dampak
lingkungan dan yang diwajibkan menyusun AMDAL Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.17 tahun 2001 .......................... 51
5 Skala banding secara berpasangan dalam AHP ...................................... 58 6 Review kebijakan AMDAL dengan substansi penentuan dampak
penting..................................................................................................... 64 7 Review kebijakan AMDAL dengan substansi kerangka acuan............... 65 8 Review kebijakan AMDAL dengan substansi ANDAL.......................... 67 9 Review kebijakan AMDAL dengan substansi RKL................................ 68 10 Review kebijakan AMDAL dengan substansi RPL ................................ 69 11 Review kebijakan AMDAL dengan substansi kedudukan komisi
penilai AMDAL ...................................................................................... 70 12 Review kebijakan AMDAL dengan substansi pembiayaan .................... 71 13 Kelemahan-kelemahan kebijakan AMDAL............................................ 77 14 Analisis kualitas dokumen AMDAL....................................................... 103 15 Frekuensi dan jumlah tumpahan minyak (barrel) periode 2003 –2005 .. 107 16 Tumpahan minyak (barrel) periode 2000-2007 ...................................... 108 17 Nilai ekonomi total ekosistem mangrove Ujung Pangkah, 2007............ 129 18 Nilai ekonomi total ekosistem hutan sekunder Mandau, 2007 ............... 133
15
DAFTAR GAMBAR Gambar Teks Halaman 1 Kerangka pikir penelitian........................................................................ 7 2 Aktivitas pembangunan menimbulkan dampak ...................................... 18 3 Perkembangan produksi minyak bumi indonesia ................................... 45 4 Perkembangan produksi gas bumi indonesia .......................................... 46 5 Tahapan penelitian .................................................................................. 55 6 Volume tumpuhan minyak pada kegiatan hulu dan hilir migas.............. 109 7 Kandungan minyak lemak di enam lokasi kegiatan usaha migas ........... 111 8 Kandungan H2S di enam lokasi kegiatan usaha migas ........................... 112 9 Kandungan COD di enam lokasi kegiatan usaha migas ......................... 113 10 Kandungan Amoniak di enam lokasi kegiatan usaha migas................... 114 11 Kandungan SO2 di enam lokasi kegiatan usaha migas ........................... 116 12 Kandungan H2S di enam lokasi kegiatan usaha migas ........................... 117 13 Kandungan NOx di enam lokasi kegiatan usaha migas........................... 118 14 Kebisingan di enam lokasi kegiatan usaha migas ................................... 119 15 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan
Kabupaten Bengkalis .............................................................................. 121 16 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan Kota Palembang ...................................................................................... 122 17 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan
Kabupaten Sidoarjo................................................................................. 123 18 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan
Kabupaten Muara Enim .......................................................................... 124 19 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan
Kabupaten Musi Banyuasin .................................................................... 125 20 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan
Kabupaten Morowali............................................................................... 126 21 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan
Kabupaten Sorong................................................................................... 127 22 Nilai ekonomi total ekosistem mangrove Ujung Pangkah, 2007............ 132 23 Nilai ekonomi total ekosistem hutan sekunder Mandau, 2007 ............... 134 24 Diagram alir penentuan komponen utama .............................................. 143 25 Hasil analisis penentuan komponen utama ............................................. 144 26 Diagram strategi peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas.......... 150 27 Prosedur penyusunan AMDAL migas saat ini........................................ 154 28 Diagram strategi penyempurnaan prosedur AMDAL migas .................. 155 29 Diagram strategi penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL............ 156 30 Strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas ................................ 160 31. Diagram strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas .................. 168
16
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran Teks Halaman 1 Peta cadangan minyak bumi Indonesia ................................................... 178 2 Peta cadangan gas bumi Indonesia.......................................................... 179 3 Peta lokasi penelitian KKKS HESS Gresik Jawa Timur ........................ 180 4 Peta lokasi penelitian PT. CPI Mandau Riau .......................................... 181 5 Perkembangan aspek sosial ekonomi Kabupaten Bengkalis .................. 182 6 Perkembangan aspek sosial ekonomi Kota Palembang .......................... 183 7 Perkembangan aspek sosial ekonomi Kabupaten Sidoarjo..................... 184 8 Perkembangan aspek sosial ekonomi Kabupaten Muara Enim .............. 185 9 Perkembangan aspek sosial ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin ........ 186 10 Perkembangan aspek sosial ekonomi Kabupaten Morowali................... 187 11 Perkembangan aspek sosial ekonomi Kabupaten Sorong....................... 188 12 Nilai manfaat langsung ekosistem hutan mangrove Kecamatan Ujung
Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ............................................... 189 13 Nilai manfaat tidak langsung ekosistem hutan mangrove Kecamatan
Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur .................................... 189 14 Nilai ekonomi total ekosistem mangrove Kecamatan Ujung Pangkah,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur............................................................... 189 15 Nilai manfaat langsung ekosistem hutan sekunder Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau...................................................... 190 16 Nilai manfaat tidak langsung ekosistem hutan sekunder Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau...................................................... 190 17 Nilai ekonomi total ekosistem hutan sekunder, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis, Riau..................................................................... 190 18 Output analisis komponen utama pengembangan kebijakan AMDAL
di masa datang dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas ............................................................................................. 191
19 Hasil analytical hierarchy process strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas dalam mencegah kerusakan lingkungan ....................... 195
17
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang turut aktif dalam
menandatangani kesepakatan internasional tahun 1972 di Stockholm Swedia,
terkait dengan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu integrasi
aspek lingkungan ke dalam proses pembangunan. Konsep pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) dirumuskan sebagai suatu upaya
mengelola sumberdaya alam dan lingkungan secara arif dan bijaksana untuk
memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang dengan
tanpa merusak dan menurunkan kualitas lingkungan (WCED, 1987). Dengan kata
lain, pertumbuhan ekonomi negara terus meningkat dan fungsi lingkungan tetap
lestari serta kondisi sosial masyarakat tetap stabil, harmonis dan sejahtera
(Munasinghe, 1993).
Pemanfaatan sumberdaya alam harus diusahakan secara cermat dan
bijaksana agar tidak merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut
berarti bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, integrasi
pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan syarat mutlak yang
harus dianut dalam proses pembangunan disemua sektor. Salah satu upaya dalam
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan adalah hasil pertemuan para
pemimpin dunia yang sepakat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK)
yang diatur dalam Kyoto Protokol tahun 1997 dan telah diratifikasi oleh Indonesia
melalui UU No. 17 tahun 2004 tentang ratifikasi Kyoto Protokol.
Keputusan Kyoto Protokol yang paling utama adalah kesepakatan negara-
negara maju untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi tingkat
emisi sebanyak 5% dari tahun 1990. Keputusan lainnya adalah turut sertanya
negara-negara berkembang dalam menjaga dan memelihara hutan melalui
pemberian insentif karbon yang dapat dipakai untuk mengelola lingkungan
(Murdiyarso, 2003).
Tindakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca merupakan bukti
kesadaran manusia terhadap lingkungan yang kondisinya makin memperhatinkan.
18
Pemanasan global yang berdampak sangat besar terhadap lingkungan menjadi
ancaman bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi.
Karbon dioksida (CO2) di atmosfer merupakan senyawa gas yang
berpotensi menimbulkan pemanasan global. Gas tersebut dihasilkan dari berbagai
aktivitas manusia dalam pembangunan, diantaranya adalah produksi dan konsumsi
energi serta aktivitas industri. Aktivitas produksi dan konsumsi energi merupakan
penyumbang terbesar penghasil gas rumah kaca (GRK) berupa gas CO2 yang
sangat berperan dalam peningkatan pemanasan global yakni sekitar 57%.
Aktivitas tersebut mencakup pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas
dan batu bara sebagai sumber energi bagi keperluan rumah tangga, industri dan
transportasi (Kristanto, 2002).
Tingginya kontribusi gas CO2 di atmosfer yang bersumber dari
penggunaan bahan bakar fosil tidak lain disebabkan oleh kebutuhan dunia
terhadap energi yang sangat tinggi yakni diperkirakan mencapai 88% atau sekitar
13.700 metrik ton pada tahun 2030. Kondisi tersebut akan menyebabkan
peningkatan emisi CO2 sekitar 43 miliar metrik ton. Disisi lain kontribusi kegiatan
usaha migas dalam perubahan iklim adalah bersumber dari pembakaran sisa gas
bumi dengan flare stake yang merupakan salah satu teknologi pengelolaan
lingkungan namun masih menghasilkan gas CO2. Data Ditjen Migas (2007)
menunjukkan bahwa pada tahun 2006 gas bumi yang dibakar di flare stake adalah
sebesar 111.831.560 MSCF (306.388 MSCFD). Jumlah tersebut berasal dari
kegiatan usaha migas di daratan sebesar 73.336.374 MSCF (200.922 MSCFD)
dan di lepas pantai 38.495.185 MSCF (105.466 MSCFD).
Menyadari akan pentingnya kebutuhan energi di satu sisi dan
kelangsungan hidup manusia di sisi lain, maka upaya penurunan emisi gas CO2
sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak
baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Upaya pencegahan kerusakan
lingkungan hidup harus senantiasa dilakukan dengan prediksi dan antisipasi
terhadap berbagai potensi dampak penting yang akan terjadi akibat adanya
kegiatan pembangunan tersebut, sejak tahap perencanaan, tahap konstruksi, tahap
operasi hingga tahap pasca operasi. Selanjutnya berbagai alternatif solusi untuk
mencegah dan menanggulangi dampak, harus dirumuskan sejak awal yakni pada
19
tahap perencanaan kegiatan serta dievaluasi secara terus menerus pada tahapan
kegiatan selanjutnya.
Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan migas juga sangat berpengaruh
terhadap kualitas lingkungan perairan, berupa kandungan minyak dan H2S
terlarut. WHO merekomendasikan kadar sulfat yang diperkenankan pada air
minum sekitar 400 mg/liter dan kadar hidrogen sulfida (H2S terlarut) sekitar 0,05
mg/liter (Moore, 1991). Disamping itu, sulfur yang diemisikan dari bahan bakar
fosil (minyak bumi) yang berlebihan di atmosfir (kualitas udara) dapat juga
membentuk gas hidrogen sulfida (H2S) yang bersifat asam.
Secara ekonomi kegiatan migas memberikan pengaruh yang besar
terutama dalam peningkatan pendapatan penduduk karena dapat menyerap
peluang tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dengan demikian kegiatan
minyak dan gas tersebut menjadi salah satu sumber perekonomian bagi
masyarakat yang berada di sekitarnya. Namun bila dilihat secara ekologis dan
kesehatan lingkungan, keberadaan kilang minyak tersebut berpotensi
menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di sekitar lokasi. Permasalahan
lingkungan yang terjadi di lokasi kegiatan migas diantaranya berupa peningkatan
kadar debu, kebisingan, bau dan gangguan kenyamanan. Hasil survey PPLH
UNRI (2004) menunjukkan bahwa penyakit ISPA yang disebabkan oleh debu
merupakan penyakit yang paling banyak terjadi di masyarakat sekitar lokasi
kilang minyak yaitu sebesar 42,7%. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan,
sehingga dibutuhkan kesadaran dan kepedulian akan pengelolaan lingkungan
hidup sebagai upaya terpadu dalam pemanfaatan sumberdaya alam, sejalan
dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang
pengelolaan lingkungan hidup, bahwa setiap orang berkewajiban memelihara
pelestarian lingkungan, mencegah dan menanggulangi lingkungan. Demikian pula
dinyatakan dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, bahwa
upaya preventif yang dilakukan adalah dengan mewajibkan semua kegiatan usaha
migas untuk melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan sejak tahap
perencanaan hingga pasca operasi dan menjamin keteknikan yang baik.
20
Salah satu upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan dalam
mencegah terjadinya kerusakan lingkungan adalah dengan melakukan studi
AMDAL. Dalam PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL dinyatakan bahwa
analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai
dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. AMDAL berfungsi sebagai upaya
preventif dalam menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan serta menekan
pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Oleh karena
itu dokumen AMDAL bersifat mengikat berbagai pihak yang terlibat di dalamnya
serta mempunyai konsekuensi bagi status perijinan dari usaha dan atau kegiatan
(Suratmo, 2002).
Proses AMDAL kemudian bersifat wajib (mandatory) untuk dilakukan
bagi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat
menimbulkan dampak penting. AMDAL terdiri atas kerangka acuan (KA),
analisis dampak lingkungan (ANDAL), rencana pengelolaan lingkungan (RPL)
dan rencana pemantuan lingkungan (RPL). KA adalah dokumen pertama yang
berisi pedoman penyusunan ANDAL. ANDAL adalah kajian utama tentang
dampak besar dan penting dari suatu usaha atau kegiatan. RKL adalah dokumen
alternatif solusi yang dibuat dalam pengelolaan dampak lingkungan dari suatu
kegiatan. RPL adalah dokumen yang berisikan alternatif pemantauan dampak dari
suatu kegiatan. Dengan demikian AMDAL yang terdiri atas empat dokumen
tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan
satu sama lain, fleksibel dan terbuka untuk selalu dikoreksi dan menjadi salah satu
sistem manajemen lingkungan (SML).
SML adalah suatu sistem atau cara dalam menangani lingkungan hidup
yang mencakup: 1) organisasi dan kebijakan lingkungan, 2) perencanaan, 3)
implementasi dan operasi, 4) pengawasan dan tindakan koreksi, dan 5) pengkajian
manajemen. SML lainnya dalam upaya pengelolaan lingkungan yang dapat
dilakukan bagi perencana dengan penerapan ISO 14000. Namun penerapan ISO
14000 hanya bersifat voluntary (sukarela), sementara AMDAL bersifat mandatory
(wajib).
21
AMDAL diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969 oleh National
Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Penerapan sistem evaluasi laporan
AMDAL di Kanada untuk proyek-proyek federal dikeluarkan oleh kabinet pada
tanggal 20 Desember 1973. Sedangkan penerapan AMDAL di Indonesia
dilakukan sejak dikeluarkannya PP No. 29 tahun 1986.
Untuk sektor migas, studi lingkungan telah dimulai sejak tahun 1987 yang
dikenal dengan dokumen studi evaluasi mengenai dampak lingkungan
(SEMDAL) bagi kegiatan yang sudah berjalan dan dokumen AMDAL bagi
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan PP No. 29 tahun 1986 (periode
1986-1993). Dokumen studi evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL)
terdiri atas: KA-SEL, SEL, RKL/RPL, sedang dokumen AMDAL terdiri atas:
KA-ANDAL, ANDAL, RKL/RPL. Dokumen SEMDAL yang telah disetujui
dalam periode 1986-1993 sebanyak 23 dokumen dan dokumen AMDAL sebanyak
16 dokumen. Sejak tahun 1993 studi SEMDAL ditiadakan, sehingga studi
lingkungan keseluruhan dikenal dengan studi AMDAL untuk kegiatan yang
berdampak penting berdasarkan PP No. 51 tahun 1993 (periode 1993-1997),
jumlah dokumen yang telah disetujui sebanyak 22 dokumen. Pada tahun 1999
sampai sekarang dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka terjadi perubahan
PP No. 51 tahun 1993 menjadi PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL, dengan
perubahan mendasar antara lain komisi pusat AMDAL yang tadinya berada pada
masing-masing sektor dibagi menjadi dua yakni: komisi pusat AMDAL
berkedudukan di kementerian lingkungan hidup dan komisi daerah yang
berkedudukan di propinsi dan kabupaten. Khusus untuk sektor migas karena
merupakan industri yang strategis, sehingga berada di bawah komisi pusat
AMDAL KLH. Sesuai PP No. 27 tahun 1999, bahwa kegiatan yang mempunyai
dampak besar dan penting terhadap lingkungan harus menyusun dokumen
AMDAL. Dokumen AMDAL yang telah disetujui hingga saat ini sebanyak 30
dokumen.
Walaupun kebijakan AMDAL telah diterapkan pada kegiatan usaha migas
lebih dari 20 tahun, namun masih terdapat persepsi negatif dari masyarakat
terhadap pengelolaan lingkungan kegiatan migas dan masih terdapat isu
pencemaran lingkungan serta sering terjadi emergency (antara lain: tumpuhan
22
minyak). Mengingat pentingnya kegiatan pengelolaan lingkungan berdasarkan
uraian di atas, maka kajian mengenai pengembangan kebijakan AMDAL dalam
mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas menjadi sangat
penting untuk dilakukan.
1.2 Kerangka Pemikiran
Kegiatan usaha migas di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1968.
Kegiatan tersebut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pengangkutan dan
pemasaran/niaga. Hingga saat ini terdapat sebanyak 115 kegiatan usaha migas
yang beroperasi di Indonesia, sekitar 30% beroperasi di lepas pantai (off shore)
dan 70% beroperasi di darat (on shore).
Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam migas untuk
memenuhi devisa dalam negeri dilakukan dengan berbagai upaya inovasi
teknologi terutama dalam mencari sumber-sumber baru, teknik eksploitasi, teknik
pengolahan, serta sistem ketataniagaan yang efektif dan efisien. Di sisi lain
kegiatan tersebut juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan manusia.
Kondisi demikian menjadi sangat dilematis. Oleh karena itu, mutlak dilakukan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sinergitas antara aspek ekologi,
ekonomi dan sosial.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap
usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting wajib
dilengkapi dokumen AMDAL. Namun dalam peraturan perundang-undangan
tersebut belum diatur secara komprehensif sejauh mana kedalaman studi AMDAL
tersebut, yang merupakan studi ilmiah yang mengkaji dampak besar dan penting
yang ditimbulkan dari suatu kegiatan terhadap komponen biologi, geologi, fisik,
kimia serta sosial ekonomi dan budaya. Meskipun kebijakan AMDAL telah
diterapkan sejak diterbitkannya PP No. 29 tahun 1986, PP No. 51 tahun 1993 dan
PP No. 27 tahun 1999, namun hingga saat ini masih banyak permasalahan
lingkungan yang muncul seperti pencemaran, degradasi lahan dan sumberdaya
alam serta konflik sosial. Kondisi tersebut disebabkan karena masih lemahnya
hasil kajian studi AMDAL yang dilakukan oleh pihak-pihak terlibat.
AMDAL berperan sebagai instrumen SML untuk mencegah kerusakan
lingkungan hidup. AMDAL merupakan kajian kelayakan lingkungan hidup
23
Rumusan Kebijakan AMDAL Migas yang Efektif dan Efisien dalam Mencegah
Kerusakan Lingkungan
Strategi Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas
Permasalahan Lingkungan
Kegiatan Usaha Migas (1960)
Komponen Utama Kebijakan AMDAL Migas
Kegiatan Usaha Migas Berwawasan Lingkungan
Kebijakan AMDAL (1986)
Perlu Kajian Pengembangan Kebijakan
AMDAL Migas yang
Prioritas Strategi Kebijakan AMDAL Migas
Kebutuhan Stakeholders
Review Kebijakan AMDAL saat ini
Kualitas Dokumen AMDAL saat ini
Penilaian Kinerja
Lingkungan Implementasi
AMDAL
mengenai dampak besar dan penting tentang perubahan lingkungan hidup yang
sangat mendasar dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup. Pesatnya aktivitas manusia dan pembangunan ekonomi untuk
mencapai kesejahteraan manusia hampir pasti selalu diiringi dengan timbulnya
dampak lingkungan. Untuk menghindari timbulnya dampak lingkungan negatif
yang tidak dapat ditoleransi tersebut, maka perlu dipersiapkan langkah-langkah
operasional rencana pengendalian dampak lingkungan tersebut sekaligus dengan
rencana pemantauannya dalam bentuk dokumen RKL dan RPL. Dengan
demikian, AMDAL bertujuan untuk menjamin tujuan-tujuan proyek
pembangunan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat tanpa merusak
kualitas lingkungan hidup.
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan analisis efektifitas
dan efisiensi kebijakan AMDAL dalam mencegah terjadinya kerusakan
lingkungan pada kegiatan usaha migas. Hasil analisis kebijakan diharapkan
menghasilkan rumusan kebijakan implementatif yang lebih efektif dan efisien.
Gambar 1 Kerangka pikir penelitian
Pencemaran
Konflik Sosial
24
1.3 Perumusan Masalah
Mencermati amanat dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan
lingkungan hidup dan PP No. 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak
lingkungan (AMDAL) maka permasalahan pengelolaan lingkungan pada dasarnya
merupakan tanggung jawab semua pihak baik sebagai pelaku pembangunan
maupun masyarakat. Sasaran pengelolaan lingkungan adalah terjaminnya mutu
hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang tanpa merusak
sumberdaya alam dan lingkungan. Namun kenyataannya selama kurang lebih 25
tahun sejak diterbitkannya undang-undang lingkungan hidup (UU No. 04 tahun
1982) dan telah lebih 20 tahun diterapkannya kebijakan AMDAL (PP No. 29
tahun 1986), kemajuan dari pengelolaan lingkungan hidup sangat lambat bahkan
kualitas lingkungan cenderung turun, yang ditandai dengan seringnya terjadi
gejolak-gejolak masyarakat, dan isu pencemaran serta seringnya terjadi tumpahan
minyak, limbah B3 yang semakin menumpuk dan belum jelasnya solusi
pengelolaannya. Akhir-akhir ini banyak sorotan bahwa dokumen AMDAL hanya
bersifat formalitas karena yang seharusnya dokumen AMDAL disusun sebelum
kegiatan berjalan yang merupakan studi kelayakan lingkungan tetapi dalam
kenyataannya, dokuemen AMDAL disetujui oleh komisi AMDAL setelah
kegiatan berjalan.
Tiga faktor penting yang sangat berpengaruh dalam dokumen AMDAL: (a)
peraturan perundang-undangan, (b) penyusun AMDAL dan pemrakarsa, (c)
komisi penilai AMDAL dan tim teknis serta instansi yang bertanggung jawab dan
instansi yang terkait dari pusat dan daerah. Tiga faktor ini berpengaruh dalam
penerapan prosedur dan substansi dokumen AMDAL untuk menentukan kualitas
dokumen AMDAL. Apabila tiga faktor ini berjalan dengan baik maka kualitas
AMDAL akan baik dan dapat bersifat operasional. Selanjutnya masuk tahap
implementasi (pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan) serta
pengawasan pelaksanaannya yang dilakukan oleh instansi terkait dan penegakan
hukum.
Prosedur penyusunan AMDAL yang telah berjalan selama ini adalah tim
penyusun dokumen AMDAL ditunjuk oleh Pemrakarsa dan belum terakreditasi
oleh pemerintah. Dalam hal ini pemrakarsa dimungkinkan dapat mempengaruhi
25
tim penyusun (tidak bersifat independen). Substansi dokumen AMDAL mengenai
kajian-kajian analisis ekonomi, kajian dampak terhadap ekosistem sangat minim
dan tidak memperhitungkan dampak perubahan lingkungan yang potensial
(eksternalitas) yang tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-
undangan atau kebijakan saat ini sehingga dokumen AMDAL yang telah disetujui
sulit untuk diimplementasikan oleh pemrakarsa.
Penentuan isu pokok di dalam kerangka acuan (KA-ANDAL), serta
penentuan dampak besar dan penting di dalam dokumen ANDAL masih bersifat
umum, tidak dikaji secara komprehensif dan belum memasukkan kajian-kajian
aspek ekologi, ekonomi dan sosial, sehingga penentuan dampak penting seringkali
kurang tepat dan pada akhirnya dokumen AMDAL kualitasnya diragukan dan
tidak bersifat operasional. Hal tersebut menyebabkan dokumen AMDAL yang
merupakan acuan di dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama
kegiatan berlangsung tidak dapat diterapkan di lapangan, sehingga mengakibatkan
terjadinya pencemaran lingkungan bahkan kerusakan lingkungan.
Sesungguhnya dokumen AMDAL merupakan hasil studi kelayakan
lingkungan yang mengkaji secara cermat dan mendalam tentang berbagai dampak
penting yang akan terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang akan
dilaksanakan tidak layak atau layak lingkungan, maka kegiatan dapat ditolak dan
atau sebaliknya. Proses persetujuan dokumen AMDAL dari KA-ANDAL, RKL
dan RPL membutuhkan waktu paling cepat 2-3 tahun. Penilaian AMDAL yang
dibantu oleh tim teknis dan para pakar hanya pada waktu rapat komisi seterusnya
evaluasi untuk persetujuan AMDAL dilaksanakan oleh komisi dan disetujui oleh
komisi.
Dokumen AMDAL yang efektif dan efisien ditentukan dari peraturan
perundangan dan atau kebijakan yang dipakai sebagai acuan di dalam penyusunan
dokumen AMDAL tersebut, prosedur penyusunan AMDAL, waktu penyusunan,
kualitas penyusun AMDAL dan pemrakarsa, kinerja komisi penilai dan tim teknis
AMDAL serta kualitas dokumen AMDAL (substansi dokumen AMDAL) maka
dirumuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Kebijakan AMDAL yang ditetapkan selama ini belum efektif dan belum
efisien, kekurangan dari peraturan perundangan yang sudah ada antara lain:
26
PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL yang tidak mengatur substansi-
substansi untuk prakiraan dampak penting dan evaluasi dampak penting
sehingga muncul isu bahwa dokumen AMDAL hanya bersifat formalitas dan
mahal.
2. Kinerja komisi penilaian AMDAL belum efektif dan belum efisien yang
menyebabkan kualitas AMDAL diragukan. keputusan menteri negara
lingkungan hidup No. 40 tahun 2000 tentang pedoman tata kerja komisi
penilai AMDAL, tim teknis tidak ikut memberikan evaluasi dalam penerbitan
persetujuan AMDAL hanya ikut diwaktu penilaian sidang komisi.
3. Pelaksanaan dan waktu pengumuman masyarakat serta waktu penerbitan
persetujuan dokumen AMDAL terlalu lama. Keputusan kepala Bapedal No.
08 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL,
menentukan waktu terlalu lama untuk mengumpulkan pendapat masyarakat
dan berdasarkan PP. 27 tahun 1999 tentang AMDAL bahwa dokumen KA-
ANDAL disetujui selama 75 hari kerja dan dokumen ANDAL, RKL, RPL
disetujui juga selama 75 hari.
4. Kualitas tim penyusun AMDAL tidak independen dan ditunjuk langsung oleh
Pemrakarsa. Sampai saat ini belum ada landasan hukum yang mengatur
tentang konsultan penyusun AMDAL.
5. Pedoman penyusunan AMDAL lebih terfokus pada sistematika penulisan
dokumen, sedangkan penentuan isu pokok dan prakiraan dampak besar dan
penting serta evaluasi dampak penting tidak terdapat arahan metode-metode
yang baku untuk aspek ekologi, ekonomi dan sosial, tidak memasukkan
metode valuasi ekonomi (sesuai Kepdal No. 229 tahun 1996). Namun hanya
disebutkan secara garis besar memakai metode formal/non formal, baik di
dalam peraturan menteri negara lingkungan hidup No. 08 tahun 2006 tentang
pedoman penyusunan AMDAL maupun di dalam keputusan menteri energi
sumberdaya mineral No.1457 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan
AMDAL kegiatan usaha migas.
Dengan demikian maka pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan
dalam penelitian ini adalah:
27
1. Bagaimana efektivitas dan efisiensi kebijakan AMDAL migas yang ada saat
ini ?
2. Bagaimana merumuskan kebijakan AMDAL migas yang efektif dan efisien di
masa mendatang ?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah merumuskan kebijakan AMDAL yang efektif dan
efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas. Untuk
mencapai tujuan tersebut secara operasional dilakukan tahapan penelitian
meliputi:
1. Mereview kebijakan AMDAL saat ini.
2. Menganalisis kualitas dokumen AMDAL migas.
3. Menganalisis kinerja lingkungan implementasi AMDAL kegiatan migas.
4. Menganalisis kebutuhan stakeholders terhadap kebijakan AMDAL migas
dimasa mendatang
5. Merumuskan strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas.
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dari sisi ilmiah adalah sebagai upaya pengembangan
ilmu dan pengetahuan, khususnya kajian lingkungan yang menyangkut analisis
mengenai dampak lingkungan dalam kegiatan usaha migas.
Manfaat penelitian dari sisi praktis adalah sebagai bahan pertimbangan
dalam penetapan kebijakan AMDAL yang efektif dan efisien pada kegiatan usaha
migas di masa datang serta sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan
dokumen AMDAL migas.
1.6 Kebaruan Penelitian
Kebaruan dari penelitian ini berupa kajian terhadap kebijakan AMDAL
yang efektif dan efisien yang terfokus pada substansi, prosedur dan kelembagaan
di dalam AMDAL kegiatan usaha migas. Kebaruan dari aspek metode pendekatan
yang digunakan yakni melibatkan semua stakeholder dengan teknik analisis yang
terintegrasi antara FGD, PCA dan AHP serta valuasi ekonomi.
28
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lainnya (UU No. 23 tahun 1997). Lingkungan hidup sebagai suatu sistem
yang terdiri atas: lingkungan alam (ecosystem), lingkungan buatan (technosystem)
dan lingkungan sosial (sociosystem) dimana ketiga sub sistem ini saling
berinteraksi dan membentuk suatu sistem yang dinamis. Ketahanan masing-
masing sub sistem akan memberikan jaminan berkelanjutan yang tentunya akan
memberikan peningkatan kualitas hidup setiap makhluk hidup didalamnya
(Hendartomo, 2001).
Masalah lingkungan hidup pada dasarnya timbul karena dinamika
penduduk, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang kurang bijaksana serta
kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju.
Dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya
positif dan memberikan manfaat yang besar terhadap manusia seringkali terjadi
sebaliknya, manusia menjadi korban akibat dampak yang ditimbulkan dari
aktivitas ekonomi yang dilakukan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
merupakan dua permasalahan yang paling banyak timbul, sebagai dampak dari
kegiatan ekonomi dan pembangunan.
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup
oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan
peruntukannya, sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan
atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam
menunjang pembangunan berkelanjutan (UU No. 23 tahun 1997).
Dalam perspektif ekonomi lingkungan dipandang sebagai asset gabungan
yang menyediakan berbagai jasa/fungsi yakni untuk mendukung kehidupan
29
manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Lingkungan menyediakan bahan
baku yang ditransformasikan ke dalam bentuk barang dan jasa melalui proses
produksi dan energi selanjutnya menghasilkan residual yang kembali ke
lingkungan (Kusumastanto, 2000).
Hubungan timbal balik antara aspek ekonomi dan sumberdaya alam dan
lingkungan kemudian menjadi sangat penting. Ekstraksi terhadap sumberdaya
alam yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan
menghasilkan benefit dan limbah. Aktivitas manusia secara langsung maupun
tidak langsung telah dan akan memberikan dampak terhadap resistensi
sumberdaya alam dan lingkungan.
Manusia melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan memanfaatkan sumberdaya alam (air, udara, tanah, hutan,
minyak, dan ikan) namun disisi lain pemanfaatan tersebut juga menimbulkan
residual (limbah) yang kembali ke lingkungan, dan berdampak terhadap kualitas
lingkungan tersebut. Sebagai salah satu negara yang luas di dunia, Indonesia
tidak hanya memiliki wilayah daratan dan perairan yang luas tetapi juga kaya
dengan sumberdaya alam. Hutan tropis yang luasnya diperkirakan mencapai 144
juta hektar sangat kaya dengan ribuan jenis burung, ratusan jenis mamalia dan
puluhan ribu jenis tumbuhan. Perairan yang luas menjadi tempat bagi
perkembangan populasi ikan dan hasil perairan lainnya. Demikian pula dengan
buminya yang mengandung deposit berbagai jenis mineral dalam jumlah yang
tidak sedikit.
Pengelolaan sumberdaya alam merupakan suatu hal yang sangat penting
dibicarakan dan dikaji dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional kita.
Dengan potensi sumberdaya alam yang berlimpah sesungguhnya kita dapat
melaksanakan proses pembangunan bangsa ini secara berkelanjutan tanpa harus
dibayangi rasa cemas dan takut akan kekurangan modal bagi pelaksanaan
pembangunan tersebut. Pemanfaatan secara optimal kekayaan sumberdaya alam
ini akan mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa
Indonesia.
Namun demikian perlu kita sadari eksploitasi secara berlebihan tanpa
perencanaan yang baik bukannya mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan
30
namun malah sebaliknya akan membawa malapetaka yang tidak terhindarkan.
Akibat dari pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang tidak memperhatikan
keseimbangan dan kelestarian lingkungan dapat kita lihat pada kondisi lingkungan
yang mengalami degradasi baik kualitas maupun kuantitasnya. Hutan tropis yang
kita banggakan setiap tahun luasnya berkurang sangat cepat, demikian juga
dengan jenis flora dan dan fauna di dalamnya sebagian besar sudah terancam
punah. Perairan yang sangat luas sudah tercemar sehingga ekosistemnya
terganggu. Demikian juga dengan dampak eksploitasi mineral yang terkandung
dalam perut bumi juga mulai merusak keseimbangan dan kelestarian alam sebagai
akibat proses penggalian, pengolahan dan pembuangan limbah yang tidak
dilakukan secara benar.
Pengelolaan sumberdaya alam selama ini tampaknya lebih mengutamakan
meraih keuntungan dari segi ekonomi sebesar-besarnya tanpa memperhatikan
aspek sosial dan kerusakan lingkungan. Pemegang otoritas pengelolaan
sumberdaya alam berpusat pada negara yang dikuasai oleh pemerintah pusat,
sedangkan daerah tidak lebih sebagai penonton. Berbagai kebijakan yang
dikeluarkan cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala menjadi kebijakan
yang tumpang tindih. Sentralisasi kewenangan tersebut juga mengakibatkan
pengabaian perlindungan terhadap hak azasi manusia. Selama puluhan tahun
praktek pengelolaan sumberdaya alam tersebut dilaksanakan telah membawa
dampak yang sangat besar bagi daerah.
Berdasarkan implementasi dari UU No. 23 tahun 1997 tentang
pengelolaan lingkungan hidup yang mendefinisikan tiga konsep utama dalam
pembangunan berkelanjutan yaitu: kondisi SDA, kualitas lingkungan dan faktor
demografi. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi usaha untuk menyusun
penghitungan kualitas lingkungan. Tujuan dari penghitungan kualitas lingkungan
adalah: a) memberikan deskripsi tujuan dari aktivitas manusia (sosial dan
ekonomi) dan fenomena alami keadaan lingkungan dan demografi, b)
memberikan informasi yang komprehensif untuk masyarakat dan pembuat
kebijakan, c) sebagai alat yang sangat membantu dalam mengevaluasi
pengelolaan demografi dan lingkungan (Landiyanto dan Wardaya, 2005).
31
Agar upaya pelestarian lingkungan berjalan secara efektif dan efisien serta
berkelanjutan, dibutuhkan kebijakan untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam
skenario politik ekonomi yang rumit saat ini, amatlah penting untuk menetapkan
kebijakan lingkungan dan sosial yang kuat disemua tingkatan. Demikian juga
penegakan hukum harus berjalan secara efektif agar pelestarian keanekaragaman
hayati dapat berjalan dengan baik.
Kebijakan adalah peraturan yang telah dirumuskan dan disetujui untuk
dilaksanakan guna mempengaruhi suatu keadaan (mempengaruhi pertumbuhan)
baik besaran maupun arahnya yang melingkupi kehidupan masyarakat umum.
Kebijakan dikatakan efektif apabila penerapan kebijakan dan instrumennya dapat
menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sedangkan
dikatakan efisien jika kebijakan tersebut membutuhkan biaya yang rendah.
Tahapan kebijakan terdiri dari fase formulasi kebijakan dan fase implementasi
kebijakan, sedangkan analisis kebijakan aktivitas menciptakan pengetahuan
tentang proses pembuatan kebijakan Clay dan Shaffer (1984) dalam Sanim
(2003).
Salah satu tindakan pemerintah dalam analisis kebijakan lingkungan
adalah dengan menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan dalam setiap
pelaksanaan usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. AMDAL merupakan
kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap
perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Tujuan secara umum
AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan
pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin.
AMDAL di Indonesia telah lebih dari 20 tahun diterapkan. Meskipun
demikian berbagai hambatan dan masalah selalu muncul dalam penerapannya,
seperti juga yang terjadi pada penerapan AMDAL di negara-negara berkembang
lainnya. Dalam komisi penilai AMDAL, sangat jelas terlihat kerancuan dalam
proses penilaian, dengan tidak adanya kriteria dan indikator penilaian yang
standar, sehingga menjadikan proses penilaian AMDAL menjadi sangat subyektif.
Kriteria dan indikator merupakan jembatan yang menghubungkan antara
tujuan dan aksi yang dilakukan. Ada empat indikator untuk melihat keberhasilan
sebuah kebijakan (Kusumastanto, 2003) yakni: 1) kebijakan tersebut harus
32
memiliki instrumen yang efektif untuk menjalankannya (policy tools) dengan
kriteria: dapat diaplikasikan secara leluasa (discretionary) dan universal, serta
dapat ditegakkan secara hukum dan memiliki kewenangan administratif yang
mencakup aspek insentif dan regulatif, 2) kebijakan tersebut dapat memberikan
dampak terhadap perekonomian domestik maupun global. Artinya, kebijakan itu
mendapatkan dukungan/konsensus secara nasional (khususnya di level pemerintah
dan legislatif) maupun internasional, 3) kebijakan tersebut harus efisien dan
efektif secara ekonomi serta adil, sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan
pemerataan kesejahteraan rakyat, dan 4) kebijakan tersebut harus mampu
mendorong kemandirian rakyat dan berlandaskan nilai-nilai luhur agama dan
moralitas.
Agar indikator atau persyaratan tersebut dapat terpenuhi, maka diperlukan
beberapa pendekatan, yakni: 1) pendekatan pasar yang didukung oleh instrumen
kebijakan yang diterapkan, misalnya pajak, pungutan, sanksi dan insentif serta
disinsentif, 2) pendekatan kelembagaan. Aturan yang diterapkan dalam
pendekatan ini harus dikenal dan diikuti secara baik oleh seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) dan memberi naungan serta konstrain terhadap
mereka. Kebijakan ini mampu memberikan perlindungan dan pembatasan akses
terhadap sumberdaya, adanya peraturan perundangan yang mendukungnya.
Aturan ini ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, atau tidak
ditulis formal sampai pada aturan adat dan norma masyarakat serta kearifan lokal.
Aspek penting lainnya dari aturan tersebut adalah dapat diprediksi, essentially
stable dan dapat diaplikasikan pada situasi berulang, 3) pendekatan percampuran
pasar dan bukan pasar serta pendekatan kelembagaan yang efektif dan efisien.
Pendekatan ini dapat menilai sumberdaya alam dan lingkungan secara wajar dan
tidak undervalue, sehingga kesejahteraan yang hakiki bagi masyarakat Indonesia
serta pembangunan yang bersifat lestari dapat terwujud.
Optimalisasi nilai manfaat sumberdaya alam dan lingkungan yang ada bagi
pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan menjamin kepentingan umum
secara luas, diperlukan intervensi kebijakan dan penanganan pengelolaan dalam
pengembangan wilayah. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan dapat
terselenggara secara optimal jika arah kebijakan pengembangan wilayah dan
33
tata ruang menjadi instrumen intervensi kebijakan dengan memperhatikan
kepentingan stakeholders selain didukung oleh program-program sektoral yang
melibatkan para pihak yang terkait dalam pengelolaan wilayah.
Kebijakan dengan berbagai indikator dan pendekatan yang dilakukan
merupakan upaya untuk senantiasa menjaga keberhasilan dalam implementasi
kebijakan yang dilakukan. Dalam kaitannya dengan kebijakan pengelolaan
lingkungan pada kegiatan usaha migas, berbagai undang-undang, peraturan
pemerintah hingga keputusan menteri diterbitkan, sebagai upaya untuk menjaga
keberlanjutan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
dinyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan,
mencegah dan menanggulangi pencemaran. Kemudian dalam UU No. 22 tahun
2001 tentang migas dinyatakan bahwa semua kegiatan usaha migas wajib
melakukan pengelolaan lingkungan hidup, mulai tahap perencanaan hingga pasca
operasi. Artinya kegiatan usaha migas harus menyusun AMDAL sebelum
kegiatan operasi baik kegiatan hilir maupun kegiatan hulu.
2.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
2.2.1 Defenisi AMDAL
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. AMDAL merupakan
bagian kegiatan studi kelayakan perencanaan usaha dan atau kegiatan dan
merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha yang mana hasil dari AMDAL
digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.
AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang
direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL
dirumuskan sebagai suatu analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek
yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak proyek dari
pembangunannya (Suratmo, 2002).
34
Dampak lingkungan adalah perubahan yang terjadi dalam lingkungan
akibat adanya aktivitas manusia. Aktivitas tersebut dilakukan sebagai upaya untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, kimia, fisik
maupun biologi. Dampak kemudian menjadi permasalahan akibat perubahan yang
terjadi dan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan.
Dampak dalam kaitannya dengan pembangunan memiliki dua batasan
yakni: 1) Dampak pembangunan terhadap lingkungan yakni perbedaan antara
kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan setelah ada pembangunan, 2)
Dampak pembangunan terhadap lingkungan, yakni perbedaan antara kondisi
lingkungan yang diperkirakan terjadi tanpa adanya pembangunan dan yang
diperkirakan terjadi dengan adanya pembangunan tersebut (Mun, 1979 dalam
Sumarwoto, 2005). Lebih jauh Clark (1978) dalam Sumarwoto (2005) bahwa
aktivitas pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
menimbulkan efek yang tidak direncanakan di luar sasaran yaitu yang disebut
dampak. Dampak dapat bersifat biofisik dan atau sosial-ekonomi-budaya yang
memiliki pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dampak primer dapat
menimbulkan dampak sekunder dan tersier. Lebih rinci, tampak pada Gambar 2.
Gambar 2 Aktivitas pembangunan menimbulkan dampak (Clark, 1978 dalam Suratmo, 2002)
Dampak
Dampak Sekunder
Dampak Sosial-Ekonomi-Budaya
Dampak Biofisik
Pembangunan
Kenaikan Kesejahteraan
Dampak Biofisik
Dampak Sosial-Ekonomi-Budaya
Kegiatan Dampak
Tujuan
Dampak Primer
35
Dampak yang muncul kemudian harus teridentifikasi dan diketahui secara
dini, apakah dampak tersebut menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hidup. Untuk mengukur dan menentukan dampak besar dan penting
tersebut, digunakan beberapa kriteria yakni: a) besarnya jumlah manusia yang
akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan, b) luas wilayah
penyebaran dampak, c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung, d)
banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, e) sifat
kumulatif dampak dan f) sifat berbalik (reversible) dan tidak berbalik
(irreversible) dampak (Hendartomo, 2001).
Mengacu pada PP No. 27 tahun 1999 pasal 3 ayat 1 bahwa usaha dan atau
kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup meliputi: a) pengubahan bentuk lahan dan bentang
alam, b) eksploitasi sumberdaya alam baik yang terbaharui (renewable) maupun
yang tak terbaharui (non-renewable), c) proses dan kegiatan yang secara potensial
dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
serta kemerosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya, d) proses dan
kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan
dan lingkungan sosial budaya, e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat
mempengaruhi pelesatarian kawasan konservasi sumberdaya dan atau
perlindungan cagar budaya, dan f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan
dan jenis jasad renik.
Tujuan umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas
lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi
serendah mungkin. Sementara tujuan studi AMDAL adalah mengidentifikasi
rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting,
mengidentifikasi komponen atau parameter lingkungan yang akan terkena dampak
penting, melakukan prakiraan dan evaluasi dampak penting sebagai dasar untuk
menilai kelayakan lingkungan, menyusun strategi pengelolaan dan pemantauan
lingkungan. Menurut Mukono (2005) bahwa tujuan dan sasaran AMDAL adalah
untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara
berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi
AMDAL diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan
36
dan mengelola sumberdaya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif
dan memaksimalkan dampak positip terhadap lingkungan hidup.
Untuk itu, AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan
hidup. Proses AMDAL kemudian menjadi wajib dilakukan bagi setiap rencana
usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting.
2.2.2 Landasan Hukum Pelaksanaan AMDAL
Landasan hukum pelaksanaan AMDAL migas di Indonesia adalah:
1. UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL.
3. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 tentang pengawasan pelaksanaan
eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran
dan atau perusakan laut.
6. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran
udara.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006 tentang jenis
rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 tahun 2006 tentang
pedoman penyusunan AMDAL.
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 tahun 1998 tentang
pedoman penetapan baku mutu lingkungan.
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 tahun 1996 tentang
baku mutu limbah cair bagi kegiatan minyak dan gas serta panas bumi.
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 tahun 1998 tentang
baku mutu tingkat kebisingan.
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 tahun 2000 tentang
panduan penilaian dokumen AMDAL.
37
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 1457 tahun 2000
tentang pedoman teknis pengelolaan lingkungan dibidang pertambangan dan
energi.
14. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 08 tahun
2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses
AMDAL.
15. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 299 tahun
1996 tentang pedoman teknis kajian aspek sosial dalam penyusunan AMDAL.
2.2.3 Prosedur Pelaksanaan AMDAL
Proses pelaksanaan AMDAL terdiri atas: 1) penapisan (screening) atau
penentuan rencana kegiatan wajib AMDAL atau tidak, 2) pelingkupan (scoping)
adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang barkaitan dengan
dampak penting. Pelingkupan dampak penting yakni identifikasi dampak penting,
evaluasi dampak potensial dan pemusatan dampak penting. Pelingkupan wilayah
studi dengan memperhatikan batas proyek, batas ekologi, batas sosial, dan batas
administratif. Beanlands dan Dunker (1983) dalam Suratmo (2002)
mengelompokkan scoping sosial yaitu scoping yang menetapkan dampak penting
berdasarkan pandangan dan penilaian masyarakat. Scoping ekologis adalah proses
dari scoping yang menetapkan dampak penting berdasarkan nilai-nilai ekologi
atau peranannya di dalam ekologi, 2) penyusunan dokumen kerangka acuan (KA-
ANDAL) merupakan ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan
yang merupakan hasil pelingkupan yang memuat isu pokok yang perlu dikaji di
dalam dokumen AMDAL, 3) melaksanakan studi analisis dampak lingkungan
(ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar
dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang direncanakan, 4)
penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya
pengelolaan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang
ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan, dan 5) penyusunan
rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari
rencana usaha dan atau kegiatan.
38
Proses AMDAL tersebut menghasilkan empat buah dokumen AMDAL
terdiri atas: a) dokumen KA-ANDAL, b) dokumen ANDAL, c) dokumen RKL
dan d) dokumen RPL. Untuk menghasilkan keempat dokumen tersebut, dilakukan
prosedur pelaksanan AMDAL yakni: a) penapisan (screening), b) proses
pengumuman dan konsultasi masyarakat, c) penyusunan dan penilaian KA-
ANDAL, dan penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL (Hendartomo,
2001).
Proses penapisan merupakan proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yakni
untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib AMDAL atau tidak,
sementara proses pengumuman dan konsultasi masyarakat didasarkan pada UU
No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:
a) setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta
menanggulangi kerusakan dan pencemarannya, b) setiap orang mempunyai hak
dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
dan c) lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan
lingkungan hidup serta mengacu pada keputusan Kepala Bapedal No. 08 tahun
2000, bahwa pemrakarsa wajib mengumunkan rencana kegiatannya selama waktu
yang ditentukan dalam peraturan tersebut menanggapi masukan yang diberikan
dan melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun
KA-ANDAL.
Berdasarkan undang-undang dan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut
maka tujuan dasar dari partisipasi masyarakat di Indonesia ialah: a)
mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, b)
mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan negara dan c) membantu
pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan dan keputusan yang lebih baik dan
tepat.
Diharapkan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam penyusunan
dokumen AMDAL pada suatu kegiatan usaha yaitu: 1) masyarakat mendapatkan
informasi mengenai rencana pembangunan didaerahnya sehingga dapat
mengetahui dampak apa yang akan terjadi baik yang positif maupun yang negatif
dan cara menanggulangi dampak negatif yang akan dan harus dilakukan. 2)
masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan,
39
pembangunan, dan hubungan pembangunan dengan lingkungan sehingga
pemerintah dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan
tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan 3) masyarakat dapat
menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah
terutama masyarakat di tempat proyek yang akan terkena dampak.
Implementasi AMDAL sangat perlu disosialisasikan tidak hanya kepada
masyarakat namun perlu juga pada para calon investor agar dapat mengetahui
perihal AMDAL di Indonesia. Karena proses pembangunan digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, sosial dan budaya.
Dengan implementasi AMDAL yang sesuai dengan aturan yang ada, maka
diharapkan akan berdampak positif pada pembangunan yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan (Mukono, 2005).
AMDAL didasarkan atas berbagai regulasi nasional yang telah ditetapkan
dengan baik serta berbagai acuan yang dikenal di seluruh sektor utama di
pemerintahan. Prosedur review dan persetujuan secara relatif telah menjadi
kebiasaan yang diterima dengan baik di dalam organisasi dan berlaku secara
umum di tingkat nasional dan propinsi, berdasarkan komite administratif dan
teknis lintas pemerintahan. Sistem tersebut didukung oleh suatu jaringan pusat
studi lingkungan yang menyediakan berbagai masukan teknis, pelatihan formal
dan kendali mutu, sementara berbagai reformasi penting juga telah dilakukan
untuk mencoba menstimulasi keterlibatan publik dalam jumlah yang lebih besar
dalam AMDAL (Purnama, 2003).
Secara lebih rinci prosedur teknis penyusunan dokumen AMDAL di
Indonesia sebagaimana termaktub dalam PP No. 27 tahun 1999 terdiri atas:
1. Pemrakarsa kegiatan menyampaikan ke instansi yang bertanggung jawab
terhadap rencana kegiatan.
2. Instansi yang bertanggung jawab berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup No. 17 tahun 2001 yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006 tentang kegiatan-kegiatan yang wajib
AMDAL.
3. Pemrakarsa diwajibkan melakukan pengumuman masyarakat dalam waktu 30
hari kerja dan selanjutnya menunggu tanggapan dari masyarakat.
40
4. Pemrakarsa menyusun kerangka acuan (KA-ANDAL).
5. Kerangka acuan dinilai oleh tim teknis, pakar pada sidang komisi.
6. Komisi AMDAL menerbitkan surat keputusan kelayakan dalam waktu 75 hari
kerja.
7. Pemrakarsa menyusun AMDAL bersama dengan pihak ketiga yang ditunjuk
oleh pemrakarsa.
8. Dokumen AMDAL dinilai oleh tim teknis dan para pakar pada sidang komisi
(sidang komisi 1 dan sidang komisi 2).
9. AMDAL disetujui dalam jangka 75 hari kerja.
AMDAL bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri tetapi merupakan
bagian dari proses AMDAL yang lebih besar dan lebih penting sehingga AMDAL
dapat dikatakan berguna bagi pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan,
pengelolaan proyek, pengambilan keputusan, dan menjadi dokumen yang penting.
Sedangkan peranan AMDAL dalam pengelolaan kegiatan yakni sebagai: a) fase
identifikasi, b) fase studi kelayakan, c) fase desain kerekayasaan (engineering
design) atau disebut juga sebagai fase rancangan, d) fase pembangunan proyek, e)
fase proyek berjalan atau fase proyek beroperasi, dan f) fase proyek telah berhenti
beroperasi atau pascaoperasi.
Lingkupan dan fase-fase dalam proses penyusunan AMDAL tersebut
memerlukan pengembangan metodologi. Metode yang dipakai dalam penentuan
dampak besar dan penting antara lain:
1. Metode Leopold ini juga dikenal sebagai Matriks Leopold atau matriks
interaksi dari Leopold. Metode matriks ini mulai diperkenalkan oleh Leopold
dan teman-temannya pada tahun 1971. Matriks yang diperkenalkan adalah
matriks dari 100 macam aktivitas dari suatu proyek dengan 88 komponen
lingkungan. Identifikasi dampak lingkungan dari proyek ditulis dalam
interaksi antara aktivitas dan komponen lingkungan. Macam-macam aktivitas
proyek dan komponen-komponen lingkungan dalam Matriks Leopold.
Aktivitas proyek dibagi menjadi 100 aktivitas yang terdiri dari 10 kelompok:
a) modifikasi areal 13 aktivitas, b) perubahan lahan dan pembuatan bangunan
fisik, c) ekstraksi sumberdaya, d) pemrosesan, e) perubahan lahan, f)
pembaharuan sumberdaya, g) perubahan lalu lintas, h) penempatan dan
41
pengolahan limbah, i) pengolahan bahan kimia dan j) kecelakaan. Komponen
lingkungan dibagi menjadi 88 yang terdiri dari 5 kelompok sebagai berikut: a)
fisik dan kimia yang terdiri dari bumi, air, atmosfer dan proses, b) keadaan
biologi yang terdiri dari flora dan fauna dan c) sosial budaya yang terdiri dari
tata guna lahan, rekreasi, estetika dan minta masyarakat, status budaya,
fasilitas dan aktivitas buatan manusia, ekologi dan lain-lain komponen.
2. Metode yang diperkenalkan Moore tahun 1973 dikenal pula dengan nama
Matriks dampak dari Moore. Keistimewaan dari metode Moore adalah
dampak lingkungan dilihat dari sudut dampak pada kelompok daerah yang
sudah atau sedang dimanfaatkan manusia atau dapat digambarkan pula sebagai
proyek pembangunan manusia lainnya.
3. Metode yang dikembangkan Sorenson pada tahun 1971 merupakan analysis
networks yang pertama. Disusun untuk digunakan pada proyek pengerukan
dasar laut (dreging). Bentuk jaringan kerja ini diberi nama sebagai aliran
dampak.
Penggunaan metode-metode tersebut merupakan metode standar yang
umumnya digunakan dalam penyusunan AMDAL. Selain itu untuk lebih
mengetahui sisi AMDAL di Indonesia, berbagai pengalaman penyusunan
AMDAL di negara maju dan berkembang dapat dijadikan sebagai bahan
perbandingan ke arah yang lebih baik. AMDAL negara lain diambil untuk melihat
kegiatan usaha AMDAL di negara berkembang yaitu Filipina dan negara maju
yakni Kanada.
1. Philipina
Pedoman sistem evaluasi laporan AMDAL di Filipina ditetapkan pada
tahun 1978 oleh National Environmental Protection Council (NEPC) yang berada
di bawah departemen sumberdaya alam. Skema dapat dijelaskan secara singkat
sebagai berikut:
Langkah pertama NEPC menetapkan instansi mana yang akan menjadi
instansi yang bertanggung jawab atau lead agency dari proyek yang diusulkan.
Langkah kedua pemrakarsa proyek menyampaikan usulan proyeknya
dengan laporan Initial Environmantal Evaluation (IEE) atau PIL yang disusun
42
menyampaikan usulan proyeknya dengan pemerintah kepada instansi yang
bertanggung jawab.
Langkah ketiga instansi yang bertanggung jawab mengevaluasi usulan dan
laporan IEE untuk menetapkan perlu studi AMDAL atau tidak. Hasil evaluasi
yang merupakan tiga kemungkinan sebagai berikut: a) apabila diputuskan perlu
studi AMDAL maka pemrakarsa proyek diberitahu untuk menyelenggarakan studi
ANDAL, b) apabila diputuskan tidak perlu mengadakan studi AMDAL maka
proses perizinan dapat dilakukan untuk dapat membangun proyek, c) apabila
instansi yang bertanggung jawab ragu-ragu atau tidak tahu maka instansi ini dapat
berkonsultasi dan menanyakan kepada NEPC.
Langkah keempat adalah langkah yang harus dilakukan pemrakarsa
proyek apabila ditetapkan harus melakukan studi ANDAL. Maka pelaksanaan
studi ANDAL merupakan tanggung jawab pemrakarsa proyek dan kemudian
menyusun laporan draft ANDAL. Masih disebut draft karena belum dievaluasi
dan belum disetujui oleh yang mengevaluasi.
Langkah kelima menyerahkan laporan draft ANDAL kepada instansi yang
bertanggung jawab. Instansi yang bertanggung jawab mengirim ke instansi-
instansi lain yang erat hubungannya dengan proyek (berdasarkan suatu pedoman
atau suatu surat keputusan) untuk mendapatkan pendapat-pendapat atau saran-
sarannya. Instansi yang bertanggung jawab tersebut juga menetapkan apakah
usulan proyek ini perlu dengar pendapat atau public hearing karena tidak semua
proyek harus ada dengar pendapat. Apabila dianggap perlu pemrakarsa proyek
diberitahu. Apabila ditetapkan perlu dengar pendapat maka instansi yang
bertanggung jawab menyelenggarakan dengar pendapat.
Langkah keenam merupakan kesibukan dari instansi yang bertanggung
jawab untuk mengumpulkan semua pendapat-pendapat dari berbagai instansi yang
ikut mengevaluasi (secara tertulis) dan hasil dari dengar pendapat kalau diadakan,
kemudian mengirimkannya ke NEPC. NEPC menyusun reviews dari laporan
draft, pendapat-pendapat dari berbagai instansi pemerintah dan dengar pendapat
apabila ada. NEPC menyampaikan hasil reviews kepada instansi yang
bertanggung jawab. Instansi yang bertanggung jawab meneruskan reviews ke
pemrakarsa proyek. Pemrakarsa proyek berdasarkan review termasuk saran-saran
43
dari NEPC menyusun laporan akhir AMDAL dan dikirim ke instansi yang
bertanggung jawab.
2. Kanada
Sistem evaluasi laporan AMDAL di Kanada yang berlaku untuk proyek-
proyek federal dikeluarkan oleh kabinet pada tanggal 20 Desember 1973. Sistem
evaluasi di Kanada disebut sebagai Environmental Assestment and Review
Process (EARP) atau proses pendugaan dampak dan review. Berdasarkan
pedoman yang telah diperbaiki dan dikeluarkan pada tahun 1979, pedoman sistem
evaluasi yang dikeluarkan tahun 1973 tersebut terus dilakukan penyempurnaan, di
antaranya penyempurnaan pedoman pada tahun 1979, tahun 1984, dan pada tahun
1985 sedang disempurnakan lagi pada bagian penyaringan dan pelaksanaan PIL.
Secara garis besar skema tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pemrakarsa proyek menyampaikan usulannya kepada instansi yang
bertanggung jawab terhadap proyek tersebut dan melakukan penyaringan
atau screening untuk menilai potensi dampak lingkungan dari proyek.
Pedoman dari penyaringan dibuatkan oleh kantor lingkungan yang disebut
The Federal Environtmental Assestment Review Office (FEARO) dalam
pekerjaannya memberikan laporannya langsung kepada Menteri Lingkungan
Federal.
2. Secara garis besar kesimpulan dari penyaringan tersebut adalah: a) proyek
yang tidak ada dampak negatifnya atau dampak negatifnya ada tetapi tidak
nyata atau penting atau telah tersedia teknologi yang dapat menekan atau
menghilangkan dampak tersebut maka proyek tersebut dapat dibangun tanpa
PIL atau ANDAL, b) proyek yang mempunyai potensi dampak lingkungan
yang tidak atau belum diketahui maka perlu dilakukan studi IEE atau PIL
yang kemudian akan dilakukan penyaringan kembali untuk menentukan
apakah potensi dampaknya nyata atau tidak. Kalau dianggap perlu
mengadakan review dari dengar pendapat masyarakat, maka suatu panel
yang dibentuk oleh FEARO akan menyelenggarakan penyaringan tersebut.
Bila penyaringan menghasilkan kesimpulan bahwa potensi dampak
lingkungan tidak dapat diterima atau tidak diizinkan terjadi maka proyek
tersebut dapat ditolak untuk dibangun atau apabila pemrakarsa proyek
44
bersedia mengadakan perubahan dalam usulan proyeknya maka akan dapat
dilakukan evaluasi atau penyaringan lagi. Kalau hasil dari studi PIL
menyimpulkan bahwa proyek tersebut potensi dampaknya tidak ada atau
tidak nyata atau tersedia teknologi untuk menekan proyek tersebut boleh
dibangun tanpa membuat ANDAL tetapi kalau hasil penyaringan
menunjukkan dampak negatif nyata dan penting proyek tersebut harus
melakukan ANDAL. Dua langkah pertama yaitu penyaringan dan studi PIL
masih merupakan tanggung jawab instansi atau departemen yang
bertanggung jawab mengenai proyek, sedang FEARO dan Departemen
Lingkungan belum ikut berperan walaupun konsultasi dan permintaan
pedoman penyaringan dan IEE diminta dari FEARO.
3. Apabila ada proyek yang diputuskan oleh instansi yang bertanggung jawab
bahwa proyek tersebut perlu melakukan studi AMDAL maka usulan proyek
dikirim ke FEARO. Kemudian FEARO akan membentuk suatu kelompok
ahli yang disebut panel khusus untuk menangani ANDAL proyek tersebut.
Biasanya panel ini terdiri dari empat sampai delapan anggota yang dipilih
berdasarkan keahliannya dan pengalamannya yang berhubungan dengan
AMDAL, proyek tersebut, pengetahuan dan pengalaman dalam lingkungan
dan dampak sosial pada proyek tersebut. Ketua FEARO atau wakilnya yang
ditunjuk akan menjadi sekretaris eksekutif dari panel.
4. Setelah panel dibentuk maka panel menyusun pedoman atau TOR mengenai
penyusunan analisis dampak lingkungan (ANDAL) khusus untuk usulan
proyek tersebut dan menyampaikan kepada pemrakarsa proyek untuk
dijalankan. Dalam penyusunan pedoman tersebut panel juga mengadakan
konsultasi dengan instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang sangat
erat hubungannya dengan proyek tersebut dan juga masyarakat.
5. Kemudian pemrakarsa atau konsultasi yang diminta bantuannya melakukan
studi ANDAL dan menyusun laporan ANDAL. Dalam melakukan studinya
atau penyusunan laporan ANDAL-nya selalu dapat melakukan konsultasi
dengan panel.
6. Hasil laporan ANDAL akan langsung dievaluasi oleh panel apakah sudah
cukup baik atau masih ada kekurangan dan kalau masih ada kekurangan
45
pemrakarsa proyek harus melengkapinya. Dalam melakukan evaluasi
laporan ini panel dapat meminta bantuan pendapat dari berbagai instansi
yang erat hubungannya dengan proyek.
7. Apabila laporan ANDAL tersebut sudah dinilai baik dan diterima oleh panel
maka panel lalu menyelenggarakan review. Dalam review ini panel
mengumpulkan pendapat-pendapat dari berbagai instansi teknis dan
masyarakat baik secara tertulis maupun secara lisan dalam suatu pertemuan.
Bila panel akan menyelenggarakan dengar pendapat masyarakat atau public
hearing, maka biasanya diselenggarakan di tempat proyek yang akan
dibangun. Dengan demikian masyarakat setempat yang akan terkena dampak
dapat memberikan pendapatnya.
8. Setelah semua pendapat-pendapat baik dari instansi-instansi pemerintah,
ahli-ahli, dan masyarakat maka panel melakukan evaluasi pendapat-pendapat
dan menyusun sarannya atau rekomendasinya mengenai proyek tersebut
langsung kepada menteri lingkungan dan menteri yang bertanggung jawab
atas proyek tersebut. Dalam menyusun rekomendasi tersebut panel selalu
dapat berkonsultasi dengan kedua menteri tersebut. Apabila proses review
yang dilakukan oleh panel selesai maka akan disusun suatu laporan hasil
review untuk menteri lingkungan yang biasanya sebagai berikut : a) sejarah
kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pembangunan proyek, b)
deskripsi dari proyek, c) keadaan dan sifat lingkungan dari lokasi yang
dimasukkan akan dibangun proyek tersebut, d) dampak lingkungan dan
sosial dari proyek dalam review termasuk pendapat instansi pemerintah, ahli-
ahli, dan masyarakat, e) kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari panel
mengenai pelaksanaan pembangunan proyek. Saran dari panel dapat
berbentuk tiga kemungkinan sebagai berikut: a) proyek boleh dibangun atau
dijalankan sesuai dengan rencana, b) proyek boleh dibangun tetapi dengan
perubahan baik dalam proyeknya ataupun pengelolaan lingkungan, c) proyek
tidak boleh dibangun.
9. Menteri lingkungan dan menteri yang bertanggung jawab atas proyek akan
mempertimbangkan saran panel apakah dapat diterima. Bila kedua menteri
telah mendapatkan suatu kesepakatan maka menteri lingkungan
46
mengeluarkan keputusan yang akan dilaksanakan oleh departemen atau
instansi yang bertanggung jawab atas proyek. Namun apabila kedua menteri
tidak menemukan kesepakatan, maka persoalan tersebut akan dibawa ke
kabinet untuk diputuskan.
2.3 Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
Berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Minyak
bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan
dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral
atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak
termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan
gas bumi.
Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam
kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari
proses penambangan minyak dan gas bumi. Bahan bakar minyak adalah bahan
bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Kegiatan migas meliputi
eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/pengolahan dan pengangkutan/pemasaran. Pada
saat ini terdapat kurang lebih 115 perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia,
baik yang berstatus eksplorasi maupun produksi. Perusahaan-perusahaan tersebut
sekitar 70% beroperasi di darat (on shore) dan sekitar 30% beroperasi di lepas
pantai (off shore) baik di laut dangkal maupun di laut dalam. Operasi di laut
dangkal antara lain di Laut Jawa, Kalimantan Timur, dan Sumatera sedangkan
yang operasi di laut dalam mencakup perairan laut Makasar, Natuna, Irian Jaya
dan Selat Malaka.
Kegiatan migas pada masa mendatang dengan kemajuan teknologi dan
perkembangan ilmu pengetahuan dimungkinkan untuk mencari cebakan minyak
pada daerah-daerah "frontier" khususnya Indonesia bagian Timur ke arah laut
dalam. Sebagaimana pengembangan migas 25 tahun mendatang antara lain
meningkatkan produksi dan pengembangan lapangan-lapangan migas lepas pantai
(off shore) yang sudah berproduksi, meningkatkan eksplorasi ke kawasan timur
47
Indonesia seperti cekungan Makassar, Irian Jaya dan juga kawasan karat
Indonesia.
Kegiatan migas di Indonesia tersebar pada beberapa kepulauan yaitu di
pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan serta Irian Jaya meliputi:
1. Kegiatan hulu terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi, kegiatan eksploitasi
yaitu: a) kegiatan pemboran eksplorasi untuk mencari cadangan minyak
kegiatan ini tidak berdampak penting sesuai keputusan menteri LH No. 11
tahun 2006 tidak mewajibkan menyusun AMDAL, b) kegiatan eksploitasi
yaitu kegiatan operasi produksi, memproduksi minyak dan pemboran sumur-
sumur produksi, c) kegiatan yang berstatus eksplorasi dan produksi (hulu)
antara lain :1) Pertamina eksplorasi: Sumatera Utara, Sumatera bagian tengah
(Riau, Sumatera Selatan), Jawa Barat (Cirebon, Cepu), Kalimantan, dan
Papua, 2) kontraktor/kontrak kerja sama (KKS), swasta-swasta asing maupun
nasional antara lain, Chevron Pasifik Indonesia (CPI), Total Indonesia,
UNOCAL, CONOCO Phillip, CNOOC, dan Petrochina. 3) JOB : Joint
Operation Body dan 4) TAC Technic Assistance Contract.
2. Kegiatan hilir terdiri dari: a) unit pengolahan minyak (UP) yaitu pengelolaan
minyak untuk menjadi produk BBM antara lain : UP I Pangkalan Berandan,
UP II Dumai, UP III Pelaju Sungai Gerong, UP IV Cilacap, UP V Balikpapan,
UP VI Balongan dan UP VII Sorong, b) unit pengolahan gas LPG dan LNG,
dan c) kegiatan niaga/pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia.
2.4 Konsep Valuasi Ekonomi
Valuasi ekonomi adalah suatu upaya untuk memberikan nilai kuantitatif
terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan
terlepas dari apakah nilai pasar (market price) tersedia atau tidak (Fauzi, 1999).
Akar dari konsep penilaian ini sebenarnya berlandaskan dari teori ekonomi neo-
klasikal yang menekankan pada kepuasan atau keperluan konsumen. Berdasarkan
pemikiran neo-klasik ini dikemukakan bahwa setiap individu pada barang dan jasa
tidak lain adalah selisih antara keinginan membayar (willingness to pay) dengan
biaya untuk mensuplai barang dan jasa tersebut (Barbier, 1995).
48
Nilai ekonomi dapat diartikan sebagai ukuran jumlah keinginan
maksimum seseorang yang bersedia mengorbankan barang dan jasa untuk
mendapatkan barang dan jasa lainnya. Konsep ini sering disebut sebagai
keinginan membayar (willingness to pay) seseorang terhadap barang dan jasa
yang dihasilkan oleh sumberdaya alam (tidak selalu bahwa nilai tersebut harus
diperdagangkan untuk mengukur nilai moneternya). Sebaliknya dapat diukur dari
sisi lain yakni seberapa besar masyarakat harus diberikan kompensasi untuk
menerima pengorbanan atas hilangnya barang dan jasa dari sumberdaya dan
lingkungan.
Dalam memberikan penilaian terhadap hasil dari suatu kegiatan, perlu
diketahui urutan dalam memberikan penilaian (Suparmoko, 2000), yaitu: 1)
mengidentifikasi dampak penting lingkungan, 2) mengkuantifikasi besarnya
dampak dan 3) perubahan kuantitas fisik kemudian diberi harga/nilai uang dalam
rupiah.
Masalah yang perlu diperhatikan dalam penilaian ekonomi adalah hasil
total atau produktivitas atau keuntungan yang didapat dari semua sumber yang
dipakai dalam suatu kegiatan untuk masyarakat sehingga diperoleh ”social
returns” atau ”economic return” yang paling tinggi (Kadariah et al., 1978).
Setiap kegiatan pembangunan umumnya menghasilkan dampak terhadap
lingkungan, demikian pula dalam setiap tahap kegiatan industri minyak dan gas
bumi termasuk unit pengolahan minyak. Industri ini berpotensi menimbulkan
dampak yang bersifat positif maupun yang negatif terhadap lingkungan alam
(ekosistem), sosial budaya, sosial politik dan ekonomi (Abda’oe, 1994). Dampak
lingkungan, ekonomi dan sosial dari kegiatan unit pengolahan minyak secara
umum dapat terlihat dari pengaruhnya secara langsung terhadap aktivitas utama di
wilayah pesisir. Permasalahan dan isu lingkungan mengenai dampak aktivitas
migas di suatu wilayah, namun tidak jarang hanya ditanggapi dengan melakukan
identifikasi tanpa ada tindak lanjut untuk menghitung besarnya nilai ekonomi
yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumberdaya alam. Kondisi ini diperparah
dengan tidak tersedianya data ekonomi dan lingkungan suatu wilayah. Tujuan
valuasi ekonomi pada dasarnya adalah membantu pengambil keputusan untuk
menduga efisiensi ekonomi dari berbagai pemanfaatan (competing use) yang
49
mungkin dilakukan terhadap ekosistem yang ada. Asumsi yang mendasari fungsi
ini adalah bahwa alokasi sumberdaya yang dipilih adalah yang mampu
menghasilkan manfaat bersih bagi masyarakat (net gain to society) yang diukur
dari manfaat ekonomi dari alokasi tersebut dikurangi dengan biaya alokasi
sumberdaya tersebut (Adrianto, 2005)
Pengelolaan lingkungan dapat dicapai dengan menerapkan ekonomi
lingkungan sebagai instrumen yang mengatur alokasi sumberdaya secara rasional
(Steer, 1996). Nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam sumberdaya alam
sangat peran dalam penentuan kebijakan pengelolaannya, sehingga alokasi dan
alternatif pengelolaannya dapat efisien dan berkelanjutan. Hilangnya ekosistem
atau sumberdaya alam dan lingkungan merupakan masalah ekonomi karena
hilangnya ekosistem berarti hilangnya kemampuan ekosistem tersebut untuk
menyediakan barang dan jasa. Dalam beberapa kasus, hilangnya ekosistem ini
tidak dapat dikembalikaqn seperti sediakala (irreversible). Pilihan kebijakan
pembangunan yang melibatkan sumberdaya alam (ekosistem) seperti kebijakan
tetap mempertahankan ekosistem apa adanya atau dikonversi menjadi
pemanfaatan lain merupakan persoalan pembangunan yang dapat dipecahkan
dengan menggunakan pendekatan valuasi ekonomi (Adrianto, 2006).
Valuasi ekonomi sumberdaya alam adalah seluruh manfaat yang
disediakan oleh sumberdaya alam dari yang digunakan saat ini dan manfaat untuk
masa yang akan datang. Valuasi ekonomi adalah salah satu dari banyak cara
untuk menggambarkan dan mengukur nilai sumberdaya alam, baik yang bernilai
pasar (dapat diperdagangkan) maupun yang tidak bernilai pasar (tidak dapat
diperdagangkan) (Williamson, 2003).
Tujuan penilaian ekonomi lingkungan adalah untuk memperkuat mata
rantai antara lingkungan dan ekonomi. Penerapan penilaian ekonomi dalam
sumberdaya alam dan lingkungan melalui berbagai teknik ekonomi adalah salah
satu metode untuk mempromosikan pengintegrasian dari lingkungan, ekonomi
dan sosial (Williamson, 2003). Selain itu, tujuan valuasi ekonomi pada dasarnya
adalah membantu pengambil keputusan untuk menduga efisiensi ekonomi dari
berbagai pemanfaatan (competing use) yang mungkin dilakukan terhadap
ekosistem yang ada. Asumsi yang mendasari fungsi ini adalah bahwa alokasi
50
sumberdaya yang dipilih adalah yang mampu menghasilkan manfaat bersih bagi
masyarakat (net gain to society) yang diukur dari manfaat ekonomi dari alokasi
tersebut dikurangi dengan biaya alokasi sumberdaya tersebut (Adrianto, 2005).
Kerangka nilai ekonomi yang sering digunakan dalam valuasi ekonomi
sumberdaya alam adalah konsep total economic value (TEV) atau nilai ekonomi
total. Terdapat tiga metode yang digunakan secara umum dalam valuasi ekonomi
dan dampak ekonomi terhadap lingkungan. Ketiga metode tersebut adalah: 1)
Market valuation adalah pendekatan yang menggunakan penilaian ekonomi dari
sumberdaya alam alam berdasar nilai pasar. Pendekatan ini biasanya digunakan
untuk menilai aset ekonomi (economic asset) dari sumberdaya alam. Apabila nilai
pasar dari sumberdaya alam tidak tersedia, karena jumlah sumberdaya alam
tersebut tidak diketahui, nilai ekonomi dari sumberdaya alam tersebut dapat
ditemukan dari jumlah penerimaan potensial dari sumberdaya tersebut dengan
pendekatan diskonto, 2) Maintenance valuation adalah pendekatan yang
didasarkan pada penilaian terhadap opportunity cost yang hilang sebagai akibat
suatu tindakan ekonomi dan juga opportunity cost dari tindakan maintenance
untuk mengurangi dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan, dan 3)
Contingent and related damaged valuation adalah pendekatan yang didasarkan
penggunaaan cost-benefit analysis dan feasibility study dalam melakukan kegiatan
ekonomi (Bartelmus and Vespers, 1999).
Pendekatan ini sangat efektif untuk digunakan dalam penilaian kegiatan
ekonomi skala kecil, akan tetapi sangat sulit untuk diimplementasikan dalam
penilaian skala luas/nasional. Penentuan nilai ekonomi sumberdaya alam
merupakan hal yang sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam
mengalokasikan SDA yang semakin langka (Kramer et al., 1995). Penilaian
manfaat lingkungan secara ekonomi dengan sangat kecil atau sangat besar harus
ditinggalkan, saat ini barang atau jasa lingkungan yang diperoleh harus dinilai
keuntungannya secara finansial (Barbier, 1995).
Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh para peneliti saat menghitung nilai
suatu sumberdaya adalah adanya nilai dari barang atau jasa yang tidak dapat
dikuantifikasikan dengan nilai pasar, karena memang barang atau jasa tersebut
tidak dijual di pasaran, seperti keindahan alam. Memahami permasalahan tersebut,
51
Krutila (1967) dalam Fauzi (2002) memperkenalkan konsep total economic value
(TEV) atau nilai ekonomi total bagi setiap individu atas sumberdaya alam dan
lingkungan. Secara garis besar jenis-jenis nilai dari TEV dibagi menjadi dua,
yaitu nilai kegunaan dan nilai bukan kegunaan.
1. Nilai Kegunaan
Nilai kegunaan adalah nilai yang dihasilkan dari pemanfaatan aktual dari
barang dan jasa seperti menangkap ikan, menebang kayu dan sebagainya. Nilai ini
juga termasuk pemanfaatan secara komersial atas barang dan jasa yang dihasilkan
oleh sumberdaya alam, misalnya ikan dan kayu yang hasilnya dapat dijual (Fauzi,
2002). Nilai kegunaan ini merupakan nilai manfaat yang dirasakan oleh
masyarakat. Nilai kegunaan ini lebih mudah diukur dengan menggunakan harga
pasar. Nilai kegunaan sendiri dibagi menjadi dua yaitu nilai kegunaan langsung
yakni: 1) nilai kegunanaan langsung dari suatu sumberdaya yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara komersial maupun non komersial.
Misalkan jika kita sedang menghitung nilai ekonomi dari sumberdaya danau,
maka yang dimaksud dengan nilai kegunaan langsung adalah menangkap ikan, 2)
nilai kegunaan tidak langsung yaitu nilai yang dirasakan secara tidak langsung
oleh masyarakat terhadap suatu sumberdaya. Contoh dari nilai ini adalah fungsi
pencegah abrasi pada hutan mangrove.
2. Nilai Bukan Kegunaan
Nilai bukan kegunaan atau non use value merupakan nilai yang tidak
berhubungan dengan pemanfaatan aktual barang dan jasa yang dihasilkan oleh
sumberdaya alam (Fauzi, 2002). Nilai bukan kegunaan ini bersifat sulit diukur
karena nilai-nilai tersebut sulit dikuabtifikasikan dengan harga pasar dan
menyangkut kesukaan (preferensi) seseorang.
Nilai bukan kegunaan ini secara lebih mendetail dibagi lagi menjadi tiga
jenis yaitu option value, existence value dan bequest value. Option value atau nilai
pilihan adalah nilai yang diberikan oleh masyarakat atas adanya pilihan untuk
menikmati barang atau jasa dari sumberdaya alam dimasa yang akan datang
(Fauzi, 2002). Pada dasarnya option value ini mengandung makna ketidakpastian
atas ketersediaan sumberdaya pada masa yang akan datang maka nilai option
52
value kita akan menjadi nol. Begitu juga sebaliknya nilai dari option value akan
semakin besar jika masyarakat tidak yakin akan ketersediaan suatu sumberdaya
pada masa yang akan datang.
Existence value atau nilai keberadaan adalah nilai yang diberikan atas
keberadaan atau terpeliharanya sumberdaya alam dan lingkungan meskipun
masyarakat tidak akan memanfaatkan atau mengunjunginya. Nilai eksistensi ini
sering juga disebut dengan intrinsic value atau nilai intrinsik dari sumberdaya
alam atau nilai yang memang sudah melekat pada sumberdaya alam itu (Fauzi,
2002).
Bequest value atau nilai pewarisan artinya nilai yang diberikan oleh
generasi kini dengan menyediakan atau mewariskan (bequest) sumberdaya untuk
generasi mendatang atau mereka yang belum lahir. Jadi bequest value diukur
berdasarkan keinginan membayar masyarakat untuk memelihara (to preserve)
sumberdaya alam dan lingkungan untuk generasi mendatang (Fauzi, 2002).
2.5 Hasil Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan
kebijakan AMDAL dan valuasi ekonomi sebagai berikut:
Tabel 1 Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan AMDAL dan valuasi ekonomi
Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Alshuwaikkat (2004)
Strategic Environment Assessment (SEA) sebagai Alternatif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Negara Berkembang
- SEA dapat memunculkan dampak dari aktivitas skala kecil yang sesungguhnya dampaknya penting.
- SEA memunculkan dampak kumulatif dari beberapa proyek, mampu menjelaskan dampak potensial yang tidak diatur dalam undang-undang, serta dapat menunjukkan aktivitas proaktif yang terstruktur terhadap pengaruh kebijakan dan perencanaan
Purnama (2003) Public Involment in the Indonesia EIA Process, Perceptions, and Alternative
- EIA sama pada semua negara berkembang, khususnya pada peran masyarakat, keterbatasan panduan, dasar hukum yang
53
Lanjutan Tabel 1
Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian kurang memadai, perencanaan TOR kurang jelas, perbaikan hukum dan perencanaan yang menyeluruh.
Tiwi (2003) Evaluasi AMDAL dalam Menunjang Pengelolaan Pantai Terpadu di Teluk Banten
- Ketersediaan informasi lingkungan di Tk II dalam hal ini kawasan Teluk Banten untuk menyusun dan menilai laporan AMDAL maupun dari hasil pemantauan lingkungan adalah sangat terbatas, terutama informasi tentang biologi laut, informasi penting dalam pengelolaan pantai terpadu.
- Penelitian penunjang keberadaan informasi tersebut juga masih terbatas, kalaupun ada informasinya berada di instansi tingkat pusat.
- Pertukaran informasi lingkungan yang tersebar di beberapa instansi juga belum terjadi, sementara pemda sendiri belum dilengkapi dengan peraturan yang mendukung aksesibilitas mereka terhadap informasi lingkungan tentang daerahnya.
- Kapasitas Pemda Tk II pada kasus Teluk Banten masih membutuhkan suatu perbaikan dalam penyediaan informasi lingkungan baik untuk proses AMDAL maupun untuk pengelolaan terpadu kawasan pantainya.
Finnveden et al., (2002)
Metode Aplikasi SEA dalam Sektor Energi
- SEA yang berhubungan dengan pencemaran energi diusulkan antara lain: ecological impact assesment, envromentally estended input/output analysis,
54
Lanjutan Tabel 1
Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian multiple atribut analysis, environmental objective, dan risk assessment.
Azis (2006) Nilai Ekonomi Total Ekosistem Hutan Mangrove di Kawasan Pesisir sebagai Alternatif Pengelolaan
- Nilai ekonomi total ekosistem hutan mangrove yaitu Rp. 1,24 milyar per tahun.
Santoso (2005) Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove di Desa Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat,
- Nilai ekonomi total ekosistem hutan mangrove yaitu Rp.3,7 milyar per tahun.
Sofyan (2003) Pengkajian Nilai
Ekonomi Lingkungan Ekosistem Hutan Mangrove, di Desa Blanakan Kabupaten Subang, Jawa Barat
- Nilai ekonomi total ekosistem hutan mangrove yaitu Rp.2,8 milyar per tahun.
Supriyadi dan Wouthuyzen (2005)
Valuasi Ekonomi terhadap Ekosistim Mangrove di Teluk Kotania, Propinsi Maluku
- Nilai ekonomi total dari hutan mangrove di Teluk Kotania pada tahun 1999 adalah Rp.64,8 milyar atau Rp.60,9 juta per ha. Nilai ini masih terlalu rendah, karena masih banyak komponen lain pada hutan mangrove yang sulit untuk ditentukan baik fungsi maupun harga pasarnya.
- Keunikan mangrove di Teluk Kotania dimana mangrove, padang lamun dan terumbu karang hidup berdampingan secara harmonis.
- Khusus untuk kasus Teluk Kotania, valuasi ekonomi perlu dilalukan untuk ketiga ekosistim tersebut.
Haya et al., (2003)
Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang dengan Studi Kasus Penangkapan
- Kebijakan yang ada dalam menanggulangi penggunaan sianida dan bom di Kepulauan Spermonde, tidak efektif dan efisien.
55
Lanjutan Tabel 1
Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Ikan Yang Merusak (sianida dan bom) di Kepulauan Spermonde, Propinsi Sulawesi Selatan
- Pembuatan produk hukum dan perundangan tidak didasarkan pada kepentingan publik dan kelestarian terumbu karang sehingga aktivitas tersebut terus berlangsung.
- Dengan menggunakan pendekatan AHP dalam kerangka manfaat dan biaya (B/C) diperoleh empat opsi kebijakan untuk menanggulangi kasus penggunaan sianida dan bom di Kepulauan Spermonde yaitu: pendidikan dan informasi lingkungan (0,275) diversifikasi usaha dan pengembangan mata pencaharian alternatif (0,273) koordinasi antar stakeholders (0,253) serta peraturan dan penegakkan hukum (0,199).
Rahmalia (2003) Analisis Tipologi dan Pengembangan Desa-Desa Pesisir Kota Bandar Lampung
- Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa para stakeholders cenderung lebih memilih industri sebagai prioritas utama dalam pengembangan dan pengelolaan desa-desa pesisir Kota Bandar Lampung yang dititik beratkan pada aspek ekonomi melalui kriteria utama peningkatan lapangan kerja dengan pelaku utama pemerintah diikuti swasta.
- Sektor industri sifatnya tidak sensitif terhadap perubahan preferensi dan untuk hasil analisis analisis tipologi sebagian besar desa pesisir tergolong tipologi II yaitu wilayah dengan tingkat perkembangan rendah atau kurang maju dibanding
56
Lanjutan Tabel 1
Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian kelurahan-kelurahan lain di Bandar Lampung.
- Adapun ciri-ciri dari tipologi II ini adalah: tingkat kesejahteraan penduduknya rendah ditandai dengan tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan besarnya surat keterangan miskin yang dikeluarkan kantor desa. Walaupun demikian dijumpai beberapa pemukiman mewah sebagai rumah peristirahatan di lokasi ini.
- Aksesibilitas cukup tinggi tetapi tidak ditunjang oleh fasilitas kesehatan yang cukup.
PPLH UNRI (2004)
Aspek Sosial Ekonomi Budaya di PT.Pertamina Kilang Produksi UP II Dumai, Riau
- Ada beberapa dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar kilang seperti gangguan bau, debu dan kebisingan.
- Persepsi masyaralkat terhadap pertamina memperlihatkan kecenderungan makin positif, proporsi yang mempunyai hubungan akrab dengan karyawan mengalami peningkatan dari 23% (tahun 2000) menjadi 505 (tahun 2003 dan 2004) demikian pula halnya dengan buruh kontraktor (mitra kerja pertamina) pada umumnya positif, dengan proporsi 49% responden (tahun 2000) akrab dengan buruh kontraktor dan meningkat menjadi 75,5% (tahun 2003 dan 2004).
57
III. GAMBARAN UMUM KEGIATAN MIGAS DI INDONESIA
3.1 Sejarah Kegiatan Migas di Indonesia
Kegiatan pencarian minyak dan gas bumi di Indonesia telah berlangsung
sejak tahun 1871, hanya berselang dua belas tahun setelah minyak dunia pertama
di bor di Pennsylvania. Produksi komersil pertama minyak dan gas bumi di
Indonesia dimulai pada tahun 1885 dan pada pengujung abad 1800, minyak bumi
telah diproduksi di kilang-kilang Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur dan
Kalimantan.
Pada tahun 1912 Standard Oil of New Jersey masuk ke Indonesia dan
kemudian menggabungkan kepentingan mereka di timur jauh dengan Mobil Oil
untuk membentuk Stanvac. Pada tahun 1936 terjadi penggabungan saham Asia
dengan Texaco untuk membentuk Caltex. Dengan demikian tercatat lima
perusahaan minyak internasional di Indonesia pada tahun 1940an. Pada tahun
tersebut produksi minyak Indonesia berada pada tingkat kelima di dunia, namun
dua puluh lima tahun kemudian, turun menjadi peringkat kedua belas dunia,
sekalipun terdapat kenaikan produksi minyak secara signifikan.
Pada tahun 1961 lahirlah Undang-undang No. 44 tahun 1961 tentang
migas. Selain itu dibentuk pula 3 (tiga) perusahaan negara bidang migas yaitu PT.
Permina, PT. Permigan dan PT. Pertamin. Dari ketiga perusahaan negara tersebut
hanya Permina dan Pertamin saja yang mampu beroperasi dengan baik, sedangkan
Permigan dilikuidasi. Penggabungan selanjutnya dilakukan terhadap Permina dan
Pertamin menjadi Pertamina pada 20 Agustus 1968 melalui dekrit. Pada tahun
1962 selanjutnya ditandatangani 40 kontrak dengan pendapatan lebih kurang US$
6 juta. Pada awal penggabungan, Permina memiliki kapal sebanyak 55 unit kapal,
dengan tonase lebih dari 320.000 DWT. Pertamina terus meluaskan armadanya,
baik domestik maupun internasional. Data tahun 2007 Pertamina memiliki 36 unit
kapal yang terdiri dari tipe LR/MR/GP/Small/Lighter dengan tonase lebih kurang
770.000 DWT dan mengoperasikan lebih dari 100 unit kapal bukan milik, dengan
konsentrasi trading domestik untuk menjalankan misi pemerintah (PSO) dalam
menjamin keamanan supply BBM nasional. Meskipun dalam kurun waktu hampir
58
40 tahun terjadi peningkatan tonase kapal milik sebesar lebih dari 100%, namun
dengan jumlah ketersediaan cargo yang diangkut mencapai 28,359 juta LT (crude
oil) dan 47,174 juta LT (BBM) serta 805 ribu ton (non BBM) atau total 76,338
juta LT (2005).
Era kebangkitan kembali industri migas terjadi pada tahun 1970-an di
mana Indonesia kembali di barisan depan dalam pengembangan minyak dunia,
setelah Pertamina berhasil menemukan sumber-sumber minyak baru di berbagai
tempat di penjuru tanah air seperti di Jatibarang, Sumatera Utara, Kalimantan
Timur, yang diteruskan dengan melakukan pembangunan stasiun pengumpul
minyak dan prasarana lifting cargo, pengambil alihan Stanvac (Sungai Gerong)
oleh Pertamina dan pembangunan kilang minyak baru Dumai serta meningkatnya
jumlah penandatanganan kontrak bagi hasil (production sharing contract) dengan
IIAPCO, Total dan Union. Hal tersebut menunjukkan bahwa bisnis migas
Indonesia adalah bisnis internasional dan Pertamina telah memperoleh tempatnya
dalam masyarakat minyak dunia.
Pada 15 September 1971 disahkan dan diberlakukan undang-undang No.
08 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
(Pertamina). Dengan undang-undang ini Pertamina memperoleh hak kuasa
pertambangan dengan batas-batas wilayah dan persyaratan yang ditetapkan oleh
Presiden se-panjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi (migas).
Melalui undang-undang ini Pertamina melakukan peningkatan pengusahaan migas
di seluruh wilayah Indonesia dan pengem-bangan usaha, baik yang terkait dengan
migas maupun yang bukan migas.
Pada tanggal 17 September 2003, Pertamina berubah menjadi sebuah
perseroan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang
migas. Kedudukan Pertamina sama dengan perusahaan lain yang wajib tunduk
dengan UU No. 01 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, UU No. 19 tahun 2003
tentang BUMN dan ketentuan lain yang berlaku bagi perseroan pada umumnya.
Dari hasil produksi migas tahun 2006 dapat mencapai keuntungan sebesar US$ 3
miliar atau sekitar Rp. 24 triliun dan menjadi BUMN terbesar di Indonesia.
Berdasarkan data OPEC (2006), sekitar 77% (922 milyar barrel) minyak
dunia bersumber dari negara-negara anggota OPEC dan selebihnya sekitar 23%
59
(272 milyar barrel) bersumber dari negara-negara non OPEC. Indonesia
merupakan salah anggota OPEC yang memberikan sumbangan terhadap
pemenuhan kebutuhan minyak dunia, bersama Kuwait, Lybia, Nigeria, Venezuela,
Qatar, dan Anggola menyumbang sekitar 44% (405,68 milyar barrel), sementara
Saudi Arabia, Irak dan Iran menyumbang sekitar 56% (516,32 milyar barrel).
3.2 Potensi Minyak dan Gas Bumi Indonesia
Potensi cadangan minyak bumi dan kondensat Indonesia secara total pada
tahun 2006 yaitu 8.928,50 MMSTB (million million stock tank barrel), terdiri
atas: cadangan terbukti 4.558,20 MMSTB dan cadangan potensial 4.370,30
MMSTB. Cadangan tersebut mengalami penurunan, khususnya dalam kurun
waktu tujuh tahun terkahir, dengan cadangan minyak bumi dan kondesat pada
tahun 2001 tercatat secara total sebesar 9.753,40 MMSTB terdiri atas: cadangan
terbukti 5.094,60 MMSTB dan cadangan potensial 4.689,90 MMSTB. Data
tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan telah terjadi penuruan cadangan
minyak bumi dan kondensat sebesar 724,30 MMSTB atau sekitar 14,22%.
Cadangan minyak bumi dan kondensat tersebut tersebar pada 13 propinsi
yakni dengan cadangan terbesar terdapat di propinsi Riau dengan total potensi
yaitu 4.692,00 MMSTB. Sedangkan cadangan potensi terendah berada di propinsi
Sulawesi Selatan yaitu 23,39 MMSTB.
Tabel 2 Cadangan minyak bumi dan kondensat Indonesia tahun 2006 No. Propinsi Cadangan (MMSTB) 1 Nangroe Aceh Darussalam 114,29 2 Sumatera Utara 141,24 3 Riau 4,692,00 4 Sumatera Selatan 874,95 5 Kepulauan Riau 54,41 6 Jawa Barat 719,70 7 Jawa Timur 947,30 8 Sulawesi Selatan 23,39 9 Sulawesi Tengah 69.,07 10 Kalimantan Timur 985,48 11 Kalimantan Selatan 60,63 12 Maluku 97,89 13 Papua 148,94 Total 8.929,50
Sumber: Ditjen Migas, 2007 (MMSTB: million million stock tank barrel)
60
Cadangan gas bumi Indonesia secara total pada tahun 2006 yaitu sebesar
187,16 TSCF (triliun stock crude fuel) terdiri atas: cadangan gas terbukti 94,00
TSCF dan cadangan potensial 93,10 TSCF. Dalam kurun waktu tujuh tahun
terakhir kondisi cadangan gas bumi Indonesia meningkat sebesar 18,90 TSCF atau
naik sekitar 11,24% dari total cadangan gas bumi pada tahun 2001 yaitu 168,20
TSCF terdiri atas cadangan gas terbukti 92,10 TSCF dan cadangan potensial 76,10
TSCF. Cadangan gas bumi tersebut tersebar pada 14 propinsi yakni dengan
cadangan terbesar terdapat di Kepulauan Riau (Natuna) dengan total potensi yaitu
53,58 TSCF dan cadangan terendah berada di Propinsi Maluku yaitu 0,006 TSCF.
Tabel 3 Cadangan gas bumi Indonesia tahun 2006
No. Propinsi Cadangan (TSCF) 1 Nangroe Aceh Darussalam 4,57 2 Sumatera Utara 1,38 3 Riau 7,83 4 Sumatera Selatan 24,30 5 Kepulauan Riau 53,58 6 Jawa Barat 6,04 7 Jawa Timur 6,20 8 Salawesi Selatan 0,79 9 Sulawesi Tengah 3,92 10 Kalimantan Timur 42,40 11 Kalimantan Selatan 2,37 12 Maluku 0,006 13 Papua 24,47 14 Nusa Tenggara Timur 6,30
Total 184,16 Sumber: Ditjen Migas, 2007
3.3 Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia
Total produksi minyak bumi Indonesia tahun 2006 adalah sekitar 1 juta
barel per hari, terdiri atas produksi minyak 883 ribu barel per hari dan kondesat
yaitu 123 ribu barel per hari. Produksi minyak dalam kurun waktu tujuh tahun
terkahir, telah terjadi penurunan produksi minyak bumi sekitar 335 ribu barel per
hari atau sekitar 24,99% dibanding produksi pada tahun 2001 yaitu 1,3 juta barel
per hari, terdiri atas produksi minyak sebanyak 1,2 juta barel per hari dan
kondensat sebanyak 132 ribu barel per hari. Perkembangan produksi minyak bumi
Indonesia dalam kurun waktu 2001 hingga 2006.
61
Gambar 3 Perkembangan produksi minyak bumi Indonesia (Ditjen Migas, 2007)
Kondisi produksi gas bumi Indonesia berbeda dengan produksi minyak
bumi. Produksi gas bumi mengalami peningkatan dalam kurun waktu tujuh tahun
terkahir. Tercatat bahwa produksi gas bumi Indonesia pada tahun 2006 yaitu
sebesar 8.093,0 MMSCFD terdiri atas pemanfaatan 7.783,0 MMSCFD dan
dibakar 308,0 MMSCFD.
Produksi gas bumi Indoensia pada tahun 2001 yaitu hanya sebesar 7.690,0
MMSCFD terdiri atas pemanfaatan 7.188,0 MMSCFD dan dibakar 502,0
MMSCFD. Data produksi tersebut menunjukkan peningkatan produksi gas bumi
Indonesia sebesar 403,0 MMSCFD atau sekitar 5,24%. Perkembangan produksi
gas bumi Indonesia dalam kurun waktu tahun 2001 hingga 2006.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Rib
u Ba
rel P
erha
ri
Total 1,340.6 1,249.4 1,146.8 1,094.4 1,062.1 1,005.6
Minyak 1,208.7 1,117.6 1,013.0 965.8 934.8 883.0
Kondensat 131.9 131.8 133.8 128.6 127.3 122.6
2001 2002 2003 2004 2005 2006
62
Gambar 4 Perkembangan produksi gas bumi Indonesia (Ditjen Migas, 2007)
3.4 Kontribusi Minyak dan Gas Bumi
Peranan minyak dan gas bumi sangat penting antara lain: penghasil devisa
negara, penyedia energi dalam negeri, penyedia bahan baku industri, wahana alih
teknologi, pencipataan lapangan kerja, mendorong pengembangan sektor non
migas dan pendukung pengembangan wilayah. Meskipun kontribusi sektor
minyak dan gas bumi terhadap devisa dan APBN semakin menurun seiring
menurunnya produksi minyak, namun kontribusi tersebut masih signifikan
terhadap pendapatan negara. Sebagai sumber energi dalam negeri peran minyak
dan gas bumi dalam penerimaan negara/devisa (pajak dan bukan pajak) sekitar
30% dari penerimaan negara keseluruhan. Penerimaan minyak dan gas bumi
dipengaruhi antara lain: besarnya tingkat produksi minyak mentah dan kondesat,
volume ekspor LNG dan LPG, harga minyak mentah dari biaya produksi.
Penurunan produksi minyak terjadi disebabkan oleh sumur-sumur yang ada sudah
tua, teknologi yang digunakan sudah ketinggalan dan iklim investasi di sektor
pertambangan minyak kurang kondusif sehingga tidak banyak perusahaan asing
maupun nasional melakukan investasi di sektor perminyakan.
Disisi konsumsi terhadap produk minyak/bahan bakar minyak yang terus
mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
MM
SCFD
Produksi 7,690 8,318 8,644 8,278 8,179 8,093
Pemanfaatan 7,188 7,890 8,237 7,909 7,885 7,785
Dibakar 502 428 407 369 294 308
2001 2002 2003 2004 2005 2006
63
ekonomi di Indonesia. Sejak tahun 2004, jika hasil produksi minyak Indonesia di
semua kilang dihitung, maka hasilnya tetap tidak dapat mencukupi kebutuhan
dalam negeri. Sejak tahun 2004, Indonesia telah mengalami defisit sebesar 49,3
ribu barel per hari. Namun demikian peranan minyak bumi tidak bisa diabaikan
(Dartanto, 2005).
Fluktuasi harga minyak dunia selain berpengaruh terhadap penerimaan
negara juga berpengaruh terhadap pengeluaran negara khususnya subsidi bahan
bakar dan bagi hasil sumberdaya alam kepada pemerintah daerah. Perhitungan
bagi hasil minyak dan gas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan
mekanisme bagi hasil berdasarkan berbagai skema kontrak kerjasama (Dartanto
dan Khoirunurrofik, 2006).
Dengan demikian bahwa produksi minyak Indonesia bukan hanya milik
pemerintah semata, akan tetapi juga dibagi dengan kontraktor perusahaan minyak
asing (production sharing contract) yang beroperasi. Skema bagi hasil yaitu
sebesar 85% pemerintah dan 15% kontraktor. Pembagian 85%:15% tersebut
merupakan hasil produksi minyak bersih artinya nilai produksi dikurangi dengan
biaya ekploitasi, pajak, land-rent, dan royalti. Sehingga bagi hasil minyak mentah
antara pemerintah dan KPS umumnya menjadi 60% untuk pemerintah dan 40%
untuk kontraktor. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka minyak mentah yang
diterima pemerintah adalah sebesar 656.64 ribu barel per hari (60% x 1.094,4)
sedangkan KPS menerima 437.76 ribu barel per hari (40% x 1.094,4). Bagian
minyak KPS diekspor keluar negeri dan semua hasilnya merupakan milik KPS.
Selanjutnya berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan
daerah, maka hasil minyak yang diperoleh pemerintah pusat harus dibagi dengan
daerah penghasil dengan proporsi 85% dan 15%. Pada pasal 14 UU No. 33 tahun
2004 bagi hasil sumberdaya alam khususnya minyak dan gas bumi dijabarkan
sebagai berikut: a) penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari
wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan
pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan
imbangan 84,50% untuk pemerintah dan 15,50% untuk daerah, b) penerimaan
pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan
64
setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 69,50% untuk pemerintah dan
30,50% untuk daerah, c) pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah
daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak
(PNBP), dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk
daerah (Dartanto dan Khoirunurrofik, 2006).
Berdasarkan pasal 19 ayat 2 UU No. 33 tahun 2004, 15,5% bagian
pemerintah daerah yang disebutkan pada pasal 14 huruf e angka dibagi dengan
rincian lebih kurang sebagai berikut: 3% untuk pemerintah propinsi, 6% untuk
kabupaten/kotamadya penghasil, 6% untuk kabupaten/kotamadya lain di dalam
satu propinsi. Penerimaan pemerintah pusat dari sumberdaya alam minyak bumi
dan gas alam yang akan dibagihasilkan ke daerah adalah bagian pemerintah dari
hasil produksi minyak bumi dan gas alam yang sudah dikurangi pajak dan
pungutan lainnya. Pola bagi hasil antara pemerintah dengan korporasi yakni: 1)
pola bagi hasil produksi antara kontraktor (production sharing contractor dan
joint operation body) dan pemerintah diatur berdasarkan NOI (net operating
income), pada dasarnya NOI merupakan lifting (hasil produksi minyak bumi/gas
alam yang dijual) setelah dikurangi biaya eksplorasi.
Bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor ini baru dilakukan setelah
biaya eksplorasi tertutupi. Jika pemerintah tidak mendapatkan penerimaan dari
sumberdaya alam ini pada awal periode kontraktor berproduksi. Kebijakan ini
diterapkan karena resiko kerugian (eksplorasi) ditanggung sepenuhnya oleh
perusahaan/kontraktor yang terlibat. Ketentuan bagi hasil antara kontraktor dan
pemerintah ini disebut sebagai equity share (entitlement) dan 2) equity share
(entitlement) pada dasarnya belum mengeluarkan komponen pajak pusat (masih
ada pajak perseroan dan pajak dividen di dalamnya). Bagian pemerintah dari
kontraktor yang telah dikurangi komponen pajak dan pungutan inilah yang akan
dibagihasilkan ke daerah.
Besarnya penerimaan pemerintah yang akan dibagihasilkan ke daerah
dipengaruhi oleh: 1) proses produksi (eksploitasi) yang terdiri dari primary
recovery, secondary recovery dan third recovery, 2) pola bagi hasil atau equity
65
share (entitlement) yang tentunya tergantung dari jenis production sharing dan 3)
rejim pajak yang berlaku (Dartanto dan Khoirunurrofik, 2006).
Mengingat kontribusi yang besar terhadap devisa negara, maka upaya-
upaya pengembangan akan tetap dilakukan. Upaya tersebut diimplementasikan
dengan meningkatkan cadangan dan produksi migas serta mengembangkan
lapangan marginal dan optimalisasi penerapan teknologi echanges oil recovery
(EOR), serta insentif untuk daerah remote, laut dalam, lapangan marginal dan
brown field.
Pengembangan lapangan marginal, daerah remote dan laut dalam,
merupakan sasaran pengembangan kedepan. Dengan demikian pengaruh limbah
dan eksternalitas negatif yang dapat muncul dari kegiatan usaha migas, menjadi
kecil. Pengembangan tersebut dilakukan dengan program produksi bersih, zero
discharge, penggunaan bahan dasar non toxic, serta desain peralatan pengolahan
limbah.
3.5 Permasalahan dalam Kegiatan Migas
Kegiatan usaha migas tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi
ekonomi dan pendapatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai
permasalahan-permasalahan yang umumnya dihadapi seperti: perijinan usaha,
konflik pemanfaatan ruang, konflik sosial dengan masyarakat lokal, permasalahan
lingkungan akibat limbah dan ekses dari aktivitas yang dilakukan serta
permasalahan kesehatan masyarakat disekitar lokasi kegiatan.
Permasalahan perijinan merupakan permasalahan klasik yang umum
dihadapi oleh investor (pemrakarsa) dalam rencana pelaksanaan kegiatannya.
Permasalahan ini merupakan permasalahan administratif birokrasi yang dihadapi
oleh hampir semua proses perijinan di Indonesia. Permasalahan perijinan
seringkali menjadi batu sandungan pertama ayang dihadapi oleh para investor.
Sehingga tidak sedikit biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh investor dalam
proses perijinan suatu kegiatan.
Permasalahan pemanfaatan ruang seringkali muncul menjadi konflik
sektoral pada suatu kegiatan usaha migas. Kegiatan migas yang sekitar 70%
berada di daerah on shore dan 30% di daerah off shore berpotensi memunculkan
konflik ruang dengan berbagai aktivitas pembangunan lainnya seperti
66
perhubungan laut, untuk alur laut Kepulauan Indonesia. Konflik sektoral dengan
Departemen Kehutanan tentang cagar alam, kawasan lindung dan kawasan
konservasi. Konflik dengan Departemen Pariwisata tentang taman wisata alam
dan cagar budaya. Konflik dengan Departemen Kelautan dan Perikanan untuk
areal pertambakan dan kawasan nelayan. Konflik dengan Departemen Perumahan
Rakyat untuk areal pemukiman penduduk.
Konflik sosial antara KPS dengan masyarakat lokal, juga sering menjadi
permasalahan dalam kegiatan usaha migas. Seringkali, masyarakat sulit untuk
menerima keberadaan kegiatan migas di suatu lokasi, disebabkan minimnya
umpan balik dari kegiatan tersebut terhadap masyarakat. Kondisi ini, tidak
terlepas dari kenyataan bahwa kegiatan usaha migas merupakan kegiatan dengan
teknologi tinggi (high tech) dan sifat bukan kegiatan padat karya. Sehingga
penyerapan tenaga kerja lokal, sangat sulit terakomodir dalam pelaksanaan
kegiatan. Kenyataan lainnya sumberdaya manusia yang berada di sekitar lokasi
kegiatan migas juga tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan yang dilakukan,
sehingga alternatif umpan balik dari pelaksanaan kegiatan usaha tersebut,
umumnya dilakukan dalam bentuk community development. Kasus yang terjadi di
Kecamatan Ujung Pangkah Gresik, dimana kegiatan usaha migas oleh HESS sulit
sekali diterima oleh masyarakat dan membutuhkan waktu 3-4 tahun dalam proses
negosiasi pelaksanaannya. Kasus lainnya terjadi pada PT. CPI Riau yang
masyarakat lokalnya meminta kepada perusahaan agar penyerapan tenaga kerja
lokal dapat ditingkatkan sementara di sisi lain kegiatan tersebut tidak memerlukan
tenaga kerja dengan kualifikasi yang dimaksud, sehingga konflik sosial seperti
dalam bentuk demonstrasi seringkali terjadi.
Permasalahan krusial lainnya yang umumnya terjadi pada kegiatan usaha
migas adalah pengelolaan limbah dan ekses negatif dari kegiatan usaha yang
dilakukan. Permasalahan ini terklasifikasi dalam kelompok permasalahan
lingkungan. Isu lingkungan hidup dalam dua dekade terakhir menjadi isu global
dan permasalahan bersama. Permasalahan lingkungan yang dihadapi pada
hakikatnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah ini timbul karena perubahan
lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak atau kurang sesuai
67
dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia akibatnya
adalah terganggunya kesejahteraan umat manusia.
Kegiatan usaha migas berpotensi menimbulkan dampak dan efek terhadap
lingkungan seperti dari limbah hasil proses produksi yang dihasilkan seperti:
emisi SO2, NOx, hidrogen sulfida, HCs, bensen, CO, CO2, gas metan, kandungan
organik berbahaya, kaustik, tumpahan minyak, fenol, kalium, efluen gas, serta
efluen lumpur. Bahan dan gas tersebut dapat menyebabkan pemanasan global
secara makro dan degradasi sumberdaya serta kerusakan lingkungan hidup secara
mikro serta berdampak terhadap kesehatan manusia. Bahan dan gas-gas tersebut
tidak hanya menimbukan pemanasan global, tetapi juga menyebabkan kenaikan
muka air laut (sea level rise) sebagai akibat meningkatnya suhu permukaan bumi,
yang disebabkan oleh efek rumah kaca (green house effect) dan penipisan lapisan
ozon. Selain itu juga dapat menimbulkan terjadinya hujan asam, dan dampaknya
menyebabkan terjadinya kerusakan dan kematian organisme hidup.
Tabel 4 Kegiatan usaha migas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan yang diwajibkan menyusun AMDAL keputusan menteri negara lingkungan hidup No.17 tahun 2001
No Kegiatan Migas Limbah yang dihasilkan Potensi Dampak
1. Kegiatan hulu/produksi
- Air terproduksi
- Sludge minyak
- Gas emisi
- Tumpahan minyak
- Kebocoran pipa dan kapal
- Penurunan kualitas air, tanah, air tanah dan udara
2. Kegiatan hilir/pengolahan
- Sludge minyak
- Limbah cair
- Limbah padat
- Tumpahan minyak
- Penurunan kualitas air, tanah, air tanah dan udara
3. Niaga/pemasaran
- Tumpahan minyak
- Kebocoran pipa
- Kebocoran kapal
- Penurunan kualitas air
68
Pelaksanaan kegiatan migas terdiri dari empat tahapan baik di darat
maupun di laut yakni: 1) Tahap pra konstruksi, pada tahap pra-konstruksi akan
dilakukan beberapa kegiatan, yakni perizinan dan pembebasan lahan. 2) Tahap
konstruksi untuk kegiatan di darat terdiri atas: pembuatan mobilisasi dan
demobilisasi tapak sumur pemboran serta mobilisasi peralatan dan material,
mobilisasi tenaga kerja, pemasangan pipa penyalur minyak dan gas: mobilisasi
peralatan dan material, mobilisasi tenaga kerja, pembangunan fasilitas produksi
pemrosesan produksi stasiun pengumpul minyak dan gas dan fasilitas penunjang
dan penyerapan tenaga kerja, sedangkan untuk kegiatan di laut terdiri atas:
mobilisasi tenaga kerja di laut untuk pemasangan anjungan tapak sumur (wellhead
platform/WHP), pembangunan compression and processing platform/CPP,
pembangunan pipa penyalur dan uji hidrostatis. 3) Tahap operasi terdiri atas:
produksi, pengoperasian pipa penyalur (dasar laut dan darat), pemisahan minyak
dan gas serta pengolahan minyak dan gas. 4) Tahap pasca operasi.
69
IV. METODE PENELITIAN
4.1 Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari sampai September 2007.
Penelitian dilakukan pada tujuh lokasi kegiatan usaha migas, yakni: 1) Pertamina
Plaju Palembang, 2) PT. CPI Duri Riau, 3) Suryaraya Teladan Muara Enim, 4)
Lapindo Berantas Sidoarjo, 5) Expan Toili Morowali, 6) BP Tangguh Sorong dan
7) Hess Pangkah Gresik. Kegiatan review kebijakan AMDAL migas, analisis
kualitas dokumen AMDAL migas dan analisis kinerja lingkungan implementasi
AMDAL migas dilakukan pada tujuh KKKS tersebut. Kegiatan analisis
kebutuhan stakeholders dan focus group discussion dilakukan di Jakarta.
Sementara kegiatan analisis ekonomi lingkungan dilakukan pada dua lokasi
kegiatan migas yakni: Hess di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Jawa
Timur dan PT. CPI di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Riau.
Kedua lokasi yang dipilih sebagai penggambaran dari kegiatan usaha
migas yang ada di Indonesia. KKKS Hess Pangkah merupakan corparate yang
baru memulai melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sehingga dapat
menjadi sampel yang mewakili corparate yang baru memulai suatu kegiatan
usaha. PT. CPI Riau merupakan corparate yang telah lama melakukan kegiatan
eksplorasi, eksploitasi dan juga penghasil minyak terbesar di Indonesia.
Kabupaten Gresik mempunyai posisi yang strategis dan secara geografis
terletak pada 70 LS – 80 LS dan 1120 BT – 1130 BT. Sebagian besar wilayahnya
merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12 meter di atas permukaan
laut. Kabupaten Gresik secara administratif berbatasan dengan Laut Jawa di
sebelah utara, Selat Madura di sebalah timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah
selatan dan Kabupaten Lamongan di sebelah barat.
Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 11.481,77 km2 yang meliputi
pesisir timur pulau Sumatera dan daerah kepulauan. Kabupaten Bengkalis secara
geografis terletak pada 00 170 LU – 20 300 LU dan 00 520 BT – 10 200 BT. Secara
administratif berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Siak di
sebelah selatan, Kota Dumai di sebelah barat dan Kepulauan Riau di sebelah
timur.
70
4.2 Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian pengembangan kebijakan AMDAL dalam mencegah
kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas terdiri atas lima tahapan,
sebagai berikut:
Tahap pertama: melakukan review kebijakan AMDAL saat ini dengan
menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif. Tahap
ini dimaksudkan untuk mereview kebijakan AMDAL yakni terhadap PP No. 29
tahun 1986, PP No. 51 tahun 1993 dan PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL,
Permen LH No. 08 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan AMDAL dan
Permen LH No. 11 tahun 2006 tentang jenis kegiatan yang wajib AMDAL,
Kepmen ESDM No. 1457 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan
lingkungan di bidang pertambangan dan energi, keputusan Kepdal No. 229 tahun
1996 tentang pedoman teknis kajian aspek sosial dalam penyusunan AMDAL dan
keputusan Kepdal No. 08 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan
keterbukaan informasi dalam proses AMDAL. Selanjutnya melakukan analisis
kualitas dokumen AMDAL migas. Melakukan penilaian kinerja lingkungan
sebagai implementasi AMDAL pada tujuh perusahaan yakni: PT.CPI Lapangan
Duri, Pertamina UP III Plaju, PT.Lapindo Brantas, Suryaraya Teladan Pendopo,
BP Tangguh, Expan Toili dan Hess Pangkah. Metode studi yang digunakan yakni:
studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif dan studi lapangan (survei)
untuk analisis ekonomi lingkungan dengan pendekatan total economic valuation.
Kemudian melakukan analisis kebutuhan stakeholders.
Tahap kedua: menentukan komponen utama pengembangan kebijakan
AMDAL migas dalam mencegah kerusakan lingkungan. Tahapan ini dilakukan
dengan mengidentifikasi komponen-komponen penting dari hasil review
kebijakan, analisis kualitas dokumen, analisis kinerja lingkungan serta analisis
kebutuhan stakeholders. Tahapan ini dilakukan dengan pendekatan principle
component analysis (PCA).
Tahap ketiga: menyusun strategi pengembangan kebijakan AMDAL
migas. Tahapan ini didasarkan pada hasil penentuan komponen utama kebijakan
AMDAL migas dalam mencegah kerusakan lingkungan. Pendekatan focus group
discussion digunakan dalam penyusunan strategi.
71
Tahap keempat: melakukan penentuan prioritas strategi pengembangan
kebijakan AMDAL migas dalam mencegah kerusakan lingkungan. Pendekatan
analytical hierarchy process digunakan dalam penentuan prioritas strategi.
Tahap kelima: merumuskan kebijakan AMDAL migas yang efektif dan
efisien dalam mencegah kerusukan lingkungan. Tahapan ini dilakukan dengan
pendekatan focus group discussion.
Gambar 5 Tahapan penelitian
4.3 Jenis dan Sumber Data
Data sekunder yang dibutuhkan yakni: perundang-undangan dan peraturan
tentang AMDAL, luas kawasan, pertambakan, perkebunan dan hutan, jumlah
penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan dan kesehatan, PDRB dan data
hasil pemantauan kegiatan usaha migas. Data sekunder dikumpulkan melalui studi
pustaka bersumber dari Ditjen Migas, KLH, Departemen Kehutanan, Departemen
Kelautan dan Perikanan, KKKS, Bappeda, Bapedal, BPS dan instansi terkait
lainnya. Data primer yang diperlukan yakni: pendapat tentang pelaksanaan
AMDAL dan data sosial ekonomi masyarakat seperti: jenis mata pencaharian,
biaya produksi, jumlah produksi, jumlah tenaga kerja, modal, pendapatan,
pendidikan, jumlah anggota keluarga dan data yang terkait dengan kajian sosial-
AD
Review Kebijakan
AMDAL saat ini
Tahap-2 Kualitas
Dokumen AMDAL saat ini
Penilaian Kinerja
Lingkungan sebagai
Implementasi AMDAL
Kebutuhan Stakeholders
Komponen Utama
Kebijakan AMDAL Migas
Strategi Pengembangan
Kebijakan AMDAL Migas
Prioritas Strategi
Kebijakan AMDAL Migas
Rumusan Kebijakan
AMDAL Migas yang Efektif dan
Efisien dalam Mencegah Kerusakan
Lingkungan
Tahap-1
Tahap-4
Tahap-3
Tahap-5
72
ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan. Data primer dikumpulkan melalui
wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden.
4.4 Rancangan Penelitian
4.4.1 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data terdiri atas studi pustaka dan survei.
Pengumpulan data untuk review kebijakan AMDAL, dilakukan dengan metode
studi literatur. Jenis data sekunder yang dikumpulkan terdiri atas: PP No. 29 tahun
1986, PP No. 51 tahun 1993 dan PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL serta
peraturan menteri negara LH No. 08 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan
AMDAL dan peraturan menteri LH No. 11 tahun 2006 tentang jenis rencana
usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal serta keputusan menteri
esdm No. 1457 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan lingkungan di
bidang pertambangan dan energi. Keputusan kepala badan pengendalian dampak
lingkungan No. 299 tahun 1996 tentang pedoman teknis kajian aspek sosial dalam
penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dan keputusan kepala badan
pengendalian dampak lingkungan No. 08 tahun 2000 tentang keterlibatan
masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses analisis mengenai dampak
lingkungan hidup.
Pengumpulan data untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan stakeholders
pada kebijakan AMDAL dalam upaya pengembangan ke arah yang lebih efektif
dan efisien di masa datang dilakukan dengan interview dan pengisian kuesioner
oleh stakeholders yang terdiri atas keterwakilan instansi/lembaga masing-masing
oleh satu orang. Stakeholders terdiri atas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Departemen ESDM, BP Migas, KLH, Pemerintah Daerah, Pemrakarsa, Perguruan
Tinggi, dan LSM.
Penentuan nilai ekonomi lingkungan dilakukan dengan metode survei
dengan pendekatan pengisian kuesioner. Penentuan responden untuk analisis nilai
ekonomi lingkungan dilakukan pada 2 lokasi sampling yakni Kecamatan Ujung
Pangkah sebanyak 115 responden terdiri atas: 43 orang nelayan, 37 orang petani
tambak, dan 35 orang pemanfaat hutan mangrove. Jumlah responden Kecamatan
Mandau sebanyak 95 responden terdiri atas: 30 orang nelayan, 32 orang petani
73
kebun, dan 33 orang pemanfaat hutan. Penentuan responden dilakukan dengan
metode purposive sampling yang merupakan masyarakat pemanfaat sumberdaya
alam dan lingkungan.
Perumusan strategi implementasi kebijakan AMDAL yang efektif dan
efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas
dilakukan dengan pendekatan FGD. Kegiatan ini untuk menerima masukan dari
stakeholders tentang langkah-langkah strategis kebijakan AMDAL di masa
datang. Penentuan peserta diskusi dilakukan dengan memilih stakeholders kunci
yang merupakan keterwakilan dari masing-masing stakeholders yang terdiri atas:
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Departemen ESDM, BP Migas, Pertamina,
KLH, Pemerintah Daerah, Pemrakarsa, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian
dan LSM.
4.4.2 Metode Analisis Data
4.4.2.1 Analisis Komponen Utama
Analisis komponen utama/principle component analysis (PCA) dilakukan
untuk menjawab faktor-faktor yang utama berpengaruh terhadap kebijakan
AMDAL dengan melihat korelasi antara variabel yang signifikan. Tujuan PCA
adalah untuk melihat korelasi antara variabel dan melihat similarity antar individu
(Bengen, 2002). Analisis PCA dalam penelitian ini menggunakan software
statistic 6.0 dengan tahapan sebagai berikut:
1. Membuat simbol variabel.
2. Menyusun struktur data asal (kualitatif) kedalam data kuantitatif.
3. Menginput data kuantitatif ke dalam software statistic 6.0..
4. Menentukan jumlah faktor utama berdasarkan eigenvalues tertinggi.
5. Menyederhanakan variabel berdasarkan tingkat korelasi (α=0,05), dan tingkat
kontribusi tertinggi dari masing-masing variabel terhadap faktor utama.
6. Menyimpulkan hasil analisis komponen utama.
Hasil review kebijakan, review kualitas dokumen, review kinerja
lingkungan dan analisis kebutuhan stakeholders selanjutnya dianalisis dengan
pendekatan principle component analysis dengan menggunakan perangkat lunak
statistic 6.0.
74
4.4.2.2 Analytical Hierarchy Process
Analytical hierarchy process (AHP) merupakan metode analisis yang
dapat digunakan secara luwes yang memungkinkan pengambilan keputusan
dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis
sehingga dapat ditentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan (Ma’arif
dan Tanjung, 2003). Beberapa tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan tujuan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan.
2. Menyusun struktur hirarki strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas.
3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan pengaruh
relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan yang
setingkat di atasnya. Perbandingan berdasarkan “judgement” dari pengambil
keputusan dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen dibandingkan
dengan elemen lainnya. Pembobotan penilaian menggunakan skala Saaty
(1993) seperti disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5 Skala banding secara berpasangan dalam AHP
Tingkat Kepentingan Keterangan
1 3 5 7 9
2,4,6,8 Kebalikan
Kedua elemen sama pentingnya Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lain Elemen yang satu jelas lebih penting dari elemen yang lain Elemen yang satu mutlak lebih penting dari elemen yang lain Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan Jika untuk aktifitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktifitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i
Sumber: Saaty (1993)
4. Menyusun data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner AHP.
5. Menginput data kedalam software expert choice.
6. Menyimpulkan hasil analisis hirarki proses.
4.4.2.3 Focus Group Discussion
Focus group discussion (FGD) merupakan teknik penggalian informasi
secara luas yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari stakeholder
secara bersamaan dalam satu kelompok diskusi, dan setiap kegiatan akan
75
menggali informasi yang lebih fokus ke topik-topik tertentu yang paling penting
untuk dianalisa (Eriyatno dan Sofyar, 2005). Dalam penelitian ini FGD
dimaksudkan sebagai teknik untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan
AMDAL yang efektif dan efisien. Menurut Whelan (1996) bahwa FGD sudah
menjadi prosedur riset yang dapat diandalkan guna mengkaji perihal yang
kompleks dan dinamik tanpa harus melakukan reduksi faktor.
Pelaksanaan focus group discussion (FGD) dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:
1). Presentasi tentang topik dan tujuan dari pelaksanaan FGD. Moderator
menyampaikan tujuan dan topik disdukusi kepada peserta. Disukusi dilakukan
dalam 2 sesi yakni :. Sesi-1 adalah menyusun strategi implementasi kebijakan
AMDAL migas serta menyusun tahapan strategi implementasi kebijakan
AMDAL migas. Sesi-2 adalah merumuskan pengembangan kebijakan
AMDAL migas yang efektif dan efisien
2). Diskusi merupakan tahapan inti pelaksanaan FGD. Pada tahap ini masing-
masing peserta diminta untuk menyampaikan tanggapan, pendapat dan
rumusan tentang topik yang didiskusikan. Tahapan ini menjadi penting
sebagai wahana sharing pendapat dan tanggapan atas apa yang telah
disampaikan, untuk selanjutnya didiskusikan secara mendalam dan
merumuskan hasil bersama sebagai sebuah kesimpulan.
3). Perumusan hasil yang telah didiskusikan selanjutnya disampaikan secara detil
dan terstruktur kepada peserta.
4.4.2.4 Analisis Nilai Ekonomi Total
Pada dasarnya nilai ekonomi suatu sumberdaya secara garis besar dibagi
menjadi dua, yaitu nilai manfaat (use value) dan nilai bukan manfaat (non use
value). Nilai manfaat terbagi menjadi dua, yaitu: nilai manfaat langsung (direct
use value) dan nilai manfaat tidak langsung (indirect use value). Sedangkan nilai
bukan manfaat dibagi menjadi tiga, meliputi: nilai pilihan (option value), nilai
keberadaan (existence value), dan nilai pewarisan (bequest value).
76
1. Nilai Manfaat Langsung
Nilai manfaat langsung adalah nilai yang dihasilkan dari pemanfaatan
secara langsung dari suatu sumberdaya. Nilai manfaat langsung yang dihitung
merupakan nilai dari jenis manfaat langsung yang telah termanfaatkan oleh
masyarakat sekitar dan mempunyai nilai ekonomis. Sebagai contoh pada hutan
yang ada di lokasi penelitian, nilai manfaat langsung yang dapat diidentifikasi
antara lain: pemanfaatan kayu bakar, penangkapan satwa di sekitar hutan dan
pemanfaatan langsung lainnya. Nilai manfaat langsung dari hutan tersebut dapat
dirumuskan sebagai berikut :
∑= niNMLNML
1 Keterangan :
NML : Nilai Manfaat Langsung NML1 : Nilai Manfaat Langsung (kayu bakar) NML2 : Nilai Manfaat Langsung (penangkapan satwa) NMLn : Nilai Manfaat Langsung lainnya
2. Nilai Manfaat Tidak Langsung
Nilai manfaat tidak langsung adalah nilai manfaat dari suatu sumberdaya
yang dapat dimanfaatkan secara tidak langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh,
manfaat tidak langsung dari hutan mangrove dapat berupa manfaat fisik yaitu
sebagai penahan abrasi air laut dan juga manfaat biologis yaitu sebagai tempat
pemijahan ikan, daerah asuhan ikan dan sebagai tempat penyedia makanan bagi
ikan.
Estimasi manfaat hutan mangrove sebagai penahan abrasi pantai dapat
didekati dengan pembuatan beton pantai yang setara dengan fungsi hutan
mangrove sebagai penahan abrasi pantai. Metode yang digunakan untuk
mengukur nilai tersebut adalah replacement cost atau biaya pengganti. Biaya dari
pembuatan beton tersebut sebagai biaya pengganti akibat dampak lingkungan,
dapat digunakan sebagai perkiraan minimum dari manfaat yang diperoleh untuk
memelihara maupun memperbaiki lingkungan.
Estimasi manfaat hutan mangrove sebagai nursery ground, spawning
ground dan feeding ground bagi biota perairan didekati dari hasil tangkapan
nelayan untuk ikan di wilayah perairan laut sekitarnya. Menurut Adrianto (2005),
77
teknik pengukuran untuk menilai manfaat tersebut adalah pendekatan
produktivitas (productivity approach), karena ekosistem mangrove memiliki
fungsi sebagai tempat pembesaran ikan (nursery ground) sehingga luas ekosistem
menjadi input bagi produktivitas hasil tangkapan ikan yang menjadi produk akhir
bagi masyarakat. Nilai total dari manfaat tidak langsung dapat dirumuskan sebagai
berikut:
∑= 2
1NMTLiNTML
Keterangan:
NTML : Nilai Total Manfaat Tidak Langsung NMTL1 : Nilai Total Manfaat Tidak Langsung (penahan abrasi) NMTL2 : Nilai Total Manfaat Tidak Langsung (nursery ground)
3. Nilai Manfaat Pilihan
Manfaat pilihan umumnya didekati dengan menggunakan metode benefit
transfer yaitu dengan cara menilai perkiraan benefit dari tempat lain (dimana
sumberdaya tersedia) kemudian benefit tersebut ditransfer untuk memperoleh
perkiraan yang kasar mengenai manfaat dari lingkungan (Fauzi, 1999). Metode
tersebut didekati dengan cara menghitung besarnya nilai keanekaragaman hayati
(biodiversity) yang ada di ekosistem mangrove tersebut. Menurut Ruitenbeek
(1991) hutan mangrove Indonesia mempunyai nilai biodiversity sebesar US$15
per ha. Nilai ini dapat dipakai di seluruh hutan mangrove yang ada di Indonesia
apabila ekosistem hutan mangrovenya secara ekologis penting dan tetap dipelihara
secara alami. Nilai manfaat pilihan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Keterangan:
MP : Manfaat Pilihan (US$15 per ha x Kurs Rupiah pada saat penelitian)
4. Nilai Manfaat Keberadaan
Manfaat keberadaan didefinisikan sebagai nilai yang dirasakan masyarakat
dari keberadaan sumberdaya. Metode yang digunakan dalam perhitungan ini
adalah contingent valuation method (CVM). Metode CVM ini didasarkan pada
MP = US$15 per ha x Luas hutan mangrove
78
kesediaan seseorang untuk membayar (willingness to pay) keberadaan sebuah
sumberdaya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan interview
kepada masyarakat/ responden. Pemilihan responden dilakukan secara purposive
sampling berdasarkan karakteristik masyarakat sekitar sumberdaya tersebut.
Menurut Fauzi (2004), pada metode pengukuran dengan teknik ini,
responden diberi suatu nilai rupiah, kemudian diberi pertanyaan ya atau tidak.
Dalam operasionalnya untuk melakukan pendekatan CVM dilakukan lima tahapan
kegiatan atau proses. Tahapan tersebut sebagai berikut:
1) Membuat hipotesis pasar.
2) Mendapatkan nilai lelang (bids).
3) Menghitung rataan WTP.
Metode yang digunakan untuk mengukur besarnya WTP setiap responden,
yaitu model discrete choice. Menurut Adrianto (2005) rumus untuk rataan WTP
adalah sebagai berikut:
∑=
=n
iiy
nMWTP
1
1
Keterangan :
n : jumlah responden yi : besaran WTP yang diberikan responden ke-i
4) Memperkirakan kurva lelang (bid curve).
5) Mengagregatkan data: Mengagregasikan nilai rataan WTP terhadap populasi
masyarakat pengguna hutan mangrove (Grigalunas dan Conges, 1995).
5. Kuantifikasi Manfaat Total
Nilai ekonomi total/total economic value (TEV) merupakan penjumlahan
dari seluruh manfaat yang telah diidentifikasi, yaitu:
TEV = NML + NMTL + NMP + NMK
Keterangan:
TEV : Total Economic Value NML : Nilai Manfaat Langsung NMTL : Nilai Manfaat Tidak Langsung NMP : Nilai Manfaat Pilihan NMK : Nilai Manfaat Keberadaan
79
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Kebijakan AMDAL
Kebijakan AMDAL selama ini diatur dalam peraturan pemerintah yakni:
PP No. 29 tahun 1986, PP No. 51 tahun 1993, PP No. 27 tahun 1999 tentang
AMDAL, serta dalam peraturan menteri yakni: Permen LH No. 08 tahun 2006
tentang pedoman penyusunan AMDAL dan Permen LH No. 11 tahun 2006
tentang jenis kegiatan yang wajib AMDAL. Kebijakan AMDAL diatur pula dalam
bentuk keputusan menteri ESDM No. 1457 tahun 2000 tentang pedoman teknis
pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi. Selanjutnya dalam
bentuk keputusan kepala Bapedal No. 299 tahun 1996 tentang kajian aspek sosial
ekonomi dalam penyusunan AMDAL, keputusan kepala Bapedal No. 08 tahun
2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses
AMDAL.
Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif yang
berkekuatan hukum dalam mencegah terjadinya kerusakan fungsi lingkungan
hidup. Kebijakan-kebijakan tersebut baik dalam bentuk peraturan pemerintah,
keputusan menteri serta keputusan kepala Bapedal, diharapkan manpu menjamin
keberlanjutan pembangunan dengan tetap menjaga fungsi-fungsi lingkungan
dengan baik melalui upaya pencegahan dampak terhadap lingkungan serta
penegakan hukum. Dengan demikian sasaran pengelolaan lingkungan dapat
terwujud yakni terpenuhinya devisa negara, lingkungan hidup lestari dan
kesejahteraan masyarakat meningkat.
5.1.1 Peraturan Pemerintah tentang AMDAL
Kebijakan pengelolaan lingkungan pada suatu usaha dan atau kegiatan
baik oleh perseorangan maupun badan hukum diatur dalam peraturan pemerintah.
Untuk kebijakan AMDAL, telah dilakukan penerapan kebijakan pengelolaan
lingkungan dengan menerbitkan peraturan pemerintah No. 29 tahun 1986,
kemudian direvisi menjadi PP No. 51 tahun 1993 dan terakhir PP No. 27 tahun
1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.
80
Tabel 6 Review kebijakan AMDAL dengan substansi penentuan dampak penting
PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999 Dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan
Dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan
Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu dan atau kegiatan
Kategori dampak dalam PP No. 29 tahun 1986 dan PP No. 51 tahun 1993
tidak disebutkan adanya dampak besar tetapi hanya mengkategorikan dampak
penting. Hal ini berbeda dengan kategori dampak dalam PP No. 27 tahun 1999
disebutkan bahwa dampak dari rencana suatu usaha dan atau kegiatan
dikategorikan menjadi dua yakni dampak besar dan penting. Namun
sesungguhnya kategori dampak besar tersebut merupakan satu kesatuan dalam
kategori dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
Dalam PP No. 27 tahun 1999 dampak besar dan penting adalah perubahan
lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan
atau kegiatan. Selanjutnya bahwa kriteria dampak besar dan penting suatu usaha
dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yakni: a) jumlah manusia yang
terkena dampak, b) luas wilayah penyebaran dampak, c) intensitas dan lamanya
dampak berlangsung, d) banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena
dampak, e) sifat kumulatif dampak dan f) berbalik (reversible) atau tidak
berbaliknya (irreversible) dampak.
Pembagian ketagori penentuan dampak berdasarkan dampak besar dan
dampak penting menjadi salah satu kelemahan PP No. 27 tahun 1999 dalam
kaitannya dengan penentuan dampak penting dari suatu kegiatan usaha migas.
Besaran dampak yang dikategorikan dapat menimbulkan dampak dari sisi besaran
dampak adalah untuk kegiatan eksploitasi minyak di darat > 5000 BOPD (barrel
oil per day), untuk eksploitasi gas > 30 MMSCFD (million million stock crude
feet per day). Sebagaimana yang ditetapkan dalam Kepmen No. 11 tahun 2006
tentang kegiatan yang wajib AMDAL bahwa penentuan besaran minimal tersebut
menjadi dasar penentapan suatu kegiatan usaha migas wajib AMDAL atau tidak.
Sehingga peluang terjadinya dampak terhadap lingkungan, sangat memungkinkan
81
dengan tidak diwajibkan studi AMDAL bagi suatu kegiatan usaha yang tingkat
produksinya di bawah ketentuan yang telah ditetapkan. Seharusnya, penentuan
dampak penting dan wajib tidaknya suatu kegiatan usaha untuk melakukan studi
AMDAL tidaklah didasarkan pada besaran produksinya, tetapi semua kegiatan
usaha migas yang memungkinkan menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan, diwajibkan melakukan studi AMDAL. Hal ini sangat mendasar,
mengingat kegiatan usaha migas merupakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi
terhadap lingkungan, baik dari sisi ekologi, ekonomi maupun sosial.
Usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak
besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi: a) pengubahan bentuk
lahan dan bentang alam, b) eksploitasi sumberdaya alam baik yang terbaharui
maupun yang tak terbaharui, c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat
menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta
kemorosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya, d) proses dan kegiatan
yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta
lingkungan sosial budaya, e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat
mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumberdaya dan atau perlindungan
cagar budaya, f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik,
g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati, h) penerapan
teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi
lingkungan hidup, i) kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau
mempengaruhi pertahanan negara (pasal 3 ayat 2 PP No. 27 tahun 1999 tentang
AMDAL) hal ini bertentangan dengan Kepmen LH No. 11 tahun 2006 tentang
kegiatan wajib AMDAL yang mana kategori kegiatan yang wajib menyusun
AMDAL berdasarkan volume produksi.
Tabel 7 Review kebijakan AMDAL dengan substansi kerangka acuan PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999
- Kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan ditetapkan oleh komisi dan disampaikan kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 12 hari sejak diterimanya pengajuan tersebut
- Kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan ditetapkan oleh komisi dan disampaikan kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 12 hari sejak diterimanya pengajuan
- Keputusan atas penilaian kerangka acuan diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 hari sejak tanggal diterimanya pengajuan
82
Aturan tentang penyusunan kerangka acuan disebutkan dalam PP No. 29
tahun 1986 dan PP No. 51 tahun 1993 bahwa apabila pemrakarsa berpendapat
bahwa rencana kegiatannya akan menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan hidup, maka pemrakarsa bersama instansi yang bertanggung jawab
langsung menyusun kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan
tanpa membuat penyajian informasi lingkungam terlebih dahulu, dimana kerangka
acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan ditetapkan oleh komisi dan
disampaikan kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari sejak
diterimanya pengajuan kerangka acuan tersebut. Sementara dalam PP No. 27
tahun 1999 disebutkan bahwa suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan
menimbulkan dampak diwajibkan menyusun kerangka acuan, namun apabila
rencana usaha dan atau kegiatan tersebut diperkirakan tidak menimbulkan dampak
besar dan penting, maka diharuskan menyusun UKL dan UPL. Keputusan atas
penilaian kerangka acuan juga diatur dalam PP No. 27 tahun 1999 sebagaiman
termaktub dalam pasal 16 ayat 2, keputusan atas penilaian kerangka acuan
sebagaimana dimaksud pada jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh
lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuan.
Hal ini menjelaskan bahwa kerangka acuan disetujui oleh instansi yang
bertanggung jawab dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima)
hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuan tersebut. Perubahan
waktu atas keputusan penilaian kerangka acuan dari 12 (dua belas) hari menjadi
75 (tujuh puluh lima) hari kerja menjadi sangat penting mengingat kebutuhan
waktu yang lama dapat menghambat jalannya investasi, begitu pula waktu yang
sangat singkat, akan memberikan penilaian yang tidak maksimal, sehingga dengan
demikian waktu persetujuan kerangka acuan didasarkan pada kebutuhan waktu.
83
Tabel 8. Review kebijakan AMDAL dengan substansi ANDAL
PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999 - Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan
- Keputusan atas andal diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan analisis dampak lingkungan
- Apabila keputusan atas andal berupa penolakan berhubung kurang sempurnanya, maka keputusan perbaikan andal diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan kembali perbaikan analisis dampak lingkungan tersebut
- Keputusan atas andal diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya pengajuan analisis dampak lingkungan
- Apabila keputusan atas andal berupa penolakan berhubung kurang sempurnanya, maka keputusan perbaikan ANDAL diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan kembali perbaikan analisis dampak lingkungan tersebut
- Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan
- Keputusan atas ANDAL diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen ANDAL, RKL, RPL
- Apabila instansi yang bertangungjawab tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu tersebut maka rencana usaha dan atau kegiatan yang dimaksud dianggap layak lingkungan
Keputusan atas ANDAL diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan analisis
dampak lingkungan tersebut. Apabila keputusan atas ANDAL berupa penolakan
berhubung kurang sempurnanya, maka keputusan perbaikan ANDAL diberikan
oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya pengajuan kembali perbaikan analisis dampak lingkungan
tersebut. Dalam PP No. 27 tahun 1999 dibutuhkan waktu sebanyak 75 hari kerja
sebagaimana termaktub dalam pasal 20 ayat 1, instansi yang bertanggung jawab
menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 75 (tujuh puluh lima) jari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
84
dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan
hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
Namun demikian, waktu yang dibutuhkan tersebut (75 hari) tidak berdasar,
sehingga perlu direvisi mengingat lamanya proses persetujuan AMDAL tersebut
dapat menghambat iklim investasi dalam kegiatan usaha migas. Dari sisi efisiensi,
hal ini akan sangat berdampak terhadap rencana implementasi kegiatan yang akan
dilakukan. Penekan sesungguhnya bukanlah pada lamanya waktu prosedur
persetujuan AMDAL, namun lebih ditekankan pada tingkat kebutuhan usaha
dengan prinsip-prinsip kelestarian ekologi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam
proses persetujuan dapat diterapkan prosedur yang mudah, cepat dan
bertanggungjawab dengan demikian semangat investasi dapat tetap terjaga dalam
upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.
Tabel 9 Review kebijakan AMDAL dengan substansi RKL
PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999 - Keputusan persetujuan atas rencana pengelolaan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rencana pengelolaan lingkungan tersebut
- Keputusan persetujuan atas rencana pengelolaan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya rencana pengelolaan lingkungan tersebut
- Keputusan persetujuan atas rencana pengelolaan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pengelolaan lingkungan tersebut
Prosedur persetujuan dokumen RKL dan RPL dalam PP No. 27 tahun
1999 dilakukan bersamaan dengan pengajuan dokumen ANDAL dengan waktu
yang dibutuhkan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak diajukannya
dokumen tersebut. Sementara dalam PP No. 51 tahun 1993, prosedur persetujuan
dokumen RKL dan RPL dilakukan terpisah dengan pengajuan dokumen ANDAL.
Waktu yang dibutuhkan dalam proses persetujuan dokumen RKL dan RPL yakni
45 (empat puluh lima) hari kerja.
85
Tabel 10 Review kebijakan AMDAL dengan substansi RPL
PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999 - Keputusan
persetujuan atas rencana pemantauan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rencana pemantauan lingkungan tersebut
- Keputusan persetujuan atas rencana pemantauan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya rencana pemantauan lingkungan tersebut
- Keputusan persetujuan atas rencana pemantauan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemantauan tersebut
Seperti pada Tabel 10 tampak perubahan waktu keputusan persetujuan
RPL yang semakin lama yakni dari 30 hari kerja (PP No. 29 tahun 1986), 40 hari
kerja (PP No. 51 tahun 1993) dan menjadi 75 hari kerja (PP No. 27 tahun 1999).
Perubahan waktu persetujuan RPL tersebut tidak memiliki dasar penetapan waktu
yang jelas. Seharusnya waktu penyusunan tidak ditetapkan sama untuk semua
kegiatan, harus mempertimbangkan lokasi kegiatan yang sulit dijangkau, perlu
pengkajian yang mendalam berdasarkan ekosistem masing-masing kegiatan,
pertimbangan efisiensi waktu, yang dapat menghambat kegiatan karena kegiatan
usaha migas sangat dinamis, akhirnya dapat berakibat timbulnya pelanggaran-
pelanggaran, sebelum AMDAL disetujui kegiatan telah dimulai karena mengejar
produksi dan juga dapat menghambat investasi (investasi tidak kondusif).
Faktor lain yang juga penting dalam review kebijakan peraturan
pemerintah dalam kaitannya penerapan AMDAL yang efektif dan efisien adalah
tentang kedudukan komisi penilai atau komisi pusat AMDAL. Perubahan besar
yang terdapat dalam PP No. 27 tahun 1999 adalah disatukannya komisi penilai
pusat dan berkedudukan di kementerian negara lingkungan hidup. Apabila
penilaian tersebut tidak layak lingkungan maka instansi yang berwenang boleh
menolak permohonan ijin yang diajukan oleh pemrakarsa. Kedudukan komisi ini
menjadi sangat penting, khususnya dalam kaitannya dalam mencegah kerusakan
lingkungan pada kegiatan usaha migas. Kedudukan komisi penilai AMDAL pusat
saat ini berkedudukan di kementerian negara lingkungan hidup yang merupakan
86
instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. Kondisi ini kemudian
menjadi sangat penting untuk direview mengingat kegiatan usaha migas yang
bersifat sangat teknis dengan aspek profesionalitas yang tinggi. Kegiatan usaha
migas menggunakan teknologi tinggi dalam operasinya, sehingga dampak
lingkungan yang ditimbulkan, sangat memungkinkan dari kesalahan teknis
operasional. Berdasarkan hal itu, maka dibutuhkan komisi penilai antara lain, ahli
dalam bidang perminyakan dan geologi, ahli proses untuk kilang, ahli kimia,
sehingga dapat memprediksi dan mengetahui kemungkinan-kemungkinan dampak
besar dan penting yang ditimbulkan dalam kegiatan.
Tabel 11 Review kebijakan AMDAL dengan substansi komisi penilai
PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999 - Komisi AMDAL pusat
dibentuk oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sektoral dan berkedudukan di departemen atau LPND, dengan status keanggotaan tetap dan anggota tidak tetap
- Komisi AMDAL daerah dibentuk oleh Gubernur dan berkedudukan di Bapedalda propinsi dengan status keanggotaan tetap dan tidak tetap
- Komisi AMDAL pusat dibentuk oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sektoral dan berkedudukan di departemen atau LPND, dengan status keanggotaan tetap dan anggota tidak tetap
- Komisi AMDAL daerah dibentuk oleh Gubernur dan berkedudukan di Bapedalda propinsi dengan status keanggotaan tetap dan tidak tetap
- Komisi penilai AMDAL pusat dibentuk oleh menteri dan berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan
- Komisi penilai AMDAL daerah dibentuk oleh Gubernur dan berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan di tingkat I (Bapedalda propinsi)
Komisi pusat AMDAL dalam PP No. 27 tahun 1999 disebut komisi penilai
pusat yang dibentuk oleh kementerian negara lingkungan hidup dan berkedudukan
di Bapedal pusat dengan keanggotaan lebih representatif yang bertugas menilai
hasil AMDAL. Keberadaan komisi pusat AMDAL di bawah kewenangan
kementerian lingkungan hidup tersebut dianggap kurang tepat, mengingat
AMDAL pada kegiatan usaha migas sangat terkait dengan potensi dampak yang
muncul dari penerapan teknologi-teknologi yang digunakan. Untuk itu, keahlian
minyak dan gas dalam penilaian dokumen AMDAL menjadi sangat penting,
87
terkait dengan metode eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan tata
niaga. Metode-metode yang dikembangkan sangat spesifik dan membutuhkan
ahli-ahli di bidangnya. Dengan demikian, usulan pengembalian komisi pusat
AMDAL pada departemen teknis/sektor menjadi sangat penting.
Tabel 12 Review kebijakan AMDAL dengan substansi pembiayaan
PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999 - Biaya untuk membuat
KA-ANDAL,ANDAL, RKL, RPL dibebankan kepada pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan
- Untuk biaya tertentu dibebankan kepada menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup dan atau menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan dan atau gubernur kepala daerah tingkat I
- Biaya penyusunan kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan dibebankan kepada pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan
- Biaya penyusunan dan penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dibebankan kepada pemrakarsa
- Biaya pembinaan teknis dan pengawasan dibebankan pada anggaran instansi yang bertanggung jawab
Faktor pembiayaan juga menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat
kualitas dokumen yang dihasilkan akan sangat dipengaruhi oleh besaran biaya
studi yang dialokasikan. Pembiayaan yang proporsional dan jelas akan
memberikan hasil yang baik. Biaya akan sangat penting bagi terlaksananya
kegiatan sebagaimana tujuan yang akan dicapai. Pembiayaan studi yang sesuai
dengan kegiatan akan menjamin pelaksanaan kegiatan yang baik. Untuk faktor
pembiayaan menjadi hal yang positif apabila dimanfaatkan sesuai dengan
proporsinya. Demikian pula sebaliknya, pembiayaan studi yang minim dan tidak
proporsional akan menyulitkan dalam pelaksanaan studi yang sesuai dengan
tujuan. Pembiayaan tentu terkait dengan keahlian dari penyusun dan biaya dapat
menunjukkan/mencerminkan kedalaman studi dan analisis yang digunakan oleh
penyusun. Namun, hal ini sulit diukur karena sangat bervariasi.
88
5.1.2 Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri ESDM
Peraturan menteri dan keputusan menteri negara lingkungan hidup yang
terkait dalam pelaksanaan AMDAL di Indonesia antara lain Permen LH No. 08
tahun 2006 tentang pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan
dan Kepmen LH No. 11 tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan
yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
Peratuan menteri negara lingkungan hidup No. 08 tahun 2006 tentang
pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan merupakan
penjabaran kebijakan AMDAL yakni PP No. 27 tahun 1999 pasal 14 ayat (2) dan
pasal 17 ayat (2). Dalam Permen LH No. 08 tahun 2006 tersebut terdapat
beberapa hal yang perlu direview antara lain; pelingkupan, metode studi,
penyusun, serta biaya dan waktu studi.
Pelingkupan merupakan proses awal untuk menentukan lingkup
permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotesis) yang terkait
dengan rencana usaha dan atau kegiatan. Pelingkupan meliputi dampak penting
hipotetik, lingkup wilayah studi ANDAL didasarkan pada beberapa pertimbangan:
batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administratif, batas waktu
kajian, kedalaman studi ANDAL mencakup metode yang digunakan, jumlah
sampel yang diukur, dan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan sumberdaya
yang tersedia (dana dan waktu). Proses pelingkupan dampak penting terdiri atas;
identifikasi dampak potensial dan evaluasi dampak potensial. Hal ini sangat rancu
karena bila dampak potensial hanya sebagai dampak tunggal yang memperkirakan
potensi dampak, sedangkan isu pokok merupakan dampak yang terintegrasi dari
dampak yang komprehensif dan interaksi dampak kumulatif dari keseluruhan
dampak, jadi bukan hanya dampak tunggal, sangat penting didalam AMDAL
adalah isu pokok (main issue). Hal ini merupakan kelemahan dari Kepdal No. 08
tahun 2006 untuk menentukan dampak, pada skoping (pelingkupan) di KA-
ANDAL terdiri atas: skoping sosial, skoping ekologis, skoping perencanaan dan
kebijaksanaan (Beanlands dan Dunker, 1983).
Metode studi terdiri atas: metode pengumpulan data, metode analisa data,
metode prakiraan dampak dan metode evaluasi dampak. Metode disebutkan
89
merupakan metode yang baku dan sesuai dengan komponen lingkungan yang
dianggap akan terkena dampak (fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya).
Dengan kejelasan metode yang digunakan akan memudahkan pemrakarsa dan
penyusun AMDAL dalam menyusun dokumen AMDAL yang berkualitas dan
sesuai dengan kondisi di lapangan. Peraturan ini semestinya menjadi pedoman
dan panduan bagi pemrakarsa dan penyusun AMDAL dalam menyusun dokumen
AMDAL yang efisien dan efektif.
Penyusun terdiri atas kualifikasi ketua dan anggota tim. Ketua tim
penyusun studi disebutkan harus bersertifikat AMDAL penyusun dan sesuai
ketentuan yang berlaku, sedang anggota tim harus memiliki keahlian yang sesuai
dengan lingkup studi yang dilakukan.
Biaya studi diprosentasekan berdasarkan jenis-jenis biaya yang dibutuhkan
dalam rangka penyusunan studi AMDAL termasuk biaya untuk pelaksanaan
konsultasi masyarakat. Sedang waktu studi merupakan jangka waktu pelaksanaan
studi ANDAL sejak tahap persiapan hingga penyerahan laporan ke instansi yang
bertanggung jawab.
Keputusan menteri negara lingkungan hidup No. 11 tahun 2006 tentang
jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis
mengenai dampak lingkungan hidup merupakan penjabaran dari PP No. 27 tahun
1999 pasal 3 ayat (2) dan ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia
untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul. Namun dalam
penetapan jenis kegiatan khususnya pada sumberdaya minyak dan gas bumi
dengan menggunakan indikator jumlah produksi. Hal ini sangat tidak realiable
mengingat potensi dampak yang dapat terjadi tidak hanya pada skala usaha
dengan produksi yang tinggi, tapi juga pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan
akan berpotensi menghasilkan dampak penting. Dampak tidak hanya dilihat dari
sisi kuantitas atau besaran dampak tetapi juga dari sisi berbahayanya dampak
tersebut terhadap lingkungan hidup dan manusia. Penentuan dampak terhadap
lingkungan didasarkan pada perubahan indikator-indikator kualitas lingkungan.
Untuk mengetahui suatu perubahan aspek lingkungan dari suatu kegiatan tidak
berarti cukup menggunakan satu indikator (Suratmo, 2002).
90
Review kebijakan AMDAL migas dilakukan terhadap keputusan menteri
energi dan sumberdaya mineral No. 1457 tahun 2000 tentang pedoman teknis
pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi. Ada dua poin penting
yang perlu diperhatikan yakni isu pokok dan metode prakiraan dampak. Isu pokok
harus telah tercantum di dalam kerangka acuan. Sedang metode prakiraan dampak
besar dan penting disebut menggunakan metode formal (matematik, statistik) dan
non formal (analog dan professional judgement), serta metode evaluasi dampak.
Penentuan dampak besar dan penting menjadi sangat krusial, mengingat
potensial dampak yang dapat terjadi pada suatu kegiatan usaha. Untuk itu, selain
kriteria dan identifikasi bentuk-bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan dampak
besar dan penting, hal lain yang juga sangat menentukan adalah pengambil
keputusan penentuan dampak besar dan penting dari suatu rencana kegiatan.
Selama ini, sebagaimana diacu dalam PP No. 27 tahun 1999 pasal 5 ayat (2)
bahwa pedoman mengenai penentuan dampak besar dan penting ditetapkan oleh
kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
Pedoman penentuan dampak besar dan penting pada kegiatan usaha migas
ditetapkan oleh menteri ESDM. Selanjutnya dinyatakan bahwa untuk menetapkan
suatu dampak diperlukan tiga tahapan yakni: a) tahapan pertama yakni melakukan
identifikasi dampak yang terjadi pada komponen lingkungan, b) tahap kedua
yakni pengukuran atau perhitungan dampak yang akan terjadi pada komponen
lingkungan, dan c) tahapan ketiga yakni penggabungan beberapa komponen
lingkungan yang sangat berkaitan, kemudian dianalisis dan digunakan untuk
menetapkan refleksi dari dampak komponen-komponen sebagai indikator menjadi
gambaran perubahan lingkungan atau dampak lingkungan, d) menetapkan
parameter atau indikator dari komponen lingkungan yang akan diukur
(Sumarwoto, 2005).
Mengingat pentingnya penentuan dampak besar dan penting, sehingga
indikator penentuan dampak pada kegiatan usaha migas didasarkan pada aspek
teknologi, aspek produksi, aspek sosial budaya serta aspek ekonomi sumberdaya
alam dan lingkungan. Selain itu, penentuan dampak tersebut sebaiknya dilakukan
oleh lembaga independen yang terdiri atas unsur-unsur lembaga/instansi teknis,
kementerian lingkungan hidup, pemerhati lingkungan/LSM, praktisi lingkungan,
91
pakar/perguruan tinggi dan masyarakat dimana lokasi rencana kegiatan akan
dilakukan.
5.1.3 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Peraturan dalam bentuk keputusan kepala badan pengendalian dampak
lingkungan merupakan penjabaran dari peraturan keputusan menteri lingkungan
hidup. Ada beberapa keputusan kepala Bapedal yang mendukung pelaksanan
AMDAL agar terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan pemerintah yang telah
ditetapkan.
Keputusan kepala Bapedal yang direview antara lain keputusan kepala
badan pengendalian dampak lingkungan No. 229 tahun 1996 tentang pedoman
teknis kajian aspek sosial dalam penyusunan analisis mengenai dampak
lingkungan dan kepala badan pengendalian dampak lingkungan No. 08 tahun
2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses
analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
a. Penggunaan kata aspek sosial dalam peraturan ini diusulkan menjadi kata
aspek sosial ekonomi.
b. Pada lampiran I bagian C ruang lingkup pada poin 1 dinyatakan bahwa
komponen sosial yang ditelaah meliputi: demografi, ekonomi dan budaya.
Komponen yang direview yakni: ekonomi, demografi dan budaya yang
merupakanbukan bagian dari komponan sosial namun merupakan komponen
yang berdiri sendiri.
c. Pada lampiran III bagian A poin 1.5 untuk indikator ekonomi yang nilai
moneternya tidak bisa dianalisis dengan akurat, diperlukan value judgement
dari penyusun AMDAL. Caranya antara lain dengan menggunakan analogi
terhadap fenomena-fenomena dampak penting yang timbul menurut dokumen
AMDAL sejenis. Pernyataan mengenai diperlukan value judgement dari
penyusun AMDAL akan terlaksana dengan baik jika penyusun AMDAL
merupakan ahli ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan karena dengan
hanya menggunakan metode analogi tidak akan cukup untuk memberikan
nilai ekonomi yang akurat pada suatu sumberdaya alam dan lingkungan
hidup.
92
d. Pada lampiran III bagian A poin 2.b metode informal antara lain: 1) penilaian
pakar (professional judgement), 2) komparatif antar budaya (cross cultural),
3) teknik analogi dan 4) metode delphi. Penjabaran metode informal menjadi
4 teknik salah satunya penilaian akan bersifat objektif dan tingkat terjadinya
bias terhadap penilaian akan lebih tinggi.
e. Keputusan Kepala Bapedal No. 229 tahun 1996 sebaiknya dijadikan pedoman
wajib dalam menilai komponen sosial ekonomi dalam menyusun dokumen
KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL pada kegiatan usaha migas karena
berdasarkan hasil review kualitas dokumen AMDAL migas tidak satupun
penyusun yang melaksanakan metode analisis data ekonomi dengan
pendekatan pemberian nilai moneter (lampiran III bagian A poin 1.5)
dinyatakan bahwa data ekonomi sedapat mungkin diberi nilai moneter
(valuation) karena sebagian besar indikator-indikator ekonomi dapat
dikuantifikasi.
Pendekatan memberikan nilai moneter pada sumberdaya alam sering
diistilahkan dengan pendekatan valuasi ekonomi atau lebih dikenal total economic
valuation. Metode ini merupakan salah satu metode ekonomi sumberdaya yang
dapat memberikan nilai moneter pada sumberdaya baik tidak bernilai pasar
maupun yang bernilai pasar. Selain itu, dengan menggunakan metode TEV akan
diperoleh informasi nilai estimasi moneter suatu lingkungan/lahan yang akan
dialih fungsikan misal dari hutan menjadi daerah kegiatan usaha migas serta
dengan mengetahui nilai moneter suatu lingkungan akan dapat dijadikan salah
satu acuan dalam menentukan nilai ganti rugi terhadap lahan yang terpakai oleh
kegiatan migas.
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 08 tahun
2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses
analisis mengenai dampak lingkungan hidup, serta mekanisme keterlibatan
masyarakat dan keterbukaan informasi dalam PP No. 27 tahun 1999 disebutkan
secara jelas jangka waktu pelaksanaannya yakni 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diumumkannya rencana usaha dan atau kegiatan tersebut, serta merupakan bagian
tersendiri. Dalam penjelasannya tentang keterbukaan informasi dan peran
masyarakat yakni setiap usaha dan atau kegiatan wajib mengumumkan terlebih
93
dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai
dampak lingkungan hidup. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang
bertanggungjawab dan pemrakarsa dan tatacara pengumuman serta tatacara
penyampaian saran, pendapat dan tanggapan ditetapkan oleh kepala instansi yang
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dasar penentuan 30 hari kerja tidak
jelas, masyarakat hanya memberi tanggapan, selanjutnya tidak terlibat lagi sampai
pasca operasi.
Berdasarkan uraian dari hasil review kebijakan diperoleh sembilan
komponen mendasar yang merupakan perbedaan mendasar dan kelemahan dari
peraturan pemerintah No. 29 tahun 1986, PP No. 51 tahun 1993 dan PP No. 27
tahun 1999 tentang AMDAL, peraturan menteri negara LH No. 08 tahun 2006
tentang pedoman penyusunan AMDAL, dan Permen LH No. 11 tahun 2006
tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL,
keputusan menteri ESDM No. 1457 tahun 2000 tentang pedoman teknis
pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi, keputusan kepala
badan pengendalian dampak lingkungan No. 229 tahun 1996 tentang pedoman
teknis kajian aspek sosial dalam penyusunan AMDAL dan keputusan kepala
badan pengendalian dampak lingkungan No. 08 tahun 2000 tentang keterlibatan
masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL.
Tabel 13 Kelemahan-kelemahan kebijakan AMDAL migas
Substansi Kelemahan-kelemahan 1.Penentuan dampak
penting - Penentuan dampak tidak hanya didasarkan pada
dampak penting tetapi juga pada dampak besar, penyusunan AMDAL berdasarkan volume produksi bukan dampak penting dari suatu kegiatan migas.
- PP No. 29 tahun 1986 dan PP No. 51 tahun 1993 dikategorikan dampak penting, sedangkan PP No. 27 tahun 1999 dikategorikan dampak besar dan penting
2. Efisiensi penyusunan AMDAL
- PP No. 27 tahun 1999 waktu penyusunan relatif lama yakni 75 hari KA dan 75 hari ANDAL, RKL dan RPL, pada PP No. 29 tahun 1986 dan PP No. 51 tahun 1993 waktu penyusunan lebih singkat.
- Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL, mulai dari pengajuan hingga persetujuan AMDAL relatif 1-3 tahun.
- Biaya penyusunan AMDAL dibebankan kepada pemrakarsa tapi biaya lain dibebankan pada kementerian lingkungan hidup, departemen teknis/sektoral atau gubernur
94
Lanjutan Tabel 13 3. Komisi AMDAL
pusat - Komisi AMDAL dalam PP No. 27 tahun 1999
berada dibawah kewenangan kementerian lingkungan hidup
- Komisi AMDAL dalam PP No. 29 tahun 1986 dan PP No. 51 tahun 1993 berada pada masing-masing sektor
4. Metode pelingkupan
- Metode pelingkupan yang digunakan umumnya bergantung pada keahlian masing-masing penyusun, sehingga sulit melakukan penilaian metodologi yang tepat, kerena tidak adanya penetapan metode-metode standar/baku
5. Metode studi - Dalam Permen LH No. 08 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan AMDAL, metode perkiraan dan evaluasi dampak hanya disebutkan metode formal dan professional judgement, tidak terdapat metode yang baku yang dapat diacu bersama
6. Aspek sosial ekonomi
- Dalam keputusan kepala Bapedal No. 229 tahun 1996, komponen sosial ekonomi masih sekitar penyerapan tenaga kerja dan bantuan-bantuan sosial seperti pembangunan jalan, gedung sekolah dan sarana umum lainnya, dan belum banyak mengedepankan aspek ekonomi lingkungan, sehingga ketika terjadi emergency yang berdampak terhadap lingkungan maka sangat sulit melakukan penilaian
7. Keterlibatan masyarakat
- Dalam keputusan kepala Bapedal No. 08 tahun 2000, keterlibatan masyarakat selama ini hanya bersifat formalitas yang porsinya adalah pada waktu pengumuman masyarakat, dengan demikian tidak ada check and balances dari masyarakat secara langsung terhadap dampak yang dapat terjadi
8. Analisis valuasi ekonomi lingkungan
- Analisis valuasi ekonomi lingkungan/total economic valution sesungguhnya telah dicantumkan dalam Keputusan Kepala Bapedal No. 229 tahun 1996 tentang pedoman teknis kajian aspek sosial ekonomi, namun belum ada peraturan yang mewajibkan penggunaan metode TEV dalam penyusunan AMDAL, sehingga hingga saat ini belum ada bukti penerapannya
9. Emergency/ Keadaan Darurat
- Masalah emergency/keadaan darurat tidak ada keterkaitan dengan AMDAL dan tidak disebutkan dalam Kepmen ESDM No. 1457 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan lingkungan
95
5.2 Kualitas Dokumen AMDAL Migas
Pelaksanaan AMDAL pada kegiatan usaha migas diterapkan mulai tahun
1986 dengan menghasilkan beberapa dokumen AMDAL. Untuk mengetahui
sejauhmana kualitas dokumen AMDAL pada kegiatan usaha migas maka perlu
dilakukan review dokumen. Hasil review terhadap kualitas dokumen AMDAL
pada tujuh dokumen AMDAL yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan bahwa
umumnya pemrakarsa dan tim penyusun AMDAL dapat memenuhi kriteria
indikator sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Analisis kualitas dokumen AMDAL migas dilakukan pada tujuh
perusahaan migas yaitu perusahaan PT.CPI Lapangan Duri, Pertamina UP III
Plaju, PT.Lapindo Brantas, KKKS Suryaraya Teladan Pendopo, BP Tangguh,
Expan Blok Toili dan KKKS Hess Pangkah.
1. PT.Chevron Pacific Indonesia Duri
Dokumen KA-ANDAL disahkan pada tahun 1990 sementara dokumen
ANDAL disetujui pada tahun 1991, RKL dan RPL-nya disetujui pada tahun 1993,
hal ini karena sesuai PP 29/1989 yang diajukan dan disetujui secara bertahap atau
terpisah oleh masing-masing dokumen setelah ANDAL disetujui dan kegiatan
berlangsung baru dimulai penyusunan dokumen RKL dan RPL dan disahkan oleh
komisi AMDAL.
Dokumen AMDAL ini disusun oleh tim penyusun dari PPLH UNRI dan
PT Bumi Prasidi. Hasil dari review dokumen ternyata tim penyusun tidak lengkap
yang mana ahli geologi dan ahli perminyakan tidak tersedia. Tim penyusun
AMDAL terbagi dalam dua tim yakni; a) tim inti yang terdiri atas penanggung
jawab, staf konsultan senior dan tim pemantau rona awal dan penilai lingkungan,
b) tim studi tata guna tanah, sosial ekonomi dan budaya, yang terdiri atas;
penanggung jawab, koordinator sosial ekonomi, koordinator sosial budaya, dan
koordinator tata guna tanah. Anggota tim terdiri: ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli
pendidikan, ahli kepustakaan, ahli perikanan, ahli sosiologi.
Review dokumen KA-ANDAL PT. CPI Lapangan Duri bahwa deskripsi
rencana kegiatan dan rona lingkungan awal dijelaskan secara rinci dan lengkap
dan metode prakiraan dampak dalam dokumen ANDAL ini terdiri atas; a)
96
pemantauan meteorologi, b) pemantauan kualitas udara sekitar dan c) analisa
dampak kualitas udara. Demikian pula dengan uraian batas wilayah studi
dijelaskan dengan rinci dan dilengkapi dengan peta-peta. Namun, rumusan
pelingkupan tidak dijelaskan dalam dokumen ANDAL. Metode prakiraan dampak
sama dengan yang ada dalam dokumen KA-ANDAL, hanya lebih lengkap dan
detail. Sedangkan metode evaluasi dampak penting tidak disebutkan dalam
dokumen ANDAL ini dan tidak dilakukan evaluasi dampak penting yang di dalam
dokumen AMDAL.
Review dokumen RKL dan RPL yang disahkan pada tahun 1992,
menunjukkan bahwa dampak yang harus dikelola dan dipantau antara lain:
penurunan kualitas udara, penurunan air permukaan, penurunan kualitas air tanah,
perubahan vegetasi dan penurunan populasi fauna, terbukanya kesempatan kerja
dan jasa setempat. Dan langkah-langkah pengelolaan yang diterapkan antara lain :
membakar limbah gas di flare, memproses air limbah sebelum dibuang
kelingkungan, membuat kanal untuk pendingin air buangan (air terproduksi),
melakukan penghijauan pada areal-areal yang terbuka, melestarikan tanaman
hutan didaerah kantong antara lokasi sumur dan kawasan lain, penimbunan sludge
dan sisa lumpur pemboran tidak disebutkan teknologi dalam pengelolaan limbah
tersebut, memanfaatkan tenaga kerja dan jasa setempat. Sedangkan pemantauan
lingkungan yang dilakukan antara lain: pemantuan kualitas air limbah,
pemantauan kualitas udara, pemantauan kualitas air tanah, pemantauan flora dan
fauna.
2. Pertamina UP III Plaju
Dokumen KA-ANDAL Pertamina UP III Plaju Sungai Gerong, disahkan
pada tahun 1990 sementara dokumen ANDAL disetujui pada tahun 1991, RKL
dan RPL disetujui pada tahun 1993, hal ini karena sesuai PP 29/1989 yang
diajukan dan disetujui secara bertahap atau terpisah oleh masing-masing dokumen
setelah ANDAL disetujui dan kegiatan berlangsung baru dimulai penyusunan
dokumen RKL dan RPL dan disahkan oleh komisi AMDAL.
Kegiatan studi evaluasi lingkungan kilang Musi Pertamina UP III Plaju,
Sungai Gerong disusun oleh tim penyusun PT.Unisystem Utama (Ltd) dengan
kualifikasi terdiri atas ketua tim, ahli teknik proses kilang/perminyakan, ahli
97
iklim,udara dan bising, ahli hidrologi, ahli geologi, ahli biologi darat, ahli biologi
perairan, ahli kesehatan lingkungan, ahli sosio ekonomi dan ahli sosial budaya.
Berdasarkan hasil review kualitas dokumen KA-ANDAL bahwa deskripsi
rona lingkungan awal lengkap dan jelas. Deksripsi kegiatan terdiri atas tiga
kegiatan yaitu kegiatan utama, kegiatan utilitas dan kegiatan unit off site.
Parameter lingkungan yang perlu ditelaah yaitu:
a. Komponen fisik-kimia yang meliputi: suhu udara rata-rata dan increment
persatuan tinggi dari permukaan bumi), curah hujan, kecepatan angin rata-rata,
arah angin rata-rata, stabilitas angin, wind rose, fisiografi, stratiografi, adanya
keunikan, keistimewaan dan kerawanan bentuk lahan dan batuan secara
ekologi, parameter udara lingkungan, parameter emisi dari cerobong, kualitas
air tanah saat musim hujan dan musim kemarau, kualitas air sungai.
b. Komponen biologi meliputi: fauna darat dan air, flora darat dan air, flora dan
fauna yang dilindungi.
c. Komponen sosial ekonomi dan budaya meliputi: taraf hidup masyarakat,
lapangan kerja, pendidikan, mental ideologi dan agama, warisan alam dan
budaya, kesehatan masyarakat dan citra pertamina.
Metode analisis dan evaluasi dampak hanya menggunakan metode
identifikasi/prediksi dampak dengan menggunakan metode bagan alir dan matrik
dan evaluasi dampak penting yang sudah ada dan yang mungkin timbul dengan
mengacu pada keputusan menteri LH No. 49 tahun 1987.
Hasil review kualitas dokumen ANDAL menunjukkan bahwa batas
wilayah studi lengkap dan disertai dengan peta pengambilan sampel dengan skala
yang memadai. Komponen lingkungan yang ditelaah pada dokumen KA-ANDAL
dan ANDAL isinya sama namun dalam dokumen ANDAL lebih detail
dijelaskannya. Metode studi hanya dibuat dalam bentuk matriks. Metode studi
yang digunakan lebih banyak yang bersifat kuantitatif.
Hasil review kualitas dokumen RKL yang disahkan pada tahun 1993
bahwa pendekatan pengelolaan lingkungan yang diuraikan terdiri atas tiga
pendekatan yakni; pendekatan teknologi, ekonomi dan institusi. Uraian
pendekatan teknologi cukup jelas dan operasional dengan ditunjang oleh data-data
hasil monitoring, sedangkan untuk pendekatan ekonomi pembahasannya terbatas
98
pada dampak yang akan timbul terhadap prosedur dan alokasi anggaran
perusahaan tidak membahas masalah dampak ekonomi terhadap masyarakat dan
untuk pendekatan institusi tidak jelasnya sistem koordinasi yang dibentuk dan
dengan siapa perusahaan melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan
lingkungan.
Dampak penting yang dikelola mencakup tiga dampak yaitu air limbah
kilang, emisi gas dan limbah padat dengan jenis dampak meliputi: kenaikan kadar
minyak di Sungai Komering dan Sungai Musi, akumulasi endapan minyak setebal
20 cm di dasar Sungai Komering sekitar outfall, akumulasi Pb dan Hg dalam
ruang, kerusakan ekosisten perairan sungai Komering dan sungai Musi yang
menjadi tidak produktif untuk mencari ikan sehingga sebagian besar kebutuhan
ikan di Palembang harus diproduksi di tambak dan didatangkan dari Riau,
menurunnya kualitas udara ambien sebagai akibat adanya emisi gas, indikasi
dominannya penyakit pada saluran pernapasan yang diduga salah satunya karena
pengaruh kualitas udara di Plaju dan Mariana.
Rencana pengelolaan lingkungan terdiri atas: perusahaan membangun
kanal khusus untuk mengalirkan discharge air pendingin sehingga outlet
pembuangan air pendingin terpisah dengan outlet pembuangan air, memperbaiki
sistem netralisasi di TA/PTA, memasang CPI di kilang plaju dan Sungai Gerong
pada lokasi tertentu dengan skala yang telah ditetapkan, pemilihan CCR yang
berkadar rendah, mengganti oil recovery dan membakar sludge di Incinerator,
mengganti strainer Incinerator TA/PTA, membuat dumping area kedap air.
Review kualitas dokumen RPL menunjukkan bahwa dampak penting yang
dipantau sama dan konsisten dengan dampak penting yang dikelola, yakni ada 3
buah dampak penting. Metode analisis yang digunakan dalam pemantauan
lingkungan adalah pemuaian, potensi metrik, gravimetrik, spektofotometrik dan
titrimetrik. Metode rencana pemantauan berdasarkan dampak penting tidak
dijelaskan secara jelas dan operasional.
3. PT. Lapindo Brantas Sidoarjo
Kegiatan pengembangan lapangan gas bumi wunut Blok Brantas,
Kabupaten Sidoarjo propinsi Jawa Timur disusun oleh tim penyusun PT.Corelab
Indonesia yang terdiri atas ketua tim, sub tim iklim dan kualitas udara, sub tim
99
hidrologi dan kualitas air, sub tim geologi, sub tim biologi terestrial, sub tim
tanah, ruang dan lahan, sub tim sosial ekonomi dan budaya. Dari hasil review
menunjukkan tidak tersedianya ahli perminyakan dalam tim penyusun AMDAL.
Berdasarkan hasil review kualitas dokumen KA-ANDAL diperoleh bahwa
komponen rencana kegiatan yang diduga akan menimbulkan dampak sehingga
perlu ditelaah berdasarkan tahapan kegiatan terdiri atas: tahap prakonstruksi
sebanyak dua kegiatan/parameter, tahap konstruksi dan pemboran sebanyak empat
kegiatan/parameter, tahap operasi produksi sebanyak 3 kegiatan/parameter, tahap
pasca operasi sebanyak 3 kegiatan/parameter.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam dokumen AMDAL
yakni pengumpulan data primer dan data sekunder namun tidak dijelaskan secara
rinci. Metode analisis data diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif, namun lebih banyak yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.
Metode prakiraan dampak penting hanya menggunakan metoda formal yaitu
pendekatan matematis dan penggunaan baku mutu lingkungan seharusnya batas
baku mutu lingkungan bukan merupakan metode prakiraan dampak tapi sebagai
baku mutu lingkungan (BML) dan metoda informal berupa penilaian para ahli
(profesionel judgement).
Metode evaluasi dampak lingkungan dilakukan secara lintas disiplin yang
mencakup komponen lingkungan fisik, kimia, geologi, biologi, dan sosial
ekonomi serta budaya. Masing-masing dampak diberi bobot nilai pentingnya
dengan angka dan penilaiannya didasarkan pada penilaian para ahli penyusun
AMDAL dengan memperhatikan baku mutu lingkungan yang berlaku di lokasi
dimaksud. Dalam dokumen ini terdapat sub bab yang menjelaskan tentang metoda
penetapan arahan penanganan lingkungan.
Uraian rona lingkungan awal cukup jelas dan lengkap. Ada tiga komponen
lingkungan yang diuraikan yaitu; komponen lingkungan geofisik-kimia,
komponen lingkungan biologi dan komponen lingkungan sosial dan kesehatan
masyarakat.
Hasil review kualitas dokumen ANDAL menunjukkan bahwa komponen
rencana kegiatan yang diduga akan menimbulkan dampak sama dengan yang
diuraikan dalam dokumen KA-ANDAL. Uraian batas wilayah studi dijelaskan
100
dengan lengkap dan rinci serta dilengkapi dengan peta-peta lokasi kegiatan.
Dalam dokumen ANDAL ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah
pengumpulan data primer dan data sekunder dan tidak dijelaskan secara rinci.
Metode analisis data diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif, namun lebih banyak yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.
Metode prakiraan dampak penting menggunakan metoda formal
(pendekatan matematis dan penggunaan baku mutu lingkungan) dan metoda
informal berupa penilaian para ahli (professional judgement). Metode evaluasi
dampak lingkungan dilakukan secara lintas disiplin yang mencakup komponen
lingkungan fisik, kimia, geologi, biologi, dan sosial ekonomi serta budaya.
Masing-masing dampak diberi bobot nilai pentingnya dengan angka dan
penilaiannya didasarkan pada penilaian para ahli penyusun AMDAL dengan
memperhatikan baku mutu lingkungan yang berlaku di lokasi dimaksud. Dalam
dokumen ini terdapat sub bab yang menjelaskan tentang metoda penetapan arahan
penanganan lingkungan. Uraian rona lingkungan awal cukup jelas dan lengkap.
Ada tiga komponen lingkungan yang diuraikan yaitu komponen lingkungan
geofisik-kimia, komponen lingkungan biologi dan komponen lingkungan sosial
dan kesehatan masyarakat
Dokumen ANDAL telah dilengkapi dengan matriks prakiraan dampak
penting yang cukup jelas demikian juga matriks dan bagan alir evaluasi dampak
penting ada dan jelas. Jumlah dan jenis dampak penting yang dievaluasi konsisten
dengan hasil prakiraan dampak penting. Arahan pengelolaan lingkungan dalam
dokumen ANDAL disajikan dan konsisten dengan hasil prakiraan dan evaluasi
dampak penting.
Hasil review dokumen RKL menunjukkan bahwa komponen lingkungan
yang akan dikelola; kualitas udara, kualitas air sungai, sosial ekonomi dan budaya,
uraian pendekatan pengelolaan dampak lingkungan cukup jelas, terdiri atas
pendekatan teknologi, sosial-ekonomi-budaya dan kelembagaan.
a. Pendekatan Teknologi
Penanganan dampak melalui pendekatan teknologi yang akan dilakukan;
teknologi pengendalian pencemaran kualitas udara akibat adanya pembakaran
limbah gas. CPF mempunyai sebuah flare stack yang bertujuan untuk membakar
101
gas dari degassing boot dan membakar gas yang harus dikeluarkan dari generator,
kompresor, reboiler, dan glycol. Teknologi pengendalian pencemaran kualitas
perairan akibat kegiatan proses pemisahan gas. Proses pemisahan gas dan cairan
(air dan kondesat) terjadi didalam separator. Pemisahan dilakukan dengan prinsip
perbedaan berat jenis antara gas dan cairan.
b. Pendekatan Sosial dan Ekonomi
Penanganan dampak lingkungan dari sudut pendekatan sosial ekonomi;
memprioritaskan penyerapan tenaga kerja penduduk setempat, sepanjang
kualifikasinya terpenuhi dan dibutuhkan, pelaksanaan ganti rugi pembebasan
lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat atau agama setempat untuk
mencegah kemungkinan timbulnya keresahan sosial, memelihara dan
memperbaiki lahan sepanjang jalur pemasangan pipa (dengan lebar 3 meter) dan
memberi ganti rugi kepada petani yang tanamannya rusak karena proses
pemasangan pipa, penyuluhan kepada penduduk tentang adanya manfaat kegiatan
di daerahnya sehingga mereka dapat mempunyai kesempatan untuk mencari
peluang ekonomi maupun pekerjaan yang tadinya belum terpikirkan.
c. Pendekatan Kelembagaan
Penanganan dampak yang akan dilakukan melalui pendekatan
kelembagaan; melakukan koordinasi dengan Ditjen Migas (c.q. Direktorat Teknik
Pertambangan Migas) dalam rangka pembinaan dan pengawssan terhadap
kemungkinan timbulnya kasus pencemaran dan keselamatan kerja, melakukan
koordinasi dengan Pemda Dati II Sidoarjo Jawa Timur dalam rangka penyelesaian
masalah keamanan dan konflik sosial yang mungkin timbul, melakukan
koordinasi dengan Ditjen Migas, BPPKA Pertamina, bagian lingkungan Pemda
Dati II Sidoarjo Jawa Timur, serta Bapedal dan instansi terkait lainnya dalam
penanganan masalah pencemaran lingkungan.
Prioritas yang akan dilakukan dalam RKL ini diarahkan pada upaya
penanganan kemungkinan timbulnya dampak-dampak; penurunan kualitas
perairan sungai di sekitas lokasi pembuangan limbah cair hasil proses produksi,
bila kasus terburuk terjadi, penurunan kualitas udara di sekitar lokasi CPF dan
pemukiman terdekat akibat pembakaran gas, peningkatan pendapatan penduduk di
102
sekitar kegiatan akibat kemungkinan adanya kesempatan kerja dan kesempatan
memanfaatkan keberadaan proyek. Dokumen RKL dilengkapi dengan institusi
dan pelaksana pengelolaan lingkungan, peta lokasi pembuangan air terproduksi
dilengkapi dengan legenda dan skala 1:50000 dan matriks ringkasan rencana
pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan penjelasan narasinya.
Berdasarkan hasil review dokumen RPL menunjukkan bahwa dalam
dokumen RPL ada satu komponen dari tiga komponen yang dipantau berbeda
dengan komponen yang dikelola, komponen yang dikelola yaitu kualitas udara,
kualitas air dan sosial ekonomi budaya sedangkan komponen yang dipantau yaitu
kualitas udara, kualitas air terproduksi, sosial ekonomi dan budaya. Dokumen
RPL dilengkapi dengan peta lokasi rencana pemantauan dampak yang disajikan
per jenis dampak yang dipantau (air, udara dan sosial, ekonomi dan budaya) dan
matriks RPL yang sesuai dan konsisten dengan narasi dan RKL.
4. Pertamina-Suryaraya Teladan Pendopo
Dokumen ANDAL disetujui tanggal 6 Januari 2000 melalui surat No.
0022/31/SJN.T/2000. Kegiatan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi
Benakat Barat, Pendopo disusun oleh PPLH UGM terdiri atas ketua tim, ahli fisik
kimia udara, ahli kimia limbah/perminyakan, ahli pertambangan, ahli
geomorfologi, ahli biotik, ahli sosial ekonomi budaya, ahli kesehatan masyarakat.
Berdasakan hasil review kualitas dokumen AMDAL dalam tim penyusun tidak
terdapat ahli perminyakan dan ahli geologi. Penyusun dokumen ANDAL yang
memiliki sertifikat AMDAL A dan B sejumlah 4 orang (44%), sedangkan Ketua
Tim hanya mempunyai sertifikat AMDAL B.
Dalam dokumen ANDAL, deskripsi kegiatan dan batas wilayah studi
cukup jelas dan lengkap serta disertai dengan peta-peta yang berskala memadai.
Adapun jenis rencana kegiatan yang diprakirakan akan menimbulkan dampak
lingkungan; tahap pra kontruksi meliptui pengadaan lahan, tahap kontruksi
meliputi pengerahan dan pelepasan tenaga kerja, mobilisasi peralatan dan
material, pembukaan dan pematangan lahan, pembangunan prasarana dan sarana,
pembangunan fasilitas produksi dan penunjangnya, pemboran sumur
pengembangan, uji hidrostatik, dan tahap operasi meliputi pengerahan dan
pelepasan tenaga kerja, proses produksi, kerja ulang sumur, injeksi sumur,
103
pembersihan tangki, serta tahap pasca operasi meliputi pengerahan dan pelepasan
tenaga kerja, penanganan lokasi, penanganan bahan kimia bekas, program
penghijauan dan demobilisasi alat.
Komponen lingkungan hidup yang diprakirakan akan terkena dampak
terdiri atas 12 (parameter) yakni; iklim dan kualitas udara, kebisingan, persepsi
masyarakat, kuantitas dan kualitas air permukaan, kesuburan tanah, pola
hubungan dan nilai tanah, flora dan fauna darat, erosi dan kualitas tanah,
pendapatan penduduk, kualitas dan kuantitas air formasi, struktur geologi dan
kualitas air tanah dangkal.
Jenis rencana kegiatan yang terdapat di KA-ANDAL dan dokumen
ANDAL sama dengan pembagian berdasarkan empat tahap kegiatan yaitu; tahap
pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Untuk komponen
lingkungan yang diprakirakan terkena dampak dalam dokumen ANDAL sama
dengan yang ada dokumen KA-ANDAL sebanyak 12 parameter. Namun dalam
komponen lingkungan hidup yang diprakirakan terkena dampak terdapat
inkonsistensi antara narasi dengan tabel, antara lain; kegiatan pembukaan dan
pembersihan lahan, dalam narasi disebutkan terdapat penurunan kuantitas dan
kualitas air permukaan sedangkan dalam tabel disebutkan terdapat run off,
pembangunan fasilitas produksi. Dalam narasi disebutkan terdapat kerusakan
struktur tanah, sedangkan dalam tabel disebutkan penurunan kualitas udara dan
peningkatan kebisingan, kerja ulang sumur, dalam narasi disebutkan terdapat
penurunan kualitas air formasi, sedangkan dalam tabel disebutkan ada
peningkatan kebisingan, penanganan lokasi, dalam narasi tidak disebutkan bahwa
terdapat perubahan pola hubungan nilai tanah, sedangkan dalam narasi disebutkan
terdapat perubahan pola hubungan nilai tanah.
Dampak penting yang dikaji pada dokumen ANDAL, yakni; tahap pra
kontruksi. Dalam kegiatan pengadaan lahan, dampak penting yang dikaji adalah
terganggunya pola hubungan dan nilai tanah (-P).
a. Tahap konstruksi. Beberapa kegiatan dalam tahap konstruksi yang
menimbulkan dampak penting yang perlu dikaji pada dokumen ANDAL
antara lain: 1) Dalam kegiatan pengerahan dan pelepasan tenaga kerja,
dampak penting yang dikaji adalah terganggunya persepsi masyarakat (-P), 2)
104
Dalam kegiatan mobilisasi peraltaan dan material, dampak penting yang
dikaji adalah terganggunya persepsi masyarakat (-P) dan perubahan sanitasi
lingkungan dan pola penyakit (-P) dan 3) Dalam kegiatan pembukaan dan
pematangan lahan, dampak penting yang dikaji adalah; peningkatan kuantitas
air permukaan (run off) (-P), penurunan kualitas air permukaan (-P),
peningkatan erosi (-P), perubahan bentuk lahan, relief dan sudut kemiringan
lereng (-P), turunnya tingkat kesuburan tanah (-P), kerusakan struktur tanah (-
P), perubahan tata ruang, lahan, dan tanah (-P), penurunan keanekaragaman
fauna darat (-P), penurunan tingkat penutupan lahan oleh flora darat (-P),
dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, dampak penting yang
dikaji adalah kerusakan struktur tanah (-P), dalam kegiatan pemboran sumur
pengembangan, dampak penting yang dikaji adalah penurunan kuantitas air
permukaan (-P) dan persepsi negatif masyarakat (-P).
b. Tahap operasi; beberapa kegiatan dalam tahap operasi yang menimbulkan
dampak penting yang perlu dikaji pada dokumen ANDAL antara lain; dalam
kegiatan pegerahan dan pelepasan tenaga kerja, dampak penting yang dikaji
adalah persepsi negatif masyarakat (-P), dalam kegiatan proses produksi,
dampak penting yang dikaji adalah penurunan kualitas udara (-P), penurunan
kualitas air permukaan (-P), dan penurunan kesuburan tanah (-P), dalam
kegiatan pembersihan tangki, dampak penting yang dikaji adalah tingkat
kesuburan tanah (-P), penurunan kualitas air tanah dangkal (-P), dan persepsi
negatif masyarakat (-P).
c. Tahap pasca operasi; beberapa kegiatan dalam tahap pasca operasi yang
menimbulkan dampak penting yang perlu dikaji pada dokumen ANDAL
antara lain; dalam kegiatan penanganan lokasi, dampak penting yang dikaji
adalah peningkatan kualitas air permukaan (+P), dalam kegiatan program
penghijauan, dampak penting yang dikaji adalah; peningkatan kualitas udara
(+P), penurunan kuantitas air permukaan (+P), peningkatan kualitas air
permukaan (+P), berkurangnya erosi (+P), meningkatnya kesuburan tanah
(+P), perbaikan struktur tanah (+P), perbaikan tata ruang, lahan dan tanah
(+P), peningkatan keanekaragaman fauna darat (+P), peningkatan penutupan
105
lahan flora darat (+P), peningkatan keanekaragaman flora darat (+P),
peningkatan kemelimpahan flora darat (+P).
Hasil review pada dokumen RKL untuk kegiatan pengembangan lapangan
migas Benakat Barat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan yang
dibagi dalam 4 tahap yaitu tahap persiapan (pra-konstruksi), tahap pembangunan
(konstruksi), tahap operasi dan tahap pasca operasi. Pada tahap pra konstruksi
terdapat satu dampak lingkungan yang ditimbulkan, tahap konstruksi terdapat 15
dampak, tahap operasi terdapat delapan dampak dan tahap pasca operasi terdapat
13 dampak.
Komponen lingkungan yang akan dikelola terdiri atas: 1) komponen geo-
fisik-kimia yang dipantau adalah kualitas dan kuantitas air permukaan, run off,
erosi, bentuk lahan, relief, kemiringan lereng, struktur tanah, kesuburan tanah, tata
ruang-lahan-tanah, dan kualitas udara, 2) komponen biotis yang dipantau adalah
keanekaragaman flora dan fauna darat, penutupan lahan oleh flora darat,
keanekaragaman ikan, dan kelimpahan flora darat, 3) komponen sosial, ekonomi,
budaya-kesehata masyarakat yang dipantau adalah pola hubungan dan nilai tanah,
persepsi masyarakat, sanitasi lingkungan dan pola penyakit.
Uraian pendekatan pengelolaan dampak lingkungan cukup jelas terdiri atas
pendekatan teknologi, pendekatan ekonomi, sosial dan budaya dan pendekatan
institusi. Beberapa upaya pengelolaan dampak berdasarkan tahap kegiatan,antara
lain; pendekatan persuasif dan memberikan penggantian yang layak, negosiasi
langsung dengan pemilik tanah, pemberian penyuluhan, melibatkan pihak bank
pada saat pembayaran (apabila dimungkinkan), memberikan informasi yang jrlas
tentang tenaga kerja yang dibutuhkan, pendekatan masyarakat dan penyuluhan,
penyuluhan kesehatan masyarakat, penanaman tanaman pioner merambat yang
cepat tumbuh, memulihkan kembali tanah yang sudah rusak strukturnya,
meminimalkan perubahan tata ruang, lahan dan tanah setelah kegiatan proyek
selesai, mempertahankan keanekaragaman jenis fauna yang ada, menurangi
perluasan tanah terbuka, memulihkan kembali tanah yang sudah rusak
strukturnya, mencegah penurunan kuantitas air permukaan, mengelola penurunan
kuantitas air permukaan, pembakaran gas sisa di flare stake, menyediakan
tambahan pompa menjadi 3 sampai dengan 4 pompa dengan kapasitas injeksi
106
13000 barel/hari, menyediakan skimming pit, pemeliharaan atau pemantauan
pompa injeksi, bantuan ekonomi masyarakat, pengangkutan sisa-sisa pembersihan
tangki bleber ke unit pengelolaan limbah B3, tempat penimbunan sementara harus
pudal lapisan kedap air dan jauh dari badan air, mengembangkan kegiatan
penghijauan.
Hasil review untuk dokumen RPL bahwa dampak penting yang dipantau
sama dengan dampak penting yang dikelola yaitu pada tahap pra konstruksi ada
satu dampak lingkungan yang ditimbulkan, tahap konstruksi terdapat 15 dampak,
tahap operasi terdapat 8 dampak dan tahap pasca operasi terdapat 13 dampak.
Selain itu, komponen lingkungan yang dikelola sama dengan komponen
lingkungan yang dipantau. Komponen lingkungan yang akan dipantau terdiri atas:
1) komponen geo-fisik-kimia yang dipantau adalah kualitas dan kuantitas air
permukaan, run off, erosi, bentuk lahan, relief, kemiringan lereng, struktur tanah,
kesuburan tanah, tata ruang-lahan-tanah, dan kualitas udara, 2) komponen biotis
yang dipantau adalah keanekaragaman flora dan fauna darat, penutupan lahan oleh
flora darat, keanekaragaman ikan, dan kelimpahan flora darat dan 3) komponen
sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat yang dipantau adalah pola
hubungan dan nilai tanah, persepsi masyarakat, sanitasi lingkungan dan pola
penyakit.
Metode rencana pemantauan dampak lingkungan pada semua komponen
masih bersifat umum dan tidak operasional seperti metode rencana pemantauan
untuk komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat
menggunakan metode wawancara dan pengamatan langsung dan untuk komponen
geo-fisik-kimia dan biologis menggunakan metode pengamatan di lapangan dan
analisis laboratorium. Dokumen RPL dilengkapi dengan peta lokasi dan matriks
rencana pemantauan dampak lingkungan.
5. Expan Toili Sulawesi
Kegiatan pengembangan minyak Tiaka dan fasilitas penunjangnya, blok
Toili, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah di susun
oleh PPLH-IPB dengan tim penyusun terdiri atas: ketua tim dan anggota tim,
fisik-kimia (9 orang), sub biologi (4 orang), sub tim sosial ekonomi budaya (8
107
orang), penyelam (2 orang), tenaga pendukung (6 orang) dan narasumber (1
orang).
Berdasarkan hasil review dokumen KA-ANDAL yang disetujui pada tahun
2002 menunjukkan bahwa komponen lingkungan yang diprakirakan terkena
dampak yakni: a) fisik kimia 10 parameter, b) biologi 3 parameter, dan c) sosial,
ekonomi, bududaya dan kesehatan lingkungan masyarakat 8 parameter. Deskripsi
rencana kegiatan terdiri atas 4 tahap yakni: tahap pra konstruksi, konstruksi,
operasi dan pasca operasi. Tahap pra konstruksi meliputi perizinan, survei
kelayakan teknis dan rekruitmen dan seleksi tenaga kerja, tahap konstruksi
meliputi mobiliasi tenaga kerja, pembangunan porta camp dan workshop,
pembangunan temporary jetty (di darat dan Gosong Tiaka), pengadaan dan
pengangkutan material reklamasi, reklamasi tapak kegiatan, pembangunan
pelabuhan khusus jetty, pembangunan porta camp, pemboran sumur produksi
dengan sistem cluster dan pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas
pendukung, tahap operasi meliputi mobilisasi tenaga kerja, produksi dan
pengoperasian jetty dan tahap pasca operasi meliputi penutupan sumur produksi,
demobiliasi peralatan dan penanganan lokasi setelah penutupan.
Deskripsi rona lingkungan awal cukup jelas dan lengkap dengan isu pokok
yang diperoleh adalah; 1) penurunan produktivitas dan keanekaragaman hayati, 2)
pertumbuhan ekonomi daerah, dan 3) perubahan lingkungan fisik. Uraian batas
wilayah studi cukup jelas dan didukung oleh peta-peta. Dalam uraian metode studi
parameter yang diukur pada komponen fisik kimia, biologi, sosial ekonomi
budaya dan kesehatan lingkungan masyarakat cukup jelas. Demikian pula untuk
metode pengumpulan data dan analisis data cukup jelas. Sedangkan, dalam
metode prakiraan dampak penting juga dijelaskan secara jelas metode yang
digunakan yang terdiri atas; model matematik, baku mutu lingkungan, analog dan
penilaian para ahli.
Berdasarkan hasil review dokumen ANDAL yang disahkan pada tahun
2002 menunjukkan bahwa jenis rencanan kegiatan yang diprakirakan akan
menimbulkan dampak lingkungan sama dengan yang dibuat di KA-ANDAL
demikian pula pada komponen lingkungan yang diprakirakan terkena dampak
108
terdiri atas 21 buah parameter yaitu fisik kimia sebanyak 10 parameter, biologi
sebanyak tiga parameter dan sosekbud dan keslingmas sebanyak 8 parameter.
Rumusan isu pokok terdiri atas tiga isu yang berarti sama dengan yang
dirumuskan di KA-ANDAL dan dampak penting hipotetik yang dikaji pada
dokumen ANDAL ada 12 buah yang terdiri atas: kualitas air laut, kualitas udara,
fisiografi pulau, jenis dan kelimpahan biota perairan, satwa liar, hasil tangkapan
laut, kesempatan kerja dan berusaha, perekonomian lokal, resiko kecelakaan laut,
pengusahaan dan pemanfaatan pulau, kesehatan masyarakat, persepsi masyarakat
terhadap proyek.
Dokumen ANDAL telah dilengkapi dengan matriks prakiraan dampak
penting yang cukup jelas demikian juga matriks dan bagan alir evaluasi dampak
penting ada dan jelas. Jumlah dan jenis dampak penting yang dievaluasi konsisten
dengan hasil prakiraan dampak penting. Arahan pengelolaan lingkungan dalam
dokumen ANDAL disajikan dan konsisten dengan hasil prakiraan dan evaluasi
dampak penting.
Review dokumen RKL, uraian pendekatan pengelolaan lingkungan cukup
jelas yang terdiri atas pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi budaya
dan pendekatan institusi. Dampak yang akan dikelola terdiri atas tiga komponen
yaitu: komponen fisik-kimia terdiri atas kualitas air laut (pemboran sumur
produksi), kualitas udara dan kebisingan, komponen biologi terdiri atas biota laut,
komponen sosial ekonomi budaya terdiri atas kesempatan kerja dan berusaha,
resiko kecelakaan laut dan persepsi masyarakat.
Upaya pengelolaan dampak berdasarkan komponen yakni komponen fisik-
kimia meliputi; mencegah kebocoran pada saluran lumpur bor, menampung
limbah lumpur dan serbuk pemboran pada suatu struktur penampung yang
dirancang khusus, memperkecil jumlah lumpur bor yang digunakan dalam seluruh
kegiatan pemboran, mencegah kebocoran pada saluran minyak dalam drill steam
test (DST), menampung minyak mentah hasil DST pada wadah dengan
struktur,bahan, ukuran, jumlah dan penempatan yang layak dan aman, seluruh
sistem pemompaan dilakukan dengan sistem tertutup, pada titik-tritik rawan
sepanjang saluran pemompaan akan disediakan bak penampung untuk
meminimkan kemungkinan pencemaran lingkungan di sekitarnya, minyak mentah
109
yang ditampung sementara dalam tangki terapung akan dipindahkan setiap sekitar
15 hari sekali ke dalam tanker pengangkut, sarana pemindahan akan dibuat
dengan bahan dan rancangan terbaik untuk mencegah terjadinya kebocoran dan
atau tumpahan minyak ke lingkungan sekitarnya, menaati standard operation
procedure (SOP) tentang K3 dalam proses transportasi, pada pembakaran gas di
flare, diusahakan dalam keadaan normal dan hanya pilotnya yang menyala,
pemasangan flare trap, memasang tanda peringatan tentang konsentrasi gas yang
tinggi di sekitar sumur Tiaka, mobiliasi alat dan bahan dilakukan pada siang hari,
memasang rambu pembatas kecepatan kendaraan (maksimal 40 km/jam),
mewajibkan setiap pengemudi mematuhi peraturan lalu lintas.
Komponen biologi meliputi; membuat karang buatan dan transplantasi
karang. Komponen sosial ekonomi budaya meliputi; meningkatkan kualitas SDM
secara periodik melalui pendidikan dan pelatihan, mengadakan pelatihan bagi
masyarakat berupa kegiatan diversifikasi usaha selain usaha nelayan, membuat
dan menempatkan rambu-rambu lalulintas pelayaran, dan peta jalur keselamatan,
mobilisasi alat dan bahan dilakukan pada siang hari, identifikasi dan evaluasi
potensi resiko kecelakaan laut, mengadakan sarana dan prasarana untuk
penanganan kecelakaan laut, membuat organisasi keselamatan kerja, sosialisasi
prosedur dan instruksi kesiagaan dan tanggap darurat, pelatihan keselamatan
kerja, sosialisasi dan konsultasi publik, melakukan seleksi penerimaan secara
transparan dengan kriteria penerimaan yang jelas, memberikan prioritas
penerimaan kerja kepada tenaga kerja lokal, menerapkan standar upah sesuai
dengan upah minimum kabupaten, memberikan jaminan asuransi tenaga kerja,
meliputi asuransi jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian dan kesehatan,
melakukan prosedur kegiatan mobilisasi alat dan bahan dengan benar,
menginformasikan jadwal kegiatan mobilisasi alat dan bahan kepada masyarakat.
Dokumen RPL, dampak penting yang dipantau sama dengan dampak
penting yang dikelolah. Komponen lingkungan yang dipantau meliputi:
Komponen fisik-kimia terdiri atas kualitas air laut (pemboran sumur produksi),
kualitas udara dan kebisingan. Komponen biologi terdiri atas biota laut.
Komponen sosial ekonomi budaya terdiri atas kesempatan kerja dan berusaha,
resiko kecelakaan laut dan persepsi masyarakat.
110
Metode rencana pemantauan berdasarkan komponen yang dipantau, yaitu:
komponen fisik-kimia menggunakan metode pengambilan contoh: air, lumpur,
sludge, pengukuran, analisis laboratorium, pengukuran lapang dan sound level
meter. Komponen biologi menggunakan pengamatan lapang terhadap
pertumbuhan karang (tingkat kepadatan/penutupan karang pada karang buatan).
Komponen sosial ekonomi budaya menggunakan metode survei, wawancara, data
sekunder perusahaan tentang rekruitmen tenaga kerja dan pengamatan lapang
(observasi).
6. BP Tangguh Sorong
Tim penyusun KA-ANDAL dan ANDAL, RKL, RPL adalah PT. Intersys
Kelola Maju, Continental Shelf Associates Inc, Research Institute of
Cenderawasih University, PT.Geotek Minergi. Bidang keahlian tim penyusun
AMDAL masih belum lengkap karena tidak ada anggota tim yang memiliki
keahlian perminyakan. Dokumen KA-ANDAL disahkan pada tahun 2001
sedangkan dokumen ANDAL, RKL dan RPL disahkan pada tahun 2002.
Diperlukan waktu satu tahun dari kerangka acuan ke penyusunan dokumen
ANDAL, RKL dan RPL.
Isu pokok dalam dokumen KA-ANDAL yang muncul dari identifikasi;
dampak sosial ekonomi, pemukiman kembali penduduk Desa Tanah Merah,
hilangnya hak ulayat masyarakat lokal atas tanah dan daerah perairan dekat
pantai, gangguan terhadap lahan, hilangnya kayu, dan hilangnya habitat satwa liar
karena pembukaan lahan, dampak terhadap daerah hutan mangrove dari perpipaan
dan fasilitas dermaga khusus, dampak terhadap kualitas air akibat pembuangan air
terproduksi (produced water), air limbah domestik, dan air buangan lainnya, dan
dari sedimen selama konstruksi dan saat pengerukan di dekat pantai dan juga
lepas pantai, dampak terhadap perikanan lepas pantai dan dekat pantai serta jalur
penangkapan ikan (right of way), limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri
dan kegiatan masyarakat, dampak kualitas udara selama konstruksi dan operasi
dari sumber bergerak dan tidak bergerak, dan dari debu halus lepasan (fugitive
dust), dampak kebisingan dan penyinaran (lampu), dampak dari keterbatasan
akses untuk daerah penangkapan ikan dekat pantai, daerah pertanian dan
perburuan tradisional, dan penggunaan lahan yang lain.
111
Deskripsi rencana kegiatan meliputi kegiatan pada tahap prakonstruksi,
konstruksi, operasi dan pasca operasi, pada bagian ini cukup jelas diuraikan secara
rinci. Namun penentuan batas wilayah studi keliru, karena batas administrasi
dianggap sebagai batas wilayah studi yang seharusnya batas wilayah studi
merupakan keseluruhan dari batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas
administrasi.
Metode pengumpulan data cukup jelas, namun untuk metode analisis data
untuk komponen sosial kurang jelas lebih banyak menggunakan metode
kuantitatif. Dalam metode pengambilan sampel, komponen lingkungan fisik
kimiawi dan biologi diukur dengan mengacu pada buku panduan penyusunan
AMDAL Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan oleh Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan tahun 1996. Untuk komponen fisika:
batimetri, debit sungai, arah dan kecepatan angin, pasang surut, gelombang, arus,
suhu, sedimentasi/erosi, tekstur sedimen, komponen kimiawi: salinitas,, kimia
sedimen, DO, pH, BOD5, phenol, minyak dan lemak, nutrien, logam berat, muatan
parameter tersuspensi, komponen biologi: plankton, benthos, nekton. Dalam
uraian metode studi parameter yang diukur pada komponen fisik-kimia dan
biologi, sosial, demografi, ekonomi dan kesehatan masyarakat cukup jelas.
Review terhadap kualitas dokumen ANDAL meliputi: rencana kegiatan
yang menimbulkan dampak penting yaitu; 1) tahap pra konstruksi, perijinan-
perijinan, 2) tahap konstruksi; pengeboran dan pemasangan anjungan lepas pantai,
pemasangan transmisi gas (jalur pipa lepas pantai), pembangunan kilang LNG dan
fasilitas penunjang, pembangunan pelabuhan khusus (dermaga/jeti), pembangunan
bandar udara khusus, 3) tahap operasi; eksploitasi/produksi gas, pemboran sumur-
sumur produksi, transmisi gas, pengoperasian kilang LNG, pengeoperasian
pelabuhan khusus, dan pengapalan, pengoperasian bandar udara khusus, 4) tahap
pasca operasi; penutupan lapangan apabila kegiatan telah berakhir antara lain
penutupan sumur-sumur produksi gas, pembongkaran anjungan lepas pantai,
penutupan kilang LNG dan pembongkaran fasilitas utama dan fasilitas penunjang,
5) metode prakiraan dampak besar dan penting serta evaluasi dampak penting
tidak disebutkan secara spesifik untuk masing-masing komponen lingkungan
(biologi, geologi, fisika, kimia dan sosial ekonomi dan budaya).
112
Dalam prakiraan dampak penting pada aspek biologi, geologi, fisika,
kimia seperti; kualitas udara dan kebisingan, ekologi daratan, ekologi lepas pantai
dan pantai dinyatakan tidak penting, ternyata di dalam evaluasi dampak penting
dikategorikan dampak penting kecuali kebisingan pada tahap operasi adalah; 1)
tahap pra konstruksi terdiri atas pembukaan lahan, perataan dan pemadatan tanah
dan mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, 2) tahap konstruksi terdiri atas; a)
pengeboran sumur produksi (pembuangan lumpur bor dan serbuk bor), b) potensi
tumpahan bahan bakar kondensat, c) pengerukan, d) solid fill cause ways, e)
mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, e) penerimaan tenaga kerja dan peluang
ekonomi, f) penempatan pipa transmisi gas di lepas pantai, g) penerimaan tenaga
kerja, h) kontrol klan terhadap sumberdaya alam, i) konstruksi dermaga, j)
konstruksi kilang LPG, k) mobilisasi dan demobilisasi peralatan/material. 3)
tahap operasi terdiri atas; a) potensi tumpahan bahan bakar kondensat, b)
pembuangan air ballast, c) potensi tumpahan minyak/bahan bakar, d) operasi
penerbangan berjadwal, e) pemukiman liar dan peladangan berpindah, f) kawasan
tertutup untuk keselamatan, g) pemasaran LNG, h) operasi kapal tunda, i)
penerimaan tenaga kerja. 4) tahap pasca operasi meliputi penanganan lokasi dan
instalasi dan penanganan prasarana.
Hal ini terlihat tidak konsisten antara prakiraan dampak dan evaluasi
dampak. Metode yang dipakai dalam prakiraan dampak tidak jelas disebutkan.
Seharusnya di dalam memprakirakan dampak penting harus ada matrik
identifikasi dampak penting untuk melihat dampak primer, sekunder, tersier dan
seterusnya. Dalam menentukan dampak penting negatif penting ataupun positif
penting. Dampak-dampak penting tersebut kemudian dilakukan evaluasi dampak
penting tersebut antara lain; apakah dampak penting tersebut bisa dikelola dengan
teknologi yang tersedia atau sebaliknya. Apakah dampak penting tersebut akan
berlangsung terus menerus sampai pasca operasi atau akan terus berlanjut ternyata
di dalam dokumen ini antara prakiraan dampak dan evaluasi dampak adalah sama.
Pada evaluasi dampak hanya mengulang yang sudah diuraikan dalam bab
prakiraan dampak. Di dalam evaluasi dampak ada dicantumkan matrik identifikasi
dampak, matrik prakiraan dampak yang seharusnya matrik-matrik tersebut
113
dilakukan pada prakiraan dampak. Di dalam dokumen ini tidak ada arahan
RKL/RPL.
Rencana kegiatan yang diprakirakan akan menimbulkan dampak
lingkungan pada dokumen ANDAL terdiri atas 12 kegiatan. Baik jumlah maupun
jenisnya, rencana kegiatan pada dokumen ANDAL tersebut sama dengan apa
yang dijelaskan pada dokumen KA-ANDAL. Sebanyak 904 dampak potensial
teridentifikasi dalam 6 matrik untuk masing-masing dari ke-6 kegiatan utama
proyek. Sebanyak 25 dampak potensial ditambahkan pada matrik berkenaan
dengan adanya sedikit revisi pada deskripsi proyek. Sub komponen fisik, kimia
dan biologi terdiri atas: kualitas udara dan kebisingan, ekologi daratan (tidak
termasuk kualitas udara dan kebisingan), ekologi lepas pantai dan dekat pantai
(tidak termasuk kualitas udara dan kebisingan).
Metode studi lebih lengkap atau ada perubahan (antara lain pada
komponen biologi, sosek-budaya. Dalam metode prakiraan dampak penting yang
dibahas hanya parameter: emisi udara, kebisingan, pembuangan lumpur dan
serbuk bor, lintasan tumpahan potensial diesel dan kondesat, pembuangan air
terproduksi (di lepas pantai), pembuangan material keruk, pembuangan air dari uji
hidrostatik perpipaan, pembuangan air limbah dari kilang LNG, erosi tanah.
Sedangkan, metode prakiraan dampak tidak disebutkan secara kuantitatif.
Deskripsi rencana kegiatan: lebih banyak, kuantitatif dan ilustratif
(didukung oleh gambar dan peta-peta). Demikian juga rona lingkungan hidup
disajikan dan dideskripsikan lebih lengkap dan didukung oleh hasil analisis data
primer (laboratorium).
Berdasarkan hasil review kualitas dokumen RKL menunjukkan bahwa
RKL/RPL tidak bersifat operasional, harusnya didalam RKL/RPL ada pendekatan
institusional, teknologi dan sosial. Untuk pengelolaan ekologi (biogeofisikkimia)
tidak disebutkan peralatan yang dipakai, dimensi, ukuran dan kapasitasnya serta
waktu kapan penglolaan dilaksanakan. Teknologi pengelolaan lingkungan masih
bersifat naratif seperti teknologi pengelolaan, periode pengelolaan.
Pengelolaan lingkungan masih bersifat alternatif-alternatif. Upaya
pengelolaan sosial terdiri atas mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan
nilai lahan di lokasi dan di desa-desa sekitarnya, mengganggu kegiatan perikanan,
114
mengurangi pendapatan keluarga dari perikanan, meningkatkan potensi terjadinya
konflik karena adanya daerah-daerah tempat terjadinya kegiatan penangkapan
ikan secara berlebihan, mempengaruhi sikap dan persepsi masyarakat terhadap
proyek, mengganggu ketertiban masyarakat di desa-desa sekitarnya, dan merubah
gaya hidup penduduk di Desa Tanah Merah. Semua upaya yang dilakukan seperti
ini namun tidak disebutkan cara pelaksanaannya/teknisnya, waktu/tahapan, lokasi
dan siapa yang melaksanakan. Pada tahap operasi, dampak sosial tidak ada
dampak penting terhadap lingkungan karena disebutkan pada saat penjualan LNG
akan menimbulkan dampak positif ekonomi lokal dan regional.
Hasil review kualitas dokumen RPL menunjukkan bahwa upaya
pemantauan tidak jelas pemantauan yang dipantau, teknik pemantauan, frekwensi
pemantauan, alat pemantauan, waktu pemantauan, cara pemantauan, parameter
yang dipantau. Beberapa pemantauan masih bersifat alternatif, salah satu contoh
untuk pemantauan dampak sosial memantau penurunan peredaran uang di pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi.
7. Hess Pangkah Gresik
Tim penyusun AMDAL pada kegiatan pengembangan lapangan minyak
dan gas Ujung Pangkah, Blok Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur terdapat
perbedaan penyusun KA-ANDAL yang disusun oleh LP UNAIR dan LP ITS 10
Nopember dan PPLH-LPM IPB yang menyusun ANDAL, RKL dan RPL. Bidang
keahlian tim penyusun AMDAL masih belum lengkap karena tidak ada anggota
tim yang memiliki keahlian ekonomi atau ekonomi sumberdaya atau ekonomi
lingkungan, padahal dalam metode studi dicantumkan akan menggunakan metode
valuasi ekonomi dalam studi ANDAL. Sebagian besar (58%) anggota tim
penyusun sudah memiliki sertifikat AMDAL. Sertifikat AMDAL A dimiliki oleh
3 orang anggota tim, AMDAL A dan B oleh 7 orang dan AMDAL A, B, dan C
oleh 1 orang. Anggota tim yang tidak memiliki sertifikat AMDAL ada 8 orang
(42%). Salah seorang anggota tim penyusun tidak dilengkapi dengan CV (daftar
riwayat hidup).
Dokumen KA-ANDAL disahkan pada tahun 2003 sementara Dokumen
ANDAL, RKL dan RPL-nya disahkan pada tahun 2006. Diperlukan waktu 3
tahun untuk menyusun Dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Penyebab hal tersebut
115
tidak ada penjelasannya di dalam dokumen, tetapi diduga karena adanya
perubahan tim penyusun dokumen dari LP UNAIR dan LP ITS 10 Nopember
(sebagai penyusun KA-ANDAL) menjadi PPLH-LPM IPB (penyusun ANDAL,
RKL, RPL).
Deskripsi rencana kegiatan meliputi kegiatan pada tahap prakonstruksi,
konstruksi, operasi dan pascaoperasi. Kelemahan yang ditemukan dalam bagian
ini adalah (1) deskripsi kegiatan sosialisasi rencana proyek pada bagian ruang
lingkup sangat minim (naratif kualitatif), sedangkan aspek yang sama dijelaskan
cukup panjang pada bagian pendahuluan dengan dibuatnya satu subbagian
kegiatan konsultasi masyarakat, dan (2) deskripsi kegiatan mobilisasi peralatan
pada tahap konstruksi kurang jelas (tidak ada kuantifikasi peralatan yang akan
digunakan). Kelebihan deskripsi kegiatan antara lain tim penyusun menyajikan
alternatif rencana kegiatan dalam hal jalur pipa.
Rencana kegiatan yang diprakirakan akan menimbulkan dampak
lingkungan tidak mudah disarikan pada bagian narasi. Jika dilihat pada matriks
identifikasi dampak potensial terdapat 11 kegiatan pada tahap prakonstruksi, 3
kegiatan utama pada tahap konstruksi, 8 kegiatan pada tahap operasi dan 2
kegiatan pada tahap pascaoperasi yang diprakirakan akan menimbulkan dampak
lingkungan. Tiga rencana kegiatan utama pada tahap konstruksi meliputi sekitar
14 sub-kegiatan. Pada matriks tersebut ditemukan minimal ada 4 (empat) rencana
kegiatan yang tidak diketahui dampaknya terhadap lingkungan hidup, yakni; 1)
pengurusan perijinan penentuan lokasi WHP, 2) pengurusan perijinan penentuan
lokasi pipa bawah laut, 3) pengurusan perijinan penentuan lokasi pipa di darat,
dan 4) pengurusan perijinan penentuan lokasi fasilitas pengolahan gas. Semua
rencana kegiatan tersebut ada pada tahap pra-konstruksi. Apabila rencana kegiatan
tersebut diprakirakan tidak mempunyai dampak lingkungan maka tidak perlu
dicantumkan pada matriks identifikasi tersebut.
Deskripsi rona lingkungan awal lengkap dan jelas serta cukup banyak yang
disajikan secara kuantitatif. Deskripsi rona lingkungan hidup yang diprakirakan
akan terkena dampak rencana kegiatan dijelaskan cukup baik dan meliputi
Komponen fisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, sanitasi lingkungan dan
kesehatan lingkungan masyarakat, Transportasi darat dan laut dan komponen
116
lingkungan lain (utilitas lain, suplai air bersih dan suplai gas). Secara keseluruhan
dari matriks identifikasi dampak potensial ada 35 buah komponen lingkungan
hidup (parameter) yang diprakirakan akan terkena dampak rencana kegiatan.
Namun demikian dampak potensial yang tertera pada bagan alir pelingkupan ada
34 buah mencakup komponen fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya,
kesehatan lingkungan masyarakat, transportasi dan lingkungan lainnya. Ada
ketidakkonsistenan antara matriks dan bagan alir terkait dengan parameter tata
guna Lahan yang ada pada matriks tetapi tidak ditemukan pada bagan alir.
Dampak penting hipotetik sebagai hasil evaluasi dampak potensial ada 31
buah. Ada tiga buah dampak potensial yang dievaluasi tidak menjadi dampak
penting hipotetik, yakni; 1) arus dan gelombang, 2) transport sedimen dan 3) flora
darat. Isu pokok yang dirumuskan dalam dokumen KA-ANDAL masih dibatasi
oleh komponen lingkungan, misalnya pada komponen fisik-kimia ada tujuh buah
isu pokok, komponen sosial ekonomi dan budaya ada dua isu pokok dan
seterusnya sehingga isu pokok ada 15 buah. Hal itu tidak lazim.
Uraian batas wilayah studi cukup jelas dan didukung oleh peta-peta yang
berskala (namun terlalu kasar atau skala peta kecil, sekitar 1:400.000) dan
berwarna. Pada uraian metode studi parameter yang diukur pada komponen fisik-
kimia dan biologi cukup jelas, tetapi pada komponen sosek-budaya kurang jelas,
misalnya tidak dijelaskan apa yang akan diukur untuk menjelaskan parameter
kamtibmas. Pada dokumen AMDAL sektor lain kamtibmas (keamanan dan
ketertiban masyarakat) merupakan komponen lingkungan hidup yang terpisah,
bukan merupakan parameter.
Metode pengumpulan dan analisis data cukup jelas, tetapi kuesioner untuk
aspek sosek-budaya tidak dilampirkan. Metode prakiraan dampak pentingnya
cukup jelas, bahkan disajikan juga penggunaan metode valuasi ekonomi untuk
menganalisis besar dan pentingnya dampak, sedangkan metode evaluasi dampak
pentingnya kurang jelas, dinyatakan menggunakan pertimbangan pakar.
Dalam dokumen ANDAL, rencana kegiatan yang diprakirakan akan
menimbulkan dampak lingkungan pada dokumen ANDAL terdiri atas 11
kegiatan, baik jumlah maupun jenisnya. Rencana kegiatan pada dokumen
ANDAL tersebut sangat berbeda dengan apa yang dijelaskan pada dokumen KA-
117
ANDAL. Jenis rencana kegiatan yang diprakirakan akan menimbulkan dampak
lingkungan tersebut adalah perijinan, sosialisasi, mobilisasi/demobilisasi,
pemboran, pemasangan anjungan dan pipa, produksi minyak dan gas, penjualan
minyak dan gas, pemeliharaan fasilitas, pembongkaran fasilitas dan penutupan
sumur.
Komponen lingkungan hidup yang diprakirakan akan terkena dampak
terdiri atas 16 buah (parameter), jumlah dan jenis komponen lingkungan hidup
yang diprakirakan akan terkena dampak tersebut berbeda dengan (lebih sedikit
daripada) isi dokumen KA-ANDAL. Rumusan isu pokok pada dokumen ANDAL
terdiri atas 7 isu rumusan isu pokok tersebut lebih sederhana daripada isi dokumen
KA-ANDAL yang memuat 15 buah isu pokok dengan demikian isu pokok KA-
ANDAL dan ANDAL sangat berbeda.
Metode studi lebih lengkap atau ada perubahan (antara lain pada
komponen biologi, sosek-budaya). Namun demikian dalam hal metode prakiraan
dampak penting tidak mencantumkan lagi metode valuasi ekonomi, padahal dari
segi bidang keahlian tim studi memungkinkan untuk menggunakan metode
tersebut.
Deskripsi rencana kegiatan: lebih banyak, kuantitatif dan ilustratif
(didukung oleh gambar dan peta-peta). Demikian juga rona lingkungan hidup
disajikan dan dideskripsikan lebih lengkap dan didukung oleh hasil analisis data
primer (laboratorium). Dampak penting hipotetik yang dikaji pada dokumen
ANDAL ada 12 buah. Jumlah dampak penting hipotetik di atas berbeda dengan
apa yang diuraikan dalam dokumen KA-ANDAL (31 buah). Hasil prakiraan
dampak penting tersebut adalah 10 dampak penting yang terdiri atas 2 buah
dampak penting positif dan 9 buah dampak penting negatif.
Hal yang cukup menarik untuk dikritisi adalah semua rencana kegiatan
pada tahap prakonstruksi dan pascaoperasi dinilai (diprakirakan) tidak akan
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan (agak tidak logis!). Hal
tersebut antara lain dapat disebabkan karena rencana kegiatan perijinan dan
sosialisasi proyek (pada tahap prakonstruksi) hanya dianalisis dampaknya
terhadap keresahan dan persepsi masyarakat (nelayan dan petambak), sedangkan
dampaknya (khususnya proses perijinan) terhadap PAD tidak dianalisis.
118
Kemudian prakiraan dampak penting pada tahap pascaoperasi, yakni rencana
kegiatan pembongkatan fasilitas, penutupan sumur hanya dianalisis terhadap
aktivitas nelayan dan petambak, pendapatan masyarakat, persepsi dan keresahan
masyarakat (nelayan dan petambak), dan lalu-lintas laut, sedangkan terhadap
karyawan dan (hilangnya) kesempatan kerja dan berusaha tidak dilakukan.
Dokumen ANDAL telah dilengkapi dengan matriks prakiraan dampak
penting yang cukup jelas. Demikian juga matriks dan bagan alir evaluasi dampak
penting ada dan jelas. Jumlah dan jenis dampak penting yang dievaluasi konsisten
dengan hasil prakiraan dampak penting. Justifikasi kelayakan lingkungannya
bersifat kualitatif-naratif. Rumusan kalimat utama yang digunakan yakni: segala
dampak negatif yang akan timbul pada dasarnya dapat diatasi dengan biaya yang
lebih rendah daripada manfaat yang akan diperoleh. Padahal tidak ada kajian
berapa besar biaya pengelolaan dampak-dampak tersebut dan berapa besar
manfaat rencana kegiatannya.
Arahan pengelolaan lingkungan dalam dokumen ANDAL disajikan dan
konsisten dengan hasil prakiraan dan evaluasi dampak penting. Arahan tersebut,
masing-masing untuk rencana kegiatan pada tahap konstruksi dan operasi yang
menjadi sumber dampak penting terhadap lingkungan.
Dokumen RKL dilengkapi dengan surat pernyataan pihak pemrakarsa
dengan materai yang cukup sehingga memenuhi aspek legal. Uraian pendekatan
pengelolaan dampak lingkungan cukup jelas, terdiri atas pendekatan teknologi,
sosial-ekonomi-budaya dan institusi. Dampak penting yang dikelola mencakup 10
dampak penting dan sesuai dengan hasil prakiraan dampak penting. Dokumen
RKL dilengkapi pula dengan peta lokasi pengelolaan dampak disajikan per jenis
dampak yang dikelola (udara dan kesehatan masyarakat, kualitas air laut, biota
laut, sosek-budaya) dilengkapi dengan legenda dan skala (sekitar 1:400.000 atau
cukup kecil/kasar) dan matriks RKL yang sesuai dengan penjelasan narasinya.
103
Tabel 14 Analisis kualitas dokumen AMDAL migas
Indikator PT.CPI Duri (PP 29/1986)
Pertamina UP III Plaju
(PP 29/1986)
PT.Lapindo Brantas Sidoarjo
(PP 51/1993)
Pertamina-Suryaraya Teladan Pendopo
(PP 51/1993)
Exspan Toili Sulawesi (PP 27/1999)
BP Tangguh Sorong
(PP 27/1999)
Hess Pangkah Gresik
(PP 27/1999)
Kelengkapan Dokumen Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap
Penyusun AMDAL
Tim penyusun tidak lengkap, ahli geologi dan ahli perminyakan tidak tersedia PPLH UNRI dan PT Bumi Prasidi Tidak ada CV penyusun
Bidang keahlian tim penyusun tidak sesuai dengan dampak penting yang akan dianalisis (tidak lengkap) yaitu ahli perminyakan tidak tersedia PT.Unisystem Utama (Ltd) Pengalaman Ketua tim 14 tahun
Tim penyusun tidak lengkap, ahli perminyakan tidak tersedia PT. CORELAB INDONESIA Pengalaman Ketua Tim 3 tahun
Tim penyusun tidak lengkap, ahli geologi tidak tersedia Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM Pengalaman Ketua Tim 3 tahun
Tersedia semua ahli sesuai dengan kebutuhan penyusunan dokumen PPLH IPB Pengalaman ketua tim 11 tahun
Tim penyusun tidak lengkap, ahli perminyakan tidak tersedia PT.INTERSYS Kelola Maju Pengalaman Ketua Tim 13 tahun
Tersedia semua ahli sesuai dengan kebutuhan penyusunan dokumen PPLH IPB Pengalaman ketua tim 10 tahun
Substansi Dokumen 1. KA-ANDAL a. Pendahuluan b. Ruang Lingkup Studi c. Metode Studi d. Pelaksana Studi
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
104
Indikator PT.CPI Duri (PP 29/1986)
Pertamina UP III Plaju
(PP 29/1986)
PT.Lapindo Brantas Sidoarjo
(PP 51/1993)
Pertamina-Suryaraya Teladan Pendopo
(PP 51/1993)
Exspan Toili Sulawesi (PP 27/1999)
BP Tangguh Sorong
(PP 27/1999)
Hess Pangkah Gresik
(PP 27/1999)
2. ANDAL meliputi: a. uraian kegiatan b. rona lingkungan awal c. Metode Studi d. prakiraan dampak
penting e. evaluasi dampak
penting f. diagram alir dampak
penting g. matrik identifikasi
dampak h. matrik prakiraan
dampak i. arahan RKL dan RPL j. daftar pustaka k. lampiran
Lengkap
Lengkap Tidak ada arahan RKL dan RPL yang ada hanya tindak lanjut
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap, Tidak ada arahan RKL dan RPL
Lengkap
RKL mencakup: a. Ringkasan evaluasi
dampak penting b. Pendekatan
pengelolaan lingkungan: teknologi, institusi/kelembagaan, social ekonomi
c. Rencana pengelolaan lingkungan,
d. matrik pengelolaan
Tidak ada ringkasan (tidak dipersyaratkan dalam Kepmen PE No.0185/1988 dan 1158/1989
Tidak ada ringkasan (tidak dipersyaratkan dalam Kepmen PE No.0185/1988 dan 1158/1989 Tidak ada pendekatan sosial
Lengkap
Lengkap
Tidak ada ringkasan
Tidak ada pendekatan sosial ekonomi RKL tidak bersifat operasional, teknologi masih bersifat alternatif
Tidak ada ringkasan
Lanjutan Tabel 14
105
Indikator PT.CPI Duri (PP 29/1986)
Pertamina UP III Plaju
(PP 29/1986)
PT.Lapindo Brantas Sidoarjo
(PP 51/1993)
Pertamina-Suryaraya Teladan Pendopo
(PP 51/1993)
Exspan Toili Sulawesi (PP 27/1999)
BP Tangguh Sorong
(PP 27/1999)
Hess Pangkah Gresik
(PP 27/1999)
lingkungan dan peta lokasi
e. institusi dan pelaksana pengelolaan lingkungan
Program RKL tidak membahas masalah sosial budaya dan sosial ekonomi
RPL mencakup: a. Identitas proyek dan
ringkasan ANDAL, b. rencana pemantauan, c. pelaksanaan
pemantauan lingkungan,
d. matrik pemantuan e. peta pemantuan
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Tidak ada bab identitas proyek dan ringkasan ANDAL
Lengkap
Waktu Penyusunan a. KA-ANDAL/KA-SEL b. ANDAL/SEL c. RKL/RPL
1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun 3 tahun
1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun
1 tahun 1,5 tahun
1 tahun 1 tahun
1 tahun 3 tahun
Lanjutan Tabel 14
106
Berdasarkan hasil penilaian diperoleh bahwa secara umum kualitas
dokumen AMDAL kurang. Hal ini tampak pada empat indikator yang digunakan
dalam penilaian yakni; kelengkapan dokumen, tim dan lembaga penyusun,
substansi dokumen dan waktu penyusunan. Meskipun keempat indikator tersebut
terpenuhi, namun ada beberapa hal esensial yang belum dipenuhi dari ketentuan
yang telah ditetapkan, seperti tidak tercantumnya biodata penyusun, tidak adanya
ahli perminyakan dan geologi dalam tim penyusun, minimnya pengalaman tim
penyusun, rendahnya kualifikasi tim penyusun khususnya anggota tim, serta
adanya dokumen yang tidak memberikan arahan dan minimnya kajian sosial
ekonomi serta waktu penyusunan yang relatif lama yakni berkisar antara satu
hingga tiga tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas dokumen
AMDAL dipengaruhi oleh masih terdapatnya beberapa kelemahan-kelemahan
mendasar dalam kebijakan AMDAL migas.
5.3 Kinerja Lingkungan Implementasi AMDAL Kegiatan Migas
Kegiatan usaha migas antara lain pemboran sumur, pengembangan
lapangan, pembangunan fasilitas produksi/transmisi dan pengoperasiannya,
perawatan sumur dan eksploitasi migas serta pengolahan minyak dan gas yang
merupakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Evaluasi kinerja lingkungan untuk kegiatan usaha migas dilakukan dengan
mengevaluasi volume tumpuhan minyak yang terjadi, kualitas limbah cair,
kualitas udara dan kebisingan serta perkembangan produk domestik regional bruto
(PDRB), perkembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat di daerah operasi
kegiatan usaha migas.
Mengingat hal di atas, maka perlu dilakukan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan seperti yang dirumuskan dalam dokumen rencana pengelolaan
lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL). Pemantauan
dilakukan terhadap tumpuhan minyak, kualitas limbah cair meliputi: kandungan
minyak dan lemak, konsentrasi H2S, konsentrasi COD, dan kandungan amoniak
bebas dalam air. Parameter kualitas udara dan kebisingan meliputi: kandungan
SO2, kandungan H2S, kandungan NOx, dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan
dari aktivitas migas tersebut.
107
5.3.1 Tumpahan Minyak
Pelaksanaan kegiatan usaha migas, pada hakekatnya merupakan kegiatan
yang memiliki standar operasional prosedur (SOP), dimana setiap rangkaian
kegiatan memiliki prosedur yang baku, mulai tahap persiapan hingga pasca
operasi, begitu juga kondisi emergency. Pelaksanaan kegiatan migas terdiri dari
empat tahapan baik di darat maupun di laut yakni: 1) tahap pra konstruksi, 2)
tahap konstruksi, 3) tahap operasi dan 4) tahap pasca operasi. Pada beberapa
tahapan kegiatan, berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti
dari limbah hasil proses produksi yang dihasilkan maupun dari kejadian
emergency. Bahan-bahan yang menjadi limbah dari sisa hasil produksi dan
emergency tersebut dapat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan hidup
dan sumberdaya alam.
Pada tahap operasi potensi tumpahan minyak dapat terjadi melalui
kebocoran pipa dan semburan liar sewaktu pengeboran sumur produksi.
Sedangkan pada tahap pasca operasi, tumpuhan minyak dapat terjadi sewaktu
pengapalan dan pengangkutan. Tumpahan minyak tersebut dapat berdampak
secara langsung terhadap ekosistem dan lingkungan hidup serta manusia yang ada
disekitarnya. Besaran dampak akibat tumpahan minyak sangat ditentukan oleh
volume dan frekuensi tumpahan yang terjadi.
Tabel 15 Frekuensi dan jumlah tumpuhan minyak pada KKKS
2003 2004 2005 2006 2007 KKKS frek barel frek barel frek barel frek barel frek barel
BP Indonesia - - - - 1 47.0 1 3.5 - -
Caltex Pacific Indonesia
6 274.0 6 470.0 5 189.0 - - - -
Conoco Phillips 9 364.0 - - 2 52.5 - - 2 200.0
Exxon Mobil Oil Indonesia
- - - - 1 55.0 - - - -
Unocal Indonesia 20 554.1 - - - - 1 13.5 - -
Total EP Indonesia - - - - - - - - - -
CNOOC SES - - 2 195.0 1 183.3 1 6.6 1 31.7
Petro China - - - - - - - - 2 177.0
Medco EP Indonesia - - 1 250.0 5 130.0 - - 3 118.0
Kondur Petroleum - - 1 20.0 1 15.0 - - 1 6.9
Pearl Oil (Tungkal) Ltd - - - - 1 89.4 - - - -
PT Pertamina EP - - - - 2 25.0 2 111.0 5 452.0
Total 35 1192.1 10 935.0 19 786.2 19 786.2 19 786.2
Sumber: Ditjen Migas, 2007
108
Pada tahun 2003, tumpahan minyak terjadi sebanyak 35 kali dengan
volume 1.192,1 barrel. Tumpahan tertinggi terjadi pada KKKS Unocal Indonesia
yakni sebanyak 20 kali dengan volume sekitar 554,1 barrel. Sementara pada tahun
2004, tumpahan minyak terjadi sebanyak 10 kali dengan volume 935,0 barrel.
Tumpahan tertinggi terjadi pada KKKS Caltex Pacific Indonesia yakni sebanyak 6
kali dengan volume sekitar 470,0 barrel. Tumpahan minyak pada tahun 2005,
terjadi sebanyak 19 kali dengan volume 786,2 barrel, dengan tumpahan tertinggi
terjadi pada KKKS Caltex Pacific Indonesia yakni sebanyak 5 kali dengan volume
189,0 barrel.
Tabel 16 Tumpahan minyak (barel) periode 2000-2007 Tahun Hilir Hulu 2000 4.007,6 17.570,0 2001 - 11.522,0 2002 - 6.467,0 2003 - 1.192,1 2004 5.000,0 9.801,6 2005 - 770,9 2006 - 1.188,6 2007 452,0 144,9
Sumber: Ditjen Migas, 2007
Potensi tumpahan minyak juga dapat terjadi pada operasi hilir atau
pemasaran/niaga, baik dari transportasi melalui pipa maupun kapal.
Sesungguhnya tumpuhan minyak yang terjadi, umumnya merupakan kejadian
emergency, yang terjadi karena kebocoran atau pecahnya tanker. Tumpahan
minyak dapat menimbulkan dampak pencemaran bahkan kerusakan lingkungan
hidup bila tidak ditanggulangi dengan segera, karena lapisan minyak yang
menutupi permukaan air dapat menyebabkan kurangnya cahaya yang masuk
kedalam perairan, sehingga fotosintensis tidak terjadi dan berdampak terhadap
matinya berbagai biota perairan, termasuk matinya terumbu karang. Jika
tumpuhan minyak menutupi akar mangrove serta tumbuhan hijau di daratan.
Tumpahan minyak tersebut menutupi akar nafas dari mangrove, sehingga
mangrove mengalami kekurangan oksigen dan akhirnya mengalami kematian
(Dahuri et al., 1996).
109
Tumpahan minyak merupakan keadaan darurat (emergency) yang selama
ini tidak dikaji di dalam AMDAL, padahal hal tersebut dapat menimbulkan
pencemaran dan bahkan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup
menurut UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah
masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen
lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun
sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat
berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Definisi tersebut sangat sulit dijabarkan,
sehingga perlu dirumuskan definisi pencemaran lingkungan hidup yang lebih
operasional. Hasil penelitian diperoleh bahwa pencemaran lingkungan hidup
adalah turunnya kualitas lingkungan hidup dan atau ekosistem yang disebabkan
oleh aktivitas manusia, sehingga tidak berfungsi lagi sesuai peruntukkannya pada
waktu dan wilayah tertentu. Sedangkan perusakan lingkungan hidup menurut UU
No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah tindakan yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik
dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi
dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Pada hakekatnya, kerusakan
lingkungan hidup adalah terjadinya perubahan ekosistem (fisik, kimia, hayati
termasuk sosial ekonomi dan budaya) yang disebabkan oleh aktivitas manusia
Gambar 6 Volume tumpahan minyak pada kegiatan hulu dan hilir migas
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Barel
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Tahun
HULUHILIR
110
secara langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan terhambatnya
pembangunan yang berkelanjutan pada waktu tertentu.
Masih seringnya terjadi tumpuhan minyak (emergency) yang
menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga
membutuhkan penanganan keadaan darurat yang terencana. Menurut Suratmo
(2002), bahwa walaupun dampak emergency belum pasti terjadi (uncertain
negative impact), tapi harus dikaji di dalam AMDAL.
Selain dari tumpahan minyak dapat juga terjadi pencemaran dan kerusakan
lingkungan akibat semburan liar (blow out) dari sumur pemboran baik umur
eksploitasi maupun sumur produksi, semburan liar yang biasanya diikuti dengan
kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian waktu, biaya dan rusaknya
lingkungan. Semburan liar merupakan peristiwa mengalirnya fluida (minyak, gas
dan air) dari formasi kedalam sumur, lalu menyembur ke permukaan tanpa dapat
dikendalikan (Purnomo dan Tobing, 2007).
5.3.2 Kualitas Limbah Cair
Polusi air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan
dari kemurniannya. Air yang tersebar di alam tidak pernah terdapat dalam bentuk
murni, tapi bukan berarti semua air terpolusi. Sebagai contoh, meskipun di daerah
pegunungan atau hutan yang terpencil dengan udara yang bersih dan bebas dari
polusi, air hujan selalu mengandung bahan-bahan terlarut seperti CO2, O2 dan N2
serta bahan-bahan tersuspensi seperti debu dan partikel-partikel lainnya yang
terbawa dari atmosfer (PPLH UNSRI, 2003).
Salah satu hasil sampingan dari kegiatan industri migas adalah limbah cair
dengan kadar minyak yang tinggi, limbah cair ini dapat mencemari terhadap
perairan di sekitarnya, dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan
dampak negatif terhadap kualitas air apabila dibuang secara langsung tanpa diolah
terlebih dahulu. Untuk mengurangi kadar minyak yang tinggi tersebut maka
diperlukan suatu sistem pengolahan (Effendi, 2003).
Kualitas air digunakan baku mutu kualitas air limbah untuk kegiatan usaha
migas yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan menteri negara lingkungan
hidup No. 42 tahun 1996 tentang baku mutu limbah bagi usaha dan/atau kegiatan
111
minyak dan gas serta panas bumi. Parameter kualitas limbah cair yang dianalisis
yakni minyak dan lemak, COD, sulfida dan amoniak.
a. Minyak dan Lemak
Keberadaan minyak dan lemak dalam limbah cair atau dalam badan air
akan membentuk lapisan yang tipis disebut film minyak pada permukaan air
(massa jenis minyak/lemak lebih kecil dari massa jenis air). Lapisan tipis ini akan
menghambat kelarutan udara terutama oksigen ke dalam badan air padahal
kelarutan oksigen dalam air dibutuhkan oleh biota perairan. Selain itu keberadaan
lapisan minyak dalam badan air akan menghambat masuknya cahaya matahari ke
dalam air, sehingga proses fotosintesis dalam badan air akan terhambat. Proses
fotosintesis sangat berguna untuk meningkatkan kandungan oksigen yang terlarut
dalam badan air. Kadar maksimum minyak dan lemak dalam limbah cair adalah
35 mg/l.
Kandungan minyak dan lemak dalam perairan dapat berasal dari berbagai
sumber, antara lain: pembersihan dan pencucian kapal tangker (water blase),
pengeboran minyak di dekat perairan, kebocoran kapal pengangkut minyak serta
sumber-sumber lainnya seperti buangan pabrik. Hal tersebut, disebabkan karena
minyak tidak larut dalam air, sehingga apabila terjadi tumpahan minyak di
perairan maka, minyak akan mengapung dan dalam beberapa hari akan
mengalami penguapan dan mengalami emulsifikasi yang akhirnya air dan minyak
dapat bercampur.
Gambar 7 Kandungan minyak lemak di enam lokasi kegiatan usaha migas
- 5 10 15 20 25 30 35 40
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
mg/L
CPI Duri Pertamina PlajuSuryaraya Teladan Lapindo BrantasExpan Toili BP Tangguh Baku Mutu Lingkungan
112
Hasil pemantauan yang dilakukan pada enam perusahaan migas, pada
masing-masing lokasi masih memiliki kandungan minyak dan lemak di bawah
baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Kondisi tersebut dimungkinkan karena
pada umumnya perusahaan migas dalam melakukan operasi telah menerapkan dan
menggunakan teknologi tinggi, dengan kemungkinan kebocoran minyak yang
sangat kecil. Disisi lain, apabila terjadi kebocoran minyak, kesiapan penanganan
keadaan darurat (emergency response plan) dan treatment merupakan prosedur
utama, sehingga kemungkinan untuk menjumpai luberan minyak ataupun
kandungan minyak lemak di atas ambang batas sangat jarang. Kadar minyak dan
petroleum yang diperkenankan terdapat pada air minum berkisar antara 0,01-0,1
mg/l. Kadar yang melebihi 0,3 mg/l bersifat toksik terhadap beberapa jenis ikan
air tawar (Effendi, 2003).
b. Hidrogen Sulfida
Senyawa hidrogen sulfida (H2S) merupakan senyawa yang terbentuk dari
penguraian anaerobik terhadap senyawa yang mengandung belerang. Senyawa ini
akan menimbulkan bau dan warna terhadap badan air dimana H2S ini bersifat
racun terhadap biota perairan. Baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH
No. 42 tahun 1996 untuk bahan pencemar adalah 1,0 mg/l.
Gambar 8 Kandungan H2S di enam lokasi kegiatan usaha migas
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
mg/L
Pertamina Plaju CPI Duri Suryaraya Teladan
Lapindo Brantas BP Tangguh Expan Toili
Buku Mutu Lingkungan
113
Hasil pemantauan yang dilakukan pada enam perusahaan migas,
ditemukan bahwa pada tahun 1993 di lokasi Pertamina UP III Plaju kandungan
H2S melebihi baku mutu lingkungan yang ditetapkan namun di tahun berikutnya
hingga tahun 2007 kadungan H2S di bawah baku mutu lingkungan yang
ditetapkan (0,5 mg/l). Sedangkan pada perusahaan PT.CPI Lapangan Duri,
kandungan H2S melebihi baku mutu lingkungan (1,0 mg/l) terjadi pada tahun
1994-1995 dan selanjutnya terjadi penurunan hingga tahun 2006. Gambar 8
menunjukkan bahwa perusahaan sangat peduli pada lingkungan. Hal tersebut
tergambarkan pada nilai H2S yang dari tahun ke tahun berada di bawah baku mutu
lingkungan untuk H2S (0,5 mg/l).
c. Kebutuhan Oksigen Kimiawi
Kebutuhan oksigen kimiawi/chemical oxygen demand (COD)
menunjukkan kandungan bahan organik dan anorganik yang dapat didegradasi
dan dinyatakan dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses
degradasinya. Makin tinggi nilai COD pada badan air (air permukaan) dan air
limbah maka kualitas air tersebut makin buruk. COD menggambarkan jumlah
total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi,
baik yang dapat didegradasi secara biologi (biodegradable) maupun yang sukar
didegradasi secara non biologi (non biodegradable) menjadi CO2 dan H2O
(Effendi, 2003).
0
50
100
150
200
250
300
350
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
mg/L
Pertamina Plaju CPI Duri Suryaraya Teladan Lapindo Brantas BP Tangguh Expan ToiliBaku Mutu Lingkungan
Gambar 9 Kandungan COD di enam lokasi kegiatan usaha migas
114
Hasil pemantauan diperoleh bahwa pada enam lokasi kegiatan usaha migas
ternyata tidak terdapat kandungan kebutuhan oksigen kimiawi (COD) yang
melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan (300 mg/l). Hal tersebut
dimungkinkan karena dalam kegiatan usaha migas telah diterapkan penggunaan
teknologi yang ramah lingkungan, serta telah dilakukan pengelolaan limbah.
Kesemua hal tersebut menjadi perhatian serius dari perusahaan yang beroperasi,
sehingga kemungkinan kandungan COD yang melebihi baku mutu lingkungan
tidak dan jarang terjadi.
d. Amoniak Bebas
Amoniak dalam air permukaan (badan air) dapat berasal dari hasil degradasi
baik secara aerobik maupun anaerobik, bahan yang mengandung unsur nitrogen
misalnya protein. Adanya amoniak dalam air permukaan dapat menimbulkan bau.
Batas maksimum amoniak yang diperbolehkan berdasarkan Kepmen LH No. 42
tahun 1996 adalah 10 mg/l.
Gambar 10 Kandungan amoniak di enam lokasi kegiatan usaha migas
Berdasarkan Gambar 10 menunjukkan bahwa kandungan amoniak di
Pertamina-Suryaraya Teladan pada awal operasi melebihi baku mutu amoniak
yang telah ditetapkan (10 mg/l) dan mengalami penurunan mulai dari tahun 2001
hingga tahun 2006. Hal ini terjadi karena meningkatnya penggunaan teknologi
0
2
4
6
8
10
12
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
mg/L
Pertamina Plaju CPI DuriSuryaraya Teladan Lapindo BrantasBP Tangguh Expan ToiliiBaku Mutu Lingkungan
115
yang digunakan untuk mengurangi kandungan amoniak. Sedangkan pada PT.CPI
Lapangan Duri dan Pertamina UP III Plaju, kandungan amoniaknya dari tahun
1993-2006 tidak melampaui baku mutu amoniak yang telah ditetapkan (10 mg/l).
Demikian pula kandungan amoniak di BP Tangguh, PT.Lapindo dan Expan Blok
Toili yang dipantau dari tahun 2001-2006 tidak melampaui batas baku mutu yang
telah ditetapkan (10 mg/l).
5.3.3 Kualitas Udara dan Kebisingan
Pencemaran udara didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya
zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia,
sehingga mutu udaara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang meyebabkan
udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Sedangkan yang dimaksud
dengan emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari
suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya kedalam udara ambien yang
mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar (PPLH
UNSRI, 2003).
Udara adalah media pencampur untuk limbah gas. Limbah gas atau asap
yang diproduksi dari sisa pembakaran dan kendaraan bermotor, gas buangan
keluar menempati ruang atmosfir yang selanjutnya bercampur dengan asap hasil
pembakaran dan udara. Secara alamiah udara mengandung unsur kimia seperti
O2, N2, NO2, CO2, H2 dan lain-lain. Penambahan gas kedalam udara melampaui
kandungan alami akibat kegiatan manusia khususnya dalam pembukaan lahan,
pertambangan dan kegiatan migas dapat menimbulkan polusi yang akan
menurunkan kualitas udara.
Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu
partikel dan gas. Partikel adalah butiran halus yang masih mungkin terlibat
dengan mata telanjang seperti uap air, debu, asap, kabut dan fume, namun yang
dikaji dalam penelitian ini hanya partikel debu. Sedangkan pencemaran berbentuk
gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman (untuk gas tertentu) atau akibat
langsung antara lain SO2, Nox, CO, CO2, hidrogen dan lain-lain.
116
a. Kandungan SO2
Sifat dari gas SO2 adalah gas yang tidak berwarna, namun memiliki bau
sangat tajam. Bahan-bahan yang mengandung belerang teroksidasi membentuk
sulfur dioksida. Sulfur dioksida dapat berubah menjadi asam belerang (asam
sulfat) di atmosfir dan di dalam jaringan tubuh manusia. Sulfur dioksida stabil
dalam beberapa hari, di udara teroksidasi menjadi SO3 yang akhirnya membentuk
aerosol asam higroskopik H2SO4 lalu akan terjadi hujan asam. Gas SO2 dapat
merusak tanaman, menyebabkan korosi pada permukaan logam dan merusak
bahan nilon dan lain-lain (PPLH-UNSRI, 2003).
Kandungan SO2 di udara diduga berasal dari bocoran gas alam pada SKG,
bocoran dari separator minyak pada stasiun pengumpul, sisa pembakaran pada
flare dan genset. Data hasil pemantauan untuk enam lokasi kegiatan usaha migas
menunjukkan bahwa nilai kandungan SO2 di lingkungan relatif sangat kecil, jauh
di bawah baku mutu (0,365 ppm) berdasarkan peraturan pemerintah No. 41 tahun
1999 tentang pengendalian pencemaran udara (baku mutu ambien nasional).
Gambar 11 Kandungan SO2 di enam lokasi kegiatan usaha migas
b. Kandungan H2S
Senyawa H2S dalam bentuk gas bersifat racun dan berbau busuk, H2S di
udara pada musim hujan akan larut dalam air yang merubah sifak fisik air
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900
1000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertamina Plaju CPI Duri Suryaraya Teladan Lapindo BrantasBP Tangguh ExpanToili Baku Mutu Lingkungan
117
menjadi hitam, dan dengan senyawa besi membentuk Fe2S. Kandungan H2S
dapat berasal dari sisa pembakaran pada flare atau pada genset dan sisa tumpahan
minyak mentah yang tercecer maupun pada oil catcher yang menguap akibat dari
penguapan oleh panas matahari.
Nilai kandungan dalam udara di lingkungan dari hasil pelaporan relatif
sangat kecil dan masih di bawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan.
Indikator ini diperkuat dengan tidak adanya keluhan dari pekerja dan masyarakat
desa sekitar mengenai gangguan pernafasan. Demikian juga tingkat korosif di
lokasi yang dipantau umumnya kurang terlihat.
Gambar 12 Kandungan H2S di enam lokasi kegiatan usaha migas
c. Kandungan NOx
Kandungan NOx terbentuk pada temperatur tinggi dan pada kondisi kaya
oksigen. Sumber pembentuk NOx dari kegiatan penambangan minyak dapat
berasal dari flare pada gas buangan di daerah pengeboran maupun pada stasiun
pengumpul dan dapat berasal dari aktivitas kendaraan operasional dari dan
menuju lokasi.
Dengan demikian, temperatur tinggi pada pembakaran gas sisa di flare,
kendaraan operasional, dari knalpot genset dapat mendorong terbentuknya
nitrogen monoksida. Jika pada saat pembentukan pada temperatur tinggi dan pada
0.0000
0.0050
0.0100
0.0150
0.0200
0.0250
0.0300
0.0350
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertamina Plaju CPI Duri Suryaraya Teladan Lapindo BrantasBP Tangguh Expan Toili Baku Mutu Lingkungan
118
kondisi oksigen berlebihan. Kehadiran NOx adalah sama seperti kandungan SO2.
Hasil pelaporan pemantauan di enam lokasi kegiatan usaha migas menunjukkan
bahwa tingkat kandungan NOx dalam udara di lingkungan relatif rendah masih di
bawah nilai baku mutu lingkungan. Oleh karena itu wajar, bila pengaruh terhadap
lingkungan pada saat ini belum terjadi seperti belum adanya gangguan
pertumbuhan vegetasi ataupun kesehatan pekerja.
Gambar 13 Kandungan NOx di enam lokasi kegiatan usaha migas
Hasil pemantuan kinerja lingkungan tampak bahwa kandungan NOx pada
enam lokasi pengamatan untuk enam lokasi kegiatan usaha minyak dan gas
diperoleh bahwa kandungan NOx terukur tidak melebihi baku mutu lingkungan
yang dipersyaratkan. Kandungan NOx dari masing-masing lokasi pengamatan
menunjukkan kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha migas telah
menjadi perhatian utama. Penggunaan teknologi pengelolaan limbah dan buangan
serta dampak yang dapat muncul telah menjadi salah satu prioritas utama dalam
kegiatan usaha migas.
d. Kebisingan
Pengukuran kualitas udara dan kebisingan dilakukan pada lokasi lapangan
minyak dan gas yang sudah beroperasi. Analisis terhadap data kualitas lingkungan
0.0000
50.0000
100.0000
150.0000
200.0000
250.0000
300.0000
350.0000
400.0000
450.0000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertamina Plaju CPI Duri Suryaraya Teladan Lapindo BrantasBP Tangguh Expan Toili Baku Mutu Lingkungan
119
yang diperoleh dari lapangan akan selalu didasarkan pada baku mutu lingkungan
(BML) yang telah ditetapkan. Penilaian untuk kebisingan digunakan baku mutu
bagi kawasan industri berdasarkan keputusan menteri LH No. 48 tahun 1996.
Hasil analisis kebisingan pada pemantauan periode 1993-2006 disajikan pada
Gambar 14.
Sumber bising pada lokasi pemantauan berasal dari kompresor gas pada
booster dan SKG, selain dari genset dan pompa. Pemantauan dilakukan hanya
untuk kawasan industri (pusat) dengan baku mutu bising (>70 dBA) berdasarkan
keputusan menteri LH No. 48 tahun 1996 untuk kawasan industri.
Berdasarkan Gambar 14 menunjukan bahwa tingkat kebisingan pada enam
lokasi kegiatan migas tidak ada yang melampaui baku mutu bising sebagaimana
yang telah ditetapkan pada Kepmen LH No. 48 tahun 1996. Hasil ini diperkuat
dengan tidak adanya keluhan dari pekerja dan masyarakat sekitar daerah industri.
Tingkat kebisingan merupakan hal yang perlu dicermati karena dapat diukur
secara langsung (didengar) oleh pekerja dan masyarakat di sekitarnya. Untuk
mereduksi kebisingan dapat dilakukan penanaman pohon-pohon seperti bambu
atau pohon-pohon tegakan tinggi di sekitar sumber kebisingan (pompa, genset
atau kompresor).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pertamina Plaju CPI Duri Suryaraya Teladan Lapindo BrantasBP Tangguh Expan Toili Baku Mutu Lingkungan
Gambar 14 Kebisingan di enam lokasi kegiatan usaha migas
120
5.3.4 Aspek Sosial Ekonomi
Aspek sosial ekonomi di dalam penyusunan dokumen AMDAL didasarkan
pada keputusan menteri No. 229 tahun 1996 tentang pedoman kajian aspek sosial
ekonomi. Di dalam keputusan menteri tersebut, salah satu parameter untuk
mengukur aspek sosial adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB).
Perkembangan PDRB merupakan salah satu kriteria penilaian keberhasilan
pembangunan daerah. Keadaan ekonomi makro regional suatu daerah dapat
dilihat dari perkembangan PDRB, baik dari besaran nilainya maupun perkapita.
Distribusi PDRB suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya sumbangan yang
diberikan oleh tiap-tiap sektor yang terbagi dalam beberapa sub sektor.
Indikator lain yang digunakan untuk mengukur aspek sosial ekonomi pada
enam kegiatan usaha migas adalah aspek pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek
tersebut merupakan aspek sosial masyarakat yang umumnya banyak digunakan
sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi sosial masyarakat. Aspek
pendidikan dapat diidentifikasi berdasarkan perkembangan jumlah gedung
sekolah maupun taraf pendidikan (lamanya sekolah), sedang aspek kesehatan
diidentifikasi berdasarkan perkembangan jumlah gedung kesehatan dan tingkat
kesehatan masyarakat.
Berdasarkan daerah operasi kegiatan migas yang dikaji pada enam lokasi
kegiatan usaha migas yakni PT.CPI Duri Kabupaten Bengkalis, Pertamina UP III
Plaju Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin, Pertamina-Suryaraya
Teladan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin, PT.Lapindo
Kabupaten Sidoarjo, Expan Toili Sulawesi Kabupaten Morowali dan BP Tangguh
Kabupaten Sorong.
121
Gambar 15 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan
Kabupaten Bengkalis (BPS Kabupaten Bengkalis, 1986-2005)
Berdasarkan Gambar 15 menunjukkan bahwa kontribusi sektor migas
sangat mempengaruhi perekonomian daerah Kabupaten Bengkalis. Kondisi ini
terjadi seiring berkembangnya sektor migas salah satunya sejak beroperasinya
PT.CPI Lapangan Duri di Kabupaten Bengkalis. Namun, peningkatan sektor
migas terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis tidak mempengaruhi perkembangan
jumlah gedung sekolah sebagai salah satu parameter dari sektor pendidikan
demikian halnya pada perkembangan jumlah fasilitas kesehatan. Hal ini
menggambarkan bahwa kontribusi sektor migas tidak dinikmati secara merata,
khususnya yang berkaitan dengan dimensi sosial masyarakat. Saat ini, sumbangsih
sektor migas lebih menjadi sumber APBD yang selanjutnya menjadi bagian dari
belanja dan penggunaan anggaran daerah dalam pembangunan. Rendahnya
korelasi antara sumbangan migas terhadap pertumbuhan pendidikan dan
kesehatan, lebih disebabkan oleh fokus dan penekanan pembangunan daerah
bersangkutan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sarana penerangan
(listrik) lebih menjadi fokus pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1986
19
87
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Gedung sekolah (unit)Fasilitas kesehatan (unit)PDRB tanpa Migas (Rp. X 10000)PDRB dengan Migas (Rp. X 10000)
122
Gambar 16 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan Kota Palembang (BPS Kota Palembang, 1986-2005)
Berdasarkan Gambar 16 menunjukkan bahwa dengan berkembangnya
sektor migas di Kota Palembang, perekonomian daerah (PDRB) meningkat secara
signifikan. Kondisi ini terjadi sejak beroperasinya Pertamina UP III Plaju pada
tahun 1993. Namun, peningkatan ini tidak diiringi oleh peningkatan jumlah
gedung sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan di Kota Palembang. Hal ini berarti
peningkatan kontribusi sektor migas tidak mempengaruhi sektor pendidikan dan
sektor kesehatan di Kota Palembang.
Kontribusi sektor migas terhadap PDRB Kota Palembang, menunjukkan
perkembangan yang signifikan. Kontribusi migas tampak pada tahun 2002,
mengalami peningkatan terus menerus hingga tahun 2005. Namun kondisi
tersebut belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap kondisi sosial
masyarakat seperti pertumbuhan taraf pendidikan yang ditandai dengan masih
minimnya gedung sekolah serta perkembangan jumlah tahunan yang rendah.
Demikian pula untuk sektor kesehatan dimana perkembangan jumlah gedung
kesehatan belum menunjukkan hubungan yang signifikan dengan sumbangan
sektor migas di Kota Palembang.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Gedung sekolah (unit)
Fasilitas kesehatan (unit)
PDRB tanpa Migas(Rp. x10000)
PDRB dengan Migas(Rp. x10000)
123
Gambar 17 Perkembangan PDRB, gedung dan fasilitas kesehatan Kabupaten Sidoarjo (BPS Kabupaten Sidoarjo, 1986-2005)
Berdasarkan Gambar 17 menunjukkan bahwa kontribusi sektor migas
tidak terlalu signifikan mempengaruhi perekonomian daerah Kabupaten Sidoarjo.
Kontribusi sektor migas baru dinikmati mulai pada tahun 2001 karena pada tahun
tersebut sektor migas mulai berkembang, salah satunya dengan beroperasinya
PT.Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo. Namun, kontribusi sektor migas tidak
mempengaruhi perkembangan jumlah gedung sekolah dan fasilitas kesehatan di
Kabupaten Sidoarjo.
Kontribusi sektor migas terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang
diukur dari sisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Sidoarjo tidak menunjukkan
hubungan yang signifikan. Kondisi tersebut, sangat dipengaruhi oleh kondisi
daerah secara umum yang didominasi oleh sektor industri. Hal ini, tampak pada
perkembangan PDRB tanpa migas sama dengan perkembangan PDRB dengan
migas. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi secara mikro di Kabupaten
Sidoarjo dalam kaitannya dengan sumbangan PDRB sektor migas masih sangat
rendah. Namun demikian, perkembangan ekonomi secara makro tetap
memberikan sumbangan yang besar. Kesempatan kerja dan peluang berusaha di
sektor migas tetap menjadi bagian dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Sidoarjo.
0
50
100
150
200
250
300
350
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Gedung sekolah (unit)
Fasilitas kesehatan (unit)
PDRB tanpa Migas(Rp. x100000)
PDRB dengan Migas(Rp. x100000)
124
Perkembangan aspek sosial ekonomi di Kabupaten Muara Enim diukur
dari perkembangan PDRB dengan migas, PDRB tanpa migas dan jumlah gedung
sekolah. Berdasarkan Gambar 18 menunjukkan bahwa sejak tahun 1995
perkembangan sektor migas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
perekonomian daerah, hal ini terlihat dari perkembangan PDRB dengan migas dan
PDRB tanpa migas. Namun, kontribusi sektor migas terhadap PDRB ternyata
tidak mempengaruhi perkembangan jumlah gedung sekolah dan fasilitas
kesehatan di Kabupaten Muara Enim.
Masih minimnya sumbangsih sektor migas terhadap pertumbuhan
ekonomi mikro dan kesejahteraan sosial masyarakat, lebih disebabkan oleh
konsep pemerataan pembangunan daerah yang masih sangat bergantung pada
pertumbuhan dan perkembangan jumlah APBD. Prioritas pembangunan lebih
dikedepankan pada infrastruktur jalan dan aksesibilitas informasi serta
pembiayaan pembangunan dan belanja daerah.
Gambar 18 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan Kabupaten Muara Enim (BPS Kabupaten Muara Enim, 1986-2005)
Kondisi di Kabupaten Muara Enim tidak jauh berbeda dengan yang terjadi
di Kabupaten Musi Banyuasin. Kontribusi sektor migas sangat mempengaruhi
perekonomian daerah, terlihat dari perbedaan nilai PDRB tanpa migas dan PDRB
dengan migas yang tinggi mulai tahun 1995. Namun, disisi lain perkembangan
0
200
400
600
800
1000
1200
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Gedung sekolah (unit)
Fasilitas kesehatan (unit)
PDRB tanpa Migas(Rp. x10000)
PDRB dengan Migas(Rp. x10000)
125
jumlah gedung sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan sangat jauh berbeda dengan
perkembangan PDRB dengan migas. Jumlah gedung sekolah dan fasilitas
kesehatan berdasarkan Gambar 19 tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan
atau dianggap tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun.
Gambar 19 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 1986-2005)
Sumbangan sektor migas terhadap PDRB menunjukkan nilai yang
signifikan terutama pada dua tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa
sektor migas di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi tulang punggung
pembangunan daerah. Namun demikian sumbangan sektor yang besar tersebut,
belum memberikan sumbangan yang nyata terhadap aspek kesejahteraan sosial
masyarakat seperti taraf pendidikan dan tingkat kesehatan. Kedua aspek tersebut
diukur dari sisi perkembangan jumlah fasilitas gedung sekolah dan gedung
kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh kedua aspek tersebut belum
mengalami perkembangan yang berarti. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh
pemerataan pembangunan dan prioritas pembiayaan pembangunan. Kedua faktor
tersebut menjadi jawaban terhadap belum signifikannya sumbangan migas
terhadap aspek kesejahteraan sosial.
Perkembangan PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas Kabupaten
Morowali, menunjukkan perbedaan yang sangat kecil. Kontribusi sektor migas
0 200 400
600 800
1000 1200
1400 1600 1800
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Gedung sekolah (unit)
Fasilitas kesehatan (unit)
PDRB tanpa Migas(Rp. x10000)
PDRB dengan Migas(Rp. x10000)
1992
126
mulai terlihat pada tahun 2001, yakni pada tahun tersebut sektor migas mulai
berkembang dengan beroperasinya PT.Expan Toili di Kabupaten Morowali.
Gambar 20 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan Kabupaten Morowali (BPS Kabupaten Morowali, 1986-2005)
Perkembangan PDRB tanpa migas tidak berbeda dengan perkembangan
PDRB dengan migas. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh besarnya peranan
sektor-sektor lain seperti perkebunan dan pertanian, perikanan dan kelautan serta
kehutanan. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pembangunan sumbangan sektor migas belum memberikan dampak yang nyata
khususnya terhadap aspek sosial masyarakat yakni: taraf pendidikan dan tingkat
kesehatan masyarakat.
Kontribusi sektor migas di Kabupaten Sorong salah satunya dapat diukur
dari perkembangan PDRB. Pada Gambar 21 terlihat bahwa dari tahun 1993 sektor
migas mulai berkembang dengan nilai kontribusi terhadap perekonomian daerah
yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Namun, perkembangan sektor migas
tidak menujukkan pengaruh yang positif terhadap perkembangan jumlah gedung
sekolah dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sorong. Jumlah gedung sekolah dan
fasilitas kesehatan dari tahun ke tahun tidak menunjukkan kenaikan. Hal ini
berarti kontribusi sektor migas yang begitu besar tidak merata pada seluruh sektor
di Kabupaten Sorong.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Gedung sekolah (unit)Fasilitas kesehatan (unit)
PDRB tanpa Migas(Rp.x1000)PDRB dengan Migas(Rp.x1000)
127
Gambar 21 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan Kabupaten Sorong (BPS Kabupaten Sorong, 1986-2005)
Perkembangan aspek sosial ekonomi yang diukur dari nilai PDRB, gedung
sekolah dan fasilitas kesehatan pada tujuh kabupaten/kota di enam lokasi kegiatan
usaha migas menunjukkan bahwa kontribusi sektor migas yang begitu besar tidak
dinikmati secara merata pada seluruh sektor di daerah.
Peningkatan PDRB secara umum dengan keberadaan perusahaan migas,
menunjukkan nilai yang signifikan. Kabupaten/kota dengan PDRB yang tinggi,
diharapkan mampu memberikan perkembangan terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah, pemerataan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan PDRB secara umum pada kabupaten/kota dimana perusahaan
beroperasi, ternyata tidak diikuti dengan perkembangan kondisi sosial yang
signifikan. Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan indikator yang dapat
digunakan untuk melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat.
Berdasarkan evaluasi aspek sosial ekonomi pada tujuh kabupaten/kota di
enam lokasi kegiatan usaha migas, diperoleh bahwa meskipun aspek ekonomi
makro yakni PDRB daerah mengalami peningkatan yang signifikan dengan
kehadiran perusahaan-perusahaan minyak tersebut, namun disisi lain aspek sosial
dengan menggunakan indikator pendidikan yakni perkembangan jumlah gedung
dan jumlah fasilitas kesehatan tidak menunjukkan peningkatan yang nyata.
0
50
100
150
200
250
300
350
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Gedung sekolah (unit)
Fasilitas kesehatan (unit)
PDRB tanpa Migas(Rp. X 10000)
PDRB dengan Migas(Rp. X 10000)
128
Kondisi ini menjadi permasalahan klasik yang umum dijumpai di daerah-daerah
lokasi kegiatan usaha migas dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena tidak
diwajibkannya pembangunan dimensi sosial oleh perusahaan-perusahaan yang
beroperasi, namun hal tersebut hanya bersifat voluntary, sehingga dimensi sosial
masyarakat seperti pengembangan pendidikan masyarakat lokal sangat bergantung
pada keberpihakan perusahaan yang beroperasi. Dengan demikian, secara umum
pembangunan dimensi sosial tidak menjadi tanggung jawab perusahaan, namun
hanya menjadi bagian dari program kepedulian sosial semata. Tanggung jawab
kemudian dilimpahkan pada pemerintah daerah yang memperoleh share lifting
dari kegiatan usaha migas.
5.3.5 Nilai Ekonomi Lingkungan
Nilai ekonomi lingkungan merupakan nilai moneter dari sumberdaya alam
dan lingkungan. Estimasi nilai moneter telah banyak dilakukan dalam kerangka
pengembangan perhitungan biaya kerugian akibat dampak yang ditimbulkan dari
suatu kegiatan usaha pembangunan. Kegiatan usaha migas yang merupakan
kegiatan ektraksi sumberdaya alam memungkinkan menimbulkan dampak
terhadap lingkungan. Estimasi nilai ekonomi sejak awal perencanaan kegiatan,
semestinya dilakukan sebagai bagian dari penggambaran rona awal lingkungan
serta sebagai dasar atau acuan kompensasi kerusakan lingkungan.
Perhitungan nilai ekonomi lingkungan dalam penelitian ini, dilakukan
pada dua lokasi kegiatan usaha migas yakni pada perusahaan yang baru akan
beroperasi dan perusahaan yang telah lama beroperasi, dengan maksud kedua
lokasi kegiatan tersebut dapat menggambarkan nilai ekonomi lingkungan sebelum
kegiatan usaha migas dan setelah kegiatan usaha migas beroperasi.
1. Kabupaten Gresik
Kabupaten Gresik memiliki kawasan kepulauan yakni Pulau Bawean dan
beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas daratan wilayah Kabupaten Gresik
seluruhnya 1.192,25km2 terdiri dari 996,14 km2 luas daratan ditambah sekitar
196,11 km2 luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80
km2 yang sangat potensial dari sub sektor perikanan laut.
129
Jumlah penduduk Kabupaten Gresik yaitu 1.164.024 jiwa terdiri atas: laki-
laki 586.484 jiwa dan perempuan 577.540 jiwa yang tergabung dalam 286.986
keluarga. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Gresik sebanyak 19.023 orang terdiri
atas: laki-laki 10.023 orang dan perempuan 9.211 orang. Tingkat pendidikan di
Kabupaten untuk tingkat SD/MI yaitu 187.041 orang (25,94%), tingkat SMP/MTs
sebanyak 638.933 orang (54,89%), tingkat SMA/MA 129.516 orang (11,13%),
dan untuk tingkat akademi/sarjana 11.175 (0.96%). Berdasarkan struktur
pendidikan, jumlah pencari kerja terdiri atas: tamat SD 3 orang (0,02%), tamat
SLTP 267 orang (1,39%), tamat SMA 6.918 rang (35.97%), tamat sekolah
kejuruan 5.188 orang (26,97%), tamat akademi 2.637 (13,71%) dan sarjana 4.221
(21,95%). Jumlah yang tenaga kerja yang telah ditempatkan sebanyak 1.822 orang
terdiri atas: laki-laki 1016 orang (55,76%) dan perempuan 806 orang (44,24%).
Perusahaan minyak di Gresik saat beroperasi kegiatan usaha Hess dengan
produksi maksimum minyak 20.000 barrel per hari dan produksi gas 100
MMSCFD. Ladang produksi diperkirakan selama 20 tahun.
Hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik baik
secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan manfaat kepada
masyarakat disekitarnya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu konsep
pengelolaan yang diawali dengan mengetahui seberapa besar total nilai ekonomi
dari hutan mangrove yang menjamin keberlanjutan sumberdaya.
Total nilai ekonomi hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah
dihitung dari manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat pilihan dan
manfaat keberadaan. Hasil perhitungan valuasi ekonomi diperoleh nilai ekonomi
total ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah sebesar Rp.
1.235.996.678,00 per hektar per tahun dengan rinciannya disajikan pada Tabel 17.
Tabel 17 Nilai ekonomi total ekosistem mangrove Ujung Pangkah, 2007 No Jenis Manfaat Manfaat Ekonomi (Rp/ha/tahun)
1 Manfaat Langsung 541.677.344,00
2 Manfaat Tidak Langsung 692.096.552,00
3 Manfaat Pilihan 138.000,00
4 Manfaat Keberadaan 2.084.783,00
Nilai Ekonomi Total 1.235.996.678,00
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2007
130
Berdasarkan hasil identifikasi, manfaat langsung hutan mangrove
mencakup manfaat usaha tambak, manfaat hasil kayu bakar dan manfaat
penangkapan hasil perikanan seperti kepiting, udang dan ikan. Sedangkan manfaat
tidak langsung dari hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah diperoleh
dengan pendekatan manfaat fisik dan manfaat biologi. Manfaat fisik adalah
sebagai penahan abrasi pantai yang diestimasi melalui replacement cost dengan
pembuatan beton pantai untuk pemecah gelombang (break waters). Hasil yang
diperoleh berdasarkan biaya pengganti dari nilai pemecah gelombang, yang diacu
dari estimasi yang dilakukan Aprilwati (2001) yaitu bahwa biaya pembangunan
fasilitas pemecah gelombang (break waters) ukuran 1 m x 11 m x 2,5 m (panjang
x lebar x tinggi) dengan daya tahan 10 tahun sebesar Rp. 4.153.880,00. Panjang
pantai hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah adalah 140 km, maka biaya
pembuatan pemecah gelombang dengan daya tahan 10 tahun seluruhnya adalah
Rp. 58,15 milyar.
Selain manfaat tidak langsung berupa fisik, hutan mangrove juga
memberikan manfaat biologi. Manfaat biologi berupa hutan mangrove sebagai
spawning ground yang diperoleh dengan pendekatan menghitung manfaat hutan
mangrove sebagai penyedia pakan alami bagi udang. Luas hutan mangrove pada
saat ini adalah 84,10 ha. Hal ini berarti bahwa udang yang dapat diproduksi
sebesar 16,32 ton per tahun. Produksi udang dikalikan dengan harga udang yang
ada dipasaran saat ini yaitu sebesar Rp. 125.000 per kg, diperoleh nilai manfaat
hutan mangrove sebagai spawning ground sebesar Rp. 606.421.000 per hektar
per tahun.
Untuk mengetahui manfaat pilihan ekosistem hutan mangrove di
Kecamatan Ujung Pangkah diperoleh dengan pendekatan manfaat sebagai
keanekaragaman hayati (biodiversity) dari ekosistem mangrove, dengan
menggunakan metode benefit transfer. Menurut Krupnick (1993) dalam Fauzi
(2004) bahwa benefit transfer bisa dilakukan jika sumberdaya alam tersebut
memiliki ekosistem yang sama, baik dari segi tempat maupun karakteristik pasar
(market characteristic). Mengacu pada nilai keanekaragaman hayati hutan
mangrove di Teluk Bintuni Irian Jaya adalah sebesar US$ 15 per ha per tahun oleh
131
Ruitenbeek (1991). Nilai manfaat pilihan diasumsikan sama dengan nilai
biodiversity di Teluk Bintuni Irian Jaya.
Nilai manfaat pilihan didapatkan dengan mengalikan nilai biodiversity
dengan nilai kurs rupiah terhadap dollar pada saat penelitian yaitu sebesar Rp.
9.200. Berdasarkan perhitungan maka diperoleh hasil bahwa nilai manfaat pilihan
hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah adalah sebesar Rp. 138.000 per
hektar per tahun. Luas hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah adalah
seluas 84,10 ha, sehingga nilai manfaat pilihan (option value) secara keseluruhan
adalah Rp. 11.605.800 per tahun. Nilai tersebut dijadikan sebagai dasar untuk
melindungi sumberdaya alam dari kemungkinan pemanfaatannya untuk masa
datang.
Menghitung nilai manfaat keberadaan dari hutan mangrove didekati
dengan menggunakan teknik contingent valuation method (CVM). Metode ini
diterapkan kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive) sebanyak
115 responden. Nilai manfaat keberadaan hutan mangrove yang diperoleh sebesar
Rp. 2.084.783,00 per ha per tahun. Alasan dari responden menilai sumberdaya
seperti nilai di atas karena responden baik yang berhubungan langsung dengan
hutan mangrove maupun yang tidak berhubungan langsung akan bersedia untuk
mengeluarkan sejumlah uang untuk melindungi ekosistem hutan mangrove di
Kecamatan Ujung Pangkah. Umumnya responden mempunyai kesadaran bahwa
melindungi lingkungan dan sumberdaya alam merupakan tanggung jawab setiap
manusia agar tetap dapat mendukung kehidupannya secara berkelanjutan.
Berdasarkan Tabel 17 diperoleh manfaat tidak langsung memberikan nilai
manfaat hutan mangrove tertinggi dan memiliki persentasi paling besar
dibandingkan dengan manfaat lainnya. Manfaat tidak langsung dengan presentase
55,48% dengan nilai sebesar Rp. 692.096.552,00 per hektar per tahun. Nilai
tersebut lebih besar dari manfaat lainnya karena manfaat fisik berupa penahan
abrasi dan manfaat biologi sebagai penyedia pakan alami ternyata memiliki nilai
paling tinggi. Persentase nilai ekonomi ekosistem hutan mangrove di Kecamatan
Ujung Pangkah dapat dilihat pada Gambar 22.
132
Manfaat Tidak
Langsung 55.48%
Manfaat Langsung 43.42%
Manfaat Pilihan 0.93%
Manfaat Keberadaan
0.17%
Gambar 22 Nilai ekonomi total ekosistem mangrove Ujung Pangkah, 2007
Nilai ekonomi total ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Ujung
Pangkah sebesar Rp. 1.235.996.678,00 per hektar per tahun. Nilai ini masih terlalu
rendah bila melihat fungsi-fungsi ekosistem itu sendiri. Namun dengan nilai
tersebut, menggambarkan bahwa ternyata sumberdaya alam dan lingkungan hidup
dalam pemanfaatan minimal sekalipun memberikan nilai yang cukup tinggi.
Keberadaan nilai menjadi sangat penting sehubungan dengan keberlanjutan
pembangunan. Ketersedian sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup
menjadi entry point pembangunan berkelanjutan. Selain itu nilai tersebut
memberikan alternatif dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.
2. Kabupaten Bengkalis
Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan daratan rendah, rata-rata
ketinggian 2,0 – 6,1 meter diatas permukaan laut, sebagian besar merupakan tanah
organosol, yakni jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Terdapat
sungai, danau serta pulau besar dan kecil yang berjumlah 26 buah.
Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis yaitu 711.233 jiwa, terdiri atas:
378.003 jiwa (53,15%) laki-laki dan 333.230 jiwa (46,85%) perempuan.
Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: tidak tamat sekolah sebanyak 143.811
jiwa (20,22%), tamat SD sebanyak 227.381 (31,97%), tamat SLTP sebanyak
138.619 (19,49%), tamat SLTA sebanyak 129.587 (18,22%), 42.603 (5,99%),
tamat sekolah kejuruan sebanyak 4.054 (0,57%), tamat diploma sebanyak 9.317
133
(1,31%), dan sarjana sebanyak 15.932 (2,24%). Untuk jumlah pencari kerja
sebanyak 3.064 orang terdiri atas: laki-laki 1.707 orang dan perempuan 1.359
orang. Sedang struktur penduduk pencari kerja berdasarkan pendidikan terdiri
atas: tamat SD 9 orang, tamat SLTP 49 orang, tamat SMA 1.970 orang, tamat
akademi 529 orang dan sarjana sebanyak 409 orang. Untuk lowongan pekerjaan
yang ada terdiri atas: sektor pertanian 7 orang, pertambangan 56 orang, industri
pengolahan 11 orang dan perbankan 36 orang.
Kabupaten Bengkalis merupakan potensi penghasil minyak terbesar kedua
di Indonesia setelah Kutai. Saat ini ladang-ladang minyak bumi terdapat di
Kecamatan Mandau, Bukit Batu dan Merbau pengelolaannya dilakukan oleh
perusahaan minyak PT. Caltex Pasific Indonesia dengan wilayah operasi di
Kecamatan Mandau dan Bukit Batu serta perusahaan minyak Kondur Petroleum
S.A yang wilayah konsesi/operasinya meliputi Kecamatan Merbau, Tebing
Tinggi, Rangsang, Bengkalis dan perairan Bengkalis sekitar Selat Malaka.
Produksi minyak mentah oleh PT CPI yaitu 295.000 barrel per hari, lebih dari
separuh produksi minyak Propinsi Riau yaitu 455.000 barrel per hari.
Selain memiliki potensi minyak bumi yang melimpah Kabupaten
Bengkalis juga memiliki potensi sumberdaya alam terbarukan antara lain: sektor
perikanan, pertanian dan holtikultura, serta sektor kehutanan. Untuk sektor
kehutanan Kabupaten Bengkalis memiliki hutan produksi seluas 322.931,46 ha,
atau sekitar 48,25% dari total hutan produksi propinsi Riau. Hutan produksi
tersebut dikelola oleh 13 perusahaan dengan total produksi per tahun mencapai
1.127.209 meter kubik.
Hasil perhitungan valuasi ekonomi Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis berupa hutan sekunder sebesar Rp. 1.244.786.305,00 per ha per tahun.
Nilai ekonomi total merupakan penjumlahan dari manfaat langsung, manfaat tidak
langsung, manfaat pilihan dan manfaat keberadaan.
Tabel 18 Nilai ekonomi total ekosistem hutan sekunder Mandau, 2007 No Jenis Manfaat Manfaat Ekonomi (Rp/Ha/Th) 1 Manfaat Langsung 1.160.141.198,00 2 Manfaat Tidak Langsung 80.400.000,00 3 Manfaat Pilihan 302.250,00 4 Manfaat Keberadaan 3.942.857,00
Nilai Ekonomi Total 1.244.786.305,00 Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2007
134
Berdasarkan hasil identifikasi manfaat langsung yang diperoleh
masyarakat dari hutan sekunder adalah hasil getah karet, kelapa sawit dan arang.
Untuk manfaat tidak langsung dari ekosistem hutan sekunder yang berhasil
diidentifikasi adalah besarnya peranan ekosistem hutan sekunder sebagai
pencegah erosi, penjaga siklus makanan serta habitat flora dan fauna langka.
Untuk menghitung besarnya biaya pencegah erosi didekati berdasarkan
penggantian dari biaya yang diperlukan untuk rehabilitasi lahan apabila tidak ada
ekosistem hutan sekunder. Penafsiran penjaga silkus makanan terukur dari 20 ton
per ha per tahun serasah setara dengan harga kompos @ Rp3.700/kg. Sedangkan
untuk habitat flora dan fauna didekati dengan biaya penghijauan (reboisasi).
Manfaat pilihan hutan sekunder dalam penelitian ini diperhitungkan
berdasarkan manfaat keanekaragaman hayati yang dapat diperoleh dari
keberadaan hutan. Nilai manfaat keanekaragaman hayati hutan sekunder sebesar
US$32,5 per hektar per tahun, apabila keberadaan hutan tersebut secara ekologis
penting dan tetap terpelihara relatif alami (Ministry of State for Population and
Environment USA, 1993). Berdasarkan hasil analisis dengan 42 responden
diperoleh nilai manfaat keberadaan hutan mangrove sebesar Rp. 3.942.857,00 per
hektar per tahun. Persentase nilai ekonomi ekosistem hutan sekunder di
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, disajikan pada Gambar 23.
Manfaat Keberadaan,
0.32%
Manfaat Tidak Langsung,
5.39%
Manfaat Pilihan 0.02%
Manfaat Langsung,
94.26%
Gambar 23 Nilai ekonomi total ekosistem hutan sekunder Mandau, 2007
135
Nilai ekonomi total hutan sekunder di Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis yaitu Rp. 1.244.786.305,00 per hektar per tahun. Nilai ini sangat rendah
bila dibandingkan nilai produksi dari kegiatan usaha migas yang dilakukan,
namun dengan nilai sumberdaya tersebut telah memberikan gambaran yang jelas
bahwa pemanfaatan yang sangat minimal sekalipun sumberdaya alam dan
lingkungan hidup telah memberikan nilai yang cukup signifikan. Estimasi nilai
ekonomi lingkungan tersebut dapat memberikan pilihan-pilihan dalam
pemanfaatan sumberdaya alam.
Nilai ekonomi total tersebut memberikan gambaran betapa nilai dari suatu
sumberdaya dengan tingkat pemanfaatan yang paling sederhana sekalipun dapat
memberikan manfaat yang besar terhadap ekosistem dan manusia. Hasil ini
memberikanan gambaran bahwa suatu sumberdaya memiliki potensi pemanfaatan
dengan berbagai alternatif.
Berdasarkan nilai ekonomi lingkungan yang diperoleh dari hasil analisis
TEV, mengindikasikan bahwa sumberdaya alam dan lingkungan memerlukan
penghargaan yang lebih tinggi dan dapat menjadi dasar informasi secara
kuantitatif untuk menentukan berbagai pilihan pengelolaan sumberdaya alam serta
menjadi informasi dalam penentuan alternatif kebijakan. Penilaian dampak
pembangunan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan merupakan suatu
langkah menuju pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Namun,
pemahaman akan pentingnya pelaksanaan valuasi ekonomi masih sangat kurang
khususnya di kalangan pemerintah dan perusahaan. Hal ini terlihat dalam hasil
analisis PCA dan AHP, dimana strategi pengkajian nilai ekonomi lingkungan
sebagai pengembangan metode analisis dampak lingkungan dianggap kurang
penting bagi kalangan pemerintah dan pelaksana kegiatan (perusahaan migas).
Metode valuasi ekonomi lingkungan merupakan salah satu metode
pengumpulan data dan analisis data sebagaimana diatur dalam Kepdal No. 299
tahun 1996. Berdasarkan hasil review dokumen pada 7 lokasi kegiatan usaha
migas tidak satupun penyusun dokumen AMDAL yang menghitung valuasi
ekonomi. Hal ini terjadi karena penerapan Kepdal No. 299 tahun 1996 bukan
merupakan peraturan yang wajib dilaksanakan dalam menyusun dokumen
AMDAL.
136
Pada dasarnya valuasi ekonomi lingkungan penting dilakukan agar
lingkungan dipertimbangkan sebagai aset ekonomi sehingga AMDAL yang juga
merupakan bagian dari kelayakan suatu proyek dapat melihat untung rugi dari
konteks lingkungan secara moneter. AMDAL yang merupakan kajian dampak
besar dan penting terhadap lingkungan hidup, digunakan sebagai pertimbangan
pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL aspek fisik-
kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai
pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
Selain itu, nilai ekonomi lingkungan yang diperoleh dari hasil estimasi
sumberdaya alam dan lingkungan dapat dijadikan sebagai standar perhitungan
kompensasi maupun asuransi lingkungan (environment insurence). Dengan
demikian, suatu rencana kegiatan dapat berjalan dengan baik, sekalipun terjadi
hal-hal emergency maupun pencemaran terhadap lingkungan hidup (Fauzi, 2004).
Adapun pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya pelaksanaan
valuasi ekonomi dalam penyusunan AMDAL antara lain:
1) Sebagai salah satu aspek yang perlu ditambahkan dalam pengkajian proses
AMDAL.
2) Sebagai salah satu bahan pembuatan keputusan dalam pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan di sekitar kegiatan migas seperti mangrove,
perikanan, DAS, hutan, dan ekosistem lainnya.
3) Memberikan input informasi dalam mengukur jasa lingkungan.
4) Menggambarkan nilai suatu dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau
kegiatan secara lebih jelas dengan menyajikan kerugian lingkungannya.
5) Sebagai dasar perhitungan nilai ganti rugi lahan atas dampak lingkungan yang
akan ditimbulkan.
6) Memberikan nilai moneter terhadap dampak lingkungan yang diprakirakan
akan timbul. Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar bagi penentuan
nilai penting suatu dampak pada tahap evaluasi dampak penting.
Valuasi ekonomi dimasukkan dalam penyusunan KA-ANDAL sebagai
bagian dari isu pokok, kemudian dikaji di dalam ANDAL yang dilakukan sebagai
salah satu analisis dampak besar dan penting terhadap sumberdaya alam dan
lingkungan hidup.
137
Valuasi ekonomi dipersyaratkan sebagai salah satu metode dalam
penyusunan AMDAL migas, yang nantinya hasil valuasi ekonomi dapat dijadikan
sebagai acuan di dalam penentuan ganti rugi atau kompensasi terhadap
pembebasan lahan masyarakat, tuntutan dari terjadinya pencemaran dan sebagai
dasar penentuan dana jaminan lingkungan sewaktu pasca operasi (penutupan
lapangan).
5.4 Kebutuhan Stakeholders
Hasil analisis kebutuhan stakeholders dalam pengembangan AMDAL
migas di masa datang diperoleh 12 komponen. Kedua belas komponen tersebut
merupakan hasil identifikasi dari stakeholders yang terdiri atas: Direktorat
Jenderal Migas DESDM, BP Migas, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah
Daerah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bengkalis, PT.CPI dan Hess Pangkah,
perguruan tinggi (IPB dan UI) serta masyarakat/LSM (INRR).
Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh bahwa kebutuhan stakeholders
dalam pengembangan AMDAL migas di masa datang pada umumnya sama
dengan AMDAL migas saat ini membutuhkan pengembangan yang lebih
komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan metodologi.
Penekanan stakeholders adalah bagaimana melakukan AMDAL migas yang
efektif dan efisien di masa datang. Pengembangan tersebut terkait pada beberapa
aspek yakni: aspek pembiayaan dan metodologi, aspek prosedur persetujuan
AMDAL, aspek kualitas penyusun, lembaga penyusun dan komisi penilai, serta
keterlibatan masyarakat.
1. RKL/RPL secara dinamis dapat diperbaharui seiring dengan perubahan teknologi yang digunakan
2. Pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian dari anggota komisi AMDAL
3. Simplifikasi pembahasan dan persetujuan dokumen AMDAL migas 4. Peningkatan SDM komisi AMDAL pusat 5. Mekanisme keterlibatan masyarakat lokal yang jelas 6. Penetapan proporsi/persentase pembiayaan studi yang jelas/baku 7. Estimasi pembiayaan pengelolaan lingkungan selama umur kegiatan
dengan mempertimbangkan teknologi alternatif, sesuai dengan perkembangan teknologi
8. AMDAL sebagai dokumen yang berkekuatan hukum 9. Pengembangan metodologi AMDAL migas 10. Perlu akreditasi lembaga penyusun AMDAL migas
138
11. Pengkajian nilai ekonomi lingkungan 12. Perlunya mengintegrasikan kajian keadaan darurat dengan dokumen
AMDAL
RKL/RPL seharusnya secara dinamis dapat diperbaharui seiring dengan
perubahan teknologi yang digunakan. Hal tersebut mengingat apabila terjadi
perubahan teknologi yang digunakan, maka akan menyebabkan terjadinya
perubahan-perubahan lingkungan di sekitar kegiatan dengan hasil monitoring
yang dilakukan selama operasi. Dengan demikian perubahan-perubahan
lingkungan yang terjadi mengharuskan pemrakarsa untuk merevisi dokumen
RKL/RPL. Perubahan teknologi yang digunakan dalam suatu kegiatan usaha
menjadi sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang kian maju
memungkinkan bagi setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha migas
mengadopsi teknologi-teknologi baru dalam rangka efisiensi dan efektivitas
operasionalisasi. Adopsi teknologi tersebut sangat memungkinkan terjadi
mengingat kegiatan usaha migas merupakan kegiatan yang bersifat high tech
dalam setiap fase kegiatannya. Dengan demikian dinamika RKL/RPL menjadi
kunci perkembangan AMDAL yang dinamis, efektif dan efisien.
Pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian
dari anggota komisi AMDAL. Komponen tersebut menjadi kebutuhan lainnya
dari stakeholders mengingat peran pemerintah daerah dan masyarakat diera
otonomi menjadi sangat krusial. Pelibatan pemerintah daerah dan lembaga
swadaya masyarakat dalam komisi AMDAL daerah menjadi alternatif objektivitas
penilaian suatu studi AMDAL.
Simplifikasi pembahasan dan persetujuan dokumen AMDAL juga menjadi
kebutuhan stakeholders dalam pengembangan AMDAL migas di masa datang.
Penyederhanaan antara pembahasan dan persetujuan diharapkan dapat mereduksi
perbedaan antara hasil pembahasan dengan rekomendasi persetujuan sehingga
efektivitas dan efisiensi AMDAL dapat terwujud.
Peningkatan SDM komisi AMDAL pusat perlu dilakukan mengingat
kualitas dokumen AMDAL selain ditentukan oleh kualitas penyusun, juga sangat
dipengaruhi oleh kualitas komisi AMDAL. Hal ini menjadi penting mengingat
kajian tentang lingkungan hidup dalam dua dekade terakhir menjadi sangat serius
139
dan mendapat perhatian yang besar dari masyarakat dunia. Pemanasan global
akibat dampak yang muncul dari aktivitas pembangunan telah mengancam
kelansungan hidup manusia. Akibat tersebut menimbulkan polusi dan kerusakan
lingkungan sehingga dokumen AMDAL sebagai upaya untuk menjaga kelestarian
lingkungan dalam keberlanjutan menjadi sangat penting. Komisi penilai AMDAL
pusat adalah salah satu komponen penting yang berperan dalam kegiatan
penyusunan AMDAL migas. Sumberdaya manusia yang berkualitas khususnya
untuk kegiatan migas akan sangat menentukan hasil studi AMDAL migas selain
kualitas tim penyusun itu sendiri. Sinergitas antara tim penyusun dengan komisi
penilai dengan sumberdaya yang berkualitas diharapkan menghasilkan dokumen
AMDAL yang berkualitas pula.
Mekanisme keterlibatan masyarakat lokal yang jelas juga menjadi
perhatian stakeholders. Keterlibatan masyarakat lokal selama ini hanya sebatas
pada tahap pengumuman masyarakat. Tahap ini merupakan satu-satunya tahap
keterlibatan masyarakat dengan pemberian tanggapan dan masukan akan rencana
kegiatan. Kondisi demikian menyebabkan keterwakilan masyarakat sering tidak
diperhatikan sehingga peran serta masyarakat menjadi sangat minim. Disisi lain
masyarakat merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan.
Pertimbangan umum pelibatan masyarakat adalah masyarakat merupakan
komponen yang akan merasakan langsung dampak yang ditimbulkan dari suatu
kegiatan usaha. Selain itu masyarakat juga merupakan komponen yang paling
mengetahui kondisi wilayah dimana kegiatan tersebut dilakukan.
Penetapan pengumuman masyarakat selama 30 hari di dalam Kepdal
No.08 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat kurang tepat. Dasar penentuan
waktu 30 hari tidak jelas, keterlibatan masyarakat didalam kegiatan usaha migas
bukan hanya sekedar memberikan pengumuman/pemberitahuan bahwa suatu
kegiatan akan dimulai tapi yang lebih penting memberikan pembekalan
pengetahuan tentang kegiatan migas secara rinci dari awal perencanaan sampai
pasca operasi antara lain dampak positif dan dampak negatif dari kegiatan usaha
migas secara nasional, regional dan lokal. Sehingga dengan demikian mekanisme
keterlibatan masyarakat lokal perlu diatur secara jelas dan berkekuatan hukum
140
agar dalam pelaksanaannya mendapat perhatian yang serius dari penyusun
AMDAL.
Penetapan proporsi atau persentase pembiayaan studi AMDAL untuk
masing-masing komponen lingkungan khususnya pada komponen pembiayaan
studi lapangan dan pembiayaan laboratorium. Kedua komponen tersebut perlu
mendapat persentase yang cukup tinggi, mengingat keberhasilan studi dan kualitas
dokumen AMDAL terletak pada pelaksanaan studi lapangan serta pengujian
sampel yang tepat. Hal ini dapat mengukur sejauh mana kedalam dari studi
AMDAL tersebut. Persentase pembiayaan perlu diperhitungkan secara cermat,
mengingat kegiatan studi AMDAL senantiasa memerlukan pembiayaan yang
cukup besar.
Estimasi pembiayaan pengelolaan lingkungan selama umur kegiatan
dengan mempertimbangkan teknologi alternatif sesuai dengan perkembangan
teknologi juga menjadi perhatian stakeholders dalam pengembangan AMDAL di
masa datang. Estimasi pembiayaan pengelolaan lingkungan yang mencakup
perkembangan teknologi yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan kegiatan
dan teknologi perlu mendapat perhatian yang serius mengingat sering terjadi
permasalahan lingkungan akibat minimnya pembiayaan yang dialokasikan.
Langkah preventif dan antisipatif seringkali diabaikan, khususnya yang berkaitan
dengan aspek lingkungan hidup, sehingga tidak mengherankan bila akhir-akhir ini
banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat dampak yang dihasilkan dari suatu
kegiatan yang kurang memperhatikan aspek pembiayaan lingkungan selama
kegiatan itu berlangsung. Umumnya, pembiayaan lingkungan dialokasikan ketika
telah terjadi kerusakan lingkungan sehingga sering menjadi terlambat.
Kebutuhan selanjutnya adalah dokumen AMDAL migas sebaiknya dapat
dijadikan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini sangat
penting mengingat cakupan yang komprehensif dari dokumen AMDAL dalam
upaya pencegahan kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas. Selain itu
dokumen AMDAL juga menjadi dasar pemberian ijin pelaksanaan suatu kegiatan
dan atau usaha dari aspek lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti degradasi
lahan, punahnya flora dan fauna, serta rusaknya ekosistem dapat menimbulkan
kerugian yang cukup besar terhadap lingkungan itu sendiri serta bagi masyarakat
141
di sekitar dampak tersebut. Class action dengan kasus lingkungan hidup akhir-
akhir ini marak terjadi. Namun dokumen AMDAL migas yang ada belum dapat
dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat dalam pengajuan gugatan terhadap
kerusakan lingkungan yang terjadi.
Perlunya memperhatikan lembaga tim penyusun AMDAL migas yang
independen dan terakreditasi. Akreditasi lembaga merupakan bukti kualifikasi
sebuah lembaga. Dengan demikian, harapan akan peningkatan kualitas dokumen
AMDAL migas di masa datang dapat terwujud dengan persyaratan penyusunan
AMDAL migas harus dilakukan oleh lembaga yang independen dan telah
terakreditasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga lembaga-lembaga yang tidak
memenuhi kualifikasi serta lembaga-lembaga sempalan yang tidak memiliki
integritas dan tanggung jawab yang baik dalam pelaksanaan studi AMDAL migas.
Pengkajian nilai ekonomi lingkungan sebagai pengembangan metodologi
AMDAL migas di masa datang perlu dilakukan mengingat isu lingkungan hidup
saat ini yang banyak berkaitan dengan etimasi nilai moneter lingkungan. Ekonomi
sumberdaya merupakan suatu cabang ilmu yang memadukan antara ekonomi dan
lingkungan. Ekonomi sumberdaya kemudian sering digunakan sebagai justifikasi
penilaian lingkungan dari sisi moneter. Konversi nilai sumberdaya alam dan
lingkungan kedalam nilai moneter menjadi salah satu kajian yang banyak
mendapat perhatian para ilmuan dan praktisi serta aktivis lingkungan dan
ekonomi. Pengkajian nilai ekonomi lingkungan dalam suatu kegiatan AMDAL
saat ini belum pernah dilaksanakan sehingga kedepan harapan stakeholders akan
penghitungan estimasi nilai ekonomi lingkungan dapat menjadi bagian dari studi
AMDAL yang dilakukan pada kegiatan usaha migas.
Mengingat besarnya tumpuhan minyak yang terjadi setiap tahunnya, maka
dampak dari kondisi darurat yang ditimbulkan (emergency) harus dikaji didalam
ANDAL untuk penanggulangannya. Didalam pengkajian ANDAL terdapat
pengkajian dampak penting kondisi normal dan kondisi darurat, didalam RKL
terdapat pengelolaan kondisi normal dan kondisi darurat, sementara dalam RPL
terdapat lembaga pengawasan kondisi normal dan kondisi darurat (emergency).
Senantiasa dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipatif terhadap tumpahan
maupun kebocoran minyak yang dapat terjadi kapan saja. Meskipun,
142
sesungguhnya segala kemungkinan telah diprediksi dan diperkirakan dengan
sebaik-baiknya, namun kejadian emergency juga selalu terjadi. Untuk itu
emergency response plan, menjadi sangat penting sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan khususnya
pada kegiatan usaha migas. Hasil perhitungan nilai ekonomi lingkungan dan
sumberdaya alam, dapat dijadikan basis perhitungan risk analysis. Seperti nilai
ekonomi lingkungan yang diestimasi pada lokasi lapangan Duri PT.CPI sebesar
1,24 milyar per hektar per tahun dan lokasi lapangan Pangkah Hess Limited
Indonesia sebesar 1,23 milyar per hektar per tahun. Nilai-nilai ekonomi tersebut,
selanjutnya menjadi dasar perhitungan asuransi lingkungan dan sosial maupun
perhitungan biaya kompensasi (ganti kerugian) yang dapat terjadi kapan saja.
5.5 Komponen Utama Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas
Pengembangan kebijakan AMDAL migas dalam mencegah kerusakan
lingkungan selanjutnya dianalisis dengan menentukan komponen utama
pengembangan kebijakan yakni meliputi: komponen kebijakan, komponen
kualitas dokumen, komponen kinerja lingkungan dan komponen kebutuhan
stakeholders.
Komponen kebijakan terdiri atas: penentuan dampak penting (DAM),
efisiensi penyusunan (EFI), kedudukan komisi AMDAL (KOM), metode
pelingkupan (PEL), metode studi (MET), aspek sosial ekonomi (ASP),
keterlibatan masyarakat (KTL), analisis total economic valuation (TEV) dan
pengkajian keadaan darurat/emergency (KAD). Komponen kualitas dokumen
meliputi: kelengkapan dokumen (KEL), penyusun AMDAL (PEA), substansi
dokumen (SUB) dan prosedur penyusunan AMDAL (PRO). Komponen kinerja
lingkungan meliputi: teknologi pengelolaan limbah minyak (TLM), teknologi
pengelolaan limbah gas (TLG), kontribusi migas terhadap PDRB (KTR), taraf
pendidikan dan tingkat kesehatan (PDK), serta tumpuhan minyak (TPM).
Komponen kebutuhan stakeholders terdiri atas: RKL/RPL secara dinamis
dapat diperbaharui seiring dengan perubahan teknologi yang digunakan (RPL),
pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian dari
anggota komisi AMDAL (PEM), simplifikasi pembahasan dan persetujuan
dokumen AMDAL (SIM), peningkatan SDM komisi AMDAL pusat (SDM),
143
mekanisme keterlibatan masyarakat lokal yang jelas (KET), penetapan
proporsi/persentase pembiayaan studi yang jelas/baku (PER), estimasi
pembiayaan pengelolaan lingkungan selama umur kegiatan dengan
mempertimbangkan teknologi alternatif, sesuai dengan perkembangan teknologi
(EST), AMDAL sebagai dokumen yang berkekuatan hokum (HUK),
pengembangan metodologi AMDAL (PMA), akreditasi lembaga penyusun
AMDAL (AKR), dan nilai ekonomi lingkungan (NEL) serta melakukan
pengkajian dan pengintegrasian keadaan darurat/emergency (INT). Selanjutnya
dilakukan analisis penentuan komponen utama pengembangan kebijakan AMDAL
migas di masa mendatang dengan melihat komponen-komponen kebijakan
AMDAL yang ada.
Hasil review kebijakan diperoleh sembilan komponen yang merupakan
kelemahan-kelemahan mendasar dalam peraturan kebijakan AMDAL, selanjutnya
hasil analisis kualitas dokumen AMDAL diperoleh empat komponen mendasar
dalam kaitannya dengan kualitas sebuah dokumen AMDAL, hasil evaluasi kinerja
lingkungan diperoleh lima komponen serta hasil analisis kebutuha stakeholders di
masa mendatang terhadap kebijakan AMDAL diperoleh dua belas komponen.
Dengan demikian, diperoleh tiga puluh total komponen mendasar yang
mendukung pengembangan kebijakan AMDAL migas di masa mendatang.
Review Kebijakan AMDAL
Analisis Kualitas
Dokumen
Analisis Kinerja
Lingkungan
13 Komponen
Analisis Kebutuhan
Stakeholders
9 Komponen
30 Komponen
3 Faktor
4 Komponen
5 Komponen
12 Komponen
Gambar 24 Diagram alir penentuan komponen utama
144
Berdasarkan hasil analisis komponen utama (principle component
analysis), diperoleh 13 komponen yang berpengaruh yakni: efisiensi penyusunan
(EFI), kelengkapan dokumen (KEL), substansi dokumen (SUB), keterlibatan
masyarakat (KTL) dan penyusun AMDAL (PEA), pengembangan metodologi
AMDAL (PMA), nilai ekonomi lingkungan (NEL), teknologi pengelolaan limbah
minyak (TLM), keadaan darurat (KAD) dan simplifikasi penyusunan AMDAL
(SIM), peningkatan sumberdaya manusia (SDM), kontribusi migas terhadap
PDRB (KTR) dan AMDAL berkekuatan hukum (HUK). Ketigabelas komponen
tersebut termasuk dalam tiga faktor utama (komponen utama).
Projection of the variables on the factor-plane ( 1 x 2)
Active
DAM
PEM
KOM EFI
PMA
PER
ASP
NEL
KET
KEL
SDM
AKR
TEV
PEL
TLM
MET PDK
TPM
RPL
INT SUB KTR
HUK
KTL
KAD
PRO PEA
EST
SIM
TLG
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
Factor 1 : 25.27%
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
Fact
or 2
: 21
.58%
Gambar 25 Hasil analisis penentuan komponen utama
Komponen biaya dalam penyusunan AMDAL merupakan komponen
langsung dalam implementasi kebijakan AMDAL. Komponen tersebut merupakan
faktor yang penting dalam penyusunan AMDAL. Biaya yang rendah akan
berdampak terhadap hasil penyusunan AMDAL begitu pula pada penggunaan
biaya yang tinggi akan membebani pemrakarsa sehingga efisiensi penyusunan
menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Dengan demikian diharapkan biaya
penyusunan AMDAL memperhitungkan aspek proporsional dalam analisis
145
dampak lingkungan. Penetapan proporsi atau persentase pembiayaan studi
AMDAL untuk masing-masing komponen lingkungan khususnya pada komponen
pembiayaan studi lapangan dan pembiayaan laboratorium. Kedua komponen
tersebut perlu mendapat persentase yang cukup tinggi, mengingat keberhasilan
studi dan kualitas dokumen AMDAL terletak pada pelaksanaan studi lapangan
serta pengujian sampel yang tepat. Hal ini dapat mengukur sejauh mana kedalam
dari studi AMDAL tersebut. Persentase pembiayaan perlu diperhitungkan secara
cermat, mengingat kegiatan studi AMDAL senantiasa memerlukan pembiayaan
yang cukup besar.
Kelengkapan dokumen AMDAL meliputi: dokumen kerangka acuan,
dokumen ANDAL, dokumen RKL dan RPL. Selain itu perlu pula diperhatikan
ketersediaan, ringkasan ekskutif. Ketidaklengkapan dokumen merupakan pertanda
terhadap lemahnya dokumen hukum akan kewajiban pelaksanaan AMDAL.
Kelengkapan dokumen merupakan indikator utama kualitas dokumen AMDAL
yang disusun. Kelengkapan menjadi sangat penting, mengingat keterkaitan
keempat dokumen utama (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) sangat
berhubungan. KA-ANDAL merupakan acuan penyusunan ANDAL, RKL dan
RPL. Sehingga apabila terjadi ketidaklengkapan dokumen akan sangat berpenaruh
terhadap kinerja pengelolaan lingkungan yang dilakukan. Dengan demikian,
kekuatan hukum dan persyaratan administratif secara hukum positif tidak
terpenuhi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan klaim.
Pengkajian nilai ekonomi lingkungan dalam suatu kegiatan AMDAL saat
ini belum pernah dilaksanakan sehingga kedepan harapan stakeholders akan
estimasi nilai ekonomi lingkungan dapat menjadi bagian dari studi AMDAL yang
dilakukan. Pengkajian nilai ekonomi lingkungan perlu dilakukan dalam
penyusunan AMDAL migas sehingga diharapkan dampak suatu kegiatan tidak
hanya dilihat dari sisi biofisik-kimia semata, tetapi juga dari nilai estimasi
ekonomi lingkungan. Kegiatan ini diharapkan menjadi estimasi moneter dari
sumberdaya alam dan lingkungan yang ada dalam wilayah kegiatan tersebut
dengan demikian kerusakan lingkungan yang umumnya terjadi baik kualitas
maupun kuantitas dapat diestimasi dengan baik. Nilai estimasi ekonomi
lingkungan ini dapat juga dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menentukan
146
nilai kompensasi (ganti rugi) terhadap pengelolaan sumberdaya lingkungan
tersebut.
Simplifikasi pembahasan dan persetujuan dokumen AMDAL juga menjadi
kebutuhan stakeholders dalam pengembangan AMDAL migas di masa datang.
Penyederhanaan antara pembahasan dan persetujuan diharapkan dapat mereduksi
perbedaan antara hasil pembahasan dengan rekomendasi persetujuan sehingga
efektivitas dan efisiensi AMDAL dapat terwujud. Simplifikasi pembahasan dan
persetujuan dokumen AMDAL migas perlu dilakukan mengingat pemisahan
kedua prosedur tersebut akan menyebabkan terjadinya inefisiensi dan inefektivitas
dalam pelaksanaannya. Dengan demikian pembahasan yang awalnya terpisah
dengan prosedur persetujuan membutuhkan waktu dan sumberdaya yang banyak.
Simplifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dualisme penilaian
dokumen AMDAL migas.
Akreditasi lembaga penyusun AMDAL merupakan komponen kebutuhan
yang penting di masa datang. Lembaga penyusun sangat menentukan kualitas
dokumen AMDAL. Dengan demikian, kualitas lembaga menjadi perhatian yang
serius, untuk itu indikator kinerja dan profesionalitas lembaga penyusun dapat
dilihat dari akreditasi lembaga yang dimiliki. Lembaga yang terakreditasi sangat
mungkin diragukan kualitas dan profesionalitasnya.
Waktu persetujuan kerangka acuan merupakan salah satu komponen
efektivitas AMDAL. Saat ini waktu persetujuan untuk dokumen AMDAL
didasarkan pada PP No.27 tahun 1999 adalah 75 hari. Waktu tersebut terbilang
cukup lama sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Terlebih lagi
penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL tidak dapat dilaksanakan sebelum
dokumen KA-ANDAL disetujui. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap
efektivitas penyusunan AMDAL. disisi lain waktu pengambilan keputusan
masyarakat juga terbilang tidak proporsional. Saat ini, waktu pengumuman dan
pengambilan keputusan masyarakat ditentukan 30 hari kerja, sejak
diumumkannya. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan dan
masukan kepada pemrakarsa, pemerintah dan penyusun AMDAL untuk kemudian
segera memperbaiki sesuai dengan tanggapan yang masuk. Waktu yang terbilang
singkat tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap tanggapan dan masukan yang
147
terbatas. Dengan demikian dokumen AMDAL menjadi tidak berkualitas
disebabkan karena minimnya tanggapan yang masuk dari masyarakat. Akhirnya
AMDAL yang dihasilkan dalam implementasinya tidak menjadi efektif.
Dokumen AMDAL migas harus berkekuatan hukum sehingga dapat
dijadikan sebagai dasar penuntutan hukum bagi para pelanggar hukum. Dokumen
AMDAL secara umum selama ini hanya menjadi dokumen pelengkap dalam ijin
pelaksanaan suatu kegiatan. Kondisi ini kemudian menjadikan dokumen AMDAL
hanya formalitas dan hanya merupakan suatu studi lingkungan biasa termasuk
pula AMDAL migas. Kebutuhan selanjutnya adalah dokumen AMDAL migas
sebaiknya dapat dijadikan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Hal
ini sangat penting mengingat cakupan yang komprehensif dari dokumen AMDAL
dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas. Selain
itu dokumen AMDAL juga menjadi dasar pemberian ijin pelaksanaan suatu
kegiatan dan atau usaha dari aspek lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti
degradasi lahan, punahnya flora dan fauna, serta rusaknya ekosistem dapat
menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap lingkungan itu sendiri serta
bagi masyarakat di sekitar dampak tersebut. Class action dengan kasus
lingkungan hidup akhir-akhir ini marak terjadi. Namun dokumen AMDAL migas
yang ada belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat dalam pengajuan
gugatan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.
Kualitas penyusun AMDAL sangat berpengaruh terhadap hasil studi
AMDAL yang dilakukan. Tim penyusun yang berkualitas diyakini menghasilkan
dokumen AMDAL yang berkualitas pula. Dengan demikian AMDAL akan
menjadi efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Perlunya memperhatikan
lembaga tim penyusun AMDAL migas yang independen dan terakreditasi.
Akreditasi lembaga merupakan bukti kualifikasi sebuah lembaga. Dengan
demikian, harapan akan peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas di masa
datang dapat terwujud dengan persyaratan penyusunan AMDAL migas harus
dilakukan oleh lembaga yang independen dan telah terakreditasi. Hal ini
dimaksudkan untuk menjaga lembaga-lembaga yang tidak memenuhi kualifikasi
serta lembaga-lembaga sempalan yang tidak memiliki integritas dan tanggung
jawab yang baik dalam pelaksanaan studi AMDAL migas. Kebutuhan
148
stakeholders tersebut selanjutnya dianalisis untuk menentukan komponen utama
yang berpengaruh, sebagaimana disajikan pada Gambar 25. Kualitas komisi
penilai AMDAL juga menjadi salah satu komponen efektivitas AMDAL pada
kegiatan usaha migas. Kualitas komisi penilai akan menentukan hasil akhir dari
penyusunan dokumen AMDAL. Komisi penilai yang berkualitas, diharapkan
mampu menghasilkan hasil review dokumen yang baik. Kualitas komisi penilai
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kualitas dokumen AMDAL.
Mekanisme keterlibatan masyarakat lokal yang jelas juga menjadi
perhatian stakeholders. Keterlibatan masyarakat lokal selama ini hanya sebatas
pada tahap pengumuman masyarakat. Tahap ini merupakan satu-satunya tahap
keterlibatan masyarakat dengan pemberian tanggapan dan masukan akan rencana
kegiatan. Kondisi demikian menyebabkan keterwakilan masyarakat sering tidak
diperhatikan sehingga peran serta masyarakat menjadi sangat minim. Disisi lain
masyarakat merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan.
Pertimbangan umum pelibatan masyarakat adalah masyarakat merupakan
komponen yang akan merasakan langsung dampak yang ditimbulkan dari suatu
kegiatan usaha. Selain itu masyarakat juga merupakan komponen yang paling
mengetahui kondisi wilayah dimana kegiatan tersebut dilakukan.
Pengembangan metodologi untuk menentukan isu pokok harus terus
dilakukan dan isu pokok tersebut harus telah tercantum pada KA-ANDAL, tidak
hanya dampak potensial yang teridentifikasi. Sehingga dokumen KA-ANDAL
menjadi lebih baik dan komprehensif. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar
penyusunan dokumen ANDAL. Pengembangan metodologi akan memberikan
pengaruh yang nyata terhadap kualitas dokumen AMDAL yang disusun. Metode
praktis dan memiliki validitas yang tinggi akan memberikan hasil yang maksimal.
Dengan demikian, dampak dari kegiatan migas selama ini terhadap lingkungan
dan sumberdaya alam dapat diminimalisir dan mengarah pada zero discharge.
5.6 Strategi Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas
Strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas dilakukan dengan
pendekatan expert judgement. Penyusunan strategi didasarkan pada hasil
penentuan komponen utama pengembangan kebijakan AMDAL migas dalam
mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Hasil focus group discussion
149
diperoleh tiga strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas, yakni:
peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas, penyempurnaan prosedur
penyusunan AMDAL migas, serta penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL
migas.
Peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas meliputi: perbaikan
metode-metode di dalam penyusunan AMDAL untuk aspek ekologi dan sosial
ekonomi. Metode penentuan isu pokok untuk kerangka acuan, metode prakiraan
dan evaluasi dampak ANDAL, teknologi RKL dan institusi/kelembagaan dalam
RPL. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas penyusun AMDAL migas
yang mencakup independensi, kompotensi dan komposisi serta perlunya
mengintegrasikan dalam ANDAL dengan kajian keadaan darurat/emergency dan
dicantumkan dalam kebijakan AMDAL migas yakni dalam peraturan perundang-
undangan teknis AMDAL. Penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL
meliputi: waktu penyusunan persetujuan dokumen, waktu pengumuman
masyarakat serta penunjukan pelaksanaan studi AMDAL oleh lembaga
independen. Penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL migas meliputi:
penguatan sumberdaya manusia, khususnya komisi AMDAL pusat (KLH) dan tim
teknis AMDAL migas, penerapan sanksi administrasi dan pidana sesuai UU No.
23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, perbaikan mekanisme
keterlibatan masyarakat dan kelembagaan pengawas pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan pada kegiatan usaha migas. Selanjutnya berdasarkan hasil
rumusan tersebut, disusun strategi implementasi kebijakan AMDAL migas.
5.6.1 Peningkatan Kualitas Dokumen AMDAL Migas
Strategi peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas didasarkan pada
proses pelaksanaan AMDAL itu sendiri yakni: a) proses pelingkupan, b)
penyusunan dokumen KA-ANDAL, c) dokumen ANDAL, d) dokumen RKL dan
e) dokumen RPL. Untuk meningkatkan kualitas dokumen AMDAL, kelima
komponen tersebut menjadi sangat penting diperhatikan. Perlunya ditetapkan
metode-metode yang baku dalam pelingkupan, seperti metode dalam penentuan
isu pokok untuk KA-ANDAL dan bukan penentuan prioritas dampak penting
hipotetik sebagaimana yang diatur di dalam Permen LH No. 08 tahun 2006,
seharusnya dalam KA-ANDAL dari suatu kegiatan yang direncanakan telah
150
muncul isu pokok yang akan dikaji di dalam ANDAL. Metode prakiraan dampak
penting dan evaluasi dampak penting dalam dokumen ANDAL, harus telah
dicantumkan metode untuk aspek ekologi, fisik, kimia seperti kualitas air, kualitas
udara, tanah, biota perairan, flora dan fauna, sosial, ekonomi dan budaya dengan
menerapkan metode valuasi ekonomi untuk penilaian sumberdaya alam dan
lingkungan yang terkena kegiatan usaha migas. Teknologi pengelolaan
lingkungan untuk aspek limbah cair, gas, limbah padat dan limbah B3 di dalam
RKL harus telah dicantumkan teknologi alternatif sesuai dengan perkembangan
teknologi, sehingga apabila terdapat perubahan teknologi di dalam
pelaksanaannya tanpa harus merevisi dokumen RKL dan RPL. Dokumen RKL
harus bersifat dinamis dengan pengelolaan dampak negatif dan pengembangan
dampak positif. Institusi/kelembagaan di dalam dokumen RPL harus dicantumkan
secara jelas. Metode-metode ini dicantumkan dalam rumusan kebijakan baru
sebagai hasil dari konfirmasi dan modifikasi dari kebijakan terdahulu (PP No. 27
tahun 1999, Permen LH No. 08 tahun 2006, Permen LH No. 11 tahun 2006,
Kepmen ESDM No. 1457 tahun 2000, Kepdal No. 08 tahun 2000, dan Kepdal No.
229 tahun 1996).
Gambar 26 Diagram strategi peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas
Peningkatan Kualitas Dokumen AMDAL Migas
Substansi Dokumen
Pelingkupan
KA-ANDAL
ANDAL
RKL
RPL
metode, isu pokok
metode perkiraan &
evaluasi
teknologi alternatif
teknologi, kelembagaan
metodologi
Kualitas Tim Penyusun
Independensi Kompetensi
Kualifikasi
Pengalaman
Integritas
Komposisi
Data Base
Keahlian Struktur
Terdaftar di Migas
1. Ekologi- Fisika kimia - Biologi
lingkungan - pencemaran
2. Keteknikan - geologi
- perminyakan 3. Sosial budaya 4. Ekonomi
1. Tim Ahli - tenaga ahli - asisten ahli - operator
2. Tim Pengolahan dan Analisis Data
Keadaan Darurat/ Emergency
151
Peningkatan kualitas penyusun AMDAL dapat ditempuh melalui langkah-
langkah strategis yakni: melakukan standarisasi kompetensi tim penyusun dengan
memperhatikan kualifikasi, integritas dan tanggungjawab serta memiliki reputasi
yang baik. Menjaga independensi tim penyusun melalui penunjukan oleh
pemerintah atau lembaga yang independen.
Kualitas penyusun AMDAL sangat berpengaruh terhadap hasil studi
AMDAL yang dilakukan. Tim penyusun yang berkualitas diyakini menghasilkan
dokumen AMDAL yang berkualitas pula. Dengan demikian AMDAL akan
menjadi efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Perlunya memperhatikan
lembaga tim penyusun AMDAL migas yang independen dan terakreditasi.
Akreditasi lembaga merupakan bukti kualifikasi sebuah lembaga. Dengan
demikian, harapan akan peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas di masa
datang dapat terwujud dengan persyaratan penyusunan AMDAL migas harus
dilakukan oleh lembaga yang independen dan telah terakreditasi. Hal ini
dimaksudkan untuk menjaga lembaga-lembaga yang tidak memenuhi kualifikasi
serta lembaga-lembaga sempalan yang tidak memiliki integritas dan tanggung
jawab yang kurang baik dalam pelaksanaan studi AMDAL migas, melakukan
studi ANDAL.
Kualifikasi tim penyusun minimal bersertifikat AMDAL-A bagi anggota
tim dan bersertifikat minimal AMDAL-B untuk ketua tim serta telah memiliki
pengalaman dibidangnya. Pentingnya kualitas tim penyusun AMDAL sangat
berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi studi ANDAL. Kegiatan akan menjadi
lebih efisien dan efektif bila dilakukan oleh tenaga-tenaga yang telah memiliki
pengalaman dalam penyusunan dokumen AMDAL, sehingga inovasi-inovasi
dalam studi dapat diimplementasikan dengan baik. Tim penyusun yang telah
berpengalaman serta berkualifikasi baik dalam penyusunan dokumen akan
memberikan hasil yang lebih baik. Tim penyusun AMDAL migas selanjutnya
disusun berdasarkan kualifikasi yang dimiliki dan disusun dalam data base
(sistem informasi).
Studi AMDAL merupakan studi komprehensif dan kajian multidisiplin
ilmu sehingga sangat membutuhkan tim penyusun yang berpengalaman dibidang
kajian AMDAL. Penguasaan metodologi yang baik dengan pengembangan-
152
pengembangan yang inovatif memungkinkan terjadi pada tim yang memiliki
pengalaman lebih banyak. Kondisi ini menjadi sangat penting mengingat
perkembangan keilmuan dan metodologi studi yang begitu pesat. Komposisi tim
penyusun AMDAL migas, selain ahli-ahli lingkungan biologi, fisika, kimia dan
sosial ekonomi budaya juga perlu ahli perminyakan dan geologi.
Disisi lain setiap tenaga ahli hanya diperbolehkan tergabung pada tiga
lembaga konsultan dengan persyaratan tenaga ahli tidak boleh duduk sebagai tim
teknis dan atau komisi AMDAL. Tim penyusun harus terdiri atas: tim ahli, tim
pengambil sampel di lapangan dan tim pengolahan data. Contoh: kualifikasi
lembaga konsultan dan tim ahli yang telah berpengalaman lebih dari lima tahun
diberi warna biru, telah berpengalaman 3-5 tahun diberi warna kuning dan kurang
dari tiga tahun diberi warna hijau. Sementara lembaga atau atau tenaga ahli yang
dianggap bermasalah berdasarkan kinerja selama melakukan pekerjaan AMDAL
migas diberi warna merah.
Kualitas dokumen AMDAL haruslah ditunjang oleh substansi dokumen
yang terdiri atas dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-
ANDAL), dokumen analisis dampak lingkungan (ANDAL), dokumen rencana
pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan dokumen rencana pemantauan
lingkungan hidup (RPL). Dokumen KA-ANDAL disusun terlebih dahulu untuk
menentukan lingkup studi dan mengidentifikasi isu-isu pokok yang harus
diperhatikan dalam penyusunan AMDAL. Dokumen KA-ANDAL dinilai oleh
komisi penilai AMDAL dan bila telah disetujui maka kegiatan penyusunan
dokumen ANDAL, RPL dan RKL dilaksanakan. Ketiga dokumen tersebut
merupakan bahan penilaian bagi komisi AMDAL untuk kemudian menjadi dasar
penentuan rencana kegiatan usaha layak secara lingkungan atau tidak dan apakah
perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak. Selain itu dokumen AMDAL
juga menjadi bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, memberi masukan
dalam penyusunan desain teknis rencana kegiatan usaha, serta memberi informasi
bagi masyarakat atas dampak yang dapat ditimbulkan.
Pengkajian keadaan darurat/emergency juga menjadi bagian dari upaya
peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas. Pengkajian keadaan darurat
merupakan upaya antisipasi dari kegiatan diluar kondisi normal, seperti kejadian
153
tumpahan minyak. Pengkajian keadaan darurat harus diintegrasikan dalam
dokumen AMDAL.
5.6.2 Penyempurnaan Prosedur Penyusunan AMDAL Migas
Prosedur persetujuan dokumen AMDAL migas yang telah berjalan selama
ini terdiri atas: proses penapisan, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat,
penyusunan dan penilaian KA-ANDAL, serta penyusunan penilaian ANDAL,
RKL dan RPL. Proses penapisan merupakan proses seleksi wajib AMDAL yakni
untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau
tidak. Proses ini sangat penting, mengingat pentingnya suatu kegiatan untuk
menyusun AMDAL, sehingga dampak terhadap lingkungan (eksternalitas) dapat
diminimalisasi.
Penentuan suatu kegiatan wajib AMDAL atau UKL/UPL didasarkan pada
Permen LH No. 11 tahun 2006 tentang jenis kegiatan yang wajib menyusun
AMDAL. Kegiatan usaha migas yang wajib menyusun AMDAL yakni didasarkan
pada volume produksi. Kegiatan eksploitasi di onshore untuk minyak lebih dari
5000 BOPD dan untuk gas lebih dari 30 MMSCFD, serta kegiatan eksploitasi di
offshore untuk minyak lebih dari 15000 BOPD dan untuk gas lebih dari 90
MMSCFD, diwajibkan menyusun AMDAL. Selanjutnya untuk kegiatan
pemasangan pipa wajib AMDAL lebih dari 100 km dengan diameter pipa lebih
dari 20 inchi. Penentuan suatu kegiatan wajib AMDAL atau tidak pada kegiatan
usaha migas menjadi penting, mengingat potensi dampak pada setiap rencana
kegiatan akan senantiasa muncul.
Prosedur penyusunan AMDAL migas selama ini yakni pengajuan
dilakukan oleh pemrakarsa kepada kementerian lingkungan hidup. Penentuan
kegiatan tersebut wajib AMDAL atau UKL/UPL didasarkan pada Permen LH No.
11 tahun 2006. Kegiatan yang wajib AMDAL, selanjutnya menyusun KA-
ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL dilakukan oleh konsultan penyusun yang
ditunjuk langsung oleh pemrakarsa. Pengajuan dokumen KA-ANDAL dievaluasi
dan disetujui selama 75 hari oleh komisi AMDAL pusat (KLH) dibantu tim teknis
(Ditjen Migas), selanjutnya dikembalikan dan apabila telah disetujui maka
pemrakarsa dapat melakukan kegiatan penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan
RPL. Namun apabila belum disetujui maka pemrakarsa dan atau penyusun
154
AMDAL diharuskan untuk melengkapinya. 2) pengajuan Dokumen ANDAL,
RKL dan RPL kepada komisi AMDAL untuk dilakukan penilaian selama 75 hari
dan apabila ketiga dokumen telah memenuhi syarat dan diterbitkannya SK
persetujuan maka dapat diajukan untuk mendapat ijin usaha. Namun apabila
ketiga dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan AMDAL maka diharuskan
untuk melengkapinya. Lebih detil, prosedur penyusunan AMDAL migas selama
ini disajikan pada Gambar 27 berikut.
Gambar 27 Prosedur penyusunan AMDAL migas selama ini
Penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL migas dilakukan dengan
pemrakarsa menyampaikan pelaksanaan kegiatan ke Ditjen Migas, selanjutnya
Ditjen Migas menyampaikan ke lembaga independen untuk penentuan jenis studi,
apakah wajib atau tidak. Apabila wajib AMDAL, maka lembaga independen
menunjuk konsultan penyusun melalui tender dan sekaligus lembaga independen
menentukan biaya studi yang didasarkan pada kedalaman studi dan komposisi tim
penyusun (kualifikasi) serta jenis data yang ditampilkan. Lembaga independen
UKL & UPL Ya Tidak
Pemrakarsa
Penilaian oleh Komisi-Tim Teknis
(Ditjen Migas)
Layak Lingkungan
KLH
Dampak Penting (Permen No.11/2006)
SK KA-ANDAL Oleh Komisi
Penilaian oleh Komisi -Tim Teknis
Persetujuan Komisi AMDAL pusat (KLH)
Konsultan Penyusun
KA-ANDAL
Penyusunan ANDAL, RKL dan RPL
155
juga akan membayar biaya studi kepada konsultan penyusun, agar dalam
penyusunan dapat bersifat independen.
Pengajuan KA-ANDAL ke komisi yang selanjutnya dibahas dalam sidang
komisi bersama tim teknis dan pakar serta wakil dari instansi terkait. Setelah SK
KA-ANDAL diterbitkan, selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen ANDAL
dan RKL/RPL yang dinilai oleh tim teknis AMDAL migas, dan dibahas dalam
sidang komisi beserta pakar dan wakil dari instansi terkait. Apabila dokumen
tersebut layak lingkungan maka diterbitkan SK bersama antara menteri ESDM
dan ketua komisi AMDAL, dan apabila tidak layak maka dokumen AMDAL
ditolak.
Simplifikasi penyusunan terkait dengan masalah waktu penyusunan
dokumen AMDAL. Waktu penyusunan sesungguhnya sangat relatif dan
bergantung pada kasus per kasus, sehingga sangat sulit untuk menentukan waktu
yang dibutuhkan dalam penyusunan AMDAL. Penilaian KA-ANDAL selama ini
Gambar 28 Diagram strategi penyempurnaan prosedur AMDAL migas
KA-ANDAL UKL & UPL Ya Tidak
Pemrakarsa
Penilaian oleh Komisi AMDAL –
Tim Teknis
Konsultan Penyusun
Layak Lingkungan Penolakan Persetujuan
SKB KLH dan DESDM
KA-ANDAL
Ya
Ditjen Migas
Dampak Penting
SK KA-ANDAL Oleh Komisi
Penyusunan ANDAL, RKL/RPL
Penilaian oleh Komisi -Tim Teknis
Tidak
Lembaga Independen
156
dilakukan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen
tersebut. Begitu pula untuk penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang
diajukan secara bersama-sama untuk dinilai selama 75 (tujuh puluh lima) hari
kerja. Namun, seringkali dalam implementasi, sebagaimana hasil analisis kualitas
dokumen AMDAL migas diperoleh bahwa waktu penyusunan relatif lama yakni
1-3 tahun. Semestinya, waktu penilaian disesuaikan dengan kebutuhan usaha
untuk masing-masing kegiatan yang berbeda. Disisi lain penambahan anggota tim
komisi harus dilakukan sebagai upaya efisiensi waktu pemeriksaan dan penilaian.
5.6.3 Penguatan Hukum dan Kelembagaan AMDAL Migas
Strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas dalam mencegah
kerusakan lingkungan harus dilakukan melalui penguatan hukum dan
kelembagaan. Komponen penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL terdiri
atas: peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pada semua tingkatan,
namun lebih ditekankan pada tingkat komisi AMDAL pusat dan tim teknis
AMDAL migas. Penerapan sanksi administrasi dan pidana sesuai UU No. 23
tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Mekanisme keterlibatan
masyarakat yang jelas dalam penyusunan AMDAL migas. Lembaga pengawas
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan usaha migas.
Gambar 29 Diagram strategi penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL migas
Keterlibatan Masyarakat
Pemahaman dan Pengetahuan
Perguruan Tinggi
Tokoh Masyarakat
Pemerintah
Penguatan Hukum dan Kelembagaan
AMDAL Migas
Tahap Perencanaa
Tahap Operasi
Tahap Pasca Operasi
Penguatan SDM
Komisi AMDAL Pusat
Tim Teknis AMDAL Migas
Penerapan Sanksi
Sanksi Administrasi
Sanksi Pidana (UU N0.23/1997)
Perizinan Pengawasan Pelaksanaan RKL, RPL
Ditjen Migas
Pemda Instansi Terkait
Komponen Masyarakat
157
Penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL migas dalam rangka
pengembangan dilakukan dengan tiga pendekatan terintegrasi yakni: penguatan
SDM, penerpanan sanksi administrasi dan pidana sesuai UU No. 23 tahun 1997
tentang pengelolaan lingkungan hidup, perbaikan mekanisme keterlibatan
masyarakat dan kelembagaan pengawas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan pada kegiatan usaha migas. Penguatan SDM ditekankan pada
penguatan kualitas SDM komisi AMDAL pusat (KLH) dan tim teknis AMDAL
migas (Ditjen Migas). Kualitas komisi penilai AMDAL juga menjadi salah satu
komponen efektivitas AMDAL pada kegiatan usaha migas. Kualitas komisi
penilai akan menentukan hasil akhir dari penyusunan dokumen AMDAL. Komisi
penilai yang berkualitas, diharapkan mampu menghasilkan hasil review dokumen
yang baik. Kualitas komisi penilai menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
kualitas dokumen AMDAL. Kualitas tim teknis merupakan komponen yang juga
berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan AMDAL dalam upaya mencegah
kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas. Kualitas tim teknis sangat
penting mengingat kegiatan studi AMDAL merupakan kegiatan multidisiplen
dengan aspek linkungan sebagai inti kajian. Kualitas tim teknis sangat terkait
dengan keahlian dibidangnya. Kegiatan usaha migas merupakan kegiatan dengan
teknologi tinggi serta bersifat teknis profesional sehingga dibutuhkan kajian
AMDAL yang mendalam dan komprehensif agar dihasilkan kualitas AMDAL
yang baik, khususnya dalam upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan.
Tim teknis diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik dalam
keterlibatannya dalam pengkajian dan penilaian AMDAL.
Penerapan sanksi terhadap pelanggaran AMDAL yang dilakukan sangat
penting diterapkan, mengingat aspek penguatan hukum merupakan salah satu
faktor penting pengembangan AMDAL migas dalam mencegah kerusakan
lingkungan pada kegiatan usaha migas. Penerapan sanksi dapat dilakukan berupa
sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan UU No. 23 tahun 1997.
Penerapan sanksi diharapkan manpu menekan tingkat pelanggaran yang terjadi,
sehingga efisiensi dan efektifitas kbijakan AMDAL dapat terwujud.
Peningkatan keterlibatan masyarakat dilakukan melalui pelibatan
masyarakat pada setiap tahap kegiatan. Pembekalan pemahaman tentang AMDAL
158
yang diinisiasi oleh pemrakarsa dengan bekerjasama dengan lembaga penelitian,
perguruan tinggi dan atau organisasi non-pemerintah. Melakukan sosialisasi
kegiatan lebih awal kepada masyarakat serta memastikan keterwakilan
masyarakat dari semua komponen. Mekanisme keterlibatan masyarakat dapat
dilakukan melalui pengumuman pada media massa baik lokal maupun nasional,
diskusi interaktif secara langsung dengan masyarakat yang kemungkinan terkena
dampak serta dilibatkan sejak penyusunan dokumena AMDAL sampai tahap
pelaksanaan kegiatan mulai persiapan sampai pasca operasi. Pola pendekatan
yang digunakan disarankan bersifat partisipatif.
Pendekatan partisipatif merupakan pola distribusi kekuasaan dari
pengelola ke masyarakat. Dengan pola partisipasi masyarakat tidak hanya
dilibatkan sebagai objek tapi juga bagian dari subjek, sehingga kegiatan dan atau
usaha yang dilakukan menjadi tanggung jawab bersama. Pola ini juga akan
memberikan kesadaran yang tinggi terhadap masyarakat dengan mengharapkan
partisipasi yang lebih bermanfaat. Prinsip partisipasi adalah mendorong setiap
warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung. Analisis partisipatif dilakukan guna memahami suara
masyarakat bawah tentang apa yang mereka hadapi serta mengakomodasikan
suara masyarakat bawah dalam perumusan kebijakan. Partisipasi masyarakat
selalu memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bukan reaktif (artinya masyarakat
ikut menalar baru bertindak) ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang
terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian
kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.
Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil
dapat mencerminkan aspirasi masyarakat. Saluran komunikasi sebagai salah satu
wadah atau media yang sangat urgen bagi masyarakat dalam memudahkan
penyampaian pendapatnya kerap menjadi salah satu kendala tersendiri dalam
memaksimalkan peran partisipasi masyarakat. Dengan demikian perlu penyediaan
sarana maupun jalur komunikasi yang efektif meliputi pertemuan-pertemuan
umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat baik tertulis maupun
tidak tertulis.
159
Perencanaan partisipatif juga merupakan salah satu metode yang efektif
untuk menstimulasi keterlibatan masyarakat menyiapkan agenda pembangunan
yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan secara
partisipatif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah di masyarakat yang
dilakukan secara bersama-sama. Satu hal terpenting dalam menjamin hak warga
masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan
adalah adanya keinginan dari semua pihak, mulai dari tataran pemerintah pusat
sampai ke daerah, sehingga masyarakat itu sendiri mengedepankan nilai-nilai
luhur dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dan dilestarikan (demokrasi,
partisipasi, transparansi dan akuntabilitas serta desentralisasi).
Berpegang pada nilai dan prinsip tersebut, diharapkan akan terbangun
kebersamaan yang berdampak pada terbukanya akses bagi masyarakat lokal dalam
merumuskan dan menentukan arah kebijakan bagi dirinya sendiri tanpa terus
menerus tergantung pada pihak-pihak tertentu. Ini sudah tentu harus didukung
oleh keberpihakan pemerintah dan pihak-pihak peduli lainnya terhadap
masyarakat, terutama masyarakat lokal. Tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah dan pemrakarsa serta sebaliknya diharapkan dapat
meningkatkan peran masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.
Kegunaan keterlibatan masyarakat adalah sebagai sumber informasi
keadaan lingkungan, sumber informasi persepsi masyarakat terhadap kegiatan,
ikut memantau dampak yang terjadi, sebagai mitra dalam memecahkan masalah
yang timbul serta sebagai penerima sarana-sarana penunjang (Carter, 1977 dalam
Suratmo, 2002). Dengan dua sub aspek penekanan yakni komponen masyarakat
yang terlibat dan pemberian pemahaman dan pengetahuan secara dini tentang
kegiatan usaha migas dan kemungkinan dampak yang dapat terjadi beserta seluruh
resiko dan keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh.
Kelembagaan pengawas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan pada kegiatan usaha migas perlu diatur secara jelas antara pengawasan
aspek teknis oleh Ditjen Migas antara lain instalasi dan atau peralatan yang akan
digunakan di dalam operasi migas termasuk peralatan pencegahan
penanggulangan pencemaran. Pengawasan aspek sosial ekonomi dan budaya oleh
pemerintah daerah dan pengawasan terhadap media penerima limbah oleh
160
pemerintah daerah antara lain penetapan baku mutu badan air penerima limbah
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Koordinasi kelembagaan untuk izin lokasi
kegiatan usaha migas sebelum beroperasi wajib mendapat izin dari instansi terkait
sesuai rencana pemanfaatan kegiatan seperti kehutanan, perhubungan laut,
kelautan dan perikanan.
5.7 Prioritas Strategi Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas
Didasarkan pada hasil perumusan kebijakan dan penyusunan strategi
implementasi selanjutnya dilakukan penentuan strategi pengembangan kebijakan
AMDAL migas dengan pendekatan hierarchy process analysis. Penentuan strategi
pengembangan kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan pada
kegiatan usaha migas, dilakukan dengan pendekatan aspek aktor dan tujuan
pengembangan AMDAL migas.
Analisis prioritas strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas
disusun dengan lima level yakni level-1 goal: strategi pengembangan kebijakan
AMDAL migas dalam mencegah kerusakan lingkungan, level-2 aktor: penyusun,
pemrakarsa serta komisi AMDAL dan tim teknis, level-3 tujuan: efektif dan
efisien, level-4 sub tujuan: operasional, menjadi acuan, implementatif, biaya,
waktu dan sumberdaya manusia, level-5 alternatif: peningkatan kualitas dokumen
AMDAL migas, penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL migas, serta
penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL migas.
Strategi Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan
Peningkatan Kualitas Dokumen
AMDAL Migas (0.441)
Penyempurnaan Prosedur Penyusunan AMDAL Migas (0.263)
Penguatan Hukum dan Kelembagaan
AMDAL Migas (0.296)
Penyusun (0.297)
Pemrakarsa (0.163)
Komisi-Tim Teknis (0.540)
Efektif (0.500) Efisien (0.500)
Operasional (0.270)
Acuan (0.082)
Implementasi (0.149)
Biaya (0.143)
Waktu (0.072)
SDM (0.286)
Gambar 30 Strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas
161
Strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas dalam mencegah
kerusakan lingkungan dilakukan dengan pendekatan aktor yakni: komisi dan tim
teknis (0.540), penyusunan (0.297) dan pemrakarsa (0.163). Komisi AMDAL dan
tim teknis merupakan aktor utama dalam pengembangan kebijakan AMDAL
migas. Hasil menunjukkan bahwa bobot peranan komisi AMDAL dan tim teknis
merupakan bobot tertinggi dari kedua aktor lainnya. Komisi dan tim teknis
menjadi kunci kualitas dokumen AMDAL yang dihasilkan. Komisi penilai
merupakan komponen yang sangat penting dalam implementasi kebijakan
AMDAL. Komisi penilai akan sangat berperan dalam penilaian dokumen
AMDAL yang telah disusun, diterima atau ditolaknya dokumen tersebut.
Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL yakni
pasal 1 ayat (11) bahwa komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai
dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian di
tingkat pusat oleh komisi penilai pusat dan di tingkat daerah oleh komisi penilai
daerah. Komisi penilai menilai kerangka acuan, analisis dampak lingkungan
hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan
lingkungan hidup.
Tim teknis merupakan tim yang membantu komisi penilai dalam
memberikan pertimbangan teknis terhadap dokumen AMDAL yang diajukan oleh
pemrakarsa. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang
AMDAL yakni pasal 8 ayat (4) bahwa dalam menjalankan tugasnya, komisi
penilai dibantu oleh tim teknis yang bertugas memberikan pertimbangan teknis
atas kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan
lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Selanjutnya pasal
12 ayat (1) bahwa tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri
atas para ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang
bersangkutan dan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan serta
ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai
susunan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1)
ditetapkan oleh menteri untuk komisi penilai pusat dan oleh gubernur untuk
komisi penilai daerah tingkat I.
162
Kualitas tim teknis merupakan komponen yang juga berpengaruh terhadap
efektivitas kebijakan AMDAL dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan pada
kegiatan usaha migas. Kualitas tim teknis sangat penting mengingat kegiatan studi
AMDAL merupakan kegiatan multidisiplen dengan aspek linkungan sebagai inti
kajian. Kualitas tim teknis sangat terkait dengan keahlian dibidangnya. Kegiatan
usaha migas merupakan kegiatan dengan teknologi tinggi serta bersifat teknis
profesional sehingga dibutuhkan kajian AMDAL yang mendalam dan
komprehensif agar dihasilkan kualitas AMDAL yang baik, khususnya dalam
upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan. Tim teknis diharapkan
mampu memberikan hasil yang lebih baik dalam keterlibatannya dalam
pengkajian dan penilaian AMDAL.
Aktor berikutnya adalah penyusun. Kualitas penyusun terdiri atas
kualifikasi ketua dan anggota tim. Ketua tim penyusun studi disebutkan harus
bersertifikat AMDAL penyusun dan sesuai ketentuan yang berlaku, sedang
anggota tim harus memiliki keahlian yang sesuai dengan lingkup studi yang
dilakukan. Kualitas penyusun AMDAL sangat berpengaruh terhadap hasil studi
AMDAL yang dilakukan. Tim penyusun yang berkualitas diyakini menghasilkan
dokumen AMDAL yang berkualitas pula. Dengan demikian AMDAL akan
menjadi efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Bobot penyusun lebih tinggi,
bila dibandingkan dengan bobot aktor, lebih dikarenakan peran dan tugas dari
penyusun yang sangat menentukan isi dan kualitas dokumen yang dihasilkan.
Dalam pelaksanaan dan penyusunan dokumen AMDAL, kualifikasi dan integritas
penyusun sangat menentukan. Selain itu pengalaman penyusun dalam menyusun
AMDAL juga sangat penting, mengingat kompleksitas aspek dan dimensi-dimensi
dalam suatu studi AMDAL.
Aktor pemrakarsa juga menjadi bagian dari pengembangan kebijakan
AMDAL migas yang efektif dan efisien. Pemrakarsa merupakan pihak pengguna
langsung kebijakan AMDAL. Pemrakarsa memiliki kewenangan menunjuk
langsung tim penyusun AMDAL kegiatan usaha yang dilakukan, begitu pula
dengan pembiayaan kegiatan studi AMDAL. Kewenangan dalam penentuan
pelaksana studi dan penyusun dokumen AMDAL sangat penting, mengingat
otoritas sepenuhnya yang dimiliki oleh pemrakarsa, menjadi awal kualitas
163
dokumen AMDAL yang dihasilkan. Penunjukan tim penyusun yang tepat, akan
memberikan hasil yang baik dengan kualitas dokumen AMDAL yang dihasilkan.
Disisi lain, pemrakarsa merupakan pengguna langsung dari dokumen AMDAL
yang dihasilkan. Analisis mengenai dampak penting yang teridentifikasi akan
menjadi rambu-rambu pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
Selanjutnya indikator efektif dan efisien sebagai pendekatan untuk melihat
sejauh mana pengembangan kebijakan AMDAL migas di masa datang. Indikator
efektivitas dan efisiensi meliputi: operasional (0.270), menjadi acuan (0.082) dan
implementasi (0.149), biaya penyusunan (0.143), waktu penyusunan (0.072) dan
sumberdaya manusia (0.286).
Kebijakan AMDAL yang operasional, implementatif serta dapat menjadi
acuan dalam pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha migas, merupakan
sesuatu yang sangat penting, mengingat kebijakan AMDAL adalah dokumen
kebijakan, dokumen publik dan berkekutan hukum. Dokumen AMDAL adalah
satu-satunya dokumen pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengendalian
dampak pada suatu kegiatan usaha. Dengan demikian, dokumen tersebut harus
bersifat operasional, dapat diimplementasikan serta dapat menjadi acuan dalam
pengelolaan lingkungan dalam kaitannya dengan pengendalian dampak
lingkungan.
Peningkatan SDM penyusunan AMDAL perlu dilakukan mengingat
kualitas dokumen AMDAL selain ditentukan oleh kualitas penyusun, juga sangat
dipengaruhi oleh kualitas komisi AMDAL. Hal ini menjadi penting mengingat
kajian tentang lingkungan hidup dalam dua dekade terakhir menjadi sangat serius
dan mendapat perhatian yang besar dari masyarakat dunia. Pemanasan global
akibat dampak yang muncul dari aktivitas pembangunan telah mengancam
kelansungan hidup manusia. Akibat tersebut menimbulkan polusi dan kerusakan
lingkungan sehingga dokumen AMDAL sebagai upaya untuk menjaga kelestarian
lingkungan dalam keberlanjutan menjadi sangat penting. Komisi penilai AMDAL
pusat adalah salah satu komponen penting yang berperan dalam kegiatan
penyusunan AMDAL migas. Sumberdaya manusia yang berkualitas khususnya
untuk kegiatan migas akan sangat menentukan hasil studi AMDAL migas selain
kualitas tim penyusun itu sendiri. Sinergitas antara tim penyusun dengan komisi
164
penilai dengan sumberdaya yang berkualitas diharapkan menghasilkan dokumen
AMDAL yang berkualitas pula.
Komponen efisiensi kebijakan AMDAL lainnya adalah biaya dalam
penyusunan dokumen. Komponen pembiayaan sangat berpengaruh terhadap
kualitas AMDAL yang dihasilkan. Pembiayaan yang minim akan menyulitkan
dalam kegiatan studi, sehingga komponen pembiayaan menjadi sulit dilakukan
dan menyebabkan kegiatan menjadi sekedar dilaksanakan. Disisi lain pembiayaan
yang tinggi akan memberatkan pemrakarsa dan pemborosan biaya dapat terjadi
sehingga kegiatan studi menjadi tidak efisien. Untuk itu, proporsionalisasi
pembiayaan menjadi sangat penting, mengingat efisien kebijakan AMDAL.
Komponen waktu merupakan salah satu indikator efisiensi kebijakan
AMDAL. Waktu persetujuan dokumen AMDAL 75 hari kerja yang didasarkan
pada PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL. Waktu tersebut terbilang cukup
lama sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Terlebih lagi
penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL tidak dapat dilaksanakan sebelum
dokumen KA-ANDAL disetujui. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap
efisiensi penyusunan AMDAL. Waktu pengambilan keputusan kelayakan
dokumen AMDAL menjadi penting dalam kaitannya dengan efisiensi kebijakan
AMDAL untuk mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas.
Waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan kelayakan dokumen AMDAL secara
keseluruhan yakni 150 hari teridir dari 75 hari untuk penilaian persetujuan
dokumen KA-ANDAL dan 75 hari untuk penilaian persetujuan dokumen
ANDAL, RKL dan RPL. Dengan demikian kurang lebih lima bulan waktu yang
dibutuhkan untuk mengeluarkan keputusan kelayakan lingkungan. Sementara
waktu pengambilan keputusan masyarakat dimana saat ini ditentukan sekitar 30
hari sejak diumumkannya. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberi
tanggapan dan masukan kepada pemrakarsa, pemerintah dan penyusun AMDAL
untuk kemudian segera memperbaiki sesuai dengan tanggapan yang masuk.
Waktu yang terbilang singkat tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap
tanggapan dan masukan yang terbatas. Dengan demikian dokumen AMDAL
menjadi tidak berkualitas disebabkan karena minimnya tanggapan yang masuk
165
dari masyarakat. Akhirnya AMDAL yang dihasilkan dalam implementasinya
tidak menjadi efektif.
Hasil penentuan prioritas strategi pengembangan kebijakan AMDAL
migas dalam mencegah kerusakan lingkungan berturut-turut: peningkatan kualitas
dokumen (0.441), penguatan hukum dan kelembagaan (0.296) dan
penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL (0.263). Peningkatan kualitas
dokumen menjadi strategi utama, mengingat AMDAL sebagai dokumen
manajemen lingkungan, dokumen publik dan dokumen hukum. Kualitas dokumen
AMDAL migas merupakan salah satu strategi penting dan kaitannya dengan
pengembangan kebijakan AMDAL. Strategi tersebut harus didukung oleh
peningkatan kualitas penyusun, meliputi; kualifikasi, independensi dan komposisi.
Perbaikan substansi dokumen AMDAL dengan memperbaiki metode-metode
didalam penyusunan AMDAL seperti; kajian aspek ekologi dan sosial ekonomi.
Selain itu, juga harus dilakukan pengintegrasian dengan kajian emergency dalam
penyusunan AMDAL, dengan harapan bahwa hal-hal emergency, seperti yang
sering terjadi selama ini yakni tumpuhan minyak dapat diatasi.
Kualitas dokumen AMDAL merupakan komponen yang terdiri atas
dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL), dokumen
analisis dampak lingkungan (ANDAL), dokumen rencana pengelolaan lingkungan
hidup (RKL) dan dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL).
Dokumen KA-ANDAL disusun terlebih dahulu untuk menentukan lingkup studi
dan mengidentifikasi isu-isu pokok yang harus diperhatikan dalam penyusunan
AMDAL. Dokumen KA-ANDAL dinilai oleh komisi penilai AMDAL dan bila
telah disetujui maka kegiatan penyusunan dokumen ANDAL, RPL dan RKL
dilaksanakan. Ketiga dokumen tersebut (ANDAL, RKL dan RPL), merupakan
bahan penilaian bagi komisi penilai AMDAL untuk kemudian menjadi dasar
penentuan rencana usaha dan atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau
tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak. Selain itu
dokumen AMDAL juga menjadi bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah,
memberi masukan untuk penyusunan disain teknis dari rencana usaha dan atau
kegiatan, serta memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan
dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
166
Strategi kedua dalam upaya pengembangan kebijakan AMDAL kaitannya
dengan mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas adalah
penguatan aspek hukum dan kelembagaan. Dokumen AMDAL yang merupakan
dokumen hukum, harus menjadi barometer keberlanjutan pembangunan dari sisi
ekologi. Hal ini sangat terkait dengan dampak yang senantiasa mengikuti aktivitas
pembangunan yang dilakukan. Dokumen AMDAL kemudian menjadi sangat
penting, sebagai dokumen yang bersifat preventif (pencegahan) akan terjadinya
kerusakan lingkungan. Penegakan hukum (law enforcement) terhadap
pelanggaran-pelanggaran lingkungan, diharapkan menjadi prioritas penguatan
hukum dan kelembagaan AMDAL migas.
Strategi ketiga adalah penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL
migas. Strategi ini juga menjadi penting, mengingat salah satu permasalahan yang
umumnya dihadapi dalam investasi pembangunan adalah aspek prosedural yang
seringkali berbelit-berbelit dan membutuhkan waktu yang lama. Kondisi ini
diperparah dengan banyaknya birokrasi yang harus dilalui dalam kaitannya
dengan penanam investasi tersebut. Demikian pula halnya dalam kegiatan
penyusunan AMDAL. Pemrakarsa dan penyusun seringkali mengalami hambatan,
terutama dalam aspek waktu dan pembiayaan yang begitu besar.
5.8 Rumusan Kebijakan AMDAL Migas
Hasil focus group discussion diperoleh rumusan pengembangan kebijakan
AMDAL migas yang efektif dan efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan
adalah dengan peningkatan kualitas dokumen, penguatan hukum dan kelembagaan
serta penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL migas. Rumusan kebijakan
AMDAL migas tersebut didasarkan pada hasil analisis komponen utama dan
analytichal hierarchy process yang dirumuskan secara bersama-sama dengan
stakeholders AMDAL migas beserta pakar dibidang lingkungan hidup.
Rumusan pengembangan kebijakan AMDAL migas yang efektif dan
efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan diimplementasikan dalam strategi-
strategi kebijakan AMDAL migas yakni: peningkatan kualitas dokumen AMDAL
migas, penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL migas serta penyempurnaan
prosedur penyusunan AMDAL migas.
167
Mengingat pentingnya strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas
tersebut, maka perlu dilakukan pengintegrasian strategi secara komprehensif,
antara strategi peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas, strategi penguatan
hukum dan kelembagaan AMDAL migas, serta strategi penyempurnaan prosedur
penyusunan dokumen AMDAL migas. Dengan demikian, AMDAL migas
diharapkan dapat menjadi efektif dan efisien dalam mencegah kerusakan
lingkungan pada kegiatan usaha migas.
168
SK KA-ANDAL oleh Komisi
KA-ANDAL
UKL & UPL
Dampak Penting ya tidak
Pemrakarsa Ditjen Migas
Lembaga Independen
Komisi AMDAL Tim Teknis
Konsultan Penyusun
ANDAL, RKL, RPL
SKB KLH dan DESDM
KA-ANDAL
Komisi-Tim Teknis
tidak layak
Peningkatan Kualitas Dokumen AMDAL Migas
Penguatan Hukum dan Kelembagaan
AMDAL Migas
Substansi Dokumen
metode, isu pokok
metode perkiraan evaluasi dampak
teknologi alternatif
teknologi, kelembagaan
Penerapan Sanksi
sanksi administrasi
sanksi pidana (UU N0.23/1997)
penilaian
penilaian
penyusunan
layak lingkungan
pelingkupan
independensi
kompetensi komposisi
Keadaan Darurat/ Emergency
Keterlibatan Masyarakat
pemahaman, pengetahuan
komponen masyarakat
integrasi
Gambar 31 Diagram strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas
Lembaga Pengawas Pengelolaan, Pemantauan
Ditjen Migas
Pemda
Instansi terkait
Penguatan SDM
Penyempurnaan Prosedur AMDAL Migas
Penolakan
169
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil review kebijakan terdapat beberapa kelemahan dalam pedoman dan
petunjuk teknis penyusunan AMDAL baik di level PP No. 27 tahun 1999,
Permen LH No. 11 tahun 2006 Permen LH No. 08 tahun 2006, Kepmen
ESDM No. 1457 tahun 2000, Kepdal No. 229 tahun 1996 dan Kepdal No. 08
tahun 2000, antara lain: penentuan dampak penting, efisiensi dalam
penyusunan, kedudukan komisi AMDAL, metode pelingkupan dan metode
studi yang digunakan, aspek sosial ekonomi, mekanisme keterlibatan
masyarakat, serta belum diaplikasikannya analisis valuasi ekonomi lingkungan
dan pengkajian keadaan darurat/emergency.
2. Hasil analisis kualitas dokumen diperoleh enam dokumen termasuk kategori
kurang baik yakni dokumen AMDAL PT.CPI Duri, Pertamina Plaju,
Suryaraya Teladan, Lapindo Brantas, BP Tangguh dan Hess Pangkah, serta
satu dokumen dikategorikan cukup baik yakni dokumen AMDAL Expan
Toili, sedangkan hasil analisis kinerja lingkungan implementasi AMDAL pada
enam lokasi kegiatan usaha migas diperoleh kualitas limbah cair, kualitas
udara dan kebisingan di bawah baku mutu, untuk aspek sosial ekonomi
menunjukkan peningkatan yang signifikan khususnya kontribusi PDRB,
sementara pendidikan dan kesehatan tidak menunjukkan pengaruh yang
signifikan.
3. Kebutuhan stakeholders AMDAL migas di masa mendatang antara lain:
RKL/RPL secara dinamis dapat diperbaharui seiring dengan perubahan
teknologi yang digunakan, simplifikasi pembahasan dan persetujuan dokumen
AMDAL migas, peningkatan SDM komisi AMDAL pusat, mekanisme
keterlibatan masyarakat lokal yang jelas, AMDAL sebagai dokumen yang
berkekuatan hukum, pengembangan metodologi AMDAL migas, perlu
akreditasi lembaga penyusun AMDAL migas, pengkajian nilai ekonomi
lingkungan, serta perlunya mengintegrasikan kajian keadaan
darurat/emergency dengan dokumen AMDAL.
170
4. Rumusan kebijakan AMDAL yang efektif dan efisien dalam mencegah
kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas meliputi: a) Peningkatan
kualitas dokumen AMDAL migas dengan memperbaiki metode-metode di
dalam penyusunan AMDAL untuk aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Metode
penentuan isu pokok untuk KA-ANDAL, metode prakiraan dampak penting
dan evaluasi dampak penting untuk dokumen ANDAL, teknologi alternatif
untuk RKL dan institusi/kelembagaan untuk RPL. Selain itu juga diperlukan
peningkatan kualitas penyusun AMDAL migas yang mencakup independensi,
kompotensi dan komposisi serta perlunya pengintegrasian kajian keadaan
darurat/emergency di dalam AMDAL dan dicantumkan dalam pedoman teknis
penyusunan AMDAL migas. b) Penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL
migas meliputi; penguatan sumberdaya manusia, khususnya komisi AMDAL
pusat (KLH) dan tim teknis AMDAL migas, penerapan sanksi administrasi
dan pidana sesuai UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan
hidup, perbaikan mekanisme keterlibatan masyarakat dan kelembagaan
pengawas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan
usaha migas. c) Penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL meliputi
waktu penyusunan persetujuan dokumen, waktu pengumuman masyarakat
serta penunjukan pelaksana studi AMDAL oleh lembaga independen.
6.2 Saran
Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diperoleh tersebut disarankan:
1. Perlu dilakukan revisi terhadap pedoman teknis AMDAL migas, begitu pula
pedoman umum penyusunan AMDAL dengan mencantumkan metode-
metode ilmiah yang harus diacu di dalam penyusunan AMDAL (KA-
ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL)
2. Untuk peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut untuk menetapkan metode-metode yang diterapkan
untuk aspek ekologi, ekonomi dan sosial sebagai penyempurnaan pedoman
teknis dalam penyusunan AMDAL migas.
3. Perlu mengintegrasikan kajian penanggulangan keadaan darurat/emergency
di dalam AMDAL migas.
171
4. Pembentukan lembaga independen dalam prosedur pelaksanaan AMDAL
migas perlu pengkajian lebih lanjut.
5. Hasil penelitian ini, perlu diimplementasikan.
172
DAFTAR PUSTAKA
Abda’oe, F. 1994. Peran Direktur Utama Pertamina dalam Mengenal Potensi
Dampak Lingkungan dan Pengelolaannya di Sekitar Migas dan Panas Bumi dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta
Adrianto, L. 2006. Ekonomi dan Pengelolaan Mangrove dan Terumbu Karang.
Working Papaer Program Pascasarjana Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB. Institut Pertanian Bogor.
Adrianto, L. 2005. Sinopsis Pengenalan Konsep dan Metodologi Valuasi Ekonomi
Sumberdaya Pesisir dan Laut. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor.
Alshuwaikkat, H.A. 2004. Strategic Environtmental Assessment can Help Solve
Environmental Developing Countris. Internasional Journal of Environmental Impact Assessment Review. Departemen of City and Regional Planning King Fahd University of Petroleum & Mineral, Vol. 25 (2005): 307-317.
Azis, N. 2006. Analisis Ekonomi Alternatif Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. [Tesis]. Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
Barbier, E.B. 1995. The Economics of Forestry and Conservation: Economic
Values and Policies. Journal of Commonwealth Forestry Review. Vol 74. Bartelmus, P and Vesper, A.1999. Green Accounting and Material Flow Analysis:
Alternatives of Complement. Journal of Environtment and Energy. Wuppertal Institute of Climmate.
Bealands and Dunker, P.N. 1983. Effect monitoring in environmental impact
assessment. Paper for work and management on New Directions in Environmental Assessment : The Canadian experience. Departement of Georaphy and Institute for Environmental Studies, University of Toronto.
Bengen, D.G. 2002. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut
serta Prinsip Pengelolaannya. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB. Institut Pertanian Bogor.
BPS Kabupaten Bengkalis, (1986-2005). Kabupaten Bengkalis Dalam Angka.
Kerjasama BPS dan Bappeda Kabupaten Bengkalis. BPS Kabupaten Muara Enim, (1986-2005). Muara Enim Dalam Angka.
Kerjasama BPS dan Bappeda Kabupaten Muara Enim.
173
BPS Kabupaten Musi Banyuasin, (1986-2005). Musi Banyuasin Dalam Angka. Musi Banyuasin.
BPS Kota Palembang, (1986-2005). Kota Palembang Dalam Angka. Palembang. BPS Kabupaten Sidoarjo, (1986-2005). Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka.
Kerjasama BPS dengan Bappekab Sidoarjo. BPS Kabupaten Morowali, (1986-2005). Morowali Dalam Angka. Kerjasama
BPS dan Bappeda Kabupaten Morowali. BPS Kabupaten Sorong, (1986-2005). Sorong Dalam Angka. Kerjasama BPS dan
Bappeda Kabupaten Sorong. BPS Indonesia, (1993-2005). PDRB Kabupaten/Kotamdya di Indonesia Tahun
1993-2005. Jakarta. Clark, J.R.1978. Thermal Pollution and Aquatic Life. Scientific American. 220
(3): 19-27. Dahuri, R., dan Rais, J., Ginting, S.P. 1996. Pengelolaan Sumerdaya Wilayah
Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. Dartanto, T dan Khoirunurrofik. 2006. Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas di
Indonesia. Studi Kasus: Blok Cepu, Bojonegero, Jawa Timur. Jurnal Indonesia Energy Information Center.
Dartanto, T. 2005. BBM, Kebijakan Energi, Subsidi dan Kemiskinan di Indonesia.
Jurnal Inovasi Online Edisi 5/XVII/November 2005. [Ditjen MIGAS] Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 2007. Perkembangan
Cadangan dan Produksi MIGAS 2001-2006. Jakarta. Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan
Lingkungan Perairan. Kanisius. Jakarta. Eriyatno dan Sofyar, F. 2005. Riset Kebijakan. Metode Penelitian Untuk
Pascasarjana. IPB Press. Fauzi, A. 2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Fauzi, A. 2002. Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Lautan. [Bahan
Pelatihan]. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan. Semarang. Universitas Diponegoro.
Fauzi, A. 1999. Teknik Valuasi Ekosistem Mangrove. Bahan Pelatihan
Management for Mangrove Forest (Rehabilitation). Bogor.
174
Finnveden, G., Nilson, M., Johansson, J., Persson, A., Moberg, A, dan Carlsson, T. 2002. Strategic Enviromental Assessment Methodologies Application within the Energy Sector, Volume 25.
Grigalunas, T. A and Conges, R. 1995. Environmental Economics for Integrated
Coastal Area Management: Valuation Methods and Policy Instrument. UNEP Regional Seas Report and Studies. No.164.
Hendartomo, T. 2001. Permasalahan dan Kendala Penerapan AMDAL dalam
Pengelolaan Linkungan. www.freewebs.com/mastomi. Kadariah. 1978. Pengantar Evaluasi Proyek. Jakarta: Universitas Indonesia.
Fakultas Ekonomi. [Kepmen LH 04/2007] Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04
tahun 2007 tentang Baku Mutu limbah Cair Bagi Kegiatan Industri. Jakarta. [Kepmen LH 08/2006] Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08
tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL. Jakarta. [Kepmen LH 129/2003] Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
129 tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi. Jakarta.
[Kepmen LH 42/1996] Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 42
tahun 1996 tentang Baku Mutu limbah Cair Bagi Kegiatan Industri. Jakarta. [Kepmen LH 48/1996] Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48
tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Jakarta. [Kepmen ESDM 1457/2000] Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral
Nomor 1457 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Bidang Pertambangan Dan Energi.Jakarta.
[Kepdal 08/2000] Keputusan Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup
Nomor 08 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Jakarta.
[Kepdal 299/1996] Keputusan Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup
Nomor 299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Jakarta.
Kramer, R.A. 1995. Valuing Tropical Forest. Washington DC. Journal of World
Bank. Kristanto, P. 2002. Ekologi Industri. Andi. Yogyakarta.
175
Kusumastanto, T. 2003. Ocean policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Kusumastanto, T. 2000. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. [Makalah]
Bogor. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Haya, L.O.M.Y. Zubair, H dan Salman, D. 2003. Analisis Kebijakan Pengelolaan
Sumberdaya Terumbu Karang. Studi Kasus Penangkapan Ikan yang Merusak (Sianida dan Bom) di Kepulauan Spermonde, Propinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Pascasarjana UNHAS. Vol. 1. No. 02.
Landiyanto, E. A dan Wardaya, W. 2005. Framework of Regional Development in
Agenda 21: Sustainability and Environmental Vision. Jurnal Munich Personal RePEc Archive (MPRA). Vol. No. 2381.
Ma’arif, S dan Tanjung, H. 2003. Teknik-Teknik Kuantitatif untuk Manajemen.
Jakarta: Grasindo. Moore, J.W. 1991. Inorganic Contaminations of Surface Water. Springer-Verlag,
New York. 334 p. Murdiyarso D, 2003. Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang.
PT Kompas Media Nusantara. Jakarta. Munasinghe, M. 1993. Economic and Policy Issues in Natural Habitats and
Protected Crew. Protected Area Economis and Policy: Lingking Conservation and Sustainable Development. Edited by Mohan Munasinghe and Jeffrey McNeely. Washington DC. Journal of World Bank.
Mukono, H.J. 2005. Kedudukan AMDAL dalam Pembangunan Berwawasan
Lingkungan yang Berkelanjutan. Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 02 Juli. [Permen LH 08/2006] Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08
tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Jakarta.
[Permen LH 11/2006] Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11
tahun 2006 tentang Jenis Kegiatan yang Wajib dilengkapi AMDAL. Jakarta. [PP 41/1999] Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara (Baku Mutu Ambien Nasional). Jakarta. [PP 27/1999] Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan. Jakarta. [PP 51/1993] Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan. Jakarta.
176
[PP 29/1986] Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Jakarta.
Purnama, D. 2003. Public Involment In The Indonesian EIA Process, Perceptions,
and Alternatif. Department or geographical and Enviromental Studies. University of Adelaide.
Purnama, D. 2003b. Reformasi atas proses AMDAL di Indonesia: meningkatkan
peran dari keterlibatan publik. Kajian Pemantuan Dampak Lingkungan. Jurnal INDENI. Vol 23: 415-439.
Purnomo, H dan E.M.L. Tobing. 2007. Pengembangan Simulator Pengendalian
Sumur pada Pemboran Vertikal, Berarah Maupun Horizontal. Lembaran Publikasi LEMIGAS. Vol. 41. No.1 April.
Rahmalia, E. 2003. Analisis Tipologi Dan Pengembangan Desa-Desa Pesisir Kota
Bandar Lampung. [Tesis]. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
Ruitenbeek, H.I. 1991. Mangrove Management: An Economic Analysis of
Management Option with a Focus an Bintury Bay Irian Jaya. EMDI. Saaty, T.L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin (Proses Hierarki
Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi Kompleks). Terjemahan. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
Saaty, T.L. 1994. Decision Making in Economic, Political, sosial and
Technological Environments With the Analytical Hierarchy Process. America : University of Pittssburgh.
Sanim, B. 2003. Environmental Protection and Regional Development. Paper
disampaikan pada The 16th General Conference of IFSSO On Environmental Protection and Regional Development.
Santoso, J. 2005. Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove di Kawasan
Pondok Ball, Desa Legonwetan, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang, Jawa Barat. [Skripsi]. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
Sofyan, A. 2003. Valuasi Ekonomi Pemanfaatan Hutan Mangrove di Desa
Blanakan Kabupaten Subang, Jawa Barat. [Skripsi]. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
Sumarwoto, O. 2005. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gajah Mada
University Press. Yogyakarta. Suparmoko. 2000. Penilaian Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. UGM
Yokyakarta.
177
Supriyadi, H. I dan Wouthuyzen, S. 2005. Penilaian Ekonomi Sumberdaya Mangrove di Teluk Kotania, Seram Barat, Provinsi Maluku. Jurnal Oseanologi dan Limnologi di Indonesia 2005. No. 38 : 1 – 21.
Suratmo, G.F. 2002. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. UGM. Yogyakarta. Steer, A. 1996. Ten Principles of the New Environmentalism. Journal of Finance
and Development. Tiwi, D.A. 2003. Evaluasi AMDAL dalam Menunjang Pengelolaan Pantai
Terpadu. Prosiding Seminar Teknologi. Vol. IV hal 29-31. BPPT. [UU 17/2004] Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Ratifikasi Kyoto
Protokol. Jakarta. [UU 22/2001] Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi. Jakarta. [UU 6/1999] Undang-Undang Nomor 06 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konversi
Perubahan Iklim. Jakarta. [UU 23/1997] Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Penjelasannya. Jakarta. [WCED] World Commision on Environment and Development. 1987. A Global
Perspective. Oxford UK. Blackwell Business. Whelan, S. A. 1996. An Initial Exploration of the Relevance of Complexity Theory
to Group Research and Practice. J. of System Practice. Vol. 9 (1), 49:70. Williamson, M. 2003. Introduction to Environmental Economic Valuation and Its
Relationship to Environmental Impact Assessment: Environmental Impact Assessment. Journal of Environmental Protection Agency. Queensleand GB.
178
148.940.000 Papua
97.890.000 Maluku
90.460.000 Sulawesi
1.046.110.000 Kalimantan
1.667.010.000 Jawa
5.876.890.000 Sumatera
Cadangan Minyak (Barrel) Wilayah
CADANGAN MINYAK BUMI (Barrel)
TERBUKTI = 4.370,29 MMSTB = 4.370.290.000 Bbl POTENSIAL = 4.558,16 MMSTB = 4.558.160.000 Bbl TOTAL = 8.928,45 MMSTB = 8.928.450.000 Bbl
WILAYAH KERJA KEGIATAN MIGAS
WILAYAH KEPULAUAN INDONESIA
WILAYAH KEPULAUAN NEGARA LAIN
CADANGAN MINYAK
Lampiran 1. Cadangan minyak bumi Indonesia
179
24.470.000 Papua
6.000 Maluku
6.300.000 Nusa Tenggara
4.710.000 Sulawesi
47.770.000 Kalimantan
12.240.000 Jawa
91.640.000 Sumatera
Cadangan Gas (Kubik Feet)
Wilayah
WILAYAH KERJA KEGIATAN MIGAS
WILAYAH KEPULAUAN INDONESIA
WILAYAH KEPULAUAN NEGARA LAIN
CADANGAN MINYAK
CADANGAN GAS BUMI (Kubik Feet)
TERBUKTI = 93,95 TSCF =93.950.000 MMSCF/Ft3 POTENSIAL = 93,14 TSCF =93.140.000 MMSCF/Ft3 TOTAL = 187,09 TSCF =187.090.000 MMSCF/Ft3
Lampiran 2. Cadangan gas bumi Indonesia
181
Lampiran 4. Peta Lokasi penelitian PT. CPI, Kabupaten Bengkalis, Riau
Lampian 3d. Peta Lokasi Amerada Hess di Blok Pangkah, Gresik Jawa Timur
182
Lampiran 5. Perkembangan aspek sosial ekonomi di Kabupaten Bengkalis Tahun Gedung
Sekolah Fasilitas
Kesehatan PDRB
tanpa Migas PDRB
dengan Migas 1986 370 11 442.219 - 1987 370 11 507.497 - 1988 370 11 597.180 - 1989 370 13 730.655 - 1990 370 19 839.135 - 1991 370 36 996.585 - 1992 437 44 1.146.595 - 1993 437 44 1.324.246 11.121.327 1994 440 51 1.525.051 11.030.805 1995 440 51 1.735.724 10.755.327 1996 440 59 1.990.883 11.960.796 1997 441 65 2.239.646 13.159.208 1998 460 73 2.779.740 23.787.273 1999 460 73 3.595.194 27.359.563 2000 520 73 1.623.629 14.536.379 2001 534 74 3.358.116 15.755.622 2002 534 87 4.323.472 25.135.143 2003 534 92 5.711.969 26.141.326 2004 535 92 7.253.462 30.906.866 2005 538 93 8.771.652 37.873.971
Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis (1986-2005)
183
Lampiran 6. Perkembangan aspek sosial ekonomi di Kota Palembang Tahun Gedung
Sekolah Fasilitas
Kesehatan PDRB
tanpa Migas PDRB
dengan Migas 1986 526 116 1.242.990 - 1987 526 120 1.448.969 - 1988 526 120 1.558.291 - 1989 526 124 1.744.069 - 1990 526 131 1.860.222 - 1991 526 131 2.100.531 - 1992 540 134 2.386.222 - 1993 540 136 3.224.275 - 1994 540 139 2.012.060 3.145.213 1995 545 145 3.011.539 3.344.913 1996 545 147 3.576.032 3.980.787 1997 545 147 4.238.830 4.670.319 1998 545 150 6.189.483 6.809.872 1999 545 150 7.169.264 7.941.073 2000 545 155 8.019.471 9.362.828 2001 545 155 9.301.812 12.329.627 2002 545 155 10.699.707 14.460.830 2003 545 156 12.425.650 16.815.478 2004 545 156 14.508.625 19.287.616 2005 545 156 17.278.525 24.595.162
Sumber: BPS Kota Palembang (1986-2005)
184
Lampiran 7. Perkembangan aspek sosial ekonomi di Kabupaten Sidoarjo Tahun Gedung
Sekolah Fasilitas
Kesehatan PDRB tanpa
Migas PDRB dengan
Migas 1986 846 69 658.900 - 1987 846 69 759.212 - 1988 846 73 886.795 - 1989 846 75 1.097.246 - 1990 870 77 1.417.150 - 1991 870 78 1.770.102 - 1992 870 78 1.988.359 - 1993 870 87 2.358.832 - 1994 870 88 2.862.438 - 1995 879 88 4.226.782 - 1996 879 91 4.895.642 - 1997 879 97 5.781.614 - 1998 879 97 8.348.791 - 1999 879 97 9.548.538 - 2000 886 100 10.707.550 - 2001 886 117 18.999.062 18.999.098 2002 886 117 21.490.066 21.490.102 2003 886 122 23.825.672 23.825.758 2004 886 120 27.071.870 27.072.023 2005 886 129 31.841.543 31.841.677
Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo (1986-2005)
185
Lampiran 8. Perkembangan aspek sosial ekonomi di Kabupaten Muara Enim Tahun Gedung
sekolah Fasilitas
Kesehatan PDRB tanpa
Migas PDRB dengan
Migas 1986 427 103 486.209 - 1987 427 117 633.068 - 1988 427 118 731.043 - 1989 427 121 938.293 - 1990 474 122 1.195.898 - 1991 474 126 1.375.651 - 1992 474 127 1.301.252 - 1993 474 132 2.338.335 - 1994 474 133 2.502.145 - 1995 546 136 1.326.817 2.042.088 1996 550 136 1.587.853 2.440.630 1997 550 136 2.047.810 3.258.753 1998 550 137 2.730.911 5.203.269 1999 550 137 2.627.335 5.235.797 2000 571 138 3.324.127 6.135.777 2001 571 144 4.236.087 6.698.215 2002 571 144 3.982.794 6.157.875 2003 572 144 4.517.749 6.874.889 2004 571 144 5.048.118 7.683.414 2005 568 144 5.849.054 9.825.106
Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim (1986-2005)
186
Lampiran 9. Perkembangan aspek sosial ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Gedung sekolah
Fasilitas Kesehatan
PDRB tanpa Migas
PDRB dengan Migas
1986 725 83 1.048.082 - 1987 725 83 1.318.721 - 1988 725 83 1.487.754 - 1989 725 83 1.674.059 - 1990 740 85 1.676.838 - 1991 740 90 1.916.567 - 1992 740 95 2.084.757 - 1993 740 95 2.115.927 - 1994 740 96 2.082.876 - 1995 756 96 1.715.467 2.496.290 1996 756 98 2.012.979 2.880.787 1997 756 98 2.370.597 3.404.768 1998 756 100 3.457.637 5.504.512 1999 756 103 3.933.373 6.305.896 2000 756 103 4.860.637 8.695.098 2001 756 105 5.587.388 12.811.508 2002 756 105 6.187.942 12.505.302 2003 756 107 3.585.087 9.950.942 2004 756 107 4.206.525 12.046.457 2005 756 107 5.032.206 16.962.398
Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin (1986-2005)
187
Lampiran 10. Perkembangan aspek sosial ekonomi di Kabupaten Morowali
Tahun Gedung sekolah
Fasilitas Kesehatan
PDRB tanpa Migas
PDRB dengan Migas
1986 280 69 67.934 - 1987 280 69 98.456 - 1988 280 69 112.285 - 1989 280 75 135.285 - 1990 280 75 155.125 - 1991 280 78 171.145 - 1992 280 81 187.989 - 1993 280 82 208.925 - 1994 280 82 201.407 - 1995 280 82 223.084 - 1996 280 84 334.491 - 1997 280 85 398.078 - 1998 280 85 467.031 - 1999 280 87 680.987 - 2000 291 87 708.750 - 2001 291 89 826.456 826.456 2002 291 89 949.424 949.424 2003 291 99 1.041.321 1.041.321 2004 291 87 1.167.923 1.167.923 2005 291 92 1.333.342 1.333.749
Sumber: BPS Kabupaten Morowali (1986-2005)
188
Lampiran 11. Perkembangan aspek sosial ekonomi di Kabupaten Sorong
Tahun Gedung Sekolah
Fasilitas Kesehatan
PDRB tanpa Migas
PDRB dengan Migas
1986 121 41 447.024 - 1987 121 41 428.316 - 1988 121 41 469.409 - 1989 121 47 487.519 - 1990 131 47 639.793 - 1991 131 47 681.128 - 1992 131 47 810.207 - 1993 131 47 445.283 683.401 1994 131 50 496.840 794.851 1995 133 50 563.649 836.871 1996 133 50 641.339 920.140 1997 133 50 932.798 1.272.016 1998 133 55 1.327.589 2.154.606 1999 133 57 613.643 1.237.666 2000 133 57 752.437 1.718.854 2001 133 57 778.241 1.910.443 2002 133 58 876.414 2.035.147 2003 138 58 557.729 1.961.384 2004 138 58 623.551 2.525.057 2005 138 59 701.871 3.185.063
Sumber: BPS Kabupaten Sorong (1986-2005)
189
Lampiran 12. Nilai manfaat langsung ekosistem hutan mangrove Kecamatan Ujung Pangkah Gresik Jawa Timur
No Jenis Manfaat Nilai Manfaat Langsung (Rp/Ha/Th)
1 Perikanan budidaya (tambak) 45.956.080,00
2 Perikanan tangkap 416.499.500,00
3 Pemanfaatan mangrove 4.766.500,00
Total 467.222.080,00
Sumber: Data primer setelah diolah, 2007 Lampiran 13. Nilai manfaat tidak langsung ekosistem hutan mangrove
Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik Jawa Timur
No Jenis Manfaat Nilai Manfaat Tidak Langsung (Rp/Ha/Th)
1 Penahan abrasi 691.490.131,00
2 Penyedia pakan 606.421,00
Total 692.096.552,00
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2007
Lampiran 14. Nilai ekonomi total ekosistem mangrove Kecamatan Ujung Pangkah Gresik Jawa Timur
No Jenis Manfaat Nilai Ekonomi Total (Rp/Ha/Th)
1 Manfaat Langsung 541.677.344,00
2 Manfaat Tidak Langsung 692.096.552,00
3 Manfaat Pilihan 138.000,00
4 Manfaat Keberadaan 2.084.783,00
Nilai Ekonomi Total 1.235.996.678,00
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2007
190
Lampiran 15. Nilai manfaat langsung ekosistem hutan sekunder Kecamatan Mandau Bengkalis Riau
No Jenis Manfaat Nilai Manfaat Langsung (Rp/Ha/Th)
1 Karet 947.184.625,00
2 Sawit 179.015.627,00
3 Arang 4.821.750,00
Total 1.131.022.002,00
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2007 Lampiran 16. Nilai manfaat tidak langsung ekosistem hutan mangrove Kecamatan Mandau Bengkalis Riau
No Jenis Manfaat Nilai Manfaat Tidak Langsung (Rp/Ha/Th)
1 Penjaga siklus makanan 74.000.000,00
2 Habitat flora dan fauna 6.400.000,00
Total 80.400.000,00
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2007
Lampiran 17. Nilai ekonomi total ekosistem hutan sekunder Kecamatan Mandau Bengkalis Riau
No Jenis Manfaat Nilai Ekonomi Total
(Rp/Ha/Th)
1 Manfaat Langsung 1.160.141.198,00
2 Manfaat Tidak Langsung 80.400.000,00
3 Manfaat Pilihan 302.250,00
4 Manfaat Keberadaan 3.942.857,00
Nilai Ekonomi Total 1.244.786.305,00
Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2007
191
Lampiran 18. Output analisis komponen utama pengembangan kebijakan AMDAL di masa datang dalam mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas
Akar ciri (Eigenvalues)
Faktor Eigenvalue % Total Variance
Cumulative Eigenvalue Cumulative %
1 7.581975 25.27325 7.58198 25.27332 6.475323 21.58441 14.05730 46.85773 5.976343 19.92114 20.03364 66.77884 4.547562 15.15854 24.58120 81.93735 3.136916 10.45639 27.71812 92.39376 2.281880 7.60627 30.00000 100.0000
Korelasi variabel terhadap Faktor (Faktor Loadings)
Variabel Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6DAM 0.572315 0.668309 -0.175141 0.164647 0.291000 0.288712PEM 0.631812 0.282424 0.402482 -0.126324 -0.578404 -0.092467KOM 0.433909 -0.588774 -0.047886 0.090932 0.650822 -0.175887EFI 0.780436 -0.531174 -0.078891 0.249747 0.199162 -0.022619
PMA 0.287117 -0.744378 -0.217735 0.158115 -0.181278 0.508128PER 0.321887 -0.610896 -0.358335 0.619594 0.082598 0.063801ASP -0.065825 0.145063 0.026324 0.525801 -0.308308 -0.776151NEL -0.333307 0.828284 0.207863 0.006437 0.397837 0.036453KET 0.673554 0.150831 0.370755 0.537225 0.019316 0.311659KEL -0.740202 0.457702 -0.045598 -0.036489 0.397277 -0.285253SDM -0.067131 -0.126517 -0.900558 0.073379 -0.307393 0.261929AKR -0.698597 0.242914 0.604627 0.166308 0.209087 0.126515TEV 0.062316 0.076154 -0.234570 0.063624 -0.894152 -0.362957PEL -0.367453 -0.277770 -0.505995 0.702820 -0.056711 -0.186060TLM -0.037097 0.820541 0.025622 0.397996 -0.292256 0.284369MET -0.672690 -0.450729 0.368219 0.037076 -0.195231 0.411408PDK -0.437703 -0.521981 0.611848 -0.028950 0.394042 0.074071TPM -0.294854 -0.435724 0.527832 0.649084 -0.152476 0.006238RPL 0.519144 -0.060685 0.624669 0.570415 -0.102748 0.025802INT 0.140138 0.256923 0.221134 0.581552 0.521930 -0.504815SUB 0.861342 0.139896 -0.163321 -0.365501 -0.082282 -0.267365KTR 0.023969 0.178216 0.913453 -0.255431 -0.257579 0.040941HUK 0.397941 0.265276 -0.800348 -0.282867 0.193253 0.115559
192
Variabel Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6KTL 0.783056 -0.056537 0.244456 -0.511839 0.048272 -0.244047KAD 0.211708 0.773777 -0.301940 0.471693 0.127226 0.163096PRO 0.673554 0.150831 0.370755 0.537225 0.019316 0.311659PEA 0.767618 0.178686 0.582782 0.157066 -0.025141 -0.117886EST 0.566712 -0.681228 -0.099773 -0.278456 0.331501 -0.131836SIM 0.209503 0.753345 -0.551657 0.184016 0.184910 0.127281TLG -0.367453 -0.277770 -0.505995 0.702820 -0.056711 -0.186060
Kontribusi variabel terhadap faktor
Variabel Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6DAM 0.043200 0.068975 0.005133 0.005961 0.026995 0.036529PEM 0.052649 0.012318 0.027106 0.003509 0.106650 0.003747KOM 0.024832 0.053535 0.000384 0.001818 0.135027 0.013557EFI 0.080333 0.043572 0.001041 0.013716 0.012645 0.000224
PMA 0.010873 0.085571 0.007933 0.005498 0.010476 0.113150PER 0.013666 0.057633 0.021485 0.084418 0.002175 0.001784ASP 0.000571 0.003250 0.000116 0.060794 0.030302 0.263997NEL 0.014652 0.105949 0.007230 0.000009 0.050455 0.000582KET 0.059836 0.003513 0.023001 0.063465 0.000119 0.042566KEL 0.072263 0.032352 0.000348 0.000293 0.050313 0.035659SDM 0.000594 0.002472 0.135703 0.001184 0.030122 0.030066AKR 0.064368 0.009113 0.061170 0.006082 0.013936 0.007014TEV 0.000512 0.000896 0.009207 0.000890 0.254871 0.057732PEL 0.017808 0.011915 0.042841 0.108620 0.001025 0.015171TLM 0.000182 0.103977 0.000110 0.034832 0.027229 0.035438MET 0.059683 0.031374 0.022687 0.000302 0.012151 0.074174PDK 0.025268 0.042077 0.062640 0.000184 0.049497 0.002404TPM 0.011467 0.029320 0.046618 0.092645 0.007411 0.000017RPL 0.035546 0.000569 0.065293 0.071549 0.003365 0.000292INT 0.002590 0.010194 0.008182 0.074370 0.086840 0.111679SUB 0.097852 0.003022 0.004463 0.029376 0.002158 0.031327KTR 0.000076 0.004905 0.139617 0.014347 0.021150 0.000735HUK 0.020886 0.010868 0.107182 0.017595 0.011906 0.005852KTL 0.080873 0.000494 0.009999 0.057609 0.000743 0.026101KAD 0.005911 0.092464 0.015255 0.048926 0.005160 0.011657
193
Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 PRO 0.059836 0.003513 0.023001 0.063465 0.000119 0.042566PEA 0.077716 0.004931 0.056830 0.005425 0.000201 0.006090EST 0.042359 0.071668 0.001666 0.017050 0.035032 0.007617SIM 0.005789 0.087645 0.050922 0.007446 0.010900 0.007100TLG 0.017808 0.011915 0.042841 0.108620 0.001025 0.015171
Proyeksi variabel terhadap faktor utama 1 dan 2
Projection of the variables on the factor-plane ( 1 x 2)
Active
DAM
PEM
KOM EFI
PMA
PER
ASP
NEL
KET
KEL
SDM
AKR
TEV
PEL
TLM
MET PDK
TPM
RPL
INT SUB KTR
HUK
KTL
KAD
PRO PEA
EST
SIM
TLG
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
Factor 1 : 25.27%
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
Fact
or 2
: 21
.58%
194
Keterangan:
No. Komponen Simbol 1. Dampak penting DAM 2. Keadaan darurat/emergency KEA 3. Komisi AMDAL KOM 4. Efisiensi penyusunan EFI 5. Pelingkupan PEL 6. Metode studi MET 7. Aspek sosial ekonomi ASP 8. Keterlibatan masyarakat KTL 9. Analisis TEV TEV 10. Kelengkapan dokumen KEL 11. Penyusun AMDAL PEA 12. Substansi dokumen SUB 13. Prosedur penyusunan PRO 14. Teknologi pengelolaan limbah minyak TLM 15. Teknologi pengelolaan limbah gas TLG 16. Kontribusi PDRB KTR 17. Taraf pendidikan dan Kesehatan PDK 18. Tumpahan Minyak TPM 19. RKL/RPL secara dinamis dapat diperbaharui
seiring dengan perubahan teknologi yang digunakan
RPL
20. Integrasi keadaaan darurat dengan AMDAL INT 21. Pemerintah daerah dan lembaga swadaya
masyarakat merupakan bagian dari anggota komisi AMDAL
PEM
22. Simplifikasi penyusunan AMDAL SIM 23. Peningkatan SDM komisi AMDAL pusat SDM 24. Mekanisme keterlibatan masyarakat lokal yang
jelas KET
25. Penetapan proporsi/persentase pembiayaan studi yang jelas/baku
PER
26. Estimasi pembiayaan pengelolaan lingkungan selama umur kegiatan dengan mempertimbangkan teknologi alternatif, sesuai dengan perkembangan teknologi
EST
27. AMDAL sebagai dokumen yang berkekuatan hukum
HUK
28. Pengembangan metodologi AMDAL PMA 29. Perlu akreditasi lembaga penyusun AMDAL AKR 30. Pengkajian nilai ekonomi lingkungan NEL
195
Lampiran 19. Hasil analytical hierarchy process strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas dalam mencegah kerusakan lingkungan
Model Name: AHP-OK
Treeview
Goal: Stretegi Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas dalam MencegahKerusakan Lingkungan
PENYUSUN (L: .297) EFEKTIF (L: .500)
Operasional (L: .540) Menjadi Acuan (L: .163) Implementasi (L: .297)
EFISIEN (L: .500) Biaya (L: .286) Waktu (L: .143) SDM (L: .571)
PEMRAKARSA (L: .163) EFEKTIF (L: .500)
Operasional (L: .286) Menjadi Acuan (L: .143) Implementasi (L: .571)
EFISIEN (L: .500) Biaya (L: .571) Waktu (L: .286) SDM (L: .143)
KOMISI DAN TIM TEKNIS (L: .540) EFEKTIF (L: .500)
Operasional (L: .400) Menjadi Acuan (L: .400) Implementasi (L: .200)
EFISIEN (L: .500) Biaya (L: .143) Waktu (L: .286) SDM (L: .571)
196
Model Name: AHP-OK
Priorities with respect to: Goal: Stretegi Pengembangan Kebi...
KOMISI DAN TIM TEKNIS .540PENYUSUN .297PEMRAKARSA .163 Inconsistency = 0.01 with 0 missing judgments.
Model Name: AHP-OK
Synthesis: Summary
Synthesis with respect to: Goal: Stretegi Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan
Overall Inconsistency = .01
Peningkatan Kualitas Dokumen .441Penyempurnaan Prosedur .263Penguatan Hukum dan .296

























































































































































































































![Environmental Impact Assessment [Handbook of EIA and SEA Follow-up] - Referensi Penyusunan Amdal dan UKL-UPL](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63419e2ea89d37c99303ae83/environmental-impact-assessment-handbook-of-eia-and-sea-follow-up-referensi.jpg)