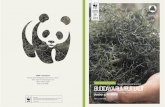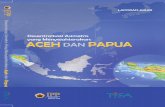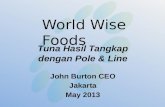WWF Indonesia 1962–2002: Melestarikan Alam Indonesia dengan Menyejahterakan Manusianya
-
date post
21-Oct-2014 -
Category
Education
-
view
939 -
download
0
description
Transcript of WWF Indonesia 1962–2002: Melestarikan Alam Indonesia dengan Menyejahterakan Manusianya

WWF Indonesia 1962 – 2002
Melestarikan Alam Indonesia dengan
Menyejahterakan Manusianya
Pengantar
Perjalanan sejarah sebuah organisasi tidak bisa dilepaskan dari konteks lingkungan
tempat ia berdiri, dan asal muasal gagasan pembentukannya. Oleh karena itu, bicara tentang
WWF Indonesia sejak awal berdirinya hingga tahun 2002, ketika naskah ini ditulis, mau tak
mau harus bicara dulu tentang WWF (World Wide Fund for Nature).
Berdirinya WWF (waktu itu masih kependekan dari World Wildlife Fund) bermula dari
pemikiran energik seorang pakar biologi berkebangsaan Inggris, Sir Julian Huxley. Huxley
saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal pertama badan milik PBB, UNESCO. Selama
dalam di UNESCO, Huxley acapkali melakukan perjalanan ke negara-negara baru merdeka di
benua Afrika. Hasil dari perjalanan ilmiahnya itu, Huxley mendapat masukan yang berarti,
khususnya dalam hal pelestarian hidupan liar di sana.
Dari hasil pengamatannya tersebut, Huxley berupaya menggugah kesadaran masyarakat
Inggris saat itu melalui berbagai tulisannya di media massa. Tujuannya, agar masyarakat
Inggris menghentikan kebiasaan berburu binatang di Afrika, karena binatang tersebut terancam
punah. Dari tulisan itu, gayung bersambut. Seorang pengusaha, Victor Stolan, menanggapi dan
menekankan perlunya dibentuk organisasi internasional, yang mengurusi pelestarian alam.
Dari rangkaian dialog Huxley dengan Stolan, kemudian Huxley menghubungi
rekannya, Direktur Jenderal Pelestarian Alam Inggris, Max Nicholson. Pembicaraan pun
berkembang. Nicholson lalu mengundang sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu, untuk
mendirikan organisasi internasional yang menangani pelestarian alam.
Tepatnya pada 11 September 1961, WWF berdiri, di mana Peter Scott menjadi
ketuanya yang pertama. Scott saat itu juga menjabat sebagai Wakil Presiden Persatuan
Pelestarian Alam Dunia (IUCN). Negara yang dipilih menjadi markas adalah Swiss, karena
sudah terkenal dengan sikap kenetralannya. Pada saat bersamaan, tiba seekor beruang Panda
bernama Chi-Chi di kebun binatang London. Momentum itu kemudian mengangkat binatang
berbulu tebal, dengan titik hitam di sekitar matanya, sebagai simbol organisasi.
Sejak itu, WWF Internasional memulai debutnya secara global, dengan membuka
jaringan lintas benua dan negara, serta mengeluarkan berbagai ―imbauan nasional‖ yang
menekankan pentingnya pelestarian alam. Dana akhirnya berdatangan, sebagai wujud simpati

masyarakat dunia terhadap kiprah WWF. Organisasi ini pernah dipimpin Pangeran Bernhard
dari Negeri Belanda dan Pangeran Phillips dari Kerajaan Inggris.
Pada era 1980-an, WWF memperluas jaringan kerja dengan berbagai organisasi serupa
bertaraf internasional, misalnya, dengan badan-badan PBB. Strategi ini memungkinkan
penyebarluasan kepedulian secara global dan holistik. WWF Internasional lalu mengubah
nama organisasi, agar lebih pas dengan perluasan aktivitasnya, yakni dari World Wildlife Fund
menjadi World Wide Fund For Nature. Saat ini WWF adalah organisasi pelestarian lingkungan
independen terbesar di dunia. WWF memiliki 4,7 juta pendukung dan sebuah jaringan global
yang terdiri dari 27 organisasi nasional, 22 kantor program, dan lima organisasi afiliasi.
"Diplomasi Satwa" dan WWF Indonesia
WWF Indonesia didirikan pada tahun 1962, kurang dari setahun setelah WWF
Internasional didirikan. Selama lebih dari 33 tahun, WWF Indonesia telah bekerjasama dengan
badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah, universitas dan para pemuka
masyarakat, untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian alam di
Indonesia. Ini punya arti penting karena Indonesia adalah wilayah yang secara hayati paling
beraneka-ragam di dunia.
Dengan 17.000 pulau dan populasi penduduk sebesar 210 juta, Indonesia memiliki
kekayaan flora dan fauna yang hampir tak tertandingi di planet ini. Indonesia juga menjadi
kediaman lebih dari 500 species mamalia, dan memiliki species reptil hampir dengan jumlah
yang sama. Sekitar 17 persen species burung dunia berada di Indonesia. Begitu juga, lebih dari
25 persen species ikan yang dikenal dunia. Kenyataannya, ekosistem air tawar dan laut
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang terkaya di dunia. Pada akhirnya, kegiatan-
kegiatan ini menjadikan WWF Indonesia sebagai Kantor Program (Program Office) WWF
yang terbesar di kawasan Asia-Pasifik.
Kemudian, pada tahun 1996 didirikanlah Yayasan WWF Indonesia, sebagai badan
hukum Indonesia, untuk membantu dan mendukung WWF Indonesia Programme (WWF/IP)
dalam program operasional dan perkembangan kelembagaannya. Langkah ini akhirnya
merintis jalan bagi pendirian Organisasi Nasional (National Organization) WWF Indonesia
dalam keluarga WWF Internasional. Mantan Dubes Indonesia untuk Jepang (1969-1972)
Letjen (Purn.) D. Ashari dan pemimpin Majalah Femina Pia Alisjahbana termasuk yang aktif
mengurus pembentukan yayasan ini ke notaris waktu itu, selain Haroen Al Rasjid, yang Ketua
Dewan Komisaris Caltex Pacific Indonesia (CPI).
Ashari dan Pia sudah punya hubungan dengan WWF/IP, sebelum WWF/IP berubah
status menjadi Organisasi Nasional. Yakni, ketika Representative WWF/IP dijabat oleh Dr.
Russel Betts (1989-1996). Ashari sudah punya hubungan pribadi dengan Betts, karena Ashari
kebetulan menjabat Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (1984-1995) dan
President of South East Asian Zoological Parks' Association (1990-1996). Ashari, didampingi
Agus Purnomo, sering memberi ceramah di Departemen Luar Negeri RI kepada calon-calon
duta besar. Materinya tentang isu lingkungan. Kegiatan ini disebutnya "Diplomasi Satwa".
"Saat itu, kami juga mengajak Russel Betts untuk ikut memberikan ceramah. Tradisi ini
diteruskan sesudah Agus Purnomo menggantikan posisi Betts. Itu terus berlangsung selama
sepuluh tahun, setiap ada pembekalan untuk kelompok calon duta besar. Sebab saat itu posisi
Indonesia sudah disorot di dunia dalam masalah lingkungan, sedangkan diplomat-diplomat kita
belum punya latar belakang pengetahuan tentang lingkungan hidup. Pengetahuan dasar saja

belum," tutur Ashari. Sedangkan Pia mengungkapkan, keterlibatannya di yayasan ini bermula
dari ajakan Russel Betts dan Haroen Al Rasjid.
Anggaran Dasar Yayasan WWF Indonesia itu ditandatangani pada 11 September 1996
di depan notaris, di Jakarta, dan pendaftaran Yayasan pada saat itu sedang diproses. Dewan
Penyantun yayasan telah dibentuk dan rapat pertama dilaksanakan pada 10 Desember 1996.
Rapat pertama Badan Pengurus, di mana Ashari menjadi Ketua Badan Pengurus dengan Pia
sebagai Wakil Ketua, itu dilaksanakan pada 9 Januari 1997.
Dewan Pendiri sekaligus Dewan Penyantun Yayasan semula adalah: Haroen Al Rasjid,
Ketua Dewan Komisaris CPI; Prof. Dr. Emil Salim, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia dan mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup; Dr. Russel
Betts, mantan Representative WWF/IP; Agus Purnomo, Representative WWF/IP; Pia
Alisjahbana, pemilik dan pemimpin Majalah Femina; Letjen (Purn.) D. Ashari, Presiden
Asosiasi Kebun Binatang Asia Tenggara (SEAZA) dan mantan Duta Besar RI untuk Jepang
dan Amerika Serikat; dan Dawood Ghaznavi, Direktur Bagian Asia-Pasifik, WWF
Internasional. Namun semenjak berdirinya yayasan ini, Dr. Betts telah mengundurkan diri
karena keperluan lain.
Para pendiri yayasan ini adalah pribadi-pribadi yang sangat peduli pada kelestarian
alam dan lingkungan hidup Indonesia. Karena kesibukan mereka yang tinggi, untuk
menghimpun mereka dibutuhkan upaya tersendiri. Seperti diungkapkan Pia, mereka yang
menjadi pendiri yayasan ini berasal dari latar belakang yang beragam. Ada yang memiliki basis
ekonomi kuat, sehingga bisa memberi sumbangan materi. Ada juga yang memberi kontribusi
dalam bentuk krida. "Tetapi semuanya bersifat sukarela dan tidak ada yang digaji," kata Pia.
Menjadi Organisasi Nasional
Pada Juli 1998, WWF Indonesia mengubah statusnya dari Kantor Program (Program
Office) menjadi Organisasi Nasional (National Organization) ke-27 dalam jaringan
internasional WWF. Perubahan status ini merupakan bagian dari rencana strategis, untuk
memenuhi tuntutan-tuntutan yang lebih besar yang diharapkan dari organisasi. Perubahan
status diharapkan akan memungkinkan WWF Indonesia memperluas cakupan bidang kerja dan
kemampuannya, dan menyelenggarakan pengumpulan dana terpisah dari markas besar WWF
Internasional di Gland, Swiss. Ashari dan Pia waktu itu datang ke Gland, dalam kaitan
perubahan status WWF Indonesia menjadi Organisasi Nasional.
Perubahan status WWF Indonesia juga diiringi kemudian dengan perubahan jajaran
pengurusnya. Sebelum ini, WWF Indonesia –sebagai organisasi yang masih berstatus Kantor
Program dari WWF Internasional—dikelola oleh warga non-Indonesia. Mereka menentukan
proyek pelestarian yang mau dijalankan di Indonesia, membawa dana dari luar, dan kemudian
dana tersebut dikelola sendiri. "Lalu kita sebagai nasionalis menyadari, mengapa tidak kita
yang menjalankan sendiri, dan mereka boleh terus menyokong," jelas Ashari.
Namun, itu tidak berarti WWF Indonesia mengabaikan prinsip profesionalisme. Dalam
mencari figur untuk mengisi jabatan Direktur Eksekutif, WWF Indonesia bersikap terbuka.
Ashari menceritakan, bagaimana Agus Purnomo bersaing dengan calon-calon dari bangsa lain,
karena WWF Indonesia harus setaraf dengan organisasi (WWF) internasional lainnya.
"Kebetulan, Direktur Eksekutif pertama nasional yang kita pilih itu Agus Purnomo, yang dari
dulu sudah menjadi wakilnya Russel Betts. Jadi sudah qualified sekali. Maka kita tunjuk dia
dengan hati yang mantap," lanjut Ashari.

Pembentukan Yayasan dan berubahnya status WWF Indonesia menjadi Oganisasi
Nasional, adalah langkah yang penting dan strategis. Menurut Agus Purnomo, yang
sebelumnya pernah aktif di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), ada beberapa
pertimbangan yang mendasarinya.
Pertama, karena memang ada keinginan untuk menyeimbangkan proses pengambilan
keputusan di WWF secara global. WWF sebelum ini sangat berorientasi pada pendekatan
Eropa dan Amerika Utara, karena jumlah para CEO-nya jauh lebih besar yang berasal dari
kawasan tesebut. Kalau para CEO-nya berkumpul, otomatis 80 persennya adalah orang Eropa.
Akibatnya, meskipun mereka tidak ingin keeropa-eropaan, misalnya, orientasi ke Eropa dan
Amerika itu tak terhindarkan. Untuk penyeimbangan, mereka ingin jumlah organisasi yang
masuk diperbanyak, dengan memasukkan organisasi dari negara-negara di benua yang punya
banyak negara berkembang.
Sebaliknya, dari perspektif kepentingan nasional, dengan status sebagai Organisasi
Nasional, WWF Indonesia akan ditempatkan pada posisi yang setara dengan WWF-WWF di
negara lain. "Kita ingin suara kita didengar. Karena kalau ada masalah hutan, di WWF waktu
itu bukan perspektif negara pemilik hutan yang didengar, tapi perspektif negara yang
mengkonsumsi hutan atau melihat hutan dari jarak jauh," tutur Agus.
Bagi para aktivis lingkungan Indonesia, konsekuensi dari komposisi kepemimpinan
WWF yang kurang berimbang itu menimbulkan persoalan tersendiri. Karena, misalnya, tiba-
tiba datang berbagai poster dan program dari luar, yang tidak jelas harus diapakan, sebab
kemasan dan isinya tidak pas dengan konteks Indonesia. Poster mengenai pelestarian hutan,
contohnya, tidak akan menarik bagi orang Indonesia karena perumusannya asing, dan gambar-
gambar hutannya juga bukan hutan Indonesia. Bahan-bahan kampanye itu akhirnya tak bisa
dipakai.
Kepentingan kedua, adalah soal pendanaan. Dengan status lamanya sebagai Kantor
Program, WWF Indonesia tidak boleh mencari dana sendiri. Dengan status lama, WWF
Indonesia tiap tahun menerima subsidi yang diberikan oleh WWF Internasional, sebesar
300.000 frank Swiss (sekitar 200.000 US$) atau setara Rp 1,8 milyar, dengan kurs 1 US$ = Rp
9.000.
Sementara itu, secara tak resmi, sebenarnya ada dua status di WWF Internasional.
Yakni, WWF yang punya uang dan WWF yang membutuhkan uang. WWF Indonesia, India,
Pakistan, dan negara berkembang lain adalah WWF yang --meski berstatus organisasi
nasional-- membutuhkan uang. Itu disadari semua pihak. Jadi, dengan menjadi Organisasi
Nasional, sebenarnya tidak ada ekspektasi bagi WWF Indonesia untuk menjadi mandiri secara
keuangan dan tidak minta uang lagi dari WWF Internasional.
Namun yang diharapkan adalah, dengan menjadi Organisasi Nasional, WWF Indonesia
menjadi lebih efektif. Karena memang, status lama sebagai Kantor Program itu ibaratnya
adalah menjadi tamu di negara bersangkutan. Jadi secara politis, posisinya lemah. Seorang
tamu, selama masih disenangi, boleh tinggal. Tapi kalau sudah tidak disenangi, dengan mudah
diusir.
Diharapkan, dengan menjadi Organisasi Nasional, suara pihak Indonesia didengar lebih
keras oleh kalangan WWF yang memiliki dana. Jadi waktu itu dilihat, menjadi Organisasi
Nasional itu untungnya banyak, dan ruginya sedikit. Apalagi untuk tiga tahun pertama setelah
peralihan status, subsidi yang diberikan sebesar 300.000 frank Swiss itu masih akan dinikmati

oleh Organisasi Nasional. Dengan harapan, setelah tiga tahun, Organisasi Nasional itu akan
mampu mencari uang sendiri. Jadi memang, untuk tiga tahun pertama tidak ada perubahan dari
segi pendanaan.
Mulai dari Kocek Sendiri
Konsekuensi sebagai Organisasi Nasional adalah WWF Indonesia harus berusaha
mencari dana sendiri. Pia Alisjahbana masih mengingat saat-saat pertama pembentukan
Yayasan WWF Indonesia, di mana masing-masing anggota pendiri dan anggota Dewan
Penyantun harus mengeluarkan dana dari kocek sendiri. "Pak Haroen (Al Rasjid) yang
pertama. Donor-donor pertama ya kita sendiri. Masing-masing Rp 10 juta di notaris. Lalu baru
kami mulai mencari anggota Dewan lainnya," ungkapnya.
Sedangkan Agus menambahkan, "Sayangnya memang, sampai sekarang kita tidak
pernah berhasil mendapatkan dana setara 300.000 frank Swiss kontan dari dalam negeri
Indonesia, yang bisa digunakan untuk apa saja." Dari perusahaan besar seperti Caltex Pacific
Indonesia, cuma diperoleh Rp 750 juta untuk tiga tahun. Jadi, artinya Rp 250 juta per tahun.
Karena cuma ada sumbangan dari dua perusahaan besar, berarti cuma pemasukan Rp 500 juta
per tahun.
Padahal waktu masih berstatus Kantor Program, WWF Indonesia bisa mendapat setara
Rp 2 milyar, dan terserah mau dipakai buat apa saja. Itu memang menjadi modal. Misalnya,
dulu jika WWF Indonesia perlu komunikator, tinggal menyewa orang. Jika perlu akuntan, juga
tinggal menyewa orang. Sekarang, kalau WWF Indonesia membuat proposal dan mau
menyewa akuntan, tak ada yang mau membayar.
Jadi, dengan peralihan status menjadi Organisasi Nasional, tidak pernah diharapkan
bahwa WWF Indonesia akan mampu memenuhi seluruh keperluannya sendiri. Apalagi dalam
pembiayaan proyek. WWF Indonesia kini beroperasi pada tingkatan 4 sampai 6 juta dollar
dollar AS. Pendanaan yang bisa digali dari dalam negeri sangat minim. Jadi, jika WWF
Indonesia bisa menggali 5 persennya saja dari dalam negeri, WWF Internasional sudah
mengerti.
Sebagai gambaran, pemasukan dana untuk WWF Indonesia pada tahun anggaran 2000
sampai 30 Juni 2000 berjumlah Rp 31,080 miliar. Dari jumlah itu, 47 persen diperoleh dari
Jejaring WWF, 39 persen dari berbagai badan bantuan dan pemerintah, 12 dari berbagai
yayasan, dan sisanya dua persen dari berbagai donor lain. Ditambah dengan perolehan bunga
bank, nilai tukar valuta asing, dan bayaran konsultasi dan pemasukan lain, total WWF
Indonesia memperoleh Rp 36,054 miliar.
Sedangkan pengeluaran terbesar adalah untuk pembiayaan proyek-proyek di lapangan,
yang untuk tahun anggaran 2000 mencapai hampir 70 persen dari total pengeluaran. Untuk
biaya operasi kantor, sekitar 11 persen. Sedangkan hibah dari WFF Indonesia untuk berbagai
badan dan lembaga non-WWF, yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, mencapai
hampir tiga persen dari total pengeluaran. Aset bersih total WWF Indonesia pada 30 Juni 2000
adalah Rp 10 miliar.
Pembagian properti dan perlengkapan berdasarkan kawasan hayati (bioregion) pada
tahun anggaran 2000, adalah: Jakarta (60 persen), Dangkalan Sunda (20 persen), Sahul (11
persen), dan Wallacea (sembilan persen).

Suara Indonesia Lebih Didengar
Kentungan WWF Indonesia menjadi Organisasi Nasional adalah, di tingkat WWF
Internasional, pihak Indonesia bisa mempengaruhi suara dan itu sekarang sudah terbukti.
Bahkan Ketua Dewan Penyantun WWF Indonesia, Haroen Al Rasjid, sekarang duduk di
International Board. Dewan WWF secara keseluruhan itu hanya beranggota belasan orang dan
orangnya itu merupakan perwakilan dari berbagai Organisasi Nasional.
Sekarang ini, untuk periode tiga tahun, Indonesia mendapat jatah duduk di Dewan
tersebut bersama beberapa wakil negara lain. Dengan demikian, Haroen Al Rasjid terlibat
dalam proses untuk menentukan disetujui-tidaknya suatu proyek, pesannya apa, strateginya
bagaimana, dan sebagainya. Kemudian Dewi Suralaga, National Program Director WWF
Indonesia, menjadi salah satu anggota Steering Committee dari enam proyek prioritas WWF
sedunia. Dewi bisa duduk di sana karena dia berasal dari WWF Indonesia, yang sudah
berstatus Organisasi Nasional. Kalau statusnya cuma Kantor Program, rankingnya akan sangat
rendah di bawah.
Dulu, ketika Agus Purnomo menjadi Country Representative dalam status WWF
Indonesia sebagai Kantor Program, di hirarki organisasi WWF Internasional, ia menempati
eselon lima. Urutannya, dari Dirjen, Wakil Dirjen, Direktur Program, Direktur Wilayah Asia,
dan baru Country Representative. Begitu Agus menjadi Direktur Eksekutif Yayasan WWF
pada 1996, tiba-tiba posisinya naik setingkat dengan Dirjen. Otomatis, tingkatan di bawah
Dirjen itu tak bisa lagi mengatur-ngatur WWF Indonesia. Itulah keuntungan politis dari
perubahan status WWF Indonesia di dalam WWF.
Berkat peningkatan posisi politis ini, isu-isu yang dilontarkan pihak Indonesia
kemudian lebih mudah diadopsi oleh WWF Internasional. Misalnya, isu penebangan hutan
secara liar, yang kemudian menjadi prioritas bagi WWF International. Juga masalah kebakaran
hutan dan isu-isu lainnya. Satwa prioritas yang ditangani WWF juga paling banyak terdapat di
Indonesia. Mulai dari harimau, orangutan, badak, penyu, dan terumbu karang. Hal ini juga
dimungkinkan karena meningkatnya status WWF Indonesia.
Waktu Yayasan baru dibentuk dan Agus Purnomo terpilih menjadi Direktur Eksekutif
yang pertama tahun 1996, WWF Indonesia beroperasi dengan anggaran 3 juta dollar AS.
Sekarang WWF Indonesia beroperasi dengan 6 juta dollar AS. Kenaikan itu berlangsung
bertahap. Jadi dari segi dana, ada kenaikan. Sedangkan dari segi pengaruh, jelas juga ada
peningkatan yang jauh lebih besar.
Waktu WWF Indonesia berubah menjadi Yayasan, sejumlah pejabat pemerintah
Indonesia tidak dapat memahami alasannya. Sebab, ketika masih berstatus Kantor Program,
WWF Indonesia bisa memasukkan barang dari luar negeri dengan bebas pajak, juga bagi para
stafnya tak perlu membayar pajak penghasilan. Ini tentu menyenangkan bagi para tenaga kerja
asingnya. Jelas, dengan berubah menjadi yayasan, WWF akan menjadi organisasi dan badan
hukum biasa seperti yayasan Indonesia lainnya, dan semuanya harus membayar pajak.
Mengapa tiba-tiba WWF Indonesia rela menghilangkan semua kenikmatan itu?
Jawaban WWF Indonesia adalah, dalam status lamanya, ia hanya akan dianggap
sebagai organisasi asing, dan posisi itu lemah karena sewaktu-waktu bisa ditendang keluar
begitu saja. Sebaliknya, dengan menjadi yayasan dan badan hukum Indonesia, untuk
membubarkannya tidaklah mudah dan harus lewat pengadilan. Jadi posisi politisnya menjadi

jauh lebih kuat. Bahwa hal tersebut harus dibayar dengan kehilangan sejumlah kenikmatan,
berupa pembebasan pajak dan sebagainya, itu adalah risiko.
Meski sudah berubah status, toh kadang-kadang WWF Indonesia tetap saja dipandang
orang sebagai organisasi internasional. WWF Indonesia lebih senang diakui sebagai organisasi
Indonesia. Perlu satu sampai dua tahun untuk meyakinkan berbagai pihak, khususnya para
pejabat departemen pemerintahan terkait –seperti Departemen Kehutanan, Biro Hubungan
Luar Negeri, Sekretaris Kabinet, dan sebagainya-- bahwa WWF Indonesia adalah betul-betul
badan hukum Indonesia. Juga, bahwa WWF Indonesia tidak main-main, dan tidak ada maksud
mencari keuntungan material tertentu dengan perubahan status tersebut.
Di mata pemerintah Indonesia, organisasi WWF Indonesia adalah organisasi nasional.
Maka pengurus WWF Indonesia bisa ikut dalam delegasi Republik Indonesia ke Konferensi
Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan, yang
berakhir 4 September 2002. Karena para pimpinannya adalah orang Indonesia, dan badan
hukumnya memang yayasan, secara struktural WWF Indonesia adalah organisasi nasional.
WWF Indonesia berdiri sendiri, tidak di bawah instruksi WWF Internasional.
WWF Indonesia beruntung, karena yang menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup
waktu itu adalah Sarwono Kusumaatmadja. Sebagai orang politik, Sarwono bisa langsung
menangkap esensi perubahan status WWF Indonesia, tanpa perlu banyak penjelasan lagi. Yang
menjabat Menteri Kehutanan waktu itu adalah Djamaludin Suryohadikusumo. Djamaludin juga
bisa memahami. Dengan dukungan dari dua tokoh itu, pihak Sekretaris Negara akhirnya juga
lebih mudah menerima WWF Indonesia. Dan WWF Indonesia bisa dibilang adalah organisasi
pertama yang melakukan perubahan status semacam itu, di antara sekian organisasi lingkungan
di Indonesia.
Pada 13 Maret 1998, WWF Indonesia melakukan kerjasama dengan Departemen
Kehutanan, diawali dengan pensahan Memorandum of Understanding (MoU). MoU ini
ditandatangani oleh Ashari atas nama Yayasan WWF Indonesia dan Dirjen PHPA Ir.
Sumarsono atas nama Menteri Kehutanan RI. Proyek yang didanai WWF itu bernilai ratusan
juta rupiah dan tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.
Dengan menjadi Yayasan, WWF Indonesia memang boleh mencari dana sendiri.
Namun jika ada tuduhan bahwa perubahan status WWF Indonesia itu bertujuan semata-mata
untuk mencari pemasukan uang sebanyak-banyaknya, itu sama sekali tidak benar. Karena
penggalian dana di dalam negeri Indonesia, dengan segala potensi kekayaannya, persentasenya
di WWF cuma lima persen. Dengan perubahan status tersebut, WWF Indonesia malah
kehilangan subsidi yang besarnya 300.000 frank Swiss.
Mengapa penggalian dana dari dalam negeri tak bisa diandalkan? Hal ini karena
sumber-sumber uang yang besar di Indonesia itu adalah mereka yang --kalau tidak sedang
bermasalah-- berpotensi bermasalah. Mereka menyumbang justru karena punya masalah.
Karena sedang digebukin dan masuk headline, maka mereka menyumbang WWF guna
menetralisir gebukannya. Jadi, bukan menyumbang karena sudah baik dan ingin berbuat lebih
baik.
Jadi WWF Indonesia tidak pernah mengharapkan banyak pemasukan sebagai yayasan.
Bahwa WWF Indonesia bisa memperoleh satu-dua miliar rupiah setahun, itu sudah luar biasa.
Karena WWF Indonesia memperolehnya tanpa paksaan, tanpa intimidasi, dan tanpa
memanfaatkan kedekatan dengan pejabat tinggi militer ataupun sipil. WWF Indonesia juga

tidak oportunistik. Karena, kalau mau mau jadi oportunis, semua perusahaan yang bermasalah
bisa dimintai uang.
Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Sejak menjadi yayasan, keunggulan komparatif WWF Indonesia adalah kehadirannya
di lapangan tidak lagi dilihat sebagai organisasi asing. Paling tidak, WWF Indonesia bisa
berargumentasi bahwa pihaknya bukan organisasi asing, karena faktanya memang berbentuk
yayasan dan semua Dewan Penyantunnya adalah orang Indonesia. Dengan demikian, dalam
berhubungan dengan pejabat dan birokrasi Indonesia, pendekatannya juga lebih enak dan jujur.
Tidak ada yang ditutup-tutupi.
Ini menjadi penting dalam kaitan perkembangan politik dan pemerintahan di Indonesia
pasca jatuhnya rezim Soeharto. Yakni, dengan makin surutnya peranan pemerintah pusat dan
mengemukanya otonomi daerah akhir-akhir. Pemerintah Daerah sampai tingkat Bupati dan
DPRD menjadi pemain-pemain lokal yang ikut menentukan.
Dalam status lama sebagai Kantor Program, jelas WWF Indonesia akan sulit bicara
tentang legislasi di tingkat kabupaten. Padahal otonomi daerah sekarang sudah sampai ke
tingkat itu. Jangankan bicara soal kabupaten, sedangkan untuk mempermasalahkan legislasi
nasional saja WWF Indonesia tidak boleh. Masa sebuah organisasi asing mau mempersoalkan
undang-undang Republik Indonesia atau mau melobi ke DPR? Itu bisa dianggap intervensi
asing. Tapi dalam status baru dengan bentuk yayasan, itu tak lagi menjadi masalah.
Untuk menghadapi isu-isu lingkungan hidup yang semakin terdesentralisasi dan lokal,
status baru WWF Indonesia ini menguntungkan. Namun desentralisasi dan otonomi daerah ini
juga membuat masalah lingkungan menjadi lebih banyak, sehingga pekerjaan WWF Indonesia
juga menjadi lebih berat, dan keberhasilannya lebih kecil.
Sebagai gambaran, adalah program WWF Indonesia di Taman Nasional Kerinci Seblat
(TNKS), yang terbentang di kawasan seluas lebih dari 1,3 juta hektar, dan mencakup sembilan
kabupaten dan empat provinsi di Sumatera bagian selatan. Kawasan ini merupakan taman
nasional terluas di Pulau Sumatera dan nomor dua terluas di Indonesia. TNKS menjadi sangat
penting karena kekayaan keanekaragaman hayatinya, yang memiliki lebih dari 4.000 spesies
tanaman, termasuk bunga bangkai (Raflesia arnoldi) yang terbesar di dunia itu. Sebagai daerah
resapan air bagi sejumlah aliran sungai besar, TNKS memiliki fungsi hidrologis yang penting.
Karena kawasannya yasng amat kuas, vegetasi TNKS juga memiliki peran kritis dalam
menstabilkan cuaca regional, mencegah banjir, erosi dan tanah longsor.
Bayangkan, betapa rumitnya mengkoordinasikan kegiatan konservasi di wilayah yang
begitu luas, serta mencakup begitu banyak kabupaten dan provinsi, yang masing-masing
sedang sangat bersemangat menerapkan otonomi daerah. Apalagi, selama ini pemerintah
daerah dan masyarakat setempat merasa tidak pernah memperoleh manfaat ekonomi dari
sumberdaya alam tersebut. Dalam pandangan mereka, upaya konservasi justru akan makin
menyulitkan mereka dalam menggali sumber pendapatan potensial.
Kesulitan dalam menangani kawasan konservasi yang sangat luas di daerah, termasuk
mengubah kekeliruan cara pandang para pejabat daerah dan masyarakatnya tentang makna
konservasi, tidak mungkin ditangani secara efektif dari kantor WWF Indonesia di Jakarta.
Untunglah, sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah itu dibuat, tanpa sengaja WWF
Indonesia sudah mendesentralisasikan diri. Kegiatan kantor WWF Indonesia yang sebelumnya

semua dipusatkan di Jakarta, sebelum tahun 1998, telah dipecah ke dalam beberapa kantor
kawasan hayati.
Untuk Indonesia bagian timur, khususnya di Papua, administrasi dan manajemennya
semua dilakukan di Jayapura. Untuk Jawa, Kalimantan dan Sumatera, administrasi dan
manajemennya dilakukan di Balikpapan. Sedangkan untuk daerah di antaranya –Bali, Nusa
Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Sulawesi-- administrasi dan
manajemennya dari Denpasar.
Jadi kantor-kantor di Balikpapan, Denpasar, dan Jayapura itu diperlengkapi dengan --
selain direktur—juga dukungan kemampuan manajemen untuk administrasi, keuangan,
pengelolaan proyek, dan segala macam. Juga ada ahli komunikasi, konservasi, biologi, yang
setingkat master atau doktor, dan ahli prakarsa kebijakan (policy). Jadi sangat terdesentralisasi.
Masing-masing kantor itu tidak hanya bekerjasama dengan masyarakat setempat, tetapi juga
dengan pemerintah daerah dan LSM, sejauh masih terlingkup dalam upaya konservasi dalam
arti luas. Sedangkan Kantor Pusat di Jakarta mengkoordinasikan aktivitas dari ketiga kantor
tersebut.
Maka, begitu UU Otonomi Daerah dikeluarkan, mereka telah siap. Semuanya ditangani
dengan baik, dan WWF Indonesia sudah melengkapi ketiga kantor tersebut dengan berbagai
data lokal. Data ini memang tidak untuk semua tempat, namun hanya di kawasan yang menjadi
prioritas WWF Indonesia. Sehingga WWF Indonesia bisa langsung merasa "tersambung"
dengan berbagai isu lingkungan yang mencuat di daerah.
Tentu, ketersambungan ini tidak lantas berarti semua masalah menjadi beres begitu
saja. Tapi kalau WWF Indonesia belum terdesentralisasi, memang penanganan masalah akan
lebih berat. Desentralisasi sudah menjadi kebutuhan WWF Indonesia sekarang ini, dan harus
tetap dijalankan dengan dukungan kelengkapan teknisnya.
Kalau tak ada desentralisasi, banyak kebijakan yang merusak alam di berbagai daerah
akan lolos begitu saja. Hal itu terjadi karena yang mempengaruhi kebijakan adalah pengusaha-
pengusaha yang berniat buruk. Mereka akan mengubah tata ruang, membabat hutan,
mengambil kayu, dan melakukan hal-hal lain yang merusak lingkungan. Jadi kalau WWF
Indonesia tidak hadir di sana guna mengimbangi setiap langkah mereka, segala hasil kerjanya
akan hilang. Dan untuk mengcounter itu tidak mudah, karena WWF Indonesia lebih banyak
dalam posisi defensif ketimbang ofensif.
Sari Ayu pun Ikut Mendukung
Misi utama WWF adalah tercapainya perlindungan dan pelestarian alam serta proses-
proses ekologinya. Hal ini dicapai melalui tiga cara. Pertama, perlindungan keanekaragaman
genetik dan ekosistem. Kedua, pemanfaatan sumberdaya terbarukan secara lestari, di masa
sekarang maupun di masa mendatang, demi kepentingan semua makhluk di bumi. Ketiga,
menggalakkan upaya pengurangan polusi, eksploitasi, dan konsumsi sumberdaya alam serta
energi yang berlebihan, sampai ke tingkat minimum.
Tujuan utama WWF adalah menghentikan laju kerusakan lingkungan alami di bumi ini,
dan kalau bisa bahkan memulihkannya kembali, serta membantu membangun suatu masa
depan di mana manusia dapat hidup harmonis dengan alam.

Sasarannya adalah membantu mendukung dan melestarikan keanekaragaman alam,
untuk generasi sekarang dan masa mendatang. Tujuannya, melindungi faktor-faktor utama
lingkungan hidup, untuk konservasi keanekaragaman hayati dan mengurangi pengaruh negatif
manusia terhadap alam.
Dalam kaitan itu, strategi yang diterapkan WWF di Indonesia adalah membantu
menciptakan dan melestarikan sistem yang efektif dan berkelanjutan, untuk cagar alam. Juga
mempromosikan praktek-praktek pembangunan yang berkelanjutan, sehingga terjadi kaitan
antara pelestarian dan kebutuhan manusia. Juga, upaya pelestarian spesies hidupan liar dan
populasi yang penting.
WWF Indonesia mendukung dikuranginya konsumsi sumber-sumber alam dan polusi,
dengan mempengaruhi kebijakan publik, serta praktek konsumen, bisnis dan industri. Serta
mendorong pelaksanaan perjanjian internasional, kebijaksanaan nasional dan perundang-
undangan yang mendukung konservasi dan lingkungan hidup. Terakhir, memajukan
pendidikan lingkungan dan pengembangan kemampuan, yang memungkinkan orang untuk
mengelola sumberdaya alam --yang menjadi tempat bergantungnya kehidupan-- secara
berkesinambungan.
WWF Indonesia saat ini aktif di 19 kawasan konservasi (laut dan terestrial) di
Indonesia. Anggaran tahun 1996 sekitar empat juta dollar AS, di mana proporsi yang lebih
banyak diperoleh dari dana multilateral, bilateral, dan swasta. Pada tahun fiskal 1996, sekitar
dua persen dari anggaran ini diperoleh dari sumber-sumber di Indonesia.
Jumlah total stafnya adalah 300 orang, yang terbagi: di Sumatera (120); Papua (60);
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Bali dan Jawa (70); dan Jakarta (50). Jika dibagi
berdasarkan kewarganegaraan, pembagiannya adalah: 285 warga Indonesia dan 15 warga
negara asing. Dari tingkat pendidikan, mayoritas 150 staf berlatar pendidikan sarjana (S-1), 20
master (S-2), dan sembilan doktor (S-3). Sisanya, 16 dari jenjang pendidikan D3, 63 dari SMA,
18 dari SMP dan 24 dari SD.
Organisasi WWF Indonesia terbagi dalam enam departemen: Kebijaksanaan dan
Dukungan Teknis; Administrasi Proyek; Pendidikan Lingkungan Hidup dan Komunikasi;
Pengembangan Dana; Keuangan; serta Administrasi dan Personalia.
Departemen Kebijaksanaan dan Dukungan Teknis ini mendukung inisiatif program dan
kebijaksanaan nasional dan regional dalam bidang konservasi. Unit ini juga menyediakan
petunjuk, bantuan teknis, dan pengembangan kapasitas untuk proyek-proyek lapangan WWF
Indonesia.
Inisiatif yang telah dilakukan antara lain: Program Konservasi dan Pembangunan
Terpadu (ICDP), guna mempromosikan program-program yang mendukung pengembangan
secara terus-menerus bersama tujuan konservasi. Kemudian, Konservasi Keanekaragaman
Hayati (CBD), guna mempromosikan implementasi yang cepat dan efektif, serta memantau
Konvensi Keanekeragaman Hayati, terutama di tingkat nasional dan lokal.
Hal lain adalah Konservasi Spesies, yakni mengimplementasikan rencana aksi guna
menjaga spesies yang terancam punah –terutama gajah, harimau, badak, penyu laut dan
orangutan—melalui kampanye kesadaran, perlindungan habitat. Juga, mendukung usaha
pemerintah Indonesia untuk membatasi perdagangan organ-organ tubuh binatang.

Inisiatif ini juga menyangkut kebijaksanaan kelautan di Asia-Pasifik. Seperti, upaya
menggantikan penggunaan sianida dalam metode penangkapan ikan di Asia Tenggara,
terutama di Indonesia dan Filipina. Caranya, dengan mempromosikan metode penangkapan
ikan yang ramah terhadap lingkungan yang berkelanjutan, melalui kebijaksanaan, proyek
lapangan, dan memantau perdagangan.
Dalam hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat dan daerah, yang
memiliki program kawasan konservasi kelautan, WWF Indonesia mengadakan koordinasi dan
lobi dengan instansi terkait. Terutama dalam menangani dan memecahkan persoalan-persoalan
yang muncul di kawasan konservasi tersebut.
WWF Indonesia juga mengembangkan Sistem Informasi Geografis (GIS), yang
mengintegrasikan peta digital dan data lain yang tersedia, sehingga mendukung penggambaran
kondisi pelestarian alam di Indonesia secara lebih utuh. Data lain tersebut, misalnya,
penyebaran spesies dan habitat, status kawasan lindung, dan informasi lain tentang kawasan
lindung.
Departemen Pendidikan Lingkungan Hidup dan Komunikasi mempromosikan
kesadaran konservasi dan pendidikan lingkungan kepada publik secara keseluruhan, dan juga
kepada publik tertentu di Indonesia. Aktivitasnya termasuk kampanye kesadaran media cetak,
yakni penerbitan majalah dwibahasa Conservation Indonesia, distribusi buku dan poster,
pemasangan iklan layanan masyarakat, dan distribusi artikel feature untuk media lokal.
Media elektronik tentu tak bisa ditinggalkan. WWF Indonesia memproduksi beberapa
acara bincang-bincang mingguan di 600 stasiun radio swasta, menyediakan berita dan berita
utama di stasiun-stasiun radio daerah, serta mendukung LSM-LSM lokal, untuk
mengembangkan sendiri program radio mereka. WWF Indonesia juga memasang iklan layanan
masyarakat di stasiun televisi swasta, serta mengembangkan program televisi mengenai
lingkungan.
Program pendidikan lingkungan yang telah diproduksi, termasuk program televisi
Bumiku Satu, sebuah serial terdiri dari 13 episode yang masing-masing sepanjang 13 menit.
Lewat serial yang disiarkan di stasiun televisi nasional pada Juli-Oktober 1999 ini, pesan
konservasi WWF sampai ke rumah 20 juta penduduk Indonesia. Program ini dirancang untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya yang berusia muda antara 15-25 tahun,
tentang keberadaan WWF Indonesia, serta menambah jumlah keanggotaan dan basis bagi
penggalangan dana.
Dalam upaya menyebarkan pesan-pesan konservasi, WWF Indonesia juga meluncurkan
situs dan perpustakaan digital yang bisa diakses lewat internet. Situs ini memberi informasi
tentang berbagai kegiatan WWF di Indonesia, keanggotaan, peluang kerja, dan galeri foto.
Situs WWF Indonesia juga mempunyai link dengan situs WWF Internasional di
www.wwf.or.id atau Panda.org, yang memiliki 15.000 halaman informasi dan secara terus-
menerus diperbarui.
WWF Indonesia juga mendukung upaya pemerkayaan kurikulum sekolah. Yakni,
dengan pembuatan dan distribusi materi pendidikan lingkungan, bekerjasama dengan
Departemen Pendidikan Nasional dan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Departemen Pengembangan Institusi dan Pengumpulan Dana mempromosikan berbagai
aktivitas WWF Indonesia, serta mencari dana guna mendukung program yang ada. Jenis

aktivitasnya beragam. Sejak tahun 1995, misalnya, melalui program Kerabat WWF, terkumpul
dana ribuan dollar dengan mendaftarkan ratusan anggota (fee minimum Rp. 50.000).
Perusahaan maupun perorangan dapat berpartisipasi dalam pelestarian lingkunghan, dengan
menjadi anggota Kerabat WWF. Setiap anggota berhak atas diskon 10 persen untuk seluruh
produk WWF Indonesia. Sampai saat ini, Kerabat WWF telah memiliki sedikitnya 731
anggota.
Beberapa perusahaan ternama yang sudah menjadi anggota, di antaranya: Reebok,
Body Shop, Caltex, Hewlett Packard, Conoco Indonesia, Restoran Komodo, PT. Asri Desindo
Intiwidya, dan The Jakarta Post. Bahkan lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan
juga ikut serta, seperti: Jakarta International School, North Jakarta International School, SMU
70, British School, Canadian Women's Association – Jakarta, dan American Women's
Association. Sedangkan melalui program Partners in Conservation, juga sudah terkumpul dana
ribuan dollar.
Pemasukan selain itu, adalah pembentukan lisensi perizinan dengan perusahaan-
perusahaan yang tertarik dalam mempromosikan citra "hijau" dan kesadaran berkonservasi.
Salah satunya adalah dengan Martina Berto (Sari Ayu), yang menghasilkan pendapatan
minimum US$ 45.000/tahun mulai periode 1996/1997.
WWF Indonesia juga bekerjasama dengan berbagai perusahaan, dalam pengumpulan
dana pelestarian lingkungan. Dengan Telkomsel dan Fuji Image Plaza, kerjasama itu adalah
lewat penjualan kartu prabayar Simpati edisi Fauna Indonesia. Dengan pusat perbelanjaan
Metro, kerjasama itu berupa penyediaan fasilitas Metro untuk pameran dan berbagai kegiatan
WWF Indonesia. Sedangkan Mal Taman Anggrek, Jakarta Barat, mengadakan pameran dan
bulan pengumpulan dana untuk WWF Indonesia.
Sejumlah acara khusus juga pernah diadakan untuk penggalangan dana. Termasuk di
antaranya adalah peluncuran perangko seri badak, peluncuran Kodak Film untuk
menyelamatkan harimau Sumatera, serta sebuah kampanye di Bali untuk menyelamatkan
pantai.
Penjualan cenderamata yang berbentuk kerajinan tangan, barang-barang hadiah dan
kartu ucapan, tak boleh dianggap remeh. Untuk tahun anggaran 1996, misalnya, WWF
Indonesia memperoleh US$ 25.000 dari penjualan cenderamata saja. Hingga saat ini, masalah
yang masih dihadapi WWF Indonesia adalah tradisi filantropis untuk masalah konservasi, yang
masih sangat minim di Indonesia, serta konsumerisme "hijau" yang masih dalam tahap awal.
Sedangkan unit manajemen lapangan WWF Indonesia dibagi menjadi tiga koordinator
daerah, yakni untuk Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur. Untuk wilayah Indonesia
Bagian Barat, daerah yang dijadikan sasaran kegiatan adalah: Taman Nasional Gunung Leuser
(Provinsi Sumatera Utara dan Aceh), Taman Nasional Kerinci Selabat (di empat provinsi
Sumatera bagian Selatan), dan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (di Riau).
Untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah, daerah yang dijadikan sasaran kegiatan
adalah: Taman Nasional Ujung Kulon (Jawa Barat), Taman Nasional Betung Karimun
(Kalimantan Barat), Taman Nasional Kayan Mentarang (Kalimantan Timur), Taman Nasional
Laut Taka Bone Rate (Sulawesi Selatan), Cagar Alam Gunung Mutis (Nusa Tenggara Timur),
dan Koservasi Penyu (Bali).

Untuk wilayah Indonesia Bagian Timur, daerah yang dijadikan sasaran kegiatan adalah:
Cagar Alam Yapen Waropen dan Cagar Alam Supiori (sebelah utara Teluk Cenderawasih,
Provinsi Papua), Suaka Margasatwa Jamursba Medi (pantai utara Papua), Cagar Alam
Pegunungan Arfak (Kabupaten Manokwari, Papua), Cagar Alam Lorentz (Provinsi Papua
bagian Selatan), Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih (Papua), Cagar Alam Pegunungan
Cyclops (berbatasan dengan kota Jayapura), Taman Nasional Wasur (berbatasan dengan
negara Papua Niugini), dan Cagar Alam Laut Aru Tenggara.
Dari Harimau Sampai Terumbu Karang
Sejalan dengan prioritas-prioritas global WWF, WWF Indonesia memiliki empat
bidang utama berskala nasional yang ditanganinya, yakni: kehutanan, kelautan, air tawar (fresh
water) dan spesies (satwa). Dalam masalah kehutanan, tujuan nasionalnya adalah pelestarian
dan pengelolaan yang lebih baik terhadap kawasan yang dilindungi di Sumatera, Jawa,
Kalimantan dan Papua. Sasarannya adalah untuk memastikan, agar prinsip pemanfaatan
sumberdaya yang berkelanjutan, perencanaan tata ruang, dan pengelolaan partisipatif
dipraktikkan di kawasan-kawasan tersebut.
Tujuan program kelautan adalah mengurangi ancaman pembangunan terhadap
konservasi laut dan pesisir di tiga kawasan hayati: Dangkalan Sunda, Wallacea dan Sahul. Ada
kemajuan berarti yang tercatat di kawasan tersebut selama tiga tahun terakhir. Termasuk
peningkatan pengawasan terhadap kerusakan terumbu karang, serta pengurangan kegiatan
perburuan ilegal di wilayah laut yang dilindungi tersebut.
Dalam survai terumbu karang tahun 1999, ada indikasi bahwa dari delapan kawasan
yang dipantau oleh 33 stasiun, hanya 5,56 persen terumbu karang Indonesia yang dalam
keadaan baik. Padahal Indonesia, dengan lautannya yang sangat luas, memiliki terumbu karang
seluas 42.000 km persegi atau 16,5 persen dari terumbu karang dunia.
Banyak terumbu karang ini yang rusak atau dieksploitasi, terutama oleh nelayan
komersial yang menggunakan sianida dan bahan beracun lain, untuk menangkap ikan di daerah
terumbu karang tersebut. Penyebab kerusakan lain adalah pengambilan karang untuk souvenir
dan bahan bangunan. Pemantauan sekarang dilakukan lewat Reef Check Indonesia, sebuah
program pemantauan yang dikoodinasikan oleh WWF Indonesia bekerjasama dengan LSM
lain, universitas, operator selam, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Dalam masalah air tawar, tujuannya adalah untuk memperkecil ancaman pembangunan
terhadap kawasan air tawar ini, melalui perencanaan dan pengelolaan berkelanjutan. Sebagian
besar aktivitas difokuskan di kawasan hayati Sahul, di mana diberikan pelatihan terhadap
anggota masyarakat setempat, pihak-pihak yang berkepentingan, dan staf lembaga swadaya
masyarakat (LSM).
Selama 19 tahun terakhir, WWF Indonesia telah aktif di sejumlah taman nasional dan
cagar alam di Papua. Perburuan ilegal telah berhasil dikurangi di lima kawasan laut yang
dilindungi ini. Sementara WWF Indonesia masih terus memperjuangkan pengurangan yang
sama dalam hal tingkat degradasi lingkungan, serta musnahnya habitat dan satwa di kawasan
Sahul.
Sedangkan tujuan kegiatan konservasi satwa WWF indonesia adalah untuk menjamin
agar satwa-satwa yang terancam punah –khususnya harimau Sumatera, gajah Sumatera,

orangutan Kalimantan dan tentu saja badak Jawa—mendapat perlindungan yang memadai di
tiga kawasan hayati tersebut.
Dari ribuan harimau Sumatera, saat ini cuma tersisa 450 harimau, menurut data terakhir
WWF Indonesia. Harimau ini terkonsentrasi di taman-taman naasional. Meski perdagangan
harimau Sumatra dilarang keras, perdagangan ilegal masih terus berlangsung. Harimau
Sumatera terancam punah, seperti nasib yang sudah dialami harimau Jawa dan Bali.
Ancaman terhadap orangutan juga sangat serius. Sejak tahun 1998, populasi orangutan
telah merosot drastis, terutama akibat rusaknya habitat alamiah mereka: hutan hujan-tropika
Indonesia. Lebih dari 80 persen hutan ini rusak dalam dua dasawarsa terakhir. Belum lagi
ditambah kebakaran hutan tahun 1997 dan 1998, yang menghancurkan sekitar 95 persen
habitat utama orangutan.
Dalam masalah penyu, data WWF Indonesia menunjukkan, populasi penyu di Bali
telah menurun drastis dengan tingkat kemerosotan sampai 80 persen, dalam periode 50 hingga
60 tahun terakhir. Pada peralihan abad yang lalu, kawasan ini diperkirakan menjadi tempat
berdiam bagi sepertiga populasi penyu dunia. Kini angka itu sudah merosot jauh, menjadi
hanya lima persen.
WWF Indonesia telah bekerja keras menghapuskan kebiasaan makan sate penyu di
Bali, dan berkat dukungan warga setempat dan para aktivis LSM, sate penyu kini hampir tidak
diperdagangkan lagi secara terbuka. WWF Indonesia juga melobi pemuka masyarakat dan
tokoh agama, untuk mendukung pelestarian penyu Bali, karena ada yang berdalih bahwa
penggunaan penyu dalam berbagai upacara di Bali ini bersifat religius dan budaya. Berkat
pendekatan WWF Indonesia, pembunuhan penyu atas alasan religius dan budaya sudah
berkurang sebesar 80 persen.
Penderitaan gajah Sumatera juga cukup mendesak. Populasi gajah di Sumatera kini
sekitar 2.500 ekor. Namun gajah Sumatera mungkin akan punah, jika tanah yang mereka diami
terus digusur untuk perkebunan kelapa sawit. Antara tahun 1967 hingga 1997, wilayah
perkebunan kelapa sawit telah meluas, dari sekitar 100.000 menjadi 2,5 juta hektar.
Pembentukan suaka gajah di Tesso Nilo, Riau adalah kemungkinan yang bisa dilakukan di
masa depan untuk penyelamatan gajah Sumatera ini.
Sedangkan badak Jawa kini hanya tersisa sekitar 50 ekor di Taman Nasional Ujung
Kulon. Bersama sekitar 360 badak Sumatera, badak-badak ini menjadi sasaran perburuan liar.
Berkat peningkatan patroli satuan-satuan antiperburuan badak yang dibentuk WWF Indonesia,
tidak ada laporan badak yang terbunuh akibat perburuan antara Juli 1999 hingga Juni 2000.
WWF Indonesia menggabungkan berbagai macam pendekatan, untuk mengurangi
tekanan terhadap populasi badak dan habitatnya. Termasuk, antara lain: sensus populasi badak,
pengambilan contoh DNA, patroli di daratan dan pantai, pemantauan terhadap perdagangan
dan pasar gelap, serta mengupayakan tumbuhnya usaha ekonomi bagi penduduk setempat.
Sisi Manusia dalam Konservasi Alam
Dalam semua upaya pelestarian satwa ini, WWF Indonesia tidak melupakan aspek
manusia yang hidup di lingkungan bersangkutan. Maka WWF Indonesia, misalnya, membantu
warga Ujung Kulon setempat untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar dari sektor
pariwisata, dengan memberikan pelatihan tentang pelaksanaan tur dan pengelolaan fasilitas

wisata. WWF Indonesia juga mendukung 22 koperasi unit desa, yang sepenuhnya dikelola oleh
masyarakat setempat –sebagian besar perempuan—di sekitar Ujung Kulon. Dengan demikian,
diharapkan dorongan untuk memburu satwa-satwa yang dilindungi makin diperkecil.
Dalam empat tahun terakhir, seraya meneruskan upaya pelestarian di sekitar 17 taman
nasional dan cagar alam, WWF Indonesia juga telah menerapkan pendekatan kawasan hayati
(bioregional) baru. Hal ini dimaksudkan guna mengkonsolidasikan upaya-upaya konservasi,
dan menangani masalah-masalah yang bercakupan lebih luas. Yaitu, masalah yang berkaitan
dengan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, kualitas lingkungan, dan kualitas
kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam.
Keprihatinan terhadap tiga masalah yang saling berkaitan tersebut telah disalurkan ke
dalam program-program, di tiga kawasan hayati, yakni: Dangkalan Sunda (Kalimantan, Jawa
dan Sumatera), Wallacea (Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku), dan Sahul (Papua).
Kawasan hayati adalah satuan wilayah daratan atau perairan yang memiliki iklim khas, jenis
perilaku dan tingkat keanekaragaman hayati yang mirip, serta spesies-spesies, dengan berbagai
bentuk adaptasi dan ancaman yang mirip terhadap lingkungan mereka.
Ashari, yang juga menjadi pengurus Yayasan Pembinaan Suaka Alam dan Margasatwa
Indonesia (YSI) menjelaskan, dulu langkah konservasi yang diperjuangkan WWF masih
terfokus pada satwa yang terancam punah. Karena satwa itu hidup di hutan, maka hutannya
ikut terbawa juga dalam program konservasi. Namun dalam sejarah konservasi di dunia,
kemudian muncul cara pendekatan lain yang lebih utuh dan menyeluruh. Dalam pendekatan
holistik ini, upaya pelestarian tak bisa lagi terpusat semata-mata pada satwa, mengingat satwa
ini hidup pada suatu wilayah, dan di dalam wilayah ini banyak sistem lingkungannya, sehingga
disebut ekosistem.
WWF Indonesia pun kemudian bergeser dan mengadopsi pendekatan holistik ini, yang
bersifat lebih seimbang. Sekitar 35 proyek lepas WWF Indonesia telah diubah ke struktur
kawasan hayati ini untuk mencakup kawasan darat dan laut yang lebih luas, jauh melampaui
batasan taman nasional, cagar alam, dan bahkan batas-batas wilayah nasional. Yang
diperhatikan WWF Indonesia kini bukan cuma satwa yang terancam punah, tetapi juga
melindungi keanekaragaman hayati, pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan,
penurunan pola konsumsi dan pengurangan pencemaran.
Dalam konteks sekarang dan keterkaitannya dengan cara pendekatan baru tersebut,
WWF Indonesia sedikit memodifikasi visi dan misinya. Yakni, dalam rumusan visi dan misi
baru tersebut, WWF Indonesia mencantumkan isu-isu yang berkaitan dengan peningkatan
pendapatan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan, sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari upaya pelestarian lingkungan. Ini dilakukan karena memang itulah agenda terpenting
Indonesia sekarang. WWF Indonesia mengakui, upaya untuk memelihara dan melestarikan
keanekaraganan alam Indonesia hanya bisa berhasil jika melibatkan masyarakat setempat.
Jadi, persoalannya kemudian adalah bagaimana melestarikan alam dengan sekaligus
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena, dengan masyarakat yang sejahtera,
kemungkinan alamnya juga menjadi lebih lestari. Dengan upaya pelestarian yang sekaligus
mendatangkan pendapatan, keduanya diuntungkan. "Jadi agenda pengentasan kemiskinan itu
masuk. Agenda itu tidak akan ada secara otomatis, kalau WWF Indonesia adalah organisasi
konservasi internasional. Greenpeace tidak punya program penghapusan kemiskinan. Friends
of the Earth saya rasa juga tidak ada," ujar Agus, yang pernah aktif di Yayasan Pelangi dan
Rockefeller Foundation.

Tantangan Masa Mendatang
Meskipun Indonesia dihantam krisis ekonomi dan politik yang parah dan berlarut-larut,
operasi-operasi lapangan WWF Indonesia sebagian besar tak banyak terganggu. Sejumlah
program memang harus dijadwalkan ulang dalam beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah
yang paling banyak terpengaruh oleh kerusuhan dan aksi kekerasan, seperti di Maluku dan
Kalimantan Tengah. Namun sesudah kondisi membaik, program-program itu berjalan lagi.
Beberapa kalangan donor yang prospektif juga sempat bimbang, untuk berinvestasi
dalam program pelestarian alam jangka panjang. Hal ini disebabkan mereka merasa tidak pasti
dengan kelangsungan bisnisnya selama krisis ekonomi Indonesia. Namun sesudah
penyelenggaraan Pemilu 1999 --Pemilu demokratis pertama sejak era Orde Baru—yang relatif
aman, kepercayaan kalangan donor meningkat.
Tantangan yang dihadapi WWF Indonesia untuk lima tahun ke depan adalah,
bagaimana mengangkat masalah konservasi ini dalam satu paket dengan upaya memberantas
kemiskinan. Pengikutsertaan isu pengentasan kemiskinan tersebut semakin tidak bisa dihindari
dalam konteks sekarang. Jadi WWF Indonesia juga perlu punya keterampilan untuk bicara
tentang pembangunan. Mungkin tidak harus WWF Indonesia sendiri yang melakukannya.
Namun, WWF Indonesia harus bisa menggandeng mitra yang memang pelaku pembangunan.
Bisa saja itu organisasi seperti CARE, OXFAM, atau siapa saja yang memang bekerja di
bidang pembangunan ekonomi masyarakat. Bahkan, bisa juga dengan lembaga seperti Bank
Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), atau bahkan perusahaan-perusahaan swasta.
Komponen pembangunannya itu harus ada. Namun WWF Indonesia bukan ahli
pembangunan, dan tidak berpretensi untuk bisa membangun jalan, jembatan, dan lapangan
terbang, misalnya, walaupun mungkin itu yang diminta masyarakat. Sehingga, yang dilakukan
WWF Indonesia adalah menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang bisa melakukan
pembangunan, dan pada saat yang sama memberikan arahan-arahan atau batasan, agar program
pembangunan yang dijalankan itu sejalan dengan atau mendukung upaya pelestarian alam.
Tantangannya, saat ini justru sulit menemukan investor yang bisa diajak bermitra.
Dalam situasi transisi politik Indonesia yang belum stabil seperti sekarang, di mana
Presidennya sudah tiga kali berganti sejak gerakan reformasi tahun 1998, begitu juga menteri-
menterinya, ditambah kondisi keamanan yang tidak kondusif, investor-investor yang
diharapkan jadi tidak kunjung muncul. Sedangkan pihak yang masih mau berinvestasi
bukanlah investor jangka-panjang untuk pembangunan, tetapi mereka yang mau mencuri kayu
atau merusak hutan.
Tantangan berikutnya adalah soal penegakan hukum. Itu sifatnya mutlak. "Nah,
susahnya 'kan aparat keamanan kita lebih merupakan masalah daripada solusi. Sehingga kita
mesti mencari cara. Kita harus bereksperimen beberapa tahun, bagaimana agar penegakan
hukum itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Bagaimana agar proses pengelolaan
lingkungan itu tidak secara kuno: pemerintah mengelola, masyarakat menikmati, aparat
penegak hukum yang menjaga," ujar Agus.
Karena Pemerintah tidak punya anggaran, orangnya tidak ada, dan aparat hukumnya
juga tak bisa dipegang, muncul gagasan ke arah pengelolaan bersama (co-management).
Masyarakat ikut mengelola lingkungan, sehingga masyarakat diharapkan akan ikut
menjaganya. Tentang apakah gagasan itu akan berhasil, perlu dua-tiga tahun untuk
membuktikan. Tetapi, dengan rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi

program, serta lemahnya penegakan hukum, tak ada pilihan lain. Karena jika WWF Indonesia
hanya diam, hutan akan rusak. Jadi lebih baik berusaha membuat hal yang baru.
Satu hal yang sejak awal disadari, WWF Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Jadi,
kemampuan membangun kerjasama dan memperoleh mitra-mitra baru itu penting. WWF
Indonesia tak bisa eksklusif, walaupun selama ini juga sudah tidak eksklusif. WWF Indonesia
bergaul dengan siapa saja: LSM, pengusaha, Bank Dunia, dan pemerintah. Basis untuk
kerjasama itu memang sudah dikembangkan sejak lama. Sekarang tinggal mengembangkan
kemampuan untuk mengerjakan hal yang kongkret bersama.
Pemerintah sudah membuka pintu terhadap WWF Indonesia Maka, persoalannya
kemudian adalah bagaimana mengisi peluang itu dengan kegiatan konkret. Masalahnya,
kegiatan itu butuh uang dan uang itu tidak akan datang dari pemerintah. Uangnya harus WWF
yang mencarikan. Memang, tantangannya kemudian adalah bagaimana mencari uang untuk
membiayai kemitraan-kemitraan, dan untuk memperkuat kelembagaan lokal.
Agus memberi contoh, di Papua –salah satu wilayah garapan WWF Indonesia yang
terpenting-- ada lima atau enam organisasi yang diciptakan WWF Indonesia, karena tak ada
LSM lokalnya. Sumberdaya manusia di kawasan itu juga lemah. Maka, staf WWF Indonesia
disuruh bekerja dan bertahan di sana, untuk memperkuat organisasi tersebut. Kepada
organisasi itu diberi hibah dan disubsidi. "Jadi kita sampai melakukan itu. Kita potong satu jari
untuk bikin di sana, potong lagi jari lain untuk bikin di sini," tutur Agus, untuk
menggambarkan betapa sulitnya membangkitkan kelembagaan lokal tersebut. Kadang-kadang
upaya menghidupkan kelembagaan lokal ini berhasil, namun sering juga gagal.
Pola ini memang harus diperbanyak dan dicari sumber-sumber baru, untuk memperkuat
kelembagaan yang dibuat tersebut. Jika dilepas begitu saja pada saat sekarang, lembaga-
lembaga lokal itu akan mati. Namun jika tidak dilepas, memberatkan juga bagi WWF
Indonesia. "Tapi kalau mereka mati, dan kita juga sudah pergi, hancurlah sumberdaya alam di
sana. Sepuluh tahun lebih kita bekerja, hilang tak ada bekasnya. Karena kalau menebang hutan
itu, sebulan juga sudah cukup untuk menghabiskan hutan yang kita pelihara selama 10 tahun,"
tutur Agus.
Di masa mendatang, langkah dan kiprah WWF Indonesia dalam upaya pelestarian alam
di Indonesia tidak akan menjadi lebih ringan. Besar kemungkinan, justru akan menjadi lebih
berat karena perkembangan tantangan yang dihadapi. Namun perjalanan organisasi WWF
Indonesia, yang secara tak langsung juga mencerminkan dinamika dan kompleksitas
permasalahan lingkungan hidup di negeri ini, akan terus berlanjut.
Karena, dengan cara itu, WWF Indonesia akan dapat ikut memberi sumbangan bagi
pelestarian alam Indonesia, sekaligus menyejahterakan manusianya. Dan dengan demikian,
seperti dikatakan Haroen Al Rasjid, "WWF Indonesia telah membuktikan sekali lagi, bahwa
dimungkinkan adanya sinergi antara rakyat dan kesejahteraan alam yang melingkupi mereka."
***
Jakarta, November 2002
*Ditulis sebagai bagian dari kerjasama (kontrak tugas penulisan) antara WWF Indonesia
selaku pemberi dengan Satrio Arismunandar selaku penulis. Tulisan ini sudah diterbitkan oleh
WWF Indonesia.

Biodata Penulis:
* Satrio Arismunandar adalah anggota-pendiri Aliansi Jurnalis Independen atau AJI (1994), Sekjen AJI (1995-
97), anggota-pendiri Yayasan Jurnalis Independen (2000), dan menjadi DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(SBSI) 1993-95. Pernah menjadi jurnalis Harian Pelita (1986-88), Kompas (1988-1995), Majalah D&R (1997-
2000), Harian Media Indonesia (2000-Maret 2001), Produser Eksekutif Divisi News Trans TV (Februari 2002-
Juli 2012), dan Redaktur Senior Majalah Aktual – www.aktual.co (sejak Juli 2013). Alumnus Program S2
Pengkajian Ketahanan Nasional UI ini sempat jadi pengurus pusat AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) 2002-
2011.
Kontak Satrio Arismunandar:
E-mail: [email protected]; [email protected]
Blog pribadi: http://satrioarismunandar6.blogspot.com
Mobile: 081286299061