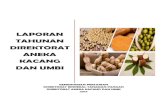· Web view., (2012) hal ini dimungkinkan karena kacang bogor termasuk dalam kacang-kacangan yang...
Transcript of · Web view., (2012) hal ini dimungkinkan karena kacang bogor termasuk dalam kacang-kacangan yang...
(MINI BOOKBIOTEKNOLOGI TANAMAN LANJUTANDosen Pengasuh : Dr. Noer Rahmi Ardiarini, SP.,MP.Mahasiswa: Ika Dyah SaraswatiPRODI PEMULIAAN DAN BIOTEKNOLOGI TANAMANPROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS BRAWIJAYAMALANG 2014)
BAB I BIOTEKNOLOGI UNTUK KACANG BOGOR
A. Asal Kacang bambara
Kacang Bambara mulanya berasal dari daerah Bambara, Niger Afrika dan dikenal sebagai kacang tanah dengan bentuk polong yang bulat. Menurut Rukmana dan Oesman (2000), nama yang diberikan oleh para ahli botani bermacam macam, misalkan Linnaeus di tahun 1763 memberikan nama Glycine subterra selanjutnya Du Patit Thouars tahun 1806 memberikan nama Voandzria subterranea dan saat ini berkembang dengan nama ilmiah Vigna subterranea atas peran (Verdcourd, 1970) yang menyatakan bahwa kacang bogor atau kacang Bambara ini lebih cenderung memiliki kemiripan dengan genus Vigna. Meskipun secara hasil kacang ini berpotensi panen lebih rendah dari genus Vigna yang lain, menurut Rungnoi et al., (2012) hal ini dimungkinkan karena kacang bogor termasuk dalam kacang-kacangan yang sering ditanam di lahan marginal atau sering disebut sebagai landrace crop. Mukakalisa (2010) juga menambahkan bahwa bambara yang ditanam di daerah semi-arid Afrika berdaya hasil rendah dengan rata-rata hasil hanya 300-800 kg/ha, hal ini berhubungan dengan distribusi hujan, temperatur udara yang ekstrim, tanah yang miskin hara, serangan hama penyakit, dan teknik budidaya yang buruk.
Tanaman asli Nigeria ini selanjutnya tersebar di berbagai negara misalkan Srilanka, Brasil, India, Malaysia, Indonesia, dan Australia. Di Indonesia, kacang Bambara untuk pertamakali dapat beradaptasi dengan baik di Bogor sehingga saat ini disebut sebagai kacang Bogor. Perkembangan kacang Bogor di Indonesia tidak terbatas di Bogor saja tetapi juga berkembang di daerah lain seperti Sukabumi dan Bandung sehingga terkadang juga disebut sebagai kacang Bandung, Liu (2010) menambahkan terkadang kacang Bogor juga dikenal dengan nama kacang manila, kacang gengge, kacang baleud, dan kacang banten. Menurut Rukmana dan Oesman (2000), kacang Bogor juga berkembang di daerah Pati, Kudus, Lampung, NTB dan NTT. Menurut Chomchalow (1993), kacang bogor termasuk dalam jenis kacang-kacangan yang toleran terhadap keadaan tanah yang kurang subur sehingga banyak ditanam di daerah dengan kesuburan rendah dan kering.
B. Anatomi dan Morfologi Kacang Bambara
Kacang bambara atau bogor membutuhkan waktu paling tidak 7-15 hari untuk berkecambah. Benih yang disimpan paling lama adalah 12 bulan saja, selebihnya benih dapat kehilangan viabilitasnya. Setelah tanaman melewati masa vegetatif selanjutnya masa pembungaan terjadi antara 30-35 hst dan termasuk dalam tanaman berhari pendek. Polong dan biji terbentuk sekitar 30-40 hari setelah terjadinya fertilisasi. Polong terbentuk di atas permukaan tanah, sekitar 30 hari setelah fertilisasi lalu 10 hari berikutnya biji mulai terbentuk. Biji masak saat jaringan parenkim yang menutupi embrio hilang dan polong berubah warna menjadi coklat cerah. Sementara Nishitani et al., 1981 dalam Ratih (1991) dalam Hamid (2009) menambahkan bahwa pembungaan pada kacang bogor terjadi pada 55 hst pada musim hujan dan 45 hst pada musim kemarau. Pemanenan biasanya dapat dilakukan saat 80% dari polong masak dan siap dipanen (Swanevelder, 1998). Berchie et al., (2010) menambahkan bahwa siklus hidup secara lengkap kacang bogor memerlukan waktu selama 110 hingga 150 hari untuk pertumbuhan dan perkembangannya, meskipun pernah tercatat di Ghana semua siklus hanya membutuhkan 90 hari dari tanam hingga panen, sedangkan Karikari et al., (1995) dalam Hamid (2009) menambahkan bahwa biji masak fisiologis pada umur antara 120-155 hst.
Rukmana dan Oesman (2000) menjelaskan bahwa tanaman kacang bogor termasuk dalam famili kacang-kacangan yang berbunga kupu-kupu (Papilionaceae). Secara morfologi, kacang bogor memiliki bagian akar, batang, daun, dan polong.
Menurut Rukmana dan Oesman (2000), akar tanaman menyebar ke segala arah, rata-rata kedalaman sebaran akar adalah 30 cm. Kacang bogor termasuk dalam kacang-kacangan sehingga akar tanamanannya dapat bersimbiosis dengan bakteri penambat N Rhizobium dan membentuk bintil-bintil pada akar dan merupakan pengganti pupuk nitrogen. IPGRI (2000) menambahkan bahwa akar kacang bogor adalah perakaran lateral yang menyebar dan bersifat geotropikal.
Kacang bogor memiliki batang yang pendek dan berjumlah banyak. Cabangnya ada yang berwarna merah muda, ungu atau hijau kebiruan (Doku dan Karikari, 1971). Cabang tanaman kacang bogor merupakan salah satu bagian yang mendukung potensi hasil kacang bogor, rata-rata cabang tanaman kacang bogor terdiri atas ruas-ruas, rata-rata jumlah ruasnya 12 ruas. Ezedinma dan Maneke (1985) mengelompokkan kacang bogor menjadi tiga kelompok didasarkan pada diameter tutupan kanopi yaitu bunch 40 cm, semi bunch 40-80 cm dan open lebih dari 80 cm.
Daun kacang bogor berbentuk lonjong dan berwarna hijau muda hingga hijau tua, setiap tangkai daun terdiri dari 3 helai daun disebut sebagai trifoliat. Rata-rata panjang daun 6 cm dan rata-rata lebar daun 3 cm (Rukmana dan Oesman, 2000).
Kacang bogor termasuk dalam tanaman menyerbuk sendiri dan kelamin jantan dan betina berada dalm satu bunga yang sama, susunan kromosmnya yaitu dengan rumus 2n=2x=22 kromosom. Bunga kacang bogor muncul dari ketiak daun sehingga dalam satu rumpun kacang bogor akan muncul banyak bunga. Bunganya terdiri atas 5 kelopak dengan 4 kelopaknya terletak di atas dan hampir bergabung sementara 1 kelopak terletak di bawah (IPGRI, 2000). Bunga kacang bogor berwarna putih kekuningan saat pagi dan berubah menjadi kuning kecoklatan saat menjelang malam. Doku dan Karikari (1971) menjelaskan bahwa kematangan pollen dan reseptifitas stigma terjadi sebelum hingga saat sayap petal atau petal standart telah terbuka. Saat petal standart terbuka ½ atau lebih dari lebar bunga maka pollinasi terjadi. Meskipun termasuk tanaman menyerbuk sendiri, tanaman kacang bogor dapat kawin silang dengan bantuan serangga semut. Saat bunga membuka, semut akan masuk dengan membawa pollen. Selanjutnya setelah pembungaan dan pembuahan, tangkai bunga akan memanjang ke dalam tanah, membentuk genofor dan membentuk buah yang berupa polong (Fachruddin, 2000).
Menurut Duke et al., (1977) dan Mergeai (1986) kultivar kacang bogor dapat dibedakan berdasarkan morfologinya yaitu meliputi ukuran polong, adanya kerutan pada polong, ukuran biji, warna biji, jumlah polong per tanaman dan warna daun. Polong melekat pada tangkai panjang dan berbentuk bulat. Setiap polong berisi satu biji meskipun ada beberapa yang berbiji dua hingga tiga biji per polong. Polong kacang bogor saat masih muda berwarna putih susu dan berubah putih kecoklatan saat tua. Polongnya berbentuk membulat dan berkerut-kerut dengan panjang berkisar antara 1-1,5 cm. Umumnya dalam satu polong terisi satu hingga dua biji (Rukmana dan Oesman, 2000).
Biji kacang bogor umumnya membulat, halus dan keras jika telah masak dan kering. Warna bijinya bervariasi yaitu putih, kuning, ungu (Linneman dan Azam-Ali, 1993), krem, coklat, kehitaman, merah atau ada juga yang bercorak tutul-tutul (Rukmana dan Oesman, 2000). Kacang bogor adalah tanaman berkeping dua atau dycotiledone dengan struktur bijinya seperti kebanyakan kacang-kacangan yang terdiri dari kulit biji (spermodermis), tali pusat (feniculus) berwarna keputih-putihan, dan inti biji (nucleus seminis) yang merupakan cadangan makanan (Rukmana dan Oesman, 2000).
Meskipun kacang bogor termasuk dalam tanaman landrace yang dapat bertahan hidup pada kondisi kekurangan hara dan air namun menurut Astawan (2009), kacang bogor memiliki syarat tumbuh optimum yaitu ketinggian tempat 1600 meter di atas permukaan laut, suhu udara 19-27oC, pH tanah 5,0-6,5 dan curah hujan antara 500- 3500 mm per tahun.
C. Pengembangan Bioteknologi Kacang Bambara
Pengembangan bioteknologi kacang bambara saat ini sudah semakin banyak, hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu genetik melalui beberapa cara misalkan melalui teknik kultur jaringan, mutasi, transformasi genetik dan MAS (Marker Assist Selection). Teknik kultur jaringan dilakukan sebagai awal dari pelaksanaan kegiatan bioteknologi yang lainnya, misalkan mutasi, transformasi genetik dan memperpendek siklus hidup. Mutasi dilakukan untuk meningkatkan keragaman dalam kacang bambara, sementara transformasi genetik dilakukan untuk meningkatkan mutu genetik dengan cara mengintroduksikan gen baru. MAS adalah teknik yang digunakan dalam membantu proses seleksi gen secara molekuler, ada banyak tipe MAS yang sudah dilakukan untuk identifikasi karakter secara molekular pada kacang bambara.
Daftar pustaka
Berchie J.N., J. Sarkodie –Addo, H. Adu-Dapaah, A. Agyemang, S. Addy, E. Assare, and J. Donkor. (2010), Yield Evaluation Of Three Early Maturing Bambara Groundnut (Vigna Subterranea L. Verdc.) Landraces at The Csir-Crops Research Institute, Fumesua-Kumasi, Ghana. J. Agric. Sci. 9: 175 - 179
Chomchalow, N. 1993. Bambarra Groundnut. In Prociding FAO/UNDP project/RAS/89/040 Workshop Underxploited dan Potencial Food Legumes in Asia “ Food dan Agriculture Organization of the United Nation Regional Office for Asia dan Pacific, Bangkok. Thailan. pp. 30-34
Doku, E.V. and S.K. Karikari. 1971. Bambara Groundnut. J. Agric. Sci. Hamid (2009)
Duke, J.A., B.N. Okigbo, C.P. Reeds dan J.K.P. Weder. 1977. Bambara Groundnut (Vodanzeia subterranea (L). Thours). J. Agric. Sci, 10: 8-10.
Liu, H. 2010. Kacang Bogor Sehat dan Enak. Available at: File://localhost/F:/Bambara/Kacang-Bogor-Sehat-dan-Enak.html
Mukakalisa, C., 2010. Molecular, Environmental And Nutritional Evaluation Of Bambara Groundnut (Vigna Subterranea (L.) Verdc.) For Food Production In Namibia. Ph.D. Thesis. The University Of Namibia. Namibia
Rukmana, R., dan Y.Y. Oesman., 2000. Kacang Bogor: Budidaya dan Prospek Usahatani. Kanisius. Jogjakarta
Rungnoi, O., J. Suwanprasert, P. Somta and P. Srinives. 2012. Molecular Genetic Diversity Of Bambara Groundnut (Vigna subterranea L. Verdc.) Revealed By Rapd and Issr Marker Analysis. Sabrao. J. Breed. Genet. 44 (1) 87-101
Swanevelder, C.J., 1998. Bambara: food for Africa (Vigna subterranea . bambara groundnut). National Department of Agriculture. ARC- Grain Crops Institute. Pretoria South Africa
BAB II KULTUR EMBRIO KACANG BOGOR
A. Pendahuluan
· Kultur Jaringan
Kultur jaringan atau Kultur In Vitro adalah suatu teknik untuk mengisolasi, sel, protoplasma, jaringan, dan organ dan menumbuhkan bagian tersebut pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh tanaman pada kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman sempurna. Kultur jaringan disebut juga sebagai kultur in vitro karena jaringan dibiakkan di dalam tabung kaca, botol kaca, cawan Petri dari kaca, atau material tembus pandang lainnya.
Kultur jaringan tanaman secara teoritis dapat dilakukan terhadap semua jaringan, namun masing-masing jaringan memerlukan komposisi media tertentu. Dasar teori teknik kultur jaringan adalah teori Totipotensi Sel yaitu bahwa setiap sel memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu yang sempurna apabila diletakkan pada lingkungan yang sesuai.
Metode kultur jaringan dikembangkan untuk membantu memperbanyak tanaman, khususnya untuk tanaman yang sulit dikembangbiakkan secara generatif. Bibit yang dihasilkan dari kultur jaringan mempunyai beberapa keunggulan, antara lain: mempunyai sifat yang seragam dan identik dengan induknya, dapat diperbanyak dalam jumlah yang besar tanpa membutuhkan tempat yang luas, mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar dalam waktu yang singkat, kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin, kecepatan tumbuh bibit lebih cepat dibandingkan dengan perbanyakan konvensional, pengadaan bibit tidak tergantung musim, biaya pengangkutan bibit relatif lebih murah dan mudah.
· Metode Kultur Jaringan
Prinsip utama dari teknik kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman menggunakan media buatan yang dilakukan dalam wadah yang steril. Dengan demikian Kultur Jaringan Tanaman dapat didefinisikan sebagai teknik menumbuh kembangkan bagian tanaman, baik berupa sel, jaringan maupun organ dalam kondisi aseptik secara in vitro.
Dalam pelaksanaannya, mikropropagasi dilakukan di dalam suatu laboratorium yang terjaga sterilitasnya. melalui beberapa tahapan:
· Tahap 0 – preparasi yang terdiri atas proses pemilihan dan persiapan tanaman induk, pembuatan media tanam dan sterilisasi bahan tanaman
· Tahap I - inisiasi dilakukan dengan persiapan eksplan
· Tahap II – inokulasi dilakukan dengan penanaman eksplan pada media tanam
· Tahap III - inkubasi dilakukan dengan multiplikasi (perbanyakan) tunas dan menumbuhkan akar
· Tahap IV – Aklimatisasi dilakukan dengan proses adaptasi pada lingkungan luar botol
· Eksplan
Eksplan adalah bagian dari tanaman yang digunakan dalam mikropropagasi atau kultur jaringan tanaman. Seluruh bagian tanaman (daun, batang, dan akar) dapat dipergunakan sebagai eksplan, namun yang biasanya dipergunakan adalah meristem (jaringan muda), mata tunas dan tunas pucuk (shoot tip). Eksplan dapat juga berupa embrio (kelapa), benih (anggrek), biji (sengon), umbi (wortel), keping biji (kotiledon), benang sari dan putik.
Pembuatan eksplan dari bahan induk dilakukan dengan mempergunakan peralatan yang bersih dan tajam. Eksplan selanjutnya dibawa ke dalam laboratorium untuk dilakukan sterilisasi. Tahapan sterilisasi, bahan sterilisasi, dan durasi sterilisasi tiap jenis eksplan tidak sama, namun secara umum sterilisasi eksplan dilakukan dengan mencuci eksplan dalam air bersih yang mengalir.
· Media Tanam
Media merupakan faktor utama dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media adalah tempat bagi jaringan untuk tumbuh dan mengambil nutrisi yang mendukung kehidupan jaringan. Media tumbuh menyediakan berbagai bahan yang diperlukan jaringan untuk hidup dan memperbanyak dirinya.
Media yang digunakan biasanya terdiri dari unsur hara makro dan mikro dalam bentuk garam mineral, vitamin, dan zat pengatur tumbuh (hormon). Selain itu, diperlukan juga bahan tambahan seperti gula, agar, arang aktif, bahan organik lain (air kelapa, bubur pisang, ekstrak buah, ekstrak kecambah) . Media yang sudah jadi ditempatkan pada tabung reaksi atau botol kaca dan disterilisasi. Komposisi media yang digunakan tergantung dari tujuan dan jenis tanaman yang dikulturkan.
Berdasarkan komposisi dan kesesuaian media terhadap jenis tanaman yang akan dikulturkan, dikenal beberapa jenis media dasar:
· Media VW yang diformulasikan dan diperkenalkan oleh E. Vacin dan F. Went (1949), untuk tanaman Anggrek
· Media MS yang diformulasikan dan diperkenalkan oleh Murashige dan Skoog (1962) untuk berbagai tanaman hortikultura
· Media Euwen untuk tanaman kelapa
· Media B5 atau Gamborg, digunakan untuk kultur suspense sel kedelai, alfafa dan legume lain.
· Media White, untuk kultur akar
· Media Woody Plant Madium (WMP) untuk tanaman berkayu
· Media N6 untuk tanaman serealia
· Media Nitsch dan Nitsch untuk kultur sel dan kultur tepung sari
· Media Schenk dan Hildebrandt untuk tanaman berkayu
Pada semua komposisi media kultur jaringan, hormon dan vitamin diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Masing-masing komponen media memiliki peran, unsur hara makro berfungsi dalam metabolisme tanaman, unsur hara mikro: pengaturan enzym, vitamin: regulasi (pengaturan), sukrosa sebagai suplay karbohidrat, sumber karbon, sumber energi, Zat Pengatur Tumbuh (ZPT) untuk merangsang, menghambat atau mengubah pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman, arang aktif untuk mengarbsorbsi senyawa fenolik dan untuk merangsang pertumbuhan akar, agar sebagai pemadat dan aquades sebagai pelarut.
Media dasar tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, dengan menambahkan vitamin dan zat pengatur tumbuh (hormon). Zat pengatur tumbuh diperlukan untuk mengatur diferensiasi tanaman.
Pada umumnya, hormon yang banyak dipergunakan adalah golongan auksin dan sitokinin. Perbandingan komposisi antara kedua hormon tersebut akan menentukan perkembangan tanaman, yaitu:
· Auxin lebih rendah dari Cytokinin maka terjadi perkembangan akar
· Cytokinin lebih rendah dari Auxin maka terjadi perkembangan tunas
· Auxin sama dengan Cytokinin maka terjadi perkembangan kalus
Salah satu kendala dalam pengembangan kacang bambara adalah karena tidak adanya pengembangan genetik. Peningkatan nilai genetik kacang bambara dapat diakukan dengan rekombinasi genetik dan seleksi. Terdapat beberapa penelitian mengenai efisiensi sistem regenerasi yang sesuai untuk perkembangan sel dan manipulasi genetik, kultur jaringan harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan transformasi genetik. Kacang-kacangan dengan ukuran benih yang besar kebanyakan termasuk dalam kelompok rekalsitran dapat disimpan dalam bentuk regenerasi in vitro. Kone et al., (2013) menyatakan bahwa penelitian mengenai kacang bambara di bidang bioteknologi juga dilakukan untk pengembangan teknik integrasi gen dalam tanaman secara langsung untuk perbaikan plasma nutfah dengan persilangan antar taxa. Pengembangan teknologi ini tergantung pada efisiensi regenerasi untuk tanaman dewasa yang fertil dengan menggunakan organ, jaringan dan protoplas, meskipun demikian, kultur jaringan untuk kacang bambara sangat jarang meskipun perbanyakan dapat dilakukan dengan menggunakan eksplan embrio, epikotil, hipokotil dan kotiledon.
Beberapa penelitian terdahulu menurut Owonubi et al., (2011) telah dilakukan kultur jaringan kacang bambara yang berasal dari jaringan adventif batang dari embrio, ada pula penelitian yang menggunakan eksplan yang berasal dari kotiledon dan jaringan epikotil, sementara untuk kultur jaringan organogenesis secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan eksplan yang berasal dari epikotil dan hipokotil. Organogenesis secara langsung pada eksplan adalah metode multiplikasi yang berguna dalam proses pengembangan tanaman transgenik. Karena plantlet langsung terbentuk tanpa melalui fase kalus sehingga variasi somaklonal dapat diminimalisis. Organogenesis sangat berguna dalam kegiatan modifikasi genetik pada tanaman. Dalam pelaksanaan kultur jaringan kacang bambara ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dua diantaranya adalah asal eksplan dan juga komposisi media yang digunakan.
· Aklimatisasi
Tahapan akhir dari perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan adalah aklimatisasi planlet (tanaman kecil). Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan planlet keluar dari ruangan aseptik. Tahap aklimatisasi merupakan tahap yang sangat penting dan kritis dalam rangkaian budidaya tanaman in vitro, karena kondisi lingkungan di rumah kaca atau rumah plastik dan di lapangan sangat berbeda dengan kondisi di dalam botol kultur.
Aklimatisasi dilakukan dengan memindahkan planlet ke media aklimatisasi dengan intensitas cahaya rendah dan kelembapan nisbi tinggi, kemudian secara berangsur-angsur kelembapannya diturunkan dan intensitas cahayanya dinaikkan. Pemindahan ini dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar, sinar matahari langsung dan serangan hama penyakit karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar.
Media tanaman yang dipergunakan dalam tahap ini biasanya berupa bubuk arang, arang sekam, mos, pakis halus, campuran tanah halus dan kompos, dan sebagainya. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit generatif. Selanjutnya bibit siap dipindahkan ke lapang atau lahan penanaman.
Lingkungan in vitro
Lingkungan ex vitro
Suhu 25±2oC
Suhu 23-36oC
Intensitas cahaya 1200-200 lux
Intensitas cahaya 4000-12000 lux
Spektrum cahaya sempit
Spektrum cahaya luas
Kelembaban relatif 98-100%
Kelembaban relatif 40-80%
Akar hampir tidak berfungsi
Akar sangat berfungsi
Sistem fotosintesis hampir tidak berfungsi
Sistem fotosintesis sangat berfungsi
Hormon eksogen
Hormon endogen
Kondisi steril
Kondisi tidak steril
Keberhasilan teknik propagasi secara in vitro ini ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:
a. Faktor tanaman: Genotipe tanaman (varietas, species tanaman induk), dan kondisi eksplan (jenis eksplan, ukuran, umur, fase fisiologis jaringan ).
b. Faktor lingkungan tumbuh: Suhu ± 25 oC , kelembaban : 80-99% (botol tertutup rapat), cahaya dari lampu TL ±1000 lux, dan media tanam jenis media, komposisi media, hormon
c. Faktor sterilitas / kondisi aseptik: sterilitas bahan dan peralatan laboratorium degan penggunaan autoklaf, sterilitas ruang dengan penggunaan bahan antiseptic (kloroform, alkohol), dan sterilitas dalam pelaksanaan dengan penggunaan entkas dan laminar air flow
B. Teknik kultur embrio pada kacang bogor
1. Organogenesis kacang bambara oleh Owonubi et al., (2011)
Owonubi et al., (2011) dalam penelitian mengenai organogenesis pada kacang bambara menggunakan teknik in-vitro dengan media MS. Prosedur pelaksanaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut,
Benih dari aksesi yang digunakan disterilisasi dengan ethanol 70% untuk satu menit yang dilanjutkan dengan sterilisasi permukaan dengan 10% larutan sodium hipoklorit dan dua tetes minyak Tween-20 selama 20 menit. Eksplan dicuci sebanyak tiga kali dengan aquades dan dikocok semalaman. Sterilisasi kedua dilakukan dengan menggunakan larutan sodium hipoklorit 5% dengan dua tetes minyak tween-20 selama 10 menit dan dicuci dengan aquades sebelum dipotong-potong menggunakan stereomikroskop pada LAFC.
Embrio yang sudah diberikan perlakuan dikulturkan pada test tube dengan medium MS bervitamin. Media MS mengandung 3% sukrosa, 100mg/l myo-inositol, 0,7% agar dengan pH media 5,8 dan dilanjutkan dengan autoclav dengan tekanan 15 psi dan suhu 121oC selama 15 menit dan diinkubasi pada ruang pertumbuhan dengan suhu 24±2oC dibawah penyinaran 16 jam. Masa inkubasi dilakukan selama 4 minggu.
Setelah 4 minggu, plnanlet dengan pertumbuhan akar yang baik dapat dipindahkan dari media kultur dan setelah pencucian dengan air mengalir, tanaman dapat dipindahkan ke media yang berisi 70% topsoil, 20% serat kelapadan 10% pasir yang telah disterilisasi selam 4 jam sebelum digunakan. Setelah 3 minggu, tanaman dapat dipindahkan ke media yang mengandung tanah, pasir dan pupuk dan ditumbuhkan di dalam rumah kaca selama 3 minggu untuk aklimatisasi.
2. Kultur kotiledon pada kacang bambara oleh Kone et al., (2013)
Pada penelitian lain oleh Kone et al., (2013) dalam penelitiannya mengenai organogenesis kacang bambara dengan eksplan kotiledon melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut,
Keterangan: (a) Benih yang digunakan untuk regenerasi, (b) benih yang sudah dibuang kulit luarnya, (c) benih yang dipotong transvesal, (d) benih yang dipotong longitudinal, (e) eksplan dalam media organogenesis, (f) regenerasi batang langsung dari kotiledon dengan bagian adaxial pada medium, (g) regenerasi batang langsung dari kotiledon dengan bagian abaxialpada medium, (h) pembentukan akar pada medium pengakaran MS tanpa ZPT, (i) pemindahan plantlet ke medium tanah:pasir, (j) tanaman yang diaklimatisasi pada greenhouse (Kone et al., 2013)
Benih kacang bambara yang diambil dari kotiledon yang memiliki kemampuan untuk regenerasi, mudah ditumbuhkan dan dapat dikembangkan dalam jumlah yang banyak. Benih kemudian disterilisasi dengan menggunakan ethanol 70% selama satu menit dan dilanjutkan dengan 7% kalsium hipoklirit selama 30 menit. Pada tahap selanjutnya benih dicuci dengan aquade sebanyak 4 kali dan dikocok pada air steril 25oC selama 48 jam dalam keadaan gelap. Setelah proses ini selesai kemudian benih dikeringkan dengan kertas filter, kulit benih dilepaskan dan kotiledon dipisahkan dengan embrio, tahap ini yang disebut sebagai de-embrionasi. Kotiledon ditanam dengan terlebih dulu memoting kotiledon dengan ukuran 0,5 cm2 dan eksplan kemudian diinkubasi pada media kultur MS.
Setelah batang adventif terbentuk sekitar 2-3 cm maka eksplan dipindahkan ke media pengakaran dengan komposisi dasar MS tanpa penambahan ZPT. Saat batang sudah mencapai 3-4 cm dan akar sudah terbentuk sekitar 6-8 dengan 4 atau 5 daun maka dilanjutkan dengan pemindahan pada media baru yang berisi tanah dan pasair 1:1 dengan penutup untuk menjaga kelembaban. Pot yang diguanakan sebagai media harus dijaga suhu dan kelembabannya yaitu 25 ± 2 ºC, dan kelembaban 40–50% dan fotoperiodisitas atau penyinaran 16 jam penyinaran 8 jam. Setelah tanaman tidak lagi ditutup dengan plastik, maka tanaman sudah bisa ditransfer pada greenhouse.
3. Pemendekan sikluas generasi kacang bambara dengan kombinasi teknik In vitro dan in vivo oleh Dapaah dan Sangwan (2004)
Mutasi dengan kombinasi teknik in vitro dan in vivo dilakukan dengan melalui empat tahap yaitu:
· Media kultur: media yang digunakan adalah media MS dengan komposisi makro elemen, mikro elemen dan vitamin, 2% sukrosa dan 0,6% agar. Medium yang dibuat sudah didesain untuk media kultur bambara yang mengandung jenis dan konsentrasi ZPT berbeda. Untuk mendukung pertumbuhan akar maka ditambahkan ZPT 0,5-1,0mg/l NAA.
· Sterilisasi: kacang bambara dikocok dengan aquades selama satu malam, setelah pengocokan selama satu malam kemudian benih dicuci debanyak 3-4 kali pencucian. Setelah semua proses tersebut dilanjutkan dengan sterilisasi permukaan dengan ethanol 70% dan 5% kalsium hipoklorit.
· Kondisi kultur: untuk memperpendek siklus generasi, terdapat tiga perlakuan yaitu dengan menggunakan eksplan (1) benih kacang bambara kontrol, (2) benih yang kulit bijinya sudah dilepaskan dan (3) embrio yang diisolasi dari benih, embrio dipisahkan dari benih dengan hati-hati dengan skapel. Benih dan embrio ditanam di cawan petri, kondisi ruang kultur dibuat dengan kondisi 5000 lux dengan lama penyinaran 10 jam dan rata-rata 27oC saat siang dan 25oC. Saat eksplan setinggi 3-4 cm maka eksplan dipindahkan ke greenhouse.
C. Evaluasi hasil kultur embrio kacang bogor
1. Organogenesis pada kacang bambara oleh Owonubi et al., (2011)
Konsentrasi dari dua hormon auksin dan sitokinin pada media memberikan pengaruh yang besar terhadap regenerasi planlet. Kombinasi BA 0,45mg/l dan NAA 0,25mg/l menghasilkan jumlah batang yang banyak dengan nilai panjang batang yang tinggi. Pengurangan konsentrasi NAA menjadi 0mg/l ternyata dapat menurunkan regenerasi batang dan daun. Hasil menunjukkan bahwa konsentrasi yang berbeda dari NAA antara 0-0,25mg/l dapat mempengaruhi frekuensi regenerasi dengan peningkatan konsentrasi NAA, sementara konsentrasi BA yang rendah dapat menginduksi pembentukan batang. Keberhasilan kultur in vitro didapatkan dengan mengatur konsentrasi hormon sitokinin dan uksin pada meda. Keseimbangan hormon menjadi sangar penting. Pembelahan sel dan pembesaran sel terjadi pada jaringan yang aktif dengan sitokinin dan auksin yang simbang. Sementara itu, pembentukan kalus terjadi pada media yang lebih banyak mengandung auksin-NAA pada media sehingga pembentukan akar lebih tingi.
2. Kultur kotiledon pada kacang bambara oleh Kone et al., (2013)
Kone et al., (2013) dari hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa regenerasi batang yang paling optimum adalah dari kotiledon dengan konsentrasi hormon BAP tinggi, hal ini dikarenakan sitokinin dapat meningkatkan deferensiasi dan laju translokasi.pada beberapa spesies kacang-kacangan, efek dari konsentrasi tinggi dari sitokinin dan konsentrasi auksin yang rendah dapat menyebbkan respon organogenesis batang lebih baik daripada media dengan hormon sitokinin saja. Pada kultur kotiledon V.subterranea, tunas muncul dari adaxial dan abaxial dari kotiledon.
3. Pemendekan sikluas generasi kacang bambara dengan kombinasi teknik In vitro dan in vivo oleh Dapaah dan Sangwang (2004)
Rerata perkecambahan dan pertumbuhan plantlet menunjukkan bahwa benih tanpa kulit berkecambah 7 hari setelah penanaman, benih dengan kulit berkecambah 14 hari. Pada 21 hst persentase perkecambahan sudah sempurna.
Persentase perkecambahan menunjukkan bahwa pada eksplan yang berasal dari embrio menghasilkan persentase perkecambahan yang paling besar hampir dua kali benih yang dikupas dan tidak dikupas, hal ini dimungkinkan karena proses perkecambahan semakin cepat jika embrio dikeluarkan dari kotiledon. Untuk ukuran plantlet dan panjang akar untuk benih yang dikupas dan tidak dikupas menunjukkan hasil yang lebih tinggi yaitu tiga kali lipatnya dari eksplan embrio hal ini dikarenakan eksplan benih dengan kotiledon memiliki cadangan makanan yang lebih banyak untuk mendukung regenerasi eksplan, meskipun demikian jumlah cabang lebih banyak tiga kali lipat pada eksplan embrio.
Kultur in vitro dilakukan untuk memperpendek siklus generasi pada kacang bambara sehingga pertumbuhan vegetatif dapat dikurangi untuk membentuk beberapa biji. Sebenarnya teknik ini dikembangkan untuk seleksi SSD (Single Seed Descent) untuk mendapatkan benih dari satu tanaman untuk ditanam kembali secara in vivo dan diseleksi. Dengan sistem ini maka dalam satu tahun dapat digunakan untuk menyeleksi empat generasi secara langsung yang tidak mungkin dilakukan jika dilakukan secra in vivo.
Durasi yang semakin pendek akan menyebabkan perbanyakan dengan teknik gabungan in vitro dan in vivo semakin efisien and independensi genetik sehingga sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai aplikasi bioteknologi. Teknik gabungan ini juga pernah digunakan dalam pengembangan benih kacang bambara dalam jumlah banyak yang merupakan hasil mutasi dengan irradiasi sinar gamma.
D. Penutup
a. Kesimpulan
Dalam kegiatan kultur pada kacang bambara seperti kultur jaringan yang lain, media perlu untuk diperhatikan selain komposisi dasar yaitu ZPT. ZPT sangat penting untuk diperhatikan karena konserntrasi ZPT akan mempengaruhi pemanjangan akar, batang dan pembentukan kalus. Seperti pada penelitian yang pernah dilakukan untuk perlakuan ZPT BA yang tinggi dan NAA yang rendah menginduksi pembentukan akar sebaliknya ZPT BA rendah dan NAA tinggi menginduksi pembentukan batang dan pada konsentrasi keduanya yang sama menginduksi pembentukan kalus.
Selain itu, pada penelitian lain yang menggunakan eksplan berupa benih (dengan pengupasan dan tanpa pengupasan) dan kultur embrio menunjukkan perbedaan dalam beberapa hal yaitu kecepatan kecambah, panjang akar, batang dan jumlah batang. Kultur in vitro pada kacang bambara dapat dilakukan untuk membantu memperpendek siklus hidup sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pemuliaan tanaman sehingga dapat menghemat waktu satu tahun dapat digunakan untuk perkembangan empat generasi kacang bambara.
b. Rekomendasi
Penggunaan teknik in vitro dari beberapa penelitian yang pernah ada maka kultur in vitro dapat digunakan untuk kegiatan pemuliaan bioteknologi misalkan transformasi genetik, mutasi atapun memperpendek masa regenerasi sehingga lebih efektif dan efisien.
Daftar Pustaka
Dapaah, A., and Sangwan. 2004. Improving bambara groundnut productivity using gamma irradiation and in vitro techniques. African Journal of Biotechnology. 3(5): 260-265
Kone, M., T. Kone., H.T. Kouakou, S. Konate and J.S. Ochatt. 2011. Plant regeneration via direct shoot organogenesis from cotyledon explants of Bambara groundnut, Vigna subterranea (L.) Verdc. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2013 17(4), 584-592
Nugrahani, P., Sukendah dan Makziah. 2011.Teknik Propagasi Secara In Vitro. Universitas Pembangunan Nasional. Surabaya
Owonubi, S.J., O.B. Ojuederie, dan M.N.Olayode. 2011. Organogenesis of Bambara Groundnut (Vigna subterranea (L.) Verdc.) through in Vitro Culture from Nodal Segmen. International Journal of Plant Development Biology
BAB III INDUKSI MUTASI KACANG BOGOR
A. Pendahuluan
· Pengertian Mutasi
Menurut Warianto, (2011) mutasi berasal dari kata Mutatus (bahasa latin) yang artinya adalah perubahan. mutasi didefenisikan sebagai perubahan materi genetic (DNA) yang dapat diwariskan secara genetis keketurunannya. Mutasi adalah perubahan pada materi genetik suatu makhluk yang terjadi secara tiba-tiba, acak, dan merupakan dasar bagi sumber variasi organisme hidup yang bersifat terwariskan (heritable). Mutasi juga dapat diartikan sebagai perubahan struktural atau komposisi genom suatu jasad yang dapat terjadi karena faktor luar (mutagen) atau karena kesalahan replikasi. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan dan factor penyebab mutasi disebut mutagen (mutagenic agent). Perubahan urutan nukleotida yang menyebabkan protein yang dihasilkan tidak dapat berfungsi baik dalam sel dan sel tidak mampu mentolerir inaktifnya protein tersebut, maka akan menyebabkan kematian (lethal mutation).
Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik (DNA maupun RNA), baik pada taraf urutan gen (disebut mutasi titik) maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosomal biasanya disebut aberasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar bagi kalangan pendukung evolusi mengenai munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Mutasi dapat mempengaruhi DNA maupun kromosom. DNA dapat dipengaruhi pada saat sintesis DNA (replikasi). Pada saat tersebut factor mutagenic mempengarugi pasangan basa nukleutida sehingga tidak berpasangan dengan basa nukleutida yang seharusnya (mismatch). Misalnya triplet DNA cetakan adalah TTA. Namun karena adanya mutagen menyebabkan DNA polymerase memasangkan A dengan C, bukan dengan T.
· Jenis-jenis mutasi
Menurut Kejadiannya Mutasi dapat terjadi secara spontan (spontaneous mutation) dan juga dapat terjadi melalui induksi (induced mutation). Mutasi spontan adalah mutasi (perubahan materi genetik) yang terjadi akibat adanya sesuatu pengaruh yang tidak jelas, baik dari lingkungan luar maupun dari internal organisme itu sendiri. Sedangkan mutasi terinduksi adalah mutasi yang terjadi akibat paparan dari sesuatu yang jelas, misalnya paparan sinar UV. Secara mendasar tidak terdapat perbedaan antara mutasi yang terjadi secara alami dan mutasi hasil induksi.
Berdasarkan sel yang mengalami mutasi, mutasi dibedakan atas mutasi somatik dan mutasi gametik atau germinal. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik. Sedangkan mutasi gametik atau germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Mutasi somatik dapat diturunkan dan dapat pula tidak diturunkan. Sedangkan mutasi gametik, karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan oleh keturunannya.
Mutasi secara umum menurut tempat terjadinya ada dua yaitu:
a. Mutasi gen ialah perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya.
b. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada kromosom yang disertai dengan perubahan struktur dan jumlah kromosom.
Mutasi kromosom atau sering juga disebut dengan mutasi besar/gross mutation atau aberasi kromosom adalah perubahan jumlah kromosom dan susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Mutasi kromosom berdasarkan jumlah kromosomnya dibagi menjadi dua yaitu Aneuploid dan Aneusomi:
· Aneuploidi adalah perubahan jumlah kromosomnya. Aneuploidi dibagi menjadi 2, yaitu:
· Autopoliploidi, yaitu kromosomnya mengganda sendiri karena kesalahan meiosis.
· Allopoliploidi, yaitu perkawinan atau hibrid antara spesies yang berbeda jumlah set kromosomnya.
· Aneusomi adalah perubahan jumlah kromosom. Penyebabnya adalah anafase lag (peristiwa tidak melekatnya beneng-benang spindel ke sentromer) dan non disjunction (gagal berpisah).
Mutasi kromosom menurut Suparmuji (2009) berdasarkan jumlah kromosomnya dibagi menjadi empat yaitu duplikasi, translokasi, delesi (defisiensi) dan inversi:
1. Delesi adalah mutasi karena kekurangan segmen kromosom. Penghilangan dapat terjadi pada segmen panjang lengan kromosom seperti yang dilaporkan pada tanaman gandum. Tergantung pada gen dan tingkat ploidi, defisiensi dapat menyebabkan kematian, separuh kematian, atau menurunkan viabilitas. Pada tanaman defisiensi yang ditimbulkan oleh perlakuan bahan mutagen (radiasi) sering ditunjukkan dengan munculnya mutasi klorofil. Kejadian mutasi klorofil biasanya dapat diamati pada stadia muda (seedling stag), yaitu dengan adanya perubahan warna pada daun tanaman.
2. Duplikasi adalah mutasi karena kelebihan segmen kromosom. Mutasi ini terjadi pada waktu meiosis, sehingga memungkinkan adanya kromosom lain (homolognya) yang tetap normal. Duplikasi menampilkan cara peningkatan jumlah gen pada kondisi diploid. Dulikasi dapat terjadi melalui beberapa cara seperti: pematahan kromosom yang kemudian diikuti dengan transposisi segmen yang patah, penyimpangan dari mekanisme crossing-over pada meiosis (fase pembelahan sel), rekombinasi kromosom saat terjadi translokasi, sebagai konsekuensi dari inversi heterosigot, dan sebagai konsekuensi dari perlakuan bahan mutagen. Beberapa kejadian duplikasi telah dilaporkan dapat miningkatkan viabilitas tanaman.
3. Translokasi ialah mutasi yang mengalami pertukaran segmen kromosom ke kromosom non homolog. Translokasi terjadi apabila dua benang kromosom patah setelah terkena energi radiasi, kemudian patahan benang kromosom bergabung kembali dengan cara baru. Patahan kromosom yang satu berpindah atau bertukar pada kromosom yang lain sehingga terbentuk kromosom baru yang berbeda dengan kromosom aslinya. Translokasi dapat terjadi baik di dalam satu kromosom (intrachromosome) maupun antar kromosom (interchromosome). Translokasi sering mengarah pada ketidakseimbangan gamet sehingga dapat menyebabkan kemandulan (sterility) karena terbentuknya chromatids dengan duplikasi dan penghapusan.
4. Inversi ialah mutasi yang mengalami perubahan letak gen-gen, karena selama meiosis kromosom terpilin dan terjadi kiasma. Inversi terjadi karena kromosom patah dua kali secara simultan setelah terkena energi radiasi dan segmen yang patah tersebut berotasi 180o dan menyatu kembali. Kejadian bila centromere berada pada bagian kromosom yang terinversi disebut pericentric, sedangkan bila centromere berada di luar kromosom yang terinversi disebut paracentric.
· Induksi Mutasi
Mutasi berdasarkan mutagennya dibagi menjadi dua yaitu mutasi alami dan mutasi buatan.
· Mutasi alam atau mutasi spontan biasanya terjadi karena kesalahan pemasangan basa pada waktu proses replikasi, perbaikan, atau rekombinasi DNA sehingga mengarah pada terjadinya substitusi, insersi atau delesi pasangan basa. Selain itu mutasi secara alami dapat terjadi karena radiasi radioaktif alam, sinar kosmis dan sinar ultraviolet.
· Mutasi buatan, yaitu mutasi yang ditimbulkan akibat campur tangan manusia (telah direncancanakan). Dengan memperlakukan sel menggunakan zat-zat kimia, sinar-X, sinar gamma, sinar alfa, dan beberapa jenis radiasi hasil sampingan tenaga nuklir. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat fisik menurut Warianto (2011) adalah radiasi dan suhu. Radiasi sebagai penyebab mutasi dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi bukan pengion.
· Radiasi pengion adalah radiasi berenergi tinggi sedangkan radiasi bukan pengion adalah radiasi berenergi rendah. Contoh radiasi pengion adalah radiasi sinar X, sinar gamma, radiasi sinar kosmik. Contoh radiasi bukan pengion adalah radiasi sinar UV. Radiasi pengion mampu menembus jaringan atau tubuh makhluk hidup karena berenergi tinggi.
· Radiasi bukan pengion hanya dapat menembus lapisan sel-sel permukaan karena berenergi rendah. Radiasi sinar tersebut akan menyebabkan perpindahan elektron-elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi.
· Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat kimiawi disebut juga mutagen kimiawi. Mutagen-mutagen kimiawi tersebut dapat dipilah menjadi 3 kelompok, yaitu analog basa, agen pengubah basa dan agen penyela.
B. Teknik induksi mutasi pada kacang bogor
Kacang bambara adalah kacang-kacangan yang banyak diproduksi di Nigeria, Niger, dan Ghana dan pada daerah-daerah di Afrika barat. Kacang bambara mengandung protein lysin dan methonine, kandungan proteinnya sekitar 18%-24%, karbohidrat 51%-70%, energi 367-414 kcal per 100g, zat besi 4,9-48 mg/100g. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan kacang bogor yaitu potensi hasil yang rendah, rentan terserang penyakit seperti Cercospora, virus mozaic, dan hama. Induksi nutasi pada kacang bambara juga dilakukan untuk mengembangkan potensi hasil bambara sementara sedikit sekali pengembangan indksi mutasi dengan tujuan untuk mengamati pengaruh terhadap resistensi penyakit. Dengan dilakukannya mutasi maka variasi genetik yang terbentuk menjadi lebih banyak sehingga memudahkan dalam melakukan seleksi untuk tindakan pemulian selanjutnya.
Mutasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah mutasi dengan irradiasi, contohnya dengan penyinaran sinar gamma. Pembelajaran mengenai mutagen kimia didahului dengan percobaan dengan mutasi menggunakan radiasi sebagai agen mutagenik. Saat ini mutasi kimia telah banyak diuji cobakan dengan beberapa sistem mutagen biologis, contohnya yaitu ethylenimine, N-ethyl-N-nitrisomourea, diethylsulphonate, ethyle methane sulphonate, sodium azide, hydroxylamine, colchicin dan streptomycin.
Streptomycin adalah antibiotik yang bekerja sebagai reaktor dengan elemen non-kromosomal dalam sel. Efek strpthomycin pada jagung dan bunga matahari dapat menyebabkan male sterility, pada rye menyebabkan pengkerdilan dan penebalan pada akar. Pemberian streptomycin pada perkecambahan dapat menyebabkan rendahnya klorofil karena hambatan yang disebabkan karena streptomycin terhadap pembentukan klorofil.
Peningkatan produksi kacang bambara dapat dilakukan dengan teknik rekombinasi genetik dan seleksi, induksi mutasi, dan bioteknologi. Penggunaan streptomycin dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor genetik yang dapat meningkatkan program pemuliaan pada tanaman. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui frekuensi, efektifitas dan efisiensi streptomycin sebagai mutagen pada kacang bambara untuk pertama kali.
Pada dasarnya, semua materi mutagen yang diberikan adalah sebagai satu upaya untuk membetntuk rekombinasi genetik dengan cara bereaksi dengan kromosom dalam sel untuk merekombinasi susunan baik pada kromosom, DNA aupun RNA. Mutasi dapat terjadi pada gen yang disebut dengan mutasi titik yang dapat memunculkan adanya alel baru dan juga dapat terjadi pada kromosom yang disebut dengan aberasi. Maka penelitian oleh Adu-Dapaah (2004) dan Mensah et al, (2012) memfokuskan untuk meneliti mengenai mutasi pada kacang bambara untuk meningkatkan ketahanan penyakit dan peningkatan hasil.
Mutasi pada kacang bambara sudah pernah dilakukan beberapa kali dalam beberapa penelitian mengenai pembentukan variasi genetik kacang bambara melalui teknik induksi mutasi.
1. Mutagen Streptomycin
Benih kacang bambara Africa dari petani lokal diambil sebagai sampel yang memiliki keseragaman ukuran, warna cream dan bebas hama penyakit. Benih diberikan perlakuan rendaman streptomycin dengan konsentrasi 0% (kontrol), 0,005%, 0,05%, 0,5%, 0,75% dan 1,0% (berat/volum) larutan streptomycin pada cawan petri dengan suhu ruang (25oC).
Benih masing-masing 50 benih per perlakuan, dimasukkan dalam beaker glass bersama dengan larutan streptomycin dan dikocok dengan alat shaking selama 24 jam. Setelah treatment selesai, benih dicuci pada ddH2O untuk menghilangkan bahan kimia dan racun yang terbentuk dan ditiriskan pada kain selama satu minggu kemudian ditanam di plot hingga panen.
Parameter-parameter yang diamati adalah perkecambahan, persentase tanaman bertahan, jumlah daun, hari berbunga, berat kering, jumlah nodule per tanaman, jumlah cabang per tanaman, abnormalitas, dan infeksi penyakit. Efektifitas mutagenik da efisiensi dihitung dengan menggunakan persentase lethal sebagai dasar perhitungan efisiensi mutagenik.
2. Mutagen Sinar Gamma dan Mutagen Ethylmethan sulphonate (EMS)
Mutasi dengan sinar gamma (GR) dengan 60C gamma 220 unit dosis 0, 50, 100, 150, 200,250, 300, 350, 400 Gy yang dicobakan pada kacang bambara yang berproduksi tinggi tetapi rentan terhadap serangan Cercospora dan virus Mosaic. Benih yang diambil adalah benih aksesi lokal yang seragam dan memiliki daya kecambah 100%. Setelah dilakukan perlakuan selanjutnya benih ditanam dengan jarak tanam 20 cm x 30 cm.
Mutasi dengan EMS dengan dosis 0,0%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8%, 1,0% dan 1,2%. Benoh diambil dari varietas Tom dan Nav dengan daya kecambah 98%. Benih sebanayak 200 benih tiap perlakuan direndam pada EMS yang telah dilarutkan pada beaker glass dan diletakkan pada shaker selama 6 jam. Setelah 6 jam, benih dicuci dan ditanam pada lahan dengan jarak tanam 20 cm x 30 cm.
C. Evaluasi hasil induksi mutasi kacang bogor
1. Mutagen Streptomycin
a. Perkecambahan, tanaman bertahan, sensitifitas, dan efektifitas mutagen.
Perkecambahan benih terhadap dosis mutasi adalah berbanding terbalik, semakin tinggi dosis maka persentase perkecambahan akan semakin rendah. Pengamatan ertumbuhan dan kemampuan bertahan tanaman juga menunjukkan pola yang sama dengan perkecambahan. Perlakuan kontrol memiliki kemampuan bertahan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsentrasi mutagen yang lain.
Kemampuan 50% tanaman dalam populasi untuk bertahan (LC50) telah terbukti terjadi pada kacang bambara yang telah direndam streptomycin 0,5% w/v selama 24 jam. Pola survival tanaman mingikuti pola perkecambahan hanya saja lebih rendah. Pada konsentrasi 0,5% dan 1,0% ST menunjukkan penurunan perkecambahan dengan cepat. Berdasarkan persentase pertahanan tanaman LC50 ditunjukkan oleh konsentrasi ST 0,5% w/v. Penurunan perkecambahan dan pertahanan tanganan dapat dipengaruhi oleh gangguan fisiologi atau kromosom pada sel yang menyebabkan mutasi.
Frekuensi mutagenik antara 2,75% hingga 42,7%, frekuensi akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi mutagen. Aberasi morfologi digunakan untuk perhitungan frekuensi mutasi yang meliputi bentuk daun, internode, klorofil. Efektifitas mutagenik ST menurun dengan meningkatnya konsentrasi ST, hal ini terbukti dengan lebih efektifnya konsentrasi rendah 0,005% dan 0,05% untuk menginduksi mutan pada kacang bambara. Efisiensi mutagenik dapat dihitung berdasarkan kemampuan untuk menyebabkan kematian pada hst 21. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi maka level kematian akan semakin besar. Terkadang, semakin tinggi konsentrasi maka efisiensi makin tinggi, hal ini bertentangan dengan hasil yang diperoleh bahwa efektifitas mutagenik tertinggi ada pada konsentrasi mutagenik terendah.
b. Pengamatan Agronomi
Peningkatan konsentrasi ST menunjukkan reduksi jumlah daun pada 0,005%, 0,5%, dan 0,75% sementara jumlah daun maksimum terdapat pada konsentrasi ST 0,05%.
Hasil pengamatan terhadap jumlah cabang menunjukkan bahwa tidak ada efek yang tinggi akibat peningkatan konsentrasi ST pada setiap tanaman. Peningkatan konsentrasi ST pada 0,005% dan 0,05% mempengaruhi pengurangan pemebentukan daun sebagai akibat inisiasi pembentukan bunga. Konsentrasi 0,5%, 0,75%, dan 1,0% ST menyebabkan penundaan pembunggan.
Hasil menunjukkan bahwa ST dapat digunakan untuk menghasilkan varian kacang bambara dengan waktu pemasak yang cepat.
Konsentrasi 0,05% ST menunjukkan peningkatan yang tajam terhadap jumlah nodule antara minggu ketiga dan kelima. Pada minggu ketujuh, jumlah nodule mengalami penurunan pada setiap konsentrasi, hal ini menunjukkan tidak efektifnya sistem nodule akar terhadap waktu, nodule memiliki waktu fungsional yang pendek.
c. Hasil Vegetatif
Peningkatan konsentrasi ST menunjukkan pengurangan berat kering per tanaman, tetapi pada konsentrasi 0,05% berat kering meningkat signifikan.
d. Infestasi spot daun
Pada konsentrasi ST yang lebih tinggi serangan penyakit spot daun semakin menurun. Setiap peningkatan konsentrasi streptomycin, jumlah daun per tanaman yang terinfestasi menurun kecuali dibawah 0,005%, karena pada konsentrasi dibawah 0,005% mengalami peningkatan jumlah daun yang terinfestasi spot daun, hal ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi 0,005% ST terlalu rendah untuk secara efektif mengatasi infestasi Cercospora spot daun. Hasil menunjukkan bahwa konsentrasi 1,0% menghasilkan tanaman dengan jumlah spot daun paling rendah.
2. Mutagen Sinar Gamma dan Mutagen Ethylmethan sulphonate (EMS)
a. Perkecambahan, tanaman bertahan, frekuensi mutasi, dan efektifitas mutagen.
Secara umum hasil yang ditunjukkan melalui mutasi sinar gamma lebih baik daripada hasil EMS. Hasil menunjukkan bahwa LD50 untuk varietas Tom optimum berkisar pada 175 Gy dan 182 Gy pada Nav. Penurunan vigor tanaman meningkat seiring dengan peningkatan dosis mutasi yang diberikan.
Mutagenik EMS LD50 pada persentase 0,75% Tom dan 0,82 pada Nav. Populasi dengan perlakuan EMS, persentase tanaman bertahan tidak terlalu bervariasi jika dibandingkan dengan kontrol pada dosis antara 0,2% dan 0,4%, sementara pada dosis 0,6% hingga 1,2% dosis EMS menyebabkan penurunan kemampuan tanaman untuk bertahan hidup. Efektifitas mutasi ditunjukkan oleh dosis efektif dari kedua kultivar (Tom dan Nav) yaitu 0,6%.
Seiring dengan meingkatya dosis irradiasi sinar gamma maka frekuensi terjadinya mutasi akan semakin tinggi, namun efektifitas mutasi paling tinggi terjadi pada dosis mutasi antara 150 Gy untuk Tom dan 200 untuk Nav, hari berkecambah juga berbanding lurus dengan dosis yang diberikan, semakin tinggi dosis irradiasi sinar gamma yang diberikan maka waktu berkecambah semakin lama, sedangkan untuk jumlah tanaman bertahan semakin rendah seiring dengan meningkatnya dosis, pada varietas Tom jumlah bertahan 50 (LD50) pada konsentrasi maksimal 175 Gy sedangkan LD50 pada Nav maksimal pada 182 Gy.
Seiring dengan meingkatya dosis EMS maka frekuensi terjadinya mutasi akan semakin tinggi, namun efektifitas mutasi paling tinggi terjadi pada dosis mutasi antara 0,6% untuk Tom dan Nav, hari berkecambah juga berbanding lurus dengan dosis yang diberikan, semakin tinggi dosis irradiasi sinar gamma yang diberikan maka waktu berkecambah semakin lama, sedangkan untuk jumlah tanaman bertahan semakin rendah seiring dengan meningkatnya dosis, pada varietas Tom jumlah bertahan 50 (LD50) pada konsentrasi maksimal 0,75% sedangkan LD50 pada Nav maksimal pada 0,82%.
b. Pengamatan agronomi
Efek stimulasi terhadap hari berkecambah, tinggi tanaman, lama menuju fase generatif, jumlah pod per tanaman dan jumlah hasil biji per tanaman terdapat pada dosis lebih rendah pada 50 Gy dan 100 Gy pada irradiasi sinar gamma dan 0,2% dan 0,4% pada EMS. Pada parameter yang sama terjadi reduksi sifat karakter pada dosis irradiasi sinar gamma 150 Gy dan 300 Gy sedangkan 0,6% dan 1,2% pada EMS terhadap kedua kultivar Tom dan Nav.
Variasi genetik meningkat pada semua variabel pengamatan. Peningkatan hasil pengamatan pada populasi dengan perlakuan irradiasi sinar gamma dan EMS yang tinggi 2-4x jika dibandingkan dengan tanpa irradiasi dan tanpa EMS pada waktu generatif, jumlah pod per tanaman, ukuran biji, dan hasil biji dari dua varietas tersebut.
Pada semua karakter yaitu jumlah pod per tanaman, ukuran biji, hasil benih, dan persentase kulit biji perlakuan irradiasi sinar gamma menunjukkan rerata populasi yang lebih besar dari tanpa perlakuan, hal ini mempengaruhi variasi genetik yang terbentuk semakin besar yang ditunjukkan dengan nilai heritabilitas yang tinggi dan pertumbuhan genetik yang signifikan.
Sementara pada populasi dengan perlakuan EMS menunjukkan bahwa rerata populasi untuk karakter jumlah pod, ukuran biji, pada kedua varietas lebih rendah dari tanpa perlakuan namun tetap menunjukkan peningkatan pada pembentukan varieasi genetik yang ditandai dengan nilai heritabilitas dan kemajuan genetik pada populasi hasil mutasi dengan EMS.
c. Infestasi spot daun
Berdasarkan pegamatan terhadap semua tanaman, skoring serangan penyakit ditunjukkan dengan lima skor dengan rerata yaitu 1,0-1,4 untuk resisten, 1,5-2,5 agak tahan, 2,6-3,5 agak rentan, 3,6-5,0 sangat rentan. Rerata skor penyakit menunjukkan persentase tanaman terinfeksi. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil mutasi terhadap ketahanan penyakit spot daun Cercospora.
Umumnya, semua perlakuan radiasi dan EMS pada kultivar menunjukkan hasil lebih baik jika dibandingkan dengan kontrol. Ketahanan terhadap virus menunjukkan serangan infeksi lebih rendah pada 150 Gy- M3 dan EMS daripada galur lain. Terjadinya infeksi adalah sekitar 50-80%.
Pada kasus antraknose yang disebabkan karena Colletotrichum dematium lebih merata daripada spot daun Cercospora pada galur radiasi dan EMS. Persentase terjadinya infeksi lebih besar antara 0-100 pada Colletotrichum dematium jika dibandingkan dengan Cercospora berkisar antara 0-40%. Meski demikian persentase serangan pada galur-galur hasil mutasi menunjukkan persentase serangan yang lebih rendah daripada kontrol, sehingga irradiasi dan EMS dapat diambil sebagai langkah menangani penyakit pada kacang bambara.
E. Penutup
a. Kesimpulan
Observasi yang dilakukan dengan induksi mutasi kimia Streptomycin pada kacang bambara menunjukkan hasil yang bervariasi pada parameter pengamatan yang diamati. Hasil yang penting dalam observasi ini adalah untuk mengetahui resistensi terhadap penyakit spot daun, seiring dengan peningkatan konsentrasi maka resistensi akan dapat dicapai. Selain itu, mutasi kimia ST dapat digunakan untuk mempercepat masa pembungaan dan meningkatkan jumlah daun, jumlah cabang, jumlah nodule pada konsentrasi dibawah 0,05%. Pemberian ST dapat membentuk varietas resisten terhadap penyakit spot daun. Studi tentang pewarisan sifat pada karakter agronomi penting untuk mendukung peningkatan kualitas genetik untuk petani lokal dan untuk meningkatkan produktifitas tanaman.
Kesimpulan yang hampir serupa dengan perlakuan mutagen Streptomycin dari perlakuan mutagen sinar gamma dan EMS adalah tingkat kematian 50% (LD50) pada irradiasi sinar gamma adalah pada 178,56 rata-rata antara 175 Gy pada Tom dan 182 Gy pada Nav, dan 0,78 pada perlakuan EMS. Mutasi dapat meningkatkan adanya variasi genetik menjadi 4x dari tanpa perlakuan. Mutagenesis juga dapat digunakan untuk meningkatkan produkrifitas dan mengendalikan penyakit yang menyerang pada kacang bambara.
b. Rekomendasi
Penggnaan teknik mutasi untuk kacang bambara memiliki peluang yang baik untuk meningkatkan nilai keragaman, meskipun hasil yang didapat tidak dapat diperkirakan, tetapi dengan meningkatnya keragaman maka sumber gen akan tersedia dalam jumlah yang banyak yang berguna dalam kegiatan pemuliaan baik secara konvensional ataupun modern.
Daftar Pustaka
Adu-Dapaah, H.K., J.Y. Asibuo, O.A. Danquah, M. Owusu Akyaw, J. Haleegoah. 2004. Bambara Groundnut Improvement Through Mutation Breeding In Ghana. Proceedings Of A Final Research Coordination Meeting Organized By The Joint Fao/Iaea Division Of Nuclear Techniques In Food And Agriculture And Held In Pretoria, South Africa, 19–23 May 2003
Mensah, J.K., N.E. Edema, G. Okooboh, and S.O. Aifuwa. 2012. Effects of Streptomycin on the chemo-sensitivity and agronomic parameters of bambara groundnut (Vigna subterranea (L.) Verdc.). J.Nat.Prod.Plant Resour. 2 (1): 113-118
Suparmuji, 2009. Diktat Pembelajaran Biologi Kelas XII IPA: Genetika Mutasi. _______. ________
Warianto, C., 2011. Modul Perkuliahan 2010-2011: Mutasi. _______. ________
BAB IV PENGGUNAAN MARKA SELEKSI
A. Pendahuluan
Salah satu tujuan pemuliaan tanaman menurut Warta Biogen (2004) adalah merakit suatu tanaman yang memiliki sifat lebih baik dari yang sudah ada. Perakitan tanaman baru ini biasanya dengan memasukkan gen-gen tertentu yang memiliki ketahanan terhadap sifat tertentu. Dua tahap yang umum dilakukan dalam program pemuliaan tanaman adalah membuat variabilitas genetik dengan program persilangan, kemudian diikuti dengan seleksi masing-masing individu hasil persilangan yang mengandung gen yang diinginkan.
Seleksi pada umumnya dilakukan dengan menanam tanaman hasil persilangan dan mengujinya dengan perlakuan tertentu. Namun pada kenyataannya ketika ditanam di lapang masih ada kemungkinan terjadinya ketidak sesuaian antara tanaman yang diujikan dengan lingkungan sehingga gen yang diharapkan tidak terekspresi dengan baik, hal ini tentu saja menyebabkan pemulia mengalami kesulitan dalam seleksi. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini maka saat ini telah ada teknologi seleksi dengan menggunakan penanda DNA ataupun protein sehingga hasil seleksi lebih akurat.
Warta Biogen (2004)
Marka-marka inilah yang kemudian digunakan untuk seleksi yang kemudian terkenal dengan istilah Marker Assisted Selection (MAS). Penggunaan marka molekuler ini dapat digunakan bersamaan dengan pengujian fenotipik atau dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menguji tanaman yang terpilih secara molekuler dengan pengujian fenotipik.
Menurut Ahmad (2010), evaluasi dari variasi genetik dalam ataupun antar populasi dan interaksi gen dengan lingkungannya dapat diketahui dengan menggunakan marka. Marka penanda DNA secara prinsip dikembangkan dari teknik Southern blot untuk mengetahui polimorfisme dalam genom yang kompleks.
Karakteristik
RFLP
SSR
AFLP
RAPD
SNP
Nomer Lokus terdeteki
Satu lokus
Satu lokus
Multi lokus
Multi lokus
Satu lokus
Alel
Co-dominan
Co-dominan
dominan
Dominan
Co-dominan
Level polimorfisme
Baik
Sangat baik
baik
Baik
Sangat baik
Polimorfisme lokus
2-5 alel
Banyak alel
-
-
4 alel
Kuantitas DNA yang dipakai
Banyak
Sedikit
sedikit
Sedikit
Sedikit
Kualitas DNA yang dipakai
Sangat baik
Sedang
baik
sedang
Sedang
Reproduktibilitas
Baik
Baik
Baik
Rendah
Baik
Waktu
Lama
Cepat, jika sudah ditemukan marker
cepat
Cepat
Cepat, jika sudah ditemukan marker
Biaya
Mahal
Rata-rata
Murah
Murah
Mahal
Teknik
Sulit
Mudah
Medium
Medium
Sulit
(Ahmad, 2012).
a. RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism)
RFLP merupakan marka molekuler yang menggunakan enzim restriksi untuk mengidentifikasi susunan sekuen DNA. Analisis RFLP telah banyak digunakan untuk mencapai berbagai tujuan karena dengan enzim restriksi maka variasi keberadaan situs restriksi dapat menunjukkan adanya variasi susunan DNA. RFLP dapat digunakan sebagai penduga variasi DNA. Variasi DNA dapat dideteksi dengan pemotongan rangkaian panjang polimorfik (ganda) yang memungkinkan dari fragmen itu sendiri, rangkaian variasi yang panjang dalam suatu bagian dapat dinilai dari subtitusi nukleotida.
b. RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)
RAPD adalah jenis reaksi PCR, tetapi segmen DNA yang digunakan adalah acak. primer yang digunakan dalam RAPD adalah primer acak dan pendek dengan ukuran basa nukleotida 8-12 nukleotida, bahan yang digunakan sebagai template PCR adalah DNA genom atau DNA total. RAPD adalah teknik amplifikasi secara acak baik primer atau tempat penempelan primer, sehingga pengguna sama-sama tidak bisa memperdiksi primer yang tepat untuk urutan basa yang sesuai. Dalam beberapa tahun terakhir, RAPD telah digunakan untuk mengkarakterisasi, dan melacak, filogeni dari spesies tanaman dan hewan yang beragam.
c. AFLP (Amplified fragment length polymorphism)
AFLP adalah metode yang juga menggunakan PCR sebagai teknik dasar dalam pelaksanaannya. AFLP menggunakan enzim restriksi untuk memotng genom DNA yang diikuti dengan ligasi dari hasil fragmen restriksi. Hasil fragmen selanjutnya diperbanyak pada PCR, fragmen-fragmen itu kemudian diseparasi dalam gel poliakrilamid dan divisualisasi untuk mengetahui band yang terbentuk.
d. SSR
Mikrosatelit dapat digunakan untuk memperkuat identifikasi yang dapat dilakukan dengan reaksi berantai polimerase (PCR), primer yang dipakai adalah dua primer yang melekat pada dua daerah penempelan yang berbeda. DNA didenaturasi pada suhu tinggi untuk memisahkan untai ganda, kemudian didinginkan untuk memungkinkan penempelan primer dan pemanjanga nukleotida. Proses ini menghasilkan produksi DNA yang banyak sehingga dapat terlihat pada agarose atau gel poliakrilamida; jumlah DNA yang diperlukan untuk amplifikasi hanya sedikit karena dengan PCR maka DNA dapat ditingkatkan jumlahnya secara eksponensial pada daerah pemotongan yang kemudian direplikasi
e. SNP (Single Nucleotide Polymorphism)
SNP adalah variasi urutan DNA yang terjadi dalam populasi. Urutan nukleotida tunggal A, T, C, dan G dalam susunan genom memiliki perbedaan antara spesies. Contohnya pada sampel DNA dua individu dalam spesies yang sama memiliki perbedaan nukleotida tunggal yaitu CCTAGTC dan CGTAGTC.
B. Teknik Seleksi dengan Marka Seleksi
Menurut Amadou et al., (2001), Rungnoi et al., (2012), taksonomi dari kacang bogor pada dasarnya berbeda berdasarkan morfologinya namun sering kali penampilannya dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga untuk menghindari adanya pengaruh lingkungan dalam melihat keragaman kacang bogor maka dilakukan pelacakan keragaman kacang bogor dengan menggunakan pengujian secara molekular, salah satunya adalah teknologi RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) dan didasarkan pada marker atau penanda genetik.
Sebagian besar teknik marka molekuler adalah teknik hasil modifikasi dari teknik PCR (Polymerase Chain Reaction) dengan mengamplifikasi genom dengan menggunakan primer acak dan menghasilkan perbedaan urutan DNA antara sampel-sampel DNA yang diambil dari individu-individu yang diuji. Perbedaan urutan basa pada DNA disebabkan karena pengikatan primer oligonukleotida berbeda sehingga menyebabkan pola larik hasil amplifikasi yang berbeda pula yang disebut polimorfisme. Polimorfisme inilah yang kemudian dijadikan penanda adanya keragaman genetik (Kusumawaty, 2007).
Aryani dan Diah (2007) menambahkan bahwa secara umum ada tiga tahap dalam amplifikasi yaitu denaturasi (denaturation), penempelan (annealing) dan pemanjangan (extension).
1. Tahap denaturasi terjadi pada suhu tinggi 94oC sehingga utas ganda DNA terpisah menjadi utas tunggal
2. Tahap penempelan sekuens primer dinamakan annealing dalam suhu berkisar 60oC yaitu peristiwa saat primer menempel pada DNA utas tunggal sebagai cetakan. Sintesis DNA berlangsung dari arah sekuens 5’ menuju 3’. Dalam tahap ini ditambahkan DNA polymerase contohnya Taq polymeras dan MgCl2 dan untuk kebutuhan energi ditambahkan dNTPs terdiri atas dTTP, dGTP, dATP dan dCTP.
3. Tahap ekstensi atau pemanjangan utas DNA terjadi pada suhu 72oC dilakukan hingga terbentuk utas DNA ganda yang baru.
Teknik analisis DNA dengan marka molekuler secara umum terdiri atas empat tahapan yaitu ekstraksi DNA, pengujian kualitas dan kuantitas DNA hasil ekstraksi, amplifikasi DNA dengan teknik RAPD dan pengujian kualitas dan kuantitas hasil amplifikasi
Berdasarkan Zulkifli et al., (2009), hasil DNA hasil amplifikasi kemudian diberikan skor sebelum diproses ke dalam software untuk mengetahui kedekatan antar sampel. Cara untuk pemberian skor adalah dengan memasukkan hasil amplifikasi ke dalam gel agarose 2,0% dan dilakukan elektroforesis dibawah UV transluminator dan difoto menggunakan dengan gel documentation system. Pemberian skor dalam penilaian saat elektroforesis adalah nilai 1 jika terdapat pita yang jelas dan 0 jika tida muncul pita yang jelas, Kusumadewi et al., (2010) menambahkan bahwa agar pemberian skor lebih standart maka skoring dengan berpatokan pada marker atau penanda sebagai penanda untuk menetapkan ukuran pita DNA. Data hasil skoring kemudian dimasukkan ke dalam software dan menghasilkan file dendrogram yang menunjukkan jarak genetik dari sampel.
Melalui sumber Anonymous (2013), setelah didapatkan skor data biner maka selanjutnya dilakukan analisis. Filogenetik adalah cabang ilmu genetik yang berhubungan dengan penilaian kekerabatan dan kedekatan genetik antar individu dalam satu atau lebih populasi. Organisme yang berkerabat dekat maka akan cenderung menunjukkan sekuens yang sama lebih tinggi, sementara jika jarak kekerabatannya jauh maka jumlah sekuens yang sama akan lebih sedikit. Filogenetik memiliki fungsi untuk menunjukkan hubungan evolusioner spesies divergen antar dua organisme sejak keduanya terpisah dari tetua yang sama (asal mula). Dalam pelaksanaannya, filogenetik terbagi atas dua metode yaitu metode fenetik yang berfungsi untuk menunjukkan pohon filogeni dengan memperhitungkan kemiripan sekuens yang dihasilkan. Pohon filogeni disebut dengan dendogram. Metode kedua adalah metode kladistik yaitu pembentukan pohon filogeni dengan dihitung dengan pertimbangan adanya jalur evolusi yang variatif. Pohon filogeninya disebut dengan cladogram.
Sekuens yang mirip diartikan sebagai sekuens yang memiliki kekerabatan yang lebih dekat. Jarak sekuens dapat ditunjukkan dengan matriks jarak (distance matrix) selanjutnya filogeni dilakukan kalkulasi algoritma untuk didapatkan cluster. Metode filogeni dapat mengkonstruksi taxa paling jauh hingga taxa yang paling dekat kekerabatannya. Manfaat dari pembentukan pohon filogeni salah satunya adalah untuk menunjukkan UPGMA (Unweighted Pair Group using Aritmathic Average).
C. Evaluasi hasil Seleksi dengan Marka Seleksi
Perkembangan kacang bogor di bidang molekular masih sedikit atau jarang dilakukan, seperti yang dilakuan oleh Posquet et al., (1999) menggunakan Isozim dan Amadou et al., (2001) menggunakan RAPD yang merupakan salah contoh pengembagan penelitian kacang bogor di bidang molekular. Namun demikian, Saleh (2012) menyebutkan bahwa hasil amplifikasi dengan menggunakan RAPD dalam Amadou et al., (2001) menunjukkan polimorfisme yang lebih tinggi jika dibandingkan amplifikasi dengan metode AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphisms) dalam Massawe et al., (2002) dan dengan metode isozyme dalam Pasquet et al., (1999).
Molosiwa (2012) juga melakukan penelitian mengeai kacang bambara, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa persentase polimorfisme dengan menggunakan teknik RAPD berkisar antara 57% hingga 100% dengan rata-rata dari 7 primer 85%, sementara dengan mikrosatelit menunjukkan polimorfisme antara 0% hingga 100% dengan rata-rata 29% polimorfis, hal ini menunjukkan bahwa RAPD memiliki tingkat polimorfis tinggi dan banyak digunakan karena lebih mudah.
Keunggulan RAPD dibandingkan dengan teknik yang lainnya seperti misalkan teknik mikrosatelit seperti yang pernah diteliti oleh Mukakalisa (2010) terletak pada persentase polimorfiknya. Mukakalisa menunjukkan bahwa dari 7 primer RAPD yang digunakan yaitu OPA07 100%, OPAI15 68%, OPB08 100%, OPL12 75%, OPP04 57%, OPP15 100%, dan OPP19 100%, sehingga didapatkan rata-rata persentase polimorfisme 85%. Mukakalisa juga menunjukkan dalam penelitian yang sama menggunakan bahan kacang bogor menggunakan primer mikrosatelit persentase polimorfik yaitu MARA001 0%, MARA020 0%, MARA037 100%, MARA038 14%, MARA043 14%, MARA046 0%, MARA052 0%, dan MARA065 50%, sehingga rata-rata persentase polimorfisme 29%. Hasil persentase polimorfisme dari dua teknik tersebut, RAPD dan mikrosatelit menunjukkan bahwa polimorfisme yang paling besar ditunjukkan oleh teknik RAPD sehingga teknik tersebut menurut pendapat Mukakalisa (2010) merupakan teknik yang cocok untuk dijadikan sebagai marker untuk kacang bambara.
Berbeda dengan hasil persentase polimorfisme Mukakalisa (2010), Rungnoi et al., (2012) menyatakan bahwa persentase polimorfisme dari 14 primer RAPD adalah 70,1% lebih rendah dibandingkan dengan persentase polimorfisme 3 primer ISSR yaitu 72,37%, meskipun demikian, polimorfisme pada teknik RAPD sangat ditentukan oleh kesesuaian antra nomer primer yang digunakan dengan sampel, sehingga pada nomer primer yang tidak sesuai akan menunjukkan polimorfisme yang lebih rendah. Sementara Amadou et al., (2001) dalam penelitiannya tentang eksplorasi keragaman plasma nutfah kacang bogor menggunakan teknik RAPD menunjukkan bahwa persentase polimorfisme dari 17 primer RAPD yang digunakan menunjukkan persentase 51% dan telah mampu menghasilkan informasi mengenai keragaman beberapa aksesi kacang bogor yang ditelitinya, sehingga RAPD dapat dijadikan sebagai teknik marker untuk kacang bogor seperti yang dikemukakan oleh Mukakalisa (2010).
D. Penutup
a. Kesimpulan
Marka molekuler dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk mengetahui kekerabatan dalam spesies itu sendiri, selain itu hal ini untuk memudahkan pengelompokan karena dimungkinkan selama identifikasi morfologi terjadi bias karena adanya pengaruh lingkungan.
b. Rekomendasi
Marka molekuler dapat digunakan dalam identifikasi kedekatan secara genetik dan dibandingkan dengan hasil pengamatan secara morfologi sehingga dapat diketahui adanya perbedaan dan kemiripan antara sampel yang diteliti.
Daftar Pustaka
Ahmad, N.,S. 2012. Genetic Analysis Of Plant Morphology In Bambara Groundnut [Vigna Subterranea (L.) Verdc.]. Degree of Doctor of Philosophy University of Nottingham. UK
Amadou, H.I., P.J. Bebeli, and P.J. Kaltsikes. 2001. Genetic diversity in Bambara groundnut (Vigna subterranea L.) germplasm revealed by RAPD markers. Can. J. Agric. Sci. 44 (6): 995-999
Anonymous. 2013. Principles of PCR: Phylogenetics. Available at http://www.bioline.org.br/request?ej990!7-28/03/2010-10:26
Aryani, A., dan D. Kusumawaty. 2007. Prinsip-prinsip (Polymerase Chain Reaction) PCR dan Aplikasinya. Program Studi Biologi Jurusan Pendidikan Biologi UPI. Jakarta. Pp. 71-74
Kusumadewi, Y., Y.S. Poerba, T. Partomihardjo. 2010. Keragaman Genetika Ramin [Gonystylus bancanus (Miq.) Kurz] dari Provinsi Riau Berdasarkan Profil Random Amplified Polymorphic DNA. Indoensia. J. Agric. Sci. 6(2): 173-183
Kusumawaty, D. 2007. RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). Program Studi Biologi Jurusan Pendidikan Biologi UPI. Jakarta
Massawe, F.J., M. Dickinson, J.A. Roberts, S.N. Azam-Ali. 2002. Genetic Diversity in Bambara Groundnut Landrace (Vigna Subterranea (L.) Verdc.) Revealed by RALF Markers. Canada. J. Agric. Sci. 45:1175-1180
Molosiwa, O.O. 2012. Genetic Diversity And Population Structure Analysis Of Bambara Groundnut [Vigna Subterranea (L.) Verdc.] Landraces Using Morpho-Agronomic Characters And Ssr Markers. Ph.D. Thesis. Division Of Plant And Crop Sciences The University Of Nottingham Sutton Bonington Campus Loughborough, Leicestershire UK
Mukakalisa, C., 2010. Molecular, Environmental And Nutritional Evaluation Of Bambara Groundnut (Vigna Subterranea (L.) Verdc.) For Food Production In Namibia. Ph.D. Thesis. The University Of Namibia. Namibia
Pasquet. R.S., S. Schwedes., and P. Gepts. 1999. Isozyme Diversity in Bambara Groundnut. Crop. Sci. 39:1228-1236
Rungnoi, O., J. Suwanprasert, P. Somta and P. Srinives. 2012. Molecular Genetic Diversity Of Bambara Groundnut (Vigna subterranea L. Verdc.) Revealed By Rapd and Issr Marker Analysis. Sabrao. J. Breed. Genet. 44 (1) 87-101
Warta Biogen. 2008. Perkembangan Marka Molekuler untuk Seleksi Tanaman. Warta Biogen 4(1): Pp1-4
Zulkifli. Y., N.B. Alitheen, R. Son, A.R. Raha, L. Samuel, S.K. Yeap and M. Nishibuchi. 2009. Random Amplified Polymorphic DNA-PCR and ERIC-PCR Analysis on Vibrio Parahaemolyticus Isolated From Cockles In Padang, Indonesia. J. Agric. Sci. 16: 141-150
1