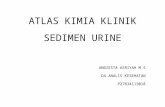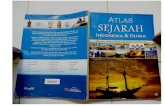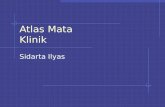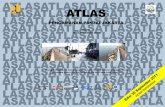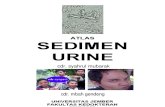Penyelidikan Prospek Pasir Besi di Dusun Sungai Topo, Desa ...
Tugas Praktikum Atlas ,Posisi Peta, Peta Topo Fix Print
description
Transcript of Tugas Praktikum Atlas ,Posisi Peta, Peta Topo Fix Print

TUGAS PRAKTIKUM GEOLOGI FISIK
PENGENALAN ATLAS, POSISI PETA, DAN
PETA TOPOGRAFI
Disusun oleh :
BEKTI GUNAWAN
410013002
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL
YOGYAKARTA
JURUSAN TEKNIK GEOLOGI
PROGRAM STUDI S1
2013

BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengertian Peta
Peta ialah gambaran permukaan bumi yang lebih terperinci dan diperkecil menurut ukuran
geometris pada suatu bidang datar sebagaimana penampakannya dari atas. Secara umum, peta
berfungsi untuk:
a) menunjukkan lokasi pada permukaan bumi;
b) menggambarkan luas dan bentuk berbagai gejala, baik gejala alamiah maupun gejala
insaniah;
c) menentukan arah serta jarak suatu tempat;
d) menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat;
e) menyajikan persebaran sifat-sifat alami dan nonalami;
f) melukiskan luas dan pola;
g) memungkinkan pengambilan kesimpulan dari data atau informasi yang tersaji, serta;
h) memperlihatkan gerak perubahan dan prediksi dari pertukaran barang-barang persebaran
aktivitas industri, arus produksi, mobilitas manusia, dan sebagainya.
Suatu peta dikatakan baik dan lengkap apabila memuat unsur-unsur peta sebagai berikut.
a. Judul Peta
Judul peta terletak di bagian atas yang biasanya menyebutkan jenis peta, lokasi wilayah
yang dipetakan, serta keadaan yang digambarkan dalam peta tersebut.
b. Skala Peta
Merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jarak dalam peta jika dibandingkan
dengan jarak sesungguhnya.
c. Tanda Arah
Tanda arah atau sering pula disebut mata angin, biasanya menyerupai panah yang ujungnya
runcing menunjukkan arah utara.
d. Tata Warna
Penggunaan warna pada peta bertujuan untuk memperjelas atau mempertegas objek-objek
yang ingin ditampilkan.

e. Simbol Peta
Merupakan tanda-tanda konvensional yang umum dipakai untuk mewakili keadaan yang
sesungguhnya ke dalam peta. Simbol peta dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
1) Simbol fisiografis, seperti: relief, hidrologis, oseanologis, klimatologis, dan sebagainya.
2) Simbol kultur, seperti: jalur transportasi, batas wilayah, dan sebagainya.
f. Lettering
Lettering ialah semua tulisan atau pun angka yang lebih mempertegas arti dari simbol-
simbol yang ada.
g. Legenda
Merupakan usaha memperjelas keterangan dari simbol yang ada dalam peta. Biasanya
terletak di bagian tepi peta.
h. Inset Peta
Merupakan upaya untuk memberikan tekanan terhadap sesuatu yang ada dalam peta. Inset
peta bertujuan untuk:
1) menunjukkan lokasi yang penting, tetapi kurang jelas dalam peta, dan
2) mempertajam atau memperjelas salah satu bagian peta.
i. Garis Astronomis
Berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat. Biasanya hanya dibuat tanda di tepi atau
pada garis tepi dengan menunjukkan angka derajat, menit, dan detiknya tanpa membuat garis bujur
atau lintangnya.
j. Garis Tepi
Biasanya dibuat rangkap. Garis ini dapat dijadikan pertolongan dalam membuat peta pulau,
atau suatu wilayah agar tepat di tengah-tengahnya.
k. Tahun Pembuatan
Tahun pembuatan atau reproduksi berlainan dengan tahun keadaan peta. Misalnya, peta
yang kita buat adalah tentang sebaran penduduk Indonesia tahun 2000, yang kita buat pada tahun
2006, maka dalam judul harus kita cantumkan “Peta Sebaran Penduduk Indonesia Tahun 2000”.
Sedangkan, di luar garis kita tuliskan tahun reproduksinya, yaitu tahun 2006.

B. Jenis-jenis Peta
Menurut jenisnya, peta dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai
berikut.
a. Jenis Peta Berdasarkan Skalanya
1) Peta teknik/kadaster, yaitu peta yang berskala 1 : 100 s.d. 1 : 5000.
2) Peta berskala besar, 1 : 5.000 s.d. 1 : 250.000.
3) Peta berskala medium, 1 : 250.000 s.d. 1 : 500.000.
4) Peta berskala kecil, 1 : 500.000 s.d. 1.000.000.
b. Jenis Peta Berdasarkan Keadaan Objek
1) Peta dinamik, yaitu peta yang menggambarkan labil atau meningkat. Misalnya peta
transmigrasi atau urbanisasi, peta aliran sungai, peta perluasan tambang, dan
sebagainya.
2) Peta stasioner, yaitu peta yang menggambarkan keadaan stabil atau tetap. Misalnya, peta
tanah, peta wilayah, peta geologi, dan sebagainya.
c. Jenis Peta Topografi
Yang dimaksud peta topografi adalah peta yang menggambarkan konfigurasi permukaan
bumi. Peta ini dilengkapi dengan penggambaran, antara lain, perairan (hidrografi), kebudayaan,
dan sebagainya.
d Jenis Peta Statistik
1) Peta statistik distribusi kualitatif, adalah peta yang menggambarkan kevariasian jenis
data, tanpa memperhitungkan jumlahnya, contohnya: peta tanah, peta budaya, peta
agama, dan sebagainya.
2) Peta statistik distribusi kuantitatif, adalah peta yang menggambarkan jumlah data, yang
biasanya berdasarkan perhitungan persentase atau pun frekuensi. Misalnya, peta
penduduk, peta curah hujan, peta pendidikan, dan sebagainya.
e Jenis Peta Berdasarkan Fungsi atau Kepentingan
Berdasarkan fungsi atau kepentingannya, peta dapat dibedakan menjadi:
1) peta geografi dan topografi;
2) Peta geologik, hidrologi, dan hidrografi;

3) peta lalu lintas dan komunikasi;
4) peta yang berhubungan dengan kebudayaan dan sejarah, misalnya: peta bahasa, peta ras;
5) peta lokasi dan persebaran hewan dan tumbuhan;
6) peta cuaca dan iklim;
7) peta ekonomi dan statistik.

BAB II
PEMBAHASAN
A.1. ATLAS
1. Pengertian atlas
Atlas yaitu kumpulan peta-peta yang disusun secara teratur dan dijilid rapi menjadi
sebuah buku. Nama atlas berasal dari nama dewa bangsa Yunani, yaitu Atlas, dewa yang
memegang bumi di atas pundaknya. Pngertian yang lain Atlas adalah kumpulan peta yang
disatukan dalam bentuk buku, tetapi juga ditemukan dalam bentuk multimedia. Atlas dapat
memuat informasi geografi, batas negara, statisik geopolitik, sosial, agama, dan ekonomi.
2. Jenis-jenis atlas
Atlas dapat dibedakan menurut wilayah, tujuan dan isinya.Berdasarkan luas
jangkauan peta-peta yang dimuat dalam atlas, atlas dibedakan menjadi:
a. Atlas berdasarkan wilayah
1) Atlas semesta, yaitu atlas yang memuat peta-peta tentang alam semesta/jagad raya.
Contoh: peta tata surya, galaksi, planet-planet, satelit, peredaran benda angkasa, dan
perbintangan.
2) Atlas dunia, yaitu atlas yang memuat peta-peta keadaan alam negara di seluruh
dunia. Isi atlas dunia antara lain: peta-peta benua, peta wilayah negara, dan peta
samudra.
3) Atlas nasional, yaitu atlas yang memuat peta-peta wilayah atau pulau dalam satu
wilayah negara. Contoh atlas nasional, yaitu: Atlas Nasional Indonesia, Atlas
Nasional Malaysia.
4) Atlas regional, yaitu atlas yang menyajikan gambaran mengenai aspek geografi dari
suatu provinsi.
5) Atlas kota, yaitu atlas yang menyajikan informasi tentang kondisi geografis suatu
kota.

b. Atlas berdasarkan tujuan
1) Atlas referensi, atlas yang dibuat sebagai referensi terhadap suatu hal. Contoh : atlas
perencanaan wilayah.
2) Atlas wisata, atlas yang memuat informasi-informasi wisata dalam suatu wilayah.
3) Atlas pendidikan, atlas yang dibuat untuk kepentingan pendidikan. Contoh : atlas
yang memuat informasi flora-fauna, kependudukan dan lain-lain.
c. Atlas berdasarkan isi
1) Atlas umum, atlas yang memberikan informasi umum. Contoh : atlas dunia
2) Atlas tematik, atlas yang memberikan informasi khusus. Contoh : atlas wisata.
3. Unsur-unsur atlas
a. Judul atlas, Judul atlas menunjukkan isi atau jenis atlas.
b. Daftar isi, memuat judul-judul peta dengan disertai halamannya. Daftar isi akan
memudahkan pengguna atlas dalam mencari peta yang dibutuhkannya.
c. Legenda, berisi simbol-simbol dan singkatan-singkatan pada setiap peta dalam atlas.
d. Tahun pembuatan atlas, tujuan mencantumkan tahun pembuatan atlas adalah untuk
mengetahui kapan atlas tersebut dibuat. Hal ini penting karena ada sebagian informasi
dalam atlas yang bersifat dinamis, misalkan tempat wisata yang seringkali ada
penambahan, pemindahan atau pengurangan.
e. Indeks, merupakan keterangan dari simbol-simbol yang ada di dalam atlas. Dengan
indeks, pengguna atlas akan mudah untuk menemukan obyek yang dicari dalam suatu
peta wilayah. Indeks pada atlas berisi nama-nama sungai, kota, danau, dan penjelasan-
penjelasan lainnya. Contoh penggunaan indeks pada atlas yaitu:
Misalnya, kita akan mencari Kota Surakarta, langkah-langkahnya adalah sebagai
berikut:
- Kita cari pada indeks deretan huruf S.
- Setelah menemukan deretan huruf S, kita cari Surakarta. Misalnya dalam indeks
tertulis 20 D4, artinya:
20 : menunjukkan nomor urut halaman atlas.
D : menunjukkan kolom di antara dua garis vertikal atau garis bujur.

4 : menunjukkan di antara dua garis horizontal atau garis lintang.
- Langkah seterusnya kita cari atlas halaman 20, kolom D, lajur 4, maka kita akan
menemukan letak Kota Surakarta.
Gambar. Contoh Daftar indeks yang terdapat pada atlas
4. Manfaat atlas
a. Mencari informasi keadaan fisik alam, seperti: keadaan iklim, flora, danau, laut, dan
lain-lain.
b. Mencari informasi letak suatu tempat, seperti: letak suatu negara, provinsi, kota,
pelabuhan
c. membandingkan luas, letak, dan lokasi tertentu antarwilayah (provinsi, negara, benua).
d. membandingkan perbedaan relief antarwilayah.
5. Mencari informasi geografi pada atlas
Cara mencari informasi geografi pada atlas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:
a. Mencari informasi geografi pada atlas dengan daftar isi
Cara mencari informasi geografi pada atlas dengan daftar isi sangat mudah, seperti
kita mencari halaman pada buku pelajaran biasa. Contoh: Kita akan mencari Pulau
Jawa dalam atlas, caranya sangat mudah, yaitu:
a. Kita lihat daftar isi.
b. Setelah kita lihat dalam daftar isi akan tertulis "Peta Pula Jawa ............ 16".

c. Berarti kita tinggal membuka atlas pada halaman 16, maka kita dapat menemukan
Peta Pulau Jawa.
b. Mencari informasi geografi pada atlas dengan menggunakan indeks
Mencari informasi geografi pada atlas dengan indeks sangat mudah.
Contoh: Kita akan mencari letak kota Bekasi, langkah-langkahnya yaitu:
a. Kita cari pada kelompok kota berabjad B.
b. Jika sudah ketemu di indeks, kita cari Bekasi, misal Bekasi tertulis, 40 D3.
c. Maka kota Bekasi pada atlas terdapat pada halaman 40, kolom D, baris ke 3.
d. Dengan demikian, kita tinggal mencari kota Bekasi tersebut pada atlas.
c. Mencari informasi geografi pada atlas menggunakan garis lintang dan garis bujur
Untuk mencari letak suatu tempat atau kota di dalam atlas dengan bantuan garis
lintang dan garis bujur, kita dapat melihat titik potong kedua garis tersebut. Misalnya,
kita ingin mencari letak kota Semarang. Kita lihat letak astronomi kota Semarang. Jika
letak astronomis kota Semarang 7° LS dan 111° BT, maka kota Semarang terletak pada
perpotongan garis lintang 7° LS dan garis bujur 111° BT.
6. Syarat-syarat Atlas
Atlas sebagai sumber informasi geografi hendaknya memenuhi syarat sebagai
berikut.
1. Menggambarkan suatu daerah dengan data yang akurat.
2. Memiliki formulasi warna atau simbol lain yang tepat sehingga menarik.
3. Dilengkapi dengan diagram-diagram dan data statistik daerah yang dipetakan.
4. Dalam membuat peta harus mengikuti aturan-aturan kartografi dan menggunakan
proyeksi peta tertentu yang disesuaikan dengan tujuan.

A.2. POSISI PETA
Orientasi peta adalah menyamakan kedudukan peta dengan medan sebenarnya (secara
praktis menyamakan utara peta dengan utara magnetis). Untuk keperluan orientasi ini, kita perlu
mengenal tanda-tanda medan yang ada dilokasi. Ini bisa dilakukan dengan menanyakan kepada
penduduk setempat nama-nama gunung, bikit, sungai, atau tanda-tanda medan lainnya, atau
dengan mengamati kondisi bentang alam yang terlihat dan mencocokkan dengan gambar kontur
yang ada dipeta, untuk keperluan praktis, utara magnetis dianggap sejajar dengan utara
sebenarnya, tanpa memperlitungkan adanya deklinasi. Langkah-langkah orientasi peta :
a) Cari tempat terbuka agar dapat melihat tanda-tanda medan yang menyolok;
b) Letakkan peta pada bidang datar;
c) Letakkan kompas diatas peta dan sejajarkan antara arah utara peta dengan utara magnetis/utara
kompas, dengan demikian letak peta akan sesuai dengan bentang alam yang dihadapi.
d) Cari tanda-tanda medan yang
paling menonjol disekeliling dan temukan tanda medan tersebut dipeta, lakukan untuk beberapa
tanda medan.
e) Ingat tanda medan itu, bentuknya dan tempatnya dimedan sebenarnya maupun dipeta, ingat-
ingat tanda medan
yang khas dari setiap tanda medan.
Azimuth dan Back Azimuth
Azimuth ialah besar sudut antara utara magnetis (nol derajat) dengan titik/sasaran yang kita
tuju,azimuth juga sering disebut sudut kompas, perhitungan searah jarum jam. Ada tiga macam

azimuth yaitu :
a) Azimuth Sebenarnya,yaitu besar sudut yang dibentuk antara utara sebenarnya dengan titik
sasaran;
b) Azimuth Magnetis,yaitu sudut yang dibentuk antara utara kompas dengan titik sasaran;
c) Azimuth Peta,yaitu besar sudut yang dibentuk antara utara peta dengan titik sasaran.
Back Azimuth adalah besar sudut kebalikan/kebelakang dari azimuth. Cara
menghitungnya : bila sudut azimuth lebih dari 180 derajat maka sudut azimuth dikurangi 180
derajat, bila sudut azimuth kurang dari 180 derajat maka sudut azimuth dikurangi 180 derajat, bila
sudut azimuth = 180 derajat maka back azimuthnya adalah 0 derajat
atau 360 derajat.
Resection
Resection adalah menentukan kedudukan/ posisi di peta dengan menggunakan dua atau
lebih tanda medan yang dikenali. Teknik resection membutuhkan bentang alam yang terbuka
untuk dapat membidik tanda medan. Tidak selalu tanda medan harus selalu dibidik, jika kita
berada di tepi sungai, sepanjang jalan, atau sepanjang suatu punggungan, maka hanya perlu satu
tanda medan lainnya yang dibidik.
Langkah-langkah resection :
a) Lakukan orientasi peta;
b) Cari tanda medan yang mudah dikenali dilapangan dan di peta, minimal dua buah;
c) Dengan penggaris buat salib sumbu pada pusat tanda-tanda medan itu;
d) Bidik dengan kompas tanda-tanda
medan itu dari posisi kita,sudut bidikan dari kompas itu disebut azimuth;
e) pindahkan sudut bidikan yang didapat
ke peta, dan hitung sudut pelurusnya;
f) perpotongan garis yang ditarik dari sudut-sudut pelurus tersebut adalah
posisi kita di peta
Intersection
Prinsip intersection adalah menentukan posisi suatu titik (benda) di pet dengan
menggunakan dua atau lebih tanda medan yang dikenali dilapangan. Intersection digunakan untuk

mengetahui atau memastikan posisi suatu benda yang terlihat dilapangan, tetapi sukar untuk
dicapai. Pada intersection, kita sudah yakin pada posisi kita di peta. Langkah-langkah melakukan
intersection :
a) lakukan orientasi medan, dan pastikan posisi kita;
b) bidik obyek yang kita amati;
c) pindahkan sudut yang kita dapat dipeta;
d) bergerak ke posisi lain, dan pastikan posisi tersebut
di peta, lakukan langkah b dan c;
e) perpotongan garis perpanjangan dari dua sudut yang didapat adalah posisi
obyek yang dimaksud.
Koreksi sudut
Pada pembahasan utara telah dijelaskan bahwa utara sebenarnya dan utara kompas
berlainan. Hal ini sebetulnya
tidaklah begitu menjadi masalah penting jika selisih sudutnya sangat kecil, akan tetapi pada
beberapa tempat, selisih sudut/deklinasi sangat besar sehingga perlu dilakukan perhitungan koreksi
sudut yang didapat dari kompas(azimuth)yaitu :
A. Dari kompas (K) dipindahkan ke peta (P): P= K +/- (DM +/- VM)
B. Dari peta( P) dipindahkan ke kompas (K): K= P +/- (DM +/- VM)
Keterangan:
Tanda +/- diluar kurung untuk DM (deklinasi magnetis/iktilaf magnetis)
= dari K ke P: DM ke timur tanda (+), DM ke barat tanda (-) = dari P ke K: DM ke timur tanda (-),
DM ke barat
tanda (+)
Tanda +/- di dalam kurung untuk VM (variasi magnetis)
=tanda (+) untuk increase/naik; tanda (-) untuk decrease/turun.
Contoh Perhitungan:
Diketahui sudut kompas/azimuth 120 derajat, pada legenda peta tahun 1942 tersebut: DM 1
derajat 30 menit ketimur, VM 2 menit increase, lalu berapa sudut yang akan kita pindahkan ke
peta?
P= K=+/- (DM +/- VM) ingat! kompas ke peta, DM ke timur VM increase

besar VM sekarang (2002)= (2002-1942)x 2 menit
= 120 menit= 2 derajat (1 derajat=60 menit)
sudut P= 120 derajat + (1 menit 30 detik + 2 derajat)
= 123 derajat 30 menit, jadi sudut yang dibuat di peta adalah 123 1/2 derajat.
Analisa Perjalanan
Analisa perjalanan perlu dilakukan agar kita dapat membayangkan kira-kira medan apa yang
akan kita lalui, dengan mempelajari peta yang akan dipakai. Yang perlu di analisa adalah jarak,
waktu dan tanda medan.
a. Jarak
Jarak diperkirakan dengan mempelajari dan menganalisa peta, yang perlu diperhatikan
adalah jarak yang sebenarnya yang kita tempuh bukanlah jarak horizontal. Kita dapat
memperkirakan jarak (dan kondisi medan) lintasan yang akan ditempuh dengan memproyeksikan
lintasan, kemudian mengalihkannya dengan skala untuk memperoleh jarak sebenarnya.
b. Waktu
Bila kita dapat memperkirakan jarak lintasan, selanjutnya kita harus memperkirakan berapa
lama waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Tanda medan juga bisa untuk
menganalisa perjalanan dan menjadi
pedoman dalam menempuh perjalanan.
c. Medan Tidak Sesuai Peta
Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan bahwa peta yang kita pegang salah. Memang
banyak sungai-sungai
kecil yang tidak tergambarkan di peta, karena sungai tersebut kering ketika musim kemarau. Ada
kampung yang sudah berubah, jalan setapak yang hilang, dan banyak perubahan-perubahan lain
yang mungkin terjadi.

A.3.PETA TOPOGRAFI
Peta Topografi
Berasal dari bahasa yunani, topos yang berarti tempat dan graphi yang berarti
menggambar. Peta topografi memetakan tempat-tempat dipermukaan bumi yang berketinggian
sama dari permukaan laut menjadi bentuk garis-garis kontur, dengan satu garis kontur mewakili
satu ketinggian. Peta topografi mengacu pada semua ciri-ciri permukaan bumi yang dapat
diidentifikasi, apakah alamiah atau buatan, yang dapat ditentukan pada posisi tertentu.
Oleh sebab itu, dua unsur utama topografi adalah ukuran relief (berdasarkan variasi elevasi
axis) dan ukuran planimetrik (ukuran permukaan bidang datar). Peta topografi menyediakan data
yang diperlukan tentang sudut kemiringan, elevasi, daerah aliran sungai, vegetasi secara umum
dan pola urbanisasi. Peta topografi juga menggambarkan sebanyak mungkin ciri-ciri permukaan
suatu kawasan tertentu dalam batas-batas skala.
Gambar 1. Contoh Peta Topografi Wilayah Lumadjang, Indonesia
Peta topografi dapat juga diartikan sebagai peta yang menggambarkan kenampakan alam
(asli) dan kenampakan buatan manusia, di perlihatkan pada posisi yang benar. Selain itu peta
topografi dapat
di artikan peta yang menyajikan informasi spasial dari unsur-unsur pada muka bumi dan dibawah
bumi meliputi, batas administrasi, vegetasi dan unsur-unsur buatan manusia.

Fungsi Peta Topografi dalam Pemetaan Geologi
Peta topografi adalah peta yang menggambarkan tinggi rendahnya muka bumi. Dari peta
topografi kita dapat mengetahui ketinggian suatu tempat secara akurat. Cara menginterpretasikan
peta topografi berbeda dengan peta umum karena symbol-simbol yang digunakan berbeda.
Pada peta topografi terdapat garis-garis kontur yang menunjukkan relief muka bumi. Peta
topografi menunjukkan bentuk-bentuk muka bumi. Bentuk-bentuk muka bumi tersebut adalah
sebagai berikut.
Lereng
Gambar 2. Kenampakan Lereng pada Peta Topografi
Cekungan (Depresi)
Cekungan (Depresi) pada peta topografi digambarkan seperti di bawah ini!
Gambar 3. Cekungan atau Depresi
Bukit

Bukit pada peta topografi digambarkan seperti di bawah ini.
Gambar 4. Bukit pada Peta Topografi
Pegunungan
Pegunungan pada peta topografi digambarkan seperti di bawah ini!
Gambar 5. Kenampakan Pegunungan pada Peta Topografi
Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi

Gambar 6. Penampang Melintang Bentuk Muka Bumi
Penampang melintang adalah penampang permukaan bumi yang dipotong secara tegak
lurus. Dengan penampang melintang maka dapat diketahui/dilihat secara jelas bentuk dan
ketinggian suatu tempat yang ada di muka bumi. Untuk membuat sebuah penampang melintang
maka harus tersedia peta topografi sebab hanya peta topografi yang dapat dibuat penampang
melintangnya.
Peta merupakan gambaran dua dimensi dari suatu obyek yang dilihat dari atas yang
ukurannya direduksi. Hakekat dari interpretasi peta topografi adalah sebagai pelengkap ilmu
geologi dengan latihan teknik penafsiran geologi melalui peta topografi.
Pengertian dari peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk penyebaran dan
ukuran dari roman muka bumi yang kurang lebih sesuai dengan daerah yang sebenarnya.
Unsur-unsur yang penting terdapat dalam suatu peta topografi meliputi :
1. Relief
Adalah beda tinggi suatu tempat atau gambaran kenampakan tinggi rendah suatu daerah
serta curam landainya sisi-sisi perbukitan. Jadi menunjukkan perbedaan tinggi rendahnya
permukaan bumi.
Sebagai contoh :
bukit
lembah
daratan
lereng

pegunungan
Relief terjadi antara lain karena perbedaan resistensi antara batuan terhadap proses erosi
dan pelapukan (eksogen) juga dipengaruhi gejala-gejala asal dalam (endogen) perlipatan, patahan,
kegiatan gunung api dan sebagainya. Dalam peta topografi penggambaran relief dengan :
Garis hachures
Yaitu garis-garis lurus yang ditarik dari titik tertinggi ke arah titik yang lebih rendah
disekitarnya dan ditarik searah dengan lereng. Semakin curam lerengnya maka semakin rapat pula
garisnya sebaliknya garis akan renggang jika reliefnya landai.
Shading (bayangan)
Bayangan matahari terhadap earth feature dan biasanya dikombinasi dengan peta kontur.
Pada daerah yang curam akan memberikan bayangan gelap sebaliknya daerah yang lancai
berwarna cerah.
Tinting (pewarnaan)
Warna-warna tertentu. Semakin tinggi reliefnya warna akan semakin gelap.
Kontur
Yaitu dengan cara menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian sama. Peta ini
paling penting untuk geologi karena sifatnya kualitatif dan kuantitatif.
Kualitatif : hanya menunjukkan pola dan penyebarannya bentuk-bentuk roman muka bumi.
Kuantitatif : selain menunjukkan pola dan penyebaran bisa juga mengetahui ukuran baik
secara horisontal maupun vertikal sehingga jelas gambaran tida dimensinya.
2. Drainage
Drainage pattern/pola pengaliran atau pola penyaluran adalah segala macam bentuk-bentuk
yang hubungannya dengan penyaluran air baik di permukaan maupun di bawah permukaan bumi.
Sebagai contoh sungai-sungai, danau atau laut dan sebagainya. Sungai-sungai itu sendiri

dipermukaan bumi ada yang terpolakan dan tidak terpolakan. Hal ini tergantung dari batuan dasar
yang dilaluinya.
Dalam hal ini pola/pattern didefinisikan sebagai suatu keseragaman di dalam :
bentuk (shape)
ukuran (size)
penyebarannya/distrubusi
Hubungan antar relief, batuan, struktur geologi dan drainage dalam macam-macam pola
penyaluran :
a. Dendritik
Mencerminkan sedimen yang horisontal atau miring, resistensi batuan seragam, kemiringan
lereng secara regional kecil. Bentuk pola penyaluran seperti pohon. Contohnya pada daerah
dengan sedimen lepas, daratan banjir, delta, rawa, pasang surut, kipas-kipas alluvial, dll.
b. Parallel
Umumnya mencirikan kemiringan lereng yang sedang-curam tetapi juga didapatkan pada
daerah-daerah dengan morfologi yang parallel dan memanjang. Contohnya pada lereng-lereng
gunung api. Biasanya akan berkembang menjadi pola dendritik atau trellis.
c. Trellis
Terdapat pada daerah dengan batuan sedimen yang terlipat, gunung api, daerah dengan
rekahan parallel. Contohnya pada perlipatan menujam, patahan parallel, homoklin dan sebagainya.
d. Rectangular
Mengikuti kekar-kekar dan patahan.
e. Radial
Mencerminkan gunung api kubah (dome). Terdapat pula pola yang sentripetal (kebalikan
dari radial).
f. Annular
Mencerminkan struktur kubah yang telah mengalami erosi bagian puncaknya.
Dari contoh-contoh pola pengaliran tersebut merupakan pola dasar penyaluran yang sangat
membantu untuk penafsiran suatu struktur geologi.

3. Culture
Yaitu segala bentuk hasil budi daya manusia. Misalnya perkampungan, jalan, persawahan
dan sebagainya. Culture membantu geologi dalam penentuan lokasi. Pada umumnya pada peta
topografi, relief akan digambarkan dengan warna coklat, drainage dengan warna biru dan culture
dengan warna hitam.
4. Kelengkapan Peta Topografi
Pada peta topografi yang baik harus terdapat unsur/keterangan yang dapat digunakan untuk
berbagai kegiatan penelitian atau kemiliteran, yaitu :
a. Skala
Merupakan perbandingan jarak horisontal sebenarnya dengan jarak pada peta. Perlu
diketahui bahwa jarak yang diukur pada peta adalah menunjukkan jarak-jarak horisontal. Ada 3
macam skala yang biasa dipakai dalam peta topografi.
1. Representative Fraction Scale (Skala R.F.)
Ditunjukkan dengan bilangan pecahan. Contohnya 1 : 10.000. Artinya 1 cm di dalam peta
sama dengan 10.000 cm di lapangan (sama dengan 100 meter di lapangan). Kelemahan dari skala
ini bila peta mengalami pemuaian/penciutan maka skala tidak berlaku lagi.
2. Graphic Scale
Yaitu perbandingan jarak horisontal sesungguhnya dengan jarak dalam peta, yang
ditunjukkan dengan sepotong garis. Contohnya
0 300 m
Skala ini adalah paling baik karena tidak terpengaruh oleh pemuaian maupun penciutan dari peta.
3. Verbal Scale
Dinyatakan dengan ukuran panjang. Contohnya 1 cm = 10 km ato 1 cm = 5 km.
Skala ini hampir sama dengan skala R.F.
Dari ketiga macam skala tersebut di atas, yang umum/paling banyak digunakan dalam peta geologi
atau topografi adalah kombinasi skala grafis dan skala R.F.
b. Arah Utara Peta

Salah satu kelengkapan peta yang tidak kalah penting adalah arah utara, karena tiap peta
yang dapat digunakan dengan baik haruslah diketahui arah utaranya. Arah utara ini berguna untuk
penyesuaian antara arah utara peta dengan arah utara jarum kompas.
Ada 3 macam arah utara jarum kompas, yaitu :
1. Arah Utara Magnetik (Magnetic North = MN)
2. Grid North
3. True North
c. Legenda
Pada peta topografi banyak digunakan tanda untuk mewakili bermacam-macam keadaan
yang ada di lapangan dan biasanya terletak di bagian bawah dari peta.
d. Judul Peta
Judul peta merupakan nama daerah yang tercantum dalam peta dan berguna untuk
pencarian peta bila suatu waktu diperlukan.
e. Converage Diagram
Maksudnya peta tersebut dibuat dengan cara atau metoda yang bagaimana, hal ini untuk
dapat memperkirakan sampai sejauh mana kebaikan/ketelitian peta, misalnya :
- Dibuat berdasarkan foto udara
- Dibuat berdasarkan pengukuran di lapangan
f. Indeks Administrasi
Pembagian daerah berdasarkan hukum pemerintahan, hal ini penting untuk memudahkan
pengurusan surat izin untuk melakukan atau mengadakan penelitian/pemetaan.
g. Index of Adjoining Sheet
Menunjukkan kedudukan peta yang bersangkutan terhadap lembar-lembar peta
disekitarnya.
h. Edisi Peta
Dapat dipakai untuk mengetahui mutu daripada peta atau mengetahui kapan peta tersebut
dicetak atau dibuat.

Peta topografi dengan garis kontur
Untuk memahami peta kontur perlu dipelajari terlebih dahulu tentang garis kontur beserta
sifat-sifatnya yang antara lain adalah sebagai berikut :
1. Garis Kontur
Adalah merupakan garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian
sama, yang diukur dari suatu bidang pembanding. Bidang ini biasanya diambil dari permukaan air
laut rata-rata.
2. Interval Kontur
Jarak vertikal antara garis kontur satu dengan garis kontur lainnya yang berurutan.
3. Indeks Kontur
Garis kontur yang dicetak tebal pada peta, yang mana merupakan kelipatan tertentu dari
beberapa garis kontur (kelipatan lima atau sepuluh).
4. Kontur Setengah
Garis kontur yang harga ketinggiannya adalah setengah interval kontur. Biasanya digambar
dengan garis putus-putus.
Penentuan interval kontur.
Biasanya interval kontur pada peta tergantung dari :
1. Skala peta
2. Relief dari daerah yang bersangkutan
3. Tujuan dari peta, apakah untuk pekerjaan geologi umum maupun geologi teknik atau
untuk kepentingan militer. Jika tidak ada hal-hal khusus atau dalam keadaan umum, maka
interval kontur dapat ditentukan sebagai berikut :
IK (Interval Kontur) = skala peta X 1/2000
Misalnya skala peta 1 : 50.000
IK = 50.000 X 1/2000 = 25 meter

Sifat-sifat garis kontur :
1. Garis tidak bisa saling berpotongan kecuali dalam keadaan yang ekstrim, dimana topografi
berupa over hanging cliff.
2. Garis kontur tidak akan bertemu dengan garis kontur yang mempunyai nilai ketinggian
yang berlainan.
3. Garis kontur akan renggang jika topografi landai dan akan rapat jika topografi curam.
4. Garis kontur menutup, menunjukkan naik ke arah dalam, kecuali garis kontur bergigi
menunjukkan depresi.
5. Garis kontur yang memotong lembah/sungai akan meruncing ke hulu.
6. Garis kontur harus digambarkan hingga batas tepi peta.
Menentukan titik ketinggian :
1. Pada indeks kontur langsung diketahui.
2. Pada intermediate kontur dihitung dari indeks kontur dengan memperlihatkan interval
kontur.
3. Diantara intermediate kontur dengan cara interpolasi.
Misal : Tinggi titik = x
= 150 + (3/4 x 25)
= 168 meter
4. Titik triangulasi.
Quadrangle System Peta Topografi di Indonesia
Indonesia mempunyai luas + 2.800.000 km2 dan terletak pada 6oLU – 11oLS dan 95oBT –
140oBT. Dalam pembuatan peta topografinya, dimana untuk memudahkan penyusunan
registrasinya, maka Indonesia dilakukan sistem Quadrangle. Adapun sistem quadrangle di

Indonesia ada dua macam, yaitu Sistem lama dan Sistem Baru, perbedaannya adalah pada
perbandingan luas peta, notasi dan pembagian derajat bujurnya.
1. Quadrangle Peta Sistem Lama
Pembagian kotak-kotak dengan luas 20’ X 20’
Titik 0o bujur di Jakarta, titik 0o Lintang Equator
Penomoran garis-garis lintang dengan angka romawi, sedang penomoran
garis bujur dengan angka Romawi.
Contoh :
No. lembar peta 45/XXI
Berskala 1 : 100.000
No. lembar peta 45/XXI-A
Berskala 1 : 50.000
No. lembar peta 45/XXI-c
Berskala 1 : 25.000
Luasnya + 9 x 9 km2.
2. Quadrangle Peta Sistem Baru
Perhatikan perubahan angka vertikal maupun horisontal.
Pembagian kotak-kotak 30’ X 20’
Titik 0o Lintang pada Equator
Titik 0o Bujur di Greenwich.
Contoh : - Peta dengan No. 1550
Berskala 1 : 100.000
- Peta dengan No. 1550-I
Berskala 1 : 50.000

Profil Topografi (Penampang Topografi)
Untuk mengetahui kenampakan morfologi dan kenampakan struktur geologi pada suatu
daerah, maka diperlukan suatu penampang tegak atau profil (section). Penampang tegak atau
sayatan tegak adalah gambaran yang memperlihatkan profil atau bentuk dari permukaan bumi.
Profil ini diperoleh dari line of section yang telah ditentukan lebih dulu pada peta topografi,
misalnya A – A’ atau B – B’.
Skala pada profil :
1. Skala normal (nature scale) : yaitu skala vertikal diperbesar sama dengan
skala horisontal.
2. Skala perbesaran (exaggerated) : yaitu skala vertikal diperbesar lebih besar
dari skala horisontal.
Persyaratan pembuatan profil :
1. Profil line/topographic line yaitu garis potong antara permukaan bumi dengan
bidang vertikal.
2. Base line letaknya mendatar dipilih pada jarak tertentu di daerah profil line, dimana
tinggi base line tergantung kebutuhan. Seingkali dipilih 0 meter sesuai ketinggian
permukaan air laut. Pada base line terletak jarak mendatar sesuai dengan jarak
horisontal.
3. End line/garis samping dikiri dan kanan tegak lurus base line. Disini tertera angka
ketinggian sesuai interval kontur.
Guna peta Topografi dalam Geologi :
Secara khusus peta topografi digunakan untuk merekam segala data geologi, misalnya :
penyebaran batuan
struktur geologi
morfologi suatu daerah dan sebagainya

selain itu juga untuk memudahkan rekonstruksi genesa, cara terjadinya dan konfigurasi aspek-
aspek geologis di atas.
KESIMPULANPeta ialah gambaran permukaan bumi yang lebih terperinci dan diperkecil menurut ukuran
geometris pada suatu bidang datar sebagaimana penampakannya dari atas.
Atlas yaitu kumpulan peta-peta yang disusun secara teratur dan dijilid rapi menjadi sebuah
buku. Nama atlas berasal dari nama dewa bangsa Yunani, yaitu Atlas, dewa yang memegang bumi
di atas pundaknya. Pngertian yang lain Atlas adalah kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk

buku, tetapi juga ditemukan dalam bentuk multimedia. Atlas dapat memuat informasi geografi,
batas negara, statisik geopolitik, sosial, agama, dan ekonomi.
Orientasi peta adalah menyamakan kedudukan peta dengan medan sebenarnya (secara
praktis menyamakan utara peta dengan utara magnetis).
Pengertian lain mengenai peta topografi ada dua, yaitu:
a. Peta yang menggambarkan relief permukaan bumi beserta bangunan alami maupun buatan
manusia yang ada di atasnya.
b. Peta yang menggambarkan relief/sifat permukaan bumi yang digambarkan dengan garis
kontur.