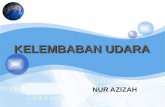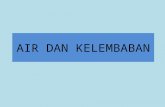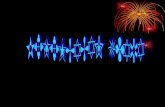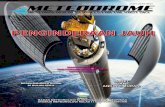STUDI IDENTIFIKASI KETAHANAN...
Transcript of STUDI IDENTIFIKASI KETAHANAN...


1
STUDI IDENTIFIKASI KETAHANAN PANGAN DAN PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP KONSUMSI BAHAN PANGAN POKOK DAGING SAPI Dalam Upaya Mengembangkan Naskah Kebijakan Sebagai Masukan pada
RPJMN 2015 - 2019
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DIREKTORAT PANGAN DAN PERTANIAN

2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. 2
DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... 4
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................................... 7
BAB 1. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 9
1.1. Latar Belakang ............................................................................................................ 9
1.2. Tujuan ...................................................................................................................... 10
1.3. Manfaat .................................................................................................................... 11
1.4. Ruang Lingkup Materi .............................................................................................. 11
BAB 2. KERANGKA PENELITIAN ........................................................................................... 13
2.1. Alur Kerangka Berfikir .............................................................................................. 13
2.1.1. Identifikasi Permasalahan ........................................................................................ 13
2.2. Hipotesis Penelitian ................................................................................................. 14
2.2.1. Loop Kesetimbangan................................................................................................ 16
2.2.2. Loop Penguatan (Reinforcing loop) ......................................................................... 16
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN ....................................................................................... 18
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian ............................................................................. 18
3.2. Prosedur Penelitian .................................................................................................. 18
3.3. Populasi dan Sampel ................................................................................................ 19
3.4. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................................... 20
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data ....................................................................... 20
3.6. Lokasi Penelitian ...................................................................................................... 21
3.6.1. Tingkat Propinsi........................................................................................................ 21
3.6.2. Tingkat Kabupaten ................................................................................................... 24
3.7. Operasionalisasi Konsep .......................................................................................... 40
3.7.1. Supply Side ............................................................................................................... 40
3.7.2. Demand Side ............................................................................................................ 40
BAB 4. PENGERTIAN, KARAKTERISTIK DAN KONDISI UMUM KETAHANAN PANGAN ......... 42
4.1. Pengertian Ketahanan Pangan ................................................................................. 42
4.2. Kondisi Umum Bahan Pangan Pokok ....................................................................... 46
4.2.1. Kondisi Umum Tata Niaga Sapi dan Daging Sapi ..................................................... 48
4.2.2. Kondisi Umum Pelaku Usaha ................................................................................... 50
4.2.3. Kondisi Umum Pembentukan Harga ........................................................................ 63
4.2.4. Kondisi Umum Preferensi dan Pola Konsumsi ......................................................... 66

3
BAB 5. HASIL PENELITIAN .................................................................................................... 67
5.1. Kapabilitas Strategis Produksi Daging Sapi .............................................................. 67
5.1.1. Isu Pergeseran Musim dan Fluktuasi Curah Hujan terhadap Kapabilitas Strategis
Produksi Daging Sapi ................................................................................................ 67
5.1.2. Produktifitas Sapi Potong Sebagai Variabel Supply Daging Sapi ............................. 70
5.1.3. Pondasi Dasar Sistem Produk Daging Sapi ............................................................... 78
5.2. Perkiraan Permintaan Daging Sapi Nasional Rumah Tangga dan Preferensi
Konsumsi Terhadap Kualitas Pangan Daging Sapi ................................................... 83
5.2.1. Perkiraan Demand Konsumsi Daging Sapi Rumah Tangga ...................................... 83
5.2.2. Preferensi Konsumsi terhadap Kualitas Pangan Daging Sapi dan Prediksi Kebutuhan
Kualitas Pangan Rumah Tangga Ekonomi Menengah Atas dalam 5 Tahun
Mendatang ............................................................................................................... 85
5.3. Perkiraan Permintaan Daging Sapi Nasional untuk Industri Berdasarkan Kategori
Potongan Daging Sapi .............................................................................................. 91
5.4. Rantai Pasokan Sebagai Alur Respon Persediaan dan Respon Produksi ................. 95
5.4.1. Mekanisme Pembentukan Harga Jual Beli Daging Sapi Lokal dan Impor ................ 97
5.4.2. Persepsi terhadap Kemandirian dan Stabilitas Pasokan Daging Sapi .................... 101
5.4.3. Arahan Penerapan Rantai Tata Niaga Bahan Pangan Pokok/ Supply Chain
Management Normatif berdasar Faktual .............................................................. 106
BAB 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ........................................................................ 111
6.1. Kesimpulan ............................................................................................................. 111
6.2. Rekomendasi untuk RPJMN 2015 – 2019 .............................................................. 116
6.2.1. Arah Kebijakan ....................................................................................................... 116
6.2.2. Strategi dan Fokus Prioritas ................................................................................... 118
6.2.3. Sasaran dan Indikator ............................................................................................ 122
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................. 123

4
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1. Kategori Responden Penelitian ...................................................................... 19
Tabel 3.2. Produksi Padi Nasional ................................................................................... 21
Tabel 3.3. Produksi Kedelai Nasional .............................................................................. 22
Tabel 3.4. Produksi Jagung Nasional ............................................................................... 22
Tabel 3.5. Produksi Bawang Merah Nasional ................................................................. 22
Tabel 3.6. Produksi Cabai Nasional ................................................................................. 23
Tabel 3.7. Produksi Cabai Rawit Nasional ....................................................................... 23
Tabel 3.8. Produksi Tebu Nasional .................................................................................. 23
Tabel 3.9. Produksi Kelapa Sawit/CPO Nasional ............................................................. 24
Tabel 3.10. Produksi Sapi Nasional ................................................................................... 24
Tabel 3.11. Produksi Padi Jawa Barat ............................................................................... 25
Tabel 3.12. Produksi Padi Jawa Timur ............................................................................... 25
Tabel 3.13. Produksi Padi Jawa Tengah ............................................................................ 25
Tabel 3.14. Produksi Padi Sulawesi Selatan ...................................................................... 26
Tabel 3.15. Produksi Padi Sumetera Utara ....................................................................... 26
Tabel 3.16. Produksi Kedelai Jawa Timur .......................................................................... 26
Tabel 3.17. Produksi Kedelai Jawa Tengah ....................................................................... 27
Tabel 3.18. Produksi Kedelai NTB ..................................................................................... 27
Tabel 3.19. Produksi Kedelai Jawa Barat .......................................................................... 27
Tabel 3.20. Produksi Jagung Jawa Timur .......................................................................... 28
Tabel 3.21. Produksi Jagung Jawa Tengah ........................................................................ 28
Tabel 3.22. Produksi Jagung Lampung .............................................................................. 28
Tabel 3.23. Produksi Jagung Sulawesi Selatan .................................................................. 29
Tabel 3.24. Produksi Jagung Sumatera Utara ................................................................... 29
Tabel 3.25. Produksi Bawang Merah Jawa Tengah ........................................................... 29
Tabel 3.26. Produksi Bawang Merah Jawa Timur ............................................................. 30
Tabel 3.27. Produksi Bawang Merah Jawa Barat .............................................................. 30
Tabel 3.28. Produksi Bawang Merah NTB ......................................................................... 30
Tabel 3.29. Produksi Cabai Jawa Barat ............................................................................. 31
Tabel 3.30. Produksi Cabai Sumatera Utara ..................................................................... 31
Tabel 3.31. Produksi Cabai Jawa Tengah .......................................................................... 31
Tabel 3.32. Produksi Cabai Jawa Timur ............................................................................. 32
Tabel 3.33. Produksi Tebu Jawa Timur ............................................................................. 32
Tabel 3.34. Produksi Tebu Lampung ................................................................................. 32
Tabel 3.35. Produksi Tebu Jawa Tengah ........................................................................... 33
Tabel 3.36. Produksi Tebu Jawa Barat .............................................................................. 33
Tabel 3.37. Produksi Kelapa Sawit Riau ............................................................................ 33

5
Tabel 3.38. Produksi Kelapa Sawit Sumatera Utara .......................................................... 34
Tabel 3.39. Produksi Kelapa Sawit Sumatera Selatan ....................................................... 34
Tabel 3.40. Produksi Kelapa Sawit Kalimantan Tengah .................................................... 34
Tabel 3.41. Produksi Kelapa Sawit Jambi .......................................................................... 35
Tabel 3.42. Produksi Sapi Potong Lampung ...................................................................... 35
Tabel 3.43. Produksi Sapi Potong Jawa Timur .................................................................. 36
Tabel 3.44. Produksi Sapi Potong Bali ............................................................................... 36
Tabel 3.45. Produksi Sapi Potong NTB .............................................................................. 36
Tabel 3.46. Lokasi Survei Supply by Kategori Komoditas .................................................. 37
Tabel 3.47. Komposisi Jumlah Penduduk 8 Area Lokasi SurveiDemand Side ................... 39
Tabel 3.48. Operasionalisasi Konsep Supply Side ............................................................. 40
Tabel 3.49. Operasionalisasi Konsep Demand Side .......................................................... 40
Tabel 4.1. Biaya Usaha Penggemukan Sapi ..................................................................... 58
Tabel 4.2. Struktur Populasi Sapi Potong pada Peternakan Rakyat ............................... 60
Tabel 4.3. Penyebaran Sapi Potong pada 8 Provinsi ....................................................... 61
Tabel 5.1. Indeks Suhu dan Kelembaban Relative untuk Sapi Menyusui ....................... 69
Tabel 5.2a. Populasi sapi potong berdasarkan usia pada tahun 2006 (Ekor) dan Beberapa
asumsi pendukung lainnya ............................................................................. 71
Tabel 5.2.b. ProsesPembibitan........................................................................................... 72
Tabel 5.2.c. Biaya proses pembibitan dan penggemukan ................................................. 72
Tabel 5.2.d. Sapi yang banyak beredar pada responden ................................................... 73
Tabel 5.3. Proyeksi Angka Permintaan Produksi Daging Sapi Nasional hingga tahun 2020
........................................................................................................................ 76
Tabel 5.4. Presentase Penduduk Menurut Pengeluaran Per Kapita Sebulan ................. 83
Tabel 5.5.a. Proyeksi Konsumsi Daging Sapi Berdasarkan Kebutuhan Rumah Tangga
Golongan Menengah Atas .............................................................................. 84
Tabel 5.5.b. Proyeksi Konsumsi Daging Sapi Berdasarkan Kebutuhan Rumah Tangga
Golongan Menengah Bawah .......................................................................... 84
Tabel 5.6.a. Preferensi Subtitusi Daging Sapi Berdasarkan Kategori Penghasilan RT Per
Bulan (Kondisi Harga DS Normal) ................................................................... 86
Tabel 5.6.b. Bersedia Tidaknya Konsumen Melakukan Substitusi Terhadap Daging Sapi
(Kondisi Harga DS Mahal) Berdasarkan Jumlah Pendapatan ......................... 88
Tabel 5.6.c. Preferensi Subtitusi Daging Sapi Berdasarkan Kategori Penghasilan RT Per
Bulan (Kondisi Harga DS Mahal) ..................................................................... 88
Tabel 5.6.d. Preferensi Konsumen Terhadap Substitusi Daging Sapi (saat pasokan langka)
Berdasarkan Jumlah Pendapatan ................................................................... 90
Tabel 5.7. Permintaan Daging Sapi untuk Industri Berdasarkan Jenis Potongan ........... 91
Tabel 5.8. Permintaan Daging Berdasarkan Kategori Konsumen ................................... 92
Tabel 5.9. Ringkasan Permintaan Konsumen Industri .................................................... 93

6
Tabel 5.10.a. Proyeksi Nasional Permintaan Daging Lokal Per Potongan ........................... 94
Tabel 5.10.b. Proyeksi Nasional Permintaan Daging Impor Per Potongan .......................... 94
Tabel 5.11.a. Harga Jual maksimum dari Pemotong Daging, Bandar Daging, dan Distributor
Daging Impor .................................................................................................. 98
Tabel 5.11.b. Harga Jual Maksimum dari Pengecer dan Supplier Daging............................ 98
Tabel 5.12. Biaya Pengiriman dan Distribusi (per-satu kali pengiriman) ........................ 109
Tabel 6.1. Proyeksi Permintaan Daging Sapi Lokal dan Impor...................................... 113

7
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Diagram Alur Penelitian ................................................................................. 13
Gambar 2.2. Pergerakan perubahan harga beberapa komoditi pokok di Indonesia tahun
2013 ................................................................................................................ 14
Gambar 2.3. Model Umum Hipotesis ................................................................................. 15
Gambar 4.1. Sub Sistem Ketahanan Pangan ....................................................................... 44
Gambar 4.2. Sub Sistem Ketersediaan Pangan ................................................................... 44
Gambar 4.3. Sub Sistem Akses Pangan ............................................................................... 45
Gambar 4.4. Sub Sistem Penyerapan Pangan ..................................................................... 46
Gambar 4.5. Sumber Pembelian Pedagang Daging Sapi ..................................................... 49
Gambar 4.6. Tujuan Penjualan Pedagang Daging ............................................................... 49
Gambar 4.7. Kondisi Tata Niaga Daging Sapi Saat Ini ......................................................... 50
Gambar 4.8. Pola Pemasaran Sapi Potong Pada Peternak Kelompok dan Individu ........... 51
Gambar 4.9. Imbangan Jalur Pemasaran Sapi Potong Kabupaten Garut (2000 – 2003) .... 52
Gambar 4.10. Model Transaksi Jual Beli Sapi Potong dan Ternak ........................................ 53
Gambar 4.11. Peta Persaingan Importir Sapi Potong di Indonesia ....................................... 55
Gambar 4.12. Rantai Kegiatan Perusahaan Pengimpor Sapi Potong .................................... 55
Gambar 4.13. Harga Daging Dunia Sapi Tahun ke Tahun ..................................................... 63
Gambar 4.14. Rata-rata Harga Daging Sapi Nasional ............................................................ 64
Gambar 4.15. Kondisi Harga Daging Sapi di Berbagai Wilayah Indonesia ............................ 65
Gambar 5.1.a. Tiga Daerah Iklim Indonesia, Daerah A (kurva tebal) – Daerah Monsun,
Daerah B (kurva putus-putus) – Daerah Semi-Monsun dan Daerah C (kurva
putus-putus pisah) – Daerah Antimonsun ..................................................... 67
Gambar 5.1.b. Siklus Curah Hujan Tahunan Masing-Masing Daerah .................................... 68
Gambar 5.1.c. Rata-rata Suhu (oC) dan Curah Hujan (mm/bulan) di Indonesia 1901-2009 . 69
Gambar 5.2.a. Simulasi Populasi Sapi Potong ....................................................................... 74
Gambar 5.2.b. Populasi Sapi Potong berdasarkan Umur Ternak ........................................... 74
Gambar 5.2.c. Penyembelihan Sapi Potong ........................................................................... 75
Gambar 5.2.d. Perbandingan Jumlah Sapi yang Dipotong Aktual dan Simulasi ..................... 75
Gambar 5.2.e. Perbedaan antara Proyeksi Produksi dan Konsumsi Daging Sapi .................. 76
Gambar 5.2.f. Populasi yang meningkat dengan penerapan strategi yang tepat ................ 77
Gambar 5.2.g. Produksi daging sapi yang mampu mengejar permintaannya ...................... 78
Gambar 5.3.a. Simulasi Struktur Proses Produksi Sapi Potong Nasional .............................. 79
Gambar 5.3.b. Hasil Simulasi Populasi Pedet dan Sapi Muda (belum produktif) .................. 80
Gambar 5.3.c. Populasi Sapi Indukan dan Sapi Siap Potong .................................................. 82
Gambar 5.4.a. Preferensi Konsumen Terhadap Substitusi Daging Sapi (saat harga normal) 86

8
Gambar 5.4.b. Preferensi Konsumen Terhadap Substitusi Daging Sapi (saat harga mahal) . 87
Gambar 5.4.c. Preferensi Konsumen Terhadap Substitusi Daging Sapi (Kondisi Saat DS
Langka) ........................................................................................................... 89
Gambar 5.5. Prioritas Substitusi Daging Sapi Konsumen Rumah Tangga ........................... 90
Gambar 5.6. Rantai Pasokan Komoditi Sapi Nasional (existing) ......................................... 96
Gambar 5.7. Sebaran Populasi Sapi Nasional ..................................................................... 97
Gambar 5.8. Pembentukan Harga Sapi ............................................................................... 99
Gambar 5.9. Pembentukan Harga Daging Sapi ................................................................. 100
Gambar 5.10. Tantangan Rantai Pasokan Sapi ................................................................... 102
Gambar 5.11. Dimensi Ketahanan Pangan: Sapi ................................................................. 103
Gambar 5.12.a Perceptual Map Ketahanan Pangan menurut Konsumen .......................... 103
Gambar 5.12.b Perceptual Map Ketahanan Pangan menurut Pengusaha .......................... 104
Gambar 5.12.c Perceptual Map Ketahanan Pangan menurut Konsumen ........................... 104
Gambar 5.12.d Perceptual Map Ketahanan Pangan menurut Pengusaha .......................... 105
Gambar 5.13. Sumber Pasokan Bahan Pangan Pokok di Indonesia tahun 2013 ................ 105

9
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagai negara agraris, Indonesia merupakan negara produsen produk pertanian ke-10
terbesar di dunia. Sektor pertaniannya memberikan kontribusi sebesar 15persen
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 38persen terhadap lapangan kerja (OECD,
2012). Mengingat sektor pangan sangat strategis bagi Indonesia, kebijakan pangan yang
dibuat harus memiliki dasar yang kuat dan pertimbangan yang logis karena berkaitan
erat dengan stabilisasi ekonomi, politik dan keamanan negara. Krisis pangan yang
muncul dalam beberapa dekade terakhir menjadi alasan utama untuk menciptakan
kebijakan sektor pangan yang berlaku secara komprehensif pada jangka menengah dan
jangka panjang di Indonesia.
Indonesia masih banyak memiliki potensi dalam sektor pertaniannya. Pertama, masih
banyaknya lahan subur yang belum digunakan secara optimal, yaitu baru 47 juta Ha
lahan subur yang sudah dimanfaatkan dari 110 juta Ha lahan budidaya yang berpotensi
untuk menjadi areal pertanian. Kedua, rata-rata pertumbuhan penduduk yang mencapai
lebih dari 1persen pada setiap tahunnya (BPS, 2013) menunjukkan besarnya jumlah
potensi konsumen yang ada di Indonesia. Tren positif pertumbuhan ekonomi yang terus
meningkat dapat menunjukkan bahwa daya beli konsumen untuk memenuhi kebutuhan
bahan pangan mereka juga telah meningkat.
Sayangnya, dengan kondisi saat ini peluang tersebut bisa menjadi ancaman bagi
Indonesia. Mulai pada tahun 2010, angka produksi komoditas pangan mulai menurun
(BPS, 2012). Pada tahun 2011, tingkat produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang akan
diproses menjadi beras hanya mampu mencapai jumlah 65.76 juta ton atau lebih
rendah 1.07persen dibandingkan dengan tahun 2010. Pada sisi lainnya, Jagung
mengalami penurunan yang lebih buruk, yaitu 5,99 persen lebih rendah dibandingkan
dengan tahun 2010 atau sekitar 17,64 juta ton pipilan kering (Jagung Pipilan Kering –
JPK). Dan tidak jauh berbeda dengan jagung, produksi kedelai turun 4,08 persen
dibandingkan 2010 atau hanya sebesar 851,29 ribu ton biji kering. Hal tersebut
menunjukkan ketidak selarasan antara pertumbuhan populasi penduduk Indonesia
dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Kemampuan produksi bahan pangan sebagai
pemasok persediaan pangan tidak mampu memenuhi percepatan permintaan bahan
pangan. Pada akhirnya, berdasarkan dengan hukum sederhana supply-demand,
kurangnya pasokan mengakibatkan meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Fakta-fakta yang telah disampaikan sebelumnya bisa saja disebabkan oleh beberapa
faktor. Faktor alam merupakan salah satu faktor luar yang tidak dapat dikendalikan
oleh manusia. Pergeseran musim dan fluktuasi curah hujan menyebabkan
ketidakpastian panen tanaman pangan (Kementrian Pertanian, 2011). Faktor lain yang

10
sering kali terjadi adalah penurunan jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor
pertanian. Pada tahun 2013, jumlah rumah tangga pertanian turun menjadi 26.13 juta
atau kurang dari 11persen dari jumlah populasi Indonesia. Penurunannya sebesar 5.04
juta rumah tangga dalam satu dekade atau kurang lebih sekitar 1.75 persen pada setiap
tahunnya. Hal ini diperkirakan karena bekerja di sektor pertanian tidak lagi mampu
memenuhi kebutuhan hidup layak bagi para petani. Walaupun harga pasar untuk
produk-produk hasil pertanian tinggi, adanya jalur rantai pasokan yang panjang
menyebabkan keuntungan hanya dimiliki oleh distributor dan para pedagang besar, dan
bukan oleh petani. Sebagai hasilnya, banyak lahan pertanian yang dimiliki oleh petani
dialihfungsikan menjadi berbagai lahan komersial yang dapat mendukung kebutuhan
pokok tempat tinggal keluarga petani atau dijual kepada pihak lain yang kemudian
mengubah lahan pertanian tersebut menjadi lahan untuk industri lainnya.
Ancaman lainnya bisa juga disebabkan oleh berubahnya preferensi konsumen terhadap
bahan pangan. Produk impor cenderung menawarkan harga yang lebih kompetitif
dengan kualitas yang lebih baik, sehingga produk lokal tidak dapat bersaing dalam
harga dan terlebih dalam sisi kualitas. Masalah menjadi semakin rumit ketika
permintaan produk impor meningkat. Tingginya jumlah impor membuat negara
kehilangan kekuatannya untuk menjaga kualitas produk lokal serta kekuatan dimata
persaingan internasional. Menghadapi banyaknya masalah dalam hal ketahanan
pangan, serta untuk mempersiapkan rencana pembangunan di bidang pangan dan
pertanian Indonesia untuk 5 tahun kedepan,maka perlu dirumuskan dokumen
kebijakan yang menganalisis pola penawaran dan permintaan (konsumsi rumah tangga
dan industri ) di sektor pertanian.
Untuk menyusun dokumen kebijakan tersebut, , Direktorat Pangan dan Pertanian
Bappenas bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)
melakukan penelitian terhadap "Studi Identifikasi Ketahanan Pangan dan Preferensi
Konsumsi terhadap Bahan Pangan Pokok " melalui analisis terhadap beberapa faktor
diantaranya faktor alam (pergeseran musim dan fluktuasi curah hujan), produktivitas,
dan supply chain management dalam merespon demand bahan pangan yang
terpengaruh oleh preferensi konsumsi yang bervariatif. Adapun bahan pangan pokok
yang masuk ke dalam studi ini diantaranya adalah beras, kedelai, daging sapi, kelapa
sawit, gula, cabai, bawang merah, dan jagung. Studi tersebut merupakan penggalian
data primer dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut.
1.2. Tujuan
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:
1. Menganalisis kapabilitas strategis produksi untuk mengembangkan rekomendasi
kebijakan dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi bahan pangan nasional.

11
2. Memberikan gambaran serta memperkirakan permintaan bahan pangan nasional
baik oleh individu rumah tangga (direct consumption)ataupun oleh industri
pengolahan makanan (indirect consumption).
3. Menyusun analisis preferensi konsumsi terhadap kualitas pangan, khususnya untuk
masyarakat dengan kelas ekonomi menengah keatas yang dapat digunakan untuk
memprediksi kualitas makanan yang dibutuhkan dalam 5 tahun mendatang.
4. Menganalisa rantai pasokan, respons persediaan, dan respons produksi untuk
mengembangkan rekomendasi yang menjembatani sisi persediaan dan sisi
permintaan.
1.3. Manfaat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa laporan/makalah/kajian
sebagai masukan terhadap perumusan arah kebijakan, strategi dan fokus prioritas,
sasaran dan indikator dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 terkait ketahanan pangan nasional dalam
menjawab preferensi konsumsi bahan pangan pokok.
1.4. Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi yang akan menjadi fokus pembahasan pada kajian studi
identifikasi ketahanan pangan dan preferensi konsumen terhadap konsumsimeliputi
bahan pangan terkait beras, daging sapi, kedelai, kelapa sawit, jagung, tebu, cabai,
dan bawang merah.Masing-masing dari bahan pangan pokok tersebut akan dianalisis
terkait kapabilitas strategis produksi terhadap tujuan penelitian. Hasil analisis tersebut
kedepannya akan menjadi landasan dan masukan terhadap arah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
Analisis studi akan dibagi menjadi delapan buku sesuai dengan kategori jenis bahan
pangan pokok yang dianalisis. Masing-masing buku akan mengulas hal-hal terkait
tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan analisis tersebut, diharapkan dapat
terumus sebuahkerangka pengembangan ketahanan pangan dan solusi pergeseran
preferensi konsumsi rumah tangga kelas menengah atas dan industri. Hal demikian
yang kedepannya dapat menjadi rekomendasi sebagai bahan masukan untuk
penyusunan RPJMN 2015-2019 terkait ketahanan pangan nasional.
1.5. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan terbagi sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, tujuan, manfaat, ruan
lingkup materi dan sistematika pembahasan secara general.

12
BAB 2. KERANGKA PENELITIAN
Bab ini akan menjelaskan secara general mengenai kerangka penelitian, landasan
variabel yang menghubungkan antara identifikasi ketahanan pangan dan preferensi
konsumsi terhadap bahan pangan pokok melalui analisis terhadap beberapa faktor
diantaranya faktor alam (pergeseran musim dan fluktuasi curah hujan), produktivitas,
dan supply chain management dalam merespon demand bahan pangan yang
terpengaruh oleh preferensi konsumsi yang bervariatif.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
Bagian ini secara general membahas metodologi penelitian yang meliputi pendekatan
dan jenis penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan
data, teknik pengolahan dan analisa data, operasionalisasi konsep dan lokasi penelitian.
BAB 4. PENGERTIAN, KARAKTERISTIK DAN KONDISI UMUM KETAHANAN PANGAN
Pengertian, karakteristik dan kondisi umum ketahanan pangan nasional per kategori
komoditas yang menjadi objek penelitian, yaitu beras, kedelai, daging sapi, kelapa sawit,
gula, cabai, bawang merah, dan jagung akan dibahas secara mendalam pada bagian ini.
BAB 5. HASIL PENELITIAN
Bagian ini akan membahas mengenai analisis laporan dalam menjawab tujuan
penelitian. Perihal kapasitas strategis produksi; perkiraan permintaan bahan pangan
nasional baik direct consumption maupun indirect consumption; preferensi konsumsi
terhadap kualitas pangan, khususnya untuk masyarakat dengan kelas ekonomi
menengah keatas; serta analisis rantai pasokan, respons persediaan, dan respons
produksi.
BAB 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI UNTUK RPJMN 2015-2019
Berdasarkan hasil penelitian dirumuskan sebuah kesimpulan yang mengarah kepada
rekomendasi yang menjembatani sisi persediaan dan sisi permintaan. Kesimpulan
tersebut akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kerangka pengembangan
ketahanan pangan dalam rangka perumusan arah kebijakan, strategi dan fokus
prioritas, sasaran dan indikator dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 terkait ketahanan pangan nasional

13
Mulai
Tidak
Selesai
Ya
Identifikasi Permasalahan: Perumusan Masalah: efisiensi rantai pasokan komoditi yang belum diketahui degan pasti ?
Perumusan Tujuan dan Manfaat
Studi Literatur
Pengumpulan data:
Sekunder dan Primer
Pembuatan Mental Model: Penentuan Variabel, Perumusan Hipothesis Dinamis dengan Causal Loop
Diagram
Pembentukan Formal Model: Stock and Flow Diagram (Consistency Test)
Expert Knowledge Elicitation: Depth Interview, Focused
Group Discussion (Struktural Test)
Reference Data: Behavior over Time of Historical Data
Simulasi: Menghasilkan Data (Extreme Test)
Sesuai? (Behavioral Test)
Pengembangan Kebijakan
BAB 2. KERANGKA PENELITIAN
2.1. Alur Kerangka Berfikir
Gambar 2.1. Diagram Alur Penelitian
2.1.1. Identifikasi Permasalahan

14
Perkembangan komoditi pangan dan holtikultura di Indonesia menunjukkan data yang
kurang menggembirakan. Dalam hal ini adalah faktor harga, dimana dalam setiap
kesempatan selalu menjadi topic pembahasan dan sorotan oleh berbagai pihak
termasuk media massa. Kecenderungan harga yang dirasakan konsumen saat ini secara
cepat bisa naik dan turun. Kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan persepsi
ketidakstabilan kondisi pasar komoditi. Beberapa pergerakan perubahan harga dari
komoditi pokok di Indonesia selama tahun 2013 tampak pada grafik berikut:
Gambar 2.2. Pergerakan perubahan harga beberapa komoditi pokok di Indonesia tahun 2013
Sumber: Kemendag 2013
Tampak pada grafik di atas bahwa seluruh komoditi yang ditampilkan mengalami
perubahan harga yang bervariasi. Variasi yang sangat tinggi selama tahun 2013 dialami
oleh komoditi cabai merah, kemudian oleh komoditi kedelai dan daging sapi, dimana
kedua komoditi ini lebih bergejolak pada periode akhir Bulan pengamatan yakni dari
Juni hingga Oktober.
Menjadi sebuah tantangan besar untuk mewujudkan harga komoditi yang stabil dari
waktu-kewaktu secara berkesinambungan. Tantangan besar ini tentu harus dijawab
dengan pemahaman yang komprehensif dari aspek permintaan dan penawaran untuk
menyasar akar masalahnya sehingga dinamika harga komoditi tidak mengalami gejolak.
2.2. Hipotesis Penelitian
Hypothesis dikembangkan dengan membentuk struktur umum yang didasarkan pada
prinsip hubungan kausal timbal balik. Dasar pembentukan struktur ini dari literature
review dan teori yang sudah baku. Struktur model awal ini merupakan cerminan

15
mental model dari pemodel dalam usaha mencari akar permasalahan dari
permasalahan penelitian yang diajukan.
Gambar 2.3. Model Umum Hipotesis
Mental model ini selanjutnya akan terus dikembangkan dan diperbaiki sehingga
menjadi formal model dengan Expert Knowledge Elicitation atau EKE (Ford and
Sterman, 1998). Proses adopsi pendapat ahli ataupun pelaku sesungguhnya, ini bisa
dilakukan dengan wawancara medalam atau dengan focused group discussion (FGD).
Dalam proses tersebut bisa dilakukan quantifikasi beberapa variabel yang mungkin
masih bersifat kualitatif. Selain itu dengan masukan pendapat para ahli maka model
awal bisa diperbaiki. Perbaikan ini penting karena adanya pengalaman yang unik dari
para ahli yang mungkin belum tertangkap dalam mental model.
Simulasi merupakan langkah selanjutnya guna membuktikan bahwaa data yang
dihasilkan dari simulasi tidak bergerak sesuai teori, atau logika, atau bergerak sesuai
dengan data referensi yang merupakan data riil masa lalu. Analisis sensitivitas dari satu
variabel dan beberapap ilihan scenario kebijakan ataupun menentukan kebijakan baru
dengan menambah variabel baru yang bersifat exogenous akan membuat design
kebijakan akan menjadi lebih kokoh.Secara umum, model di atas memiliki dua jenis
putaran kausal tertutup (closedloop) pertama adalah balancing closed loop dan
reinforcing closed loop.
Harga PasarRatio Produksi dan
Konsumsi
Sub Sistem
Konsumsi
--
Sub Sistem
Produksi
+
+
B2
B1
Ekspektasi
Konsumsi
+
+
R1
Impor
+
Iklim Ekstrim
-
Harga referensi
GAP Harga
+
+-
Pendapatan RT
-
+
B3
Konversi Lahan
+
+
R2
Kebutuhan
minimum
GAP Nutrisi
(malnutrisi)-
+
-
R3

16
2.2.1. Loop Kesetimbangan
Model umum di atas dibentuk pada awalnya dengan menelaah harga pasar untuk
komoditi. Pergerakan harga dipengaruhi oleh kesetimbangan antara persediaan dan
konsumsi dimana semakin besar persediaan tentu akan membuat harga komoditi
tersebut menjadi lebih murah dengan konsumsi tidak mengalami perubahan. Bila mana
kesetimbangan terjadi maka harga tidak berubah dibandingkan waktu sebelumnya.
Kesetimbangan initentu juga dipengaruhi oleh variabel lain, dalam hal ini adalah
kondisi sub system konsumsi dan produksi. Seberapa besar kemampuan sub system
produksi menghasilkan komoditi yang diminta oleh pelanggan yang dicerminkan oleh
besarnya permintaa dari sub system konsumsi.
Dari sisi konsumsi, besaran pendapatan rumah tangga akan menentukan besarnya
konsumsi, dimana dengan asumsi komoditi adalah barang normal maka semakin besar
pendapatan tentu akan semakin besar jumlah komoditi yang akan dikonsumsi.
Sedangkan harga pasar yang turun dan naik tentu akan menentukan besaran pendapat
riil dari pendapatan rumah tangga. Rangkain hubungan sebab akibat ini akan
membentuk closed loop B1.
Di sisi lain, harga pasar komoditi tentu akan memeberiakn insentif (disinsentif) bagi
kalangan produsen. Dimana semakin tingga harga, secara normal, maka akan
memberikan insentif bagi produsen untuk memperbesar produksi sehingga dalam
jangka panjang harga akan segera kembali pada kesetimbangan awal. Rangkain
hubungan sebab akibat ini akan membentuk closed loop B2. Atau sebaliknya, bila harga
turun maka produsen akan melakukan langkah-langkah pengurangan produksi
sehingga dalam jangka panjang akan menurunkan rasio perbandingan jumlah produksi
dan konsumsi sehingga terjadi kelangkaan komoditi yang lebih lanjut akan
menggerakkan harga naik.
Balancing loop yang lain adalah closed loop B3, pada loop ini kenaikan harga pasar
komoditi akan membuat selisih (gap) dengan harga referensi semakin lebar, dengan
semakin melebarnya gap ini maka akan semakin menekan pemerintah untuk
melakukan impor (ekspor) komoditi. Impor secara langsung ini akan mempercepat
pertambahan ketersediaan komoditi di pasar sehingga akan membuat rasio produksi
dan konsumsi akan naik. Seperti pada loop lain sebelumnya, kenaikan rasio ini akan
membuat harga pasar akan turun.
2.2.2. Loop Penguatan (Reinforcing loop)
Selain loop kesetimbangan, dalam model umum juga terdapat loop penguatan, yakni
closed loop R1, R2, dan R3. Pada closed loop R1, Naiknya harga pasar komoditi akan
menurunkan nominal pendapatan rumah tangga. Dengan adanya penurunan
pendapatan ini maka rumah tangga dituntut untuk menyesuaikan besaran konsumsi
atas komoditi tertentu, dalam hal ini mengurangi besarannya.

17
Perubahan besaran konsumsi ini kemudian akan digunakan oleh kalangan produsen
dalam merencanakan produksi atas komoditas tersebut dengan membangun ekspektasi
konsumsi. Dimana, semakin besar konsumsi maka semakin besar pula ekspektasi
konsumsi untuk periode berikutnya dan sebaliknya bila semakin kecil konsumsi maka
akan semakin kecil pula ekspektasinya. Semakin besar (kecil) ekspektasi maka akan
membuat produsen memperbesar (memperkecil) rencana produksi. Dalam hal faktor
produksi tetap maka semakin besar (kecil) rencana produksi maka akan semakin besar
(kecil) pula realisasi produksi. Dalam hal ini tentu saja, realisasi produksi akan terbatasi
dengan kondisi faktor produksi dalam perusahaan, sehingga dengan realisasi produksi
yang semakin besar maka rasio produksi dan konsumsi juga akan naik dan pada
akhirnya akan menurunkan harga pasar komoditi tersebut.
Pada closed loop lain, dimana harga pasar komoditi yang naik akan memberikan
insentif pula kepada pihak-pihak yang selama ini tidak tertarik untuk masuk ke pasar
komoditi. Dengan tingkat harga tertentu maka konversi lahan yang selama ini dianggap
tidak ekonomis akan menjadi ekonomis, sehingga naiknya harga komoditi akan
memancing pemilik atau pemegang hak atas lahan untuk mengubah peruntukan
lahannya menjadi lahan untuk budidaya komoditi, misalnya kelapa sawit dalam hal ini.
Konversi lahan bisa terjadi dari lahan non pertanian misal; hutan, lahan gambut dengan
ekosistem dan system sosialnya, menjadi lahan pertanian. Kemudian konversi dari
lahan pertanian menjadi peruntukan lahan non-pertanian missal; perumahan, pabrik,
dan lain-lain. Namun secara umum konversi lahan yang terjadi diakibatkan lebih pada
pertimbangan ekonomis. Pada akhirnya konversi lahan yang semakin besar tentu akan
memiliki dampak kepada cuaca yang ekstrim dan sulit diperkirakan. Variabilitas cuaca
yang tinggi tentu akan menyulitkan produsen komoditi dalam memulai masa produksi
(tanam), mengganggu proses produksi, dan menurunkan hasil panen. Dengan begitu
cuaca yang ekstrim tentu juga akan berdampak pada instabilitas ketersediaan komoditi
(produksi), dimana hal ini bisa dimaknai dengan rasio produksi dan konsumsi yang
tidak terkendali, sehingga harga juga akan sulit terkendali. Rangkaian hubungan
kasualitas dalm loop ini akan membentuk closed loop R2.
Closed loop R3, menjelaskan hubungan kausal variabel yang terkait dengan kecukupan
nutrisi masyarakat secara umum. Pada kasus yang sedikit ekstrim, pengurangan
konsumsi komoditi tertentu hingga dibawah level yang dibutuhkan oleh tubuh, maka
akan berdampak pada tingginya kasus malnutrisi. Semakin tinggi malnutrisi pada
akhirnya akan mempengaruhi kesehatan dan produktivitas masyarakat. Dalam hal ini,
masyarakat merupakan salah satu faktor produksi yang Utama, sehingga bilamana
produktivitas menurun maka sudah barang tentu jumlah produksi atas komoditi akan
menurun juga. Sehingga pada akhirnya menjadikan rasio produksi dan konsumsi turun
dan menjadikan harga melambung naik.

18
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan utama yang akan dijalankan dalam penelitian ini adalah paradigma
kuantitatif atau paradigma positivistik (Denzin, 2003). Dalam pendekatan kuantitatif
peneliti melakukan suatu rangkaian penelitian yang berawal dari sejumlah teori, yang
kemudian dideduksikan menjadi suatu hipotesa dan asumsi-asumsi suatu kerangka
pemikiran yang terjabarkan dalam sebuah model analisa, yang terdiri dari variabel-
variabel yang akan mengarah kepada operasionalisasi konsep (Brannen, 2002). Oleh
sebab itu reliabilitas atau konsistensi merupakan kunci dari penelitian kuantitatif,
selain harus bebas nilai (value free) atau obyektif dan bebas dari konteks situasional
(Neuman, 2006).
Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini menggunakan cross sectional design yaitu
disain penelitian yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya
dilakukan satu kali dalam suatu periode waktu tertentu (Malhotra, 2007). Jika dilihat
dari jenis penelitiannya, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian
dikategorikan ke dalam dalam penelitian deskriptif (descriptive research). Penelitian
deskriptif pada prinsipnya memiliki 7 (tujuh) tujuan yaitu: menyediakan profil atau
gambaran yang tepat tentang suatu kelompok; menggambarkan suatu proses,
mekanisme serta hubungan; memberikan gambaran verbal dan numerik misalnya
persentase dari responden; menemukan informasi untuk merangsang penjelasan-
penjelasan baru (new explanations); menampilkan latar belakang yang bersifat dasar
dari sebuah informasi atau kejadian; membuat serangkaian kategori atau jenis-jenis
pengklasifikasian dan menjelaskan bagian serta langkah-langkah dalam penelitian
(Neuman, 2006).
3.2. Prosedur Penelitian
Kerangka atau prosedur penelitian sangat penting dalam melakukan tahapan penelitian,
karena hal tersebut yang akan menjadi landasan atau blueprint dalam mengurai
permasalahan serta memberikan solusi pemecahan yang efektif dan efisien dengan
menggunakan metodologi yang tepat guna (Malhotra, 2007). Prosedur dalam penelitian
ini terdiri dari tahapan:
1) Mengumpulkan berbagai macam literatur yang mendukung penelitian ini dan
membuat model/ kerangka penelitian.
2) Membuat kuesioner dan melakukan pretest instrumentasi kepada 50 (lima puluh)
responden. Hasil pretest dianalisis menggunakan SPSS 17.0. Setelah hasil dianggap
memenuhi syarat maka untuk selanjutnya kuisioner dapat diterapkan pada proses
selanjutnya.

19
3) Melakukan penyebaran kuisioner terhadap responden yang terpilih di 13 lokasi
penelitian.
3.3. Populasi dan Sampel
Populasi sasaran adalah sekumpulan data atau elemen yang memiliki informasi yang
dibutuhkan untuk dapat dianalisa dan ditarik kesimpulannya (Malhotra, 2007).
Populasi juga didefinisikan sebagai himpunan yang lengkap atau sempurna dari semua
elemen atau unit observasi yang mungkin diteliti. Adapun populasi penelitian ini
adalahkelompok atau elemen yang selama ini tercakup dalam rantai tata niaga bahan
pokok penelitian (beras, kedelai, daging sapi, kelapa sawit, gula, cabai, bawang merah,
dan jagung) di wilayah yang menjadi fokus kajian.
Adanya keterbatasan seperti hal waktu, biaya, tenaga peneliti dan keberaksian yang
dapat mengubah hasil penelitian mengakibatkan perlunya ditarik sampel dalam suatu
penelitian. Sampel adalah bagian atau satuan dari keseluruhan objek penelitian
(populasi). Pada penelitian ini jumlah total sampel adalah 2620 responden, dengan
klasifikasi sebagai berikut:
Tabel 3.1. Kategori Responden Penelitian
No. Komoditas/ Commodities Supply Side Demand Side
Respondent Jumlah Respondent Jumlah
1. Beras/ Rice 1) Farmer/ Plantation
2) Collector 3) Wholesaler 4) Grocery/Agent 5) Retailer 6) Distributor
7 x 30 (minimal kecukupan sample untuk industri, Malhotra 2007) x 6 = 1260 respondent
1) Rumah tangga/ Household
2) Industri
1) 800 Rumah tangga/ Household
1) 200 industri pengolahan makanan
2. Kedelai/ Soybean
3. Gula/ Sugar
4. Kelapa Sawit/ CPO
5. Cabai/ Chili
6. Bawang Merah/ Red Onion
7. Jagung/ Corn
8. Daging Sapi/ Meat 1) Breeders 2) Cattle Broker
(Belantik) 3) Cattle
Wholesaler 4) Feedlot 5) Meat Retailer 6) Distributor
30 x 6 = 180 respondent
Total Respondent 1620* 1000
* ditambahkan 180 responden untuk mencukupi sampel responden disisi supply
Mengingat adanya kendala di lapangan, maka pemilihan responden untuk kategori
supplydan demand kategori industri akan menggunakan teknik Convenience Sampling
(Aaker, 2001). Teknik ini berupaya untuk mendapatkan sebuah sampel yang tepat dari
elemen populasi. Pemilihan unit sampel diserahkan sepenuhnya kepada peneliti,
Umumnya respoden dipilih karena mereka berada pada tempat dan waktu yang tepat
(at the right place and the right time) atau on the spot.

20
Sedangkan pemilihan responden untuk kategori demand rumah tangga akan
menggunakan teknik Stratified Sampling dengan menggunakan metode systemic random
sampling berdasarkan proporsi jumlah penduduk usia 20 – 65 tahun di masing-masing
wilayah kajian yang mengacu pada data sensus penduduk 2010, Daerah Dalam Angka
(DDA) 2011-2012, dan seleksi kriteriamiddle-up class SSE A, B+, dan B berdasarkan AC
Nielsen dan Milward Brown.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari:
1) Survei
Dalam penelitian ini digunakan metode survei yaitu penelitian yang mengambil
sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan
data yang pokok. Pada umumnya yang merupakan unit analisa dalam penelitian
survei adalah individu. Hal ini sesuai dengan pernyatan bahwa penting bagi peneliti
untuk menggunakan within methods yaitu metode yang digunakan berasal dari satu
pendekatan, misalnya dalam satu penelitian kuantitatif digunakan metode survei
dan penggunaan kuesioner, serta analisis statistik (Neuman, 2006). Pada penelitian
ini digunakan kuesioner yang urutan pertanyaannya bersifat baku, terdiri dari
pertanyaan tertutup (close-ended question) dan pertanyaan terbuka (open-ended
question) dan disamakan untuk setiap responden (Bailey, 1994).
2) Wawancara mendalam
Dalam rangka memperkuat dan mengkonfirmasi hasil-hasil temuan yang diperoleh
dari survei dan analisa kebijakan, maka akan dilakukan wawancara mendalam
kepada pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam proses tata niaga
bahan pokok, baik di tingkat nasional maupun di masing-masing lokasi kajian.
Penentuan informan lain yang akan diwawancara bergantung kepada
perkembangan kebutuhan data di lapangan. Ditargetkan akan diwawancara
sebanyak 30 (tiga puluh) informan yang mewakili beragam kelompok kepentingan
tersebut.
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data
Adapun teknik yang akan digunakan untuk menerangkan dan menganalisis data yang
diperoleh melalui pengumpulan data adalah sebagai berikut:
1) Uji validitas dan reliabilitas pada tahap pre-test kuesioner. Analisis reliabilitas dan
validitas yang merupakan analisis presisi dan akurasi suatu indikator. Standar nilai
alpha yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.60, yang artinya pada nilai
tersebut suatu alat ukur dikatakan reliabel dan dapat diterima.

21
2) Analisis frekuensi dan cross tabulation untuk melihat susunan data dalam suatu
tabel yang telah diklasifikasikan menurut kategori-kategori tertentu (Neuman,
2006). Hal ini dilakukan untuk menyimpulkan informasi tentang suatu indikator
melalui penghitungan data mentah atau persentase dari frekuensi. Pada penelitian
yang menggunakan skala interval dan likert juga dapat dilakukan pengukuran
tendensi sentral yaitu nilai rata-rata (mean) dan modus atau nilai yang sering
muncul (frequently occuring number) maupun median atau nilai tengah.
3) Analisis historical data analysis untuk menemukan pola kondisi kekinian bahan
pangan pokok dan preferensi konsumsinya.
4) Analisis mapping dan forecasting untuk memetakan simpul-simpul permasalahan
secara lebih detil, dan memprediksi efektivitas calon kebijakan yang akan diambil.
5) Untuk analisis terhadap hasil wawancara mendalam dilakukan analisis terhadap
catatan lapangan, catatan atau transkrip wawancara. Data ini dikumpulkan sebagai
data sekunder untuk mendukung penelitian ini.
3.6. Lokasi Penelitian
3.6.1. Tingkat Propinsi
Survei dilakukan di beberapa propinsi yang menjadi irisan penghasil komoditas
terbanyak, rincian besarnya hasil produksi setiap komoditas menurut data dari
Kementerian Pertanian sebagai berikut:
1) Komoditas Padi (Beras)
Tabel 3.2. Produksi Padi Nasional
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi padi per propinsi di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Timur,
Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara merupakan 5 propinsi penghasil
padi terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.

22
2) Komoditas Kedelai
Tabel 3.3. Produksi Kedelai Nasional
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi kedelai per propinsi di Indonesia, Jawa Timur, Jawa
Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat dan Aceh merupakan 5 propinsi
penghasil kedelai terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
3) Komoditas Jagung
Tabel 3.4. Produksi Jagung Nasional
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi jagung per propinsi di Indonesia, Jawa Timur, Jawa
Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara merupakan 5 propinsi
penghasil jagung terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
4) Komoditas Bawang Merah
Tabel 3.5. Produksi Bawang Merah Nasional
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi bawang merah per propinsi di Indonesia, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan merupakan 5
propinsi penghasil bawang merah terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.

23
5) Komoditas Cabai Besar
Tabel 3.6. Produksi Cabai Nasional
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi cabai besar per propinsi di Indonesia, Jawa Barat,
Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat merupakan 5 propinsi
penghasil cabai besar terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Komoditas Cabai Rawit
Tabel 3.7. Produksi Cabai Rawit Nasional
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi cabai rawit per propinsi di Indonesia, Jawa Timur, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Aceh merupakan 5 propinsi penghasil cabai
rawit terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
6) Komoditas Tebu (Gula)
Tabel 3.8. Produksi Tebu Nasional
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi tebu per propinsi di Indonesia, Jawa Timur, Lampung,
Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan merupakan 5 propinsi penghasil tebu
terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.

24
7) Komoditas Kelapa Sawit (Minyak Kelapa Sawit/CPO)
Tabel 3.9. Produksi Kelapa Sawit/CPO Nasional
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi kelapa sawit per propinsi di Indonesia, Riau, Sumatera
Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jambi merupakan 5 propinsi
penghasil kelapa sawit terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
8) Sapi Potong (Daging sapi)
Tabel 3.10. Produksi Sapi Nasional
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah sapi potong per propinsi di Indonesia, Jawa Timur, Jawa tengah,
Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Bali
merupakan propinsi-propinsi dengan jumlah sapi potong terbanyak yang menjadi
pilihan lokasi tujuan survei.
Berdasarkan persebaran wilayah penghasil komoditas pertanian tersebut diatas,
beberapa propinsi yang menjadi tujuan survei adalah sebagai berikut:
1. Jawa Timur 2. Jawa Tengah 3. Jawa Barat 4. Nusa Tenggara Barat 5. Sumatera Utara 6. Lampung
7. Sulawesi Selatan 8. Sumatera Selatan 9. Riau 10. Jambi 11. Bali 12. Kalimantan Tengah
3.6.2. Tingkat Kabupaten
Pada masing-masing propinsi, survei akan lebih difokuskan pada tingkat
kota/kabupaten. Penentuan kota/kabupaten sebagai lokasi tujuan survei didasarkan
pada kota/kabupaten dengan jumlah produksi komoditas paling banyak.
2010 2011 Rata-rata
Nasional 21.958.120 23.081.429 22.519.775 100%
Riau 6.358.703 5.736.722 6.047.713 27% 1
Sumatera Utara 3.113.006 4.071.143 3.592.075 16% 2
Sumatera Selatan 2.227.963 2.203.275 2.215.619 10% 3
Kalimantan Tengah 2.251.077 2.146.160 2.198.619 10% 4
Jambi 1.509.560 1.684.174 1.596.867 7% 5
Propinsi
% Terhadap
Produksi
Nasional
PeringkatProduksi Kelapa Sawit (Ton)

25
Berikut disajikan tabel jumlah produksi komoditas-komoditas yang diteliti berdasarkan
kabupaten penghasil terbesar pada masing-masing propinsi:
1) Padi (Beras)
Tabel 3.11. Produksi Padi Jawa Barat
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi padi per kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Indramayu,
Karawang, Subang, Garut, dan Tasikmalaya menjadi 5 besar kabupaten penghasil padi
terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.12. Produksi Padi Jawa Timur
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi padi per kabupaten di Jawa Timur, Kabupaten
Bojonegoro, Jember, Banyuwangi, Lamongan dan Ngawi menjadi 5 besar kabupaten
penghasil padi terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.13. Produksi Padi Jawa Tengah
Sumber: Kementrian Pertanian

26
Berdasarkan jumlah produksi padi per kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap,
Grobogan, Demak, Brebes, dan Pati menjadi 5 besar kabupaten penghasil padi
terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.14. Produksi Padi Sulawesi Selatan
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi padi per kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone,
Wajo, Pinrang, dan Gowa menjadi 4 besar kabupaten penghasil padi terbanyak yang
menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.15. Produksi Padi Sumetera Utara
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi padi per kabupaten di Sumatera Utara, Kabupaten
Simalungun, Deli Serdang, Serdang Berdagai, dan Langkat menjadi 4 besar kabupaten
penghasil padi terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
2) Kedelai
Tabel 3.16. Produksi Kedelai Jawa Timur
Sumber: Kementrian Pertanian

27
Berdasarkan jumlah produksi kedelai per kabupaten di Jawa Timur, Kabupaten
Banyuwangi, Lamongan, Sampang, Ponorogo, dan Pasuruan menjadi 5 besar kabupaten
penghasil kedelai terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.17. Produksi Kedelai Jawa Tengah
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi kedelai per kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten
Grobogan, Wonogiri, Brebes, Blora, dan Klaten menjadi 5 besar kabupaten penghasil
kedelai terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.18. Produksi Kedelai NTB
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi kedelai per kabupaten di Nusa Tenggara Barat,
Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Dompu, dan Sumbawa menjadi 4 besar kabupaten
penghasil kedelai terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.19. Produksi Kedelai Jawa Barat
Sumber: Kementrian Pertanian

28
Berdasarkan jumlah produksi kedelai per kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Garut,
Cianjur, Sumedang, dan Indramayu menjadi 4 besar kabupaten penghasil kedelai
terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
3) Jagung
Tabel 3.20. Produksi Jagung Jawa Timur
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi jagung per kabupaten di Jawa Timur, Kabupaten Tuban,
Sumenep, Jember, Malang, dan Probolinggo menjadi 5 besar kabupaten penghasil
jagung terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.21. Produksi Jagung Jawa Tengah
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi jagung per kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten
Grobogan, Wonogiri, Blora, Kendal, dan Boyolali menjadi 5 besar kabupaten penghasil
jagung terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.22. Produksi Jagung Lampung
Sumber: Kementrian Pertanian

29
Berdasarkan jumlah produksi jagung per kabupaten di Lampung, Kabupaten Lampung
Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Utara menjadi 4 besar
kabupaten penghasil jagung terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.23. Produksi Jagung Sulawesi Selatan
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi jagung per kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten
Jeneponto, Gowa, Bone, dan Bulukumba menjadi 4 besar kabupaten penghasil jagung
terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.24. Produksi Jagung Sumatera Utara
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi jagung per kabupaten di Sumatera Utara, Kabupaten
Karo, Simalungun, Dairi, dan Langkat menjadi 4 besar kabupaten penghasil jagung
terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
4) Bawang Merah
Tabel 3.25. Produksi Bawang Merah Jawa Tengah
Sumber: Kementrian Pertanian

30
Berdasarkan jumlah produksi bawang merah per kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten
Brebes, Demak, Kendal, Tegal, dan Pati menjadi 5 besar kabupaten penghasil bawang
merah terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.26. Produksi Bawang Merah Jawa Timur
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi bawang merah per kabupaten di Jawa Timur, Kabupaten
Probolinggo, Nganjuk, Sampang, dan Mojokerto menjadi 5 besar kabupaten penghasil
bawang merah terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.27. Produksi Bawang Merah Jawa Barat
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi bawang merah per kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten
Cirebon, Bandung, Majalengka, dan Garut menjadi 5 besar kabupaten penghasil bawang
merah terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.28. Produksi Bawang Merah NTB
Sumber: Kementrian Pertanian

31
Berdasarkan jumlah produksi bawang merah per kabupaten di Nusa tenggara Barat,
Kabupaten Bima, Lombok Timur, dan Sumbawa menjadi 3 besar kabupaten penghasil
bawang merah terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
5) Cabai
Tabel 3.29. Produksi Cabai Jawa Barat
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi cabai per kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Garut,
Cianjur, dan Bandung menjadi 3 besar kabupaten penghasil cabai terbanyak yang
menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.30. Produksi Cabai Sumatera Utara
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi cabai per kabupaten di Sumatera Utara, Kabupaten Karo,
Simalungun, dan Deli Serdang menjadi 3 besar kabupaten penghasil cabai terbanyak
yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.31. Produksi Cabai Jawa Tengah
Sumber: Kementrian Pertanian

32
Berdasarkan jumlah produksi cabai per kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes,
Magelang, dan Boyolali menjadi 3 besar kabupaten penghasil cabai terbanyak yang
menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.32. Produksi Cabai Jawa Timur
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi cabai per kabupaten di Jawa Timur, Kabupaten Gresik,
Tuban, Banyuwangi, Sampang, dan Malang menjadi 3 besar kabupaten penghasil cabai
terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
6) Tebu (Gula)
Tabel 3.33. Produksi Tebu Jawa Timur
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi tebu per kabupaten di Jawa Timur, Kabupaten Malang,
Jombang, Lumajang, Kediri, dan Situbondo menjadi 5 besar kabupaten penghasil tebu
terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.34. Produksi Tebu Lampung
Sumber: Kementrian Pertanian

33
Berdasarkan jumlah produksi tebu per kabupaten di Lampung, Kabupaten Way Kanan,
Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Tulang Bawang menjadi 4 besar kabupaten
penghasil tebu terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.35. Produksi Tebu Jawa Tengah
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi tebu per kabupaten di Jawa Tengah, Kabupaten Pati,
Sragen, Tegal, Remang, dan Pemalang menjadi 5 besar kabupaten penghasil tebu
terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.36. Produksi Tebu Jawa Barat
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi tebu per kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon,
Majalengka, Kuningan, Garut, dan Indramayu menjadi 5 besar kabupaten penghasil tebu
terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
7) Kelapa Sawit (Minyak Kelapa Sawit)
Tabel 3.37. Produksi Kelapa Sawit Riau
Sumber: Kementrian Pertanian
Riau 6.358.703 100%
Kab. Kampar 498.849 8% 1
Kab. Rokan Hilir 460.718 7% 2
Kab. Rokan Hulu 441.298 7% 3
Kab. Siak 393.287 6% 4
Kota/Kabupaten
% Terhadap
Produksi
Propinsi
Peringkat
Produksi
Kelapa Sawit
(2010,Ton)

34
Berdasarkan jumlah produksi kelapa sawit per kabupaten di Riau, Kabupaten Kampar,
Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak menjadi 4 besar kabupaten penghasil kelapa sawit
terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.38. Produksi Kelapa Sawit Sumatera Utara
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi kelapa sawit per kabupaten di Sumatera Utara,
Kabupaten Asahan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Labuhan Batu Selatan, dan
Simalungun menjadi 5 besar kabupaten penghasil kelapa sawit terbanyak yang menjadi
pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.39. Produksi Kelapa Sawit Sumatera Selatan
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi kelapa sawit per kabupaten di Sumatera Selatan,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Musi Banyu Asin, dan Muara Enim menjadi
4 besar kabupaten penghasil kelapa sawit terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan
survei.
Tabel 3.40. Produksi Kelapa Sawit Kalimantan Tengah
Sumber: Kementrian Pertanian
Sumatera Utara 3.113.006 100%
Kab. Asahan 223.102 7% 1
Kab. Labuhan Batu Utara 181.297 6% 2
Kab. Langkat 125.472 4% 3
Kab. Labuhan Batu Selatan 112.027 4% 4
Kab. Simalungun 111.755 4% 5
Kota/Kabupaten
% Terhadap
Produksi
Propinsi
Peringkat
Produksi
Kelapa Sawit
(2010,Ton)
Sumatera Selatan 2.227.963 100%
Kab. Ogan Komering Ilir 253.205 11% 1
Kab. Musi Rawas 186.503 8% 2
Kab. Musi Banyu Asin 175.403 8% 3
Kab. Muara Enim 129.722 6% 4
Kota/Kabupaten
% Terhadap
Produksi
Propinsi
Peringkat
Produksi
Kelapa Sawit
(2010,Ton)
Kalimantan Tengah 2.251.077 100%
Kab. Lamandau 55.062 2% 1
Kab. Kota Waringin Barat 52.640 2% 2
Kab. Kota Waringin Timur 37.144 2% 3
Kota/Kabupaten
% Terhadap
Produksi
Propinsi
Peringkat
Produksi
Kelapa Sawit
(2010,Ton)

35
Berdasarkan jumlah produksi kelapa sawit per kabupaten di Kalimantan Tengah,
Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat, dan Kota Waringin Timur menjadi 3 besar
kabupaten penghasil kelapa sawit terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
Tabel 3.41. Produksi Kelapa Sawit Jambi
Sumber: Kementrian Pertanian
Berdasarkan jumlah produksi kelapa sawit per kabupaten di Jambi, Kabupaten Muaro
Jambi, Tanjung Jabung Barat, Batang Hari, Merangin, dan Bungo menjadi 5 besar
kabupaten penghasil kelapa sawit terbanyak yang menjadi pilihan lokasi tujuan survei.
8) Sapi Potong (Daging Sapi)
Tabel 3.42. Produksi Sapi Potong Lampung
Sumber: Daerah Dalam Angka 2012
Berdasarkan jumlah populasi sapi potong di propinsi Lampung, kelima daerah diatas
yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tulang Bawang Barat dan
Way Kanan menjadi pilihan lokasi survei.
Jambi 1.509.560 100%
Kab. Muaro Jambi 300.163 20% 1
Kab. Tanjung Jabung Barat 253.258 17% 2
Kab. Batang Hari 177.348 12% 3
Kab. Merangin 157.269 10% 4
Kab. Bungo 145.288 10% 5
Kota/Kabupaten
% Terhadap
Produksi
Propinsi
Peringkat
Produksi
Kelapa Sawit
(2010,Ton)
Kabupaten Populasi Sapi potong
(ekor) Peringkat
Lampung Tengah 163.019 1
Lampung Timur 95.823 2
Lampung Selatan 50.966 3
Tulang Bawang Barat 33.048 4
Way Kanan 27.383 5
Total 496.066
Lampung

36
Tabel 3.43. Produksi Sapi Potong Jawa Timur
Sumber: Daerah Dalam Angka 2012
Berdasarkan jumlah populasi sapi potong dan jumlah sapi yang dipotong di propinsi
Jawa Timur, kesepuluh daerah diatas yaitu Kab. Sumenep, Kab. Jember, Kab. Tuban, Kab.
Kediri, Kab. Malang, Kab. Sidoarjo, Kab. Surabaya, Kota Malang, Kab. Lumajang dan Kab.
Lamongan menjadi pilihan lokasi survei.
Tabel 3.44. Produksi Sapi Potong Bali
Sumber: Daerah Dalam Angka 2012
Berdasarkan jumlah populasi sapi potong dan jumlah sapi yang dipotong di propinsi
Bali, kedelapan daerah diatas yaitu Buleleng, Karang Asem, Bangli, Tabanan, Jembrana,
Denpasar, Badung dan Gianyar menjadi pilihan lokasi survei.
Tabel 3.45. Produksi Sapi Potong NTB
Sumber: Daerah Dalam Angka 2012
Berdasarkan jumlah populasi sapi potong dan jumlah sapi yang dipotong di propinsi
Nusa Tenggara Barat, kedelapan daerah diatas yaitu Sumbawa, Lombok Tengah, Bima,
Lombok Timur, Dompu, Kota Mataram dan Lombok Barat menjadi pilihan lokasi
penelitian
Dari tabel-tabel tersebut diatas dapat dirangkum kota/kabupaten tujuan lokasi survei
serta komoditas yang disurvei adalah sebagai berikut:
Kabupaten Populasi Sapi potong
(ekor) Peringkat Kabupaten
Sapi Yang dipotong
(ekor) Peringkat
Kab Sumenep 357.038 1 Kab Sidoarjo 20.708.898 1
Kab Jember 324.230 2 Kota Surabaya 20.576.337 2
Kab Tuban 312.013 3 Kota Malang 4.946.239 3
Kab Kediri 268.139 4 Kab Lumajang 4.444.501 4
Kab Malang 225.895 5 Kab Lamongan 4.152.773 5
Total 4.727.298 Total 112.446.815
Jawa Timur
Kabupaten Populasi Sapi potong
(ekor) Peringkat Kabupaten
Sapi Yang dipotong
(ekor) Peringkat
Buleleng 136.191 1 Denpasar 13.347 1
Karangasem 135.507 2 Buleleng 9.951 2
Bangli 94.063 3 Badung 9.148 3
Tabanan 66.812 4 Gianyar 4.707 4
Jembrana 54.777 5 Karangasem 3.193 5
Total 637.461 Total 47.648
Bali
Kabupaten Populasi Sapi potong
(ekor) Peringkat Kabupaten
Sapi Yang dipotong
(ekor) Peringkat
Sumbawa 162.924 1 Kota Mataram 12.240 1
Lombok Tengah 119.029 2 Lombok Timur 8.394 2
Bima 117.842 3 Lombok Barat 7.560 3
Lombok Timur 99.092 4 Lombok Tengah 5.760 4
Dompu 85.612 5 Sumbawa 4.320 5
Total 784.019 Total 50.521
NTB

37
Tabel 3.46. Lokasi Survei Supply by Kategori Komoditas
Padi Jagung Sapi CPO
Jawa Timur Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab. Sumenep
Kab. Jember Kab. Sumenep Kab. Jember
Kab. Banyuwangi Kab. Jember Kab. Tuban
Kab. Lamongan Kab. Malang Kab. Kediri
Kab. Ngawi Kab. Probolinggo Kab. Malang
Jawa Tengah Kab. Cilacap Kab. Grobogan
Kab. Grobogan Kab. Wonogiri
Kab. Demak Kab. Blora
Kab. Brebes Kab. Kendal
Kab. Pati Kab. Boyolali
Jawa Barat Kab. Indramayu
Kab. Karawang
Kab. Subang
Kab. Garut
Kab. Tasikmalaya
Nusa Tenggara Barat Sumbawa
Lombok Tengah
Bima
Lombok Timur
Dompu
Sumatera Utara Kab. Simalungun Kab. Karo Kab. Asahan
Kab. Deli Serdang Kab. Simalungun Kab. Labuhan Batu Utara
Kab. Serdang Bedagai Kab. Dairi Kab. Langkat
Kab. Langkat Kab. Langkat Kab. Labuhan Batu Selatan
Kab. Simalungun
Lampung Kab. Lampung Selatan Lampung Tengah
Kab. Lampung Timur Lampung timur
Kab. Lampung Tengah Lampung Selatan
Kab. Lampung Utara Tulang Bawang barat
Way kanan
Sulawesi Selatan Kab. Bone Kab. Jeneponto
Kab. Wajo Kab. Gowa
Kab. Pinrang Kab. Bone
Kab. Gowa Kab. Bulukumba
Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ilir
Kab. Musi Rawas
Kab. Musi Banyu Asin
Kab. Muara Enim
Riau Kab. Kampar
Kab. Rokan Hilir
Kab. Rokan Hulu
Kab. Siak
Jambi Kab. Muaro Jambi
Kab. Tanjung Jabung Barat
Kab. Batang Hari
Kab. Merangin
Kab. Bungo
Bali Buleleng
Karangasem
Bangli
Tabanan
Jembrana
Kalimantan Tengah Kab. Lamandau
Kab. Kota Waringin Barat
Kab. Kota Waringin Timur

38
Kedelai Bawang Merah Tebu Cabe
Jawa Timur Kab. Banyuwangi Kab. Probolinggo Kab. Malang Kab. Gresik
Kab. Lamongan Kab. Nganjuk Kab. Jombang Kab. Tuban
Kab. Sampang Kab. Sampang Kab. Lumajang Kab. Banyuwangi
Kab. Ponorogo Kab. Mojokerto Kab. Kediri Kab. Sampang
Kab. Pasuruan Kab. Situbondo Kab. Malang
Jawa Tengah Kab. Grobogan Kab. Brebes Kab. Pati Kab. Brebes
Kab. Wonogiri Kab. Demak Kab. Sragen Kab. Magelang
Kab. Brebes Kab. Kendal Kab. Tegal Kab. Boyolali
Kab. Blora Kab. Tegal Kab. Rembang
Kab. Klaten Kab. Pati Kab. Pemalang
Jawa Barat Kab. Garut Kab. Cirebon Kab. Cirebon Kab. Cianjur
Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Majalengka Kab. Bandung
Kab. Sumedang Kab. Majalengka Kab. Kuningan Kab. Garut
Kab. Indramayu Kab. Garut
Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Bima
Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur
Kab. Dompu Kab. Sumbawa
Kab. Sumbawa
Sumatera Utara Kab. Karo
Kab. Deli Serdang
Kab. Simalungun
Lampung Kab. Way Kanan
Kab. Lampung Tengah
Kab. Lampung Utara
Kab. Tulang Bawang
Sulawesi Selatan
Sumatera Selatan
Riau
Jambi
Bali
Kalimantan Tengah

39
9) Lokasi Penelitian untuk Daerah dengan Konsumen Kelompok Ekonomi Menengah
Keatas (Demand Side)
Surveikonsumen dilakukan di 27 kota kabupaten dengan asumsi jumlah populasi
masyarakat menengah keatas terbanyak di Indonesia. Populasi ini diasumsikan tersebar
di 8 wilayah Indonesia, yaitu: Jakarta dan Sekitarnya, Surabaya dan Malang, Bandung
dan Sekitarnya, DI Yogyakarta, Semarang dan Sekitarnya, Makassar, Medan, dan
Denpasar. Komposisi jumlah penduduk dan kota kabupaten yang dipilih adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.47. Komposisi Jumlah Penduduk 8 Area Lokasi SurveiDemand Side

40
3.7. Operasionalisasi Konsep
3.7.1. Supply Side
Tabel 3.48. Operasionalisasi Konsep Supply Side
Variabel Konsep pertanyaan
Proporsi Penggunaan Lahan Pertanian
Kepemilikan lahan
Status pengelolaaan Lahan
Status kepemilikan lahan
Profil penggunaan lahan
Rencana penggunaan lahan
Iklim (Pengaruh Iklim Terhadap Pola Tanam)
Profil curah hujan
Profil temperature
Profil kelembaban
Profil sistem irigasi
Profil bencana alam pengganggu komoditas
Profil hama pengganggu
Profil serangan penyakit dan virus
Produktivitas
Jenis varietas bibit dan asal pasokan
Profil pembelian pasokan bibit
Profil penggunaan varietas bibit
Jenis pupuk dan asal pasokan
Profil pembelian pasokan pupuk
Profil penggunaan varietas pupuk
Jenis pestisida dan asal pasokan
Profil pembelian pasokan pestisida
Profil penggunaan varietas pestisida
Profil panen dan sistem panen
Profil ongkos usaha tani
Supply Chain Management
Alur tata niaga pasokan per kategori pelaku usaha
Profil pembentukan harga komoditas
Profil moda transportasi penjualan komoditas
3.7.2. Demand Side
Tabel 3.49. Operasionalisasi Konsep Demand Side
Variabel Konsep pertanyaan
Product Knowledge and Used
Profil keterkenalan produk per kategori komoditas
Profil penggunaan produk per kategori komoditas
Preferensi pertimbangan konsumsi produk per kategori
komoditas
Product Preference Profil pola konsumsi bahan pangan
Profil preferensi subtitusi bahan pangan

41
Variabel Konsep pertanyaan
Profil karakteristik kelengkapan kualitas produk per
kategori komoditas (lokal dan impor)
Profil persepsi (4P) produk per kategori komoditas
Stimuli for Consumer
Preference
Profil faktor yang mempengaruhi konsumsi produk per
kategori komoditas
Profil persepsi berdasarkan faktor ekonomi (peningkatan
daya beli)
Profil persepsi berdasarkan faktor kebijakan (impor
komoditas, dan lainnya)
Profil persepsi berdasarkan faktor lainnya (budaya,
kesehatan, dan lainnya)

42
BAB 4. PENGERTIAN, KARAKTERISTIK DAN KONDISI UMUM
KETAHANAN PANGAN
4.1. Pengertian Ketahanan Pangan
Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak
adanya Conference of Food and Agriculture tahum 1943 yang mencanangkan konsep
“secure, adequate and suitable supply of food for everyone”. Definisi ketahanan pangan
sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan
Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni akses semua orang setiap saat pada pangan
yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all times to sufficient food for a healthy
life).
Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan
450 indikator tentang ketahanan pangan (Weingartner, 2000). Berikut disajikan
beberapa definisi ketahanan yang sering diacu :
1) Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996: kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan
bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari
jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau
2) USAID (1992): kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses
secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup
sehat dan produktif.
3) FAO (1997) : situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik
maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya,
dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.
4) FIVIMS (2005): kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, social
dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk
pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan seleranya (food preferences)
demi kehidupan yang aktif dan sehat.
5) Mercy Corps (2007) : keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai
akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap terhadap kecukupan pangan, aman dan
bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan
sehat.
Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan
memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi :

43
1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu
2. Dimensi watu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses
3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan
sosial
4. Berorientasi pada pemenuhan gizi
5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif
Di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1996, pengertian ketahanan
pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1)
tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3)
merata; dan (4) terjangkau. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan
pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:
a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan
ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman,
ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak,
vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan
kesehatan manusia.
b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran
biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan
membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.
c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus
tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.
d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah
diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.
Ketahanan pangan memiliki tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan, akses, dan
penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan
pangan. Ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan merupakan sub sistem yang harus
dipenuhi secara utuh. Salah satu subsistem tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara
belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik.
Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses
individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan
masih dikatakan rapuh.

44
Gambar 4.1. Sub Sistem Ketahanan Pangan Sumber: USAID (1999), dan Weingartner (2004)
Sub sistem ketersediaan pangan (food availability) adalah ketersediaan pangan
dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara
baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan
pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan
sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.
Gambar 4.2. Sub Sistem Ketersediaan Pangan
Sumber: Patrick Webb and Beatrice Rogers (2003)

45
Sedangkan akses pangan (food access)adalah kemampuan semua rumah tangga dan
individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup
untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri,
pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri
dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan,
kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan
prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan.
Gambar 4.3. Sub Sistem Akses Pangan Sumber: Patrick Webb and Beatrice Rogers (2003)
Penyerapan pangan (food utilization)adalah penggunaan pangan untuk kebutuhan
hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan.
Efektifitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan
rumahtangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan,
serta penyuluhan gisi dan pemeliharaan balita. (Riely et.al , 1999).
Stabiltas (stability) merupakan dimensi waktu dari ketahanan pangan yang terbagi
dalam kerawanan pangan kronis (chronic food insecurity) dan kerawanan pangan
sementara (transitory food insecurity). Kerawanan pangan kronis adalah ketidak
mampuan untuk memperoleh kebutuhan pangan setpa saat, sedangkan kerawanan
pangan sementara adalah kerawanan pangan yang terjadi secara sementara yang
diakibatkan karena masalah kekeringan banjir, bencana, maupun konflik sosial.
(Maxwell and Frankenberger 1992).
Status gizi (Nutritional status) adalah outcome ketahanan pangan yang merupakan
cerminan dari kualitas hidup seseorang. Umumnya satus gizi ini diukur dengan angka
harapan hidup, tingkat gizi balita dan kematian bayi.

46
Dengan demikian, sistem ketahanan pangan secara komprehensif dapat dirangkum
menjadi empat sub-sistem, yaitu: (i) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis
yang cukup untuk seluruh penduduk, (ii) distribusi pangan yang lancar dan
merata, (iii) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi
seimbang, yang berdampak pada (iv) status gizi masyarakat .
Gambar 4.4. Sub Sistem Penyerapan Pangan
Sumber: Patrick Webb and Beatrice Rogers (2003)
4.2. Kondisi Umum Bahan Pangan Pokok
Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam
yang melimpah. Hal ini terbukti dengan keadaan tanah Indonesia yang sangat subur.
Oleh karena hal tersebut, Indonesia memiliki peran penting sebagai produsen bahan
pangan di mata dunia. Indonesia merupakan produsen beras terbesar ketiga dunia
setelah China dan India. Kontribusi Indonesia terhadap produksi beras dunia sebesar
8,5persen atau 51 juta ton. China dan India sebagai produsen utama beras
berkontribusi 54persen. Vietnam dan Thailand yang secara tradisional merupakan
negara eksportir beras hanya berkontribusi 5,4 persen dan 3,9 persen.

47
Dalam konteks pertanian umum, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Kelapa
sawit, karet, dan coklat produksi Indonesia mulai bergerak menguasai pasar dunia.
Namun, dalam konteks produksi pangan memang ada suatu keunikan. Meski
menduduki posisi ketiga sebagai negara penghasil pangan di dunia, hampir setiap tahun
Indonesia selalu menghadapi persoalan berulang dengan produksi pangan terutama
beras. Produksi beras Indonesia yang begitu tinggi belum bisa mencukupi kebutuhan
penduduknya, akibatnya Indonesia masih harus mengimpor beras dari Negara
penghasil pangan lain seperti Thailand.
Salah satu penyebab utamanya adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Data
statistik menunjukkan jumlahnya pada kisaran 230-237 juta jiwa, selain itu makanan
pokok hampir semua penduduk adalah beras sehingga sudah jelas kebutuhan beras
menjadi sangat besar.
Penduduk Indonesia merupakan konsumen beras terbesar di dunia dengan jumlah
konsumsi mencapai 154 kg per orang per tahun, apabila dibandingkan dengan rerata
konsumsi di China yang hanya 90 kg, India 74 kg, Thailand 100 kg, dan Philppine 100
kg. Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan beras Indonesia menjadi tidak terpenuhi
jika hanya mengandalkan produksi dalam negeri, dan oleh karena hal tersebut
Indonesia harus mengimpornya dari negara lain.
Selain beras, Indonesia juga masih mengimpor komoditas pangan lainnya seperti 45
persen kebutuhan kedelai dalam negeri, 50 persen kebutuhan garam dalam negeri,
bahkan 70 persen kebutuhan susu dalam negeri dipenuhi melalui impor. Faktor lain
yang mendorong adanya impor bahan pangan adalah iklim, khususnya cuaca yang tidak
mendukung keberhasilan sektor pertanian pangan, seperti yang terjadi saat ini.
Pergeseran musim hujan dan musim kemarau menyebabkan petani kesulitan dalam
menetapkan waktu yang tepat untuk mengawali masa tanam, menentukan penggunaan
benih beserta pupuk, dan sistem pertanaman yang akan digunakan.
Tidak menentunya jadwal tanam juga menyebabkan tidak menentunya penyediaan
benih dan pupuk yang semula terjadwal. Hal tersebut akhirnya menyebabkan
kelangkaan karena keterlambatan pasokan benih dan pupuk. Akhirnya hasil produksi
pangan menurun.Bahkan terjadinya anomali iklim yang ekstrem dapat secara langsung
menyebabkan penurunan produksi tanaman pangan tertentu, karena tidak mendukung
lingkungan yang baik sebagai syarat tumbuh suatu tanaman. Contohnya saat terjadi
anomali iklim El Nino menyebabkan penurunan hasil produksi tanaman tebu, negara
melalukan impor gula.
Penyebab impor bahan pangan selanjutnya adalah luas lahan pertanian yang semakin
sempit. Terdapat kecenderungan bahwa konversi lahan pertanian menjadi lahan non
pertanian mengalami percepatan. Dari tahun 1981 sampai tahun 1999 terjadi konversi
lahan sawah di Jawa seluas 1 Juta Ha di Jawa dan 0,62 juta Ha di luar Jawa. Walaupun
dalam periode waktu yang sama dilakukan percetakan sawah seluas 0,52 juta ha diJawa

48
dan sekitar 2,7 juta Ha di luar pulau Jawa, namun kenyataannya percetakan lahan
sawah tanpa diikuti dengan pengontrolan konversi tidak mampu membendung
peningkatan ketergantungan Indonesia terhadap beras impor.
Ketergantungan impor bahan baku pangan juga disebabkan oleh biaya transportasi di
Indonesia yang mencapai 34 sen dolar AS per kilometer. Apabila diandingkan dengan
negara lain seperti Thailand, China, dan Vietnam yang rata-rata sebesar 22 sen dolar AS
per kilometer, biaya di Indonesia relatif lebih mahal. Sepanjang kepastian pasokan tidak
kontinyu dan biaya transportasi tetap tinggi, maka industri produk pangan akan selalu
memiliki ketergantungan impor bahan baku.
laporan ini untuk seterusnya akan membahas mengenai kondisi umum bahan pangan
pokok yaitu Daging Sapi. Selama periode 1987-1996 rataan laju peningkatan konsumsi
daging sebesar 7,36 persen per tahun(DITJEN PETERNAKAN, 1997). Kontribusi daging
sapi (21,27 persen) menduduki urutan kedua setelahdaging unggas (58,02 persen)
dalam memenuhi kebutuhan daging. Pada periode yang sama konsumsidaging sapi
tumbuh sebesar 4,43 persen, sedangkan produksi yang sebagian besar berasal dari
peternakanrakyat, populasinya hanya tumbuh 2,33 persen. Tanpa upaya-upaya
peningkatan produksi, diduga akanterjadi pengurasan populasi.
Indonesia belum mandiri dalam penyediaan kebutuhan daging sapi nasional karena
baru mampu memproduksi 70 persen dari kebutuhan daging sapi nasional dimana 30
persen kebutuhan lainnya dipenuhi melalui impor (DITJENNAK, 2008) dalam bentuk
sapi bakalan untuk penggemukan, daging beku dan jeroan yang didominasi oleh hati
dan jantung beku. Besarnya impor ini dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan
kesejahteraan dan pertambahan penduduk. Daging sapi yang paling banyak dikonsumsi
oleh masyarakat Indonesia adalah dalam bentuk daging bakso yang menyebar dari
kawasan perkotaan sampai ke pedesaan.
4.2.1. Kondisi Umum Tata Niaga Sapi dan Daging Sapi
Berdasarkan analisis tata niaga daging sapi di Indonesia (Saptana dan Nuryanti 2013),
terdapat beberapa aktor dalam alur perdagangan daging sapi di sisi hulu yaitu;
pengecer desa, pengecer pasar, meatshop, supermarket, grosir, dan pedagang
pengumpul. Masing-masing aktor memiliki sumber pembelian masing-masing.
Misalnya; sumber pembelian daging sapi untuk pengecer desa, pengecer pasar, dan
supermarket, mayoritas adalah grosir dan RPH. Sedangkan untuk pedagang grosir dan
pengumpul mayoritas sumber pembelian daging sapi berasal dari RPH dan peternak.
Rata-rata diatas 75 persen transaksi perdagangan daging sapi tersebut terjadi di dalam
wilayah kabupaten.

49
Gambar 4.5. Sumber Pembelian Pedagang Daging Sapi
Sumber: Kementerian Perdagangan, 2011
Sedangkan alur perdagangan di sisi hilir dilakukan oleh aktor-aktor seperti pengecer
desa, pengecer pasar, grosir, dan pedagang pengumpul dengan mayoritas tujuan
penjualan akhir ke rumah tangga, horeka, dan industri.
Gambar 4.6. Tujuan Penjualan Pedagang Daging
Sumber: Kementerian Perdagangan, 2011
Jika dilihat dari pencapaian target visi pembangunan dengan periode waktu 2005 –
2025 maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2005 adalah sebesar 241,9 juta
orang dan pada tahun 2025 akan mencapai 273,1 juta orang yang berarti naik sebesar
12,9 persen. Jika produksi daging sapi yang pada tahun 2005 adalah sebesar 358.700
ton (setara dengan 1,8 juta ekor sapi) maka jika tingkat konsumsi tidak berubah yaitu
1,7 kg per kapita per tahun maka akan dibutuhkan daging sebesar 464.270 ton yang

50
setara dengan jumlah pemotongan sebesar 2,4 juta ekor sapi (dianalisis kembali dari
BIRO STATISTIK INDONESIA, 2007).
Kebutuhan daging masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh produksi daging sapi dalam
negeri. Dengan asumsi tersebut maka total konsumsi daging sapi oleh masyarakat
mencapai 385.000 ton/tahun, sementara produksi daging sapi lokal hanya 271.000 ton.
Artinya masih ada kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan produksi daging
sapi lokal yang besarnya mencapai 114.000 ton.Konsekuensinya, Indonesia harus
melakukan impor, selain untuk memenuhi segmen pasar industri, juga memenuhi
tuntutan konsumen terhadap kualitas daging sapi yang lebih baik. Sayangnya, hal
tersebut memiliki efek samping terhadap gejolak kompetisi harga daging sapi yang
beredar di pasaran.
4.2.2. Kondisi Umum Pelaku Usaha
Secara garis besar alur tata niaga daging sapi yang terjadi saat ini adalah sebagai
berikut:
Gambar 4.7. Kondisi Tata Niaga Daging Sapi Saat Ini
Sumber: Asosiasi Pengusaha Daging dan Sapi Potong Indonesia (APDASI) Jawa Barat, 2013
4.2.2.1. Peternak
Peternakan sapi potong di Indonesia sebagian besar merupakan peternakan rumah
tangga (RTP) dimana memelihara ternak hanya sebagai komplemen (Fauzi dan
Djajanegara, 2006). Kompelemen disini maksudnya adalah sebuah usaha sampingan
yang diintegrasikan dengan usaha tanaman pangan (pertanian) yang dikelola secara
LOKAL
BANDAR SAPI
IMPOR
IMPORTIR DAGING
DISTRIBUTOR DAGING IMPOR
HOREKA/ SUPERMARKET
IMPORTIR SAPI/FEEDLOTER
PENGIRIMAN SAPI/ BELANTIK
PEMOTONG/ BANDAR
KONSUMEN (Masy/ UKM)
INDUSTRI OLAHAN DAGING
SAPI PENGECER/ SUPLIER

51
tradisional dan dijual sewaktu ada keperluan mendesak (Fauzi dan Djajanegara, 2006).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005, rumah tangga peternak (RTP) di
Indonesia berjumlah 4.980.302 dan 58 persen dari jumlah tersebut atau sebesar
2.888.575 adalah rumah tangga peternak sapi potong. Fauzi dan Djajanegara (2006)
menambahkan bahwa kepemilikan RTP sapi potong tersebut memiliki skala/jumlah 1-3
ekor.
Menurut Fauzi dan Djajanegara (2006) kondisi usaha yang dimiliki peternak bersifat
kurang profesional, sehingga menyebabkan lemahnya posisi tawar petani dalam sistem
pemasaran sapi potong dan sering dimanfaatkan oleh pedagang
sapi/bandar/tengkulak. Berdasarkan studi di kabupaten Garut (Fauzi dan Djajanegara,
2006), ditemukan bahwa proses penjulan sapi oleh peternak RTP diawali dengan
kegiatan penawaran sapi ke sesama peternak di daerah sekitarnya. Proses ini dianggap
lebih mudah karena secara personal mereka sama-sama telah mengenal, sudah terjalin
hubungan antar peternak dalam aktifitas mereka melakukan usaha tani ternak. Namun
jika penawaran sapi potong tidak diminati oleh peternak sekitarnya, barulah peternak
mencari pedagang yang juga tidak jauh dari tempat tinggalnya.
Gambar 4.8. Pola Pemasaran Sapi Potong Pada Peternak Kelompok dan Individu Sumber: Kajian Pemasaran Sapi Potong Dalam Pengembangan Sistem Integrasi Tanaman Ternak. Seminar
Nasional Sistem Integrasi Tanaman-Ternak. Fauzi dan Djajanegara (2006)
Selain itu, dalam keadaan terdesak, petani ternak akan mencari blantik sapi (bandar)
dimana blantik dapat menghubungkan mereka dengan pedagang sapi keliling, pedagang
besar atau peternak besar. Hal diatas diperkuat dengan temuan penelitian peternakan
sapi potong individu di daerah Kediri (Daroini, 2013) dimana peternak juga

52
menunjukkan perilaku penjualan sapi potong yang sama seperti menjual sapi juga ke
peternak lain, seperti yang tergambar pada gambar berikut:
Dari pemain-pemain tata niaga sapi yang tergambar pada gambar-gambar diatas,
berdasarkan studi di daerah Garut, Fauzi dan Djajanegara (2006) menyimpulkan bahwa
rantai perdagangan sapi dari peternak dan persentase kemungkinan penjualan sapi
diantara pemain tata niaga sapi adalah sebagai berikut:
Gambar 4.9. Imbangan Jalur Pemasaran Sapi Potong Kabupaten Garut (2000 – 2003)
Sumber: Pola Pemasaran Sapi Potong pada Peternak Skala Kecil di Kabupaten Kediri. Daroini (2013)
Dalam memasarkan ternaknya, peternakan sapi potong rakyat memiliki ketergantungan
yang tinggi pada jasa pedagang pengumpul dalam memasarkan ternaknya. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya (Daroini, 2013):
1) Skala usaha yang relatif kecil sehingga biaya angkutan ke pasar tidak efisien .
2) Minimnya pengetahuan akses pasar oleh peternak.
3) Transaksi didasarkan oleh pembeli, bobot badan ternak dan indikator-indikator
lainnya terabaikan sehingga posisi tawar peternak lemah.
4) Adanya blantik dadung sebagai makelar dipasar yang berpotensi mengurangi
pendapatan peternak.
Pada kenyataannya, berdasarkan studi petani-peternak di Kabupaten Garut (Fauzi dan
Djajanegara, 2006) petani-peternak lebih memilih menjual pada tipe pedagang sapi
yang juga merangkap sebagai pejagal (penjual daging sapi) yang memotong sendiri sapi.
Hal ini dikarenakan pedagang tipe tersebut diperkirakan memiliki kekuatan finansial

53
yang lebih baik dibanding pedagang sapi biasa. Maka, jalur pemasaran sapi potong
(Fauzi dan Djajanegara, 2006): jika dicermati dan dipelajari melibatkan:
1) Jagal merangkap penjual daging yang tidak membayar secara kontan kepada
penjual sapi
2) Pedagang dan bandar sapi yang membeli dari petani tidak kontan atau dengan uang
muka
3) Porsi daging yang diambil jagal saat sapi dipotong.
Faktanya, harga seekor sapi ditentukan oleh performance fisik. Hal ini dikarenakan
pedagang umumnya tidak menggunakan timbangan dalam menghitung berat sapi
(Daroini, 2013). Berdasarkan studi yang dilakukan di daerah Kediri, gambaran
perhitungan seekor harga sapi adalah sebagai berikut (Daroini, 2013) :
Selain itu, Fauzi dan Djajanegara (2006) juga menemukan catatan transaksi antara
pedagang sapi potong dan peternak dimana transaksi tersebut melibatkan pembayaran
secara tunai dan hutang bagaimana tergambar pada tabel berikut:
Gambar 4.10. Model Transaksi Jual Beli Sapi Potong dan Ternak Sumber: Kajian Pemasaran Sapi Potong Dalam Pengembangan Sistem Integrasi Tanaman Ternak. Seminar
Nasional Sistem Integrasi Tanaman-Ternak. Fauzi dan Djajanegera (2006)
Jika seekor sapi potong yangditimbang memiliki berat hidup 400 kg,dengan asumsi harga/kg berat hidup sebesarRp 21.000,- untuk sapi jenis (crossing IB) dan sapi lokal Rp 19.000,-, makaberdasarkan hasil penimbangan diperolehharga berat hidup sapi untuk sapi jenis(crossing IB) sebesar Rp 8.400.000,-, dan untuk sapi lokal sebesar Rp 7.600.000,-. Realitas harga yang diberikanoleh pembeli akan lebih rendah sekitar Rp500.000,-, atau bahkan bisa lebih darinominal tersebut. Dalam istilah mereka,pedagang atau pembeli akan mencari “stan”atau celah longgar (low estimation) dari hasil timbangan berat hidup, yang didasarkan padakondisi tampilan fisik sapi potong.

54
Sikap peternak terkait pada proses penjualan sapi potong, dikategorikan dalam dua
status produksi sapi potong yaitu sapi potong yang dijual masih dalam masa produktif
dan sapi potong yang dijual sudah mengalami penurunan produksi (Daroini, 2013).
Selain itu, berdasarkan pengklasifikasian tersebut, Daroini (2013) jug amenambahkan
bahwa terdapat proses pembelajaran ekonomi oleh peternak melalui upaya untuk
mempertimbangkan ketika menjual sapi tidak pada periode terlalu muda meskipun
dapat dianggap sapi yang dijual masih berpotensi dipelihara lagi oleh calon pembeli.
Menurut Suryana (2009), sistem pemeliharaan sapi potong di Indonesia dibedakan
menjadi tiga, yaitu : intensif, ekstensif, dan usaha campuran (mixed farming). Pada
pemeliharaan secara intensif, sapi dikandangkan secara terus-menerus atau hanya
dikandangkan pada malam hari dan pada siang hari ternak digembalakan. Pola
pemeliharaan sapi secara intensif banyak dilakukan petani peternak di Jawa, Madura,
dan Bali. Pada pemeliharaan secara ekstensif, ternak dipelihara di padang
penggembalaan dengan pola pertanian menetap atau di hutan. Pola tersebut banyak
dilakukan peternak di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.
Terkait waktu penjualan sapi, peternak akan menjual sapi potong mereka setelah sapi
mengalami pertambahan berat badan atau menghasilkan anak sapi (Daroini , 2013).
Selain itu, berdasarkan penelitian di daerah Kediri yang dilakukan oleh Daroini (2013)
juga dijelaskan bahwa sikap peternak sikap peternak terkait pada proses penjualan sapi
potong, dikategorikan dalam dua status produksi sapi potong yaitu sapi potong yang
dijual masih dalam masa produktif dan sapi potong yang dijual sudah mengalami
penurunan produksi.
Dilihat dari sisi pendidikan, RTP umumnya dimiliki oleh sebagian besar para peternak
dengan pendidikan terakhir adalah tamat sekolah dasar mengalami peningkatan dari
tahun 2009 sebesar 1,4 juta orang menjadi 1,5 juta orang ini menunjukan pendidikan
para peternak masih rendah atau sekitar 37 persen adalah tamat Sekolah Dasar, yang
tamat Diploma dan Sarjana hanya 0 persen, sedangkan tidak tamat SD sekitar 25
persen. yang berimplikasi terhadap skala kepemilikan ternak masih kecil dan bersifat
tradisional, kelmbagaan peternak belum kuat yang juga berdampak kepada sulitnya
para peternak untuk mengakses lembaga pembiayaan karena dinilai tidak bankable dan
feasible oleh lembaga pembiayaan (Hendri, 2013).
4.2.2.2. Belantik
Belantik merupakan makelar sapi yang umumnya berada di pedesaan dimana menjadi
mediator antara petani-peternak dan pedagang sapi (Daroini, 2013). Apabila terdapat
peluang keuntungan dari sapi yang akan dijual oleh petani, blantik sapi akan
menghubungi pedagang sapi yang memiliki uang tunai (Daroini, 2013). Blantik atau
pedagang yang mengetahui informasi terkait sapi yang dijual akan memberitahu
peternak besar jika pedagang kecil tidak memiliki uang tunai atau kekurangan uang
untuk membelinya (Daroini, 2013). Peternak besar akan menyediakan dana pembelian

55
dan orang kepercayaannya untuk memastikan kebenaran informasi dari belantik
tersebut (Daroini, 2013).
4.2.2.3. Importir Sapi dan Daging
Pada awalnya kebijakan izin impor sapi bakalan dan daging sapi yang dikeluarkan
pemerintah tahun 1980an untuk menyediakan daging murah, sehingga konsumsi
daging masyarakat meningkat (Ramadhany, 2011). Namun, saat ini proporsi daging sapi
impor terus meningkat dengan semakin meningkatnya permintaan dan pemain dalam
kegiatan impor sapi dan daging impor (Ramadhany, 2011). Berikut adalah gambar yang
menunjukkan bagaiamana kegiatan importir serta beberapa perusahaan importir besar
di Indonesia:
Gambar 4.11.
Peta Persaingan Importir Sapi Potong di Indonesia
Sumber: Strategi Bersaing Komoditas Sapi Potong di Indonesia, Studi Kasus Pada PT. Elders Indonesia,
Ramadhani 2011
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ramadhany (2011) kegiatan sebuah perusahaan
importir dapat dijelaskan pada gambar berikut:
Gambar 4.12. Rantai Kegiatan Perusahaan Pengimpor Sapi Potong
Sumber: Strategi Bersaing Komoditas Sapi Potong di Indonesia, Studi Kasus Pada PT. Elders Indonesia,
Ramadhani 2011
Importir Sapi Potong & Daging Sapi
Sertifikasi dan Standar Internasional
PT. Hutama PT. Santeri PT. Elders PT. SInar PT. Bira
Mentari
Distributor
Pasar Indonesia
Importir Sapi Potong &
Daging Sapi
Pasar Indonesia 3. Pemotongan
4. Packaging
5. Merk
6. Distributor
2. Penggemukan
1. Bibit

56
Impor daging sapi dan sapi bakalan semula dimaksudkan hanya untuk mendukung dan
menyambung kebutuhan daging sapi yang terus meningkat, atau dengan kata lain
sebagai penyeimbang untuk mencegah terjadinya pengurasan sumberdaya domestik.
Namun kini telah berkembang ke arah yang berbeda (Ramadhani, 2011). Di beberapa
daerah ternyata daging sapi dan sapi bakalan impor justru berpotensi mengganggu
usaha agribisnis sapi potong lokal (Ramadhani, 2011).Hal ini dikarenakan harga daging,
jeroan dan sapi bakalan impor relatif murah, karena sebagian besar merupakan produk
yang kurang berkualitas. Selain menjadi importir, seperti yang tampak pada grafik
diatas, beberapa importir sapi impor juga merangkap sebagai feedlot atau penggemuk
sapi.
4.2.2.4. Feedloter
Menurut Hafid (2005), produktivitas peternakan di Indonesia tergolong rendah dan
masih bersifat subsisten serta mengandalkan peternakan rakyat sehingga menyebabkan
tidak terpenuhinya permintaan terhadap komoditas hasil ternak, khususnya kebutuhan
daging sapi. Hal ini mendorong berkembangnya industri feedloting di Indonesia dengan
bakalan impor yang berasal dari Australia dan New Zealand. Kegiatan impor juga tidak
hanya dalam hal mendatangkan bakalan sapi saja, tetapi juga berupa karkas dan daging
beku yang jumlahnya terus meningkat. Jumlah ini berkembang terus hingga mencapai
lebih dapi 40 perusahaan pada tahun 1997 yang tersebar terutama di Pulau Jawa dan
Lampung dengan total impor sapi bakalan berkisar antara 300.000 - 400.000 ekor per
tahun (binaukm.com.htm 17/07/2010 ).
Feedlot atau usaha penggemukan didefinisikan sebagai suatu usaha pemeliharaan sapi
yang bertujuan untuk mendapatkan produksi daging berdasarkan pada peningkatan
bobot badan tinggi melalui pemberian makanan yang berkualitas dan dengan waktu
yang sesingkat mungkin (Suganda, Arifin danSitumorang, 2012).Feedlot diklasifikasikan
dalam 2 jenis: feedlot secara dikandangkan (feedlot fattening), feedlot di padang
rumput (pasture fattening). Tujuan pemeliharaan sapi sistem feedlot adalah untuk
mendapatkan keuntungan dari penjualan sapi dikurangi biayaproduksi yang terdiri dari
biaya bibit (bakalan), pemeliharaan bakalan,biaya pakan, upah tenaga, dan lain-lain
(Basuki, 2000). Biaya pakan dapat mencapai 70-80 persen dari biaya (Pakan hijauan,
pakan konsentrat). Menurut Rianto (2009) perbandingan kebutuhan hijauan dan
konsentrat untuk penggemukan sapi potong adalah 30:70.
Parameter yang penting diperhatikan dalam operasional usaha feedlot adalah laju
pertumbuhan, efisiensi pertambahan bobot badan, nilaikonversi pakan yang efisien,
produksi karkas dan daging, dan rasio feed cost gain yang ekonomis (Dyer dan O’Mary,
1977). Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan meliputi seleksi jenis bibit, sistem
perkandangan, pemberian pakan hijau, pemberian air minum, kebersihan ternak sapi
potong dan kandang, serta pemberian obat-obatan (Santoso, 2008).

57
Menurut Rianto (2009) sistim usaha penggemukan sapi potong dibagi menjadi tiga
metode, yaitu (1) pasture fattening, (2) dry lot fattening, dan (3) kombinasi antara
keduanya. Sapi bakalan yang digunakan dalam kereman umumnya sapi-sapi jantan
yang berumur sekitar 1-2 tahun dalam kondisi kurus dan sehat. Sistem pasture
fattening memerlukan waktu yang relatif lama, yaitu sekitar 8-10 bulan, dengan sapi
bakalan yang digunakan pada pasture fattening adalah sapi jantan atau betina dengan
umur minimal sekitar 2,5 tahun. Sistem dry lot fattening adalah sistem penggemukan
dimana sapi berada terus-menerus dalam kandang dan tidak di gembalakan ataupun
dipekerjakan diamanumumnya sapi-sapi jantan yang telah berumur dari 1 tahun
dengan lama penggemukan sekitar 2-6 bulan.
Beberapa manfaat dengan adanya feedlot adalah (Banumastya, 2011):
1) Menghasilkan pertambahan nilai (value adding) dan penggandaan sumber daya
melalui kenaikan berat badan sapi yang dihasilkan dari kegiatan penggemukan
2) Membantu mengurangi laju pengurasan sumber daya ternak sapi potong lokal dan
menjaga kesimbangan supply-demand dalam mengatasi laju pertumbuhan
demand/konsumsi daging terhadap kemampuan pertumbuhan supply sapi lokal
yang terbatas.
3) Menghasilkan output daging sapi segar yang memenuhi kaidah ASUH (Aman, Sehat,
Utuh, Halal)
Dalam pencarian sapi potong untuk digemukkan, usaha Feedlot lebih cenderung untuk
memilih sapi berdasarkan kualitas dikarenakan harga yang ditawarkan pedagang sapi
cenderung mirip (Banumastya, 2011). Terkait dengan pengaruh kebijakan PSDS 2014
dimana terdapat pembatasan impor sapi bakalan, secara tidak langsung hal ini justru
meningkatkan tingkat efisiensi yang berdampak pada peningkatan daya saing usaha
penggemukan sapi potong (berdasarkan penelitian Banumastya, 2011 di PT Widodo
Makmur Perkasa). Kebijakan tersebut menyebabkan Feedloter mengeluarkan biaya
lebih rendah dari opportunity cost untuk berproduksi dan menetapkan harga output di
atas harga efisiensinya, serta meningkatkan surplus usaha. (Banumastya, 2011).
Penanganan yang intensif terhadap ternak: Sapi yang telah sampai ke kandang
karantina sebelum masuk untuk penggemukkan terlebih dulu dilakukan penimbangan
di tempat penimbangan yang dilengkapi dengan alat pencatat (printer), apabila
teridentifikasi sakit, maka sapi yang sakit tersebut dipisahkan untuk dikarantina atau
diisolasi dari sapi yang sehat. Selama sapi dikarantina upaya penyembuhan terus
dilakukan sampai sapi tersebut sehat sedangkan sapi yang mati dikubur di tempat yang
sudah disediakan di lokasi kegiatan, hal itu digunakan agar pencegahan penularan
penyakit terhadap sapi yang sehat dalam kandang karantina.

58
Tabel 4.1. Biaya Usaha Penggemukan Sapi
Sumber:Kajian Usaha Penggemukan Sapi Bali Di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Seminar
Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner, Qomariyah dan Bahar 2011
Setelah sapi-sapi mengalami serangkaian proses penggemukkan dan pemeliharaan
selama 90 hari, usaha Feedlot akan melakukan kegiatan penjualan sapi potongnya
(Ramadhany, 2011).. Setelah sapi dinyatakan aman untuk dijadikan sapi potong akan
langsung disalurkan kepada para pelanggan yang rata-rata penjual sapi potong skala
kecil atau pada pejagalan-pejagalan yang memproduksi daging sapi atau karkas yang
dikonsumsi oleh masyarakat. Skala kecil atau pejagalan-pejagalan di sini artinya
pembelian sapi potong dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar (Ramadhany,
2011).
Hasil pengkajian Qomariyah dan Bahar (2010) di daerah Maros, Sulawesi Selatan
menunjukkan bahwa teknologi penggemukan sapi mampu menghasilkan pertambahan
bobot badan (PBB) rata-rata sebesar 0,6 kg/ekor/hari. Jadi, dalam periode 3 bulan
usaha tani penggemukan sapi dan pemanfaatan limbah ternak sebagai biogas,
memberikan pendapatan bersih kepada kelompok tani sebesar Rp. 1.069.854 per ekor
dengan R/C sebesar 1,2 yang berindikasi bahwa usaha tersebut menguntungkan untuk
dilakukan (Qomariyah dan Bahar, 2010).
Menurut Sarwono dan Arianto (2006), keberhasilan penggemukan sapi potong sangat
tergantung pada pemilihan bibit yang baik dan kecermatan selama pemeliharaan.
Bakalan yang akan digemukkan dengan pemberian pakan tambahan dapat berasal dari
sapi lokal yang dipasarkan di pasar hewan atau sapi impor yang belum maksimal
pertumbuhannya.

59
4.2.2.5. Bandar Sapi
Kondisi usaha yang dapat dikatakan kurang profesional yang dilakukan oleh petani-
peternak menyebabkan lemahnya posisi tawar petani dalam sistem pemasaran sapi
potong. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pedagang sapi/bandar/tengkulak. Hasil kajian
Rahmanto (2004) Analisis usaha peternakan sapi potong rakyat bahwa para peternak
dalam memasarkan ternaknya memiliki ketergantungan yang tinggi pada jasa pedagang
pengumpul dalam memasarkan ternaknya.
Bandar penjual di pasar hewan umumnya merupakan penjual yang sudah lama
melakukan kegiatan penjualan bakalan sapi potong. Skala penjualan bandar tergolong
cukup besar, ini dilihat dari banyaknya bakalan sapi potong yang dibawa untuk
diperdagangkan yaitu sebanyak 5 ekor atau lebih. Selain itu beberapa bandar penjual
tergolong pengusaha sapi potong yang juga melakukan aktivitas jual beli bakalan sapi
potong di luar hari pasar. Sebagian besar bandar penjual memiliki usaha jual beli ternak
sapi potong di wilayah peternakannya.
4.2.2.6. Bandar Daging dan Rumah Potong Hewan
Bandar daging adalah pelaku usaha yang melakukan aktivitas jual beli sapi dan daging
sapi sampai menjadi bentuk potongan akhir baik itu dalam wujud karkas, kulit, dan
potongan daging sapi. Bandar daging umumnya menggunakan jasa Rumah Potong
Hewan (RPH) untuk melakukan aktivitas penyembelihan sapi dan produksi daging
potong untuk dijual ke konsumen akhir.
Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan
desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi
konsumsi masyarakat umum (PerMenTan No.13 tahun 2010). RPH merupakan unit
pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal,
serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan beberapa hal yang di antaranya
adalah:
1) Pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan
masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama);
2) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem insoection) dan
pemeriksaan karkas, dan jeroan (post-mortem inspection) untuk mencegah
penularan penyakit zoonotik ke manusia;
3) Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada
pemeriksaan aante-mortem dan pemeriksaan post-mortem guna pencegahan,
pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah
asal hewan (PerMenTan No.13 tahun 2010).

60
Pertumbuhan permintaan terhadap daging sapi yang cukup tinggi, membuat “pemain”
di struktur pelaku usaha sapi dan daging sapi semakin berkembang. Terutama pelaku
usaha dengan modal tafsiran (belantik) yang masih cukup marak di Indonesia.
Menghadapi hal tersebut, penting untuk menyikapi pelaku usaha yang paling berperan
dalam pencapaian sistem ketahanan pangan daging sapi.Dalam penyediaan daging sapi
ada tiga pelaku utama yang perlu diperhatikan dengan baik karena peranan ketiganya
yang cukup signifikan. Ketiga pelaku tersebut adalah peternakan sapi rakyat yang
mengusahakan sapi lokal, industri penggemukan sapi yang mengandalkan pada sapi
bakalan impor dan industri daging dan jeroan yang menggunakan produk daging sapi
asal impor.
a. Peternakan sapi rakyat
Peternakan sapi rakyat diperkirakan menyumbangkan kurang lebih 70 persen
produk daging sapi nasional yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Produk
tersebut dihasilkan dari sekitar 10.7 juta ekor sapi potong, 2.2 juta ekor kerbau
(yang dikenal di masyarakat umum juga sebagai daging sapi) dan 0,3 juta ekor sapi
perah (DITJENNAK, 2008). Produk hewani tersebut dihasilkan oleh minimal 3.6 juta
rumah tangga peternak (BPS, 2007). Setiap keluarga peternak hanya memelihara
antara 2 – 6 ekor dengan pemilikan terbanyak antara 2 – 4 ekor per keluarga.
Dengan jumlah pemilikan yang sangat terbatas tersebut dapat dibayangkan bahwa
penerapan teknologi akan sulit diadopsi oleh para peternak.
Untuk menanggulangi hal tersebut maka sekarang telah banyak diadopsi sistem
kandang kelompok untuk sapi potong yang terbukti dapat meningkatkan daya
reproduksi yang dihasilkan melalui perbaikan efisiensi pelayanan perkawinan dan
kesehatan ternak seperti yang terjadi di NTB (DAHLANUDIN et al., 2008). Pemda
NTB mengadopsi sistem ini dengan membuat program setiap ekor induk
menghasilkan satu ekor pedet setiap tahun. Struktur populasi sapi potong yang ada
dimasyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.2.Struktur Populasi Sapi Potong pada Peternakan Rakyat
Struktur Populasi Sapi Potong Populasi
Betina Dewasa 44.3 %
Jantan Dewasa 10.1 %
Betina Muda 14.86 %
Jantan Muda 11.61 %
Betina Sapihan 9.87 %
Jantan Sapihan 9.35 %
Total Populasi 10.726.347 ekor
Sumber: Sumber: TALIB (2007)

61
Jika dilihat dari struktur populasi sapi Jika dilihat dari struktur populasi sapi potong
tersebut dengan tingkat pemotongan di tahun 2008 yang sudah melebihi 2 juta ekor
maka tentunya hampir semua sapi jantan potong tersebut dengan tingkat
pemotongan di tahun 2008 yang sudah melebihi 2 juta ekor maka tentunya hampir
semua sapi jantan dewasa dan muda yang baik dipotong untuk konsumsi termasuk
pemotongan sapi betina sudah pasti dilaksanakan. Dampaknya adalah kekurangan
pejantan yang baik dan kehilangan sapi betina produktif yang sangat dibutuhkan
untuk meningkatkan populasi.
Berdasarkan penyebaran populasi, sapi potong menyebar di seluruh Indonesia
tetapi ada 8 provinsi dengan populasi tertinggi sebagai kawasan sumber bibit dan
bakalan sapi lokal karena memelihara sekitar 70 persen sapi potong di Indonesia
seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3.Penyebaran Sapi Potong pada 8 Provinsi
Provinsi Populasi
Jawa Timur 23.5 %
Jawa Tengah 12.0 %
Sulawesi Selatan 7.0 %
NAD 6.6 %
Sumatera barat 5.8 %
Bali 5.0 %
NTT 4.9 %
Sumatera Selatan 4.7 %
Total Populasi 10.726.347 ekor
Sumber: Sumber: DITJENNAK (2007)
Pengembangan sapi potong di Indoneia saat ini dilihat dari ketersediaan pakan
terutama dari perkebunan sawit maka Sumatera dan Kalimantan yang memiliki
kebun sawit hampir 7 juta ha sangat potensial, karena setiap ha sawit dapat
menampung 2 unit ternak (TALIB et al., 2007). Di Sumatera baru diwakili oleh 2
propinsi sedangkan Kalimantan malah belum tampil, maka prioritas kawasan
pengembangan baru sapi potong tentu perlu diberikan perhatian lebih besar pada
kedua wilayah tersebut.
b. Industri penggemukan sapi
Industri penggemukan sapi berkembang pesat di sekitar kawasan pasar utama
yaitu di Jabodetabek. Kawasan ini menampung sapi bakalan untuk penggemukan
baik dari sapi lokal maupun sapi impor. Alur tataniaga pemasaran sesudah periode
waktu tahun 1990 terjadi perkembangan pasar dimana kawasan Kalimantan dan
Sumatera Utara semakin tumbuh menjadi pasar potensial di Luar Jabodetabek.
Terbukanya peluang pasar yang baru tersebut semestinya ditindak lanjuti dengan
percepatan penyediaan sapi bakalan yang bersumber dari induk sapi sebagai mesin

62
penghasil pedet. Hanya saja karena jumlah populasi yang terbatas dan tingginya
permintaan, maka pada kawasan sumber bibit/bakalan terjadi hal sebaliknya yaitu
hampir semua ternak jantan diekspor ke kawasan lain dan untuk konsumsi lokal
dilakukan pemotongan sapi betina termasuk juga yang produktif. Diperkirakan
jumlah tersebut sekitar 200 ribuan ekor. Puslitbangnak dengan sistem observasi
cepat pada Tahun 2009 mendapatkan pada salah satu kawasan tersebut memotong
97 persen sapi betina dan 80 persennya adalah betina produktif (PUSLITBANGNAK,
2008).
Tentu saja kejadian tersebut membutuhkan langkah cepat penanggulangan yang
komplit tetapi tetap harus dilakukan. Memang berbagai daerah melaksanakan
pencegahan pemotongan spi beina produktif tetapi karena keterbatasan dalam
dana dan sistem birokrasi sehingga langkah-langkah tersebut masih belum
signifikan dalam mencegah pemotongan tersebu. Perlu dibuat langkah lain
misalnya melalui sistem koperasi pembibitan dengan bunga rendah untuk
penanggulangannya seperti yang dilakukan oleh sistem PUSKUD pembibitan sapi
potong di NTT yang mampu membangun sistem bagi hasil dengan peternak yaitu
80 persen keuntungan untuk peternak dan 20 persen untuk koperasi (BENYAMIN,
2008).
Kelemahan lainnya dalam sistem tataniaga sapi potong adalah karena
penyebarannya yang luas maka dibutuhkan infrastruktur transportasi ternak yang
tahan terhadap perubahan cuaca terutama gelombang laut. Infrastruktur tersebut
masih lemah sehingga harga jual selalu dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan musim.
Alat transportasi kapal sapi yang standard sudah harus mulai dipikirkan oleh
pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan efisiensi pemasaran sapi
nasional.
Jika diperhatikan sapi bakalan impor dari Australia walaupun harga ketika tiba di
Indonesia banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti musim, cuaca, jarak
yang lebih jauh, freight trasportasi dan currency, tetapi tetap diminati oleh pihak
industri penggemukan sebagai prioritas utama. Tentunya ini terjadi karena harga
beli oleh industri dapat lebih menguntungkan dari mengunakan sapi lokal. Oleh
karena itu usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem tataniaga sapi nasional
perlu dikaji untuk dibuat suatu program aksi yang dapat diterapkan secara masive.
Sapi bakalan impor dalam penggemukan di Indonesia dilakukan dengan sangat
intensif, padat modal dan walaupun haga pakan telah naik sekitar 30 persen dari
Tahun 2006 tetap saja diminati. Tahun 2007 impor sapi bakalan mencapai 520.000
ekor (atau setara dengan 104 ribu ton daging) dari kapasitas penggemukan 600
ribu ekor (ISPI, 2008).
Terdapat sedikit penurunan impor dari Tahun 2002 -2005 tetapi kemudian
meningkat kembali sampai ke tahun 2007. Hal ini disebabkan karena Tahun 2002
sampai Tahun 2005 suplai sapi bakalan lokal mencapai jumlah 350 – 400 ribu ekor

63
sehingga mampu menekan impor. Tetapi sesudah periode tersebut sapi lokal yang
dapat dikirim ke pusat penggemukan bekurang sehingga impor kembali meningkat
(ISPI, 2008). Kelihatannya penurunan jumlah impor masih dapat ditekan dengan
perbanyakan sapi bakalan lokal terutama yang berasal dari kawasan Indonesia
bagian Selatan (NTT, NTB, Bali, Jawa dan Lampung).
c. Importir daging dan jeroan
Importir daging dan jeroan melaksanakan impor daging yang bagian terbesarnya
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan makanan dan jeroan.
Bagian terbesar dari jeroan impor tersebut digunakan untuk industri daging bakso
yang pemasarannya diperkirakan mencapai seluruh Indonesia dan inilah yang
membuat masyarakat Indonesia adalah konsumen andalan daging sapi. Angka pasti
penyebarannya per provinsi belum ada data yang pasti tetapi diperkirakan impor
daging dan jeroan sapi ini mencapai kurang lebih 50 – 75 ribu ton per tahun (ISPI,
2008).
4.2.3. Kondisi Umum Pembentukan Harga
Harga daging dunia cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan
data United States Departement of Agriculture Economic Research Service (USDA-ERS)
selama periode tahun 2000 sampai dengan 2012, harga daging sapi internasional
mengalami kenaikan sebesar 51,5 persen dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar
4,3 persen. Jika diamati pola perkembangannya, harga daging sapi internasional
mengalami lonjakan yang relatif tinggi terjadi pada tahun 2003, kemudian tahun 2008
dan tahun 2011.
Gambar 4.13. Harga Daging Dunia Sapi Tahun ke Tahun
Sumber: United States Departement of Agriculture Economic Research Service (USDA-ERS)

64
Selama tahun 2003, harga daging sapi mengalami kenaikan sebesar 23,6 persen,
dengan harga pada awal tahun 2003 sebesar US$6,79/kg dan akhir tahun mencapai
US$8,49/kg. Kenaikan harga daging sapi internasional tahun 2003 seiring dengan
ditemukan pertama kalinya kasus penyakit sapi gila (Mad Cow) di Amerika Serikat.
Setelah mengalami kenaikan yang relatif tinggi pada tahun 2003, harga daging sapi
internasional kembali naik pada tahun 2008, dengan tingkat kenaikan selama tahun
tersebut sebesar 6,3 persen dan selama tahun 2011 harga daging sapi international
mengalami kenaikan sebesar 12,4 persen. Pada awal tahun 2012 harga daging sapi
internasional mencapai US$10,2/kg dan pada bulan September 2012 sedikit turun
menjadi US$9,89/kg.
Di dalam negri, harga daging sapi dari tahun ke tahun menunjukkan trend naik. Hal ini
terlihat dari harga daging selama sepuluh tahun terakhir yang selalu naik setiap
tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, rata-rata kenaikan harga
daging sapi per tahun mencapai 9 persen. Dengan kenaikan harga tertinggi terjadi pada
tahun 2008 yang mencapai 14,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp
50.036/kg menjadi Rp 57.259/kg. Harga daging sapi (periode tahun 2003-2012)
mengalami gejolak harga dengan koefisien variasi sebesar 27,3 persen.
Gambar 4.14. Rata-rata Harga Daging Sapi Nasional Sumber: Kementerian Perdagangan, 2012
Secara nasional, situasi harga daging sapi pada tahun 2012 (sampai dengan bulan
September 2012) berangsur-angsur naik dari awal Januari dan mulai mengalami
lonjakan pada Juli 2012 (menjelang puasa), yaitu mencapai 3,36 persen dari Rp
74.393/kg menjadi Rp 76.895/kg dan Agustus 2012 naik 3.78 persen dari Rp 76.895/kg
menjadi Rp 79.800/kg.Berdasarkan pemantauan di beberapa daerah sentra
produksi,terjadi fluktuasi harga daging sapi tingkat konsumen antar waktu dan antar
provinsi. Fluktuasi harga terbesar antar waktu terjadi pada tahun 2012. Sementara itu

65
juga terdapat fluktuasi harga antar wilayah atau provinsi di Indonesia. Harga daging
sapi tertinggi terjadi di Provinsi Aceh dan terendah terjadi di Nusa Tenggara Timur.
Tingginya harga daging sapi di Provinsi Aceh disebabkan oleh adanya tradisi meugang
yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Aceh untuk membeli
daging bagi keluarganya menyambut Ramadhan. Daging sapi disajikan sebagai lauk
utama, sehari sebelum Ramadhan tiba atau Hari Raya. Tak peduli kaya atau
miskin,setiap kepala keluarga harus berusaha membeli minimal satu atau dua kilo
daging untuk keluarganya.Bagi keluarga mampu, bahkan akan membeli sampai lima
kilo untuk dihabiskan selama bulan Ramadhan sebagai menu sahur.
Kenaikan harga daging sapi signifikan terjadi pada waktu/periode Hari Besar
Keagamaan nasional (HBKN). Setidaknya selama empat tahun terakhir, harga daging
sapi tertinggi terjadi disaat HBKN, yaitu menjelang puasa hingga Idul Adha. Hal ini
dikarenakan permintaan yang tinggi dari efek psikologis konsumen yang cenderung
membeli daging lebih banyak pada periode tersebut serta adanya ekspektasi dan
perilaku pedagang yang cenderung meningkatkan harga secara tidak wajar. Pada tahun
2009, harga daging sapi tertinggi terjadi pada saat menjelang lebaran hingga lebaran
dan tahun 2010, harga daging sapi tertinggi terjadi pada saat menjelang Idul Adha.
Tahun 2011, harga daging sapi tertinggi terjadi pada saat Bulan Puasa. Sementara itu,
harga daging sapi untuk tahun 2012 terus merangkak naik dari awal tahun hingga
lebaran dan tetap berada pada posisi tinggi setelah lebaran sehingga diperkirakan
menjelang Idul Adha harga daging sapi naik mencapai Rp 110.000/kg-Rp 120.000/kg.
Gambar 4.15. Kondisi Harga Daging Sapi di Berbagai Wilayah Indonesia
Sumber: Kementerian Perdagangan, 2012

66
4.2.4. Kondisi Umum Preferensi dan Pola Konsumsi
Rataan jumlah daging yang dikonsumsi oleh masyarakat di DKI Jakarta adalah sebanyak
9,56 kg per bulan atau setara dengan 2,02 kg/orang/bulan atau 24,2 kg/orang/tahun
(Deptan, 2008). Tingkat konsumsi daging ini adalah dua kali lipat lebih banyak daripada
yang direkomendasikan yaitu sebesar 10,3 kg/orang/ tahun (LIPI, 2004), angka
tersebut bahkan juga lebih tinggi dari rataan tingkat konsumsi daging warga Jakarta
yang dilaporkan hanya sebesar 19,3 kg/orang/tahun (DINAS PEKANLA, 2006).
Masyarakat mengonsumsi daging sebagai salah satu penghasil protein hewani karena
masyarakat mengetahui bahwa kandungan gizi daging sapi sangat baik untuk
kesehatan. Selain itu, rasanya yang enak, sifat daging yang mudah disajikan dalam
berbagai bentuk olahan, selama harganya masih dapat dijangkau oleh rumah tangga
konsumen serta ketersediaannya di pasaran tidak tergangu, masyarakat akan tetap
mengonsumsi daging sapi.
Beberapa dari berbagai bentuk olahan daging sapi adalah bakso dan sosis. Preferensi
konsumen terhadap produk olahan daging sapi menyebar pada jenis produk olahan
daging sapi tertentu yang ditawarkan dan terkelompok pada tingkat pendapatan.
Masyarakat memiliki preferensi yang tinggi terhadap bakso karena harganya lebih
murah serta mudah diakses sedangkan sosis merupakan produk olahan yang memiliki
harga yang cukup mahal serta terbatas ketersediannya, namun dengan meningkatnya
pendapatan masyarakat maka produk tersebut semakin disukai, sehingga apabila selalu
tersedia dengan harga yang murah sosis dapat diterima konsumen sepopuler bakso.
Konsumen produk olahan daging sapi mengkonsumsi produk tersebut karena memiliki
manfaat praktis dan lebih cepat dalam proses memasaknya.

67
BAB 5. HASIL PENELITIAN
5.1. Kapabilitas Strategis Produksi Daging Sapi
5.1.1. Isu Pergeseran Musim dan Fluktuasi Curah Hujan terhadap Kapabilitas Strategis
Produksi Daging Sapi
Menurut McSweeney (2010) dalam laporanUNDP CountryProfile, perubahan iklim,
secara umum, iklim di Indonesia dapat dikategorikan dalam iklim ekuator yang bersifat
lembab dan panas sepanjang tahun. Perubahan musim dipengaruhi oleh Inter-Tropical
Convergence Zone (ITCZ). Secara normal, musim hujan yang dimulai November hingga
Maret memiliki puncaknya pada saat Januari dan Februari. Curah hujan pada daerah
dataran rendah rata-rata 1800 hingga 3200 mm per tahunnya angka ini akan meningkat
untuk daerah pegunungan hingga rata-rata 6000 mm. Kelembaban rata-rata di Indonesia
berada diantara 70 hingga 90 persen.
Indonesia juga dipengaruhi oleh perubahan iklim dari tahun-ketahuun terkait dengan
baik El Nino Sothern Oscillation (ENSO) atau Indian Ocean Dipole (IOD). Enino akan
membuat kondisi iklim yang lebih panas dan kering, sedangkan La Nina akan membawa
kondisi iklim menjadi lebih basah dan lembab sehingga curah hujan akan lebih tinggi dan
ekstrim dari rata-ratanya dan menyebabkan banjir.
Gambar 5.1.a. Tiga Daerah Iklim Indonesia, Daerah A (kurva tebal) – Daerah Monsun, Daerah B
(kurva putus-putus) – Daerah Semi-Monsun dan Daerah C (kurva putus-putus pisah) – Daerah
Antimonsun Sumber: Aldrian, 2003
Menurut pembagian daerah iklim yang dilakukan oleh Aldrian dan Susanto (2003),
Indonesia dapat dibagi dalam tiga daerah iklim (Gambar 5.1.a ). Daerah A disebut juga
sebagai daerah monsun, daerah B kita kenal sebagai daerah semi-monsun dan daerah C

68
merupakan daerah anti monsun. Karakter yang hampir sama dari tiga daerah ini
ditemukan oleh Wyrtki (1956) dan Hamada et al. (2002), walaupun mereka tidak
menggambarkan daerahnya secara jelas.
Daerah A seperti yang terlihat pada Gambar 5.1.b merupakan wilayah dengan curah
hujan maksimum pada bulan Desember/Januari/Februari (DJF) dan minimum pada
bulan Juli/Agustus/September (JAS). Hal ini mengilutrasikan dua rezim monsun :
monsun basah timur laut dari November hingga Maret (NDJFM) dan monsun kering
tenggara dari Mei hingga September (MJJAS). Dengan suatu siklus monsunal yang kuat
dan lokasinya berada di arah selatan,maka deerah ini bisa kita sebut sebagai daerah
monsun arah selatan (southern monsoon region).
Gambar 5.1.b. Siklus Curah Hujan Tahunan Masing-Masing Daerah
Sumber: Aldrian, 2003
Siklus tahunan daerah B mempunyai dua puncak pada bulan
Oktober/November/Desember (OND) dan juga pada bulan Maret/April/Mei (MAM).
Puncak-puncak pada OND dan MAM ini masing-masing mewakili pergerakan ke arah
utara dan selatan dari dari ITCZ. Daerah ini kemudian bisa kita sebut sebagai daerah
semi monsun (northwest semi-monsoonal). Dari Gambar 5.1.b Aldrian juga menjelaskan
perbedaan yang cukup mencolok daerah C dimana daerah ini mempunyai satu puncak
pada bulan May/Juni/Juli dan Aldrian menyatakan daerah ini sebagai daerah
antimonsun maluku (Molucca anti-monsoonal region).Namun menurut World Bank,
rata-rata curah hujan dan suhu di Indonesia secaa berturut-turut lebih rendah pada
Bulan Mei hingga Oktober dan Juni hingga September untuk rata-rata suhu udara. Hal
tersebut tampak seperti pada Gambar 5.1.c.
Variabilitas musim yang tinggi akan berdampak pada ketersediaan pakan dan kesehatan
ternak sapi. Secara umum, ada empat unsur iklim mikro yang dapat mempengaruhi
produktivitas ternak secara langsung yaitu: suhu, kelembaban udara, radiasi dan
kecepatan angin, sedangkan dua unsur lainnya yaitu evaporasi dan curah
hujanmempengaruhi produktivitas ternak secara tidak langsung. Suhu dan kelembaban
udara merupakan dua faktor iklim yang mempengaruhi produksi susu sapi, karena dapat
menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh ternak, keseimbangan air,

69
keseimbangan energi dan keseimbangan tingkah laku ternak (Esmay, 1982). Dengan
terganggunya produksi susu ini maka sedikit banyak juga akan berdampak pada
keberlangsungan hidup anak sapi (pedet) sehingga juga akan memiliki dampak pada
rantai produksi sapi potong secara umum.
Gambar 5.1.c. Rata-rata Suhu (oC) dan Curah Hujan (mm/bulan) di Indonesia 1901-2009
Sumber: Aldrian, 2003
Kehidupan dan produksi pada ternak memerlukan suhu lingkungan yang optimum
(McDowell 1974). Zona termonetral suhu nyaman untuk sapi Eropa berkisar 13 – 18°C
(McDowell, 1972); 4 – 25°C (Yousef, 1985), 5 – 25°C (Jones & Stallings, 1999).Suhu
udara dan kelembaban harian di Indonesia umumnya tinggi, yaitu berkisar antara 24 –
34°C dan kelembaban 60 – 90 persen. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat
produktivitas sapi, khususnya sapi jenis Frisian- Holstein (FH).
Tabel 5.1. Indeks Suhu dan Kelembaban Relative untuk Sapi Menyusui
Sumber: Wierema, 2002

70
Pada suhu dan kelembaban tersebut, proses penguapan dari tubuh sapi akan terhambat
sehingga mengalami cekaman panas. Pengaruh yang timbul pada sapi akibat cekaman
panas adalah penurunan nafsu makan, peningkatan konsumsi minum, penurunan
metabolisme dan peningkatan katabolisme, peningkatan pelepasan panas melalui
penguapan, penurunan konsentrasi hormon dalam darah, peningkatan temperatur
tubuh, respirasi dan denyut jantung (McDowell, 1972) dan perubahan tingkah laku
(Ingram & Dauncey, 1985), pada sapi menyusui hal ini menyebabkan peningkatan
terhadap konsumsi air (Smith et al, 2001).
5.1.2. Produktifitas Sapi Potong Sebagai Variabel Supply Daging Sapi
Ketersediaan daging sapi nasional Indonesia saat ini memiliki sumber dari tiga hal
pokok yakni pertama dari sapi potong yang diternakkan di dalam negeri baik melalui
inseminasi buatan maupun alamiah. Sumber yang kedua berasal dari sapi potong yang
diimpor dan digemukkan terlebih dahulu di dalam negeri hingga siap dipotong. Sumber
berikutnya adalah sapi potong yang diimpor dan sudah siap potong. Sumber yang
terakhir adalah impor daging sapi yang merupakan daging jenis prime-cut untuk
mencukupi kebutuhan selain pasar tradisional.
Menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mencukupi kebutuhan penduduk
dengan melakukan kombinasi sumber pemenuhannya tersebut. Terkait dengan
penyediaan daging sapi nasional dari sumber peternak, maka ada beberapa faktor yang
mempengaruhi:
1. Pertumbuhan Populasi Sapi Potong
Pertumbuhan rata-rata sapi potong dari 2006 hingga 2012 adalah 5.54 persen.
Namun, menurut Survei Ternak (ST) 2013 jumlah populasi sapi potong pada tahun
hingga 2013 (Bulan) adalah 13 juta ekor yang berarti terjadi penurunan sekitar 20
persen dari proyeksi jumlah sapi tahun sebelumnya yakni kurang lebih 16 juta
ekor sapi potong. Sapi potong di Indonesia diternakkan pada umumnya oleh
peternak-peternak rumahan yang berskala kecil, rata-rata setiap peternak
memiliki 1-2 ekor sapi potong, yang terkonsentrasi pada provinsi-provinsi sentra
sapi potong sepeti Jawa Timur, Lampung, Nusa tenggara barat.
Mengacu data Sensus Pertanian tahun 2011, populasi sapi potong terbesar
terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera yaitu 69,06 persen dari populasi sapi potong
nasional. Populasi sapi potong di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua
mencapai16,77 persen,sedangkan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebanyak14,18
persen dari total populasi sapi potong.
Para pelaku dalam tata niaga sapi potong seperti peternak penggemukan, belantik,
Bandar sapi, Feedloter, dan lain-lain dimungkinkan untuk memiliki semua kategori

71
sapi potong bila dilihat dari kategori usia ternak. Kategori tersebut adalah Pedet
atau anak sapi (1-9 bulan), Sapi Usia Muda (9-21 bulan), Sapi Indukan (Jantan dan
Betina), dan Sapi siap potong—usia maksimum 5 tahun, termasuk sapi indukan
yang sudah tidak produktif lagi.Para pelaku pasar tersebut bebas melakukan
transaksi jual dan beli sepanjang memiliki informasi atas disparitas harga yang
menguntungkan. Hal ini menjadi salah satu cerminan dari ketidakteraturan
informasi (unsymetric information) dalam tata niaga sapi potong. Masing-masing
pelaku pasar juga bisa memiliki peran yang berbeda-beda dari waktu-ke waktu
dalam rangka menjadi pelaku “intermediary role”. Misalnya, feedloter juga bisa
menjadi Bandar sapi, contoh lainnya misalnya petani penggemuk sekaligus juga
memegang peran sebagai belantik (penghubung).
Beberapa fakta lain yang dapat ditarik dari pengumpulan data primer dari survei
dan data sekunder terkait populasi sapi potong pada peternak dengan adalah rata-
rata peternak membeli sapi dengan umur antara 6-12 bulan. Dari responden
peternak yang menjawab sebesar 101 peternak 40 responden atau 39,6 persen nya
membeli sapi dengan umur 6-12 bulan. Sedangkan untuk peternak yang membeli
sapi yang berumur 12-24 bulan adalah 21,78 persen.
2. Proyeksi Populasi Sapi Potong dalam Upaya Menjawab Proyeksi Produksi dan
Konsumsi Daging Sapi
Kondisi awal yang dipakai dalam simulasi adalah kondisi pada tahun 2006, dimana
masing-masig jumlah populasi sapi potong dikategorikan menurut usianya, seperti
yang tampak pada Tabel 5.2.a. berikut:
Tabel 5.2a. Populasi sapi potong berdasarkan usia pada tahun 2006 (Ekor) dan Beberapa
asumsi pendukung lainnya
Kondisi Awal Simulasi (awal 2006)
1 Populasi Anak Sapi (< = 9 bulan) 2,117,000
2 Populasi Sapi Muda [ (9<x<=21) bulan] 2,482,000
3 Populasi Sapi Induk Betina 5,938,000
4 Populasi Induk Jantan 593,000
5 Populasi Sapi Potong siap potong 2,200,000
6 Tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) 70%
7 Tingkat keberhasilan Inseminasi Alamiah (IA) 15%
8 Tingkat Kematian Pedet 10% per tahun
9 Impor Sapi Siap Potong hingga tahun 2013 100,000
10 Jumlah RPH 640 unit
11 Kapasitas RPH 130 Ekor/Bulan Sumber: BPS dan kompilasi sumber lain

72
Sedangkan bilamana dilihat dari proses pembibitan, dari 177 responden, yang
memberikan jawaban adalah sebanyak 58,2% atau 102 orang. Dari 102 responden
itu, yang melakukan pembibitan hanya sebesar 8,74% sedangkan sisanya sebanyak
91,26% tidak melakukan pembibitan sehingga bisa dikatakan hanya melakukan
penggemukan saja. Secara lebih rinci, proses pembibitan yang dilakuakan petani
dan waktu yang dibutuhkan terlihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 5.2.b.ProsesPembibitan
No Pembibitan Lama (Bulan)
1 Inseminasi Buatan 6
2 Inseminasi Alamiah 6
3 Masa bunting 9
4 Masa menuju pedet 12
5 Masa menuju bakalan indukan betina (jantan) 20 (24)
6 Masa menuju bakalan sapi siap potong 12
Sumber: Olahan Data Primer
Tampak pada tabel tersebut, menurut peternak yang melakukan pembibitan,
proses inseminasi buatan maupun alamiah memerlukan waktu 6 bulan, dengan
masa bunting selama 9 bulan. Seekor indukan betina akan produktif dari umur
18/24 bulan hingga 6/7 tahun, sehingga supaya indukan bisa menghasilkan pedet
setiap tahun harus dilakukan uapaya pengaturan reproduksi yang tepat. Adapun
biaya yang dibutuhkan dalam proses pembibitan dan penggemukan adalah sebagai
berikut:
Tabel 5.2.c. Biaya proses pembibitan dan penggemukan
No. Item Biaya (Rp) Satuan
1 Inseminasi 50.000 Per satu kali suntik
2 Obat-obatan (Vitamin) 41.000 per bulan/ekor
3 Konsentrat 9.000 Per hari/ekor
4 Rumput 7.000 per hari/ekor
Sumber: Olahan Data Primer
Tampak pada tabel di atas, inseminasi per ekor sapi indukan merupakan item yang
paling tinggi nilainya untuk sekali inseminasi buatan yang dilakukan pada satu
indukan membutuhkan biaya sedikitnya Rp.50.000 untuk satu kali suntik, padahal
seringnya sapi tidak bisa hamil hanya dengan satu kali suntik saja, perkiraan biaya
IB (Inseminasi Buatan) menurut peternak dapat mencapai + Rp.300.000,- s.d.
Rp.600.000,-. Sedangkan untuk proses penggemukan ternak, dibutuhkan biaya

73
obat-obatan (vitamin) sedikitnya Rp.40.000,- per bulan. Untuk pakan, peternak
bisa menggunakan konsentrat (campuran antara hijauan dan bahan lain) atau
murni hijauan, umumnya rumput. Biaya pakan rata-rata berkisar Rp.7.000,- s.d.
Rp.9.000,-. Per hari per ekor, sehingga sedikitnya dalam satu bulan dibutuhkan
biaya Rp.200.000,- s.d. Rp.300.000,-.
Kemudian bila dilihat dari jenis sapi yang beredar di pasaran sesuai dengan
responden dalam penelitian ini, ternyata terdapat hanya beberapa sapi saja yang
diminati yakni sapi brahman, sapi ongole, dan sapi peranakan ongole (po), seperti
yang tampak pada Tabel 5.2.d. berikut.
Dari 177 responden yang menjawab, responden memiliki lebih dari satu sapi
ternak dengan total sapi yang dipelihara ke 177 responden itu adalah sebanyak
374 ekor sapi. Dari sejumlah sapi itu, sapi yang terbanyak dipelihara adalah sapi
ongole (35,83%), namum rata-rata ketiga sapi itu dipelihara oleh 30% lebih
responden.
Tabel 5.2.d. Sapi yang banyak beredar pada responden
Sumber: Olahan Data Primer
Pemasok ketiga jenis sapi itu adalah dari provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dam
Lampung. Untuk Jawa Timur memasok paling besar untuk setiap sapi, yang kedua
adalah Lampung, kemudian NTB dan Bali.Dari segi umur, ketiga sapi ini banyak
diperjual belikan pada saat umur berkisar antara 6 hingga 12 bulan (pedet), atau
pada umur sapi 25 hingga 36 bulan, untuk yang kedua paling banyak beredar di
pasaran menurut responden.
Untuk sapi brahman, bobot yang paling sering diperjualbelikan diantara responden
adalah sapi dengan bobot 200 hingga 350 kg, sedangkan untuk sapi Ongole dan
peranakan ongole yang paling banyak beredar pada responden adalah sapi dengan
berat badan 100 hingga 200 kg.
Kemudian, masing-masing kategori usia sapi potong disimulasikan dengan
menggunakan model yang tampak pada Gambar 5.2.a yang dilakukan dari tahun
2006 hingga tahun 2013 (awal 2014), seperti yang tampak pada gambar berikut
ini:

74
2,006 2,008 2,010 2,012 2,014 2,016 2,018 2,020
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
ekor
Populasi Anak Sapi Populasi Sapi Muda Indukan Betina
Indukan Jantan Ternak Sapi Siap Potong
Non-commercial use only!
Gambar 5.2.a. Simulasi Populasi Sapi Potong
Sumber: Olahan Data Primer
Tampak pada grafik di atas, populasi sapi siap potong terus mengalami kenaikan
hingga tahun 2011, namun setelahnya mengalami penurunan. Dibandingkan
dengan tahun 2012, populasi sapi potong menurun sebesar 5,25 persen.
Sedangkan dari populasi sapi indukan betina dari tahun 2006 hingga tahun 2013
akhir, terus mengalami penurunan yakni sebesar 31,1 persen. Tentu saja
penurunan ini secara umum memiliki dampak yang cukup besar terhadap rantai
pasokan sapi potong dan daging sapi potong pada tingkat nasional. Dengan kata
lain, selama periode 2006 hingga tahun 2013 akhir, peternak terus melakukan
pemotongan terhadap sapi indukan.
Gambar 5.2.b.Populasi Sapi Potong berdasarkan Umur Ternak
Sumber: Olahan Data Primer
Sedangkan hingga tahun 2019, simulasi model menunjukkan penurunan jumlah
populasi sapi untuk setiap kategori usia, seperti tampak pada Gambar
5.2.b.Sedangkan dampak dari penurunan secara kontinu populasi sapi dari tahun
ke tahun dengan asumsi kapasitas rumah pemotongan hewan (RPH)/ tempat
pemotongan hewan (TPH) tidak banyak berubah maka jumlah sapi yang akan
2,006 2,008 2,010 2,012 2,014
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
ekor
Populasi Anak Sapi Populasi Sapi Muda Indukan Betina
Indukan Jantan Ternak Sapi Siap Potong
Non-commercial use only!

75
2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012
1,000,000
1,500,000
2,000,000
ekor/year
Penyembelihan SP Oleh RPH *Penyembelihan per tahun actual
Non-commercial use only!
disembelih oleh RPH/TPH juga akan mengalami penurunan. Penurunan itu dapat
dilihat seperti pada grafik berikut ini:
Gambar 5.2.c.Penyembelihan Sapi Potong
Sumber: Olahan Data Primer
Pertumbuhan kapasitas RPH (sangat kecil), data tahun 2006 adalah 660 unit
dengan kapasitas rata-rata 130 ekor per bulan, sehingga waktu tunggu
penyembelihan seolah-olah membutuhkan waktu yang sangat lama, karena
terbatasnya fasilitas yang ada (bootleneck). Hasil simulasi dari model yang
dibangun, bilamana diperbandingkan dengan data aktual terkait dengan jumlah
sapi potong yang di sembelih baik yang disembelih di RPH maupun TPH dapat
dilihat pada Gambar 5.2.d berikut ini:
Gambar 5.2.d.Perbandingan Jumlah Sapi yang Dipotong Aktual dan Simulasi Sumber: Olahan Data Primer
Gambar di atas sekaligus menunjukkan secara intuitif bahwa model yang
dibangun dalam pemodelan ini bisa dikatakan baik, dimana pergerakan grafik
2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019
1,000,000
1,500,000
2,000,000
ekor/year
Penyembelihan SP Oleh RPH *Penyembelihan per tahun actual
Non-commercial use only!

76
jumlah sapi yang disembelih dapat diikuti oleh pergerakan grafik sapi yang
disembelih yang merupakan hasil dari simulasi model.
Kemudian, bilamana produktivitas bahan pokok ini (daging sapi) diperbandingkan
dengan kebutuhan untuk mengkonsumsinya, dari hasil simulasi dari mulai dari
tahun 2014 hingga 2020 tampak adanya defisit yang sangat kentara dan semakin
melebar, seperti tampak pada gambar berikut:
Gambar 5.2.e. Perbedaan antara Proyeksi Produksi dan Konsumsi Daging Sapi
Sumber: Olahan Data Primer
Produksi daging sapi tampak terus mengalami penurunan walaupun pada simulasi
telah dimasukkan realisasi kebijakan terbaru dari pemerintah seperti impor sapi
bakalan dimana hingga 27 Desember 2013 realisasinya mencapai 312.687 ekor,
naik dari tahun lalu sebanyak 297.462 ekor. Sedangkan impor sapi potong tahun
ini mencapai 94.949 ekor, untuk tahun lalu tidak ada impor sapi potong. Untuk
impor daging sapi terealisir selama tahun ini hingga 22 Desember 2013 mencapai
55.840,6 ton atau meningkat dibandingkan 2012 yang sebesar 41.027,2 ton.
Tabel 5.3. Proyeksi Angka Permintaan Produksi Daging Sapi Nasional hingga tahun 2020
Sumber; Olahan Data Sekunder (BPS, 2012)
Padahal dari sisi pertumbuhan permintaan yang diproyeksikan dari terus
meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dengan laju pertumbuhan 1,23 persen
per tahun dan jumlah penduduk awal simulasi pada tahun 2006 sebesar
2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
kg/year
Konsumsi DS Nasional Produksi DS Nasional
Non-commercial use only!
Tahun Konsumsi DS Nasional (kg/year)Proyeksi Penduduk (ppl)Konsumsi DS per Kapita (kg/(year*ppl))Produksi DS Nasional (kg/year)
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
366,218,606.88
392,168,240.79
422,477,051.41
445,166,469.04
495,079,804.86
541,767,952.96
583,272,004.48
649,258,549.70
687,088,964.48
708,056,222.24
727,278,641.49
734,000,000.00
230,384,999.08
233,231,831.99
236,113,842.79
239,031,466.16
241,985,142.17
244,975,316.30
248,002,439.58
251,066,968.56
254,169,365.46
257,310,098.22
260,489,640.55
263,708,472.00
1.59
1.68
1.79
1.86
2.05
2.21
2.35
2.59
2.70
2.75
2.79
2.78
652,971,616.69
660,319,350.07
588,082,125.79
486,251,142.23
455,754,463.16
421,012,348.04
386,637,879.40
354,679,138.90
329,052,280.99
304,533,316.36
274,684,736.44
245,314,886.40
5
6
Non-commercial use only!

77
222,051,300 Jiwa maka permintaan daging sapi hingga tahun 2020 dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tampak pada tabel di atas perbedaan yang sangat mencolok antara proyeksi
permintaan dan konsumsi daging sapi nasional hingga tahun 2020. Puncaknya
pada tahun 2020, tanpa ada upaya terpadu maka defisit daging sapi nasional
mencapai hampir 500,000 ton.
Namun demikian dalam simulasi model juga telah dilakukan simulasi upaya yang
dapat dilakukan untuk menghindari terus menurunnya populasi sapi tersebut,
salah satunya dengan melakukan strategi breeding yang masif terhadap sapi lokal.
Breeding ini harus disertai dengan beberapa strategi seperti; pertama, upaya
peningkatan sapi yang diinseminasi buatan dari tahun 2014 hingga tahun 2015
masing masih diusahan untuk naik 10 persen sehingga menjadi 70 persen dari
yang sebelumnya hanya 50 persen. Kedua, meningkatkan keberhasilan inseminasi
buatan dengan menggunakan tenaga riset dan ahli dalam bidang inseminasi
buatan ini hingga meningkat setiap tahunnya 10 persen pada tahun 2014 dan
2015 sehingga menjadi 90 persen dari yang awalnya hanya 70 persen.
Ketiga, mencegah kematian pedet yang selama ini adalah 20 persen menjadi
setengahnya dan keempat, dilakukan pembatasan usia penyembelihan sapi muda
hingga 3 tahun, sehingga rata-rata sapi potong yang akan disembelih menjadi
berusia 4 tahun. Hal ini perlu, agar sapi muda tidak segera disembelih melainkan
dijadikan indukan dahulu.
Apabila keempat strategi itu dijalankan maka proyeksi populasi yang semula
tampak pada Gambar 5.2.e akan menjadi seperti tampak pada Gambar 5.2.f
berikut:
Gambar 5.2.f. Populasi yang meningkat dengan penerapan strategi yang tepat
Sumber: Olahan Data Primer
Tampak populasi sapi pada seluruh kategori mengalami kenaikan yang signifikan.
Khususnya tampak bahwa populasi sapi potong indukan betina akan
2,006 2,008 2,010 2,012 2,014 2,016 2,018 2,020
3,000,000
6,000,000
ekor
Populasi Anak Sapi Populasi Sapi Muda Indukan Betina
Indukan Jantan Ternak Sapi Siap Potong
Non-commercial use only!

78
dimungkinkan bertambah.Selain itu, hasil dari penerapan strategi tersebut di atas
juga mampu memperkecil defisit prosuksi daging sapi nasional dengan kebutuhan
konsumsinya seperti yang tampak pada Gambar 5.2.g. berikut:
Gambar 5.2.g. Produksi daging sapi yang mampu mengejar permintaannya Sumber: Olahan Data Primer
Tampak pada gambar di atas produksi daging sapi mulai meningkat pada
pertengahan 2014 dan mulai terus mengurangi defisit daging sapi nasional
kemudian pada akhirnya akan mampu memenuhi kebutuhan daging sapi nasional
padatahun 2018.
5.1.3. Pondasi Dasar Sistem Produk Daging Sapi
Pondasi dasar dari sistem produksi daging sapi sangat terkait dengan subsitem
produksi sapi potong, yang mana sub system produksi untuk sapi potong dalam
penelitian ini adalah seperti yang tampak pada Gambar 5.3.a. Pada gambar tersebut
tampak alur sub system produksi dari sapi potong melalui sudut pandang usia hewan
ternak. Pada alur proses produksi sapi potong dapat diamati melalui dua perspektif;
yang pertama adalah perspektif berat ternak dan yang kedua adalah umur usia ternak
(sapi). Dalam alur proses produksi di atas kami menggunakan perspektif usia ternak.
Dalam perspektif itu, maka ternak sapi potong akan dikategorikan menjadi; Sapi anakan
(pedet); Sapi muda (belum produktif); Sapi indukan jantan dan betina (merupakan sapi
muda yang telah dewasa/ produktif/ dapat dikawinkan secara alamiah ataupun buatan,
dan; Sapi yang siap potong.
2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
kg/year
Konsumsi DS Nasional Produksi DS Nasional
Non-commercial use only!

79
Gambar 5.3.a. Simulasi Struktur Proses Produksi Sapi Potong Nasional
Sumber: Olahan Data Primer
Menaikkan % Keberhasilan IB
0 5 10 15
%
Non-commercial use only!
Keberhasilan IB
0 20 40 60 80 100
%
Non-commercial use only!
Kebijakan pada Prosentase IB
0 5 10 15
%
Non-commercial use only!
Prosentase Inseminasi Buatan
0 20 40 60 80 100
%
Non-commercial use only!
Populasi Sapi SiapPotong
Pejantan SiapPotong
Penyembelihan SPOleh RPH
Populasi Sapi Muda Populasi Anak Sapi
Pendewasaan Angka Kelahiran
WaktuPenggemukan
Menjadi Sapi Muda
Populasi Induk Betina
PertambahanIndukan Betina
Induk Siap Potong
Umur Sapi IndukSiap Potong
Maturity Time Betina
Waktu Bunting
Umur Sapi JantanSiap potong
Populasi Induk Jantan
PertambahanIndukan Jantan
Maturity TimePejantan
Kebarhasilan IAKeberhasilan IB
ProsentaseInseminasi Buatan
Prosentase SPJantan
Rate_1
WaktuPenggemukan Sapi
Siap Potong
Policy on Impor SapiBakalan
Kematian Anak Sapi
Prosentasekematina naka sapi
per tahun
Kuota impor Sapi
Bottleneckkapasitas
Impor sapi siappotong
Waktu yangdibutuhkan untuk
impor
Policy_Impor or NoImpor
Tambahan Imporsapi siap potong
Menaikkan %Keberhasilan IB
Botleneck kapasitasRPH
Kebijakan padaProsentase IB

80
1. Pedet (Sapi yang Berumur< 9 Bulan)
Jumlah pedet dari waktu-kewaktu tentu saja akan berubah-ubah, perubahan ini
diakibatkan oleh adanya pertambahan pedet dan berkurangnya pedet karena
kematian--10 persen per tahun. Selain itu, jumlah populasi pedet tentu akan
berkurang karena bertambahnya umur pedet sehingga tidak dapat dikatakan
pedet lagi sehinggasapi tersebut masuk dalam kategori sapi muda.
Angka pertambahan pedet itu sendiri akan tergaantung pada proses inseminasi
baik buatan maupun alamiah. Dalam penelitian ini kami menggunakan asumsi
dasar seperti yang sudah tertera dalam Tabel 5.2 bahwa kesuksesan inseminasi
alamiah adalah 15 persen dan buatan adalah 70 persen. Sedangkan
untukkuantitas sapi betina yang diinseminasi buatan adalah 50 persen dari
populasi betina sedangkan yang kawin alamiah adalah sebanyak indukan
jantannya sebesar pada tahun 2006 yakni sejumlah 539 ribu ekor atau sekitar 10
persen dari total indukan betina. Selain itu, pertambahan pedet secara alamiah
juga tergantung pada lama masa bunting induk betina yakni 9 bulan.
Setelah dilakukan simulasi dengan asumsi tersebut, hasilnya tampak pada gambar
berikut:
Gambar 5.3.b. Hasil Simulasi Populasi Pedet dan Sapi Muda (belum produktif)
Sumber: Olahan Data Primer
Tampak pada gambar di atas, populasi anak sapi mengalami penurunan dari
waktu ke waktu. Penurunan ini tentu dalam jangka panjang akan mempengaruhi
suplai sapi potong. Sehingga bila dibiarkan kondisi ini berjalan terus maka
kebutuhan sapi potong impor baik bakalan maupun sapi siap potong akan terus
dibutuhkan guna mencukupi permintaan daging sapi nasional.
2,006 2,008 2,010 2,012 2,014 2,016 2,018 2,020
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
ekor
Populasi Anak Sapi Populasi Sapi Muda
Non-commercial use only!

81
2. Sapi Muda
Seekor pedet akan menjadi sapi muda dan produktif setelah mencapai hampir dua
tahun, sehingga waktu yang dibutuhkan dalam penggemukan pedet hingga
produktif adalah satu tahun dari usia pedet. Selain itu, populasi sapi muda juga
akan bertambah oleh karena adanya impor sapi bakalan yang memiliki berat
badan maksimal 350 kg dengan usia maksimal 30 bulan. Secara rata-rata para
importir sapi mengimpor sapi bakalan dengan usia sapi lebih dari satu tahun,
dengan pertimbangan ketahanan sapi bakalan ketika pengapalan yang
membutuhkan waktu sekitar satu minggu.
Masih pada Gambar 5.3.b, tampak juga dalam gambar tersebut penurunan yang
terus-menerus populasi sapi potong yang belum produktif. Kenaikan populasi
pada usia ini pada gambar tersebut lebih diakibatkan oleh adanya impor sapi
bakalan, bukan bersumber dari proses inseminasi alamiah maupun buatan dari
sapi lokal.
3. Sapi Indukan Jantan dan Betina
Setelah sapi lokal memasuki usia dewasa atau produktif, para peternak bisa
menggunakan sapi produktif tersebut baik jantan maupun betina sebagai indukan.
Sedangkan sapi impor bakalan tidak dapat digunakan sebagai indukan, maka
dalam usia tertentu setelah digemukkan kurang lebih selama satu tahun akan
menjadi sapi siap potong.
Dalam hal ini sapi muda yang jantan akan dijadikan indukan sebesar 10 persen
dari populasi sapi usia muda untuk kemudian dibiarkan secara alamiah berkawin.
Sapi indukan jantan akan mejadi matang setelah dua tahun, sedangkan untuk
indukan betina membutuhkan waktu yang lebih pendek yakni 1,67 tahun atau
sekitar 20 bulan.
Masa produktif sapi betina adalah hingga berumur kira-kira 6 tahun yang
dimungkinkan bunting dan melahirkan paling bayak 4 kali. Sedangkan sapi jantan
akan produktif hingga usia 5-6 tahun. Setelah usia produktif itu sapi indukan
jantan dan betina akan disembelih, dalam hal ini masuk menjadi kategori sapi siap
potong.
Dengan beberapa kondisi tersebut, simulasi terhadap populasi sapi indukan baik
jantan maupun betina hingga tahun 2020 dapat dilihat dalam gambar 5.3.c.
Dimana tampak pada gambar tersebut populasi kedua macam indukan terus
menurun juga. Yang patut menjadi perhatian adalah penurunan sapi indukan
betina yang sangat tajam dari 3 juta ekor di tahun 2013 hanya menjadi 1,5 juta
ekor saja di tahun 2020, menurun hampir 50 persen.

82
4. Sapi Siap Potong
Jumlah populasi sapi siap potong dipengaruhi oleh pertambahan dan
perkurangannya. Pertambahannya akan terkait dengan; pertama dari proses
penggemukan dari sapi bakalan impor dan sapi lokal yang memng disembelih
pada usia produktif. Kedua, pertambahan populasi sapi siap potong baru-baru ini
juga diakibatkan oleh kebijakan dari pemerintah yang membuka kran impor sapi
siap potong.
Dengan berbagai usaha untuk melakukan usaha tersebut, tampaknya jumlah sapi
siap potong tetap akan mengalami penurunan hingga tahun 2020. Penurunan
tersebut tampak dari hasil simulasi yang tergambar pada gambar di bawah ini:
Gambar 5.3.c. Populasi Sapi Indukan dan Sapi Siap Potong
Sumber: Olahan Data Primer
Dari sisi perkurangannya, sapi siap potong hanya akan berkurang karena
disembelih. Penyembelihan selama ini dilakukan oleh RPH yang memiliki jumlah
dan kapasitas yang sangat terbatas, sehingga dapat diaktakan terjadi “bottleneck”
dalam tata niaga sapi potong dan proses produksi daging sapi.
Kedua faktor yang mempengaruhi jumlah populasi siap potong tersebut yakni
pertambahan dan pengurangan melalui penyembelihan ternyata faktor
pengurangnyalah yang lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan terus
turunnya populasi sapi siap potong di Indonesia. Hal ini bertolak belakang
dengantingkat kebutuhan daging sapi nasional yang menuntut ketersediaan sapi
potong yang cukup dalam memenuhi kebutuhan daging sapi nasional.
2,006 2,008 2,010 2,012 2,014 2,016 2,018 2,020
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
ekor
Indukan Betina Indukan Jantan Ternak Sapi Siap Potong
Non-commercial use only!

83
5.2. Perkiraan Permintaan Daging Sapi Nasional Rumah Tangga dan Preferensi
Konsumsi Terhadap Kualitas Pangan Daging Sapi
Penelitian ini berupaya memperkirakan permintaan daging sapi nasional sebagai
konsumsi langsung (rumah tangga) dan konsumsi tidak langsung. Untuk mengetahui
rata-rata permintaan daging sapi rumah tangga, survei dilakukan terhadap 800
responden yang tersebar di 27 kota besar di 13 provinsi. Sedangkan untuk permintaan
industri, mengacu kepada laporan survei pemetaan potensi demand daging sapi yang
dilakukan oleh Laboratorium Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia (LSM FEUI), bersama dengan Kementerian Perdagangan RI Tahun 2013.
5.2.1. Perkiraan Demand Konsumsi Daging Sapi Rumah Tangga
Kategori responden rumah tangga dipilih dengan menggunakan teknik stratified
random sampling berdasarkan kriteria pemilihan rumah tangga yang memiliki kondisi
rumah layak huni, memiliki fasilitas MCK yang layak, berpenerangan listrik dengan
sumber daya minimal 900 watt, tidak masuk kedalam kategori keluarga miskin, dengan
rata-rata pengeluaran kotor rumah tangga sebulan minimal Rp.2.000.000,-.
Berdasarkan kategori rumah tangga tersebut, profil demografi singkat dipetakan
sebagai berikut. Mayoritas responden rumah tangga adalah mereka yang memiliki
jumlah anggota keluarga 4 – 6 orang (53 persen), dengan rata-rata pengeluaran per
bulan berkisar Rp.2.000.001 – Rp. 3.000.000,- (78 persen).Maka pengeluaran per kapita
per bulan berkisar + Rp.1.000.000,-.
Setiap bulannya mayoritas rumah tangga mengkonsumsi sekitar 3 Kg daging sapi. Jika
dalam satu rumah tangga rata-rata memiliki 5 anggota keluarga, maka dalam satu bulan
konsumsi daging sapi per kapita adalah 0,6 Kg atau setara 7,2 Kg per kapita per tahun.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS, Maret 2013), persentase
penduduk berdasarkan golongan pengeluaran per kapita per bulan adalah sebagai
berikut;
Tabel 5.4. Presentase Penduduk Menurut Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Sumber: SUSENAS, Maret 2013.
Untuk membuat proyeksi permintaan daging sapi nasional berdasarkan kategori
penduduk golongan menengah, menengah atas, dan atas. Maka diambil kelompok
penduduk dengan pengeluaran per kapita Rp.750.000,- s.d. lebih dari Rp.1.500.000,-.

84
Dengan tingkat pertumbuhan konsumsi daging sapi rata-rata 7% dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,23% maka kondisi proyeksi
permintaan daging sapi disimulasikan sebagai berikut.Untuk melengkapi data permintaan konsumsi rumah tangga golongan menengah
bawah, simulasi dilakukan dengan menggunakan tingkat konsumsi nasional daging sapi menurut statistic peternak (2013), yaitu 2,05
Kg per kapita per tahun seperti digambarkan pada tabel 5.5.b.
Tabel 5.5.a. Proyeksi Konsumsi Daging Sapi Berdasarkan Kebutuhan Rumah Tangga Golongan Menengah Atas
Tabel 5.5.b. Proyeksi Konsumsi Daging Sapi Berdasarkan Kebutuhan Rumah Tangga Golongan Menengah Bawah
* Survey dilakukan pada akhir tahun 2013.
Sumber: Olahan Data Primer

85
Secara keseluruhan maka total permintaan daging sapi rumah tangga Indonesia
mencapai angka + 679.888 ton. Meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa konsumsi
daging sapi tersebut bisa jadi adalah daging sapi dalam bentuk daging segar, maupun
produk olahan daging yang dikonsumsi melalui sentra produksi seperti HoReKa, serta
Industri RT dan Industri Besar. Demikian juga berdasarkan asal produk lokal maupun
impornya, karena jika di kategorikan berdasarkan kategori potongan daging yang
dikonsumsi maka proporsi konsumsi berdasarkan urutan terbesar sampai terkecil
adalah; Daging sapi olahan (kornet/sosis/bakso/lainnya) sebesar 31,49%; potongan
primer (26,30%); jeroan (14%); potongan sekunder (11,18%); daging variasi (9,53%);
dan kulit (7,5%).
5.2.2. Preferensi Konsumsi terhadap Kualitas Pangan Daging Sapi dan Prediksi
Kebutuhan Kualitas Pangan Rumah Tangga Ekonomi Menengah Atas dalam 5
Tahun Mendatang
Terdapat 2 (dua) hal yang perlu ditinjau sebagai landasan untuk melakukan intervensi
terhadap pola konsumsi daging sapi nasional pada tingkatan konsumen rumah tangga
maupun konsumen industri. Pertama, pola konsumsi daging sapi di masa mendatang
perlu mempertimbangkan proporsinya dalam ‘piring’ konsumen (in plate nutrition
composition). Saat ini daging sapi telah cukup masih mendominasi proposi bahan
makanan dalam menu masakan masyarakat Indonesia. Proporsi ini perlu sedikit demi
sedikit dikurangi, digantikan dengan bahan makanan hewani (ikan, kerbau, kambing
dan jenis-jenis unggas) yang melimpah di daerah setempat.
Kedua, perlu diketahui elastistas preferensi konsumen untuk melakukan substitusi
daging sapi dengan sumber protein lainnya. Pada Gambar 5.4.a. ditunjukkan preferensi
substitusi oleh konsumen saat harga daging sapi pada kondisi normal (tidak mengalami
kenaikan ataupun penurunan yang drastis). Pada kondisi normal dimana harga daging
sapi normal (terjangkau), komoditi yang paling diminati sebagai substitusi daging sapi
berturut-turut adalah daging ayam (49,21%), daging kambing (11,77%), ikan (11,62%),
tempe (10,99%), daging kerbau (7,23%), telur (6,46%), daging bebek (1,16%), tahu
(1,16%), dan jamur (0,39%). Seperti diketahui sumber alternatif protein tersebut cukup
banyak di masing-masing kuliner lokal, sehingga tidak terlalu sulit untuk dilakukannya
intervensi demi mendorong konsumsi sumber-sumber protein alternatif tersebut
sebagai pemenuhan kebutuhan kualitas pangan setara daging sapi di masa-masa
mendatang.
Sementara jika dianalisis lebih lanjut, pada Tabel 5.5.a dapat kita lihat preferensi
substitusi daging sapi ini berdasarkan besaran pendapatan konsumen rumah
tangga.Konsumen berpendapatan menengah ke bawah (dibawah Rp 7 juta per-bulan)
cenderung menempatkan daging ayam sebagai substitusi utama daging sapi. Sementara
untuk konsumen yang berpendapatan lebih tinggi (diatas Rp 7 juta per-bulan) lebih
memilih non-ayam sebagai substitusi utama, yaitu tempe dan telur. Kemudian baru

86
diikuti oleh daging ayam sebagai substitusi peringkat kedua.Daging ikan mendapatkan
persentase yang cukup besar, hampir menyamai daging ayam, pada kelompok
berpenghasilan tinggi ini.
Hal yang juga menarik adalah cukup tingginya preferensi terhadap Jamur sebagai
substitusi daging sapi. Data ini cukup mewakili dugaan bahwa taste maupun perilaku
konsumsi konsumen kelompok ini cenderung berbeda, dimana alternatif seperti daging
bebek, tahu, dan daging kerbau, tidak terlalu populer. Hal ini kemungkinan disebabkan
lebih rendahnya toleransi kelompok konsumen ini terhadap faktor-faktor yang terkait
dengan pertimbangan substitusi, seperti faktor rasa, kesehatan, dan ketersediaan.
Gambar 5.4.a.Preferensi Konsumen Terhadap Substitusi Daging Sapi (saat harga normal)
Sumber: Olahan Data Primer
Satu-satunya sumber protein non-hewani yang cukup populer sebagai substitusi sapi
berdasarkan hasil penelitian adalah tempe. Bahkan untuk kategori konsumen
berpendapatan Rp6 juta - 7 juta, tempe menjadi opsi yang paling populer sebagai
pengganti daging sapi. Dengan demikian, untuk tujuan diversifikasi sumber protein,
maka tempe perlu mendapat perhatian yang cukup besar dalam strategi ketahanan
pangan nasional.
Tabel 5.6.a Preferensi Subtitusi Daging Sapi Berdasarkan Kategori Penghasilan RT Per Bulan
(Kondisi Harga DS Normal)
Preferensi Substitusi Daging Sapi Saat Harga
Normal
Persentase Responden yang Memilih Substitusi Daging Sapi (dikelompokkkan berdasarkan penghasilan konsumen rumah tangga per-bulan)
Total
Rp2.000.001 –3.000.000
Rp3.000.001 –4.000.000
Rp4.000.001 – 5.000.000
Rp5.000.001 – 7.000.000
Rp7.000.001 – 8.000.000
diatas Rp8.000.000
Daging Kambing 11.0% 14.7% 11.2% - 20.0% 9.1% 11.77%
Daging Ayam 47.4% 52.1% 50.6% 55.6% 20.0% 27.3% 49.21%
Daging Ikan 12.1% 11.8% 6.7% 11.1% 20.0% 18.2% 11.62%
Daging Bebek 1.1% 1.9% - - - - 1.16%

87
Preferensi Substitusi Daging Sapi Saat Harga
Normal
Persentase Responden yang Memilih Substitusi Daging Sapi (dikelompokkkan berdasarkan penghasilan konsumen rumah tangga per-bulan)
Total
Rp2.000.001 –3.000.000
Rp3.000.001 –4.000.000
Rp4.000.001 – 5.000.000
Rp5.000.001 – 7.000.000
Rp7.000.001 – 8.000.000
diatas Rp8.000.000
Tempe 13.3% 7.1% 7.9% 11.5% 40.0% - 10.99%
Tahu 1.1% .5% 2.2% 3.8% - - 1.16%
Telur 5.7% 6.6% 6.7% 3.7% - 36.4% 6.46%
Daging Kerbau 7.8% 4.7% 10.1% 11.1% - - 7.23%
Jamur .2% - 1.1% - - 9.1% 0.39%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Olahan Data Primer
Responden dalam penelitian ini juga diminta untuk menyebutkan preferensi substitusi
daging sapi saat harga mahal karena adanya kenaikan yang signifikan.Hasilnya, seperti
terlihat pada Gambar 5.4.b., jumlah responden yang bersedia melakukan substitusi
terhadap daging sapi adalah sebesar 62,81%, sementara 37,19% tidak mau.Yang
menarik, justru konsumen dengan pendapatan menengah ke bawah (dibawah Rp 5 juta
per-bulan) yang cenderung tidak bersedia untuk melakukan substitusi dari daging sapi
ke komoditi lainnya. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.6.b.,sebagian besar
responden (65%) dengan pendapatan Rp2-3 juta per-bulantidak bersedia melakukan
substitusi terhadap daging sapi, diikuti oleh responden berpendapatan Rp 3-4 juta
(64,3%), dan responden berpendapatan Rp 4-5 juta (58,4%).
Gambar 5.4.b.Preferensi Konsumen Terhadap Substitusi Daging Sapi (saat harga mahal)
Sumber: Olahan Data Primer

88
Sedangkan komoditi yang menjadi pilihan utama untuk subsitusi daging sapi secara
berurutan adalah: ayam (41,03%), ikan (15,56%), daging kambing (12,85%), tempe
(11,34%), telur (7,68%), daging kerbau (7,48%), tahu (2,03%), bebek (1,82%), dan
jamur (0,20%).Sama dengan kondisi normal, pada kondisi harga mahal ini Konsumen
berpendapatan menengah ke bawah (dibawah Rp 7 juta per-bulan) cenderung
menempatkan daging ayam sebagai substitusi utama daging sapi. Sementara untuk
konsumen yang berpendapatan lebih tinggi (diatas Rp 7 juta per-bulan) lebih memilih
non-ayam sebagai substitusi utama, yaitu tempe, telur dan daging ikan. Telur sangat
dominan, dimana 50% responden berpendapatan Rp 7-8 juta per-bulan memilih telur
sebagai substitusi sapi, begitu juga 80% responden berpendapatan di atas Rp 8 juta.
Tabel 5.6.b. Bersedia Tidaknya Konsumen Melakukan Substitusi Terhadap Daging Sapi (Kondisi
Harga DS Mahal) Berdasarkan Jumlah Pendapatan
Bersedia Melakukan Substitusi
Daging Sapi Saat Harga Mahal
Persentase Responden yang Bersedia Melakukan Substitusi Daging Sapi (dikelompokkkan berdasarkan penghasilan konsumen rumah tangga per-bulan)
Total
Rp2.000.001 –3.000.000
Rp3.000.001 –4.000.000
Rp4.000.001 – 5.000.000
Rp5.000.001 – 7.000.000
Rp7.000.001 – 8.000.000
diatas Rp8.000.000
Ya 35.0% 35.7% 41.6% 57.1% 60.0% 54.5% 37.19%
Tidak 65.0% 64.3% 58.4% 42.9% 40.0% 45.5% 62.81%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Olahan Data Primer
Tabel 5.6.c.Preferensi Subtitusi Daging Sapi Berdasarkan Kategori Penghasilan RT Per Bulan
(Kondisi Harga DS Mahal)
Preferensi Substitusi
Daging Sapi Saat Harga Mahal
Persentase Responden yang Memilih Substitusi Daging Sapi (dikelompokkkan berdasarkan penghasilan konsumen rumah tangga per-bulan)
Total
Rp2.000.001 –3.000.000
Rp3.000.001 –4.000.000
Rp4.000.001 – 5.000.000
Rp5.000.001 – 7.000.000
Rp7.000.001 – 8.000.000
diatas Rp8.000.000
Daging Kambing 10.6% 19.6% 11.3% - - - 12.85%
Daging Ayam 40.6% 42.8% 39.6% 61.5% - - 41.03%
Daging Ikan 17.0% 13.8% 15.1% 7.7% - 20.0% 15.56%
Daging Bebek 2.5% 1.4% - - - - 1.82%
Tempe 12.4% 10.1% 11.3% - 50.0% 11.34%
Tahu 1.8% 2.9% 1.9% - - - 2.03%
Telur 6.0% 4.3% 15.1% 15.4% 50.0% 80.0% 7.68%
Daging Kerbau 9.2% 4.3% 5.7% 15.4% - - 7.48%
Jamur - .7% - - - - 0.20%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Olahan Data Primer
Terakhir, pada saat kondisi langka(Gambar 5.4.c.), konsumen diminta untuk
membayangkan bahwa pasokan daging sapi sulit didapat.Hal tersebut bisa disebabkan
oleh kondisi ekstrem seperti perang atau bencana alam dalam skala besar.
Berdasarkan data yang terkumpul, dalam kondisi pasokan yang langka responden
menetapkan prioritas substitusi daging sapi berturut-turut sebagai berikut; ayam
(45,60%), ikan (12,54%), tempe (11,64%), daging kambing (11,13%), telur (7,84%),
daging kerbau (6,40%),tahu (2,49%), bebek (1,70%), dan jamur (0,20%).

89
Pada Tabel 5.6.d.,responden berpendapatan menengah ke bawah (dibawah Rp 7 juta
per-bulan) cenderung menempatkan daging ayam sebagai substitusi utama daging
sapi.Hal ini berarti konsisten untuk tiga kondisi berbeda, yaitu baik saat kondisi harga
normal, kondisi harga mahal dan kondisi pasokan yang langka.Berdasarkan temuan
tersebut, maka daging ayam sebagai komoditi pangan harus menjadi prioritas untuk
diamankan.
Kebutuhan pengamanan daging ayam ini semakin mendesak, mengingat proyeksi
pasokan sapi di masa mendatang akan mengalami penurunan. Sementara untuk
masyarakat kelas yang berpendapatan diatas Rp 8 juta per-tahun, sebagian besar
menempatkan telur sebagai substitusi utama untuk daging sapi. Hal ini selaras dengan
preferensi konsumen berpendapatan di bawah Rp 7 juta yang menginginkan ayam
sebagai prioritas utama. Baik ayam maupun telur bisa disiapkan dalam satu sistem dan
rantai produksi yang sama, sehingga cukup memudahkan bagi strategi peningkatan
ketahanan pangan nasional.
Gambar 5.4.c.Preferensi Konsumen Terhadap Substitusi Daging Sapi (Kondisi Saat DS Langka)
Sumber: Olahan Data Primer
Namun tantangannya, Indonesia menjadi tempat terjadinya penyebaran penyakit flu
burung yang tidak hanya berbahaya bagi unggas, namun juga berbahaya bagi manusia.
Peningkatan produksi daging ayam dan telur nasional tentu akan meningkatkan risiko
penyebaran dan intensitas terjadinya penularan penyakit tersebut kepada manusia.
Gambar 5.5.menunjukkan bagan peringkat substitusi daging sapi dan tantangan yang
dihadapi untuk menyiapkan prioritas substitusi daging sapi nasional.

90
Tabel 5.6.d.Preferensi Konsumen Terhadap Substitusi Daging Sapi (saat pasokan langka)
Berdasarkan Jumlah Pendapatan
Preferensi Substitusi
Daging Sapi Saat Pasokan Langka
Persentase Responden yang Memilih Substitusi Daging Sapi (dikelompokkkan berdasarkan penghasilan konsumen rumah tangga per-bulan)
Total
Rp2.000.001 –3.000.000
Rp3.000.001 –4.000.000
Rp4.000.001 – 5.000.000
Rp5.000.001 – 7.000.000
Rp7.000.001 – 8.000.000
diatas Rp8.000.000
Daging Kambing 9.2% 15.8% 12.0% - 20.0% 9.1% 11.13%
Daging Ayam 46.5% 42.3% 46.0% 65.4% - 18.2% 45.60%
Daging Ikan 13.1% 13.0% 5.7% 7.7% 40.0% 27.3% 12.54%
Daging Bebek 1.6% 1.4% 2.3% - - 9.1% 1.70%
Tempe 12.9% 11.1% 6.9% 12.0% - 9.1% 11.64%
Tahu 2.3% 2.9% 2.3% 4.0% - - 2.49%
Telur 5.1% 8.7% 13.8% 11.5% 40.0% 27.3% 7.84%
Daging Kerbau 8.1% 3.4% 8.0% - - - 6.40%
Jamur 1.2% - - - - - 0.65%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Olahan Data Primer
Menyikapi preferensi subtitusi daging sapi terhadap komoditas lainnya di masa yang
akan datang. Penting untuk pemerintah mengamankan sektor komoditas ayam sebagai
alternatif, karena selain daging ayam menjadi mayoritas subtitusi nomor satu, telur juga
menjadi alternatif pilihan yang tak kalah prioritas.
Gambar 5.5.Prioritas Substitusi Daging Sapi Konsumen Rumah Tangga
Sumber: Olahan Data Primer
Untuk subtitusi protein lainnya yang penting untuk diamankan selanjutnya adalah ikan
dan tempe. Untuk komoditas ikan saat ini Indonesia mungkin masih bisa merasa aman,
karena kondisi geografis yang dikelilingi oleh oleh mayoritas bahari sebagai produsen
natural. Namun komoditas lainnya seperti tempe, yang berbahan baku kedelai harus
Prioritas Substitusi Daging Sapi Konsumen Rumah Tangga
Harga Mahal
Kondisi Normal
Pasokan Langka
Prioritas 3:
Daging Ikan
(11,62%)
Prioritas 1:
Daging Ayam
(49,21%)
Prioritas 2:
Daging Kambing
(11,77%)
Prioritas 3:
Daging Kambing
(12,85%)
Prioritas 1:
Daging Ayam
(41,03%)
Prioritas 2:
Daging Ikan
(15,56%)
Prioritas 3:
Tempe
(11,64%)
Prioritas 1:
Daging Ayam
(45,60%)
Prioritas 2:
Daging Ikan
(12,54%)
Tantangan Tempe:
Pasokan Kedelai
Tantangan Ayam:
Flu burung
Tantangan Ikan:
Distribusi (jaringan
pendingin)
Tantangan Kambing:
Populasi

91
segera diwaspadai, atas dasar komoditas bahan baku yang saat ini mulai melemah, dan
mulai tergantikan oleh komoditas impor.
5.3. Perkiraan Permintaan Daging Sapi Nasional untuk Industri Berdasarkan
Kategori Potongan Daging Sapi
Ada enam jenis potongan daging sapi segar yang dikenal secara umum, yaitu potongan
primer, potongan sekunder, daging industri, daging variasi, jeroan, dan potongan lain-
lain. Berdasarkan Tabel 5.7., sepertiga permintaan untuk daging lokal adalah dalam
bentuk potongan primer. Sementara, potongan sekunder dan daging industri jika
digabung, memberi kontribusi sekitar 45persen dari total permintaan daging sapi lokal.
Sementara untuk daging sapi impor, daging sekunder dan daging industri berkontribusi
terhadap 62persen dari total permintaan. Sedangkan potongan primer hanya 16,6 dari
total permintaan.
Tabel 5.7. Permintaan Daging Sapi untuk Industri Berdasarkan Jenis Potongan
Jenis Potongan Asal Daging Sapi
Lokal Impor
Potongan Primer 28,9% 16,6%
Potongan Sekunder 23,1% 31,8%
Daging industri 22,4% 30,2%
Daging variasi 10,5% 9,0%
Jeroan 7,6% 7,3%
Potongan lain-lain 7,5% 5,1%
Sumber: Olahan Data Primer, Survei Potensi Demand Daging Sapi (LSM FEUI – Kemendag RI, 2013).
Data tersebut menunjukkan adanya preferensi konsumen industri yang berbeda ketika
mengkonsumsi daging lokal dan daging impor. Berdasarkan penggalian lebih lanjut,
determinan dari perbedaan preferensi ini adalah: harga, kualitas daging dan stabilitas
pasokan. Harga potongan primer untuk daging impor relatif lebih tinggi dibandingkan
daging lokal. Hal ini terkait dengan preferensi konsumen di negara pengekspor (i.e.
Australia), dimana permintaan terhadap potongan primer sangat dominan, sementara
potongan lain kurang populer (bahkan beberapa jenis potongan, seperti jeroan dan
potongan lain-lain, dianggap kurang layak dikonsumsi manusia). Hal ini membuat harga
potongan primer untuk daging impor relatif lebih tinggi dibandingkan harga potongan
primer dari daging lokal. Sebaliknya, harga potongan lain seperti potongan sekunder
dan potongan variasi dari daging impor relatif jauh lebih murah dibandingkan potongan
yang sama dari daging lokal.
Konsumen terbesar untuk potongan primer daging lokal adalah industri Besar (43,7%),
sedangkan untuk potongan primer daging impor, konsumen terbesarnya adalah
Supermarket (34,1%). Berdasarkan jenis usaha responden, misalnya Hotel berbintang
dan Restoran, potongan primer daging impor merupakan kebutuhan utama, dan
seringkali sulit untuk melakukan subsitusi antara daging impor dengan daging lokal.
Misalnya untuk jenis daging impor khusus seperti wagyu, kobe, angus.

92
Selain potongan primer, sepertinya juga menarik untuk dilihat hasil analisis terhadap
daging industri. Supermarket/Hypermarket menjadi konsumen terbesar untuk daging
industri lokal. Hal ini diduga sebagai reaksi konsumen rumah tangga terhadap harga
daging dengan jenis potongan primer, sekunder dan variasi yang cukup tinggi.
Konsumen rumah tangga (masyarakat) kemudian beralih ke jenis daging industri yang
harganya lebih murah. Pergeseran perilaku ini diantisipasi dan dilayani oleh
Supermarket/Hypermarket. Hal ini ditunjukkan dari jenis daging industri (lokal dan
impor) yang paling banyak diminta oleh Supermarket/Hypermarket adalah hindquarter
(sekitar 48%) dan forequarter (sekitar 24%). Baik hindquarter maupun forequarter
bisa digunakan sebagai substitusi potongan primer atau sekunder untuk memasak
menu masakan khas Indonesia seperti rawon, soto, dan sebagainya.
Temuan menarik lainnya terkait dengan kecenderungan industri pengolahan untuk
menggunakan jeroan sebagai bahan baku mereka. Sumber pasokan utama jeroan untuk
industri besar adalah daging impor, dimana harga jeroan daging impor relatif sangat
murah. Sementara konsumen terbesar jerohan daging impor lainnya adalah
supermarket/hypermarket. Sama dengan daging industri, jerohan menjadi alternatif
substitusi bagi konsumen rumah tangga semenjak harga daging (terutama potongan
primer dan sekunder) melonjak tajam.
Sementara data dari Tabel 5.8. untuk angka relatif per-kategori konsumen, permintaan
terbesar untuk daging lokal datang dari Industri Besar, diikuti oleh
Supermarket/Hypermarket dan Pasar Tradisional. Sedangkan untuk daging impor,
permintaan terbesar datang dari Supermarket/Hypermarket, diikuti oleh Industri Besar
dan Pasar Tradisional. Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi permintaan untuk
daging lokal cukup merata diantara para perantara dalam rantai pasokan sapi.
Perbedaan permintaan diantara industri besar, supermarket, dan pedagang pasar tidak
signifikan untuk daging lokal. Sebaliknya, untuk daging impor terjadi ketimpangan
proporsi permintaan. Supermarket menjadi pemain yang permintaan daging impornya
paling tinggi, disusul industri besar.
Tabel 5.8. Permintaan Daging Berdasarkan Kategori Konsumen
Kategori Konsumen Asal Daging Sapi
Lokal Impor
Industri Besar 27,1% 26,5%
Supermarket/Hypermarket 25,7% 43,2%
Pedagang Pasar Tradisional 23,4% 12,1%
Sumber: Olahan Data Primer, Survei Potensi Demand Daging Sapi (LSM FEUI – Kemendag RI, 2013).
Pedagang pasar sebenarnya tidak diperbolehkan menjual daging impor, meskipun
demikian terdapat indikasi adanya kebocoran pasokan daging impor ke pasar
tradisional, dimana responden pedagang pasar yang ikut mendistribusikan daging
impor. Meski jumlahnya paling kecil (12,1%), namun hal ini perlu mendapat perhatian
karena menunjukkan bahwa pedagang pasar memilih untuk menjual daging impor yang

93
disinyalir harganya lebih murah untuk potongan selain potongan primer dibanding
daging lokal.
Proyeksi permintaan daging sapi untuk kategori industri, supermarket dan pasar
tradisional diproyeksikan secara nasional pada Tabel 5.10.a dan Tabel 5.10.b.
Berdasarkan proyeksi tersebut, secara agregat, permintaan total daging lokal secara
nasional diproyeksikan sebesar 554.024 ton/tahun dan daging impor sebesar 108.759
ton/tahun. Berdasarkan proyeksi pada tabel 5.5., maka + 25 persen dari permintaan
daging lokal tersebut dikonsumsi oleh rumah tangga golongan menengah atas.
Lebih lanjut, terdapat tiga jenis konsumen industri yang permintaan terhadap pasokan
daging lokalnya paling besar, yaitu Restoran, UKM dan Pedagang Pasar. Meski terdapat
kemungkinan triangulasi pada data ini (pedagang pasar juga menjual daging kepada
restoran dan UKM, selain kepada konsumen rumah tangga), namun dapat disimpulkan
permintaan terbesar untuk daging lokal berasal dari ketiga konsumen industri tersebut.
Sementara untuk daging impor, konsumen terbesarnya adalah Restoran, UKM dan
Supermarket. Dengan demikian, untuk daging lokal maupun daging impor, posisi
Restoran dan UKM adalah sangat strategis dalam rantai permintaan daging sapi
nasional. Kebutuhan keduanya harus dijadikan prioritas untuk diamankan agar
persepsi umum terhadap stabilitas pasokan tetap positif. Keduanya juga sensitif
terhadap stabilitas harga dan kualitas daging. Jika Restoran dan UKM mengeluh dan
mendeteksi adanya permasalahan dalam pasokan daging sapi nasional, maka
dampaknya akan menyeluruh dan merembet ke persepsi konsumen lainnya.
Sementara, ada empat jenis konsumen industri dengan kuantitas permintaan yang lebih
kecil, yaitu Hotel Bintang 4-5, Hotel Bintang 3, Industri Pengolahan dan Katering.
Konsumen ini tidak terlalu sensitif terhadap besaran dan pasokan daging lokal maupun
impor, terutama karena mereka berani membayar pada harga yang lebih mahal.
Namun, khusus untuk Hotel, mereka memiliki kebutuhan potongan dan kualitas daging
yang spesifik. Sehingga faktor yang mereka prioritaskan adalah faktor kualitas dan
stabilitas pasokan untuk daging yang berkualitas tersebut. Berikut adalah ringkasan
dari permintaan konsumen industri pada Tabel 5.10.a dan Tabel 5.10.b.:
Tabel 5.9. Ringkasan Permintaan Konsumen Industri Kategori Industri Demand DS Lokal (‘000)
per tahun Demand DS Impor (‘000)
per tahun Hotel Bintang 4 dan 5 2.368 1.648 Industri Besar 10.704 2.021 Supermarket/ Hypermarket 8.348 8.070 Hotel Bintang 3 1.709 1.400 Restoran 141.800 76.012 Katering 16.795 566 UKM 181.295 17.596 Pasar Tradisional 191.005 1.446
Sumber: Olahan Data Primer, Survei Potensi Demand Daging Sapi (LSM FEUI – Kemendag RI, 2013).

94
Tabel 5.10.a. Proyeksi Nasional Permintaan Daging Lokal Per Potongan
Demand/ Responden Daging Lokal (Ton) Total
Hotel Bintang 4 dan 5
Industri Pengolahan
Supermarket/ Hypermarket
Hotel Bintang 3
Restoran Katering Industri RT/UKM
Pasar Tradisional
Potongan Primer 988 4,980 659 620 58,917 8,059 68,776 34,389
Potongan Sekunder 365 3,408 2,111 299 18,326 5,364 49,468 24,019
Daging Variasi 319 1,511 312 346 23,653 1,621 45,851 15,999
Daging Industri 286 - 4,779 17 2,882 - 17,201 54,150
Jeroan 364 806 323 289 31,866 1,506 - 11,190
Potongan Lainnya 46 - 165 139 6,155 246 - 51,258
Total 2,368 10,704 8,348 1,709 141,800 16,795 181,296 191,005 554,024
Sumber: Olahan Data Primer, Survei Potensi Demand Daging Sapi (LSM FEUI – Kemendag RI, 2013)
Tabel 5.10.b. Proyeksi Nasional Permintaan Daging Impor Per Potongan
Demand/ Responden Daging Impor (Ton) Total
Hotel Bintang 4
dan 5
Industri Pengolahan
Supermarket/ Hypermarket
Hotel Bintang 3
Restoran Katering Industri RT/UKM
Pasar Tradisional
Potongan Primer 938 - 1,056 760 36,653 317 1,205 455
Potongan Sekunder 465 922 1,916 153 19,335 171 14,983 217
Daging Variasi 233 - 983 303 10,317 26 1,408 183
Daging Industri - 1,100 2,883 - 7,153 - - -
Jeroan 13 - 977 185 2,555 52 - 164
Potongan Lainnya - - 256 - - - - 427
Total 1,648 2,021 8,070 1,400 76,012 566 17,596 1,446 108,759
Sumber: Olahan Data Primer, Survei Potensi Demand Daging Sapi (LSM FEUI – Kemendag RI, 2013)

95
5.4. Rantai Pasokan Sebagai Alur Respon Persediaan dan Respon Produksi
Ketahanan pangan untuk komoditi daging sapi sangat dipengaruhi oleh rantai pasokan
dan perilaku para pemain distribusi di dalamnya. Hal ini terkait dengan karakteristik
komoditi daging yang unik, dimana pasokan dan harga dipengaruhi oleh kemampuan
para pemain untuk mendistribusikan komoditi ini secara cepat dan efisien.
Rantai pasokan daging sapi sendiri merasakan tekanan peningkatan jumlah permintaan
yang begitu cepat dari tahun ke tahun. Tekanan ini merupakan dampak dari
membaiknya kesejahteraan masyarakat dan naiknya jumlah kelas menengah. Seperti
juga terjadi di negara lain, peningkatan kesejahteraan berbanding lurus dengan
kenaikan konsumsi daging. Yang menarik untuk kasus Indonesian adalah, kenaikan
jumlah konsumsi daging secara signifikan ini tidak dibarengi dengan kenaikan jumlah
populasi sapi potong dalam negeri yang mencukupi, sehingga akhirnya perlu dibuka
keran impor sapi. Tidak hanya itu, rantai pasokan sapi yang exisiting saat ini juga tidak
siap menghadapi permintaan yang semakin besar.
Berdasarkan Gambar 5.6., terdapat beberapa titik dalam rantai pasokan existing yang
menjadi sumber lemahnya respon terhadap permintaan, yaitu titik A, B dan C. Masing-
masing titik penting karena punya pengaruh yang besar dalam skema ketahanan
pasokan daging nasional yang diukur berdasarkan stabilitas pasokan, stabilitas harga,
keterjangkauan harga dan kualitas daging.
Titik A adalah belantik (pedagang kecil) yang biasanya membeli sapi milik peternak di
pasar hewan yang ada di berbagai pelosok provinsi penghasil sapi, seperti Jawa Timur
dan Bali. Pada titik rantai pasokan ini, peran blantik sangat dominan dalam menentukan
harga. baik harga beli dari peternak, maupun harga jual kepada pedagang yang lebih
besar.
Titik kedua yang kritikal adalah Titik B, Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Pada titik
ini, akumulasi pasokan sapi hidup, baik di pedagang besar antar provinsi/pulau
maupun feedloters, kemudian diproses di RPH menjadi potongan daging dan lain-lain.
Kapasitas dan kapabilitas RPH dari sisi manajemen dan teknologi merupakan hal yang
sangat strategis, sebab menentukan kuantitas dan kualitas pasokan daging nasional.
Titik terakhir, Titik C, adalah wholesaler atau bandar daging sapi. Mereka menentukan
berapa dan kepada siapa saja daging sapi didistribusikan, termasuk kualitas daging dan
rasio penyebaran berdasarkan karakteristik permintaan. Peran dominan bandar daging
dalam rantai ini semakin besar karena mereka mampu memprediksi dan
mengendalikan jumlah pasokan.

96
Gambar 5.6. Rantai Pasokan Komoditi Sapi Nasional (existing)
Sumber: Olahan Data Primer
Berdasarkan Gambar 5.7. diatas juga dapat dilihat bahwa untuk sapi lokal terdapat
lebih dari satu perantara yang menghubungkan antara peternak dengan RPH.
Sementara jalur untuk sapi dan daging impor relatif lebih pendek. Rantai pasokan ini
akan bervariasi di beberapa daerah, tergantung karakteristik pasokan sapi di daerah
tersebut. Untuk daerah penghasil sapi, seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, rantai
pasokan untuk sapi impor dan daging impor hampir tidak ada karena jumlah pasokan
Peternak
pembudidaya sapi
(breeder)
Pedagang antar
daerah
(kabupaten/kota)
Pedagang antar
pulau antar
provinsi
Peternak
penggemuk sapi
(fattener)Blantik
(pedagang kecil)
Pengrajin kulit
Negara
pengekspor sapi
Perusahaan
penggemukan
(feedloters)
Rumah
Pemotongan
Hewan
Bandar DagingImportir daging
sapi
Industri pengolahan
daging sapi
Hotel,
Restoran,
Katering
Ritel ModernRitel
TradisionalPasar
KONSUMEN
Titik Kritis
A
B
C

97
impor tidak signifikan. Sementara untuk daerah yang defisit sapi, seperti DKI Jakarta
dan Jawa Barat, model rantai pasokannya mencakup keseluruhan elemen yang ada.
Pada Gambar 5.7. dapat dilihat persebaran pasokan sapi nasional. Sembilan provinsi
menyumbang 83% dari total populasi dan pasokan sapi nasional, dengan Jawa Timur
sebagai yang terbesar dengan 34% (sepertiga populasi sapi nasional), diikuti oleh Jawa
Tengah (14%), Sulsel (7%), NTT (6%), NTB (5%), Bali (5%), Lampung (5%), Sumut
(4%) dan DIY Yogyakarta (4%). Sisanya sebesar 17% dibagi ke provinsi-provinsi
lainnya.
Gambar 5.7. Sebaran Populasi Sapi Nasional
Sumber: Olahan Data Primer dan Sekunder (Sensus Peternakan, 2013)
Jumlah populasi sapi tersebut tidak serta merta mencerminkan jumlah pasokan yang
berasal dari daerah tersebut. Untuk beberapa daerah, persentase jumlah pasokan ke
sistem rantai pasokan daging nasional bisa lebih tinggi dibandingkan persentase
populasi sapi daerah tersebut terhadap populasi sapi nasional. Daerah-daerah yang
dekat dengan Jabodetabek (yang merupakan daerah pengkonsumsi terbesar daging
sapi), akan mendapat tarikan permintaan pasokan yang lebih kuat. Karena itu, provinsi
seperti Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, dipaksa memasok sapi dengan
jumlah persentase pasokan yang melebihi tingkat pasokan alaminya. Jika ini diteruskan,
akan menjadi sebuah tantangan bagi provinsi-provinsi tersebut untuk menjaga
sustanaibility populasi sapi mereka.
5.4.1. Mekanisme Pembentukan Harga Jual Beli Daging Sapi Lokal dan Impor
Untuk melihat kemampuan rantai pasokan daging sapi Indonesia merespon fluktuasi
pasokan, fluktuasi harga dan perubahan permintaan konsumen, maka kita perlu
melakukan reviewterhadap mekanisme pembentukan harga potongan daging sapi (baik
lokal maupun impor) yang terjadi di masing-masing pelaku usaha.
Jawa Tengah
14%
Jawa Timur
34%NTB
5% NTT
6%
Bali
5%
SEBARAN POPULASI SAPI NASIONAL
Sulawesi Selatan
7%
Lampung
5%
Sumatera Utara
4%
DI Yogyakarta
4%

98
Pada Tabel 5.11.a dapat dilihat bahwa harga jual maksimum potongan daging lokal dari
Pemotong Daging dan Bandar Daging berkisar antara Rp.79.333/kg, yaitu kepada para
Pengecer dan Supplier Daging, sampai dengan yang tertinggi sebesar Rp.95.000/kg
kepada Hotel, Restoran dan Katering. Variasi antara harga tertinggi dengan harga
terendah untuk potongan daging lokal bisa dikatakan tidak terlalu jauh.
Tabel 5.11.a.Harga Jual maksimum dari Pemotong Daging, Bandar Daging, dan Distributor
Daging Impor
Harga jual maksimum Pemotong daging dan Bandar Daging kepada:
Harga (per-kg)
Lokal Impor
Potongan Daging Potongan Daging
Rumah Potong Hewan (RPH) 80,000 --
Pengecer dan Supplier Daging 79,333 --
Industri Pengolahan Daging Sapi 86,625 55,000
Pasar Tradisional dan UKM 84,375 127,500
Hotel, Restoran dan Katering 95,000 220,000
Sumber: Olahan Data Primer
Sementara, harga maksimum potongan daging impor yang dijual oleh Distributor Impor
berbeda secara signifikan antara yang paling rendah (Industri Pengolahan:
Rp.55.000/kg) dan yang paling tinggi (Hotel, Restoran dan Katering: Rp.220.000).
Perbedaan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa karakteristik harga potongan
daging impor berbeda dengan potongan daging lokal. Pada daging impor, potongan
utama (prime cuts) benar-benar dihargai sehingga nilainya sangat mahal. Sementara
potongan non-prime cut dihargai sangat rendah, bahkan lebih rendah untuk potongan
yang sama dari daging lokal. Misalnya, jeroan dan daging variasi impor merupakan
produk yang dianggap tidak layak dikonsumsi manusia, sehingga harganya sangat
murah pada level importir. Padahal untuk daging lokal, jeroan dan daging variasi masih
memiliki harga yang cukup tinggi karena permintaanya yang juga tinggi. Lebih lanjut,
Tabel 5.11.b. juga menunjukkan bahwa harga jual dari Pengecer dan Supplier Daging
memiliki perbedaan karakteristik ini.
Tabel 5.11.bHarga Jual Maksimum dari Pengecer dan Supplier Daging
Harga jual maksimum Pengecer dan Supplier Daging kepada:
Harga (per-kg)
Lokal Impor
Karkas Potongan Daging Potongan
Daging
Industri Pengolahan Daging Sapi 43,000 92,500 98,000
Pasar Tradisional dan UKM 63,000 81,667 -
Hotel, Restoran dan Katering - 91,458 147,000
Sumber: Olahan Data Primer

99
Berdasarkan data harga tersebut, dipetakan sebuah pembentukan harga sapi
berdasarkan hasil survei sebagaimana diterakan pada Gambar 5.8. Untuk sapi lokal,
harga awal dari peternak memiliki variasi yang cukup tinggi, tergantung kepada
pembelinya. Jika Blantik yang membeli, harga jual sapi bervariasi antara Rp.34.451,- s.d.
Rp.38.070/kg. Variasi harga yang lebih tinggi terjadi jika yang melakukan pembelian
adalah peternak penggemuk sapi (fattener), yaitu antara Rp.29.333,- s.d. Rp. 40.188/kg.
Peternak
pembudidaya sapi
(breeder)
Pedagang antar
daerah/bandar
sapi
Peternak
penggemuk sapi
(fattener)
Blantik
(pedagang kecil)
Rp 34.887 – 48.198/kg
Negara
pengekspor sapi
Perusahaan
penggemukan
(feedloters)
Bandar Daging
Rumah
Pemotongan
Hewan
Rp34.451 - 38.070/kg
Rp 30.000/kg
Rp 29.333 – 40.188/kg
Rp 30.030 – 34.978/kg
Rp34.206- 39.693/kgRp 38.173/kg
Rp30.000 -34.286/kg
Gambar 5.8. Pembentukan Harga Sapi Sumber: Olahan Data Primer
Penggemuk sapi ini kemudian menjual kepada blantik dengan kisaran Rp.30.030,- s.d.
Rp.34.978/kg. Blantik sendiri menjadi salah satu titik krusial dari rantai pasokan sapi

100
lokal, dimana mereka akan mendapatkan marjin yang cukup baik dengan menjual sapi
kepada Bandar Sapi dengan kisaran harga antara Rp.34.887,- s.d.
Rp.48.198/kg.Sementara untuk sapi impor, harga per-kilogram-nya dari Negara
pengekspor sapi rata-rata adalah Rp.30.000/kg. Setelah melalui proses penggemukan di
feedloter, harganya naik menjadi kisaran Rp.30.000,- s.d. Rp. 34.286/kg saat dijual
kepada Bandar Daging. Setelah sampai di Bandar Daging, harga daging lokal berkisar
antara Rp.73.563,- s.d. Rp.48.198/kg.
Sapi tersebut kemudian di proses di RPH (Rumah Potong Hewan), dengan rata-rata
biaya produksi per ekor sapi berkisar Rp.150.000,-. Biaya tersebut sudah termasuk
dalam jasa penitipan sapi, jasa potong, dan jasa pakan selama sapi dititipkan sementara
di RPH tersebut. Pada praktik tata niaga, RPH secara teknis tidak berperan aktif, karena
umumnya hanya sebagai penyedia jasa potong, meskipun demikian, di beberapa daerah
terdapat RPH yang turut serta berperan aktif sebagai pengecer daging sapi skala besar
yang umumnya dilakukan dalam bentuk koperasi daging daerah.
Pembentukan harga potongan daging diteruskan pada gambar 5.9., dimana alur
pembentukan harganya berporos pada Pengecer dan Supplier Daging.
Pengecer dan
supplier
Importir daging
sapi
Industri pengolahan
daging sapi
Hotel,
Restoran,
Katering
UKM
Lokal: Rp81.400 – 83.500/kg
Impor: Rp127.500/kg
Rp62.000 – 98.000/kg
Lokal: Rp85.000 – 92.167/kg
Impor: Rp220.000/kg
Lokal: Rp81.000-
Rp85.000/kg
Bandar Daging
Lokal: Rp73.563 – 86.250/kg
Impor: Rp100.000/kg
Rp87.500 – 127.500/kg
Rp175.000 – 204.000/kg
Gambar 5.9. Pembentukan Harga Daging Sapi
Sumber: Olahan Data Primer

101
Untuk daging lokal, Bandar Daging menjual kepada Pengecer seharga Rp75.563 –
86.250/kg. Kemudian Pengecer akan mendistribusikan kepada Industri Pengolahan
(berkisar antara Rp81.400 – 83.500/kg), UKM (berkisar antara Rp81.000 – 85.000/kg),
dan Hotel Restoran Katering (berkisar antara Rp.85.000 – 92.167/kg).
Sementara untuk potongan daging impor, alur pembentukan harganya berporos pada
Importir Daging Impor serta pada Pengecer. Dari Importir, harga kepada UKM berkisar
antara Rp62.000 – 98.000/kg, kemudian kepada Industri Pengolahan berkisar antara
Rp87.500– 127.500/kg, dan kepada Hotel Restoran Katering berkisar antara Rp175.000
– 204.000/kg. Sedangkan daging impor yang berasal dari feedloter dan disalurkan oleh
Bandar Daging, harganya rata-rata adalah Rp100.000/kg saat dijual kepada Pengecer.
Pengecer akan menjual gading impor tersebut pada Industri Pengolahan dengan harga
rata-rata Rp.127.500/kg, dan kepada Hotel Restoran Katering dengan harga rata-rata
Rp.220.000/kg.
5.4.2. Persepsi terhadap Kemandirian dan Stabilitas Pasokan Daging Sapi
Dalam penelitian ini, coba diidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh rantai pasokan
sapi (existing) sebagai proxy dari ketahanan pangan, terhadap perubahan iklim (lihat
Gambar 5.10.). Hubungan antara perubahan iklim dan ketahanan pangan tersebut
memiliki beberapa aspek, sebagai berikut:
(1) Perubahan iklim memperbesar kemungkinan terjadinya peningkatan intensitas
serangan penyakit pada hewan ternak, termasuk sapi. Hal ini mengancam proses
penggemukan dan reproduksi sapi, yang pada gilirannya mengancam
produktivitas dan supply, serta meningkatkan risiko terjadinya volatilitas harga
daging sapi.
(2) Perubahan iklim mengakibatkan semakin langkanya sumberdaya alam, terutama
air bersih dan keanekaragaman hayati (pakan sapi). Hal ini menjadi salah satu
faktor yang menyebabkan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan peternak
untuk mencari dan menyiapkan makanan yang murah untuk sapi mereka.
(3) Perubahan iklim juga memberi tekanan kepada pemerintah untuk memperbaiki
infrastruktur dan teknologi, sebagai bagian strategis dari sistem ketahanan
pangan nasional, terutama untuk menunjang proses distribusi sapi dari satu
daerah ke daerah lain.

102
Gambar 5.10. Tantangan Rantai Pasokan Sapi Sumber: Olahan Data Primer
Selain itu, penelitian ini juga menggali persepsi para stakeholder yang terlibat dalam
rantai pasokan sapi (termasuk pengusaha dan konsumen) terhadap ketahanan pasokan
komoditi daging sapi nasional. Ada 4 (empat) dimensi yang digunakan (lihat Gambar
5.11.), yaitu: (1) kemandirian pasokan (self-sufficiency); (2) stabilitas pasokan (stability
of supply); (3) keterjangkauan harga (affordability); dan (4) kualitas (quality). Persepsi
diukur menggunakan skala 1 sampai 5, dimana semakin tinggi angka menunjukkan
tingkat yang lebih baik.
Distribusi sapi
hidup
Peternakan,
penggemukan dan
pembibitan sapi
Pemrosesan
Konsumsi
Penyembelihan
Distribusi
daging
Sumberdaya: Air, pakan, energi,
Tantangan: Perubahan cuaca, penyakit, limbah
Sumberdaya: Energi (BBM)
Tantangan: Cuaca ekstrem, bencana alam, infrastruktur
Sumberdaya: Air, energi
Tantangan: Limbah, teknologi
Sumberdaya: Air, energi
Tantangan: Limbah, teknologi
Sumberdaya: Energi (BBM)
Tantangan: Cuaca ekstrem,
bencana alam, infrastruktur
Breeders,
fatteners,
feedloters
Blantik,
pedagang
besar
RPH
Industri
pemrosesan
Bandar
daging, ritel
modern, ritel
tradisional
Rumah
tangga, hotel,
restoran

103
Gambar 5.11. Dimensi Ketahanan Pangan: Sapi
Sumber: Olahan Data Sekunder
Berdasarkan Gambar 5.12.a, persepsi konsumen terhadap kemandirian pasokan dan
stabilitas pasokan untuk komoditi daging sapi dapat dikatakan sangat negatif. Persepsi
yang serupa juga dimiliki oleh pengusaha yang bisnisnya terkait dengan pasokan daging
sapi (lihat Gambar 5.12.b). Hasil ini mencerminkan kondisi kelangkaan pasokan daging,
serta simpang-siurnya informasi dan data jumlah populasi sapi secara nasional.
Konsumen dan pebisnis merasa bahwa kejadian tersebut merupakan gambaran nyata
dari kondisi pasokan daging sapi nasional.
Gambar 5.12.a Perceptual Map Ketahanan Pangan menurut Konsumen Sumber: Olahan Data Sekunder
Stabilitas Pasokan
(stability of supply)
Apakah pasokan daging sapi stabil dan stok cadangan nasional mencukupi?
Kemandirian Pasokan
(self-sufficiency)
Apakah produksi daging sapi mampu memenuhi kebutuhan domestik?
Keterjangkauan Harga (affordability)
Apakah harga daging sapi relatif terjangkau dan tidak fluktuatif?
Kualitas (quality)
Apakah rasa, nutrisi dan kalori yang terkandung memenuhi kualitas yang
diharapkan?
Ketahanan Pangan: Daging Sapi
Padi
Sapi
Kedelai
Kelapa Sawit
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5
Self
-Su
ffic
ien
cy
Stability of Supply

104
Gambar 5.12.b Perceptual Map Ketahanan Pangan menurut Pengusaha
Sumber: Olahan Data Sekunder
Ukuran persepsi terhadap ketahanan pangan juga perlu mempertimbangkan
keterjangkauan (affordability) komoditi dan kualitas (quality) komoditi tersebut. Pada
Gambar 5.12.c,terlihat bahwa keterjangakauan harga untuk komoditi daging sapi
dipersepsikan tidak baik oleh konsumen. Hal ini wajar mengingat harga daging sapi
terus naik dengan signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Harga daging sapi
saat ini menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan harga daging sapi
tertinggi di dunia. Sementara, persepsi konsumen terhadap kualitas daging sapi yang
mereka konsumsi cenderung netral. Konsumen mempersepsikan bahwa daging sapi
yang mereka konsumsi aman, termasuk dari berbagai penyakit yang selama ini sering
dihadapi oleh negara lain. Indonesia masih bisa menjaga dari penyakit yang menjangkiti
sapi di luar negeri, seperti penyakit gigi dan mulut.
Gambar 5.12.c Perceptual Map Ketahanan Pangan menurut Konsumen
Sumber: Olahan Data Primer
Padi
Sapi
Kedelai
Kelapa Sawit
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5
Padi
Sapi
Kedelai
Kelapa Sawit
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5
Self
-Su
ffic
ien
cy
Stability of Supply
Aff
ord
abili
ty
Quality

105
Gambar 5.12.d Perceptual Map Ketahanan Pangan menurut Pengusaha
Sumber: Olahan Data Primer
Meski demikian, pada Gambar 5.12.d, ditunjukan bahwa persepsi pengusaha terhadap
kualitas daging sapi justru lebih rendah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hal
ini lebih terkait pada kemampuan rantai pasokan (terutama RPH) untuk menyediakan
potongan daging yang mereka inginkan. Belum banyak RPH di Indonesia yang memiliki
kemampuan memotong daging sesuai standar internasional, seperti yang dibutuhkan
oleh hotel, restaurant maupun konsumen spesifik lainnya.
Gambar 5.13. Sumber Pasokan Bahan Pangan Pokok di Indonesia tahun 2013 Sumber: Olahan Data Primer
Padi
Sapi
Kedelai
Kelapa Sawit
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5
5
15
70
0
95
85
30
100
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Padi
Sapi
Kedelai
Sawit
Impor
Domestik
Aff
ord
abili
ty
Quality

106
Jika ditilik dari angka impor pada Gambar 5.13., sapi lokal masih menjadi sumber utama
pasokan. Sapi impor hanya menyumbang sekitar 15% dari pasokan sapi nasional.
Dengan kata lain, yang dikhawatirkan (dipersepsikan negatif) oleh konsumen dan
pebisnis lebih kepada tren pasokan jangka panjang.
5.4.3. Arahan Penerapan Rantai Tata Niaga Bahan Pangan Pokok/ Supply Chain
Management Normatif berdasar Faktual
Berdasarkan analisis terhadap rantai pasokan dan tata niaga yang saat ini telah berlaku
untuk komoditi daging sapi, telah terindentifikasi 4 (empat) permasalahan utama,
sebagai berikut:
1) Rendahnya pertumbuhan populasi sapi nasional:
Sebagian besar peternak dan breeder di daerah tidak memiliki akses yang baik
pada inseminasi buatan, sehingga pertumbuhan populasi sapi cenderung stagnan
dan bahkan menurun. Minimal, pertumbuhan populasi sapi harus sama tinggi
dengan pertumbuhan permintaan. Saat ini tingkat pertumbuhan permintaan jauh
melebihi tingkat pertumbuhan populasi sapi. Pola manajemen peternakan sapi
yang masih tradisional juga mempersulit tercapainya skala ekonomis, sehingga
biaya yang diperlukan untuk melakukan inseminasi buatan menjadi lebih besar.
Kebijakan breeding dalam rangka memenuhi pasokan sapi lokal nasional
diperlukan sebagai reaksi dari aksi pemotongan sapi lokal (terutama sapi betina
produktif) yang kontinu dalam jumlah besar. Jika breeding tidak segera dilakukan
dan dikontrol sebagai intervensi pemerintah, maka stok sapi lokal semakin lama
akan semakin habis. Terkait kebutuhan pembibitan, langkah-langkah kebijakan
yang bisa dimajukan:
a. Program breeding secara khusus harus ditangani oleh lembaga tersendiri, dan
tidak bisa lagi mengandalkan kemampuan peternak semata karena
berhadapan dengan jangka waktu produksi dan perhitungan bisnis
pembibitan yang tidak menjanjikan. Dalam hal ini, pemerintah harus
memaksimal peran balai benih dan bibit unggul yang tersebar di sejumlah
daerah.
b. Potensi besar yang bisa dimaksimalkan adalah program breeding inisiatif oleh
feedloter dalam jumlah besar untuk mempertahankan supply. Mayoritas
feedloter berskala besar sudah memiliki teknologi handal untuk menjalankan
program breeding dan menghasilkan bibit sapi berkualitas baik. Mereka juga
umumunya didukung oleh kondisi lahan yang masih luas dan pasokan pakan
yang lebih dari cukup, sehingga menjadi modal utama untuk
mengembangbiakan sapi berskala masif.

107
c. Pembibitan oleh peternak harus dijalankan secara berkelompok untuk
memudahkan dalam pendampingan manajemen dan monitoring populasi.
Secara mendasar harus dijalankan upaya penguatan kelompok peternak
rakyat untuk melakukan breeding massal secara intensif, dengan
memaksimalkan dukungan pendanaan dari Bank dan kerjasama pengadaan
pakan dari perusahaan feedloter. Penguatan kelompok peternak juga akan
menjadi “entry point” dalam membangun data base stok populasi sapi secara
terukur dan berkesinambungan. Ke depannya, jika pembibitan oleh kelompok
peternak ini berjalan sempurna maka akan memudahkan bagi pemerintah
untuk monitoring stok sapi karena populasi terukur sudah tercatat di masing-
masing kelompok dan untuk itu sedari awal harus dibangun sistem informasi
pasokan sapi di setiap desa.
d. Optimalisasi protein hewani lokal (setempat) sebagai optimalisasi alternatif
protein hewani sebagai substitusi dari daging sapi. Hal ini terutama untuk
daerah yang bukan sentra penghasil sapi. Tujuannya adalah mengurangi
ketergantungan daerah tersebut terhadap pasokan daging sapi dari daerah
lain, sehingga sumber protein untuk masyarakat di daerah tersebut lebih
sustainable. Misalnya, daerah pesisir perlu mengoptimalkan sumber protein
dari hasil laut. Begitu juga dengan daerah di sepanjang aliran sungai besar
dan danau, diharapkan bisa mengoptimalkan sumber protein dari perairan.
Untuk itu, kearifan lokal perlu dikembalikan lewat intervensi sosial oleh
pemerintah. Diantaranya adalah dengan mempromosikan makanan lokal
yang menggunakan sumber protein yang gampang ditemukan atau
diternakkan di daerah tersebut. Ini harus menjadi unggulan strategi untuk
meningkatkan ketahanan pangan nasional. Selain itu, hal ini akan
meningkatkan efisiensi rantai pasokan komoditas bahan pokok, karena
saluran distribusi menjadi lebih pendek. Jumlah perantara menjadi lebih
sedikit, dan waktu maupun jarak tempuh menjadi lebih rendah.
2) Lemahnya peran RPH:
RPH seharusnya bisa menjadi alat bagi pemerintah untuk melakukan kontrol
terhadap jumlah populasi sapi dan stabilitas pasokan. Namun pada kenyataannya,
banyak sekali RPH yang tidak dikelola secara professional, dan bahkan
membahayakan kesehatan konsumen karena sering melanggar prosedur baku
dalam penyembelihan dan pemotongan sapi. Selain itu, RPH tidak memberikan
masukan berupa data kepada pengambil keputusan mengenai total jumlah sapi
yang dipotong, asal daerah sapi dan tujuan distribusi daging. Ide untuk mendata
sapi dan memberikan tanda pengenal, dapat terealisasi jika peran RPH diperkuat
oleh pemerintah.

108
3) Kuatnya jaringan pedagang besar di daerah:
Pada daerah-daerah sentra penghasil sapi, terdapat pedagang besar yang
menguasai pasokan sapi dari daerah tersebut. Kumpulan pedagang-pedagang
besar ini menimbulkan ketergantungan yang tinggi kepada mereka atas stabilitas
pasokan. Mereka memiliki modal yang besar dan jaringan blantik, sehingga bisa
menentukan kapan dan berapa jumlah pasokan yang harus dikirimkan ke daerah
yang membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, seperti misalnya Jabotabek.
Menyikapi hal ini, penting untuk dapat meninjau kembali upaya revitalisasi pasar
hewan dalam perannya sebagai pasar komodit. Hal tersebut dilakukan dalam
upaya memperluas jangkauan pasar hewan di tingkat kota atau kabupaten. Pasar
hewan harus dikelola dengan aspirasi menjadikannya sebagai pasar komoditi
yang modern dan fair.
Selama ini peternak tidak mendapatkan informasi yang sempurna mengenai
jumlah permintaan dan harga. Perolehan informasi didominasi oleh blantik atau
pedagang, sehingga marjin keuntungan tertinggi dinikmati oleh perantara, bukan
oleh peternak. Pasar hewan bisa menjembatani kesenjangan informasi ini,
sehingga tercapai perdagangan yang menguntungkan semua pihak.
4) Distribusi yang tidak efisien karena buruknya infrastruktur:
Tantangan lain yang harus dihadapi adalah buruknya infrastruktur, baik secara
kualitas maupun kuantitas. Beberapa infrastruktur yang penting dalam distribusi
sapi adalah jalan raya, pelabuhan penyeberangan dan rel kereta api. Buruknya
infrastruktur berpengaruh kepada waktu tempuh dan jumlah bahan bakar yang
menjadi lebih tinggi. Akibatnya, biaya distribusi seringkali lebih mahal
dibandingkan harga daging sapi dari peternak.
Tabel 5.12. menunjukkan besaran biaya pengiriman dan distribusi sapi dan daging
sapi. Data ini berasal dari hasil survei terhadap pelaku usaha yang ada dalam
rantai pasokan sapi, untuk setiap kali pengiriman sapi atau daging sapi yang
mereka lakukan. Komponen pertama biaya pengiriman adalah penyewaan
kendaraan pengangkut.
Komponen lainnya yang cukup signifikan adalah retribusi dan pungli. Peternak
mengalami pungli yang paling besar diantara para pemain lainnya. Kemungkinan
hal ini terjadi karena posisi tawar peternak yang lemah dibandingkan oknum yang
melakukan pungli. Sementara untuk retribusi, pembayar terbesar adalah Bandar
Sapi dan Blantik. Secara total, pemain dengan biaya pengiriman dan distribusi
terendah adalah Bandar Daging, sementara yang tertinggi adalah Feedloters.

109
Tabel 5.12. Biaya Pengiriman dan Distribusi (per-satu kali pengiriman)
Jenis Biaya
Kategori Responden
Rata-rata Peternak
Sapi Blantik
Bandar Sapi
Feed-loter RPH Bandar Daging
Pengecer dan Supplier
Daging
Sewa Kendaraan 345,000 464,286 1,425,000 2,350,000 850,000 - 500,000 738,000
Pengangkutan Lokal 168,611 183,167 550,000 130,000 102,500 218,833 95,000 201,865
Parkir - 6,600 4,500 5,000 5,000 2,000 - 5,400
Pungli 85,667 6,000 10,000 - 6,000 - - 36,375
Retribusi 5,444 339,333 509,000 171,667 5,000 60,000 2,000 114,222
Total 604,722 999,386 2,498,500 2,656,667 968,500 280,833 597,000 1,229,373
Persepsi biaya total 337,158 388,214 1,328,750 1,826,667 252,400 29,500 220,500 626,170
Gap 267,564 611,171 1,169,750 830,000 716,100 251,333 376,500 603,203
Gap (%) 56% 39% 53% 69% 26% 11% 37% 51%
Sumber: Olahan Data Primer
Kami kemudian membandingkan total biaya aktual berdasarkan survey tersebut
dengan persepsi biaya yang ditanyakan kepada responden pada bagian terpisah.
Tujuannya adalah untuk melihat gap antara persepsi biaya dengan biaya aktual
yang dibayarkan oleh para pemain dalam rantai pasokan sapi.
Gap terbesar dialami oleh feedloter (69%), kemungkinan disebabkan persepsi dan
ekspektasi feedloter (yang sebagian adalah pengusaha asing) bahwa biaya
pengiriman seharusnya lebih rendah. Kurangnya pengetahuan feedloter terhadap
kualitas infrastruktur, juga menjadi faktor terjadinya hal tersebut. Gap terbesar
kedua dialami oleh Peternak. Kemungkinan hal ini terjadi karena peternak tidak
menghitung besarnya pungli yang harus mereka bayarkan. Gap ketiga terbesar
adalah Bandar Sapi. Menilik komponen biayanya, maka gap tersebut disebabkan
ketidakakuratan Bandar Sapi menghitung biaya pengangkutan lokal.
Pengangkutan lokal dari sentra-sentra atau desa-desa penghasil sapi memerlukan
biaya ekstra karena infraktruktur yang kurang mendukung.
Sementara gap terendah dimiliki oleh Bandar Daging (11%). Hal ini disebabkan
Bandar Daging paling mudah memprediksi biaya yang harus mereka keluarkan
karena mereka tidak sering melakukan aktivitas pengiriman, sehingga terbebas
dari biaya sewa kendaraan (yang ongkosnya sulit diprediksi mengingat buruknya
infrastruktur) dan pungli.
Rata-rata pelaku usaha sapi dan daging sapi menggunakan moda transportasi
kendaran roda empat. Mobil pick up digunakan untuk pengiriman sapi antar
kabupaten (jarak dekat). Satu mobil pick up dapat memuat sekitar 6 ekor sapi
ukuran sedang/kecil dan 4 ekor sapi ukuran besar. Sedangkan untuk truk
umumnya digunakan untuk pengiriman sapi jarak jauh (lokal dan sapi impor).
Kapasitas angkut disesuaikan berdasarkan kebutuhan, jarak tempuh, dan jenis

110
truk yang digunakan. Kapasitas truk satu kali pengiriman dapat memuat
sedikitnya 9 sampai maksimal 22 ekor sapi (lokal/impor).
Sedangkan untuk pengiriman karkas dan potongan daging sapi, digunakan mobil
jenis pick-up dengan jarak antar sekitar 30 – 1 jam perjalanan maksimal, untuk
menjaga kondisi daging sapi tetap segar paska produksi (pemotongan) di RPH.
Untuk potongan daging sapi impor (daging sapi beku), langsung didistribusikan
oleh distributor menggunakan mobil pick-up tertutup oleh cool box. Khusus untuk
potongan daging sapi impor (daging beku) jarak antar disesuaikan berdasarkan
kebutuhan.

111
BAB 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6.1. Kesimpulan
1. Menganalisis kapabilitas strategis produksi untuk mengembangkan rekomendasi
kebijakan dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi bahan pangan nasional.
Untuk meningkatkan kapasitas produksi daging sapi nasional perlu untuk
mempertimbangkan beberapa hal penunjang kapabilitas strategi produksi
sebagai berikut:
a) Pergeseran Musim dan Fluktuasi Curah Hujan
Secara umum, ada empat unsur iklim mikro yang dapat mempengaruhi
produktivitas ternak secara langsung yaitu: suhu, kelembaban udara,
radiasi dan kecepatan angin, sedangkan dua unsur lainnya yaitu evaporasi
dan curah hujanmempengaruhi produktivitas ternak secara tidak langsung.
Suhu dan kelembaban udara merupakan dua faktor iklim yang
mempengaruhi produksi susu sapi, karena dapat menyebabkan perubahan
keseimbangan panas dalam tubuh ternak, keseimbangan air, keseimbangan
energi dan keseimbangan tingkah laku ternak (Esmay, 1982). Dengan
terganggunya produksi susu ini maka sedikit banyak juga akan berdampak
pada keberlangsungan hidup anak sapi (pedet) sehingga juga akan memiliki
dampak pada rantai produksi sapi potong secara umum.
Kehidupan dan produksi pada ternak memerlukan suhu lingkungan yang
optimum (McDowell 1974). Zona termonetral suhu nyaman untuk sapi
Eropa berkisar 13 – 18°C (McDowell, 1972); 4 – 25°C (Yousef, 1985), 5 –
25°C (Jones & Stallings, 1999).Secara kapabilitas strategis produksi suhu
udara dan kelembaban harian di Indonesia umumnya tinggi, yaitu berkisar
antara 24 – 34°C dan kelembaban 60 – 90 persen. Hal tersebut akan sangat
mempengaruhi tingkat produktivitas sapi, khususnya sapi jenis Frisian-
Holstein (FH).
b) Produktifitas Sapi Potong
Pertumbuhan rata-rata sapi potong dari 2006 hingga 2012 adalah 5.54
persen. Namun, menurut Survei Ternak (ST) 2013 jumlah populasi sapi
potong pada tahun hingga 2013 (Bulan) adalah 13 juta ekor yang berarti
terjadi penurunan sekitar 20 persen dari proyeksi jumlah sapi tahun
sebelumnya yakni kurang lebih 16 juta ekor sapi potong.

112
Sedangkan dari populasi sapi indukan betina dari tahun 2006 hingga tahun
2013 akhir, terus mengalami penurunan yakni sebesar 31,1 persen. Dengan
kata lain, selama periode 2006 hingga tahun 2013 akhir, peternak terus
melakukan pemotongan terhadap sapi indukan.Tentu saja penurunan ini
secara umum memiliki dampak yang cukup besar terhadap rantai pasokan
sapi potong dan daging sapi potong pada tingkat nasional.
Jika penurunan produktivitas ini tidak segera diatasi, akan terjadi defisit yang
sangat besar dan melebar terhadap produktivitas dan konsumsi daging sapi
nasional. Berdasarkan data olahan (BPS, 2012), pada tahun 2014 diprediksi
akan terjadi defisit sebesar 120.755.604 Kg Daging sapi.
Produksi daging sapi terus mengalami penurunan walaupun pada simulasi
telah dimasukkan realisasi kebijakan terbaru dari pemerintah seperti impor
sapi bakalan dan sapi potong. Dampak terparah jika tidak dilakukan strategi
apapun terhadap peningkatan produktifitas adalah pada tahun 2020, defisit
daging sapi nasional di prediksi akan mencapai 500.000 ton.
c) Pondasi Dasar Sistem Produksi Daging Sapi
Hasil simulasi data memperlihatkan bahwa persoalan penurunan jumlah
populasi sapi terjadi pada setiap jenjang/kategori usia sapi, yakni: 1) sapi
anakan (pedet), 2) sapi muda (belum produktif), 3) sapi indukan jantan dan
betina (merupakan sapi muda yang telah dewasa/produktif/dapat
dikawinkan secara alamiah ataupun buatan, dan 4) yang terakhir adalah sapi
yang siap potong.
Populasi anak sapi mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Penurunan
ini tentu dalam jangka panjang akan mempengaruhi suplai sapi potong.
Sehingga bila dibiarkan kondisi ini berjalan terus maka kebutuhan sapi
potong impor baik bakalan maupun sapi siap potong akan terus dilakukan
guna mencukupi permintaan daging sapi nasional.
Kondisi penurunan yang terus-menerus juga terjadi untuk populasi sapi
potong yang belum produktif. Kenaikan populasi pada usia ini pada gambar
tersebut lebih diakibatkan oleh adanya impor sapi bakalan, bukan
bersumber dari proses inseminasi alamiah maupun buatan dari sapi lokal.
Populasi indukan terus menurun juga.
Yang patut menjadi perhatian adalah penurunan sapi indukan betina yang
sangat tajam dari 3 juta ekor di tahun 2013 hanya menjadi 1,5 juta ekor saja
di tahun 2020, menurun hampir 50%.

113
2. Gambaran serta memperkirakan permintaan bahan pangan nasional baik oleh
individu rumah tangga (direct consumption)ataupun oleh industri pengolahan
makanan (indirect consumption).
Berdasarkan hasil survei, permintaan daging sapi untuk rumah tangga golongan
menengah atas mencapai 7,2 kgper kapita per tahun. Bersama dengan asumsi
permintaan daging sapi per kapita per tahun versi statistik peternakan, data
tersebut diproyeksikan sehingga secara keseluruhan total permintaan daging
sapi rumah tangga Indonesia mencapai angka + 679.888 ton.
Meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa konsumsi daging sapi tersebut
bisa jadi adalah daging sapi dalam bentuk daging segar, maupun produk olahan
daging yang dikonsumsi melalui sentra produksi seperti HoReKa, serta Industri
RT dan Industri Besar. Demikian juga berdasarkan asal produk lokal maupun
impornya, karena jika di kategorikan berdasarkan kategori potongan daging
yang dikonsumsi maka proporsi konsumsi berdasarkan urutan terbesar sampai
terkecil adalah; Daging sapi olahan (kornet/sosis/bakso/lainnya) sebesar
31,49%; potongan primer (26,30%); jeroan (14%); potongan sekunder
(11,18%); daging variasi (9,53%); dan kulit (7,5%).
Angka konsumsi rumah tangga tersebut pada akhirnya menyepakati simulasi
perhitungan yang dilakukan melalui sisi industri, yang memproyeksikan
kebutuhan daging sapi nasional (lokal maupun impor) berdasarkan kategori
industri (HoReKa, Supermarket/Hypermarket, UMKM, dan Pasar Tradisional)
mencapai angka 629.644,1ton< x<695.922,1 tonper tahun 2013 (Survey Potensi
Demand Daging Sapi, LSM FEUI – Kemendag RI, 2013).
Tabel 6.1.Proyeksi Permintaan Daging Sapi Lokal dan Impor
Sumber : Olahan Data Primer, Survei Potensi Demand Daging Sapi (LSM FEUI – Kemendag RI,
2013)
3. Analisis preferensi konsumsi terhadap kualitas pangan, khususnya untuk
masyarakat dengan kelas ekonomi menengah keatas yang dapat digunakan
untuk memprediksi kualitas makanan yang dibutuhkan dalam 5 tahun
mendatang.

114
a. Preferensi Konsumsi Daging Sapi Masyarakat Kelas Ekonomi Menengah Atas.
Persepsi konsumen rumah tangga terhadap kemandirian pasokan dan stabilitas
pasokan untuk komoditi daging sapi dapat dikatakan sangat negatif. Persepsi
yang serupa juga dimiliki oleh pengusaha yang bisnisnya terkait dengan pasokan
daging sapi. Hal ini mencerminkan kondisi kelangkaan pasokan daging, serta
simpang-siurnya informasi dan data jumlah populasi sapi secara nasional.
Konsumen dan pebisnis merasa bahwa kejadian tersebut merupakan gambaran
nyata dari kondisi pasokan daging sapi nasional. Padahal jika ditilik dari angka
impor, sapi lokal masih menjadi sumber utama pasokan. Sapi impor hanya
menyumbang sekitar 15% dari pasokan sapi nasional. Dengan kata lain, yang
dikhawatirkan (dipersepsikan negatif) oleh konsumen dan pebisnis lebih kepada
tren pasokan jangka panjang.
Ukuran persepsi terhadap ketahanan pangan juga perlu mempertimbangkan
keterjangkauan (affordability) komoditi dan kualitas (quality) komoditi tersebut.
Penelitian ini menunjukan bahwa keterjangkauan harga untuk komoditi daging
sapi dipersepsikan tidak baik oleh konsumen. Hal ini wajar mengingat harga
daging sapi terus naik dengan signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Harga daging sapi saat ini menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara
dengan harga daging sapi tertinggi di dunia. Sementara, persepsi konsumen
terhadap kualitas daging sapi yang mereka konsumsi cenderung netral.
Konsumen mempersepsikan bahwa daging sapi yang mereka konsumsi aman,
termasuk dari berbagai penyakit yang selama ini sering dihadapi oleh negara
lain. Indonesia masih bisa menjaga dari penyakit yang menjangkiti sapi di luar
negeri, seperti penyakit gigi dan mulut.
Meski demikian, ditunjukan bahwa persepsi pengusaha terhadap kualitas daging
sapi justru lebih rendah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, hal ini lebih
terkait pada kemampuan rantai pasokan (terutama RPH) untuk menyediakan
potongan daging yang mereka inginkan. Belum banyak RPH di Indonesia yang
memiliki kemampuan memotong daging sesuai standar internasional, seperti
yang dibutuhkan oleh hotel, restaurant maupun konsumen spesifik lainnya.
b. Preferensi Konsumsi Daging Sapi Industri.
Preferensi konsumsi daging sapi untuk industri berbeda ketika mengkonsumsi
daging lokal dan daging impor. Berdasarkan penggalian lebih lanjut, determinan
dari perbedaan preferensi ini adalah: harga, kualitas daging dan stabilitas
pasokan. Harga potongan primer untuk daging impor relatif lebih tinggi
dibandingkan daging lokal. Hal ini terkait dengan preferensi konsumen di negara
pengekspor (i.e. Australia), dimana permintaan terhadap potongan primer
sangat dominan, sementara potongan lain kurang populer (bahkan beberapa
jenis potongan, seperti jeroan dan potongan lain-lain, dianggap kurang layak

115
dikonsumsi manusia). Hal ini membuat harga potongan primer untuk daging
impor relatif lebih tinggi dibandingkan harga potongan primer dari daging lokal.
Sebaliknya, harga potongan lain seperti potongan sekunder dan potongan variasi
dari daging impor relatif jauh lebih murah dibandingkan potongan yang sama
dari daging lokal.
Supermarket/Hypermarket menjadi konsumen terbesar untuk daging industri
lokal. Hal ini diduga sebagai reaksi konsumen rumah tangga terhadap harga
daging dengan jenis potongan primer, sekunder dan variasi yang cukup tinggi.
Konsumen rumah tangga (masyarakat) kemudian beralih ke jenis daging
industri yang harganya lebih murah. Pergeseran perilaku ini diantisipasi dan
dilayani oleh Supermarket/Hypermarket. Hal ini ditunjukkan dari jenis daging
industri (lokal dan impor) yang paling banyak diminta oleh
Supermarket/Hypermarket adalah hindquarter dan forequarter. Baik
hindquarter maupun forequarter bisa digunakan sebagai substitusi potongan
primer atau sekunder untuk memasak menu masakan khas Indonesia seperti
rawon, soto, dan sebagainya.
Temuan menarik lainnya terkait dengan kecenderungan industri pengolahan
untuk menggunakan jeroan sebagai bahan baku mereka. Sumber pasokan utama
jeroan untuk industri besar adalah daging impor, dimana harga jeroan daging
impor relatif sangat murah. Sementara konsumen terbesar jerohan daging impor
lainnya adalah supermarket/hypermarket. Sama dengan daging industri, jerohan
menjadi alternatif substitusi bagi konsumen rumah tangga semenjak harga
daging (terutama potongan primer dan sekunder) melonjak tajam.
4. Menganalisa rantai pasokan, respons persediaan, dan respons produksi untuk
mengembangkan rekomendasi yang menjembatani sisi persediaan dan sisi
permintaan.
Berdasarkan analisis terhadap rantai pasokan dan tata niaga yang saat ini telah
berlaku untuk komoditi daging sapi, telah terindentifikasi 3 (tiga) permasalahan
utama, yakni 1) Rendahnya pertumbuhan populasi sapi nasional; 2) Lemahnya
peran RPH; 3) Kuatnya jaringan pedagang besar di daerah, dan; 4) Distribusi
yang tidak efisien karena buruknya infrastruktur.
Ketiga tantangan tersebut dapat dijawab dengan tiga strategi, yakni melalui
kebijakan breeding (pembibitan)sapi nasional untuk memenuhi pasokan sapi
lokal, lalu strategi optimalisasi protein hewani lokal dan strategi revitalisasi
pasar hewan sebagai pasar komoditi. Kebijakan pembibitan berskala nasional ini
diperlukan sebagai reaksi dari aksi pemotongan sapi lokal (terutama sapi betina
produktif) yang kontinu dalam jumlah besar. Jika breeding tidak segera
dilakukan dan dikontrol sebagai intervensi pemerintah, maka stok sapi lokal
semakin lama akan semakin habis.

116
Strategi optimalisi protein hewani lokalbertujuanuntuk mengurangi
ketergantungan daerah tersebut terhadap pasokan daging sapi dari daerah lain,
sehingga sumber protein untuk masyarakat di daerah tersebut lebih sustainable.
Misalnya, daerah pesisir perlu mengoptimalkan sumber protein dari hasil laut.
Begitu juga dengan daerah di sepanjang aliran sungai besar dan danau,
diharapkan bisa mengoptimalkan sumber protein dari perairan.
Untuk itu, kearifan lokal perlu dikembalikan lewat intervensi sosial oleh
pemerintah. Diantaranya adalah dengan mempromosikan makanan lokal yang
menggunakan sumber protein yang gampang ditemukan atau diternakkan di
daerah tersebut. Ini harus menjadi unggulan strategi untuk meningkatkan
ketahanan pangan nasional. Selain itu, hal ini akan meningkatkan efisiensi rantai
pasokan komoditas bahan pokok, karena saluran distribusi menjadi lebih
pendek. Jumlah perantara menjadi lebih sedikit, dan waktu maupun jarak
tempuh menjadi lebih rendah.
Strategi ketiga terkait dengan kebutuhan menjadikanpasar hewan yang dikelola
sebagai pasar komoditi yang modern dan fair. Selama ini peternak tidak
mendapatkan informasi yang sempurna mengenai jumlah permintaan dan harga.
Perolehan informasi didominasi oleh blantik atau pedagang, sehingga marjin
keuntungan tertinggi dinikmati oleh perantara, bukan oleh peternak. Pasar
hewan bisa menjembatani kesenjangan informasi ini, sehingga tercapai
perdagangan yang menguntungkan semua pihak.
6.2. Rekomendasi untuk RPJMN 2015 – 2019
6.2.1. Arah Kebijakan
Dalam blue print program swasembada daging sapi (PSDS) tahun 2014 yang sudah di
revisi tahun 2012, beberapa program yang akan dilakukan untuk mencapai
swasembada adalah penyediaan bakalan sapi dan kerbau, peningkatan produktivitas
dan reproduktivitas sapi lokal, pengendalian sapi/kerbau betina produktif, penyediaan
bibit sapi/kerbau lokal dan pengaturan stock daging sapi/kerbau dalam negeri.
PSDS-2014 juga diharapkan berlangsung secara berkelanjutan, artinya, swasembada
tidak hanya terlaksana pada tahun 2014, tapi juga diharapkan berlangsung selamanya.
Swasembada daging secara langsung akan berdampak positif pada pemerintah dalam
bentuk penghematan devisa, dan bagi para peternak akan merasakan dampak
positifnya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja yang pada gilirannya akan memberi
dampak peningkatan kesejahteraan peternak dan berdampak lanjutan pada
peningkatan perekonomian di pedesaan.
Dalam perkembangannya, target yang dibangun dalam PSDS 2014 ini beresiko tidak
memenuhi target. Meskipun berbagai kegiatan yang mengarah pada produktivitas telah
dilakukan di banyak provinsi dengan jumlah anggaran yang besar, namun hasil sensus

117
pertanian menunjukkan adanya penurunan populasi ternak sapi sebesar 15% dalam
dua tahun terakhir (BPS, 2013). Hal ini antara lain disebabkan oleh terus
berlangsungnya pemotongan sapi betina produktif pelaku industri di indonesia. Dari
jumlah sapi yang dipotong, 60% – 80% merupakan sapi betina produktif. Ini
merupakan kontradiksi, karena sapi betina produktif seharusnya bukan menjadi
produk akhir, melainkan komoditi yang bisa melipatgandakan populasi sapi.
Pada aspek budidaya ternak, keterbatasan yang dimiliki peternak membuat banyak sapi
yang terabaikan, sehingga kondisi sapi yang dihasilkan tidak mencapai berat yang layak.
Sebagian besar peternak tidak berorientasi berbisnis, dan hanya sekadar memelihara
ternak serta menjadikannya aset yang mudah untuk ditukar dengan uang pada saat
dibutuhkan. Berangkat dari fakta tersebut, nyaris tidak ada perencanaan dalam usaha
peternakan karena nyatanya mayoritas peternak hanya memiliki 2-3 ekor sapi.
Dapat dimaklumi, karena selain permasalahan waktu yang panjang, faktor biaya
(modal) juga menjadi bahan pertimbangan bagi peternak. Butuh waktu panjang dari
mulai sapi dalam masa partus (9 bulan), sampai menjadi sapi siap potong (2-4 tahun).
Hal ini sangat terkait dengan faktor biaya yang sangat besar baik untuk pakan,
operasional maupun tenaga kerja. Fakta ini yang menjadi penyebab kebanyakan
peternak kita hanya menjadikan aktivitas beternak sebagai pekerjaan sambilan.
Secara makro, Indonesia tidak memiliki sapi lokal berkualifikasi bibit. Kurangnya
pemahaman tentang bibit melahirkan anggapan di kalangan peternak bahwa betina
produktif cukup dianggap sebagai bibit, atau sapi dengan postur tubuh besar disebut
sebagai bibit yang bagus sehingga sapi silangan yang pada umumnya berpostur lebih
besar dianggap lebih unggul dibandingkan sapi lokal.
Dari sisi distribusi, rantai yang cukup panjang dari peternak sampai ke rumah potong
hewan (RPH) telah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Selanjutnya, pada mata rantai
RPH, pola penyembelihan sapi masih dianggap sangat tidak standar dan jauh dari
pemenuhan prinsip kesejahteraan hewan. Belum lagi dugaan kecurangan para tukang
daging di RPH ketika melakukan proses penyembelihan sapi sampai distribusi daging
ke pasar tradisional. Hal ini ditengarai terkait dengan ketidakberdayaan petugas
pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengelola RPH sehingga kondisi RPH
makin hari selalu makin memburuk. Hal yang tidak kalah penting adalah tidak
akurasinya informasi tentang sapi, seperti bangsa sapi, bobot badan saat potong, dan
bobot karkas yang diterbitkan petugas RPH karena tidak diterapkannya standar yang
telah digariskan pemerintah.
Gambaran di atas menunjukkan kompleksitas pengelolaan sapi oleh peternak.
Ironisnya, data ini yang dijadikan sebagai landasan dalam menyusun strategi nasional,
termasuk strategi menuju swasembada daging sapi. Berdasarkan kondisi tersebut,
setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya pencapaian swasembada:
di bagian hulu adalah 1) mayoritas usaha peternakan adalah petani kecil dengan skala

118
kepemilikan 1-3 ekor yang tidak berorientasi bisnis, 2) Manajemen peternakan yang
masih sederhana, 3) produktivitas yang masih rendah, dan 4) manajemen yang masih
tradisional.
Sementara itu, tantangan di bagian hilir adalah 1) pasar yang semakin terbuka terhadap
produk/daging impor, 2) Belum terintegrasinya kegiatan industri dengan penggemukan
sapi, bahkan cenderung menggunakan produk impor karena relatif mudah didapatkan
dengan harga yang lebih kompetitif, 3) Preferensi konsumen terutama di restoran
daging dan supermarket lebih menyukai daging sapi impor.
Ke depannya, kebutuhan daging sapi dan sapi potong lokal maupun impor bisa tetap
harus mengutamakan dipenuhi melalui ekstensifikasi pembibitan sapi lokal. Namun
perlu dipertimbangan masa menunggu panen yang cukup lama. Sehingga untuk mengisi
kekosongan yang terjadi pada saat proses pembibitan diperlukan adanya kebijakan
untuk memenuhi supply sapi potong, salah satunya adalah impor sapi bakalan. Impor
sapi bakalan lebih disarankan dibandingkan impor sapi siap potong, untuk memberikan
nilai tambah kepada pelaku usaha dalam negeri, dan tidak sekaligus memukul peternak
sapi lokal yang terlanjur melakukan breeding atau mekanisme usaha menggunakan
harga pasaran baru yang terbentuk pasca kelangkaan sapi.
6.2.2. Strategi dan Fokus Prioritas
Secara mendasar dan terukur harus dilakukan program breeding (pembibitan) sapi
lokal secara masif dan berskala nasional. Strategi ini merupakan respon terhadap
persoalan situasi kelangkaan stok sapi lokal selama kurun waktu setahun terakhir.
Pelaku usaha merasakan selama kurun waktu setahun ini semakin sulit mendapatkan
pasokan sapi, baik usia bibit, bakalan maupun siap potong. Belum lagi kompetisi harga
yang sangat tinggi sehingga beresiko menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan
pelaku usaha lain. Jika breeding tidak segera dilakukan dan dikontrol sebagai intervensi
pemerintah, maka stok sapi lokal semakin lama akan semakin habis.
Program breeding secara khusus harus ditangani oleh lembaga tersendiri, dan tidak
bisa lagi mengandalkan kemampuan peternak semata karena berhadapan dengan
jangka waktu produksi dan perhitungan bisnis pembibitan yang tidak menjanjikan.
Dalam hal ini, pemerintah harus memaksimal peran balai benih dan bibit unggul yang
tersebar di sejumlah daerah.
Berbeda dengan konsep ekonomi bisnis dimana suatu investasi yang high risk akan
berdampak pada high return, maka proses breeding sapi dinilai sebagai bisnis yang high
risk-low return-long time. Hal ini yang menyebabkan makin sedikit pelaku usaha sapi
yang fokus di area pembibitan. Selama ini, mekanisme pembibitan masih mengandalkan
kemampuan peternak lokal/rakyat untuk menjalankannya karena bisa dijalankan
berbarengan dengan kegiatan bertani dan “mengisi waktu luang”.Secara perhitungan

119
bisnis, upaya pembibitan sapi tidak menguntungkan dan cenderung merugi, apalagi jika
tidak mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah.
Potensi besar yang bisa dimaksimalkan adalah program breeding inisiatif oleh feedloter
dalam jumlah besar untuk mempertahankan supply. Mayoritas feedloter berskala besar
sudah memiliki teknologi handal untuk menjalankan program breeding dan
menghasilkan bibit sapi berkualitas baik. Mereka juga umumunya didukung oleh
kondisi lahan yang masih luas dan pasokan pakan yang lebih dari cukup, sehingga
menjadi modal utama untuk mengembangbiakan sapi berskala masif.
Prinsip ketahanan pangan harus tetap mengutamakan peran peternak kecil sehingga
upaya pembibitan harus tetap memberi ruang bagi peternak dalam menjalan upaya
penambahan populasi sapi lokal dan juga memastikan roda ekonomi mereka tetap
berjalan.Pembibitan oleh peternak harus dijalankan secara berkelompok untuk
memudahkan dalam pendampingan manajemen dan monitoring populasi. Secara
mendasar harus dijalankan upaya penguatan kelompok peternak rakyat untuk
melakukan breeding massal secara intensif, dengan memaksimalkan dukungan
pendanaan dari Bank dan kerjasama pengadaan pakan dari perusahaan feedloter.
Penguatan kelompok peternak juga akan menjadi “entry point” dalam membangun data
base stok populasi sapi secara terukur dan berkesinambungan. Ke depannya, jika
pembibitan oleh kelompok peternak ini berjalan sempurna maka akan memudahkan
bagi pemerintah untuk monitoring stok sapi karena populasi terukur sudah tercatat di
masing-masing kelompok dan untuk itu sedari awal harus dibangun sistem informasi
pasokan sapi di setiap desa.
Dalam rangka memastikan pertumbuhan jumlah pasokan sapi lokal dan mendukung
kebijakan breeding sapi lokal secara masif, maka pemerintah idealnya mulai
membangun rencana program penomoran dan identifikasi sapi. Di sisi peternak
pemerintah dapat melakukan intervensi dalam bentuk registrasi sapi sejak lahir oleh
pemerintah daerah. Setiap sapi memiliki nomor identitas yang tercatat secara resmi.
Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir pengulangan penghitungan sapi beredar di
pasar hewan. Selain itu, penomoran atau registrasi ini dapat menjadi alat kontrol untuk
mencegah/mengurangi pemotongan sapi betina produktif.
Intervensi pemerintah di RPH dapat berupa pencatatan sapi potong berdasarkan nomor
registrasi tersebut untuk memperkirakan stok daging sapi yang akan beredar di pasar.
Pencatatan tersebut juga dapat digunakan untuk melihat pemotongan sapi secara ilegal
yang dilakukan diluar RPH.Pihak terdepan yang bisa dilibatkan adalah para penyuluh
pertanian lapangan (PPL). Normatifnya, setiap ekor sapi yang akan dijual dan keluar
dari suatu desa harus mendapatkan saurat pengantar. Tetapi prasyarat ini tampaknya
belum dijalankan maksimal. Karena itu, selain bertugas meng-update sapi-sapi yang
diperjual belikan, peran PPL juga bisa ditambahkan untuk membangun dan
menjalankan sistem identitas dan nomor sapi sejak dilahirkan.

120
Pencatatan identitas sapi melalui sistem barcode sejatinya sudah dijalankan untuk sapi
bakalan impor yang digemukan oleh feedloter di Indonesia. Melalui barcode ini maka
pergerakan sapi bisa dipantau secara jelas dan terukur. Merujuk pada hal ini, maka ide
penomoran dan identitas sapi lokal bisa meniru model yang diterapkan pada sapi
bakalan impor.
Ketika kebijakan pembibitan nasional dijalankan, di saat bersamaan laju permintaan
akan daging sapi tetap akan terus tumbuh. Menghadapi situasi ini maka pilihan strategis
yang paling terukur dan cepat untuk memenuhi stok sapi nasional adalah melalui
kebijakan impor sapi bakalan. Kebijakan mengimpor sapi bakalan merupakan “trigger”
dalam menyeimbangkan sekaligus menstabilkan harga pasaran sapi hidup lokal. Sapi
bakalan impor diharapkan dapat menambah jumlah pasokan sapi yang ada di pasaran,
sehingga variasi perebutan sapi lokal dan impor seimbang dengan demikian harga jual
sapi hidup dan potongan daging yang beredar dapat kembali stabil.
Dalam kebijakan impr sapi bakalan ini harus diperhitungkan masa penggemukan sapi
bakalan impor hingga siap menjadi sapi potong, juga mekanisme harga pasar yang
sudah terbentuk saat ini, dimana peternak sudah mulai membibit sapi lokal dengan
harga pasar yang tinggi.Selain itu, kebijakan importasi sapi bakalan harus diawali
dengan revitalisasi RPH karena kondisi kekinian mayoritas RPH belum memenuhi
kelayakan untuk memotong sapi impor.
Mekanisme distribusi daging sapi impor yang sangat ekslusif juga akan memudahkan
pemerintah untuk mengawasi supply chain yang terbentuk. Pasokan sapi tercatat dari
jumlah sapi impor yang masuk ke RPH lolos audit, sehingga jika sapi tersebut
diproduksi menjadi potongan daging sapi, dapat diketahui stok opname yang tersedia
untuk menjawab permintaan daging sapi yang ada di Indonesia. Dalam titik ini,
pemerintah bisa menetapkan dan mengawasi harga referensi potongan daging mulai
dari feedlotter, lalu ke bandar daging di RPH hingga ke pengecer daging. Sistem supply
chain sapi impor yang cenderung tertutup sangat mendukung bagi pemerintah untuk
monitoring secara ketat terhadap pergerakan harga daging dari sapi bakalan impor.
Terkait dengan kebutuhan pengendalian harga, maka kebijakan tata niaga sapi
berdasarkan harga referensi harus dijalankan secara terukur dan mempertimbangkan
aspek ekonomis bagi peternak yang merupakan pemilik terbesar populasi sapi di
Indonesia.Harga referensi akan menjadi harga keseimbangan baru sepanjang jumlah
pasokan sapi (lokal dan impor) ditambah dan menjamin kebutuhan pelaku usaha sapi.
Kesinambungan stok pasokan menjadi prasyarat utama untuk mencapai harga
keseimbangan ini. Kondisi lain yang harus terpenuhi adalah memastikan simpul-simpul
tata niaga seperti pasar hewan dan RPH bisa berjalan dengan dan mendukung
penambahan supply tersebut.
Harga referensi akan terbentuk sepanjang bisa terbangun harga keseimbangan agar
tidak merugikan para pelaku usaha. Prinsip awalnya, feedlotter akan mengikuti harga

121
sapi lokal di pasar hewan, untuk selanjutnya diseimbangkan dengan harga jual ke jagal
(bandar daging). Persoalannya jika harga dari supplier/pemasok (belantik) sudah
mahal, maka jagal akan membeli lebih mahal lagi dari feedlotter dan akhirnya
menanggung kerugian. Intinya, harus tercipta keseimbangan agar setiap pelaku (rantai)
bisa berjalan. Jadi pemegang kuncinya di harga awalan pemasok, nanti tinggal
disesuaikan harga jual ke pasar/jagal. Jadi feedlotter harus bisa menjaga keseimbangan,
di satu sisi tidak menekan petani, di sisi lain bagaimana supplyernya (belantik) tetap
bisa untung, dan para jagal juga tetap bisa dapat untung.
Proses mencapai harga referensi ini juga harus dijalankan secara perlahan (tidak bisa
drastis) agar tidak menimbulkan keguncangan di pelaku usaha, terutama peternak yang
sudah membeli sapi di harga mahal, padahal biaya produksi mereka berasal dari
pinjaman di bank. Sejak awal juga harus ada upaya untuk meminimalkan praktek re-
seller oleh belantik di pasar hewan. Ketika sapi perjualbelikan berulangkali di satu atau
antar pasar hewan maka semakin panjang jalur tata niaga yang tercipta,
konsekuensinya akan menaikan harga sapi di pasaran.
Upaya lain untuk mencapai harga referensi adalah memastikan penggunaan alat
timbangan sebagai media utama dalam perhitungan bobot/berat sapi di pasar hewan.
Kondisi terkini menunjukan bahwa belum banyak pelaku usaha yang bersedia yang
menggunakan alat timbangan dalam menghitung berat sapi ketika bertransaksi.
Langkah strategis lain adalah memaksimalkan peran bandar daging untuk mau dan
selalu memotong sapi di RPH. Selain untuk menjamin terpenuhinya standar kebersihan
potongan daging agar aman untuk dikonsumsi, juga akan tersaji data faktual mengenai
jumlah sapi potong setiap harinya. Selain itu, bagi para bandar daging yang sudah
memotong sapinya di RPH akan relatif lebih mudah untuk dipantau dan “dikendalikan”
pergerakan harga potongan daging yang akan mereka jual ke pengecer di pasar
tradisional dan supermarket.
Di masa mendatang kebutuhan akan konsumsi daging dan protein hewani tidak bisa
lagi mengandalkan pemenuhan dari daging sapi dengan mempertimbangkan tantangan
untuk penyediaan stok sapi lokal yang sangat sulit. Terdapat 2 (dua) hal yang perlu
ditinjau sebagai landasan untuk melakukan intervensi terhadap pola konsumsi daging
sapi nasional pada tingkatan konsumen rumah tangga maupun konsumen industri.
Pertama, pola konsumsi daging sapi di masa mendatang perlu mempertimbangkan
proporsinya dalam ‘piring’ konsumen (in plate nutrition composition). Saat ini daging
sapi telah cukup masih mendominasi proposi bahan makanan dalam menu masakan
masyarakat Indonesia. Proporsi ini perlu sedikit demi sedikit dikurangi, digantikan
dengan bahan makanan hewani (kerbau, kambing dan jenis-jenis unggas) yang
melimpah di daerah setempat.
Kedua, perlu diketahui elastistas preferensi konsumen untuk melakukan substitusi
daging sapi dengan sumber protein lainnya. Penelitian ini menunjukanbahwa terdapat

122
delapan sumber protein yang dianggap bisa menjadi substitusi, yaitu: ikan air tawar,
ikan laut, daging ayam, daging kambing, daging kerbau, daging ayam, daging unggas,
daging kuda, tahu tempe, dan lain-lain. Penggunaan berbagai macam sumber protein ini
telah ada di masing-masing kuliner lokal, sehingga tidak terlalu sulit untuk
dilakukannya intervensi demi mendorong konsumsi sumber-sumber protein alternatif
tersebut.
Yang menjadi permasalahan, preferensi dari konsumen industri terhadap substitusi
daging sapi terbatas pada empat sumber protein: daging ayam, daging kerbau, daging
kambing, dan daging unggas. Preferensi konsumen industri ini penting untuk dicermati,
mengingat mereka adalah konsumen terbesar dari daging sapi segar. Perlu ada langkah
untuk menyiapkan alternatif sumber protein selain daging sapi, yang bisa digunakan
oleh industri pengolahan makanan, tentunya dengan mempertimbangkan rasa dan
kualitasnya.
6.2.3. Sasaran dan Indikator
Indikator penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan ketahanan pangan adalah
kemampuan untuk melakukan penambahan jumlah populasi sapi lokal secara terukur
dan masif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Di dalamnya yang menjadi tolok
ukur adalah perluasan daerah basis produksi dan penambahan stok sapi lokal baik yang
dimiliki oleh peternak maupun perusahaan feedlotter yang juga memegang simpul
dalam upaya pembibitan sapi. Terkait dengan indikator di atas, maka harus ada
keseriusan pemerintah untuk memberikan dukungan insentif, baik pembiayaan
maupun kemudahan berbisnis bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam tata niaga
daging sapi.
Cita-cita untuk mencapai ketahananpangan juga membutuhkan berbagai kegiatan
Penelitian dan Pengembangan.Harus terjadi peningkatan sosialisasi oleh pemerintah
yang ditindaklanjuti dalam bentuk penerapan benih sapi unggul bersertifikat oleh
peternak. Kegiatan-kegiatan ini yang mencerminkan diterapkannya bentuk peternakan
yang tingkatkeberhasilannya dapat dikur melalui pengamatan atas produktivitas,
efisiensi, mutu dan kontinyuitas pasokan yang terus menerus, meningkat serta
terpelihara. Intervensi pemerintah sangat strategis dalam wujud memastikan bahwa
rantai tata niaga sapi berjalan secara sehat melalui mekanisme control harga referensi
untuk terwujudnya iklim bisnis perniagaan sapi yang mampu memberikan nilai tambah
ekonomi untuk semua pelaku usaha di dalamnya.
Pengembangan produksi sapi lokal juga akan terlihat melalui ketersediaan anggaran
pembangunan dan penyediaan sistem insentif yang dialokasikan untuk mendorong
peningkatan produksi dan pendapatan pelaku usaha terutama peternak kecil sebagai
kelompok usaha mayoritas. Memperbanyak akses terhadap sumber permodalan formal
beserta skema bantuan yang ditawarkan dilengkapi dengan memperluas cakupan
masing-masing skema bantuan tersebut.

123
DAFTAR PUSTAKA
Adiyoga, W., M. Ameriana dan A. Hidayat. 1998. Efisiensi tataniaga dan informasi harga
bawang merah. Laporan Hasil Penelitian, Balai Penelitian Tanaman Sayuran,
Lembang-Bandung : 26 h.
Aldrian E, Susanto RD (2003) Identification of three dominant rainfall regions within
Indonesia and their relationship to sea surface temperature. Int J Climatol 23:
1435–1452
Amerina, M., W.G. Koster dan A. Asgar. 1991. Pemasaran Bawang Merah : Analisa
Praktek Grading Sebagai Dasar Untuk Standarisasi Kualitas. Bul.Penel.Hort. XX. EK
(1) : 39-48.
Amerina, M., W.G. Koster dan A. Asgar. 1991. Pemasaran bawang merah : analisa
praktek grading sebagai dasar untuk standarisasi kualitas. Bul.Penel.Hort. XX. EK
(1) : 39-48.
Arifin, Bustanul (2004), Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia, Jakarta: Kompas.
Arifin, Bustanul, A. Munir, E. Sri Hartatai dan Didik J. Rachbini (2001), “Food Security
and Markets in Indonesia: State and Market Interaction in Rice Trade”, Quezon
City: MODE Inc.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2013), “Keunggulan Varietas Kedelai
di Kabupaten Grobogan” Kementrian Pertanian Republik Indonesia.
Badan Pusat Statistik (2013), “Sensus Pertanian 2013”, Jakarta.
Badan Pusat Statistik. (2010), “Sensus Penduduk”, Jakarta
Badan Pusat Statistik. (2013), “Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai”, Jakarta.
Bank Indonesia. (2007), “BOKS 1. Pola Pembentukan Harga Beras di Jawa Barat”.
Basuki, R.S. 1987. Efisiensi Sistem Pemasaran Cabe (Capsicum annum L.) : Studi Kasus
Di Pasar Tanjung Brebes. Bul.Penel.Hort. XV (4) : 81-85.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian (2006), “Potensi
Pertanian Indonesia”, Jakarta.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (2013), “Potensi Pertanian Padi di Kalimantan
Barat”, Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

124
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (2013), “Potensi Pertanian Padi di Kalimantan
Selatan”, Kementrian Pertanian Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (2013), “Potensi Pertanian Padi di Provinsi Bali”,
Kementrian Pertanian Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (2013), “Potensi Pertanian Padi di Nusa Tenggara
Timur”, Kementrian Pertanian Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (2013), “Potensi Pertanian Padi di Nusa Tenggara
Barat”, Kementrian Pertanian Republik Indonesia.
Djulin, Adimesra (2004), “Analisis Sistem Distribusi Gabah/Beras di Sumatera Barat”,
dalam Handewi P. Saliem, Saptana and Edi Basuno (ed.), Prospek Usaha Dan
Pemasaran Beberapa Komoditas Pertanian, Monographs Series No.24, Bogor:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian
dan Pengembangan Pertanian.
Esmay, M. L. 1982. Principle of Animal environmental. Connecticut: AVI Publishing
Company, Inc.
Food And Agriculture Organization (FAO). (2013), “Food And Agricultural Price
Statistics”.
HamadaJI,YamanakaMD,MatsumotoJ,FukaoS,WinarsoPA,Sribimawati T (2002) Spatial
and temporal variations of the rainy season over Indonesia and their link to
ENSO. J Meteor Soc Japan 80: 285–310
Hendayana, Rachmat. Hidayat, Deri. (1999), “Pemasaran dan Distribusi Hasil Pertanian
di Lahan Rawa Pasang Surut Sumatera Selatan”, Lembaga Penelitian Tanaman
Pangan Puntikayu, Palembang.
Ingram, D.L. & M.J. Dauncey. 1985. Thermoregulatory Behavior. In: Stress Physiology of
Livestock. Vol. 1. Yousef (Ed),. Florida: CRC Press, Inc.
Jasis dan Karama, A. S. 1998. Kebijakan Departemen Pertanian Dalam Mengantisipasi
Penyimpangan Iklim. Prosiding Stategi Antisipatif Menghadapi Gejala Alam La
Nina dan El-Nino. Kerjasama PERHIMPI dengan Jurusan GEOMET-IPB Puslittanak
dan ICSEA.
Jones, G.M. & C.C. Stallings. 1999. Reducing heat stress for dairy cattle. Virginia
Cooperative Extension. Publication Number 404-200.
http://www.ext.vt.edu/index.html. [21 Oktober 2005].
Koster, W.G. 1990. Exploratory survei on : shallots in rice-based cropping systems in
Brebes. Bul.Penel.Hort. XVIII. EK (1) : 19-30.

125
Koster, W.G. and R.S. Basuki. 1991. The structure, performance & efficiency of the
shallot marketing system in Java. Internal Communication LEHRI/ATA-395 No. 35
: 132 h.
McDowell, R.E. 1972. Improvement of Livestock Production in Warm Climate. San
Frascisco: W.H. Freeman and Co.
McDowell, R.E. 1974. The Environment Versus Man and His Animals. In: H.H. Cole & M.
Ronning (Eds.). San Fransisco: Animal Agriculture. W.H. Freeman and Co.
McSweeney, C., New, M. & Lizcano, G. 2010. UNDP Climate Change Country Profiles:
Indonesia.Available:http://www.geog.ox.ac.uk/research/climate/projects/undp-
cp/UNDP_reports/Indonesia/Indonesia.hires.report.pdf (diakss 31 Desember
2013)
Natawidjaya, Ronnie S. (2000), "Pengembangan Sistem Intelijen Pasar sebagai Usaha
Monitoring Kelancaran Arus Distribusi Bahan Makanan Pokok Dalam Menunjang
Penyediaan Kebutuhan Pangan Masyarakat yang Efektif dan Efisien", Laporan
Tahunan Riset Unggulan Terpadu (RUT), Menristek, DRN dan LIPPI, Jakarta.
Natawidjaya, Ronnie S. (2001), "Dinamika Pasar Beras Domestik", dalam Suryana,
Achmad dan Sudi Mardianto (penyunting), Bunga Rampai Ekonomi Beras,
Penerbit LPEM-UI, Jakarta.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012), “Country Statistical
Profile: Indonesia”, Country statistical profiles: Key tables from OECD.
Putra, Sindhu Hanggara. (2007), “Analisis Aspergillus flavus Pada Berbagai Tingkat
Distribusi Jagung Sebagai Bahan Baku Pangan (Studi Kasus di Bogor dan
Boyolali)”, Institut Pertanian Bogor.
Saliem, Handewi P. (2004), “Analisis Marjin Pemasaran: Salah Satu Pendekatan Dalam
Sistem Distribusi Pangan”, dalam Handewi P. Saliem, Saptana and Edi Basuno
(ed.), Prospek Usaha Dan Pemasaran Beberapa Komoditas Pertanian, Monographs
Series No.24, Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi
Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Samadi, B. 1996. Pembudidayaan tomat hibrida : teknik pengembangan untuk usaha
komersial. CV. Aneka, Solo : 96-103.
Siaran Pers. (2013), “Gambaran Harga Kedelai Di Setiap Titik Rantai Pasok”, Kementrian
Perdagangan Republik Indonesia.
Smith et al. 2001, Drinking water requirements for lactating dairy cows. http://krex.k-
state.edu/dspace/handle/2097/6880 (diakses 27 Des 2013)

126
Soetiarso, T.A. 1995. Deskripsi kualitas, pengkelasan dan pemasaran cabai merah di
tingkat pasar grosir. Dalam Duriat, A.S., R.S. Basuki, R.M. Sinaga, Y. Hilman dan Z.
Abidin (Eds.). Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Sayuran. Balai Penelitian
Tanaman Sayuran, bekerjasama dengan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia
Komda Bandung dan Ciba Plant Protection, Lembang : 568-674.
Soetiarso, T.A. 1996. Usahatani dan pemasaran cabai merah. Dalam Duriat, A.S., A. W. W.
Hadisoeganda, T.A. Soetiarso dan L. Prabaningrum (Eds.). Teknologi produksib
cabai merah. Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Bandung : 85-101.
Soetiarso, T.A. 1997. Analisis Usahatani Dan Pemasaran Tomat. Dalam Duriat, A.S., W.W.
Hadisoeganda, A.H. Permadi, R.M. Sinaga, Y. Hilman, R.S. Basuki dan S.
Sastrosiswojo (Eds.). Teknologi Produksi Tomat. Balai Penelitian Tanaman
Sayuran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian. Bandung : 130-145.
Soetiarso. (1998), “Pemasaran Bawang Merah dan Cabai Merah”, Badan Penelitian Dan
Pengembangan Pertanian.
Sumarno. (2000), “Periodisasi Musim Tanam Padi Sebagai Landasan Manajemen
Produksi Beras Nasional”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan,
Bogor.
Supratna, Ade. (2005), “Analisis Sistem Pemasaran dan Gabah/Beras (Studi Kasus
Petani Padi di Sumatera Utara)”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial
Ekonomi Pertanian, Jawa Barat.
Supriyanto, Bambang. (2013), “Membangkitkan Kenangan Manis Negeri Agraris”, Bisnis
Indonesia (bisnis.com), 11 September 2013.
Swastika, DKS. Agustian, Adang. Sudaryanto, Tahlim. (2011), “Analisis Senjang
Penawaran Dan Permintaan Jagung Pakan Dengan Pendekatan Sinkronisasi Sentra
Produksi, Pabrik Pakan, Dan Populasi Ternak Di Indonesia” Departemen
Pertanian.
Tambunan, Tulus. (2008), “Tata Niaga dan Pengendalian Harga Beras di Indonesia”,
Kadin Indonesia
United Stated Department of Agriculture (USDA). (2012), “Indonesia Milled Rice
Production, Domestic Consumption, Exports, and Imports”.

127
United Stated Department of Agriculture (USDA). (2012), “Indonesia Maize Corn
Production, Domestic Consumption, FSI Consumption, Feed Domestic
Consumption, Exports, and Imports”.
Warsana. (2007), “Analisis Efisiensi Dan Keuntungan Usaha Tani Jagung (Studi Di
Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)”, Universitas Diponegoro, Semarang.
World Bank, http://data.worldbank.org/country/indonesia#cp_cc (diakses tanggal 31
Desember 2013)
Wyrtki K. 1956. The rainfall over the Indonesian waters. Verhandelingen, 49.
Kementrian Perhubungan Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Jakarta
Yousef, M.K. 1985. Thermoneutral Zone. In: M.K. Yousef (Ed.). Stress Physiology of
Livestock.Vol.II. Florida: CRC Press, Inc.