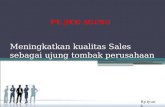SoehartodalamCerpen Indonesiafib.unair.ac.id/jdownloads/Penelitian/mozaik_1_isi.pdf · Pendahuluan...
Transcript of SoehartodalamCerpen Indonesiafib.unair.ac.id/jdownloads/Penelitian/mozaik_1_isi.pdf · Pendahuluan...

DAFTAR ISI
Moch Jalal1
Made Pramono9
Ida Nurul Chasanah
19
Nur Wulan
28
DiahArianiArimbi
36
Edi Dwi Riyanto
50
Purnawan Basundoro58
Sarkawi B Husain
67
Kontradisksi Logika Filsafat dengan Logika Simbolisasi Bahasa -
Etika Sosialisme Religius Bung Hatta -
Representasi Reaksi-Kreatif Literer atas Penguasa Orde Baru dalam KumpulanCerpen
Gender Relations in Late Colonial Indonesia: A Brief Overview and TheirPortrayal in Three Modern Indonesia Novels -
Politics and Social Representation in Literatures:AFeminist of Ratna IndraswariIbrahim’s Work -
Korelasi antara Pengguna Multimedia Komputer dengan Peningkatan SkorTOEFLPeserta UNAIR -
Menggagas Historiografi (Indonesia) yang Demokratis -
Resensi BukuKeroncong Cinta KaryaAhmad Faishal“Antara Cara Pemahaman, Cara Perhubungan, dan cara Penciptaan” -
Soeharto dalam Cerpen Indonesia -
SelfAcces


PendahuluanDalam kajian filsafat, eksistensi
Logika dapat diibaratkan sebagai ujungtombak yang kedudukannya sangatdikedepankan serta mendapatkan porsisorotan terpenting. Dikatakan demikian,mengingat dalam kegiatan berfilsafat,cara berpikir dan bernalar secara benarmerupakan syarat utama yang selalu harusdijunjung tinggi. Tata cara benalar danberpikir secara benar dan logis inilahyang kemudian lebih dikenal denganistilah logika. Secara singkat dapatdikatakan, logika merupakan ilmupengetahuan dan kecakapan untukberpikir lurus atau tepat. Mengingat ilmupengetahuan adalah kumpulan pe-ngetahuan tentang objek tertentu,kesa tuan yang sis temat i s , ser tamemberikan penjelasan yang dapatd ipe r t anggu ng jawabkan . Se ga l apenjabaran tentangnya harus dilakukandengan memberikan penjelasan mengenai
sebab musababnya. Aspek penjelasansebab musabab secara masuk akal danilmiah juga merupakan bidang logika.L a p a n g a n p e n g e t a h u a n l o g i k akefilsafatan secara umum yaitu meliputiasas-asas yang menentukan pemikiranyang lurus, tepat, dan sehat. Dalam hal inilogika menyelidiki, merumuskan, sertamenerapkan hukum yang harus ditepatiagar manusia dapat berpikir lurus, tepat,dan teratur. Popkin dan Stroll (Bawengan,1990: 64) berpendapat bahwa logikamerupakan salah satu cabang filsafat yangtergolong penting sekali. Semua bagianatau cabang-cabang filsafat tidak dapatlepas pada penggunaan pikiran atau caraberpikir. Apakah pikiran itu benar atauk e l i r u a k a n t e r g a n t u n g p a d apenyesuaiannya dengan asas-asas logika.Disitulah letak logika diperlukan sebagaidasar penggunaan pikiran.
Menurut Sudarsono (Sudarsono,1993: 146), Logika memiliki objek
KONTRADIKSI LOGIKA FILSAFATDENGAN LOGIKA SIMBOLISASI BAHASA
Moch. Jalal*))
AbstractNot agreement between Ianguage base aspect with philosophy logic characteristic nonmeaning both this science area have to be dissociated in order not to each other bringinginto contact. Philosophy logic always claim truth, accuracy, decision, and universality. Onthe other side, Ianguage simbol measure up to base which contradiction with philosophylogic demand. Related to this problem both science area, Ianguage and also philosophy donot have to avoiding each other. Without have logic, study to reality problem of usage ofIanguage will never earn to find problems answer. On the other hand, philosophizingimpossible can be conducted without using Ianguage media to pour all object presentationand also all behavior which is contemplating. On the contrary, both have to earn issearching each other gap among to pruduce of interesting and sharper multidimensionalscience.
Keywords: Philosophy logic, Language base aspect
* Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya UniversitasAirlanga, telp (031) 5035676)
1

material yaitu berpikir. Sedangkan yangdimaksud dengan berpikir ialah kegiatanpikiran, akal budi manusia. Apabilaseseorang berpikir, maka berarti diamengolah, mengajarkan pengetahuanyang diperoleh. Dengan demikian berartidalam hal ini telah terjadi kegiatanmempertimbangkan, menguraikan, mem-bandingkan, serta menghubungkanpengertian yang satu dengan lainnyasecara teratur dan acak. Sedangkan objekformalnya adalah berpikir benar dan tetap.
S e l a n j u t n y a d a l a m l o g i k akefilsafatan ini akan diatur bagaimana tatacara berpikir dan benalar yang benar.Sebab ada dua kemungkinan implikasicara berpikir dalam berfilsafat, logis atautidak logis. Jika hasil kegiatan berpikirdan bernalar itu telah sesuai dengansyarat-syarat logika yang benar, berartihasil pemikiran itu dapat dikatakan logis.Sebaliknya, jika kurang memenuhi syaratlogika yang benar, berarti kurang ataubahkan dianggap tidak logis.
Selain logika, dalam kegiatanberfilsafat ternyata masih terdapatperangkat alat yang tak kalah pentingnya,yaitu bahasa. Barangkali tidak satu punlinguis yang meragukan adanya pendapatbahwa antara ilmu filsafat dengan ilmulinguistik (kajian terhadap bahasa)terdapat kedekatan hubungan. Pendapatadanya kedekatan hubungan ini jauh-jauhhari memang sengaja diperkenalkan,bahkan menjadi semacam bagipara pemerhati ilmu linguistik agar segeramembuka jendela wawasannya. Karenamengkaji persoalan linguistik mau tidakmau akan dihadapkan pada persoalan-persoalan nonlinguistik yang tidak jarangj u s t r u m a m p u s e c a r a s i n e r g i smempertajam serta melengkapi kajian
terhadap berbagai persoalan bahasa.tentang kedekatan hubungan
tersebut sebenarnya tidak hanya ditujukanterhadap bidang filsafat, namun jugaberbagai disiplin ilmu lain sepertisosiologi, antropologi, psikologi, dankedokteran.
Khusus bidang filsafat, hubunganantara keduanya memang telah terjalinsejak masa-masa awal kelahiran keduabidang keilmuan tersebut, baik itu bidangfilsafat maupun linguistik. Secaramendasar, antara keduanya bahkancenderung menjadi satu kesatuan yangtidak dapat terpisahkan. Pada kegiatanberfilsafat, bahasa menjadi saranat e r p e n t i n g d a l a m r a n g k akeberlangsungannya. Dengan kata laindalam setiap aktifitas berfilsafat atauberpikir tidak akan pernah dapatberlangsung tanpa adanya bahasa sebagaimedianya. Hal itu masuk akal, mengingatapapun dunia fakta yang menjadi objekperenungan dapat dipastikan telahtertransformasikan dalam dunia simbolikyang terwakili dalam bahasa. Objek-objek yang dipikirkan dan direnungkandalam filsafat tidak lain adalah realitasalam maupun perilaku yang telahterlabelisasi dalam bentuk-bentuk simbol-simbol bahasa. Seperti langit, bintang-bintang, hukum, aturan, norma, kearifan,kejahatan, dan lain-lain. Dalam sebuahpe-mikirannya, ahli filsafat W.D. Whitneypernah mengungkapkan bahwawarning
Warning
Language is not only necessary for theformulation of thought but is part of thethinking process it self we cannot getoutside language to reach thought, noroutside language to reach language
.
.(Bolinger & Sears, 1981: 135)
2
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

Di sisi lain, jika dilihat dari sudutpandang linguistik, bidang kajian ini puntidak akan pernah dapat dipisahkan darikegiatan berfilsafat. Sebab pada dasarnyasemua kegiatan kaji-mengkaji keilmuanitu tidak akan pernah terlepas darikegiatan berpikir dan bernalar. Sebagaisalah satu cabang keilmuan yang sudahmendapatkan pengakuan secara universal,di dalam kajian linguistik tentu sajaterdapat kegiatan berpikir dan bernalar.Senada dengan hal itu Durant (1933: 14)pernah berpendapat jika filsafat itu padadasarnya merupakan awal atau langkahpertama dari berbagai kegiatan keilmuan.Jika diibaratkan sebagai strategi militer,filsafat merupakan pasukan marinir yangditerjunkan pertama kali ke medan perangguna mencari jalan bagi pasukan infantri(bidang ilmu yang dimaksud), yangs e l a n j u t n y a a k a n m e n g a d a k a npenyerangan dan aksi lanjutan. Tanpakeberadaan pasukan marinir tersebutmaka juga tidak akan pernah terdapatkegiatan penyerangan dan aksi lanjutanoleh pasukan infantri. Ilustrasi Durant inise bena rn ya ing in menun jukkanbagaimana posisi filsafat —yang dalamhal ini diibaratkan sebagai pasukanmarinir— dengan ilmu lain yangdiibaratkan sebagai pasukan infantri.Sehingga makin jelaslah bahwa mungkintidak akan pernah muncul kajian tentangbahasa yang selanjutnya dikenal denganlinguistik jika seandainya manusia tidakmelakukan kegiatan berfilsafat.
Tulisan singkat ini ingin men-jabarkan kontradiksi yang terdapat antarakelogisan bernalar pada logika filsafatdengan logika simbolisasi bahasa,terutama yang terepresentasikan dalambeberapa sifat bahasa yang dicetuskan
oleh Alston (1964: 6), yaitu
dan
Hubungan kedekatan yang ter-dapatantara kajian filsafat secara umum denganbahasa bukan berarti antara keduanyamemiliki sistematika serta cara bernalaryang sama. Bahkan dalam hal-hal tertentudapat dijumpai adanya sistematika ataucara bernalar filsafat yang seringtersandung dengan logika simbolisasidalam bahasa. Untuk itu melalui makalahsingkat ini, penyusun sangat tertarik untukmem-bahas salah satu kontradiksi yangcukup tampak, terutama tentang sifat-sifatdasar bahasa yang dianggap sebagaikekurangan atau penghambat jikadibenturkan dengan tuntutan kelogisanbernalar dalam kajian filsafat secaraumum.
Kepemilikan dan pemakaian bahasamerupakan satu hal yang menunjukkankeunggulan serta nilai lebih luar biasa daridiri manusia dibandingkan denganmahluk lainnya. Sehubungan dengan halitu Ernst Cassirer (Cassirer,
(1944) menyebut manusia adalah, yaitu makhluk yang
meng-gunakan media berupa simbol-simbol kebahasaan dalam memberi artiserta mengisi dan mengatur kehidupannyasecara keseluruhan. Cassirer lebih lanjutmenyatakan bahwa keberadaan manusiasebagai ini dianggaplebih berarti daripada keberadaannyasebagai , yaitu makhlukyang memiliki kemampuan berpikir.
Alasannya, media bahasa dengansimbol-simbol yang terdapat didalamnyalah yang mampu menjadikanmanusia untuk melangsungkan kegiatan
vagueness,inexplicitness, ambiguity, context-dependence, misleading-ness.
An Essay onMananimal simbolicum
animal simbolicum
Homo sapiens
Pembahasan
Kontradiksi Logika Filsafat dengan Logika Simbolisasi Bahasa
3

berpikirnya. Tanpa memiliki kemampuanberbahasa ini tidak mungkin kegiatanberpikir secara teratur dan sistematisdapat dilakukan. Selain itu, denganadanya simbol-simbol bahasa pula yangmemungkinkan manusia tidak hanyasekedar berpikir, namun sekaligusmengadakan kontak dengan realitaskehidupan di luar lingkungannya sertamemanfaatkan hasil berpikirnya itu untukkelangsungan kehidupan dunia.
Ibarat sebagai suatu alat, bahasamerupakan kendaraan yang telah dan akanmembawa filsafat dalam menjelajahialam semesta. Namun sayang, sebagaikendaraan yang seharusnya sehati dansejalan, bahasa ternyata masih memilikicela atau kelemahan dalam mengantarkanfilsafat ke tujuan akhir petualangannya.Kelemahan mendasar bahasa dalam halini terletak pada sifat-sifat dari bahasasendiri yang terkadang memang tidakmemiliki konsistensi acuan yang tetap.Padahal ciri pemikiran filsafat jelas-jelasmenuntut dan mensyaratkan adanyakonsistensi pada setiap gejala realitasyang menjadi objek perenungannya.Filosof Bertrand Russel berpendapatbahwa menyusun simbol kebahasaansecara logis merupakan dasar dalammemahami struktur realitas secara benar.Sebab itu, kompleksitas simbol bahasajuga harus memiliki kesesuaian dengankompleksitas realitas itu sendiri. Sehinggaantara keduanya akan dapat ber-hubungansecara tepat dan benar (Alston, 1964: 2).Bagi aliran filsafat analitik —termasuk didalamnya
, dan lain-lain— bahasa bahkan bukan saja hanyasebagai alat berpikir atau berfilsafat,melainkan merupakan bahan dasar dan
bah-kan hasil akhir dari kegiatan filsafatitu sendiri. (Kaplan, 1961: 61)
Bahasa jika dikaitkan dengan sepertiyang diharapkan Russel di atas ternyatamasih memiliki kelemahan-kelemahan.Sifat-sifat bahasa yang dianggap sebagaikelemahan di dunia kefilsafatan pernahdiformulasikan oleh Alston, yaitu:
danSifat berarti samar, artinya,simbol-simbol bahasa itu pada dasarnyamasih bersifat samar dan abstrak. Dengankata lain keberadaan-nya sering tidakmampu mewakili sebuah realitas secarajelas. Kejelasan acuannya baru dapatmun cu l ke t ika o r ang lang sungdihadapkan pada realitasnya. Misalnyajika kita menjabarkan tentang parahnyakekeringan di wilayah Trenggalek, simbolyang kita gunakan untuk mewakili realitasitu cenderung kurang mampu secara jelasdalam menggambarkan kondisi riilnya.Kata-kata yang kita pilih guna melukiskankondisi kekeringan itu mungkin hanyadapat menyiratkan kondisi kurang-lebihnya. Sedangkan yang paling tepatdan benar hanyalah realitasnya. Hal itupula yang me-nyebabkan bahasa seringdikatakan memiliki sifat .
Sifat ini ditekankanpada anggapan mengenai kemampuanperujukan simbol-simbol bahasa denganrealitas yang diacunya itu hanya bersifatimplisit saja. Dengan kata lain bahasakurang dapat secara eksplisit dan tepatd a l a m m e w a k i l i r e a l i t a s y a n gdibicarakannya. Misalnya ketika kitamengambarkan adanya sebuah kejadiankecelakaan antara sepeda motor danbecak, dengan konstruksi simbol bahasa“Becaknya hancur!”. Maka kata hancur
logical positivism, logicalempirism, scientific empirism
vagueness, inexplicitness, ambiguity,context-dependence, misleadingness.
vagueness
inexplicitnessinexplicitness
4
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

ini mungkin tidak akan dapat sama dantepat dalam menggambarkan ataumewakili kondisi riil becak yangtertabrak sepeda motor itu.
Sifat ketiga, berkaitandengan ciri ketaksaan makna dari suatubentuk kebahasaan (Aminuddin, 1988:19). Setiap konstruksi simbol bahasahampir selalu memiliki potensi untukmengacu pada lebih dari satu referensiatau realitas. Konsep “kendaraan”misalnya, bisa mengacu pada motor,mobil, andong, dan lain-lain. Demikianjuga kata “naik” dapat mengacu padamenggunakan kendaraan, gerak daribawah ke atas pada konteks pemakaian“naik pohon”, dari jenjang rendah keyang lebih tinggi pada konteks pemakaian“naik kelas”, mendaki pada “naikgunung”, dan lain-lain. Acuan dari suatukonsep simbol bahasa baru benar-benardapat d imaknai ke t ika kontekspemakaian-nya jelas. Maka sifatselanjutnya, yaitudianggap sebagai sisi kelemahan daribahasa juga.
Sifat dapatdimaknai sebagai sifat ketergantunganbahasa terhadap berbagai setting konteks,baik itu gramatikal, situasional, sosial,dan setting konteks komunikasinya.Simbol “bunga” baru dapat bermaknaketika konteks pemakaiannya telah jelas.Pada kon-teks gramatikal “Bunga desa itukini telah tidak secantik dulu lagi”, bungaberarti gadis, namun pada konteks yanglain juga akan bermakna lain pula.
Sifat kelemahan bahasa selanjut-nyaadalah . Hal ini berkaitandengan po tens i kesa lahan a t auketidaktepatan penafsiran simbol bahasadalam mengacu pada realitas yang
diwakilinya. Pada realitas pemakaianbahasa, potensi kesalahan penafsiran inimungkin dapat terjadi pada tingkat
(penyusunan pesan) maupuntingkat (penerimaan pesan).Misalnya, “Istri profesor yang baru itusangat cantik”. Potensi makna daripenafsiran per-nyataan tersebut dapatmuncul sebagai, pertama, yang baru itukeprofesorannya, kedua, yang baru adalahistri cantiknya.
Bagi bidang filsafat, sifat-sifatseperti yang telah dirumuskan Alston diatas jelas- jelas merupakan sifatkelemahan yang kontradiktif dengankarakteristik metode berpikir ilmiahdalam dunia kefilsafatan. Sebagaimanayang diungkapkan Sudarsono (1993: 165),Logika berpikir dalam filsafat memilikiobjek material cara berpikir itu sendiri,sedangkan objek formalnya adalahberpikir benar dan tetap. Di setiapaktivitas berpikir haruslah ditunjukkandalam logika wawasan berpikir yang tepatatau ketepatan pemikiran, yang padapenggarisan logika lebih dikenal denganistilah berpikir logis. Dengan demikian,kalau kita melihat berbagai ciri sifatbahasa di atas, jelas-jelas acuan daripemakaian simbol bahasa itu seringkalitidak dapat tepat dalam mengacurealitasnya. Sedangkan ketepatan dankebenaran jelas-jelas sangat dituntut danmenjadi syarat mutlak pada modelberpikir logis dalam filsafat.
Kond is i yang demik ian i tumerupakan contoh dari kontradiksi yangterjadi antara kelogisan berpikir dalamfilsafat dengan bahasa sebagai alat ataukendaraan dalam rangka berpikir. Jelassekali bahwa bahasa memiliki tingkatfleksibilitas yang tinggi dalam hal sering
ambiguity
context-dependence
context-dependence
misleadingness
encodingdecoding
5
Kontradiksi Logika Filsafat dengan Logika Simbolisasi Bahasa

berubah dan sering tidak tepat dalammengacu realitas. Persoalannya, justrutingkat fleksibilitas yang tinggi ini akandimaknai dengan bahasa logikakefilsafatan menjadi tidak konsisten,ambigu, bahkan tidak memiliki ketepatandan ketetapan dalam merujuk dunia luar.Sehingga wajar jika kemudian munculpernyataan dari beberapa kalanganpemikir/filosof bahwa bahasa seringkalitidak konsisten. Padahal konsistensi inisangatlah disyaratkan dan menjadi ciriutama dalam setiap pemikiran filsafat.
Akhirnya persoalan bahasa memangbenar-benar menjadi objek kajian seriusbagi filosof-filosof modern. Dengan ciri,sifat, dan karakteristik unik dari bahasa,seringkali perenungan terhadapnyamengalami jalan buntu atau seringkalibelum selesai sampai tuntas. Senadadengan kondisi ini Wittgenstein (dalamSuriasumantri, 2001: 187) pernahmenyatakan, bahwa kekacauan dalamfilsafat antara lain disebabkan banyaknyapernyataan dan pertanyaan filosof yangtimbul dari kegagalan mereka dalammenguasai logika bahasa. Wittgensteinpernah menawarkan dengan apa yangdisebutnya sebagai metode netral dalammelihat bahasa. Dalam kajian bahasajangan lagi dilihat kaitan antara bahasadengan acuan dunia nyata, tetapi haruslebih ditekankan pada bagaimana bahasadapat direalisasikan penggunaannya.Meskipun dalam hal itu justru berdampakpada mun-culnya kekacauan dankekeliruan logis jika dikaitkan denganlogika pada umumnya. Bagi Wittgensteintidak penting benar salahnya acuanataupun ucapan dalam berbahasa. Yanglebih penting adalah bahwa dibalikrealisasi bahasa tersebut terdapat maksud
dan makna yang dapat diterimapemakaiannya.
Kontradiksi lain antara bahasadengan ciri pemikiran filsafat adalahpada persoalan universalitas. Ciri utamadari pemikiran filsafat adalah hasil-hasilpemikirannya akan men-capai padatingkat kebenaran yang universal, yaitukebenaran yang bersifat umum dan tidakterbatas oleh ruang maupun waktu.Kebenarannya akan berlaku untuk kapandan di mana saja (Sudarsono, 1993: 102-103). Kalau kita menengok pada bahasa,rupa-rupanya bahasa dengan segala latarbelakang penciptaannya hingga pada pe-makaiannya secara praktis, tidak terdesainseperti itu. Kita tentunya sudah seringmenemukan bukti adanya teori-teori yangdiciptakan dalam rangka perenunganterhadap suatu bahasa yang ternyatamemang sering tidak dapat diberlakukanuntuk bahasa-bahasa lainnya. MisalnyaHukum Grim yang terkenal juga hanyadapat diberlakukan untuk sebagianbahasa-bahasa Proto Indo-Jerman saja. Disisi lain, sistem alfabet latin yang sangatluar biasa dalam mewakili bunyi bahasa-bahasa dunia, ternyatajuga masih terdapat kekurangan di sana-sini ketika diterapkan untuk bahasa-bahasa lain di berbagai belahan dunia.
Kondisi itu membuktikan bahwabahasa dengan berbagai realitas danpersoalannya telah gagal dalammenyamai hukum universalitas dalamlogika pemikiran filsafat pada umumnya.J i k a p e m i k i r a n l o g i s f i l s a f a tmenghasilkan pernyataan: “Semuamanusia dilahirkan dan akan mati. EmanSuherman adalah manusia. Maka EmanSuherman pasti dilahirkan dan nanti pastiakan mati juga”. Sedangkan dalam bahasa,
major language
6
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

pemunculan dan pemakaiannya sangatditentukan oleh keberagaman latarb e l a k a n g d a n s e t t i n g k o n t e k skemasyarakatan yang seringkali berbedaantara satu dengan yang lain.
Sebagai kesimpulan penulis inginmenegaskan bahwa dalam mengacu dunialuar, antara logika simbolisasi bahasadengan logika dunia kefilsafatan memangmemiliki sisi perbedaan. Sisi perbedaanini muncul karena antara keduanyaberangkat dari visi dan fungsi yangberbeda. Logika filsafat menekankanpada aspek kelogisan berpikir, dalam halini memuat ketepatan, kebenaran,konsistensi, serta keuniversalan fenomenapada setiap objek kajian berpikir.Sedangkan dalam logika bahasa lebihbanyak ditekankan pada sisi pragmatik,aspek fungsional, serta aspek komunikatifdalam pemakaian riil berbahasa. Hal itujelas-jelas merupakan dua aspek yangj a u h b e r b e d a l a t a r b e l a k a n gkeberangkatannya.
M e l i h a t k e n y a t a a n a d a n y aketimpangan antara sistem logikapemikiran filsafat dengan kenyataanfleksibilitas cara kerja bahasa hendaknyadilihat bukan dari kacamata kelemahanatau kekurangannya. Namun harusdisadari bahwa masing-masing padahakikatnya terlahir dan diciptakan untuktujuan berbeda. Sudah menjadi ciri daripola kelogisan berpikir filsafat bahwakebenaran, ketepatan, ketetapan, danuniversalitas merupakan syarat yangselalu dipegang teguh. Sedangkan bahasatercipta dan dipakai semata-mata bukanhanya untuk mengejar acuan kebenaran,ketepatan, ketetapan, dan selain itumasing-masing bahasa juga hidup dalam
sistemnya sendiri-sendiri.Fungsi dan peran bahasa bersifat
multidimensional. Dalam praktikpemakaiannya, misalnya selain memilikifungsi simbolik, bahasa juga memilikifungsi afektif dan emotif. Namun banyakj u g a y a n g b e r p e n d a p a t b a h w akeberagaman fungsi dan fleksibilitaskarakter dan peran yang dimiliki simbolbahasa itu justru menjadi kelebihan daribahasa itu sendiri.
Sampai kapan pun filsafat tidak akanpernah dapat menghindar dari realitasbahwa bahasa akan tetap menjadi mitraatau kendaraannya. Adanya kontradiksiyang disebabkan oleh sifat-sifat bahasaseperti yang telah diuraikan tidakmungkin dapat mengubah kenyataanbahwa kalau hendak berfilsafat juga harusberbahasa. Mungkin sebagai jalantengahnya adalah ket ika meng-komunikasikan suatu pemikiran filsafat,sedapat mungkin menghindari pemakaiansimbol-simbol bahasa yang dapatmenimbulkan aspek emotif.
Alston, P. William. 1964., London: Prentice-Hall.
Aminuddin. 1988.Bandung:
CV Sinar Baru Offset.
Bawengan, G.W. 1990.. Jakarta: Rineka
Cipta.
Bolinger, Dwight L., & Sears, A. Donald.1981. , New
Penutup
DAFTAR PUSTAKA
Philosophi ofLanguage
Semantik PengantarStudi Tentang Makna.
Sebuah Studitentang Filsafat
Aspects of Language
7
Kontradiksi Logika Filsafat dengan Logika Simbolisasi Bahasa

York: Harcourt Brace Jovanovich,Inc
Cassirer, Ernst. 1944.New Heaven: Yale UniversityPress.
Durant, Will. 1933.. New York: Simon &
Schuster.
Kaplan,Abraham. 1961., New York:Alfred A.
Knopf & Random House Inc.
Sudarsono. 1993.. Jakarta: PT Rineka
Cipta
Suriasumantri, Jujun S. 2001.,
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
An Essay on Man.
The Story ofPhilosophy
The NewWorld ofPhilosophy
Ilmu Filsafat SuatuPengantar
FilsafatIlmu Sebuah Pengantar Populer
8
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

PendahuluanPemikiran tentang sosialisme
religius bukan barang baru dan asing.Wacana pemikiran tentang sosialismereligius dalam tradisi agama besar duniadapat dirunut ratusan tahun lampau.Dalam konteks Indonesia, antara lainpernah dikemukakan oleh Haji Misbachyang meramu Islam dan marxisme sertaH.O.S Cokroaminoto yang telahmeletakkan dasar sosialisme religiusdalam nya: Islam danSosialisme (Dahlan, 2000: xix). Padazaman pergerakan nasional, para pe-mimpin Indonesia banyak yang meng-adopsi pemikiran tersebut sepertiSoekarno, M. Hatta, Sutan Syahrir,Syafruddin Prawiranegara, dan lain-lain.Bung Hatta menyatakan sosialismereligius pertama kali pada pidatonya dibukit tinggi tahun 1932, kemudian olehBung Karno dan juga Soeharto dalampidato pada Dies Natalis UniversitasIndonesia tahun 1975 (Swasono, 1987:138).
Pemikiran Bung Hatta tentangsosialisme religius tidak dapat dilepaskan
dari peran dirinya sebagai tokoh yangmengalami langsung jaman pergerakannasional menuju Indonesia merdeka yangpenuh lika-liku. Cita-cita sosialisme lahirdari pergerakan kebangsaan Indonesia,dalam per-gerakan yang menujukebebasan dari penghinaan diri danpenjajahan (Hatta, 1967: 13). Selain itucita-cita tersebut tertangkap pula oleh jiwaIslam, yang menghendaki pelaksanaanperintah Allah Yang Pengasih danPenyayang serta Adil dalam dunia yangtidak sempurna, supaya manusia hidupdalam sayang-menyayangi dan dalamsuasana persaudaraan dengan tolongmenolong (Hatta, 1967: 13).
Pemikiran Hatta tentang sosialismereligius berhubungan dengan pemikiran-pemikiran lainnya yang memang sangatluas, tidak cukup ratusan halaman untukmengungkapkan sepenuhnya diri BungHatta dengan ide-idenya membangunbangsa dan negara ini (Swasono, 1995:94). Sosialisme bukanlah semata-matapersoalan ekonomi, akan tetapi jugamempunyai bidang sosial dan kultur yangluas. Ia meliputi seluruh hidup manusia,
magnus opus-
ETIKA SOSIALISME RELIGIUS BUNG HATTAMade Pramono*)
AbstrakHatta’s ideas about religious socialism is an entry point to his other ideas such as ineconomic, cooperation, politic, democracy, an Pancasila. This paper discusses the ideasfrom the perspective of ethical values. the discussion is initiated by looking at the basicelements of the ideas itself that is religious imperative, rebellious characteristic ofIndonesian people, and indigenous to Indonesian values. those three factors are analyzedand it shows that those ethical values inherit the previous athical values. the relevance ofBung Hatta’s idea and the recent context becomes an important final stage in this paper,using critical evaluation, refer to further construction of the ideas.
Keyword: Hatta, ethic, religious socialism
* )Pengajar Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Keolahragaan, email: [email protected]
9

memberikan kepercayaan kepadamanusia, bahwa hidup dalam dunia fanaini diliputi kebahagiaan. Tetapi ekonomiadalah dasarnya, sebab masyarakat yangtidak mem-punyai dasar ekonomi yangkuat, tidak sanggup melaksanakanpendidikan yang sempurna danperbaikan sosial serta tidak sanggupmenikmati kebudayaan (Hatta, 1967: 27).Atas dasar kesengsaraan dan kemiskinanhidup rakyat Indonesia, maka dasarperekonomian rakyat mestilah usahabersama dikerjakan secara kekeluargaan.Yang dimaksud usaha bersamaberdasarkan kekeluargaan ialah koperasi(Abdulmanap, 1987: 66).
Sosialisme menghendaki suatu per-gaulan hidup, di mana tidak ada lagipenindasan dan penghisapan, dimanatiap-tiap orang dijamin kemakmurannya,kepastian penghidupannya sertaperkembangan kepribadiannya (Hatta,1967: 12). Sosialisme yang mempunyaidasar-dasar peri-kemanusiaan dankeadilan sosial yang seperti itulah yangdapat menjadi akar demokrasi Indonesia.Demokrasi barat bersumber dari revolusiPerancis hanya membawa kepadapersamaan politik. Dalam perekonomiantetap berlaku dasar tidak sama, hal itudikarenakan berkobarnya semangat in-dividualisme yang menumbuhkankapitalisme. Maka menurut Hattademokrasi politik saja tidak cukup, disebelahnya harus ada demokrasiekonomi (Hat ta, 1967: 22-23).Demokrasi bukan hanya persamaandalam politik, tetapi demokrasi adalahsesuatu yang harus, dan kadang-kadangmesti, me-nyinggung kehidupan rakyatsehari-hari dalam segala hal (Hatta,1957: 51). Demokrasi yang sesuai cita-
cita demokrasi Indonesia itu ialahdemokrasi sosial (Hatta, 1966: 24).
Menurut Bung Hatta dalam(1966) cita-cita demokrasi
sosial itulah dasar bagi pembentukanNegara Republik Indonesia yang merdeka,bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita tersebut dituangkan di dalamPembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Terdapat tiga pernyataan penting dalampembukaan tersebut yaitu pertama,pernyataan dasar politik dan cita-citabangsa Indonesia; kedua, pernyataantentang berhasilnya tuntutan politik bangsaIndonesia, dengan kurnia Allah; dan ketiga,pernyataan tentang Pancasila sebagaifilsafat atau ideologi negara (Hatta, 1966:29-30).
Berangkat dari beberapa hal di atas,dapat dinyatakan bahwa pemikiran BungHatta tentang Sosialisme Religius ber-hubungan dengan pemikiran-pemikiranpokok Bung Hatta yang lain sepertikonsepsi ekonomi, koperasi, demokrasi,politik, sampai dengan dasar negarapancasila. Dengan adanya hubungan-hubungan tersebut, maka pemikiranSosialisme Religius dapat menjadi salahsatu titik masuk untuk dapat melihat pe-mikiran-pemikiran Bung Hatta lainnya.Itulah salah satu alasan untuk menulistentang pemikiran Sosialisme ReligiusBung Hatta ter-utama dari nilai-nilai etisyang terkandung di dalamnya.
Menurut Bung Hatta sosialismeIndonesia timbul dari tiga faktor,singkatnya sebagai berikut:
Sosialisme Indonesia timbulkarena . Karena adanya etikagama yang menghendaki adanya rasapersaudaraan dan tolong menolong antara
FilsafatNegara Kita
Pertama,suruhan agama
Sosialisme Religius
10
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

sesama manusia dalam pergaulan hidup,orang mendorong ke sosialisme.Melaksana-kan bayangan kerajaan Allahdi atas dunia adalah tujuannya.
Sosialisme Indonesia me-rupakan ekspresi daripada iwa berontakbangsa Indonesia yang memperolehperlakuan yang sangat tidak adil dari sipenjajah. Sosialisme Indonesia lahirdalam pergerakan menuju kebebasan daripenghinaan dan dari penjajahan.
Sosialisme Indonesia adalahsosialisme yang mencari sumber-sumbernya dalam masyarakat sendiri,karena tidak dapat menerima pandanganberdasarkan materialisme. Sosialismeadalah suatu tuntutan jiwa, kemauanhendak mendirikan suatu masyarakatyang adil dan makmur, bebas dari segalatindasan. Sosialisme dipahamkan sebagaituntutan institusional, yang bersumberdalam lubuk hat i yang nurani ,berdasarkan perikemanusiaan dankeadilan sosial (Swasono, 1987: 138-139,Swasono, 1995: 84-85, Hatta, 1967:1-29)
Di atas tiga faktor itulah dibangunpemikiran Bung Hatta tentang SosialismeReligius. Dengan menganalisa ke tigafaktor tersebut akan didapatkan nilai-nilaietis yang terkandung dalam pemikiran itu.
Sosialisme Indonesia muncul darinilai-nilai agama (Islam) yang terlepasdari marxisme. Artinya, yang adahanyalah perjumpaan cita-cita sosial-demokrasi barat dengan sosialisme-religius (Islam), di mana marxismesebagai pandangan hidup materialismetetap ditolak. Sosialisme memang tidakharus merupakan marxisme, tidak harusdiartikan sebagai hukum dialek-tika,
tetapi sebagai tuntunan hati nurani,sebagai pergaulan hidup yang menjaminkemakmuran bagi segala orang,memberikan kesejahteraan yang merata,bebas dari segala tindasan (Swasono,1987: 139). Jadi sosialisme bagi BungHatta sudah me-ngandung nilai etik,karena setiap keputusan (moral) memangharus diambil sesuai dengan suara batin,w a l a u p u n h a r u s t e r u s - m e n e r u sdisesuaikan dengan apa yang objektifbetul, dan oleh karena itu wajibmemperhatikan semua argumen, unsur-u n s u r , i n f o r m a s i - i n f o r m a s i ,pertimbangan-pertimbangan dan lain-lainyang didapat (Suseno, 1975: 33).
Karena sosialisme Indonesia mun-cul dari nilai-nilai agama, maka BungHatta mendasarkannya pada nilai-nilaietik agama, terutama agama Islam. Sendipandangan hidup Islam adalah bahwabumi dan alam sekitarnya bukanlahkepunyaan manusia , mela in-kankepunyaan Allah, Tuhan seru sekalianalam. Tuhan yang menjadikan alam danbumi tempat kediaman manusia.Kedudukan manusia di atas bumi tidaklain melainkan sebagai jurukuasa, yangbertanggung jawab atas keselamatannyadan generasi penerusnya. Sebab itukewajiban manusia yang mendiami bumiAllah ini ialah memelihara sebaik-baiknya dan me-ninggalkannya kepadaangkatan kemudian dalam keadaan lebihbaik dari yang diterimanya dariangkatan yang terdahulu dari dia (Hatta,1957, 27-28).
Dari pandangan di atas maka dapatdilihat beberapa hal, antara lain: ,bahwa bukan hanya alam dan bumi,bahkan manus ia sendi r i adalahmerupakan ciptaanAllah. Sebagai ciptaan
Kedua,j
Ketiga,
pertama
Suruhan Agama
Etika Sosialisme Religius Bung Hatta
11

Allah maka manusia mencerminkanadanya kualitas Tuhani dalam dirimanusia (Hasan, 1987: 163). Implikasietis (normatif) nya adalah bahwamenghormati martabat manusia berartimenghormati ke-mahadaulatan Tuhan.Dan sebalik-nya, tidak mungkinmenghormat i Tuhan ka lau ki tamemperkosa martabat manusia (Suseno,2000: 15). Menurut Frans Magnis Suseno,hormat terhadap manusia berarti:mengakui kedudukannya yang sama,tidak memperlakukannya sebagai objekperencanaan, berorientasi pada harapan-harapannya, tidak pernah mengorbankanpihak yang satu demi keuntungan pihakyang lain, tidak membeli kemajuandengan menyengsarakan yang lain.Sedangkan bagi Hatta, melaksanakanperbuatan baik (terhadap manusia lain) didunia fana adalah sebuah pujian yangdipanjatkan kepada-Nya. Karena kalautidak: apalah artinya pujian yangsebanyak itu dipanjatkan ke hadiratAllah?Tuhan tidak kekurangan apapun juga,tidak kurang besar dan tidak kuranghormat. Ia adalah Dzat yang lengkapdengan segala rupa (Hatta, 1957: 22).Akhirnya Bung Hatta (1957: 18)mengutip salah satu ayat Al Qur’an: “ ......
Untuk dapat memeliharasebaik-baiknya dan meninggalkan kepadaangkatan kemudian dalam keadaan lebihbaik, maka manusia dianugerahkan akalbudi oleh Tuhan. Dengan akal manusiabisa menciptakan ilmu yang bisa
digunakan untuk memelihara danmengelola alam ini, juga dengan akal,manusia dapat berpikir bahwa apa yangtelah dia perbuat sekarang adalah bukanhanya untuk kepentingannya sekarang,tetapi juga demi kepentingan generasimendatang yang tentu tujuan akhirnyaadalah melestarikan peradaban manusia.Implikasi etisnya (normatif) adalahbahwa manusia selalu harus diperlakukansebagai tujuan pada dirinya sendiri, iatidak pernah boleh digunakan sebagaisarana untuk tujuan lebih lanjut, manusiatidak boleh dibiarkan, apalagi disebabkan,menderita apabila dapat dicegah.Penderitaan seseorang tak pernah bolehmenjadi sarana bagi masyarakat ataunegara untuk memperoleh suatukeuntungan (Suseno, 2000: 17-18). Ilmuadalah alat; tujuan ialah kemakmuranjasmani dan rohani ! Negara bukan tujuantersendiri, melainkan alat untuk mencapaik e b a h a g i a a n , p e r d a m a i a n d a nkemerdekaan bagi rakyat. Bukan rakyatuntuk negara, melainkan sebaiknyanegara untuk rakyat (Hatta, 1957, 27).
Kemudian seperti dikatakan BungHatta, etik Islam yang mengandung
dan – benar karenaberasal dari Tuhan dan manusia adalahkhalifahnya di dunia, serta adil karenamanusia diper-lakukan sama dan sederajatsebagai tujuan pada dirinya – harusmemerlu-kan untuk bertindakdan memperjuangkannya di atas bumi ini,keberanian menghadapi berbagaikesulitan, keberanian menderita danberkurban untuk kemenangan cita-cita(Hatta, 1957: 19). Etika adalah bagaimanaia harus bertindak (Suseno, 1975: 13).Maka tugas seorang muslim adalahmencapai masyarakat, yang menjamin
dan berbuat kebajikanlah (kepada oranglain) sebagai Tuhanpun berbuatkebajikan kepadamu, dan janganlahberusaha menimbulkan kebinasaan dimuka bumi; Tuhan tidak menyukai orang-orang yang berbuat kebinasaan”.
Kedua,
kebenaran keadilan
keberanian
12
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

kebahagiaan dan keselamatan hidup bagisegala orang (Hatta, 1957: 21).
Jiwa pemberontak itu berasal dariperlakuan tidak adil dari penjajah.Sosial isme Indonesia lahir daripergerakan menuju kebebasan daripenghinaan dan penjajahan (Swasono,1987: 139). Penjajahan bersifat tidak adilkarena memperlakukan secara sewenang-wenang rakyat dari negara yang dijajah,menindas, menghisap sumber dayajajahan atau seperti yang dikatakan BungHatta (1957: 54), struktur ekonomi negarajajahan ditujukan untuk keuntungan kaumpenjajah, bukan kaum jajahan,ekonomi kaum yang dijajah dibatasisampai pada saluran-saluran yangmenguntungkan kaum penjajah. Makabangsa Indonesia berontak dengankondisi ini dan menuntut keadilan, karenakeadilan adalah suatu norma dasar moralyang mengandung kewajiban untukmemberikan perlakuan yang sama kepadasemua orang demi mencapai kebahagiaanmanusia (Suseno, 1975: 105).
Selain tidak adil, penjajahan jugabertentangan dengan perikemanusiaan,yaitu kondisi dasar manusia, kebebasan.Pen ja jahan bers i f a t mengekangkebebasan rakyat negara jajahan,m e m b a t a s i d a n b a h k a nmenghancurkannya. Seseorang disebutb e b a s a p a b i l a k e m u n g k i n a n -kemungkinan untuk bertindak tidakdibatasi oleh sesuatu paksaan dari atauketerikatan kepada orang lain. Itulah titiktolak etika dari paham kebebasan, bebasdari paksaan (Suseno, 1975: 44). MenurutK. Bertens (1993: 94-95) kebebasandibedakan dua, yaitu: , kebebasansosial-politik – yang subjeknya bangsa
atau rakyat; , kebebasan individual– yang subjeknya manusia perorangan.Salah satu bentuk kebebasan sosial-pol i t ik i tu adalah suatu prosesdekolonisasi yang biasanya kita sebut“kemerdekaan”. Ide di belakang proses inibersifat etis, suatu ke-yakinan bahwa
suatu bangsa dijajah olehbangsa lain dan karena itu situasikolonialisme terjadilagi, sistem kolonialisme ditolak secaraumum sebagai tidak etis (Bertens, 1993:98). Alasan etis itulah yang memunculkantekad kuat bangsa Indonesia untukmenyatakan kemerdekaannya: “B
“.Pengalaman dengan pemerintahan
autokrasi kolonial dalam bentuk negara-polisi menghidupkan dalam kalbupemimpin dan rakyat Indonesia cita-citanegara hukum yang demokratis. Negaraitu haruslah berbentuk republikberdasarkan kedaulatan rakyat (Hatta,1966: 22). Dalam karya
tahun 1932, BungHatta mengatakan bahwa arti kedaulatanrakyat adalah tidak adanya lagi orangseorang atau kumpulan orang pandai atausa tu golongan keci l sa j a yangmemutuskan nasib rakyat dan bangsa,melainkan Pendek katarakyat itu alias raja atas dirinya.Karena rakyat itu badan dan jiwa bangsa,rakyat itulah ukuran tinggi rendah derajatkita. Dengan rakyat kita akan naik dandengan rakyat kita akan turun. Kebebasanrakyat tidak boleh lagi dirampas olehdiktator siapa pun juga. Kedaulatan
Jiwa Pemberontak Bangsa Indonesia
aktivitet
pertama
kedua
tidaklah pantas
tidak pernah boleh
ahwasesungguhnya kemerdekaan itu ialah haksegala bangsa dan oleh sebab itu, makapenjajahan di atas dunia harusdihapuskan, karena tidak sesuai denganperikemanusiaan dan perikeadilan
Ke ArahIndonesia Merdeka
rakyat sendiri.daulat
harus
13
Etika Sosialisme Religius Bung Hatta

14
tetap di tangan rakyat danberada pada instansi lain. Itulah suatutuntutan etis (Bertens, 1993: 97).Kedaulatan rakyat inilah dasar demokrasi,demokrasi adalah pe-merintahan rakyat,yaitu rakyat memerintah diri sendiri(Hatta, 1995: 168). Dalam demokrasi,kemerdekaan pribadi warganegara mestidijamin, karena kemerdekaan pribadiadalah urat tunggang demokrasi, akantetapi kemerdekaan pribadi itu berada didalam lingkungan tanggung jawabbersama atas nama bangsa, negara,pemerintah dan kemakmuran rakyat(Hatta, 1957: 58). Maka dari itupemerintahan rakyat harus membawakeadilan dan kesejahteraan bagi orang-orang, karena kalau tidak akan lahirtenaga dan aliran yang menentang, yangmembawa robohnya. Pendapat itu sejalandengan pendapat yang dikemukakanTeichman (1998: 28) bahwa ketika orangmulai merasa bahwa hukum-hukum yangdibuat oleh pemerintah tidak adil ataupelaksanaannya menyeleweng atau secaraumum membuat kehidupan bukannyalebih baik, melainkan justru lebih buruk,maka gagasan tentang hak kodrati akantampak atau tampak kembali. Yangdimaksudkan oleh Teichman adalahbahwa ada hak-hak kodrati yangfundamental dan bersifat universal,sesuatu yang dimiliki oleh semua manusia.Sesuatu yang dimiliki oleh semuamanusia semata-mata karena ia manusiaadalah premis dasar yang diperlukanuntuk menjamin legitimasi dan kewajaranhukum dan pemer in t ahan . Jad ikemerdekaan pribadi adalah merupakanhak-hak kodrati yang universal. Hak-hakitu antara lain hak untuk hidup, hak untukkebebasan, hak milik, hak untuk mencapai
kebahagiaan, hak untuk merasa aman, hakuntuk melawan penindasan. Suatupendasaran etis haruslah sesuai dengankondisi manusia, harus bersi fatmanusiawi, tidak boleh memperlakukanfungsi-fungsi sosial yang salah, yangdihasilkan dari situasi perang, kemiskinanekstrem dan kolonisasi yang brutalsebagai standar untuk ditiru (Teichman,1998: 6). “
begitulahkira-kira seruan yang selalu diulang olehBung Hatta.
Karena marxisme yang mempunyaipandangan materialisme tidak dapatditerima, maka ia harus dicari di dalammasyarakat sendiri. Selain itu juga dengand i c a r i n y a d as a r - d a s a r n y a p a d amasyarakat sendiri akan membuatsosialisme menjadi bukan sekedar utopia(Hatta, 1967: 16). Sosialisme Indonesiaadalah suatu tuntutan jiwa, kemauanhendak mendirikan suatu masyarakatyang adil dan makmur, bebas dari segalatindasan (Hatta, 1967: 15). Dasar-dasarbagi sosialisme Indonesia terdapat padamasyarakat , yang bercorak
, yang banyak sedikitnya masihbertahan sampai sekarang (Hatta, 1967:16). Pada bagian lain Bung Hatta juga me-nyebutnya sebagai (Hatta,1995: 178). Menurut Hatta, masyarakatIndonesia asli tidak ada perpisahan tegasantara apa yang dikatakan hukum publikdan hukum prive, seperti yang lazimdibuat masyarakat Barat berdasarkanindividualisme. Hatta setuju dengan yangdikatakan Van Vollenhoven tentanghukum adat Indonesia yang menyatakan
tidak boleh
Kita mempunyai kewajibanterhadap peri kemanusiaan”,
desa yang aslikolektif
desa demokrasi
Mencari Sumber-Sumber Sosialismedalam Masyarakat Sendiri
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

bahwa hukum adat hanya dapat dipahamibi la orang memperhatikan sifa tperkauman yang kuat dalam pergaulanhidup di Jawa dan Madura, tetapi Hattamenambahkan bahwa sifat perkaumantidak saja terdapat pada hukum adat diJawa dan Madura, juga terdapat diseluruh Indonesia (Hatta, 1967: 18-19).Sifat perkauman hukum adat tersebutadalah bahwa pada pusat penghidupanhukum terletak masyarakat, orangseorang terutama dipandang sebagaianggauta masyarakat, sebagai alat yanghidup untuk melaksanakan tujuanmasyarakat (Hatta, 1967: 19). MenurutFrans Magnis Suseno (1975: 20) hukumadat seperti itu termasuk dalam norma-norma hukum, yaitu norma yangpelaksanaannya dapat dituntut dandipaksakan serta pelanggarannya ditindakdengan pasti oleh penguasa syah dalammasyarakat. Walaupun hukum adat initermasuk norma hukum tetapi biasanyaberlaku tidak berdasarkan perundang-undangan (yang positif). Cita-citaperkauman, , persekutuanhidup itulah yang merupakan cikal bakaldemokrasi asli Indonesia yang telah hidupdi desa-desa di seluruh pelosok Indonesia.
Adapun demokrasi asli yang ada didesa-desa di Indonesia mempunyai tigasifat utama, yaitu cita-cita yang adadalam sanubari rakyat Indonesia; cita-cita
yaitu hak rakyat untukmembantah dengan cara umum segalaperaturan negeri yang dipandang tidakadil; cita-cita ! Sanubarirakyat Indonesia penuh dengan rasabersama, (Hatta, 1995: 179-180). Pada bagian lain (Hatta, 1966: 26),disebutkan adanya lima anasir demokrasiasli itu: rapat, mufakat, gotong royong,
hak mengadakan protes bersama, dan hakmenyingkir dari daerah kekuasaan raja.
Anasir-anasir itu berhubungan eratdengan adat perkauman seperti telahdisebutkan diatas, sebagaimana dikatakanHatta (1966: 25-26) bahwa adat semacamitu (perkauman) itu membawa kebiasaanbermusyawarah. Segala yang mengenaikepent ingan umum dipersoalkanbersama-sama dan keputusan diambildengan kata sepakat. Kebiasaanm e n g a m b i l k e p u t u s a n d e n g a nmusyawarah dan mufakat menimbulkanistitut rapat pada rapat tertentu, dibawahpimpinan kepala desa, dan tentu sajaanasir gotong-royong atau tolong-menolong. Karena anasir-anasir tersebutberlaku berdasarkan kebiasaan-kebiasaan,maka menurut Frans Magnis Suseno(1975: 20) termasuk dalam norma sopansantun, yaitu norma yang berlakuberdasarkan suatu kebiasaan ataukonvensi atau menurut pendapatkebanyakan orang saja. Sedangkan duaanasir lainnya (hak untuk protes dan hakuntuk menyingkir) lebih dekat denganhukum adat karena cara-cara untukmelakukannya diatur oleh adat antara lainmisalnya dalam penggunaan hak protesdilakukan apabila rakyat merasakeberatan sekali atas peraturan yangdiadakan oleh pembesar daerah, makakelihatan rakyat datang banyak sekali kealun-alun di muka rumahnya dan duduk disitu beberapa lama dengan tiada berbuatapa-apa (Hatta, 1966: 26).
Norma-norma yang telah disebutkandi atas merupakan hasil cetusanpengalaman masyarakat yang perludiperhatikan, tetapi tidak langsung bolehdiikuti dengan mutlak karena masih adanorma-norma moral yang menjadi dasar
kolektivitet
rapat
massa protest,
tolong menolong
kolektivitet
15
Etika Sosialisme Religius Bung Hatta

penilaian kita terhadap norma-normalain yang berlaku, termasuk ketentuanpe-nguasa. Terhadap norma-normamoral, semua norma yang lain mengalah(Suseno, 1975: 20-21). Sikap kritis itukita ambil sebagai tanggung jawab moralyang menuntut agar kita terus menerusmemperbaiki apa yang ada supaya lebihadil dan supaya orang dapat hidup lebihberbahagia. Kaidah-kaidah norma moraldasar itu adalah dan
(Suseno, 1975: 103-104).
B i l a p e n d a p a t t e r s e b u tdihubungkan dengan pembicaraan kitatentang anasir-anasir demokrasi asliIndonesia, maka norma-norma yangterdapat dalam anasir-anasir tersebutharus dapat dikembalikan pada duakaidah norma moral dasar itu. Normadalam anasir gotong-royong atau tolong-menolong dapat dikembalikan padakaidah sikap baik dalam artian bahwakita memandang seseorang atau sesuatutidak hanya berguna bagi saya. Normadalam anasir rapat dan mufakat selainmengandung kaidah sikap baik, dalamartian kita menghormati pendapat oranglain, juga membiarkan seseorang atausesuatu berkembang demi kepenting-andia sendiri, juga mengandung kaidahkeadilan dalam arti memberikan hakyang sama kepada semua orang untukhadir dan berpendapat. Norma dalamanasir hak untuk protes dan hak untukmenyingkir dapat dikembalikan kepadakaidah norma moral dasar keadilankarena hak protes adalah untukmenyatakan bahwa bahwa mereka butuhkeadilan dari keputusan yang dibuat olehpenguasa, sedangkan dalam hak untukmenyingkir terdapat terdapat hak
seorang untuk menentukan nasibnya sendiri(Hatta, 1966: 26).
Proses terjadinya suatu pemikiranpada suatu masa berhubungan dengankondisi lingkungan sosial budaya padamasa ketika proses pemikiran tersebutterjadi, demikian juga dengan pemikiranBung Hatta. Perubahan kondisi lingkungansosial budaya tentunya telah terjadi dalamrentang waktu yang panjang sampai masasekarang, yang mau tidak mau ikutberpengaruh terhadap pemikiran BungHatta, sehingga pemikiran tersebut perludiinterpretasikan kembali sejalan denganperubahan yang terjadi agar tetap aktual.
Pe mi k i r an t en t an gsosialisme sebagai dari kapitalismememang pada jaman Bung Hatta sedangsubur, apalagi yang berbau marxis-leninisme yang waktu itu baru saja menangdi Rusia. Walaupun sosialisme yangdimaksudkan Hatta ada perbedaan darisosialisme Barat (apalagi historismaterialisme Marx), tapi seperti yangdiakui Hatta sendiri ada titik temu antarakeduanya. Mereka (Sosialisme Indonesiadan Sosialisme Barat) sama-samamengkritik kapitalisme yang menindas danmenghisap masyarakat bawah dengan caraakumulasi dan konsentrasi kapital padagolongan tertentu. Tapi kritik tersebut telahmembuat kapi ta l isme mengoreksik e l e m a h a n - k e l e m a h a n n y a d a nmemperbaikinya (antara lain dikenal lewat“ , Hatta tahu juga tentang itu),yang menjadikannya mampu bertahanterhadap kritik sosialisme, bahkansosialisme sendiri yang kedodoran dengansistemnya yang cenderung sentralistik(malahan sosialisme yang berhaluanmarxisme/komunisme sudah hancur
kaidah sikap baikkaidah keadilan
P er t a m a ,counter
welfare state”
Relevansi Pemikiran
16
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

berkeping-keping). Maka seruan yangberkali-kali diteriakkan Hatta bahwadalam Sosial isme, t idak adanyakemiskinan dan kemelaratan hidup terasanaif dan malah menjadi utopia (yang maudia hancurkan dengan cara mencarisumber sosialisme di bumi Indonesiasendiri). Data menunjukkan bahwa justrudi negara-negara sosialis jumlahpenduduk miskin dan melarat lebihbanyak dari negara kapitalis dan sekarangkapitalisme malahan telah mengglobalke seluruh pelosok dunia (sebuah akhirsejarah kata Fukuyama). Tapi di lain pihakteriakan itu justru mengungkapkanharapan-harapannya yang tulus yangmenunjukkan bahwa Hatta adalahseorang yang religius, yang mendasarkanpada Etik Islamnya, bahwa kemiskinan,kemelaratan, penindasan adalah tidak adilpada dirinya, manusia harus diperlakukansebagai tujuan pada dirinya sendiri, danitulah yang relevan sekarang ini, dimanakemiskinan terjadi dimana-mana (apalagidi Indonesia), penindasan (dalam bentukapapun), manusia diperlakukan layaknyabinatang (dibakar, ditembak, dipancung,dll), dan memang itu semua harus kitaperangi dan dicoba untuk dihapuskan,walaupun (mungkin) tidak melaluisosialisme (lagi)!
Konsistensinya dalammenentang segala penindasan danpenjajahan di dunia bersumber dari nilai-nilai etis humanismenya, walaupunsekarang hampir tidak ada penjajahandalam arti konvensional (pendudukansuatu wilayah oleh negara lain). Nilai etishumanismenya terletak pada bahwa suatupenindasan atau penjajahan tidak bisadibalas dengan penindasan atau pejajahanbaru, tidak dibenarkan aksi balas
membalas yang tidak ada akhirnya danmengajak negara-negara untuk bersama-sama menjaga perdamaian dunia,membangun kesejahtera-an dunia,menghormati kemerdekaan masing-masing negara, menghapuskan kekerasandan eksploitasi seperti dikatakannyadalam IndonesianAims dan Ideals:
Tentunya patut diperhitungkanbahwasanya sekarang penjajahan itu lebihbersifat hegemonis, sangat halus yangdatang bersama globalisasi, tapi kalaupunarti kemerdekaan Hatta lebih cenderungdalam arti konvensional sesuai denganmasa itu, itupun tetap bernilai karena itupaling tidak menjadi kondisi dasar kitauntuk menjadi titik tolak ke arah refleksidan antisipasi tentang adanya penjajahanbentuk lain.
Keinginannya untuk“membumikan” demokrasi denganmencar inya d imembuatnya sampai pada kenyataanbahwa sifat dasar kita adalah .Lepas dari benar tidaknya kenyataantersebut, “pembelaannya” cenderungbersifat ideologis karena dia sampai padapernyataan bahwa individu adalah alatuntuk melaksanakan tujuan masyarakat,dengan mengatakan bahwa dia telahberjuang menentang individualisme yangberkaitan dengan perlawanannyaterhadap kapitalisme (walaupun padabagian lain menyatakan bahwa manusia(individu) harus diperlakukan padadirinya; ilmu adalah alat, negara adalah
Kedua,
Ketiga,
desa demokras i
kolektivitet
Men of all nations wanted lasting peace,prosperity for the whole world andfreedom for every country. They wantedto make it possible for all peoples to berid of evi ts of oppresion andexploitation”
17
Etika Sosialisme Religius Bung Hatta

alat untuk kepentingan rakyat, yangmempunyai hak-hak individu seperti hakberserikat, berkumpul, hak menyatakanpendapat, dan lain lain). Memangperdebatan tentang apakah individu ataumasyarakat yang lebih didahulukan telahmenjadi klasik tetapi tetap relevan sampaidewasa ini, secara kongkrit hal itu bisadilihat dewasa ini, dimana kapitalismetelah meresapi setiap relung hati manusia,semangat individual terasa dominan dancenderung egoistik. Disinilah letakrelevansi pemikiran Hatta, menjadis e m a c a m s e n t a k a n d e n g a nmembalikkannya bahwa masyarakatlahyang utama. Sentakan itu merupakankritikan yang tajam dimana bila sesuatumenjadi dominan maka cenderunghegemonis, tetapi bersifat otokritik jugakarena bila masyarakat menjadi dominanmaka cenderung hegemonis juga.
Bertens, K. , 1993, PT GramediaPustaka Utama, Jakarta.
Frans Magnis Suseno, 1975,
Penerbitan YayasanKanisius,Yogyakarta.
____________ , 2000,PT. Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.
Kumpulan Karangan,1995,
LP3ES, Jakarta.
Mohammad Hatta, 1945,Yayasan Idayu,
Jakarta.
____________ , 1954,Penerbitan
dan Balai Buku Indonesia,Jakarta.
_____________ , 1954,Penerbitan
dan Balai Buku Indonesia,Jakarta.
____________ , 1957,Tintamas, Jakarta.
____________ , 1957,Tintamas, Jakarta.
____________ , 1966,PT. PustakaAntara, Jakarta.
____________ , 1967,
Djambatan, Jakarta.
Muhidin M. Dahlan (Ed.), 2000,
Kreasi Wacana,Yogyakarta.
Sri Ed Swasono (Ed.), 1987,
UI-Press, Jakarta.
Teichman, Jenny, 1998,Pustaka Filsafat Kanisius,Yogyakarta.
DAFTAR PUSTAKA
Etika,
Etika Umum:Masalah-masalah pokok filsafatmoral,
Kuasa dan Moral,
PemikiranPembangunan Bung Hatta,
Indonesian Aimsand Ideals,
KumpulanKarangan Jilid III,
KumpulanKarangan Jilid IV,
Demokrasi danPerdamaian,
Islam, Ilmu danMasyarakat,
Demokrasi Kita,
PersoalanEkonomi Sosialis Indonesia,
Sosialisme Religius: Suatu JalanKeempat?,
MembangunSistem Ekonomi Nasional: SistemE kon o m i d an D emo kr as iEkonomi,
Etika Sosial,
18
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

PendahuluanSeiring dengan perkembangan
media massa, khususnya koran danmajalah, cerita pendek Indonesia akhirnyamemiliki kecenderungan mengikutitradisi jurnalistik: memburu keaktualan.Tema-tema yang diangkat para penulismempunyai per-singgungan yang mesradengan peristiwa yang sedang terjadi dimasyarakat.
Sebagai genre sastra yang banyakmendapat kapling di media massa, jugakarena iklim politik yang mencengkeram,cerita pendek Indonesia menjadi sangatakrab dengan tema-tema sosial politikdalam nuansa kritik. Dalam tahap ini,cerita pendek Indonesia merupakan
, yakni hubunganantara karya dengan konteks sosialpenciptaan: pengaruh-pengaruh sosial
politik atau kecenderungan budaya yangtercermin dalam suatu karya. Suatu karyasastra adalah dokumen sosial ataudokumen human tentang keadaanmasyarakat dan alam pikiran dimanasuatu karya diciptakan (Kleden, dalamKompas, 1997:126).
Pada dekade terakhir ini (1990 –2000), tema-tema cerita pendek Indonesiajuga diwarnai oleh tema-tema kritik sosialpolitik. Para penulis yang terlibat tema-tema ini diantaranya Satyagraha Hoerip,Y.B. Mangunwijaya, M. Fudoli Zaini,Hamsad Rangkuti, Moes Loindong, F.Rahardi, Yudhistira A.N.M. Massardi,Seno Gumira Ajidarma, Jujur Prananto,Bonari Nabonenar, Agus Noor, dan masihbanyak lagi. Sasaran kritis mereka adalahrezim Orde Baru dengan Soeharto sebagaititik sentralnya. Beberapa dari cerpen-
documentary meaning
*) Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra UNAIR telp (031) 5035676
REPRESENTASI REAKSI-KREATIF LITERER ATAS PENGUASAORDE BARU DALAM KUMPULAN CERPEN SOEHARTO
DALAM CERPEN INDONESIAIda Nurul Chasanah*)
ABSTRACT
Key words:
The varians imaging on New Order’s rezime is represented by the text structure of Soehartodalam Cerpen Indonesia (SDCI). The relation of SDCI’s text structure represents thecharacteristics of Soeharto’s power which is run arrogantly, for the sake of personal needs.This phenomena is applied in varians policies New Order Government, which underlinesthe whole idea of the story. All seven short stories that are made as the research objectsaveragely shows the Java culture setting variously. This implies how influential Javaculture was on the New Order government.Various Soeharto’s imaging as a literary creative-reaction of New Order’s rezime couldbe classified as (1) Soeharto’s image as an animal; (2) Soeharto’s image as afictimal character; (3) Soeharto’s image as a dalang; (4) Soeharto’s image as a characterin wayang; (5) Soeharto’s image as a village chief.The hegemonics relation between the people and New Order’s rezime on the short storiesanthology SDCI shows a hegemony which put dominance in the front line, which meansusing coersive apparatus to up hold hegemony. By so, the representation of New Order’srezime hegemony which puts dominance in the front line.
Soeharto, New Order’s rezime, hegemony, and literary creative-reaction
19

cerpen tersebut pada akhirnya diterbitkandalam sebah kumpulan cerpen yangberjudul
Sebagai sosok atau bahkan“ikon” Orde Baru” maka berbicarat e n t a n g S o e h a r t o b e r a r t i p u l amembicarakan tentang kekuasaan OrdeBaru yang otoriter dan menghegemonirakyat dari segala lapisan.
Rezim otoriter Orde Baru yangditancapkan oleh Golkar-Soeharto-Mi l i t e r se lama 30 tahun lebihmengumandangkan kengerian dankeangkeran panjang di negeri ini.Kekuasaan dan simbol-simbol yangmengiringi atau sengaja mereka ciptakanpun menjadi demikian sakral, sehinggatak seorang pun boleh dan beranimenyentuhnya. Apalagi mengkritik,m en g e ca m , a t a u m en g h u j a t n y a(Massardi, dalam ,2000:90).
Cerita pendek Indonesia, sebagaiekspresi pengarang yang hidup dalamsistem yang dibangun Soeharto, sudahsemestinya pula jika ada yang berbicaratentang Soeharto itu, baik sebagai pribadimaupun sebagai rezim dengan sistemkenegaraan yang dibangunnya. Soehartotidak lain adalah simbolisasi Orde Baru.
merupakan kumpulan cerpen Indonesiayang mengambil tokoh Soeharto sebagaisumber inspirasinya. Tokoh utama OrdeBaru itu memang merupakan ladanginspirasi yang subur untuk dieksploitasi;beragam pencitraan sebagai reaksi-kreatifliterer atas tokoh tersebut, muncul dalamkumpulan cerpen ini.
Kumpulan cerpen(selanjutnya disebut
) memuat 17 cerpen karya 13
sastrawan Indonesia yang diedit oleh M.ShoimAnwar dan diterbitkan pertama kalio leh Yayasan Bentang Budaya.Ketujuhbelas cerpen tersebut mempunyaikesamaan indeks tentang citra “ke-Soeharto-an” sebagai penguasa OrdeBaru.
Berdasar uraian di atas maka dapatdikatakan bahwa kumpulan cerpen inimengedepankan berbagai ragampencitraan kekuasaan Orde Baru,khususnya pencitraan Soeharto sebagaipenguasa Orde Baru. Pen-citraan inidiwujudkan melalui gaya dan simbolisasiyang berbeda dari masing-masingpengarang. Hasil tulisan pengarangmerupakan suatu hasil reaksi-kreatifliterer atas pembacaan mereka terhadapsosok penguasa Orde Baru. Dengandemikian karya sastra merupakan salahsatu sarana untuk merepresentasikankekuasaan melalui berbagai simbol danpencitraan.
Berbagai reaksi-kreatif literer ataspenguasa Orde Baru yang terkumpuldalam kumpulan cerpen antara lainmengedepankan mengenai fenomenakekuasaan di Indonesia. Berbagai ragampenc i t r aan men gen a i f enomenakekuasaan di Indonesia yang ditampilkandalam kumpulan penelitian ini menarikpeneliti untuk membacanya denganmemanfaatkan teori hegemoni Gramscidan teori semiotik.
Permasalahan yang dibahas dalampenelitian ini meliputi ragam pencitraanpenguasa Orde Baru dalam struktur teks
, representasi reaksi-kreatif litereratas penguasa Orde Baru dalam kumpulancerpen dan makna relasi hegemoniantara rakyat dan penguasa Orde Baruyang tercermin dalam kumpulan cerpen
Soeharto dalam CerpenIndonesia.
Forum Keadilan
Soeharto dalam Cerpen Indonesia
Soeharto dalamCerpen IndonesiaSDCI
SDCI
SDCI
SDCI
20
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

SDCI
textualresearchcontent analysis
Pertama,Soeharto
dalam Cerpen IndonesiaKedua,
SDCI
Ketiga,
Soeharto dalam Cerpen Indonesia
.
Penelitian ini menggunakan karyasastra (kumpulan cerpen) sebagai objekkajian. Hal ini berarti penelitian inimerupakan model kajian tekstual (
) dengan memanfaatkan metodemelalui pembacaan
sastra: heuristik dan hermeneutik. Dalamproses meraih makna pada saatpembacaan hermeneutik, penelitian inimemanfaatkan teori hegemoni dansemiotik sebagai alat menganalisis modelkekuasaan Orde Baru yang diekspresikandalam teks.
Langkah-langkah yang dilakukandalam penelitian ini adalah:
Menentukan objek pe-nelitian, yaitu kumpulan cerpen
(2000);Menentukan korpus pe-nelitian,
yaitu tujuh cerpen dari tujuh belas cerpendalam yang memuat wacanakekuasaan sebagai reaksi-kreatif litereratas penguasa Orde Baru. Ketujuh cerpentersebut adalah, Menembak Bantengkarya F. Rahardi; Paman Gober karyaSeno GumiraAjidarma; Diam karya MoesLoindong; Tembok Pak Rambo karyaTaufik Ikram Jamil; Bukan Titisan Semarkarya Bonari Nabonenar; Celeng karyaAgus Noor; Senotaphium karya AgusNoor.
Menganalisis korpus pe-nelitian dengan memanfaatkan teorihegemoni dan teori semiotik, denganlangkah-langkah sebagai berikut;melakukan pembacaan heuristik, denganmendata kata-kata yang bersifatungramatikalitas pada kartu data.Berdasarkan pembacaan heuristik inidiharapkan dapat diketahui model-model
kekuasaan Orde Baru yang ditampilkandalam karya sastra (kumpulan cerpen)ini; m e l a k u k a n p e m b a c a a nhermeneut ik, mencari informasimengenai kata-kata yang bersifatungramatikalitas pada data sekunder(artikel, rujukan tentang relasi hegemoniantara rakyat dan penguasa) danmelakukan analisis semiotik (memaknaisimbol-simbol yang digunakan) denganmeman-faatkan teori hegemoni dansemiotik; merumuskan makna relasihegemoni antara rakyat dan penguasaserta merumuskan fungsi sosial teks bagimasyarakat.
Karya sastra merupakan dokumensosial atau dokumen human tentangkeadaan masyarakat dan alam pikirantempat suatu karya sastra dicipta dandilahirkan (Kleden, 1997:126). Karyasastra yang mengangkat tema-tema sosialpolitik pasti lebih banyak me-nohok parapenguasa, baik penguasa sebagai pribadimaupun sistem yang dibangunnya. Ketikapenguasa dan sistem yang dibangunnyasemakin tidak demokratis. Semakinbanyak pula karya sastra yang berusahamembebaskannya.
merupakan kumpulan cerpen Indonesiayang mengangkat tema-tema sosialpolitik, dengan merepresentasikan tokohSoeharto sebagai penguasa (tokoh utama)Orde Baru. Tokoh utama Orde Baru inimemang merupakan ladang inspirasiyang subur untuk dieksplorasi dandieksploitasi melalui beragam pencitraansebagai hasil reaksi kreatif literer ataspenguasa Orde Baru tersebut.
Metode
Pembahasan
Representasi Reaksi-Kreatif Literer ...
21

Ragam Pencitraan Penguasa OrdeBaru dalam Struktur Teks SDCI
Ragam pencitraan penguasa OrdeBaru direpresentasikan melalui strukturteks Struktur karya sastra padahakikatnya tidak dapat dipisahkan dariunsur luar karya sastra atau dunia nyata,maka beragam pencitraan sebagai hasilreaksi kreatif literer atas penguasa OrdeBaru dalam kumpulan cerpendirepresentasikan melalui struktur teks
yang meliputi (kulit muka)buku, judul, tokoh, latar dan alur.
Representasi reaksi kreatif litereratas penguasa Orde Baru dihadirkanmelalui cover Soeharto berbusana RajaJawa lengkap dengan atributnya pluslambang garuda sebagai ikon Indonesia.Atribut tersebut antara lain adalah hiasansumping makara di telinga, kulukkanigara (tutup kepala yang menyerupaibentuk kaleng), celana cindhe, bajuberupa sikepan bludiran, kalung beruparantai yang dikaitkan pada baju, rantaiarloji. Beberapa atribut yang dikenakantersebut seperti atribut yang biasadikenakan oleh raja Jawa.
Sehubungan dengan hal in iCondronegoro (1995) mengemukakanbahwa salah satu atribut yang dipakai rajaadalah hiasan sumping mangkara ditelinga. Hiasan ini hanya dikenakan bagiraja dan putra mahkota. Selain itu,pakaian raja terdiri dari ,
(tutup ke-pala),(baju), rantai yang dikalungkan
di leher, dan karset (rantai arloji).Segala atribut yang dikenakan oleh
tokoh yang berwajah “Soeharto” dalamcover kumpulan cerpen ini merupakansimbol. Dengan demikian coverkumpulan cerpen yang memuatgambar Soeharto berpakaian raja Jawa
dengan segala atributnya plus lambangburung Garuda merupa-kan salah saturepresentasi tentang Soeharto sebagaitokoh penguasa Orde Baru yangmenjalankan kekuasaannya di Indonesiadengan model kekuasaan seorang rajaJawa.
Konsep kekuasaan yang dipegangoleh raja-raja Jawa bersifat absolut(mutlak) yang biasa dikenal dengandoktrin Dalambahasa pe-dalangan kekuasaan demikiandisebut
(sebesar kekuasaan dewa,pemelihara hukum dan penguasa duia)dank arena itu raja dikatakan
(memegangkekuasaan tertinggi di seluruh negeri)(Moedjanto, 1987:123).
Judul kumpulan yang secaraeksplisit menyebutkan nama Soehartojuga mengacu pada satu sosok pe-nguasaOrde Baru sebagai bahasan sentralkumpulan cerpen ini. Masing-masingcerpen mempunyai alur yang koherendengan peristiwa yang terjadi pada masaOrde Baru.
Ketujuh cerpen yang dijadikan objekpenelitian ini rata-rata menggambarkanlatar budaya Jawa secara variatif. Hal inimengimplikasikan besarnya pengaruhbudaya Jawa pada pemerintahan OrdeBaru. Latar yang dihadirkan baik berupalatar tempat ataupun waktu berlakusebagai penanda terhadap latar Indonesia(khususnya masa pemerintahan OrdeBaru). Penokohan atas penguasa OrdeBaru dicitrakan sangat variatif denganpenekanan karakter yang berbeda-beda.
Relasi struktur teks me-representasikan karakteristik kekuasaanSoeharto yang dijalankan secara semena-mena demi kepentingan pribadi.
SDCI.
SDCI
SDCI cover
celana cindhekuluk kanigara sikepanbludiran
SDCI
ke-agungbinataraan.
gung binathara bau dhendhanyakrawati
wenangwisesa ing sanagari
SDCI
22
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

Fenomena ini teraplikasikan dalamberbagai kebijakan pemerintah Orde Baruyang mendasari ide keseluruhan cerita.
Berdasarkan analisis struktur ketujuh cerpen di atas, ditemukan relasicerpen-cerpen tersebut dengan fenomenaper-politikan Indonesia pada masa ordebaru, baik yang berlaku untuk rezim ordebaru secara umum maupun yangmenunjuk secara spesifik kepadaperistiwa atau momen tertentu. Beberapacerpen juga menunjuk kepada personpenguasa Orde Baru secara langsung
meskipun sebenarnya antara Soehartodengan Orde Baru mempunyai hubunganpersamaan yang timbal balik. Ragampencitraan penguasa Orde Baru dalamtujuh cerpen yang dijadikan objekpenelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.
Secara umum, ketujuh cerpen yangmenjadi objek penelitian ini berelasisecara afirmatif atau mengikuti faktaperpolitikan Orde Baru. Benang merahdari relasi ketujuh cerpen di atas terdapatpada aspek ke-Soeharto-an. Aspek ke-Soeharto-an yang dimaksud hingga tahaptertentu memiliki keseragaman, meskipunmasing-masing cerpen memilik ikarakteristik yang membedakannyadengan cerpen lain.
Representasi Reaksi-Kreatif LitererAtas Penguasa Orde Baru dalamKumpulan Cerpen SDCI
23
Judul Cerpen Reaksi Kreatif Literer Acuan Relasi Kontekstual
“MenembakBanteng”
1. Jenderal Purnawirawan Basudewo2. Menembak Banteng3. Banteng jantan tua
1. Jenderal PurnawirawanSoeharto
2. MenghambatPerkembangan PDI
3. Soerjadi
Campur tangan pemerintah untukmenggagalkan terpilihnyaSoerjadi kembali pada Munas PDIIV di Medan karena dianggaptelah menaikkan perolehan suaraPDI dalam Pemilu
“Paman Gober”
1. Paman Gober2. Kota bebek3. Ketua terlama Perkumpulan Unggas
Kaya4. Gudang Uang Paman Gober
1. Soeharto2. Indonesia pada masa
Orde Baru3. Presiden terlama di
Indonesia4. Kekayaan Soeharto
Perilaku politik Soeharto selakuindividu dan pemimpin negaraterutama tentang status quo danrepresifitas
“Diam”
1. Dalang2. Penonton wayang3. Diam
1. Soeharto2. Rakyat Indonesia3. Tidak bersuara karenaadanya tekanan
Represi terhadap kritik dan bedapendapat
“Tembok PakRambo”
1. Pak Rambo2. Syam3. Tembok tidak tembus pandang
1. Soeharto2. B.J. Habibie3. Pertahanan Status Quo
Usaha mempertahankankekuasaan dan sistem keamananyang dibangun oleh Soeharto
“Bukan TitisanSemar”
1. Kepala Desa Kadhung Makmur2. Hari jadi kelimapuluh sekian3. Pagelaran wayang dgn lakon Semar
1. Soeharto2. Hari jadi Ind ke 52-53
(1997-1998)3. Pagelaran wayang:
“Semar Mbabar Jati Diri”
Peristiwa menjelang kejatuhanSoeharto dari jabatankepresidenan dan masalahrepresifitas
“Celeng”
1. Celeng2. Jalan Cendana3. Orang yang berseragam dan
bersenjata4. Pembunuhan warga kota
1. Soeharto2. Kediaman Soeharto3. ABRI4. Pembunuhan anggota
masyarakat
Fenomena penghilangan paksa(militerisme)
“Senotaphium”
1. Papa Hartanaga2. Jendral Wirenatopolus3. Inklonesia4. Jalan Canderanasia5. Bukit Harbangus6. Neo Sliokartus
1. Soeharto2. Jenderal Wiranto3. Indonesia4. Jalan Cendana5. Bukit Astana Giri Bangun6. Solo atau Surakarta
Rekayasa seputar penghentianpenyidikan terhadap Soeharto
Tabel 1. Ragam Pencitraan Orde Baru pada Tujuh Cerpen dalam SDCI
Representasi Reaksi-Kreatif Literer ...

Keragaman wujud pencitraanSoeharto sebagai reaksi kreatif literer atasp e n g u a s a O r d e B a r u d a p a tdikelompokkan menjadi beberapa hal,yaitu (1) Pencitraan Soeharto sebagaibinatang; (2) Pencitraan Soeharto sebagaitokoh fiktif; (3) Pencitraan Soehartosebagai dalang; (4) Pencitraan Soehartosebagai tokoh pewayangan; dan (5)Pencitraan Soeharto sebagai Kepala Desa.
Hegemoni memiliki makna ideologidominan. Pada rezim Orde Baru ideologidominan yang dijadikan pembenarankebijakan bagi apparatus pemerintahyaitu “pembangunan”. Di Indonesia kata“pembangunan” sudah menjadi katakunci bagi segala hal. Secara umum kataini diartikan sebagai usaha untukmemajukan kehidupan masyarakat danwarganya. Seringkali kemajuan yangdimaksud adalah kemajuan material.Pembangunan seringkali diartikansebagai kemajuan yang dicapai olehsebuah masyarakat di bidang ekonomi(Budiman, 1995:1). Pembangunan selaludijadikan pembenaran terhadap setiapkebijakan yang diambil masyarakatpolitik ( ).
Di Indonesia, penguasa sangatsedikit yang mendapatkan persetujuantotal (hegemoni total tanpa dominasi atasmasyarakat). Negara Orde Baru justrulebih mengedepankan dominasi, yangberarti penggunaanuntuk penegakan hegemoni. Hal ini dapatterbaca melalui pola tindakan yangdiambil terhadap masyarakat apabilamereka melakukan oposisi politik secaraterbuka. Para buruh, mahasiswa, dan
intelektual lebih sering berhadapan secarafrontal dengan aparat kekerasan negaraseperti militer, polisi, dan penjara, setiapkali menyuarakan pendapat yangberoposisi dengan hegemoni politikpenguasa (Patria danArif, 1999:185).
Kisah dalam cerpen “MB” meng-i n d i k a s i k a n p r o s e s p e rg a n t i a nkepemimpinan dalam tubuh PartaiDemokrasi Indonesia pada tahun 1993.Relasi hegemoni antara rakyat danpenguasa yang tercermin dalam cerpen“MB” adalah bahwa pemerintah, dalamusahanya untuk membatasi populasibanteng atau pendukung PDI, jugamelakukan infiltrasi ke dalam tubuh partaipolitik. Soerjadi atau “banteng jantan tua”sebagai -nya, menjadi ketua umumPDI akibat campur tangan pemerintah.Artinya, bisa jadi pemerintah mencobamemasukkan orang-orang yang dianggap“dapat dikendalikan” ke dalam tubuhparpol untuk mencegah parpol tersebutmelakukan manuver-manuver yangmengancam stabilitas politik. Soerjadisendiri bisa jadi pula tidak mengetahuiskenario tersebut, sehingga ketikalangkah-langkah politiknya mulaimelenceng dari garis yang ditetapkanpemerintah atau penguasa, ia harusdihentikan. Dengan demikian, salah satukecenderungan perpolitikan Soehartosebagai penguasa Orde Baru berupamanipulasi serta rekayasa politik.Artinya,semua aset politik dalam sistempemerintahan, dikelola serta dikondisikansedemikian rupa hingga mencapaistabilitas yang menguntungkan penguasaitu sendiri. Fenomena ini bisa jadimerupakan alat untuk melegitimasiawetnya pemerintahan Soeharto.
Cerpen “PG” mengisahkan tentang
Relasi Hegemoni antara Rakyat danPenguasa Orde Baru dalamKumpulan Cerpen SDCI
political society
apparatus koersif
ground
24
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

ketidakberdayaan masyarakat dalammenghadapi seorang penguasa besertasistem yang dibangunnya. Penduduk tiaphari berharap agar ada kabar tentangkematian penguasa tersebut. Fenomenaini me-nunjukkan adanya keterpaksaanuntuk mengakui dominasi penguasa yangsedang berkuasa. Kekuasaan hegemonikdalam cerpen ini ditunjukkan denganmempergunakan “musuh” untukmelegitimasi kekuasaannya dan melaluipembangunan-pembangunan yang telahdilaksanakan. Paman Gober berusahamemaparkan tentang has i l -has i lpembangunannya untuk kemajuan kotabebek. Warga kota bebek sebenarnyatidak setuju, tetapi mereka tidak kuasa,tidak ada yang berani melawan kebesaranPaman Gober. Kekuasaan hegemonikdapat dilihat dengan berjalannyademokras i , t e tap i t idak pernahbergantinya pimpinan.
Cerpen “Diam” mengabstraksikankehidupan politik masyarakat Indonesiayang beku. Masyarakat diumpamakanseperti menonton pertunjukan wayangkulit, di mana sang dalang berperansebagai aktor tunggal. Tidak boleh adayang mencampuri, sebab dalang telahmen-jalankan pakemnya. Relasihegemoni dalam cerpen “Diam” tampakpada situasi “pasif” dari penonton yangsengaja diciptakan. Hal ini merupakanrepresentasi dari tokoh Soeharto yangdalam gelaran wayang Orde Baru jugamenjadikan rakyat pasif. Partisipasipolitik yang dibangun adalah partisipasisemu, demokrasi yang dibangun adalahdemokrasi terpimpin (serupa dengan OrdeLama) yang mengakibatkan bencana.
Cerpen “Tembok Pak Rambo”berbicara tentang usaha mempertahankan
kekuasaan dan sistem keamanan yangdibangun oleh Soeharto. Relasihegemoni dalam cerpen “TPR” antara laintercermin melalui kata-kata berikut“kekuasaan yang ada padaku”, dan“menolak permintaan Pak Rambo pula,sama artinya membenturkan muka kedinding sampai hancur”. Kekuasaanhegemonik di tun jukkan denganditampilkannya beberapa orang dekat PakRambo yang mengatakan bahwa tembokPak Rambo yang sedang dibangun Syamtembus pandang. Padahal dalamkenyataannya, tembok tersebut samasekali tidak tembus pandang. Denganmenggunakan kekuasaannya, Pak Rambodapat menekan s iapapun untukmengatakan sesuatu seperti apa yangdikehendaki-nya.
Cerpen “BTS” merupakan re-presentasi dari Soeharto yang dalamrangka HUT RI ke 50 mengumpulkanpara dalang untuk menggelar pertunjukanwayang dengan lakon “Semar Mbabar JatiDiri”. Lakon tersebut dipergunakansebagai alat untuk melegitimasi diri dankekuasaannya. Relasi hegemoni dalamcerpen “BTS” tampak pada sikap KepalaDesa yang memaksa para dalang untukmenggelar pertunjukan dengan lakonsesuai pesanannya. Konsep dasarhegemoni adalah kesepakatan (konsesus)bukan paksaan, namun fenomena dilapangan menunjukkan bahwa posisitawar-menawar dalang dengan kepaladesa sangat lemah, sebab diibaratkansebagai hubungan buruh dan majikan.Dalang dalam hal ini memposisikandirinya sebagai alat legitimasi kekuasaanK e p a l a D e s a . D a l a m h a l i n i ,pembangunan ternyata selalu meng-untungkan apparatus negara namun
25
Representasi Reaksi-Kreatif Literer ...

menyengsarakan rakyat. Dalang sebagaiintelektual tradisional di pedesaans e h a r u s n y a i n d ep e n d en t d a l a mpertautannya dengan negara, namundominasi negara tidak ter-hindarkan.Fenomena di atas merupakan representasidari tindakan Soeharto pada awal tahun1995, dimana pada saat itu para dalangberkumpul dan sepakat akan me-mainkanlakon “Semar Mbabar Jati Diri” sebagaipelegitimasi kekuasaan dirinya sebagaipemimpin negara.
Cerpen “Celeng” menceritakanfenomena penghilangan paksa. Dalamcerita tersebut dikisahkan bahwa banyakwarga kota yang mati terbunuh atau hilangkarena serangan celeng. Warga kota punmemburu celeng sampai akhirnyaberhenti di ibukota, tepat di Jalan Cendana.Relasi hegemoni dalam cerpen “Celeng”ini tampak pada fenomena dihadangnyapara pembur celeng itu oleh orang-orangyang berseragam dan bersenjata.Fenomena ini merupakan representasidari para mahasiswa atau masyarakatyang sedang melakukan demontrasi padapenguasa, tetapi pada saat merekademonstrasi mereka sering di-hadapkansecara frontal dengan aparat kekerasannegara seperti polisi dan militer.Fenomena ini selalu terjadi setiap kalianggota masyarakat menyuarakanpendapat yang beroposisi denganhegemoni politik pe-nguasa.
C e r p e n “ S e n o t a p h i u m ”mengisahkan tentang rekayasa seputarpenghentian penyidikan terhadap kasusSoeharto. Kisah dalam cerpen inimerupakan representasi dari rekayasaseputar dihentikannya penyidikanterhadap mantan Presiden Soeharto.Artinya, alasan sakit yang digunakan
Jaksa Agung untuk menghentikanpenyidikan terhadap Soeharto hanyalahs t ra teg i yang di ja l ankan untukmengamankan Soeharto dari jeratanh u k u m . S e m e n t a r a d i t e m p a tperlindungannya, Soeharto tengahmempersiapkan diri atau penerusnyauntuk kembali berkuasa di bumi Indonesia.Asumsi ini tampaknya hampir menjadikebenaran dengan munculnya Tutut atauSiti Hardiyanti Indra Rukmana, putrit e r t u a S o e h a r t o d a l a m k a n c ahperpolitikan Indonesia. Tutut yangdikenal paling aktif dalam bidang politik,pada kampanye Pemilu legilatif 2004dicalonkan oleh Partai Karya PeduliBangsa (PKPB) sebagai calon presiden.Rekayasa di atas merupakan salah satubentuk kekuasaan hegemonik yang dapatter jadi karena Soeharto masihmempunyai kekuasaan cukup besar untukmempengaruhi kebijakan dalam negeriIndonesia melalui tangan para loyalisnyadalam struktur pemerintahan.
Berdasarkan pembahasan di atasdapat dikatakan bahwa relasi hegemonid a l a m k u m p u l a n c e r p enm e n g h a d i r k a n h e g e m o n i y a n gmengedepankan dominasi, yang berartidengan menggunakanuntuk penegakan hegemoni. Dengandemikian, representasi hegenonip e n g u a s a O r d e B a r u l e b i hmengedepankan dominasi. Hal ini dapatterbaca melalui pola tindakan yangdiambil terhadap masyarakat apabilamereka melakukan oposisi politik secaraterbuka. Mereka akan lebih seringberhadapan dengan aparat kekerasannegara secara frontal dalam menyuarakanpendapat yang beroposisi denganhegemoni politik penguasa.
S D C I
apparatus koersif
26
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

SimpulanRagam pencitraan penguasa Orde
Baru direpresentasikan melalui strukturteks mulai dari cover, judulkumpulan , judul cerpen, rangkaianalur, latar, dan tokoh. Relasi Struktur teks
merepresentasikan karakteristikkekuasaan Soeharto yang dijalankansecara semena-mena demi kepentinganpribadi. Fenomena ini teraplikasikandalam berbagai kebijakan pemerintahOrde Baru yang mendasari idekeseluruhan cerita.
Keragaman wujud pencitraanSoeharto sebagai reaksi kreatif literer atasp e n g u a s a O r d e B a r u d a p a tdikelompokkan menjadi (1) pencitraanSoeharto sebagai binatang; (2) pencitraanSoeharto sebagai tokoh fiktif (3)pencitraan Soeharto sebagai dalang (4)pencitraan Soeharto sebagai tokohpewayangan (5) pencitraan Soehartosebagai Kepala Desa.
Relasi hegemoni antara Rakyat danPenguasa Orde Baru dalam kumpulancerpen menghadirkan hegemoniyang mengedepankan dominasi, yangberarti menggunakanuntuk penegakan hegemoni. Dengandemikian, representasi hegemonip e n g u a s a O r d e B a r u l e b i hmengedepankan dominasi.
DAFTAR PUSTAKA
SDCISDCI
SDCI
SDCI
apparatus koersif
Anwar, M. Shoim (editor). 2001..
Yogyakarta: Yayasan BentangBudaya.
Budiman, Arief. 1995.. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Condronegoro, Mari S. 1995.
Yogyakarta: YayasanPustaka Nusatama.
Kleden, Ignas. 1997. “Simbolisme CeritaPendek” dalam
1997. Kompas, hal 126.
Massardi, Noorca M. 2000. “Awas, OrdeBaru….!” dalam ,No. 35, 3 Desember 2000, hal 90.
Moedjanto, G. 1987.
Yogyakarta:Kanisius.
Patria, Nezar dan Andi Arief. 1999.
. Yogyakarta: PustakaPelajar.
Riffaterre, Michael. 1978.. Bloomington and London:
Indiana University Press.
Soehartodalam Cerpen Indonesia
Teori PembangunanDunia Ketiga
Busana AdatKraton Yogyakarta 1977-1937:Makna dan Fungsi dalam BerbagaiUpacara.
Anjing-AnjingMenyerbu Kuburan. Cerpen PilihanKompas
Forum Keadilan
Konsep KekuasaanJawa: Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram.
Antonio Gramsci: Negara danHegemoni
Semiotics ofPoetry
27
Representasi Reaksi-Kreatif Literer ...

Introduction
Colonial intrusion and its impacts ongender relations and masculinities
Colonialism is a form of culturalcontact which is influential in theconstruction of gender relations. BesideIndian and Islamic influences, Europeaninfluences brought about by Dutchcolonialism were pivotal in theconstruction of gender relations during theprocess of state formation that eventuallyresulted in the modern nation state ofIndonesia.
In relation to the construct ofmasculinities, the rising awareness ofwomen’s rights as one of the impacts ofmoderni ty introduced by Dutchcolonisation needs to be taken intoaccount. The awareness emerged as Dutchcolonial policies to reform the wellbeingo f i n d i g e n o u s p e o p l e b e c a m e
institutionalised in the late phase ofcolonial period.This article discusses theways these reformative policies affectedwoman’s identity and how theychallenged indigenous masculinities inthe late stages of the colonial encounter.Sources discussed are drawn both fromhistorical accounts on the impacts of thepolicies on education for girls andmarriage, as well literary representationsthat touch on related issues.
In late colonial period, both inIndonesia and elsewhere, female colonialsubjects often became the object and siteof the imposition of reformative colonialpolicies. In the minds of reformist and
*) Departemen sastra Inggris Fakultas sastra UNAIR telp (031) 5035676,email [email protected]
GENDER RELATIONS in LATE COLONIAL INDONESIA: ABRIEF OVERVIEW and THEIR PORTRAYAL in THREE
MODERN INDONESIAN NOVELSNur Wulan*)
AbstractIn late colonial period of Dutch colonisation in the Indies, reformative policies in educationand marriage potentially opened up more room for women’s autonomy. These policieschallenged the full autonomy of indigenous men. However, the growth of the nationalistspirit of the period had the effect of re-asserting hegemonic masculinity. The ambivalencesand ambiguities accompanying the interference of the colonial authority in gender-relatedmatters, such as marriage and education for girls, can be seen in the representation of maleprotagonists in three novels written in the late phase of Dutch colonisation. These novels areBelenggu, Layar Terkembang, and Manusia Bebas. There are clear indications in all threenovels that modern values are important and are to be embraced. Yet, reluctance to adoptmodern ideas emerges when they can potentially reduce the privileges and autonomy thathave been long enjoyed by men. This emerges in the writers’ portrayals of their femalecharacters as they pursue and enact their own ideals of autonomy. In all cases, the novelsrepresent changes which are occurring in gender relations among the urban, nationalistelite of the time. They do not speak for changes in Indonesian society as a whole, but theypoint towards changes that were to affect broader segments of Indonesian society in thepostcolonial period.
Keyword: gender relation, colinal indonesia, novel
28

liberal colonial authorities, these policiesoften reflected a modernist intention to‘liberate’ native women. The modernistintention can be seen in, among otherthings, education and marriage.
It is hardly surprising that the processaccompanying the formulation andimplementation of these policies wasoften imbued with controversies anddebates, since they drew together diverseand contradictory ideologies representedby the social elements involved. Theseelements included local and Dutchpolitical elites, proponents of feminism,religious leaders and people of high rankin indigenous society. In spite of the factthat the reformative policies revolvedaround the position and roles of women,the complexities and ambiguities thatcharacterised the implementation of thesepolicies are relevant because they alsoreveal aspects of the ways in whichindigenous masculinities were challengedand changed in the late stages of thecolonial encounter. Something of thisprocess can be understood from theliterature on the impact of reformativecolonial policies on education for girls andpolygamous marriage.
Since the beginning of the twentiethcentury, the colonial government began tobe more active in initiating reformativepolicies on the education of girls. This wasreflected in two congresses on the subject,which were held in the Dutch capital, TheHague, in 1916 and 1919 (Blackburn 2004,42). In the 1916 congress, views on theimportance of education for girls wereslightly varied, with most of thearguments revolved around thesignificance of girls’ education forimproving their knowledge and skills in
household matters (Blackburn 2004, 43-46). A. Limburg, whose ideas were veryinfluential in this congress, asserted thateducation for girls should be practical,covering issues such as “...hygiene ofbody, house and yard, domestic science,handicrafts, singing, nursing of youngchildren and the sick, good manners, and afeeling for all that is fine and good andtrue” (Blackburn 2004, 43).
Limburg’s affirmation of thefeminine roles of women was closelyrelated to the glorification of motherhoodin early twentieth century Britain.According to Ann Davin, at a time whenpopulation growth was considered crucialto sustain the superiority of the imperialrace, “the authority of state overindividual, of professional over amateur,of science over tradition, of male overfemale, of ruling class over working class,were all involved in the redefining ofmotherhood in this period, and in ensuringthat the mothers of the race would becarefully guided, not carried away by self-impor tance” (Davin 1978, 13) .Meanwhile, the ideas about virile andphysically healthy males who wereproduced by responsible mothers werevalorised as the primary role of men was todefend the imperial race (Davin 1978, 15).
In the colonial context, thesereformative policies intended to reinforcethe domestic and nurturing roles ofwomen had ambiguous, and sometimescontradictory outcomes. For youngwomen who first gained access to moderneducation through the expansion ofeducation for girls, the modern ideal ofwoman as manager of her own domesticsphere was accompanied by a muchhigher level of participation in the public
29
Gender Ralation in Late Colonial Indonesia ...

sphere. Women in the Indies during the1920s and 30s became much moreprominent in social and political activism,standing alongside young educated men,even as they maintained domestic rolesand responsibilities. Furthermore, therea r e i n d i c a t i o n s t h a t f a r f r o mcircumscribing the role and self-awareness of women, modern Europeannotions of woman as wife and mothermanaging her own nuclear familyhousehold actually had a liberating andaffirming role for many Indonesianwomen, rather than “re-traditionalising”their roles. The introduction of theWesternised notion of nuclear family andthe concept of housewife as beingresponsible for household matters wasresponded enthusiastically by manyyoung educated women in the 20s and 30sas a form of “liberation rather thanconfinement” (Barbara Hatley 2002,168).
Marriage was another aspect ofcolonial life on which the colonialgovernment began to exercise control. Asin the case of education and female labour,the colonial rule attempted to mould thesocial institution based on modernWestern values. Locher-Scholten’s studyon marriage in the colonial Indies pointsout that the Dutch government’s attemptto impose modern monogamous marriageas an ideal form of marriage to replacepolygamous marriages invoked protestsand debates from various groups. Theoppositions mainly came from Islamicclerks, as polygamy in the Koran is notexplicitly prohibited. The reformativemarriage law manifested, among otherthings, in the 1937 marriage draft wasmainly motivated by the request from the
Minister of the colonies, H. Colijn. Hisintention in proposing the draft was toprotect European women who married toIndonesian (Islamic) men from thepractice of polygamy (Locher-Scholten2000, 194). The protests from Islamicorganisations against the draft resulted inthe withdrawal of the draft in February1938 (Locher-Scholten 2000, 206). Inprotecting women’s rights in marriage andaccommodating these objectionssimultaneously, secular women’sorganisations proposed the reinforcementof conditional repudiation or the(Locher-Scholten 2000, 209). Throughthe , women can have more accessfor divorce.
Opposition by native males againstcolonial interferences in their most privateaffairs in colonised societies were in mostcases coloured by anti-colonial andnationalist spirit. In the Indonesiancontext, the colonial state’s attempts tointrude in marriage laws were potentialsites utilised by religious groups tomaintain the distance between IndonesianIslamic society and the “non-believers”.This could effectively justify thei n a p p r o p r i a t e n e s s o f c o l o n i a linterferences in marriage and familymatters because the colonial governmentwas the heathens who did not have anyrights to regulate Islamic marriage.Besides, family in Islam is considered tobe the most fundamental institution inwhich religious belief is inculcated(Cammack, Young, and Heaton 1996, 50).The non-interference policy in marriagelaws was disadvantageous for women as itreduced their autonomy in marriage. In thecontext of nationalist ideology, they assertthe conception that women are expected to
1
ta’lik
ta’lik
30
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

be the bearers of cultural maintenance andpurity. Women are supposed to remainpure, untainted by modern influences.Meanwhile, men are more associated withprogress characterising nationalistmovements.
Overall, it can be said that despitesome compromises and failures ininstituting reformist laws designed toimprove women’s condition in the Indiesalong the lines of Western notions ofmodernity, the modern and feminist ideasreflected in these policies did potentiallysucceed in opening up more room forwomen’s autonomy. In some areas, and tosome extent, the full autonomy ofindigenous men was challenged andreduced by the impact of these policies.However the growth of the nationalistspirit in the later period of Dutchcolonisation had the effect of re-assertinghegemonic masculinities. The centralityof this masculinity was brought to the forewithin nationalist ideology. Nevertheless,it did not go unchallenged by indigenouswomen. Compromises and ambiguitieswhich ultimately affected Indonesian men,and notions of masculinities, continued tobe present.
The dominance of men’s roles in thenationalist movements partly incited byWestern modernity, and the challenges tothem which modern women’s identitiesposed, can be seen in three late colonialIndonesian novels, namely
(With Sails Unfurled),(Shackles), and
(Free Human Beings). Written in the lateperiod of Dutch colonisation, the novelsportray in different ways the emerging
identity of modern men within theframework of the nationalist movementand how this is related to changingperspectives on women’s roles. The socialsettings of these novels are nationalist andwomen’s movements that intensified theiractivities during the final phase of Dutchcolonisation in the 1930s.
Despite the presence of main femalefigures with their feminist vision in thethree texts, is the one whichplaces the ambiguities and uncertainties ofa modern man in the centre of the novel.Depicting a triangle love relationshipinvolving Sukartono, his wife Tini, andSukartono’s mistress, Yah,captures Sukartono’s ambivalent attitudesin embracing modern values.
Sukartono’s ambiguities as a modernman are apparent in his attitudes towardhis wife, Tini. Tini is a beautiful, outgoing,and energetic woman whose involvementin women’s organisations required her tobe constantly active outside her home. Hersocial activities make her unable to playher ‘natural’ role as a dutiful wife who cangive emotional warmth to her husband.This is what Tono expects her to be,especially when he arrives home from hiswork as a general practitioner. The clashbetween Tono’s traditional expectationsof his wife and Tini’s westernised views ofa modern woman results in her rebelliousattitudes in her relationship with Tono. AsBarbara Hatley notes, this is apparent inthe opening paragraph of the novel inwhich Tini removes the notebookcontaining telephone messages fromTono’s patients. According to Hatley,Tini’s deliberate action in hiding thenotebook is a form of provocative protestat her expected role as an obedient wife
Gender Relations Portrayed inModern Indonesian Literature
LayarTerkembangBelenggu Manusia Bebas
Belenggu
Belenggu
31
Gender Ralation in Late Colonial Indonesia ...

whose duty at home is taking telephonemessages from Tono’s patients (Hatley2002, 158).
The representation of Tini as anoverly westernised woman is in starkcontrast with Yah. As the other woman inTono’s life, Yah is portrayed as being ableto provide emotional comfort that Tono isunable to obtain in his marriage with Tini.Yah is an independent but emotionallyexpressive woman who can fulfil Tono’sconservative expectations of a goodwoman. Yah is even willing to take offTono’s shoes when he visits her. Thedescription of Tini as a flirtatious andrebellious wife can be seen as the malewriters’way of highlighting the idea that amodern woman can potentially destabilisethe harmony of a marital life.
The contrasting portrayals of Tiniand Yah can be said to be the embodimentof Tono’s ambiguous attitudes toward thechanging roles of women in modern time.Despite the dominance of rationality andanalytical thinking that governs his views,his perspectives on women’s roles seem tobe less progressive. Hatley asserts that thecontradictions are some of main themesthat the novel reveals (Hatley 2002, 159).He feels emotionally secure with Yah,who is devoted and can provide him withaffection that his marriage with Tini lacks.He thinks that Jah is a ‘wanita sedjati’(Pane 1961, 28), a real woman who canshow her affection openly. Meanwhile,Tini is too independent to be controlledand willing to express her longing forTono’s attention.
Tono’s conservative views of anideal woman are significantly differentfrom Sudarmo’s in .Running an independent school not
funded by the colonial government as aform of active involvement in nationaliststruggles, Sudarmo expects his wife to beextremely tough and resilient. Because oftheir independent and nationalistcommitment not to cooperate with thecolonial authority, they have to be willingto work underground and move from oneplace to another. This difficult situationdemands them to be mentally strong.Sudarmo thinks that his wife, Sulastri, isbourgeois when she pays attention totrivial things, such as the furniture anddecoration of their house, and her dresswhen they go out to a meeting discussingthe operation of their school. Even thoughSudarmo is not depicted as craving forwomanly affection as Tono does in
deep in his heart he cannotaccept the fact that Sulastri goes on herown ways and does not listen to his advicewhen they are in marital disagreement.Sudarmo finds it unacceptable as heconsiders a woman’s position in marriageis lower than man, despite his modernviews of women’s equality: “He is hurtand humiliated, because according totraditional cultures, a woman’s position islower than a man’s, although theoreticallyhe has modern views of women’sliberation and equality.” In this situation,it is Sulastri who usually takes an initiativeto apologise.
Sulastri’s initiative confirms her“womanly desire for marital harmony”(Hatley 2002, 165). It is by no meanseasily taken as she frequently is scepticalabout her ability to endure this situation inher marriage and has to subdue her ownpride. Sulastri herself is an intellectual andsocially active woman who participatessignificantly as a teacher in her husband’s
Manusia Bebas
Belenggu,
2
32
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

independent school. Unlike Tini in, who totally challenges the
traditional role of a woman in marriage,Sulastri painstakingly attempts toreconcile the demands of her idealist andnationalist vision with her traditionalduties in marriage. This makes herportrayal as a modern woman trying to fitin with a changing world plausible.
By bringing a woman’s experiencesin undergoing conflicts, pains, and the upsand downs of marital life to the centre ofthe text, does not exploremuch of Sudarmo’s experiences inreconciling his modern views of women’sroles with his long-held opinion ofwomen’s status in marriage.Although thisconflict is apparent in his unwillingness totake the initiative to ask for forgivenesswhen he is in disagreement with Sulastri,his internal hesitation is not elaborated asmuch as Sulastri’s.
S u d a r mo ’s p e r s i s t en c e an ddetermination to realise his nationalistvision is very strong, although he has tosacrifice financially and mentally. Thisalso demands a strong commitment fromhis wife, his loyal partner in marriage andhis nationalist struggle. He is neverpresented as having uncertainty inpursuing his goals. On the other hand,Sulastri is frequently depicted as beingmentally exhausted, having to move fromone place to another without beingaccompanied by her husband. Being usedto be living in an independent household,separated from Sudarmo’s and her ownextended family, she has to sacrifice herindependence and live with her sister’sfamily when her financial ability requiresher to do so. In one time, she complains toher husband about their nomadic life-style,
and Sudarmo replies straightforwardly:“You are materialistic and troublesomewith your views of the future. If you loveme, be loyal to me. You can go if you don’tstand it anymore” . This brings a sharpcontrast between Sudarmo’s totaldeterminacy and certainty in pursuing hisnationalist visions and Sulastri’s frequenthesitation and uncertainty to move on.
Conflicts experienced by a modernwoman in her attempts to negotiateprogressive gender conceptions withtraditional gender expectations areillustrated in a more clear-cut manner inthe third text, . Thefemale protagonists of the novel, Tuti andMaria, have opposing characteristics. Tutirepresents an intellectual, independent,and modern woman, who is very active inwomen’s organisations promotingwomen’s equality. The portrayal of herpersonality is in stark contrast with hersister, Maria, who is more feminine,sociable, affectionate, and emotionallyexpressive. To some extent, Maria’spersonality echoes Yah’s in .Maria is engaged to Yusuf, a student in amedical school, who is also active innationalist movements. The story endstragically with Maria’s death oftuberculosis and, in order to realiseMaria’s wish, Yusuf and Tuti get married.The complexity accompanying a modernwoman’s attempts to fit in with amodernised world is negated by the factthat Tuti’s internal conflicts between thedemands of her activities in feministmovements and her womanly desire for aman’s love are easily resolved when sheconsiders of accepting Supomo’smarriage proposal. Although Tuti finallyrejects his proposal, she thinks the two can
Belenggu
Manusia Bebas
Layar Terkembang
Belenggu
3
33
Gender Ralation in Late Colonial Indonesia ...

coexist harmoniously. Another part of thenovel which is somewhat illogical is thedecision of Tuti and Jusuf, who previouslydo not have romantic relationship, to getmarried to realise Maria’s last wish.
The i l lust rat ion of modern,intellectual, and independent womenrepresented in different ways through Tini,Sulastri, and Tuti, can be used as a meansto examine how male protagonists viewthe roles of women in a changing world.
and , writtenby Armyn Pane and Sutan TakdirAlisyahbana respectively, can also be readas the projection of the male writers’perspectives in viewing the emergence offeminist ideas within the context ofnationalism. In Tono reflectstraditional and less progressive remnantsof patriarchal values which assume theidea that women should be able to provideemotional comfort to men. The portrayalof Yusuf in , despite hisexplicit opinion that young people,women and men, should participateactively in progressive movements toimprove the wellbeing of their people,also affirms Tono’s tendency to be morecomfortable with women whosepersonality is similar to Yah. Yusuf likesMaria more than Tuti as Maria is moreexpressive and affectionate.
, being written by a female writer,can articulate in more convincing wayshow a modern, intellectual, andindependent woman finds it very difficultto negotiate traditional and normativeexpectations of women’s roles with herown struggle to be able to voice herindividuality.
In terms of the depiction of maleprotagonists in the three novels, all ofthem represent normative masculinities ofthe period when the coming of Europeanmodern values shaped the formation oftheir identity as modern men, at the sametime when they also clashed with lessprogressive cultural values. This results inambivalent modern men represented byTono, Yusuf, and Sudarmo. Tono is adoctor whose formal training in medicalscience forms his analytical thoughtsprofoundly. Although he is not politicallyactive as the other two protagonists, hismodern perspectives are apparent in histendency to analyse events happening inhis life. Yusuf displays his progressiveattitudes through his suggestion to Mariato be actively involved in nationalistmovements. Sudarmo is the most radicalnationalist among the three. He is also themost determined in his pursuit ofnationalist visions. In short, they are allthe embodiment of rationalist andprogressive men characterising Westernmodernism.
In spite of their strongly progressiveoutlooks, the three male protagonistsseem to struggle to embrace modernvalues fully when they come to terms withthe emerging ideas of women’s liberationand equality. Their vision of ideal womenhas not shifted from traditional notions ofwomen’s roles. This can be seen fromTono’s preference for Yah who still retainstraditional characteristics of an idealwoman, namely being able to soothe andgive emotional comfort to men. Similar toTono, Yusuf also prefers an emotionallyexpressive woman. Slightly differentfrom the two, Sudarmo displays moreprogressive views in relation to modern
Conclusion
Belenggu Layar Terkembang
Belenggu,
Layar Terkembang
ManusiaBebas
34
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

women’s roles. However, as it has beendiscussed above, he also holds lessprogressive gender values apparent in hisreluctance to take an initiative toapologise when he is in disagreement withhis wife.
Alisjahbana, Sutan Takdir. 1937.. Jakarta: Balai
Pustaka.
Blackburn, Susan. 2004..
C a m b r i d g e : C a m b r i d g eUniversity Press.
Cammack, Mark, Lawrence A. Young,Tim Heaton. 1996. “LegislatingSocial Change in an IslamicSociety-Indonesia’s MarriageLaw”.
44(1): 45-73.
Davin, Anna. 1978. “Imperialism andMotherhood”.no. 5:9-57.
Djojopuspito, Suwarsih. 2000.. J a k a r t a : P e n e r b i t
Djambatan.
Hatley, Barbara. 2002. “Postcolonialityand the feminine in modernIndonesian literature” in
edited by Keith Foulcher and TonyDay. Leiden: KITLV Press.
Locher-Scholten, Elsbeth. 2000.
.A m s t e r d a m : A m s t e r d a mUniversity Press
Pane, Armyn. 1961. . Djakarta:P.T. Pustaka Rakjat.
DAFTAR PUSTAKA
LayarTerkembang
Women and theState in Modern Indonesia
The American Journal ofComparative Law
History Workshop
ManusiaB e b a s
Clearinga Space: Postcolonial readings ofmodern Indonesian literature
Women
and the Colonial State: Essays onGender and Modernity in theNetherlands Indies 1900-1942
Belenggu
35
Gender Ralation in Late Colonial Indonesia ...

The Politics of Literature1
Literature is political, JudithFetterley argues in ‘Introduction to ThePolitics of Literature ’(Fetterly, 1978:XIII) She further claims that like in thepolitics of anything else which power isthe main issue, so is in literature. The coreof power in literary politics isconsciousness:
It is also such new consciousness offeminist readings that meticulously offernew ways of reading and interpretingliterary writings.
Catherine Belsey and Jane Mooreposit that there is no such thing as neutrala p p r o a c h t o l i t e r a t u r e . A l lreadings/interpretations are political.
.
Consciousness is power. To create anew understanding of our literature is tomake possible a new effect of thatliterature on us. And to make possible anew effect is in turn to provide theconditions for changing the culture thatthe literature reflects. To expose andquestion that complex of ideas andmythologies about women and menwhich exist in our society and areconfirmed in our literature is to make thesystem of power embodied in theliterature open not only to discussion
even to change. Such questioning andexposure can, of course, be carried ononly by a consciousness radicallydifferent from the one that informs thatliterature. Such a closed system cannotbe opened up from within but only fromwithout. It must be entered into from apoint of view which questions its valuesand assumptions and which has itsinvestment in making available toconsciousness precisely that which theliterature wishes to keep hidden.Feminist criticism provides that pointand embodies that consciousness.(Fetterley, 1978)
*) Departemen Sastra Inggris Fakultas Sastra UNAIR telp (031) 5035676
POLITICS AND SOCIAL REPRESENTATIONS INLITERATURES: A FEMINIST READING OF RATNA
INDRASWARI IBRAHIM’S WORKSDiah Ariani Arimbi*)
AbstractThis paper aims to scrutinize the works of Ratna Indraswatio Ibrahim, one of Indonesianfemale writers who gives a strong concern on the politics of women’s identity in fiction. Herworks are truly reflections of how literary fictions can house as representations of femaleidentities. From the perspective of feminist readings, in her narratives women function asobjects inherited from a society that says women matter less than men: a society that thinkswomen barely belong to the culture that marginalizes and silences them through domesticity.Ratna raises critical issues about the subjugation and domination of women, and capturesthe imbalance in social relations. Yet Ratna’s women are not all submissive: those deniedtheir rights respond to the injustice they experience. Through her narratives Ratnaacknowledges the struggles of women, especially those in under-privileged conditions.
Key words: politics, representation, women and identity
36

(Belsey, 1989: I-XX) Necessarily allspecific kinds of readings inexorablycount for or against certain kinds of issues,addressing them in ways such issuesexplicitly or implicitly are talked about.Feminist literary critique may question,among other things, the ways in aparticular text represent women, how itportrays gender relations, how it labelssexual different, how it terms power-relation between different gender roles,and so forth. Even if a particular text saysnothing about gender relations, depicts nowomen at all, it is too a pivotalsignification for feminist critique.
Literature is no longer a specialcategory simply depicting reality,embodying timeless truths and neutralagendas. Literature is then ceased to beunbiased, making it parallel to theimpossibility to approach any humanproblem with a free mind, as de Beauvoirstates, “The ways in which the questionsare put, the points of view assumed,presuppose a relativity of interest; allcharacteristics imply values, and everyobjective description, so called, implies anethical background.( Beauvoir, 1953:xxvi) Hence, literature is also perceivedas interpretations of the world, just likeother kinds of art. Writing is no longer anindividual phenomenon, as it is a socialand cultural institution, in which its socialcontexts are more than just shadowingbackgrounds. Fiction becomes amanifestation in which its various formsare subjective to the ways societiescomprehend and identify themselves andthe world they live in or imagine. Thereinlies the importance of history for feministcriticism as literature has in this termturned to be exceptionally historical.
Can fiction be accounted for truerepresentation of actual life? The notionthat fiction and reality is cut cleanly seemsrather opaque when the difference of howfictitious is fact and how factual is fictionis quintessentially blurring. On one hand,the claim that literature is a mere fictitiousworld is problematic. Since there is no realwo man in th e l i t e r a tu r e , on lyrepresentation itself, then there is no oneto liberate. In this respect, feminismbecomes dematerialised and in the endwill simply turn as anachronism. Yet,there are still women who experiencesexual discrimination, who are not beingable to find jobs because they are women,who are denied their rights because theyare women, who are written out of historybecause they are women, and there arealso women who write out theseimperishable facts in literature. On theother hand, taking literature as fact willunavoidably neglect that literature is ahome-made world, a world made with theassistance of imaginative creative processof the author. A literary product does notautomatically duplicate the real. For thisreason, i t holds its reflections,exemplifying representations of the real.
Indeed, representation of the realdoes not come into a linear singularity.Asserting a singularity of representationignores the dynamic of social-historicalnotions of women crossing the spacio-temporality of their subsistence. With thehelp of deconstructionist theories that aimto decentre the subject, the relationship offemale subjective identity to sex isintricate. As identity is an on-growingprocess, a fixation of identity reflective to
Between Facts and Fiction: The ProblematicImages of Women in Fiction
37
Politics and Social Representation in Literatures ...

all women all ages is an absoluteimpossibility:
For literary analysis, the images ofwomen in fiction result in critical readingof the text to a degree that fiction isreflection to a history and narrative ofcontexts, within which the structures ofideology lie. As ideology does not appearas mere ideology, rather as subtle networkrepresenting “the imaginary relationshipof individuals to their real conditions ofexistence,”(Althusser, 1988: 85) in thisrespect, literature is ideological in itsnature, “[i]n imaginative works a movingideology can be fixed and brought toconsciousness and its contradictions canbe made visible.”(Althusser, 1988: 86)Perhaps, it may be added that in literaryworks, the structures of ideology do notappear as immediately as thematicsignification, but disperse in everyelements of the works. Thus, any literaryanalysis in conjunction with othertheoretical criticism is crucial indisclosing how the notion of ideology andits structures are maintained as literature -as one of many sides of culture - is thedomain where ideology is fabricated andrefabricated. The inclusion of analysis ofideology in literary analysis is thereforecrucial:
Even, in the case where ideologicalstructures seem to be missing in theliterary production – identifying themproves difficulty, feminist criticism musttake such absence into a considerableaccount as the absence and presence ofany ideological structures symboliseunderlying construction from which aliterary production is taken shape.
Images of women in male-dominated literary production are madeproblematic, particularly by feministcritiques. Cornillion’s
(1972) isconsidered to be one amongst theantecedent writings that scrutinise womenimages in literary production. Throughliterature, Cornillion believes, thehistoricity of women’s oppression can betraced, and by understanding theirsubjection, women can raise newconsciousness of how women were, nowand might become, provoking newdirections for women in reading andunderstanding fiction which in the endmay contribute to women’s personalgrowth.(Cornillon, 1973: ix-x) Theproblematic of images of women criticismdoes not inevitably say that they cannot
Literary works gives images ofwomen that are not absolutely identical,and the differences among them must besignificant. Historical flux and changeshould not be prematurely ended insymbolic stasis that women can sufferonce and for all an identity fixation onthe level of style, releasing action only to‘the woman’of the semiotic.
Criticism using the notion of
ideology focuses both on what is stressedas intentional and what appearssubliminal, discordant and unintentional.With the notion, we can read against thegrain, not aiming to uncover a truth butinvestigating how a transcendentalconcept of truth was formed at all.Literature inevitably colludes withideology, which is in turn inscribed inliterary forms, style, conventions, genresand institution of literary production. Butit does not simply affirm, and it canexpose and criticize as well asrepeat.(
(Todd, 1988)
Althusser, 1988: 86)
Images of Womenin Fiction Feminist Perspectives
38
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

function as a focus for feminist literaryanalysis, as such criticism may serve as apart of “solution” as Ruth Robbins argues.Literary images are definitely differentfrom reality, however those images orrepresentations are reflection of reality: toa certain degree, the presence of reality isincorporated in them. Analysis of literaryrepresentations presents a locus ofimportance for feminists who examine theways in which representations of womenand their real lives are dissimilar. Throughthe means of representations, a politicisedanalysis of reality may derive, and byreading against the grain of suchrepresentations, one can changeperceptions of reality. (Robbins: 2000: 51)
Reading images is not all times one-sided direction of the viewer looking at animage. Who is the viewer, what imagesshe looks, and how images are looked atcomplicate the problem. Looking itself isa complicated and ambiguous act ofreading, working multiple directions andcreating multiple impacts:
One may respond differently to agiven image, depending on one’sconditions of times and places. The notionof looking (the ways one looked then, onelooks now, one may look tomorrow and
one’s perception of looking at looking andre-looking) denies an assumption that agiven set of images subsists and carries afixed meaning once for all therefore easilyshape one woman’s experience and senseof her struggle in being and becoming.Looking at images, or reading images ofwomen in fiction is then not a simple act ofreading but a rich and complicated waysof looking, looking at what others look athow women were defined, are defined andmay defined. Accordingly, feministliterary criticism develops a criticalpresentation of such looking by adding thedynamic of the whole process ofreading/looking aiming to invigoratemultiple relationships between the femalesubjective and the social and they appearin fiction through literary representations.
For literary analysis fiction is nolonger read without critically questioningimages produced within its narrative. Asfict ion is constructed from theinterweavings of cultural narratives, itthus for feminists is “a cultural strategy forperforming identity claims,” when thesefeminist “become aware of the hugeimpact that literary works can have onpublic opinion.” (Lara, 1998: 92) Infiction, identity formation is amongst themost observable materials constantlylocated within its narratives. Throughnarratives which, by and large, is drawn onthe materials of everyday life, charactersliving in the narratives generate theiridentity formation translating eachindividual meanings through their stories.For the readers, reading such stories –looking at other stories – creates a boundconnecting the readers and the charactersthat continuously engage themselves inthe process of identity formation:
The way a woman looks mightmean either a description of herappearance, or a description of her act oflooking at others; the two kinds oflooking might even be modified by eachother. As such, images at which one lookscan e simultaneously both a call towardsor a warning against a particular way oflooking . . . and an opportunity to lookdifferently, to criticise or refuse that lookin favour of another way of looking.(Robbin, 2000: 57)
39
Politics and Social Representation in Literatures ...

Women have use the word‘personal’because emplotment has beentheir tool to create individual meaningthrough other stories – of the women ofthe past – in order to tie into a historicalunderstanding the ongoing content ofwomen’s lives within narratives that offera wider conception of ‘agents’ as moralsubjects. In this sense, individuals do notsimply have memories in the historicalsense, but, by adopting everchangingattitudes toward them, continuouslyreconstructing them, they can developnew interpretations. . . . Identity isconceived differently in narratives notonly because past experiences arerewoven through time, but also becauseeach new and broader narrative givesnew meaning to society’s own largernarrative.
Saya kira negeri ini berkaraktermaskulin. Karena itu dia suka padasimbol simbol kekerasan. Sebagaiilustrasi, bias-bias ideologi patriarkiyang ada di negeri kita memunculkansebuah dampak yang besar, melebarpada system di negeri ini. Artinya negerid a l a m k o n t e k s i n i l e b i hmempresentasikan laki-laki. Danperempuan seperti apakah yangdibesarkan oleh tradisi maskulin?Seperti biasanya, mereka terbentukmenjadi silence mass dan masyarakatmarjinal. Disadari atau tidak, lelaki dinegeri ini masih beranggapan, perananperempuan berada tetap di domesticsocial. Jadinya dalam cerita apapunyang jadi super hero adalah laki-laki.(Ibrahim, 2003: 1)
(Lara, 1998: 93)
The problematic of fictitious fact orfactual fiction lies on the fact that theexchange between renders it difficult tosolely divorce each other. But, as fiction isone of privileged sites of representation, itdoes celebrate its positioning of asdownright subject of images of womencriticism, as fiction translates the verydichotomy – fiction/fact, art/life intohybrids of forms and languages.
In Indonesian Literary tradition, oneof authors strongly presents politics ofgender and social representations,especially of women in fictions is RatnaIndraswari Ibrahim.
Since she started writing in 1975,numerous of her short stories werepublished in collections including
(2001),(2003),
(2002),(2002),(2003), and her recent novel
(2003). Ratna is probably part oftradition as her works were
scattered in various newspapers such as, before issued in
collection of short stories mentioned afore.Not so dissimilar with other women
authors, Ratna’s writing object is womenwhom she knows well. She believes thather narratives shapes a women’smovement as it also functions as counterdiscourse of masculinity that has beenrooted in Indonesian public for times. Shewrites:
Consequently in a country likeIndonesia which is largely characterisedby masculinity, women’s literature is, to acertain extend, marginalised. However, bythe same token, literature can play as apowerful means to vocalise against suchmarginalisation it is put into. Literature
Ratna Indraswari Ibrahim and HerChallenges to Gender Inequality
Namanya Masa Noda PipiSeorang Perempuan Aminah Di
Satu Hari Lakon di Kota KecilBukan Pinang Dibelah Dua
LemahTanjungSastra Koran
Kompas Jawa Pos
40
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

alone, for Ratna is capable of protestingthe marginalisation and victimisation ofwomen. Taken within the standpoint ofliterature and women’s movement,resistance writings are explorative andpowerful media against injustice andoppression. Through writings, Ratnaconcludes, she can break the women’ssilence mass, and enunciate injusticesforced upon them. At the same time, tobring women’s voice into public hearing,she attempts to smash women’smarginalisation by repositioning themfrom the periphery to the central. Sheexemplifies further with her newest novel
, a novel based on truestory. All female characters in the novelare resisting domination forced againstthem. Ibu Indri, one protagonist in thenovel, for example, never surrenders herstruggles to protect the only green area inher city against attempt transferring it intoa shopping mall. Nevertheless, Bu Indri’sstruggles are kept silenced by simplybeing unrecorded in the public mind.Ratna’s retelling Bu Indri’s story marksher struggle to reconstitute one localwoman’s history into the public memory.This is exactly how Ratna positions herrole as an author: believing that with herwritings she can record the history of thewomen’s struggles and bring it to thepublic’s attention.
A literary work is the soul of itsauthor, Ratna strongly believes. Howeverit is a product of literary imagination, thefactuality in this so-called imaginativeworld is still reflective of the real: therepresented real of its author and hersurrounding world, creating the world in ita reality of its own. Through her storiesRatna presents us the revival of socialrealities in fiction. Her fiction is not aproduct of literary imaginationrather her fiction shows a reality andawakens our dreams in a story. In aninterview, Ratna reveals that hernarratives are based on factual researches,which then blended with her imagination,and certainly her reading of suchexperience. Her works thus are speakingreality. Furthermore, the politics of herworks lies on her goal to treat her fiction asa witness of injustice. She states:
Ratna’s short stories are shaped totell the tales of injustices and repression inIndonesian lives, especially experiencedby women. Through them only Ratna hasher ways in showing her concerns ofwomen’s problems. Accordingly, fiction
Lemah Tanjungper se
Ketertarikan saya itu karena . ..saya bukan ahli sejarah . . . tapi sayamencoba. Tokoh ini namanya IbuIndrasih, sekarang beliau sakit kerast i d a k b i s a j a l a n , t a p i d i amemperjuangkan sendiri dengan tigaanaknya, dengan komunitas kita sampaihari ini. Kembali ke masalah sejarahtadi, saya coba merekamnya, sejarah
lokal ini. . . . Jadi semuanya itu true story. . . .Tapi karena saya bukan ahli sejarah,saya mencoba meramunya dalam segifiksi.
Saya dapat melihat dan merasakanmaskulinitas itu dari “teks-teks” sosialyang sarat dengan pelecehan sosialterhadap perempuan. Dan saya kira itusemua akibat hegemoni patriarki yangtelah tumbuh cukup lama dalam negeriini. Untuk itu, saya tertantang untukmenulis cerpen sebagai saksi atasketidakadilan.
2
3
(Subiantoro, 2002: 103-114)
41
Politics and Social Representation in Literatures ...

is a reflection of culture. The more womenwrite from their own perspectives,especially in fiction, the more they areaware of their domestic and public roles,and this awareness will empower them todefend their rights out of men’sexploitation. (Ibrahim, 2003: 2)
Ratna’s foremost depiction of femalecharacters in her nar ra t ives i smarginalised and victimised Muslimwomen who largely dwell in rural areas,especially in Malang and its surroundingareas. According to her, these women areusually erased from public rememberingas they are simply forgotten or assumed tobe unimportant, while they are typical toaround 70% of Indonesian women. It isher privilege to enliven them in her stories,narrating their pain and misery mostly dueto patriarchal dominated culture whichgives these women no room for theirautonomy. Her narratives indeed project avariety of images of Indonesian Muslimwomen. Her refusal to portray urban andc o s m o p o l i t a n w o m e n w h o a r eautonomous individuals as in
’s writings breaths souls to thewomen who are not urban and who are stillby and large victims of patriarchaldomination, reminding us that feminismstill has a long way to go: to finally reachits ideal of justice and equality for allwomen. Her narratives are also areminiscence stating that most Indonesianwomen are still experiencing gender-biassystem lamentably placing them inambivalence position bordering betweentraditionalism and modernism. She says:
Tradisionalism she means is thenotion of domestication of women, whilemodernism tends to situate them in publicsocial arenas. This is her other messageworthy of noting on the ambiguity ofwomen’s position in Indonesian society.
Claiming her writings to be counterdiscourse of which citefrequently open sex discourse, Ratnainsists that there should be no such talk inwomen’s writing, for it is the language ofman that performs sex as open and vulgar.Woman language is more lyrical andrefined as it is closer to affection yetunemotional. Her opposition to
is made clear when saying that it iserroneous to juxtapose sexual liberationand feminism. Sexual liberation, as muchseen as the most salient feature of
, is a narrowly defined feminism.The danger of exposing sex and sexualactivity openly lies on its presumption thatit is feminism in its nature. Femininity isof natural God given, thus its muchexploration will reduce its beauty, and sois sex, she reasons furthermore. Sheobserves that the vulgar sexual discourseis undeniably written in(male language) as opposed to
. This is the trap that shenecessitates to avoid in her writings.Writing in female language andprivileging female experiences is heressential proposal since the achievementof equality for both sexes is crucial in anywomen’s movement.
Denying to labelled feminist, Ratnais, in a number of ways, a feminist for inher writings she puts “the woman
sastrawangi
sastra wangi
sastrawangi
sastrawangi
bahasa laki-lakibahasa
perempuan
Kalau kita bicara masalahperempuan Indonesia, satu kakinya ditradisional, satu kakinya di modern, diasendiri ambigu. . . . Tapi saya kira
masyarakat Indonesia, perempuan,ideologinya itu masih ideologi laki-laki.Cinderella complex. 4
42
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

question” into account, attempting tocritically read and attack sexual divisionof labour since such division is reflectiveof patriarchy and gender bias, not ofnatural order. Islam, in Ratna’s opinion,has introduced justice and equality forbo th sexes s in ce Muhammad’sprophethood began. As a reference to theProphet’s attempt to position men andwomen of equality the literaturehave shown these evidences.Alas, in mostMuslim world, women are historicallylimited only to domesticity and deniedtheir public rights. Like other Muslimfeminists, Ratna believes that it is notIslam that is oppressive to women, it is theculture, and Islam alone is protective tofreedom and the rights of women.Documenting social history in local,national or global level is necessary inorder to continuously challenge theprevailing roles of women assumed to bethe second sex.
In her introduction to one collectionof her short stories entitled
(a spot in a woman’scheek) Ratna professes that most of herwritings are interconnected with a singlegrand theme: the dispowerment( ) of those marginalisedlike children, women and the elderlyagainst the power of superiority; be it thesuperiority of the state, of the patriarchaldomination or even of the feudalismlegitimised by the New Order regimespeaking only in the name of authority anddominance.(Ibrahim, 2003: viii) Her shortstory entitled
exemplifies her argumentclearly. This story narrates the fear of awife believing that she was no longerattractive as she had a spot at her cheek.She told herself that it was a problem thatshe was beautiful then and not now:
Believing that previously wasrespected due to her beauty, loosing herbeauty equalled her to those disabled,deeming that her attractive nature had lefther in despair with huge burden of beingnot beautiful. Beauty seems to be aprimary category of how a woman isvalued as she underwent a medicaltreatment for her cheek and persistentlywished for a cosmetic surgery in case hermedication failed. When her husbanddeclined her need for the surgery, she wasfurious and initiated to find another manwho desired and found that she was stillbeautiful. When this other man asked herto be his mistress she suddenly realisedthat she did not want to betray hermarriage and decided to tell her husbandhonestly that her intention was merely toprove herself still beautiful even with aspot in her cheek. Her husband simplyreplied that it started out with a spot on hercheek. In the end of the story, the spotremoval was not implemented, in fact shefinally decided not to problematise it and
hadith
Noda PipiSeorang Perempuan
ketidakberdayaan
Noda Pipi Seorang
Perempuan
Valuing the Price of A Woman:Female Subjectivity, Identity and TheBody
Sekarang dia merasa menyeretbeban yang berkepanjangan. Rasanyatidak ada orang lagi yang memujikecantikannya. Padahal dulu, sekalipunmasih kanak-kanak, dia merasa punyakelebihan yang dibanggakan orang.Sekali lagi dia berkaca di depan cerminitu. Lalu dia mulai mengeluh, “Kau lihat,betapa jeleknya noda di pipi saya.(Ibrahim, 2003:9)
43
Politics and Social Representation in Literatures ...

accepted as a mark on her body.is
tactical as it brings the notion of woman’sbody right to the centre of representationof women in the literary and culturalexpressions in Indonesian tradition. InRatna’s argument, woman’s beauty whichis indeed much appreciated by womenthemselves, evidenced with the numerouscirculations of women magazines mostlydictating women tips to be physicallyattractive and beautiful, is howeverproblematic. The close associationbetween woman and her body, and howshe is valued and devalued in terms of herbeauty reformulate what has beensustaining so long in a society wherefemininity should be articulated onlythrough woman’s body. The bodynarrative in women’s literatures calls intoquestion the necessarily “true” vision onvaluing woman, at the same time itproposes the articulation of woman’s bodythrough female narrative voices whichaims to ascertain that woman’s body is notjust woman’s own affairs. Woman’s bodyhas became a battle field where politics offemale positioning is debated andpolemicised, and that woman’s body isnever free from any interpretation,particularly from male vision attemptingto dominate with his superior status. Evenif the story ends with this woman valuingher body, such valuing results from male’sinterfere, her other man. Her earlyrejection of her body is then negated byman’s acceptance. Here, it suggests thatwoman’s body can never radically escapefrom male gaze, signifying that woman isby and large identified under the man’seyes. Nevertheless, the male gaze for herbody does not rest and stop all together,
she returns such gaze by looking at herbody and feeling that her burden has beenlifted. Looking at her own body signals thegaze returned which commemorates herreturn in valuing female body. In otherwords, the woman’s identity operates in acircular motion of how woman devaluesherself from male gaze from which shereturns the gaze and enables herself tovalue her body. She then begins visible,turning herself from observed and passiveobject to active subject defining herownership of the body.
The main character inremains nameless throughout thenarrative. By not naming her maincharacter, not determining a specialindividual Ratna seems to view that theproblems of woman’s beauty might beapplicable to all women, making it centralto woman’s identity. The nameless womanhas generated two dichotomisedinterpretations. On one hand, namelesswoman involves a lacking of identity, of apersonhood that is essential in anyindividual. On the other hand, thisnameless woman transports her act fromspecific to general. This goes the samewith the husband who also remainsnameless throughout the story. Theparallelisation between the namelesshusband and wife (of man and woman)acts progressively playing the genderpolitics of equality between nameless manand woman. Nevertheless, the relativeabsence of personhood of commonwomen in every day life story must becritically signalled as it may embodyattempts of dominating authority tosimply erase these woman’s voices fromthe historical documentations in bothforms of fictional writing and non
Noda Pipi Seorang Perempuan
Noda Pipi
44
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

fictional writings.(Juminten’s
hair) as also centralises on thepolitics of woman’s body. Ratna herselfadmits that this story was created as aresult of patriarchal ideology imposing ahusband’s authority on his wife’s body,her hair for this matter.(Ibrahim, 2002)The story recalls how Juminten mustsubmit her wish to model her hair underher husband’s command. Panuwun,Juminten’s husband, never ceased toremind her that she beautified herself forher husband only. At first Jumintenwanted to have her hair cut for easier carebut Panuwun declined her request sayingthat with long hair she would look likeNawang Wulan, a beautiful goddess.Despite her allergy to the shampooPanuwun gave her, and showing herloyalty to Panuwun, Juminten persisted togrow her hair. The long hair Juminten wasseen to be more beautiful that sheattracked Nardi, the son of Panuwun’semployer. Caught in jealousy, Panuwunlimited Juminten to only domesticpresence, she was prohibited to leave theirhouse without her husband’s escort, evento join female congregation of Qur’anicreading and reciting ( ). Thisraised pros and cons on Panuwun’sdecision. Some villagers supported hisprohibition while others deemed thatPanuwun oppressed his wife. Believingthat it was all because of her hair, despiteher protest, Panuwun finally orderedJuminten to have her hair cut very short.
An Indonesian proverb says that hairis a woman’s crown. This, by and large,places woman’s body central to female’sidentity that dialogically woman’ssubjectivity and the body are parcelled
and policed through discursive systemthat establish identity through the processof relationship between a part of the bodyand assigned cultural meaning in the bodypolitics. Hair representing the bodybecomes a fragmented agent indetermining the sexual identification,strongly suggesting that the body partsmust implement specific functions and besituated in appropriate places to beconsidered normal. This what JudithButler calls as the “integrity” and “unity”of the body. Drawing her reading fromMonique Wittiq’s theory on sex andgender, Butler posits that “numerousfeatures [of the body] gain social meaningand unification through their articulationwithin the category of sex [consequently]“integrity” and “unity” of the body, oftenthought to be positive ideals, serve thepurposes of fragmentation, restriction anddomination.”(Butler, 1990: 114-115) As apart of her body, Juminten has no rightover her hair. She must relinquish herownership and is subjected to herhusband’s order.
The cultural meaning assigned to thismaterial body part pervades the bodypolitics through the metaphorisation of thesocial through the body. Hair thensignifies fragmentation, restriction anddomination at the same time. Because ofthis part of the body, Juminten is confinednot to expose it to public admiration.Public act of brazen stare to Juminten’shair showing admiration must certainly beprohibited and declared to be a breach ofrefined manners. As this was caused byJuminten’s hair, placing the blame onJuminten alone is necessary. Theproblematic body part in the storystimulates subject position and narrative
Rambutnya JumintenNoda Pipi
pengajian
45
Politics and Social Representation in Literatures ...

paradigm in which the contemporarywomen take up the body through literarypractices. The body story, for the author,the character and the reader, functionssimultaneously as a personal and political,psychological and ideological boundaryof meaning, a subjected agency throughwhich identity and objectification emerge.The corporeal body is turned into acultural “body” in which oppressivecultural identification is clearly visibleand articulated. This short story is indeedinteresting as the author illustrates therepression and the marginalisation of thefemale body by unfolding the power ofdomination and directly scrutinising thebody and its cultural meanings. In sodoing, this particular story is in itself acultural critique to the patriarchalhegemony and at the same time creatingan awareness of the relationship between aspecific body to the cultural “body” andthe body politics.
(mel ted) (Ra tna ,2002)engages the story of Liana who had toaccept a man’s marriage proposal againsther wish. This story is not in comparableto Siti Nurbaya’s force marriage.Eventually Liana would accept Jono’sproposal but the timing was not right. Shewas not ready for marriage as shepreferred to have a job of her own whichenabled her to finance the education of heryounger siblings. As the eldest child, hermother – her father deceased – reliedheavily on her to help financing hersiblings’ education. This is typical inIndonesian values: the eldest childculturally has more responsibility in
helping the family’s financial sources. Asshe failed to have a job, Liana had nochoice but to accept Jono’s proposal forJono had promised her and her mother tofinance her siblings’ education. Here,economic hardship becomes central indefining female identity. Liana mustsurrender her own wish and submit to thefamily’s interest, never her own. Jono’swealth and Liana’s poverty is juxtaposedto give readers clear distinction that thepolitics of economy is closely intertwinedin shaping female subjectivity and identity.Liana was, by no means, unconscious ofher situation. She understood that her lifewas similar to Cinderella story which sheobjected. Having no intention ofbecoming a victim of Cinderella complex,she still was incapable in reacting againsteconomic positioning.
Liana then exchanged her freedomwith economic position, and mostimportantly being a “true” woman whowas expected to sacrifice her own will.Her identity has already been fixed anddelimited; martyrdom is a female affair.The value of this story lies in its ability toexplore subtly the cultural norms whichlargely delimit female space withoutblatantly attacking on such oppression.The author concurrently informs readersof the marginality and exploitationsendured by Muslim women.
( a f l o w e rname)(Ratna, 2002) is yet anotherrestriction of female space and freedom.The story narrates about Rusmini, a juniorhigh school teacher who has to give up herdream of becoming a flight attendant dueto her sex. In this story, public anddomestic space is sharply divided. Onlymen can occupy public space while
Delimitation and Definition of FemaleIdentity
Lebur
B u n g a M e n t e g a
46
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

women domestic. By cultural norms andsex, Rusmini had abandoned her yearningto “see the world” and it was her who hadto reside in domestic world and took careof her ill mother and not her brother whowas given opportunities to “see theworld.”
Adventure is not woman’s world,only man can travel and be adventurous.Female domestic and male public isnatural division. If Rusmini is confinedinto solely domestic world, her brotherRahman is given vast opportunity to livethe outside world. He decided to quit hisuniversity study so he could see the world.“Seorang laki-laki harus melihat duniadulu sebelum menikah,”(Ratna, 2002: 42)their mother replied when Rahman toldher his desire. But when Rusminimentioned the same thing as herapplication to be a flight attendant wasaccepted, her mother and all familymembers simply said, “Kau sebaiknyamenjadi guru dan menemani Ibumu dirumah. Kalau kau dan adikmu kepinginkeliling dunia, dengan siapa Ibumutinggal?”(Ratna, 2002: 43) For Rusminiher identity has already been fixed andsealed that she soon was to get marriedwith Hadi her boyfriend or Yusuf, hersuitor. For woman, marriage is their finalgoal, and only through it in the eyes ofcultural norms she rests firmly heridentification. It is culturally determinedthat as a daughter Rusmine must attend thedomestic world, caring for the elderly,experiencing the strict confinement ofwomen in society because she is a woman.Rusmini’s restriction to live outsidedomestic world functions both sign andproof of the culture’s devaluation ofwomen.
It is indeed interesting that the authoruses “the female job” in juxtaposing thestrict dichotomy between domestic andpublic sphere. Flight attendance is largelyregarded as woman’s job as it mainlyprovides services and cares which areclosely associated with female world.Therein, it shows that the author attemptsto indicate that to a certain degree womenare essentialised with women’s cultureand constructed world of domesticity. Shecritically accommodates what society hasplaced women even in different spheres,that the subject status of women embodiestactical reintepellations of dominantpatriarchal ideologies, and that the sharpdivision between women’s and men’ssphere becomes powerful ways ofexpelling patriarchal transcriptions.
Within the delimitation of women’sidentity, one discursive practicecontributing to such delimitation is thelimited freedom given for women. If menare supported to extend their privateterritorial boundaries, women arediscouraged. If freedom is associated withmen, women are restriction. Women aremore or less defined limitedly as wives,mothers and bearers of future citizensrather than in terms of their social rolesthat portray them as full social beingsendowed with autonomy, social control,and prestige in their own right. Women’sfreedom often becomes social baggageonly situated at home, constructingfemaleness that is consciously forged byideologies that women are moralguardians, domestic managers whoseroles are only meaningful throughdomesticity. Freedom is certainly acontested arena, strongly administered toensure that it will not contradict women’s
47
Politics and Social Representation in Literatures ...

48
domesticity.
In Ratna’s narratives, womenfunction as objects inherited from asociety that says women matter less thanmen do, a society that think women barelybelong to in the culture that defines themat best marginal and silent members of ahouse called domesticity. Raising criticalissues on how women are subjugated andobjects of domination, Ratna is productiveis capturing a vision of art and ofimbalanced social relations. Yet, Ratna’swomen are not all submissive; those whohave been denied their rights are alsoresponsive to injustices they experience.In so doing, the author acknowledges theexistence and struggle of women,especially those of under privilegeconditions.
Ratna has indeed created “feministnovels”, opening up silence and providingroom for expression. Her works, in ethicaland moral position, consist of didacticelement related to the project of culturaltransformation, of establishing newvalues which underline justice andequality. She is revisionist mythmakers,refusing to keep being silent by replacingheroes with heroines, and revising storiesof grand heroic figures with stories ofordinary women. Female survival may befound in the different ways in whichwomen have responded to their historicalsituations, and indeed these authorscelebrate such survival in anyway at allcost.
Althusser, 1988,‘Ideology and StateApparatuses,’ quoted in JanetTodd,
, Pol i ty Press ,Cambridge and Oxford, .
Belsey, Catherine and Jane Moore,1989,‘Introduction: The Story So Far,’
, ed. CatherineBelsey and Jane Moore ,Macmillan Education, Ltd.,London, .
Butler, Judith, 1990,
, Routledge, New YorkLondon, .
de Beauvoir, Simone, 1953,, trans. and ed. H.M. Parshley,
Jonathan Cape, London, .
Cornillon, Susan K,1973,, Rev. ed.,
Bowling Green UniversityPopular Press, Bowling Green,Ohio.
Fetterley, Judith, 1978, ‘Introduction onthe Politics of Literature,’
Fiction,Indiana Universi ty Press,Bloomington.
Ibrahim, Ratna Indraswari,,
unpublished manuscript, paperpresented on a seminar held by
Conclusion
DAFTAR PUSTAKA
Feminist Literary HistoryA Defence
The Feminist Reader Essays inGender and the Politics ofLiterary Criticism
Gender TroubleFeminism and The Subversion ofIdentity
The SecondSex
Images ofWomen in Fiction
TheResisting Reader A FeministApproach to American
Sastra DanG e r a k a n P e r e m p u a n
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

Jawa Pos,April 19, 2003 in GrahaPena Surabaya.
Ibrahim, Ratna Indraswari, ‘BungaMentega’. ,Galang Press,Yogyakarta, 2002.
Ibrahim, Ratna Indraswari, 2002, ‘Lebur’., Galang
Press,Yogyakarta.
Ibrahim, Ratna Indraswari, 2002, ‘BungaMentega’. ,Galang Press,Yogyakarta.
Ibrahim, Ratna Indraswari, ‘Noda PipiSeorang Perempuan’.
.
Ibrahim, Ratna Indraswari, 2002,‘Rambutnya Juminten’.
, Penerbit Jendela,Yogyakarta.
Lara, Maria Pia, 1998,,
Polity Press.
Robbins, Ruth, 2000, ,MacMillan Press, London.
Subiantoro, Eko Bambang, 2002, ‘RatnaIndraswari Ibrahim; MenulisC e r p e n M e n g a b a r k a nKenyataan,’No. 23.
Todd, Janet, 1988,, Polity Press,
Cambridge and Oxford.
Interview with Ratna Indraswari Ibrahim,20 July 2004, Malang, JawaTimur, Indonesia..
Aminah di Satu Hari
Aminah Di Satu Hari
Aminah Di Satu Hari
Noda PipiSeorang Perempuan
LakonDi Kota Kecil
FeministNarratives in the Public Sphere
Literary Feminisms
Jurnal Perempuan
Feminist LiteraryHistory A Defence
49
Politics and Social Representation in Literatures ...

Latar BelakangPada dekade sekarang ini, berbagai
sarana pembelajaran bahasa Inggris telahdipakai untuk meningkatkan keberhasilanproses pembelajaran bahasa Inggris baikkepada anak usia dini, bahkan balita,remaja dan orang tua. Yang palingsederhana adalah buku bergambar atauyang biasa dikenal dengan
. Buku bergambar memberigambaran secara visual menunjukkankosakata bahasa Inggris dalam bukutersebut. Namun bentuk ini memilikikelemahan secara audio, karenapemberian rangsang pendengaran kurangpeka. Untuk mengatasi hal ini ,berkembanglah model audio dengan
. Namun model kedua inimemiliki kelemahan dalam aspek visual.Penampakan objek tidak ada sehinggabentuk dari benda yang disebutkan tidaktergambar secara nyata.
Perkembangan teknologi telahmenutupi kelemahan yang ada, yaitupengajaran bahasa melalui VCD atau
media televisi. Melalui model inidiharapkan kelemahan pada mediasebelumnya dapat diatasi selainpenyajiannya yang tidak menimbulkankebosanan pada peserta belajar.
Perkembangan teknologi yang bisadikatakan paling mutakhir adalahkomputer multimedia. Komputer inimemiliki berbagai macam kemampuanmedia dalam satu perangkat yang meliputiaudio dan video. Sehingga komputermul t imed ia b isa dipaka i untukmendengarkan ucapan-ucapan yang baikdan benar serta dapat melihat danmembaca teks maupun konteksnya. Lebihdari itu multimedia memungkinkandilakukannya ‘interaksi maya’ antarakomputer dengan peserta. Sifat interaktifini memungkinkan keaktifan pesertas e s u a i d e n g a n k e a d a a n d a nk e m a m p u a n n y a d a n k e m u d i a nmendapatkan respon yang bisa langsungdilakukan oleh komputer. Respon ini bisaberupa pemberian kalausalah atau pun kalau benar.
dictionarypicture
cassette recorder
‘punishment’‘reward’
KORELASI ANTARA PENGGUNAAN MULTI MEDIAKOMPUTER DENGAN PENINGKATAN SKOR TOEFL PESERTA
SELF ACCESS UNAIREdi Dwi Riyanto*)
AbstractThis article is about the correlation between multimedia computer usage and toefl scoreimprovement among Self Access member at UNAIR. 44 students were treated usingmultimedia computer and then tested using toefl. The students were suggested to usemultimedia computer as facitilites available at Self Access. The toefl tests are conductedthree time, pre, mid, and post test. Using one way Anava analysis, the result shows a positivecorelation between the length of multimedia computer usage and the toefl score in which thelonger the usage the higher the score.
Keyword: multimedia computer, toefl score
*) Departemen Sastra Inggris, Fakultas Sastra UniversitasAirlangga, 031-5035676
50

Karena tidak melibatkan orang lain samasekali, maka ‘ yang sangatjelek sekali pun tidak perlu membuat malupeserta.
In t e rne t juga sesungguhnyamerupakan sumber dan sarana belajaryang luar biasa besar dan bermanfaat bagimahasiswa. Di internet terdapat informasimengenai hampir semua hal.
Namun demikian menghadirkankomputer multimedia dan internet dalamkerangka pembelajaran tidaklah mudah.Ada masalah-masalah yang kemungkinanbesar muncul. Pertama dan pasti adalahpembiayaan. Yang kedua adalah strukturinformasi di internet maupun padakomputer multimedia perlu diselaraskandengan tujuan-tujuan pembelajaran itusendiri. Masalah lain adalah kemandirianpeserta; serta berbagai masalah yang bisas a j a m u n c u l k e t i k a s e d a n gberlangsungnya proses pembelajaranmelalui komputer multimedia dan internetini.
Masalah-masalah tersebut di atasjuga bisa diperkirakan akan muncul ketikaSelf Access Center di Unair yangmenghadirkan sejumlah multimediakomputer yang diharapkan akanmembawa peningkatan intensitas prosespembelajaran bahasa Inggris bagimahasiswa Unair. Harapan selanjutnyaadalah pada giliranya nanti kemampuanbahasa Inggris mahasiswa Unair jugameningkat.
Bagaimanapun juga kedua hal di atasadalah harapan yang perlu diuji palingtidak oleh potensi masalah yang tertulis didepan. Oleh karena itu peneliti merasatertarik untuk mengadakan kajian secarakhusus mengenai kedua hal tersebut yaituantara harapan peningkatan intensitas danharapan peningkatan kemampuan bahasa
Inggris mahasiswa yang disebabkan olehkeberadaan komputer multimedia daninternet.
Namun masih ada satu masalahmendasar dari korelasi tersebut, yaitu alatukur. Seperti sering disebutkan bahwasalah satu masalah utama dari sebuahproses adalah pengukuranya. Adakah caraterbaik untuk bisa mengukur keberhasilansebuah proses pembelajaran bahasaInggris? Bagaimana caranya bisadiyakinkan bahwa kenaikan skor tertentudisebabkan oleh faktor tertentu?
Berbagai test kemampuan bahasaInggris yang tersedia antara lain adalahIELTS, TOEIC, dan TOEFL. Sementaraitu bisa dikatakan bahwa TOEFL (
) lebihbersifat universal secara internasional.Test ini juga mengukur kemampuanbahasa Inggris dari berbagai aspekketrampilan misalnya mendengar, tatabahasa dan membaca. Kadang-kadangTOEFL juga dilengkapi dengan test tulis.Sampai saat ini TOEFL dianggap sebagaisalah satu alat ukur bahasa Inggris terbaik.Seperti kita ketahui test ini dipakaisebagai standar penerimaan mahasiswa
maupun dihampir semua perguruan tinggi diAmerika Serikat, Kanada, Inggris, danlainnya.
Sejak tahun ajaran 2002/2003 iniUniversitas Airlangga telah mewajibkanseluruh mahasiswa barunya untukmengikuti test TOEFL sebagai bagian dariproses registrasi. Keputusan ini sempatmengundang berbagai pertanyaan yangkritis maupun bersifat protes. Hal initerutama disebabkan karena beberapasebab antara lain: (1) keputusan ini barupertama kali dilakukan sehingga pihak
punishment’
Test ofEnglish as a Foreign Language
graduate post graduate
Korelasi antara Penggunaan Multimedia ...
51

penyelenggara maupun pihak lain yangterkait juga masih meraba-raba apa yangakan terjadi pada pelaksananaan nanti, (2)keputusan ini terkesan mendadak,terutama bagi peserta, (3) peserta harusmenanggung biaya tambahan untukproses registrasi mereka, dan (4) test inimasih dikira sebagai bagian dari seleksimasuk sehingga banyak peserta atauorang tua mereka yang khawatir tentangkelulusan test TOEFL ini. Pada akhirnyatest TOEFL berjalan dengan lancar dansangat baik. Hampir semua pihak merasapuas.
Permasalahan berikut muncul antaralain ketika para mahasiswa yang merasaperlu meningkatkan kemampuan bahasaInggrisnya tidak bisa mengikuti kursuskonvensional. Jumlah mereka sangatbesar dibanding dengan jumlahmahasiswa yangmempunyai waktu sertadana untuk mengikuti kursus baik didalam kampus Unair maupun di luar.Alternatif utama pemecahan ini adalahpenyediaan SelfAccess. Salah satu bagianpenting dari layanan ini adalahpenyediaan multimedia komputer sebagaisarana bantu belajar.
Berkaitan dengan itu perlu kiranyadiadakan penelitian mengenai efektifitasmanfaat komputer multimedia bagipeningkatan skor toefl. Oleh karena itupeneliti mengajukan topik penelitian kaliini berupa hubungan antara penggunaanm u l t e i m e d i a k o m p u t e r d e n g a npeningkatan skor toefl peserta self access.
Masalah yang diteliti adalah apakahpenggunaan komputer multimedia bisamempengaruhi peningkatan skor TOEFLanggota Self Access Unair. Secara khususmasalah yang akan diteliti meliputipeningkatan pada skor TOEFL, berapa
lama anggota Self Access Unairmenggunakan komputer multimedia, danprogram-program apa saja yangdimanfaatkan mereka.
Belakangan diketahui bahwa belajarbahasa Inggris harus menekankan padaaspek komunikasi. Tujuannya adalahmengasah kemampuan komunikasidengan menggunakan bahasa Inggris.Sehingga kemampuan berkomunikasiakan langsung meningkat pada murid.Maka pendekatan komunikatif perluditerapkan. Berbagai buku sudahditerbitkan menyangkut hal ini. Contohpenting adalah
(Collie dan Slater, 1987) yangmenekankan pada pemanfaatan karyasastra dalam pengajaran Bahasa Inggrisdan (Carter dan Long,1987) yang mengambil sudut pandanglinguistik (dalam Elisabeth B. Ibsen 1995).
Selain dari itu, minat memegangperanan penting dalam keberhasilanbelajar seseorang. Berbagai bukumutakhir tentang teknik belajarmenekankan pada aspek kesiapan mentalyang menyebutkan bahwa sisi afeksi atauemosi sangat menentukan keberhasilanbelajar, secara sempit, atau keberhasilanhidup secara luas. Teori seperti QuantumLearning mendukung hal itu. GordonDryden dan Jeannette Vost dalambukunya Revolusi Belajar (1999) sangatmenekankan aspek “ ” atau unsurkesenangan dalam belajar. Bagi mereka,tanpa rasa senang maka keberhasilanbelajar akan minimal. Dengan demikianpermainan juga bisa digunakan untuk alatpendidikan karena permainan bisamemberikan rasa kepuasan, kegembiraan,
Aspek Komunikasi versus AspekPengukuran
Literature in the LanguageClassroom
The Web of Words
fun
52
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

dan kebahagiaan kepada diri peserta didik.(Kartono, Kartini, Psikologi Anak. Hal.117-122).
A s p e k k o m u n i k a t i f d a nmenyenangkan semakin mendapat tempatdengan adanya teknologi multimedia daninternet. Richard I. Arends dalambukunga ( 2001: 85)mengatakan bahwa sebagian besar guruyang menggunakan teknologi di dalamproses belajar mengajar mendapatpeningkatkan aspek motivasi dalam halpemakaian komputer dan internet.Dengan menggunakan simulasi komputerdan website yang kreatif maka para siswatertantang untuk terus menerus belajarseraya meningkat ke tingkat kesulitanyang lebih tinggi.
Dibagian lain Arends mengatakanbahwa komputer multimedia juga bisamembuat presentasi jauh lebih menarik;misalnya dengan menggunakan softwarePowerpoint, ClarisWorks, atau Persuasion.Teknologi ini bisa membantu guru dansiswa dalam membuat ilustrasi danmenampilkan laporan, cerita, maupunkegiatan-kegiatannya. (2001: 253).Secara khususArends menegaskan bahwainternet bisa sangat membantu prosespembelajaran dengan pengawasantertentu (2001:361). Bahkan internet jugam e m u n g k i n k a n a d a n y a p r o s e spembelajaran secara online dengan caramasuk terlibat ke “ ” atau forum-forum diskusi lainnya. (2001:393).
Komputer multimedia dan internetyang secara khusus diperuntukkan bagipembelajaran bahasa bisa disediakan diSelf Access Center. Di dalam Self Accessini lingkungan luas di luar kelas yangberagam dan bisa menjadi pendukungatau penghambat proses belajar dipilih
dan dihadirkan secara ‘mini’di dalam saturuangan atau satu gedung. Keterbatasanruang kelas bisa sangat terbantu denganadanya fasilitas ini. David Nunanmengatakan bahwa tidak semua hal bisadiajarkan di dalam ruang kelas (Nunan1988a:3 dalam Harmer 2001 : 335). Untukmengurangi dampak dari keterbatasankelas ini maka siswa harus mampumengembangkan strategi belajar mandiri.Di dalam melaksanakan belajar mandiriini siswa memerlukan Self Access Centeryang, bagi Harmer sudah bukan hanyamelengkapi ruang kelas tetapi bahkan bisamenjadi penggantinya (2001 : 340).Ketersediaan komputer multimedia didalam ruang ini saat ini sudah menjadi halyang tidak dapat ditawar lagi mengingatmanfaat dan kegunaannya sedemikianbesar.
Namun peluang yang begitu besaruntuk meningkatkan efektifitas prosespem-belajaran dengan memanfaatkanteknologi tidak bisa dengan mudahditerapkan terutama untuk kasus SelfAccess Unair ini. Masalah pertama adalahsifat Self Access yang menuntutkemandirian para peserta. Secara umumbisa dirujuk sebuah penelitian yangdilakukan oleh Marie-Christine Presssebagai bagian dari disertasi M.A.nya.Press mencoba menghubungkan antaraumur, jenis kelamin, latar belakangpendidikan, dan etnis dengan tingkatkemandirian dalam belajar. Dalampenelitian ini ditemukan bahwa para siswayang berasal dari Asia yang meliputiantara lain Pakistan, India, Cina danJepang mempunyai tingkat kemandirianyang paling rendah. (Phil Benson, 2001 :193-197). Ketidakmandirian ini sedikitbanyak terkait dengan latarbelakang
Learning to Teach
chat room
53
Korelasi antara Penggunaan Multimedia ...

budaya komunal orangAsia.Kemandirian orang Asia yang relatif
rendah ini bisa saja membuat penyediaansarana belajar mandiri menjadi tidakterlalu efektif. Kenyamanan ruang,kelengkapan koleksi dan sarana belajarserta tersedianya teknologi canggih disuatu self access terasa menjadi sia-siadikarenakan kebutuhan peserta akan‘instruktur’ masih tinggi. Lalu munculpertanyaan apakah sebenarnya self accessdengan berbagai macam fasilitasnya bisabenar-benar meningkatkan kemampuanpara peserta yang ‘seharusnya’ belajarmandiri.
Masalah yang bisa diajukankemudian adalah bagaimana carapengukuran keberhasilan itu. Di sini adakontradiksi yang sangat menonjolmengenai pengukuran yaitu bahwa dalamprinsip belajar mandiri seharusnyasasaran, tujuan, maupun hasil akhir prosesbelajar ditentukan dan diukur secaramandiri oleh peserta. Tetapi untuk tujuan-tujuan penelitian (dalam kasus ini) tujuan,sasaran, dan standar proses belajarditentukan peneliti yaitu skor TOEFL.
Satu hal mendasar dalam pengukurankemampuan bahasa yang sangat sulitdipenuhi adalah pengukuran yang sesuaidengan program pela t ihan ataupengajaran yang telah diberikan. (Beretta,1986). Beretta lebih lanjut menjelaskanbahwa pengukuran terstandar yangdiberikan memang sangat perlu danmembantu skoring bisa diterima olehbanyak orang di banyak tempat, tetapisecara langsung hal ini seringkalibertentangan dengan kondisi khususprogram yang telah atau akan diberikan.Bahkan Arthur Hughes mengatakanbahwa seringkali test atau pengukuran
yang dilakukan mempunyai dampaknegatif atau merusak terhadap prosesbelajar mengajar dan gagal mengukursecara tepat apa-apa yang ingin di ukur.
Sebuah kurikulum yang berisi prosespembelajaran bahasa tidak bisa disebutkurikulum tanpa adanya evaluasi untukmengukur keberhasilan program yangtelah dilaksanakan sekaligus menjadiacuan untuk merancang programselanjutnya. David Nunan dalam bukunya
(1988) menjelaskan bahwa pengukuranbisa bersifat mikro dan makro.Pengukuran mikro dilakukan di dalamkelas. Sedangkan pengukuran makro bisabesifat nasional bahkan internasional.Resiko ketimpangan pada programpengukuran makro mungkin saja terjadi,tetapi pada saat tertentu hal ini harusdilakukan.
Bagaimanapun val idi tas danreliabilitas pengukuran mikro seringterlalu berbeda dari satu kelas ke kelas lain.Pengukuran yang bersifat makro lebihmemungkinkan dalam menjaga kedua haltersebut yang oleh Nahla Nola Bachadalam
(dalam jurnal, April 2002) sebagai unsur-unsur
yang sangat vital bagi suatu test ataupengukuran. Untuk kedua hal ini makaTOEFL bisa dikatakan cukup memenuhisyarat bila dilihat dari dua sisi: (1) klaimETSsebagai ‘pemilik’ TOEFL dan (2)pengguna.
Dari brosur resmi yang diterbitkanoleh ,Univesitas Princeton, (1999) disebutkanbahwa tujuan test TOEFL adalah untuk
The Learner-Centred Curriculum; AStudy in Second Language Teaching
Testing Writing in the EFLClassrom English TeachingForum
(Educational Testing Service)
Educational Testing Service
54
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

mengukur kemampuan mengenali bahasaInggris standar; baik mendengarkan,tatabahasa, membaca, maupun menulis.Yang dimaksud dengan standar di siniadalah bahasa Inggris yang dipakai dibenuaAmerika bagian utara yang meliputiAmerika Serikat dan Kanada; jadi bukanbahasa Inggris Australia atau KerajaanInggris, apalagi bahasa Inggris Singapuraatau Hong Kong.
Dari sisi pengguna diAmerika danKanada sendiri terdapat 2.400 perguruantinggi yang mensyaratkan TOEFL (ETS.1999). Michael Thompson dalam Jurnal
(Juli, 2001)menambahkan bahwa dua universitas diMilan, Italia, sekarang ini juga sudahmewajibkan TOEFL bagi mahasiswanya.Di Indonesia sendiri pemakaian TOEFLuntuk program pascasarjana sudah lamaditerapkan seperti di UI, UGM, UNAIRdan lainnya. Bahkan di sejumlahperguruan tinggi, seperti ITS misalnya,sudah mensyaratkan TOEFL bagimahasiswa S-1-nya. UNAIR barumemulai program itu tahun ajaran2002/2003 ini. Bagi lulusan S-1 yangingin melanjutkan studi ke perguruantinggi di Amerika, Inggris, Australia, danlainnya bisa melampirkan skor TOEFLsebagai bukti awal tingkat kemampuanbahasa Inggris mereka. Saat ini bahkanTOEFL sudah merambah ke dunia non-akademik, yaitu profesional. Padaberbagai lowongan pekerjaan nampakjelas mereka meminta skor TOEFLtertentu.
Validitas dan reliabilitas testTOEFL sudah diakusi secara luas. RektorUNAIR sudah memutuskan untukm e n g a d a k a n t e s t TO E F L b a g imahasiswanya. Masalahnya sekarang
adalah ket ika mahasiswa Unairm e m p u n y a i k e i n g i n a n b e l a j a rmeningkatkan skor TOEFLnya, apakahsarana yang disediakan Unair cukupmemadai, efektif, dan terjangkau?Penelitian ini hanya dimaksudkan untukmelihat salah satu dari ketiga aspek tadi,yaitu aspek efektifitas salah satusaranyanya,dalam hal ini komputermultimedianya.
TOEFL test dilakukan secaraberulang sebanyak tiga kali dengan jangkawaktu yang berbeda. Data dari tes pertamadiambil dari data tes TOEFL sampelketika mereka berada di semester I(Pretest), yaitu sekitar September 2002.Tes kedua (Midtest) dilakukan pada 23September 2004 dan tes ketiga (Posttest)pada 7 Oktober 2004. Antara tes keduadan ketiga diisi kegiatan pembelajaranbahasa Inggris oleh sampel denganmemanfaatkan sarana yang terdapat diSelfAccess. Dari sebanyak 52 mahasiswa,beberapa gugur di tengah jalannyapenelitian sehingga pada akhir penelitianhanya 44 mahasiswa saja yang dapatdianalisis hasilnya. Data hasil tes tersebutkemudian dianalisis menggunakananalisis varians satu jalur (AnavaA).
Berdasarkan hasil analisis varians,secara umum dapat dikatakan bahwa lamabelajar dan media belajar yang digunakanmahasiswa diikuti dengan peningkatannilai TOEFL secara signifikan. Hal iniberarti bahwa hipotesis penelitian yangberbunyi “Lama dan cara penggunaankomputer multimedia meningkatkan skorTOEFL anggota Self Access Unair”terbukti dengan nilai F test sebesar 28.215(p< 0.01) (dengan Anava satu jalur). Hasildeskriptif menunjukkan bahwa nilai
English Teaching Forum
Hubungan Keduanya
55
Korelasi antara Penggunaan Multimedia ...

tengah akhir (midtest) memiliki rata-ratayang lebih baik dari tes-tes yang lain.Kesimpulan ini juga didukung oleh datadeskriptif yang menunjukkan bahwasampel penelitian yang memiliki nilaiTOEFL t ingg i (ke lompok a tas )menggunakan waktu belajar yang lebihlama dan lebih banyak menggunakanmedia komputer dan internet jikadibandingkan dengan sampel penelitianyang memiliki nilai TOEFL rendah(kelompok bawah). Namun demikian,berdasarkan data deskriptif saja tidakmungkin untuk menyimpulkan bahwafaktor lama belajar dan media yangdigunakan berpengaruh langsungterhadap nilai TOEFL.
Dari hasil analisis regresi terhadapmasing-masing section tes TOEFLterhadap nilai post test menunjukkanbahwa nilai post test TOEFL lebih banyakberasal dari section 2 (dari sumbanganrelatif section 2 ( ) sebesar42.825 % dibandingkan dengan section 1sebesar 31.651 % dan section 3 sebesar25.523 %). Namun peningkatan nilaimenunjukkan bahwa peningkatanterbesar berasal dari section 3 ( ),yaitu dari rata-rata 50.5682 pada midtestmenjadi 53.7500 pada posttest (Tabel 1),sedangkan section 1 dan 2 justrumengalami penurunan. Jika dibandingkandari hasil data gaya belajar, kebiasaanmembaca buku memberikan kontribusicukup besar terhadap peningkatankemampuan (baca buku: 84%pada kelompok atas dan 100% padakelompok bawah).
Dari hasil dan pembahasan di atassecara teoretis bisa dikatakan di sinibahwa komputer multimedia membantupeningkatan perolehan hasil belajar. Hal
ini sesuai dengan pendapat Richard I.Arends dalam yangmenyatakan bahwa pemakaian komputerm u l t i m e d i a d i k e l a s t e r b u k t imeningkatkan aspek motivasi siswa(2001: 235). Sedangkan kelebihan lainadalah komputer multimedia tidak terlalumembutuhkan ruang yang terlalu besar,kalau pun harus diadakan di luar kelas.S e m e n t a r a k ap as i t a s k o m p u t e rmultimedia yang sangat besar, apalagiyang sudah tersambung ke jaringaninternet, bisa memenuhi banyak hal yangdikatakan oleh David Nunan sebagai tidakbisa diajarkan di dalam ruang kelas(dalam Harmer 2001: 335).
Lama pese r t a menggunakankomputer multimedia kelompok bawahberbeda dari kelompok atas. Kelompokbawah hanya menggunakan komputerrata-rata 4.04 jam per minggu, sedangkankelompok atas menggunakannya selama7.65 jam / minggu.
Sedangkan pertanyaan ketiga dalamperumusan masalah berupa “program-program apa saja yang dimanfaatkanpeserta” tidak bisa dijawab. Hal inidisebabkan oleh karena sampai denganlaporan in i d isusun pengadaanmultimedia komputer yang dijadwalkandalam program SP-4 untuk bisadirealisasikan pada bulan Juli belumterlaksana. Pendeknya, komputer belumtersedia di SelfAccess.
Berdasarkan uji hipotesis yang telahdilakukan didapat kesimpulan sebagaiberikut:
terdapat peningkatan skorpada peserta. Kelompok atas mengalamikenaikan dari Pre test ke Mid test dan dariMid test ke Post test. Kelompok bawah
grammar
reading
reading
Learning to Teach
Pertama,
Kesimpulan
56
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

mengalami kenaikan dari Pre test ke Midtest tetapi mengalami penurunan dari Midtest ke Post test.
kelompok atas lebih lamamemanfaatkan komputer multimediadibanding dengan kelompok bawah.
karena kendala teknis,pertanyaan tentang program yang dipakaipeserta tidak bisa dijawab.
Arends, I. Richard. 2001.
. 5 edition. New York.McGraw-Hill.
Benson, Phil. 2001.
. PearsonEducation Limited, England.
Dryden, Gordon dan Jeannete Vost. 1999.(terjemahan)
. Kaifa.Bandung.
Hadi, Sutrisno. 1996..Yogyakarta.Andi Offset.
Hadinoto,S.R. dkk. 1999.
,Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press.
Harmer, Jeremy. 2001..
England. Longman.
Hughes, Arthur. 1989.. Cambridge.
Cambridge University Press.
Ibsen, Elizabeth H. 1998. “The DoubleRole of Fiction in ForeignLanguage Learning: towards aCreative Methodology” dalam
Quezon City.Philippine.
Kartono, Kartini. 1995.. J a k a r t a .
Erlangga.
Nunan, David. 1988.. New York.
Cambridge University Press.
Kedua,
Ketiga,
Learning to
Teach
Teaching andResearching Autonomy inLanguage Learning
Revolusi BelajarBelajar akan Efektif Kalau AndaDalam Keadaan “Fun”
Statistik 2; CetakanXVI
PsikologiPerkembangan: PengantarDalam Berbagai Bagiannya
The Practice ofEnglish Language Teaching
Testing forLanguage Teachers
Creative Training: a user’s guide.
PsikologiP e r k e m b a n g a n
The LearnerCentered Curriculum
DAFTAR PUSTAKA
th
57
Korelasi antara Penggunaan Multimedia ...

Akhir-akhir ini di kalangansejarawan beredar wacana tentangpentingnya mendemokrasikan sejarahatau historiografi. Wacana tersebut tentusaja didasari asumsi atau pemikiranbahwa historiografi yang berkembangsaat ini adalah historiografi yang tidakdemokratis. Oleh karena itu perludipertanyakan ramai-ramai agar lebihjelas maksudnya. Apa yang dimaksuddengan historiografi yang demokratis?Apakah yang dimaksud demokratis di sinisama maknanya dengan demokrasi dalamsebuah sistem politik, yaitu sebuah sistemdi mana segala hal yang berlaku didalamnya harus melibatkan anggotasistem?
Kita mengenal jargon demokrasiadalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untukrakyat. Sebuah jargon yang tidak pernahbisa dibuktikan efektifitasnya dimana pundi belahan bumi ini, karena padakenyataannya dalam sistem politik manapun siapa yang paling menguasai sumberdaya maka dialah yang ditakdirkan paling
berkuasa. Amerika Serikat selalu gembar-gembor agar sistem politik yang berlakudi dunia ini adalah sebuah sistem yangmayoritas didukung oleh rakyat (yangdimaknai sebagai sistem yang palingdemokratis), tetapi ketika Hamas diPalestina memenangkan pemilihan umum,yang artinya didukung sepenuhnya olehrakyat, Amerika Serikat seperti kebakaranjenggot. Buntutnya, semua bantuan yangtadinya disediakan oleh Amerika Serikatuntuk Palestina dicabut. Bahkan AmerikaSerikat juga mengompori negara donaturyang lain untuk mengikuti langkahnya.Dalam konteks ini demokrasi yangdidengung-dengungkan dan dipuja-pujaoleh Amerika Serikat bak harimauompong yang paranoid.
Di setiap episode sejarah, biasanyaorang besar merupakan aktor utama dalampanggung sejarah. Ketika sejarah pertamakali digagas oleh Herodotus maka yangpertama kali diangkat adalah perang
Historiografi Orang Besar
MENGGAGAS HISTORIOGRAFI (INDONESIA) YANGDEMOKRATIS
Purnawan Basundoro
AbstractLargery people view history submissive to its creator. This condition often trapshistory to the complicated reality because it is frequently used as a justification forthe authority. in this situation history shows its tyranny and to be very undemocratic.recentlym there is a movement in the society to democratize the history. in otherwords, the history, which tends to take side to power, must be deconstructed in orderto be closer to the reality of the common people. This article is intended to discussthe effort that need to be done so that the history can be more democratic and to beable to express reality as the way it is.
Kata kunci: historiografi, demokratis, Indonesia sentris
*) Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Sastra UniversitasAirlangga, tlp 031-5035676email: [email protected]
58

Persia. yang berisi kisahtentang perang antara YunaniPersia merupakan karya pertama sejarahkritis yang ditulis oleh Homerus. Iabanyak me-wawancarai para jendral yangterlibat dalam peperangan tersebut,disamping ia sendiri adalah jendral yangjuga terlibat dalam perang itu. Karenayang ia wawancarai adalah orang-orangbesar yaitu para jendral, maka sejarahtentang perang antara Yunani dan persiatersebut pada hakekatnya juga sejarahorang-orang besar. Tidak berbeda jauhdengan yang dilakukan oleh Herodotus,Thucydides dalam karyanya
juga lebih banyakmengungkap peranan para jendral dankelompok militer dalam peperanganantara polis Athena dengan polis Sparta.Mereka adalah orang-orang besar yangberada di panggung sejarah padazamannya.
Tradisi penulisan sejarah padaperiode selanjutnya juga masih tidakmampu untuk melepaskan diri dariketerlibatan tokoh politik, raja-raja, dankelompok bangsawan lainnya dariperjalanan sejarah sebuah bangsa. Ketikaterjadi revolusi Perancis pada abad ke-18maka yang paling banyak diekspos dalamsejarah adalah kelompok borjuis, kaummiliter, dan kaum bangsawan. Jarangdisinggung misalnya bagaimana anak-anak pada saat terjadinya revolusi tersebut,di mana kaum perempuan berada danposisinya bagaimana dalam revolusi itu.Dalam tradisi penulisan sejarah,kelompok-kelompok kedua
selalu tidak jelas posisinya sertadianggap sebagai kelompok-kelompokyang tidak memiliki sejarah, tidak terlibatda l a m men c ip t ak an pe rub ah an .
Perubahan adalah milik orang besar ataumilik .
Dalam pandangan Suhartono, sejarahsecara umum selalu menguntungkanpihak atau
, sebaliknya yangkarena struktur sosial yang berlaku dalammasyarakat menyebabkan merekat e r p i n g g i r k a n k e t i k a s e j a r a hdi rekons t ruks i . Da lam berbaga irekonstruksi sejarah posisi wong ciliklenyap “ditelan” orang-orang besarkarena posisi mereka dianggap tidakpenting. Mereka ibarat “
” (Pranoto; 2001:ix).Dengan posisi yang demikian maka benarapa yang dikatakan oleh Purwanto bahwasebagian besar historiografi tidak pernahmenampilkan rakyat secara maksimaldalam panggung sejarah. Hal ini terjadikarena sebagian besar historiografi masihberkutat pada sejarah politik daripadamenampilkan historiografi sosial secaraluas yang mampu menghadirkan rakyatsecara utuh.
Situasi yang demikian telah me-nyebabkan banyak orang baik sebagaiindividu maupun kelompok tidakmemiliki sejarah atau dianggap tidakberhak memiliki sejarah, walaupunmereka semua memiliki masa lampau,sehingga muncul situasi atau ungkapan-ungkapan seperti rakyat tanpa sejarah,atau sejarah tanpa rakyat, perempuantanpa sejarah, atau sejarah tanpaperempuan (Purwanto, 2006: xiv).Historiografi orang besar adalahhistoriografi yang elitis dan formal yangtidak memberi ruang pada keseharian,kemanusiaan, dan segala sesuatu yangterpinggirkan. Historiografi seperti inisangat tidak demokratis karena biasanya
The Historiesversus
History ofthe Peloponessian War
(the secondclass)
the first class
the rulling class the rullinggovernment wong cilik
gupak pulut oramangan nangkane
Menggagas Historiografi (Indonesia) ...
59

hanya memiliki interpretasi tunggal, yaituinterpretasi masa lalu oleh orang-orangbesar. Seolah-olah merekalah aktor utamadalam panggung sejarah.
Di Indonesia tradisi penulisan sejarahdengan orang besar sebagai aktor utamatelah terjadi sejak lama dan belum terkikishabis hingga hari ini. Kalaupun orang-orang kecil semisal petani miskindiungkap dalam historiografi, tetap sajakeberadaan mereka sebenarnya tidakterlepas dari sejarah orang-orang besar.Berbagai risalah tentang kemiskinan dankehidupan petani yang miskin pada abadke-19 yang diakibatkan kebijakan sistemtanam paksa, konteksnya adalah sejarahkebijakan pemerintah kolonial Belanda diIndonesia (Jawa), yang merupakankebijakan kaum elit. Dengan demikianalur sejarah orang kecil dalam konteks inijuga mengekor pada alur sejarah orangbesar, yaitu para pembuat kebijakan diJawa pada waktu itu. Bisa dilihat misalnyapada disertasi Surojo tentang kemiskinanyang melanda Kedu pada abad ke-19 yangdiakibatkan oleh kebijakan Sistem TanamPaksa yang sangat eksploitatif dan sangatmemeras tenaga kerja kaum tani (Surojo,2000).
Apa yang diungkap oleh Surojo padahakekatnya tetap saja sejarah orang besar,sejarah para pembuat kebijakan (yangmerupakan kolusi antara pemerintahkolonial dengan pemerintahan tradisionalsetempat) yang berimbas pada orang-orang kecil seperti petani. Padahal, dalamkonteks ini sebenarnya petani memilikisejarahnya sendiri yang bisa jadi terlepasdan tidak terkait dengan Sistem TanamPaksa. Banyak sisi terang dari petani padawaktu itu yang tidak pernah diungkap.
Banyak sejarawan yang terjebak
dalam kelatahan dan hanya mengekortulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya,yang cenderung menampilkan kaum elit.Hal ini tercermin pada periodisasi yangmereka buat dalam berbagai kajiannya.Suhartono misalnya memulai kajianuntuk perubahan sosial di Surakarta padatahun 1830, bersamaan dengandimulainya kebijakan Sistem TanamPaksa di Jawa (Pranoto, 1991). Apakahperubahan sosial baru bisa dimulai ketikaeksploitasi terhadap masyarakat pribumimulai dilakukan oleh pemerintah kolonial?Padahal jauh sebelum pemerintahkolonial memberlakukan Sistem TanamPaksa, masyarakat pribumi telahmengalami berbagai tekanan yangdiakibatkan oleh perilaku eksploitatif daripara penguasa pribumi dalam bentukberbagai upeti dan kerja wajib lainnya. Disisi yang lain, bukankah perubahansenantiasa terjadi setiap saat, yang berartisetiap saat pula perubahan sosial terus-menerus terjadi dan melibatkan rakyatpedesaan? Periodisasi yang dibuat olehSuhartono adalah periodisasi sejarahorang besar di Jawa. Masih banyak contohkarya-karya sejarah yang jatuh padapilihan-pilihan dengan mengikuti alursejarah orang besar. Padahal masing-masing kelompok masyarakat, entah itupetani, kelompok-kelompok keagamaan,orang miskin, kaum perempuan, anak-anak, maupun yang lain memilikisejarahnya sendiri yang independen danterlepas dari . Kita tidak harusi k u t - i k u t a n m e m a k s a k a n d i r i“memasang” alur sejarah orang besarpada sejarah yang memiliki alurnyasendiri.
mainstream
60
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

Nasionalisme dan PenyeragamanSejarah
Kemerdekaan Indonesia ditandaioleh berdirinya negara yang disebutIndonesia, yang wilayahnya adalahdaerah-daerah bekas jajahan kerajaanBelanda yang membentang dari Sabangsampai Merauke yang terdiri daribermacam-macam etnis di dalamnya.Negara yang demikian besar ini danpernah me-rasakan perasaan senasibsepenanggung-an, ketika menjadi daerahjajahan memerlukan legitimasi berupasejarah nasional. Yaitu sebuah sejarahyang bisa melukiskan situasi masa laluyang “seolah-olah” mereka memilikipersamaan nasib. Dari sinilah maka lahir“Sejarah Nasional Indonesia” yang berisicerita yang seragam untuk masing-masingwilayah dan masing-masing etnis. Sejarahy a n g s e r a g a m i n i k e m u d i a ndisebarluaskan. Semua murid-murid dariSD sampai SMA diberi bacaan sejarahyang sama di mana pun mereka beradadan dari etnis apa pun asal mereka. Murid-murid di Aceh terbingung-bingung ketikamereka membaca bahwa Indonesia telahdijajah oleh Belanda selama 350 tahun.Padahal nenek moyang mereka barumerasakan benar-benar diperlakukansebagai orang yang terjajah pada akhirabad ke-19, yang artinya tidak lebih dari100 tahun sampai Indonesia merdeka.Tidak kalah bingungnya murid-murid diIndonesia Timur yang diberi bacaan yangsama dengan murid-murid di Aceh.Betulkah kita yang tinggal di IndonesiaTimur telah dijajah selama 350 tahun olehBelanda? Kebingungan ini adalahdampak penyeragaman sejarah dengandalih untuk menumbuhkan j iwanasionalisme.
Menumbuhkan rasa nasionalismebagi sebuah bangsa yang baru sajamerdeka memang wajar, apalagi bangsaIndonesia terdiri atas beribu-ribu pulaudan beribu-ribu etnis yang mencoba“disatukan” dalam satu kesatuan yangdisebut bangsa Indonesia. Dari ribuanmenjadi satu tentu saja membutuhkan talipengikat, yang salah satunya adalahsejarah. Pulau-pulau dan etnis-etnis diwilayah yang saat ini disebut Indonesiapada awalnya adalah wilayah yang beradadalam yurisdiksi pemerintah kolonialHindia Belanda, sehingga sejarah yangmula-mula mereka kenal adalah sejarahversi kolonial Hindia Belanda. Merekamengenal ikatan kebangsaan merekasebagai bangsa Hindia-Belanda, yangdiperintah oleh pemerintahan penjajah.Ketika Jepang mulai menduduki wilayah-wilayah yang semula disebut Hindia-Belanda, maka istilah Hindia-Belandaberangsur-angsur hilang. Seiring dengansemangat kebangsaan yang mencapaipuncak istilah tersebut berganti menjadiIndonesia. Dengan demikian makasejarah yang dikenal menjadi sejarahIndonesia walaupun isinya belumsepenuhnya “sejarah Indonesia”. MenurutAli pada saat itulah lahirnya sejarahIndonesia (Ali, 2005: 139) . Bukan lagisejarah Hindia-Belanda, bukan sejarahNusantara atau sejarah Hindia, tetapisejarah Indonesia. Pada periode inilahistilah historiografi Indonesiasentris lahir,menggantikan historiografi yangNerlando-sentris atau histriografikolonialsentris.
P e r m a s a l ah a n y an g m u n c u lkemudian adalah ketika apa yang disebutsebagai sejarah Indonesia mulai lahir sifatkediktatoran, sehingga sejarah Indonesia
61
Menggagas Historiografi (Indonesia) ...

mulai mengabaikan “anak-anaknya” yangberupa sejarah lokal. Sejarah Indonesiaberubah menjadi sejarah dengan mono-perspektif tanpa melihat aspek lokalitasyang juga memiliki masa lalu, dalam artidaerah-daerah, etnis-etnis dari yang besar(dalam skala propinsi) sampai yang kecil-kecil (kabupaten, kecamatan, bahkandesa) juga memiliki sejarahnya sendiri.Sejarah telah kehilangan fungsinya untuk“mengikat” unsur-unsur kebangsaan itumenjadi satu kesatuan. Yang munculkemudian adalah meleburkan sertamancampurkan unsur-unsur sebuahbangsa menjadi satu, sehingga warnalokalnya menjadi tidak kelihatan. Di manaletak sejarah “orang Madura” dalamsejarah Indonesia? Di mana posisi sejarahBali, Ambon, Ternate, dan seterrusnyadalam perjalanan bangsa Indonesia?
Sifat kediktatoran sejarah Indonesiamenampakkan wajahnya dengan garangketika Suharto yang berasal dari militermulai memerintah negeri ini. Dalambidang penulisan sejarah, pemerintahdalam hal ini Departemen Pendidikan danKebudayaan (pada waktu itu) memilikiotoritas penuh dan menjadi satu-satunyapintu keluar bagi sejarah yang akandiberikan kepada masyarakat. Instrumenutama dari tindakan ini adalah sebuahbuku babon yang berjudul “SejarahNasional Indonesia” yang prosespenyusunannya dilakukan dan disponsorioleh pemerintah. Semua buku sejarahyang akan diberikan kepada masyarakatharus merujuk kepada babon sejarahtersebut. Penulisan buku sejarah versi lainsulit dilakukan, dan dikontrol secara ketatoleh pemerintah. Dengan kontrol yangketat ini maka ratusan hasil penelitiansejarah yang dilakukan oleh para
akademisi tetap dibiarkan menjadipenghuni abadi rak-rak perpustakaan diuniversitas-universitas. Nasib kurang baikditerima oleh Muljono, karena bukunyatentang keruntuhan Majapahit dilarangberedar oleh pengadilan.
Sejarah betul-betul menjadi elitis danformal, yang tidak memberi ruang kepadakeseharian, kemanusiaan, dan berbagaihal yang terpinggirkan. Dalam kacamataBambang Purwanto, sejarah Indonesiapasca kemerdekaan seakan-akan hanyapengumbar nafsu kebangsaan tanpamelihat dimensi lain yang membentukmasa lalu yang dilalui oleh bangsa ini(Purwanto, 2006: xiv). Dalam konteks inimaka Ali menjadi contoh yang palingnyata dari generasi yang mengendakisejarah sebagai aspek paling mendasaruntuk menjadi legitimasi keberadaan“Indonesia”, sehingga sejarah masihberkutat apakah kata “Indonesia” dapatdigunakan atau tidak untuk menggantikankata “Hindia-Belanda”. Karena sejarahhanya berkuta t pada persoa lanpemupukan paham kebangsaan ataunasionalisme, maka bisa kita lihat padapembahasan sejarah Indonesia untukrentang waktu 1900-1942 yang menjadipokok pembicaraan adalah bangkitnyasemangat nasionalisme para pemudaIndonesia. Lalu di mana posisi orang-orang desa, para petani, para pedagangkecil di perkotaan, anak-anak, ibu rumahtangga pada waktu itu? Historiografimenjadi sangat tidak demokratis karenaelitis dan tidak mampu menguak masa lalurakyat Indonesia (sebagai elemen utamabangsa ini) apa adanya. Rekonstruksimasa lalu bangsa Indonesia hanyadilakukan secara parsial dan sangat tidakdemokratis.
62
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

Demokratisasi HistoriografiSejarah orang besar bukan berarti
hanya mengungkap kisah besar mereka.Orang besar juga mempunyai kisah-kisah“kecil”. Sukarno misalnya, selama inihanya dikenal sebagai pejuang,proklamator, dan orator ulung yangmampu memukau rakyat Indonesia.Sejarawan selalu gagal (atau tidak mau)mengungkap sisi-sisi kemanusiaanSukarno apa adanya, Sukarno sebagaimanusia yang suka makan tempe dan nasipecel misalnya, atau Sukarno yang sukadengan parfum tertentu untuk menarikperhatian lawan jenisnya. Kita tahu bahwaSukarno adalah pencinta wanita, sehinggaistri resminya pun lebih dari tiga belumlagi yang tidak resmi. Kita tidak pernahberusaha mengungkap para pahlawan darisisi humanisme mereka. Kita hanyaterpukau dengan sepak terjang merekadalam bidang politik yang tampil denganwajah ’orang besar’ tanpa cela. Bisadicontohkan misalnya tulisan Lubis,
yang mengangkat eksistensikaum priyayi Sunda dalam pentas politikIndonesia sejak abad ke-19 sampai zamanJepang (Lubis, 1998). Membaca buku ituibarat kita disuruh menyelami kehidupanpara priyayi lengkap dengan segalakepahlawanan mereka.
Paling tidak ada dua hal yang perludilakukan oleh para sejarawan agarhistoriografi (Indonesia) menampakkanwajahnya lebih demokratis dan humanis.
harus dilakukan dekonstruksitentang makna sejarah. Saat ini sebagianbesar sejarawan melupakan kenyataanpenting bahwa sejarah sebagai realitasobjektif yang terjadi pada masa lalumerupakan tindakan apa saja yang bersifat
sangat manusiawi, bukan sesuatu yangseharusnya dilakukan manusia secaranormatif. Kecenderungan yang terjadisaat ini, sebagai sebuah peristiwa, sejarahhanya dikaitkan dengan sesuatu yangpenting secara sosial. Sehingga ketikaorang akan menulis sejarah kemiskinanyang melanda sebuah wilayah akan selaludikaitkan dengan kebijakan tertentu yangmonumental semisal Sistem Tanam Paksaatau kebijakan pemerintahan tertentuyang tidak tepat. Bagi peristiwa yangdianggap tidak memiliki arti pentingsecara sosial, yang sebagian besarm er u p ak an se j a r ah mas y a r a ka tkebanyakan, maka seolah-olah tidak adasejarah di dalamnya.
Apakah perubahan upacarabeserta perubahan-perubahan berbagai
di dalamnya bukan termasuksejarah? Dulu orang menyebut ritualtertentu yang ditujukan kepada “kekuatanyang berpengaruh atas manusia” denganistilah Kemudian ada tahapan dimana orang menyebut kegiatan tersebutsebagai , dan saat ini ketikadimensi keagamaan mulai mengentalpada masyarakat Jawa khususnya agamaIslam, maka istilah tersebut berubahmenjadi atau yaitupembacaan doa-doa yang diakhiri denganpembagian makanan. Selain itu, berbagai
dalam ritual itu pun mengalamiperubahan. Dalam misalnya,makanan utama yang akan dihidangkan dihadapan undangan adalah tumpengberbentuk gunungan atau kukusan yangdikelilingi berbagai lauk-pauk khas desa.Setelah acara doa selesai tumpengtersebut akan dibagi-bagi dan dibungkusdengan daun pisang kemudian dibawapulang. Proses pembungkusannya cukup
Kehidupan Kaum Menak Periangan1800-1942,
slametan
uba rampe
slametan.
kenduren
tahlilan tasyakuran
uba rampeslametan
Pertama
63
Menggagas Historiografi (Indonesia) ...

ribet
ubarampe
urap-urap peyek
capcay
slametan, kenduren tahlilantasyakuran
mbah-mbah
subalternunderside
mainstream
subaltern
no document no history
dan kurang praktis. Saat ini dimanakepraktisan lebih diutamakan, kerapianjuga diperhatikan, serta berbagai
juga menjadi bagian dari kelassosial dari siapa yang menyelenggara-kantahlilan, maka tumpeng digantikandengan makanan yang dikemas dengankotak kardus yang rapi. Lauk-pauk khasdesa semisal , , atau ikanasin, digantikan dengan menu-menu khasrestoran semisal empal, rendang, atau
. Namun, apakah kita menganggap halini sebagai sejarah? Padahal upacara
, atau ataumemiliki makna humanis
yang luar biasa, karena dalam ritualsemacam ini kita dibuat untuk guyub-rukun antar sesama tetangga. Sejak zaman
kita sampai saat ini dimanasistem sosial sudah banyak mengalamiperubahan, ritual-ritual semacam inimasih etap lestari walaupun mengalamiberbagai perubahan. Ini adalah bagiansejarah penting bagi manusia Indonesia.
Agar historiografi menjadi lebihdemokratis maka kajian sejarah sejenis
harus menjadi perhatian atauharus mulai diperhatikan dan
harus diberi tempat yang memadai dalamsejarah Indonesia. Sayang sekali sampaisaat ini sebagian besar sejarawanIndonesia masih terpaku kepadapenulisan-penulisan yang dapat dikatakan
, dan cenderung mengulang-ulang yang sudah ditulis. Periodisasi yangdibuat juga mengekor kepada periodisasisejarah indonesia yang sudah kadaluarsa.Perhatian kepada sejarah justrudatang dari sejarawan asing. Frederickmisalnya telah merekonstruksi kehidupankeseharian masyarakat kota Surabayapada periode 1926-1946. Dengan
pembacaan sumber yang luar biasabanyak ia bisa mengungkap kehidupanmasyarakat kampung-kampung di kotakita dengan sangat bagus (Federick, 1998).Hal serupa dilakukan oleh Ingleson yangmerekonstruksi kehidupan buruh dipelabuhan, prostitusi, serta kehidupanmasyarakat kecil lain di perkotaan(Ingleson, 1986).
Untuk menciptakan historiografiyang demokratis tentu saja kita tidakboleh terpaku kepada sumber-sumbertertulis semata. Masalahnya berbagairealitas keseharian masyarakat tidakpernah terekam dalam sumber-sumbersejarah formal (tertulis), karena yangterbesar justru yang mengendap dalammemori-memori masyarakat yang terlibatdi dalamnya. Dengan demikian makayang , perlu dilakukan reorientasipemahaman atas sumber-sumber sejarah.Saat ini sejarawan terlalu mendewa-dewakan sumber tertulis. Hal initercermin dalam jargon yang selaludidengung-dengungkan oleh sejarawanbahwa . Jargonsemacam ini harus sudah dilenyapkan daripemikiran siapapun yang menginginkanagar historiografi menjadi lebihdemokratis. Persoalannya adalah,tindakan masyarakat yang terekam didalam sumber-sumber tertulis rata-rata(atau sebagian besar) adalah tindakan danperilaku orang besar, bukan perilakurakyat kebanyakan. Rekaman-rekamantertulis masa lalu rata-rata hanya berisiberbagai tindakan yang pada waktu itudianggap penting, bukan tindakankeseharian. Oleh karena itu metodesejarah lisan menjadi sangat penting. Kitaharus menyadari bahwa “yang tidakterjadi” dan tidak terekam dalam
kedua
64
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

dokumen juga merupakan bagian darisejarah. Tuyul misalnya, ia banyakdibicarakan oleh masyarakat Jawa, tetapikarena tidak terekam dalam dokumenmaka tuyul dianggap bukan bagian darisejarah. Demikian juga dengan perilaku
, , atau tindakan yangdianggap bekerja sama dengan makhlukhalus juga tidak pernah dianggap sebagaibagian dari dinamika perubahan sosialdan ekonomi pada masyarakat agraris,karena tidak pernah terekam dalamdokumen tertulis. Setelah Boomgardmenulis hubungan antara perubahanekonomi dengan tuyul, maka baru munculkesadaran bahwa yang tidak terjaditernyata bagian dari sejarah Indonesia(Bambang Purwanto, 2006: 44). Realitaskeseharian semacam inilah yang perlumendapat perhatian para sejarawan.
keterlibatan negara dalampenulisan sejarah hendaknya dikurangiatau malah ditiadakan. Serahkanpenulisan dan penafsiran masa lalukepada masyarakat. Biarkan masyarakatmenilai dengan kritis masa lalu mereka.Penyeragaman sejarah oleh negara yangterjadi pada masa pemerintahan OrdeBaru justru telah menjerumuskan generasisesudahnya. Bagaimana tidak bingungmisalnya, ketika orang-orang yang tinggaldi Kediri dipaksa untuk memahami bahwatelah terjadi pemberontakan yangdilakukan oleh PKI di Jakarta, karenamereka tidak pernah merasakannya. Yangmereka lihat justru beberapa bulan setelahbulan Oktober 1965 para tetangga merekasatu per satu mengambang di sungaiBrantas dalam kondisi yang tidakbernyawa akibat dibantai (Sulistyo, 2000).Berikan porsi yang lebih luas kepadadaerah untuk menampilkan sejarah
lokalnya. Sejarah nasional mestinya tidakdibangun dari keseragaman, tetapi lebihmerupakan mozaik dari keragamansejarah lokal dari berbagai daerah.
Akhirnya perlu dikemukakanbahwa tulisan ini bukan dimaksudkanuntuk menjadikan penuntun tentangmakna historiografi yang demokratis.Masalahnya, demokrasi sendiri memilikimakna yang amat beragam dan sangatt e rgan tung , s i apa yang sedangmenginterpretasikan makna demokrasi itu.Seperti dikatakan di bagian awal daritulisan ini, negara yang menjadi dewademokrasi di dunia ini pun bertindaksangat t idak demokrat i s ke t ikakepentingan mereka terganggu. Apakahhistoriografi juga akan tetap berkubangpada kepentingan kelompok tertentu,sehingga demokratisasi historiografi jugatidak memiliki makna yang baku? Semuakembal i kepada masing-mas ingsejarawan, yang tentu saja memilikikepentingan yang berbeda-beda atassejarah yang sedang dibangun.
Ali, R. Moh.. 2005., LkiS:
Yogyakarta, hlm. 139
Frederick, William H.. 1989.
Gramedia: Jakarta
Ingleson, John, 1986.
babi ngepet nyupang
Pengantar IlmuSejarah Indonesia
Pandangandan Gejolak: Masyarakat Kotadan Lahirnya Revolusi Indonesia( S u r a b a y a 1 9 2 6 - 1 9 4 6 ) ,
Search of Justice:Work and Union in Colonial Java,
Ketiga,
Penutup
DAFTAR PUSTAKA
65
Menggagas Historiografi (Indonesia) ...

1908-1924,
KehidupanKaum Menak Periangan 1800-1942,
GagalnyaHistoriografi Indonesiasentris?!,
EksploitasiKolonial Abad XIX: Kerja Wajibdi Karesidenan Kedu 1800-1890,
Palu Arit diL a d a n g Te b u : S e j a r a hPembantaian Massal yangTerlupakan (1965-1966),
Apanage dan Bekel:Perubahan Sosial di PedesaanSurakarta, 1830-1930,
SerpihanBudaya Feodal,
Oxford UniversityPress: Singapore
Lubis, Nina Herlina. 1998.
Pusat InformasiKebudayaan Sunda: Bandung
Purwanto, Bambang. 2006.
Ombak, Yogyakarta
Surojo, Djuliati. 2000.
YUI:Yogyakarta
Sulistyo, Hermawan. 2000.
KPG:Jakarta
Suhartono. 1991.
TiaraWacana:Yogyakarta
Suhartono W. Pranoto. 2001.Agastya Media:
Yogyakarta
66
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

PrologKalimat di atas adalah petikan
pernyataan Taufik Abdullah (seorangsejarawan terkemuka Indonesia) dalambuku Apa dan Siapa sejumlah orangIndonesia 1985-1986. Bagi Taufik, sastrasangat dekat dengan sejarah. Menurutnya,sejarawan terkemuka pastilah seorangliterer. Bagi Taufik, novel memperkayapengertian tentang dinamika dan sejarah.Selain Taufik, Kuntowijoyo (alm.) adalahsejarawan terkemuka lainnya yang sangatakrab dengan karya sastra. Menurutnyakarya sastra adalah simbol verbal yangmempunyai beberapa peranan, antara lainsebagai cara pemahaman (
), cara perhubungan (), dan cara penciptaan
( ). Obyek karya sastraadalah realitas – apa pun juga yangdimaksud dengan realitas oleh pengarang.Apabila realitas itu berupa peristiwasejarah maka karya sastra dapat, ,mencoba menerjemahkan peristiwa itudalam bahasa imaginer dengan maksuduntuk memahami peristiwa sejarah; ,karya sastra dapat menjadi sarana bagi
pengarangnya untuk menyampaikanpikiran, perasaan, dan tanggapanmengenai suatu persitiwa sejarah; dan
, seperti juga karya sejarah, karyasastra dapat merupakan penciptaankembali sebuah peristiwa sejarah sesuaidengan pengetahuan dan daya imaginasipengarang (Kuntowijoyo, 1999:127).
L e b i h j a u h K u n t o w o j i y omenjelaskan, dalam karya sastra yangmenjadikan peristiwa sejarah sebagaibahan, ketiga peranan simbol itu dapatmenjadi satu. Perbedaan masing-masinghanya dalam kadar campur tangan danmotivasi pengerangnya. Sebagai carapemahaman, misalnya, kadar peristiwasejarah sebagai aktualitas atau kadarfaktisitasnya, akan lebih tinggi daripadakadar imaginasi pengarang. Dalam karyayang berupa cara perhubungan, keduaunsur itu sama kadarnya. Dan dalam karyasastra sebagai penciptaan, kadar aktulitasatau faktisitasnya lebih rendah dibandingimaginasi pengarang. Namun demikian,Kuntowijoyo mengingatkan bahwaperbedaan itu lebih merupakan asumsiteoretis yang dalam pelaksanaannya sulit
mode ofcomprehension modeof communicationmode of creation
pertama
kedua
ketiga
RESENSI BUKU
ANTARA CARA PEMAHAMAN, CARAPERHUBUNGAN
dan CARA PENCIPTAAN
KERONCONG CINTA:
1
Sarkawi B. Husain
“Perang terlalu besar untuk diberikan pada jenderal saja,dan sastra terlalu penting dibiarkan untuk sastrawan saja!”
(Abdullah,1986: 10-11)
*) Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra UniversitasAirlangga, tlp 031-5035676
67

membedakan cara-cara itu dalam sebuahatau di antara karya-karya sastra.
Historiografi dan karya sastrakeduanya merupakan simbol verbal, tapimemiliki perbedaan yang tegas antarakeduanya. Untuk memperjelas perbedaanini, klasifikasi yang dilakukan olehKoestler (dalam Kuntowijoyo, 1999: 128)kiranya dapat membantu. MenurutKoestler penemuan manusia bergerak daridari bentuk yang keyang dengan urut-urutan: Kimia, Biokimia, Biologi,Kedokteran, Psikologi, Antropologi,Sejarah, Biografi, Novel, Epik, dan Lirik.Dari deretan ini tampak bahwa antarasejarah dan novel memiliki hubunganyang dekat untuk saling melakukanhubungan.
Menurut Collingwood (dalamKuntowijoyo, 1999: 128) pertanggung-jawaban sejarah dan sastra berbeda.Sejarah mempunyai tugas kembar.
, sejarah bertujuan menceritakanhal yang sebenarnya terjadi. Sejarahmengemukakan gambaran tentang hal-halsebagai adanya dan kejadian-kejadiansebagai sesungguhnya terjadi. ,sejarah harus mengikuti prosedur tertentu:harus tertib dalam penempatan ruang danwaktu, harus konsisten dengan unsur-unsur lain seperti topografi dan kronologi,dan harus berdasarkan bukti-bukti. Karyasastra tidaklah seketat sejarah. Dia tidaktunduk pada metode-metode tertentu.Karya sastra seperti kata Henry James,mempunyai sedikit pembatasan tetapimempunyai kesempatan yang tidakterhitung jumlahnya.
Peristiwa sejarah sebagai bahan bakudiolah secara berbeda oleh tulisan sejarah
dan oleh karya sastra. Dalam tulisansejarah, bahan baku telah diproses melaluiprosedur tertentu. Dari sumber-sumbersejarah, sejarawan melakukan kritik(ekstern dan intern), analisis, dan sintesissampai pada penyuguhan dalam bentukrekonstruksi sejarah. Sebaliknya, karyasastra memiliki pendekatan lain. Peristiwasejarah dapat menjadi titik tolak bagisebuah karya sastra, menjadi bahan baku,tetapi tidak perlu dipertanggungjawabkanterlebih dahulu. Persitiwa sejarah, situasi,kejadian, perbuatan, cukup diambil darikhazanah bagi hal-haldari masa lalu atau dari common sensebagi peristiwa-persitiwa kontemporer.Prosedur kritik, interpretasi, dan sintesa,tidak diperlukan oleh sastrawan(Kuntowijoyo, 1999: 130).
Sebagai seorang [ ] sejarawandan tentu sebagai sastrawan, AhmadFa i sha l t ahu pe rs i s bag a imanamemperlakukan fakta sejarah sebagaibahan untuk novelnya. Jika memakaipembagian Kuntowijoyo tentang peranankarya sastra, tampak Ahmad Faishalmemperlakukan novelnya dalam tigape rspek t i f , yakn i seb aga i ca rapemahaman ( ),c a r a p e r h u b u n g a n (
), dan cara penciptaan( ). Namun demikian, carayang pertama dan kedua lebih dominandibandingkan dengan cara yang ketiga.
Dengan bahasa yang baik, mengalir,dan mengesankan, penulis novel iniberhasil melakukan dan
terhadap sepotong fenomenasejarah yang terjadi di Surabaya bahkan diIndonesia. Namun demikian, ada
Antara Historiografi dan Karya Sastra
Membaca “Keroncong Cinta” &Beberapa Catatan Kecil
objective-verifiablesubjective-emotional
Pertama
Kedua
accepted history
calon
mode of comprehensionm o d e o f
communicationmode of creation
pemahamanpenciptaan
68
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

beberapa catatan kecil yang hendak sayasampaikan.
misalnya,sebagai titik tolak dari awal cerita novelini merupakan pilihan yang tepat untukmenggambarkan tumbuh kembangnyapergerakan nasional. Taylor Scraap, putraRobert Neiss dan Nyai Zubaidah yangbaru pulang menempuh studi di negeriBelanda yang kemudian mengorganisirsecara diam-diam pemuda-pemudaSurabaya untuk melakukan perlawananterhadap pemerintah kolonial Belandalewat pers merupakan contoh keterlibatankaum intelektual dalam menumbuhkans em an ga t p e r l aw a na n t e r h ad a pkolonialisme.
Dalam berbagai analisis sejarahpergerakan, keterlibatan kaum intelektualdalam menumbuhkan nasionalisme telahbanyak mendapat perhatian ilmuan.Mereka mengembangkan suatu analisisyang menempatkan kaum intelektualsebagai penggerak utama dari berbagaigerakan nasionalis. John Kautskymisalnya, setelah mengidentifikasi kelas-kelas “tradisional” dan “baru” di dalammasyarakat berkembang, berpendapatbahwa peranan sebagai pemrakarsa utamadalam mengerahkan dukungan rakyat danmengorganisasi suatu pergerakan politiknasionalis dimainkan oleh kaumintelektual yang telah menyerap sejumlahwawasan dan nilai peradaban baratmelalui pendidikan yang disediakan olehnegara penjajah dan merasa frustrasikarena keterbatasan kesempatan politikdan kesempatan yang lain di dalam rezimkolonial (Kautsky, 1963: 44-56; Legge,1993: 23).
Menurut J. D. Legge, mereka yangtelah memperoleh pendidikan di berbagai
lembaga pendidikan yang ada, baik diHindia Belanda maupun di negeri Belandamerasa sebagai partisipan dalam –m e m i n j a m k a t a - k a t a S h i l l s –“kebudayaan intelektual modern” atauyang lebih tegas disebutkan HildredGeertz tentang suatu “SuperkulturMetropolitan Indonesia” (
), yangmencakup orang-orang berpendidikanbarat yang antara lain memungkinkanmereka menguasai bahasa asing danpekerjaan serta tingkat penghasilan yangsesuai (Geertz, 1967:33-41).
Akan tetapi, implikasi kehadiranintelektual berubah menjadi suatubumerang bagi sistem kolonial Belanda.Hal tersebut tidak hanya karena merekatelah mengetahui (lewat bangku sekolah)rahasia kekuatan dan keunggulan Eropa,tetapi juga karena mereka mendapatkenyataan bahwa preferensi hanyadiberikan kepada orang-orang Belandadan Indo-Eropa. Kesadaran tentangkondisi yang mereka alami diwujudkandalam berbagai bentuk , seper t ipembentukan organisasi, penerbitan suratkabar [
], kelompok studi, pemogokan,dan partai politik (Scherer, 1985: 52).Keragaman bentuk perjuangan inimengalami pertumbuhan yang pesat padaparuh pertama abad ke-20, sehingga awalabad ke-20 dapat dikatakan sebagaibabakan baru dalam menentangimperialisme Belanda.
Sayang sekali, tahun 1930 sebagaizaman Malaise (sering diplesetkanmenjadi zaman ) tidak dijadikansebagai latar sosial oleh penulis untukmenceritakan pengaruh krisis ekonomiterhadap pertumbuhan pers yang dikelola
Pertama, Tahun 1930
Indonesiametropolitan superculture
seperti yang dilakukan oleh TaylorScraap
meleset
Resensi Buku: Keroncong Cinta ....
69

oleh Taylor dan kawan-kawannya. [
]Dari aspek (yang menjadi
salah satu ciri pokok sejarah) segera bisadisimpulkan bahwa cerita dalam novel iniberlangsung antara tahun 1930 hingga1 9 4 2 . A k a n t e t a p i , F a i s h a l“kecolongan”dari aspek (yangmenjadi ciri pokok lain dari sejarah). Dihalaman pertama memang disebutkanbahwa sepulang dari negeri BelandaTaylor Scraap menjadi redaktur koranberbahasa Belanda di Surabaya. Namundalam episode-episode selanjutnya kitakehilangan jejak di mana peristiwa ituberlangsung. Misalnya: apa nama koranitu dan berkantor di jalan mana? Gerejabergaya barok yang ujung-ujung atapnyatinggi mengerucut (hal. 103) terletak dimana? Kafe tempat Melissa dan Frederickbanyak menghabiskan waktu (hal. 136)terletak di mana? Gunung Geger danPasar Jurang tempat Taylor melarikan diri(hal. 194) berada di mana?
Berbeda denganyang aspek spasialnya kabur, novelsejarah karyaSuparto Brata (2005) misalnya memulaikalimat pertamanya dengan “Darwansampai di Embong Malang”. Dalambagian selanjutnya disebutkan denganjelas tempat episode berlangsung diBlauran, Ketandan, Tembok, Gunung Sari,dan lain-lain. Demikian pula dengannovel sejarah lainnyayang ditulis oleh H.J. Friedericy (1990)dengan je la s menyebu t t empa tber l angsungnya pers i t iwa yangdiceritakan: Makassar, Gowa, Jongaya,Takalar, Jeneponto, dan lain-lain.
sebagaiseorang Indo (putra Robert Neiss danNyai Zubaidah) yang berhaluannasionalis adalah fenomena yang banyakdijumpai dalam sejarah Indonesia.Douwes Dekker adalah salah seorangIndo yang sangat terkenal dalam sejarahpergerakan Indonesia.
Untuk mewujudkan gagasannyadalam hal persamaan warna kulit,k e a d i l a n s o s i a l e k o n o m i , d a nkemerdekaan penuh, atas dasar kerjasamaorang Eurasia-Indonesia, Douwes Dekkerd a n k a w a n - k a w a n n y a b e r h a s i lmendirikan suatu partai politik pada bulanDesember 1912, dikenal sebagaiNationale Indische Partij (N.I.P.).Mottonya adalah: “Hindia Belanda adalahuntuk mereka yang berkehendak terustinggal di sana”, dan di samping 1300orang Indonesia, perkumpulan itu segeramenarik sekitar 6.000 orang Indo,terutama mereka yang menolak untuk ikutserta dalam pertumbuhan persaingan darimakin banyak orang Belansa totok untukpulang ke negeri Belanda setelah karirnyadi Hindia berakhir seperti umumdilakukan. Selama setahun, partai itumendapat tekanan, dan Douwes Dekker,Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, sertaSuwardi Soeryaningrat (kelak dikenaldengan nama Ki Hajar Dewantoro),keduanya orang Indonesia, dipenjarakan,tetapi diizinkan pergi ke negeri Belanda.Dengan demikian, ancaman pertama danterakhir dari kombinasi orang Indonesiadan Eurasia melawan pemerintahBelanda akan lenyap. Pada KabinetSjahrir Ketiga (2 Oktober 1946 – 27 Juni1947) Douwes Dekker (Dr. Setiabudhi)ditunjuk menjadi Menteri Negara (Kahin,1995: 91; 246).
Tapibuat apa mengharapkan sesuatu yangtidak hendak ditulis oleh penulishe…he…
temporal
spatial
Keroncong Cinta
Mencari Sarang Angin
Sang Penasihat
Kedua,Taylor Scraap
70
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

Ketiga,
Keempat ,colour
line.
Nyai Zubaidah,
Pendidikan yangdiskriminatif, segregatif, dan
“istri” dariRobert Neiss, mengingatkan kita padacerita tentang Nyai Dasima. Ceritatersebut (yang terjadi pada awal abad ke-19) mengisahkan kehidupan Dasima,gadis malang yang menjadi “nyai”seorang Inggris. Dengan “pernikahan” inilahir seorang anak bernama Nancy.Kemudian Dasima jatuh ke tanganseorang petualang Sunda yangmengawininya secara paksa, padahal iahanya mengincar har tanya la lumembunuhnya. Munculnya banyakdalam sejarah Indonesia terutama terjadipada abad ke-19 di mana orang-orangEropa terutama kalangan militerdiperkenankan mempunyai gundikpribumi, yang anak-anaknya mendapatsebutan khas “anak kolong”. Karenaprasangaka-prasangka tertentu, wanitaseperti ini dan anak yang dilahirkannyacenderung tidak dihargai (Lombard,2000: 80; 264).
Penulis novel ini menceritakandengan sangat baik bagaimana rendahnyastatus seorang nyai dan anak Indo di mataBelanda totok. Ketika Frederick (anakJenderal L.S. Covet dan Ny. Wenny Vrije)mengutarakan niatnya untuk menikahiMelissa (anak Nyai Zubaidah dan RobertNeiss), Ny Wenny serta merta menjadiberang.
Sayang sekali kisah tentang Nyai(Nyai Dasima, Nji Paina, Nji Sarikem dll.)hanya dapat ditemui dalam karya-karyasastra. Saya sependapat dengan Lombardtentang jarangnya fenomena per-Nyai-andijelaskan dalam perspektif sosiologisyang melatarinya. Padahal, hal tersebutdapat dilihat sebagai akibat “menurunnyastatus” istri pribumi yang tersingkir ketingkat gundik setelah kedatangan wanitaEropa secara besar-besaran pada abad ke-20.
Pembelaan yang dilakukan olehJenderal L.S. Covet ketika mengadiliTaylor yang dianggap menghianatipemerintah Belanda adalah pembelaanyang khas kolonial. Hal tersebutdigambarkan dengan baik oleh penulisnovel ini.
nyai
… “Saya betul-betul mencintainya, Ma.Apa Mama tidak mencintai Frederick?”Nyonya Wenny mengangkat tangan kepinggangnya, “Cinta tidak diletakkan disembarang tempat, Frederick! Danperempuan itu terlalu hina untukberdampingan denganmu. Apa pantassepatu diletakkan di atas piring,Frederick?”
“Mama, Mama jangan terlalu keras
kepala begitu. Tolong hargai pilihanFrederick, Ma.”
“Saya tidak akan menghargai apa pundari kecoak. Dan perempuan itu bukanpilihan, tapi kutukan atas keluarga besarkita.”
“Saya mencintainya,Ma.”
“Jangan mengumbar kata cinta,Frederick. Percuma kamu lulus sekolahtinggi-tinggi jika masih dapat dibodohipelacur keturunan itu. Buka pikiranmuFrederick, pandanglah dunia ini.”
“Pemerintah sudah memberikanperbaikan pendidikan. Kamu tahu itu,kan? Tapi nyatanya mereka tetap sajabuta huruf. Apa itu bukan nilai positifdari pemerintah? Saya tidak bisamembayangkan kalau mereka hanya
(hal.176)
71
Resensi Buku: Keroncong Cinta ....

72
bisa membaca aksara Jawa kuno.”
“Betul sekali, Jenderal. Tapi Jenderaljangan lupa bahwa mereka yang dapatm e m e b a c a d i p e k e r j a k a n o l e hpemerintah hanya sebagai pegawaiadministrasi rendahan. Itu pun untukmempermudah kerja dan kontrolpemerintah Hindia belaka.”
Mendengar ucapan Taylor, Jenderal L.S.Covet menyemprotkan ludahnya kewajah Taylor.
“Tutup mulutmu, pengkhianat”
Taylor langsung membersihkan ludahJenderal L.S. Covet, lantas tangan yangdipenuhi ludah tersebut diciumnya,“Ludah Tuan harum, tapi lebih wangidarah dan keringat yang diderita olehorang pribumi.” (hal. 133-134)
Akses yang agak lebih luas terhadappendidikan bagi pribumi ditandai denganpidato tahunan Ratu Wilhelmina padaSeptember 1901 tentang era baru dalampolitik kolonial yang ditandai denganpolitik etis: , , dan(trilogi kebijakan). Hal ini dianggapsebagai “Kewajiban moral” dan “hutangbudi” ( ) terhadap tanahjajahan.
“ ” dan “” pernah dikemukakan pada tahun
1899 oleh C.Th. Van Deventer, seorangahli hukum yang pernah menetap diIndonesia selama 1880-1897 & menulisartikel tersebut dlm majalahNamun demikian, kebijakan ini dikritikoleh kaum Marxis yang melihat kentalnyamotivas i dan kepent ingan yangmenyertanya. Menurut mereka seluruhkebijakan sebagai suatu muslihatkapitalis-kapitalis, dan apa saja yg
diusulkan dan dijalankan pemerintahBelanda adalah untuk kepentingankeuangan dan kapitalis negeri Belanda.
Kepentingan ekonomi pemerintahkolonial sangat berkaitan dengan situasipada akhir abad ke-19 & awal abad ke-20yang merupakan periode tumbuhpesatnya perkebunan swas ta &perusahaan lain, baik di Jawa maupun luarJawa. Perkembangan ini harus ditunjangoleh sistem administrasi, sistem produksi,manajemen modern, dan birokrasi(pemerintah yg bersifat legal rasional,yang butuh tenaga-tenaga ahli). Dalamposisi inilah pribumi-pribumi yang sudahmen dapa t pend id ikan rendahandipekerjakan.
(hal. 197-213) Masyarakat Jawa Timur khususnyaSurabaya sebagai kota besarnyamerupakan salah satu kota pertama yangmemperhi tungkan secara se r iuskedatangan perang. Pemerintah HindiaBelanda membentuk korps sipi lpertahanan udara sejak tahun 1937, sertamula i melembagakannya da lamperingatan-peringatan. Ketika negeriBelanda dapat dijatuhkan oleh Jermanyang merupakan kelompok Jepang danItalia pada bulan Mei 1940, kegelisahanakan serangan yang akan dilancarkan olehJepang mulai menampak denganpemadaman lampu, serta munculnya usul-usul yang secara serius menjadipembicaraan tentang pendirian kantorpenerangan berbahasa Indonesia danpenempatan radio umum di setiapkampung (Soeara Oemoem, 24 Agustus1941).
Menjelang awal tahun 1941,
edukasi irigasi emigrasi
een eereschuld
Kewajiban moral hutangbudi
de Gids.
Kelima, Kekalahan Belanda,Pendudukan Jepang, dan nasibperempun Indo dan pribumi
.
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74

Surabaya mulai di ambang keruntuhan.Pengungsian masyarakat Surabaya terjadibesar-besaran dan terus menerus kewilayah pedalaman dan segera diikutidengan gerak yang berkebalikan yangdilakukan oleh para pangreh praja danorang-orang Belanda menuju ke kota.Gelombang perpindahan masyarakatawam ini dipicu oleh ketidakstabilankarena pokok perhatian pemerintah kotahanya kepada persiapan-persiapan militer,sehingga timbul kecemasan-kecemasanakan terjadinya perang yang besar diSurabaya.
Sampai bukan Januari hinggaFebruari 1942, perang yang sebelumnyamasih tampak samar-samar dan jauh, kinitiba-tiba datang dan jelas menjadikenyataan saat pasukan Jepangmelakukan pengeboman pertama darilebih enam puluh jkali di atas kotaSurabaya selama kurang dari satu bulan(Frederick, 1989: 110).
Ketika pasukan Jepang berbarismemasuki kota Surabaya, masyarakatmemberikan sambutan yang luar biasa.Sambutan ini digambarkan oleh Faishalsebagai berikut:
Dalam berbagai sumber, misalnya
dalam novel Idrus yang berjudul“ dan film-film dokumenterJepang memang terlihat sambutan yangluar biasa dari rakyat, tetapi teriakanmereka bukan kata , melainkan
! yang artinya.
Tentang tindakan tentara Jepang yangmenangkap orang-orang Belanda dandimasukkan ke dalam kamp, seperti yangdigambarkan dengan sangat baik olehpenulis, memang itulah yang terjadi. Adadua prioritas kebijakan Jepang pascakemenangannya terhadap Belanda, yaitumenghapus pengaruh Barat di kalanganrakyat dan memobilisasi rakyat demikemenangannya. Untuk kepentingantersebut, secara cepat Jepang mengambilalih kekuasaan atas Indonesia dari tanganBelanda dengan memecat dan menggiringsemua personil Belanda, Indo, dan orang-orang yang dicurigai untuk dimasukkanke dalam kamp konsentrasi. Dalamkeadaan inilah mereka yang masih mudadan cantik menjadi “santapan” tentaraJepang yang digambarkan dengan sangathidup oleh mas Faishal. Mereka inilahyang kemudian dikenal dalam sejarahIndonesia sebagai .
. , dalammelakukan penyiksaan terhadap RobinJoong, tentara Belanda dibantu olehSersan Jono (hal. 90). Dalam sejarahIndonesia adalah jamak diketahuipemerintah Hindia Belanda merekrutorang-orang pribumi sebagai tentaranyayang umumnya adalah orang-orangAmbon.Akan tetapi, dari namanya SersanJono pastilah orang Jawa, bukan Ambon.
, t o k o h R u s m a n t o y a n gmencemburui Qomar dan Aminah tiba-
Di jalan kota, pasukan Jepangmelakukan pawai keliling kota.Kendaraan-kendaraan militer danpasukan-pasukan Jepang memenuhijalan. Jenderal Nakabata melambai-lambaikan tangannya ke orang pribumiyang menyambutnya dengan antusiasdan bahagia.
Orang pribumi menyambut lambaiantangan mereka sambil berteriak,“Merdeka! Merdeka! Merdeka!.” (hal.207-208)
Surabaya”
MerdekaBanzai!, Banzai!, BanzaiHidup! Hidup! Hidup!
Jugun Ianfu
Pertama
K e d u a
Keenam, Ada beberapa hal kecilyang menggelitik saya
73
Resensi Buku: Keroncong Cinta ....

tiba muncul di sekitar rumah Haji Anwar(bapak Aminah) , sehingga bisamengetahui sepak terjang Aminah danQomar. Tidak diceritakan dalam novelapakah Rusmanto juga anak buah dariHajiAnwar di pasarnya atau bukan.
Terlepas dari beberapa catatan kecildi atas, saya sangat menghargai kerjakeras mas Faishal dalam menulis novel ini.Terpilihnya novel ini sebagai novelunggulan dan diterbitkan oleh Grasindo(PT. Gramedia Widiasarana) bersamaRad io Ne der l and Weeldomr oepmerupakan garansi akan layaknya novelini menjadi bacaan bagi kalangan yangmendedikasikan dirinya pada studisejarah dan sastra atau mereka yang sukamenikmati karya sastra dan sejarah. Jikabanyak tulisan sejarah harus dibacadengan kening yang mengkerut, makanovel ini akan menambah pengetahuankita tentang sejarah tanpa harusmengerutkan kening. Tentunya apa yangditulis dalam novel ini tidak serta mertamerepresentasikan realitas sejarah yangsesungguhnya terjadi di Surabaya. Sepertikata Els Bogaerts di suatu kesempatan,“
”. Demikian pula, novel initidak bisa dijadikan jalan tikus untukmemahami sepotong sejarah Surabaya,karena bagaimanapun “Membaca adalahwajib hukumnya, tapi tidak wajib untukpercaya pada isi bacaan”.
. Jakarta: Grafitipers,1986.
Geertz, Hildred, “Indonesian Cultures andCommunities” dalam Ruth T.McVey, peny. . NewHaven, Conn.: Human RelationArea Files Press, 1967.
Kahin, George Mc Turnan.
.Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
Kautsky, John H., “An Essay in thePolitics of Development” dalamJohn H. Kautsky, ed.
. New York: Wiley,1963.
Kuntowijoyo. .Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
Legge, J.D.
.Jakarta: Grafiti, 1993.
Lombard, Denys.. Jilid 1. Jakarta: Gramedia,
2000.
Scherer, Savitri Prastiti.
Jakarta: SinarHarapan, 1985.
Epilog
DAFTAR PUSTAKA
Sejarah adalah jalan panjang danberliku, kita tidak boleh mencari danmelewati jalan tikus untuk segera sampaipada tujuan
Apa & Siapa sejumlah orang Indonesia1985-1986
Indonesia
Nasionalismedan Revolusi di Indonesia. RefleksiPergumulan Lahirnya Republik
PoliticalChange in UnderdevelopedCountries: Nationalism andCommunism
Budaya & Masyarakat
Kaum Intelektual danPer juangan Kemerdekaan.Peranan Kelompok Syahrir
Nusa Jawa: SilangBudaya
Keselarasan danK e j a n g g a l a n : P e m i k i r a n -pemikiran Priyayi NasionalisJawa Awal Abad 20.
74
MOZAIK : Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 1, No.1
Januari-Juni 2007: 1 - 74