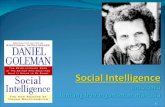social forestry di sulawesi
Transcript of social forestry di sulawesi


BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

SOCIAL FORESTRY DI
SULAWESI
Penulis : Achmad Rizal H. Bisjoe Nurhaedah M.
Hasnawir Nur Hayati Bugi K. Sumirat Abd. Kadir Wakka Muh. Asdar Priyo Kusumedi
Penyunting : Prof. Dr. Ir. Supratman, M.P. Dr. Ir. Murniati, M.Si. Dr. Ir. Dede Rohadi, M.Sc.
Sekretariat : Kepala Seksi Data, Informasi dan Kerjasama Sahara Nompo
Masrum Kasmawati Arman Suarman
BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASSAR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN Jl. Perintis Kemerdekaan Km 16 Makassar, Telp. 0411 554049,
Fax. 0411 554058, Email : [email protected]
Website: http://balithutmakassar.org

iii
Sekilas tentang Penulisan Buku ini
Social Forestry sebagai payung institusi kehutanan dalam
mengemban amanat pembangunan, ditetapkan pada tahun 2003.
Sehubungan dengan itu, Badan Litbang Kehutanan menetapkan
substansi Social Forestry sebagai satu di antara UKP (Usulan Kegiatan
Penelitian) dengan judul Teknologi dan Kelembagaan Social Forestry
jangka waktu 5 tahun (2003 - 2009). Balai Penelitian Kehutanan
Makassar (dulu: BP2KS) ditunjuk sebagai salah satu pelaksana.
Sebenarnya, sudah sejak lama praktik bernafas Social Forestry
dijumpai dalam pengelolaan hutan di Sulawesi. Berawal dari gagasan
Bapak Dr. Ir. Dede Rohadi, M.Sc sebagai Kepala Balai pada waktu itu
(tahun 2003) untuk membuat buku tentang Social Forestry di
Sulawesi yang merupakan wilayah kerja Balai Penelitian Kehutanan
Makassar. Diskusi awal pun dilakukan dalam suatu rapat konsinyasi
yang dipimpin oleh Bapak Ir. Misto, MP (Kepala Seksi Publikasi dan
Dokumentasi) yang menghasilkan draf sistematika buku dan
pembagian tugas di antara personil tim penulis yang diawaki oleh
Bapak Ir. Priyo Kusumedi, MP (peneliti yang diperbantukan pada
struktural balai) dibantu oleh Ibu Tipuk Wulandari, S.Hut., M.Sc. Tim
ini - dengan bongkar pasang personil - sejalan dengan dinamika
balai, sukses menelorkan draf nol serpihan buku, terus berlanjut ke
draf satu, dan akhirnya draf final.
Setelah melalui diskusi panjang, pada tahun 2007 draf final
oleh manajemen (Bapak Ir. Djohan Utama Perbatasari, MM. selaku
kepala balai pada waktu itu) dianggarkan untuk naik cetak, namun
batal dengan pertimbangan tertentu. Akhirnya, draf buku tersebut
tinggal sebagai draf. Sangat disayangkan, kalau informasi - yang
boleh jadi, sangat berarti - hanya tersimpan sebagai berkas projek.
Personil tim yang masih bertugas di balai tetap memperbincangkan
nasib “Si Draf Buku” kepada kepala balai berikutnya, Bapak Ir.
Kudeng Sallata, M.Sc yang hanya sebentar menjabat karena segera
beralih kembali menjadi pejabat fungsional peneliti.
Akhirnya, peluang itu pun datang juga! Kepala balai
berikutnya, Bapak Ir. Muh. Abidin, M.Si pada awal 2013 menerbitkan
SK Tim Penyusun Buku, dan salah satu tugasnya adalah melanjutkan

iv
buku Social Forestry, segera setelah diterimanya hasil review dari
Sekretariat Badan Litbang Kehutanan (pada waktu itu dipimpin oleh
Bapak Ir. Wisnu Prastowo, M.Sc) terhadap draf buku tersebut.
Dengan dukungan penuh manajemen balai, tim penulis
mengusulkan draf revisi 2013. Bersamaan waktu penyelesaian draf
dimaksud, manajemen balai mengamanahkan peran editor kepada
beberapa pakar, yaitu Bapak Prof. Dr. Supratman, Ibu Dr. Murniati,
dan Bapak Dr. Dede Rochadi untuk memberikan koreksi pada draf
buku. Komunikasi intensif pun berlangsung antara tim penulis
didampingi tim sekretariat dengan tim editor dalam upaya
merumuskan perbaikan dan penyempurnaan draf buku Social
Forestry. Proses tersebut masih berlangsung dan seiring dengan
pergantian pimpinan balai kepada Bapak Ir. Misto, MP maka
pekerjaan yang memakan waktu cukup panjang tersebut, mendekati
perumusan draf final, dan akhirnya buku tersebut siap untuk
diterbitkan. Alhamdulillah.
Semoga buku Social Forestry ini dapat diterima dulu apa
adanya, sambil terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan
berdasarkan saran dan masukan dari pembaca yang budiman. Terima
kasih.

v
UCAPAN TERIMA KASIH
Catatan tentang social forestry di Sulawesi, baik bersifat riset
maupun tinjauan dan berbagai pustaka penunjangnya, yang
dihimpun dalam buku yang tersaji di hadapan pembaca, merupakan
hasil kerjasama tim penulis dengan bantuan dari berbagai pihak.
Pada bagian ini, secara khusus diucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada:
1. Bapak Dr. Dede Rohadi sebagai pencetus ide penulisan buku
social forestry di Sulawesi;
2. Bapak Ir. Wisnu Prastowo, M.Sc. yang telah berkenan
memberikan koreksi awal atas naskah buku ini;
3. Kepala Balai Penelitian Kehutanan Makassar sebagai pengarah
selama proses penulisan buku social forestry di Sulawesi;
4. Para Narasumber sebagai pemerkaya tulisan buku social forestry
di Sulawesi;
5. Para peer-review sebagai pencermat dan pemeriksa naskah buku,
dan
6. Semua pihak yang turut berperan dalam proses penyusunan buku
ini.
Semoga jerih-payah pihak yang telah disebutkan di atas
dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wata’ala Yang
Maha Mengetahui. Amin.
Buku ini hanyalah sebagian kecil saja dari khasanah
pengetahuan tentang social forestry, yang tentu akan ditemui
kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Oleh karena itu, segala
saran dan masukan demi perbaikan buku ini, diterima dengan
segenap sukacita dan ucapan terima kasih.
Makassar, Desember 2014
Kepala Balai.
Ir. Misto, MP.
NIP. 19620711 199002 1 001

vi

vii
KATA PENGANTAR
Penyusunan buku “Social Forestry di Sulawesi”, dilaksanakan
untuk mendorong pengembangan social forestry baik di kawasan
hutan negara maupun di hutan hak milik, serta bentuk-bentuk
pengelolaan hutan lainnya oleh masyarakat, seperti hutan adat.
Penyusunan buku ini diharapkan dapat mendokumentasikan
beberapa informasi mengenai dinamika kegiatan social forestry di
Sulawesi, model dan pola social forestry yang berkembang di
beberapa daerah di Sulawesi, sistem pengelolaan social forestry yang
berbasis pada kearifan dan pengetahuan lokal serta permasalahan
dan solusinya.
Isi buku ini dihimpun dari hasil penelitian Balai Penelitian
Kehutanan Makassar dan studi pustaka dari lembaga penelitian lain,
lembaga perguruan tinggi, penelitian perorangan dan penelitian dari
lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten dengan kegiatan
social forestry. Isi buku ini menekankan pada proses belajar bersama
dan berbagi pengalaman tentang pengelolaan hutan pada berbagai
tempat dan karakteristik, untuk memahami paradigma social forestry
secara lebih luas. Kedalaman ulasan pada masing-masing lokasi
kajian berbeda, berdasarkan fokus kegiatan yang telah dilaksanakan.
Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat. Segala masukan
dan saran perbaikan bagi kelengkapan buku ini, disambut dengan
tangan terbuka dan ucapan terima kasih.
Hormat kami,
Tim Penulis

viii

ix
DAFTAR ISI
Sekilas Tentang Penulisan Buku ............................................... iii
Ucapan Terima Kasih .................................................................. v
Kata Pengantar ........................................................................... vii
Daftar Isi ..................................................................................... ix
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................... 1
A. Latar Belakang .......................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan ................................................................... 2
BAB II. KEBIJAKAN ................................................................... 3
A. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan ................................................ 3
B. Kebijakan Hutan Desa ................................................................ 7
C. Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ..................................... 7
D. Pengembangan Hutan Kemitraan ................................................ 8
BAB III. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN SOCIAL FORESTRY .................................................................... 11
A. Faktor Sosial Budaya ................................................................. 11
B. Faktor Sosial Ekonomi ............................................................... 13
C. Faktor Kelembagaan .................................................................. 13
BAB IV. KONSEPSI DAN BEBERAPA PRAKTIK SOCIAL FORESTRY DI SULAWESI ............................................ 17
A. Konsepsi Social Forestry ............................................................ 17
B. Beberapa Praktik Social Forestry di Sulawesi ................................. 22
BAB V. STRATEGI PENGEMBANGAN SOCIAL FORESTRY DI SULAWESI ...................................................................... 47
BAB VI. PENUTUP ....................................................................... 55
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................... 57

x

1
I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Istilah social forestry (SF) atau perhutanan sosial muncul di
dunia kehutanan pada tahun 1970-an. Tambahan kata social
menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan pengertian forestry,
yang secara tradisional bertumpu pada produksi kayu, sehinggga
social forestry dapat diartikan sebagai suatu pola manajemen yang
berbeda dengan pola manajemen kehutanan tradisional/
konvensional, yaitu dengan menambahkan aspek manajemen sosial
di dalam manajemen hutan. Penekanan pendekatannya kepada
pemberian akses yang lebih besar kepada masyarakat dalam
mengelola hutan. Social Forestry merupakan suatu pendekatan
pengelolaan hutan yang bertujuan membangun struktur dan sistem
pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan tipologi sosial,
tipologi fungsi hutan dan tipologi fungsi wilayah dan bersifat local
specific. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tujuan SF adalah 1.
mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di
dalam dan sekitar hutan; dan 2. menerapkan atau mewujudkan
prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (Pasaribu, 2003). Sejalan
dengan itu, Rusli (2003) menyatakan bahwa SF menempatkan
masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai pelaku utama dengan
maksud meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan
kelestarian hutan di lingkungannya dengan mempercepat rehabilitasi
hutan dengan menyatukan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
Definisi social forestry (perhutanan sosial) sangat beragam
dan dapat saling melengkapi. Beberapa ahli berpendapat istilah
perhutanan sosial adalah padanan kata dari “social forestry”. Gilmore
dan Fisher (1998), menyatakan bahwa social forestry adalah bentuk
kehutanan industrial atau konvensional yang dimodifikasikan untuk
memungkinkan distribusi keuntungan kepada masyarakat lokal.
Sedangkan beberapa ahli mendefinisikan social forestry sebagai
kegiatan yang berkenaan dengan semua aktivitas kehutanan dengan
sasaran spesifik partisipasi masyarakat lokal dan pemenuhan

2
kebutuhan serta aspirasi masyarakat tersebut yang berkaitan dengan
hutan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa social forestry
merupakan bentuk pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang
menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.
Menurut Simon (1998), perkembangan teori pengelolaan
hutan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori
kehutanan konvensional dan kategori kehutanan modern (kehutanan
sosial). Teori pengelolaan hutan yang termasuk ke dalam kehutanan
konvensional adalah eksploitasi kayu atau Timber Extraction (TE) dan
pengelolaan kayu atau Timber Management (TM). Sementara itu
yang termasuk ke dalam golongan kehutanan sosial (social forestry)
adalah pengelolaan hutan sebagai sumberdaya atau Forest Resource
Management (FRM) dan pengelolaan hutan sebagai ekosistem atau
Forest Ecosystem Management (FEM). Keempat teori pengelolaan
hutan tersebut, secara evolutif berkembang, sejak mulai eksploitasi
kayu hingga sampai pada pengelolaan ekosistem hutan. Program
social forestry di Indonesia yang merupakan bagian dari
perkembangan pengelolaan hutan, dimulai pada tahun 1984 di Pulau
Jawa oleh Perum Perhutani. Pada tahun 1986, social forestry mulai
diterapkan juga di luar Pulau Jawa. Namun, saat ini yang
dilaksanakan secara massal hanyalah social forestry di Pulau Jawa,
sedangkan social forestry di luar Pulau Jawa, termasuk Sulawesi
masih dalam skala “pilot project”. Namun, sebelum adanya program
social forestry dimaksud, telah ada praktik pengelolaan hutan oleh
masyarakat setempat dengan beragam istilah.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk
mendokumentasikan beberapa informasi tentang social forestry di
Sulawesi, mencakup: perkembangan dan dinamika kegiatan social
forestry, model dan pola social forestry yang berkembang di
beberapa daerah di Sulawesi, sistem pengelolaan social forestry yang
berbasis pada kearifan dan pengetahuan lokal, serta permasalahan-
permasalahan yang muncul dan kemungkinan-kemungkinan
solusinya.

3
II KEBIJAKAN
Pengertian kebijakan kehutanan (forest policy) merupakan
pertimbangan yang dimaksudkan untuk mengarahkan kegiatan atau
nonkegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam
kaitan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan. Kebijakan kehutanan
biasanya memandu atau mengarahkan bagaimana hutan akan
dimanfaatkan untuk mencapai berbagai tujuan, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis (Cubbage et al., 1993).
Dalam kaitannya dengan pengembangan social forestry,
pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan
Pemerintah (PP) No.1/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Rangka Social Forestry. PP No.1/2004 menjadi landasan
hukum dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan, baik yang berada
pada kawasan hutan negara maupun pada kawasan hutan hak.
Masyarakat sekitar menjadi pelaku dan atau mitra utama dalam
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan
kelestarian hutan.
Pengembangan social forestry dalam kawasan hutan negara
dilakukan dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa
(HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemitraan.
Sementara social forestry pada kawasan hutan hak/hutan milik
dilakukan dalam bentuk Hutan Rakyat (HR). Sejumlah stakeholder
yang dapat terlibat dalam pengembangan social forestry adalah
pemerintah pusat, pemerintah daerah, Non Government Organisation
(NGO), badan usaha, Perguruan Tinggi, kelembagaan masyarakat
dan lembaga internasional.
A. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan
Untuk mengantisipasi tuntutan kebutuhan dan menampung
aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam pengelolaan hutan,
maka pada tahun 1995 pemerintah menerbitkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan (SK Menhut) No. 622/Kpts-II/1995 tentang

4
Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Dalam keputusan tersebut, yang
dimaksud dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah sistem
pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya dengan mengikutsertakan
masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan.
Apabila mencermati definisi HKm tersebut diatas nampak
bahwa peranan masyarakat dalam pengelolaan HKm sangat kecil. Hal
ini tergambar dari kata “mengikutsertakan masyarakat” yang dapat
berarti bahwa masyarakat tidak diberikan kewenangan penuh dalam
hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini juga
mengindikasikan bahwa perencanaan HKm bersifat ”top down” dan
masyarakat belum mendapatkan kepercayaan penuh dari pemerintah
dalam pengelolaan hutan.
Masyarakat sekitar hanya berfungsi sebagai penyedia “jasa
tenaga kerja” yang diupah untuk melakukan kegiatan penanaman
pada areal hutan yang kritis. Disamping itu, masyarakat hanya dapat
memungut hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari jenis tanaman serba
guna (multi purpose trees species/MPTS) yang dikembangkan seperti
buah-buahan, getah-getahan, dan lain sebagainya pada areal HKm
meskipun lahan yang dikelola merupakan kawasan hutan produksi
yang memungkinkan masyarakat mengembangkan tanaman
penghasil kayu.
Kurangnya kepercayaan pemerintah kepada masyarakat
dalam pengelolaan HKm dapat menyebabkan kurangnya kepedulian
masyarakat untuk memelihara tanaman yang dikembangkan dalam
areal HKm (kurangnya sense of belonging). Dampak yang
ditimbulkan adalah rendahnya persen tumbuh dari tanaman yang
telah dikembangkan pada areal HKm.
Menyadari kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan
kegiatan HKm sebelumnya, maka pada tahun 1998 diterbitkan
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (SK Menhutbun) No.
677/Kpts-II/1998 tentang HKm. Dalam keputusan tersebut
disebutkan bahwa HKm adalah hutan negara yang dicadangkan atau
ditetapkan menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat
dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan
fungsinya dan menitikberatkan pada kepentingan mensejahterakan
masyarakat.

5
SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998 menegaskan bahwa
areal HKm berada pada kawasan hutan negara sehingga harus
mengikuti ketentuan-ketentuan negara dalam pengelolaan hutan.
Selain itu SK Menhutbun ini juga berusaha memberikan kepastian hak
bagi masyarakat dengan jalan memperpanjang jangka waktu
pengelolaan dari 5 tahun dan dapat diperpanjang (SK Menhut No.
622/Kpts-II/1995) menjadi 35 tahun dan dapat diperpanjang
(Dipokusumo et al., 2011).
Dalam SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998, masyarakat
sudah mulai mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dalam
pengelolaan hutan. Hal ini dapat dilihat dimana masyarakat tidak lagi
diikutsertakan dalam pengelolaan HKm tetapi sebagai pelaku utama
dan pengambil keputusan dalam menentukan sistem pengusahaan
HKm.
Hasil yang diperoleh dari areal pengusahaan HKm bukan lagi
semata-mata HHBK tetapi lebih bervariasi yaitu hasil kayu, jasa
rekreasi, pemanfaatan dan penangkaran satwa liar dan tumbuhan air.
Dengan bervariasinya hasil yang dapat diperoleh oleh masyarakat
diharapkan pengusahaan HKm dapat lebih meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar.
Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat yang tertuang dalam SK Menhutbun No. 677/Kpts-
II/1998 nampaknya masih setengah hati. Hal ini tergambar dari
wujud pengelolaan HKm yang berbentuk pengusahaan HKm.
Masyarakat yang terhimpun dalam suatu wadah koperasi jika ingin
memungut hasil hutan kayu pada areal HKm dengan fungsi produksi
terlebih dahulu harus mendapatkan ijin usaha pemungutan hasil
hutan kayu (IUPHHK) HKm. Selain itu untuk mendapatkan hak
pengusahaan HKm (HPHKm), masyarakat (koperasi) perlu menyusun
RIPHKm, RKLHKm dan RKTHKm.
Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam
pengusahaan HKm. masih sulit dipenuhi oleh masyarakat (koperasi)
meskipun pemerintah telah memberikan bantuan fasilitas melalui
pendampingan, pelatihan dan penyuluhan. Hal ini disebabkan
beberapa LSM yang mendampingi masyarakat belum memiliki
pengetahuan yang cukup dalam membuat RIPHKm, RKLHKm dan
RKTHKm. Sebagian besar LSM pendamping yang ada baru terbentuk

6
setelah adanya program HKm karena keberadaan LSM pendamping
merupakan salah satu prasyarat yang harus ada dalam program
pengembangan HKm.
Menyadari kendala-kendala yang dihadapi dalam
implementasi SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998, Pemerintah
kemudian melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan SK
Menhutbun No. 865/Kpts-II/1999. Beberapa penyempurnaan yang
dilakukan dalam SK Menhutbun No. 865/Kpts-II/1999 diantaranya; a)
mengubah istilah Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan menjadi
Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, b) pemegang Ijin tidak lagi
diwajibkan membuat RIPHKm tetapi cukup membuat rencana
pemanfaatan HKm, c) koperasi bukan merupakan persyaratan mutlak
bagi masyarakat setempat untuk mengajukan permohonan tetapi
dapat melalui lembaganya (kelompok).
Sehubungan dengan terbitnya UU No. 22/1999 tentang
Pemerintahan Daerah, UU No. 25/1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No. 41 tentang
Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 25/2000 tentang
Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, pemerintah kemudian
melakukan langkah-langkah penyesuaian dan penyempurnaan
kebijakan hutan kemasyarakatan. Hal ini ditandai dengan
diterbitkannya SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001 tentang
penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri
Kehutanan (Permenhut) No.P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan
Kemasyarakatan.
SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001 dan Permenhut
No.P.37/Menhut-II/2007 mengharapkan partisipasi aktif masyarakat
selaku pengelola HKm mulai dari penataan batas areal sampai
dengan perencanaan pemanfaatan dan rencana kerja. Selain itu,
kedua kebijakan tersebut mendorong masyarakat selaku pengelola
HKm untuk lebih profesional dalam mengelola kawasan HKm melalui
kelembagaan koperasi (Dipokusumo et al., 2011). Agar dapat
profesional dalam mengelola kawasan HKm, pemerintah setempat
diharapkan lebih proaktif melakukan kegiatan pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan kapasitas dan kemudahan akses
sehingga kemampuan dan kemandirian masyarakat semakin
meningkat.

7
B. Kebijakan Hutan Desa
Salah satu wujud komitmen pemerintah untuk
memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya
sangat tergantung kepada sumberdaya hutan adalah dengan
menebritkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.
P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Hutan Desa (HD) yang
dimaksud dalam Permenhut ini adalah hutan negara yang dikelola
oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum
dibebani izin/hak. Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk
memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga
desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.
Kehadiran Permenhut No. P.49/2008 membawa angin segar
bagi masyarakat desa sekitar hutan karena dipercaya untuk
mengelola kawasan hutan dengan kearifan-kearifan lokal yang
dimilikinya (Hermawansyah, 2013). Permenhut ini membuka peluang
bagi masyarakat desa sekitar hutan untuk meningkatkan
kesejahteraannya. Hal ini disebabkan karena pemagang hak
pengelolaan hutan desa dapat melakukan kegiatan pemanfaatan
kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu
(HHBK) dan hasil hutan kayu (HHK). Pemungutan HHK tidak
dimungkinkan pada areal hutan desa dengan fungsi lindung.
Namun pada kenyataannya, untuk mendapatkan Surat
Keputusan Penetapan Areal Kerja (SK PAK) Hutan Desa harus melalui
proses yang rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Kondisi ini
dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah masih setengah hati
memberikan kepercayaan kepada masyarakat sekitar hutan untuk
mengelola kawasan hutan (Hermawansyah, 2013).
C. Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui pemberian akses
pengelolaan kawasan hutan adalah dengan mengeluarkan kebijakan
pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Kebijakan pemerintah
tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 6/2007 jo PP
No.3/2008.

8
Peraturan Menteri Kehutanan No.P.3/Menhut-II/2012 tentang
Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu, Hutan
Tanaman Rakyat. Dalam Peraturan ini, beberapa pengertian
dijelaskan sebagai berikut :
1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin
usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa
kayu pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau
koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan
produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin
kelestarian sumber daya hutan.
2. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah
kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang
tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan
kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pembangunan
usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya.
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR
adalah rencana kerja IUPHHK-HTR untuk seluruh areal kerja
yang berlaku selama daur tanaman pokok yang dominan, antara
lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek
keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi
setempat.
3. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat RKTUPHHK-
HTR adalah rencana kerja IUPHHK-HTR dalam satu KTH
dan/atau Koperasi dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusun berdasarkan RKUPHHK-HTR.
4. Tanaman Pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil
hutan berupa kayu perkakas/pertukangan dan atau bukan
perkakas/ pertukangan.
D. Pengembangan Hutan Kemitraan
Peraturan Menteri kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013
tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan
Kehutanan. Dalam peraturan menteri kehutanan ini dijelaskan bahwa

9
pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan
adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya
hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Maksud
pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan adalah
mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat
setempat dalam rangka kerjasama dengan Pemegang Izin
pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha
industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan
wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat setempat. Tujuan Pemberdayaan masyarakat setempat
melalui Kemitraan Kehutanan adalah terwujudnya masyarakat
setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui
penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam
mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat
berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri,
bertanggung jawab dan profesional. Ruang lingkup peraturan ini
meliputi : a. Pelaku Kemitraan Kehutanan; b. Fasilitasi; c.
Pelaksanaan Kemitraan Kehutanan; d. Pembinaan dan Pengendalian;
e. Insentif.

10

11
III FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN SOCIAL FORESTRY
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan social forestry ditentukan
oleh tiga faktor penting. Adapun faktor-faktor tersebut menurut
Awang (2004) adalah sebagai berikut: (1) Faktor sosio-kultural, (2)
Faktor sosial ekonomi dan (3) Faktor kelembagaan.
A. Faktor Sosial Budaya
Kebudayaan adalah hasil upaya yang terus menurus dari
manusia di dalam ikatan masyarakat dalam menciptakan sarana dan
parsarana yang diperlukan untuk menjawab tantangan
kehidupannya. Selain yang sudah dilakukan dan diciptakan juga
tercakup apa yang masih dicita-citakan termasuk norma, pandangan
hidup dan sistem nilai (Syahyuti, 2006).
Faktor sosial budaya yang menentukan keberhasilan program
social forestry antara lain lahan, kependudukan, organisasi formal
dan informal, pendidikan, penyuluhan dan faktor ideologi (Awang,
2004). Faktor sosial budaya ini menurut Wakka (2005) ditujukan
untuk mengungkap tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam
masyarakat yang terpelihara dengan baik dan memiliki peran, baik
dalam pengelolaan sumber daya alam maupun dalam kehidupan
sehari-hari dalam pengembangan social forestry.
Faktor lahan biasanya terkait dengan tata penguasaan lahan
(land tenure), sistem penggunaan lahan, dan lahan warisan nenek
moyang. Sistem penggunaan lahan yang memperhatikan ekologi dan
penggunaan input informasi yang sesuai dengan kondisi lokal untuk
mendorong produktivitas, stabilitas, pemerataan dan keberlanjutan.
Menurut Hakim et al. (2010), pengakuan dan kepastian tentang
kepemilikan lahan masyarakat tradisional melalui formulasi baru
kebijakan penggunaan lahan yang sesuai dengan cara hidup
masyarakat sehingga tidak muncul isu dan masalah-masalah antara
pemerintah dan masyarakat adat. Bentuk hak masyarakat atas lahan

12
diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku agar aset
masyarakat di atas lahan hutan tersebut secara yuridis terlindungi
dan terjamin keamanannya.
Pendekatan kehutanan sosial diperlukan untuk memecahkan
beberapa masalah kependudukan yaitu tekanan penduduk,
pendidikan, dan tingkat kehidupan. Pendataan faktor demografi
seperti kerapatan penduduk, rasio ketergantungan, dan pola
pergerakan penduduk desa digunakan untuk merencanakan proyek
social forestry. Sementara itu ketersediaan tenaga kerja yang cukup
merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu program
pembangunan yang akan dilaksanakan.
Pendidikan perlu diperhatikan secara baik, terutama bagi
mereka yang terlibat dalam kegiatan social forestry. Menurut Wakka
(2005), pendidikan masyarakat merupakan salah satu indikator
kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Tingkat
pendidikan masyarakat mempengaruhi cara berpikir seseorang,
terutama dalam menganalisis suatu masalah. Tingginya tingkat
pendidikan masyarakat memungkinkan masyarakat lebih cepat
menerima dan memberikan respon terhadap hal-hal yang
membutuhkan kemampuan berpikir dari inovasi-inovasi baru yang
dianjurkan kepadanya. Kecenderungan yang ada, semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang, maka semakin responsif orang
tersebut terhadap perubahan–perubahan.
Strategi dan pendekatan untuk mengantisipasi kelemahan
organisasi formal dan informal dalam kegiatan social forestry adalah
kepemimpinan, partisipasi, dan organisasi masyarakat lokal. Menurut
Wakka (2005), pelibatan pemimpin formal dan nonformal dalam
pengembangan social forestry perlu mendapat perhatian, baik
sebagai motivator maupun sebagai penyambung informasi dan
instruksi dari pelaksana program ke masyarakat sasaran sebagai
pelaksana kegiatan dari program tersebut.
Menurut Rahayu dan Wianti (2010) partisipasi merupakan
suatu tahapan menuju upaya pemberdayaan, supaya program social
forestry berhasil maka perlu disediakan insentif dan kesempatan bagi
masyarakat yang terlibat langsung dalam kegaiatan social forestry.

13
B. Faktor Sosial Ekonomi
Faktor sosial ekonomi yang menentukan keberhasilan social
forestry adalah ketersediaan sumberdaya hutan, ketersediaan lahan
dan kualitas lahan, ketersediaan tenaga kerja, permodalan, teknologi
tepat guna, pendapatan masyarakat, standar kehidupan, dan
kemampuan ekonomi (Awang, 2004). Kemampuan ekonomi ini
terkait dengan kelembagaan (makro), ketersediaan pasar,
pemerataan, peluang kerja, infrastruktur, pendidikan di pedesaan,
motivasi, persepsi, kesadaran, tingkah laku, kesehatan, aspirasi dan
politik.
Suatu program yang menyangkut aspek sosial ekonomi
masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran aktif masyarakat, baik
kedudukannya sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan
(Awang, 2003). Menurut Subarudi (2005), identifikasi karakteristik
sosial ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam
pelaksanaan social forestry karena berdasarkan pengalaman
‘kegagalan’ semua kegiatan pemberdayaan masyarakat disebabkan
pengabaian kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
Disamping itu juga disebabkan karena kegiatan tersebut tidak
dirancang dalam skala ekonomi sehingga keberlanjutan dari usaha
tersebut hanya dirasakan dalam satu atau dua tahun saja setelah itu
menghilang ditelan waktu.
C. Faktor Kelembagaan
Kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku (ways) yang
hidup pada suatu kelompok orang. Kelembagaan merupakan sesuatu
yang stabil, mantap dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan
tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional
dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern dan
berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial (Syahyuti, 2006).
Faktor kelembagaan yang terkait dengan keberhasilan social forestry
mencakup tentang kelembagaan pembuat kebijakan, pelaksanaan
kelembagaan, institusi klien (peserta program), keterkaitan dan
dukungan lembaga-lembaga (Awang, 2004).
Kelembagaan dapat mempunyai dua arti, yaitu suatu
perangkat peraturan dan organisasi yang membuat serta mengawasi

14
pelaksanaan peraturan–peraturan tersebut. Sebagai suatu perangkat
peraturan, kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu tatanan dan
pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang
saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar
manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi
atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan
pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal maupun informal
untuk pengendalian prilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama
dan mencapai tujuan bersama (Djogo et al., 2003).
Pembangunan kelembagaan (institutional buildings) merupakan
upaya mendapatkan inovasi melalui perubahan-perubahan dalam
norma-norma, dalam pola-pola prilaku, dalam huhungan-hubungan
perorangan dan antar kelompok. Setiap bentuk kelembagaan adalah
hasil dari sebuah evolusi yang salah satunya bertujuan untuk
meminimalkan konflik antar masyarakat maupun konflik dengan
pemerintah. Perubahan (evolusi) kelembagaan terjadi karena ada
perubahan nilai yang mendorong para pelaku untuk menjadi lebih
baik dengan memilih alternatif atau memodifikasi kelembagaan yang
ada sehingga sesuai dengan ketersediaan sumberdaya yang ada
(Esman, 1962 dalam Haddade, 2004).
Pengenalan kelembagaan dan rencana penguatan
kelembagaan perlu juga dilakukan agar semua rencana makro social
forestry dapat dijalankan secara tepat sesuai dengan tujuannya.
Sehingga perlu penguatan kemampuan lokal agar program social
forestry lebih efektif (Awang, 2004). Menurut Djogo et al. (2003),
kelembagaan berjalan baik apabila semua komponen dalam lembaga
tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Secara umum beberapa
aspek dalam kelembagaan yang dapat dijadikan kriteria dan indikator
antara lain: keorganisasian, kepemimpinan, pengembangan
kapasitas, manajemen konflik dan kegiatan yang dilakukan.
1. Keorganisasian, meliputi ketertataan (struktur organisasinya
modern atau tradisional), keanggotaan (apakah anggota masuk
secara otomatis/pasif atau harus melalui prosedur
pendaftaran/aktif), daya akomodasi aspirasi (apakah lembaga
aspiratif atau tidak terhadap setiap masukan dari anggotanya),
aturan organisasi (sifatnya formal/tertulis atau informal/tidak
tertulis), aset organisasi (areal kerja/lahan, sarana-prasarana).

15
2. Kepemimpinan, terdiri dari gaya pemimpin (tradisional/
feodalistik atau demokratis), posisi pemimpin (dominan/tidak
dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan).
3. Pengembangan Kelembagaan, seperti kursus, pelatihan, studi
banding, penyuluhan dan lain-lain.
4. Manajemen Konflik, dimana organisasi mampu mengelola
konflik yang terjadi dalam lembaga/organisasinya, dalam hal
klasifikasi, penyelesaian, penegakan sanksi-sanksi serta
kemampuan mengelola dampak dari konflik-konflik yang terjadi.
5. Kegiatan-kegiatan produktif, misalnya uji coba penerapan
HKm, uji coba pemanfaatan kayu, patroli mencegah penebangan
liar, penataan kebun, pengembangan peternakan, simpan pinjam
dan lain-lain.
Kelembagaan social forestry merupakan legitimasi terhadap
pencadangan kawasan, serta struktur menajemen dan usaha. Secara
sangat jelas kebijakan pencadangan kawasan bukanlah untuk
merubah status dan fungsi kawasan, dan juga bukan untuk
memberikan kepemilikan atas kawasan. Pencadangan kawasan untuk
pembangunan social forestry dapat menjamin dilakukan kegiatan
menajemen dan usaha menuju tercapainya sasaran social forestry
yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan,
dan mewujudkan kelestarian hutan yang kedua-duanya diibaratkan
sebagai dua sisi mata uang. Dalam kelembagaan tersebut melekat
tugas, tanggung jawab dan hak masing-masing mitra.
Pengembangan kelembagaan merupakan proses transformasi dari
sistem yang ada dan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan
kebijakan pusat, daerah dan masyarakat (Rusli, 2007).

16

17
IV KONSEPSI DAN BEBERAPA PRAKTIK SOCIAL FORESTRY DI SULAWESI
A. Konsepsi Social Forestry
Konsepsi social forestry (perhutanan sosial) diawali oleh
konsepsi community forestry (kehutanan masyarakat) sebagai
tanggapan atas kegagalan konsep industrialisasi kehutanan pada
sekitar tahun 1960-an. Konsep tersebut digagas oleh Jack Westoby
yang termasuk penggagas tema pokok Kongres Kehutanan Dunia
VIII tahun 1978 di Jakarta, Forest for People.
Gagasancommunity forestry tersebut kemudian banyak
dipublikasikan FAO. Pada tahun 1983 secara resmi FAO
mendefinisikan community forestry sebagai konsep radikal kehutanan
yang berintikan partisipasi rakyat, artinya rakyat diberi wewenang
merencanakan dan memutuskan sendiri apa yang dikehendaki. Hal ini
berarti memfasilitasi masyarakat dengan saran dan masukan yang
diperlukan untuk menumbuhkan bibit, menanam, mengelola dan
melindungi Sumberdaya Hutan (SDH) yang dimiliki, memanennya dan
mendapatkan keuntungan maksimal dari usaha tersebut. Dengan
demikan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dapat
meningkat.
Selanjutnya, dalam perkembangannya konsepsi kehutanan
masyarakat sering dikonfrontasikan dengan konsep perhutanan sosial
yang merupakan terjemahan dari social forestry (Social Forestry).
Konsepsi social forestry dipahami sebagai bentuk pengusahaan hutan
yang dimodifikasi supaya keuntungan yang diperoleh dari
pembalakan kayu didistribusikan kepada masyarakat lokal. Di
Indonesia Perum Perhutani - sebagai salah satu pelopor social
forestry di Indonesia - mendefinisikan bahwa social forestry adalah
suatu sistem dimana masyarakat lokal berpartisipasi dalam
manajemen hutan dengan tekanan pada pembuatan hutan tanaman.
Tujuan social forestry adalah menyelenggarakan reforestasi yang
akan meningkatkan fungsi hutan dan pada saat yang bersamaan

18
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada definisi
Perum Perhutani, memang jelas terlihat perbedaan antara kehutanan
masyarakat dan social forestry. Adapun definisi Social Forestry yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.01/Menhut-
II/2004 adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan
hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada
masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam
rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian
hutan.
Terlepas dari adanya perbedaan dan pertentangan definisi
antara kehutanan masyarakat dan social forestry, di Indonesia kini
berkembang berbagai model dan konsepsi kehutanan yang
mengklaim sebagai derivasi dari konsepsi kehutanan masyarakat
ataupun social forestry. Berbagai model dan konsepsi tersebut,
antara lain :
1. Hutan Kemasyarakatan
Istilah hutan kemasyarakatan mulai diperbincangkan dalam
seminar Persaki (Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia) pada
tahun 1985 dan pola pengembangannya dijabarkan oleh Direktorat
Penghijauan dan Pengendalian Perladangan tahun 1986. Hutan
kemasyarakatan mulai dikembangkan dalam Repelita Kelima
(1989/1990 s/d 1993/1994). Dalam dokumen Repelita Kelima
disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perlu diusahakan agar kawasan hutan mampu memberikan manfaat
kepada masyarakat sekitarnya dalam jumlah yang lebih banyak dan
mutu yang lebih baik melalui hutan kemasyarakatan atau hutan sosial
yang dikembangkan di sekitar desa-desa dan dikelola oleh organisasi
sosial masyarakat secara mandiri.
Pada perjalanan selanjutnya pengembangan praktik hutan
serbaguna dan hutan kemasyarakatan saling tumpang tindih.
Keduanya dikembangkan dalam kawasan hutan negara.
Pengembangan di tanah milik juga menjadi tumpang tindih dengan
hutan rakyat, namun demikian sedikit berbeda penekanannya. Hutan
rakyat lebih menekankan pada hasil yang berupa kayu
(pertukangan), sementara itu pada hutan serbaguna dan hutan
kemasyarakatan lebih menekankan pada hasil yang beragam (non

19
kayu) seperti misalnya, rumput, kayu bakar, persuteraan dan lain
sebagainya.
2. Hutan Rakyat
Istilah hutan rakyat sudah lebih lama digunakan dalam
program-program pembangunan kehutanan dan disebut dalam UU
Pokok Kehutanan Tahun 1967 dengan terminologi hutan milik. Di
Pulau Jawa hutan rakyat dikembangkan pada tahun 1930-an oleh
pemerintah kolonial. Setelah merdeka pemerintah Indonesia
melanjutkan pada tahun 1952 melalui gerakan “Karang Kitri”
(Wartaputra, 1990 dalam Santoso, 1999). Secara nasional,
pengembangan hutan rakyat berada di bawah payung program
penghijauan, diselenggarakan pada tahun 1960-an, dimana Pekan
Raya Penghijauan I diadakan pada tahun 1961.
Sampai saat ini hutan rakyat telah diusahakan di tanah milik
yang diakui secara formal oleh pemerintah dan tanah milik yang
diakui pada tingkat lokal (tanah adat). Di dalam hutan rakyat ditanam
aneka pepohonan yang hasil utamanya dapat beraneka ragam. Untuk
hasil kayu misalnya, sengon (Paraserianthes falcataria), jati (Tectona
grandis), akasia (Acacia sp.), mahoni (Switenia mahagoni) dan lain
sebagainya. Sedang untuk penghasil getah, antara lain kemenyan
(Styrax benzoin) dan damar (Shorea javanica). Sementara itu, yang
hasil utamanya berupa buah antara lain kemiri (Aleurites moluccana),
durian (Durio zibethinus), kelapa (Cocos nucifera). (Suharjito dan
Darusman, 1998 dalam Santoso, 1999).
3. Perhutanan Sosial
Secara umum social forestry merupakan sistem pengelolaan
SDH yang dilaksanakan baik pada kawasan hutan negara maupun
hutan hak, dengan menempatkan masyarakat setempat sebagai
pelaku utama dengan maksud meningkatkan kesejahteraannya dan
mewujudkan kelestarian hutan di lingkungannya. Sasaran social
forestry yaitu (1) membangkitkan kegiatan ekonomi masyarakat di
dalam dan sekitar hutan, dan (2) mempercepat rehabilitasi hutan
dengan menyatukan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
Istilah perhutanan sosial pertama kali digunakan dalam
penyelenggaraan program oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa pada
tahun 1986 dan proyek percontohan oleh Kantor Wilayah

20
Departemen Kehutanan, yaitu di Belangian, Kalaan dan Selaru di
Kalimantan Selatan; Enggelam dan Karya Baru di Kalimantan Timur,
Dormena, Ormu, dan Parieri di Irian Jaya (Kartasubrata, 1988 dalam
Santoso, 1999). Pengembangannya oleh Perum Perhutani di Pulau
Jawa merupakan penyempurnaan program-program prosperity
approach, yaitu intensifikasi tumpangsari dan PMDH (Pembangunan
Masyarakat Desa Hutan).
Pada awal perkembangannya oleh Perum Perhutani, kegiatan
social forestry meliputi kegiatan di dalam kawasan hutan yaitu
pengembangan agroforestry dan di luar kawasan hutan yaitu
kegiatan pengembangan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan berbagai
usaha produktif seperti perdagangan, industri rumah tangga dan
peternakan. Pengembangan agroforestry merupakan pengembangan
pola-pola tanam yang lebih intensif sehingga masyarakat bisa
memperoleh manfaat lebih besar. Upaya yang dilakukan antara lain
dengan melebarkan jarak tanam dan mengembangkan tanaman
buah-buahan tahunan seperti srikaya, mangga, jambu dan alpokat di
samping tanaman pangan yang sudah biasa ditanam dalam program
tumpangsari. KTH dibangun untuk meningkatkan komunikasi timbal
balik antara petani dan Perum Perhutani sehingga dicapai persamaan
persepsi dan hubungan yang lebih harmonis. Sementara itu
pengembangan usaha produktif di luar kawasan hutan merupakan
kelanjutan dari program PMDH. Implementasi program ini antara lain
dalam bentuk pembinaan USKOP (Usaha Kecil dan Koperasi).
Kiat untuk membumikan konsep social forestry salah satunya
dengan strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasiskan
Masyarakat (PSDABM) yang spesifik berdasarkan pada karakteristik
sosial, ekonomi, budaya dan kondisi biofisik wilayahnya. Cara yang
harus dipikirkan ke depan adalah mewujudkan konsep manajemen
social forestry sampai tingkat pengelolaan terkecil. Beberapa alasan
untuk mendukung model unit manajemen social forestry adalah:
1. Kawasan hutan harus segera ditata secara profesional.
2. Masyarakat membutuhkan kerjasama dengan pemerintah.
3. Lahan kosong dan kritis di Indonesia cukup luas.
4. Manajemen sebagai alat untuk mencapai tujuan sangat
diperlukan.

21
5. Dalam kerangka manajemen social forestry, semua permasalahan
secara bertahap diselesaikan.
6. Banyak kawasan hutan berbatasan langsung dengan pemukiman
penduduk dan terjadi konflik akses pemanfaatan SDH dengan
masyarakat sekitar.
Tindak lanjut dari konsep ini adalah terbitnya Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2004 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar
Hutan dalam Rangka Social Forestry, yang ditetapkan pada tanggal
12 Juli 2004. Social forestry menjadi salah satu kebijakan
Departemen Kehutanan dalam rangka pengelolaan hutan lestari, dan
telah dicanangkan oleh Presiden RI sebagai program nasional pada
tanggal 2 Juli 2003 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Social
forestry dimaksudkan untuk mewujudkan kelestarian SDH dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat setempat, baik yang berada di dalam maupun di sekitar
hutan.
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pemberdayaan
masyarakat setempat adalah upaya-upaya yang ditempuh dalam
rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat. Sedangkan masyarakat setempat adalah masyarakat
yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang merupakan
kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata pencaharian yang
tergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta
pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah
kelembagaan. Dengan adanya peraturan ini peran serta masyarakat
dalam pengelolaan hutan semakin jelas. Seperti tercantum dalam
pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan bahwa social forestry adalah
sistem pengelolaan SDH pada kawasan hutan negara dan atau hutan
hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat
sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.
Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat dengan
memperhatikan prinsip-prinsip manfaat dan lestari, swadaya,
kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap,
berkelanjutan, spesifik lokal dan adaptif. Namun, penyelenggaraan
social forestry dibatasi oleh rambu-rambu, yaitu tidak mengubah

22
status dan fungsi kawasan hutan; tidak memberikan hak kepemilikan
atas kawasan hutan, kecuali hak pemanfaatan SDA; dan tidak parsial,
artinya pengelolaan hutan dilaksanakan secara utuh
(comprehensive/integral).
Sebagai program nasional, dalam peraturan disebutkan
beberapa pihak terkait yang berperan yaitu pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi non
pemerintah/LSM/NGO, badan usaha, perguruan tinggi, kelembagaan
masyarakat, dan lembaga internasional. Keterlibatan semua pihak
dimaksudkan untuk mensinergikan peran berbagai pihak terkait
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka
pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
B. Beberapa Praktik Social Forestry di Sulawesi
1. Hutan Kemasyarakatan
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa,
social forestry dapat dilaksanakan, baik pada kawasan hutan negara
maupun pada kawasan hutan hak. Pada kawasan hutan negara dapat
dilakukan dalam bentuk pengembangan Hutan Kemasyarakatan
(HKm). Pengembangan HKm di Sulawesi, khususnya di Sulawesi
Selatan antara lain terdapat di Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale,
Kabupaten Bulukumba, dan di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana,
Kabupaten Maros. Selain itu, juga dapat dijumpai di Desa Ambololi,
Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi
Tenggara.
Kegiatan HKm di Desa Anrang, Kabupaten Bulukumba
dilaksanakan pada tahun 2002 dalam bentuk pilot project
pembangunan HKm atas dukungan dana dari DFID (Department for
International Development). Pengembangan HKm di Desa Anrang
dituangkan melalui rancangan Peraturaan Daerah Kabupaten
Bulukumba No. 35 tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan. Rancangan ini telah disahkan menjadi ketetapan
peraturan daerah pada akhir Desember 2003.
Areal HKm Anrang merupakan kawasan hutan produksi
dengan luas 675 ha dan melintasi beberapa wilayah desa, seperti
Desa Anrang, Desa Bonto Manai, Desa Bulo Lohe, dan Desa Bukit

23
Harapan. Kegiatan HKm ini bertujuan untuk merehabilitasi kawasan
hutan dengan melibatkan peladang yang telah berada di dalam
kawasan hutan tersebut (Wakka et al., 2004).
HKm di Desa Anrang menerapkan pola agroforestry yang
menggabungkan jenis tanaman kehutanan dengan tanaman
pertanian dan perkebunan. Beberapa komoditas kehutanan sebagai
tanaman penghasil kayu dan MPTS (multi-purpose tree species) yang
dikembangkan, antara lain: sengon, jati, pulai, mahoni, rambutan,
kemiri, durian, petai, dan mangga. Adapun komoditas perkebunan
yang dikembangkan, antara lain: kakao, kopi, lada, cengkih, jambu
mete, dan vanili. Komoditas yang dikembangkan pada areal HKm
Anrang merupakan pilihan masyarakat sendiri. Dinas Kehutanan
Bulukumba berperan sebagai fasilitator yang mengupayakan
pengadaan bibit bersama masyarakat.
Meskipun areal HKm di Desa Anrang merupakan kawasan
hutan produksi, akan tetapi hasil hutan berupa kayu belum dapat
dinikmati masyarakat peserta HKm. Hal ini disebabkan karena belum
adanya mekanisme dan pengaturan pemanfaatan hasil hutan kayu di
areal HKm. Beberapa komoditas yang dikembangkan masyarakat
pada areal HKm di Desa Anrang yang sudah dinikmati masyarakat,
antara lain: kemiri, kakao, lada, cengkih, dan jambu mete.
Pendapatan yang diperoleh masyarakat dari areal HKm di Desa
Anrang berkisar Rp. 6,5-17 juta/tahun/KK (Wakka et al., 2004).
Jumlah kepala keluarga yang terlibat dalam kegiatan HKm di
Desa Anrang sebanyak 134 kepala keluarga. Kepala keluarga yang
terlibat dalam kegiatan HKm terhimpun dalam suatu kelompok tani
hutan (KTH) “Mattaro Deceng”. Aturan main KTH “Mattaro Deceng”
tertuang dalam aturan tertulis internal KT-HKm Mattaro Deceng
meliputi: nama kelompok tani, keanggotaan, hak dan kewajiban
anggota, kepengurusan, tugas dan fungsi pengurus, status lahan
kegiatan HKm dan sanksi-sanksi. LSM lokal berperan sebagai
pendamping dalam pelaksanaan kegiatan HKm.
Berbeda dengan HKm di Desa Anrang, Kabupaten Bulukumba
yang bekerja di hutan produksi, pembangunan HKm di Desa Labuaja,
Kabupaten Maros bekerja di hutan lindung. Hal tersebut
dilatarbelakangi oleh adanya pembukaan hutan lindung oleh
masyarakat setempat menjadi ladang. Melalui program reboisasi dan

24
pengembangan HKm yang dilakukan oleh BPDAS Jeneberang
Walanae, areal hutan yang ada di Desa Labauja kemudian ditetapkan
sebagai areal HKm pada tahun 1999.
Luas areal HKm di Desa Labuja mencapai 500 ha dengan
tanaman pokok gmelina. Dalam areal HKm Labuaja juga terdapat
tegakan kemiri yang telah dikembangkan oleh masyarakat sejak
tahun 1970-1980-an. Tanaman gmelina ditanam, baik pada areal
kosong maupun di sela-sela tanaman kemiri yang telah ada.
Semua bibit tanaman yang dikembangkan di areal HKm
Labuaja merupakan bantuan dari BP DAS Jeneberang Walanae.
Pemilihan jenis tanaman sangat tergantung dari pemberi bibit, dalam
hal ini BPDAS Jeneberang Walanae. Hal ini menandakan bahwa
petani tidak mempunyai otoritas/wewenang untuk menanam sesuai
dengan keinginannya. Hal ini berdampak pada kondisi tanaman
setelah kegiatan penanaman dimana kegiatan pemeliharaan tanaman
jarang dilakukan, sehingga tumbuhan bawah berupa semak belukar
cukup rapat dan mencapai tinggi 1 meter (Wakka et al., 2004).
Areal HKm di Desa Labuaja dikelola oleh 5 kelompok tani
dengan total anggota 190 orang dibentuk pada tahun 1999 dengan
luas lahan garapan yang beragam, yaitu: Kelompok Tani Biesu Daeng
(87 ha), Kelompok Tani Pattiro Bulu (95 ha), Kelompok Tani Bulu
Tanete (135 ha), Kelompok Bukit Harapan (92 ha), Kelompok
Madauseng (91 ha).
Pengembangan kelompok tani dilakukan melalui
pelatihan/kursus pengelolaan HKm dan hutan rakyat dari instansi
terkait, yaitu BP DAS Jeneberang Walanae dan Dinas Kehutanan
Maros. Pada awal proyek HKm berjalan, pertemuan rutin kelompok
tani dilaksanakan dua kali dalam sebulan yang membahas masalah-
masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan HKm. Struktur
organisasi serta aturan internal kelompok tani pengelola HKM di Desa
Labuaja sudah bersifat tertulis. Namun, tata hubungan antara
pengurus dan anggota kurang berfungsi, karena kesibukan dalam
mengurus lahan sawah masing-masing. Anggota kelompok tani
merupakan masyarakat sekitar yang masuk secara aktif dengan
melakukan pendaftaran.
Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 2004 sebagian
kawasan hutan di Kabupaten Maros berubah fungsi menjadi Taman

25
Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul). Sebagian areal HKm
di Desa Labuaja seluas kurang lebih 250 ha ikut berubah fungsi
menjadi TN Babul. Kondisi ini memicu konflik antara masyarakat
penggarap lahan HKm dengan pengelola TN Babul. Pada satu sisi,
masyarakat berharap masih dapat menggarap areal eks HKm
tersebut sesuai dengan aturan-aturan HKm yang berlaku, contohnya
masyarakat dapat memanfaatkan dan memungut HHK dan HHBK.
Pada sisi lain aturan taman nasional cukup ketat khususnya dalam
pemanfaatan hasil hutan kayu (Wakka et al., 2013).
Keinginan masyarakat untuk mengelola areal eks HKm di Desa
Labuaja berusaha diakomodir oleh pengelola TN Babul dengan
menjadikannya zona tradisional TN Babul. Upaya selanjutnya adalah
dengan membuat kesepakatan bersama (MoU/Memorandum of
Understanding) antara Balai TN Babul dengan masyarakat di Desa
Labuaja untuk melakukan kegiatan reboisasi pengayaan zona
tradisional. Upaya-upaya yang dilakukan pengelola TN Babul belum
seluruhnya dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Hal ini
disebabkan belum jelasnya aturan main dalam zona tradisional
tersebut. Demikian halnya dengan mekanisme pemanfaatan dan
pemungutan hasil hutan kayu dari kegiatan reboisasi pengayaan zona
tradisional di Desa Labuaja (Wakka et al., 2012; Wakka et al., 2013).
Di Desa Ambololi Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi
Tenggara dijumpai praktik Social Forestry berupa Hutan
Kemasyarakatan (HKm) yang pada mulanya merupakan areal
perladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan
sejak tahun 1980-an. Aktivitas perladangan berpindah tersebut
dikhawatirkan dapat merusak kondisi hutan yang ada, sehingga pada
tahun 1998 areal tersebut dipilih menjadi salah satu lokasi
pembangunan HKm yang dikelola oleh PT Inhutani I. Jenis tanaman
yang dikembangkan pada saat itu adalah jati.
Pembangunan HKm di Desa Ambololi tersebut kurang mendapat
sambutan dari masyarakat, karena kurangnya sosialisasi oleh pihak
PT. Inhutani I. Hal ini berakibat pada keengganan masyarakat untuk
memelihara tanaman jati yang telah ditanam. Di samping itu,
masyarakat juga merasa manfaat yang diterima dari kegiatan HKm
sangat kecil, karena jenis tanaman yang dikembangkan terbatas pada

26
jenis tanaman kayu-kayuan, yakni jati, yang belum tentu dapat
dinikmati hasilnya oleh masyarakat.
Pada tahun 1999 pengelolaan areal HKm di Desa Ambololi
beralih kepada BP DAS Sampara. Belajar dari kegagalan sebelumnya,
BP DAS Sampara mengubah bentuk pendekatan kepada masyarakat,
yaitu dengan melibatkan aparat desa. Pendekatan tersebut ternyata
cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai
dari kegiatan penanaman sampai pada pemeliharaan.
Jenis tanaman yang dikembangkan pada areal HKm di Desa
Ambololi juga bervariasi, seperti gmelina, sengon, padi ladang,
jagung, kakao, lada, dan mete. Pemilihan jenis-jenis tanaman
tersebut merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat dengan
pihak BPDAS Sampara. Pola tanaman pada areal HKm menerapkan
sistem agroforestry. Dengan sistem tersebut, hasil yang diperoleh
akan berkesinambungan dan tidak bergantung pada satu jenis saja.
Tanaman kehutanan dengan daur 8 - 15 tahun, merupakan hasil
jangka panjang bagi masyarakat.
Untuk mendapatkan penghasilan tambahan selama menunggu
hasil dari tanaman kehutanan, masyarakat menanam tanaman
semusim dan tanaman tahunan. Pada tahun pertama dapat diperoleh
hasil dari tanaman semusim. Untuk tahun kedua dan ketiga, selain
hasil dari tanaman semusim, tanaman tahunan juga sudah mulai
berbuah. Hasil dari tanaman semusim umumnya untuk dikonsumsi
sendiri, sedangkan hasil dari tanaman tahunan umumnya dijual ke
pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila melihat jenis
tanaman yang diusahakan dan pola tanam yang diterapkan di lokasi
HKm serta harapan-harapan masyarakat terhadap hasil yang akan
diperoleh di masa datang, jelas terlihat bahwa orientasi pengelolaan
HKm di Desa Ambololi adalah untuk tujuan komersil.
2. Hutan Desa
Hutan desa merupakan program pengelolaan hutan negara
melalui pemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan
sumberdaya hutan melalui lembaga desa yang diatur dalam
Permenhut No P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Program
tersebut mengatur sistem tenure formal masyarakat dalam mengelola
sumberdaya hutan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan

27
masyarakat. Pemberian hak kelola kepada lembaga desa tersebut
merupakan wujud otonomi desa dalam mengelola sumberdaya hutan
yang mencakup seluruh aspek pengelolaan hutan berdasarkan UU
No.41/1999 tentang Kehutanan, yang mencakup: a) tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan, c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
d. perlindungan hutan dan konservasi alam.
Program Hutan Desa Kabupaten Bantaeng merupakan yang
pertama kali menerima persetujuan dari pemerintah pusat
berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan No.55/Menhut-
II/2010 Tanggal 21 Januari Tahun 2010. Luasan hutan desa tersebut
mencapai 704 ha dengan fungsi hutan lindung yang secara
administratif termasuk mencakup wilayah Desa labbo, Desa
Pattaneteang, dan Kelurahan Cappaga. Pelaksanaan program hutan
desa tersebut selain melibatkan pemerintah, juga melibatkan
perguruan tinggi, yaitu Universitas Hasanuddin dan RECOFTC
(Regional Community Forestry Training Centre for Asia and Pacific)
yang merupakan organisasi nirlaba internasional yang memiliki
kekhususan pada peningkatan kapasitas kehutanan masyarakat dan
pengelolaan hutan di Kawasan Asia-Pasifik.
Kapasitas masyarakat yang ditunjukkan oleh tingkat
pendidikannya pada wilayah Hutan Desa di Bantaeng masih tergolong
rendah, karena 50% - 60% berpendidikan SD atau tidak pernah
sekolah (Nurhaedah et al., 2012). Bahkan, masyarakat di Hutan Desa
Pattaneteang lebih dari 90% berpendidikan rendah. Tingkat usia
produktif mencapai 75% - 90% di Desa Labbo dan Kelurahan
Campaga. Sedangkan jumlah tanggungan keluarga berkisar 3 - 5
orang/KK serta terdapat banyak anggota keluarga dalam satu rumah.
Luas kepemilikan lahan berkisar 0,25-2 Ha, dengan matapencaharian
utama sebagai petani. Selain sebagai petani, beberapa masyarakat
bekerja sebagai tukang ojek, kuli bangunan dan lain-lain untuk
mencukupi kebutuhannya (BPDAS Jeneberang Walanae, 2010).
Program pembangunan hutan desa Kabupaten Bantaeng
merupakan salah satu bentuk devolusi pengelolaan hutan, yaitu
pelimpahan kewenangan pemerintah kepada masyarakat desa untuk
mengelola sumberdaya hutan. Hal ini dapat dilihat pada sebagian
areal kerja hutan desa yang telah dikelola oleh masyarakat sebagai

28
areal tanaman agroforestry kopi, pemungutan hasil hutan madu dan
pengembangan tanaman markisa. Petani yang beraktivitas pada areal
kerja hutan desa sebanyak 134 KK dengan luas lahan kelola berkisar
0,033-1,98 ha untuk setiap rumah tangga petani (Supratman dan
Alif, 2010). Selanjutnya dinyatakan bahwa pendapatan rata-rata
masyarakat per tahun dari pengelolaan hutan desa bervariasi pada
setiap desa bergantung kepada potensi masing-masing wilayah.
Agroforestry kopi dan pemungutan hasil hutan rotan dan banga
merupakan potensi hutan Desa Labbo, namun ke depan memiliki
prospek pengembangan markisa, madu dan tanaman hias. Hutan
Desa Pattaneteang lebih diarahkan pada usaha pengembangan hasil
hutan non kayu, seperti: jasa air, budidaya markisa organik, kopi
organik, lebah madu, rotan dan tanaman hias. Sedangkan untuk
hutan desa di Kelurahan Campaga yang memiliki potensi air yang
strategis, maka pengelolaan lebih diarahkan pada pengembangan
objek wisata. Pengembangan fasilitas pendukung rekreasi dapat
dilakukan pada lahan milik masyarakat di sekitar kawasan. Selain itu,
kondisi alam yang ada memungkinkan untuk pengembangan
agrowisata dari jenis buah-buahan dan hortikultura (BPDAS
Jeneberang Walanae, 2010).
Pengembangan Hutan Desa di Bantaeng didukung oleh
pembangunan kelembagaan, baik lokal secara mandiri maupun
melalui kerjasama dengan lembaga lainnya. Adapun untuk
koordinasi di tingkat kabupaten, dibentuk Forum Rembug Hutan Desa
yang anggotanya meliputi pemegang izin kelola hutan, lembaga
lingkungan dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tingkat
kabupaten.
Keberadaan Hutan Desa memberikan manfaat bagi
masyarakat sekitarnya, sebagaimana dikemukakan Widianto et al.
(2012), antara lain: masyarakat dengan hak kelola hutan merasa
aman beraktivitas dalam kawasan; potensi hasil hutan bukan kayu
dapat dikelola dengan baik, termasuk berkembangnya usaha
peternakan lebah, buah-buahan dan hasil tanaman semusim seperti
kopi, kakao; terbentuknya kelompok pengelola lebah madu,
pengelolaan jasa lingkungan air minum perpipaan yang bersumber
dari Hutan Desa; terbentuknya kelompok pengelola Hutan Desa;
pengelolaan potensi kawasan hutan menjadi terencana dan

29
terkoordinasi; dan penebangan pohon secara ilegal dan kebakaran di
hutan semakin menurun.
3. Hutan Tanaman Rakyat
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebagaimana disebutkan
dalam PP No. 6 Tahun 2007 adalah hutan tanaman pada hutan
produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan
menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian
sumberdaya hutan. Salah satu wilayah di Indonesia yang
melaksanakan program pencadangan areal HTR adalah Provinsi
Sulawesi Tenggara dengan luasan 51.610 ha, yang tersebar pada 3
kabupaten yaitu: Konawe Selatan (9.835 ha), Kolaka (24.735 ha),
dan Buton Utara (17.040 ha), berdasarkan keputusan Menteri
Kehutanan tahun 2008 dan 2009.
Dalam perkembangan perizinannya, Kabupaten Konawe
Selatan yang lebih dahulu terbit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK-HTR)-nya, atas nama KHJL (Koperasi Hutan Jaya
Lestari) berdasarkan SK No. 1353 Tahun 2009 tanggal 10 Juni 2009
seluas 4.639,95 ha. Usaha dari pihak KHJl bersama LSM Jaringan
untuk Hutan (JAUH) dan Tropical Forest Trust (TFT) untuk
menginisisasi pengelolaan HTR di Kabupaten Konawe Selatan tidak
terpisahkan dengan sejarah program Social Forestry. Dalam surat
Menteri Kehutanan Nomor S.405/Menhut-VII/2004 tanggal 5 Oktober
2004 ditetapkan areal seluas 38.959 Ha sebagai pencadangan Areal
Kerja Social Forestry. Namun, program tersebut tidak dapat berjalan
sesuai rencana karena tidak ada landasan hukum. Dalam PP No.06
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, tidak dikenal
terminologi Social Forestry, dan yang ada hanyalah Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Desa.
Program HTR di Konawe Selatan melibatkan anggota
sebanyak 1.352 KK, tersebar pada 39 Desa pada 8 Kecamatan.
Konsep HTR di Konawe Selatan, sebagaimana dikemukakan Mangki
(2011) merupakan hutan tanaman campuran beda daur, yaitu hutan
tanaman yang jenis tanaman pokoknya terdiri berbagai jenis pohon,
dimana antara satu dan lainnya beda masa daurnya. Jenis tanaman

30
pokok kehutanan yang ditanam pada areal efektif terdiri dari: a. jati
meliputi 40% dari total tanaman dengan daur 16 tahun (panen tahun
ke 17); b. mahoni meliputi 20% dari total tanaman dengan daur 16
tahun (panen tahun ke 17); c. sengon meliputi 20% dari total
tanaman dengan daur 8 tahun (panen tahun ke 9); dan d. gmelina
meliputi 20% dari total tanaman dengan daur 8 tahun (panen tahun
ke 9).
Menurut Hakim (2009) kelembagaan HTR secara garis besar
terdiri dari kelembagaan inti (organisasi petani) dan kelembagaan
penunjang meliputi: penyuluh, LSM, dan aparat. Sedangkan
mekanisme hubungan kelembagaan HTR di Konawe Selatan (Mangki
et al., 2011) adalah sebagai berikut:
a. Ketua kelompok atau unit adalah perwakilan KHJL di tingkat desa
yang bertugas menjalankan tugas KHJL di tingkat Desa/Kelompok.
Wilayah kerja KHJL tersebar di beberapa kecamatan.
b. Ketua kelompok/unit masuk dalam struktur pengurus KHJL. Ketua
kelompok/unit akan mendapatkan hak yang sama dengan
pengurus KHJL.
c. Hubungan kerja antara KHJL dan kelompok unit akan dibantu oleh
Forum Kecamatan (FK) dan Lembaga Komunikasi Antar Kelompok
(LKAK).
d. Struktur kelompok atau unit minimal terdiri dari ketua, sekretaris
dan bendahara.
e. Diperlukan aturan yang mengatur tentang ahli waris, mengingat
jenis tanaman yang akan dikembangkan adalah jenis tanaman
kayu umur panjang, sementara umur rata-rata anggota adalah 40-
an tahun.
Sumber pendanaan HTR adalah Badan Layanan Umum Dephut
melalui Bank pembangunan Daerah (BPD) dengan bunga pertahun
diperkirakan sebesar 8% dan grass period 8 tahun. Skema
penggunaan dana adalah 70% untuk tanaman utama HTR dan 30%
untuk tanaman jangka pendek dan tanaman sela. Sedangkan standar
biaya yang dapat diakses oleh masyarakat kurang lebih Rp
6.410.000,- per hektare.

31
4. Perhutanan Sosial (Social Forestry)
Program Social Forestry dikembangkan oleh Departemen
Kehutanan melalui kegiatan pada masing-masing eselon sampai ke
tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Badan Litbang
Kehutanan dengan judul besar “Kajian Teknologi dan Kelembagaan
Social Forestry “. Selanjutnya masing-masing UPT melaksanakannya
dengan pendekatan spesifik lokal. Sebagai contoh adalah Kajian
Teknologi dan Kelembagaan Social Forestry di KHDTK Borisallo yang
dikerjakan oleh Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Makassar yang
dimulai pada tahun 2003.
KHDTK Borisallo dengan luas mencapai 180 ha terletak di
Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa,
kurang lebih 25 km dari Kota Makassar. Tanaman yang ada di
KHDTK Borisallo terdiri dari tanaman kehutanan, perkebunan, dan
pertanian. Jenis tanaman kehutanan yang dominan, antara lain:
Eucalyptus sp., Acacia mangium, Gmelina arborea, Swetenia
mahagoni, Vitex sp., Diospyros celebica Bakh dan Tectona. grandis.
Untuk tanaman perkebunan yang diusahakan, antara lain: pisang,
mangga, kopi, pepaya, nangka, rambutan, kakao, mete dan
langsat. Sedangkan tanaman pertanian, antara lain: jagung, padi
dan kacang-kacangan. Letaknya yang tidak lebih dari 300 meter
dari sisi jalan Poros Makassar–Malino dan Bendungan Bili-bili dan
berdekatan dan berbatasan langsung dengan lahan garapan dan
pemukiman penduduk menyebabkan KHDTK Borisallo bersifat ”open
access area”. Demikian pula, sarana sosial, pendidikan, kesehatan,
dan agama pada tingkat kelurahan relatif dekat dengan KHDTK
(Wakka et al., 2004).
Pada mulanya KHDTK Borisallo merupakan Stasiun
Penelitian Uji Coba (SPUC) berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan No. 275/Kpts-II/1994. Dalam perkembangannya, SPUC
Borisallo kemudian berubah menjadi KHDTK berdasarkan SK
Menteri Kehutanan No. 367/Menhut-II/2004. Kegiatan social
forestry dilaksanakan secara tradisional, dengan jumlah KK yang
terlibat 83 KK dan terdapat kurang lebih 207 lahan garapan/kapling.
Pola tanam dengan menggunakan campuran antara tanaman
pertanian, perkebunan dan kehutanan atau yang biasa disebut

32
dengan pola agroforestry. Kelembagaan yang ada antara lain KUD,
LKMD, Lembaga Kredit dan empat Kelompok Tani Hutan (KTH),
yaitu: KTH Bontoparang, KTH Pu’Rumbo, KTH Batu Sompoa dan
KTH Bonto Ala, serta tradisi musyawarah “Abbulo Sibatang” (Wakka
et al., 2004).
Penggunaan lahan KHDTK Borisallo oleh masyarakat
sekitarnya untuk berkebun sudah berlangsung lama, sebagai
kegiatan sampingan selain bersawah tadah hujan. Bagi masyarakat
setempat, lahan adalah anugerah Tuhan (Karaeng Allah Ta’ala)
yang merupakan tempat atau sumber mencari penghidupan (a’boya
katallassang). Namun, lahan hutan yang digarap saat ini tetap
diakui sebagai milik pemerintah, yang dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat setempat (Bisjoe, 2005). Selanjutnya dinyatakan bahwa
akibat penggunaan lahan yang sudah berlangsung lama, maka telah
terjadi pula pembagian dan penunjukan lahan garapan di antara
masyarakat berdasarkan pertimbangan kekerabatan (bija), baik
kekerabatan darah (bija pammanakang) maupun perkawinan (bija
pa’renrengang) dalam musyawarah (abbulo sibatang).
Penggunaan lahan pada KHDTK Borisallo oleh masyarakat
setempat, telah memberikan sumbangan bagi tetap terpeliharanya
tanaman hutan. Sekalipun demikian terdapat dua bentuk
penggunaan lahan pada kawasan tersebut, yaitu: lahan dipagari
tanpa digarap dan lahan digarap dengan berbagai penggunaan.
Pada faktanya, terdapat kontradiksi antara pengakuan masyarakat
bahwa lahan garapannya adalah milik negara, dengan praktik yang
dijumpai, yang menyiratkan lahan garapannya sebagai milik pribadi,
seperti pewarisan lahan garapan, jual-beli kebun, sertifikasi lahan,
dan upaya ganti rugi lahan (Bisjoe, 2005). Oleh karena itu,
pengembangan program Social Forestry diharapkan berdampak
positif bagi penggunaan lahan secara legal dan formal oleh
masyarakat sekitar KHDTK.
Sebagian besar (96%) penggarap lahan di KHDTK Borisallo
mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani. Dengan rata-
rata penguasaan lahan ± 0,64 ha/KK, kegiatan di lahan KHDTK
dapat memberikan kontribusi pada pendapatan masyarakat rata-
rata sebesar 43% dari total pendapatan bruto. Pendapatan

33
selebihnya diperoleh dari usaha atas lahan garapan milik sendiri dan
pendapatan dari bekerja sebagai buruh.
Dalam rangka pengembangan program Social Forestry di
KHDTK Borisallo, tahapan awal yang dilakukan adalah penyiapan
dan pengembangan prakondisi masyarakat. Hal ini bertujuan
menciptakan masyarakat yang kuat dengan pengetahuan dan
keterampilan teknis dan managerial dalam suatu wadah atau
kelompok (lembaga) yang kuat serta memperoleh legitimasi dari
pemerintah dan masyarakat sendiri. Proses penetapan kelembagaan
di KHDTK Borisallo berlangsung cukup lama dari tahap perencanaan
sampai pelaksanaan di lapangan. Prosesnya mulai dari survei
lapangan, koordinasi dan sosialisasi, pertemuan pleno dan diskusi
kelompok serta workshop dengan semua stakeholder yang terkait
untuk membahas dan mencari solusinya.
Dengan adanya program social forestry, peran serta
masyarakat dalam pengelolaan hutan semakin jelas, yaitu dengan
memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku
dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan. Namun,
penyelenggaraannya dibatasi oleh rambu-rambu, yaitu tidak
mengubah status dan fungsi kawasan hutan, tidak memberikan hak
kepemilikan atas kawasan hutan, kecuali hak pemanfaatan
sumberdaya alam. Pada workshop nasional KHDTK tahun 2012
yang dilaksanakan di Makassar, yang dilanjutkan dengan kunjungan
lapang (fieldtrip) ke KHDTK Borisallo, Sekretaris Badan Litbang
menyatakan dukungan terhadap program Social Forestry bersama
masyarakat dalam pengelolaan KHDTK.
Pengembangan Social Forestry juga dijumpai di Sulawesi
Tenggara, yaitu di Kabupaten Konawe Selatan dan di Kabupaten
Buton. Pengembangan Social Forestry di Konawe Selatan bermula
dengan pencanangan program tersebut pada Agustus 2003. Visi
Social Forestry ‘hutan lestari, masyarakat sejahtera’ mendapat
dukungan masyarakat dimana dalam pelaksanaannya direncanakan
akan memberikan akses kepada masyarakat sebagai pelaku utama
dalam pengelolaan hutan negara, mulai dari perencanaan sampai
dengan pemanenan. Program tersebut melibatkan masyarakat di 46
desa yang tersebar pada 4 kecamatan, yaitu: Lainea, Kolono,

34
Palangga, dan Andoolo. Kelembagaan dibentuk secara berjenjang
berdasarkan kebutuhan, mulai dari Kelompok tani Social Forestry di
tingkat desa, Forum Social Forestry di tingkat kecamatan, dan
Lembaga Komunikasi Antar Kelompok (LKAK). Lembaga yang
berperan sebagai perwakilan kelompok tani dari 46 desa dengan
total anggota 8.254 kepala keluarga tersebut, selanjutnya
melakukan serangkaian diskusi terkait rencana teknis Social
Forestry, khususnya dalam beberapa kali kunjungan Tim Pokja
Social Forestry Departemen Kehutanan ke Sulawesi Tenggara.
Namun, program Social Forestry yang telah dimulai tersebut sempat
terhenti karena tidak memiliki payung hukum yang jelas. Setahun
kemudian, pada Maret 2004 diselenggarakan workshop Social
Forestry di Konawe Selatan yang dihadiri oleh multi pihak.
Workshop tersebut bertujuan, antara lain: merumuskan rencana
teknis Social Forestry yang akan dilaksanakan oleh LKAK dan
membentuk koperasi dengan pertimbangan bahwa lembaga yang
boleh melaksanakan program Social Forestry adalah badan usaha,
seperti koperasi. Setelah melalui serangkaian diskusi multi pihak,
pada tahun itu juga terbentuklah badan usaha yang diberi nama
Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) sebagai wadah kelompok tani
Social Forestry yang sudah dibentuk di 46 desa (Cunu, 2011). Pada
dasarnya, praktik Social Forestry di Konawe Selatan bekerja di lahan
milik masyarakat. Upaya pengelolaan hutan negara oleh masyarakat
setempat dipaparkan secara terpisah pada bagian Hutan Tanaman
Rakyat (HTR).
Praktik pengelolaan hutan dengan upaya melibatkan
masyarakat dijumpai pula di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi
Tenggara, yakni di kawasan hutan Lambusango. Kawasan tersebut
merupakan lokasi Lambusango Forest Conservation Project (LFCP)
atau Proyek Konservasi Hutan Lambusango, dengan luasan
mencapai 65.000 ha. Pelibatan dimaksudkan sebagai pemberian
hak pemanfaatan dan akses kepada masyarakat, yang tinggal
berdekatan dengan hutan, untuk mengelola hutan tanpa dampak
gangguan pada fungsi hutan, yang secara luas diakui sebagai
konsep hutan kemasyarakatan atau social forestry (Social Forestry).
Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, FLCP melibatkan 5 instansi

35
di Buton, yaitu Kehutanan, Pariwisata, Pertanian, Usaha Kecil dan
Menengah, serta Penyuluhan (Purwanto, 2006).
Seperti halnya praktik Social Forestry di Konawe Selatan,
perjalanan panjang program Social Forestry dan dinamika kebijakan
terkait, dirasakan telah mengarah kepada ketidakjelasan prosedur
pengembangan Social Forestry di lapang. Kondisi tersebut
menyebabkan LFCP akhirnya menempatkan pengembangan Social
Forestry sebagai sasaran capaian jangka menengah dan jangka
panjang, sedangkan tindakan segera yang dilakukan berupa
pengembangan usaha desa. Pengembangan usaha tersebut
dirancang sebagai komitmen di tingkat desa untuk menghentikan
kegiatan ilegal di hutan dan sebagai penggantinya adalah adanya
bantuan teknis dan modal dari LFCP untuk mengembangkan usaha
di desa sebagai pendapatan alternatif, bukan sekedar pendapatan
tambahan. Dengan demikian harus ada keterkaitan langsung antara
pendapatan alternatif dan manfaat konservasi (Purwanto, 2006).
Selanjutnya, Purwanto (2006) menyatakan sebagai tahap
awal LFCP memilih desa lokasi kegiatan dan pada setiap desa
terpilih tersebut ditentukan 10-20 kepala keluarga sebagai
pelaksana kegiatan berbantuan modal bergulir. Usaha desa yang
ditentukan LFCP adalah pertanian jahe dan peternakan sapi sebagai
usaha desa. Pertanian jahe dilaksanakan di lima desa, yaitu
Lambusango, Kakenauwe, Lawele, Harapan Jaya dan Wining.
Sedangkan peternakan sapi diujicobakan pada Desa Lasembangi.
Seiring berjalannya waktu, kepercayaan (trust) para pemangku
kepentingan Hutan Lambusango, baik pemerintah maupun
masyarakat lokal terhadap LFCP telah tumbuh, dimana masyarakat
setempat telah mendapatkan manfaat dari hutan sekitarnya,
sementara kelestarian hutan Lambusango tetap terpelihara.
5. Hutan Adat
Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999, hutan adat
didefinisikan sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah adat
yang pengelolaannya diserahkan pada masyarakat hukum adat.
Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 definisi
tersebut diperbaiki menjadi hutan yang berada dalam wilayah

36
masyarakat hukum adat. Terlepas dari perubahan tersebut, pada
hutan adat tentunya dapat dikembangkan program pengelolaan dan
pemanfaatan, sepanjang mendapat persetujuan dari masyarakat adat
yang bersangkutan, termasuk program Social Forestry.
Pada faktanya, masyarakat adat dengan kearifan lokalnya
sudah mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutannya secara
turun-temurun, tanpa perlu menunggu terbitnya beberapa panduan
pengelolaan hutan oleh masyarakat. Jika melihat praktik dan aturan
yang mendasarinya, tentunya pengelolaan hutan adat dapat
dimasukkan sebagai praktik social forestry, bahkan dapat menjadi
model pengelolaan hutan.
Di Sulawesi, pengelolaan hutan adat dapat dijumpai di
Kabupaten Bulukumba yang dikenal sebagai Hutan Adat Kajang.
Hutan adat di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang, berjarak sekitar 60
km dari kota kabupaten dan 200 km arah selatan Kota Makassar.
Masyarakat Tana Toa sejak dahulu memandang hutan sebagai
sumber kehidupan dan sebagai penyangga keseimbangan
lingkungan. Mereka percaya bahwa hutan diciptakan Tuhan Yang
Maha Esa sebagai penyeimbang antara musim hujan dan musim
kemarau. Kawasan hutan adat di Desa Tana Toa seluas 716 ha
menurut ketua adat (Amma Toa), telah dikelola sejak adanya
masyarakat Kajang.
Amma Toa merupakan jabatan pemimpin tertinggi dalam
komunitas Kajang yang dijabat seumur hidup dan tidak diwariskan,
serta dipilih berdasarkan penunjukan secara adat. Dalam struktur
komunitas adat Amma Toa, pengawasan terhadap kawasan hutan
dilakukan oleh petugas yang disebut “Galla” yang berjumlah 4 orang
sesuai dengan 4 kawasan hutan adat, yaitu: Bantalang, Sangkala,
Sapayya, dan Ganta. Selain “Galla” untuk kawasan hutan, terdapat
juga lima orang “Galla” yang bertugas mengurusi masalah adat di
berbagai bidang, yaitu: a) Galla Pantama, bertugas sebagai hakim; b)
Galla Lombo, bertugas pada bidang kehutanan dan pertanian; c) Galla
Malleleng, bertugas pada bidang perikanan; d) Galla Puto, sebagai
juru bicara Amma Toa; dan Galla Angjuru, bertugas mengatur tamu
yang akan menghadap Amma Toa.
Amma Toa memberi tuntunan kepada warganya dalam
mengelola sumberdaya alam hutan melalui penyampaian pesan

37
berupa peringatan. Peringatan atau larangan Amma Toa berkenaan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan tersebut
merupakan aturan yang harus ditaati dan mengandung konsekuensi
terkena sanksi adat apabila dilanggar. Penerapan sanksi adat baik
berupa sanksi materi maupun sanksi sosial berkenaan dengan
pemanfaatan kawasan hutan, masih tetap dipegang teguh oleh
masyarakat adat, sehingga kondisi kawasan hutan di Desa Tana Toa
tetap terjaga. Bentuk sanksi berkaitan dengan pelanggaran aturan
dalam mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan adat, sebagai
berikut:
a. Sanksi materi, merupakan sanksi yang dijatuhkan dalam bentuk
uang senilai 4 - 12 real atau Rp 400.000 - Rp 1.200.000,- sesuai
kadar kesalahannya. Jenis hukuman tersebut diberi istilah cappa
ba’bala untuk hukuman ringan, tangnga ba’bala untuk hukuman
sedang dan pokok ba’bala untuk hukuman berat.
b. Sanksi sosial, merupakan bentuk sanksi yang dijatuhkan bukan
dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk pengucilan yang
dijatuhkan kepada seseorang dengan cara tidak dilibatkan dalam
kegiatan adat atau tidak dianggap lagi sebagai anggota
masyarakat adat.
Kawasan Hutan Adat Tana Toa atau hutan adat ke-Ammatoa-
an (Boronna I Bohe) dibagi ke dalam 3 zona, yaitu : a. Hutan
Keramat (Borong Karama'); b. Hutan Perbatasan (Borong
Battasayya); dan c. Borong Luarayya. Hutan Keramat (Borong
Karama') merupakan zona pertama dari hutan adat yang menurut
pasang, terlarang (kasipalli) untuk dimasuki, ataupun mengganggu
flora dan fauna yang ada di dalamnya. Borong Karama' hanya boleh
dimasuki oleh Ammatoa dan anggota adat apabila ada upacara adat
(upacara pelantikan Ammatoa, Pa'nganroang). Hutan Perbatasan
(Borong Battasayya) merupakan zona kedua dari Borong Karama'.
Antara Borong Karama' dan Borong Battasayya dibatasi oleh jalan
setapak yang digunakan oleh Ammatoa dan anggota adat sebagai
jalan untuk masuk di Borong Karama' untuk upacara ritual komunitas.
Di Borong Battasayya, komunitas Ammatoa diperbolehkan mengambil
kayu dengan syarat-syarat tertentu. Borong Luarayya merupakan
hutan rakyat yang belum dibebani hak milik. Hutan ini terletak di
sekitar kebun masyarakat ke-Ammatoa-an dengan luas ± 100 Ha.

38
Dari hutan inilah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka
terhadap kayu dengan persyaratan yang sama pada pengambilan
kayu di Borong Battasayya. Luas kawasan hutan Tana Toa yang
meliputi Hutan Keramat (Borong Karama') dan Hutan Perbatasan
(Borong Battasayya) menurut hasil tata batas yang dilakukan oleh
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba yaitu 331,17 ha, yang oleh
pemerintah ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas (Dassir,
2008).
Tingkat orientasi produksi yang dilakukan masyarakat adat di
zona kawasan penyangga dan kawasan budidaya atau pemanfaatan
masih bersifat subsisten. Masyarakat menanam padi, jagung dan
palawija atau sayur-sayuran hanya sebatas untuk memenuhi
kebutuhan pangan sehari-hari. Sementara masyarakat yang menanam
tanaman perkebunan berupa kopi, kakao dan jambu mete dengan
hasil yang relatif sedikit memang dipasarkan akan tetapi sebagian
hasil penjualannya ditukar atau dibelanjakan lagi untuk membeli
kebutuhan pokok sehari-hari seperti gula, garam, sabun dan lain-lain.
Hasil produk yang diperjualbelikan hanya kurang lebih sebesar 5 -
10% saja dan selebihnya, yaitu sekitar 90 - 95% bersifat subsisten
atau digunakan sendiri. Rendahnya tingkat orientasi produksi pada
masyarakat Tana Toa dalam mengelola lahan adat diantaranya
disebabkan oleh dua hal utama, yaitu : a. pola hidup sederhana
(kamase-mase) dan b. pola hidup mandiri.
Hasil pengamatan Hijjang (2005) menyebutkan bahwa dalam
hutan adat Tana Toa terdapat beberapa jenis kayu, antara lain:
na’nasa (bitti), kalangngireng ola’ balatung (rambutan), inru’ (nyiur),
raukang (rotan) dan sebagainya. Selain kayu, juga terdapat beberapa
jenis satwa seperti rusa, kera, kuskus, babi dan berbagai jenis
burung. Kayu balangngireng ola’, balatung, dan raukang digunakan
untuk bahan baku rumah, sedangkan kayu na’nasa selain untuk
bahan baku rumah, juga untuk bahan perahu (khususnya perahu
phinisi) oleh nelayan di kawasan Bulukumba.
Bentuk pelatihan, kursus atau penyuluhan berkenan dengan
adopsi teknologi pengelolaan kawasan hutan, tidak pernah
dilaksanakan. Masyarakat adat Kajang tidak mudah menerima
teknologi dari luar, selain apa yang mereka terima secara turun-
temurun dari orang tuanya dan atau perangkat adat.

39
6. Hutan Rakyat
Selain kawasan hutan negara, pengembangan Social Forestry
mencakup pula hutan rakyat. Hutan rakyat termasuk dalam lingkup
hutan milik yang menurut Undang-undang dipahami sebagai hutan
yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Adapun
pengertian hutan rakyat atau hutan hak, sebagaimana disebut dalam
perda salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten
Sidrap adalah hutan alam atau hutan tanaman yang berada di luar
kawasan hutan negara yang telah dibebani hak milik secara sah
sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Catatan tentang pengembangan Social Forestry di daerah tidak
terlepas dari perjalanan pemanfaatan lahan oleh masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya dan sudah lama berlangsung.
Sebagai contoh adalah terbentuknya hutan agroforestry kopi
masyarakat Kulawi di Sulawesi Tengah. Tipe hutan tersebut
terbentuk sebagai akibat intervensi masyarakat melalui perladangan
berpindah. Biasanya peladang berpindah hanya mengolah lahannya
selama setahun, dan setelah itu mencari dan membuka ladang baru.
Lahan yang ditinggalkan akan mengalami perkembangan (suksesi)
dan ladang tersebut menjadi milik umum (tribe). Biasanya di ladang
tersebut ditanami tanaman musiman, seperti jagung dan padi ladang
(Umar, 2002).
Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat dua tipe agroforest,
yaitu bone kopi dan udu. Bone kopi dipraktikkan oleh masyarakat
Kulawi sedangkan udu dipraktikkan oleh masyarakat Besoa, terutama
oleh sub-etnis Kakau (kakau berarti hutan). Biasanya satu keluarga
memiliki satu bone kopi seluas 1 hektare. Sedangkan udu biasanya
relatif lebih sempit, namun terkadang ada yang mencapai satu
hektare. Bone sebenarnya berarti kebun pada masyarakat Kulawi,
untuk bone yang ditanami padi disebut bone pare. Oleh karena
agroforest yang dipraktikkan oleh masyarakat Kulawi adalah bone
yang ditanami kopi, maka agroforest masyarakat Kulawi disebut bone
kopi. Bone kopi merupakan praktik pertanian menetap dimana
pemiliknya memanfaatkan ruang di bawah tajuk hutan sebagai lokasi
tanaman kopi. Pemilik bone pada masyarakat Kulawi juga menanam
pohon-pohon, baik pohon penghasil buah-buahan maupun

40
pepohonan sebagai peneduh dan penyubur tanah. Pohon buah-
buahan yang ditanam adalah langsat, rambutan, durian, kemiri dan
lain sebagainya. Sedangkan sebagai pohon peneduh dan penyubur
tanah, umumnya pemilik kebun menggunakan dadap hutan (Umar,
2002). Selanjutnya dikemukakan Umar (2002) bahwa pemikiran
tentang kebersamaan masyarakat hutan dan pengusaha kehutanan
untuk melakukan pengelolaan hutan merupakan konsep yang positif
karena berorientasi kepada kelestarian hutan dan pengembangan
ekonomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan prinsip Social Forestry,
hutan lestari dan masyarakat sejahtera.
Bone kopi dan udu merupakan agroforest atau traditional
forest garden khas Provinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk dari
kegiatan perladangan berpindah. Hal ini menunjukkan bahwa
hubungan kepemilikan antarlahan (bekas perladangan berpindah)
dengan peladangnya cenderung terpelihara karena mereka akan
kembali mengelola lahan dengan memanfaatkan ruang di bawah
tegakan hutan (Umar, 2002).
Selain berkembang dari pemanfaatan tradisional yang cukup
lama oleh masyarakat setempat, hutan rakyat juga dapat dibangun
sebagai suatu model oleh pemerintah. Sebagai contoh adalah hutan
rakyat di Desa Bungo Nol, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Hutan
rakyat model tersebut dikembangkan oleh pihak BP DAS Bone
Bolango, Gorontalo dengan komoditas jati dan kemiri sebagai
tanaman pokok dan jagung sebagai tanaman campuran, yang
ditanam di lahan rakyat pada tahun 2002. Kawasan hutan rakyat
dengan luasan 25 ha terletak pada lahan satu hamparan dengan
kondisi topografi bergelombang. Pengembangan dan pengelolaan
model hutan rakyat tersebut berdasarkan pertimbangan konservasi
lahan pada lereng bukit yang rawan erosi dan pertimbangan ekonomi
untuk meningkatkan kesejahteraan para petani pemilik/penggarap
lahan di lereng bukit tersebut.
Sebagai suatu program, pengembangan dan pengelolaan
hutan rakyat di Desa Bunga Nol diawali dengan pelatihan petani
peserta program dengan tujuan: (1). menciptakan sumberdaya
manusia sebagai pelaku, pelopor dan motivator; (2). menambah/
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok tani dalam
pengelolaan hutan; dan (3) membentuk kontak dan kelompok-

41
kelompok tani sebagai pelestari sumberdaya alam. Model hutan
rakyat yang dibangun melibatkan 28 orang petani (5% dari jumlah
KK yang ada) yang tergabung dalam kelompok Lembah Lestari
(BPDAS Bone Bolango, 2002).
Praktik social forestry pada hutan rakyat dengan pola
agroforestry dijumpai juga di Desa Bulo Wattang, Kabupaten Sidrap.
Desa ini terletak kira-kira 12 km dari ibukota kabupaten. Kegiatan
pembuatan hutan rakyat dimulai atas inisiatif masyarakat yang
tadinya merupakan lahan ilalang milik negara yang berada di luar
kawasan untuk dikelola, yaitu seluas 300 ha. Sistem pengolahan
lahan (land clearing) yang digunakan masih secara tradisional, yaitu
menggunakan kerbau. Pada awal kegiatan, yaitu di tahun 1978,
lahan tersebut ditanami oleh kelompok tani dengan tanaman
singkong yang dilaksanakan bekerja sama dengan salah satu
perusahaan besar di Sulawesi Selatan untuk kegiatan pembuatan
gaplek (bahan makanan yang diolah dari singkong). Namun, kegiatan
tersebut tidak berjalan lancar karena kurang jelasnya informasi pasar.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, komoditas tanaman
yang diusahakan digantikan dengan jenis tanaman buah-buahan dan
tanaman obat-obatan, seperti jeruk, mangga, kakao, jambu mete,
kelapa, palawija, kunyit, sereh dan beberapa jenis tanaman obat-
obatan lain, di samping tanaman jati. Dari 200 tanaman jeruk yang
ditanam, dapat dihasilkan 12 ton jeruk dalam satu kali panen.
Sedangkan sayur-sayuran seperti kacang panjang, timun, terung-
terungan dan cabe dapat menghasilkan sebesar Rp 400.000/hari
selama masa produksi. Dari hasil produksi tersebut anggota
kelompok tani dapat menabung antara lain untuk menunaikan ibadah
haji. Namun, dalam aspek pemasaran terdapat kendala diantaranya
adalah dan sarana transportasi untuk mengangkut hasil produksi, di
samping informasi pasar.
Seiring dengan perubahan waktu, kelompok tani mulai
mengenal tanaman gmelina (Gmelina arborea) dan melalui program
Kebun Bibit Desa (KBD) ditanam gmelina sebanyak 60.000 bibit pada
areal seluas 5 ha. Gmelina menjadi tanaman utama pada hutan
rakyat di Desa Bulo Wattang yang dikelola dengan pola agroforestry.
Pada sela-sela tanaman utama ditanami dengan tanaman
perkebunan, seperti kakao, jambu mete, dan jeruk, serta tanaman

42
semusim seperti kacang panjang. Jenis-jenis tanaman yang
diusahakan merupakan bantuan dari BPDAS Jeneberang Walanae
sebagai bagian dari Program Pengembangan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan. Tegakan gmelina berdaur delapan tahun tersebut dikelola
dengan orientasi komersial untuk keperluan pembuatan kertas dan
kayu lapis (BPDAS Jenneberang Walanae, 2010).
Dengan pola agroforestry tersebut diharapkan kegiatan pada
hutan rakyat dapat menopang pendapatan selain dari sektor
kehutanan. Hal ini disebabkan tanaman kehutanan memiliki daur
produksi yang cukup lama, yaitu berkisar 8 – 15 tahun dan petani
dapat memanfaatkannya sebagai tabungan jangka panjang.
Sementara itu, untuk mendapatkan penghasilan lain selama
menunggu hasil dari tanaman kehutanan, masyarakat menanam
tanaman semusim dan tanaman tahunan. Pada tahun pertama
mereka memeroleh hasil dari tanaman semusim, sedangkan untuk
tahun kedua dan ketiga selain hasil yang diperoleh dari tanaman
semusim, tanaman tahunan juga sudah mulai berbuah dan dapat
menambah pendapatan masyarakat. Tetapi tanaman lain di bawah
tegakan gmelina di Desa Bulo Wattang ini memperlihatkan
kecenderungan mempengaruhi hasil yang diperoleh. Hal ini terlihat
dari indikasi penurunan hasil sesudah ditanami tanaman gmelina,
misalnya: adanya penurunan hasil panen kakao dan jambu mete,
bahkan tanaman jeruk yang pada mulanya merupakan sumber
penghasilan utama masyarakat, menjadi tidak produktif lagi.
Jumlah keluarga yang terlibat dalam kegiatan hutan rakyat
gmelina sebanyak 30 KK atau 10% dari jumlah KK yang tergabung
dalam kelompok tani “Mase-mase” yang dibentuk pada tahun 1980.
Kegiatan pertemuan resmi untuk membahas hutan rakyat dilakukan
dua kali seminggu. Hasil pemanenan dari kawasan hutan rakyat
langsung dijual dan seluruh hasilnya untuk masyarakat, tanpa ada
ketentuan untuk dimasukkan ke kas desa. Pada setiap pertemuan
rutin yang dilaksanakan seminggu sekali yakni setiap hari Jumat,
semua anggota kelompok diwajibkan membayar iuran sebesar
Rp.2.500/bulan untuk keperluan sosial kelompok.
Hutan rakyat di Kabupaten Sidrap diatur dalam Perda No. 3
Tahun 2003 tentang Izin Pengelolaan/Pemanfaataan Hutan Rakyat.
Semua aturan yang ada, baik peraturan tertulis maupun tidak

43
tertulis mendukung pelaksanaan hutan rakyat di Kabupaten Sidrap.
Sedangkan Program Pengembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang kehutanan
sangat mendukung program penghijauan lahan kritis yang ada di
Kabupaten Sidrap.
Bentuk praktik Social Forestry dapat dibedakan berdasarkan
status lahannya, sekalipun pola dan komoditas yang diusahakan
sama jenisnya, sebagaimana dijumpai di Kabupaten Maros, yaitu
hutan kemiri dalam bentuk hutan kemasyarakatan (HKm) pada
kawasan hutan negara dan hutan kemiri rakyat pada lahan milik.
Kabupaten Maros memiliki hutan kemiri yang terluas di
Sulawesi Selatan, yaitu 9.200 ha dengan produksi 5.608 ton dan
sebagian besar masuk dalam kawasan hutan negara, sehingga
termasuk dalam pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm).
Usaha kemiri rakyat pernah menjadi andalan pada tahun 1970-1980-
an dan menjadi sumber pendapatan utama masyarakat Camba,
Maros.
Luas kepemilikan lahan kemiri di wilayah Camba rata-rata 1,87
ha dimana 54% mempunyai kategori luas lahan 1-2 ha yang
menunjukkan luas kepemilikan lahan yang sangat layak untuk
dikembangkan sebagai sumber pendapatan petani (Yusran, 1999).
Selain didukung oleh kelembagaan lokal yang terkait dengan
pengelolaan kemiri, masih terpelihara pula kebudayaan lokal di
masyarakat. Misalnya dalam pembukaan lahan dikenal istilah
“pakkoko”, yang sama dengan istilah “pesanggem” pada tumpangsari
jati di Jawa. Sedangkan dalam pemungutan hasil dikenal istilah
“makkalice”, yaitu sistem pemungutan hasil yang didasari
kesepakatan antara pemilik dan bukan pemilik.
Permasalahan pada hutan kemiri di Kabupaten Maros adalah
umur pohon. Sebagian besar tegakan kemiri (79%) termasuk dalam
kategori umur tua (tidak produktif), sedangkan 19% merupakan
umur produktif dan sisanya 2% merupakan umur muda. Rata-rata
umur pohon kemiri yang ada adalah sekitar 45 tahun, hal ini
menunjukkan bahwa proses permudaan atau regenerasinya tidak
berlangsung secara berkelanjutan (Yusran, 1999). Hasil pengukuran
potensi tegakan (annual standing stock) menunjukan bahwa terdapat
jumlah pohon sekitar 212/ha pada kelas umur tua, sedangkan pada

44
kelas umur produktif sebesar 324/ha. Keadaan ini menunjukkan
bahwa komposisi tegakan kemiri jauh dari komposisi yang ideal dan
memberikan dampak yang kurang bagus untuk produksi dan
kelestariannya.
Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan potensi dan
prospek pasar yang cukup luas baik di dalam maupun luar negeri.
Pohon ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi baik sebagai bahan
penyedap makanan sampai bahan baku industri dan rumah tangga,
seperti bumbu masak, obat-obatan, perawatan rambut, kecantikan,
bahan baku industri sabun, cat dan lain-lain.
Ketergantungan kepada sumberdaya hutan juga berkaitan
dengan budaya masyarakat sekitarnya, sebagaimana ditunjukkan
pada hutan rakyat “tongkonan” di Kabupaten Tana Toraja.
Masyarakat Tana Toraja sangat peduli dengan kelestarian hutannya,
yang ditunjukkan dengan harus diadakannya upacara adat yang
disebut tomina, sebelum mereka masuk ke hutan untuk memperoleh
kayu guna pembangunan rumah tongkonan. Upacara ini
dimaksudkan untuk memohon izin kepada dewa (dewata) sebelum
mengambil kayu dari hutan sesuai dengan kebutuhannya.
Kebutuhan kayu-kayuan dalam pembuatan rumah tongkonan,
mendorong berkembangnya budaya menanam kayu-kayuan di
pekarangan atau lahan-lahan kosong di sekitar rumah tongkonan.
Biasanya dalam sebuah rumah tongkonan dikelilingi oleh kombong
(hutan rakyat di sekitar tongkonan).
Selain itu ada sistem yang disebut dengan mana’, yaitu harta
warisan yang diturunkan dan dianggap sakral dalam masyarakat
Toraja termasuk emas, keris dan tanda-tanda kerjaaan sebagai
simbol status tongkonan (pemerintahan wilayah adat). Sistem mana’
juga berlaku dalam hal pemilikan lahan yang menjadi menjadi
tanggungjawab tongkonan, yaitu sebidang tanah yang diwariskan
kepada anak cucu.
Jadi, dapat dikatakan bahwa hutan rakyat tongkonan adalah
hutan yang dibangun oleh masyarakat adat Toraja yang terhimpun
dalam satu kekerabatan secara swadaya di tanah tongkonan (tanah
adat). Hutan rakyat tongkonan sebenarnya merupakan pengetahuan
lokal yang terbentuk akibat dorongan untuk mencukupi
kebutuhannya sendiri (subsisten).

45
Jenis tanaman pada hutan rakyat tongkonan adalah hutan
rakyat campuran, yang terdiri atas buangin (Casuarina
junghuhniana), uru (Elmerillia sp.), nyatoh (Palaquium sp.), kalapi
(Kallapi celebica), bambu (Bambusa sp.) dan lain-lain yang ditanam
di kombong. Kayu dari kombong tersebut digunakan unutuk
pembuatan rumah dan perbaikan tongkonan keluarga yang telah ada.
Pemanfaatan kayu-kayu dari hasil kombong secara pribadi
(individu) oleh anggota keluarga dimungkinkan dengan seizin
pengelola (pemimpin masyarakat adat/tomina), sepanjang rumah
tongkonan yang ada belum memerlukan perbaikan. Jadi, semua
pemanfaatan hasil hutan harus melalui kesepakatan antara tomina
dengan masyarakat adat dengan pertimbangan untuk kepentingan
pribadi atau umum.
Selain pola tongkonan seperti dipaparkan sebelumnya,
dijumpai pula hutan rakyat swadaya masyarakat, yakni hutan rakyat
yang dibangun di tanah milik secara swadaya oleh masyarakat.
Dengan demikian, pola dan model hutan rakyat yang ada di Toraja
ada dua, yaitu: a. Hutan rakyat murni, adalah hutan rakyat yang
terdiri dari satu jenis tanaman kayu-kayuan (monokultur), atau lebih
dari satu jenis tanaman kayu-kayuan (polikultur), contoh:
buangin/cemara gunung (C. junghuhniana) dan bambu (Bambusa
sp.); b. Hutan rakyat campuran, adalah hutan rakyat yang terdiri dari
tanaman kayu-kayuan dan tanaman pertanian (tanaman pangan,
obat, rumput/pakan ternak, perkebunan, dan holtikultura), guna
memberi hasil dalam waktu pendek dan berkesinambungan.
Tanaman tersebut antara lain buangin, uru, bambu, nyatoh, kalapi,
pinus, aren, kopi, markisa, vanili, ubi kayu dan sebagainya.

46

47
V STRATEGI PENGEMBANGAN
SOCIAL FORESTRY DI SULAWESI
Social forestry akan dapat berkembang, termasuk di Sulawesi,
jika memenuhi prasyarat faktor-faktor penentu keberhasilan
sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya serta memiliki strategi
pencapaian. Rusli (2003) mengemukakan strategi pokok Social
Forestry, yaitu kelola kawasan dan sumberdaya hutan,
pengembangan kemitraan, dan pengembangan usaha. Dalam
pelaksanaannya, Social Forestry dapat diintegrasikan dengan
program nasional strategis lainnya, seperti ketahanan pangan,
ketenagakerjaan, peningkatan kemampuan usaha berbasis
masyarakat dan sebagainya.
Pada Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.01/Menhut-II/2004 disebutkan strategi pokok pengembangan
Social Forestry dalam kerangka pengelolaan hutan lestari, yaitu:
1. Kelola Kawasan, merupakan rangkaian kegiatan prakondisi untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan social forestry dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan;
2. Kelola Kelembagaan, merupakan rangkaian upaya dalam rangka
optimalisasi pelaksanaan social forestry melalui penguatan
organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia; dan
3. Kelola Usaha, merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung
tumbuh dan berkembangnya usaha di areal kerja social forestry
melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab.
Beberapa Prasyarat Pengembangan Social Forestry di
Sulawesi
Beberapa prasyarat yang diperlukan dalam pengembangan
Social Forestry di Sulawesi dirinci, sebagai berikut:
1. Adanya upaya untuk memperjelas wilayah kelola
masyarakat
Kejelasan wilayah kelola masyarakat adalah prasyarat utama
untuk mengembangkan social forestry di Sulawesi. Salah satunya

48
adalah dengan adanya pemetaan partisipatif dan pembuatan surat
kesepakatan kerjasama kemitraan (SPK) dalam mengelola dan
memanfaatkan hutan di sekitarnya. Tujuan pemetaan dan
pembuatan SPK adalah masyarakat dapat berusaha secara legal pada
suatu lahan untuk meningkatkan pendapatannya, selain menjaga
fungsi hutan agar tetap lestari bersama stakeholder yang terkait.
Upaya pemerintah pusat, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan
untuk mengalokasikan kawasan hutan menjadi wilayah kelola
masyarakat.
Kebijakan pusat tersebut lebih lanjut perlu didukung oleh
kebijakan di tingkat daerah untuk memperkuat dan membuat suatu
aturan spesifik sesuai karakteristik daerahnya. Diharapkan dengan
adanya upaya tersebut, indikator keberhasilan baik dimensi hasil
maupun dimensi manajemen dapat terpenuhi.
2. Adanya upaya untuk melakukan perubahan kebijakan baik
pusat maupun daerah
Upaya-upaya perubahan yang harus dilakukan untuk bisa
mendukung keberhasilan social forestry , antara lain:
a. Sebagian besar upaya yang telah dan sedang dilakukan selama ini
lebih tertuju kepada aspek-aspek ekonomi dan pemanfaatan SDA
dalam jangka pendek. Sedangkan upaya pembaharuan kebijakan
jangka panjang untuk meningkatkan kinerja perlindungan,
konservasi hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
kurang mendapat perhatian.
b. Substansi pembaharuan kebijakan yang dihasilkan belum
diarahkan untuk menguatkan penyiapan prakondisi pengelolaan
hutan yang selama ini sangat kurang dan menjadi kendala utama
bagi tercapainya usaha kehutanan secara berkelanjutan.
c. Kelemahan lainnya yang belum tersentuh adalah pembaharuan
struktur kebijakan yang dijalankan, khususnya dalam pengelolaan
social forestry. Selama ini struktur kebijakan yang dijalankan
berorientasi pada input dan proses, sehingga sangat banyak
peraturan yang berorientasi teknis yang harus dibuat. Di samping
implementasi kebijakan tersebut tidak efektif (disinsentif), juga
mengakibatkan lemahnya penegakan hukum.

49
d. Berbagai kelompok kajian dan diskusi mengenai kebijakan
pengelolaan hutan yang selama ini telah dilakukan menghendaki
perubahan struktur kebijakan dari yang berorientasi input dan
proses menjadi struktur kebijakan yang berorientasi pada kinerja
yang langsung berkaitan dengan tujuan pengelolaan hutan
(outcome-based policy). Struktur kebijakan seperti ini akan
mendorong efisiensi usaha dan mendorong mudahnya
pengawasan.
e. Implikasi perubahan struktur kebijakan menjadi outcome-based
policy akan mengubah fungsi organisasi pemerintah menuju
pengambilan keputusan yang cermat dan tepat serta didasarkan
pada informasi yang akurat.
f. Mengembangkan mekanisme yang baik dalam proses pembuatan
kebijakan yang mengacu kepada empat kriteria, yaitu: adanya
transparansi, adanya konsultasi publik (sosialisasi), adanya
partisipasi masyarakat, dan adanya akuntabilitas publik (dapat
dipertanggungjawabkan).
3. Adanya upaya membangun kelembagaan masyarakat yang
kuat
Upaya penataan dan penguatan kelembagaan masyarakat
dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat dengan
pihak lain. Selain itu, posisi strategis kelembagaan dalam suatu
kegiatan memiliki dasar yang kuat, karena dapat menyamakan
persepsi dan kemauan serta mampu memecahkan masalah secara
cepat dan mampu menampung semua aspirasi anggotanya.
Kelembagaan masyarakat petani pada umunya didasarkan
pada kesepakatan bersama di antara para petani dan dilandasi
keinginan untuk lebih memajukan usaha-usaha di bidang pertanian
dan bidang–bidang lainnya yang erat hubungannya dengan usaha
tani yang dijalankan, seperti bidang kehutanan, perkebunan,
peternakan, dan lain-lain. Selain itu, kelembagaan masyarakat
dibentuk untuk mencari jalan keluar yang cepat dan tepat guna
memecahkan permasalahan yang dihadapi, dalam pengorganisasian
dan pengawasan terhadap pemakaian SDH. Sistem ini mempunyai
batas-batas hukum, hak-hak pemilikan (property rights) dan aturan-
aturan perwakilan.

50
4. Adanya upaya pengembangan praktik social forestry di
lapang
Upaya untuk mengembangkan praktik social forestry di lapang
agar dilakukan secara inovatif dan tidak digeneralisasikan tetapi
dikembangkan sesuai karakteristik/spesifik lokal dengan berbagai
macam penyempurnaan dan pengayaan untuk meningkatkan
produktivitas lahan. Upaya yang perlu dilakukan, antara lain:
identifikasi dan inventarisasi potensi SDH dan SDM secara partisipatif,
pemetaan partisipatif potensi SDH, resolusi konflik pengelolaan SDH,
pengembangan pola agroforestry adaptif yang telah ada di lokasi dan
terbukti optimal, pengakuan dan penghormatan keberagaman pola
pengelolaan hutan yang ada di masyarakat setempat, yang sesuai
dengan karakteristik lokal, penyediaan layanan informasi pasar untuk
produk-produk hutan dari masyarakat, pengembangan usaha
masyarakat dengan pola kemitraan yang melibatkan semua pihak
yang terkait dengan pengelolaan SDH, dan pengembangan
monitoring dan evaluasi partisipatif.
5. Adanya upaya pengembangan aset manusia dan aset
sosial
Prasyarat selanjutnya dalam pengembangan social forestry
adalah mengembangkan aset manusia dan sosial. Aset manusia
dikembangkan dalam hal kemampuan untuk mengidentifikasi
kebutuhan masyarakat, pengembangan keterampilan memfasilitasi
dengan menggunakan metode-metode partisipatif yang berlandaskan
pada prinsip tranparansi dan kesetaraan, pengembangan komunikasi
yang intensif dan efektif. Upaya yang sederhana dan membawa
dampak langsung dalam membuat suatu perubahan yang nyata
adalah dengan program capacity building masyarakat melalui studi
banding dan training. Adapun pengembangan aset sosial dapat
dilakukan melalui working group, jaringan kerja, dan forum dialog
multipihak yang terkait dengan pengelolaan hutan setempat.
Prasyarat yang telah dipaparkan di atas perlu ditindaklanjuti
dengan pengembangan strategi sebagai berikut:

51
1. Strategi untuk mengembangkan kebijakan nasional dan
daerah yang mendukung social forestry
Sektor kehutanan merupakan sektor yang berkaitan dengan
kebijakan publik atau kepentingan masyarakat banyak, sehingga
dalam pengambilan keputusannya harus melibatkan semua pihak
terkait dalam pengelolaan SDH. Strategi ini bertujuan untuk
mendorong kebijakan nasional (pusat) dan daerah yang mendukung
upaya-upaya masyarakat untuk mengelola/memanfaatkan hutan,
serta mendukung program social forestry secara umum.
Sejalan dengan itu, mekanisme pembuatan kebijakan di
tingkat pusat dan daerah perlu diperbaiki. Untuk itu, perlu didorong
mekanisme konsultasi publik dalam proses penyusunan, implementasi
dan pertanggungjawaban kebijakan. Beberapa cara untuk
mengembangkan mekanisme publik dalam melakukan perubahan
kebijakan melalui beberapa tahap, antara lain: a) pengumpulan/
inventarisasi/identifikasi informasi yang akurat, b) negosiasi, c)
membangun kesepakatan dan d) mengelola kesepakatan antarpihak
terkait.
2. Strategi untuk memperkuat lembaga/institusi lokal dan
proses belajar bersama
Permasalahan mendasar dalam institusi lokal dan proses
belajar bersama adalah lemahnya modal sosial, sebagai akibat
lemahnya budaya kerja bersama, kapasitas dan kapabilitas SDM
dalam hal kepemimpinan, komitmen, kemampuan serta lemahnya
insititusi dalam hal organisasi dan aturan main. Strategi
pengembangan kelembagaan lokal dan lembaga pendukung lainnya
meliputi aturan main yang disepakati bersama, hak dan kewajiban,
batas-batas kewenangan, organisasi dan pengembangan SDM dalam
mengelola SDH.
Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan usaha yang
berbasis hutan, dilakukan melalui pendampingan tenaga-tenaga ahli,
antara lain mempunyai kepakaran di bidang antropologi/sosiologi dan
sosial ekonomi pertanian/kehutanan. Pengembangan kelembagaan
masyarakat meliputi tugas dan fungsi organisasi, kelangsungan

52
kegiatan, pemeliharaan kelangsungan organisasi serta struktur
organisasi dan kepemimpinan yang dirumuskan dan dilaksanakan
melalui dialog dan pertemuan secara berjenjang.
Pengembangan kelembagaan pemerintah merupakan upaya
pengembangan organisasi, aturan main dan sumber daya aparatur
pemerintah yang dapat dilakukan dengan pembinaan teknis,
monitoring, evaluasi dan koordinasi. Penetapan dan pelembagaan
aturan main serta batas-batas kewenangan dilakukan, antara lain
melalui kesepakatan-kesepakatan bersama yang dibangun dalam
forum desa, dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan
yang berlaku.
3. Strategi kepastian wilayah kelola dan kelola usaha
masyarakat
Strategi ini dikembangkan untuk mendorong desentralisasi
dan mendapatkan kepastian wilayah kelola usaha masyarakat. Dalam
desentralisasi diperlukan penguatan kapasitas Pemda baik lembaga
legislatif maupun eksekutif untuk memberi respon terhadap
keberagaman kepentingan para pihak; kemampuan untuk
memfasilitasi forum-forum dialog; serta membangun ketrampilan
perangkat pendukung manajemen kelembagaan multipihak termasuk
mekanisme kerjasamanya.
Pemantapan prakondisi pengelolaan kawasan dan SDH,
khusus yang berada di dalam kawasan hutan harus dilakukan melalui
arahan pencadangan, penataan batas luar secara partisipatif, serta
penetapan melalui menteri, sedangkan di luar kawasan hutan diatur
oleh pemerintah daerah setempat. Pengelolaan kawasan dan SDH
meliputi penatagunaan lahan, perlindungan, rehabilitasi dan
pemanfaatan hutan.
Keseluruhan proses tersebut dilakukan secara partisipatif,
dengan melibatkan semua stakeholder (pihak terkait) baik
masyarakat, dinas kehutanan kabupaten/kota dan Unit Pelaksana
Teknis Departemen Kehutanan yang mempunyai tugas di bidang
pemantapan kawasan hutan. Pembentukan areal kerja social forestry
juga harus diikuti dengan perancangan awal dalam rangka
pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sedangkan pada

53
areal di luar kawasan hutan (hutan hak) strategi ini dilakukan melalui
pemantapan peruntukan lahan dalam kerangka tata ruang daerah
setempat.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengambil inisiatif
untuk mengembangkan kebijakan daerah tentang social forestry.
Untuk itu, perlu paduserasi dan kaji ulang atas peraturan
perundangan yang tidak sejalan dengan pengembangan social
forestry seperti PP 25, PP 34, UU 32 dan UU 41 serta Perda-Perda
yang bertentangan satu dengan yang lain. Pemda juga diharapkan
bisa menetapkan wilayah kelola masyarakat, antara lain melakukan
kaji ulang tentang kebijakan tata ruang yang ada. Kebijakan yang
muncul juga harus memperhitungkan pendapatan asli daerah, selain
harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
Selain itu, pengembangan forum dialog baik di daerah
maupun sinergis dengan pusat tetap dilakukan untuk memperjelas
dan menetapkan ruang kelola masyarakat. Forum ini untuk
memperjelas hak, wewenang dan tanggung jawab dari semua pihak
terkai yang terlibat dalam pengembangan social forestry sehingga
menjadi suatu kegiatan yang produktif, selain mencari peluang-
peluang untuk bermitra dengan pengusaha agar ada keterjaminan
pasar dan standar harga yang jelas mengenai hasil hutan yang
diperoleh. Bisa juga dibentuk suatu lembaga kemitraan antar pihak
untuk menjembatani semua kepentingan yang ada, tanpa ada pihak-
pihak yang merasa dirugikan dan agar kerjasama tersebut menjadi
pengikat yang bersifat legal formal bagi semua pihak yang terlibat.
Setelah tahapan tersebut terpenuhi, maka strategi selanjutnya
adalah diperlukan kegiatan untuk meningkatkan usaha ekonomi
masyarakat. Dalam hal ini perlu dibentuk dan dikembangkan unit-unit
kelembagaan usaha masyarakat dalam suatu lembaga ekonomi yang
mandiri dan berbasis hutan. Bentuk kegiatannya, antara lain: a)
pembangunan unit usaha masyarakat sekitar kawasan hutan (hasil
hutan non kayu atau industri rumah tangga), b) pemeliharaan unit
kelembagaan masyarakat sekitar kawasan, c) bantuan teknologi dan
sarana produksi usaha masyarakat dan d) pembangunan jaringan
usaha dan pemasaran hasil hutan.

54
4. Strategi untuk mengembangkan keselarasan kerja antar
stakeholder
Untuk mengembangkan keselarasan kerja antar stakeholder
dan padu serasi semua kegiatan/program yang ada, diperlukan
strategi, antara lain: a. peneguhan komitmen dan konsistensi, b.
komunikasi dan koordinasi, c. apresiasi terhadap berbagai
kepentingan, d. dibangunnya persepsi dan visi bersama, e.
penegakan hukum, dan f. meningkatkan posisi tawar masyarakat.
Strategi ini perlu dikembangkan untuk mendorong terwujudnya
sistem usaha kehutanan yang berdaya saing, kelola kawasan dan
kelembagaan yang berbasis masyarakat setempat dengan
mensinergiskan berbagai potensi yang ada, yaitu sumberdaya
pemerintah, swasta dan masyarakat serta sumberdaya lainnya.
Adanya tahapan strategi mengembangkan keselarasan kerja
antar stakeholder yang terlibat dari pihak swasta, pemerintah,
masyarakat dan perbank-an, maka social forestry merupakan sistem
yang tidak saja berupa usaha budidaya, tetapi termasuk juga sektor
hilirnya, yaitu industri dan pemasaran. Kondisi tersebut perlu
didukung oleh adanya kelola usaha yang merupakan rangkaian
kegiatan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha di
areal kerja social forestry, baik di dalam kawasan (hutan negara)
maupun di luar kawasan (hutan hak) melalui kemitraan dengan
perimbangan tanggung jawab dan manfaat.
Kemitraan dalam kelola usaha merupakan suatu bentuk
kerjasama antara masyarakat dengan stakeholder lainnya. Untuk
areal yang izin pemanfaatannya bukan atas nama masyarakat
setempat, kemitraan bersifat kerjasama dalam segmen usaha.
Sedangkan untuk areal hutan hak maka pemanfaatan dan
perizinannya ada pada masyarakat setempat, kemitraan bersifat
kerjasama dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil panen.
Apabila semua tahapan pengembangan keselarasan kerja antar
stakeholder sudah terwujud dari adanya komitmen bersama dan
meningkatnya posisi tawar masyarakat, maka diharapkan strategi
pengembangan social forestry akan berhasil dilaksanakan di Sulawesi.

55
VI
PENUTUP
Pemaparan pada bab sebelumnya menunjukkan adanya
keragaman pada social forestry di Sulawesi. Kondisi tersebut dapat
disebabkan oleh adanya perbedaan dalam status lahan garapan,
sistem pengelolaan, prioritas orientasi usaha (antara subsisten dan
komersial), jenis dan ragam produk.
Pada dasarnya praktik social forestry dapat dilakukan, baik di
lahan negara maupun di lahan milik. Pada lahan negara dikenal
beberapa istilah, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan
Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, dan Hutan Kemitraan. Adapun
yang dilakukan di lahan milik dikenal sebagai hutan rakyat. Praktik
social forestry tersebut telah dikembangkan di Sulawesi pada skala
dan progres yang berbeda. Namun, karena keterbatasan
sumberdaya, tidak semua praktik social forestry dimaksud dapat
disajikan.
Keragaman dijumpai pula dalam sistem pengelolaan yang
berkaitan dengan sistem penguasaan dan pengambilan keputusan,
baik secara individual maupun komunal (kelompok). Sedangkan
orientasi usaha dari setiap lokasi mempunyai karakteristik, yaitu hasil
produksi lahan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sendiri
(subsisten) atau dijual untuk menambah pendapatan (komersial).
Jenis produk yang dihasilkan juga sangat beragam, baik tanaman
kehutanan, perkebunan, maupun tanaman pertanian (tanaman
semusim).
Pada umumnya pengembangan social forestry di Sulawesi
masih bersifat tradisional dan belum menerapkan teknik silvikultur
sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dijumpai pada lahan
masyarakat, berupa belum adanya pengaturan jarak tanam (spacing)
dan belum adanya kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman,
seperti pemangkasan, penjarangan, pemupukan, dan penyiangan
tanaman dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman, yang
berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat dari praktik
social forestry.

56
Di beberapa lokasi dijumpai pengembangan social forestry
dengan struktur kelembagaan yang relatif maju, berupa struktur
organisasi dan perangkatnya, AD/ART, dan kesepakatan internal, baik
tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini dapat dipahami sebagai dampak
pendekatan yang bersifat ‘proyek’ yang memprasyaratkan adanya
‘kelompok’. Karena keberadaan dan aktivitas kelembagaan masih
bersifat keproyekan, maka partisipasi masyarakat yang terlibat dalam
kegiatan dimaksud juga masih bersifat keproyekan.
Hal lain yang dijumpai adalah pengembangan social forestry
tampaknya belum didukung oleh paket kebijakan yang komprehensif,
khususnya dalam implementasi di lapang. Demikian halnya, regulasi
inisiatif daerah yang bersifat disinsentif dan memberatkan bagi petani
hutan rakyat sebagai bagian dari social forestry karena adanya
pungutan retribusi atas hasil lahan hutan miliknya.
Pemerintah perlu membuat regulasi/kebijakan social forestry
yang bersifat insentif, fleksibel, kompehensif, dan sinergis antara
pusat-daerah, sehingga mendorong perkembangan social forestry
yang aplikatif di lapang. Kebijakan dimaksud hendaknya tidak
diberlakukan secara umum, berdasarkan pertimbangan karakteristik
lokasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat khas
setempat (local specific). Beberapa kebijakan daerah yang sifatnya
mendukung keberhasilan social forestry, hendaknya ditingkatkan.
Menyadari masih kurangnya penerapan teknik silvikultur
dalam pengembangan social forestry, maka transformasi teknologi
kepada masyarakat pengelola social forestry hendaknya semakin
ditingkatkan dan difasilitasi. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya petani hutan masyarakat,
antara lain peningkatan penyuluhan, pelatihan, dan studi banding.
Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam
masyarakat perlu dipertimbangkan dalam pengembangan social
forestry untuk memotivasi masyarakat agar lebih berpartisipasi. Di
samping itu, pendampingan dan pembinaan dari instansi terkait dan
LSM yang berpengalaman dalam kegiatan pendampingan, perlu
dilakukan terutama pada pembinaan dan pengembangan
kelembagaan masyarakat agar lebih profesional, produktif, dan
mandiri.

57
DAFTAR PUSTAKA
Awang, S.A., 2003. Politik Kehutanan Masyarakat. Penerbit. Center for Critical Social Studies (CCSS) Bekerjasama dengan Kreasi Wacana Yogyakarta.
Awang, S.A., 2004. Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan. Penerbit Bayu Indra Grafika. Yogyakarta.
Balai Pengelolaan DAS Sampara, 2004. Laporan Tahunan. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sampara Sulawesi Tenggara.
Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae. 2010. Laporan hasil kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kerja hutan desa. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
Balai Pengelolaan DAS Bone Bolango. 2002. Laporan Tahunan BP DAS Bone Bolango, Gorontalo.
Badan Pusat Statistik. 2007. Kabupaten Wajo Dalam Angka.
Bisjoe, ARH. 2005. Penggunaan Lahan Hutan oleh Masyarakat; Studi Kasus pada Kawasan Hutan Penelitian Borisallo Kabupaten Gowa (Tesis Magister Perencanaan Kota dan Daerah). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. (Tidak diterbitkan).
Center For International Forestry Research, 2003. Refleksi Empat Tahun Reformasi Mengembangkan Social Forestry di Era Desentralisasi. Intisari Lokakarya Nasional Social Forestry. Cimacan.
Cunu, S. 2011. Lahirnya Koperasi Hutan Jaya Lestari dalam Hutan Lestari Berbasis Masyarakat. Penerbit JAUH Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Koperasi Hutan Jaya Lestari Konawe Selatan.
Dassir, M. 2008. Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang. Jurnal Hutan dan Masyarakat Vol. III No. 2 Agustus 2008, 111-234. UNHAS.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros, 2009. Laporan Tahunan.

58
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2004. Statistik Kehutanan Provinsi Sulawesi
Selatan.
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2013. Rencana Pengembangan Hutan Rakyat di Sulawesi Selatan. Makalah yang disampaikan pada acara seminar hutan rakyat di Hotel Horison Makassar.
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2004. Statistik Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, 2004. Statistik Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara.
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, 2004. Statistik Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2004. Statistik Kehutanan Provinsi Gorontalo.
Dipokusumo, B., H. Kartodihardjo, D. Darusman dan A.H. Dharmawan. (2011). Kajian Dinamika Kebijakan Hutan Kemasyarakatan dan Alternatif Penyelesaian Konflik Kepentingan pada Kawasan Hutan Lindung di Pulau Lombok. Agroteksos Vol. 21 (2-3), 165 - 176.
Djogo, T., Sunaryo, Suharjito. D, dan Sirait. M, 2011. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestry. ICRAF. Bogor.
Gilmour, D.A and R.J Fisher 1998. Evolution in Community Forestry: Contesting Forest Resources, RECOFTC, Bangkok, Thailand.
Haddade, 2004. Pemberdayaan Masyarakat Melalui bantuan langsung Sebagai Salah Satu Luaran Perencanaan Pembangunan Pertanian. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.
Hayati, N. 2006. Pola Pengelolaan lahan kritis (Studi Kasus di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Info Sosek Ekonomi 6(1): 13-21. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
Hakim, I., Irawanti.S, Murniati dan Sumarhani, Widianti.A, Effendi.R, Muslich dan S. Rulliaty. Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.

59
Hakim, I. 2009. Kajian kelembagaan dan kebijakan hutan tanaman rakyat: Sebuah Terobosan dalam Menata Kembali Konsep Pengelolaan Hutan Lestari. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 6 (1) : 27-24. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan.Bogor.
Hermawansyah. 2013. Komitmen Negara, Ekspektasi Masyarakat dan Realitas Prosedural. Makalah pada Seminar dan Lokakarya Hutan Desa/HKm Kalimantan Tengah: Memajukan Perhutanan Sosial bagi Kesejahteraan Masyarakat. Diselenggarakan oleh Mitra LH Kalteng- Samdhana Institute. Palangkaraya, 30 Juli 2013.
Hijjang, P. 2005. Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan. Jurnal Antropologi Indonesia 29(3) : 255-268.
Hobley, M. 1996. Participatory Forestry. The Process of Change in India and Nepal. Rural Development Forestry Study Guide 3. London.
Mangki, L. 2011. Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Lestari Berbasis Masyarakat Pengalaman Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) Kabupaten Konawe Selatan. Penerbit Jaringan Untuk Hutan (JAUH) Sulawesi Tenggara Bekerjasama dengan Koperasi Hutan Jaya Lestari Konawe Selatan.
Mangki. L., Suardi, Sultan, Hamid. A dan A. Maal, 2011. Hutan Lestari Berbasis Masyarakat Pengalaman Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) Kabupaten Konawe Selatan. Penerbit Jaringan Untuk Hutan (JAUH) Sulawesi Tenggara Bekerjasama dengan Koperasi Hutan Jaya Lestari Konawe Selatan.
Nurhaedah, Hasnawir, Bisjoe ARH., dan E.Hapsari. 2012. Analisis sosial budaya REDD. Laporan hasil penelitian. Balai Penelitian Kehutanan Makassar. Tidak dipublikasi.
Pasaribu, HS. 2003. Social Forestry. Majalah Kehutanan Indonesia. Edisi Juni 2003.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2012. Pemerintah sahkan UMP Sulawesi Selatan. http://www.sulsel.go.id. Di akses tgl 6 Nopember 2013.
Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Izin Pengelolaan/Pemanfaataan Hutan Rakyat. Kabupaten Sidrap.

60
Purwanto, E. 2006. Lambusango Forest Conservation Project, South East Sulawesi, Indonesia GEF-MSP No. TF 054815, Fifth Progress and Implementation Plan Report (January 12, 2006). Operation Wallacea Trust. Bau-bau.
Ritchie. B, Mc Dougall C., Haggith M., de Clivera NB. 2001. Kriteria dan Indikator Keberhasilan Hutan yang di Kelola oleh Masyarakat. Center International of Forestry Research. Bogor.
Rusli, Y. 2003. Social Forestry: Pokok-pokok Pikiran. Majalah Kehutanan Indonesia. Edisi Juni 2003.
Rahayu, L., Wianti, F. 2010. Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat. Pembekalan Teknis Pejabat Fungsional PEH Lingkup Ditjen RLPS Kementrian Kehutanan RI. Ditjen RLPS Kementrian Kehutanan RI dan Fakultas Kehutanan UGM.
Simon, H. 1998. Reformasi and its effects on forest management effects on forest management policies in Indonesia. International Seminar on Decentralization and Devolution of Forest Management in Asia and The Pacific. Davao City, Philippines: 30 November - 4 December 1998.
Slamet, Y. 1989. Konsep-Konsep Dasar Partisipasi Sosial. Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Syahyuti. 2006. 30 Konsep penting dalam pembangunan pedesaan dan pertanian: penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variable. PT Bina Reka Pariwara. Jakarta.
Supratman dan Alif. 2010. Pembangunan Hutan Desa di Kabupaten Bantaeng. Konsep, Proses dan Refleksi. Regional Community Forestry Training Center for Asia and The Pacifik. CV.Bumi Bulat Bundar.
Sutrisno, L. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Kanisius Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Umar, S. 2002. Agroforestri Khas Propinsi Sulawesi Selatan. Proceeding Seminar Nasional Peranan Strategis Agroforestri dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Lestari dan Terpadu. Yogyakarta, 1-2 November 2002. Universitas Gadjah Mada. (Proceeding)
Wakka, A.K., Bisjoe ARH., Kusumedi.P. dan N. Hayati. 2004. Pengembangan Social Foresty di KHDTK Borisallo. Laporan

61
Hasil Penelitian. Balai Penelitian Kehutanan Kehutanan Sulawesi. Tidak Dipublikasi.
Wakka, A.K. 2005. Pengembangan Social Forestry di SPUC Borisallo: Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat. Info Sosial Ekonomi 5(3): 297-309. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan. Bogor.
Wakka, A.K., Muin, N., & Purwanti, R. (2012). Studi Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Secara Kolaboratif. Analisis Kebijakan Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Laporan Hasil Penelitian. Makassar. Balai Penelitian Kehutanan Makassar.
Wakka, A.K., Muin, N., & Purwanti, R. (2013). Konflik Pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan Upaya Penyelesaiannya. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 (3), 186 - 198.
Widianto, T., Hasnawir, Sumirat, B.K., dan A.K. Wakka., 2012. Kajian Tata Kelola REDD dan REDD PLUS. Laporan Hasil Penelitian. Balai Penelitian Kehutanan. Makassar. Tidak dipublikasi.

62