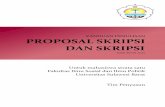SKRIPSI....UNINUS
-
Upload
iwa-kertapati -
Category
Documents
-
view
1.037 -
download
52
Transcript of SKRIPSI....UNINUS
BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah
Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu dari Pendidikan Luar Sekolah, yang mana pendidikan tersebut diberikan kepada anak sebelum masa sekolah dasar yang diwajibkan oleh negara Republik Indonesia (SD dan SMP) mulai usia kelahiran, sampai 5 tahun, maka salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah sebagai pendidik harus dapat memahami secara lebih baik tentang kemampuan-kemampuan dan kecakapan anak. Banyak orang dewasa yang gagal memahami anak kecil sebagai mahluk yang mempunyai kecerdasan, dalam kemampuan belajar, penemuan terbaru dalam hal dunia pendidikan pada saat ini sedang hangat-hangatnya membahas dan meneliti tentang pendidikan anak usia dini, mulai dari proses sampai pada hasil akhir dari pendidikan usia dini. Perlu ditekankan bahwa pendidikan anak usia dini sangatlah berbeda dengan pendidikan anak usia remaja dan usia dewasa, bahkan berhasil tidaknya pendidikan anak remaja maupun dewasa terletak pada pendidikan usia dini. Usia di bawah lima tahun (balita) adalah usia yang paling kritis atau paling menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Termasuk juga pengembangan intelegensi hampir seluruhnya terjadi pada usia di bawah lima tahun. Kalau seseorang sudah terlanjur menjadi pencuri atau penjahat, maka pendidikan Universitas bagi orang tersebut boleh dikatakan tidak berarti apa-apa. Sebagaimana halnya sebatang pohon bambu, setelah tua susah dibengkokkan.1
Anak-anak pada usia di bawah lima tahun memiliki intelegensi laten (potential intelegence) yang luar biasa. Namun pada umumnya para orangtua dan guru hanya bisa mengajarkan sedikit hal pada anak-anak. Sesungguhnya anakanak usia muda tidak complicated (ruwet) dalam belajar, tetapi orangtua atau guru yang bermasalah. Pada umumnya orang tua selalu menyalahkan anak-anak apabila tingkah laku mereka tidak seperti yang diinginkan. Hal ini lebih banyak disebabkan karena jiwa kurangnya anak, pengetahuan sering dan pemahaman terhadap dengan
perkembangan
sehingga
memperlakukannya
tidak/kurang tepat. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa dan kemampuan untuk menyerap informasi sangat tinggi. Kebanyakan orang tidak mengenali dan memahami kemampuan magic yang ada pada anak-anak. Mereka hanya bisa berkata, Saya tahu anak-anak belajar lebih cepat, tetapi mereka tidak tahu seberapa cepat anak-anak bisa belajar. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan orang tua dan guru-guru maka potensi luar biasa yang ada pada setiap anak sebagian besar tersia-siakan. Penelitian di bidang neurologi yang dilakukan Benyamin S. Bloom, seorang ahli pendidikan dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, Penelitian tersebut mengemukakan bahwa pertumbuhan sel jaringan otak pada anak usia 0 4 tahun mencapai 50%, hingga usia 8 tahun mencapai 80%. Artinya bila pada usia tersebut otak anak tidak mendapatkan rangsangan yang maksimal maka otak anak tidak akan berkembang secara optimal. Pada dasawarsa kedua yaitu usia 18 tahun perkembangan jaringan otak telah mencapai 100%.
2
Oleh sebab itu masa kanak-kanak dari usia 0 - 8 tahun disebut masa emas (Golden Age) yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia sehingga sangatlah penting untuk merangsang pertumbuhan otak anak dengan memberikan perhatian terhadap kesehatan anak, penyediaan gizi yang cukup, dan pelayanan pendidikan. Data memperlihatkan bahwa layanan pendidikan anak usia dini di Indonesia masih termasuk sangat memprihatinkan. Sampai dengan tahun 2001, jumlah anak usia 0 - 6 tahun di Indonesia yang telah mendapatkan layanan pendidikan baru sekitar 28% (7.347.240 anak). Khusus untuk anak usia 4 - 6 tahun, masih terdapat sekitar 10,2 juta (83,8%) yang belum mendapatkan layanan pendidikan. Masih banyaknya jumlah anak usia dini yang belum mendapatkan layanan pendidikan tersebut disebabkan terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Bermain menjadi sangat penting untuk ditelaah ketika pendidikan anak usia dini dibicarakan. Bermain dengan anak usia dini semisal pemain sepak bola dengan stadionnya. Para ahli memandang bahwa melalui bermain anak dapat menguasai banyak skil, konsep fisik dan sosial serta intelektual dasar. Isenberg dan Quisenberry (1988) menyatakan bahwa bermain adalah perilaku dinamis aktif, dan konstruktif yang merupakan bagian penting dan integral dari masa kanak-kanak, balita hingga masa remaja. Vigotsky (1962) meyakini bahwa permainan adalah suatu setting yang sangat bagus bagi pekembangan kognitif. Ia tertarik khususnya pada aspek-aspek simbolis dan khayalan suatu permainan, sebagaimana ketika seorang anak menirukan tongkat sebagai kuda dan mengendarai tongkat seolah-olah seekor kuda.
3
Jenis bermain dalam latar sekolah dapat digambarkan sebagai sesuatu yang kontinu mulai dari bermain bebas hingga bermain yang dipandu. Jenis bermain tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut: (1). Bermain bebas, yaitu bermain yang memberi banyak pilihan kepada anak untuk memilih dan menggunakan materi yang diinginkan; (2). Bermain dipandu, bermain yang materinya telah dipilih guru agar anak menemukan konsep-konsep tertentu; (3). Bermain diarahkan yaitu bermain atas instruksi guru seperti menyanyikan lagu dan lain-lain. Bermain memiliki karakteristik; (1). Aktivitas yang termotivasi secara personal; (2). Aktif (tidak pasif); (3). Sering beresifat nonliteral (berpura-pura); (4). Tidak memiliki tujuan ekstrinsik (tujuan dari perintah orang); (5). Tidak memiliki aturan-aturan ekstrinsik (tekanan dari luar); (6). Pemain memberikan makna pada bermain. Bermain berkontribusi pada perkembangan kognitif, sosial, emosional dan fisik anak yaitu: (1). Pada perkembangan kognitif dimaksudkan sebagai suatu peningkatan dalam simpanan dasar pengetahuan anak yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman-pengalaman dengan benda-benda dan manusia. (2). Pada peningkatan dan sosial dan emosional anak-anak terdorong keluar dari pola-pola berpikir egosentris. Mereka dirangsang untuk mempertimbangkan titik-titik pandang teman bermain mereka.(3). Pada perkembangan fisik mereka dapat terlatih skill gerak halus dan gerak berat (kasar). Peran guru dalam bermain pada latar kelas sangatlah penting. Bjorkland (1978) mengurutkan peran tersebut sebagai pengamat, penjelas, model, evaluator
4
dan perencana bermain. Bermain yang dimaksud baik bermain indoor (di dalam ruangan) ataupun outdoor (di luar ruangan). Agar dapat menjadi produktif, bermain outdoor membutuhkan perencanaan, observasi dan evaluasi yang berdasarkan pada bermain indoor. Semua anak dapat diuntungkan ketika guru memberikan materi-materi yang tepat dan mendorong mereka untuk
mengeksplorasi apa yang dapat mereka lakukan dengan tubuh mereka. Oleh karenanya guru harus benar-benar memahami kondisi setiap anak yang normal atau yang berkebutuhan khusus. Bagi guru pendidikan anak usia dini tugas dan kewajiban sebagaimana menjadi pendidik merupakan amanat yang harus diterima oleh guru atas dasar pilihannya untuk memangku jabatan guru. Amanat tersebut wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dari uraian di atas, maka dapatlah dibuat suatu penelitian tentang konsep bermain untuk meningkatkan kemampuan kreativitas dengan judul : Penerapan Konsep Bermain untuk Meningkatkan Kreativitas Anak Usia Dini oleh Guru di PAUD Al-Fitriyah Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diindentifikasi permasalahan sebagai berikut:1. Perencanaan penerapan konsep bermain anak usia dini di PAUD Al-Fitriyah
Kebonpedes Kabupaten Sukabumi oleh guru masih perlu ditingkatkan.2. Penerapan konsep bermain untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini di
PAUD Al-Fitriyah Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, belum optimal.5
3. 4.
Sarana bermain untuk anak masih perlu penambahan. Perencanaan dan pengembangan kegiatan yang dibuat oleh guru masih perlu ditingkatkan.
C. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; Bagaimana penerapan konsep bermain untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini di PAUD Al-Fitriyah Kebonpedes Kabupaten Sukabumi? Berdasarkan perumusan masalah diatas, serta agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis batasi permasalahannya pada; Penerapan konsep bermain untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini di PAUD Al-Fitriyah Kebonpedes Kabupaten Sukabumi. D. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:1. Kebijakan program anak usia dini di PAUD Al-Fitriyah Kebonpedes
Kabupaten Sukabumi.2. Penerapan konsep bermain untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini di
PAUD Al-Fitriyah Kebonpedes Kabupaten Sukabumi.3. Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan dalam penerapan konsep
bermain untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini di PAUD Al-Fitriyah Kebonpedes Kabupaten Sukabumi
6
E. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara teoritis Dengan membahas konsep bermain dalam penelitian ini, berarti akan memperkaya teori-teori tentang kajian anak usia dini. 2. Secara praktis
Membantu guru untuk memilih metode pembelajaran terutama bermain. Membantu guru memotivasi siswa menggunakan konsep bermain. meningkatkan kreativitas dengan
Membantu siswa untuk dapat aktif dan dinamis belajar dengan penuh
kesenangan dan kenyamanan di bawah pengawasan dan bimbingan guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada para guru
dalam menerapkan konsep bermain pada anak usia dini.
F. Anggapan Dasar Pembelajaran Bagi Anak Usia Dini Berdasarkan definisi Konsensus Knowles dalam pembelajaran merupakan suatu proses di dalam mana perilaku diubah, dibenarkan atau dikendalikan. Sementara itu Abdulhak menjelaskan bahwa proses pembelajaran adalah interaksi edukatif antara peserta didik dengan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Pembelajaran di kelompok bermain jelas sangat berbeda dengan di sekolah, dimana pembelajaran dilakukan dalam suasana bermain yang menyenangkan. Jerome Bruner menyatakan, setiap materi dapat diajarkan kepada
7
setiap kelompok umur dengan cara-cara yang sesuai dengan perkembangannya. pada permainan atau bermain. Permainan atau bermain adalah kata kunci pada pendidikan anak usia dini. Ia sebagai media sekaligus sebagai substansi pendidikan itu sendiri. Dunia anak adalah dunia bermain, dan belajar dilakukan dengan atau sambil bermain yang melibatkan semua indra anak. Menurut Supriadi bahwa Bruner dan Donalson dari telaahnya menemukan bahwa sebagian pembelajaran terpenting dalam kehidupan diperoleh dari masa kanak-kanak yang paling awal, dan pembelajaran itu sebagian besar diperoleh dari bermain. Bermain bagi anak adalah kegiatan yang serius tetapi menyenangkan. Menurut Conny R. Semiawan melalui bermain, semua aspek
perkembangan anak dapat ditingkatkan. Dengan bermain secara bebas anak dapat berekspresi dan bereksplorasi untuk memperkuat hal-hal yang sudah diketahui dan menemukan hal-hal baru. Melalui permainan, anak-anak juga dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal, baik potensi fisik maupun mental intelektual dan spiritual. Oleh karena itu, bermain bagi anak usia dini merupakan jembatan bagi berkembangnya semua aspek.
G. Pertanyaan Penelitian Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;1. Bagaimana kebijakan program anak usia dini di PAUD Al-Fitriyah
Kebonpedes Kabupaten Sukabumi?
8
2. Bagaimana penerapan konsep bermain untuk meningkatkan kreativitas
anak usia dini di PAUD Al-Fitriyah Kebonpedes Kabupaten Sukabumi? 3. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan dalam penerapan konsep bermain untuk meningkatkan kreativitas anak usia dini di PAUD Al-Fitriyah Kebonpedes Kabupaten Sukabumi?
H. Penjelasan Istilah Konsep Bermain Bermain bagi anak-anak bukan sekedar bermain, tetapi bermain merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran. Dalam bermain anak dapat menerima banyak rangsangan. Selain dapat membuat diri anak senang juga dapat menambah pengetahuan anak. Dalam proses belajar, anak-anak mengenalnya melalui permainan karena tidak ada cara yang lebih baik untuk merangsang perkembangan kecerdasan anak melalui kegiatan melihat, mendengar, meraba dan merasakan yang kesemuanya itu dapat dilakukan melalui kegiatan bermain. Meningkatkan Yang dimaksud dengan meningkatkan dalam tulisan ini adalah kemampuan anak menjadi bertambah setelah mengikuti kegitan bermain. Kreatifitas Adalah kemampuan anak dalam mengepresikan sesuatu berdasarkan dari hasil melihat, mendengan, meraba dan merasakan melalui kegiatan bermain.
9
Anak Usia Dini Adalah anak-anak yang berusia dibawah 5 tahun yang mengikuti proses pendidikan di PAUD Al-Fitriyah PAUD Al-Fitriyah Tempat pelaksanaan proses pendidikan anak usia dini.
I. Sistimatika Penulisan Sistimatika penelitian ini terdiri dari; Bab I; berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, anggapan dasar, pertanyaan penelitian, penjelasan istilah dan sistimatika penulisan. Bab II, mengetengahkan tentang teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, diantaranya teori tentang konsep bermain dan kreatifitas anak. Bab III, tentang prosedur penelitian yang berisi; Metode Penelitian, Sumber dan Jenis Data, subjek Penelitian, Instrumen Penelitian, TeknikPengumpulan
Data, Tahap-tahap Penelitian dan Pelaksanaan, Teknik Analisis Data, Tempat dan Waktu Penelitian Bab IV, penyajian data hasil penelitian dan pengolahan data penelitian. Bab V, mengetengahkan tentang kesimpulan dan saran.
10
BAB II PENERAPAN KONSEP BERMAIN UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS ANAK USIA DINI A. Penerapan Konsep Bermain1. Pengertian Bermain
Menurut Prasetyono, (2007) menyatakan bahwa : Bermain bagi anak-anak bukan sekedar bermain, tetapi bermain merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran. Dalam bermain anak dapat menerima banyak rangsangan. Selain dapat membuat diri anak senang juga dapat menambah pengetahuan anak. Dalam proses belajar, anak-anak mengenalnya melalui permainan karena tidak ada cara yang lebih baik untuk merangsang perkembangan kecerdasan anak melalui kegiatan melihat, mendengar, meraba dan merasakan yang kesemuanya itu dapat dilakukan melalui kegiatan bermain. Sedang menurut Conny R. Semiawan dalam Buletin PADU (2003): Bermain sangat berperan dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagi anak, bermain adalah suatu kegiatan yang serius namun mengasyikkan. Melalui aktivitas bermain, berbagai pekerjaan terwujud. Bagi anak, bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak karena menyenangkan bukan karena akan mendapat hadiah atau alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Kreativitas belajar anak melalui bermain sangat penting sekali untuk di pahami oleh orang tua dan guru didalam memberikan stimulasi (rangsangan) kepada anak sedini mungkin sesuai dengan periodesasi perkembangannya. Bruner dalam Hurlock Elizabeth; (1990 : 234), mengatakan: bahwa bermain dalam periode anak dini usia merupakan kegiatan yang serius yang merupakan bagian yang paling penting dalam perkembangan anak. Dalam bermain anak akan belajar untuk melakukan improvisasi dan kombinasi yang akan digunakan untuk mempelajari sesuatu yang mempersiapkan diri menghadapi kehidupan dewasa. Bermain juga menurut Gallahue (1989 : 212) adalah :
11
Suatu aktivitas yang langsung dan spontan dimana seorang anak menggunakan orang lain atau benda-benda disekitarnya dengan senang, sukarela dan dengan imajinatif, menggunakan perasaannya, tangannya atau seluruh anggota tubuhnya. Biasanya anak melakukan permainan dengan alasan untuk mengetahui dan bereksperimen tentang dunia sekitarnya dalam rangka mengembangkan hubungan dengan dunia sekitarnya. Anak-anak bermain karena bermain adalah aktivitas yang paling menyenangkan bagi mereka, dan mereka melakukannya bukan karena ingin dipuji atau karena ingi diberi hadiah. Bermain merupakan alat utama untuk mencapai pertumbuhannya, sebagai mediumdimana anak mencobakan diri bukan saja hanya dalam fantasinya tetapi dilakukan secara nyata. Dworetzy dikutip dalam Moeslihatun (1995 : 24), mengemukakan sedikitnya ada lima kriteria dalam bermain yakni1. Motivasi instrinsik, yaitu tingkah laku bermain dimotivasi dari
dalam diri anak itu sendir. Bukan karena adanya tuntutan dari dalam diri anak itu sendiri. Bukan karena tuntutan dari orang-orang disekitarnya atau karena kebutuhan akan fungsi-fungsi tubuhnya. 2. Pengaruh positif, yaitu tingkah laku yang menyenangkan untuk dilakukan 3. Bukan dikerjakan sambil lalu, karena itu tidak mengikuti urutan yang sebenarnya melainkan lebih bersifat pura-pura 4. Cara/tujuan , cara bermain lebih diutamakan daripada tujuannya karena anak lebih tertarik pada tingkah laku itu sendiri daripada keluaran yang dihasilkan 5. Kelenturan, yakni bermain itu perilaku yang lentur yang ditujukan baik dalam bentuk maupun hubungan serta berlaku dalam setiap situasi. Jika menggunakan kelima kriteria tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bila seseorang anak menggunakan mainan boneka dengan cara yang fleksibel tanpa tujuan yang jelas dalam pikirannya, kegiatannya pura-pura, menyenangkan
12
bagi dirinya, dan melakukan kegiatan hanya untuk kesenggangan, maka dapat dikatakan ia sedang bermain. Almy (1984) menulis bahwa : membedakan karakteristik-karakteristrik bermain membuatnya penting untuk perkembangan anak. Dalam paper yang disetujui oleh Association for Childhood Education International (ACEI), Isenberg dan Quisenberry (1988) menyatakan bahwa bermain adalah prilaku dinamis, aktif dan konstruktif, yang merupakan bagian penting dan integral dari masa kanakkanak, balita hingga masa remaja. ACEI juga menegaskan bahwa guru harus mengartikulasikan kebutuhan untuk bermain dalam kehidupan anakanak, terutama sebagai bagian dari kehidupan sekolah mereka. Dengan memahami arti bermain bagi anak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bermain adalah suatu kebutuhan bagi anak. Dengan merancang pelajaran tertentu untuk dilakukan sambil bermain, maka akan belajar sesuai dengan tuntutan taraf perkembangannya. Bahkan, kalau kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, ada satu tahap perkembangan yang berfungsi kurang baik dan ini tidak akan terlihat secara nyata segera, melainkan baru kelak bila ia sudah menjadi remaja. Ada 2 hal yang terkait dengan masalah ini. a) Perkembangan kognitif anak pada umur ini menunjukkan bahwa ia
berada pada taraf praoperasional sampai pada tahap operasi konkret. Ciri-ciri dari tahap perkembangan yang ditandai oleh Childhood education, adalah perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir memecahkan persoalan dengan menggunakan lambang tertentu. Makin ia memasuki tahap perkembangan operasi konkret, maka makin mampu ia berpikir logis, meskipun segala sesuatu pelajaran yang bersifat formal belum menjadi
13
suasana yang diakrabi secara alamiah. Makin lama maka usai fase operasi konkret, secara bertahap ia memasuki fase operasi formal. b) Hal kedua terkait dengan yang dikatakan dimuka, berkaitan dengan
fungsi otak. Seperti diketahui, kedua belahan otak, kiri dan kanan, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Belahan otak kiri memiliki fungsi, ciri dan respons untuk berfikir logis, teratur, dan linier. Sebaliknya, belahan fungsi otak kanan terutama dikembangkan untuk mampu berpikir holistik, imajinatif dan kreatif. Bila anak belajar formal (seperti banyak hafal-menghafal) pada umur muda, maka belahan otak kiri yang berfungsi linier logis, dan teratur amat dipentingkan dalam perkembangannya dan sering berakibat bahwa fungsi belahan otak kanan yang banyak digunakan dalam berbagai permainan terabaikan. Akibatnya menurut penelitian (Clark, 1986), maka yang diperlukan seperti itu, kelak akan tumbuh sering dengan memiliki sikap yang cenderung bermusuhan (hostile attitude, Clark, 1986) terhadap, sesama teman atau orang lain. Hal tersebut menunjuk pada suatu pertumbuhan mental yang kurang sehat. Jadi belajar sambil bermain bagi anak umur kurang lebih 4- - 7, tahun adalah suatu conditio sine qua non, bila mau tumbuh secara mental, bahkan sampai dengan umur 13 atau 14 tahun bermain adalah penting bagi anak. 2. Latar Belakang Konsep Bermain Dalam pandangan Piaget, bermain mendorong anak-anak keluar dari polapola berpikir egosentris. Yaitu, anak-anak dalam situasi-situasi bermain didorong untuk mempertimbangkan titik-titik pandang teman bermain mereka dan oleh karena itu menjadi kurang egosentris.14
Anak-anak belajar bekerjasama untuk
mencapai beberapa tujuan kelompok selama bermain. Mereka juga memiliki kesempatan selama bermain untuk belajar menunda kepuasan mereka sendiri selama beberapa menit. Stegelin (2005) meringkas keuntungan bermain dalam perkembangan sosial: Kompetensi sosial yang secara luas berkembang pada usia enam tahun, dipelihara dengan paling baik pada anak-anak kecil melalui sosiodrama dan bermain pura-pura dengan teman-teman sebayanya, interaksi sosial dalam latarlatar kelompok kecil, dan asimilasi keterlibatan rutin dan resiprok dengan temanteman sebaya dan orang dewasa yang peduli. a) Perkembangan Fisik Anak-anak mencapai kontrol gerak halus dan besar melalui bermain. Mereka dapat melatih semua skill gerak besar seperti berlari, melompat, dan meloncat sementara bermain. Anak-anak ketika bermain dapat didorong untuk mengangkat, mengangkut dan berjalan atau bergerak sebagai respon terhadap ritme. Mereka juga dapat melatih skill-skill gerak halus ketika mereka
menyatukan puzzle, atau memalu paku kedalam kayu. Tidak hanya anak-anak kecil yang membutuhkan bermain aktif; anak-anak yang lebih besarpun harus berpartisipasi dalam jenis bermain ini juga. Mereka dapat melempar, menangkap, menendang, dan lain-lain. b) Perkembangan Perilaku-Perilaku Bermain Perilaku bermain anak-anak berkembang dari masa kanak-kanak awal hingga masa kanak-kanak menengah. Setiap periode dicirikan oleh jenis-jenis
15
dan tujuan bermain yang berbeda. Oleh sebab itu seorang guru atau pendidik sudah selayaknya memahami tahapan atau fase-fase perkembangan anak. c) Masa Kanak-Kanak Awal Bermain pada periode ini adalah sensorimotor: mereka mengeksplorasi benda-benda dan orang-orang dan menyelidiki efek-efek tindakan mereka terhadap benda-benda dan orang-orang tersebut. Kira-kira pada akhir tahun
pertama, anak-anak mulai memperlihatkan prilaku-prilaku bermain seperti berpura-pura makan atau tidur. Mereka juga dapat memulai interaksi bermain dengan orang lain seperti bermain sembunyi-sembunyian. d) Pra Sekolah Anak-anak pra sekolah menghabiskan banyak waktu bermain mereka dalam bermain eksplorasi atau praktek. Mereka lebih memfokuskan pada proses, daripada produk bermain mereka. Sebagai contoh, mereka mungkin mencampur warna-warna cat, tetapi mereka lebih tertarik pada apa yang terjadi dengan bahanbahan tersebut, dan bukan pada hasil lukisannya. Anak-anak pra sekolah
seringkali terlibat dalam bermain sosiodrama atau fantasi, tetapi biasanya mereka memfokuskan pada pengalaman-pengalaman mereka sendiri. biasanya tertarik pada game-game dengan aturan. e) Kelas-Kelas Sekolah Dasar Awal Anak taman kanak-kanak dan sekolah dasar kelas satu terlibat dalam bermain sosiodrama yang melibatkan beberapa anak dalam episode bermain, dan mereka bermain tanpa membutuhkan objek-objek yang mereka gunakan menjadi begitu nyata. Sebagai contoh, sebuah balok, dapat menjadi apapun yang mereka Mereka juga
16
inginkan. Pada usia ini, bermain fantasi kemungkinan kurang memfokuskan pada peran-peran rumah dan lebih memfokuskan pada peran-peran yang diamati dalam masyarakat, seperti petugas polisi, atau cerita-cerita yang didengar atau dibacakan. Bermain praktek dan waktu yang dihabiskan untuk mengeksplorasi
benda-benda baru berkurang selama kelas-kelas sekolah dasar awal hingga hanya sekitar 15 persen bermain dapat dinamakan sebagai praktek. Kebanyakan anakanak kelas sekolah dasar memainkan bermain konstruksif, yaitu membangun atau membuat sesuatu. Game-game dengan aturan menjadi lebih penting dalam
bemain siswa-siswa kelas dasar. f) Masa Kanak-Kanak Pertengahan Lebih sedikit bermain konstruksif yang diamati pada anak-anak usia ini karena mereka lebih sedikit memiliki akses untuk materi-materi konstruksi dalam kelas. Bermain praktek menjadi lebih kognitif ketika anak-anak belajar menggunakan skill-skill literasi mereka untuk membuat cerita atau mempelajari informasi. Bermain sosiodrama cenderung menghilang dan digantikan dengan drama kreatif, seperti memperagakan cerita atau adegan. Anak-anak usia ini mungkin memperagakan adegan-adegan historis atau menciptakan drama untuk membantu mereka memahami fakta-fakta ilmiah. Game-game dengan aturan Game-game
mendominasi bermain anak-anak usia tujuh dan delapan tahun.
papan, game-game komputer, dan atletik, seperti sepak bola dan baseball, menjadi bagian-bagian penting dari pengalaman bermain mereka. Anak-anak usia ini
dapat menggunakan aturan-aturan game secara lebih fleksibel dan dapat
17
mengintegrasikan pengetahuan kognitif mereka dan kemampuan sosial secara lebih mudah. g) Bermain dalam Latar Sekolah Bermain di sekolah biasanya berbeda dari bermain di rumah dalam beberapa hal. Beberapa perbedaan antara keduanya diringkas pada Tabel dibawah ini. Memikirkan bermain di rumah dan di sekolah sepanjang dimensi-dimensi ini akan membantu guru menjelaskan kepada orangtua mengapa bermain di sekolah itu penting dan bukanlah duplikasi dari bermain di rumah. Tabel 1 Perbedaan-Perbedaan antara Bermain di Rumah dan di Sekolah BERMAIN RUMAH SEKOLAH Teman-teman Usia campuran Usia sebaya sebaya Dipilih sendiri Pemilihan dalam kelompok Ukuran Sendiri atau kelompok kecil Kelompok besar kelompok Materi dan Terbatas Pemilihan lebih besar peralatan Kurang dibatasi Bimbingan dan Seringkali difokuskan pada Memandu pengembangan pengawasan keselamatan konsep-konsep tertentu Mencontohkan prilaku-prilaku bermain Bertanya tentang belajar Interaksi orang Membelikan materi-materi Memfasilitasi bermain dewasa-anak Mendengarkan permintaan Berinteraksi dengan anak-anak anak perorangan Memahami isu-isu Menentukan tujuan anak keselamatan Komitmen waktu Harus sesuai dengan skedul Waktu yang dijadwal secara keluarga teratur Periode lebih pendek Periode lebih lama Perencanaan Dipandu oleh anggaran Pilihan-pilihan materi, keluarga peralatan Go play adalah petunjuk Evaluasi pengalaman umum Ruang Biasanya ruang tidur, ruang Ruang-ruang lebih luas untuk keluarga, atau ruang tamu memanjat, membangun balok, dll
18
Guru akan memilih pengalaman-pengalaman bermain yang sesuai dengan tujuan program-program mereka. Peran-peran guru dalam bermain dalam latar kelas sangatlah penting. Guru harus menjadi pengamat, penjelas, model,
evaluator dan perencana bermain (Bjorkland, 1978). Berikut adalah peran guru di sekolah : 1) Pengamat Ketika mengamati, guru harus mengawasi interaksi anak-anak dengan anak lainnya dan dengan benda-benda. Dia harus mengamati lamanya waktu anak-anak dapat mempertahankan episode bermain, dan harus mencari anak-anak yang memiliki kesulitan bermain atau bergabung dengan kelompok-kelompok bermain. Pengamatan ini harus digunakan nantinya dalam merencanakan pengalaman-pengalaman bermain tambahan, membuat keputusan-keputusan mengenai situasi bermain, dan membuat asesmen bermain terhadap anak perorangan. memberikan Phyfe-Perkins (1980) menyimpulkan bahwa jika latar akan dukungan untuk aktifitas-aktifitas yang sesuai dengan
perkembangan, maka guru harus terlibat dalam observasi yagn sistematis terhadap anak-anak yang sedang bermain. 2) Penjelas Aspek lainnya dari peran guru adalah penjelas. Jika anak-anak sedang memainkan menjadi penata rambut maka guru mungkin membantu mereka mengumpulkan item-item yang dapat digunakan untuk menggambarkan bendabenda yang ditemukan di tempat penata rambut. Guru mungkin memberikan
ilustrasi majalah yang akan membantu anak-anak membuat salon kecantikan. Jika
19
anak lain terlibat dalam mempelajari serangga, maka guru mungkin menyediakan kaset video tentang serangga sehingga anak dapat meciptakan kembali gerakan serangga dalam permainan mereka. 3) Pemberi contoh Guru yang menghargai bermain seringkali menjadi pemberi contoh prilaku-prilaku yang tepat dalam situasi-situasi bermain. Guru mungkin memilih untuk bergabung dengan permainan drama untuk dapat mencontohkan prilakuprilaku yang berguna ketika memasuki kelompok bermain dan respon-respon yang berguna untuk membantu berlanjutnya bermain 4) Evaluator Sebagai evaluator bermain, guru harus menjadi pengamat yang cermat dan ahli diagnosa untuk menentukan bagaimana peristiwa-peristiwa bermain yang berbeda memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak perorangan dan apakah pembelajaran yang sedang terjadi ketika anak-anak berpartisipasi dalam bermain. Evaluasi berarti bahwa materi, lingkungan, dan aktifitas harus dipertimbangkan secara cermat berdasarkan tujuan kurikulum, dan perubahan-perubahan harus dibuat ketika dibutuhkan. 5) Perencana Akhirnya, guru harus berfungsi sebagai perencana. Perencanaan
melibatkan semua pembelajaran yang dihasilkan dari mengamati, menjelaskan, dan mengevaluasi. Guru harus merencanakan pengalaman-pengalaman baru yang akan mendorong atau memperluas ketertarikan anak-anak. Ketika melakukan
20
perencanaan
yang
berkonstribusi
pada
perkembangan,
guru
harus
mempertimbangkan pedoman-pedoman berikut ini: Yakinkan anak-anak memiliki cukup waktu untuk bermain. Bantulah anak-anak merencanakan bermain mereka. Pantaulah kemajuan bermain. Pilihlah mainan-mainan yang tepat. Berikan tema-tema yang dapat diperluas dari satu hari ke hari berikutnya. Latihlah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Contohkan bagaimana tema-tema dapat saling berkaitan. Contohkan cara-cara yang tepat untuk menyelesailkan perselisihan.
3. Bermain Seringkali Bersifat Nonliteral Anak-anak ketika bermain dapat menangguhkan realitas, biasanya dengan kata-kata magis Mari kita berpura-pura. Waktu, latar dan karakter yang terlibat dalam bermain dapat dinegosiasikan dan tidak terikat pada realitas. Bermain juga tidak perlu menjadi mungkin; anak-anak mungkin berpura-pura terbang, atau menjadi monster. 4. Bermain Tidak Memiliki Tujuan Ekstrinsik Seandainya seorang anak sedang menyusun serangkaian huruf diatas papan magnetis. Jika tugas ini telah diberikan untuk tujuan membantu mereka
mempelajari urutan abjad, maka ini bukanlah bermain. Jika anak menyusun huruf-huruf berdasarkan tujuannya sendiri, maka ini dikatakan bermain.
21
Dalam bermain, proses, atau cara bukanlah hasil akhir, adalah yang paling penting. Hasil dari bermain tidaklah sepenting partisipasi didalamnya. 5. Pemain Memberikan Makna pada Bermain Anak-anak terkadang mengeksplorasi atau menggunakan materi-materi dalam cara-cara yang dispesifikasikan oleh orang lain, tetapi ketika bermain, mereka memberikan penafsiran mereka sendiri terhadap materi. Seorang anak
mungkin menggunakan 10 balo untuk membangun model-model angka jika diarahkan untuk melakukan hal tersebut oleh seorang dewasa. Namun jika dia dibiarkan untuk menggunakan materi secara bebas, maka dia mungkin menggunakannya untuk membuat rumah-rumahan atau jalanan. 6. Bermain Tidak Memiliki Aturan-Aturan Ekstrinsik Jika suatu aktifitas akan dianggap sebagai bermain, maka pemainnya harus dapat merubah aturan-aturan aktifitas ketika dibutuhkan. Sebagai contoh, anak-anak yang bermain dengan balok mungkin membuat aturan-aturan mengenai ruang untuk bangunan, tetapi aturan-aturan tersebut dirundingkan dengan pemain. 7. Ruang Lingkup dan Jenis Bermain Bermain dalam latar sekolah dapat digambarkan sebagai suatu kontinum mulai dari bermain bebas hingga bermain yang dipandu: Bermain bebas dapat didefinisikan sebagai bermain dimana anak-anak
memiliki sebanyak mungkin pilihan materi dan dimana mereka dapat memilih bagaimana menggunakan materi tersebut.
22
Bermain dipandu didefinisikan sebagai bermain dimana guru telah
memilih materi-materi yang dapat dipilih anak-anak agar mereka dapat menemukan konsep-konsep tertentu.
Bermain diarahkan adalah bermain dimana guru menginstruksikan anakMenyanyikan lagi, atau
anak bagaimaan untuk memenuhi tugas tertentu.
bermain game-game lingkaran adalah contoh-contohnya. Selain berpikir mengenai jenis bermain, dapat mendefinisikan bermain berdasarkan karakteristiknya. Ini termasuk motivasi personal, keterlibatan aktif, makna nonliteral, tujuan-tujuan tidak ekstrinsik, makna yang diberikan oleh pemain, dan tidak adanya aturan-aturan ekstrinsik. a) Bermain adalah Aktifitas yang Termotivasi secara Personal. Agar suatu aktifitas disebut bermain, maka pemainnya harus memilih untuk berpartisipasi. Jika seorang anak memilih suatu aktifitas, maka ini biasanya bermain, walaupun apa yang dilakukannya mungkin tampak sebagai kerja. Bermain harus selalu menjadi menyenangkan bagi partisipannya. b) Bermain adalah Aktif Semua pengalaman bermain membutuhkan beberapa keterlibatan aktif pada pemainnya. Bermain bukanlah aktifitas pasif, seperti menonton televisi,
walaupun bermain tidak membutuhkan keterlibatan fisik aktif. Anak-anak yang bermain terlibat dalam berpikir, mengatur, merencanakan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Jika keterlibatan itu pasif, maka aktifitas itu kemungkinan bukanlah bermain.
23
Bermain dapat didefinisikan dengan mempertimbangkan berbagai level dimana anak-anak terlibat didalamnya, termasuk bermain sosial, bermain dengan objek, dan bermain sosiodrama.
a) Bermain Sosial
Guru-guru yang mengamati anak-anak bermain akan memperhatikan beberapa level keterlibatan yang berbeda dengan anak-anak lainnya dalam episode bermain. Dalam studi klasiknya, Parten menggambarkan level-level ini
sebagai soliter, onlooker, paralel, asosiatif, dan koperatif. b) Bermain dengan Objek Piaget telah menggambarkan jenis-jenis bermain dengan objek yang berbedabeda: (1) Bermain praktek, atau bermain fungsional, adalah bermain dimana anak-anak mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan materi. (2) Bermain simbolis, adalah bermain dimana anak-anak mungkin mulai menggunakan bermain untuk menggambarkan sesuatu yang lain. (3) Dalam game dengan aturan, anak-anak mungkin bermain berdasarkan aturan-aturan yang telah mereka buat sendiri atau yang telah secara umum disepakati. (4) Game-game konstruksi digambarkan sebagai game yang berkembang dari bermain simbolis tetapi nantinya cenderung membentuk adaptasi murni. Level-level bermain objek tergantung pada kematangan dan pengalaman anak-anak. Ketika anak-anak matang, maka mereka menjadi lebih mampu untuk menggunakan materi-materi secara simbolis dan memainkan game dengan aturan-aturan yang diterima.
24
c)
Bermain Sosiodrama Bermain sosiodrama melibatkan sekelompok kecil partisipan yang memainkan peran-peran tertentu yang telah mereka pilih. Disebut oleh beberapa orang sebagai bermain fantasi, jenis bermain ini memungkinkan anak-anak untuk terlibat secara intelektual dengan banyak aspek kehidupan mereka sendiri. Bermain sosiodrama terutama penting dalam perkembangan kreatifitas, pertumbuhan intelektual, dan skill-skill sosial. Kemampuan untuk mengambil peran orang lain dan merubah perspektif adalah skill-skill dasar yang penting untuk pembelajaran akademik. Menurut Vygotsky, bermain berkembang dari bermain manipulatif anak-
anak kecil yang baru belajar berjalan menjadi bermain yang berorientasi secara sosial dari anak-anak pra sekolah dan taman kanak-kanak dan akhirnnya menjadi permainan. Vygostky yakin bahwa bermain sangatlah penting untuk
perkembangan anak dalam tiga cara: Bermain menciptakan zona perkembangan proksimal pada diri anak. Bermain memfasilitasi pemisahan pikiran dari tindakan dan objek. Bermain memfasilitasi pengembangan regulasi diri. Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bermain merupakan suatu cara dalam memberikan rangsangan kepada anak untuk melakukan aktivitas yang disebut dengan belajar. Melalui bermain anak akan memiliki konsep diri, bahwa dirinya memiliki teman serta harus mampu bertanggung jawab dalam permainan yang dilakukannya. 8. Tujuan Memahami Konsep Bermain25
Bermain
berkontribusi
pada
pertumbuhan
kognitif,
membantu
perkembangan sosial dan emosional, dan penting untuk perkembangan fisik. Ehart dan Leavitt (1985) menyatakan bahwa bermain memberikan anak-anak kecil kesempatan untuk menguasai banyak skill-skill dan konsep fisik, sosial dan intelektual dasar. Baik bermain eksplorasi, yaitu bermain dimana anak tidak memiliki tujuan kecuali eksplorasi, dan bermain yang ditentukan oleh aturan, yaitu bermain dimana anak memiliki tujuan seperti menemukan solusi untuk masalah, berkontribusi untuk pertumbuhan kognitif. Pertumbuhan kognitif didefinisikan sebagai suatu peningkatan dalam simpanan dasar pengetahuan anak, yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman-pengalaman dengan benda-benda dan manusia. Banyak studi melaporkan hubungan positif antara pengalaman bermain dan perkembangan kemampuan kognitif anak-anak. Kemampuan kognitif termasuk mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengamati, mendiskriminasikan, membuat prediksi, menarik kesimpulan, membandingkan dan menentukan hubungan sebab akibat. Kemampuan intelektual ini mendasari keberhasilan anak-anak dalam semua area akademik. Bermain juga membantu anak-anak mengembangkan kemampuan mengatur dan pemecahan masalah. Anak-anak yang bermain secara pasti memperlihatkan berpikir kreatif dan pemecahan masalah kreatif. Bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan dan spontan sehingga hal ini memberikan rasa aman secara psikologis pada anak. Begitu pula dalam suasana bermain aktif, dimana anak memperoleh kesempatan yang luas
26
untuk melakukan eksplorasi guna memenuhi rasa ingin tahunya, anak bebas mengekspresikan gagasannya memalui khayalan, drama, bermain konstruktif, dan sebagainya. Maka dalam hal ini memungkinkan anak untuk mengembangkan perasaan bebas secara psikologis Rasa aman dan bebas secara psikologis merupakan kondisi yang penting bagi tumbuhnya kreativitas. Anak-anak diterima apa adanya, dihargai
keunikannya, dan tidak terlalu cepat dievaluasi, akan merasa aman secara psikologis. Begitu pula anak yang diberikan kebebasan untuk mengekspresikan gagasannya. Keadaan bermain yang demikian berkaitan erat dengan upaya pengembangan kreativitas anak. Bermain memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kreativitasannya. Ia dapat bereksperimen dengan gagasan-gagasan barunya baik yang menggunakan alat bermain atau tidak. Sekali anak merasa mampu menciptakan sesuatu yang baru dan unik, ia akan melakukan kembali pada situasi yang lain. Kreativitas memberi anak kesenangan dan kepuasan pribadi yang sangat besar dan penghargaan yang memiliki pengaruh nyata pada perkembangan pribadinya. Menjadi kreatif juga penting artinya bagi anak usia dini, karena menambah bumbu dalam permainannya. Jika kreativitas dapat membuat permainan menjadi menyenangkan, mereka akan merasa bahagia dan puas Bermain memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan dorongan-dorongan kreatifnya sebagai kesempatan untuk merasakan obyek-obyek dan tantangan untuk menemukan sesuatu dengan cara-cara baru, untuk menemukan penggunaan suatu hal secara berbeda, menemukan hubungan yang
27
baru antara sesuatu dengan sesuatu yang lain serta mengartikannya dalam banyak alternatif cara. Selain itu bermain memberikan kesempatan pada individu untuk berpikir dan bertindak imajinatif, serta penuh daya khayal yang erat hubungannya dengan perkembangan kreativitas anak. 9. Urgensi Memahami Konsep Bermain Anak Usia Dini Bagi anak, bermain adalah suatu kegiatan yang serius, tetapi mengasyikan. Melalui aktivitas bermain, berbagai pekerjaanya terwujud. Bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak, karena menyenangkan bukan karena akan memperoleh hadiah atas pujian. Bermain adalah salah satu alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Bermain adalah medium, di mana si anak mencobakan diri, bukan saja dalam fantasinya tetapi juga benar nyata secara aktif. Bila anak bermain secara bebas, sesuai kemauan maupun sesuai kecepatannya sendiri, maka ia melatih kemampuannya. Permainan adalah alat bagi anak untuk menjelajahi dunianya, dari yang tidak ia kenali sampai pada yang ia ketahui dan dari yang tidak dapat diperbuatnya, sampai mampu melakukannya. Jadi, bermain mempunyai nilai dan ciri yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari seorang anak.a)
Bermain memiliki berbagai arti. Pada permulaan setiap pengalaman bermain memiliki unsur resiko. Ada resiko bagi anak untuk belajar berjalan sendiri, naik sepeda sendiri, berenang, ataupun meloncat. Betapa pun sederhana permainannya, unsur resiko itu selalu ada.
b)
Unsur lain adalah pengulangan. Dengan pengulangan, anak memperoleh kesempatan mengkonsolidasikan keterampilannya yang harus diwujudkannya28
dalam berbagai permainan dengan berbagai nuansa yang berbeda. Sesudah pengulangan itu berlangsung, anak akan meningkatkan keterampilannya yang lebih kompleks. Melalui berbagai permainan yang diulang, ia memperoleh kemampuan tambahan untuk melakukan aktivitas lain.c)
Fakta bahwa aktivitas permainan sederhana dapat menjadi kendaraan (vehicle) untuk menjadi hajat permainan yang begitu kompleks, dapat dilihat dan terbukti pada kala mereka menjadi remaja.
d)
Melalui bermain anak secara aman dapat menyatakan kebutuhannya tanpa dihukum atau terkena teguran, umpama: la bisa bermain peran sebagai ibu atau bapak yang galak, atau sebagai bayi atau anak yang mendambakan kasih sayang. Di dalam semua permainan itu ia dapat menyatakan rasa benci, takut, dan gangguan emosional.
Pada umumnya para ahli hanya membedakan atau mengkatergorikan kegiatan bermain tanpa secara jelas mengemukakan bahwa suatu jenis kegiatan bermain lebih tinggi tingkatan perkembangannya dibandingkan dengan jenis kegiatan lainnya. Adapun tahapan kegiatan bermain sebagai berikut: a) Permainan Sensori Motorik ( 3/4 bulan tahun) Bermain diambil pada periode perkembangan kognitif sensori motor, sebelum 3-4 bulan yang belum dapat dikategorikan sebagai kegiatan bermain. Kegiatan ini hanya merupakan kelanjutan kenikmatan yang diperoleh seperti kegiatan makan atau mengganti sesuatu. Jadi merupakan pengulangan dari hal-hal sebelumnya dan disebut reproductive assimilation. b) Permainan Simbolik ( 2-7 tahun)
29
Merupakan ciri periode pra operasional yang ditemukan pada usia 2-7 tahun ditandai dengan bermain khayal dan bermain pura-pura. Pada masa ini anak lebih banyak bertanya dan menjawab pertanyaan, mencoba berbagai hal berkaitan dengan konsep angka, ruang, kuantitas dan sebagainya . Seringkali anak hanya sekedar bertanya, tidak terlalu memperdulikan jawaban yang diberikan dan walaupun sudah dijawab anak akan bertanya terus. Anak sudah menggunakan berbagai simbol atau representasi benda lain. Misalnya sapu sebagai kuda-kudaan, sobekan kertas sebagai uang dan lain-lain. Bermain simbolik juga berfungsi untuk mengasimilasikan dan mengkonsolidasikan pengalaman emosional anak. Setiap hal yang berkesan bagi anak akan dilakukan kembali dalam kegiatan bermainnya. c) Permainan Sosial yang Memiliki Aturan ( 8-11 tahun) Pada usia 8-11 tahun anak lebih banyak terlibat dalam kegiatan games with rules dimana kegiatan anak lebih banyak dikendalikan oleh peraturan permainan. d) Permainan yang Memiliki Aturan dan Olahraga (11 tahun keatas) Kegiatan bermain lain yang memiliki aturan adalah olahraga. Kegiatan bermain ini menyenangkan dan dinikmati anak-anak meskipun aturannya jauh lebih ketat dan diberlakukan secara kaku dibandingkan dengan permainan yang tergolong games seperti kartu atau kasti. Anak senang melakukan berulang-ulang dan terpacu mencapai prestasi yang sebaikbaiknya.
30
Jika dilihat tahapan perkembangan bermain maka dapat disimpulkan bahwa bermain yang tadinya dilakukan untuk kesenangan lambat laun mempunyai tujuan untuk hasil tertantu seperti ingin menang, memperoleh hasil kerja yang baik. Sedang tahapan perkembangan bermain yang lain adalah sebagai berikut:a) Tahapan Penjelajahan (Exploratory stage)
Berupa kegiatan mengenai objek atau orang lain, mencoba menjangkau atau meraih benda disekelilingnya lalu mengamatinya. Penjelajahan semakin luas saat anak sudah dapat merangkak dan berjalan sehingga anak akan mengamati setiap benda yang diraihnya.b) Tahapan Mainan (Toy stage)
Tahap ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara 2-3 tahun anak biasanya hanya mengamati alat permainannya. Biasanya terjadi pada usia pra sekolah, anak-anak di Taman Kanak-Kanak biasanya bermain dengan boneka dan mengajaknya bercakap atau bermain seperti layaknya teman bermainnya.c)
Tahap Bermain (Play stage) Biasanya terjadi bersamaan dengan mulai masuk ke sekolah dasar. Pada masa ini jenis permainan anak semakin bertambah banyak dan bermain dengan alat permainan yang lama kelamaan berkembang menjadi games, olah raga dan bentuk permainan lain yang dilakukan oleh orang dewasa.
d) Tahap Melamun (Daydream stage)
Tahap ini diawali ketika anak mendekati masa pubertas, dimana anak mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermain yang tadinya mereka sukai dan
31
mulai menghabiskan waktu untuk melamun dan berkhayal. Biasanya khayalannya mengenai perlakuan kurang adil dari orang lain atau merasa kurang dipahami oleh orang lain. Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan spontan, dan perasaan gembira, tidak memiliki tujuan ekstrinsik, melibatkan peran aktif anak, memiliki hubungan sistematik dengan hal-hal diluar bermain (seperti perkembangan kreativitas), dan merupakan interaksi antara anak dengan lingkungannya, serta memungkinkan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya tersebut. .Masa bermain pada anak memiliki tahap-tahap yang sesuai dengan perkembangan anak, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor dan sejalan juga dengan usia anak. 10. Penerapan Konsep Bermain dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ketika bermain diterima sebagai alat untuk memenuhi kurikulum, anakanak dapat mempelajari skill-skill pengaturan, mengembangkan skill-skill bahasa oral, dan belajar mengambil resiko dalam memecahkan masalah. Bermain yang dapat membantu anak-anak dalam perkembangan mereka dapat dicapai di sekolah jika guru memberikan waktu, ruang, materi dan sangsi untuk aktifitas-aktifitas bermain. Ketika anak-anak mendapatkan pengalaman dan kematangan, bermain dalam kelas harus mencerminkan perubahan-perubahan ini. Anak-anak dengan usia yang berbeda dan level-level perkembangan yang berbeda menggunakan materi-materi dalam cara berbeda, sehingga guru harus waspada dalam
32
menyediakan materi-materi yang akan menantang anak-anak untuk berkembang lebih banyak dalam bermain.
a) Memilih Materi untuk Bermain Guru memiliki banyak pilihan ketika memilih materi-materi untuk bermain. Materi-materi open-ended (terbuka) yaitu yang memungkinkan banyak hasil dan penggunaan unik dalam setiap pertemuan, adalah yang paling berguna. Materi-materi tersebut mungkin berupa materi yang tidak memiliki struktur seperti pasir dan air, atau materi yang memiliki struktur seperti berbagai bentuk balok. Balok, pasir atau air tidak membatasi hasil-hasil bermain anak-anak. Oleh karena itu bersifat kondusif untuk berpikir kreatif dan pemecahan masalah pada anak-anak. Materi-materi yang memungkinkan anak-anak membuat pilihan bermain dan memungkinkan banyak hasil penting untuk lingkungan bermain yang paling baik. Banyak materi dapat dianggap terbuka jika memungkinkan anak-anak untuk menggunakannya dalam cara-cara berbeda. Sebagai contoh, guru dapat
menyediakan kotak, bola, atau roller yang akan membantu anak-anak mengembangkan konsep-konsep dalam ilmu fisika. b) Bermain sebagai Strategi Mengajar Bermain adalah salah satu strategi mengajar yang tersedia bagi para guru ketika mereka merencanakan pembelajaran anak-anak. Contoh-contoh berikut ini mengilustrasikan tujuan yang dapat dengan cepat dicapai melalui bermain:
33
Untuk mendorong anak-anak belajar tentang pakaian yang tepat untuk
cuaca. Untuk mendorong anak-anak belajar bagaimana membuat warna-warna
sekunder. Menggunakan pengalaman bermain sebagai strategi mengajar
mengharuskan guru untuk mengamati bagaimana anak-anak menggunakan materi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memandu berpikir dan refleksi anak-anak. Memilih bermain yang dipandu sebagai strategi mengajar tidak
menyiratkan bahwa bermain itu diberikan; namun berarti bahwa pemikiran yang cermat ditekankan pada pemilihan materi-materi dan intervensi dalam bermain anak. Cooper dan Dever (2001) menemukan bahwa bermain sosiodrama adalah alat yang unggul untuk mengintegrasikan kurikulum. Melalui kerja mereka, anakanak mengembangkan dan menikmati tema yang dipilih. Oleh karena itu, guru harus cermat ketika mengintervensi bermain anak-anak dan hindarilah mencoba memaksakan agenda mereka pada anak-anak. 11. Tahapan Pembelajaran Bermain Kegiatan pembelajaran pada anak Raudhatul Athfal harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. Oleh karena itu, perlulah kiranya guru dan orang tua mengetahui hakikat pembelajaran di RA. Pembelajaran di RA antara laian harus : a. Proses pembelajaran bagi anak usia dini adalah proses interaksi antar anak, sumber belajar dan pendidik dalam suatu lingkungan belajar tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.34
b.
Sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang bersifat aktif melakukan berbagai eksplorasi dalam kegiatan bermain, maka proses pembelajarannya ditekankan pada aktifitas anak dalam bentuk belajar sambil bermain. c. Belajar sambil bermain ditekankan pada pengembangan potensi di bidang fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), intelegensi (daya 35embe, daya cipta, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual), 35ember-emosional (sikap, perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi menjadi kompetensi/ kemampuan yang secara 35ember dimiliki anak. d.Penyelenggaraan pembelajaran bagi anak usia dini perlu memberikan rasa aman bagi anak usia tersebut. e.Sesuai dengan sifat perkembangan anak usia dini proses pembelajarannya di laksanakan secara terpadu. f.Proses pembelajaran pada anak usia dini akan terjadi apabila anak tersebut secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur pendidik. g.Program belajar mengajar bagi anak usia dini dirancang dan dilaksanakan sebagai suatu sistem yang dapat menciptakan kondisi yang menggugah dan 35ember kemudahan bagi anak usia dini untuk belajar sambil bermain melalui berbagai aktifitas yang bersifat konkrit, dan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan serta kehidupan anak RA. h.Keberhasilan proses pembelajaran anak usia dini ditandai dengan pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak-anak usia secara optimal dan dengan hasil pembelajaran yang mampu menjadi jembatan bagi anak usia dini untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan selanjutnya. (Balitbang, 2002 : 4 5). Uraian di atas kiranya dapat dipahami oleh pendidik, karena cukup banyak pendidik yang tidak sabar menghadapi anak-anak usia dini dalam hal ini RA, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran dan pelatihan. Mereka memperlakukan anak-anak usia dini dengan tuntutan-tuntutan kemampuan yang sering tidak tepat dan melebihi dari batas kemampuan yang dimiliki. Cukup banyak pelajaran dan pelatihan yang hanya membawa kebosanan, kejenuhan, kelelahan dan akhirnya menghasilkan kegagalan entah pada masa kanak-kanaknya entah ketika tumbuh sebagai remaja. Demikian pentingnya keberadaan RA sehingga pembelajaran harus berpusat pada anak. Artinya, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Dengan demikian, agar anak dapat mencapai tahapan perkembangan yang35
optimal, maka proses pembelajaran yang dilakukan harus memenuhi prinsipprinsip pembelajaran, yaitu; berangkat dari potensi yang dimiliki anak, belajar harus bermakna dan belajar dilakukan sambil bermain (Hartati: 2007). Selain dengan pemahaman tersebut, Prasetyono, dalam Hartati S. (2007) menyatakan bahwa : bermain bagi anak-anak bukan sekedar bermain, tetapi bermain merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran. Dalam bermain anak dapat menerima banyak rangsangan. Selain dapat membuat diri anak senang juga dapat menambah pengetahuan anak. Dalam proses belajar, anak-anak mengenalnya melalui permainan karena tidak ada cara yang lebih baik untuk merangsang perkembangan kecerdasan anak melalui kegiatan melihat, mendengar, meraba dan merasakan yang kesemuanya itu dapat dilakukan melalui kegiatan bermain. Sebagaimana diungkapkan pula oleh Conny R. Semiawan dalam Buletin PADU (2003): Bermain sangat berperan dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagi anak, bermain adalah suatu kegiatan yang serius namun mengasyikkan. Melalui aktivitas bermain, berbagai pekerjaan terwujud. Bagi anak, bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak karena menyenangkan bukan karena akan mendapat hadiah atau alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya. Kreativitas belajar anak melalui bermain sangat penting sekali untuk di pahami oleh orang tua dan guru di dalam memberikan stimulasi (rangsangan) kepada anak sedini mungkin sesuai dengan periodesasi perkembangannya. Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan tahapan perkembangan anak pra sekolah berlandaskan ajaran Islam memiliki tantangan tersendiri. Pemahaman guru tentang ajaran Islam yang komprehensif dan melibatkan seluruh domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotor perlu ditingkatkan. Islam harus menjadi landasan dalam pola pikir, pola jiwa, dan pola
36
perilaku guru sebagai pendidik. Para guru juga memerlukan informasi yang terbaru tentang teori-teori, kajian penelitian, maupun contoh pelaksanaan pembelajaran pada anak di lapangan yang berbasis ajaran Islam. Adanya pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan kemudian KTSP termasuk untuk RA dan PAUD, serta pendekatan pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk merupakan bentuk reformasi pendidikan nasional yang menambah wawasan guru dalam pembelajaran di kelas. Pada umumnya para ahli hanya membedakan atau mengkatergorikan kegiatan bermain tanpa secara jelas mengemukakan bahwa suatu jenis kegiatan bermain lebih tinggi tingkatan perkembangannya dibandingkan dengan jenis kegiatan lainnya. Adapun tahapan kegiatan bermain sebagai berikut: a) Permainan Sensori Motorik ( 3/4 bulan tahun) Bermain diambil pada periode perkembangan kognitif sensori motor, sebelum 3-4 bulan yang belum dapat dikategorikan sebagai kegiatan bermain. Kegiatan ini hanya merupakan kelanjutan kenikmatan yang diperoleh seperti kegiatan makan atau mengganti sesuatu. Jadi merupakan pengulangan dari hal-hal sebelumnya dan disebut reproductive assimilation. b) Permainan Simbolik ( 2-7 tahun) Merupakan ciri periode pra operasional yang ditemukan pada usia 2-7 tahun ditandai dengan bermain khayal dan bermain pura-pura. Pada masa ini anak lebih banyak bertanya dan menjawab pertanyaan, mencoba berbagai hal berkaitan dengan konsep angka, ruang, kuantitas dan sebagainya . Seringkali anak hanya sekedar bertanya, tidak terlalu memperdulikan jawaban yang
37
diberikan dan walaupun sudah dijawab anak akan bertanya terus. Anak sudah menggunakan berbagai simbol atau representasi benda lain. Misalnya sapu sebagai kuda-kudaan, sobekan kertas sebagai uang dan lain-lain. Bermain simbolik juga berfungsi untuk mengasimilasikan dan mengkonsolidasikan pengalaman emosional anak. Setiap hal yang berkesan bagi anak akan dilakukan kembali dalam kegiatan bermainnya. c) Permainan Sosial yang Memiliki Aturan ( 8-11 tahun) Pada usia 8-11 tahun anak lebih banyak terlibat dalam kegiatan games with rules dimana kegiatan anak lebih banyak dikendalikan oleh peraturan permainan. d) Permainan yang Memiliki Aturan dan Olahraga (11 tahun keatas) Kegiatan bermain lain yang memiliki aturan adalah olahraga. Kegiatan bermain ini menyenangkan dan dinikmati anak-anak meskipun aturannya jauh lebih ketat dan diberlakukan secara kaku dibandingkan dengan permainan yang tergolong games seperti kartu atau kasti. Anak senang melakukan berulang-ulang dan terpacu mencapai prestasi yang sebaikbaiknya. Jika dilihat tahapan perkembangan bermain maka dapat disimpulkan bahwa bermain yang tadinya dilakukan untuk kesenangan lambat laun mempunyai tujuan untuk hasil tertantu seperti ingin menang, memperoleh hasil kerja yang baik. Sedang tahapan perkembangan bermain yang lain adalah sebagai berikut:a.
Tahapan Penjelajahan (Exploratory stage)
38
Berupa kegiatan mengenai objek atau orang lain, mencoba menjangkau atau meraih benda disekelilingnya lalu mengamatinya. Penjelajahan semakin luas saat anak sudah dapat merangkak dan berjalan sehingga anak akan mengamati setiap benda yang diraihnya.b. Tahapan Mainan (Toy stage)
Tahap ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara 2-3 tahun anak biasanya hanya mengamati alat permainannya. Biasanya terjadi pada usia pra sekolah, anak-anak di Taman Kanak-Kanak biasanya bermain dengan boneka dan mengajaknya bercakap atau bermain seperti layaknya teman bermainnya.c.
Tahap Bermain (Play stage) Biasanya terjadi bersamaan dengan mulai masuk ke sekolah dasar. Pada masa ini jenis permainan anak semakin bertambah banyak dan bermain dengan alat permainan yang lama kelamaan berkembang menjadi games, olah raga dan bentuk permainan lain yang dilakukan oleh orang dewasa.
d. Tahap Melamun (Daydream stage)
Tahap ini diawali ketika anak mendekati masa pubertas, dimana anak mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermain yang tadinya mereka sukai dan mulai menghabiskan waktu untuk melamun dan berkhayal. Biasanya khayalannya mengenai perlakuan kurang adil dari orang lain atau merasa kurang dipahami oleh orang lain. Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan spontan, dan perasaan gembira, tidak memiliki tujuan ekstrinsik, melibatkan peran aktif anak, memiliki hubungan
39
sistematik dengan hal-hal diluar bermain (seperti perkembangan kreativitas), dan merupakan interaksi antara anak dengan lingkungannya, serta memungkinkan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya tersebut. .Masa bermain pada anak memiliki tahap-tahap yang sesuai dengan perkembangan anak, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor dan sejalan juga dengan usia anak.
12. Hal-hal yang harus Diperhatikan dalam Bermain Selain berpikir mengenai jenis bermain, kita dapat mendefinisikan bermain berdasarkan karakteristiknya. Ini termasuk motivasi personal,
keterlibatan aktif, makna nonliteral, tujuan-tujuan tidak ekstrinsik, makna yang diberikan oleh pemain, dan tidak adanya aturan-aturan ekstrinsik. a. Bermain adalah Aktifitas yang Termotivasi secara Personal. Agar suatu aktifitas disebut bermain, maka pemainnya harus memilih untuk berpartisipasi. Jika seorang anak memilih suatu aktifitas, maka ini biasanya bermain, walaupun apa yang dilakukannya mungkin tampak sebagai kerja. Bermain harus selalu menjadi menyenangkan bagi partisipannya. b. Bermain adalah Aktif Semua pengalaman bermain membutuhkan beberapa keterlibatan aktif pada pemainnya. Bermain bukanlah aktifitas pasif, seperti menonton televisi,
walaupun bermain tidak membutuhkan keterlibatan fisik aktif. Anak-anak yang bermain terlibat dalam berpikir, mengatur, merencanakan, dan
berinteraksi dengan lingkungan. Jika keterlibatan itu pasif, maka aktifitas itu kemungkinan bukanlah bermain. d. Bermain Seringkali Bersifat Nonliteral40
Anak-anak ketika bermain dapat menangguhkan realitas, biasanya dengan kata-kata magis Mari kita berpura-pura. Waktu, latar dan karakter yang terlibat dalam bermain dapat dinegosiasikan dan tidak terikat pada realitas. Bermain juga tidak perlu menjadi mungkin; anak-anak mungkin berpura-pura terbang, atau menjadi monster. e. Bermain Tidak Memiliki Tujuan Ekstrinsik Seandainya seorang anak sedang menyusun serangkaian huruf diatas papan magnetis. Jika tugas ini telah diberikan untuk tujuan membantu mereka
mempelajari urutan abjad, maka ini bukanlah bermain. Jika anak menyusun huruf-huruf berdasarkan tujuannya sendiri, maka ini dikatakan bermain. Dalam bermain, proses, atau cara bukanlah hasil akhir, adalah yang paling penting. Hasil dari bermain tidaklah sepenting partisipasi didalamnya. f. Pemain Memberikan Makna pada Bermain Anak-anak terkadang mengeksplorasi atau menggunakan materi-materi dalam cara-cara yang dispesifikasikan oleh orang lain, tetapi ketika bermain, mereka memberikan penafsiran mereka sendiri terhadap materi. Seorang anak mungkin menggunakan 10 balok untuk membangun model-model angka jika diarahkan untuk melakukan hal tersebut oleh seorang dewasa. Namun jika dia dibiarkan untuk menggunakan materi secara bebas, maka dia mungkin menggunakannya untuk membuat rumah-rumahan atau jalanan. g. Bermain Tidak Memiliki Aturan-Aturan Ekstrinsik Jika suatu aktifitas akan dianggap sebagai bermain, maka pemainnya harus dapat merubah aturan-aturan aktifitas ketika dibutuhkan. Sebagai contoh,
41
anak-anak yang bermain dengan balok mungkin membuat aturan-aturan mengenai ruang untuk bangunan, tetapi aturan-aturan tersebut dirundingkan dengan pemain.B. Kreativitas Anak Usia Dini
1.
Pengertian Kreativitas Kreativitas adalah suatu kondisi, sikap atau keadaan yang sangat khusus
sifatnya dan hampir tidak mungkin dirumuskan secara tuntas. Kreativitas dapat didefinisikan dalam beranekaragam pernyataan tergantung siapa dan bagaimana menyorotinya. Istilah kreativitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dikaitkan dengan prestasi yang istimewa dalam menciptakan sesuatu yang baru, menemukan cara-cara pemecahan masalah yang tidak dapat ditemukan oleh kebanyakan orang, ide-ide baru, dan melihat adanya berbagai kemungkinan Menurut Solso (Csikszentmihalyi,1996) kreativitas adalah aktivitas kognitif yang menghasilkan cara pandang baru terhadap suatu masalah atau situasi. Drevdal dalam Hurlock (1999), menjelaskan kreativitas sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Kreativitas ini dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman, mungkin mencakup pembentukan pola-pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya serta pencangkokan hubungan lama ke situasi baru dan mungkin mencakup pembentukan korelasi baru.
42
Bentuk-bentuk kreativitas mungkin berupa produk seni, kesusasteraan, produk ilmiah, atau mungkin juga bersifat prosedural atau metodologis. Jadi menurut ahli ini, kreativitas merupakan aktivitas imajinatif yang hasilnya merupakan pembentukan kombinasi dari informasi yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya menjadi hal yang baru, berarti dan bermanfaat. Munandar (1995) mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru, asosiasi baru berdasarkan bahan, informasi, data atau elemen-elemen yang sudah ada sebelumnya menjadi hal-hal yang bermakna dan bermanfaat. Sedangkan pendapat James Russell Lowel dalam Irina V. Sokolova, at.al., (2008: 261). Bahwa kreativitas bukan menemukan sesuatu, tapi membuat sesuatu darinya setelah ia ditemukan. Seringkali, kreativitas dianggap sebagai sesuatu yang artistik, agung, cerdik luar biasa, dan melampaui pemahaman. Bagaimanapun, kreativitas muncul dalam bentuk yang paling sederhana, seperti memformulasikan sebuah solusi terhadap suatu masalah sehari-hari; jika seseorang mengisi bensin di jalan, maka orang itu harus memikirkan suatu cara untuk mendapatkan tujuannya, dan ini memerlukan kreativitas meskipun hal itu dalam bentuk yang paling sederhana. Lalu apakah kreativitas itu? Morgan (1999) dalam Irina V. Sokolova, at, al., (2008: 262-263), setelah melakukan penelitian yang mendalam, mendaftar faktor kreativitas universal untuk menjadi sesuatu yang baru (Cropley, 1999). Sesuatu yang baru harus mencerminkan keaslian dan kebaruan. Dengan kata lain, kreativitas ini harus menciptakan suatu ide baru yang segar.
43
Sedang Stenberg dan Lubert (1995) menunjukkan bahwa sesuatu yang baru itu harus dianggap layak agar bisa dianggap kreatif. Sesuatu yang baru bisa berupa perpaduan antara dua pemikiran yang berbeda atau lebih. Contoh sederhana, Damienhirst adalah seniman kontroversial yang ingin dianggap kreatif dengan mengiris binatang menjadi potongan-potongan kecil, tapi banyak orang tidak menganggap hal itu sebagai tindakan kreatif meski telah menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinil. Banyak orang tidak mengakui faktor kelayakan dalam karya Hirst tersebut dan menganggapnya tidak berguna. Meski kreativitas dapat dilihat dari hasil yang diperoleh, kreativitas juga dapat dianggap dalam pengertian Proses. Weisberg (1986) menunjukkan bahwa kreativitas bisa juga didefenisikan sebagai pengunaan alat-alat baru dalam memecahkan masalah atau pemecahan masalah baru. Dr. Gunter von Hagens beberapa tahun yang lalu telah melakukan pertunjukkan tubuh-tubuh manusia yang telah di potong-potong dan transfigurasi. Profesor von Hagens adalah seorang Profesor medis di University of Heidelberg yang menyempurnakan injeksi plastik ke dalam jaringan tubuh. Ini adalah penggunaan alat yang baru untuk memecahkan masalah yang untuk memecahkan masalah tentang kebusukan dan terdistorsinya tubuh ketika menggunakan metode lama dalam
mempertahankan jaringan tubuh. Ini adalah penggunaan alat yang baru untuk memecahkan masalah tentang kebusukan dan terdistorsinya tubuh ketika menggunakan metode lama dalam mempertahankan jaringan tubuh manusia. Akhirnya, produk ini dianggap kreatif karena penggunaan alat-alatnya yang kreatif.
44
Sedangkan Ward, Finke, dan Smith (1995) mendefenisikan kreativitas dalam hasil yang dibuat, perbedaan dalam orang, berbagai tekanan yang memotivasi, dan proses di belakang kreativitas. Hasil yang dibuat haruslah baru dan segar serta merupakan contoh kreativitas yang paling jelas. Namun, mendefenisikan kreativitas pada orang, akan sedikit mengalami kesulitan; misalnya, sebagian orang dianggap lebih kreatif daripada orang lain. Disamping perbedaan-perbedaan yang inheren dalam setiap orang dalam melahirkan kreativitas, maka ada pula motivasi-motivasi berbeda dalam hal kreativitas, maka ada pula motivasi-motivasi berbeda dalam hal kreativitas (yakni, orang yang memang selalu diarahkan untuk mencipta). Pada akhirnya, proses kreativitas pun menjadi berbeda. Sebagian orang menyendirikan diri mereka, sedangkan sebagian yang lain mencari bimbingan dan nasehat. Ketika ada perdebatan tentang bagaimana memutuskan kreatif tidaknya suatu pekerjaan, maka yang paling layak untuk dijadikan patokan suatu karya itu kreatif adalah: sesuatu yang baru dan layak. Dua hal ini mungkin dipandang dalam hasil, alat, orang, motivasi dan atau proses, namun dua hal ini merupakan dua unsur yang sangat penting. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau suatu kombinasi baru berdasarkan unsur-unsur yang telah ada sebelumnya menjadi sesuatu yang bermakna atau bermanfaat dan harus mencerminkan keasliannya atau dengan kata lain baru dan layak serta original.
45
Kreativitas menjadi lebih mudah dilihat ketika orang dewasa mencoba untuk lebih perhatian pada proses kognitif anak daripada menghasilkan apa yang mereka capai dalam lapangan yang berbeda yang mereka lakukan dan pahami,oris Malaguzzi. Irina V. Sokolova, at.al., (2008:263). Tidak akan pernah ada orang yang jenius tanpa ada larutan kegilaan. (Aristoteles). Dalam Irina V. Sokolova. at.al., (2008 : 265). Ada sebuah perdebatan besar tentang apa yang membuat seseorang menjadi kreatif dan apa yang tidak. Hanya Arisrtoteles yang berkata dalam kutipan di atas, yang sebagian percaya bahwa orang yang jenius dan kreatif adalah tergantung pada penyakit gila atau penyakit mental. Vincent Van Gogh telah dianggap sebagai seorang mad genius (orang jenius yang gila) berkenaan dengan eksperimennya dalam memutilasi diri sendiri (yakni memotong telinganya sendiri) dan juga dengan karya seninya yang mengagumkan. Disebabkan karena misteri yang terkandung dalam kreativitas, maka orang tidak bisa memastikan sifat-sifat dasar apa yang membuat seseorang itu dianggap sebagai orang kreatif atau tidak. 2. Komponen Pokok Kreativitas Suharnan (dalam Nursisto, 1999) mengatakan bahwa terdapat beberapa komponen pokok dalam kreativitas yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Aktifitas berpikir, kreativitas selalu melibatkan proses berpikir di dalam diri seseorang. Aktifitas ini merupakan suatu proses mental yang tidak tampak oleh orang lain, dan hanya dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Aktifitas ini bersifat kompleks, karena melibatkan sejumlah kemampuan kognitif seperti persepsi, atensi, ingatan, imajeri, penalaran, imajinasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.46
b.
c.
d.
Menemukan atau menciptakan sesuatu yang mencakup kemampuan menghubungkan dua gagasan atau lebih yang semula tampak tidak berhubungan, kemampuan mengubah pandangan yang ada dan menggantikannya dengan cara pandang lain yang baru, dan kemampuan menciptakan suatu kombinasi baru berdasarkan konsepkonsep yang telah ada dalam pikiran. Aktifitas menemukan sesuatu berarti melibatkan proses imajinasi yaitu kemampuan memanipulasi sejumlah objek atau situasi di dalam pikiran sebelum sesuatu yang baru diharapkan muncul. Sifat baru atau orisinal. Umumnya kreativitas dilihat dari adanya suatu produk baru. Produk ini biasanya akan dianggap sebagai karya kreativitas bila belum pernah diciptakan sebelumnya, bersifat luar biasa, dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Menurut Feldman dalam Semiawan dkk, (1984), sifat baru yang dimiliki oleh kreativitas memiliki ciri sebagai berikut: 1) Produk yang memiliki sifat baru sama sekali, dan belum pernah ada sebelumnya. 2) Produk yang memiliki sifat baru sebagai hasil kombinasi beberapa produk yang sudah ada sebelumnya. 3) Produk yang memiliki sifat baru sebagai hasil pembaharuan (inovasi) dan pengembangan (evolusi) dari hal yang sudah ada. Produk yang berguna atau bernilai, suatu karya yang dihasilkan dari proses kreatif harus memiliki kegunaan tertentu, seperti lebih enak, lebih mudah dipakai, mempermudah, memperlancar, mendorong, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, dan mendatangkan hasil lebih baik atau lebih banyak.
Mencermati uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen pokok kreativitas adalah; (1) aktifitas berpikir, yaitu proses mental yang hanya dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan, (2) menemukan atau menciptakan, yaitu aktivitas yang bertujuan untuk menemukan sesuatu atau menciptakan hal-hal baru, (3) baru atau orisinal, suatu karya yang di hasilkan dari kreativitas harus mengandung komponen yang baru dalam satu atau beberapa hal dan, (4) berguna atau bernilai, yaitu karya yang dihasilkan dari kreativitas harus memiliki kegunaan atau manfaat tertentu. Sejak kecil hingga dewasa, perangsangan kreativitas sangat diperlukan
47
dan bisa dilakukan melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Hal ini menandakan bahwa kreativitas penting untuk dipupuk dan dikembangkan sejak usia dini, seperti yang dikemukakan oleh Munandar (1992:46), bahwa: Kreativitas yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam era pembangunan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan dan kejayaan masyarakat dan negara bergantung pada sumbangan kreatif, berupa ide-ide baru, penemuan penemuan baru, dan teknologi baru dari anggota masyarakatnya. Untuk mencapai hal itu, perlulah sikap dan prilaku kreatif dipupuk sejak dini, agar anak didik kelak tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan baru dan pencari kerja, tetapi mampu menciptakan pekerjaan baru (wiraswasta). Uraian diatas mengandung makna, bahwa kreativitas yang dipupuk dan dikembangkan sejak usia dini sangat penting dalam hidup manusia untuk dapat mewujudkan diri. Masa Golden Age merupakan masa yang memerlukan perhatian yang serius, karena merupakan suatu kekuatan sumber daya insani, yang sangat diperlukan kelak dikemudian hari baik dalam pemikiran logis dan penalaran, serta pemikiran, sikap, perilaku kreatif produktif. Untuk lebih menjelaskan pengertian kreativitas, berikut ini dikemukakan beberapa perumusan yang merupakan kesimpulan para ahli mengenai kreativitas menurut Munandar (1992: 47 ) bahwa: "Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Kreativitas (berpikir kreatif atau berpikir divergen) adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia-menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap sesuatu masalah, di mana penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban". Jadi secara operasional kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibilitas), dan orisinalitas dalam
48
berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu gagasan" Pengertian kreativitas di atas, mengandung makna bahwa kreativitas merupakan daya cipta sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru. Yang sesungguhnya apa yang diciptakan itu tidak perlu hal-hal yang baru sama sekali, tetapi merupakan gabungan (kombinasi) dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Artinya unsur-unsur seperti : pengalaman yang diperoleh seseorang selama hidupnya, pengetahuan yang pernah diperoleh (baik di bangku sekolah maupun yang dipelajarinya dalam keluarga dan masyarakat), masa persiapan (masa seorang anak duduk di bangku sekolah) karena pendidikan mempersiapkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah. Hal-hal tersebut, merupakan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Semua data (pengalaman) memungkinkan seseorang mencipta, yaitu dengan menggabungkan (mengkombinasi) unsur-unsurnya menjadi sesuatu yang baru dan salah satu hal yang menentukan sejauh mana seseorang itu kreatif adalah kemampuannya untuk dapat membuat kombinasi baru dari hal-hal yang sudah ada. Pengetahuan dan pengalaman memungkinkan untuk mencipta, lebih dari seseorang yang tidak mempunyai pengalaman dan pendidikan. Pendidikan selayaknya dapat membantu anak dalam mempersiapkan serta menyongsong masa depannya dengan penuh rasa percaya diri dan mempunyai keberanian dalam mengambil suatu resiko, hal ini memungkinkan seseorang untuk menjadi kreatif. Hurlock mengemukakan bahwa kreativitas dipandang
sebagai kreasi sesuatu yang baru dan orisinal secara kebetulan, sebagaimana
49
seorang anak yang bermain dengan balok-balok kayu membangun tumpukan yang menyerupai rumah kemudian menyebutnya rumah. Berfikir kreatif dinamakan berfikir divergen atau lateral. Disini terdapat banyak jawaban yang mungkin mengenai persoalan dan fikiran didorong untuk menyebar jauh dan meluas dalam mencari untuk memecahkan persoalan. Hurlock mengemukakan unsur karakteristik kreativitas sebagai berikut: Kreativitas mengarah ke penciptaan sesuatu yang baru, berbeda, dan karenanya unik bagi orang itu, baik itu berbentuk lisan atau tulisan, maupun konkret atau abstrak.
Kreativitas timbul dari pemikiran devergen, sedangkan konformitas dan pemecahan masalah sehari-hari timbul dari pemikiran konvergen. Kreativitas merupakan suatu cara berpikir, tidak sinonim dengan kecerdasan yang mencakup kemampuan mental selain berpikir. Kemampuan untuk mencipta bergantung pada perolehan pengetahuan yang diterima. Kreativitas merupakan bentuk imajinasi yang dikendalikan yang menjurus kearah beberapa bentuk prestasi, misalnya melukis, membangun dengan balok.
3. Ciri-ciri kreativitas Kreativitas sebenamya dapat terwujud dimana saja dan oleh siapa saja, tidak bergantung pada usia, jenis kelamin, keadaan sosio-ekonomi atau tingkat pendidikan tertentu. Hal ini menunjukkan jika ditinjau dari segi pendidikan, bahwa bakat kreatif itu perlu dilatih serta dapat dikembangkan dan perlu dipupuk sejak dini. Artinya, masa usia dini merupakan masa yang paling tepat untuk memupuk dan mengembangkan kreativitas agar dapat menjadi seorang manusia kreatif, yang sangat diharapkan dimasa mendatang. Supriadi (1994 : 7) mengemukakan, bahwa berdasarkan analisis faktor,
50
Guilford menemukan bahwa ada lima sifat yang menjadi ciri kemampuan berfikir kreatif: (1) Kelancaran (fluency), (2)Keluwesan (flexibility), (3)Keaslian (originality), (3)Penguraian (elaboration),(4)Perumusan kembali (redefinition). Yang dimaksud dengan kelancaran adalah kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Keluwesan adalah kemampuan untuk mengemukakan bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. Orisinalitas adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan dengan cara-cara yang asli, tidak klise. Elaborasi adalah kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara terinci. Redefinisi adalah kemampuan untuk meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah diketahui oleh banyak orang. Sedangkan karakteristik kreativitas ada lima sebagai berikut: 1) Kelancaran Kelancaran yaitu kemampuan untuk memberikan jawaban dan
mengemukakan pendapat atau ide-ide dengan lancar, 2) Kelenturan Kelenturan yaitu kemampuan untuk mengemukakan berbagai alternatif dalam pemecahan masalah, 3) Keaslian Yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide atau karya yang asli hasil pemikiran sendiri, 4) Elaborasi Kemampuan untuk memperluas ide dan aspek-aspek yang mungkin tidak terpikirkan atau terlihat oleh orang lain,
51
5) Keuletan dan Kesabaran Keuletan dalam menghadapi rintangan, dan kesabaran dalam menghadapi suatu situasi yang tidak menentu merupakan aspek yang mempengaruhi kreativitas. Karakteristik kepribadian menjadi kriteria untuk mengidentifikasikan orang-orang kreatif . Kepribadian menurut Guilford, dalam (Supriadi, 1994: 13), meliputi dimensi kognitif (yaitu bakat) dan dimensi non kognitif (yaitu minat, sikap dan kualitas temperamental). Menurut teori ini, orang-orang kreatif memiliki ciri kepribadian yang secara signiftkan berbeda dengan orang yang kurang kreatif. Dalam kaitannya dengan unsur aptitude dan non aptitude, (Semiawan, 1984) dalam (Akbar et.al., 2001 : 4), mengemukakan bahwa : Kreativitas merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kreativitas meliputi, baik ciri-ciri aptitude seperti kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility) dan keaslian (originality) dalam pemikiran iniupun ciri-ciri (nonaptitude), seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan dan selalu ingin mencari pengalaman-pengalaman baru. Uraian diatas, mengemukakan bahwa ciri-ciri kreativitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ciri-ciri kreativitas yang berhubungan dengan kemampuan berpikir atau berpikir kreatif (berpikir divergen) adalah kemampuan menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, yang penekanannya pada kuantitas, ketepatgunaan dan keragaman jawaban. Ciri lainnya adalah ciri-ciri yang menyangkut sikap dan perasaan seseorang yang disebut dengan ciri afektif dan kreativitas. Lebih lanjut Munandar (1992: 34), mengemukakan ciri-ciri kreativitas52
adalah sebagai berikut : Dorongan ingin tahu besar Sering mengajukan pertanyaan yang baik Memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah Bebas dalam menyatakan pendapat Mempunyai rasa keindahan Menonjol dalam satu bidang seni Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya tidak mudah terpengaruh orang lain Rasa humor tinggi Daya imajinasi kuat Keabsahan (orisinalitas) tinggi (tampak claim ungkapan gagasan, karangan, dan sebagainya; dalam pemecahan masalah menggunakan cara-cara orisinal, yang jarang diperlihatkan anak-anak lain). Dapat bekerja sendiri Senang mencoba hal-hal baru Kemampuan mengembangkan atau memerinci suatu gagasan (kemampuan elaborasi)".
Lebih lanjut (Munandar, 1992: 51), mengemukakan ciri-ciri afektif yang sangat esensial dalam menentukan prestasi kreatif seseorang adalah : Rasa ingin tahu, tertarik terhadap tugas-tugas majemuk yang dirasakan sebagai suatu tantangan, berani mengambil resiko untuk membuat kesalahan atau dikritik oleh orang lain, tidak mudah putus asa, menghargai keindahan, mempunyai rasa humor, ingin mencari pengalamanpengalaman baru, dapat menghargai baik diri sendiri maupun orang lain dan sebagainya. Yang dimaksud dengan rasa ingin tahu adalah mengajukan banyak pertanyaan, selalu terdorong untuk mengetahui lebih banyak. Bersifat imajinatif yaitu mampu memperagakan atau membayangkan hal-hal yang tidak atau belum pernah terjadi. Merasa tertantang oleh kemajemukan yaitu lebih tertarik pada tugas-tugas yang sulit. Sifat berani mengambil resiko yaitu berani memberikan jawaban meskipun belum tentu benar. Sifat menghargai yaitu menghargai
53
kemampuan dan bakat sendiri yang sedang berkembang. Ciri-ciri kreativitas di atas merupakan ciri kreativitas yang berhubungan dengan kemampuan berpikir seseorang, dengan kemampuan berpikir kreatif. Makin kreatif seseorang, ciri tersebut makin dimiliki. Namun memiliki ciri-ciri berpikir tersebut belum menjamin perwujudan kreativitas seseorang. Ciri lain yang berkaitan dengan perkembangan afektif seseorang sama pentingnya agar bakat kreatif seseorang dapat terwujud. Ciri-ciri yang nenyangkut sikap dan perasaan seseorang disebut ciri afektif dari kreativitas. Motivasi atau dorongan dari dalam untuk berbuat sesuatu, pengabdian atau pengikatan diri terhadap suatu tugas termasuk ciri afektif kreativitas. Semua ciri-ciri tersebut diatas, merupakan hal yang menentukan dalam mewujudkan kreativitas seseorang, dalam hal ini termasuk anak usia dini. Kreativitas merupakan salah satu kemampuan yang hendak dikembangkan dalam kebanyakan program untuk anak. Model Treffinger merupakan salah satu model untuk mendorong belajar kreatif dalam (Munandar 1999: 173), ModelTreffinger menggambarkan susunan tiga tingkat yang dimulai dengan unsur-unsur dasar dan menanjak ke fungsi-fungsi berpikir kreatif yang lebih majemuk. Model Treffinger terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut : basic tools, practice with process, working real problems. Tingkat 1, basic tools atau teknik kreativitas
tingkat I, meliputi keterampilan berpikir divergen dan teknik kreatif. Keterampilan dan teknik ini mengembangkan kelancaran dan kelenturan berpikir serta kesediaan mengungkapkan pernikiran kreatif kepada orang lain. Dengan ciri kognitif : kelancaran, kelenturan, orisinalitas, pemerincian,
54
pengenalan dan ingatan. Sedangkan ciri afektif : rasa ingin tahu, kesediaan untuk menjawab, keterbukaan terhadap pengalaman, keberanian mengambil resiko, kepekaan terhadap masalah, tenggang rasa terhadap kesamaan, kedwiartian, percaya diri. Tingkat 2, practice with process, teknik ini memberi kesempatan kepada anak untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari pada tingkat I dalam situasi praktis. Untuk tujuan ini maka digunakan strategi seperti bermain peran, simulasi dan studi kasus. Kemahiran dalam berpikir kreatif menuntut anak memiliki keterampilan untuk melakukan fimgsi seperti analisis, evaluasi, imajinasi dan fantasi. Tingkat 3, working with real problems menerapkan keterampilan yang dipelajari pada tingkat pertama terhadap tantangan dunia nyata. Anak menggunakan kemampuannya dengan cara yang bermakna untuk kehidupannya. Anak tidak hanya belajar keterampilan berpikir kreatif, tetapi juga bagaimana menggunakan informasi ini dalam kehidupan mereka.
55
BAB III PROSEDUR PENELITIAN A. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif yaitu penggambaran atau pemberian makna secara sistimatis,factual dan akurat mengenai data. Sukmadinata (2005:72) menjelaskan bahwapenelitian dengan metode deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Senada dengan pendapat di atas, Surachmad(1990:134)menyebutkan bahwa penyelidikan dengan memakai metode deskriptif bertujuan untuk memecahkan permasalahan pada masa sekarang,di antaranya adanya penyelidikan dengan penuturan,analisis dan klasifikasi. Metode biasa disebut juga metode analitik. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah(natural setting). Sebagian ahli menyebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya56
metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiono,2006:16). Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat pemikiran, persepsinya.Menurut Sukmadinata(2008:94)bahwapemahaman diperoleh melalui analisis berbagai keterkaitan dari partisipan, dan melalui penguraianpemaknaan partisipantentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. Pemaknaan partisipan meliputi perasaan, keyakinan, ide-ide, pemikiran dan kegiatan dari partisipan. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang aatau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penggunaan metode deskkriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipilih karena gejala-gejala, informasi, peristiwa, keteranganketerangan dari hasil pengamatan selama berlangsungnya proses penelitian mengenai manajemen kebijakan publik bidang keagamaan di tengah
kompleksitas perubahan sosial-budaya di kabupaten Sukabumi ini, akan lebih tepat bila diungkap dalam bentuk kata-kata. Di samping itu, data yang didapat lebih mendalam dan lebih sebenarnya. Data yang pasti yang merupakan suatu
57
nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.
B. Sumber dan Jenis Data Data dalam penelitian tergolong kepada data kualitatif. Yaitu data-data yang dikumpulkan lebih cenderung dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka, jadi hasil penilitian dan analisisnya berupa uraian. Sumber data dalam penelitian kualitatif meliputi kata-kata dan tindakan (sumber data utama), sumber data tertulis, dokumen dan data statistik. Penentuan sampel didasarkan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengembilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini didasarkan pada orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan dari penelitian ini. (Sugiyono, 2007 : 218) Sumber data penelitian ini adalah Kepala PAUD Al-Fitriyah Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, guru-guru, peserta didik, dan pelaksanaan pembelajaran di PAUD tersebut. Data lain adalah orang tua dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Moleong (2000: 3) menegaskan, bahwa sesuai dengan data yang dipilih, maka jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, tulisan, foto dan statistik. Jenis-jenis data tersebut di atas semuanya dapat digunakan sebagai informasi yang diperlukan. Perlu ditegaskan, bahwa keterangan berupa kata-kata atau cerita dari informan penelitian yang diwawancari dan tindakan yang diamati, dalam penelitian kualitatif dijadikan
58
sebagai data utama (primer), sedangkan tulisan, foto, dan data statistik dari berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dijadikan sebagai data pelengkap (sekunder). Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau informan yang diwawancarai. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain.C. Tempat Penelitian
Tempat dari penelitian ini adalah PAUD Al-Fitriyah yang berlokasi di Jl. Bojonggaling Desa Sasagaran Kp. Cikabonpedes Kabupaten Sukabumi. D. Instrumen Penelitian Instrumen adalah alat dari sebuah penelitian, instrumen penelitian ini adalah : 1. Pedoman wawancara (terlampir) 2. Pedoman observasi (terlampir) 3. Pedoman kepustakaan (terlampir)
E. Teknik Pengumpulan Data Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode kualitatif partisipatif (fieldwork relation). Di sinilah diperlukan kehadiran peneliti untuk tahu langsung kondisi dan fenomena di lapangan, tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh (Danim, 2002:
59
122). Oleh karena itu, pada tahap ini, peneliti menggunakan tiga macam metode atau teknik pengumpulan data, yaitu: 1. Observasi Partisipatif Menurut Margono (2004:158), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Subagyo (2004: 63), mengemukakan bahwa observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejalagejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan, dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan. Sedangkan Sugiono dalam Hariwij