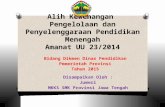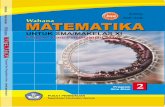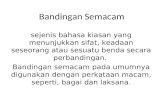alih wahana lirik lagu, cerpen, video klip malaikat juga tahu karya ...
SASTRA BANDINGAN: ALIH WAHANA
-
Upload
ingeu-widyatari-heriana -
Category
Documents
-
view
375 -
download
14
description
Transcript of SASTRA BANDINGAN: ALIH WAHANA
PENGARUH LATAR BELAKANG PENULIS TERHADAP ISI, TOKOH UTAMA DAN SUDUT PANDANG DALAM NOVELISASI BIOLA TAK BERDAWAI
INGEU WIDYATARI HERIANA 180110110055 SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS PADJADJARAN 2012
Alih wahana (transformasi) novelisasi, perubahan dari suatu jenis kesenian berupa film menjadi jenis kesenian lain berupa novel. Kebalikan dari pembahasan sebelumnya, ekranisasi, perubahan dari suatu jenis kesenian berupa novel menjadi jenis kesenian lain berupa film. Alih wahana tetap memberikan peluang boleh dikatakan sebagai bahan penelitian mata kuliah sastra bandingan. Membandin-bandingkan benda budaya yang beralih wahana itu merupakan kegiatan yang sah dan bermanfaat untuk pemahaman yang lebih dalam mengenai hakikat sastra. Misalnya, menambah wawasan untuk saya dan pembaca laporan ini mengenai bagianbagian dalam film Biola Tak Berdawai karya sutradara Sekar Ayu Asmara yang diubah, ditambahkan, dikurangi, atau diganti dalam Novel Biola Tak Berdawai (2004) karya Seno Gumira Ajidarma. Adegan-adegan yang ditampilkan dalam film oleh sutradara tidak begitu jelas dan rinci, bahkan kadang-kadang terjadi begitu saja, tetapi ada perbedaan dari kedua karya tersebut. Karena novelisasi sesungguhnya karangan yang sepenuhnya kata-kata, Seno lebih merincikan adegan-adegan yang sudah ada dalam film. Beliau menggugah citraan pembaca dengan bahasa tulisan. Sebaliknya, sesungguhnya film merupakan sama sekali bukan sekedar rekaman gambar walaupun pasti rekaman gambar, penciptaan imaji sama dengan sastra, namun film dari katakata dilanjutkan dengan rekaman gambar. Film menggunakan teknik visualisasi, teknik yang dikuasai pengarang untuk menciptakan visualisasi menjadi imaji. Namun, tidak setiap kata-kata yang ada dalam novel diterapkan semuanya dalam bentuk imaji karena akan memerlukan durasi yang sangat lama. Hal tersebut akan membosankan bagi penonton dan terkesan berlebihan untuk dimunculkan dalam film yang akan disaksikan oleh penonton.
Seno Gumira Ajidarma yang latar belakangnya memang seorang penulis Indonesia terkenal, sangat cocok mengalihwahanakan film yang berhawa klasik tersebut. Dialog-dialog dalam film mendekati bahasa sastra, terutama dialog Mbak Wid saat meramal dan dialog romatis Bhisma dan Rinjani. Cerpen-cerpennya, Pelajaran Mengarang (1993), buku kumpulan cerpen Di Larang Menyanyi di Kamar Mandi (1995), Penembak Misterius (1993), Atas Nama Malam (1999), Iblis Tidak Pernah Mati (1999), Aku Kesepian Sayang, Datanglah menjelang Kematian (2004), Saksi Mata (1995), Sebuah Pertanyaan Untuk Cinta (1996), Linguae (2007). Roman Jazz, Parfum dan Insiden (1996), Kitab Omong Kosong (2004), Nonfiksi Ketika Jurnalisme Di Bungkam Sastra Harus Bicara (2004), Wisanggeni Sang Buronan (2000), Layar Kata (Festival Film Indonesia 1973-1992), komik Jakarta 2039 (2001), Taxi Blues (2001), puisi Mati Mati Mati (1975), Bayi Mati (1978), Catatan-catatan Mira Sato (1978).
Seno Gumira Ajidarma berlatar belakang asli seorang penulis, lebih giat dalam karyanya, Biola Tak Berdawai. Beliau menovelisasi film Biola Tak berdawai dengan sukses. Berhasil menggugah citraan (imajinasi) pembaca dengan kata-kata yang telah diubah dari bahasa gambar. Adegan-adegan dalam film dikembangkan olehnya menjadi sangat rinci dan dengan kata-kata yang sangat indah. Hal tersebut yang menjadikan kisah Rinjani, Dewa, Bisma, dan Mbak Wid menjadi lebih beragam, seru, dan berbelit, serta ceritanya menjadi lebih panjang menjadikan novelnya tebal. Contohnya, Adegan Dewa hilang di pantai saat berjalan-jalan bersama ibunya, Rinjani. Sekumpulan anak-anak normal mengejek Dewa, Rinjani langsung menasehati anak-anak, ketika Rinjani kembali Dewa langsung menghilang. Sementara dalam novel dijelaskan kronologisnya sangat rinci dan sangat diindah-indahkan.
... Ketika ibuku menuntunku di pantai tadi, kami berpapasan dengan dua anak yang membawa alat-alat untuk mencari ikan dan ketam. Mereka memandang kami, kemudian memperhatikan aku dan saling berpandangan. Mereka mempercakapkan aku dengan suara keras, bahkan seperti sengaja memperdengarkannya di celah deburan ombak. Seperti anak tuyul. Mukanya aneh. Anak genderuwo. Mereka kemudian lari sambil tertawa-tawa Ibuku marah besar Kamu tunggu di sini ya? Ibuku lari memburu kedua anak itu, tetapi aku tidak peduli, karena aku hanya melihat cahaya dan merasa melayang di antara cahaya. Aku merasa melangkah menuju suatu tempat yang sangat kukenal. Apakah aku pernah berada di tempat yang aku tuju? Bagaimana mingkin? Selamanya aku selalu berada di tangan ibuku. Namun, kali ini aku melangkah sendiri,betul-betul dengan tubuhku sendiri, menuju ke lingkaran-lingkaran cahaya yang bagaikan membentuk sebuah gua. Di dalam gua cahaya aku melayang menuju ke suatu tempat yang seolah-olah sudah pernah ku datangi. Dewa! Di mana kamu Dewa! Aku mendengar debur ombak. Aku menghirup bau angin yang asin. Aku juga tahu ibuku memanggilku. Tetapi aku berada di lorong cahaya yang tidak kunjung berakhir. Aku seperti tersedot oleh pusaran cahaya yang putih kemilau. Aku tidak melihat apa-apa tenggelam dalam cahaya... Ibuuuu! Aku berteriak di dalam hati, ibuku tak akan mendengarku dengan telinganya, tapi aku yakin teriakanku sampai ke hatinya. Dewa! Bagaimana Kamu sampai di sini? Seperti dikatakan mbak Wid, aku sedang memegang kerang yang kosong. Penghuninya sudah pergi entah ke mana, kemungkinan besar sudah mati. Di belakang ibuku, dua anak kecil tadi dimarahinya, ikut mencari aku dibalik batu kerang. Mungkin itu karmanya, mungkin itu penanda... Dia sedang berjalan
ke alam yang lain. Mungkin dalam kehidupan yang sebelumnya Dewa terlahir sebagai kerang, Kata Mbak Wid sambil lalu sembari main kartu. Karma. Karmapala. Hmm. ... (Ajidarma, 2004: 46-47).
Cerita pewayangan dalam film diselipkan sedikit-sedikit. Contohnya, dalam dialog Mbak Wid saat meramal Bhisma. Mbak Wid berkata bahwa Bhisma petarung Arjuna dan hanya dirinya sendirilah yang bisa menentukan atau menjadikan kematiannya. Di Novel, Seno menceritakan bisa dalam satu bab hanya tentang pewayangan karena memang sejatinya Beliau seorang penulis. Latar belakangnya juga sebagai Magister Ilmu Filsafat Universitas Indonesia dan Doktor Ilmu Sastra Universitas Indonesia membuat dirinya mengarang novel dengan menambah-nambahkan analogi kehidupan dengan budaya dan sastra dari filsafat kehidupan pewayangan. Berikut beberapa bab Seno karang hanya mengenai pewayangan. Bab 10, Drupadi, Puteri Pancala, bab 16, Bisma yang memilih saat kematiannya sendiri, dan bab 21, Senja di tepi Sungai. Di film, Sekar Ayu menjadikan Rinjani sebagai tokoh utama, sehingga sudut pandang diambil dari tokoh Rinjani. Seno untuk novelnya, menjadikan Dewa sebagai tokoh utama, sehingga sudut pandang dari tokoh Dewa.
Hal tersebut disebabkan dalam film, tokoh Dewa yang menderita kecacatan menjadikan Dewa tokoh yang pasif tidak mungkin untuk berperan penuh dalam tiap-tiap adegan (berakting). Tidak seperti tokoh Rinjani yang normal atau aktif memungkinkan untuk berperan penuh dalam tiap-tiap gerakan adegan. Karena dalam novel hanya berupa bahasa tulisan, tidak ada adegan yang aktif diperankan oleh tiap-tiap tokoh, Dewa dijadikan sebagai tokoh utama oleh Seno dan disoroti menjadi sudut pandang untuk novelnya.