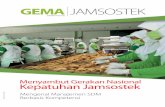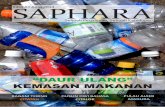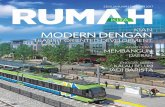Saphara Edisi 3, Januari 2014
-
Upload
kappa-fikom-unpad -
Category
Documents
-
view
261 -
download
1
description
Transcript of Saphara Edisi 3, Januari 2014

SAPHARASebuah Perjalanan, Sebuah Kehidupan
Edisi #3 Januari 2014
TAK BUAS LAGI LAUTKU
TEBING SIUNGSurga di Yogyakarta
JATINANGOR“Gak” Butuh Sawah
CIKONENGAdu Bagong & Anjing
KAREUMBIWisata Alam & Konservasi

SAPHARA | 2

Salam Pemred Tahun 2013 telah berakhir, namun ekploitasi
alam seperti perdagangan sirip hiu, penjualan
binatang secara ilegal, dan pengurangan ruang
terbuka hijau dalam hal pembangunan yang
dilakukan secara berlebihan masih kerap terjadi.
Padahal, alam merupakan sumber daya yang paling
berharga bagi manusia. Bukan hanya itu, ia nantinya
menjadi warisan yang berharga bagi anak cucu kita.
Pada edisi kali ini, Saphara mencoba meng-
ungkapkan berbagai eksploitasi alam yang terjadi di
sekitar Explorer, khususnya di Indonesia. Semoga hal
ini dapat menjadi “Eliksir” yang mampu mengurangi
berbagai eksploitasi alam.
Dimas Jarot Bayu, Pemimpin Redaksi.
SAPHARAPemimpin Umum: Thaariq Basthun Natsi
Pemimpin Redaksi: Dimas Jarot Bayu - Redaktur Opini: Ryan HilmanRedaktur Bahasa: Sri Oktika Amran - Redaktur Perjalanan: Dina Aqmarina Yanuary
Redaktur Desa dan Budaya: M. Rifqy Fadil - Redaktur Acara dan Lingkungan: Alfath AzizRedaktur Foto dan Perwajahan: Panji Arief Sumirat
Reporter: Olfi Fitri Hasanah, Tyas Dwi Pamungkas, Dhanang David Aritonang, Deando Dwi Permana, Hafiyyan, Nelly
Yustika E.B. , Dwi Desilvani, Andhika Soeminta, Nadia Septriani, Mutiara Annisa, Istnaya Ulfathin, Dwy Anggraeni, Wini Selianti, Bonny Rizaldy
Advertising: M. Hanif Izzatullah (08561610062)Email: [email protected]
Daftar Isi
Alamat Redaksi:Gedung Student Centre (SC) Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat
UNIVERSITAS PADJADJARANFAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
KLUB AKTIVIS PEGIAT DAN PEMERHATI ALAM
@kappafikom
SAPHARA | 3
Salam Pemred 3
Perjalanan 4Lokal
Desa 6
Lintas Kota 8
Laporan 10Utama
Wisata 18Budaya
Halaman 20
Acara 22
Foto 24Essay
Operasi 30
Kata 32Kita
Buah 34Pena
Refleksi 36
Etalase 38
Review 39

TEGAL ALUN
Teks: Dimas Jarot Bayu & Dina Aqmarina YanuaryFoto: Dimas Jarot Bayu
PERJALANAN LOKAL
SAPHARA | 4
Taman Buru Masigit-Kareumbi:Wisata Alam, Konservasi, dan Rusa
ebagai satu-satunya taman buru di Sregional Jawa-Bali dari 15 taman buru yang ada di Indonesia,
Kawasan Konservasi Taman Buru Masigit Kareum-bi (TBMK) kini dapat menjadi hiburan alam yang menarik bagi Explorer. Dengan menempuh perjalanan se lama dua jam dar i Bandung menggunakan kendaraan bermotor, pada kawasan di daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung ini Explorer dapat melakukan aktivitas outbound di bumi perkemahan atau rumah pohon di tengah hutan pinus.
Explorer juga dapat melakukan aktivitas hiking yang telah direncanakan oleh pihak pengelola menuju kampung wisata Cigumentong atau menuju Curug Sabuk dengan berjalan kaki. Selain itu, terdapat pula aktivitas bersepeda gu-nung, bumi perkemahan, bersampan, ataupun body board/tubing untuk melengkapi kegiatan liburan Explorer.
Aktivitas-aktivitas tersebut
merupakan salah satu program yang
tengah digalakkan dari keenam program
yang lahir atas perjanjian antara Balai
Besar Konservasi Sumber Daya Alam
(BBKSDA) dengan pihak Wanadri untuk
pengelolaan TBMK. Darmanto, Wakil Di-
rektur TBMK menjelaskan bahwa
seluruh program tersebut turut melibat-
kan masyarakat di sekitar Kareumbi.
“Sebagian besar pegawai yang
dipekerjakan di kawasan ini berasal dari
Desa Leuwiliyang. Selain dapat mengu-
rus ladang, mereka juga dapat pengha-
silan tambahan dari bekerja di sini,” ujar
Darmanto.
Selain agar masyarakat mudah
mencari pekerjaan dari kawasan TBMK,
pria yang mulai mengelola TBMK sejak
2009 ini juga menambahkan bahwa
pemberdayaan masyarakat lokal ini pula
ditujukan agar sedikit kemungkinan
masyarakat untuk merusak kawasan
konservasi dan bahkan ikut serta dalam
proses pelestariannya.
Pada kawasan TBMK terdapat
pula program “Wali Pohon Masigit-
Kareumbi” dan “Pemulihan Populasi
Buru dan Wisata Buru”. Program “Wali
Pohon Masigit-Kareumbi” merupakan
program penanaman dan penghutanan
kembali dengan cara mengajak Explorer
untuk melakukan pembibitan pohon.
Dalam program ini, Explorer
dapat membeli bibit seharga Rp50.000,-
per orang atau Rp100.000,- per komu-
nitas dan menanamnya di areal konser-
vasi dengan nama penanam dan garansi
tiga tahun. Hanya saja, program pena-
naman ini hanya diadakan pada bulan
November sampai Maret saat musim
penghujan. Tapi, proses pemesanan dan
pendaftaran Wali Pohon dapat dilaku-
kan kapanpun karena sistem online yang
sudah diterapkan pihak pengelola.
Penanaman dan penghutanan
kembali ini diadakan karena pihak
pengelola melihat bahwa sekitar 750 Ha
lahan yang berada di TBMK berada da-
lam kondisi kritis akibat penebangan.
Pasalnya pada periode 1998 saat dikelo-
la oleh PT Prima Multijasa Sarana, terjadi
penebangan ilegal secara besar-
Teks & Foto: Deando Dwi P. & Wini Selianti

SAPHARA | 5
pemindahan tangan pengelolaan kawa-
san kepada Wanadri.
Pada kawasan ini pula terdapat
areal penangkaran rusa. Warman,
Petugas Penjaga Penangkaran menjelas-
kan bahwa rusa yang ditangkarkan di
wilayah TBMK ini dikembangbiakan un-
tuk nantinya diburu atau sebagai ma-
kanan hewan karnivora di kebun bina-
tang. Namun, hal ini belum dilakukan
mengingat usia serta kuota rusa yang
belum layak.
“Saat ini rusa di sini masih tujuh
ekor, nanti kalau sudah memenuhi kuota
baru bisa diburu,” Ujar Warman.
Program penangkaran dan
perburuan rusa ini diadakan karena di-
rasa penting oleh pihak pengelola untuk
direalisasikan mengingat hanya TBMK
lah satu-satunya kawasan taman buru di
regional Jawa-Bali dari 15 taman buru di
Indonesia. Explorer dapat berkunjung
melihat rusa yang ada dalam kawasan
ini. Bahkan, Explore bisa pula ikut
memberi makan rusa atau sekedar
mengelus rusa yang ada di penangkaran
ini.
Bolehkah Rusa Diburu dan Diperda-
gangkan?
Rusa merupakan hewan yang
dilindungi berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999
tentang Pengawetan Tumbuhan dan
Satwa Liar. Berdasarkan peraturan
tersebut, bagi pelaku yang diketahui
melanggar akan diancam hukuman
maksimal 5 tahun penjara dan denda
sebesar Rp100 juta.
Lantas, bagaimana dengan
perburuan dan perdagangan rusa yang
dilakukan di TBMK? Ternyata hal
t e r s e b u t t e t a p d i p e r b o l e h k a n
mengingat rusa yang diburu dan
diperdagangkan di kawasan TBMK
merupakan rusa penangkaran. Menurut
Direktorat Jenderal Peternakan
mengacu pada Peraturan Pemerintah
N o m o r 8 ta h u n 1 9 9 9 te nta n g
Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar,
rusa dibenarkan pemanfaatannya
a p a b i l a m e r u p a ka n r u s a h a s i l
penangkaran pada keturunan kedua,
bukan rusa liar. Dengan kata lain, status
dilindungi yang dimiliki oleh rusa hilang.
M e s k i d i p e r b o l e h k a n ,
Darmanto menjelaskan bahwa tetap
saja ada peraturan yang harus dipatuhi
saat melakukan perburuan rusa di
kawasan TBMK, misalnya membayar
biaya perburuan, tidak menembak rusa
yang masih bayi dan tidak menembak
kaki rusa.
“Bila ketahuan melanggar aturan
tersebut , maka pemburu akan
dikenakan denda oleh pihak pengelola
TBMK,” ujar pria yang pernah menjabat
sebagai Ketua Wanadri. Syarat untuk melakukan
perburuan rusa di TBMK pun juga harus
menjadi anggota Persatuan Penembak
Indonesia (Perbakin) dan memiliki surat
izin kepemilikan senjata pribadi. Hal ini
serupa dengan syarat berburu yang
dimiliki oleh Perbakin. Meki, anggota
Persatuan Penembak Indonesia
(Perbakin) sendiri menjelaskan bahwa
tidak sembarang orang diperbolehkan
untuk berburu. Ada banyak syarat yang
harus dipenuhi untuk bisa melakukan
perburuan secara legal.
“Kalau ingin berburu, harus
mempunyai Kartu Tanda Anggota Per-
bakin dulu. Syarat mendapatkannya
diantaranya harus memiliki izin
kepemilikan untuk senjata pribadi,
tergabung dalam anggota resmi klub
Perbakin dengan memiliki sponsor
anggota Perbakin minimal 5 tahun,”
tuturnya.

SAPHARA | 6
Teks dan Foto: Nelly Yustika E.B.
JATINANGOR “GAK” BUTUH SAWAHTeks & Foto: Olfi Fitri Hasanah & Muhammad Rifqy Fadil
“Rumah indekos saya kan pakai pompa air, kedalaman sumurnya 15 meter yang merupakan kedalaman
maksimal untuk kos-kosan biasa. Perhitungannya sih cukup untuk 24 kamar. Ternyata hanya cukup 14 kamar saja.
Apalagi kemarau, susah dapat air. Katanya gara-gara air banyak diambil sama apartemen deket kosan saya di
daerah Jalan Sayang,” ucap Ilman, Mahasiswa Universitas Padjadjaran yang merupakan penghuni salah satu rumah
kos yang terletak tidak jauh dari Apartemen paling besar di Jatinangor.
partemen tersebut hingga saat Ai n i a d a l a h s a t u - s a t u n y a
apartemen yang telah berdiri
tegak di Kecamatan Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Sebuah kawasan pendidikan di timur
kota Bandung yang jaraknya hanya
sekitar 7 km dari batas wilayah kota
Bandung dengan Kabupaten Bandung.
Nama Jatinangor sebagai nama
kecamatan baru dipakai sejak lebih dari
satu dekade yang lalu atau sekitar tahun
2000-an. Di masa penjajahan Belanda
silam, Jatinangor merupakan hamparan
perkebunan teh dan karet yang didi-
rikan oleh Willem Abraham Baud pada
tahun 1844. Perusahaan yang bernama
Maatschappij tot Exploitatie der Baud-
Landen ini menguasai tanah seluas 962
hektar yang membentang seluruh
Jat inangor hingga kaki Gunung
Manglayang, yang kini menjadi
pembatas antara Kabupaten Sumedang
dengan Kabupaten Bandung.
Kini, kawasan tersebut berubah
menjadi sebuah kawasan pendidikan
dimana berdiri beberapa institusi
pendidikan tinggi, seperti Institut
Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),
Institut Koperasi Indonesia (Ikopin),
Universitas Padjadjaran (Unpad), serta
yang terakhir berdiri ialah Institut
Teknologi Bandung (ITB) yang berencana
memindahkan sebagian besar kegiatan
belajar mengajar dari kota Bandung ke
Jatinangor. Dengan luas wilayah mencapai
26,2 Km², serta jumlah penduduk
sebanyak 87.974 Jiwa (belum termasuk
pendatang seperti maha-siswa, staff
pengajar, dan pengusaha dari daerah
lain), Laju Pertumbuhan Penduduk
Kecamatan Jatinangor termasuk tinggi
secara relatif yaitu sebesar 2,04% per
tahun (tahun 2007), melampaui rata rata
Laju pertumbuhan penduduk Kabu-
paten yang hanya sebesar 1,9 % per
tahun. Berdasarkan data yang dirilis
oleh situs Kecamatan Jatinangor, pada
Triwulan Kedua tahun 2009 tercatat
sebagian besar wilayah jatinangor
digunakan sebagai lahan pemukiman
ataupun wilayah pengembangan
kawasan pendidikan. Untuk wilayah
pemukiman dan pengembangan
kawasan pendidikan saja mencapai
1.217 ha atau 54,1% dari luas wilayah
Kecamatan Jatinangor. Sedangkan
sisanya berupa sawah dan kebun 615 ha
atau seluas 27,3% luas wilayah, serta
sisanya terdapat kolam 14 ha, Hutan
akyat 273 Ha, Hutan Negara 130 Ha dan
penggunaan lainnya 125,15 Ha.
Ruang Terbuka Semakin Terdesak Semakin bertambahnya jumlah
mahasiswa dari tahun ke tahun, mau tak
mau membuat infrastruktur penunjang
bagi mahasiswa menjadi hal yang logis.
Merambahnya bangunan-bangunan
permanen seperti rumah kos, aparte-
men, dan perumahan menjadikan
daerah bagian di Kabupaten Sumedang
DESA

SAPHARA | 7
berkembang pesat dalam perekonomi-
an. Penampakan kios-kios makanan,
penyedia jasa cuci, serta penyewaan
rumah kos di pinggiran jalan besar
hingga gang kecil merupakan hal yang
lazim ditemui. Dijadikannya Jatinangor seba-
gai kawasan pendidikan mendorong pu-
la pesatnya pertumbuhan berbagai sek-
tor. Apalagi ketika keberadaannya
menggantikan fungsi ruang terbuka
hijau termasuk lahan persawahan yang
sebelumnya dengan mudah dapat
ditemui.. Namun, hal ini kerap berimbas
ke berbagai aspek lingkungan di
Jatinangor. Prof. Dr. Udjianto Pawitro,
M.Ars, staff pengajar Jurusan Teknik
Planologi Institut Teknologi Nasional,
menjelaskan terkait impact dari
berkembangnya wilayah Jatinangor, dari
sebuah wilayah perkebunan hingga kini
menjadi wilayah pendidikan dengan
pembangunan yang pesat. “Yang terjadi di wilayah
Jatinangor dapat disebut sebagai
fenomena pembangunan daerah
Kampung Kota. Jumlah pendatang luar
daerah meningkat, kebutuhan akan
tempat tinggal pun mengalami hal yang
sama,” ujarnya saat dihubungi (29/11)
lalu. Ia melanjutkan, lahan-lahan
d imanfaatkan untuk memenuhi
permintaan kebutuhan hunian. Harga
lahan akan meningkat, puncak akibatnya
adalah pembangunan dikuasai oleh “Si
Juragan” yang memil ik i modal .
Beberapa aspek yang harus diperhatikan
seperti sosio-budaya, sosio-politik, dan sosio-ekonomi tidak lagi menjadi
pedoman. Namun, adanya pembangun-
an yang kurang memperhitungkan
aspek-aspek tersebut dapat menyebab-
kan ket idakseimbangan kondis i
lingkungan. “Seharusnya memang feno-
mena pembangunan kampung menjadi
kota tersebut dapat dikontrol oleh pe-
merintah daerah yang berwenang
mengeluarkan Izin Mendirikan Bangu-
nan (IMB),” tutup Udjianto saat dimintai
komentar.
Perlu Ada Perhatian Khusus Hal senada juga diungkapkan
oleh Lioni Beatrix, Government Liaison
Assistant International Organization for
Migration (IOM) Bandung. Organisasi
dunia yang bergerak dalam bidang
transmigrasi bagi penduduk ini, melalui
Lioni, mengatakan bahwa untuk kasus
Jatinangor, dalam memberikan Izin
Mendirikan Bangunan, pemerintah
daerah harus sudah memperhitungkan
seberapa solid tanah di lokasi tersebut
layak didirikan bangunan. Termasuk soal
makin potensi berkurangnya Ruang
Terbuka Hijau (RTH) yang secara
perlahan tapi pasti mulai menggerogoti
wilayah ini. Jawa Barat yang termasuk
daerah rawan bencana menjadi
pandangan lain dalam menyikapi
pembangunan Jatinangor. “Dalam
pembangunan itu ada Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi
sebuah landasan. Selain itu, jika
dikaitkan dengan potensi bencana, saya
kira pemerintah daerah sudah memiliki
kebijakan dalam mengeluarkan izin
mendirikan bangunan,” singkatnya saat
menjawab pertanyaan via telepon
seluler kepada Saphara awal Desember
lalu. Banyaknya masalah terkait
sosial dan lingkungan, seperti kasus
dialirkannya limbah apartemen ke
sumur-sumur milik warga, kualitas air
yang dianggap mulai memburuk, jumlah
RTH yang terus berkurang membuat
awal Maret 2013 kemarin dikeluarkan
Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2013.
Salah satu isinya mengatur soal luas
maksimum pemukiman serta luas
minimum RTH. Untuk sisi utara
Jatinangor misalnya, dipatok minimal 40
% luas wilayah harus terdapat daerah
konservasi untuk resapan air. Menanggapi hal-hal tersebut,
Wakil Bupati Sumedang sekaligus
Pelaksana tugas Bupati Sumedang, H.
Ade Irawan mengatakan, semua
bangunan yang berdiri di Jatinangor
telah mendapatkan izin pemerintah
yang sebelumnya sudah dikaji dampak
positif dan negatifnya. Pihaknya
mengakui banyak hal yang diluar dugaan
terjadi saat pembangunan di Jatinangor
kebelakangan ini.
“Kami terus membenahi terkait
permasalahan-permasalahan tersebut.
Tentunya hal ini membutuhkan
dukungan dari berbagai pihak, termasuk
para mahasiswa yang tinggal di
Jatinangor. Intinya, kami akan memulai
pengkajian ulang dan penataan ulang
Jatinangor, terutama soal tata ruang
tersebut. Saya ingin Jatinangor jadi ikon
Kabupaten Sumedang,”singkatnya
kepada Saphara saat ditemui awal
Desember lalu.

SAPHARA | 8
LINTAS KOTA
TEBING SIUNG
SURGA PEMANJAT TEBINGDI YOGYAKARTA
Teks: Tyas Dwi P. & Nelly Yustika E.B.Foto: Hafiyyan
eberapa waktu lalu Tim Saphara Bmelakukan perjalanan ke Tebing
Siung. Tim berangkat dari
Bandung dengan menggunakan kereta
malam Kahuripan tujuan Kediri yang
berangkat dari Stasiun Padalarang. Sete-
lah itu, tim turun di Stasiun Lempuyang-
an dan melanjutkan perjalanan pukul
09.30 WIB dari kota Yogyakarta dan tiba
di Tebing Siung yang berlokasi di Ke-
camatan Tepus, Kabupaten Wonogiri
pukul 12.20 WIB. Tidak ada kendaraan
umum yang mampu mengakses tebing
tersebut, jadi Explorer harus menyiap-
kan kendaraan jika ingin berkunjung ke
sana.
Berbeda dengan jenis batuan di
tebing yang tersebar di Jawa Barat, jenis
batuan tebing Pantai Siung adalah
gamping. Jenis batuan ini terbentuk dari
endapan laut dangkal dengan bahan
utama material organik terumbu/cang-
kang hewan yang memiliki kalsium, kan-
dungan kimia CaCo3 karena tektonisme
(pengangkatan). Tinggi tebing beragam,
tapi tebing tertinggi di sini kurang lebih
15 meter.
Tim Saphara menjajal bebera-
pa jalur yang ada, dibuka dengan
“Welcome to Siung” yang legendaris
karena merupakan jalur pertama di
tebing Siung. Jalur ini tidak tinggi, hanya
tiga bolt. Namun tantangan langsung
didapatkan karena di jalur ini terdapat
overhang yang cukup menyulitkan.
Cukup lama kami mengutak-
atik jalur ini dan berusaha melewati
overhang. Bagi Explorer yang biasa
“bermain” di tebing Jawa Barat seperti
Citatah atau Gua Pawon, penyesuaian
diri atas kontur harus dilakukan dengan
cepat. Jenis batuan karang yang ada di
semua jalur terasa mengiris kulit telapak
tangan.
Jalur selanjutnya yang tim jajal adalah sebuah jalur di blok D yang tak bernama. Lokasinya berada di rekahan dua tebing yang cukup sempit. Jalur ini
tak kalah menantangnya dengan
“Welcome to Siung” karena terdapat
belokan yang cukup tajam antar bolt.
Dari semua jalur sebelumnya, jalur yang
paling mudah dilalui terletak di Blok I.
1000 Jalur dan Polemiknya
Saat ini diperkirakan ada 70
sampai 80 jalur permanen atau jalur
sport dan beberapa jalur aid climbing
(jalur yang tidak dipasangi pengaman
hanger permanen) di Tebing Siung.
Beberapa jalur yang ada di Tebing Siung
ternyata termasuk dalam 1000 jalur
yang dipasang oleh Tedi Ixdiana.
“Dari 70-an jalur yang ada di
Siung hampir 60 jalur tim kami yang
membuatnya pada era 2001-2002,” ujar
Tedi Ixdiana.
Pembuatan jalur panjat di Tebing Siung termasuk dalam rangkaian ekspedisi pembuatan 1000 jalur panjat tebing untuk Indonesia. Dalam pem-buatannya sendiri, menurut Tedi relatif ada yang sulit dan ada yang mudah.
Banyak yang mengatakan Yogyakarta adalah surga bagi pencinta budaya. Namun, sebenarnya masih ada surga lain yang tersimpan 70 km di selatan kota budaya ini. Surga itu bernama Tebing Siung, cocok untuk Explorer penikmat tebing alam dengan keindahan dan ratusan jalur yang dimilikinya.

SAPHARA | 9
Salah satu kesulitannya datang dari
masyarakat di daerah Tebing Siung itu
sendiri.
Tedi menceritakan, awalnya
ada beberapa penduduk yang kurang
setuju dengan kedatangan mereka
untuk membuat jalur pemanjatan di
sana. Hal ini dikarenakan penduduk
tersebut tidak tahu maksud atau
tujuan dari pembuatan jalur tersebut.
“Namun tim kami pada saat
itu berupaya menyampaikan maksud
dari pembuatan ja lur kepada
masyarakat setempat. Akhirnya
bertahap mereka pun mengerti dan
menyambut baik,” jelas salah satu
pemanjat terbaik Indonesia ini.
Lalu, bagaimana menurut
ahli mengenai pemasangan alat
panjat di tebing? Bombom Rachmat,
salah satu dosen Fakultas Geologi
Universitas Padjadjaran mengatakan
kalau hanya sebatas memasang alat
panjat di tebing tidak akan merusak
tebing begitu saja.
“Pemasangan alat pun hanya
memiliki kedalaman 4 cm. Selama itu
tidak merusak dan mengubah
kestabilan tebing itu sendiri, ya tidak
masalah,” ujar Bombom.
“Berbeda dengan jenis
batuan di tebing yang
tersebar di Jawa Barat,
jenis batuan tebing Pantai
Siung adalah gamping
”Bombom juga menjelaskan,
tidak ada tata cara khusus dalam
memasang sebuah alat di tebing.
Menurut Bombom, pemasangan alat
di tebing menjadi pilihan terakhir para
pamanjat bila di ketinggian tertentu
sudah tidak ada rekahan tebing yang
bisa digunakan lagi.
Berkegiatan di alam me-
nuntut kita untuk lebih arif dan bijak
dalam menggunakannya. Jangan
sampai kegiatan kita di alam bukan
mengeksplorasi alam, tapi malah
mengeksploitasi alam itu sendiri.

SAPHARA | 10
LAPORAN UTAMA

SAPHARA | 11
TAK BUAS LAGI LAUTKUHewan buas, musuh bagi para peselancar, perenang
cepat, menakutkan, serta berdarah dingin, merupakan gambaran umum hiu, si predator laut di mata sebagian orang. Hiu yang menempati puncak
rantai makanan seakan menjadi ancaman bagi hewan-hewan laut lainnya. Namun, siapa sangka kini si predator laut semakin tidak berdaya, terbelit
jala-jala manusia.
Teks & Foto:Dhanang David Aritonang
Dessy Indah W. Silitonga (Kontributor)

SAPHARA | 12
“Perdagangan hiu paling gencar terjadi
di tahun 1998 sampai tahun 2000-an.
Setelah kita sudah turun produksi ikan di
laut dan krisis moneter sedang terjadi,
nelayan mulai menangkap hiu untuk
menutupi biaya melaut yang cukup
besar di masanya,” ujar Alexander M. A.
Khan, S.Pi , M.Si , selaku dosen
Penangkapan Ikan Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadja-
ran.
Di dunia tercatat ada 1.044
spesies yang termasuk jenis hiu, 181
diantaranya tercatat dalam daftar
terancam punah atau Red List milik
International Union for Conservation of
Nature (IUCN). Sementara 488 lainnya
tidak memiliki data.
Hiu diburu karena siripnya yang
memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sirip
hiu tersebut diolah menjadi berbagai
hidangan. Dalam kebudayaan Cina, sirip
hiu menjadi sebuah barang yang mewah
dan dapat diolah menjadi sup sirip hiu.
Di luar negeri seperti di Jepang
dan Taiwan, hiu ditangkap dan diperla-
kukan dengan cara yang tidak layak. Sirip
hiu dipotong ketika hiu dalam keadaan
hidup dan hiu yang tanpa sirip tersebut
dibuang kembali ke laut. Alhasil, hiu
yang tanpa sirip tidak mampu berenang,
berburu, maupun bertahan hidup
hingga akhirnya mati tenggelam di dasar
laut karena asfiksia akibat tekanan air
laut yang tinggi.
Di Indonesia, sejak tahun 1970,
hiu sudah menjadi usaha sampingan
nelayan dari usaha perikanan lainnya.
Rata-rata nelayan menggunakan alat
tangkap pancing rawai. Sedangkan
tahun 1987 ketika harga sirip hiu
berkembang cukup pesat, nelayan
menjadikan hiu sebagai ikan komoditi
utama untuk ditangkap dengan meng-
gunakan alat tangkap seperti jaring
insang apung (drift gill net), rawai
permukaan (surface longline), rawai
dasar (bottom longline) dan jaring hiu
(dahulu dikenal sebagai jaring trawl).
Pada tahun 1988 tercatat
perdagangan sirip hiu di Indonesia
sebesar 36.884 ton, dan tahun 2000
meningkat hampir dua kali lipat yaitu
sebesar 68.336 ton. Oleh sebab itu, bisa
dikatakan perdagangan sirip hiu paling
massive terjadi awal tahun 2000
sekaligus menempatkan Indonesia
sebagai negara urutan teratas dalam
pembantaian si predator laut ini.
Indonesia termasuk dalam
Coral Triangle di dunia. Selain Indonesia,
negara seperti Malaysia, Papua Nugini,
Timor Leste, Filipina, Kepulauan
Salomon, Vietnam, dan Fiji masih
menjadi bagian dari kawasan Coral
Triangle tersebut.
Coral Triangle adalah pusat
kehidupan laut di dunia yang luas
wilayahnya mencakup 6 juta kilometer
persegi di beberapa kawasan laut di
enam negara. Coral Triangle memiliki
76% spesies karang, 37% spesies ikan
karang, dan spesies yang bernilai komer-
sil seperti tuna, paus, lumba-lumba,
pari, penyu, dan hiu yang menjadi
predator utama mereka.
(www.oseanografi.lipi.go.id. Oseana,
Volume XXX, Nomor 1, 2005 : 1-8)
Maka, kawasan Coral Triangle
merupakan habitat utama hiu. Hiu
berkembang biak dan mencari makan di
sekitar karang di mana ikan-ikan kecil
sebagai santapannya banyak terdapat di
sana. Tak heran, kurang lebih 400 spesies
hiu dari 1.044 spesies yang ada di dunia
terdapat di Indonesia.
“Hiu diburu karena siripnya
yang memiliki nilai
ekonomis yang tinggi. Sirip
hiu tersebut diolah menjadi
berbagai hidangan
” “Sebenarnya karena h iu
merupakan hasil tangkap sampingan,
tidak ada data-data yang pasti tentang
berapa jumlah hiu yang diekspor
maupun dikonsumsi oleh masyarakat.
Hanya hasil tangkapan utama saja yang
tercatat seperti tuna, cakalang, tenggiri,
tongkol,” kata Alexander.
Tamparan ombak, kerasnya
benturan karang, dan tuntutan hidup
yang semakin mencekik membuat
nelayan semakin buas bahkan lebih buas
daripada si predator laut itu sendiri. Kini,
siapa yang tahu berapa jumlah mereka
yang tersisa di lautan Nusantara. Semua
masih menjadi misteri.
LAPORAN UTAMA

SAPHARA | 13
dara gersang khas daerah Upesisir menemani perjalanan
menuju ke Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) Karangsong, Indramayu.
Aktivitas rutin dan transaksi antar
nelayan dengan para pengepul ikan
sedang berlangsung pada saat itu.
Berbagai hasil tangkapan seperti
tongkol, tenggiri, dan cakalang menjadi
komoditas utama para nelayan. Selain
ikan-ikan yang menjadi komoditas
utama nelayan, ternyata ada transaksi
yang tidak lazim ditemui sebelumnya
yaitu transaksi sirip hiu.
Spesies hiu kepala martil
(Sphyrna Lewini) merupakan jenis hiu
yang siripnya paling banyak diperjual-
belikan. Selain hiu kepala martil, ada
pula hiu macan (Atelomycterus
M a r m o r a t u s ) , d a n h i u a r o n
(Carcharhinus Amblyrhynchos) di TPI
tersebut. Hiu-hiu berukuran 1-1,5 meter
dikumpulkan ke dalam karung-karung
hingga kemudian di jual kepada
pengepul. Selain hiu dewasa, di tempat
pelelangan tersebut juga menjual daging
bayi hiu yang ukurannya masih 15-30cm.
“Sirip-sirip ini akan dijual lagi ke
daerah Jakarta karena permintaan
terbanyak ada di sana. Harganya
Rp25.000,00 per kilo jika belum diolah,
namun jika sudah diolah bisa mencapai
Rp1.500.000,00 per kilonya,” tutur
Gunawan sebagai pengepul.
Setibanya di daerah Jakarta,
menurut Gunawan sirip-sirip tersebut
akan diekspor lagi ke berbagai negara
seperti Cina, Vietnam, dan Jepang.
Meskipun hiu bukanlah komoditas
utama, namun permintaan akan sirip hiu
cukup besar karena harga jualnya yang
sangat mahal.
“Hiu-hiu ini tidak sengaja
masuk ke jala kami. Sebenarnya jika hiu
tersebut masuk ke jala kami, kami malah
rugi karena jala kami menjadi rusak. Hiu
kan hewan agresif,” keluh Rusman, salah
satu nelayan di TPI tersebut.
Fakta lainnya mengatakan
bahwa hiu-hiu tersebut sengaja
ditangkap untuk memenuhi permintaan
industri. Casim, mengaku sengaja
menangkap hiu tersebut sebagai
tangkapan utama. Ia mengaku adanya
transaksi di tengah laut selain di TPI
tersebut. Biasanya transaksi dengan
orang-orang luar negeri seperti
Singapura dan Filipina.
Sekali berlayar, Casim dan
rekan-rekannya bisa berada di laut satu
hingga dua bulan lamanya. Cara
menangkapnya, Casim menggunakan
pancing rawai untuk menangkap hiu.
Sistemnya ketika kapal berjalan, pancing
dilempar dan hiu mengejar umpan yang
ada di pancing tersebut.
Casim bercerita keluh kesahnya
sebagai nelayan. Ia harus menempuh
perjalanan jauh selama berbulan-bulan
hanya untuk mencari ikan dan harus
terpisah dengan keluarganya di Indra-
mayu. Resiko badai di laut yang meng-
hantam kapal harus dilaluinya sebagai
nelayan.
S e b a ga i n e l aya n , C a s i m
mengaku tidak tahu mengenai populasi
hiu yang terancam dan tidak pernah
tahu kalau hiu adalah hewan yang
dilindungi. Menurutnya belum ada
sanksi tegas yang mengatur perdagang-
an sirip hiu ini. Namun ia tahu kalau di
luar negeri sudah ada larangan tentang
perdagangan sirip hiu yang membuat
omzetnya menjadi menurun.
“Kalau sekarang di Indramayu
sudah mulai mengurangi. Alatnya pun
sudah beda. Kita sekarang mengguna-
kan jala nilon,” ujar Rusmadi selaku
manajer TPI Karangsong.
Sebelum menjadi manajer TPI, Rusmadi mengaku pernah menjadi
nelayan yang menangkap hiu sebagai komoditi utama. Dengan kapal ukuran 15GT (Gross Tonnage), Rusmadi berlayar hingga ke perbatasan Malaysia untuk menangkap hiu. Diakui Rusmadi, populasi hiu banyak di bulan November dan Desember karena banyaknya hiu yang melakukan migrasi.
Sirip hiu harganya kini merosot
karena di Cina sendiri sudah ada
pelarangan. Proses pengolahan sirip hiu
melewati beberapa tahap yaitu dijemur
sampai kering, direbus, kulitnya dikupas,
tulangnya dibuang, dan diambil serat-
seratnya yang berbentuk seperti bihun.
“
Sebagai nelayan, Casim mengaku tidak tahu
mengenai populasi hiu yang terancam dan tidak pernah
tahu kalau hiu adalah hewan yang dilindungi.
” “Jika dibandingkan dengan
komoditas ikan yang lain, total
penangkapan hiu tidak seberapa. Kalau
di TPI Karangsong ada 80 ton ikan yang
diturunkan dari kapal, paling hiunya
hanya satu ton,” jelas Rusmadi.
Jika dikalkulasikan dalam
sebulan ada satu ton sirip hiu yang
dikumpulkan dan dijual, maka omzetnya
bisa mencapai 1,5 Milyar. Cukup untuk
balik modal sekali berlayar yang
menghabiskan total 400 juta rupiah itu.
Akhir Cerita Predator Laut di Tangan Manusia Indramayu, Kabupaten yang terletak di Pantai Utara (Pantura), Jawa Barat, merupakan daerah yang memiliki armada nelayan terbesar di provinsi ter-sebut. Di balik kebesaran armada nelayannya, Indra-mayu ternyata menyimpan sebuah kisah pilu tentang si predator laut dan puluhan ribu nelayannya.

SAPHARA | 14
NUSANTARA BELUM PEDULIPADA HIU“Yang menjadi urusan saya sekarang adalah bagaimana 39.000 nelayan di Indramayu bisa makan. Untuk perdagangan hiu sendiri belum ada kebijakan,” ucap Ir. H. Abdur Rosyid Hakim selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.
Dengan menggunakan pakaian
santai di kediamannya, Abdur
Rosyid menjelaskan bagai-
mana kepeduliannya terhadap keber-
langsungan hidup nelayan-nelayan di
Indramayu. Di matanya, Indramayu
merupakan jantung perikanan di Jawa
Barat karena hasil tangkapannya
terbesar di provinsi tersebut.
Ketika ditanya mengenai
kebijakan serta peraturan perdagangan
sirip hiu, Abdur Rosyid mengatakan,
belum ada Perda yang mengatur
perdagangan tersebut. Sosialisasi pun
belum dilakukan dan pemahaman
nelayan masih sebatas menangkap ikan
dan menjualnya tanpa memikirkan
dampak ekosistem.
“Tidak ada kapal atau alat
tangkap khusus yang digunakan untuk
menangkap hiu. Jika ada, itu hanya
usaha sampingan karena hiu bukan
komoditas utama,” tutur Abdur Rosyid.
Abdur Rosyid mengaku tidak
masalah jika hiu diperjualbelikan
selama hiu tersebut tidak sengaja
tertangkap oleh nelayan. Ia menjelas-
kan di lautan ada yang disebut rene-
wable resource. Renewable resource
adalah sumber daya alam yang bisa
diperbarui. Jika ikan ditangkap sesuai
kebutuhan, maka populasinya akan
stabil dan tingkat kepunahan bisa
dihindari.
Di Indramayu, tidak ada data
pasti mengenai populasi hiu yang masih
tersisa. Di Indonesia sudah menerapkan
sistem Maximum Sustainable Yield
(MSY) yang dihitung bukan dari per jenis
ikan, namun dari luas wilayah
penangkapan. MSY sendiri terdiri dari
ikan wilayah pantai dan lepas pantai.
Sebenarnya sudah ada Perda
yang mengatur tentang penggunaan
alat tangkap seperti pelarangan
penggunaan pukat harimau dan bom
untuk menangkap ikan. Namun
kebijakan tersebut hanya berlaku untuk
kelestarian terumbu karang, belum
untuk hiu.
“Nelayan kan butuh uang, dan
mengeluarkan modal yang tidak sedikit
untuk melaut. Hal itu yang tidak
diketahui oleh LSM yang menyuarakan
larangan untuk berdagang sirip hiu.
Namun, jika LSM lebih mendominasi
dan nelayan menjadi tidak bekerja, ya
salah,” jelas Abdur Rosyid.
“Di Indramayu, tidak
ada data pasti mengenai populasi
hiu yang masih tersisa
” Menurut Dr. Ir. Sriati, M.Si,
dosen Fisheries Management and
Population Dynamic di Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan Univer-
sitas Padjadjaran memang belum ada
peraturan yang mengatur perdagangan
sirip hiu ini. dari Peraturan Menteri
(Permen) yang ada hanyalah peraturan
perlindungan penuh terhadap Hiu Paus
di Indonesia.
“Pemerintah belum membuat
peraturan yang mengatur regulasi
perdagangan sirip hiu ini. Setiap
nelayan sebenarnya diberikan surat izin
penangkapan, namun jika ada hewan
yang dilindungi sengaja ditangkap,
maka surat izin tersebut akan dicabut,”
tutur Sriati.
Sriati mengatakan bahwa baru
ada Keputusan Menteri (Kepmen)
mengenai Rencana Aksi Nasional
Pencegahan Dan Penanggulangan
Illegal, Unreported, And Unregulated
Fishing tahun 2012-2016. Kepmen ter-
sebut berisi pencegahan terhadap
kegiatan melaut yang melanggar aturan
seperti penangkapan ilegal, tidak ada
laporan penangkapan, dan tidak ada
regulasi penangkapan.
Sementara, di Raja Ampat
sudah terdapat Perda yang mengatur
tentang penangkapan hiu spesies
apapun. Hal tersebut tercatat dalam
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012
tentang Larangan Penangkapan Hiu,
Pari Manta, Jenis-Jenis Ikan Tertentu di
Perairan Laut Kabupaten Raja Ampat.
Diakui Sriati bahwa Raja
Ampat memiliki potensi pariwisata laut
yang nilai ekonomisnya lebih tinggi
dibanding perdagangan sirip hiu. Wajar
saja, di sana pemerintahnya sangat
peduli terhadap ekosistem laut.
Majunya pariwisata di Raja Ampat akan
menjadi pemasukan sendiri untuk
keuangan daerah.
Kenyataannya, masih banyak
pemerintah baik pusat maupun daerah
yang masih lalai dan kecolongan
mengenai hal ini. Adanya polisi laut
hanya sanggup melarang nelayan dari
luar negeri untuk menangkap ikan di
perairan Indonesia. Hal tersebut
membantu ekosistem ikan laut
khususnya hiu di Indonesia tidak dijarah
oleh negara tetangga.
LAPORAN UTAMA

SAPHARA | 15

SAPHARA | 16
Kemampuan reproduksi yang rendah, pertumbuhan yang lambat, serta resiko kematian yang tinggi di setiap umur membuat hiu tidak dapat dieksploitasi secara sembarangan. Perlu adanya manajemen yang apik serta pengawasan yang ketat agar anak cucu kita kelak bisa melihat si predator laut
ini berenang di laut.
LAPORAN UTAMA
Foto: Reza Rahmandito

“Tingkat permintaan industri tidak
sebanding dengan tingkat reproduksi
h i u . Pe r l u a d a n y a p e n e k a n a n
permintaan di sini,” tutur Alexander M.
A. Khan, S.Pi, M.Si, selaku dosen Penang-
kapan Ikan Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan Universitas Padjadjaran.
Alexander mengatakan bahwa
prinsip ekonomi “di mana ada permin-
taan, di situ ada penawaran” berlaku
dalam perdagangan sirip hiu ini. Jika
masyarakat Indonesia bisa menahan diri
untuk tidak mengonsumsi sirip hiu,
maka produksi nelayan khususnya di
Indramayu bisa berkurang.
Masalah yang sedang dihadapi
sekarang adalah ada beberapa nelayan
yang tidak sengaja menangkap hiu dan
minimnya informasi tentang angka
populasi hiu tersebut. Sumber maupun
jumlah produksi hiu yang masuk dalam
perdagangan internasional sangat sulit
terdeteksi. Publikasi tentang identifikasi
hiu di Indramayu juga menyulitkan
nelayan untuk mengenali jenis-jenis hiu
yang hampir punah.
“Dunia internasional sudah
membentuk Shark Specialist Group
(SSG) di tahun 1991 sebagai mediator
untuk usaha konservasi hiu,” jelas
Alexander.
Menanggapi makin gencarnya
konservasi hiu di dunia, pemerintah
Indonesia seperti Departemen Kelautan
dan Perikanan (DKP), serta LIPI mulai
concern terhadap konservasi hiu di
negara ini. Pemerintah bekerjasama
dengan pemerintah Australia melaku-
kan penelitian dan diharapkan dari ker-
jasama tersebut muncul sebuah rencana
aksi untuk mengelola sumber daya hiu
se-Indonesia.
“Masyarakat harus ikut ambil
bagian dalam kepedulian terhadap hiu ini
” Pemerintah sebenarnya sudah
membuat program. Seperti sensus biota
laut yang dilakukan oleh pusat pene-
litian Oseanografi LIPI, Institut Pertanian
Bogor, Akuarium Air Tawar Taman Mini,
serta pembudidayaan hiu gergaji di
beberapa daerah.
“Konservasi adalah masalah
manajemen dan memerlukan waktu.
Kepala Dinas Indramayu harusnya
berpikir bahwa penangkapan hiu adalah
fast money in the short term. Sampai
berapa lama hiu tersebut dapat dieks-
ploitasi untuk menampung kehidupan
para nelayan,” ucap Riyanni Djangkaru,
pendiri DiveMagz, serta pencetus
program SaveShark di Indonesia.
Ketika ditemui di Seminar
Jalanesia di Kampus Unpad Dipati Ukur,
Bandung, Riyanni Djangkaru menutur-
kan bahwa tidak ada salahnya jika
nelayan menangkap hiu untuk kebu-
tuhannya sehari-hari. Namun, jika sudah
masuk industri dan sirip hiu tersebut
disalahgunakan melalui regulasi yang
kacau, keserakahan, serta birokrasi yang
rumit, maka semuanya akan kembali lagi
kepada keuntungan pribadi.
Terkadang orang sering berpikir
jika ada kampanye yang dilakukan oleh
LSM, seakan-akan LSM menghambat
penghasilan nelayan yang menangkap
hiu. Namun jika disadari sudah banyak
kapal-kapal asing di tengah lautan yang
siap untuk membeli sirip hiu dari nelayan
kita. Sebuah kejahatan bisnis yang
menakutkan.
Selain ketegasan dari pemerin-
tah, masyarakat harus ikut ambil bagian
dalam kepedulian terhadap hiu ini. Tidak
ada salahnya jika kepandaian ilmu yang
dimiliki dapat berbanding lurus dengan
kepedulian lingkungan yang sudah
memberikan kehidupan sekarang, esok,
dan seterusnya. Jangan sampai nantinya
anak cucu kita tidak dapat merasakan
buasnya laut Nusantara.
SAPHARA | 17
Foto
: Rez
a R
ahm
and
ito

SAPHARA | 18
ADU BAGONG,
PERGESERAN BUDAYAPEMUSNAHAN HAMATeks & Foto: Dwy Anggraeni & Bonny Rizaldy
abi Hutan (Sus scrofa), atau yang akrab disebut BBagong oleh masyarakat Jawa Barat, adalah
salah satu jenis hewan liar yang mudah ditemui
di hutan-hutan yang terdapat di seluruh negeri ini.
Jumlah bagong cukup banyak serta mudah ditemui di
seluruh bagian negeri ini. Tetapi, binatang ini diangap
sebagai salah satu organisme yang dianggap
merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-
hari manusia, alias hama, sehingga seringkali merusak
sawah dan perkebunan warga.
Hal yang sama juga diamini masyarakat di
Cikoneng, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dianggap
kerap mengganggu perkebunan dan sawah milik
warga, sejak beberapa dekade yang lalu muncul tradisi
adu anjing dengan bagong, seperti yang terlihat pada
Minggu, 8 Desember yang lalu. Kegiatan yang sudah
mendarah daging sejak tahun 1960an tersebut telah
menjadi tradisi bagi masyarakat Sunda setempat, dan
secara umum oleh masyarakat Sunda di wilayah
Bandung timur.
Setiap akhir pekan di Cikoneng, Explorer akan
dengan mudah mendengar suara menyalak anjing-
anjing petarung yang datang dari berbagai daerah,
seperti Bandung, Sumedang, Garut, dan Tasikmalaya.
Kalau dihitung-hitung, setiap pekannya terdapat
sekitar 40 ekor anjing petarung datang ke Cikoneng
untuk “mengadu nasib” melawan para bagong.
Secara historis, adu bagong dengan anjing ini
awalnya bertujuan membunuh para bagong yang
seringkali merusak tanaman di perkebunan dan sawah
milik warga. Dan juga awalnya anjing-anjing yang
diikutsertakan adalah anjing-anjing yang dipelihara
oleh warga.
Sekarang, tujuan dari permainan adu anjing
dengan bagong telah bergeser, bukan lagi untuk saling
membunuh, tetapi dikembangkan untuk melatih
anjing agar lebih tangkas terhadap sesuatu yang
dianggapnya sebagai lawan. Dan juga, anjing-anjing
yang diikutsertakan bukan lagi jenis anjing kampung,
tetapi kebanyakan anjing ras, yaitu anjing-anjing hasil
biakan, seperti American Pit Bull Terrier misalnya, atau
lebih umum disebut anjing Pitbull. Biasanya, pemilik anjing
tersebut menginginkan untuk melatih si anjing agar lebih
tangkas terhadap sesuatu yang dianggapnya sebagai
lawan.
Bagong yang diadu dengan anjing pun kini tidak lagi
dibiarkan sampai mati. Seiring berkembangnya zaman,
bagong-bagong itu dipelihara di kandang. Apabila dalam
prosesi permainan bagong terdapat luka-luka, maka
pertandingan dihentikan serta bagong yang terluka ditarik
masuk ke kandang diganti dengan bagong yang masih
sehat.
Teknis permainan ini pun dibuat cukup simple.
Umumnya, setiap minggunya para pengelola kegiatan ini
menyediakan tiga ekor bagong untuk diadu. Saat
pengocokan nomor urut, pengelola mendapatkan 20
anjing pertama yang akan diadu dan saat itulah anjing
dimasukkan satu persatu untuk melawan bagong
WISATA BUDAYA

SAPHARA | 19
yang sudah disiapkan. Batas lamanya anjing
melawan bagong itu hanya gigitan selama 5 detik.
Hal ini terus berlanjut sampai keadaan bagong
mulai sangat melemah dan sudah terdapat banyak
luka di badannya, lalu diganti dengan bagong yang
lain
Sempat ada kecurigaan potensi timbulnya
perjudian dengan diadakan permainan ini. Tetapi
ternyata kecurigaan tersebut tidak terbukti. Dalam
permainan ini tidak ada unsur judi sama sekali.
“Pengadu hanya perlu membayar Rp50.000,-. Uang
yang terkumpul akan digunakan untuk membeli
bagong yang harganya berkisar Rp1.000.000,- per
ekor dan upah kepada para pengelola kegiatan ini,”
ujar Acu, salah seorang panitia permainan
mingguan ini.
Bagi masyarakat setempat, kegiatan ini
memang sekadar hiburan. Untuk sebagian orang,
ini merupakan penyalur hobi bagi yang memiliki ketertarikan
dalam kegiatan adu anjing dan bagong ini. Bagi warga
setempat, permainan ini memberi-kan banyak dampak positif
bagi mereka. Adu anjing dengan bagong dianggap
memberikan warga seki-tar lapangan pekerjaan, seperti
membuka usaha makan di wilayah permainan, membuka
lapangan parkir yang bisa menjadi bahan pemasukan warga.
Uang yang masuk dari lahan parkir nantinya akan dimasukkan
ke dalam kas RW yang suatu saat dapat berguna untuk warga.
“
Sekarang, tujuan dari permainan adu anjing dengan bagong telah
bergeser, bukan lagi untuk saling membunuh.
”Pro dan Kontra: Budaya vs Perikehewanan
Tentang seni adu anjing dengan bagong ini, ada
kritikan terkait dari International Animal Rescue (IAR). IAR
beranggapan hal ini melanggar prinsip kesejahteraan satwa
atau yang biasa disebut Animal Welfare. Adapun pengertian
Animal Welfare ialah suatu usaha untuk memberikan kondisi
lingkungan yang sesuai bagi satwa sehingga berdampak ada
peningkatan sistem psikologi dan fisiologi satwa.
Hal tersebut juga berkaitan dengan Animal Rights atau
Hak Asasi Hewan, yang ditafsirkan sebagai hak-hak dasar
hewan untuk hidup layak serta bebas dari intervensi manusia.
Hewan juga mempunyai hak mendapatkan perlindungan dan
perlakuan baik oleh manusia seperti dalam perawatan,
tempat tinggal, pengangkutan, pemanfaatan, cara
pemotongan, juga cara euthanasia (suntik mati).
“Tidak semua budaya bagus, tidak semua budaya bisa
dihilangkan, tapi hal yang melanggar prinsip AW memang
harus dihilangkan” tegas Indah Winarni, seorang Primatolo-
gist yang juga anggota IAR.
Menurut dia, hal seperti ini kembali pada dasarnya
kepekaan manusia terhadap satwa yang seharusnya dirawat
dan diperlakukan secara layak. “Jika memang tidak bisa
menghentikan budaya dan tradisi seperti ini, mencoba lah
untuk tidak menonton pertunjukkan yang melanggar prinsip-
prinsip Hak Asasi Hewan tersebut,” pungkasnya menutup
perbincangan singkat melalui telepon seluler saat dihubungi
pertengahan Desember lalu.

SAPHARA | 20
Foto
: M. A
nd
ika P
utra
HARIMAU SUMATERA
ELANG
KUKANG
LUTUNG JAWA
KERA EKOR PANJANG
Asal : Pulau Sumatra
Bentuk eksploitasi : Diperdagangkan
Tempat tujuan perdagangan : Pulau Jawa dan pasar gelap
hewan ke luar negeri
Asal : Jawa, Sumatra, Kalimantan
Bentuk eksploitasi : Diperdagangkan
Tempat tujuan perdagangan : Pulau Jawa dan sekitarnya
Asal : Jawa Barat
Bentuk eksploitasi : Diperdagangkan
Tempat tujuan perdagangan : Pulau Jawa
Asal : Jawa Timur
Bentuk eksploitasi : Diperdagangkan
Tempat tujuan perdagangan : Pulau Jawa dan Sumatra
Asal : Jawa Timur
Bentuk eksploitasi : Diperdagangkan
Tempat tujuan perdagangan : Pulau Jawa dan Sumatra
HALAMAN

Foto: google.com
SAPHARA | 21
LUMBA - LUMBA
KAKATUA PUTIH
KASTURI TERNATE
NURI KEPALA HITAM
HIUAsal : Di seluruh perairan di Indonesia
Bentuk eksploitasi : Dijadikan hewan sirkus
Tempat tujuan eksploitasi : Arena atraksi Lumba - lumba
Asal : Di seluruh perairan di Indonesia
Bentuk eksploitasi : Dijual siripnya
Tempat tujuan eksploitasi : Pulau Jawa, Sumatra, Indonesia
Timur
Asal : Maluku
Bentuk eksploitasi : Diperdagangkan
Tempat tujuan perdagangan : Pulau Jawa, Filipina
Asal : Ternate, Papua
Bentuk eksploitasi : Diperdagangkan
Tempat tujuan perdagangan : Pulau Jawa
Asal : Indonesia timur (Papua dan
Maluku)Bentuk eksploitasi :
DiperdagangkanTempat tujuan perdagangan :
Pulau Jawa

SAPHARA | 22
kspedisi tersebut ialah ekspedisi ERafflesia (Eksplorasi fauna flora
dan ekowisata Indonesia) dan
ekspedisi Surili (Studi konservasi
lingkungan), yang memang dilakukan
Himakova tiap tahunnya. Ekspedisi
Rafflesia dilaksanakan di Cagar Alam
Bojonglarang Jayanti, Jawa Barat
sedangkan Ekspedisi Surili dilaksanakan
di Taman Nasional Manuela, Maluku.
Ekspedis i Raff les ia yang
dilaksanakan pada tanggal 23 Januari - 1
Februari 2013 itu mendapatkan hasil
penemuan. Hasil penemuan tersebut
adalah 13 jenis mamalia, 44 jenis burung
dari 19 famili di camp selatan dan 47
jenis di camp utara, 21 jenis herpeto-
fauna dari 8 famili (4 famili reptilia dan 4
famili amfibi), 75 jenis kupu-kupu dari 5
famili, dan Kelompok Pemerhati (KP)
flora memperoleh hasil indeks keaneka-
ragaman spesies (H') 3.854 (tergolong
tinggi). Melalui Ekspedisi ini pula, KP
Flora berhasil menemukan 49 bunga
Rafflesia Patma Blume. baik berupa
kenop (kuncup), mekar, maupun yang
sudah membusuk. Penemuan ini meru-
pakan catatan baru untuk Cagar Alam
Bojonglarang Jayanti dan ilmu botani.
Selain data hasil dari flora dan
fauna ada pula KP ekowisata yang mem-
peroleh beberapa lokasi yang berpoten-
si untuk ekowisata, yaitu: Batu Kukum-
bang, Gua Landak dan Sodong Karnan,
Gua Cisela, Gua Sodong Parat. Batu
Kukumbang merupakan potensi utama
yang menjadi daya tarik, karena
sepanjang jalan menuju lokasi dapat
dijumpai batu-batu yang mempunyai
ketinggian hingga tiga meter dan
terdapat bekas jejak kaki Prabu Kian
Santang di salah satu batu.
Lalu, Ekspedisi Surili dilakukan
pada tanggal 22 Juli- 15 Agustus 2013,
dengan tema “Memahami Perubahan
Iklim dalam Konteks Keanekaragaman
Hayati dan Pengetahuan Lokal di TN.
Manusela, Maluku”.
“Surili tahun ini istimewa
terkait lokasi dan tema. Maluku adalah
lokasi kegiatan Surili terjauh selama satu
dekade (Surili 2013 merupakan Surili ke-
11) kegiatan Surili. Pemilihan perubahan
iklim sebagai tema juga memberikan
tantangan tersendiri, karena di Indo-
nesia isu-isu perubahan iklim jarang
dikaitkan dengan keanekaragaman
hayati maupun kawasan konservasi,”
ucap salah satu dosen DKSHE, Fakultas
Kehutan IPB yang akrab dipanggil Bu Ina.
Ekspedisi Surili mendapatkan
hasil penemuan. Diantaranya KP flora
berhasil menemukan 16 spesies tingkat
pohon, 3 spesies tingkat tiang, 16
spesies tingkat pancang, dan 19 spesies
tingkat semai, dan 3 spesies tumbuhan
bawah. KP Mamalia berhasil menemu-
kan 10 jenis mamalia, yang paling mena-
rik adalah ditemukannya satwa khas
wilayah peralihan, Kuskus belang
(Spilocuscus maculatus) dan kuskus
kelabu (Phalanger orientalis). KP burung
Himakova juga berhasil menemukan 64
jenis burung.
KP herpetofauna menemukan 18 jenis
yang terdisi dari 5 jenis amfibi dari 4
famili dan 13 jenis reptil dari 6 famili. KP
kupu-kupu yang berada di camp utara
menemukan 43 jenis kupu-kupu dari 5
famili dan camp selatan menemukan 16
jenis dari 3 famili. Berdasarkan kajian
etnobiologi (etno-botani dan etnozoo-
logi) yang dilakukan oleh KP flora
menunjukkan masyarakat memanfaat-
kan 33 jenis tumbuhan sebagai obat, 54
jenis tumbuhan yang dimanfaatkan
sebagai bahan kontruksi bangunan, dan
13 jenis tumbuhan lain dikategorikan
sebagai tumbuhan bermanfaat. Ber-
dasarkan kajian kondisi sosial ekonomi
masyarakat, diketahui juga adanya sasi,
yaitu berupa peraturan tidak tertulis di
masyarakat yang turut menjaga keles-
tarian hasil hutan. Selanjutnya, KP gua,
berhasil menemukan 12 gua yang
tersebar di Resort Sawai-Maihulan dan
Resort Kan ike Taman Nas iona l
Manusela.
Nah, Explorer, hasil penemuan-
penemuan dari ekspedisi Himakova
inilah yang dipublikasikan lewat seminar
nasional ini. Diakui Agung Gunadi
Andrian selaku ketua pelaksana seminar,
publikasi penemuan hasil ekspedisi ini
sangat penting karena harus diketahui
teman-teman kampus dalam mengenal
lingkungan.
Seminar Nasional
Ekspedisi Himakova IPB
ACARA
Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (Himakova), salah satu himpunan profesi di Institut Pertanian Bogor mengadakan kegiatan Seminar Hasil Ekspedisi
Himakova. Seminar nasional yang dihadiri 302 orang ini diadakan pada Sabtu, 30 November 2013 lalu di Auditorium Andi Hakim Nasution (AHN), kampus IPB Dramaga.
Teks & Foto: Dwi Desilvani

SAPHARA | 23
eluncur sungai atau River-Sboarding kini tengah menjadi
salah satu cabang olahraga eks-
trim yang mencuri perhatian melalui
diadakannya The First Riverboarding
World Competition. Indonesian River-
boarding Association (IRA) dan Face
Level Industries menggelar ke-juaraan
dunia pertama tersebut di Sungai
Citarum, daerah Bantar Caringin,
Rajamandala, Kabupaten Bandung Ba-
rat, 6-10 November 2013 lalu. Perhelat-
an diadakan sekaligus sebagai kampanye
agar pemerintah serius membersihkan
sungai yang disebut terkotor di dunia itu.
" I n i ya n g p e r ta m a b i s a
kumpulkan riverboarder sedunia dari
lima benua," kata Rahim Asik BS, ketua
panitia acara. Ia mengharapkan acara
tersebut dapat memajukan olahraga
selancar sungai di Indonesia dan kondisi
sungai Citarum.
Tercatat ada 60 peselancar
sungai dari 10 negara, seperti Indonesia,
Prancis, Amerika Serikat, Kanada, Afrika
Selatan, Selandia Baru, dan Australia.
Mereka kebanyakan para pemegang
gelar juara nasional selancar sungai di
negaranya, termasuk peselancar
legendaris. Ajang kali ini menggelar
empat nomor, yaitu slalom, boarder-
cross, freestyle surfing, dan endurocross
dengan total hadiah Rp 50 juta.
Kejuaraan dunia pertama pada
pengujung tahun 2013 ini menjadi
pembuktian kemampuan para river-
boarder dunia. Peserta asal Prancis
menguasai lomba tersebut. Pada juara
umum kategori lelaki, peselancar muda
Bob Lataste menjadi kampiun dengan
nilai 300. Juara umum kedua Gaultier
Lebegue yang mengantongi nilai 210,
sedangkan juara umum ketiga diperoleh
Tristan Guyard dengan nilai 200. Semua
peselancar asal Prancis itu merupakan
juara sejumlah lomba riverboarding di
negaranya.
Di peringkat bawah, tercatat
nama peselancar asal Indonesia yaitu
Yudi Nurdiyanto di peringkat ke-4 deng-
an nilai 100, lalu Edi "Buaya" Haryanto di
posisi ke-5 dengan nilai 75, dan Yvan
Kopczynski dari Prancis di posisi ke-6
yang mengantongi nilai 50.
Peselancar wanita asal Prancis
pun menguasai jalannya lomba. Gelar
juara umum pada posisi pertama diraih
Marine Schmitt, kedua Adeline Hachet,
dan juara umum ketiga Leonard Aude.
Sama seperti rekan lelaki senegaranya,
mereka menyapu bersih juara nomor
slalom, boardercross, dan endurocross.
Khusus Adeline Hatchet dan Marine
Schmitt, mereka juga melengkapi pres-
tasinya dengan juara kedua dan ketiga di
nomor gaya bebas (free style) di kategori
wanita.
"Slalom dan boardercross itu
nomor favorit di Prancis, peselancar
Indonesia dan negara lain masih sulit
bersaing," kata tim ofisial dari kelompok
Banyoo Woong, Tri Haryanto.
Adapun peselancar sungai asal
Indonesia, sebagai empunya hajat,
secara mengejutkan berjaya di nomor
gaya bebas (free style). Seluruh juara di
nomor itu disapu bersih oleh Yudi Nurdi-
yanto sebagai juara pertama, Edi
"Buaya" Haryanto juara kedua, dan Her-
mawan Sutanto di posisi ketiga.
"Teknik peselancar kita di free
style lebih bagus, menguasai medan,
dan dapat banyak dukungan penonton,"
jelas Rahim.
Indonesia juga menoreh juara
umum di peselancar kategori junior.
Melki Oktavian menjadi kampiun
dengan nilai 300, Luki Hidayat di posisi
kedua setelah mengumpulkan nilai 185,
dan juara ketiga M. Ramdhan Rudiana
dengan skor nilai 120.
Tak lupa jargon yang selama 5
hari senantiasa digaungkan para lakon
riverboarding di Citarum “Salam
Sejajar!”.
The First World Riverboarding Championship
Unjuk Gigi Riverboarder DuniaTeks: Olfi Fitri Hasanah
Foto
: Dim
as E
. Sem
bad
a

FOTO ESSAY

Prolog: Foto-foto setelah ini akan sedikit menceritakan bagaimana kisah mereka dibantai.
Lokasi: Tempat Pelelangan Ikan Karangsong, Indramayu.

FOTO ESSAY

Memakan sirip hiu, dulunya tradisi, kini menjadi industri. Atas dasar itu,
hiu mulai dikupas habis.

SAPHARA | 28
FOTO ESSAYFOTO ESSAY
Nantinya, sirip mereka akan dibawa ke tengkulak-tengkulak pengepul sirip hiu. Dengan harga Rp25 ribu per kilo, pengolah masakan sirip hiu
mampu mendapat untung puluhan kali lipat.

SAPHARA | 29
Inilah akhir cerita si predator laut di tangan manusia. Kerasnya tamparan ombak dan tuntutan hidup yang semakin mencekik,
membuat nelayan semakin buas, bahkan lebih buasdari si predator laut ini sendiri. Sekian.
Foto: Dhanang David Aritonang

SAPHARA | 30
7 PRINCIPAL OF LEAVE NO TRACE
Dalam berkegiatan di alam bebas, alangkah baiknya bila kita mengikuti etika-etika yang ada. Seven principal of leave no trace merupakan prinsip etika yang lebih menekankan pada sikap dan kesadaran terhadap lingkungan dan sosial dibandingkan pada peraturan yang mengikat. Berikut ini adalah penjabaran prinsip tersebut:
OPERASI
Teks & Foto: Dimas Jarot Bayu

SAPHARA | 31
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Masterplan: Perencanaan dan persiapan yang matang.
Travel and camp on durable surface: Tempat berkemah yang baik ditemu-
kan, bukan dibuat, berjalan pada jalur yang sudah ada.
Dispose of waste properly: Kurangi penggunaan barang yang menimbulkan
sampah.
Leave what you find: Jangan membawa barang yang ditemukan di hutan
seperti binatang atau tumbuhan, jangan melakukan vandalisme.
Respect wildlife: Menghormati kehidupan alam dengan tidak merusaknya.
Minimize campfire impacts: Menggunakan api unggun berdasarkan prinsip-
nya sehingga meminimalisir kebakaran.
Be considerate of other visitors: Sopan santun saat melakukan perjalanan
dan mematuhi adat istiadat yang berlaku di sebuah lokasi.

SAPHARA | 32
Teks: Ariel Driantoro & Andhika Soeminta P
KATA KITA
Di tahun 2013 banyak sekali eksploitasi hewan dan
lingkungan yang terjadi di tanah air ini, Indonesia.
Tentunya eksploitasi tersebut memberikan dampak negatif untuk kelangsungan hidup ekosistem. Lalu, apa kata
mereka mengenai eksploitasi hewan dan lingkungan ini?
Berikut Saphara merangkumnya dalam
Kata Kita.
“Jika saya diposisikan sebagai pebisnis dengan kondisi yang ada saat ini, saya mungkin akan
setuju-setuju saja dengan eksploitasi tersebut. Sebab realistis saja, itu menguntungkan. Tetapi
saat ini saya adalah seorang rakyat biasa, tentu saja saya menentang para pelaku eksploitasi tersebut,”
Dezky Oka, Sekolah Bisnis Manajemen ITB
“Untuk kasus satwa langka, seperti pembasmian Orangutan karena dianggap hama, semestinya
perlu disadari bahwa mereka juga ciptaan Tuhan. Terkadang manusia memang suka memikirkan diri
sendiri. Semestinya mereka bisa bertindak lebih bijak, seperti jika ada satwa-satwa liar yang
tergolong langka menyerang pemukiman, mengapa tidak ditangkap lalu dibius, atau diamankan
terlebih dahulu. Hukum yang mengatur, saya rasa memang sudah ada tetapi pemerintah belum
bersikap tegas,”
Fikri Maulana, Aktivis BEM Unpad
“Tindakan eksploitasi satwa dan lingkungan semestinya tidak dilakukan oleh manusia. Untuk
eksploitasi satwa langka misalnya, perlu dibangun kesadaran kepada masyarakat bahwa satwa-satwa
tersebut adalah makhluk yang perlu diproteksi keberadaannya,”
Wiraditma Prananta, Hubungan Internasional Fisip Unpad

SAPHARA | 33
“Menurut saya perlu dibedakan antara eksploitasi hewan dan lingkungan sebatas untuk budaya, dan
yang untuk kepentingan komersil. Misalnya, budaya perburuan ikan Hiu di Papua tentu tak mengganggu
ekosistem tersebut. Tetapi yang justru berbahaya ialah eksploitasi massal. Pasti kita bisa
membedakan mana yang bertujuan melestarikan kebudayaan, mana yang untuk keuntungan pribadi,”
Aris Arianto, Jurnalistik Fikom Unpad
“Masih melakukan eksploitasi hewan dan lingkungan, karena dengan alasan melestarikan
budaya misalnya, menurut saya sudah sangat tidak relevan untuk saat ini. Misal untuk budaya berburu rusa untuk dikonsumsi, kalau sekarang kan sudah
banyak daging-daging yang dikonsumsi secara masal seperti sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Mengapa masih melakukan eksploitasi terhadap
hewan hewan yang dilindungi?”
Nur Khansa Ranawati, Jurnalistik Fikom Unpad
“Untuk Eksploitasi Satwa Langka, ya pemerintah masih kurang tegas dan masih banyak oknum-
oknum yang memanfaatkan satwa langka untuk keuntungan pribadi. Jelas disini pemerintah harus
tegas. Untuk eksploitasi lingkungan sendiri, itu sudah sangat basi. Banyak lembaga-lembaga
berkedok aktivis pemerhati alam tapi tak lebih dari mengejar keuntungan semata, bukan karena hati
yang bersih,”
Mochamad Dwi, Teknologi Pangan FTIP Unpad
“Eksploitasi baik satwa langka maupun lingkungan telah benar-benar merugikan negara. Apalagi
eksploitasi lingkungan seperti pembalakan liar, jelas-jelas hanya menguntungkan pengusaha saja. Dampak negatifnya ujung-ujungnya berimbas ke masyarakat tempatan. Pemerintah juga seolah
acuh tak acuh. Untuk eksploitasi hewan misalnya, jika terus-terusan tak ada tindak tegas dari
pemerintah, bisa-bisa makin banyak yang punah,” Yudhanto Dewo Giribowo, Agribisnis Faperta Unpad
“Di Indonesia sendiri hukum pembalakan hutan sudah ada, tapi pelaksanaannya belum efektif. Padahal negara berkembang kayak Indonesia tingkat eksploitasi hutannya tinggi. Organisasi internasional yang fokus sama masalah ini ada WWF. Saya rasa perlu ada hukum internasional
sendiri tentang illegal logging karena udah melibatkan banyak aktor dan bisa menyebabkan
masalah global, climate change atau global warming contohnya. Sulit ditangani kalo negara
cuma bertindak sendiri-sendiri,”
Ziya Pranandia,Hubungan Internasional Fisip Unpad
Foto: Dok. Pribadi

SAPHARA | 34
BUAH PENA
Lebih Indah dari Diskon di MallOleh : Nadia Septriani
andung, kota yang sudah banyak memiliki perubahan. Bangunan sudah menjulang tinggi di sisi kota. Suara klakson mobil Bdan motor terdengar dimana-mana. Tapi masih asyik untuk dikunjungi. Para pelancong dengan plat nomor B, E, Z, dan
lainnya sering datang ke Kota Kembang untuk berwisata. Entah wisata kuliner maupun wisata budaya.
Sudah merupakan hal yang lumrah jika akhir minggu dipadati dengan kendaraan bermotor. Plat nomor polisi B yang
paling mendominasi. Ya, mereka dari Jakarta yang mungkin datang ke Bandung untuk melepas penat dari hiruk pikuk Ibu Kota
Negara Indonesia. Aku salah satunya, maksudku kami.
Aku dan teman-temanku memutuskan untuk pergi ke Bandung dengan tujuan mengeksplorasi kuliner di Bandung. Di
jalan-jalan protokol Bandung banyak sekali yang menjual aneka jenis makanan. Uniknya, makanan disini seperti sebuah seni yang
lezat di mata, dan lezat di mulut. Para seniman kuliner ini mampu menciptakan makanan yang mungkin orang-orang awam tidak
pernah pikirkan. Risol pelangi, sale pisang dengan berbagai rasa, keripik singkong pedas dengan tingkat kepedasan yang
bervariasi, dan masih banyak lagi.
Tapi untuk wisata kuliner kali ini, kami akan mengeksplorasi makanan khas Bandung. Bajigur, batagor, karedok, es lilin, es
goyobod, mie kocok, mie yamin, memikirkannya saja perutku langsung berbunyi keras.
“Laper neng? Keras amat bunyinya hahaha,” celetuk Vira yang kemudian membuat semua orang di mobil ini tertawa. Oh
Tuhan, aku malu.
Kami sudah sampai. Aku tidak tahu pasti ini dimana. Sepanjang perjalanan mataku asyik melirik kota ini. Tapi yang aku
tahu, di sini dingin, saking dinginnya setiap kali aku bernapas, aku mengeluarkan uap.
Pintu mobil terbuka dari berbagai sisi, satu persatu dari kami turun. Selamat datang di.....
“Lembang!” teriak Icha. “Ke kebun stroberi tante gue dulu ya. Kapan lagi coba makan stroberi langsung dari pohonnya.”
“Gak jadi wisata kuliner bajigur blablabla?” ujar Diana.
“Nanti malem aja. Nikmatin dulu nih stroberi fresh from the oven.”
Ini, menakjubkan. Hanya gunung dan pepohonan sejauh mata memandang. Tuhan, ini lebih dari luar biasa.
Tidak asyik jika memetik stroberi langung dari kebunnya tapi tidak foto-foto. Pose ini itu. Angle sana sini. Yap, langsung
kami unggah ke instagram. Tak lama mengunggah, like berdatangan. Berbagai Comment terlihat. “Ini di mana?” “Seru banget!”
“Mau dong dibawain.”
Scroll scroll timeline. Terpaku pada satu foto dengan pemandangan lautan bintang. Ini Gunung Batu. Bandung?
“Cha, cha!” teriakku keras. Icha tidak kunjung menengok. Kalau sudah begini, gak lain gak bukan, harus disenggol
makhluk Tuhan yang satu ini.
“Plis kesini. Ini di Bandung juga, di Gunung Batu katanya.”
“Apaan, Lid? Apaan? Lihat dong lihat!” Satu persatu mulai berdatangan ke arahku, Diana, Oliv, Tiara, dan Sasa. Gadgetku
yang satu ini ditarik paksa. Dioper kesana kemari.
“Wah, ini keren banget! Kita harus kesini!” Oliv berkomentar.
“Oh iya itu Gunung Batu, memang bisa liat lautan bintang sih disitu................” Icha menjelaskan ada apa saja di Gunung
Batu, apa yang bisa dilihat dan dinikmati. Terdengar seru.
.....

SAPHARA | 35
Dari Utara ke Selatan, macet sana sini, nyasar kesana kemari. Waktu menunjukkan pukul 20.00 WIB. Dingin. Hanya ini
yang ada di pikiran dan yang kami rasa.
“Ini dia, Gunung Batu, Wanita Jakarta. A good place to enjoy the night with a thousand stars. Eh tapi, mendaki dulu, baru
bisa liat deh tuh lautan bintang,” ucap Icha pasrah.
Mendaki gunung? Dengan outfit flat shoes, hot pants, tanpa jaket dengan udara sedingin ini?
“Guys, gue anak mal. Bukan anak gunung. Ngerusak sepatu gue nih. Baru beli kemarin,” ujar Tiara dengan nada sebal.
“Kita udah kesini ya guys. Balik lagi ke Lembang? Udah nyasar dan nanya sana-sini? Cuma buat liat 'Oke ini gunung batu'.
Oke kita pulang. Mind taking my place and driving that car?” jawab Icha ketus.
“Gak ada salahnya nyoba kan. Ini kan pilihan kita tadi guys,” jawab Diana.
“Ya gue kira kan gak harus mendaki gunung seperti anak gunung. Gue kira langsung sampai ke atas gitu. Kalau tau gitu
mah mending gausah kesini,” Tiara segera melanjutkan dengan nada kesal. “Gue di mobil aja deh.”
“Gak jamin deh ya lo bakalan aman di dalam mobil. Kena rampok gue angkat tangan ya. Sampe mobil gue dirampok, lo
yang ganti, Tir. Enak banget nyuruh kesana kemari giliran udah dianterin malah minta balik. Dikira gak capek apa bawa 6 cewe yang
badannya pada kayak babon. Hargain gue kek.”
Ini bukan suasana yang bagus. Icha yang sudah tampak lelah mengendarai mobil dari Jakarta ke Lembang lalu dari
Lembang Utara ke Lembang Selatan dengan jalan yang berliku-liku mulai memuncak emosinya.
“Hah, apaan? Babon? Idih sadar diri lo,” Tiara membalas dengan emosi.
Ini benar-benar bukan suasana yang bagus.
“Yaudah deh ya. Mending kita naik ke atas. Ada yang lagi kemah di atas kayaknya,” lanjutku.
“Lidya bener. Plis ini bakalan seru kalau sudah naik ke atas. Lecet dikit tidak apa-apa lah. Sepatu rusak beli lagi. Jangan
kaya orang susah deh. Beli sepatu tinggal beli. Kasian Icha juga kan udah bawa mobil,” Sasa melanjutkan.
Sejenak kedua orang tadi mereda emosinya. Kami tetap memutuskan untuk pergi mendaki. Tidak tinggi sebenarnya tapi
tetap saja ini namanya mendaki.
Banyak bebatuan. Hanya suara jangkrik yang kami dengar. Ilalang menemani pendakian kami. Gunung Batu sebenarnya
tidak tinggi, tapi medannya cukup membuat kami lecet di sekujur kaki dan lengan. Ditambah dengan udara dingin dan kami
berpakaian seperti ini. Tiara dan Icha terus menyindir satu sama lain. Siapa yang tidak lelah mendengar itu. Aku, Diana, Oliv, dan
Sasa terus memisahkan mereka, mencoba meredakan mereka.
Hanya dibekali satu senter membuat kami sering terpeleset. Kotor sudah pasti. Keluhan sudah terdengar dimana-mana.
Ini dia puncak Gunung Batu.
Oh Tuhan. Ini surga dunia.
Kami berenam hanya diam ternganga. Udara dingin sudah kami abaikan. Pemandangan ini lebih indah daripada diskon
dan cuci gudang di mal. Kerlap-kerlip lampu Bandung ada di mata kami. Langit menyambut kami dengan kerlap-kerlip bintang.
Lautan bintang dari Bandung dan langit menyatu. Ini lebih dari night with a thousand stars.
Tiara dan Icha tertawa sejenak. Mereka terlihat bodoh dengan menatap satu sama lain.
“Gue gak tau ternyata bayaran baju kotor, sepatu rusak, kaki lecet, rambut lepek, bau ketek dimana-mana, itu kayak gini.”
Tiara sambil menunjuk kota Bandung di bawah kami. Kota Bandung terlihat kecil dari atas sini. “Indah banget. Sorry ya Cha yg tadi.
Kaya anak kecil banget gue.”
Kami berempat hanya tertawa mengingat kelakuan mereka 30 menit yang lalu. Mereka berdua pun ikut tertawa,
mungkin malu dengan tingkahnya tadi. Tak lama kemudian udara dingin menyergap tubuh kami. Sebenarnya sudah daritadi,
hanya saja kami tahan-tahan.
Di ujung sana ada anak-anak pecinta alam. Bermaksud meminta sesuatu untuk menghangatkan tubuh kami. Entah
berapa suhu yang ada di sini. Dinginnya membuat gigi kami bergetar.
Dengan gaya yang jagger, anak-anak pecinta alam itu membuat kami takut. Mereka tampak tidak bersahabat.
Setelah melihat keadaan kami yang seperti ini, salah satu dari mereka mengahampiri kami. Mungkin tahu kalau kami
sudah kedinginan. Dengan hangat kami diajak untuk bergabung bersama mereka. Minuman hangat, jaket, sleeping bag, mereka
menyambut kami dengan ramah. Badan Security tapi hati Hello Kitty, begitu anak gaul zaman sekarang menyebutnya. Ucapan
terima kasih dan obrolan malam yang hangat menyertai kami berenam dan anak-anak pecinta alam tersebut. Kami diizinkan tidur
di dalam tenda mereka. Malam terasa lebih mengagumkan.
Malam ini jauh lebih indah dari apapun itu. Mulai dari pemandangannya hingga pengalamannya. Satu, buat menye-
garkan mata itu tidak harus di mall dan menghabiskan banyak uang, uang orang tua. Dua, jangan pernah pakai hot pants ke
gunung. Ya meski di film-film banyak terlihat orang-orang luar naik gunung dengan hot pants. Tiga, jangan pernah pakai flatshoes
ke gunung, sepatu rusak sudah tentu dan kaki tentu pegal. Empat, jangan pernah menyerah sama keadaan yang belum dilewati,
coba dulu. Kalau masih bisa berkeluh kesah, berarti masih bisa berusaha. Lima, awalnya aku mengira anak gunung itu brutal.
Ternyata mereka baik dan hangat. Don't jugde the book by its cover, ever.

SAPHARA | 36
REFLEKSI
HIU,
SI SERAM YANG (MUNGKIN) AKAN TINGGAL KENANGANOleh: Herlina Agustin, MTKetua Jurusan Jurnalistik Fikom Unpad dan Anggota Dewan Penasihat Profauna
iu, hewan pemakan daging Hyang hidup di laut lepas. Di-anggap sebagai pemangsa
manusia yang berenang atau berse-lancar di laut, menghabiskan ikan-ikan milik nelayan, dan hewan ber-gigi tajam yang menakutkan. Namun sesungguhnya hewan laut yang dita-kuti itu menjadi incaran nelayan pemburu di seluruh dunia. Mereka diburu untuk suatu menu masakan bernama sop hisit, menu yang dibuat untuk memuaskan selera manusia, sebagai spesies teratas dalam rantai makanan.
Hiu, mamalia besar yang ditakuti manusia, yang telah hidup jutaan tahun lamanya melawan ke-punahan di jaman dinosaurus, kini menghadapi suramnya masa depan. Diburu oleh manusia yang hanya mengejar siripnya saja. Sepertiga dari 468 jenis hiu diketahui meng-hadapi isu kepunahan.
Perburuan hiu biasanya hanya dilakukan oleh kapal ikan minimal berukuran 10 ton. Mereka
umumnya menggunakan alat tang-kap muroami, sejenis jaring besar yang dapat memerangkap segala je-nis ikan, termasuk hiu. Jaring sejenis ini kini mulai dilarang oleh peme-rintah, dan tentu saja menuai protes dari kalangan nelayan.
Hiu yang ditangkap di Indo-nesia umumnya berjenis hiu kepala martil, hiu asap, dan hiu macan tutul. Yang terbesar dalam jenis ini adalah hiu kepala martil. Dalam sebuah penangkapan di Tanjung Pandan, Belitung, pernah ditangkap seekor hiu martil dengan berat 200 kilogram.
Sekali lagi, dalam perburu-an ikan hiu, yang paling banyak di-incar hanyalah siripnya saja. Harga sirip hiu memang mahal. Harga sirip mentah sebelum diolah tergantung besarnya. Ukuran 6 cm hingga 14 cm dihargai Rp. 375.000,- sementara yang sudah diproses berharga Rp. 950.000 per kilogram. Semakin be-sar sirip hiu ini semakin mahal harga-nya. Harga paling mahal bisa menca-
pai Rp. 2.100.000 per kg untuk sirip hiu yang sudah dimasak berukuran 45 cm. Bayangkan berapa puluh ekor ikan hiu harus mati untuk siripnya karena dijual per kilogram.
Harga dagingnya sendiri sangat murah. Untuk seekor hiu macan tutul dengan berat sekitar 20 hingga 25 kg tanpa sirip punggung, dada dan ekor hanya dihargai Rp 30.000,- Karena murahnya daging ikan hiu, maka banyak nelayan mengiris sirip hiu dalam kondisi hidup-hidup dan membuang tubuh hiu hidup tanpa sirip ini ke dalam laut. Mereka malas membawa tubuh hiu ke darat karena harganya dianggap tidak sebanding dengan energi yang mereka keluarkan untuk mengangkutnya.
Bila sudah dimasak harga seporsi sirip hiu ( ingat seporsi itu adalah semangkuk kecil) dihargai sebesar Rp. 200.000,- hingga Rp. 350.000,- Sungguh suatu harga yang luar biasa untuk semangkuk kecil makanan yang mungkin tidak mem-

SAPHARA | 37
buat kenyang. Sementara dagingnya
tidak berada di restoran itu tetapi lebih
banyak dipakai sebagai umpan ikan lain.
Sementara di Amerika Serikat, sop sirip
hiu dihargai sebesar US$ 100,- per
mangkok. Harap diingat, Amerika adalah
penyantap sop hisit terbesar kedua
setelah Asia. Mereka mengimpor-nya
dari Hongkong, dan Hongkong merupa-
kan tempat sirip ikan hiu terbesar dari
Indonesia. Dan World Wildlife Fund me-
nyatakan bahwa Indonesia adalah
pengekspor sirip ikan hiu terbesar di
dunia.
Apakah sebagai pengekspor
sirip ikan hiu, kemudian nelayan kita
menjadi makmur? Jawabannya sudah
jelas di depan mata kita. Tidak. Nelayan
kita tidak menjadi makmur walaupun
mereka mengeksplorasi hasil laut habis
habisan. Mengapa? karena mereka
kalah harga melawan pengepul ikan.
Nelayan kini menjadi buruh bagi industri
perikanan. Mereka hanya mencari ikan,
semen-tara pengusaha menyediakan
kapal, bahan bakar, logistik dan perleng-
kapan lainnya dalam menangkap ikan.
Akibatnya mereka dibayar murah dalam
penangkapan ikan, sementara sang
penguasa meraup keuntungan yang
sangat besar dalam perdagangan ikan-
ikan eksotis termasuk hiu.
Kementerian Kelautan Indo-
nesia menyatakan bahwa setiap tahun
nelayan Indonesia mengirimkan 73 juta
sirip hiu ke seluruh dunia, sementara
WWF menyatakan Indonesia menyum-
bangkan sebesar 100 juta sirip hiu. Jum-
lah yang sungguh luar biasa.
Pada tahun 2010, Shark
Conservation Act di Amerika serikat te-
lah memberlakukan larangan bagi
perburuan hiu. Sayangnya, aturan ini
mengalami hambatan di beberapa
negara bagian. Delapan negara bagian
telah sepakat untuk melarang penjualan
sirip ikan hiu. Termasuk melarang
restoran-restoran memperdagangkan
masakan sop hisit yang legendaris ini.
Negara-negara itu adalah : California,
Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland,
New York, Oregon dan Washington. Hal
yang sama juga berlaku di negara pasifik
seperti American Samoa, the Common-
wealth of Northern Mariana Islands dan
Guam. Negara bagian lain yang belum
menyepakati undang-undang ini adalah
Florida dan Texas, tempat banyak warga
Amerika keturunan Cina masih menye-
diakan sop hisit dalam pesta perkawinan
dan perayaan upacara tradisional
lainnya.
Di Indonesia, perburuan hiu
masih belum masuk dalam kegiatan
illegal. Namun tahun 2013 yang lalu,
pada pertemuan 177 negara pendukung
Convention on International Trade in
Endangered Species (CITES), di Thailand,
perdagangan hiu lintas negara akan
dilarang. Bahkan Hongkong sebagai
negara pengimpor terbesar juga diminta
untuk mulai mengurangi permintaan.
Begitu pula Cina, negeri leluhur sop sirip
hiu ini, bersepakat untuk tidak menye-
diakan sop hisit dalam menu kenegara-
an. Indonesia termasuk yang sepakat
dengan peraturan tersebut, dan
Kementrian Kelautan akan membuat
ratifikasi dari kesepakatan tersebut
dalam bentuk Peraturan Menteri yang
akan segera ditetapkan pada 2014.
Masalahnya adalah bagai-
mana pengawasan peraturan ini akan
diberlakukan? Garuda Indonesia, mas-
kapai penerbangan terbesar di Indo-
nesia telah menyatakan, tidak akan
mengangkut ekspor produk ikan hiu
dalam kargonya. Kebijakan ini berlaku
efektif sejak Oktober 2013. Ini merupa-
kan langkah awal yang harus diapresiasi,
namun di pihak lain pemerintah perlu
meningkatkan kewaspadaan akan ter-
jadinya perdagangan hiu ilegal yang
dilakukan di tengah laut.
Bisa saja nelayan tidak mem-
bawa sirip hiu ke darat namun langsung
bertransaksi dengan kapal lain di tengah
laut yang susah dijangkau oleh penga-
matan patroli laut. Hal semacam ini ke-
rap terjadi dalam penyelundupan satwa-
satwa dilindungi yang semakin langka.
Selain pemerintah, saatnya lah
media massa dan media sosial memain-
kan peran yang besar dalam kampanye
penyelamatan hiu ini. Binatang yang
susah bereproduksi ini ( hanya beranak
2-3 tahun sekali) perlu mendapatkan
perhatian khusus. Karena terbukti
mereka memiliki pengaruh besar dalam
menjaga kelangsungan hidup ekosistem
di laut. Mitos-mitos bahwa hiu bisa men-
jadi obat kanker harus diluruskan, kare-
na hiu sendiri diketahui dapat terserang
bakteri dan virus yang menyerupai kan-
ker. Selain itu ingatlah bahwa sirip hiu
sesungguhnya tidak memiliki rasa apa-
pun. Yang enak adalah kuah yang
menjadi dasar dari sop tersebut, yang
umumnya dibuat dari kaldu ayam.
Media massa tidak boleh lagi
menayangkan kelezatan masakan
apapun jika masakan itu berasal dari
produk hiu dan satwa dilindungi lainnya.
Sebaliknya, media massa harus menjadi
bagian terdepan dari perlindungan
satwa dan kelestarian lingkungan hidup,
agar ekosistem di bumi ini tetap terjaga.

SAPHARA | 38
ETALASE
Amphibian Waterproof Hard Case iPhone 4
Belum lengkap rasanya bila berkegiatan di alam bebas namun tak mendokumen-
tasikan perjalanan. Explorer pasti banyak membawa berbagai macam gadget untuk mendoku-
mentasikan setiap kegiatan, entah Kamera Digital, Kamera DSLR, hingga Smartphone yang
multifungsi. Namun masih banyak pula kendala yang akan dialami Explorer, misalnya gadget
yang dibawa ternyata tidak tahan air.
Tapi tenang saja, bagi Explorer yang menggunakan iPhone 4, Proporta, Produsen
casing ponsel, sudah mengeluarkan Amphibian Waterproof Hardcase for iPhone 4. Hard Case
ini sudah diuji dan dijamin bakal tahan air sampai 3 meter. Explorer bisa mengambil foto dari
bawah air namun tetap bisa membuat dan menerima panggilan saat ponsel memakai Hard
Case . Hard Case ini Berbahan polikarbonat keras dan kulit silikon luar yang terlindung
terhadap air, kotoran, dan pasir. Harga yang dibandrol oleh produsen Hard Case ini adalah
$37,95 atau sekitar Rp455.400,-
Waterproof Case for Canon EOS 600D, Kiss X5, Rebel T3i
Mau mengabadikan momen video saat diving, Snorkeling, surfing, dan berbagai
kegiatan lainnya, tapi takut kamera rusak karena kemasukan air? Keep it Calm, Explorer!
Sekarang ada Waterproof Case untuk Canon EOS 600D. Tahan air sampai kedalaman 50
meter. Terbuat dari polikarbonat, plastik ABS, Clear plate glass, Stainless Steel, dan karet
EPDM, Waterproof Case ini tahan air sampai kedalaman 50 meter. Waterproof Case ini
juga bisa melindungi kamera Explorer dari air, pasir, salju, dan goresan. Waterproof Case
ini dibandrol dengan harga $398 atau sekitar Rp4.776.000,-. Wow! harga yang fantastis.
Tertarik untuk membeli, Explorer?
Waterproof Marine Camera HousingCase For Canon EOS DSLR
Hobi berkegiatan di air? Kali ini Dicapack berhasil meraih Korean Consumer
Award to Best New Product pada tahun 2005 karena produknya, Waterproof Marine
Camera Housing Case For Canon EOS DSLR, yang dijual dengan harga yang terjangkau.
Camera Housing ini mampu bertahan hingga kedalaman 5 meter. Desainnya yang
menarik dan simpel memudahkan Explorer berfoto dan mengambil video karena ada
tali leher dan beratnya hanya 0,8 Pound. Camera Housing ini juga tahan terhadap
berbagai cuaca. Dengan Camera Housing ini, lensa mampu memanjang hingga 3,7'' dan
diameter 82mm. Camera Housing ini dibandrol dengan harga $88,95 atau sekitar
Rp1.067.400,-
Foto: google.com

SAPHARA | 39
REVIEW
“Memahat sendi lutut dengan
pahat kayu dan martil”, “Operasi Sesar
dengan Silet”, dan “Kasus Luka Tusuk
Panah” menjadi sebagian pengalaman
tak terlupakan bagi John Manangsang,
dokter muda jebolan FKUI yang bertugas
selama dua tahun di Puskesmas Tanah
Merah Boven Digul,Kecamatan Man-
dobo, Kabupaten Merauke, Papua.
Pengalaman ini pun ia tuliskan dalam
bukunya pada BagianII: Kasus-kasus
medis sulit dalam dilema.
Seorang bapak setengah baya
dari RT Mariam, sebuah RT dari Desa
Sokanggo yang dapat ditempuh
menggunakan perahu motor sekitar 4
jam melawan arus Sungai Digul datang
ke Puskemas Tanah Merah. Dari peme-
riksaan, diketahui sang bapak menderita
artrodesis (kekakuan sendi dalam istilah
kedokteran) di bagian lutut kanan . Tidak
ada jalan keluar selain operasi. Sang
bapak yang sangat menginginkan kaki-
nya berfungsi normal pun diminta dr.
John untuk mempersiapkan diri.
Awal April 1991, operasi
dilakukan. Pasien diberikan anestesi lo-
kal, sehinga tubuh bagian bawahnya
tidak berasa. John melakukan pembe-
dahan pada bagian lipatan antara paha
dan betis. Sayangnya, tulang dan sendi
pasien sudah menyatu bagaikan sepo-
tong besi. Mau ditutup kembali, tetapi
John kemudian merasa sangat prihatin.
Pertimbangannya antara lain: pertama,
keinginan pasien untuk sembuh tidak
tercapai, dan kedua, John dan timnya
merasa telah menyakiti pasien dengan
proses pembedahan yang ternyata tidak
menghasilkan.
Dengan dua pertimbangan
utama tersebut, John memutar akal un-
tuk mengobati pasien. Ia pun meminta
salah seorang perawat untuk meminjam
obeng, pahat kayu, dan martil. Tujuan-
nya, pemahatan akan berguna memberi-
kan ruang-ruang agar sendi dan tulang
dapat bergerak seperti umumnya. Puji
syukur, operasi yang dipenuhi rasa
improvisasi, intuisi, dan keinginan besar
sang dokter menyembuhkan pasiennya
pun dapat berhasil. Enam minggu sete-
lah perawatan, pasien mulai belajar
menginjakan kaki ke tanah. Dengan se-
mangat dan dukungan dari keluarga ser-
ta pihak puskesmas, sang bapakpun da-
pat kembali ke kampung halamannya.
Selain 13 kisah yang men-
cengangkan, masih ada pula petualang-
an John dan timnya sebagai dokter ter-
bang. Hal ini dilakukan dalam rangka
pelaksanaan program “Puskesmas Keli-
ling” ke semua desa di Kecamatan Man-
dobo. Perjalanan menjelajah rimba
berhari-hari meraka lakukan. Membuat
semur ayam hutan, mendirikan bifak,
berjuang melawan serangan pacet
menjadi warna petualangan ini, disam-
ping misi utama memberikan pelayanan
kesehatan. Sekumpulan kisah ini
menghabiskan sekitar 50 halaman buku.
Menurut Penulis, buku ini
memiliki banyak keunggulan. Pertama,
John mampu memberikan gambaran
kondisi alam dan sosial-masyarakat
masyarakat pedalaman Digul melalui
kacamata seorang ahli medis. Hal ini
tentu tidak akan sahabat Explorer temui
dalam buku perjalanan ataupun gam-
baran sosial-masyarakat umumnya.
Kedua, berbagai pendapat dari ahli
kesehatan, ahli hukum, sastrawan,
budayawan Papua semakin menguatkan
kualitas buku bagi pembaca. Dari sudut
pandang ahli inilah sahabat Explorer
juga dapat memberikan penilaian.
Ketiga, John menuliskan dengan detail
setiap kronologi kejadian yang ia alami.
Contohnya, saat bercerita mengenai
operasi sesar, maka ia menuliskan
proses mulai dari adanya laporan, run-
tutan tindakan medis yang dilakukan,
apa yang ia dan timnya rasakan, sampai
pada tahap akhir kesembuhan pasien.
Hal ini tentu membuat sahabat Explorer
memiliki gambaran mengenai peristiwa
yang terjadi. Keempat, terdapat foto-
foto dokumentasi rekam medis ataupun
perjalanan. Walaupun beberapa foto
terlihat agak mengerikan (foto-foto
operasi), tetapi hal ini penting sebagai
penguat data dalam buku.
Tiada gading yang tak retak.
Ternyata ungkapan tersebut juga
berlaku bagi buku ini. Walaupun karya
indah John sangat bagus dan orisinil,
tetapi terdapat beberapa kekurangan
yang dapat mengganggu pembaca
“bertualang” dengan kisah di dalam
buku. Pertama, dalam 1 halaman, John
sering hanya menggunakan 2 atau 3
pragraf. Malah ada 1 halaman hanya
untuk menulis 1 paragraf. Hal ini dapat
membuat sahabat Explorer lelah akibat
struktur penulisan dalam paragraf yang
kurang menarik. Kedua, gaya bercerita
penulis buku yang kurang memikat. Hal
ini menurut Penulis sangat wajar karena
John memang bukan jebolan sekolah
sastra ataupun komunikasi. Walaupun
begitu, gaya bercerita John menjadi
sangat khas.
Buku yang mengantarkan John
Manansang menjadi “Pemenang
Peneliti Muda LIPI – TVRI bidang Sosial,
Kebudayaan dan Kemanusiaan 1995 –
1996” ini cocok untuk semua sahabat
Explorer yang tertarik pada dunia medis
dan sosial-budaya. Kisah-kisah di dalam-
nya akan memberikan pengalaman dan
wawasan baru bagi pembaca mengenai
dua dunia tersebut. Karya ini pun cocok
bagi sahabat Explorer yang tertarik
dengan kehidupan di belantara Papua,
yang menurut John tidak banyak
berubah sejak 15 tahun semenjak
pengabdiannya pada awal 1990-an.
Jadi, apakah sahabat Explorer tertarik
meyaksikan kisah seorang dokter di
pedalaman Papua?
“Memahat sendi lutut dengan
pahat kayu dan martil”, “Operasi Sesar
dengan Silet”, dan “Kasus Luka Tusuk
Panah” menjadi sebagian pengalaman
tak terlupakan bagi John Manangsang,
dokter muda jebolan FKUI yang bertugas
selama dua tahun di Puskesmas Tanah
Merah Boven Digul,Kecamatan Man-
dobo, Kabupaten Merauke, Papua.
Pengalaman ini pun ia tuliskan dalam
bukunya pada BagianII: Kasus-kasus
medis sulit dalam dilema.
Seorang bapak setengah baya
dari RT Mariam, sebuah RT dari Desa
Sokanggo yang dapat ditempuh
menggunakan perahu motor sekitar 4
jam melawan arus Sungai Digul datang
ke Puskemas Tanah Merah. Dari peme-
riksaan, diketahui sang bapak menderita
artrodesis (kekakuan sendi dalam istilah
kedokteran) di bagian lutut kanan . Tidak
ada jalan keluar selain operasi. Sang
bapak yang sangat menginginkan kaki-
nya berfungsi normal pun diminta dr.
John untuk mempersiapkan diri.
Awal April 1991, operasi
dilakukan. Pasien diberikan anestesi lo-
kal, sehinga tubuh bagian bawahnya
tidak berasa. John melakukan pembe-
dahan pada bagian lipatan antara paha
dan betis. Sayangnya, tulang dan sendi
pasien sudah menyatu bagaikan sepo-
tong besi. Mau ditutup kembali, tetapi
John kemudian merasa sangat prihatin.
Pertimbangannya antara lain: pertama,
keinginan pasien untuk sembuh tidak
tercapai, dan kedua, John dan timnya
merasa telah menyakiti pasien dengan
proses pembedahan yang ternyata tidak
menghasilkan.
Dengan dua pertimbangan
utama tersebut, John memutar akal un-
tuk mengobati pasien. Ia pun meminta
salah seorang perawat untuk meminjam
obeng, pahat kayu, dan martil. Tujuan-
nya, pemahatan akan berguna memberi-
kan ruang-ruang agar sendi dan tulang
dapat bergerak seperti umumnya. Puji
syukur, operasi yang dipenuhi rasa
improvisasi, intuisi, dan keinginan besar
sang dokter menyembuhkan pasiennya
pun dapat berhasil. Enam minggu sete-
lah perawatan, pasien mulai belajar
menginjakan kaki ke tanah. Dengan se-
mangat dan dukungan dari keluarga ser-
ta pihak puskesmas, sang bapakpun da-
pat kembali ke kampung halamannya.
Selain 13 kisah yang men-
cengangkan, masih ada pula petualang-
an John dan timnya sebagai dokter ter-
bang. Hal ini dilakukan dalam rangka
pelaksanaan program “Puskesmas Keli-
ling” ke semua desa di Kecamatan Man-
dobo. Perjalanan menjelajah rimba
berhari-hari meraka lakukan. Membuat
semur ayam hutan, mendirikan bifak,
berjuang melawan serangan pacet
menjadi warna petualangan ini, disam-
ping misi utama memberikan pelayanan
kesehatan. Sekumpulan kisah ini
menghabiskan sekitar 50 halaman buku.
Menurut Penulis, buku ini
memiliki banyak keunggulan. Pertama,
John mampu memberikan gambaran
kondisi alam dan sosial-masyarakat
masyarakat pedalaman Digul melalui
kacamata seorang ahli medis. Hal ini
tentu tidak akan sahabat Explorer temui
dalam buku perjalanan ataupun gam-
baran sosial-masyarakat umumnya.
Kedua, berbagai pendapat dari ahli
kesehatan, ahli hukum, sastrawan,
budayawan Papua semakin menguatkan
kualitas buku bagi pembaca. Dari sudut
pandang ahli inilah sahabat Explorer
juga dapat memberikan penilaian.
Ketiga, John menuliskan dengan detail
setiap kronologi kejadian yang ia alami.
Contohnya, saat bercerita mengenai
operasi sesar, maka ia menuliskan
proses mulai dari adanya laporan, run-
tutan tindakan medis yang dilakukan,
apa yang ia dan timnya rasakan, sampai
pada tahap akhir kesembuhan pasien.
Hal ini tentu membuat sahabat Explorer
memiliki gambaran mengenai peristiwa
yang terjadi. Keempat, terdapat foto-
foto dokumentasi rekam medis ataupun
perjalanan. Walaupun beberapa foto
terlihat agak mengerikan (foto-foto
operasi), tetapi hal ini penting sebagai
penguat data dalam buku.
Tiada gading yang tak retak.
Ternyata ungkapan tersebut juga
berlaku bagi buku ini. Walaupun karya
indah John sangat bagus dan orisinil,
tetapi terdapat beberapa kekurangan
yang dapat mengganggu pembaca
“bertualang” dengan kisah di dalam
buku. Pertama, dalam 1 halaman, John
sering hanya menggunakan 2 atau 3
pragraf. Malah ada 1 halaman hanya
untuk menulis 1 paragraf. Hal ini dapat
membuat sahabat Explorer lelah akibat
struktur penulisan dalam paragraf yang
kurang menarik. Kedua, gaya bercerita
penulis buku yang kurang memikat. Hal
ini menurut Penulis sangat wajar karena
John memang bukan jebolan sekolah
sastra ataupun komunikasi. Walaupun
begitu, gaya bercerita John menjadi
sangat khas.
Buku yang mengantarkan John
Manansang menjadi “Pemenang
Peneliti Muda LIPI – TVRI bidang Sosial,
Kebudayaan dan Kemanusiaan 1995 –
1996” ini cocok untuk semua sahabat
Explorer yang tertarik pada dunia medis
dan sosial-budaya. Kisah-kisah di dalam-
nya akan memberikan pengalaman dan
wawasan baru bagi pembaca mengenai
dua dunia tersebut. Karya ini pun cocok
bagi sahabat Explorer yang tertarik
dengan kehidupan di belantara Papua,
yang menurut John tidak banyak
berubah sejak 15 tahun semenjak
pengabdiannya pada awal 1990-an.
Jadi, apakah sahabat Explorer tertarik
meyaksikan kisah seorang dokter di
pedalaman Papua?
Kisah Dokter di Pedalaman PapuaTeks & Foto: Hafiyyan
Judul buku:
Papua Sebuah Fakta dan Tragedi Anak Bangsa
Penulis: dr. John Manangsang
Penerbit: Yayasan Obor, Jakarta
Tahun terbit: 2007 (cetakan II)
Tebal buku: 477 halaman