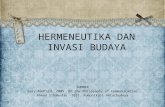REKONSTRUKSI METODOLOGI KRITIK TAFSIR:...
Transcript of REKONSTRUKSI METODOLOGI KRITIK TAFSIR:...

i
REKONSTRUKSI
METODOLOGI KRITIK TAFSIR: Studi Buku al-Dakhi>l Karya Fa>yed (1936-1999 M)
Oleh:
Muhammad Ulinnuha
NIM: 10.3.00.1.05.08.0025
Promotor:
Prof. Dr. Said Agil Husin al-Munawwar, MA.
Prof. Dr. Hamdani Anwar, MA.
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1436 H/2015 M

ii

iii
KATA PENGANTAR
Alh}amdulilla>h, puji syukur ke hadirat Allah Swt. Karena berkat
‘ina>yah, rahmat dan hidayah-Nya, penulisan disertasi ini dapat diselesaikan.
Shalawat dan salam tak luput penulis curahkan keharibaan sang penafsir
sekaligus ‘kritikus’ tafsir Al-Qur’an, Nabi Muhammad Saw, beserta para
keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.
Jamak diketahui bahwa Al-Qur’an telah melahirkan sejumlah teks
turunan yang luar biasa. Teks turunan ini dikenal dengan literatur tafsir.
Kitab-kitab tafsir tersebut tidak sekadar jumlahnya yang banyak, tapi juga
corak, pendekatan dan bentuk metode yang dipakai penulisnya pun beragam
dan berbeda-beda.
Keberagaman karya tafsir ini di satu sisi sangat membanggakan, tapi
di sisi lain memprihatinkan. Membanggakan, karena dibanding kitab suci
lain, hanya Al-Qur’an-lah yang memiliki tafsiran paling banyak dan
beraneka macam. Memprihatinkan, sebab diantara sejumlah karya tersebut,
penafsirannya banyak yang dibangun di atas pondasi kepentingan mufasir.
Mulai dari kepentingan ideologis, ekonomi, politik, sains dan seterusnya.
Universalitas dan komprehensifitas Al-Qur’an, ketika didekati dan
ditafsiri dengan basis kepentingan-kepentingan subjektif mufasir, tentu akan
tercerabut dan pada tahap tertentu akan hilang. Kekhawatiran akan
tercerabutnya universalitas dan komprehensivitas Al-Qur’an ini, coba
dijawab oleh sebagian intelektual dengan mengetengahkan metode kritik
tafsir Al-Qur’an. Salah satu yang menawarkan metode kritis tersebut adalah
‘Abd al-Wahha>b Fa>yed dengan teori kritik tafsir infiltratif (al-dakhi>l)-nya.
Hanya saja, tawaran metode kritis Fa>yed ini masih menyisakan
permasalahan, terutama pada sisi sistematika dan struktur metodisnya.
Karena itu, penulis tertarik untuk meneliti, menyelami dan menghirup
aroma kritis Fa>yed itu dengan pisau analisis dan pendekatan ilmu-ilmu
kontemporer, terutama teori kritik hadis, kritik sastra dan hermeneutika
objektif. Walhasil, penelitian dengan tajuk ‚Rekonstruksi Metodologi Kritik
Tafsir‛ ini pun berhasil dipersembahkan ke hadapan sidang pembaca yang
budiman.
Dalam penyelesaian penulisan disertasi ini, tentu tidak lepas dari
bantuan dan kontribusi banyak pihak. Untuk itu sudah selayaknya penulis
menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada
semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian disertasi ini,
baik secara moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung.
Wabilkhusus, untaian terimakasih dan penghargaan tersebut penulis
sampaikan kepada:

iv
Pertama, Prof. Dr. Said Agil Husin al-Munawwar, MA. dan Prof. Dr.
Hamdani Anwar, MA., selaku Promotor, yang telah memberikan arahan dan
bimbingan yang sangat berharga bagi penulis. Di sela-sela kesibukan beliau
berdua yang sangat padat, tak sedikit pun mengurangi keseriusan dan
kesungguhan dalam melakukan koreksi dan pengarahan untuk penulisan
disertasi ini.
Kedua, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., Direktur Sekolah
Pascasarjana UIN Jakarta yang telah menyuntikkan beragam kebijakan baru
menuju pencapaian riset yang berkualitas.
Ketiga, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA., (Rektor UIN Jakarta
Periode 2010-2014), dan Prof. Dr. Dede Rosyada, MA (Rektor UIN Jakarta
Periode 2015-2019) yang telah memberikan warna dan iklim akademik yang
kondusif bagi pembentukan kajian keislaman dan wawasan global, melalui
berbagai kebijakan strategis yang diambil.
Keempat, Deputi Sekolah Pascasarjana, Prof. Dr. Suwito, MA., dan
Dr. Yusuf Rahman, MA., beserta seluruh staf administrasi, umum dan
pustaka, khususnya Bu Imah, Bang Adam dan segenap staf SPs UIN Jakarta,
yang telah memberikan layanan, bantuan dan dukungan dalam komitmen
profesionalitas akademik yang tinggi.
Ketujuh, segenap Guru Besar dan dosen SPs UIN Jakarta yang
dengan tulus ikhlas telah mengajar, mencurahkan ilmu dan ide-ide kritisnya
kepada penulis. Wabilkhusus, Prof. Yunan Yusuf, MA., Prof. Zainun Kamal,
MA., Prof. Nazarudin Umar, MA., Prof. Ahmad Thib Raya, MA., Prof.
Salman Harun, MA., Prof. Dr. M. Ishom Yusqi, MA., Prof. Dr. Atho
Muzhor, MA., Prof. Abdul Mujib, MA., Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Dr.
Suparto, MA. dan segenap dosen Pascasarjana yang telah memberikan
curahan ilmu dan gagasan yang sangat brilian sehingga berhasil
mengantarkan penulis menyelesaikan studi doktoral ini.
Kedelapan, Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Periode
2009-2014, Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA., dan Rektor IIQ Jakarta
Periode 2014-2018, Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA., serta segenap
jajaran pimpinan kampus yang telah memberikan izin dan dukungan kepada
penulis untuk menyelesaikan program doktor di SPs UIN Jakarta. Juga
kepada segenap karyawan, dosen dan civitas akademika IIQ Jakarta yang
telah memberikan suntikan doa dan support kepada penulis.
Kesembilan, tak lupa, penulis sampaikan terima kasih juga kepada
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama Republik
Indonesia yang telah memberikan fasilitas Beasiswa Studi (BS-2010),
sehingga penulis dapat menyelesaikan program ini, walau agak sedikit
molor dari jadual yang ditetapkan. Selanjutnya, ucapan terimakasih juga
penulis sampaikan kepada teman-teman BS-10, Kang Suprapto, Kang Nurul
Huda, Keh Musholly Ready, Pak Ali Mursyid, Kang Nurjannah, Pak Eva

v
Nugraha, Pak Arifullah dan semua teman yang tidak mungkin disebutkan
namanya satu persatu. Kalian semua adalah sahabat-sahabat terbaik, semoga
kebersamaan kita dalam mengasah ketajaman intelektual terus berlanjut dan
mendatangkan manfaat untuk bangsa ini.
Teman-teman alumni Pesantren Tarbiyatut Tholabah di Jakarta
yang tergabung dalam WASIAT Jakarta, teman-teman diskusi di Al-Ghazali
Center (almarhum), teman-teman seperjuangan di STAINU Jakarta, teman-
teman diskusi di PSPP, teman-teman Pendidikan Kader Mufasir (PKM)
Pusat Studi Al-Qur’an (PSQ), khususnya angkatan 2010 dan jama’ah
pengajian Nurul Hasanah PBR. Juga kepada Kang Dr. Sahiron Syamsuddin
yang secara ikhlas telah memberikan masukan dan membagi file buku-buku
tentang hermeneutika secara gratis. Mas brow Hamam Faizin yang telah
membantu nge-proof beberapa bagian dari tulisan ini. Doa, dorongan dan
support Bapak/Ibu/Sdr/i semua adalah obat paling mujarab sekaligus
motivasi luar biasa bagi penulis dalam proses penyelesaian disertasi ini.
Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis juga menyampaikan
sungkem ta‘z}i>m dan terima kasih yang seagung-agungnya kepada kedua
orangtua penulis, Ayahanda Husnan Utsman dan Ibunda Musyariah, yang
tak henti-hentinya berdoa dan memberikan motivasi serta dukungan kepada
penulis. Semoga di usia beliau yang sudah senja, beliau berdua senantiasa
diberikan kesehatan dan keberkahan hidup oleh Allah Swt. Kepada Bapak
dan Ibu Mertua penulis, M. Yasin (alm) dan Siti Maryam, juga kepada
istriku tercinta, Yulianti, M.Si., yang telah memberikan dukungan, doa dan
cinta kasihnya. Terimaksih sayang atas pengertian, pengorbanan, dan
support yang selalu engkau berikan. Engkau telah memancarkan energi
positif di saat aku kehabisan semangat untuk merampungkan penulisan
disertasi ini.
Kepada kedua putra/putriku, Kaisa Fadhlillah (Icha) dan M. Zidny
Atho’illah (Zidny), kalian adalah permata hati ayah. Waktu ayah untuk
kalian banyak tersita demi penyelesaian disertasi ini. Pedih rasanya nak, tapi
itulah kehidupan. Ada hal yang harus ‘dikorbankan’ sementara waktu, demi
menggapai kebahagiaan selanjutnya. Namun, percayalah wahai anak-
anakku, dari relung hati yang paling dalam, ayah selalu berdoa untuk kalian,
semoga apa yang ayah lakukan ini dapat memacu kalian untuk menimba
ilmu sedalam dan setinggi mungkin. Yang lebih penting dari itu semua,
semoga kemudahan dan keberkahan hidup selalu menyelimuti kalian semua
anak-anaku sayang.
Tak lupa kepada adik-adikku, Lailatul Fawaidah, M. Asy’ari dan
istrinya, Zahra, beserta putrinya, Aisyah Aqela, juga kepada adik-adik
iparku, Ita dan suaminya, Cecep beserta kedua putrinya, serta Jamal, Dede,
dan Moyya Tahra. Semoga doa dan dukungan adik-adik sekalian dibalas

vi
oleh Allah Swt dengan pahala yang agung, dan capaian penulis ini menjadi
pemantik semangat kalian untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi.
Akhirnya, untaian terima kasih juga penulis sampaikan kepada
semua pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu namanya
dalam lembaran kertas yang terbatas ini. Penulis hanya dapat meyampaikan
doa; Jaza>kumulla>h Ah}san al-Jaza>’. Semoga Allah membalas amal baik kita
semua dengan balasan yang jauh lebih baik.
Terakhir, kendatipun penulisan disertasi ini telah dilakukan dengan
proses yang hati-hati dan teliti serta melibatkan berbagai pihak, baik dalam
maupun luar negeri, namun penulis menyadari bahwa disertasi ini tidak akan
luput dari kesalahan dan kekuarangan. Karena itu, penulis selalu terbuka
menerima masukan dan saran konstruktif dari pembaca, demi perbaikan dan
penyempurnaan disertasi ini ke depan. Akhirnya, penulis berharap semoga
Allah Swt senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemanfaatan atas
disertasi ini. Amin.
Di penghujung malam tahun baru
Puri Bintaro Residence, Serua Indah
Ciputat, 1 Desember 2015
Ttd.
Muhammad Ulinnuha

vii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Muhammad Ulinnuha
NIM : 10.3.00.1.05.08.0025
Tempat Tugas : Fak. Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta
Alamat : Puri Bintaro Residence I Blok D-27 Rt. 007/004 Serua
Indah, Ciputat, Tangerang Selatan 15414.
menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi dengan judul ‚Metodologi
Kritik Tafsir: Studi Buku al-Dakhi>l Karya Fa>yed (1936-1999 M)‛ adalah
hasil karya penulis pribadi, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan
yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di
kemudian hari terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi
tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
Ciputat, 30 Januari 2015
Muhammad Ulinnuha

viii

ix
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Setelah diadakan pembimbingan dan melalui rangkaian Ujian Works in Progress (WIP) serta Ujian Pendahuluan dan perbaikan sesuai dengan saran
Pembimbing dan Tim Penguji, maka disertasi dengan judul ‚Metodologi Kritik
Tafsir: Studi Buku al-Dakhi>l Karya Fa>yed (1936-1999 M)‛ yang disusun
oleh:
Nama : Muhammad Ulinnuha
NIM: : 10.3.00.1.05.08.0025
Konsenterasi : Tafsir Hadis
telah disetujui untuk diajukan pada Ujian Terbuka (Promosi) di Sekolah
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, Januari 2015
Promotor,
Prof. Dr. Said Agil Husin al-Muanawwar, M.A.

x

xi
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Setelah diadakan pembimbingan dan melalui rangkaian Ujian Works in Progress (WIP) serta Ujian Pendahuluan dan perbaikan sesuai dengan saran
Pembimbing dan Tim Penguji, maka disertasi dengan judul ‚Metodologi Kritik
Tafsir: Studi Buku al-Dakhi>l Karya Fa>yed (1936-1999 M)‛ yang disusun
oleh:
Nama : Muhammad Ulinnuha
NIM: : 10.3.00.1.05.08.0025
Konsenterasi : Tafsir Hadis
telah disetujui untuk diajukan pada Ujian Terbuka (Promosi) di Sekolah
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, Januari 2015
Promotor,
Prof. Dr. Hamdani Anwar, M.A.

xii

xiii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI
Setelah diadakan pembimbingan dan melalui rangkaian Ujian Works in Progress (WIP), Ujian Pendahuluan serta perbaikan sesuai dengan saran
Pembimbing dan Tim Penguji, maka disertasi dengan judul ‚Metodologi Kritik
Tafsir: Studi Buku al-Dakhi>l Karya Fa>yed (1936-1999 M)‛ yang disusun oleh
Sdr. Muhammad Ulinnuha (NIM: 10.3.00.1.05.08.0025), telah disetujui untuk
diajukan pada Ujian Terbuka (Promosi) di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, Januari 2015
TIM PENGUJI:
1. Prof. Dr. SUWITO, MA (………………………………)
(Ketua Sidang/merangkap Penguji) Tanggal:
2. Prof. Dr. AHMAD THIB RAYA, MA (………………………………)
(Penguji 1) Tanggal:
3. Prof. Dr. SALMAN HARUN, MA (………………………………)
(Penguji 2) Tanggal:
4. Prof. Dr. M. ISHOM YUSQI, MA (………………………………)
(Penguji 3) Tanggal:
5. Prof.Dr.SAID AGIL AL-MUNAWAR, MA (………………………………)
(Pembimbing/merangkap Penguji 1) Tanggal:
6. Prof. Dr. HAMDANI ANWAR, MA (………………………………)
(Pembimbing/merangkap Penguji 2) Tanggal:

xiv

xv
ABSTRAK
Disertasi ini menunjukkan bahwa kritik evaluatif-rekonstruktif atas
tafsir dapat merevitalisasi objektivitas pemahaman terhadap kitab suci (Al-
Qur’an). Maka, rekonstruksi dan strukturisasi metodologi kritik tafsir sangat
urgen dilakukan, agar produk-produk penafsiran dapat dianalisis secara
akademis, sistematis dan ‘objektif’. Disertasi ini pun menawarkan kaidah al-naqd li al-taqyi>m wa i‘a>dat al-bina>’ la> li al-tah}ki>k wa al-ifna>’ (kritik evaluatif-
rekonstruktif, bukan dekonstruktif-destruktif).
Disertasi ini sependapat dengan teori kritik inh}ira>f al-Dhahabi> (1915-
1977 M). Bedanya, jika dalam penelitian ini mengupas secara luas tentang
desain dan prinsip-prinsip metodologi kritik ‘Abd al-Wahha>b Fa>yed (1936-1999
M) dan proses rekonstruksinya, maka dalam buku al-Dhahabi> secara spesifik
mengkritisi berbagai penyelewangan (inh}ira>fa>t) penafsiran yang dilakukan
beberapa sekte dan aliran Islam. Disertasi ini juga sama dengan teori
hermeneutika objektifnya Schleiermacher (1768–1834 M) yang menekankan
pencarian makna asal teks. Sehingga perlu disusun metodologi kritik agar
makna tersebut tetap terjaga orisinalitasnya. Penelitian ini juga mendukung
teori kritik sastra Ami>n al-Khu>li> (1895-1966 M). Hanya saja al-Khu>li> lebih
spesifik mengkaji tentang kritisisme penafsiran dengan pendekatan sastra.
Sementara disertasi ini berupaya merekonstruksi, merestrukturisasi dan
melengkapi penelitian yang digagas Fa>yed dengan menambah variabel
metodologi kritik yaitu kritisisme terhadap penafsir (al-mufassir), metodologi
dan produk (content) penafsiran. Tawaran metodologis ini peneliti sebut
dengan teori kritik tafsir evaluatif-rekonstruktif.
Penelitian ini berbeda dengan teori hermeneutika Gadamer (1900–2002
M) yang memperlakukan teks sebagai barang mati, sehingga harus dibaca dan
dipahami dengan memproduksi makna baru yang sejalan dengan keinginan
pembaca. Disertasi ini juga berseberangan dengan Nas}r H{a>mid Abu> Zayd
(1943-2010) yang berasumsi bahwa Al-Qur’an adalah produk budaya (muntaj al-thaqa>fah), sehingga ia harus ditafsiri sesuai ruang dan waktu di mana sang
mufasir itu hidup.
Adapun sumber primer penelitian ini adalah buku al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m Karya ‘Abd al-Wahha>b ‘Abd al-Wahha>b Fa>yed (1936-1999
M). Sedangkan pambacaan terhadap sumber dilakukan dengan metode content analysis yang diadaptasi dari Klaus Krippendorff (l. 1932 M). Agar
mendapatkan sebuah gambaran serta hasil yang ilmiah dan komprehensif
mengenai bangunan metodologi kritik tafsir rekonstruktif, maka penelitian ini
memakai pendekatan sejarah (historical approaches), fenomonologis,
psikologis, kritik sastra, kritik hadis dan hermeneutika objektif.

xvi
ABSTRACT
This dissertation results that evaluative-reconstructive critics on
qur’anic the interpretation (tafsir) can revitalize the ‘objectivity’ of
understanding Qur'an. Therefore, the reconstruction and structuring on tafsir
methodology criticism is a must to analyze tafsirs academically, systematically
and 'objectively'. In this context, this disertation offers principle al-naqd li al-taqyi>m wa i'a>dat al-bina>' la> li al-tah}ki>k wa al-ifna>' (evaluative-reconstructive
criticism, not deconstructive-destructive one).
This dissertation is similar to the theory inh}ira>f of al-Dhahabi> (1915-
1977 AD) in his book, al-Ittija>ha>t al-Munh}arifah. But, in this research examines
widely on the design and principles of methodology criticism, and its
reconstruction process of 'Abd al-Wahha>b Fa>yed (1936-1999 AD). While al-
Dhahabi> specifically criticized various known aberration (inh}ira>fa>t) of
interpretations of some Islamic sects and mazhabs. This dissertation is also in
line with the theory of objective hermeneutic’s Schleiermacher (1768-1834
AD) that emphasized searching the the original meaning of texts. According to
him, it is necessary to arrange the criticism of methodology to maintain the
originality of meaning. This dissertation is also in line with the theory of
literary criticism’s Ami>n al-Khu>li> (1895-1966 AD). Al-Khu>li> examined more
interpretation by the literary approach. While this disertation tries to
reconstruct and complete Fa>yed’s idea by adding the variable of methodology
criticism that is criticism of the interpreter (al-mufassir) and the methodology
and product interpretation (al-tafsi>r). This methodological offering is called as
the criticism of reconstructive interpretation.
This dissertation differs from Gadamer (1900-2002 AD) theory of
hermeneutics that deal with the text as dead thing, so that the text must be read
and understood by producing new meanings that are in line with the interests of
readers. It also differs from Nas}r H{a>mid Abu> Zayd (1943-2010 AD)
methodology of interpretation stating that the Qur'an is a cultural product
(muntaj al-thaqa>fah) so it must to be interpreted according to the space and the
time of the mufasirs.
The primary sources of this dissertation is al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur'a>n
al-Kuri>m by 'Abd al-Wahha>b 'Abd al-Wahha>b Fa>yed (1936-1999 AD). While
analysis on resources will be done by the method content analysis that was
adapted from Klaus Krippendorff (b. 1932 AD). To get a clearer portrait,
comprehensive and scientific results of reconstructive criticism of
interpretation, then this research implies historical, fenomenologic, literary,
psychological, hadith criticisms and also objective hermeneutics.

xvii
ملخع البحح
ن الوكد الجكم خبجت ذى الرصالة ا
الجكم للجفشر منن ثوطؿ الفم المؽغ للن جاب وان)
ثحلو الجفشر ثحلال للدارصن لذا، فإغادة بواء مورة الوكد للجفشر مم زدا ه شو . (الكرا
هادما ومورا و ن ". مؽغا"ا
ا ؾا مبدا
ـروحة ثكدم ا
الوكد للجكم وإغادة البواء، ل "وذى ال
".للجحنم واإلفواء
ـروحة مماخلة لوظرة هكد ف ه جابي ( م1977-1915)الج لدما حشن الذب " الهحراف"وذى ال
ن ذى الدراصة ثبحح غن هفاق مورة الثراات الموحرفة ف الجفشر، بحح ن الخالف كع ف ا
اوإغادة الوظر فا، بوما وزي ه جاب الذب ( م1999-1936)ومبادئ هكد الجفشر غود غبد الاب فاد
ـروحة مع هظرة . اهجكاداثي لجفشر بػؼ الفائ ف والجارات اإلصالمة وف هفس اللت اثفكت ذى ال
غل ( م1834-1768)الرموـكا المؽغة ل طالرماخر مة البحح غن المػو ال
الذي ؤهد غل ا
غالجي لف موذ الوكد للحفاظ غل ا
ؾا موشرم مع . للوع، هما حح غل ؽرورة ثا
وذى الدراصة ا
من الخل دب ل
ل ه درا إل دراصة الجفشر من موظر الوكد ( م1966-1895)هظرة الوكد ال
الذي ا
ـروحة إل إغادة بواء هظرة هكد الدخو الذي ـرحا غبد الاب فاد، دب، بوما ثشػ ذى ال
ال
. إؽافة موا إل ثكدم ـركة الوكد من زة المفشر ومن زة مورجي ومن زة مؾمن ثفشرى
وو الذاث ل غادامر الذي ػامو الوع هطء ( م2002-1900)وثخجلف ذى الدراصة من هظرة الجا
و المفشر فم من خالل إهجاج مػو زدد جفق مع رغبات الكارئ ا و
كرا ن
. زامد ومت، لذلم رب ا
ب زد ؾا هظرة هػر حامد ا
ن موجذ خكاف، ف ال بد لي ( م2010-1943)هما غارت ا
ن الكرا
الكائو با
ثفشرا جواصب مع المنان والزمان الذي هان ػض في المفشر بغؼ الوظر غن خلفة من ثفشرى .الوزول وغػر الوبة ولدصة الن جاب
صاص لذا البحح ف ه جاب ما المػدر ال
ن النرم"وا
لػبد الاب غبد " الدخو ف ثفشر الكرا
ذا الن جاب بفركة ثحلو المحجى المكجبس من هالوس( م1999-1936)الاب فاد ، بحح كرا
وللحػل غل هظرة غامة فؾال غن هجائذ المػلمات الػلمة وظاملة غل . ( م1932. و)هرفودورف ، (الظاراثة)إغادة بواء مورة هكد الجفشر، اصجخدم ذا البحح الموذ الجارخ، والفومولزا
دب، وهكد الحدح والرموـكا المؽغة للمكاربة .وغلم الوفس الفشلز، والوكد ال

xviii

xix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
A.Konsonan
b = ب
t = ت
th = ث
j = ج
h{{{{ = ح
kh = خ
d = د
dh = ذ
r = ر
z = ز
s = س
sh = ش
s} = ص
d{ = ض
t{ = ط
z{ = ظ
ع = ‘
gh = غ
f = ف
q = ق
k = ك
l = ل
m = م
n = ن
h = ه
w = و
ء = ’
y = ي
B. Vokal
1. Vokal Tunggal
Tanda Nama Huruf Latin Nama
fath}ah a A ــــ
kasrah i I ـــــ
ـ d}ammah u U ــــ
2. Vokal Rangkap
Tanda Nama Gabungan Huruf Nama
ى ... fath}ah dan ya>’ Ay a dan y
و ... fath}ah dan wawu Aw a dan w
Contoh: سين ل H{usayn : حـ H{awl : حوـ

xx
C. Panjang (Madd)
Tanda Nama Huruf Latin Nama
fath}ah dan alif a> a dan garis di atas ــــا
kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ـــــي
d}ammah dan wawu ū u dan garis di atas ـــــو
D. Ta>’ Marbu>t}ah ( ( ت ) dan Mabsu>t}ah ( ة
Transliterasi ta>’ marbu>t}ah ditulis dengan ‚h‛ baik dirangkai dengan
kata sesudahnya maupun tidak. Contoh: مرأة : mar’ah, مدرسة : madrasah, المنورة المدينة : al-Madi>nah al-Munawwarah.
Adapun ta>’ mabsu>t}ah ditulis dengan ‚t‛ baik dirangkai dengan kata
sesudahnya maupun tidak, contoh التأويل آليات : aliya>t al-ta’wi>l, مسلمات :
muslima>t.
E. Shaddah
Shaddah atau tashdi>d, dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang
sama dengan huruf yang bershaddah tersebut.
Contoh: ربــنا : rabbana> ل دة ,nazzal : نزـ sayyidah : سي
Sedangkan khusus huruf ya>’ yang ditashdi>d dan huruf sebelumnya
berharakat kasrah, maka dilambangkan dengan huruf ‚ i> ‛ panjang dan
diikuti huruf ‚ ya>’ ‚.
Contoh ية ية ,al-mis}ri>yah : المصرـ qad}i>yah : قضـ
F. Kata Sandang ‚ ال ‚
Semua kata sandang ‚الـ ‛ dilambangkan dengan ‚al‛ baik diikuti huruf
shamsi>yah maupun diikuti huruf qamari>yah.
Contoh الشمس : al-Shams القلم : al-Qalam
Khusus untuk kata الحديث ,السنة ,القرآن dan nama-nama surat Al-Qur’an
akan ditulis sesuai standar baku, yaitu: القرآن : Al-Qur’an, السنة : Sunnah,
Al-Baqarah, kecuali bila ia adalah transliterasi dari : البقرة ,Hadis : الحديث
judul buku atau tulisan, seperti الكريم القرآن تفسير : Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m,
الحديث كتب : Kutub al-H{adi>ts, المطهرة السنة : al-Sunnah al-Mut}ahharah.
G. Pengecualian Transliterasi
Pengecualian transliterasi adalah kata-kata bahasa arab yang telah
lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dan menjadi bagian dalam
bahasa Indonesia, seperti lafal هللا (Allah), هللا رسول (Rasulullah), هللا عبد
(‘Abdullah), الرحمن عبد (‘Abdurrah}ma>n), سورة (surat), asma’ul h}usna> dan ibn,
kecuali menghadirkannya dalam konteks aslinya dan dengan pertimbangan
konsistensi dalam penulisan.

xxi
DAFTAR ISI
COVER DALAM ~ i
KATA PENGANTAR ~ iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ~ vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ~ ix
PERSETUJUAN TIM PENGUJI ~ xiii
ABSTRAK ~ xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ~ xix
DAFTAR ISI ~ xxi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN ~ xxiii
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ~ 1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah ~ 14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ~ 15
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan ~ 16
E. Metodologi Penelitian ~ 20
F. Teknik dan Sistematika Penulisan ~ 26
BAB II: DISKURSUS METODOLOGI KRITIK TAFSIR
A. Epistema Metodologi Kritik Tafsir ~ 29
1. Hakekat Metodologi Kritik Tafsir ~ 29
2. Historisitas Kritisisme ~ 36
3. Bentuk dan Tujuan Kritik ~ 41
4. Landasan Hukum Kritik Penafsiran ~ 42
5. Prinsip dan Parameter Kritik Tafsir ~ 46
B. Berbagai Metodologi dan Pendekatan Kritik Tafsir ~ 59
1. Kritik Sejarah ~ 60
2. Kritik Sastra ~ 64
3. Hermeneutika ~ 66
4. Kritik al-Inh}ira>f ~ 70
5. Kritik al-Dakhi<l ~ 71

xxii
BAB III: POTRET AL-DAKHI<L FI < TAFSI<R AL-QUR’A<N AL-KARI<M
A. Profil Penulis al-Dakhi>l ~ 75
B. Identifikasi Buku al-Dakhi>l ~ 77
1. Materi dan Sistematika Penyajian ~ 77
2. Latar Penulisan ~ 80
3. Sumber Rujukan ~ 82
4. Metode, Pendekatan dan Ideologi Buku ~ 86
BAB IV: KONSTRUKSI DAN PROSEDUR KRITIK AL-DAKH<L
A. Antara Otentisitas dan Infiltrasi Penafsiran ~ 89
B. Perkembangan, Motif dan Bentuk al-Dakhi>l ~ 94
C. Basis dan Sumber Otentik Tafsir ~ 106
D. Prosedur dan Aplikasi Kritik Tafsir Infiltratif (al-Dakhi>l) ~ 129
BAB V: STRUKTURISASI METODOLOGI KRITIK TAFSIR
A. Problem Paradigmatik ~ 161
1. Lokalitas dan Universalitas Tafsir ~ 161
2. Subjektivitas dan Objektivitas Penafsiran ~ 163
3. Validitas Penafsiran ~ 170
B. Rekonstruksi Metode Kritik Tafsir ~ 177
1. Kritik Personalitas Mufasir ~ 178
2. Kritik Metodologis ~ 199
3. Kritik Produk Penafsiran ~ 212
BAB VI: PENUTUP
A. Kesimpulan ~ 223
B. Rekomendasi ~ 224
DAFTAR PUSTAKA ~ 225
GLOSARIUM ~ 249
INDEKS ~ 253
BIODATA PENULIS ~ 263

xxiii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN
Table 1 : Klasifikasi al-Dakhi>l ~ 105
Table 2 : Sumber-sumber Otentik Tafsir Al-Qur’an ~ 129
Tabel 3 : Konstruksi Baru Metodologi Kritik Tafsir Al-Qur’an ~ 219
Tabel 4 : Struktur Baru Metode Kritik Evaluatif-Rekonstruktif ~220
Bagan 1 : Konstruksi Metode Kritik Tafsir Infiltratif (al-Dakhi>l) ~ 158
Bagan 2 : Karakter Objektivitas dan Subjektivitas ~ 165
Bagan 3 : Komponen Karakter ~ 194
Bagan 4 : Alur Kritik Personalitas Mufasir ~ 199
Bagan 5 : Aspek Kritik Metodologis Tafsir Al-Qur’an ~ 212
Bagan 6 : Alur Kritik Produk Penafsiran ~ 218

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Secara metodologis, penafsiran Al-Qur’an dapat dilakukan melalui
dua pendekatan yaitu tekstual dan kontekstual.1 Namun dua pendekatan ini
dinilai al-Dhahabi> (1915-1977 M) telah terjerembab pada kesalahan
metodis. Pendekatan pertama terjatuh pada penghambaan mutlak pada teks
sehingga kerap mengabaikan tiga variabel utama penafsiran yaitu pengarang
(al-mutakallim bih/author), kepada siapa teks itu disampaikan (mukha>t}ab)
dan konteks pembicaraan (siya>q al-kala>m). Sementara pendekatan kedua
terseret pada pendewaan konteks sehingga acapkali teks diseret dan
ditundukkan sesuai selera penafsir dengan dalih kontekstualisasi dan
penyesuaian dengan tuntutan zaman.2
Hal senada disampaikan Nas}r H{a>mid Abu> Zayd (1943-2010 M),
menurutnya kedua model pendekatan tafsir ini masing-masing
mempresentasikan sudut pandang yang berbeda atas hubungan mufasir
dengan teks. Pendekatan tekstualis cenderung mangabaikan dan
memarginalkan eksistensi mufasir, lantaran membela teks dan berbagai
1 Abdullah Saeed membagi tipologi penafsiran Al-Qur’an kontemporer
menjadi tiga yaitu; tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis. Kelompok tekstualis
meyakini bahwa makna Al-Qur’an itu sudah fixed dan harus diaplikasikan secara
universal. Kelompok salafi termasuk penganut tipologi ini. Sedangkan semi-tekstualis
beruasaha membela makna literal Al-Qur’an dengan cara memakai idiom-idiom modern
dan argumentasi rasional. Termasuk tipologi ini adalah kelompok al-Ikhwan al-
Muslimun di Mesir dan Jama’at Islamiah di India. Sementara kelompok kontekstualis
memahami Al-Qur’an dengan tidak menyampingkan konteks politik, sosial, historis,
budaya, dan ekonomi di mana Al-Qur’an diturunkan, dipahami, dan diaplikasikan.
Tipologi inilah yang diikuti oleh misalnya Fazlur Rahman, Nas}r H{a>mid Abu> Zayd, dan
juga Abdullah Saeed sendiri. Lihat selengkapnya pada Abdullah Saeed, Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach (London and New York: Routledge, 2005).
2 Muhammad H{usayn al-Dhahabi>, al-Ittija>ha>t al-Munh}arifah fi> Tafsi>r al-Qur’a>n
al-Kari>m: Dawa>fi‘uha> wa Daf‘uha> (Kairo: Maktabah Wahbah, 1986), Cet. III, 20. Lihat
juga Ayman A. El-Desouky, ‚Between Hermeneutic Provenance and Textuality: The
Qur'an and the Question of Method in Approaches to World Literature‛, Journal of Qur'anic Studies, Volume 16, Issue 3, October 2014, Edinburgh University Press, 11-
38.

2
fakta historis dan kebahasaannya. Sementara pendekatan tektualis tidak
melupakan hubungan semacam ini, tetapi menegaskan dengan tingkat
penegasan dan aktifitas yang berlainan antar berbagai kelompok dan
kecenderungan yang menformulasikan sudut ini.3
Contoh pendekatan tekstualis tersebut misalnya, penafsiran ‘Adi> ibn
H>>{a>tim (w.67 H/688 M)4 terhadap kata al-khayt} al-abyad} dan al-khayt} al-aswad ayat 187 surat al-Baqarah,5 penafsiran sebagian sahabat terhadap kata
al-z}ulm pada ayat 82 surat al-An‘a>m,6 dan penafsiran ‘Abdullah ibn al-
Zab‘ari> terhadap ayat 98 surat al-Anbiya>’.7 Penafsiran tektualis seperti ini
3 Nas}r H{a>mid Abu> Zayd, Ishka>li>ya>t al-Qira>’ah wa A<liya>t al-Ta’wi>l (Bayru>t: al-
Markaz al-Thaqa>fi> al-‘Arabi>, 2005), Cet.V, 15-16. 4 Ia adalah Abu> T{ari>f ‘Adi> ibn H{a>tim al-T{a>’i>, datang kepada Nabi Saw dan
memeluk Islam tahun 9 H. Ia melihat pembukaan kota Iraq dan tinggal di Kufah sampai
meninggal pada tahun 67 H. Lihat Ibn Sa‘d, al-T{abaqa>t al-Kubra> (Kairo: Da>r al-Tah{ri>r,
1388 H), Juz 6, 13. 5 Dalam Sah}ih} al-Bukha>ri> dijelaskan, ketika QS. Al-Baqarah [2]:178
diturunkan, ‘Adi> ibn H {a>tim memahaminya secara literal-tekstual, ia mengambil dua tali
berwarna hitam dan putih. Kedua tali itu ditaruh di atas kepalanya, lalu ia lihat
sepanjang hari tapi ketika malam tiba, warna tali tersebut tidak terlihat jelas, maka
keesokan harinya, ia datang kepada Nabi Saw dan menceritakan kejadian tersebut lalu
Nabi Saw bersabda: ‚Jika demikian berarti bantalmu cukup lebar.‛ Lalu Rasul
meluruskan pemahaman ‘Ady seraya bersabda: ‚Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah gelapnya malam dan terangnya siang.‛ Lihat Abu > ‘Abd Alla>h Muh{ammad ibn
‘Abd Alla>h ibn Isma‘i>l al-Bukha>ri>, al-Ja>mi‘ al-S{ah}ih}, Kita>b al-Tafsi>r (Istanbul: al-
Maktabah al-Isla>mi>yah, 1979), Juz 5, 156. 6 Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari ‘Abd Alla >h ibn
Mas‘u>d, dia berkata bahwa ketika ayat 82 surat Al-An’am diturunkan, para sahabat
terkejut dan bertanya kepada Rasul Saw: ‚Wahai Rasul, siapa diantara kami yang tidak
berbuat dhalim?‛ Rasul menjawab: ‚Tidak seperti yang kalian pahami, yang dimaksud
wa lam yalbasu> i>ma>nahum bi z}ulmin adalah menyekutukan tuhan. Tidakkah kalian
mendengar ucapan Luqman kepada anaknya: ‚Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sungguh menyekutuan Allah (syirik) itu adalah kez}aliman yang sangat besar.‛ (QS. Luqma>n [31]: 13). Lihat cerita selengkapnya pada Imam Bukhari,
S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz 4, 112; Abu H{asan Muslim ibn al-H{ajja>j al-Qushairi>, S{ah}ih} Muslim (Istanbul: al-Maktabah al-Isla>miyah, t.th.), Juz 1, 114.
7 Ibn al-Zab’ary menafsirkan kata ma> pada ayat 98 surat al-Anbiya>’ secara
literal-tekstual, sehingga ia memahaminya sebagai kata yang bersifat umum (‘a>m).
Karenanya ia beraggapan bahwa ia bersama kaum kafir dan sesembahannya –termasuk
di dalamnya malaikat, Uzair dan ‘Isa ibn Maryam- akan menjadi bahan bakar neraka.
Tak heran bila penafsiran seperti ini kemudian dikritik habis oleh Rasul. Lihat cerita
selengkapnya pada misalnya, Abu al-Fida>’ Isma’i>l ibn Kathi>r al-Dimashqi>, (selanjutnya
disebut Ibn Kathi>r) Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m (Kairo: Da>r al-Sya‘b, 2000), Juz 2, 198-
199; Ibrahi>m ‘Abd al-Rah}ma>n Muh}ammad Khali>fah, (selanjutnya disebut Ibrahi>m
Khali>fah), al-Dakhi>l fi> al-Tafsi>r (Kairo: Universitas Al-Azhar, 1996), 42-47.

3
dikritik oleh Rasul Saw karena tidak sesuai dengan konteks ayat dan
relasinya dengan ayat lain.
Sementara penganut kontekstualis misalnya, menafsirkan kata rajul pada QS. Al-Qas}as} ayat 20 sebagai Mirza Ghulam Ah}mad (1835-1908 M).8
Penafsiran ini berangkat dari prakonsepsi sang mufasir yang meyakini
bahwa Ghulam Ahmad adalah seorang mujaddid sekaligus nabi yang datang
dari ujung negeri (min aqs}a> al-madi>nah).9 Dengan dalih kontekstualisasi,
sekte Baha>’iyah10 juga menafsirkan ayat 4 surat Yu>suf dengan penafsiran
yang fantastis. Mirza ‘Ali> Muh}ammad (1819-1850 M), mengatakan bahwa
kata Yu>suf pada ayat tersebut adalah H{usayn –cucu Nabi Saw-, kata al-Shams berarti Fa>t}imah, al-Qamar adalah Muhammad Saw, dan al-Kawa>kib
berarti imam-imam mereka.11
Berangkat dari fenomena penafsiran seperti di atas kemudian
muncullah beberapa kelompok kritikus yang mencoba menganalisis dan
mengevaluasi kualitas penafsiran. Kendati harus diakui bahwa metodologi
dan pendekatan yang digunakan berbeda antara satu dengan lainnya.
Muh}ammad ‘Abduh (1849-1905 M) misalnya, lebih condong menggunakan
pendekatan kritik modernisme Islam,12 Ami>n al-Khu>li> (1895-1966 M)
8 Mirza Ghulam Ahmad adalah pendiri Jemaat Ahmadiyah Qadyan, lahir di
Qadyan-India pada 13 Februari 1835 dan meninggal di Lahore pada 26 Mei 1908, tapi
para pengikutnya membawa jenazahnya ke Qadyan. Jemaat Ahmadiyah memiliki kitab
tafsir lengkap dengan nama Tafsi>r al-S{aghi>r, dikarang oleh Bashi>r al-Di>n Mah}mu>d
(1889-1965 M), putra Mirza Ghulam Ah}mad dan khalifah kedua Jemaat Ahmadiyah.
Tafsir ini menggunakan pendekatan kontekstualis namun sarat dengan nuansa
ideologis, karenanya banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Lihat Tim
Penulis, Kami Orang Islam, Buku Putih Jemaat Ahmadiyah Indonesia, (T.t., t.p., 1981),
Cet. II, 20 & 29; Susmojo Djojosugito, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Bukan Nabi Hakiki (Yogyakarta: PB GAI, 1984), 7-8.
9 Lihat Bashi>r al-Di>n Mah}mu>d, Tafsi>r S{aghi>r (terj.) Al-Qur’an dengan
Terjemahan dan Tafsir Singkat dengan Restu Hadrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifat al-
Masih} IV (Jakarta: Dewan Naskah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1987), Edisi II, 104. 10
Baha>’iyah adalah sekte sempalan Syi’ah yang muncul pada abad ke-19 M di
Iran. Didirikan oleh seorang yang bernama Mirza Ali Muhammad al-Shairazy yang
bergelar al-Ba>b. Lihat ‘Abd al-Wahha>b ‘Abd al-Wahha>b Fa>yed, al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m (Kairo: Mat}ba’ah al-H}ad}arah al-‘Arabi>yah, 1980), Juz 2, 193.
11 Muh}ammad H{usayn al-Dhahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n (Kairo: Da>r al-
Kutub al-H{adi>thah, 1998), Juz 2, 265. 12
Andrew Rippin menilai, landasan utama penafsiran Al-Qur’an di kalangan
modernis Islam terdiri dari tiga agenda utama, yakni pertama, menafsirkan Al-Qur’an
berdasarkan rasionalitas dibandingkan periwayatan. Kedua, berupaya melakukan
pemurnian Al-Qur’an terhadap seluruh mitos-mitos, hikayat dan cerita rakyat, magis,
tahayul dan khurafat. Alat yang digunakan kalangan modernis adalah melakukan

4
memilih pendekatan kritik sastra,13 sementara Fazlur Rah}ma>n (1919-1988
M) memilih neo-modernisme, Mohammad Arkoun (1928-2010 M) lebih
suka menggunakan post-strukturalis, Nasr H{a>mid Abu> Zayd (1943-2010 M)
memakai metode hermeneutika dan H{asan H{anafi> (l. 1935 M) menggunakan
pendekatan pembaharuan kala>m,14
Terlepas dari heterogenitas metodologi dan pendekatan kritik
tersebut, ‘Abd al-Sala>m (2008) menilai, dengan menggunakan pendekatan
historis, bahwa tradisi kritik tafsir sejatinya telah dimulai sejak masa Nabi
Saw. Hal ini terbukti dengan respon kritis Nabi Saw terhadap beberapa
kasus penafsiran sahabat yang salah terhadap ayat Al-Qur’an.15
Tradisi ini dilanjutkan oleh sahabat, tabi‘in dan generasi setelahnya.
Hanya saja tradisi kritik tafsir pada masa dua generasi awal ini masih
bersifat sederhana, sebab penafsiran kala itu jumlahnya belum terlalu
banyak.16 Kemudian pada era pertengahan Islam, kritisisme terhadap tafsir
semakin menemukan bentuknya.17 Banyak karya dihasilkan terkait dengan
penafsiran simbolik. Ketiga, merasionalisasikan doktrin yang ditemukan dalam Al-
Qur’an atau dijustifikasi dengan merujuk kepada Al-Qur’an. Diskusi lebih dalam dapat
dilihat pada Andrew Rippin, ‚Tafsir‛ dalam Mercia Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion Vol. 13 (New York: MacMillan Library Reference, 1995), 242.
13 Lihat misalnya tulisan David Damrosch, ‚Foreword: Literary Criticism and
the Qur'an‛, Journal of Qur'anic Studies, Volume 16, Issue 3, October 2014, Edinburgh
University Press, 4-10. 14
Lihat Richard C. Martin, ‚Imagining Islam and Modernity: The
Reappropriation of Rationalism by Muslim Modernists and Postmodernists‛, Draft Prepared for Precirculation Among Participants in the Conference on Islam and Society in Southeast Asia, Jakarta, Indonesia, May, 1995, 1-31.
15 ‘Abd al-Sala>m ibn Salih} ibn Sulaima>n, Naqd al-Sah}abah wa al-Tabi‘i>n li al-
Tafsi>r: Dira>sah Naz}ariyah Tat}bi>qiyah (Riyad}: Da>r al-Tadmu>ri>yah, 2008), 42. 16
Ada dua arus utama dalam menilai kuantitas penafsiran pada masa Nabi
Saw. Di satu sisi, Ibn Taymiah berkeyakinan, semua isi Al-Qur’an telah ditafsirkan dan
karenanya penafsiran telah berakhir pada masa Rasulullah Saw, sebab salah satu misi
utama Rasul adalah sebagai penjelas/penafsir Al-Qur’an. Namun di sisi lain, al-Suyut}i
menilai bahwa Rasul Saw tidak menjelaskan seluruh isi Al-Qur’an tapi hanya sebagian
kecil saja, sehingga umatnya dikemudian hari dapat melanjutkan proses penafsiran
tersebut. Diskursus hangat ini dapat dilihat secara lengkap pada Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i,
al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Kairo: Da>r al-Turath al-‘Arabi>, 2000), 83. Bandingkan
dengan H. Birkeland, Old Muslim Opposition Against the Interpretation of the Koran
(Oslo: Norske Videnskaps Academy, 1955). 17
Kritisisme penafsiran di era ini dilakukan misalnya oleh al-T{u>si> (w. 460 H)
yang sangat keras mengkritisi model penafsiran bernuansa linguistik seperti yang
dilakukan al-Farra>’, al-Zajja>j dan semacamnya. Kemudian Abu> H{ayya>n al-Andalu>si> (w.
745 H) juga mengkritisi model penafsiran bernuansa gramatik, fikih, usul fikih dan

5
diskursus ini.18 Kendati harus diakui bahwa karya kritik penafsiran pada
masa ini masih miskin metodologi, bersifat apologetik dan bernuansa
ideologis.
Pada era modern, geliat kritisisme terhadap penafsiran semakin
menguat seiring dengan maraknya penafsiran sektarian yang subjektif dan
mengabaikan nilai-nilai universalitas Al-Qur’an. Ami>n al-Khu>li> (1895-1966
M) misalnya, dalam karyanya, al-Tafsi>r: Nash’atuh, Tadarrujuh, Tat}awwuruh, mengkritik habis berbagai penafsiran yang berbau ideologis,
sektarian dan saintifik. Kemudian ia mengusulkan kritisisme penafsiran dan
menyusun proyek tafsir baru dengan pendekatan sastra.19 Dalam konteks ini
al-Khu>li> menyuguhkan dua prinsip metodologis. Pertama, studi terhadap
apa yang mengitari teks Al-Qur’an (dira>sa>t ma> h}awl al-qur’a>n). Kedua, studi
teks Al-Qur’an itu sendiri (dira>sah ma> fi> al-qur’a>n nafsih).20
Muh}ammad H{usayn T{aba>t}aba>’i> (1903-1981 M) juga mengkritisi
penafsiran Al-Qur’an yang bernuansa dan berbasis pada kailmuan mufasir
semata, seperti tafsir linguistik, sufistik, filosofis, historis, kalam, fikih, usul
ushuluddin. Sementara S{adr al-Di>n al-Shayra>zi> (w. 1050 H) lebih fokus mengkritisi
tafsir yang bernuansa sufistik, kalam dan filosofis. Tak ketinggalan, al-Sayyid al-Khu>’i>
(w. 1413 H) juga mengkritisi tafsir-tafsir yang bernuansa sastrawi, linguistik, folosofis
dan saintifik. Lihat lebih dalam misalnya pada Jawwa>d ‘Ali> Kassa>r, Fahm al-Qur’a>n: Dira>sah Sha>milah fi> Ru’a> al-Ima>m al-Khumayni> al-Manhaji>yah fi> Fahm wa Tafsi>r al-Qur’a>n (Bayru>t: Markaz al-H{ad}a>rah li Tanmiyat al-Fikr al-Isla>mi>, 2008), Juz 1, 148-
151. 18
Beberapa karya kritisisme tafsir era ini misalnya, Abu> al-‘Abba>s Ah}mad ibn
Muh}ammad yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Muni>r (w.683 H) menulis karya al-Ins}a>f min al-Kashsha>f; Abu> ‘Ali ‘Umar ibn Muh}ammad ibn H{amd al-Suku>ni> (w.717 H)
menulis karya at-Tamyi>z li ma> Auda‘ahu al-Zamakhshari min al-I‘tiza>la>t fi> Tafsi>r al-Kita>b al-‘Azi>z.
19 Lihat Ami>n al-Khu>li>, al-Tafsi>r: Nash’atuh, Tadarrujuh, Tat }awwuruh
(Bayru>t: Da>r al-Kita>b al-Lubna>ni>, 1982), 54-65. 20
Studi pertama diarahkan untuk melakukan investigasi terhadap latar
belakang Al-Qur’an, sejak proses pewahyuan, perkembangan dan sirkulasinya dalam
masyarakat Arab sebagai obyek wahyu, serta kodifikasi dan variasi cara bacaannya.
Kajian ini juga difokuskan pada aspek sosial-historis Al-Qur’an, termasuk situasi
mental, kultural, dan geografis masyarakat Arab abad ke-7, saat Al-Qur’an diturunkan.
Kajian ini menitikberatkan pentingnya aspek-aspek historis, kultural, dan antropologis
wahyu, dan kondisi masyarakat Arab abad ke-7 sebagai objek langsung teks wahyu itu.
Studi kedua dimulai dengan penafsiran makna kata-kata tunggal (mufrada>t) yang
digunakan saat ia diwahyukan, perkembangan, dan cara pemakaiannya di dalam Al-
Qur’an. Cara ini dilanjutkan dengan pengamatan terhadap kata-kata jamak (murakkab)
plus analisis tentang pengetahuan gramatikal Arab (al-bala>ghah). Lihat Ami>n al-Khu>li>,
al-Tafsi>r: Ma’a>lim H}aya>tihi Manhajuhu al-Yawma (Kairo: Da>r al-Ma’rifah, 1962), 46.

6
fikih dan tafsir yang berdimensi keilmuan lainnya. Baginya, penafsiran
semacam itu telah terjerembab kepada pendewaan atas disiplin ilmu
tertentu. Sehingga yang sering terjadi adalah, mufasir memaksa ayat agar
sejalan dengan pemahaman dan disiplin ilmunya, padahal konteks ayat sama
sekali tidak berbicara tentang persoalan tersebut. Produk penafsiran yang
berbasis pada disiplin keilmuan semacam ini disebut oleh T{aba>t}aba>’i
sebagai tat}bi>q (implementasi) bukan tafsi>r (penjelasan) ayat.21 Karenaya, ia
harus dikritisi dan dianalisis secara mendalam agar universalitas Al-Qur’an
tetap terjaga.
H{usayn al-Dhahabi> (1915-1977 M) bahkan menulis dua karya
monumental yang khusus dipersembahkan untuk kritik tafsir yaitu, al-Isra>’iliya>t fi > al-Tafsi>r wa al-H{adi>th dan al-Ittija>ha>t al-Munh}arifah fi> Tafsi>r al-Qur’a>n. Dalam karya yang pertama, al-Dhahabi> menguraikan beragam
penafsiran yang berasal dari Ahli Kitab yang notabene bertentangan dengan
pendapat mayoritas muslim. Karenanya ia mengkritik habis berbagai
penafsiran yang tidak bersumber dari ajaran Islam.22 Pada buku kedua, al-
Dhahabi> menguraikan dan sekaligus mengkritisi beragam penafsiran
sektarian yang bernuansa ideologis dan subjektif. Baginya, penafsiran
seperti itu akan menjadikan Al-Qur’an terseret pada kepentingan sang
mufasir yang subjektif dan parsialistik, sehingga nilai universal Al-Qur’an
akan tercerabut.23 Maka kritisisme terhadap penafsiran menjadi mega
proyek yang harus didukung oleh semua pihak.
Mengamini al-Dhahabi>, Abu> Syahbah (1914-1983 M) dalam
karyanya, al-Isra>’ili>ya>t wa al-Maudhu>‘a>t fi> Kutub al-Tafsi>r, menilai bahwa
masuknya berbagai penafsiran isra>’ili>ya>t dan maud}u >‘a>t dalam kitab tafsir
21
Al-T{aba>t}aba>’i> membedakan antara terminologi tafsi>r dan tat}bi>q. Tafsi>r merupakan kegiatan mencari hakekat, maqas}id dan makna Al-Qur’an dari dalam diri
Al-Qur’an sendiri. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui proses berfikir dan bertadabbur
secara mendalam dengan menggunakan metodologi tafsir al-Qur’a>n bi al-Qur’a>n.
Sementara tat}bi>q adalah analisis ilmiah yang berbasis dan menggunakan pendekatan
ilmu tertentu, seperti ilmu filsafat, fikih dan semacamnya. Hasil analisis terhadap ayat-
ayat Al-Qur’an diarahkan untuk mendukung disiplin ilmu tersebut. Dengan demikian,
yang pertama diarahkan untuk menjawab pertanyaan, ‚apa yang dikatakan Al-
Qur’an?‛, sementara yang kedua menjawab pertanyaan, ‚ke mana Al-Qur’an harus kita
bawa?‛. Lihat Muh}ammad H{usayn al-T{aba>t}aba>’i>, al-Mi>za>n fi> Tafsi>r al-Qur’a>n (Bayru>t:
Manshu>ra>t Mu’asasah al-A‘lami> li al-Mat}bu‘a>t, 1997), Juz 1, 6 & 11. 22
Diskursus ini dapat dilihat secara lebih mendalam pada Muh}ammad Husayn
al-Dhahabi>, al-Isra>’ili>ya>t fi> al-Tafsi>r wa al-H{adi>th (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004),
Cet. IV. 23
Selengkapnya dapat dibaca pada Muhammad Husayn al-Dhahabi>, al-Ittija>ha>t al-Munh}arifah fi> Tafsi>r al-Qur’a>n (Kairo: Maktabah Wahbah, 1986), 7-8.

7
akan menciderai wajah Al-Qur’an yang suci dan komprehensif. Baginya,
kritik atas penafsiran isra>’ili>ya>t dan maud}u>‘a>t adalah sebuah usaha yang
niscaya, kendati harus diakui bahwa kerja seperti itu tidaklah mudah.24
Sementara Fazlur Rah}ma>n (1919-1988 M) mengkritik
kecenderungan penafsir yang memperlakukan ayat-ayat Al-Qur’an secara
tidak menentu (piecemeal and ad-hoc), yang hingga kini masih terus
berlanjut. Dengan perubahan sosial dan masuknya ide-ide baru dari Barat,
beberapa pemikir muslim cenderung mencari-cari dan menggunakan ayat
Al-Qur’an yang dapat menjustifikasi posisi mereka. Bagi pemikir berdarah
Pakistan ini, pembonsaian ayat-ayat atas nama kepentingan apapun -
termasuk agama- dapat memporandakan objektivitas pembacaan Al-
Qur’an.25
Muhammad Arkoun (1928-2010 M) juga mengajak melakukan kritik
penafsiran sebab penafsiran klasik telah mengalpakan analisis kritis
terhadap teks. Tafsir klasik dinilai telah melupakan epistemologi pembacaan
modern yang kontekstual. Bahkan Arkoun menilai bahwa saat ini aturan dan
batasan penafsiran telah hilang, dan semua orang bebas menjadi penafsir
(Al-Qur’an). Hal ini terjadi karena adanya trend ideologi kebebasan yang
merebak sejak beberapa dasawarsa terakhir. Tentu penafsiran seperti ini
menyebabkan terberangusnya tugas pertama dan utama wahyu (Al-
Qur’an).26
Lebih lanjut, Arkoun berseloroh, ‚Penafsiran teks suci dihantui dua
persoalan mendasar. Di satu sisi, para mufasir klasik kerap menafsirkan (Al-
Qur’an) sesuai dengan praktek keagamaan yang mereka lakukan. Di sisi
lain, para aktifis pergerakan Islam acapkali meninggalkan tanda-tanda
ketuhanan dan pra-syarat penafsiran yang jelas-jelas diketahuinya dalam
proses penafsiran.‛27 Karenanya, Arkoun mempropagandakan urgensi
kritisisme terhadap konstruksi pemikiran –termasuk di dalamnya
penafsiran- yang sudah terbangun dan mengalami kristalisasi sekian lama.28
24
Diskusi lebih mendalam tentang hal ini dapat dilihat pada Muhammad ibn
Muhammad Abu> Shahbah, al-Isra>’ili>ya>t wa al-Maud}u>‘a>t fi> Kutub al-Tafsi>r (Kairo:
Maktabah al-Sunnah, 2006), Cet. II, 5-9. 25
Fazlur Rahman, Islam and Modernity (Chicago & London: University of
Chicago Press, 1982), 2-3. 26
Mohammad Arkoun, al-Fikr al-Isla>mi>; Naqd wa Ijtiha>d (Aljazair: al-
Mu’assasah al-Wat}ani>yah li al-Kita>b, 1988), 90. 27
Mohammad Arkoun, al-Fikr al-Isla>mi>, 91. 28
Bagi Arkoun, kritisisme tidak selamanya berarti negatif, yakni dengan
melakukan dekonstruksi terhadap ajaran Islam yang h}ani>f sebagaimana dipahami
sebagian kalangan. Namun yang dimaksud kritik di sini adalah kritik terhadap

8
Kritisisme ini penting bagi Arkoun karena ia melihat hegemoni
kaum fuqaha sudah berjalan sekian lama namun umat Islam tetap dalam
kemunduran. Fuqaha –kata Arkoun- adalah kelompok yang mengklaim
dirinya paling mampu memahami dan menjelaskan makna Al-Qur’an,
kemudian menjadikannya sebagai undang-undang agama yang harus diikuti
dan ditaati. Berdasarkan hal di atas, maka wacana kritik nalar muslim29
menjadi mega proyek yang harus segera dilakukan.30
Dengan nalar kritisnya, Nas}r H{a>mid Abu> Zayd (1943-2010 M)
melalui buku naqd al-khit}a>b al-di>ni> mengkritisi tiga kelompok utama yang
memiliki andil besar dalam penafsiran dan pembacaan Al-Qur’an.31 Tiga
kelompok tersebut adalah kelompok lembaga keagamaan yang diwakili Al-
Azhar, kelompok kiri Islam (al-yasa>r al-isla>mi>) dan kelompok sekuler.
Menurut Abu> Zayd, tiga kelompok ini memiliki metodologi dan cara baca
yang berbeda-beda terhadap teks. Konsekuensi logisnya, model penafsiran
ketiganya pun berbeda.32
pemahaman dan praktek keagamaan yang terkristalisasi oleh sejarah. Karena ada
perbedaan yang sangat mendasar antara wahyu yang transenden dengan pemahaman
terahadap wahyu yang imanen dan menyejarah. Lihat Mohammad Arkoun, Min al-Ijtiha>d Ila> Naqd al-‘Aql al-Isla>mi> (Bayru>t: Da>r al-Sa>qi>, 1991), Cet. I, 7-8.
29 Menurut Arkoun, nalar Islam (al-‘aql al-isla>mi>), bukanlah nalar yang
memiliki kekhususan tersendiri yang dapat membedakannya dengan akal non Islam.
Namun yang dimaksud dengan ‚nalar‛ di sini adalah nalar secara universal yang
dimiliki setiap insan, muslim atau non muslim. Yang menjadi pembeda antara nalar
Islam dengan non Islam adalah pada kata sifatnya yaitu al-isla>mi>. Parameter yang dapat
membedakan nalar Islam dengan nalar lain adalah sejauhmana pemahaman seseorang
terhadap Al-Qur’an. Lihat Mohammad Arkoun, Min al-Ijtiha>d Ila> Naqd al-‘Aql al-Isla>mi>, 18.
30 Mohammad Arkoun, Min al-Ijtiha>d Ila> Naqd al-‘Aql al-Isla>mi>, 16-17.
31 Selain buku tersebut, Abu> Zayd juga berhasil menulis beberapa buku
bernuansa kritik yang sangat fenomenal. Untuk menyebut contoh misalnya, Mafhu>m al-Nas}: Dira>sah fi> `Ulu>m al-Qur’a>n (Konsep Teks: Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an), Isyka>liyya>t al-Qira>’ah wa A<liya>t al-Ta’wi>l (Problem Pembacaan dan Metode Interpretasi), Falsafah al-Ta’wi>l: Dira>sah fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n ‘inda Ibn ‘Arabi> (Filsafat Hermeneutika: Studi
Hermeneutika Al-Qur’an menurut Ibn ‘Arabi), al-Ima>m al-Sha>fi‘i> wa Ta’si>s al-Aydu>lu>ji>yah al-Wasat}i>yah (Imam Syafi’i dan Pembasisan Ideologi Moderatisme), al-Ittija>h al-‘Aqli> fi> al-Tafsi>r (Rasionalisme dalam Tafsir). Karya-karyanya juga terbit
dalam bahasa Inggris seperti Reformation of Islamic Thought: a Critical Historical Analysis; Rethinking the Qur’an: Towards a Humanistic Hermeneutics; dan Voice of an Exile: Reflections on Islam. Karya-karyanya sebagian telah diterjemahkan ke bahasa
Jerman, Perancis, Indonesia, Itali, Persia, dan Turki. 32
Nas}r H{a>mid Abu> Zayd, Naqd al-Khit}a>b al-Di>ni> (Kairo: Saina>’ li al-Nashr,
1994), Cet. II, 61-64.

9
Bacaan dan kritikan Abu> Zayd ini diaplikasikan dalam dua buku
monumentalnya yaitu Ishka>li>ya>t al-Qira>’ah wa A<liya>t al-Ta’wi>l dan
Mafhu>m al-Nas}: Dira>sah fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n. Dalam buku yang pertama Abu>
Zayd menawarkan metodologi hermeneutika inklusif untuk membaca dan
menafsirkan Al-Qur’an. Sementara buku kedua merupakan aplikasi
metodologis terhadap tema-tema ulumul Qur’an.33
Senada dengan para pendahulunya, ‘Ali > H{{arb (l. 1941 M), pemikir
asal Lebanon ini menilai bahwa kritik penafsiran perlu dilakukan karena
penafsir tidak bisa merepresentasikan realitas teks. Dalam arti, teks, setelah
muncul ke alam wujud berubah menjadi satu kesatuan (kaynu>nah al-nas}}). Teks memiliki ruang epistemologis tersendiri (al-mayda>n al-ma‘rafi>). Jika
demikian, ia tak bisa disangkutkan dengan realitas luar dan akan terpisah
dari penulisnya (author/al-mu’allif). Konsekuensinya, kritik teks (tafsir)
bukan saja membawa pembacaan lain yang terus diperbaharui, melainkan
akan merubah cara pandang pembacanya terhadap teks itu sendiri. Hakekat
itu merupakan potensi-potensi yang akan memunculkan makna lain dari
sebuah teks melalui kacamata dekonstruksi. Potensi yang demikian itu
kemudian diistilahkan dengan ‚strategi teks‛ (istira>ti>ji>yat al-nas}).34
33
Selengkapnya lihat Nas}r H{a>mid Abu> Zayd, Mafhu>m al-Nas}: Dira>sah fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Bayru>t: al-Markaz al-Thaqa>fi> al-‘Arabi>, 1994), Cet. II; Nas}r H{a>mid
Abu> Zayd, Ishka>li>ya>t al-Qira>’ah wa A<liya>t al-Ta’wi>l (Bayru>t: al-Markaz al-Thaqa>fi> al-
‘Arabi>, 2005), Cet.V. Sementara untuk memahami lebih jelas kerangka pemikiran Abu>
Zayd dalam Mafhûm al-Nash, Hirschkind menyatakan, ‚Titik tolak argumentasi Abu>
Zayd adalah gagasan bahwa setelah diturunkan kepada Muhammad, Al-Qur’an masuk
ke dalam dimensi sejarah dan menjadi tunduk pada hukum-hukum yang bersifat historis
dan sosiologis. Teks Al-Qur’an kemudian menjadi manusiawi (humanized/muta’annas),
memasukkan relung-relung budaya yang partikular, kondisi politik, dan unsur-unsur
ideologis masyarakat Arab abad ketujuh‛. Dikatakan manusiawi sebab Al-Qur’an turun
melalui media bahasa manusia agar dapat dipahami penerimanya. Juga karena Al-
Qur’an telah bermetamorfosis dari ‚teks Ilahi‛ menjadi ‚teks yang ditafsiri secara
manusiawi‛. Diskursus ini dapat dilihat pada Charles Hirschkind, Heresy or Hermeneutics, the Case of Nas}r H{a>mid Abu> Zayd, Volume V, Issue 1, Contested
Polities Updated, February 26, 1996. Lihat juga Nur Zainatul Nadra Zainol, Latifah
Abd Majid & Muhd Najib Abdul Kadir, ‚Nasr Hamid Abu> Zayd as a Modern Muslim
Thinker‛, International Journal of Islamic Thought, Vol. 5, The National University of
Malaysia, 2014, 61-70. 34
Bagi ‘Ali H{arb, kritik teks tidak berarti menggugurkan pendapat atau
sekadar mengoreksi, namun di atas itu semua, kritik adalah pembacaan terhadap apa
yang belum terbaca (qira>’ah ma> lam yuqra’). Lihat Ali H{arb, Naqd al-Nash} (Bayru>t: al-
Markaz al-Thaqa>}fi> al-‘Arabi>, 2005), Cet. IV, 11-20. Karya H{arb yang terkait dengan
kritisisme termuat dalam trilogi al-Nas} wa al-H{aqi>qah (teks dan kebenaran) yakni: naqd al-nas} (kritik teks), naqd al-h}aqi>qah (kritik kebenaran), dan al-mamnu>‘ wa al-mumtani‘ (yang dilarang dan yang terlarang).

10
Kritisisme penafsiran juga dilakukan oleh sarjana Barat. Sebut saja
misalnya, Jane Dammen McAuliffe (l. 1944 M). Melalui tulisannya yang
bertajuk Qur’anic Hermeneutics: The View of al-T{abari> and Ibn Kathi>r, ia
mengkritisi tafsir al-T{abari> dan Ibn Kathi>r dengan melihat horizon
sosialnya.35 Azim Nanji membahas tentang teori takwil dalam tradisi ilmuan
Isma’ili> yang banyak membantu dalam kritik sastra dan tafsir.36 Arthur
Jeffery (1893-1959 M) berpendapat bahwa belum ada satupun dari para
mufasir muslim yang menafsirkan Al-Qur’an secara kritis. Ia mengharapkan
agar tafsir kritis terhadap Al-Qur’an bisa diwujudkan dengan cara
mengaplikasikan metode ilmiah modern.37
Pada pertengahan abad ke-20, John Wansbrough (1928-2002)
menerapkan literary criticism (kritik sastra) dan form criticism (kritik
bentuk) ke dalam studi Al-Qur’an. Melalui kritik ini ia menyimpulkan teks
yang diterima dan selama ini diyakini oleh kaum muslimin sebenarnya
adalah fiksi yang belakangan direkayasa kaum muslimin.38 Kemudian pada
tahun 2001, Cristoph Luxenberg melakukan kritisisme terhadap Al-Qur’an
dengan menggunakan metode ilmiah filologi (the scientific method of philology). Menurutnya, sebagian besar Al-Qur’an tidak benar secara tata
bahasa dan Al-Qur’an ditulis dalam dua bahasa Aramaik dan Arab.39
Secara metodologis, para kritikus di atas, selain al-Dhahabi>, Abu>
Shahbah dan al-T{aba>t}aba>’i>, menggunakan metodologi kritik bibel (biblical criticism) dan sastra yang tumbuh subur di Barat. Sehingga mayoritas umat
belum dapat menerima sepenuhnya tawaran metodologi kritik tersebut.
Padahal ide-ide yang diusung para pemikir ini sangat inspiratif, tranformatif
dan menarik untuk diaplikasikan. Di sisi lain, kesadaran dan gairah umat
Islam –tepatnya para cendekiawan muslim- untuk melakukan kritisisme
35
Lihat Jane Dammen McAuliffe, ‚Qur’anic Hermeneutics: The View of al-
T{abari> and Ibn Kathir‛ dalam Andrew Rippin (ed.), Approaches to the History of the Quran (Oxford: Clarendon, 1988), 46-62.
36 Azim Nanji, ‚Toword a Hermeneutic of Quranic and Other Narratives of
Isma’ili Thoght‛ dalam Richard C. Martin (ed.), Approaces to Islam in Religious Studies (Tucson: The University of Arizona Press), 164-174.
37 Arthur Jeffery, The Qur’an as Scripture (New York: Russell F. Moore
Companya, 1952), 89-90. 38
Lihat John Wansbrough, Quranic Studies; Sources and Methods of Scriptural Interpretation (Oxford: Oxford University Press, 1970), ix.
39 Robert R. Phenix Jr. & Cornelia B. Horn, Cristoph Luxenberg, ‚Die syro-
aramaische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschusselung der Qur’ansprache‛,
dalam Adnin Armas, Metodologi Bibel dalam Studi al-Qur’an; Kajian Kritis (Jakarta:
Gema Insani Press, 2005), 60-61.

11
terhadap penafsiran Al-Qur’an sejatinya sangat besar, namun harus diakui
belum ada internal methodology yang bersumber dari rumpun kajian Islam
yang dianggap cukup mumpuni untuk dijadikan pisau analisis terhadap
kritisisme tafsir Al-Qur’an. Doktrin ideologi yang telah mengkristal
berabad-abad dalam alam ide dan alam nyata umat Islam telah
menumpulkan dan bahkan mematikan daya kreatifitas dan potensi kritis
mereka.
Salah satu tokoh yang mencoba untuk menjawab kesenjangan di atas
adalah ‘Abd al-Wahha>b ‘Abd al-Wahha>b Fa>yed (1355-1420 H/1936-1999
M),40 seorang tokoh, pemikir, penyair dan aktifis Islam yang mengabdikan
dirinya untuk kebangkitan Islam di Mesir. Fa>yed adalah seorang sastrawan,
intelektual sekaligus revivalis Islam yang hidup di masa pemerintahan
presiden Gama>l ‘Abd al-Nasser (1918-1970 M). Kompleksitas masa ketika
ia hidup mendorong Fa>yed berjuang tidak hanya dengan menggunakan pena
namun juga mengimplementasikannya dalam sebuah gerakan. Selain aktif
sebagai pengajar di Universitas Al-Azhar, ia juga terjun dalam gerakan
Ikhwan Muslimin, Ans}a>r al-Sunnah, Perkumpulan Penyair Arab, Ikatan
Sastrawan Modern, Majma’ Fiqh Mekah dan masih banyak lagi.41
40
Nama lengkapnya ‘Abd al-Wahha>b ‘Abd al-Wahha>b Mabru>k Fa>yed,
(selanjutnya ditulis Fa>yed), dilahirkan di desa Damnakah, Dasouq, Delta Mesir pada
tahun 1355 H/1936 M dan meninggal di Kota Kairo pada tahun 1420 H/1999 M.
Menghafal Al-Qur’an di sebuah Kuttab (pesantren) yang ada di kampungnya, kemudian
melanjutkan sekolah di Madrasah Keagamaan al-Dasouq hingga lulus SLTA. Lalu
melanjutkan studi ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar; S-1 lulus tahun 1963,
S2 lulus tahun 1967 dan S3 lulus tahun 1971. Karir intelektualnya semakin naik, ia pun
dipercaya sebagai Dekan Fak. Ushuluddin, kemudian dipercaya menjadi Korps
Universitas Al-Azhar hingga diangkat menjadi Guru Besar pada tahun 1981. Selain di
Universitas Al-Azhar Mesir, Fa>yed juga menjadi dosen luar biasa di beberapa
universitas antara lain: Universitas Benghazi, Libya (1973-1977), Universitas Ummu
Durman, Sudan (1981), Universitas Ummul Qura>, Mekah (1981-1999). Kepiawaian dan
dedikasinya dalam bidang keilmuan Islam dan sastra membuatnya memperoleh
penghargaan ‚Kemerdekaan Intelektual‛ (‘I>d al-‘Ilm) dari presiden Gamal Abd al-
Nasser pada tahun 1963. Lihat ‚Abd al-Wahab Fa>yed‛ dalam Mu’jam al-Ba>bat}i>n li Shu’ara>’ al-‘Arabiyah fi al-Qarnayn al-Tasi’ al-‘Ashar wa al-‘Ishri>n,
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=4548 (diakses pada tanggal 15 Januari
2012). 41
Lihat Harian al-Akhba>r, (Kairo: 1 Oktober 1999); Wawancara Mah}mu>d
Khali>l bersama salah satu putra Fa>yed dan S}a>bir ‘Abd al-Daym di Kairo tahun 2003;
lihat pula pada ‚’Abd al-Wahha>b Fa>yed‛ dalam Mu‘jam al-Ba>bat}i>n li Shu‘ara>’ al-‘Arabiyah fi al-Qarnayn al-Ta>si‘ al-‘Ashar wa al-‘Ishri>n,
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=4548 (diakses pada tanggal 15 Januari
2012).

12
Dari sisi pergerakan dan wacana intelektual, Fa>yed memiliki andil
cukup besar terutama dalam konteks perintisan tradisi kritisisme baik
kepada pemerintah maupun wacana keagamaan. Dalam konteks penafsiran,
Fa>yed sangat geram dengan munculnya beragam penafsiran sektarian yang
sangat subjektif dan hanya berdasar pada kemauan ideologi mufasir, tanpa
mengindahkan variabel-variabel penafsiran yang ada. Dalam kondisi
perjuangan intelektual inilah buku al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m
lahir.42
Dalam buku al-Dakhi>l, Fa>yed mengajak kepada para pengkaji Al-
Qur’an untuk melakukan kritik penafsiran. Baginya, manusia –siapa dan
sepandai apapun dia- adalah makhluk biasa yang berpotensi untuk
melakukan kesalahan, termasuk kesalahan dalam menafsirkan Al-Qur’an.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya melakukan kritik tafsir, terutama
kepada tafsir kaum bathini, tafsir sektarian (maz}habi), riwayat isra>‘ili>ya>t,
hadis dha’i>f dan maudhu >’.43
Buku al-Dakhi>l fi Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m menunjukkan secara
elaboratif tentang metodologi kritik tafsir. Di dalamnya juga diuraikan
langkah sekaligus aplikasi kritik tafsir Al-Qur’an. Dengan bahasa yang
lugas, tegas dan sistematis, mantan Guru Besar Fakultas Ushuluddin
Universitas Al-Azahar Kairo ini mampu meyakinkan pembacanya tentang
urgensi kritisisme terhadap tafsir. Karena kritisisme Fa>yed dibangun di atas
pondasi ilmu-ilmu keislaman, maka kelompok mayoritas Islam –khususnya
ulama Al-Azhar- tidak banyak melakukan perlawanan, bahkan banyak yang
mendukung dan menulis karya kritisisme lanjutan.44 Dalam buku ini, Fa>yed
42
Buku ini terdiri dari dua juz; juz I diterbitkan pada tanggal 19 Februari 1978
M/12 Rabi’ al-Awwal 1398 H, sementara juz II diterbitkan pada 21 November 1980
M/13 Muharram 1401 H. Sesungguhnya Fa>yed berkeinginan keras untuk melengkapi
buku al-Dakhi>l ini menjadi tiga jilid. Namun sampai ajal menjemput, cita-cita untuk
menuliskan jilid ke-3 itu belum tercapai. Padahal dalam bagian penutup juz 2, terlihat
jelas ungkapan Fa>yed tentang niatnya untuk meneruskan proyek kritisisme penafsiran
menjadi tiga jilid. Lihat ‘Abd al-Wahha>b ‘Abd al-Wahha>b Fa>yed, al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m (Kairo: Mat}ba’ah al-H{ad}a>rah al-‘Arabiyah, 1980), Jilid II, 234.
43 ‘Abd al-Wahha>b ‘Abd al-Wahha>b Fa>yed (selanjutnya ditulis Fa>yed), al-
Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m (Kairo: Mat}ba‘ah al-H{ad}a>rah al-‘Arabi>yah, 1978),
Jilid I, 102-108. 44
Diantara yang menulis metode yang serupa dengan Fa>yed antara lain;
Ibrahi>m Abd al-Rah}ma>n Muh}ammad Khali>fah, al-Dakhi>l fi> al-Tafsi>r, (Kairo:
Universitas Al-Azhar, 1996); ‘Abd al-Ghafur Mahmud Mus}t}afa> Ja’far, al-As}i>l wa a-Dakhi>l fi Tafsi>r al-Qur’a>n wa Ta’wi>lih: Riwa>yah wa Dira>yah, (Kairo: Universitas Al-
Azhar, 1995); H{usayn Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad ‘Umar, al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m, (Kairo: Universitas Al-Azhar, 2005); Jama>l Mus}t}afa ‘Abd al-Hamid

13
berhasil mengelaborasi dua pendekatan penafsiran sekaligus yaitu
pendekatan tekstual dan kontekstual. Tak ayal, daya kritisisme Fa>yed pun
mendapat sambutan yang baik dari mayoritas pengkaji Al-Qur’an di Mesir.
Namun berdasarkan pembacaan peneliti, bangunan metodologi kritik
yang dirintis Fa>yed dalam al-Dakhi>l fi> Tafsi>r belum sistematis dan masih
bersifat repetitif terhadap pendapat ulama pendahulu. Karena itulah,
penelitian yang berorientasi untuk menyempurnakan bangunan metodologi
kritik Fa>yed menemukan titik fitalnya. Terlebih bila penelitian tersebut
mampu merekonstruksi konsep dan desain kriritk al-dakhi>l dengan
mengelaborasi teori-teori modern, seperti kritik sastra, hermeneutika dan
termasuk kritik hadis.
Urgensi penelitian ini setidaknya terbangun atas empat alasan utama
yaitu; pertama, belum ada –sepanjang pengetahuan peneliti- karya ilmiah,
baik berupa buku, tesis, disertasi atau lainnya, yang secara khusus dan
komprehensif mengkaji dan mengkritisi buku al-Dakhi>l karya Fa>yed ini.
Kedua, dewasa ini, banyak berkembang penafsiran yang tidak ‚sejalan‛
dengan ruh Al-Qur’an sehingga nilai-nilai transendental dan universalitas
Al-Qur’an kerap tergores, terlukai bahkan tak jarang ternodai. Ketiga, trend
kritik penafsiran Al-Qur’an yang berkembang di Indonesia –khususnya di
dunia kampus- belum berpijak pada metodologi kritik yang terkonstruksi
dari nilai-nilai atau kaidah-kaidah kritik yang berkembang di dunia Timur-
Islam, tapi lebih banyak mengadopsi dari teori dan budaya Barat yang
notabene terkontaminasi oleh budaya kritik Bibel (biblical criticism).45
Padahal jika dikaji secara mendalam dan komprehensif, khazanah keislaman
‘Abd al-Wahha>b al-Najja>r, Us}u>l al-Dakhi>l fi> Tafsir A<yi al-Tanzi>l (Kairo: Universitas
Al-Azhar, 2009), Cet. IV. 45
Para sarjana Barat, orientalis dan Islamolog sudah mulai menerapkan metode
biblical criticism (kritik Bibel) ke dalam studi Al-Qur’an sejak abad ke-19 M.
Diantaranya seperti yang dilakukan oleh Abraham Geiger (1810-1874), Gustav Weil
(1808-1889), William Muir (1819-1905), Theodor Noldeke (1836-1930), Friederich
Schwally (m.1919), Edward Sell (1839-1932), Hartwig Hirschfeld (1854-1934), David
S. Margoliouth (1858-1940), W.St. Clair-Tisdall (1859-1928), Louis Cheikho (1859-
1927), Paul Casanova (1861-1926), Julius Wellhausen (1844-1918), Charles Cutley
Torrey (1863-1959), Leone Caentani (1869-1935), Joseph Horovitz (1874-1931),
Richard Bell (1876-1953), Alphonse Mingana (1881-1937), Israel Scha-piro (1882-
1957), Siegmund Fraenkel (1885-1925), Tor Andrae (1885-1947), Arthur Jeffery (1893-
1959), Regis Blachere (1900-1973), W. Montgomery Watt, Kenneth Cragg, John
Wansbrough (1928-2002), dan yang masih hidup seperti Andrew Rippin, Christoph
Luxemberg, Daniel A. Madigan, Harald Motzki dan masih banyak lagi. Lihat Adnin
Armas, Metodologi Bibel dalam Studi Al-Qur’an: Kajian Kritis (Jakarta: Gema Insani
Press, 2005), 47-48.

14
sejatinya cukup kaya akan metodologi kritik (manhaj al-naqd) semacam ini.
Keempat, dalam disiplin ilmu hadis telah dikenal tradisi kritisisme melalui
dua jalur yaitu: kritik sanad dan kritik matan,46 sementara dalam displin
ilmu tafsir belum ditemukan tradisi yang sama.
Karena beberapa alasan itulah, penelitian disertasi ini
dikonsentrasikan untuk mengurai dan menganalisa metodologi kritik tafsir
yang dirumuskan ‘Abd al-Wahha>b Fa>yed dalam kitabnya, al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m. Kemudian merekonstruksi dan menstrukturisasi
metodologi tersebut dengan mengelaborasi dan menggunakan pendekatan
teori-teori modern yang sedang berkembang dewasa ini, terutama teori
kritik hadis, kritik sastra, kritik historis, psikologis dan hermeneutika
objektif.
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Dari penjelasan di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi
seputar wacana metodologi kritik tafsir adalah:
a. Bagaimana tradisi kritisisme penafsiran di dunia Islam dan Barat;
b. Bagaimana teori-teori dan pendekatan-pendekatan kritik tafsir;
c. Apa urgensi mengungkap makna Al-Qur’an secara objektif;
d. Apa saja usaha para sarjana muslim –dengan segala macam aliran dan
idiologinya- dalam mengungkapkan makna objektif ayat-ayat Al-
Qur’an;
46
Tradisi kritisisme dalam disiplin ilmu hadis ini telah melahirkan banyak
karya intelektual. Untuk menyebut di antaranya misalnya, al-Ra>mahurmuzi> (w.360 H.)
dengan al-Muh}addith al-Fa>s}il bayna al-Ra>wi> wa al-Wa‘yi-nya, Ibn al-Qayyim (w. 751
H./1350 M.) dengan buku al-Manna>r al-Muni>f-nya, S{alah} ad-Di>n ibn Ah}mad al-Adlabi>
dengan Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulama>’ al-H{adith al-Nabawi>-nya (1403 H/1983
M), Musfir Azmullah al-Da>mini> dengan Maqa>yis Naqd Mutu>n al-Sunnah-nya (1404
H/1984 M). Lihat juga misalnya tulisan Jonathan A. C. Brown ‚Criticism of The
Proto-Hadith Canon: al-Da>raqut}ni>’s Adjustment of The S{ah}i>h}yn‛, Journal of Islamic Studies, Vol. 15, No. 1, Oxford Centre for Islamic Studies, 2004, 1–37. Mahdi Jalāli &
Muh}ammad H{asan Shāteri Ahmadābādi, ‚A Study of the Validity of the Hadith‛,
Hadith Studies A Journal of University of Ka>sha>n, Vol. 0, No. 11, 2014, 139-158.
Kamaruddin Amin, ‚The Reliability of The Traditional Science of H{adi>th: A Critical
Reconsideration‛, Al-Ja>mi‘ah: Journal of Islamic Studies, Vol 43, No. 2, 2005, 256-
281.

15
e. Kapan muncul dan berkembangnya ‚penyelewengan‛ penafsiran Al-
Qur’an dari masa ke masa;
f. Apa penyebab terjadinya ‚penyelewengan‛ penafsiran Al-Qur’an;
g. Apa urgensi kritik terhadap mufasir dan hasil penafsiran;
h. Bagaimana teori dan prosedur kritik inh}ira>f dalam tafsir Al-Qur’an;
i. Seperti apa perkembangan wacana al-dakhi>l dalam tafsir Al-Qur’an;
j. Bagaimana prinsip-prinsip, prosedur dan aplikasi metode kritik tafsir
Al-Qur’an dalam kitab al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m;
k. Bagaimana bentuk metodologi kritik tafsir pasca strukturisasi dan
rekonstruksi dengan pendekatan kritik sastra, hermeneutika objektif
dan kritik hadis.
2. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan
dikaji pada penelitian ini dibatasi pada poin j dan k yaitu tentang prinsip
dan prosedur kritik tafsir al-dakhi>l; dan bentuk metodologi kritik tafsir
pasca strukturisasi dan rekonstruksi dengan pendekatan kritik sastra,
hermeneutika objektif dan kritik hadis.
3. Perumusan Masalah
Beranjak dari pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: ‚Bagaimana rumusan dan
bangunan metodologi kritik tafsir Al-Qur’an yang konstruktif, sistematis
dan aplikatif?‛
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan dalam
rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis,
merekonstruksi dan merumuskan metodologi kritik tafsir Al-Qur’an yang
sistematis, praktis dan aplikatif dengan menggunakan pendekatan kritik
hadis, kritik sastra dan hermeneutika objektif.
2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapakan memberikan kontribusi positif, baik
secara teoritis, praktis maupun teologis.

16
a. Manfaat secara teoritis
1) Memahami secara mendalam basis keilmuan dan episteme yang
membentuk pemikiran dan gagasan kritisisme Fa>yed terhadap
penafsiran Al-Qur’an.
2) Memberikan pengetahuan baru tentang tradisi kritik tafsir Al-
Qur’an dalam bentangan sejarah umat Islam dan Barat;
3) Memberikan penjelasan tentang metodologi kritik tafsir Al-Qur’an
dalam buku al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m;
4) Memberikan rumusan metodologis tentang model dan langkah-
langkah kritik tafsir yang mampu memotret teks Al-Qur’an secara
holistik sehingga dapat menangkap –atau setidaknya- mendekati
‘objektivitas’ makna mura>d.
b. Manfaat secara praktis
1) Dapat digunakan sebagai masukan untuk mereformulasi dan
mengembangkan sistem pembelajaran metodologi kritik tafsir Al-
Qur’an;
2) Dapat digunakan sebagai masukan untuk mengembangkan sistem
pembelajaran mata kuliah al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n (fenomena
penafsiran infiltratif terhadap Al-Qur’an);
3) Dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyusun kitab tafsir
yang ‘objektif’ dan aktual.
c. Manfaat secara teologis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi umat Islam
secara umum, agar keyakinan mereka tentang orisinalitas dan kesucian
Al-Qur’an semakin kuat. Dengan kritisisme, di samping mengandung
sistem nilai dan way of live, hasil penafsiran Al-Qur’an juga tidak akan
mengalami distorsi ataupun ‘penyelewengan’ pemahaman, sehingga
mereka tetap menempatkan dan menjadikan Al-Qur’an sebagai media
terbaik untuk berinteraksi dengan Tuhan.
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Kajian mengenai tafsir memang telah banyak dilakukan, baik dalam
kitab-kitab klasik, buku-buku ilmiah maupun hasil penelitian dewasa ini.
Namun sejauh penelaahan peneliti belum ditemukan pembahasan khusus
dan komprehensif tentang metodologi kritik tafsir Al-Qur’an, khususnya
yang mengkaji pemikiran ‘Abd al-Wahab Fa>yed.

17
Dalam buku-buku ‘Ulu>m al-Qur’a>n klasik, seperti al-Burha>n fi>
‘Ulu>m al-Qur’a>n karya al-Zarkashi> (745-794 H),47 al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n karya al-Suyu>t}i> (w. 911 H)48 dan Mana>hil al-‘Irfa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n karya al-Zarqa>ni (w. 1367 H),49 di dalamnya memang dibahas
tentang karakter tafsir yang terpuji (mah}mu>d) dan tercela (madhmu>m), juga
syarat-syarat mufasir dan parameter diterima atau ditolaknya sebuah
penafsiran. Akan tetapi sistem penjabarannya sangat singkat dan belum
tersusun secara sistematis laiknya sebuah metodologi kritik pada umumnya.
Adapun dalam bentuk buku-buku ilmiah yang peneliti bisa dapatkan,
antara lain, al-Ittija>ha>t al-Munh}arifah fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m (1966)
karya Muh}ammad H}usayn al-Dhahabi>, al-Dakhi>l fi> al-Tafsi>r (1996) karya
Ibrahi>m ‘Abd al-Rah}ma>n Muh}ammad Khali>fah, al-As}i>l wa a-Dakhi>l fi Tafsi>r al-Qur’a>n wa Ta’wi>lih: Riwa>yah wa Dira>yah (1995) karya ‘Abd al-Ghafu>r
47
Nama lengkapnya Abu ‘Abd Alla>h Badr al-Di>n Muh}ammad ibn Baha>dir ibn
‘Abd Alla>h al-Zarkashi> al-Mas}ri>. Lahir di Kairo, Mesir pada tahun 745 H dan
meninggal di kota yang sama tahun 794 H. Ahli dalam berbagai bidang ilmu agama,
antara lain: fikih, hadis dan ‘ulu>m al-Qur’a>n. Di antara guru-gurunya adalah Sira>j ad-
Di>n al-Bulqi>ni>, Jama>l al-Di>n Isnawi>, Ibn Quda>mah al-Maqdisi>, Abu> al-Fida>’ ibn Kathi>r,
Shiha>b al-Di>n Adhru’i>. Di antara karya-karyanya, al-Burha>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (ulumul
qur’an), al-Bah}r al-Muh}i>t} (ushul fikih), al-Tadhkirah fi> al-Ah}a>di>th al-Mushtaharah
(ilmu hadis), al-Nukat ‘Ala> ‘Umdat al-Ah}ka>m (fikih), dll. Biografi secara lengkap
dapat dilihat pada: ‚al-Ima>m Badr al-Di>n al-Zarkashi>‛, Da>r al-Ifta>’ al-Mas}ri>yah,
http://www.dar-alifta.org/ViewScientist.aspx?ID=90 lihat pula al-Maktabah al-Sha>milah, http://shamela.ws/index.php/author/93 (diakses pada tanggal 18 Mei 2010).
48 Nama lengkapnya ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abi> Bakr ibn Muh}ammad ibn Sa>biq
al-Di>n ibn al-Fakhr ‘Uthma>n ibn Nas}i>r al-Di>n Muh}ammad ibn Sayf al-Di>n Khad}ari> ibn
Najm al-Di>n Abi> al-S{ala>h} Ayyu>b ibn Nas}ir al-Di>n Muh}ammad ibn al-Shaykh Hamma>m
al-Di>n al-Hamma>n al-Khad}ari> al-Suyu>t}i>. Lahir ba‘da Maghrib, pada hari Ahad, bulan
Rajab tahun 849 H di Mesir dan wafat pada hari Jum’at, 19 Jumad al-U<la> 911 H di
umurnya yang ke-61 tahun 10 bulan 18 hari. Dikuburkan di pemakaman Qaus}u>n atau
Qaisun, di luar pintu gerbang Qarra>fah, atau yang terkenal dengan sebutan Bawwa>bah
al-Sayyidah ‘A<ishah (pintu gerbang Sayyidah ‘Aishah) di Kairo. Di antara karya-
karyanya, al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, ad-Durr al-Manthu>r fi> al-Tafsi>r al-Ma’thu>r, ‘Ain al-Is}a>bah fi> Ma’rifat al-S{ah}a}bah, dan masih banyak lagi. Lihat: Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>,
Tadri>b al-Ra>wi> fi> Sharh} Taqri>b al-Nawawi>, yang di-tah}qi>q oleh Ahmad Umar Ha>shim,
(Bayru>t: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, t.th.), 2-17. 49
Nama lengkapnya Muh}ammad ibn ‘Abd al-‘Az}i>m al-Zarqa>ni>. Keturunan dari
keluarga Ja’fariyah yang berdomisili di daerah propinsi al-Gharbiyah, Mesir. Sementara
Zarqa>n (atau Zurqa>n) adalah nama kampung kelahirannya di daerah Manu>fiyah, Mesir.
Ia dilahirkan pada awal abad ke-14 H dan meninggal pada tahun 1363 H. Lihat ‘Abd al-
Rah}ma>n al-Shahri>, ‚Istifsa>r ‘an Kita>b Mana>hil al-‘Irfa>n‛, Multaqa> Ahl al-Tafsi>r, http://www.tafsir.net/vb/archive/index.php/t-38.html, (diakses pada tanggal 18 Mei
2010).

18
Mah}mu>d Mus}t}afa> Ja‘far, al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m (2005)
karya H{usayn Muhammad Ibra>hi>m Muhammad ‘Umar, Us}u>l al-Dakhi>l fi> Tafsi>r A<yi al-Tanzi>l (2009) karya Jama>l Mus}t}afa ‘Abd al-H{ami>d ‘Abd al-
Wahha>b al-Najja>r,50 memang ditemukan penjelasan mengenai pentingnya
melakukan kritik tafsir Al-Qur’an, namun penjabaran kritik dalam buku-
buku tersebut masih bersifat informatif-deskriptif dengan menyajikan secara
random berbagai contoh bentuk penyelewengan penafsiran dari beberapa
kelompok Islam, seperti Muktazilah, kelompok Sufi, Syi’ah, Khawa>rij, dan
Ba>t}i>ni>yah.51
Dalam bentuk buku-buku metodologi ilmiah berbahasa Indonesia
yang berhasil peneliti temukan, di antaranya Metodologi Studi Al-Qur’an
karya Ulil Abshar Abdalah, Abdul Muqsith Ghazali dan Lutfi Syaukani
(2010), dan buku Metodologi Penelitian Tafsir Hadis karya Hamka Hasan.
Dalam dua buku ini memang disebutkan metodologi studi tafsir, terutama
yang terkait dengan tema-tema dalam disiplin ‘ulum Al-Qur’an, tapi
penyajiannya terkesan sambil lalu sehingga terlihat kurang terfokus. Adapun
buku Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur’an Periode Klasik Hingga Kontemporer karya Abdul Mustaqim (Nun Pustaka, 2003),
terlihat bahwa penulisnya mencoba melakukan pemetaan dan kategorisasi
terhadap produk-produk penafsiran Al-Qur’an mulai dari periode klasik
hingga modern-kontemporer yang memang memiliki corak dan karakteristik
berbeda-beda. Dosen Jurusan Tafsir-Hadis IAIN Sunan Kalijaga ini
mengkombinasikan antara pendekatan historis-periodik dengan pendekatan
filosofis konseptual dalam memotret perkembangan tafsir.
Terkait dengan buku-buku kritik yang dapat penulis temukan,
diantaranya, Ami>n al-Khu>li>, al-Tafsi>r: Ma’a>lim H}aya>tihi Manhajuhu al-Yawma (1962) dan al-Tafsi>r: Nash’atuh, Tadarrujuh, Tat }awwuruh (1982);
Fazlur Rahman, Islam and Modernity (1982); Nas}r H{a>mid Abu> Zayd, Naqd al-Khit}a>b al-Di>ni> (1994) dan Mafhu>m al-Nas}: Dira>sah fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n
(1994) serta Ishka>liyya>t al-Qira>’ah wa A<liya>t al-Ta’wi>l (2005); Mohammad
Arkoun, Min al-Ijtiha>d Ila> Naqd al-‘Aql al-Isla>mi> (1991) dan al-Fikr al-
50
Ia adalah Dosen penulis (peneliti) pada Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-
Azhar Kairo, tahun 2004-2005, pengampu mata kuliah al-Dakhi>l fi> al-Tafsi>r. 51
Lihat Muh}ammad H{usayn al-Dhahabi>, al-Ittija>ha>t al-Munharifah fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), Cet.II; Ibrahi>m ‘Abd ar-Rah}ma>n
Muh}ammad Khali>fah, al-Dakhi>l fi> al-Tafsi>r (Kairo: Universitas Al-Azhar, 1996); ‘Abd
al-Ghafur Mahmud Mus}t}afa> Ja’far, al-As}i>l wa a-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n wa Ta’wi>lih: Riwa>yah wa Dira>yah (Kairo: Universitas Al-Azhar, 1995); H{usayn Muh}ammad Ibra>hi>m
Muh}ammad ‘Umar, al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m (Kairo: Universitas Al-
Azhar, 2005); Jama>l Mus}t}afa ‘Abd al-H{amid ‘Abd al-Wahha>b al-Najja>r, Us}u>l al-Dakhi>l fi> Tafsi>r A<yi al-Tanzi>l (Kairo: Universitas Al-Azhar, 2009), Cet. IV.

19
Isla>mi>; Naqd wa Ijtiha>d (1988); ‘Ali H{arb, Naqd al-Nash} (2005) dan Naqd al-Haqiqah. Buku-buku ini berbicara tentang urgensi kritisisme penafsiran
namun berbasis pada teori-teori biblical criticism.52 Kendatipun gagasan dan
bangunan metodologi yang ada dalam buku tersebut cukup memukau dan
inspiratif, namun dalam konteks kritisisme penafsiran Al-Qur’an, kelompok
mayoritas masih belum dapat menerimanya, sehingga patut diteliti dan
diadaptasi sedemikian rupa agar sejalan dengan khazanah keilmuan Islam.
Dalam bentuk buku berbahasa Indonesia, ditemukan misalnya Tafsir Kontekstual Al-Qur’an karya Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal
Panggabean. Dalam buku ini ditemukan sekelumit tentang kritik metodologi
tafsir, kendati demikian buku tersebut belum menyajikan langkah-langkah
kritik tafsir secara sistematis, praktis dan aplikatif. Sedang dalam buku Kritik Ortodoksi Tafsir Ayat Ibadah karya Muhammad Salman (LKIS,
2004), disebutkan tentang pentingnya kritik terhadap berbagai penafsiran
ayat-ayat ibadah. Jika penafsiran masih berpegang pada paradigma lama
(ortodok) dalam memahami teks keagamaan maka umat Islam tidak akan
pernah mampu menyelesaikan problem kemanusiaan yang saat ini semakin
rumit dan kompleks.
Disertasi dengan tajuk Realitas al-Dakhi>l dalam Al-Qur’an dan
Tafsirnya Departemen Agama RI Edisi 2004 karya Ibrahim Syuaib (2007)
juga layak diketengahkan di sini. Di dalamnya, Syuaib lebih menekankan
analisa terhadap fenomena tafsir infiltratif (al-dakhi>l) yang terdapat dalam
kitab Tafsir terbitan Kementerian Agama edisi 2004. Itupun fokus kajiannya
hanya pada salah satu bentuk al-dakhi>l yakni al-dakhi>l bi al-ma’thu>r dengan
menyebutkan status riwayatnya saja.53 Sementara disertasi ini
diorientasikan, selain menganalisis rumusan metodologi kritik al-dakhi>l-nya
Fa>yed, juga diproyeksikan untuk merekonstruksi, merestrukturisasi dan
menyusun metodologi kritik tafsir dengan pendekatan kritik hadis, kritik
sastra dan hermeneutika objektif.
52
Diantara bentuk biblical criticism (kritik Bibel) adalah metode kritik sejarah
(historical-critical method), kritik teks (textual criticism), kajian filologis (philological study), kritik sastra (literary criticism), kritik bentuk (form criticism), dan kritik redaksi
(redaction criticism). Lihat selengkapnya pada Edwin D. Freed, The New Tastement: A Critical Introduction (California: Wadsworth Publishing Company, 1991), Cet. II, 77.;
Edgar Krentz, The Historical-Criticism Method (Philadelpia: Fortress Press, 1975), 48-
54. 53
Lihat Ibrahim Syuaib Z, Realitas al-Dakhi>l dalam Al-Qur’an dan Tafsirnya Departemen Agama RI Edisi 2004, Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
tahun 2007, tidak diterbitkan.

20
Ecep Ismail juga menulis tentang Kritik Metodologi Tafsir: Studi al-Dakhi>l dalam Tafsir Mafa>tih} al-Ghayb (2008). Sesuai dengan judulnya, hasil
penelitian dosen UIN Bandung ini lebih menitikberatkan kepada studi al-dakhi>l yang terdapat dalam tafsir Mafa>tih} al-Ghayb karya Fakhr al-Di>n al-
Ra>zi>, baik al-dakhi>l al-naqli> maupun al-dakhi>l al- ra’yi>.54 Sementara
disertasi ini lebih fokus pada analisis konsep metode kritik al-dakhi>l yang
digagas Fa>yed dan proses rekonstruksinya.
Dengan demikian, belum ada tulisan yang secara sepesifik
menyajikan metodologi kritisisme yang konstruktif dan aplikatif terhadap
penafsiran Al-Qur’an yang dibangun di atas epistemologi keilmuan Islam
dan Barat sekaligus. Karena itu, disertasi ini mengembangkan peta kajian
yang dikembangkan oleh Alford T. Welch bahwa kajian Al-Qur’an dibagi ke
dalam tiga wilayah: (1) exegesis, atau studi teks, (2) sejarah interpretasi
(tafsir), dan (3) peran Al-Qur’an dalam kehidupan dan pemikiran kaum
Muslim (dalam ritual, teologi, dan lain sebagainya).55 Pengembangan
tersebut berhubungan dengan wilayah pertama, yakni studi teks dan
kritisisme terhadap penafsiran.
E. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif.56 Hal
ini dikarenakan dalam penelitian ini terdapat berbagai karakteristik
penelitian kualitatif, diantaranya: (1) data berupa dokumen yang bersifat
alamiah (natural setting), (2) pengambilan sampel ditetapkan secara
purposif, (3) peneliti sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan dan
menginterpretasikan data, (4) analisis data secara induktif, dan (5) makna
merupakan hal yang esensial.57
54
Lihat selengkapnya pada Ecep Ismail, Kritik Metodologi Tafsir: Studi al-Dakhi>l dalam Tafsir Mafa>tih} al-Ghayb (Bandung: Lemlit UIN Sunan Gunung Djati,
2008). 55
Dikutip dari Richard C. Martin, ‚Understanding the Qur'an in Text and
Context‛, History of Religion, 21: 4 (1980), 361. 56
Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilakan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Lihat Lexi L. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 1997), Cet. VIII, 6.
57 Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for
Education: An Introduction to Theory and Methode, (London: Allyn and Bacon, Inc,
1982), 10.

21
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan rancangan analisis isi
(content analysis). Analisis isi ini dugunakan berdasarkan pada: (1) sumber
data pada penelitian ini adalah dokumen, (2) masalah yang dianalisis adalah
isi buku al-Dakhi>l, dan (3) tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan isi buku tersebut, menganalisisnya dan membuat
inferensi.58
2. Instrumen Penelitian
Sebagai penelitian yang bersifat kualitatif, instrumen kunci dalam
penelitian ini adalah human instrumen,59 artinya, penelitilah yang
mengumpulkan data, menyajikan data, mereduksi data, mengorganisasikan
data, memaknai data, dan menyimpulkan hasil penelitian.
Penggunaan manusia (peneliti) sebagai instrumen kunci dalam
penelitian ini karena penelitilah yang lebih memahami data sesuai dengan
masalah penelitian, memahami konteks, dan memaknai data penelitian.
3. Sumber Data Penelitian
Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber
data primer dan skunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah
kitab al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>>n al-Kari>m karya ‘Abd al-Wahha>b ‘Abd al-
Wahha>b Fa>yed yang diterbitkan oleh Mat}ba‘ah H{assa>n (Jilid I), Kairo,
tahun 1978 M dan Mat}ba‘ah al-Had}a>rah al-‘Arabi>yah (Jilid II), Kairo, tahun
1980 M.
Sedang sumber data sekunder antara lain diambil dari buku-buku
‘Ulu>m al-Qur’a>n,60 kitab-kitab tafsir,61 karya-karya tentang al-dakhi>l,62
58
Inferensi adalah menarik atau mengambil kesimpulan. Lihat Darmiyati
Zuchdi, Panduan Penelitian Analisis Konten (Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta,
1993), 15. 59
Penelitian kualitatif mempunyai setting natural sebagai sumber data yang
langsung, dan peneliti adalah kunci instrumen. Lihat Kinayati Djojosuroto, Prinsip-prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia,
2000), Cet. I, 28; lalu bandingkan dengan Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen,
Qualitative Research for Education, 10; D. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1988), 55.
60 Diantaranya adalah al-Burha>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n karya Badr ad-Di>n al-
Zarkashi>, al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n karya Jala>l ad-Din Suyu>t}i>, Mana>hil al-‘Irfa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n karya al-Zarqa>ni>, dll.
61 Misalnya Ja>mi‘ al-Baya>n fi> Tafsi>r A<yi al-Qur’a>n karya Ibn Jari>r al-T{abari>,
Mafa>tih} al-Ghayb karya Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, al-Kashsha>f karya al-Zamakhshari>, dll.

22
madha>hib al-tafsi>r,63 buku-buku metodologi64 dan buku-buku tentang
kritik.65
4. Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dokumentasi. Dalam pengumpulan data ini, peneliti mengidentifikasi
prinsip-prinsip dan prosedur metodologi kritik dalam buku al-dakhi>l fi> al-tafsi>r karya Fa>yed. Sebelum mendeteksi prinsip dan prosedur, akan diawali
dengan memotret sisi genealogis kemunculan ide kritik al-dakhi>l, baik dari
sisi fisik maupun psikologis. Kemudian mendeteksi berbagai metodologi
dan pendekatan yang digunakan Fa>yed untuk mengkontruk teori kritiknya.
Pendeteksian dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis,
psikologis dan content analysis sebagai pisau analisis.
Hasil identifikasi dan analisis tersebut kemudian distrukturisasi dan
direkonstruksi ulang dengan menggunakan pendekatan hermeneutika
objektif, kritik sastra dan kritik hadis, sehingga diharapkan akan tergambar
bangunan yang jelas mengenai prosedur dan langkah-langkah kongkrit
62
Seperti bukunya Ibrahi>m ‘Abd ar-Rah}ma>n Muh}ammad Khali>fah, al-Dakhi>l fi> al-Tafsi>r, (Kairo: Universitas Al-Azhar, 1996), ‘Abd al-Ghafu>r Mah}mu>d Mus}t}afa> Ja
‘far, al-As}i>l wa a-Dakhi>l fi Tafsi>r al-Qur’a>n wa Ta’wi>lih: Riwa>yah wa Dira>yah, (Kairo:
Universitas Al-Azhar, 1995), H{usayn Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad ‘Umar, al-Dakhi>l fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m, (Kairo: Universitas Al-Azhar, 2005), Jama>l
Mus}t}afa ‘Abd al-H{amid ‘Abd al-Wahha>b al-Najja>r, Us}u>l al-Dakhi>l fi> Tafsir A<yi al-Tanzi>l, (Kairo: Universitas Al-Azhar, 2009), dll.
63 Semacam kitab al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n karya Muh}ammad H{usayn al-
Dhahabi>, al-Mufassiru>n: H{aya>tuhum wa Manhajuhum karya al-Sayyid Muh}ammad ‘Ali>
Iya>zi>, dll. 64
Seperti buku Metodologi Penelitian Tafsir Hadis karya Hamka Hasan,
Metodologi Studi Al-Qur’an karya Ulil Abshar Abdalah dkk, dll. 65
Misalnya adalah Hans-Georg Gadamer, Philosophical Hermeneutics,
diterjemahkan dan disunting oleh David E. Linge, (1976), Josef Bleicher, Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique, (1980), Ami>n al-
Khu>li>, Tafsi>r: Ma’a>lim H}aya>tihi Manhajuhu al-Yawma (1962) dan al-Tafsir: Nash’atuhu, Tadarrujuhu, Tat}awwuruhu (1982), Fazlur Rahman, Islam and Modernity
(1982), Nas}r H{a>mid Abu> Zayd, Naqd al-Khit}a>b al-Di>ni> (1994) dan Mafhu>m al-Nas}: Dira>sah fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (1994) serta Ishka>liyya>t al-Qira>’ah wa A<liya>t al-Ta’wi>l (2005), Mohammad Arkoun, Min al-Ijtiha>d Ila> Naqd al-‘Aql al-Isla>mi> (1991) dan al-Fikr al-Isla>mi>; Naqd wa Ijtiha>d (1988), ‘Ali H{arb, Naqd al-Nas} (2005) dan Naqd al-H{aqi>qah, Tafsir Kontekstual Al-Qur’an karya Taufik Adnan Amal dan Shamsu Rizal
Panggabean, Kritik Ortodoksi Tafsir Ayat Ibadah karya Muhammad Salman, dll.

23
kritisisme penafsiran. Agar hasil identifikasi, strukturisasi dan rekonstruksi
benar-benar akurat, maka akan dilakukan berulangkali.
5. Prosedur Analisis Data
Berpijak pada tujuan penelitian ini, maka analisis data dilakukan
secara kualitatif. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah model analisis isi (content analysis)66 yang diadaptasi dari Klaus
Krippendorff.67 Maka langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam
menganalisis data adalah sebagai berikut:
a. Membaca buku al-Dakhi>l fi> al-Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m secara
mendalam dan menyeluruh;
b. Menentukan unit (unitisasi). Unitisasi ini -kata Klaus- meliputi
penetapan unit-unit, memisahkan data menurut batas-batasnya, dan
mengidentifikasi data untuk analisis berikutnya.68 Dalam unitisasi ini,
peneliti mengidentifikasi model rumusan metode kritik penafsiran
infiltratif (al-dakhi>l) yang dirumuskan Fa>yed dengan menggunakan
pendekatan fenomenologis, psikologis dan content analysis.
c. Menetapkan data yang dianalisis (sampling).
d. Membuat catatan (recording) terhadap data yang telah ditetapkan untuk
dianalisis.
e. Mereduksi data (terkadang tahapan ini dilakukan bersamaan dengan
kegiatan unitisasi). Dalam mereduksi data ini, peneliti memilih dan
memilah data yang relevan dan yang kurang relevan untuk dianalisis.
Dengan kata lain, data yang relevan dengan penelitian ini dianalisis,
66
Analisis isi adalah mengklasifikasikan kata-kata ke dalam kategori-kategori
yang lebih kecil. Setiap kategori itu dibuat berdasarakan kesamaan makna kata, atau
berdasarkan kemiripan makna kata dari setiap teks atau pembicaraan. Dengan asumsi
itu, pembaca akan dapat mengetahui fokus atau pesan dari pengarang, pembuat teks,
atau pembicara dengan menghitung jumlah kategori yang ada dalam teks tersebut.
Menurut Krippendorff, setidaknya ada empat jenis analisis isi yaitu, analisis wacana
(discourse analysis), analisis retorika (rhetorical analysis), analisis isi etnografis
(ethnographic content analysis), dan analisis percakapan (conversation analysis). Lihat
Klaus Krippendorff, Content Analysis (California: Sage Publication, 2004), 17; Lihat
juga Robert Philiph Weber, Basic Content Analysis (California: Sage Publication,
1990), 9-10. 67
Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to its Metodology,
86. 68
Klaus Krippendorff, Content Analysis, 86.

24
sedangkan data yang kurang relevan dengan penelitian tidak dianalisis
(disisihkan).
f. Membuat inferensi terhadap data yang telah diidentifikasi. Dalam hal
ini, peneliti menggunakan konstruk analisis, yaitu suatu upaya
mengoperasikan pengetahuan analisis tentang saling ketergantungan
antara data dan konteks.69 Dengan demikian, dalam pembuatan inferensi, peneliti mengkaji konteks penulisan al-Dakhi>l dan menganalisis
penjelasan yang diungkapkan Fa>yed secara komparatif dengan pisau
analisis dan pendekatan kritik hadis, kritik sastra dan hermeneutika
objektif.
g. Selain itu, untuk memperkuat interpretasi dan analisis, peneliti juga
menggunakan facility conditions (kondisi kesesuaian).70 Dalam kondisi
kesesuain ini dicermati dari tiga sisi, yaitu: sisi penutur (mutakallim),
petutur (mukha>t}ab), dan pesan/isi tuturan.
h. Melakukan analisis dan membahas hasil analisis. Kegiatan yang
dilakukan dalam menganalisis data adalah menjelaskan desain dan
prinsip-prinsip metodologi kritik tafsir yang ditulis ‘Abd al-Wahha>b
Fa>yed dalam buku al-Dakhi>l, kemudian merekonstruksi metodologi
kritik tafsir tersebut dengan menggunakan pendekatan hermeneutika
objektif, kritik sastra dan kritik hadis.
i. Melakukan validasi. Teknik validasi atau keabsahan temuan yang akan
dipakai oleh peneliti adalah sebagaimana yang akan diuraikan pada butir
selanjutnya (Keabsahan Temuan).
6. Pendekatan dan Teori
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu; pendekatan
sejarah (historical approaches) dan pendekatan fenomenologi.71 Pendekatan
69
Klaus Krippendorff, Content Analysis, 99. 70
Ibrahim ‘Abd al-Shuku>r, Kajian Tindak Tutur (Surabaya: Usaha Nasional,
1992), 35. 71
Pendekatan fenomenologi dipakai karena ia berusaha menyingkap esensi dan
makna fenomena secara mendalam dan apa adanya. Pendekatan feneomenologi
berusaha menangkap fenomena sebagaimana adanya (to show itself) atau menurut
penampakannya sendiri (views itself). Diantara tokoh fenomenologi adalah Johann
Heinrich Lambert (1728-1777 M), Immanuel Kant (1724-1804 M), G.W.F. Hegel
(1770-1831 M), Edmund Husserl (1859-1938 M) dan Alfred Schutz (1899-1959 M).
Tentang pendekatan fenomenologi ini dapat dilihat antara lain dalam Antonio Barbosa
Da Silva, The Phemonemology of Religion as a Philosophical Problem (Swiss: CWK

25
sejarah digunakan untuk memotret genealogi tradisi kritisisme penafsiran,
mulai sejak awal kemunculan Islam hingga saat ini. Sementara pendekatan
fenomenologi72 digunakan untuk memotret kehidupan ‘Abd Wahha>b Fa>yed
dan konteks sosial, budaya, serta situasi lahirnya nalar kritisisme dalam
buku al-Dakhi>l tersebut.73
Adapun teori yang digunakan untuk merekonstruksi metodologi
kritik tafsir infiltratif (al-dakhi>l) pada disertasi ini adalah teori kritik sastra
Ami>n al-Khu>li> (1895-1966), teori hermeneutika objektif74 dan teori kritik
hadis. Ketiga teori ini akan digunakan untuk merekonstruksi metodologi
kritik al-dakhi>l yang digagas Fa>yed dari dua sisi sekaligus yakni, mufasir
dan produk penafsiran itu sendiri. Tiga teori ini diharapkan dapat menjadi
senjata pamungkas untuk membidik dan merekonstruksi serta
menstrukturisasi metodologi kritik tafsir yang sistematis, objektif dan
aplikatif.
Gleerup, 1982), 32; Frederick Elliston, ‚Phenomenologi Reinterpreted: From Husserl to
Heideger‛ dalam Philosopy Today, Vol. XXI, No. 3, 1997, 279. 72
Menurut Charles J. Adam, pendekatan fenomenologi bermanfaat dalam studi
teks kitab suci karena melindungi teks (Al-Qur’an) dari ‚kematian‛ sejarah masa lalu,
karena Al-Qur’an tidak menjadi relevan kalau dilihat hanya dari perspektif sejarah masa
Nabi dan generasi yang pertama kali mendengarnya. Lihat Andrew Rippin, Muslims and Their Religious Beliefs and Practice: the Contemporary Period Vol. II (London:
Routledge, 1993), 16. 73
Christine Dymon dan Immy Hooloway, Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Communications [terj.] Cahya Wiratama
(Yogyakarta: Bentang, 2008), 232. 74
Hermeneutika objektif ini dikembangkan tokoh-tokoh klasik, khususnya
Friedrick Schleiermacher (1768-1834), Wilhelm Dilthey (1833-1911) dan Emilio Betti
(1890-1968). Menurut model ini, penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang
dipahami pengarangnya, sebab apa yang disebut teks, menurut Schleiermacher, adalah
ungkapan jiwa pengarangnya, sehingga seperti juga disebutkan dalam hukum Betti, apa
yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan kita
melainkan diturunkan dan bersifat instruktif. Diskusi lebih dalam dapat dilihat pada
Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas, (terj.) Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka,
1985), 9-10; Josef Bleicher, Contemporary Hermeneutics (London: Routlege & Kegan
Paul, 1980), 29; Nas}r H{ami>d Abu> Zayd, Ishka>liya>t al-Ta’`wi>l wa A{liya>t al-Qira>’ah
(Kairo: al-Markaz al-Thaqa>fi>, t.th.), 11; dan Sumaryono, Hermeneutik (Yogyakarta:
Kanisius, 1996), 31. Bandingkan dengan Komarudin Hidayat, Menafsirkan Kehendak Tuhan (Jakarta: Teraju, 2004), Cet. II, 3.

26
7. Keabsahan Temuan
Untuk memperoleh hasil analisis atau temuan yang sahih, maka
sejak pengumpulan data hingga pada tahap analisis data digunakan teknik
pensahih data yang diadaptasi dari Lincoln dan Guba75 sebagai berikut:
a. Observasi terus menerus (persistent observation) atau membaca dan
mengkaji terhadap sumber data.
b. Memanfaatkan sumber di luar data yang dianalisis (triangulasi).
c. Mendiskusikan dengan teman sejawat dan pihak lain yang dipandang
ahli (perdebreifing).
d. Memeriksa kembali data dan catatan yang ada (referencial adequacy check).
Dalam memanfaatkan data di luar yang dianalisis (triangulasi), peneliti mengadaptasi model triangulasi yang dikemukakan Cohen dan
Manion.76 Model yang dimaksud adalah trianggulasi teori, peneliti, dan
metodologi. Dalam penelitian ini, jenis triangulasi yang digunakan adalah
trianggulasi peneliti dan metodologi.
Triangulasi peneliti dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada
para ahli yang berkompeten untuk memeriksa hasil analisis penelitian,
misalnya ahli metodologi kritik, ahli tafsir, dan ahli ulumul qur’an.
Sedangkan triangulasi metodologi dilakukan dengan cara pemanfaatan
berbagai sumber (dokumen) lain yang relevan. Sumber (dokumen) lain yang
dimaksud antara lain buku tafsir, buku metodologi dan buku kritik
penafsiran. Hal ini dilakukan dengan harapan dari ketiga jenis buku tersebut
dapat diperoleh informasi penting tentang rumusan dan konstruksi
metodologi kritik tafsir Al-Qur’an yang praktis dan aplikatif.
F. Teknik dan Sistematika Penulisan
1. Teknik Penulisan
Untuk menghindari kesalahan dalam penulisan dan memudahkan
dalam pemahaman terhadap tulisan ini, maka peneliti akan menggunakan
metode penulisan disertasi yang mengacu pada buku: Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang diterbitkan UIN Jakarta Press tahun 2002.
75
Yuna S. Lincoln dan Egon G. Guba, Naturalistic Inquiry (London: Sage
Publication, 1985), 201. 76
L. Cohen dan L. Manion, Research Methods in Educatioan (London:
Routledge, 1994), 56.

27
2. Sistematika Penulisan
Disertasi ini disusun menjadi enam bab. Satu bab pendahuluan,
empat bab pembahasan penelitian, dan satu bab penutup. Setiap bab
mengandung pasal yang merupakan pokok bahasan dari setiap bab.
Karena metode yang dipakai dalam mempresentasikan penelitian ini
adalah al-‘ard} wa al-naqd (mengetengahkan persoalan kemudian
mengkritiknya), maka empat bab pembahasan akan dibagi lagi menjadi dua
bagian. Bagian pertama (bab kedua dan ketiga) dijadikan sebagai landasan
teori, sementara bagian kedua (bab keempat dan kelima) adalah bab inti
disertasi yang berisi tentang hasil analisis penelitian dan rekonstruksi
metodologi kritik tafsir.
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah; identifikasi, batasan dan rumusan masalah; tujuan dan manfaat
penelitian, penelitian terdahulu yang relevan; metodologi penelitian; teknik
dan sistematika penulisan.
Bab kedua, berisi tentang diskursus kritik tafsir. Bab ini akan
mengupas hal ihwal kritik tafsir; mulai dari epistema kritik tafsir,
(pengertian, bentuk dan model), historisitas dan tradisi kritik tafsir yang
berkembang di dunia Barat dan Timur-Islam, hingga berbagai metodologi
dan pendekatan kritik tafsir.
Pembahasan mengenai diskursus kritik tafsir ini sengaja diletakkan
pada bab kedua dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara
komprehensif dan mendalam tentang hakekat, geliat, sekaligus tradisi kritik
tafsir dan horizonnya dari zaman klasik hingga modern. Pendekatan yang
digunakan untuk membidik tema ini adalah pendekatan kritik-historis.
Bab ketiga berisi tentang potret kitab al-Dakhi>l fi Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m. Bab ini diproyeksikan untuk mengidentifikasi buku, baik secara
fisik maupun ideologis. Agar status buku tergambar dengan jelas, maka bab
ini akan diawali dengan uraian tentang profil singkat sang penulis,
kemudian dilanjutkan dengan proses identifikasi buku; mulai dari materi
dan sistematika, latar penulisan, sumber rujukan, metode, pendekatan dan
ideologi buku. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan kritik-historis dan fenomenologis.
Bab keempat akan mengurai secara komprehensif prinsip dan
prosedur kritik al-dakhi>l yang digagas Fa>yed, serta berbagai fakta seputar
praktek penyelewengan penafsiran (tah}ri>fa>t al-tafsi>r) dari masa ke masa.
Bab ini juga mengurai persoalan orisinalitas dan infiltrasi penafsiran,
perkembangan, motif dan bentuk al-dakhi>l serta basis, prosedur dan aplikasi

28
kritik al-dakhi>l. Berbagai tema di atas merupakan pembacaan terhadap isi
teori kritik al-dakhi>l yang digagas Fa>yed. Untuk mendapatkan hasil yang
maksimal, pendekatan yang digunakan pada bagian ini adalah pendekatan
kritik-historis dan content analysis.
Bab kelima, akan mencoba untuk merekonstruksi dan
merestrukturisasi metodologi kritik tafsir Fa>yed dengan menggunakan
pendekatan kritik sastra Ami>n al-Khu>li> (1895-1966 M), hermeneutika
objektif dan kritik hadis. Dengan menggunakan tiga pendekatan ini sebagai
pisau analisis, maka bangunan metodologi baru kritik tafsir pasca
rekonstruksi dan restrukturisasi dapat dipotret dari tiga sisi, yaitu (1)
kritisisme terhadap personalitas mufasir (naqd al-mufassir) yang terdiri dari
review atas idiologi, motivasi, kompetensi dan karakter mufasir. (2)
kritisisme terhadap metodologi tafsir (naqd al-manhaj) yang diarahkan pada
kritik teknis penulisan dan aspek hermeneutika tafsir. (3) kritik terhadap
produk (content) penafsiran (naqd al-tafsi>r) diorientasikan pada studi
kualitas, otentisitas dan universalitas tafsir. Melalui langkah pertama (naqd al-mufassir), diharapkan seorang mufasir dapat terpotret dengan jelas sisi
objektivitasnya dalam proses menafsirkan Al-Qur’an. Melalui langkah
kedua dan ketiga (naqd al-manhaj wa matn al-tafsi>r), diharapkan dapat
mereview dan menangkap hasil penafsiran dengan baik, objektif dan tepat.
Bab keenam adalah penutup, berisikan beberapa kesimpulan yang
merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan saran-saran konstruktif,
baik bagi para peneliti selanjutnya atau bagi pembaca penelitian ini secara
umum.
Satu persatu pembahasan di atas akan diurai dan dijelaskan secara
elaboratif dan terstruktur pada bab-bab selanjutnya.