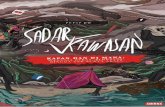Proposal Nya Alam Baru
-
Upload
rizki-amalia -
Category
Documents
-
view
73 -
download
0
description
Transcript of Proposal Nya Alam Baru

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk
yang besar. Jumlah penduduk ini terus bertambah setiap tahunnya,
pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta aktivitas pembangunan dalam
berbagai bidang tentu saja akan menyebabkan ikut meningkatnya permintaan
akan lahan. Permintaan akan lahan yang terus bertambah di satu sisi sementara
luas lahan yang tersedia jumlahnya terbatas disisi lain akan mendorong
terjadinya konversi lahan pertanian ke non-pertanian (Utomo dkk,1992).
Konversi lahan dapat diartikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau
seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan)
menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan
dan potensi lahan itu sendiri (Utomo dkk,1992) .
Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan
penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi
keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah
jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik,
konversi lahan juga merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan
jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. Konversi lahan pertanian
seringkali menimbulkan dampak negative terutama dalam konteks ketahanan
pangan dan kondisi social ekonomi petani.
Untuk negara yang masih dalam tahap berkembang seperti Indonesia,
tuntutan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, pemukiman, maupun

kawasan industri, turut mendorong permintaan terhadap lahan. Akibatnya,
banyak lahan sawah, terutama yang berada dekat dengan kawasan perkotaan,
beralih fungsi untuk penggunaan tersebut. Selain itu, adanya krisis ekonomi yang
mengakibatkan tingginya pengangguran dan menurunnya pendapatan
masyarakat, memicu para pemilik lahan untuk menjual asetnya. Selanjutnya, hak
ada pada pemilik lahan yang baru, apakah akan mengelola lahan tersebut untuk
pertanian, atau mengubah fungsinya untuk penggunaan lain (anonim 1, 2013).
Lahan pertanian dapat memberikan mamfaat baik dari segi ekonomi,
social maupun lingkungan. Oleh kareana itu semakin sempitnya lahan pertanian
akibat konversi akan mempengaruhi segi ekonomi, social dan lingkungan
tersebut. Jika fenomena konversi lahan pertanian ke non pertanian terus terjadi
secara tak terkendali, maka hal ini akan menjadi ancaman tidak hanya bagi
petani dan lingkungan, tetapi hal ini bias menjadi masalah nasional.
Lahan pertanian yang ada di Makassar mulai terpengaruh oleh
pembangunan. Dari tahun ketahun mulai terjadi penyempitan luas lahan
pertanian akibat konversi lahan. Adapun luas lahan pertanian yang mengalami
konversi lahan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1. Luas Lahan Pertanian dan Alih Fungsi Lahan di kota Makassar, 2005-2009
Sumber:
Data Sekunder
Badan Pusat
Statistik
Makassar, 2014
Saat ini bangsa bangasa Indonesia juga menghadapi masalah lain yang sangat
serius yaitu masih tingginya angka kemiskinan akibat tingginya inflasi tahun kelender
2013 secara nasional, jumlah penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,55
juta orang atau 11,47 persen, dibandingkan Maret 2013 meningkat 480 ribu orang.
Meski data kemiskinan tahun 2013 cenderung menurung dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya namun, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin diperkirakan
meningkat seiring kenaikan harga BBM dan harga pangan hingga paruh tahun 2013.
(anonim 2 2014). Kemiskinan merupakan akar berbagai masalah seperti rendahnya
pendidikan, kesehatan dan juga buruknya moral masyarakat. Salah satu factor
mendasar penyebab kemiskinan ini adalah lemahnya akses sebagian besar penduduk
terhadap sumberdaya alam dan sumber-sumber ekonomi lainnya. Banyak petani yang
tidak lagi memiliki lahan karena tingginya laju konversi lahan pertanian dan hutan untuk
dijadikan sebagai lokasi perumahan, industry, dan lain sebagainya. Saat ini telah terjadi
penurunan luas areal panen, akibat konversi lahan tanaman pangan ke : (1)
No Tahun Luas Lahan
Pertanian (Ha)
Luas Alih Fungsi Lahan
(Ha)
1. 2005 2955 -
2. 2006 2700 255
3. 2007 2700 -
4. 2008 2700 -
5. 2009 2700 -

penggunaan non-pangan (misal, perkebunan kelapa sawit) dan (2) penggunaan non-
pertanian ( misal, pemukiman, fasilitas umum, dan industri). Konversi ini juga
menyiapkan investasi untuk prasarana pertanian seperti irigasi. Sementara itu : (1)
produktivitas relatif tetap, dimana hal ini disebabkan akibat penurunan tingkat
kesuburan tanah, (2) terjadi persaingan antarakebutuhan komoditas untuk pangan atau
pakan (misalnya kedelai dan jagung), (3) margin yang diterima petani untuk tanaman
pangan sangat rendah. Pada saat yang sama indonesia memiliki ketergantungan yang
tinggi pada : (1) bahan pangan dan pakan impor, dan pada (2) input sarana produksi
pertanian dari luar wilayah produksi.
Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak terlepas akan adanya interaksi
sosial antar sesamanya. Pada dasarnya manusia sesuai dengan fitrahnya merupakan
makhluk sosial yang tidak biasa hidup sendiri melainkan membutuhkan pertolongan
orang lain. Oleh sebab itu didalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama
dan sikap gotong royong dalam menyelesaikan segala permasaiahan. Masyarakat
Indonesia terkenal dengan sikap ramah, kekeluargaan dan gotong royongnya didalam
kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk menyelesaikan segala problema yang ada
didalam kehidupan masyarakat dibutuhkan sikap gotong royong yang dapat
mempermudah dan memecahkan masalah secara efisien.
Suatu bentuk dan sikap hubungan gotong royong akan mundur ataupun punah
sama sekali sebagai akibat pergeseran nilai-nilai budaya. Akan tetapi sistem dan jiwa
gotong royong tidak akan punah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena adanya
nilai-nilai budaya yang terkandung didalam sistem budaya, budaya agama Islam,
budaya nasional merupakan suatu norma yang wajib dipatuhi oleh segenap warga

masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh gotong royong yang berasaskan
keislaman tidak akan punah melainkan mengalami pasang surut dan naik senada
dengan perubahan perekonomian masyarakatnya. Dilain pihak bentuk dan sikap
hubungan gotong royong akan berubah bahkan punah, tetapi kepunahan dengan
perubahan gotong royong tersebut melahirkan hubungan kerjasama atau gotong
royong dalam bentuk dan sikap yang lain.
Sementara itu gotong royong ataupun tolong-menolong sangat membantu
anggota masyarakat yang pada umumnya tidak mempunyai modal yang mencukupi
untuk melakukan seluruh kegiatan hidupnya jika setiap transaksi kegiatan dibayar
dengan uang dan benda-benda modal lainnya. Dengan demikian gotong royong untuk
membantu kehidupan individu keluarga sangat mempunyai arti. Di lain pihak
mengharapkan kegiatan gotong royong untuk pembangunan juga diperlukan sejumlah
dana yang mencukupi. Jadi tegasnya perpaduan antara kegiatan gotong royong dalam
segala bentuknya dengan penyediaan-penyediaan dan dan fasilitas tertentu harus
dikombinasikan sedemikian rupa sehingga pembangunan tersebut dapat dijalankan
secara efektif dan efisien. Sikap gotong royong yang dilakukan masyarakat dalam
kehidupannya memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting. Dengan adanya
gotong royong, segala permaasalahan dan pekerjaan yang rumit akan cepat
terselesaikan jika dilakukan kerjasama dan gotong royong diantara sesama penduduk
di dalam masyarakat, Pembangunan akan cepat terlaksana apabila masyarakat
didalamnya bergotong royong dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan
tersebut. Hal ini senada dengan pendapatnya Azinar Sayuti sebagai berikut:

Segi lain yang dapat diperoleh faedahnya darigotong royong ini adalah rasa
keikutsertaan tanggung jawab bersama warga masyarakat bersangkutan dalam usaha
pembangunan baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik atau menurut bidang-bidang
kehidupan yang terdapat dilingkungan masayarakat setempat.(AzinarSayuti,1983:18 7).
Gotong royong dapat diartikan sebagai sesuatu sikap ataupun kegiatan yang
ditakukan oleh anggota masyarakat secara kerjasama dan tolong menolong dalam
menyelesaikan pekerjaan maupun masalah dengan sukarela tanpa adanya imbalan.
Sikap gotong royong ini telah melekat pada diri masyarakat pedesaan dan merupakan
kebiasaan turun temurun dari nenek moyang. Sikap gotong royong ini sangat berperan
sekali untuk memperlancar pembangunan yang berguna bagi kesejahteraan
masyarakat.Kegiatan gotong royong yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam
kehidupan masyarakat desa selama ini, perlu diarahkan dan dibina sedemikian rupa
sehingga dapat menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan. Gotong royong
dalam usaha meningkatkan produksi perlu digalakan dan hasilnya digunakan untuk
pembangunan desa.
Permasalahan yang ada sekarang ialah bagaimana cara memupuk kembali nilai-
nilai gotong royong yang pernah hidup dengan kuatnya pada kehidupan masyarakat.
Walaupun tidak berarti kita harus meampertahankan faktor pendorong adanya gotong
royong tersebut. Gotong royong akan tetap hidup dikalangan masyarakat, tetapi
berbeda latar belakangnya, bentuk dan sifat dari gotong royong itu sendiri perbedaan ini
biasanya ditimbulkan oleh lingkungan masing-masing. Jadi sikap gotong royong dalam
masyarakat yang melaksanakan pembangunan mengalami perubahan berbarengan
dengan terjadinya perubahan -perubahan sosial yang berlangsung secara

berkesinambungan dengan hasil-hasil penemuan manusia itu sendiri. Sementara itu
orang-orang desa mulai menyadari dengan lebih mendalam akan perlunya kesempatan
dan tata cara berpikir baru, hal ini juga tidak terlepas dari himpitan berbagai
permasalahan yang dari waktu kewaktu semakin nyata mereka rasakan, salah satu
perubahan yang harus mereka hadapi adalah semakain berkurangnya luasan areal
lahan produktif pertanian dimana hal ini akan menyebabkan berbagai permasalahan.
Kelurahan Tamangapa kecamatan Manggala kota Makassar saat ini memiliki
total luas wilayah ……dimana kelurahan ini terbagi atas dua fungsi lahan yakni lahan
pemukiman dan lahan pertanian, seiring dengan kepadatan jumlah penduduk yang
setiap tahun mengalami peningkatan maka arus alih fungsi lahanpun tak dapat
terhindarkan, konversi lahan pertanian ke non pertanian utamanya pada sector
pemukiman yang terjadi dikelurahan ini setiap tahunnya mengalami perluasan yang
cukup signifikan, hal ini dapat kita lihat berdasarkan data luas lahan kelurahan
tamangapa kecamatan manggala kota Makassar lima tahun terakhir ini:
Berdasarkan data badan pusat statistik kota Makassar 2013, saat ini jumlah
penduduk di kelurahan tamangapa yaitu sebanyak…….jiwa. Masyarakat kelurahan
Tamangapa saat ini memiliki keanekaragaman profesi akibat dari semakin sempitnya
lahan pertanian yang beralih fungsi ke non-pertanian, hal ini pula yang menyebabkan

berbagai perubahan sosial masyarakat khususnya pada perilaku gotong royong petani
di wilayah tersebut.
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “ Dampak Konversi Lahan Terhadap Sikap Gotong royong Petani”
studi kasus di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi selatan.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penelitian ini difokuskan pada
masalah, sebagai berikut:
1. Mata pencaharian apa saja yang dijalankan masyarakat tani setelah lahan
usahatani terkonversi ke non-pertanian ?
2. Bagaimana perubahan akses masyarakat terhadap fasilitas sarana dan
prasarana umum sebelum adanya konversi lahan dan setelah adanya
konversi lahan ?
3. Bagaimana sikap gotong royong petani setelah banyaknya petani beralih
profesi ke non-pertanian ?
I.3 Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah:

1. Mengetahui mata pencaharian yang dijalankan masyarakat setelah lahan
usahataninya terkonversi ke non-pertanian
2.Mengetahui sikap gotong royong petani setelah banyaknya petani yang beralih
profesi ke non-pertanian
3.Mengetahui perubahan akses masyarakat terhadap fasilitas sarana dan prasarana
sebelum dan setelah adanya konversi lahan di daerah tersebut.
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kajian
mengenai dampak konversi lahan pada bidang sector ekonomi (mata
pencaharian petani), sosial dan ekonomi serta pengaruhnya terhadap sikap
gotong royong petani sebelum dan setelah adanya konversi lahan.
2.Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik untuk melakukan
penelitian yang sama atau penelitian lanjutan terkait kajianbmengenai konversi
lahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konversi Lahan dan Dampaknya
Tanah atau lahan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam
kehidupan manusia karena setiap aktivitas manusia selalu terkait dengan tanah.
Tanah merupakan tanah (sekumpulan tubuh alamiah, mempunyai kedalaman
yang lebar yang cirri-cirinya mungkin secara langsung berkaitan dengan vegetasi
dan pertanian sekrang) ditambah cirri-ciri fisik lain seperti penyediaan air dan
tumbuhan penutup yang dijumpai (Soepardi,1983 dalam Akbar, 2008).
Utomo (1992) menyatakan bahwa lahan sebagai modal alami yang
melandasikegiatan kehidupan dan penghidupan, memiliki dua fungsi dasar,
yakni: (1) Fungsi kegiatan budaya; suatu kawasan yang dapat dimamfaatkan
untuk berbagai penggunaan, seperti pemukiman, baik sebagai kawasan
perkotaan maupun pedesaan, perkebunan hutan produksi dan lain-lain. (2)
fungsi lindung; kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamnya untuk
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada, yang mencakup sumberdaya
alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa yang bias
menunjang pemamfaatan budidaya.
Sihaloho (2004) membedakan pengunaan tanah kedalam tiga kategori,
yaitu; (1) Masyarakat yang memiliki tanah luas dan menggarapkan tanahnya
kepada orang lain; pemilik tanah menerapkan system sewa atau bagi hasil; (2)
Pemilik tanah sempit yang melakukan pekerjaan usaha tani dengan tenaga kerja

keluarga, sehingga tidak memamfaatkan tenaga kerja buruh tani; (3) Pemilik
tanah yang melakukan usaha tani sendiri tetapi banyak memamfaatkan tenaga
kerja buruh tani, baik petani bertanah sempit maupun bertanah luas.
Bagi petani yang hanya menggantungkan kehidupan dan
penghidupannya pada usaha tani akan sulit dipisahkan dari lahan pertanian yang
dikuasainya. Mereka tidak berani menaggung resiko atas ketidak pastian
penghidupannya sesudah lahan pertaniannya dilepaskan kepada orang lain.
Disamping itu status sosial penduduk pedesaan masih ada yang dikaitkan
dengan luas kepemilikan lahannya.
Dengan memiliki lahan yang luas, petani dapat member pekerjaan kepada
tetangganya. Hubungan antara pemilik lahan dengan buruhnya diikat dalam
ikatan kekeluargaan yang saling membutuhkan, meskipun dalam status yang
berbeda. Dalam hal ini,lahan pertanian merupakan asset sosial bagi pemiliknya
yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan kehormatan
keluarganya. Lahan pertanian yang memiliki fungsi sosial seperti ini tidak mudah
tergantikan dengan imbalan ganti rugi berupa uang meskipun jumlahnya
memadai.
Lestari (2009) mendefinisikanalih fungsi lahan atau lazimnya disebut
sebagai konversi lahan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh
kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi
fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan
potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian
peruntukan pengunaan, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar

meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah
jumlahnyadan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.
Alih fungsi lahan yang umumnya terjadi adalah alih fungsi dari lahan
pertanian ke non-pertanian. Menurut suwandi (2002), lahan pertanian yang
memiliki fungsi utama untuk becocok tanam padi, palawija atau hortikultura di
karenakan gencarnya industrialisasi berakibat pada beralihnya fungsi lahan-
lahan produktif pertanian menjadi pabrik-pabrik, jalan tol, pemukiman,
perkantoran, dan lain sebagainya.
Semakin bertambahnya penduduk perkotaan akibat pertumbuhan alami
dan urbanisasi, kota semakin memerlukan fasilitas-fasilitas pendukung terutama
perumahan. Pembangunan perumahan selalu memerlukan lahan yang sudah
ada, sehingga merubah penggunaan lahan dari non perumahan ke
perumahan/pemukiman dan sarana jalan (anonim 3 2014).
Gani dan alan (2011) mengemukakan bahwa lahan-lahan persawahan di
berbagai daerah di indonesia telah menjadi kawasan permukiman, industri
perkantoran, dan bahkam untuk infrastruktur berjalan tanpa hambatan. Kebijakan
perlindungan terhadap pertanian belum efektif sehingga tidak sedikit petani padi
sawah yang lebih tergiur memilih lahan sawahnya yang sudah terbatas dijual
dengan harga yang lebih tinggi karena tekanan kebutuhan sesaat.
Secara teoritis, alih fungsi lahan sawah dapat menimbulkan kerugian,
terutama hilangnya lahan produktif penghasil beras, disamping tidak menampik
adanya mamfaat ekonomi. Namun demikian, tidaklah mudah untuk membuat

kalkulasi pasti dari mamfaat dan kerugian akibat konversi ini, karena cukup
banyak mamfaat dan kerugian yang sulit diukur.
Dampak negatif konversi lahan berdasarkan hasil penelitian adalah
hilangnya peluang memproduksi hasil pertanian di lahan sawah yang
terkonversi, diantaranya hilangnya produksi pertanian dan nilainya, pendapatan
usaha tani, dan kesempatan kerja pada usaha tani. Konversi juga
mengakibatkan hilangnya peluang pendapatan dan kesempatan kerja pada
kegiatan ekonomi yang tercipta secara langsung maupun tidak langsung
darikegiatan usaha tani tersebut, misalnya usaha traktor dan penggilingan padi.
Kerugian yang tejadi secara tidak langsung adalah meningkatkan pencemaran,
banjir, jumlah petani berlahan sempit dan tingkat kriminalitas serta moral sosial
masyarakat akan tergerus. (anonim 3 2014).
Terkait dengan dampaknya terhadap kesempatan kerja dibidang
pertanian, hal yang sama juga dikemukakan Gany dan Ala (2011) bahwa
konversi lahan pertanian berakibat pada beralihnya pekerjaanpetani rus
penyakap dan penggarap kesektor-sektor informal sebagai sumber
penghidupan. Derasnya arus konversi lahan persawahan karena kebanyakan
pemilik lahan adalah golongan petani luas yang tidak pernah memperhitungkan
betapa laranya petani-petani penggarap dan penyakap yang harus kehilangan
garapandan sumbe penghidupan satu-satunya apabila lahan tersebut beralih
fungsi.

Dampak konversi lahan sawah dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dari
fungsinya, lahan sawah diperuntukkan untuk memproduksi padi/atau tanaman
pangan lainnya. Denagn demikian adanya konversi lahan sawah kefungsi lain
akan menurunkan produksi padi nasional. Kedua, dari bentuknya perubahan
lahan sawah kepemukiman, perkantoran, prasarana jalan dan lainnya
berimplikasi besarnya kerugian akibat sudah diinvestasikannya dana untuk
mencetak sawah, membangun waduk adan system irigasi.
Namun demikian, banyak juga mamfaat yang diperoleh pasca konversi
lahan. Mamfaat itu antara lainberupa kesempatan kerja non pertanian,
peningkatan pendapatan dan dalam skala makro berupa perkembangan
ekonomi wilayah (anonim 4 2014).
2.2. Faktor penarik dan faktor pendorong konversi lahan
Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dapat disebabkan oleh
beberapa faktor. Adapun factor-faktor yanh mempengaruhi konversi lahan
pertanian di pedesaan maupun di daerah pinggiran kota sebagaimana di
kemukakan oleh Kustiawan (1997) dalam Lestari (2010), menyatakan bahwa
setidaknya ada tiga factor penting yang menyebabkan terjadinya alih fungsi
lahan, yaitu: pertama, faktor Eksternal merupakan factor yang disebabkan
oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik maupun spasial),
demografi maupun ekonomi. Kedua, factor Internal merupakan factor yang
disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna
lahan. Ketiga, factor Kebijakan merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan

oleh pemerintah pusat maupundaerah yang berkaitan dengan perubahan
fungsi lahan pertanian.
Menurut iarawan (2005) konversi lahan cenderun menular/meningkat
disebabkan oleh dua factor terkait. Pertama, sejalan dengan pembanguan
kawasan perumahan atau industry disuatu lokasiyang terkonversi, maka
aksesibilitas di lokasi tersebut semakin mendorongng meningkatnya
permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga
lahan disekitarnya meningkat. Kedua, meningkatnya harga lahan selanjutnya
mendirong petani lain disekitarnya untuk menjual lahannya. Pembeli tanah
tersebut biasanya bukan penduduk setempat sehingga akan terbentuk lahan-
lahan gutai yang secara umum rentan terhadap proses konversi lahan
Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, secara garis besar factor
penyebab konversi lahan dipilih menjadi dua, yaitu pada tingkat makro dan
mikro. Dalam tataran makro, konversi lahan sawah disebabkan oleh
peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi sektor non-pertanian
yang pesat, implementasi undang-undang yang lemah, serta nilai tukar petani
yang rendah. Dalam skala mikro, alasan utama petani melakukan konversi
lahan adalah karena kebutuhan, lahannya berada dalam kawasan industri,
serta harga lahan yang menarik. Pajak lahan yang tinggi juga cenderung
mendorong petani melakukan konversi. Factor pendorong konversi lahan
lainnya adalah adanya kesempatan membeli lahan ditempat lain yang lebih
murah. Semua penyebab konversi itu akhirnya bermuara pada motif ekonomi,

yaitu penggunaan lahan untuk peruntukan yang baru dipandang lebih
menguntungkan dari pada digunakan intuk lahan sawah (anonim 4 2014).
Silaholo (2004) membagi konversi lahan kedalam tujuh pola atau tipologi,
antara lain; (1) konversi gradual berpola sporadis; dipengaruhi oleh dua factor
uatama yaitu lahan yang kurang/tidak produktif dan keterdesakan ekonomi
pelaku konversi; (2) konversi sistematik berpola “enclave”; dikarenakan lahan
kurang produktif sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk
meningkatkan nilai tambah; (3) konversi lahan sebagai respon atas
pertumbuhan penduduk (population growth driven land conversion); lebih
lanjut disebut konversi adaptasi demografi, dimana dengan meningkatnya
pertumbuhan penduduk, lahan terkonversi untuk memenuhi kebutuhan
tempat tinggal; (4) konvers yang disebabkan oleh masalah sosial (social
problem driven land konversion); disebabkan oleh dua factor yakni
keterdesakan ekonomi dan perubahan kesejahteraan; (5) konversi tanpa
beben; dipengaruhi oleh factor keinginan untuk mengubah hidup yang lebih
baik dari keadaan saat ini dan ingin keluar dari kampong; (6) konversi
adaptasi agraris; disebabkan karena keterdesakan ekonomi dan keinginan
untuk berubah dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian;
(7) konversi multi bentuk atau tanpa bentuk; konversi dipengaruhi oleh
berbagai factor, khususnya factor peruntukan untuk perkantoran, sekolah,
koperasi, perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak dijelaskan dalam
konversi demografi.

Secara empiris menurut Winoto (2005), lahan pertanian yang paling
rentan terhadap alih fungsi lahan adalah sawah. Hal tersebut disebabkan
oleh: (1) kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem
dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan
agroekosistemlahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga
lebih tinggi. (2) daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan
dengan daerah perkotaan. (3) akibat pola pembangunan dimasa sebelumnya,
infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah
lahan kering. (4) pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, kawasan
industry, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah
bertofografi datar.
2.3. Perubahan Mata Pencaharian
Konsep mata pencaharian (livelihood) sangat penting dalam memahami
coping strategis karena merupakan bagian dari atau bahkan kadang-kadang
dianggap sama dengan strategi mata pencaharian (livelihood strategis).
Suatu mata pencaharian meliputi pendapatan (baik yang bersifat tunai
maupun barang), lembaga-lembaga sosial, relasi jender, hak-hak kepemilikan
yang diperlukan guna mendukung dan menjamin kehidupan (Elis, 1998).
Mata pencaharian di suatu wilayah akan mengalami operubahan sesuai
dengan keadaan alam, pengetahuan yang dimiliki manusia, kemampuan
teknologi yang dimiliki penduduk yang mendiami wilayah dengan kurun waktu
yang relatif cepat atau lambat. Menurut Abdurrachmat (1984:21) mengatakan

bahwa: “macam dan corak aktivitas manusia berbeda-bedapada tiap
golongan atau daerah, sesuai dengan kemampuan penduduk dan tata
geografi (geographycal setting) daerahnya”. Mata pencaharian di daerah
pedesan pada umummnya masih berorientasi pada bidang usaha mereka,
yakni pada sector peranian. Didalam pertanian terdapat empat unsur yang
terkandung didalamnya yaitu diantaranya: (1) Proses produksi, (2) Petani, (3)
Usahatani, (4) Usaha tani sebagai perusaan berbasis agribisnis.
Menurut Bintarto (1984:76), system pertanian di Indonesia ada dua jenis
pertanian yaitu; pertanian rakyat dan pertanian perkebunan besar. Pertanian
rakyat diselenggarakan oleh penduduk pedesaan atau penduduk di daerah
marginal kota. Pertanian ini didalam penyelenggaraanya mempunyai sifat-
sifat sebagai berikut: (1) modal terbatas, (2) penyerapan tenaga kerja
musiman dan bersifat kekeluargaan, (3) pengelolaan lahan dan pertanian
secara wiraswasta, (4) jenis tanaman bersifat tanaman bahan makanan (food
crops) untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsistence), (5) pertanian pada
rakyat komoditi (perdagangan) sepeti karet, cengkeh kelapa dan lada.
Sedangakan pertanian perkebuanan besar di Indonesia diselenggarakan
di tanah-tanah negara atau milik pribumi, oleh perusahaan negara,
perusahaan daerah (provinsi), dan pihak swsata nasional dan atau oleh pihak
asing. Pada pertanian perkebunan besar didapati cirri khas diantaranya: (1)
teknologi pertaniannya lebih maju, (2) penanaman modal yang besar, (3)
mempunyai staf ahli pengelola tekhnik penanaman dan pengolahan produksi,
(4) penyerapan tenaga kerja tetap, (5) produksi perkebunan dan pertanian

untuk bahan ekspor dan bahan perdagangan dalam negeri. Pada saat
sekarang ini daerah pedesaan maupun di kota cenderung mengarah pada
pergeseran mata pencaharian dari sector pertanian ke non-pertanian.
Pekerjaan diluar sector pertanian sudah mulai menjadi tumpuan harapan,
karena penyerapan tenaga kerja yang setiap tahun terus meningkat tetapi
lapangan kerja terbatas ditambah dengan adanya teknologi baru dibidang
pertanian, akhirnya banyak pekerja yang kehilangan mata pencahariaannya.
Berbagai sumber penghasilan yang diperoleh sesuai dengan
kemampuannya, keterampilan, pengetahuan dan pendidikan seseorang.
Sebagian keluarga yang mempunyai tanah yang sempit atau tidak
mempunyai tanah sama sekali, mereka banyak yang bekerja sebagai buruh
tani atau petani penggarap bagi desanya sendiri maupun di luar desanya.
Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka penggunaan lahan yang
diusahakan akan semakin relative efektif dan efisien. Sedangkan bila tingkat
pendididkan rendah maka penggunaan lahannyapun akan cenderung bersifat
tradisional. Tingkat pendidikan dan keahliah pula akan menentukan pula jenis
mata pencaharian yang mereka pilih.
Dengan demikian lahan pertanian bukan lagi merupakan asset sosial
semata, tetapi lebih diandalkan sebagai asset ekonomi atau modal kerja bila
mereka beralih profesi diluar bidang pertanian. Mereka akan keberatan
melepaskan lahan pertaniannya untuk dialihfungsikan pada penggunaan non-
pertanian. Keadaan tersebut semakin diperburuk dengan kondisi ekonomi
seperti saat ini, dimana kesempatan kerja formal semakin kecil. Tidak sedikit

petani menjual lahannya untuk biaya masuk kerja formal, atau membeli
kendaraan untuk angkutan umum.
Konversi lahan sawah menyebabkan hilangnya mata pencaharian
sebagian anggota masyarakat setempat, khususnya petani dan buruh tani.
Oleh karena itu sebagian dari mereka tidak dapat menjangkaukesempatan
kerja dan usaha yang baru, maka konversi lahan sawah diduga juga
mengakibatkan terjadinya peninkatan kemiskinan di wilayah tersebut.
Perubahan pendapatan akibat konversi lahan, dan juga terjadi perbedaan
pemamfaatan dalam alokasi dana hasil penjualan lahan antar petani. Ada
perbedaan yang nyata antara petani, lapisan menengah, atas, dan bawah
dalam pengelolaan dana hasil penjualan lahan. Petani kaya atau petani
lapisan atas cenderung kearah penggunaan produktif, sedangkan petani
miskin cenderung kearah konsumtif.
Akibat tekanan ekonomi, dana yang didapat dari hasil penjualan lahan
oleh petanilapisan bawah, cenderung dialokasikan kerah ang sifatnya
konsumtif, seperti memperbaiki rumah, member peralatan rumahtangga, naik
haji, dan juga untuk memenuhi kebutuhan pangan nya. Sedangkan penjualan
lahan untuk kegiatan yang sifatnya produktif, yakni untuk tambahan modal
usaha.
2.4. Akses Sarana dan Prasarana
Hakikat perkembangan pemukiman di desa setiap wilayah adalah
perubahan, yang dapat terjadi secara terencana Maupin secara tidak

terencana. Hal ini berakibat pada perkembangan kualitas dan kuantitas
pemukiman bervariasi secara keruangan. Beberapa masalah perdesaan yang
berkaitan dengan ruang wilayah antara lain belum serasinya perkembangan
dan keterkaitan aktifitas pertanian dengan sector laindalam pengembangan
wilayah sebagai stau kesatuan, masih banyaknya kerusakan lingkungan
akibat konversi lahan, dan masih kurang layaknya kondisi lingkngan
perumahan dan permukiman beserta sarana dan prasarana permukiman
penduduknya (Pascione, 1984; Riyadi 200). Oleh karena itu, dalam ysaha
pengembangan permukiman desa perlu kajian variasi keruangan perubahan
permukiman dan fakto-faktor pendukungnya.
Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengembangan permukiman di
Indonesia yang menekankan dua prioritas (Dirjen perumahan dan
Pemukiman, 2002). Pertama prioritas jenis kegiatan antara lain
pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendukung
pemukiman, dan prioritas kedua adalah lokasi antara lain pembangunan di
pulau-pulau kecil, dan pengembangan kualitas pemukiman di wilayah
pedesaan pinggiran kota. Kebijakan pengembangan permukiman tersebut
mendasari pentingnya penelitian tentang perkembangan permukiman,
khususnya perkembangan permukiman pedesaan pinggiran kota. Hal ini
mengingat peran wilayah pinggiran kota bagi kesejahteraan penduduk
menurun sebagai ruang tempat kehidupan penduduk, baik kehidupan sosial-
budaya maupun sosial ekonomi.

Pertimbangan mengenai kepentingan atas lahan di berbagai wilayah
mungkinberbeda tergantung kepada struktur sosial penduduk dan kebijakan
oleh pemerintah dalam mengembangkan wilayah. Aturan-aturan dalam
penggunaan lahan dijalankan berdasarkan pada beberapa kategori antara
lain kepuasan, kecenderungan untuk kegiatan dalam tata guna lahan,
kesadaran akan tata guna lahan, kebutuhan orientasi dan pemamfaatan atau
pengaturan estetika (Munir, 2008). Sehubungan dengan hal tersebut,
(Chapin, 1995 Jayadinata, 1999) menggolongkan lahan dalam tiga kategori,
yaitu; (1) nilai keuntungan, yang dihubungkan dengan tujuan ekonomi dan
yang dapat dicapai dengan jual-beli lahan dipasaran bebas.; (2) nilai
kepentingan umum, yang dihubungkan dengan pengaturanuntuk masyrakat
umum dalam perbaikan kehidupan masyarakat.; (3) nilai sosial, yang
merupakan hal mendasar bagi kehidupan dan dinyatakan oleh penduduk
dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, kepercayaan
dan sebagainya.
Perkembangan sector pertanian pada umumnya terjadi pada wilayah-
wilayah yang berlahan subur, pada wilayah inilah berkembang pusat-pusat
pemukiman penduduk sehingga menuntut pemerintah daerah setempatuntuk
membangun fasilitas-fasilitas umum dan parasarana-prasarana di wilayah
tersebut. Adanya pusat pemukiman penduduk, ketersediaan prasarana dan
berdasarkan pertimbangan factor-faktor lokasi, yaitu dekatnya lokasi dengan
pemukiman sebagai sumber tenaga kerja, maka penggunaan lahan untuk

penggunaan non-pertanian seperti perumahan dan industry cenderung untuk
berkembang di wilayah ini (Nuryati, 1995 ).
Tidak semua konversi lahan berdampak negatif namun adapula dampak
positifnya, yaitu dengan semakin padatnya penduduk di wilayah tersebut
maka dengan sendirinya desakan pemerintah akan sarana dan prasarana
umum semakin nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada
dalam cakupan wilayah tersebut, fasilitas umum yang di bangun pemerintah
antara lain sarana pendidikan, kesehatan, ibadah, jalan dan lainnya, yang
dapat dirasakan langsung mamfaatnya oleh masyarakat sekitar perumahan
yang telah mengkonversi lahannya kepada pihak yang membangun (pemilik
perumahan).
2.5. Sikap Gotong royong (Faktor dan Dorongan semangat Gotong
Royong)
Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja
bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Bersama-
sama dengan musyawarah, pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, dan
kekeluargaan, gotong royong menjadi dasar Filsafat Indonesia seperti yang
dikemukakan oleh (M. Nasroen, 1997). Sikap gotong royong adalah bekerja
bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama
menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Atau suatu usaha atau
pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua
warga menurut batas kemampuannya masing-masing.

Gotong royong dapat diartikan pula sebagai sesuatu sikap ataupun
kegiatan yang ditakukan oleh anggota masyarakat secara kerjasama dan
tolong menolong dalam menyelesaikan pekerjaan maupun masalah dengan
sukarela tanpa adanya imbalan. Sikap gotong royong ini telah melekat pada
diri masyarakat pedesaan dan merupakan kebiasaan turun temurun dari
nenek moyang. Sikap gotong royong ini sangat berperan sekali untuk
memperlancar pembangunan yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan gotong royong yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam
kehidupan masyarakat desa selama ini, perlu diarahkan dan dibina
sedemikian rupa sehingga dapat menunjang pembangunan yang sedang
dilaksanakan. Gotong royong dalam usaha meningkatkan produksi perlu
digalakan dan hasilnya digunakan untuk pembangunan desa.
Permasalahan yang ada sekarang ialah bagaimana cara memupuk
kembali nilai-nilai gotong royong yang pernah hidup dengan kuatnya pada
kehidupan masyarakat. Walaupun tidak berarti kita harus meampertahankan
faktor pendorong adanya gotong royong tersebut. Gotong royong akan tetap
hidup dikalangan masyarakat, tetapi berbeda latar belakangnya, bentuk dan
sifat dari gotong royong itu sendiri perbedaan ini biasanya ditimbulkan oleh
lingkungan masing-masing. Jadi sikap gotong royong dalam masyarakat yang
melaksanakan pembangunan mengalami perubahan berbarengan dengan
terjadinya perubahan -perubahan sosial yang berlangsung secara
berkesinambungan dengan hasil-hasil penemuan manusia itu sendiri.

Sementara itu orang-orang desa mulai menyadari dengan lebih mendalam
akan perlunya kesempatan dan tata cara berpikir baru, perencanaan
terhadap kerjasama atau gotong royong untuk memecahkan berbagai macam
problema. Dengan itu mereka akan memperoleh pengalaman bahwa dengan
bergotong royong itu akan melakukan hal-hal yang lebih banyak dan lebih
efektif dari pada cara perseorangan. Sementara itu orang-orang desa mulai
menyadari dengan lebih mendalam akan perlunya kesempatan dan tata cara
berpikir baru, perencana terhadap kerjasama utau gotong royong untuk
memecahkan berbagai macam problema. Dengan itu mereka akan
memperoleh pengalaman bahwa dengan bergotong royong itu akan
melakukan hal-hal yang lebih banyak dan lebih efektif dari pada cara
perseorangan.. (Anonim 5, 2014).
Semangat gotong royong didorong oleh yaitu:
(a). Bahwa manusia tidak hidup sendiri melainkan hidup bersama
dengan orang lain atau lingkungan sosial; (b). Pada dasarnya manusia itu
tergantung pada manusia lainnya; (c). Manusia perlu menjaga hubungan baik
dengan sesamanya; dan (d). Manusia perlu menyesuaikan dirinya dengan
anggota masyarakat yang lain. Dari inilah timbul suatu kesadaran bahwa kita
tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri. Oleh
karena itu perlu ditumbuhkan suatu kesadaran dan tanggung jawab terhadap
kepentingan bersama.

Sekarang mari kita lihat pengamalan azas gotong royong dalam berbagai
kehidupan! Perwujudan partisipasi rakyat dalam reformasi merupakan
pengabdian dan kesetiaan masyarakat terhadap program reformasi yang
mana senantiasa berbicara, bergotong royong dalam kebersamaan
melakukan suatu pekerjaan. Sikap gotong royong memang sudah menjadi
kepribadian bangsa Indonesia yang harus benar-benar dijaga dan dipelihara,
akan tetapi arus kemajuan ilmu dan teknologi ternyata membawa pengaruh
yang cukup besar terhadap sikap dan kepribadian suatu angsa, serta selalu
diikuti oleh perubahan tatanan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu
masyarakat.
Adapun nilai-nilai gotong royong yang telah menjadi bagian dari
kebudayaan bangsa Indonesia, tentu tidak akan lepas dari pengaruh
tersebut. Namun syukurlah bahwa sistem budaya kita dilandasi oleh nilai-nilai
keagamaan yang merupakan benteng kokoh dalam menghadapi arus
perubahan jaman.Untuk dapat meningkatkan pengamalan azas
kegotongroyongan dalam berbagai kehidupan perlu membahas latar
belakang dan alasan pentingnya bergotong royong yaitu: (a). Bahwa manusia
membutuhkan sesamanya dalam mencapai kesejahteraan baik jasmani
maupun rohani. (b). Manusia baru berarti dalam kehidupannya apabila ia
berada dalam kehidupan sesamanya. (c). Manusia sebagai mahluk berbudi
luhur memiliki rasa saling mencintai, mengasihidan tenggang rasa terhadap
sesamanya. (d). Dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa mengharuskan setiap manusia untuk bekerjasama, bergotong

royong dalam mencapai kesehjahteraan hidupnya baik di dunia maupun di
akhirat. (e). Usaha yang dilakukan secara gotong royong akan menjadikan
suatu kegiatan terasa lebih ringan, mudah dan lancer (Anonim 6, 2014).
2.5. Kerangka pemikiran
Mengingat bahwa dalam kegiatan konversi lahan akan memberikan
banyak dampak seperti ekonomi, sosial, maupun lingkungan yang semuanya
akan berpengaruh langsung pada sikap gotong royong petani, (sebelum dan
sesudah konversi) sehingga akan memberikan perbedaan nilai terhadap
keadaan ekonomi maupun sosial para petani di wilayah tersebut. Untuk
melengkapi uraian tersebut, maka peneliti menyajikan kerangka pemikiran
sebagai berikut.
faktor penarik konversi lahan faktor pendorong
akses fasilitas
sikap gotong royong petani
faktor semangat gotong royong Dorongan gotong royong
Gambar 1. Skema kerangka piker penelitian

Berdasarkan skema diatas dapat dilihat keterkaitan antara konversi
lahan terhadap sikap gotong royong petani di kelurahan Tamangangapa.
Konversi ini disebabkan dua factor yakni : factor pendorong dan factor
penarik. Factor pendorong disisni disebabkan oleh harga lahan yang
semakain tinggi berdsarkan tawaran para pelaku bisnis property yang
merasa ingin berinvestasi di daerah ini, sedangkan factor pendorong yakni
produktivitas lahan yang tidak lagi mengalami peningkatan yang signifikan
akibat berbagai factor, baik factor kesuburan tanah maupun factor cuaca
yang toidak menentu. Konversi lahan ini berpengaruh pada sikap gotong
royong para petani di kelurahan Tamangapa. Sikap gotonng royong disini
mencakup sikap gotong royong dari segi factor semangat gotong royong
dan dorongan gotong royong. Pada factor gotong royong mencaku factor-
faktor gotong royong akibat konversi lahan yang masih terus terjaga,
sedangkan dari segi dorongan gotong royong mencakup apa-apa saja yang
mampu member dan menjaga sikap kegotong royongan ini sebelum dan
setelah adanya konversi lahan ini.
2.5. Hipotesis
Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan
penelitian seperti yang telah di kemukakan sebelumnya, maka hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
1. Intensitas konversi lahan pertanian ke non-pertanian di Kelurahan
Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di kategorikan tinggi.

2. Perubahan harga lahan merupakan factor penarik dan produktivitas
merupakan factor pe ndorong dalam konversi lahan di Kelurahan
Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Konversi lahan berpengaruh pada sikap gotong royong petani di Kelurahan
Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

III. METODOLOGI PENELITAIAN
3.1. Tempat dan waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanaka di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara
purposive yaitu pemilihan secara langsung dengan pertimbangan bahwa daerah
ini penduduknya dulu mayoritas mata pencahariannya adalah bertani dan saat ini
semakin berkurang. Penelitian ini akan dilakasanakan selama 2 bulan, yakni
mulai bulan Maret 2014 sampai bulan Juni 2014.
3.2. Metode Penelitian dan Penentuan Sampel
Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yaitu suatu
model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu system yang berbatas pada
suatu kasus atau beberapa kasus secara mendetail disertai dengan penggalian
data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya
akan kontes. Sehingga kasus-kasus tersebut akan diteliti secara utuh yang
dalam hal ini dilakukan pada petani yang mengkonversi lahan pertanian ke non-
pertanian di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif melalui
pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat
menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Tujuan penelitiandeskriptif adalah

untuk menjelaskan suatu hal secara sistemik, factual, dan akurat serta sifat-sifat
populasi pada daerah tertentu.
Pendekatan kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan
berlandasan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi
dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif, maka dapat mengikuti dan
memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup
pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan
bermamfaat.
Penentuan sampel dilakukan secara acak sederhana (simple random
sampling), yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan penelitian
sesuai dengan tujuan penelitian. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam
simple random sampling adalah semua individu dalam populasi (anggota
populasi) berkesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Teknik penarikan contoh acak sederhana digunakan karena pada umumnya
petani dilokasi penelitian pernah menjual lahannya. Sehingga setiap sampel
yang terpilih adalah mereka yang dianggap mampu memberikan keterangan
sesuai tujuan penelitian.
3.3. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian baik
melalui hasil wawancara dengan menggunakan kusioner dan wawancara
mendalam dengan petani responden dan informan kunci.
2. Data sekunder, yaitu ada yang diperoleh dari instansi/lembaga terkait dengan
penelitian ini seperti;
a. Jumlah kepemilikan lahan, luas lahan, luas alih fungsi lahan, diperoleh dari
kantor Kelurahan Tamangapa.
b. Keadaan Kelurahan Tamangapalaiinya diperoleh dari dinas pertanian kota
Makassar, badan pusat statistic kota Makassar, kantor camat Manggala dan
kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut;
1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada lingkungan
masyrakat tani untuk mengetahui intensitas konversi lahan pertanian ke
non-pertanian yang ada di lokasi penelitian.
2. Wawancara yaitu Tanya jawab yang dilakukan terhadap petani responden
dengan menggunakan kusioner.
3. Wawancara mendaloam yaitu wawancara yang dilakukan untuk
mendapatkan data dalam bentuk diskripsi dari petani responden dan
informan kunci terkait dengan konversi lahan Kelurahan Tamangapa.

4. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari beberapa instansi
teknis yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi yang digunakan
sebagai sumber data terdiri dari Kecamatan Manggala dalam angka dari
Badan Pusat Statistik, laporan penelitian dan literatur-literatur yang terkait.
3.5. Metode Analisis
Data yang diperoleh dari pnelitian selanjutnya diolah dengan
menggunakan analisis komparasi, yakni membandingkan;
1. Jenis dan jumlah mata pencaharian sebelum dan sesudah masyarakat
Kelurahan tamangapa menkonversi lahan.
2. Jenis dan jumlah fasilitas sarana/prasarana yang bias diakses sebelum
dan sesudah masyarakat mengkonversi lahan nya.
3. Tingkat sikap gotong royong petani sebelum dan setelah adanya konversi
lahan di Kelurahan Tamangapa.
3.6. Konsep operasional
Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, maka ditetapkan
batasan konsep operasional sebagai berikut;
1. Tanah atau lahan merupakan sumberdaya yang sangat penting dimana
tempat makhluk hidup melakukan segala aktifitas.
2. Konversi lahan adalah perubahan fungsi lahan menjadi fungsi yang lain
diman akan merubah potensi lahan tersebut.

3. Konversi lahan pertanian ke perumahan yaitu perubahan fungsi
sumberdaya dan potensi lahan menjadi sebuah perumahan.
4. Dampak adalah pengaruh atau efek yang ditimbulkan dari sesuatu
tindakan atau kegiatan, dalam hal ini adalah pengaruh terhadap
kehidupan masyarakat sekitar.
5. Petani yaitu seseorang yang bergerak dibidang bisnis pertanianutamanya
dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk
menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah,
sayur dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari
tanaman untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.
6. Responden adalah petani-petaniyang dijadikan sampel penelitian yang
terlibat atau merasakan sendiri hasil dari proyek-proyek pertanian yang
ada.
7. Mata pencaharian adalah sumber penghasilah atau pendapatan
seseorang.
8. Perubahan mata pencaharian yaitu berubahnya penghasilan atau
pendapatan seseorang akibat adanya perubahan pekerjaan.
9. Intensitas adalah banyaknya petani yang pernah menjual lahannya.
10.Factor pendorong adalah hal-hal yang mendorong petani kelurahan
Tamangapa untuk menjual lahannya.
11.Factor penarik adalah hal-hal yang menjadi dasar petani di Keluarahan
Tamangapa untuk menjual lahannya.

12.Perubahan akses fasilitasyaitu perubahan sarana dan prasarana fisik
yakni adanya perubahan benda atau barang yang menunjang atau
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
13.Sikap gotong royong adalah sesuatu sikap ataupun kegiatan yang
ditakukan oleh anggota masyarakat secara kerjasama dan tolong
menolong dalam menyelesaikan pekerjaan maupun masalah dengan
sukarela tanpa adanya imbalan.
14.Factor semangat gotong royong adalah nilai-nilai semangat gotong royong
yang lahir dari tradisi asli masyrakat indonesia.
15.Dorongan gotong royong adalah suatu sikap yang lahir dari jiwa hakiki
masyrakat indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai dan
norma persatuan dan kesatuan.

SEMINARPROPOSAL PENELITIAN
Judul : Dampak Konversi Lahan terhadap Sikap Gotong Royong Petani (Studi kasus, di Desa Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar)
Nama : Syamsu AlamStambuk : G211 10 903Hari/Tanggal :Waktu :Tempat : Dosen Pembimbing : 1.
2. Dosen Penguji : 1.
2. Panitia Seminar :
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013